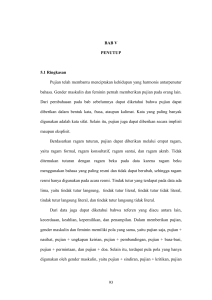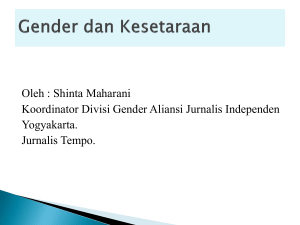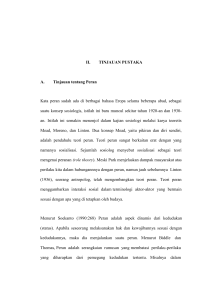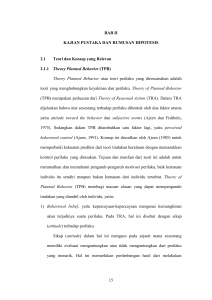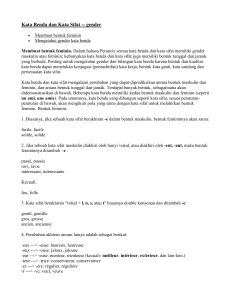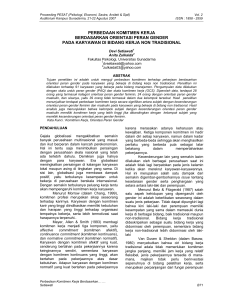gender dan implementasinya dalam pemikiran
advertisement

IMPLEMENTASI KONSEP GENDER DALAM PEMIKIRAN ISLAM ( Sebuah Pendekatan Autokritik ) By Nasyithotul Jannah Abstraksi Konsep gender dalam Islam berakar pada paradigma bahwa secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama, karenanya keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun demikian, dalam konstalasi pemikiran Islam, ada tiga pandangan yang berkembang, pandangan konservatif yang bernuansa patriarkhis, pandangan moderat yang berbasis pada paradigma keseimbangan dan keadilan dan pandangan liberal yang mencoba mendekonstruksi konsep konsep religiusitas yang dipandang merugikan pihak perempuan. Namun jika merujuk pada sejarah dan filosofi penciptaan, perempuan dengan kualitas femininitanya dan laki-laki dengan maskulinitasnya memang harus diakui memiliki kekhasan masing-masing. Justru karena kekhasan tersebut, keduanya komplementer karena merupakan wujud dualitas makrokosmos yang akhirnya menciptakan keseimbangan. Gender pada hakekatnya adalah sebuah terma yang digunakan untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, hasil dari rekayasa manusia sebagai akibat pengaruh sosial budaya masyarakat yang tidak bermakna kodrati. Di dalam Women’s Studies Encyclopedia disebutkan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Tidak dipungkiri, bahwa acapkali muncul relasi problematik antara perempuan dan laki-laki. Bukan perbedaan alamiah keduanya tapi implikasi yang tercipta dari perbedaan tersebut. Hampir tidak ada isu psikologis apapun yang begitu kontroversial dan kompleks dibandingkan dengan isu ini. Oleh karena itu berbicara gender berarti bicara tentang sebuah konsepsi yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis semata melainkan juga oleh lingkungan sosial, politik dan juga ekonomi. Hal ini perlu ditegaskan guna membedakan segala sesuatu yang normatif dan biologis dan segala sesuatu yang merupakan konstruksi sosial budaya dalam bentuk proses kesepakatan normatif dan sosial yang dapat ditransformasikan. Ambivalensi yang dihadapi publik tentang isu-isu gender semakin kompleks ketika dihadapkan pada sebuah fenomena masa kini. Wajar jika di lingkar pegiat feminis sendiri terdapat dua pandangan yang saling mengcounter. Pertama, yang berpandangan bahwa gender adalah konstruksi sosial, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran social, karenanya segala peran dan fungsi berbau gender harus dihilangkan. Sekelompok feminis lainnya menganggap perbedaan jenis 1 kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis peran berstereotip gender. Lebih lanjut, agama-agama Ibrahim (Abrahamic Religions) terutama Islam sering dianggap sebagai salah satu factor yang menjustifikasi paham patriarkhi yang bias gender. Agama dipandang terlalu bersifat maskulin dan patriakhal sehingga sering mengabaikan aspek femininitas dan peran perempuan baik secara ritual maupun institusional. Karenanya, wacana gender memang tidak dapat dilepaskan dari persoalan teologis – karena memang – posisi perempuan dalam beberapa pemikiran agama ditempatkan sebagai the second, terutama dalam persoalan asal usul kejadian laki-laki dan perempuan, juga persoalan fungsi keberadaan keduanya. Namun yang perlu dicermati adalah apakah pelanggengan ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi ataupun pandangan-pandangan lainnya. Karena itulah, sebuah keniscayaan, untuk kembali menelusuri ajaran-ajaran Islam yang autentik, karena Islam sejak awal, memiliki konsep yang sangat matang dalam memposisikan perempuan yang didasari atas tuntunan moral dasar Islam itu sendiri yang ditercantumkan di dalam Al Quran maupun hadits, justru disaat agama-agama lain hingga saat ini masih berselisih pendapat dalam menetapkan hukum perempaun dan kemanusiaanya Problematika Penciptaan Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.( An Nisa : 1) Para penafsir diantaranya Ibnu Kasir, Zamahsyari, at Tabari al Alusi memahami bahwa al nafs wahidah dalam ayat tersebut dengan tubuh Adam, dan isterinya sebagai Hawwa, sementara minha ditafsirkan dengan tulang rusuk bagian kiri Adam. Sehingga dalam penafsiran klasik, berkembang pandangan bahwa manusia yang pertama diciptakan Allah adalah Adam, kemudian setelah itu baru Allah menciptakan isterinya, Hawwa, dari salah satu tulang rusuk Adam. Seperti dikatakan Ahmad Sawi dalam Hasyiyah Tafsir Jalalain: Yang dimaksud zawj adalah Hawwa yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam, maka tulang rusuk laki-laki sebelah kiri kurang satu, bagian kanan berjumlah 18, sedangkan kiri 17. 2 Menurut Muhammad Abduh kata nafs wahidah tidak dapat dipahami sebagai Adam karena hal itu justru bertentangan dengan penelitian ilmiah dan sejarah. Hal ini dikuatkan oleh Mustafa al Maraghi yang berpendapat bahwa tafsir ulama yang mengatakan bahwa nafs wahidah adalah Adam bukanlah berdasarkan teks ayat akan tetapi berdasarkan pemahaman bahwa Adam adalah abul basyar (bapak manusia). Lebih lanjut Al Qaffal mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari diri yang satu (nafs wahidah) dan Allah jadikan dari jenis itu pasangannya (zawj) yaitu manusia yang sama dalam sifat-sifat kemanusiaannya, karena term minha menunjukan makna dari jenis yang sama. Oleh karenanya apabila Adam diciptakan dari tanah, maka dari tanah pula pasangannya diciptakan, bukan dari tulang rusuknya. Menurut Fatimah Mernisi dan Rifat Hassan al Quran tidak menyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama dan berjenis laki-laki. Istilah Adam adalah kata benda maskulin, namun hanya mengatakan jenis linguistic bukan menyangkut jenis kelamin. Jika Adam belum tentu laki-laki, zauj Adam juga belum tentu perempuan karena sebenarnya zauj juga merupakan kata benda maskulin, karena ia memiliki bentuk femininnya zaujatun. Oleh karena itu terjemah yang paling tepat dari zauj bukanlah isteri tetapi suami, bahkan suami isteri atau pasangan. Istilah nafs dalam Quran menunjukan bahwa umat manusia berasal dari asal usul yang sama. Secara tata bahasa nafs merupakan bentuk muannas (female) sedangkan secara konseptual nafs mengandung arti netral, bukan bentuk laki-laki maupun perempuan. Juga kata zauj dalam al Quran digunakan untuk menunjukan jodoh ataupun pasangan. Istilah ini digunakan dalam tahap kedua penciptaan manusia, para mufassir memahaminya sebagai Hawa, perempuan pertama. Menurut tata bahasa zawj justru merupakan bentuk mudzakkar (male), hingga secara konseptual tidak menunjukan bentuk muannas (femal ) maupun mudzakkar (male). Pemahaman bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam adalah pengaruh Israiliyat. Menurut Ruhaini, penolakan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam dibuktikan bahwa kata “Hawa” dan “tulang rusuk” ternyata tidak ada secara tersurat di dalam al Qur’an. Muhammad Rasyid Ridha menambahkan bahwa seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama dengan redaksi pemahaman harfiah ( Maka didatangkan Tuhan Allah atas Adam itu tidur yang tetap, lalu tidurlah ia. Maka diambil Allah sebilah tualang rusuknya lalu ditutupnya pula tempat itu dengan daging. Maka dari pada tulang yang telah dikeluarkannya dari dalam Adam itu diperbuat Tuhan seorang 3 perempuan. Lalu dibawanya akan dia kepada Adam ), niscaya pemahaman itu tidak ada dalam pemikiran Islam. Lebih lanjut, di Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman “ Wahai manusia ! sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa secara ontologis, manusia adalah entitas atau mikrokosmos yang terdiri dari sisi laki-laki dan perempuan. Parameter kemuliaan derajat keduanya diukur dengan kualitas takwa bukan jenis kelamin. Secara ontologis, manusia adalah merupakan wujud dari adanya proses sinergi antara unsur feminine dan unsur maskulin. Karenanya struktur kemanusiaan itu terdiri dari sisi feminin dan sisi maskulin. Maskulinitas berkonotasi pada kekuatan, sedangkan femininitas pada kelembutan. Dengan demikian ketidakseimbang keduanya hanya akan menyebabkan chaos dan disharmonisasi sistem makrokosmos. Dalam konteks ini, Ibnu Arabi sebagaimana dikutip Sachiko Murata dalam The Tao of Islam menyatakan bahwa Kemanusiaan (insaniyah) adalah suatu realitas yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan, sehingga kaum laki-laki tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi dari perempuan dalam hal kemanusiaan. Dalam kaitan dengan realitas ciptaan yang berwujud manusia, perempuan itu identik dengan laki-laki, namun dalam kaitannya dengan entifikasi, masing-masing memang memiliki kekhasan tersendiri sebagaimana dalam Surat Ali Imron ayat 36 ( walaisa adz dzakara ka al unsa ). Kekhasan itu bila ditempatkan dalam entitas realitas ciptaan yang berpasang pasangan, sesungguhnya berfungsi untuk saling melengkapi dan menggenapi dalam hubungan interdependensi. Tanpa perempuan, laki-laki bukanlah laki-laki, sebab lakilaki didefinisikan oleh perempuan, demikian juga perempuan. Inilah bagian dari misteri kekuatan perempuan, dimana eksistensi perempuan mengukuhkan laki-laki menjadi lakilaki. Namun menurut Saad Abdul Wahid, pernyataan walaisa adz dzakara ka al unsa tersebut adalah pernyataan isteri Imron (ibunda Maryam ) itu bukanlah pernyataan yang idealis tapi sesuatu yang realistis – karena dalam konteks kehidupan Ibunda Maryam – ia hidup dalam kultur patrilineal yang didominasi laki-laki. Oleh karena itu sesuatu yang realistis tidak dapat dijadikan tuntunan. Guna memperkuat tesis bahwa perempuan secara ontologism memiliki derajat yang berimbang dengan laki-laki, dalam analisa semantiknya, Ibnu Arabi – seperti dikutip Sachiko Murata - mengatakan : tidakkah kamu perhatikan kebijaksanaan Tuhan dalam kelebihan yang 4 telah Dia berikan kepada perempuan atas laki-laki dalam namanya ?. kepada manusia berjenis laki-laki, Dia menyebut mar’ dan kepada perempuan Dia menyebut mar’ah, jadi Dia menambahkan sebuah ah atau at dalam bentuk konsepsi pada nama mar’ yang diberikan kepada laki-laki. Maka perempuan mempunyai satu tingkat yang tidak dimiliki oleh laki-laki dalam konteks ini, bertentangan dengan tingkat yang diberikan kepada laki-laki dalam ayat ‘ Kaum laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi daripada mereka. Maka Tuhan menutup kesenjangan dalam ayat tersebut dengan tambahan ini dalam mar’ah. Renspon Masyarakat Islam terhadap Diskursus Gender Secara empirik persoalan gender oleh sebagian pandangan umat Islam diasosiasikan sebagai the nature yang tak bisa diubah karena sifatnya yang taken for granted , namun oleh sebagian lainnya justru diasumsikan sebagai the nuture yang dibentuk dan dikondisikan oleh sistem nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat sehingga bersifat changeable dari waktu ke waktu dan dari masyarakat ke masyarakat. Dengan demikian tafsir genderpun dalam pemikiran Islam terderivasi menjadi beberapa pandangan. Tidak ada homogenitas tafsir. Tidak ada pandangan tunggal. Dan masing-masing pandangan memilki sudut pandang tersendiri. Pandangan Konservatif Syariat Islam sejak kemunculannya telah berusaha mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat Arab yang memiliki budaya dan tradisi patriarkhi yang sangat kuat. Upaya tersebut diwujudkan dengan adanya aturan dan doktrin – doktrin yang berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari posisinya semula. Aturan-aturan syariat tersebut antara lain mengecam penguburan anak perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris, hak-hak sebagai isteri, hak sebagai saksi dan hak-hak lainnya. Dengan kata lain syariat Islam sejak semula telah memberikan hak dan peran kepada kaum perempuan baik diwilayah domestik maupun publik. Padahal tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya yang tidak memiliki hak apapun. Karena itu dapat dilihat dari sisi ini bahwa sesungguhnya semangat dan pesan moral Islam adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan berusaha menegakkan keadilan gender di tengah masyarakat. Walaupun pesan universal Islam adalah keadilan gender, namun banyak penafsir yang memahami teks – teks yang terdapat dalam alQuran hadis-hanya secara tekstual, parsial dan 5 dilepaskan dari konteks turunnya,sehingga menghasilkan interprestasi yang bias gender dan melahirkan aturan dan doktrin ketidakadilan gender. Hal ini terjadi karena setelah nabi wafat, posisi sosial perempuan yang semula membaik kembali mengalami krisis. Alih-alih stabil secara sosial, posisi Islam. Selain perempuan masalah malah menguatnya berbalik lagi kembali tribalisme ke (rasa nilai-nilai kesukuan) pra Arab, pasca Nabi, Fatimah Mernisi memvonis bahwa adanya pelepasan historis bentuk pemahaman patriarki Islam. ajaran kembali "Perempuan agama memberi kembali terhadap pengaruh tidak perempuan. kuat dipercaya," Akibatnya dalam sangat menafsirkan demikian tulis jelas, ajaran Mernisi dalam Women in Islam. Secara historis, sikap misoginis – kegusaran laki-laki atas derajat keberadaannya yang disamakan dengan perempuan – ini telah ada sejak Islam muncul sebagai gerakan reformasi budaya. Penolakan Islam oleh masyarakat Arab merupakan penolakan atas moralitas yang menghapuskan simbol-simbol superioritas kekuasaan laki-laki. Tidak semua sahabat Nabi dapat dengan segera memberikan respon yang emansipatif terhadap reformasi sosial ini. Sebagian sahabat berpandangan bahwa Nabi memberikan hak terlalu banyak kepada perempuan. Mereka menghendaki agar Islam lebih menekankan perubahan pada dunia publik tetapi tetap mempertahankan moralitas dunia privat berdasarkan tradisi Arab lama yang patriarkhis. Sepeninggal Nabi, kecenderungan pada superioritas laki-laki yang belum sepenuhnya terkikis oleh reformasi budaya Islam kembali menguat. Hal ini tampak dari interprestasi para sahabat terhadap beberapa ayat al Quran tentang hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Dari sekian sahabat yang dipandang mempunyai kapasitas penafsiran yang cerdas seperti Ibnu Abbas tetap saja laki-laki ditempatkan sebagai penguasa, pemimpin dan pengontrol perempuan. Dominasi budaya patriarkhi mencapai puncaknya di abad pertengahan Islam, dimana saat itu penafsiran agama yang diskriminatif dianggap memiliki kebenaran mutlak. Imbasnya segala produk hokum yang dihasilkan para ulama dan imam madzhab abad pertengahan secara seragam tidak memberikan ruang gerak sedikitpun bagi penghargaan terhadap hak perempuan seperti yang tercantum dalam lembaran kitab-kitab kuning. Dan ironisnya, justru kitab-kitab kuning yang sangat beraroma patriarkhis inilah yang kemudian selama berabad abad menjadi referensi utama dalam masyarakat Islam. Dalam konteks ini Karen Amstrong dalam A History of God berpendapat, “ setelah Muhammad wafat- agama Islam kemudian dibajak oleh kaum laki-laki yang menafsirkan 6 teks-teks al Quran dengan cara yang berpandangan negative terhadap perempuan. Olel karena itu begitu Islam menempati posisinya di dalam dunia peradaban, kaum muslim mengadopsi adat Oikumene yang menempatkan perempuan pada status warga kelas dua. Mereka mengadopsi kebiasaan Persia dan Kristen Byzantium untuk menutup wajah perempuan dan mengurungnya di dalam harem. Dengan cara inilah akhirnya perempuan di dalam Islam terpinggirkan, dan sama nasibnya dengan rekan mereka di kalangan masyarakat Yahudi dan Nasrani”. Hal senada juga dikatakan Leila Ahmed dalam Women and Gender in Islam bahwa setelah Muhammad, dimulailah proses kematian berangsur-angsur partisipasi perempuan dalam komunitas religius Islam dari sikap positif Muhammad kepada interprestasi misogynist di kemudian hari. Dengan membawa justifikasi agama, seperti Ar Rijalu Qawwamuna ‘ala an Nisaa, konservatisisme yang berbasis pada paradigma patriarkhis memaknai gender secara distriminatif dan stuktural, menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua (second clas ) yang bersubornidasi oleh superioritas pria dengan. Adagium seperti surga nunut, neraka katut, konco cingking, sumur, kasur, dapur dan manak, macak dan masak yang dilekatkan pada perempuan telah meredusir posisi perempuan hanya sekedar menjadi the body yang potensi soulnya apalagi mind dan spiritnya sama sekali tidak mendapat tempat. Konservatisisme.- dengan metode skripturalisnya – menarik Islam ke masa 15 abad yang lalu dalam merespon persoalan gender dalam aroma Arabisme yang sangat patriarkhis. Indikasinya interprestasi mereka terhadap konsep hijab, poligami, talak dan lainnya cenderung bernuansa semangat penaklukan terhadap perempuan. Oleh karena itu penolakan tentang ide kesetaraan ini paling artikulatif dilakukan oleh kaum “Konservativ” yang pada dasarnya merupakan gerak protes terhadap beberapa aspek dari modernisme. Resistensi ini tidaklah mengherankan karena konservatisisme menfokuskan diri pada gender sebagai isu utama dan keluarga sebagai issu utama dalam upaya menanamkan tatanan moral dan nilai yang dipercaya sebagai cetak biru yang harus diwujudkan. Bagi gerak konservatisisme keluarga adalah menjadi salah satu simbol utama pranata moral ideal yang keharusan untuk kembali ke bentuk ideal keluarga merupakan prioritas tertinggi dari agenda sosial mereka. Pada gilirannya nilai-nilai mengarah pada pembatasan peran perempuan di sektor domestik dan peran-peran tradisional atau penguatan kembali sistem patriarkhi dengan laki-laki sebagai pusat kekuasaan. Namun dalam perspektif lain, konservatisisme ini dikatakan sebagai manifestasi ketakutan akan perubahan. Feminis yang memperjuangkan kebebasan perempuan, reformasi pola relasi dan kuasa antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pribadi, keluarga dan 7 publik dilihat sebagai ancaman dan antitesa serta bentuk dekonstruksi terhadap kemapanan tradisi, institusi keluarga dan ideologi patriarkhi yang akan menggoyahkan otoritas patriarkhi. Feminisme dalam perspektif konservatif diasumsikan sebagai budaya tandingan (Counter Culture) karena menggugat dan mengkritisi nilai-nilai baku yang dipandang aksiomatik (badihi) selama ini sebagai bentuk peringatan bahwa pranata sosial yang berlaku sedang goyah, sistem pendukung kultural mitos dan simbol tidak lagi menghegemoni. Kemudian dalam konteks kekinian, neo konservatisisme Islam kembali muncul dengan kemasan yang lebih akademis dan ilmiah sebagai kultur tandingan terhadap gerak modernisme. Gaya hidup global telah menyebabkan krisis moral dan spiritual serta meningkatnya patologi sosial di tingkat lokal, dan semuanya ditimpakan pada perempuan yang berkiprah diluar rumah sebagai penyebabnya. Hal ini cukup meresahkan, karena pada tingkat tertentu konservatisisme menginginkan terealisasinya kultur Islam dengan disertai dengan domestifikasi perempuan yang tidak proporsional. Pandangan Moderat Keadilan gender pada hakekatnya sudah tercermin sejak periode awal Islam. Sejak zaman Nabi Saw. banyak wanita menduduki posisi penting. Khadijah yang juga istri Nabi misalnya, adalah seorang komisaris sebuah kongsi dagang. Begitu juga Aisyah., seorang wanita muslim pertama yang menuntut dan menjalani karir politik. Kecerdasan Aisyah sangat kentara. Ia mempunyai pengetahuan fikih yang luas dan termasuk di antara barisan orangorang yang paling terdidik. Islam telah mengakhiri praktek-praktek diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan yang terjadi pada masa itu. Pada masa Muhammad, perempuan menjadi bagian dari sebuah masyarakat yang kritis karena laki-laki hadis Muhammad dengan "Menuntut perempuan ilmu tidak pernah dalam adalah hal membuat ilmu kewajiban garis perbedaan pengetahuan setiap seperti muslim antara dalam lelaki maupun perempuan". Dalam sebuah hadis Imam Bukhari, Aisyah pernah memuji semangat para perempuan Anshar dalam menuntut ilmu. "Perempuan terbaik adalah mereka dari Anshar, mereka tidak pernah malu untuk selalu belajar agama," katanya. Will Durant, seorang sejarawan Barat terkemuka, mengakui jasa Muhammad dalam meningkatkan dan memperbaiki hak-hak wanita. Menurutnya, perlakuan yang ditunjukkan oleh Nabi terhadap kaum perempuan sungguh-sungguh berbeda dengan perlakuan masyarakat Arab saat itu menempatkan perempuan pada strata social urutan paling bawah.. 8 Pada masa mobilitas vertikal. berpartisipasi keilmuan Nabi terbuka posisi Gerak dalam luas. perempuan dan berbagai Sumbangan justru kesempatan bidang, perempuan mengalami perempuan untuk khususnya bahkan sangat bidang signifikan dalam upaya transformasi masyarakat ke arah yang lebih egaliter. Dalam seting social-kultur Arab yang sangat paternalistic, apa yang dilakukan Muhammad adalah sangat revolusionar dan sangat modern Islam telah membawa semangat reformasi, transformasi dan liberasi yang membebaskan perempuan dari praktek-praktek dehumanisme dan feodalisme.. Ketika exsistensi perempauan sama sekali tidak mendapat tempat dimasyarakat, Muhammad telah menempati laki dan perempuan pada kedudukan yang ekuvalin (Lihat QS Taubat 71, Annisa124 ). Secara empiris, penghormatan, pengakuan dan penghargaan terhadap existensi perempuan dicontohkan Muhammad dengan memposisikan isteri-isterinya sebagai patner perjuangannya, sebagai tempat saring intelektual, moral dan spiritual yang saling berbagai tugas dalam memenangkan dakwah. Dalam konteks ini salah satu isteri Hitler berkata “ sesungguhnya sistem poligami adalah salah satu faktor terbesar dalam mewujudkan keberhasilan dan kemenangan Muhammad. Untuk itu setelah perang ini aku tidak akan raguragu untuk membujuk Hitler agar mewajibkan poligami kepada masyarakat Jerman untuk menggantikan jutaan laki-laki yang menjadi korban perang”. Dengan fakta sejarah tersebut, pandangan modernis meyakini bahwa spirit Islam yang dibawa Muhammad adalam membebaskan perempuan. Secara histories dikatakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah berjalan secara gradual disesuaikan dengan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu. Meski demikian perubahan gradual itu dalam konteks historis dan cultural mestinya berjalan terus dan tidak berhenti ketika Muhammad wafat. Karena menurut pandangan ini, pola dialektika ajaran Islam menganut asas penerapan bertahap (relatifering process), karenanya di dalam memposisikan perempuan, dalam prakteknya tidak dapat sepenuhnya merujuk kepada pengalaman di masa Nabi. Meskipun nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan gender equality, tetapi kultur masyarakat saat itu belum kondusif. Wahyu baru saja selesai turun ketika Nabi wafat, maka Nabi tidak sempat menyaksikan blueprint ajarannya sepenuhnya terwujud. Terlebih kedudukan perempuan yang berkembang dalam dunia Islam pasca Nabi tidak bisa dijadikan rujukan, karena bukannya semakin mendekati kondisi ideal tetapi malah semakin jauh. Dengan demikian pemaknaan ulang harus dilakukan terhadap beberapa isu perempuan di dalam Islam seperti poligami, waris, persaksian, hijab, kepemimpinan dan lainnya. 9 Ayat-ayat dengan beberapa tema diatas tidak harus dipahami sesuati teks tertulisnya tetapi harus dipahami sesuai dengan spirit “pembebasan” yang dalam prakteknya bisa disesuaikan penerjemahannya sesuai dengan konteks perkembangan jaman. Hal itu harus dilakukan, karena menurut pandangan ini, Allah telah pemberikan otoritas kepada umat Islam untuk merefleksikan nilai-nilai unuversal al-Qur’an dalam prespektif kekinian dan kemudian mefungsikannya dalam realita empirik sehari-hari secara dinamis dan progresif agar fungsi al Qur’an sebagai sumber nilai dan norma tidak mengalam stagnasi tetapi tetap relevan dengan zaman. Secara praksis, pandangan modernis tidak menjebak perempuan pada pilihan dilematis antara dunia public dan domestic, namun tetap melihat keefektifan kedua peran tersebut. Peran domestic berarti perempuan berada di belakang layar “ kebesaran “ laki-laki, namun justru ia tidak menjadi populer dengan perannya. Seringkali keberhasilan perempuan disektor ini malah memperkuat dominasi “kekuasaan laki-laki” disektor publik. Karenanya – menurut pandangan modernis ini - hendaknya fungsi domestikasi perempuan tidak dijadikan pelengkap keperkasaan laki-laki. Peletakan perempuan dalam satu sektor domestik saja tanpa mempertimbangan semua aspek yang melatarbelakanginya merupakan upaya marginalisasi laki-laki terhadap seluruh potensi perempuan. Karenanya teks-teks agama tidak boleh ditafsirkan untuk melegitimasi otoritas kemaskulinan yang membagi peran keduanya secara dikotomis : publik dan domestik. Argumentasi “public milik laki-laki dan domestic milik perempuan” ini secara kontekstual telah menyalahi kodrat kemanusiaan. Kelahiran Hawa yang lebih kemudian dari Adam bukan berarti hawa lebih rendah. Tak ada dominasi atau resesivitas dalam hubungan gender. Keduanya komplementer. Pandangan Liberal Pandangan liberal berasumsi bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas. Bagi mereka keterbelakangan perempuan yang terjadi selama ini disebabkan karena perempuan bersikap irasional dan berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional agama, tradisi, dan budaya. Sikap seperti ini mengungkung perempuan dalam dunia domestik yang tidak produktif. Karenanya keterlibatan perempuan dalam dunia publik mutlak adanya. Menurut mereka keterlibatan perempuan dalam industrialisasi dan modernisasi adalah jalan yang harus ditempuh untuk meningkatkan status perempuan. Pandangan liberal dalam pemikiran Islam muncul karena adanya pengaruh fenimisme barat. Pandangan ini berkeyakinan bahwa jika selama ini perempuan selalu berada 10 dibawah dominasi laki-laki, maka saatnya kini perempuan menggugat dominasi laki-laki. Pandangan ini berusaha mengkritisi kembali nilai-nilai kemapanan (status quo) bahkan menggugat juga wilayah-wilayah aksiomatik (badihi) dalam Islam. Mereka bergerak dalam usaha mengubah hokum agama yang dianggap merugikan perempuan karena berkeyakinan bahwa akar ketertindasan perempuan adalah adanya tradisi dan hokum agama yang membatasi perempuan dari kesusksesan dunia public. Karena itu solusinya adalah ia harus diberi hak yang sama di semua aspek kehidupan. . Pandangan ini disatu sisi meluluhlantakan suatu sistem dominasi tapi disisi lain meneguhkan sistem dominasi yang lain. Ini tentu bukanlah jalan tengah yang mencari keseimbangan dan kesetaraan yang adil dalam hal kedudukan dan peran masing-masing jenis, laki-laki dan perempuan melainkan justru memunculkan model ketimpangan dan ketidakharmonisan social lainnya. Menanggapi fenomena ini, Nazarudin Umar mengatakan, bahwa Barat belakangan mulai mengendur dalam soal gender, sebaliknya sejumlah umat Islam yang justru bersikap lebih Barat. Dalam Islam kata Nazarudin, masalah gender sebenarnya sudah sangat jelas, yakni semangat Islam memuliakan wanita. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dipandang sama-sama memiliki kelebihan sementara gender yang diperjuangkan Barat, sebenarnya tidak menguntungkan kepada kaum perempuan Pendekatan Autokritik : Sebuah Tawaran Wanita Arab – dalam ini Islam - jauh lebih dahulu daripada Eropa dan Amerika dalam mengkritisi budaya patriarkhis. 15 abad yang lalu Ummu Salamah telah mengajukan pertanyaan begitu cerdas’ Kami masuk Islam sebagaimana laki-laki masuk Islam Kami mengerjakan apa yang mereka kerjakan, tapi mengapa mereka disebut di dalam al Quran sedangkan kami tidak ?. maka turunlah ayat yang berbunyi Kaum beriman laki-laki dan kaum beriman perempuan ... Berbeda dengan paradigma patriarkhi yang acap meredusir perempuan hanya sekedar menjadi the body, Islam sering mendeskripsikan eksistensi perempuan dalam konteks kekuatan moralitas, intelektualitas dan spiritualitas. Hal ini tercermin pada ungkapan seperti al-Ummu Madrasatun (Ibu adalah universitas kehidupan) dan al-Jannatu tahta Aqdamil Ummahati (Syurga itu berada di bawah naungan telapak kaki Ibu ). Teks-teks ini bukti pengakuan bahwa derajat perempuan memang sangat dimuliakan dalam Islam. Bahkan, 11 perempuan kemudian diakui sebagai yang paling berpengaruh dalam pembentukan peradaban sebuah generasi, sebuah posisi yang sangat strategis bila disadari. Catatan histories juga telah membuktikan bahwa dalam berbagai kasus perempuan bisa menjadi sosok yang sangat independen, penuh dedikasi bahkan nyaris terlihat seperti “tidak” memerlukan laki-laki dalam menjalankan perannya dengan sukses. Ibunda Nabi Musa dan Ibrahim merupakan figur yang dapat dijadikan referensi yang otentik untuk mendeskripsikan dedikasi seorang perempuan untuk tetap eksis, justru ketika di bawah represi laki-laki. Dan jika perempuan adalah makhluk lemah yang tak bisa memberikan kontribusi positip pada kehidupan, tentu Allah tidak akan memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan bayinya untuk berjuang hidup sendirian di Padang Gersang antara Shofa dan Marwah, Allahpun tidak mungkin menakdirkan Isa lahir dari hanya seorang perempuan, Maryam, juga Allah tidak perlu “repot-repot” menghibur dan memberi energi baru kepada Muhammad dengan Isro Mikroj karena ditinggal Khadijah. Dalam at Taubah ayat 72 Allah berfirman “ Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf (amar makruf ) dan mencegah dari yang mungkar (nahi mungkar ), melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, Sungguh Allah Maha perkasa dan Bijaksana. Dari ayat ini, dalam konteks gender, secara deskriptif perempuan diperintahkan dapat berperan pertama sebagai “mitra” yang kompetitif dan aspiratif sebagai personifikasi dari amar ma’ruf dan sekaligus – meminjam istilah Nurcholis Madjid “oposan loyal” sebagai personifikasi nahi mungkar bagi laki-laki. Sebagai Mitra Sejajar Dalam dunia nyata, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami perempuan selama ini lebih disebabkan factor internal ketakberdayaan perempuan sendiri untuk membela dirinya. Dengan kata lain terkadang disadari atau tidak, perempuan hanya pasrah dan rela atau bahkan “menyediakan diri” untuk diperlakukan sebagai obyek pelecehan. Pada tahap yang anti klimaks bahkan ada yang bersikap mashochis yang mengangap bahwa disakiti, dilemahkan memang merupakan satu bagian takdir ketika ia hadir menjadi perempuan, dan justru dengan disakiti dan dilemahkanlah ia bisa menikmati keperempuanannya. 12 Menurut Rasyid Ridlo, pembebanan kewajiban kepada laki-laki terhadap perempuan dalam hal nafkah, mahar dan melindungi merupakan sebab laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan yang kemudian menjadi semacam adat yang diterima berdasarkan akad untuk kemaslahatan. Seakan-akan perempuan menurunkan dirinya untuk tidak sama dengan lakilaki secara penuh karena pilihannya sendiri. Ia membolehkan laki-laki untuk berada pada satu tingkat diatasnya, tingkat kepemimpinannya dan ia rela dengan penggantian berupa pemberian harta dari suaminya. Untuk memperkuat pandangan ini, Will Durant – seperti dikutip Murthadha Mutahhari dalam The Right Wowen in Islam – mengatakan “ Fungsi perempuan ialah melayani kepentingan jenis, dan fungsi laki-laki adalah melayani perempuan dan anak. Mereka mungkin mempunyai fungsi lain juga, namun fungsi lain itu dengan bijaknya tunduk dapa fungsi ini; dalam tujuan tujuan yang mendasar dan setengah tak sadar inilah alam, telah menempatkan makna dan kebahagiaan. Watak perempuan adalah lebih mencari perlindungan daripada berperang dan dalam beberapa jenis, si perempuan nampaknya sama sekali tidak menaruh instink untuk berkelahi. Apabila ia berkelahi secara langsung maka itu dilakukan bukan untuk membela dirinya, melainkan justru pihak lain seperti anaknya. Perempuan lebih sabar daripada lelaki, walaupun lelaki lebih berani menghadapi masalah dan krisis kehidupan yang lebih besar, perempuan lebih memiliki ketabahan besar dalam menghadapi gangguan kehidupan yang lebih kecil dan terus menerus, tetapi perempuan juga menyukai perkelahian di pihak orang lain. Ia bersedia mengikuti seorang prajurit dan meyukai laki-laki perkasa; ada unsur mashochistis dalam getaran jiwanya apabila melihat kekuatan, sekalipun korbannya adalah dia sendiri”. Fakta lain, masuknya perempuan di sektor publik justru cenderung dimanfaatkan laki-laki untuk memperluas jiwa imperialis dan koloninya. Perempuan telah menjelma menjadi daerah eksploitasi yang bersifat pragmatis serta profit oriented yang komersiil. Kekuasaan tetaplah milik laki-laki dan perempuan tetap harus menjadi subordinat dari kepentingan laki-laki. Ini menandakan bahwa peran publik lebih menyodorkan bentuk kekuasaan di pelbagai bidang yang sangat maskulin. Idiom-idiom pembangunan publik dibingkai atas kepentingan laki-laki. Perempuan benar-benar hanya menjadi subordinat bukan komplementeer. Peran publik adalah peran politis yang mempertaruhkan prestise kemaskulinan dan kefemininan. Jika perempuan tidak hati-hati maka bisa jadi menjadi kontraproduktif. Maka sangat relevan bila dikatakan bahwa penindasan terhadap etnis perempuan adalah penindasan terpanjang sepanjang sejarah, lebih lama dari penindasan terhadap etnis manapun. Berbeda dengan penindasan lain yang acapkali menuai simpati dan 13 dukungan, penindasan terhadap perempuan cenderung dipelihara, hingga sampai saat ini bentuk penindasan hadir dalam bentuk yang tidak lagi sarkastis melainkan elastis. Penindasan ini diciptakan secara kultural maupun struktural dan penguatan mitos-mitos kultural perempuan. Sayangnya tak semua kaum perempuan memahami dan mengetahui penindasan ini atau bahkan malah menikmatinya. Bagaikan korban yang jatuh cinta pada penculiknya. Ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan di sector manapun ia berada, semestinya tak akan pernah terjadi jika saja perempuan mampu memposisikan diri sebagai mitra yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan bagi kaum laki-laki dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Mitra yang memiliki hubungan sinergi berimbang, harmonis, jauh dari semangat rivalitas yang saling menaklukan, menguasai dan mendominasi satu sama lain. Menurut Aminah Wadud, hal yang harus dilakukan perempuan modern saat ini adalah membangun relasi fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi social yang didasarkan pada semangat Al Qur’an. Dalam membangun relasi fungsional dalam kehidupan masyarakat, Wadud mengembangkan konsep diri (potensi individu) demi kemajuan hidup manusia. Kesetaraan individu merupakan kunci dalam mencapai kemajuan tersebut. Bagi Wadud ada beberapa aspek penting dalam menentukan relasi gender dalam kehidupan sosial. Yakni pertama, perspektif yang lebih adil dalam hak dan kewajiban individu baik laki-laki ataupun perempuan di dalam masyarakat. Kedua, dalam pembagian peran tersebut hendaknya tidak keluar dari prinsip umum al-Qur'an tentang keadilan sosial, penghargaan atau martabat manusia, persamaan hak di hadapan Allah, dan keharmonisan dengan alam. Ketiga, relasi gender hendaknya secara gradual turut membentuk etika dan moralitas bagi manusia. Ketiga aspek relasi gender ini menjadi prinsip utama sebuah ‘relasi fungsional’ yang tujuannya tidak lain adalah merealisasikan misi penciptaan manusia di dunia, yaitu khalifah fi al-ardi. Sebagai Oposan Loyal Dalam ayat diatas, dideskripsikan bahwa perempuan adalah “oposan loyal” yang melaksanakan peran korektif-konstruktif atau nahi mungkar terhadap kaum laki-laki. Artinya perempuan harus bisa memaknai bahwa eksistensinya di dunia ini adalah sebagai bentuk oposisi dialektis - dalam arti positif - untuk laki-laki dguna mewujudkan equilibrium. Bila secara jujur ditelusuri secara radikal, pada setiap penyimpangan moral dan sosial yang dilakukan kaum laki-laki seringkali ada pihak perempuan yang menjadi akar penyebabnya baik langsung ataupun tidak langsung, sengaja, atau tidak sengaja. Contoh 14 kongkrit, menjangkitnya penyakit KKN (korupsi dan kolusi) yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan yang kebetulan lebih banyak didominasi kaum laki-laki, bila diakui secara jujur sesungguhnya kaum perempuanlah yang ada di balik semua itu. Gaya hedonisme, konsumerisme, keinginan enak secara instan yang menjadi tuntutan sebagian kaum perempuan telah memaksa kaum laki-laki bersikap machiavellis dengan menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup pasangannya yang high cost itu, sekalipun dengan cara yang ilegal. Dalam kaitan ini, Ian Clunies Ross menggambarkan sososk perempuan sebagai jenis manusia yang belum melunasi hutangnya terhadap pengetahuan masa lalu sehingga menjadi “Nyonya besar” korban rekayasa teknologi modern. Seperti komentarnya George F Kenan ketika mengomentari pengaruh iklan terhadap pembentukan sikap hidup konsumtivisme perempuan sebagai The Greatest Evil of our nation life. Perempuan telah menjadi mangsa bisnis kaum laki-laki dan diekspolitasi untuk laki-laki. Lucunya mereka tidak pernah merasa telah melakukan dosa bagi sesama kaumnya. Karena saking biasanya dieksploitasi, perempuan menjadi keenakan di dunia yang sebenarnya tidak memberikan kebebasan lebih besar dibanding peran-peran domestik. Ini adalah kemunduran, degradasi, dekadensi dibanding masa-masa lalu. Ekploitasi kapitalisme atas perempuan tidak pernah memunculkan pemberontakan yang berarti, tidak terjadi revolusi radikal, bahkan keluhan kecil sekalipun tampaknya tak terdengar. Kebudayaaan massa telah mengobsesi perempuan tentang dunia baru yang serba instan, spontan dan absurd. Perempuan memimpikan taman firdaus diluar rumah, namun ternyata keterlibatan publik diasumsikan dengan konotasi yang tidak tepat. Sebab dunia barunya seringkali malah menciptakan neraka yang melingkari lehernya dan yang memenjarakan intuisinya. Lebih ironis lagi, keberhasilan perempuan di ranah publik, bukan saja mereka telah berhasil memasuki dunia maskulin, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai maskulin yang dikritiknya serta meninggalkan sikap kepedulian terhadap pengasuhan dan pemeliharaan. Banyak perempuan yang telah menjadi male clone (tiruan laki-laki) di peradaban modern, yaitu peradaban ekonomi pasar berdasarkan untung rugi, kompetisi, kekuasaan, materi dan eksploitasi. Status dan kekuasaan harus diperebutkan karena kesuksesan di dunia maskulin diukur oleh itu semua. Fenomena seperti itu terjadi disebabkan kaum perempuan tidak mengfungsikan peran oposannya (nahi mungkar) terhadap laki-laki, namun justru menjadi “sekutu”nya atau bahkan menyediakan diri menjadi “korban”nya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 15 dalam setiap kejatuhan sebuah masyarakat, perempuan selalu punya peran. Dalam konteks inilah paradigma ” “Wanita adalah pilar negara, jika ia baik maka negara akan menjadi baik dan bila ia buruk negara akan menjadi buruk “ menjadi menemukan relevansinya. Padahal menjadi pilar Negara berarti menjadi subyek aktif yang bermanfaat untuk menentukan nasib bangsa seperti ungkapan sang pionir, Kartini, “Perempuan itu adalah pembawa peradaban.” “Saya sendiri yakin sungguh bahwa dari perempuan itu mungkin timbul pengaruh yang besar, dalam hal membaikkan maupun memburukkan kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak membantu memajukan kesusilaan manusia.” Nah, untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang beradab, kaum perempuan harus berani bermakna mengambil peran strategis sebagai “oposan loyal”. Oposan loyal bukan asal “tampil beda” atau mengambil posisi diametral dan kontraversial yang menjadikan laki-laki sebagai “musuh’ atau “lawan” yang vis a vis dengan dirinya. Melainkan menfungsikan kefemininitas sebagai simbol nilai-nilai kelembutan yang persuasif untuk kepentingan nahi mungkar agar kaum laki-laki tidak menggunakan energi kemaskulinannya (kekuatannya) untuk membuat kerusakan (fasad) tetapi justru untuk melindungi nilai-nilai humanisme dan kebenaran. Apalagi, peradaban manusia modern semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi dan mengeksploitasi. Kerusakan alam, perkosaan terhadap bumi, kriminalitas, dan menurunnya solidaritas. Carolyn Merchant - seperti dikutip Vandana - ilmu alam modern, semuanya didasarkan pada pengrusakan dan penguasaan atas alam. Muncullah subordinasi, penindasan dan eksploitasi terhadap alam yang dilakukan guna mengungkapkan dan menghancurkan rahasia alam. Bahkan Francis Bacon menyatakan ”alam harus dipaksa dengan kekerasan untuk mengungkap tabir rahasia yang disembunyikannya, karena alam bagaikan seorang perempuan jahat yang menumpuk harta dengan serakah untuk dirinya sendiri”. Peradaban modern telah begitu tak seimbang, terlalu berat pada kualitas maskulin dan kurang pada kualitas feminine seperti cinta, pengasuhan dan pemeliharaan, karenanya kualitas feminine harus dapat ditingkatkan agar bisa menjadi penyeimbang (oposisi) agar semua kerusakan dapat dikurangi. Perempuan hendaknya menyadari bahwa sifat dan kualitas feminin bukan sesuatu yang rendah, justru sebaliknya Allah menciptakan kualitas kefemininan ini sebagi potensi keperempuanan yang perlu dijaga dalam arti yang aktif positif serta kreatif. Kualitas feminin bukanlah bentukan kultur dan struktur melainkan kodrat keperempuanan; kodrat yang harus diterima sebagai sebuah keniscayaan adanya. Dan justru dalam diri keperempuananlah 16 keseimbangan dualitas di muka bumi ini tercipta. Di bumi ini tidak hanya hadir prinsip “berjuangan” dan “memberi” yang tersimbolkan dalam maskulinitas namun juga “menerima” dan “memelihara” sebagai simbol femininitas. Agar kekuatan tidak menjelma menjadi kekerasan, maka harus pula berbarengan dengan kelembutan dan kasih. Dalam kosmologi Islam, bumi adalah lambang menerima, penuh kasih, pasif dan damai. Inilah sifat-sifat feminin. Kodrat tentu tidak bisa dilawan melainkan dikembangkan. Kemampuan manusia merekonstruksi gender feminin dan maskulin tak akan merubah substansi kualitas gender : kodrat. Bagaimanapun Islam tidak mengenal paradigma gender yang strukturalis yang melihat relasi pria dan perempuan sebagai hubungan atas dan bawah, antara inferior dan superior yang saling menguasai, tetapi sebagai hubungan fungsional ekuivalen yang saling melengkapi. Perbedaan laki-laki dan perempuan memang bukan semata-mata karena konstruksi sosial budaya namun juga intrinsik. Karenanya, yang perlu dilakukan adalah membangun paradigma bahwa yang seharusnya terjadi adalah penerimaan yang setara dari masyarakat tentang kefemininan perempuan dan segala hal yang secara sadar diketahui sebagai konstruksi kekhasan biologis perempuan. Untuk meruntuhkan sistem patriarki, hendaknya perempuan melakukan transformasi sosial melalui perubahan internal yang revolusioner, yaitu dengan menonjolkan kualitas feminin dalam dunia maskulin. Keberadaan kualitas feminin inilah yang dapat mengubah sistem patriarki yang hierarkis dan dominatif menjadi sistem matriarki yang egaliter. Kaum perempuan harus meningkatkan kualitas feminin mereka agar dominasi sistem maskulin dapat diimbangi, sehingga kerusakan (fasad), dekadensi moral dapat dikurangi Memang ada pandangan yang berbeda dari pegiat gender, yang mengangap bahwa romantisme terhadap kualitas feminin justru akan menyebabkan perempuan tetap pada posisinya sebagai figur pengasuh, pasif, dan pemelihara yang akhirnya cocok untuk menjadi ibu dan pekerjaan-pekerjaan di sektor domestik. Seperti tesis Simone de Beauvoir yang mengatakan “Norma-norma feminine yang melekat pada perempuan seperti mengasuh, memelihara, dan menerima adalah sifat yang dikulturkan oleh system patriarkhi. Kulturisasi norma feminine dilanggengkan oleh sitem agar perempuan dapat terus ditindas”. Namun demikian pengingkaran terhadap femininitas justru tidak akan meruntuhkan sistem patriarki dan jika perempuan memaksa diri untuk mengadopsi kekuatan maskulin justru hanya akan membuat perempuan menjadi tiruan laki-laki (male clone) di dunia maskulin. 17 Berbagai dilema publik tentang makna keadilan dalam diskursus gender, menurut hemat penulis harus lebih dulu dikaji sehingga tidak menemukan makna yang kontradiktif. Keadilan sebagaimana diusung feminis Barat, tidak akan menemukan kata final. Baik secara nature maupun nuture pria dan perempuan tidak bisa sama, sifat bergantung dan saling mengisi akan selalu hadir. Sebuah ”penampakan” yang nyata bahwa independensi masingmasing pihak adalah sebuah kemustahilan. Kesetaraan tidak berarti kesamaan (sameness) yang hanya menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil, yang sesuai dengan konteks masing-masing individu. Keadilan memang harus disesuaikan dengan jatidiri perempuan itu sendiri. Karena ada dari sebagian perempuan merasa ‘diperlakukan secara adil’ justru ketika disibukkan dengan urusan rumah tangga, suami, dan anak-anaknya. Propaganda bahwa bicara gender berarti bicara perempuan di dunia public, sesungguhnya justru penjajahan bagi sebagia perempuan, karena dituntut untuk go public, padahal sebagian mereka sudah merasa nyaman ketika berada di rumah. Fenomena semacam inilah yang disebut oleh Ratna Megawangi sebagai “Contradictio Interminis“. Sebuah konsep yang menginginkan kebebasan individu (liberty), yang justru dalam prakteknya dapat membuat individu menjadi tidak bebas atau tertindas. Padahal liberty menurut John Stuart Mill, adalah kondisi di mana setiap individu laki-laki dan perempuan dapat berfungsi secara bebas, dapat mengembangkan kediriannya secara komplet, serta dapat meningkatkan kepandaiannya sesuai dengan kapasitas dan karakternya masing-masing Sejatinya, hakekat wanita sangat berbeda dengan pria dari segi nature-nya (alami). Sedangkan perbedaan nuture adalah hasil konstruksi masyarakat yang bermula dari adat dan budaya. Pernyataan yang sering dilontarkan kaum feminis adalah bahwa diskriminasi pada wanita karena adanya faktor budaya, di mana budaya patriarki selalu menempatkan wanita pada posisi yang lebih rendah dari pria. Dan kendala besar yang diakui feminis untuk dapat berkiprah setara dengan pria adalah karena hanya wanita saja yang bisa hamil. Pengakuan ini dapat berarti keragaman biologis memang selalu ada dalam kenyataan, maka kesetaraan gender yang selalu dipropagandakan secara fifty-fifty adalah suatu hal yang utopis. Perbedaan fisiologis yang alami itu pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada. Perkembangan wanita dari berbagai segi disesuaikan dengan bakatbakat kewanitaan. Sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat tradisional, norma- norma agama, dan kriteria-kriteria feminis tertentu. Perbedaan eksistensi antara keduanya akan tetap ada meskipun struktur-struktur sosial yang ada dan norma-norma tradisionalnya telah berubah. Akhirnya pilihan peran 18 memang bukan persoalan bagi perempuan selama perempuan sanggup melakukannya untuk kebaikan keluarga, pengembangan kreativitas, kapasitas dan kapabilitas dirinya dan keseimbangan struktur makrokosmos. Bagaimanapun disinilah substansi persoalannya. Melakukan sebuah pilihan tentu harus didasarkan pada kondisi obyektif dan nalar yang matang. Dan hal itu harus dilakukan oleh perempuan sendiri DAFTAR PUSTAKA Aden Wijdan SZ, dkk, Pemikiran dan Peradaban Islam, Safirian Insania Press, Yogyakarta, 2007. Agus Purwadi, Islam dan Problem Gender, Aditya Media, Yogyakarta, 2000. Ahmad Fudhaili, Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadis – Hadis Shahih, Pilar Religia, Yogyakarta, 2005 Aminah Wadud, Qur’an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, PT Serambi Ilmu Semesta, 2001. Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan, Setara Di Hadapan Allah, Reflasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi, LSPPA Yayasan Prakarsa, Yogyakarta, 1995. Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Karen Amstrong, Sejarah Tuhan, Mizan, Bandung, 2007. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Muhammad Rasyid al Uwayyid, Min Ajli Tahrir Haqiqi lil Mar’ati, Terj. Ghazali Mukri, Izzan Pustaka, Yogyakarta, 2002. Murtadha Muthahhari, The Right of Women in Islam, Terj. M.Hashem, Lentera. Jakarta, 2001. M. Subhi Ridlo, Perempuan, Agama dan Demokrasi, LSIP, Yogyakarta, 2007. Nawal el Saadawi, Wajah Telanjang Perempuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Sachiko Murata, The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam, Mizan, Bandung, 2004. Vandana Shiva dan Maria Mies,Ecofeminisme, Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, IRE Press, Yogyakarta, 2005. 19 20