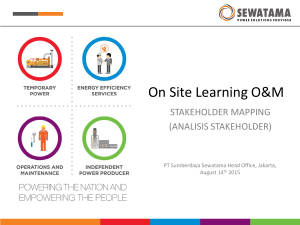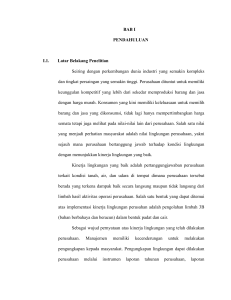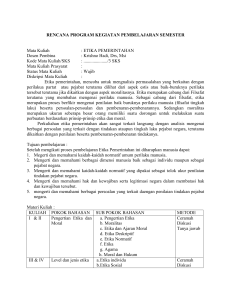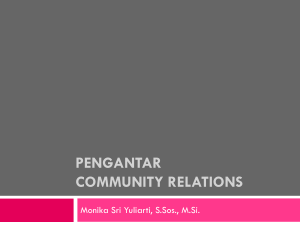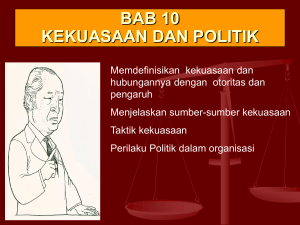Bab 1 Pendahuluan
advertisement

Bab 1 Pendahuluan A. Latar Belakang Kemunculan adat sebagai sebuah kekuatan baru yang menyandarkan diri pada legitimasi adat di era reformasi yang telah berlangsung semenjak 1998, adalah fenomena yang agaknya tidak diramalkan sebelumnya oleh para pengamat di Indonesia (Henley dan Davidson, 2010: 2). Betapa tidak, bersamaan tahun dengan diciptakannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, produk hukum yang berusaha menjawab tuntutan daerah-daerah agar kekuasaan yang semula mengumpul di pusat didistribusikan ke daerah-sebagai salah satu prasyarat demokratisasi yang dilangsungkan pasca lengsernya Soeharto-, sebuah tuntutan bernada provokatif dihasilkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam kongres pertamanya di Jakarta pada Maret 1999. Tuntutan itu berbunyi: “Kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara!” Tuntutan AMAN tersebut menggambarkan bagaimana adat sebagai sebuah kekuatan yang pernah berpengaruh secara sosial-politik paling tidak hingga masa pemerintahan colonial Belanda, merespon pergeseran kekuasaan yang terjadi di ibukota: bahwa pendistribusian kekuasaan ke daerah-daerah di era reformasi mesti dilangsungkan dengan melibatkan entitas tradisional yang bernama adat. Apa yang digaungkan oleh AMAN, kemudian menjadi semacam inspirasi bagi komunitas-komunitas tradisional yang menyandarkan diri pada legitimasi adat di banyak daerah di Indonesia guna mewujudkan tuntutan yang sama di aras lokal. Semenjak tuntutan adanya pengakuan Negara atas adat yang dilontarkan oleh AMAN, gerakan adat dengan berbagai varian, muncul di banyak daerah di Indonesia. Masyarakat adat yang mengalami marginalisasi pada masa orde baru, berusaha untuk mengembalikan hak-haknya yang terampas oleh Negara dengan cara membangun solidaritas kolektif. Tujuannya, untuk mewujudkan kembali komunitas masyarakat adat yang pernah eksis pada masa lampau, yang mampu 1 mengatur dirinya sendiri secara mandiri (self governing community) serta mempunyai sumber daya (ekonomi) yang dapat didistribusi dan diredistribusikan untuk kesejahteraan anggota masyarakatnya (Hudayana, 2009). Para pemimpin adat yang di masa sebelum berdirinya republik berada di struktur teratas masyarakat adat, juga bermunculan kembali untuk mengembalikan kekuasaan yang pernah mereka punyai. Keuntungan-keuntungan sosial, politik, ekonomi, yang mereka genggam sebagai entitas yang memiliki kekuasaan karena statusnya sebagai elit di masyarakat adat, menjadi tujuan umum para pemimpin adat tersebut memunculkan diri kembali. Status sebagai pemimpin atau anggota masyarakat adat juga digunakan sebagai alat untuk “menempel” pada Negara dan mengakses sumber daya serta fasilitas yang dimiliki oleh Negara. Meskipun sama-sama menggunakan adat sebagai landasan untuk kembali muncul, dapat dilihat dari penjabaran singkat di atas bahwa gerakan adat di Indonesia bersifat heterogen. Mereka berbeda terutama pada aktor dan tujuan gerakan. Yang pasti, semenjak kongres pertama AMAN yang terkenal dengan slogan mengenai tuntutan pengakuan negara terhadap adat, serta diterbitkannya UU pemerintahan daerah yang praktis mengubah formasi kekuasaan di tingkatan lokal pada 1999, adat dalam politik di Indonesia hadir dalam pelbagai bentuk; kelahiran kembali pemerintahan Nagari di Sumatera Barat; kemunculan desa Pakraman serta Pecalang di Bali; gerakan-gerakan masyarakat adat menuntut kembali tanah ulayatnya yang dirampas oleh negara pada masa Orde Baru misalnya yang terjadi di Papua dan Kalimantan; atau kebangkitan para pemimpin adat dengan memanfaatkan statusnya sebagai puncak dari hierarkhi masyarakat adat yang berusaha kembali meraih kekuasaan di banyak daerah di Indonesia. Di Lampung, fenomena terakhir yakni kemunculan para pemimpin adat yang lazim disebut Penyimbang atau Saibatin1, juga berlangsung secara massif. Perubahan kekuasaan di level pusat juga segera direspon para penyimbang adat 1 Penyimbang, adalah sebutan bagi orang yang memiliki status tertinggi dalam struktur pemerintahan adat di Lampung yang diwariskan secara genealogis. Istilah penyimbang, lebih banyak digunakan oleh masyarakat bersub suku Lampung Pepadun. Sementara masyarakat dengan sub suku pesisir/ peminggir menyebut pemimpin adatnya sebagai saibatin (satu pemimpin). Namun karena istilah penyimbang juga dikenal pemakaiannya di masyarakat Lampung Pesisir, maka penulis memutuskan untuk memakai penyimbang sebagai sebutan bagi para pemimpin adat agar lebih umum. Konsep mengenai kepenyimbangan, akan dibahas di bab dua. 2 yang setidaknya hingga masa Pemerintahan Kolonial Belanda, merupakan entitas puncak pada masyarakat adat di Lampung. Penggalian ulang makna adat, penegasan kembali kepemimpinan adat, hingga penentuan batas-batas wilayah kekuasaan adat dilakukan guna merespon perubahan politik di aras pusat. Seperti di daerah-daerah lainnya di Indonesia, kemunculan kembali para penyimbang adat tersebut semakin massif semenjak terbitnya UU 22/ 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya, terdapat pasal yang menyatakan bahwa negara mengakui hak asal usul yang memungkinkan pemerintahan-pemerintahan “asli” di daerah-daerah untuk muncul kembali sepanjang masih “diakui” oleh masyarakat setempat. Pengakuan tersebut misalnya dapat dilihat pada Pasal 18B ayat 2 yang bunyinya: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal pengakuan negara dalam UU 22/99 tersebut, menjadi celah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin pemerintahan-pemerintahan “asli” di daerahdaerah untuk muncul kembali. Pengakuan tersebut agaknya menjadi semacam udara yang terlalu segar untuk tidak dihirup, termasuk oleh para penyimbang di Lampung yang kekuasaannya telah tergerus sedemikian rupa secara bertahap dalam periode yang merentang sejak masa kolonial hingga Orde Baru. Menurut catatan penulis, usaha para penyimbang di Lampung untuk menegaskan kembali kekuasaannya, bahkan telah berlangsung segera setelah lengsernya Soeharto dari kekuasaan. Dari telaah literatur yang penulis lakukan, penegasan kembali wilayah adat serta penegasan penyimbang sebagai entitas pemilik kekuasaan tertinggi adat, telah dilakukan oleh para penyimbang adat di Marga Pugung, Lampung Barat, hanya berselang sebulan setelah Soeharto sebagai simbol sentralisasi kekuasaan Orde Baru, dijatuhkan pada Mei 1998. Otoritas kekuasaan penyimbang adat, wilayah kekuasaan adat dan wewenang pemberian gelar adat, diatur kembali oleh para penyimbang dari Marga Pugung dalam sebuah surat keputusan bersama yang 3 didapuk sebagai “undang-undang” yang berlaku bagi seluruh masyarakat adat di Marga Pugung, Lampung Barat2. Secara singkat, patutlah diambil kesimpulan awal bahwa telah terjadi perubahan politik di aras lokal Lampung pada era reformasi dengan kemunculan aktor baru yang melandaskan dirinya pada legitimasi kekuasaan tradisional (baca: adat). Namun sayangnya perubahan politik lokal di Lampung itu tidak ditanggapi dengan kajian yang berusaha membahas bagaimana dampak kemunculan para penyimbang adat yang sedikit demi sedikit telah berhasil membuat kehadirannya di masyarakat kembali menjadi penting tersebut-paling tidak sebagai entitas tertinggi di hierarkhi adat yang layak dihormati-terhadap wajah sosial politik di Lampung. Dari telaah literatur yang penulis lakukan misalnya, kajian-kajian mengenai adat Lampung pembahasannya masih melulu dikaitkan dengan adat sebagai budaya an sich. Tanpa mengaitkan kehadiran adat (dan pemimpin adat) dengan politik secara lebih lanjut. Padahal dalam konteks kontemporer, para penyimbang adat mulai menjadi entitas yang punya peranan di aras politik lokal. Misalnya sebagai pihak yang melegitimasi kekuasaan modern dengan kekuasaan tradisional dengan “menempelkan” kekuasaan tradisional yang mereka miliki kepada pemimpin institusi modern-terutama partai dan pemerintah daerah-lewat mekanisme pemberian gelar adat. Karenanya, studi ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah tawaran literatur mengenai tema yang telah banyak mendapat pembahasan: kemunculan elite lokal yang menyandarkan diri pada legitimasi kekuasaan tradisional seiring dengan dilokalkannya kekuasaan yang semula memusat pada masa orde baru. Penulis mafhum bahwa ada kegelisahan mengenai teks-teks yang membahas adat dan politik yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kajian-kajian yang membahas mengenai kebangkitan politik tradisi, atau bagaimana adat direvitalisasi di ranah lokal pasca kejatuhan Orde Baru (Bayo, 2010: 2). Persis seperti yang hendak dilakukan oleh tesis ini. Namun sebagai usaha awal di tengah 2 Penjabaran mengenai kasus Marga Pugung, Lampung Barat ini akan dijelaskan lebih lanjut di Bab 2. 4 kelangkaan kajian mengenai adat dan politik dalam konteks Lampung, kajian mengenai para penyimbang adat di Lampung tetap punya arti penting. B. Rumusan Masalah Pertanyaan besar yang hendak dijawab dalam studi ini adalah mengenai “Bagaimana Strategi Penyimbang-penyimbang Adat di Lampung Untuk Meraih Kekuasaan di Era Reformasi?” Hasil utama yang ingin dicapai dari pertanyaan penelitian di atas adalah menjelaskan strategi yang dilancarkan oleh para pemimpin adat (Penyimbang) di Lampung guna meraih kekuasaan di era reformasi, serta implikasinya bagi wajah sosial politik lokal di Lampung. C. Kerangka Teori Kemunculan elit lokal yang menyandarkan diri pada kekuasaan tradisionaltermasuk pemimpin adat-sebagai fenomena politik di Indonesia di tataran lokal, muncul secara massif pasca Soeharto tumbang dari kekuasaannya. Dengan jatuhnya Soeharto, praktis simbol sentralisasi kekuasaan memudar, bahkan bisa dikatakan hilang. Pudarnya pemusatan kuasa ini kemudian dipandang sebagai celah bagi elit-elit lokal dengan berbagai bentuk legitimasi kekuasaan, termasuk adat, untuk kembali hadir dan merebut lagi kekuasaannya. Fenomena kemunculan elit-elit lokal-termasuk pemimpin adat-tersebut lebih masif seiring dengan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi yang disertai dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah operasional baru. Agaknya, perubahan konstitusional tersebut membuat elit-elit yang berlandaskan adat dan tradisi yang pada masa orde baru kehadirannya biasanya hanya dimaknai tak lebih sebagai simbol-simbol kebudayaan dan pariwisata, merasa memiliki momen untuk menegaskan lagi kuasanya. Bagian ini akan membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam kajian ini. Pertama, akan dibahas mengenai literatur-literatur yang menawarkan teori mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh elit-elit tradisional pasca 5 orde baru. Kajian ini terutama akan meminjam teori yang ditawarkan oleh Greg Accaioli dan Gerry Van Klinken (akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya). Namun teori-teori yang ditawarkan oleh kajian-kajian sebelumnya mengenai kemunculan pemimpin tradisional yang akan segera penulis jabarkan, juga akan penulis pinjam sebagai pisau analisa yang berguna untuk membedah strategi yang dilakukan oleh para penyimbang adat. Dengan demikian, pendedahan mengenainya diharapkan dapat lebih komprehensif. Di bagian ini pula, akan dijabarkan mengenai teori-teori mengenai dua hal yang menjadi tema besar dalam tulisan ini yakni kekuasaan dan adat. Memetakan Strategi Para Pemimpin Tradisional Dwipayana (2004) dalam bukunya “Bangsawan dan Kuasa”, membahas fenomena kembalinya kuasa kaum bangsawan di dua kota, yakni Surakarta dan kota Denpasar. Dalam bukunya tersebut, Dwipayana berargumen bahwa kembalinya kekuasaan bangsawan tradisional di Surakarta dan Bali merupakan dampak dari bergesernya formasi kenegaraan serta formasi sosial sebagai implikasi dari proses transisi politik paska 1998. Melemahnya legitimasi negara (orba), serta usaha untuk menyebarkan kekuasaan ke daerah-daerah, menyebabkan timbulnya konflik baik antara daerah dengan pusat, ataupun antara entitas-entitas elit lokal dengan modal kuasanya masing-masing. Di sini, lebih lanjut menurut Dwipayana, bangsawan tradisional termasuk salah satu entitas elit lokal yang siap. Karena meskipun legitimasi kekuasaan mereka tergerus habis, berturut-turut oleh kolonial, kekuatan politik baru pada masa orde lama, maupun oleh orde baru, kemampuan mereka untuk survive pada era-era sebelum jatuhnya Soeharto tersebut menciptakan “kekenyalan” tersendiri bagi mereka untuk segera mengonsolidasikan kekuatan dan memasuki arena kekuasaan baik politik, negara, dan ekonomi. Memori kolektif masyarakat akan kejayaan masa lampau kekuasaan keningratan tradisional, dijadikan basis untuk menciptakan tuntutan-tuntutan “wajar” terhadap pengakuan akan kebangkitan mereka. Dengan menggunakan sisa-sisa sumber daya ekonomi yang tersisa berupa tanah-tanah kraton, serta dengan 6 mengeksploitasi status keningratan yang dilekatkan pada dirinya, keluarga ningrat-ningrat di Bali dan Surakarta berafiliasi dengan institusi demokrasi modern guna merebut kekuasaan politik. Keberhasilan mereka menembus sekat-sekat kekuasaan modern ini, kemudian mereka gunakan untuk mengembalikan legitimasi kekuasaan tradisional mereka dengan mengukuhkan kembali fungsi kraton sebagai pusat kekuasaan melalui perjuangan di level kebijakan. Tentu saja, pengukuhan kembali keberadaan mereka sebagai sentra kekuasaan kemudian diarahkan pada kebutuhan untuk mengakumulasi kapital dengan meraih kembali akses-akses ke ekonomi. Savirani (2004) mengeksplorasi kemunculan tiga elite lokal di tiga daerah; sultan di Yogyakarta yang mewakili aristokrasi; bupati di Bantul, Yogyakarta yang berasal dari kalangan pebisnis; serta ketua DPRD di Buleleng, Bali yang adalah politisi. Perbedaan basis legitimasi antara ketiganya, menyebabkan perbedaan strategi yang dipilih oleh mereka untuk kembali meneguhkan kekuasaannya. Sultan Hamengkubuwono X yang mewakili kalangan elite yang memiliki legitimasi kultural-tradisional, berusaha untuk mengukuhkan kehadirannya dengan mendesak rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta ke pemerintah pusat. Meskipun basis kekuasaan internal berupa legitimasi kultural telah melekat sedemikian kuat pada Sultan, RUU keistimewaan menjadi penting untuk meyakinkan legitimasi kultural tersebut “dilegalkan” oleh negara. Kajian yang lain mengenai kembalinya pemimpin adat juga dihasilkan oleh Haboddin (2009). Dalam tesisnya yang berjudul “Karaeng Dalam Pusaran Politik di Jeneponto,” ia memaparkan kebangkitan bangsawan tradisional Makassar yang lazim disebut Karaeng, dengan disokong terutama oleh basis kekuasaan tradisional yang menempatkannya di hierarki teratas dalam masyarakat serta basis ekonominya sebagai pemilik tanah dan usaha garam. Haboddin melihat bahwa kekuasaaan Karaeng mulai melemah ketika negara (orde baru) menguat dan menggeser posisi mereka. Dalam kasus Jeneponto, pada masa orba, Karaeng kemudian ditempatkan hanya sebagai pengorganisir institusi-institusi lokal.Itupun ketika peran mereka diperlukan oleh negara, misalnya pada saat pemilihan umum 7 untuk memenangkan partai yang berkuasa pada saat itu (Golkar). Selebihnya, Karaeng hanya menjadi simbol. Karaeng mulai menemukan kembali celah untuk kembali merebut kekuasaan normal paska lengsernya Soeharto dari kursi kekuasaan orba. Mereka menggali ulang konstruksi budaya yang menempatkan mereka sebagai entitas yang menempati posisi teratas dalam masyarakat. Ini kemudian menjadi modal yang signifikan sebagai bahan pertimbangan institusi-institusi modern untuk menaruh mereka dalam posisi teratas di hierarki institusi, misalnya saja sebagai pemimpin partai-partai yang banyak bermunculan pada masa demokratisasi, atau paling tidak sebagai calon anggota legislatif yang dianggap pasti mendulang suara yang banyak oleh partai. Selain itu menurut Haboddin, akses mereka ke ekonomi yang masih bisa mereka pertahankan saat peran mereka sebagai pelaksana pemerintahan dihapus sedemikian rupa, menjadi modal lain yang juga turut memuluskan jalan untuk memantapkan kehadiran mereka. Citra mereka sebagai pemimpin murah hati (benevolent leader) yang rela berkorban dengan memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan, misalnya dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang masih tersisa yakni tanah dan usaha garam, berhasil menempatkan mereka di posisiposisi strategis dalam jabatan-jabatan penting di politik dan birokrasi. Dan seperti pemimpin adat yang lain, kekuasaan modern yang berhasil mereka raih kemudian digunakan untuk menciptakan mitos-mitos baru guna meneguhkan status baru mereka sebagai entitas yang wajar memimpin institusi-institusi kekuasaan modern karena rekam jejak mereka sebagai pemimpin pada masa lampau. Sementara itu studi yang dilakukan oleh Abdullah (2006), meneliti mengenai strategi yang dilakukan oleh kesultanan Ternate guna memenangkan percaturan politik di ranah lokal. Simbol-simbol identitas adat hingga pengerahan masyarakat adat, digunakan oleh para pemimpin adat di kesultanan Ternate untuk meraih tampuk kepemimpinan lembaga politik modern (partai politik). Pilihan strategi merebut kekuasaan politik modern tersebut dilancarkan untuk meyakinkan usaha untuk memunculkan kembali peranan mereka di ranah lokal dapat dikuatkan 8 dengan legitimasi yang mereka dapat dari lembaga politik modern yang telah berhasil mereka rebut. Buku yang khusus membahas mengenai fenomena kebangkitan adat di Indonesia paska orde baru adalah “Adat Dalam Politik Indonesia.” 14 tulisan mengenai kemunculan (masyarakat) adat, dibahas dengan cara yang beragam. Dalam pengantarnya di dalam buku ini, Henley dan Davidson (2010) menyebutkan bahwa reorganisasi administrasi besar-besaran oleh proyek otonomi daerah di satu sisi serta pelaksanaan demokrasi elektoral di sisi yang lain, membuka ruang politik yang amat besar di tataran lokal. Lagi-lagi, terutama disebabkan oleh bayangan-bayangan masa lampau mengenai kejayaan mereka, pemimpinpemimpin adat di banyak daerahlah yang berjuang paling keras guna memenangkan kontrol atas Negara pada tingkat lokal. Kemunculan kembali adat dalam banyak bentuknya di Indonesia tersebut, menurut merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai pihak mana yang memenangkan pertarungan untuk mengendalikan sumber daya lokal paska berakhirnya sistem Negara sentralistik. Menurut mereka, yang paling siap untuk maju untuk bertarung adalah orang-orang yang secara adat memiliki kelebihan karena memenuhi syarat legitimasi kekuasaan tradisional. Pemimpin-pemimpin adat yang memiliki legitimasi kekuasaan tradisional, melihat keruntuhan rejim orde baru secara tidak terduga sebagai momen yang harus dipergunakan secara cepat untuk mendorong kebangkitan adat. Lebih lanjut, Henley dan Davidson menjelaskan bahwa kemunculan adat dalam politik di Indonesia secara massif paska turunnya Soeharto tak lain karena adat, yang utamanya berkaitan dengan tiga hal –sejarah, tanah, dan hukum- merupakan hal yang mendahului hukum-hukum yang berlaku sekarang. Karenanya, ketika ada celah untuk memunculkan kembali kejayaan adat, yang mendahului segala hukum yang berlaku sekarang itu, maka tiap masyarakat adat, dengan caranya masing-masing berusaha untuk memanfaatkannya. Tak jarang cara-cara kekerasan dilakukan oleh masyarakat adat untuk mendesakkan pelaksanaan (kembali) hukum adat atau pemberlakuan unsur-unsur adat dalam wilayah kampung halaman mereka. 9 Dua tulisan di dalam buku ini yang menurut penulis berguna untuk mengerangkai kajian ini adalah Van Klinken (2002) dan Greg Accaioli. Tulisan Klinken yang berjudul “Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian Dalam Politik Lokal,” menjabarkan fenomena usaha para keturunan kerajaan/ kesultanan di pelbagai daerah Indonesia yang berusaha untuk menggali, membangkitkan, atau malahan menaikkan pamor kesultanan mereka yang dalam kurun waktu yang lama “istirahat”. Identitas, dengan berbagai cara dibangkitkan kembali. Ketika identitas tersebut tak lagi memiliki akarnya, pilihan yang paling masuk akal kemudian adalah “menemukan kembali”. Berbagai ruang, digunakan oleh para sultan tersebut untuk kembali menempatkan dirinya sebagai bagian penting di masyarakat. Kesultanan yang memiliki legitimasi kekuasaan tradisional yang kuat seperti Yogyakarta, mampu menggunakannya untuk mendesak pemerintah pusat melalui rancangan Undang-undang Keistimewaan yang salah satu isi pentingnya adalah membuat sultan secara otomatis menjadi Gubernur. Sedangkan yang lemah, mesti rela membangkitkan kembali eksistensinya dengan misalnya memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat bupati oleh organisasiorganisasi yang berlandaskan adat. Ketika legitimasi serta sumber daya yang dipegang oleh masyarakat adat tidak begitu signifikan, maka yang logis untuk dilakukan adalah dengan “menempel” pada kekuatan-kekuatan di luar adat yang dianggap potensial untuk merebut kekuasaan politik, atau bahkan menempel pada penguasa politik itu sendiri. Tentu saja pertukaran kepentingan, terutama kepentingan ekonomi serta legitimasi untuk muncul kembali, menjadi landasan organisasi-organisasi berorientasikan adat tersebut memberikan dukungannya. Klinken, juga menjelaskan bahwa kembalinya para Sultan, bahkan dengan menempel kekuasaan, paling tidak dilakukan sebagai usaha untuk meraih peran minimal sebagai simbol masyarakat tradisional yang berperan dalam pelaksana tradisi dan kebudayaan. Meski, kebanyakan dari para Sultan tersebut jelas tidak hanya menginginkan peran minimal tersebut, namun berambisi membangun kembali kerajaannya yang tergerus habis-habisan oleh modernitas. Van Klinken, selanjutnya menerangkan bahwa terkadang beberapa pemimpinpemimpin adat secara sadar mengubah mitos-mitos tentang pemerintahan (adat) 10 hanya untuk membangun kembali kejayaannya yang telah digerus oleh modernitas dan rejim. Rekonstruksi kejayaan kepemimpinan adat ini bahkan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin adat yang kerajaannya telah lama hilang. Pemunculan kembali legitimasi kekuasaan pemimpin-pemimpin adat dengan menemukan kembali (reinvent) definisi mengenai adat tersebut menurut Van Klinken selain sebagai usaha untuk menciptakan kembali kuasa adat tradisional dalam masyarakat, juga dimaksudkan untuk menciptakan simbol-simbol sentralisasi kekuasaan baru yang menggantikan simbolisasi kuasa orde baru, namun dalam lingkup lokal. Greg Accaioli (2010), masih dalam buku Adat Dalam Politik Indonesia (2010), menyebut bahwa ada dua strategi yang dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin adat, yakni “officializing strategy” atau strategi yang diformalkan dan strategi oposisi. Menurut Accaioli, strategi pertama dilakukan oleh masyarakat adat dengan memanfaatkan hubungan-hubungan formal maupun informal dengan administrator-administrator di daerah. Tujuannya, tambah Accaioli, tak lain adalah untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah atas kehadiran adat dengan cara “menempel pada negara”. Sementara strategi oposisi dilakukan dengan berusaha memperoleh klaim atas adat mereka bukan bagian resmi dari struktur resmi pemerintahan, tetapi sebagai bentuk paralel yang juga berkedaulatan, yang haknya perlu dijamin. Penelitian ini, terutama bersandar pada argumen Van Klinken dan Accaioli tersebut di atas. Adat sebagai sesuatu yang “cair”, yang dapat dimaknai ulang untuk kemudian dijadikan basis legitimasi bagi para pemimpin adat (Sultan dalam tulisan Van Klinken) guna memunculkan kembali peranannya sebagai simbol tertinggi dalam masyarakat misalnya, penulis anggap berguna untuk menjelaskan fenomena pemaknaan ulang konsep-konsep adat yang dilakukan oleh para penyimbang adat untuk membangkitkan kembali kekuasaan tradisionalnya. Argumen Accaioli mengenai “officializing strategy” para pemimpin masyarakat adat guna mendesakkan kembali peran sentralnya dengan memanfaatkan aksesnya ke pemimpin-pemimpin serta pejabat kekuasaan formal, juga saya pinjam untuk menjelaskan fenomena pelembagaan adat serta pelekatan gelar adat ke pemimpin 11 formal di Lampung. Sebaliknya pula seperti yang dijelaskan Accaioli, kekuasaan formalpun harus bernegoisasi dengan kekuasaan informal (adat) guna memperkuat legitimasi kekuasaannya sendiri. Artinya, negara (pemerintah daerah dalam tulisan ini) tidak seperti pada masa orde baru, kemudian tidak lagi menjadi kekuatan sentral dan utama dalam konteks politik (lokal) paska orba, sehingga harus mempertimbangkan untuk memberikan ruang khusus bagi kekuatan lain di luar dirinya. (Kepemimpinan) Adat Sebagai Sumber Daya Minimum Secara umum, adat dipahami sebagai kebiasaan, “set of beliefs,” atau tradisi, yang mengatur tata laku dalam kehidupan masyarakat. Wignjodipuro (1989) mengatakan bahwa adat merupakan pencerminan dari kepribadian satu (suku) bangsa yang didapat dari proses persetujuan dari abad ke abad. Di sini, adat lebih dilekatkan dengan identitas. Artinya, adat kemudian menjadi hal utama untuk membedakan satu (suku) bangsa dengan yang lain. Selain itu, adat kemudian berhubungan dengan bagaimana masyarakat menjalankan “laku”nya berdasarkan kesepakatan yang kemudian didefinisikan dalam satu aturan tertentu, lisan maupun tulisan, termasuk mengenai kepemimpinan, dalam adat. Dalam konteks Indonesia, Burns (2010) menjelaskan bahwa terma adat mulai mendapat perhatian dari banyak pihak terutama setelah Cornelis van Vollenhoven (1876- 1972), pendiri Mazhab Leiden mengidentifikasikan adat dengan recht (hukum). Van Vollenhoven memahami adat dan hukum adat (adatrecht) sebagai manifestasi dari pandangan hidup yang khas Indonesia, dan karenanya, asing bagi cara pikir Eropa. Adat, menurutnya, kemudian adalah sesuatu yang mendahului semua hukum (dalam konteks Indonesia). Karena, ada unsur-unsur mendasar di dalam adat yang telah menyatukan masyarakat dalam lingkup tertentu di Indonesia dalam satu identitas, kebiasaan, serta laku tersendiri yang secara bersamaan memisahkan mereka dari lembaga-lembaga hukum Eropa. Wignjodipuro (1989, ibid) sendiri menjelaskan bahwa dari perspektif hukum, adat dipandang sebagai “hukum non statutair” karena pada umumnya, adat, sekaligus hukum adatbelum, atau bahkan tidak tertulis. Adat, biasanya hanya diwariskan 12 melalui kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekkan secara terus menerus dan biasanya dilestarikan lewat tradisi lisan.Dengan cara inilah adat dipelihara. Karenanya, dalam posisi yang demikian, adat merupakan sesuatu yang longgar, artinya mengenai misalnya bagaimana kepemimpinan didefinisikan, dan sebagainya bisa jadi berbeda satu sama yang lain dalam konteks waktu tertentu. Karena nilai-nilai di luar adat, ketika ia bersinggungan dengan adat, akan berpengaruh terhadap bagaimana adat kemudian mempersepsikan suatu hal. Dan pun, ketika hukum adat telah didokumentasikan, penjabaran mengenainya biasanya tidak seragam. Dalam konteks politik masa kini, terutama jika dikaitkan dengan gerakan (politik) masyarakat adat, adat didefiniskan sebagai usaha untuk merujuk praktik-praktik dan kelembagaan adat istiadat yang dihormati karena tradisinya yang panjang, yang diwarisi serta dipandang memiliki kesinambungan dengan persoalan politik masa sekarang (Henley dan Davidson, 2010). Di sini yang penting bukanlah kesahihan kerangka peraturan, praktik-praktik masa silam, atau wacana adat yang koheren yang terutama berhubungan dengan sejarah, tanah, dan hukum. Melainkan pengasosiasian kekinian dengan masa lampau. Pengasosian tersebut digunakan untuk mengejar tujuan-tujuan yang merentang dari sekadar kemunculan kembali adat sebagai entitas yang pernah eksis, hingga penegasan mengenai siapa yang berwenang atas sumber daya lokal yang kesemuanya, menurut Henley dan Davidson, atas nama adat. Namun, jika diabstraksikan, adat dalam konteks politik Indonesia masa kini, merujuk pada dua definisi utama. Pertama, adat sebagai tata rangkaian yang rumit dan saling terkait antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat tiga hal, yakni sejarah, tanah, dan hukum. Sementara, pada definisi kedua, adat diartikan sebagai gagasan atau asumsi yang samar, namun penuh kekuatan mengenai bagaimana seharusnya masyarakat yang ideal itu dijalankan. (Henley dan Davidson: 2010) Gerakan-gerakan adat yang muncul paska runtuhnya kekuasaan orde baru misalnya, lebih terkait dengan definisi abstrak yang pertama mengenai adat. 13 Adat dalam konteks masa kini, paling tidak sebagai wacana, adalah sesuatu yang betul-betul longgar, yang karenanya kehadiran (kembali) adat dan kesahihan wacana mengenai adat adalah sesuatu yang bergantung sejauhmana pihak yang ingin menghadirkan kembali adat, mendapatkan atau malahan menciptakan legitimasi. Legitimasi adat ini, paska Soeharto jatuh, terutama dengan disebarkannya kekuasaan yang semula terpusat, adat menjadi celah yang berusaha untuk dimanfaatkan oleh elit-elit lokal. Masalahnya, legitimasi adat mayoritas elit-elit lokal tersebut telah tergerus habis, terutama pada masa orde baru. Basis-basis ekonomi terutama berupa kepemilikan tanah, diambil alih oleh negara. Perangkat-perangkat pemerintahan tradisional seperti desa-desa adat, digantikan dengan perangkat-perangkat baru.Sehingga praktis legitimasi kekuasaan elit-elit tradisional tercabut hampir ke akarnya. Terkecuali tentu saja, identitas keningratan sebagai pemimpin tradisional. Schopflin (2001) mengatakan bahwa dalam sebuah formasi sosial, sekali identitas telah berhasil dikonstruksi, maka kecenderungannya untuk hilang sangat kecil. Terutama ketika konstruksi identitas tersebut “diamankan” lewat metaforametafora seperti “darah biru”, ikatan persaudaraan dan semacamnya yang diwariskan dalam masyarakat tertentu yang spesifik secara turun temurun. Jadi, meski identitas tersebut tergerus karena misalnya, kehadiran identitas yang lain. Kehadiran (kembali) identitas yang telah terkonstruksi di tatanan sosial, tetap dimungkinkan karena “kehadiran”nya lewat metafora-metafora yang terpelihara. Identitas sebagai pemimpin yang sahih secara genealogis dalam sudut pandang pemerintahan adat ini kemudian menjadi modal minimum yang digunakan untuk kembali menancapkan kekuasaannya. Namun karena di masa-masa sebelumnya, pengakuan atas keberadaan mereka oleh pemerintah hanya diakui, misalnya, sebagai simbol-simbol budaya serta pariwisata, maka pengakuan masyarakat mengenai legitimasi kekuasaan mereka sangat kecil. Karenanya kemudian, elitelit adat tradisional di daerah-daerah berusaha melunakkan definisi mengenai adat (dan kepemimpinan adat) yang semula kaku. Konsepsi mengenai kekuasaan tradisional yang bersifat genealogis misalnya, diubah sedemikian rupa agar bisa dilekatkan kepada individu-individu yang tidak 14 berada di dalam lingkaran kekuasaan tradisional (Dwipayana, 2004). Strategi pelekatan yang modern dan tradisional dilakukan oleh pemimpin tradisional untuk meruntuhkan batas-batas yang modern dan tradisional. Ketika ukuran-ukuran, kriteria-kriteria dan atribut tradisional sudah dilepaskan dan pemisah tegas antara modern dan tradisional telah bias, maka yang terjadi adalah pertukaran atribut antara keduanya. Bangsawan-bangsawan tradisional yang tidak lagi memiliki legitimasi kekuasaan yang kuat dapat meminjam legitimasi kekuasaan modern untuk mengesahkan kembali kehadirannya sembari menguatkan legitimasi kekuasaan tradisionalnya. Tujuannya, yakni untuk menghilangkan batas antara yang modern dan yang tradisional, sehingga memungkinkan elit-elit tradisional untuk mencaplok elit-elit modern untuk kemudian diberi tanggungjawab yang serupa dengan elit-elit sesungguhnya (genealogis) untuk memperjuangkan pengakuan kembali masyarakat atas legitimasinya (Dwipayana, 2004). Mekanisme pemberian gelar kebangsawanan yang terjadi di banyak keraton atau kesultanan di beberapa daerah kepada pengusaha, politisi, intelektual, dan lainnya, adalah contoh bagaimana yang tradisional dan modern dipertukarkan, bahkan disatukan. Penelitian ini berusaha untuk melihat adat tidak hanya sebagai definisi abstrak yang terutama berkaitan dengan sistem nilai, norma, dan lainnya. Namun juga dari sisi-sisi yang disebutkan di atas, adat (dan juga kepemimpinan adat) sebagai sesuatu yang longgar, yang karenanya mudah disisipi sesuatu (wacana) lain guna memuluskan kehadirannya kembali. Mendekati Kekuasaan Kekuasaan, dalam perspektif politik secara umum dimaknai sebagai kapabilitas seseorang untuk memengaruhi, serta mengontrol perilaku seorang yang lain sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya. Budiarjo (2008) menjelaskan bahwa definisi kekuasaan sebagai kemampuan memengaruhi perilaku tersebut bersumber dari perumusan yang diajukan oleh Weber (1922). Menurut Weber, orang atau kelompok yang dikuasai akan melaksanakan kehendak yang menguasainya meski pada mulanya mereka yang dikuasai menolak atau malahan melakukan perlawanan. Pendekatan Weber mengenai 15 kekuasaan ini dalam perkembangannya kemudian memengaruhi banyak ilmuwan politik dalam mendefinisikan kekuasaan. Misalnya saja Laswell dan Kaplan yang melihat kekuasaan sebagai sebuah hubungan di mana seseorang atau kelompok mampu menentukan tindakan orang atau kelompok lainnya yang diarahkan pada pemenuhan kepentingan orang atau kelompok yang menguasai tersebut (Lasswell dan Kaplan, 1950, dalam Budiardjo, 2008). Karya yang mengupas mengenai kekuasaan dengan melandaskan diri pada konsepsi Weber yang paling banyak mendapat rujukan adalah “The Concepts of Power”, ditulis oleh Robert Dahl pada 1957. Dalam artikelnya tersebut, Dahl menjabarkan kekuasaan sebagai “…kemampuan A atas B untuk membuat B melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan…”(Dahl, 1957). Kemampuan seseorang untuk membuat seorang yang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya itu menurut Dahl terbagi ke dalam “potential and actual power”. Maksud Dahl, seseorang mungkin memiliki potensi untuk berkuasa, namun potensi tersebut belum tentu mewujud ke kekuasaan aktual karena aktualisasi kekuasaan sangat bergantung pada kemampuan individu untuk melancarkan usaha yang berhasil agar kemauannya dilaksanakan oleh pihak yang ia ingin kuasai. Dalam perkembangannya, konsepsi kekuasaan a la Dahl ini disebut dengan pendekatan pluralis atau “one dimensial power”, yang melihat kekuasaan sebagai “observable behavior”, berlangsung satu arah (power a over b), karenanya dapat diamati, dan dihitung. Hal yang menjadi catatan dari konsepsi Weber, Dahl dan pengikutnya mengenai kekuasaan tersebut adalah bahwa kekuasaan cenderung berlangsung satu arah. Artinya, pihak yang telah dikuasai, dipandang sebagai pihak yang pasif, yang hanya melaksanakan kehendak dari pihak yang telah menguasainya.Selain itu, kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang terpusat dan terinstitusi pada lembagalembaga tertentu. Karenanya, kekuasaan kemudian melibatkan otoritas dan legitimasi sebagai faktor yang menentukan siapa yang berhak membuat perintah serta peraturan-peraturan yang diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang menjadi objek perintah dan peraturan tersebut. 16 Otoritas kekuasaan, masih menurut Weber (1922), dalam Budiarjo (2008: 64) kemudian terbagi dalam tiga macam, yakni tradisional, kharismatik, dan rasional legal. Otoritas jenis pertama, didasarkan pada kepercayaan di dalam masyarakat bahwa tradisi lama yang kemudian melandasi munculnya kekuasaan tradisional yang bersifat turun temurun, adalah wajar dan patut dihormati. Jenis kedua, lebih menitikberatkan pada kualitas kepemimpinan yang melekat pada person-person tertentu yang membikin masyarakat tunduk padanya karena kepercayaan atas, misalnya, kesaktian atau religiusitas seseorang. Sementara yang ketiga mendasarkan wewenang pada tatanan hukum atau peraturan yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.Ketiga hal tersebutlah yang kemudian melegitimasi otoritas kekuasaan yang melekat pada seseorang atau kelompok. Otoritas kuasa, baik tradisional, kharisma, maupun legal rasional, tidak hadir begitu saja, namun melibatkan sebuah proses untuk menghadirkan sekaligus melekatkan otoritas kuasa tersebut. Orang atau kelompok dengan otoritas kuasa tradisional misalnya, mendapatkan kuasa tersebut dengan cara penaklukan, sehingga wilayah sekaligus orang-orang yang berada dalam lingkup wilayah tersebut “menghadiahkan” legitimasi kepadanya sebagai orang yang berhak memimpin dan legitimasi tersebut kemudian diturunkan secara genealogis. Russel (1988), juga mengajukan definisi kekuasaan masih dalam kerangka pikir Weberian. Kekuasaan, menurutnya adalah hasil pengaruh yang diinginkan. Dalam pengertian ini, ia masih mempersepsikan kekuasaan sebagai keberhasilan satu pihak mempengaruhi pihak lain. Namun, Russel mengajukan pembilahan antara kekuasaan “eksplisit” dengan kekuasaan “implisit”. Kekuasaan eksplisit, berada pada pemimpin. Sedang kekuasaan implisit, berada pada pihak yang bersedia menjalankan apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya (pengikut). Kelompok kedua (pengikut) menurut Russel memiliki kuasa dengan mengikuti pemimpinnya dan menganggap “kemenangan-kemenangan” yang dicapai pemimpin sebagai kemenangan-kemenangan mereka juga. Sebelum membagi kekuasaan ke dalam dua tipe di atas, Russel terlebih dahulu menjabarkan bahwa dalam diri manusia ada “dorongan untuk berkuasa” yang karenanya manusia cenderung melakukan apapun untuk mengejawantahkan dorongan tersebut, termasuk menjadi pengikut. Dengan mengikuti, “menempel” ke pemimpin, manusia secara tidak langsung 17 telah, paling tidak merasa, mengejawantahkan dorongan untuk berkuasanya karena ia berada di lingkungan orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Lebih lanjut, Russel membedakan kuasa ke dalam beberapa bentuk yakni kekuasaan relijius, kekuasaan raja, kekuasaan tanpa persetujuan, kekuasaan revolusioner, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan atas pendapat. Bentuk-bentuk kekuasaan tersebut, bisa jadi hanya dimiliki secara terpisah oleh seseorang atau kelompok. Namun, seorang penguasa mungkin saja memiliki dan mengakumulasi kekuasaan-kekuasaan dengan bentuk yang beragam pada dirinya untuk memperluas rentang kuasa dan legitimasi kuasa yang melekat kepadanya. Lukes (1974) menawarkan pendekatan yang berbeda mengenai kekuasaan. Dalam bukunya berjudul “Power: A Radical View,” Lukes terlebih dahulu menjabarkan dua pendekatan mengenai kuasa. Pendekatan pertama yakni “one dimensional power” yang diajukan oleh Dahl serta penerus-penerusnya, yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dapat diobservasi serta berlangsung satu arah seperti yang dijelaskan di atas. Pendekatan kedua, “two dimensional power,” disampaikan oleh Peter Bachrach dan Morton Baratz. Keduanya mengkritik teori kekuasaan dalam pendekatan pluralisme yang diajukan Dahl serta pengikutnya. Bachrach dan Baratz, mengatakan bahwa kuasa memiliki dua sisi. Pertama, kuasa dari definisi Dahl, yakni “A mengontrol B.” Kedua, yang justru lebih penting adalah usaha orang atau kelompok yang telah memiliki kuasa untuk mempertahankan “kerelaan” pihak yang dikuasainya untuk dengan pemberlakuan sanksi. Sanksi ini, diberlakukan baik dengan koersi, pengaruh, otoritas (dan mesin otoritas,) serta manipulasi (Lukes, 1974: 21). Bachrach dan Baratz menegaskan bahwa pendekatan kekuasaan satu dimensi Dahl dan kawan-kawan hanya menegaskan adanya penguasaan seseorang atau kelompok pada yang lain dengan cenderung menegasikan usaha seseorang atau kelompok yang berkuasa tersebut untuk tetap berkuasa. Padahal menurut mereka, justru hal inilah yang mestinya mendapat penekanan. Pendekatan Lukes mengenai kekuasaan adalah kritiknya terhadap dua pendekatan sebelumnya mengenai kekuasaan. Teori “Two dimensional power,” menurutnya 18 tidak cukup memuaskan untuk menjelaskan mengenai misalnya adanya penolakan seseorang atau kelompok untuk dikuasai dengan tidak turut andil dalam proses politik di mana penguasaan dilangsungkan. Dalam konteks demikian, apakah kekuasaan masih berlangsung? Lukes kemudian menawarkan pendekatannya mengenai kuasa yang ia sebut sebagai “three dimensions of power.” Kekuasaan, ia definisikan sebagai “the power to avert the formation of grievances by shaping perceptions, cognitions, and preferences in a way that the acceptance of a certain role in the existing order is ensured” (Lukes, 1974). Di sini, Lukes memahami kekuasaan dengan mengandaikan bahwa aktor yang terlibat dalam proses kuasa-menguasai adalah jamak, dengan kepentingan yang beragam, dan kadang saling menegasikan satu sama lain. Artinya, kekuasaan tidak ia lihat sebagai sesuatu yang berlangsung satu arah. Penolakan seseorang atau kelompok untuk dikuasai misalnya, juga ia definisikan sebagai bentuk kuasa, yakni kuasa untuk menegasikan kekuasaan yang lain. Di sini, kemampuan seseorang atau kelompok untuk tetap menguasai kelompok yang enggan dikuasai kemudian dapat berlangsung dengan memunculkan sebuah bentuk “kesepakatan” yang meski ditolak oleh sebagian orang atau kelompok, namun secara umum tetap diakui sebagai aturan main. Dalam studi ini, konsepsi kekuasaan yang akan digunakan adalah gabungan dari pendekatan kekuasaan yang mendasarkan diri pada a) pengawasan atau kontrol, dan b) elite. Konsep kekuasaan yang pertama, diajukan oleh Talcott Parsons, Robert S. Lynd, dan Marion Levy, Jr. Menurut pendekatan ini, kekuasaan adalah sesuatu yang pokok utamanya adalah permasalahan kontrol, yang sifat atau fungsinya tidak selalu merupakan paksaan (Soemardi, 1960). Lynd misalnya, mendefinisikan kekuasaan sebagai “…suatu sumber sosial yang utama untuk mengadakan pengawasan (yang) dapat beralih wujud dari suatu paksaan sampai dengan suatu kerjasama secara sukarela, tergantung daripada perumusan ketertiban dan kekacauan sebagaimana ditentukan, diubah, dan dipelihara dalam suatu masyarakat tertentu,” (Lynd, 1951; dalam Soemardi, 1960). Implikasinya, dalam pendekatan ini permasalahan mendasar dari kekuasaan adalah permasalahan legitimasi, atau sesuatu yang membenarkan atau merasionalisasikan hadirnya kekuasaan itu. Artinya, yang paling penting dimunculkan oleh orang 19 atau kelompok yang terlibat dalam usaha kuasa- menguasai adalah bagaimana mereka membuat kekuasaan menjadi sesuatu yang melekat pada diri mereka, serta tidak dipertanyakan lagi. Selain itu, karena studi ini ingin mengkaji strategi yang dilakukan oleh para pemimpin adat di Lampung, konsepsi kekuasaan dari perspektif elite yang diajukan oleh C. Wright Mills juga dipinjam. Mills mendefinisikan elite sebagai orang-orang yang menduduki posisi tertinggi pada puncak hierarki dalam masyarakat. Kekuasaan mereka bersumber dari pranata-pranata sosial yang telah disepakati secara luas oleh masyarakat, yang karenanya keputusan-keputusan yang mereka ambil berpengaruh dalam masyarakat tempat pranata-pranata sosial itu dilembagakan (Soemardi, 1960). D. Metode dan Objek Penelitian Studi ini akan lebih menitikberatkan perhatiannya untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemimpin adat di Lampung menancapkan kembali pengaruhnya dalam pusaran politik lokal Lampung, serta bagaimana implikasinya secara sosial dan politik. Karena pertanyaan dalam tesis ini difokuskan pada pertanyaan “bagaimana”, serta pembahasan yang dibatasi pada aktor dan konteks khusus, maka studi ini akan menggunakan studi kasus eksplanatoris yang bersandarkan pada pendekatan kualitatif. Alasannya, studi kasus memang dirancang untuk studi yang mencoba membahas fenomena kontemporer yang spesifik, serta fokus pada pertanyaan mengapa dan bagaimana seperti pada tesis ini. Sedangkan jenis studi kasus eksplanatoris dipilih karena studi ini lebih menyandarkan diri pada penjelasan-penjelasan, penjabaran-penjabaran dalam menjawab pertanyaan penelitian. Objek penelitian dalam kajian ini adalah para penyimbang atau saibatin, yakni entitas yang memiliki status tertinggi dalam struktur pemerintahan adat di Lampung yang diwariskan secara genealogis. Penyimbang dan saibatin, mewakili entitas yang sama, namun penyebutan pertama lebih dikenal di masyarakat Lampung bersub-etnis Pepadun, sedangkan penyebutan terakhir digunakan oleh masyarakat Lampung bersub-etnis Pesisir. Untuk lebih memudahkan penyebutan, 20 selanjutnya dalam tulisan ini, istilah penyimbang akan digunakan untuk menyebut para pemimpin adat baik di sub-etnis Pepadun atau Pesisir. Untuk menyederhanakan objek kajian, penulis akan menyandarkan perhatian terutama pada para penyimbang-penyimbang marga yang termasuk ke dalam “Marga Regering Voor de Lampungche Districten”, daftar 84 marga yang diakui keberadaannya oleh Belanda, dikeluarkan pada 19283. Karena tak mungkin menguraikan strategi dari seluruh 84 marga “bentukan” Belanda tersebut, maka penulis memfilternya melalui pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik, serta literatur-literatur terdahulu untuk melihat penyimbangpenyimbang adat di marga mana saja yang paling getol melancarkan strategi untuk kembali punya kuasa di aras lokal. Penyimbang-penyimbang adat dari marga di luar daftar marga rilisan Belanda, juga tetap mendapat pembahasan di dalam tesis. Pembahasan mengenainya penting untuk menunjukkan argumen yang penulis bangun bahwa adat-serta pemimpin adat-di daerah dalam konteks Lampung bukanlah merupakan entitas yang tunggal seperti yang selama ini ditunjukkan oleh literatur-literatur sebelumnya. Karenanya kemunculan kembali para penyimbang adat di luar marga utama bentukan Belanda pada 1928, tentulah sangat dimungkinkan, terutama ketika penyimbang-penyimbang marga di luar marga-marga utama tersebut bisa menjaga legitimasi kekuasaan tradisionalnya sedemikian rupa, atau bisa mempertahankan sumber daya ekonominya. E. Bagaimana Data Dikumpulkan dan Dianalisa? Data dalam studi ini dikumpulkan dengan mengombinasikan wawancara mendalam serta telaah literatur. Kedua data tidak diperlakukan secara terpisah, namun saling melengkapi satu sama lain. Telaah literatur berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan daerah, berita cetak dan elektronik, serta sumber lain terkait kemunculan pemimpin tradisional secara umum atau 3 Penjelasan mengenai kepenyimbangan dan daftar marga-marga adat yang dikeluarkan oleh Belanda pada 1928 akan dijabarkan pada bab selanjutnya. 21 kemunculan penyimbang adat Lampung secara khusus misalnya, telah penulis lakukan sebelum mewawancarai narasumber-narasumber dalam tulisan ini. Wawancara, penulis lakukan dengan cara mendalam dengan menyandarkan diri pada daftar-daftar pertanyaan yang penulis buat sebagai panduan wawancara. Namun dalam prosesnya, pertanyaan-pertanyaan di luar guideline tersebut juga penulis sampaikan kepada narasumber. Artinya, daftar pertanyaan tersebut penulis perlakukan sebagai sesuatu yang cair. Ketika ada hal-hal menarik yang memiliki relevansi dengan kajian yang disampaikan oleh narasumber, penulis mengejar pernyataan narasumber meskipun tak penulis masukkan dalam daftar pertanyaan. Narasumber: 1. Azhar Marzuki Gelar Pangeran Tihang Marga (Saibatin Marga Legun, Lampung Selatan) 2. Bahri Gelar Pangeran Cahaya Marga (Saibatin Marga Ratu, Lampung Selatan) 3. Maulana Raja Niti (Ketua Dewan Perwakilan Penyimbang Adat Lampung, Way Kanan) 4. Rizani Puspawijaya (Dewan Perwatin Majelis Penyimbang Adat Lampung, penulis buku “Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran”) 5. A. Fauzie Nurdin (Dosen IAIN Raden Intan Lampung, penulis buku “Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah” 6. Barthoven Vivit Nurdin (Antropolog, penyusun “Etnografi Marga Mesuji”) 7. Bintang Wirawan (Dosen Sosiologi Universitas Lampung) 8. Hasyimkan (Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, peneliti gamolan Lampung) 9. Zulkarnain Zubairi (Wartawan, Budayawan Lampung) 22 Data yang penulis dapat dari wawancara mendalam, kemudian diolah dengan menggarisbawahi informasi-informasi yang behubungan dengan kata-kata kunci penelitian. Jawaban-jawaban dari narasumber-narasumber yang memiliki tema yang sama kemudian dikategorisasikan berdasarkan relevansinya dengan bab-bab dalam tesis. Tema-tema terutama mengenai revitalisasi adat, relasi antar pemimpin adat, relasi antara pemimpin adat dengan pemimpin formal, implikasinya secara sosial politik dan hal-hal lain yang penulis anggap penting untuk dimasukkan ke dalam kajian akan menjadi titik tekan. Setelah itu prosesnya kemudian berulang. Data-data tersebut kemudian kembali dibandingkan dengan literatur-literatur lain guna memperkaya hasil temuan yang didapat dari wawancara atau kajian literatur yang penulis lakukan di awal penulisan. Akan ada usaha untuk menyesuaikan atau bahkan mempertentangkan data-data penelitian terutama terutama dengan literatur-literatur yang membahas mengenai tema serupa. Dengan begitu, ada usaha pengayaan terhadap analisis yang penulis lakukan. F. Sistematika Penulisan Bab 1 Berisikan pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Gambaran dasar mengenai kajian, relevansi serta urgensi diadakannya kajian, serta bagaimana kajian dilakukan, digambarkan dalam bab ini. Semacam pengantar bagi pembaca untuk memahami bab-bab selanjutnya yang akan dibahas. Bab 2 Bab ini berisi penjabaran konsep-konsep kunci terkait kekuasaan dan kepenyimbangan (kepemimpinan adat). Selain itu, bab ini juga berisikan penjelasan mengenai pergeseran kuasa penyimbang adat dari masa ke masa, mulai dari masa kolonial hingga orde baru. Implikasi yang berbeda-beda yang tercipta oleh konteks sosial dan politik yang berbeda di tiap-tiap jaman terhadap 23 kekuasaan penyimbang adat, dijelaskan pada bagian ini. Runtuhnya orde baru serta pergeseran kekuasaan yang mengiringinya sebagai konteks yang melatari kemunculan para penyimbang adat juga akan diterangkan. Bab 3 Di bagian ini akan dipaparkan strategi kemunculan kembali para penyimbang adat pasca orde baru. Penulis berhipotesa bahwa otonomi kekuasaan para penyimbang yang terbatas hanya pada daerah kekuasaannya, perbedaan “derajat” kepemimpinan tradisional antar penyimbang, mekanisme yang memungkinkan munculnya marga-marga baru, serta perbedaan kepemilikan sumber daya ekonomi, membuat usaha kemunculan kembali para penyimbang adat di Lampung pasca orde baru dilakukan dengan strategi yang berbeda-beda. Teori Accaioli mengenai Officializing dan Opposing Strategy akan dieksplisitkan pada bagian ini. Pengaruh secara sosial politik terkait kemunculan kembali para penyimbang adat tersebut juga dibahas secara singkat dalam bab ini. Bab 4 Kesimpulan 24