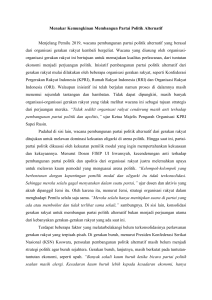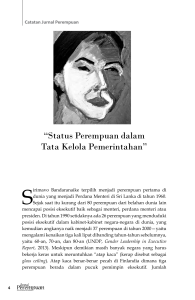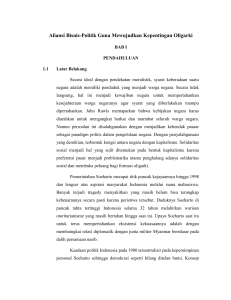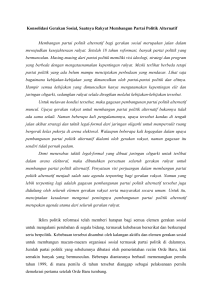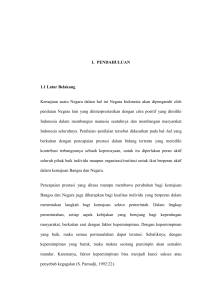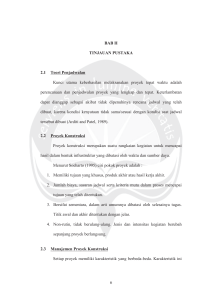Demokrasi Oligarki! Bukan Demokrasi Kebablasan
advertisement
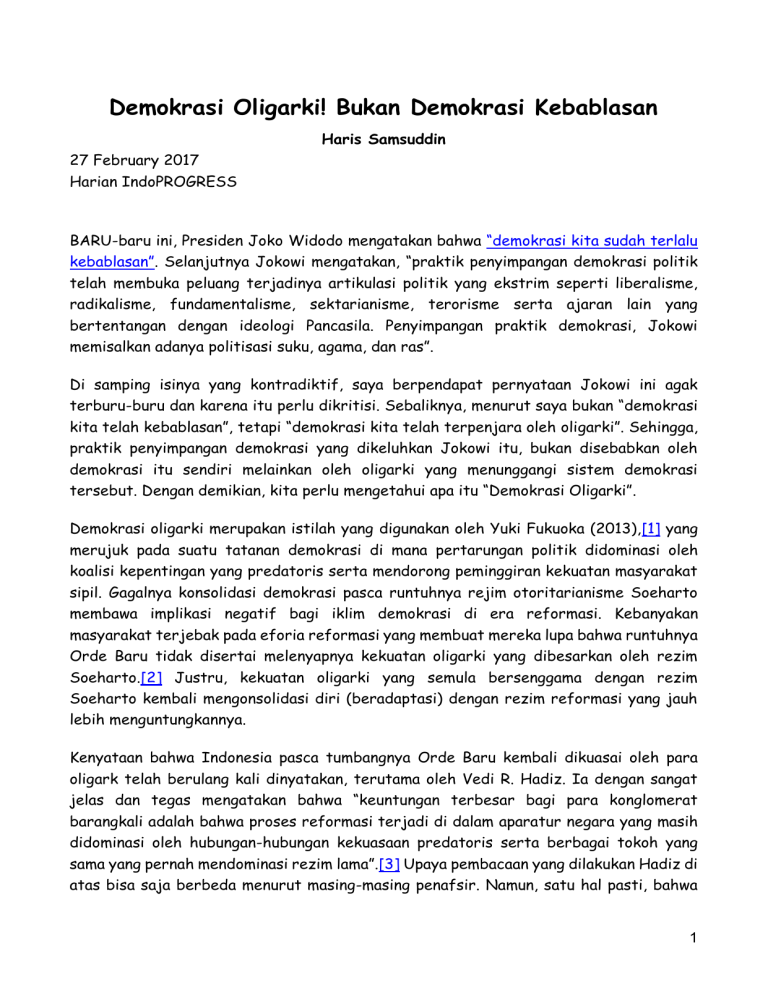
Demokrasi Oligarki! Bukan Demokrasi Kebablasan Haris Samsuddin 27 February 2017 Harian IndoPROGRESS BARU-baru ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “demokrasi kita sudah terlalu kebablasan”. Selanjutnya Jokowi mengatakan, “praktik penyimpangan demokrasi politik telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penyimpangan praktik demokrasi, Jokowi memisalkan adanya politisasi suku, agama, dan ras”. Di samping isinya yang kontradiktif, saya berpendapat pernyataan Jokowi ini agak terburu-buru dan karena itu perlu dikritisi. Sebaliknya, menurut saya bukan “demokrasi kita telah kebablasan”, tetapi “demokrasi kita telah terpenjara oleh oligarki”. Sehingga, praktik penyimpangan demokrasi yang dikeluhkan Jokowi itu, bukan disebabkan oleh demokrasi itu sendiri melainkan oleh oligarki yang menunggangi sistem demokrasi tersebut. Dengan demikian, kita perlu mengetahui apa itu “Demokrasi Oligarki”. Demokrasi oligarki merupakan istilah yang digunakan oleh Yuki Fukuoka (2013),[1] yang merujuk pada suatu tatanan demokrasi di mana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran kekuatan masyarakat sipil. Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rejim otoritarianisme Soeharto membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di era reformasi. Kebanyakan masyarakat terjebak pada eforia reformasi yang membuat mereka lupa bahwa runtuhnya Orde Baru tidak disertai melenyapnya kekuatan oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto.[2] Justru, kekuatan oligarki yang semula bersenggama dengan rezim Soeharto kembali mengonsolidasi diri (beradaptasi) dengan rezim reformasi yang jauh lebih menguntungkannya. Kenyataan bahwa Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru kembali dikuasai oleh para oligark telah berulang kali dinyatakan, terutama oleh Vedi R. Hadiz. Ia dengan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa “keuntungan terbesar bagi para konglomerat barangkali adalah bahwa proses reformasi terjadi di dalam aparatur negara yang masih didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan predatoris serta berbagai tokoh yang sama yang pernah mendominasi rezim lama”.[3] Upaya pembacaan yang dilakukan Hadiz di atas bisa saja berbeda menurut masing-masing penafsir. Namun, satu hal pasti, bahwa 1 kenyataan rezim politik hari ini benar-benar ada di bawah kuasa para oligark sulit dinafikan. Oligarki sendiri sebagai suatu aliansi cair yang menghubungkan kepentingan para konglomerat kaya raya selalu lihai dalam beradaptasi dengan sistem apapun, baik otoratirianisme maupun demokrasi. Coba amati, kebanyakan penguasa yang kini menempati posisi strategis di berbagai institusi publik hingga partai politik rata-rata adalah petarung lama. Tidak ada yang baru sama sekali. Para pimpinan (elite) partai, penguasa media mainstream, para pejabat pemerintahan yang berada di jajaran kabinet Jokowi, sampai pada seluruh jabatan strategis lainnya di dalam birokrasi pemerintahan saat ini hanyalah sirkulasi elit-elit lama yang selalu berotasi di dalam lingkar kekuasaan oligarki. Para oligark di atas, termasuk orang-orang yang pernah diistimewakan di rezim kepemimpinan Soeharto melalui relasi patron-client. Hubungan kekuasaan lama yang penuh muslihat dan tipu daya semasa Orde Baru, belakangan setelah runtuhnya “Soeharto”, tampil sebagai pejuang demokrasi berkedok populis. Inilah wajah anomali demokrasi pasca otoritarianisme Soeharto. Kebanyakan orang tertipu dengan politik pencitraan yang terus dipolesi oleh media, yang juga notabene adalah milik mereka (baca: oligark). Dominasi oligarki dalam ranah politik Indonesia terjadi karena kenaifan asumsi reformasi institusional neoliberal yang percaya akan primasi pengelolaan institusi rasional. Kenaifan ini mengabaikan keberadaan relasi ekonomi politik oligarki yang menyejarah. Kemampuan oligarki untuk menaklukkan kekuasaan negara serta melakukan disorganisasi atas kekuatan oposisi masyarakat sipil, membuat proses reformasi institusional neoliberal tidak memiliki basis sosial dan politik yang kuat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan oligarki dapat mempertahankan dominasi politiknya, yang dengannya merepresi kemungkinan bagi munculnya agensi politik non-oligarki.[4] Harus disadari bahwa reformasi politik yang beriringan dengan reformasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak sama sekali menghancurkan relasi oligarki ini. Kenyataan bahwa lemahnya kekuatan civil society belakangan ini dalam membendung gurita oligarki semakin membuktikan tesis Richard Robison dan Vedi R Hadiz bahwa penguasaan atas politik negara sekaligus disertai disorganisasi kekuatan oposisional yang tercakup dalam elemen masyarakat sipil menjadi dasar historis bagi dominasi oligarki terhadap kekuatan politik non-oligarki. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa perseteruan politik di era reformasi kembali meneguhkan posisi elit lama.[5] Jeffrey Winters, salah seorang penggagas tesis oligarki terkemuka lewat bukunya Oligarchy (2011), mengemukakan bahwa pembacaan terhadap dinamika kekuasaan politik harus didasarkan pada konsentrasi sumber daya kekuasaan yang dimiliki setiap oligark. 2 Tulisnya, “oligark didefinisikan oleh tipe dan ukuran sumber daya kekuasaan yang dikendalikannya”.[6] Winters membagi sumber daya kekuasaan mencakup hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (coercive power), kekuatan mobilisasi (mobilizational power), dan kekuasaan material (material power). Khusus untuk sumber daya kekuasaan yang terakhir (kekuasaan material) merupakan basis kekuasaan oligark. Oligark adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan (sumber daya paling menonjol di antara bentuk-bentuk kekuasaan lainnya).[7] Oligark berbeda dengan kaum elit pada umumnya yang cenderung menggunakan kekuasaan non-material. Oligark lebih cenderung menggunakan basis sumber daya material dalam melangsungkan manuver politiknya. Dalam konteks demokrasi, kaum oligark memanfaatkan situasi ketimpangan sumber daya material sebagai peluang memenangkan konstestasi politik (pemilu/pemilukada). Mahalnya biaya politik ditambah mentradisinya politik transaksional belakangan ini semakin mempermudah para oligark dalam menggeser rival politiknya yang tidak memiliki basis material yang memadai. Hemat saya, tesis oligarki Winters yang melihat kondisi ketidaksetaraan kekayaan yang ekstrem antar-warga senantiasa mengarah pada ketidaksetaraan politik yang juga ekstrem menemukan relevansinya di Indonesia saat ini. Hal ini terbukti di mana momentum pemilu/pemilukada tereduksi semata-mata sebagai ajang pertarungan kepentingan para oligark, bukan urusan menyeleksi wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas secara fair dan demokratis. Dalam demokrasi oligarki, rakyat (voters) tidak memilih apa yang mereka kehendaki, melainkan telah dipilihkan oleh segelintir elit kekuasaan yang memegang peran dominatif di dalam institusi demokrasi. Bagaimana dikatakan pilihan rakyat, jika calon pemimpin/penguasa baik di pusat maupun di daerah, melewati suatu saringan politik di internal partai (kecuali calon independen) yang sarat dengan kalkulasi kapital tanpa melalui usulan publik (rakyat) dianggap pilihan rakyat? Nalar sehat macam apa yang melihat fakta politik demikian sebagai logika publik yang mengafirmasi diri dalam bentuk pilihan rasional? Bukankah itu yang selama ini kita sebut kegilaan di atas kegilaan? Alias ketidakwarasan yang cenderung diafirmasi secara terus-menerus tanpa refleksi. Penutup Kembali ke penyataan Jokowi, sudah jelas bahwa jika Jokowi menghendaki demokrasi berjalan sebagaimana esensinya, yakni sebagai kekuasaan rakyat, maka ia harus 3 mengambil langkah-langkah politik dan ekonomi untuk membendung atau membonsai kekuasaan oligarki yang mendominasi lapangan permainan politik saat ini. Jokowi dan para penasehatnya harus ingat bahwa “politisasi suku, agama, dan ras”, yang disebutnya sebagai “penyakit demokrasi” bukanlah hal yang baru muncul sekarang ini. Ia sudah bertunas dan berkecambah sejak 10 tahun kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memuncak pada masa Pilpres 2014 lalu. Penyakit ini semakin berbiak karena tidak ada langkah-langkah politik dan ekonomi yang strategis untuk membendungnya. Bagi gerakan sosial, mandegnya agenda demokratisasi, selain karena cengkeraman oligarki yang terus bertahan, juga menandakan betapa lemahnya konsolidasi kekuatan civil society. Adalah naif belaka untuk mengharapkan Jokowi mau membonsai kekuatan oligarki. Dialektika hubungan kekuasaan seperti inilah yang mesti kita sadari dan jabarkan dalam lapangan politik yang konkret dan terukur capaiannya. Dengan demikian, kita memang perlu mengkritisi dan menentang langkah-langkah politik-ekonomi Jokowi yang pro oligarki, yang tidak memiliki imajinasi politik di luar kenyataan ekonomi-politik warisan rezim Orde Baru ini. Tetapi kita juga harus jujur sejujur-jujurnya bahwa kita tidak cukup serius membangun gerakan sosial-politik yang terorganisasi secara ideologi, politik dan organisasi untuk melawan demokrasi oligarki ini.*** Penulis adalah Anggota Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Malang dan Peneliti di Intrans Institute ————[1] Yuki Fukuoka, “Oligarchy and Democracy in Post-Soeharto”, Political Studies Review II, no. I, 2013: 52-64. [2] Terkait pembiakan para kapitalis domestik yang kemudian tumbuh bersama dengan koalisi kepentingan ekonomi politik di era Orde Baru dapat dilihat melalui karya Richard Robison, Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, ditejemahkan oleh Harsutejo dari judul asli Indonesia: The Rise of Capital, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2102). Lingkar konglomerat domestik yang dibesarkan dari hasil persenggamaan kekuasaan otoriter Soeharto inilah yang di kemudian hari setelah runtuhnya Soeharto mengambil alih 4 kekuasaan baik di tingkat nasional maupun lokal dan membentuk lingkaran kekuasaan oligarkis. [3] Vedi R Hadiz, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Diterjemahkan oleh A Zaim Rofiqi dan Dahris Setiawan, (Jakarta: LP3ES, 2005), 149-150. [4] Muhammad Ridha, “Oligarki dan Agensi Politik Indonesia di Era Neoliberal: Evaluasi Kritis Tesis Oligarki Robison-Hadiz”, Jurnal Indoprogress, no. 6, vol. II, 2016, 9. [5] Richard Robison dan Vedi R Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, (London: Routledge Curzon, 2004). [6] Jeffrey Winters, Oligarki. Diterjemahkan oleh Zia Anshor, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 17. [7] Jefrey A Winters, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, Majalah Prisma, no. 1, vol. 33, 2014, 14. 5