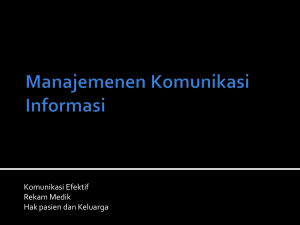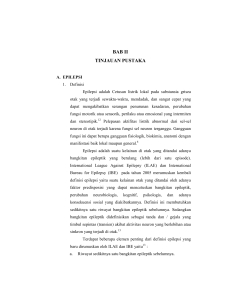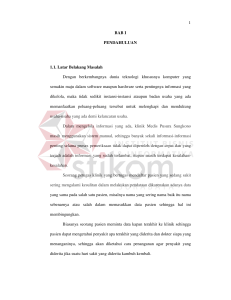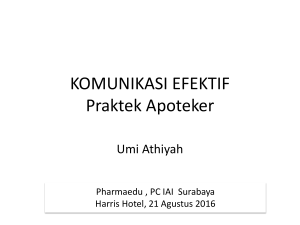evaluasi efek terapi obat antiepilepsi monoterapi
advertisement

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Epilepsi menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu kelainan otak kronis dengan berbagai macam penyebab yang ditandai serangan epilepsi berulang yang disebabkan oleh bangkitan neuron otak yang berlebihan. Gangguan ini sering dihubungkan dengan disabilitas fisik, disabilitas mental, dan konsekuensi psikososial yang berat bagi penderitanya. Di samping itu juga dihubungkan dengan angka cedera yang tinggi, angka kematian yang tinggi, stigma sosial yang buruk, ketakutan, kecemasan, gangguan kognitif, dan gangguan psikiatrik (WHO, 2001). Gambaran klinisnya dapat berupa kejang, perubahan tingkah laku, perubahan kesadaran. Kondisi ini tergantung lokasi kelainan di otak (Rahardjo, 2008). Epilepsi ditemukan pada semua umur dan dapat menyebabkan mortalitas. Diduga terdapat sekitar 50 juta orang dengan epilepsi di dunia. WHO (2001) menyebutkan bahwa kejadian epilepsi di negara maju berkisar 50 per 100.000 penduduk, sedangkan di negara berkembang 100 per 100.000 ribu. Epilepsi dapat menyerang pada laki-laki ataupun perempuan. Secara umum diperkirakan ada 2,4 juta kasus baru setiap tahun, dan 50% kasus terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja (WHO,2006). Insiden tertinggi terjadi pada umur 20 tahun pertama, menurun sampai umur 50 tahun, dan setelah itu meningkat lagi (Ikawati, 2011). Secara umum, rekomendasi terapi yang tepat pada epilepsi harus mempertimbangkan rasio risiko dan biaya obat dengan keuntungan/efek 1 terapinya. Keuntungan terapi berkaitan dengan tingkat kualitas hidup penderita dengan manifestasi adanya penurunan/pengendalian kejang, di samping perbaikan dalam aspek psikis, kognitif, dan sosial. Efek samping dan biaya terapi berhubungan dengan dampak klinik, psikologi, sosial dan ekonomi akibat penanganan epilepsi yang kurang adekuat (Heaney dkk, 2002). Obat Anti Epilepsi (OAE) merupakan terapi utama pada manajemen epilepsi. Tujuan pengobatan epilepsi dengan OAE adalah untuk menghindari terjadinya serangan epilepsi selanjutnya dengan efek samping yang minimal (Wibowo & Gofir, 2006). Terapi pilihan lainnya termasuk perubahan pola makan, menghindari faktor pencetus (contohnya alkohol atau kurang tidur), penanaman saraf stimulator dan pembedahan (Gidal dkk, 2005). Pemilihan OAE pada pediatrik bukanlah tugas yang sederhana. Banyak variabel yang harus dipertimbangkan antara lain jenis epilepsi, efikasi/efektivitas, efek samping, farmakokinetik, formulasi, latar belakang genetik, jenis kelamin, usia, komorbiditas, status sosial ekonomi, ketersediaan dan biaya OAE (Glauser dkk, 2006). OAE monoterapi menjadi pilihan dalam memulai pengobatan epilepsi, karena sebagian besar pasien berhasil dikontrol dengan obat monoterapi pertama atau kedua yang diberikan. Penggunaan monoterapi dapat mengurangi potensial interaksi obat dan efek toksik yang merugikan (Louis dkk, 2009). Sebagian besar pasien epilepsi merespon pengobatan dengan monoterapi, 47% pasien menjadi bebas kejang dengan percobaan OAE pertama dan 13% mencapai bebasan kejang dengan percobaan monoterapi kedua (Kwan & Brodie, 2000). Penggunaan politerapi baru dapat dipertimbangkan ketika pasien gagal dua atau lebih dengan 2 monoterapi (WHO, 2009). Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat keefektifan terapi obat anti epilepsi secara monoterapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada klinisi terkait pengobatan epilepsi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan/acuan dalam penyusunan standar terapi pengobatan epilepsi. Hal ini dimaksudkan agar target utama dari pengobatan epilepsi yaitu pengurangan frekuensi kejang dan keparahan kejang dapat tercapai. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang merupakan salah satu rumah sakit pendidikan tipe A yang membantu memberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan profesi calon dokter dan dokter spesialis serta menjadi lahan praktek dari Institusi Kesehatan dan Non Kesehatan baik di wilayah Provinsi DIY maupun dari luar Provinsi DIY bahkan ada dari luar negeri. Selain itu RS Dr. Sardjito merupakan rujukan tertinggi bagi pasien epilepsi untuk daerah DIY dan Jawa Tengah bagian Selatan. Pasien epilepsi sekitar 70% dari jumlah pasien yang datang ke Instalansi Kesehatan Anak Sub. Bagian Neurologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. RSUP Dr. Sardjito memiliki jumlah tempat tidur untuk pasien sebanyak 750 buah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efek terapi OAE secara monoterapi pada pengobatan pasien epilepsi pediatrik di Instalasi Kesehatan Anak RSUP Dr. Sardjito pada periode Januari-Maret 2015. 3 B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana gambaran pola pengobatan OAE secara monoterapi pada pengobatan pasien epilepsi pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada periode Januari-Maret 2015 ? 2. Bagaimanakah efek terapi OAE secara monoterapi pada pengobatan pasien epilepsi pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada periode Januari-Maret 2015 ? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui gambaran pola pengobatan OAE secara monoterapi pada pengobatan pasien epilepsi pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada periode Januari-Maret 2015. 2. Mengevaluasi efek terapi OAE secara monoterapi pada pengobatan pasien epilepsi pediatrik rawat jalan di Instalasi Kesehatan Anak RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada periode Januari-Maret 2015. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi terkait efek terapi OAE secara monoterapi pada pengobatan pasien epilepsi 4 pediatrik rawat jalan. 2. Bagi rumah sakit Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi gambaran pola pengobatan epilepsi menggunakan OAE secara monoterapi dan sebagai evaluasi dalam memberikan terapi kepada pasien epilepsi pediatrik secara tepat dan dapat memberikan umpan balik terkait dengan standar terapi pengobatan epilepsi pada pasien pediatrik. E. Tinjauan Pustaka 1. Epilepsi a. Definisi Epilepsi Epilepsi merupakan gangguan susunan saraf pusat (SSP) yang dicirikan oleh terjadinya bangkitan yang bersifat spontan (tidak ada penyebab) dan berkala. Bangkitan dapat diartikan sebagai modifikasi fungsi otak yang bersifat mendadak dan sepintas, yang berasal dari sekelompok besar sel-sel otak, bersifat sinkron dan berirama. Istilah epilepsi tidak boleh digunakan untuk bangkitan yang terjadi selama penyakit akut berlangsung, dan kejang tidak berkala misalnya kejang atau bangkitan pada hipoglikemi (Harsono, 2007a). b. Epidemiologi Epilepsi Epilepsi ditemukan pada semua umur dan dapat menyebabkan mortalitas, terdapat sekitar 50 juta orang dengan epilepsi di dunia. WHO 5 (2001) menyebutkan bahwa kejadian epilepsi di negara maju berkisar 50 per 100.000 penduduk, sedangkan di negara berkembang 100 per 100.000 ribu. Diperkirakan ada 1-2 juta penderita epilepsi di Indonesia. Prevalensi epilepsi di indonesia adalah 5-10 kasus per 1.000 orang dan insidensi sebanyak 50 kasus per 100.000 orang per tahun (Harsono, 2007a). Epilepsi dapat menyerang pada laki-laki ataupun perempuan. Secara umum diperkirakan ada 2,4 juta kasus baru setiap tahun, dan 50% kasus terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja (WHO,2006). Insiden tertinggi terjadi pada umur 20 tahun pertama, menurun sampai umur 50 tahun, dan setelah itu meningkat lagi (Ikawati, 2011). Kajian Pinzon (2006) terhadap penelitian terdahulu menunjukkan insidensi epilepsi pada anak-anak adalah tinggi dan memang merupakan penyakit neurologis utama pada kelompok usia tersebut, bahkan dari tahun ke tahun ditemukan bahwa prevalensi epilepsi pada anak-anak cenderung meningkat. Penelitian Heaney dkk (2002) di Inggris dilakukan secara prospektif terhadap 369.283 orang, sepanjang pengamatan dijumpai 190 kasus baru epilepsi, 65 diantaranya (34,2%) dimulai saat pada usia <14 tahun. Hasil menyebutkan bahwa penyandang epilepsi masih sangat banyak, hal ini juga akan menimbulkan dampak sosial masyarakat bagi penyandangnya (Heaney dkk,2002). 6 c. Etiologi Epilepsi Dasar serangan epilepsi adalah gangguan fungsi neuron-neuron otak dan transmisi pada sinaps. Setiap sel hidup, termasuk neuron-neuron otak mempunyai kegiatan listrik yang disebabkan oleh adanya potensial membran sel. Potensial membran neuron bergantung pada permeabilitas selektif membran neuron yaitu perbedaan konsentrasi ion-ion seperti K, Na, Ca, Cl (Shih, 2007). Menurut Shorvon (2001) dan Deliana (2002) ditinjau dari penyebab epilepsi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : 1). Epilepsi primer atau epilepsi idiopatik yang penyebabnya tidak diketahui meliputi ±50% dari penderita epilepsi anak, umumnya mempunyai predisposisi genetik, awitan biasanya pada usia >3 tahun. 2). Epilepsi simptomatik disebabkan oleh kelainan/lesi pada susunan saraf pusat, misalnya : post trauma kapitis, infeksi susunan saraf pusat (SSP), gangguan metabolik, malformasi otak kongenital, gangguan peredaran darah otak, toksik (alkohol, obat), kelainan neurodegeneratif dan kejang demam. 3). Epilepsi kriptogenik dianggap simptomatik tetapi penyebabnya belum diketahui, termasuk disini adalah sindrom West, sindrom Lennox-Gastaut dan epilepsi mioklonik. 7 Beberapa penyebab secara spesifik timbulnya serangan epilepsi adalah: 1). Kelainan yang terjadi selama perkembangan janin/kehamilan ibu, seperti ibu menelan obat-obat tertentu yang dapat merusak otak janin, mengalami infeksi, minum alkohol atau mengalami cedera (trauma) atau mendapat penyinaran (radiasi). 2). Kelainan yang terjadi pada saat kelahiran, seperti kurang oksigen yang mengalir ke otak (hipoksia), kerusakan karena tindakan (forsep), atau trauma lain pada otak bayi. 3). Cedera kepala yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kejang-kejang dapat timbul pada saat terjadi cedera kepala, atau baru terjadi 2-3 tahun kemudian. Bila serangan terjadi berulang pada saat yang berlainan baru dinyatakan sebagai penyandang epilepsi. 4). Tumor otak, merupakan penyebab epilepsi yang tidak umum, terutama pada anak-anak. 5). Penyumbatan pembuluh darah otak atau kelainan pembuluh darah otak. 6). Radang atau infeksi. Radang selaput otak (meningitis) atau radang otak dapat menyebabkan epilepsi. 7). Penyakit keturunan seperti fenilketonuria. Sklerosis tuberose dan neurofibromatosis dapat menyebabkan timbulnya kejang yang berulang. 8 8). Kecenderungan timbulnya epilepsi yang diturunkan. Hal ini disebabkan ambang rangsang serangan yang lebih rendah dari normal diturunkan pada anak. Kecenderungan timbulnya epilepsi yang diturunkan biasanya terjadi pada masa anak-anak (Harsono, 2005). Epilepsi dapat kambuh kembali dikarenakan beberapa faktor. Faktor pencetus timbulnya serangan pada penderita epilepsi, diantaranya yaitu : gangguan emosional, stress, tidur, haid, cahaya tertentu. Faktor yang lainnya yaitu faktor makan dan minum, suara tertentu, membaca, drug abuse, lupa atau enggan minum obat, faktor hiperventilasi dan suhu tubuh penyandangnya (Harsono, 2001). d. Patofisiologi Epilepsi Serangan epilepsi terjadi apabila proses eksitasi di dalam otak lebih dominan daripada proses inhibisi. Perubahan-perubahan di dalam eksitasi aferen, disinhibisi, pergeseran konsentrasi ion ekstraseluler, voltage-gated ion-channel opening, dan menguatnya sinkroni neuron sangat penting artinya dalam hal inisiasi serangan epileptik. Aktivitas neuron diatur oleh konsentrasi ion di dalam ruang ekstraseluler dan intraseluler, dan oleh gerakan keluar masuk ion-ion menembus membran neuron (Harsono, 2007a). Serangan epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron abnormal mengalami depolarisasi yang berkepanjangan berkenaan dengan cetusan potensial aksi secara cepat dan berulang-ulang. Cetusan 9 listrik abnormal ini kemudian menstimulasi neuron-neuron sekitarnya atau neuron-neuron yang terkait di dalam proses. Secara klinis serangan epilepsi akan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah besar neuron abnormal muncul secara bersama-sama, membentuk suatu badai aktivitas listrik di dalam otak (Harsono, 2007a). e. Klasifikasi Epilepsi Terapi epilepsi tidak hanya berdasarkan atas diagnosa yang tepat, jenis serangan juga harus ditentukan. Menurut Gidal dkk (2005) klasifikasi epilepsi berdasarkan tanda-tanda klinik dan data EEG, dibagi menjadi: 1). Kejang umum (generalized seizure) Jika aktivasi terjadi pada kedua hemisfere otak secara bersama-sama. Kejang umum terbagi atas: a). Absence (Petit mal) Jenis yang jarang dijumpai ini umumnya hanya terjadi pada masa anak-anak atau awal remaja. Kesadaran hilang beberapa detik, ditandai dengan terhentinya percakapan untuk sesaat. Penderita tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. b). Tonik-klonik (grand mal) Merupakan bentuk kejang yang paling banyak terjadi, biasanya didahului oleh suatu aura. Pasien tiba-tiba jatuh, kejang, nafas terengah-engah, dan keluar air liur. Bisa terjadi 10 juga sianosis, ngompol, atau menggigit lidah. Serangan ini terjadi beberapa menit, kemudian diikuti lemah, kebingungan, sakit kepala atau tidur. c). Mioklonik Serangan ini biasanya terjadi pada pagi hari, setelah bangun tidur pasien mengalami sentakan yang tiba-tiba. d). Atonik Serangan tipe atonik ini jarang terjadi. Pasien tiba-tiba kehilangan kekuatan otot yang mengakibatkan pasien terjatuh, namun dapat segera pulih kembali. 2). Kejang parsial Kejang parsial merupakan perubahan klinis dan elektro-ensefalografik yang menunjukan aktivitas sistem neuron yang berbatas di salah satu bagian otak. Kejang parsial ini terbagi menjadi: a). Simple partial seizure Pasien tidak mengalami kehilangan kesadaran, hanya terjadi sentakan-sentakan pada bagian tertentu dari tubuh. b). Complex partial seizure Pasien mengalami penurunan kesadaran. Penderita dengan penurunan kesadaran dapat mengalami perubahan tingkah laku. 11 3). Kejang tak terklasifikasikan Serangan kejang ini merupakan jenis serangan yang tidak didukung oleh data yang cukup atau lengkap. Jenis ini termasuk serangan epilepsi pada neonatus misalnya gerakan mata ritmis, dan gerakan mengunyah serta berenang. f. Diagnosa Epilepsi Diagnosa yang tepat sangat penting pada epilepsi. Orang yang terdiagnosa epilepsi mempunyai beberapa konsekuensi, penderita epilepsi akan meminum obat dalam jangka waktu yang lama yang berakibat pada kemungkinan adanya efek yang merugikan akibat OAE (Wibowo & Gofir, 2006). Konsekuensi psikologis dan sosial ini, dapat menciptakan disabilitas yang lebih besar pada penderita epilepsi dari disabilitas akibat gangguan otak itu sendiri. Oleh karena itu lebih baik tidak menegakkan diagnosa epilepsi sebelum dapat memastikan bahwa itu benar-benar epilepsi (Kusumaastuti, 2008). Diagnosis epilepsi ditegakkan terutama dari anamnesis, yang didukung dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Menurut Kusumastuti (2008), langkah-langkah dalam penegakkan diagnosis dalam praktik klinis adalah sebagai berikut: 1). Anamnesis Auto dan allo-anamnesis dari orang tua atau saksi mata mengenai gejala dan tanda sebelum, selama, dan pascabangkitan. Anamnesis lain yang perlu dilakukan adalah anamnesis terhadap 12 faktor pencetus, usia, durasi, dan frekuensi bangkitan, interval terpanjang antara bangkitan, kesadaran antara bangkitan, terapi epilepsi sebelumnya dan respon terhadap OAE sebelumnya, penyakit yang diderita sekarang, riwayat penyakit neurologis psikiatrik maupun sistemik yang mungkin menjadi penyebab maupun komorbiditas, riwayat epilepsi dan penyakit lain dalam keluarga, riwayat saat berada dalam kandungan- kelahiran- tumbuh kembang, riwayat bangkitan neonatal/ kejang demam, dan riwayat trauma kepala-stroke- infeksi susunan saraf pusat. 2). Pemeriksaan fisik umum dan neurologis Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mencari tanda-tanda gangguan yang berkaitan dengan epilepsi, seperti trauma kepala. Pemeriksaan neurologis berfungsi untuk mencari tanda-tanda defisit neurologis fokal atau difus yang dapat berhubungan dengan epilepsi. 3). Pemeriksaan penunjang, seperti berikut: a). Pemeriksaan elektro-ensefalografi (EEG) Rekaman EEG merupakan pemeriksaan yang paling berguna pada dugaan suatu bangkitan untuk membantu menunjang diagnosis, penentuan jenis bangkitan maupun sindrom epilepsi, prognosis, dan perlu/ tidaknya pemberian OAE. 13 b). Pemeriksaan pencitraan otak Berguna untuk mendeteksi lesi epileptogenik di otak secara non-invasif, seperti: Fuctional brain imaging seperti Positron Emission Tomography (PET), Singel Photon Emission Resonance Computed Tomography Spectroscopy (MRS), (SPECT), Magnetic Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Computed Tomography (CT) Scanning. c). Pemeriksaan laboratorium (1). Pemeriksaan hematologis Pemeriksaan hematologis di awal pengobatan sebagai salah satu acuan dalam menyingkirkan diagnosis banding dan pemilihan OAE, 2 bulan setelah pemberian OAE untuk mendeteksi efek samping OAE, rutin diulang setiap tahun sekali untuk memonitor efek samping OAE, atau bila timbul gejala klinis akibat efek samping OAE. (2). Pemeriksaan kadar OAE dilakukan untuk melihat kadar OAE dalam plasma saat bangkitan belum terkontrol, meskipun sudah mencapai dosis terapi maksimal atau untuk memonitor kepatuhan pasien. g. Prognosis Epilepsi Prognosis anak yang menderita epilepsi tergantung bermacam-macam faktor medis, sosial, dan psikologis. Secara umum prognosis epilepsi berhubungan dengan beberapa faktor seperti 14 kekerapan kejang, ada atau tidaknya defisit neurologis atau mental, jenis dan lamanya kejang (Taslim & Sofyan, 1999). Prognosis epilepsi cukup baik, pada 50-70% penderita epilepsi serangan dapat dicegah dengan minum obat-obat, sedangkan sekitar 50% pada suatu waktu akan dapat berhenti minum obat (Harsono, 2005). Prognosis epilepsi pada anak sangat tergantung pada jenis epilepsi yang dideritanya. Faktor yang berhubungan dengan baiknya prognosis diantaranya tidak terdapatnya kelainan neurologis dan mental, tidak kambuhnya kejang, terutama jenis tonik klonik umum, hanya terdapat satu jenis kejang, dan cepatnya kejang dikendalikan. Umur onset yang relatif lambat sesudah usia 2 atau 3 tahun merupakan faktor yang menguntungkan. Risiko kekambuhan setelah penghentian pengobatan tergantung pada faktor yang sama dengan remisi kejang. Faktor yang berhubungan dengan prognosis yang buruk diantaranya terdapat penyebab kejang organik, terdapatnya kelainan neurologis dan atau mental, terdapatnya beberapa jenis kejang tonik klonik umum yang sering dan atau kejang tonik dan atonik (Taslim & Sofyan, 1999). 2. Terapi Anti Epilepsi a. Prinsip Terapi Antiepilepsi Langkah selanjutnya yang diambil setelah diagnosa epilepsi ditegakkan adalah membuat rancangan tatalaksana farmakoterapeutik dengan mempertimbangkan setiap konsekuensi dari masing-masing pilihan terapi (Harsono, 2007b). 15 Prinsip pengobatan epilepsi adalah : 1). Pengobatan dilakukan bila terdapat minimum 2 kali bangkitan dalam setahun 2). Pengobatan dimulai diberikan bila diagnosa telah ditegakkan dan setelah penyandang dan atau keluarganya menerima penjelasan tujuan pengobatan dan kemungkinan efek samping 3). Pemilihan jenis obat yang sesuai dengan jenis bangkitan 4). Sebaiknya pengobatan dengan monoterapi 5). Pemberian obat dimulai dari dosis rendah dan dinaikan bertahap sampai dosis efektif tercapai 6). Pada prinsipnya pengobatan dimulai dengan obat antiepilepsi lini pertama. Bila diperlukan penggantian obat, obat pertama diturunkan bertahap dan obat kedua dinaikkan secara bertahap 7). Bila didapatkan kegagalan monoterapi maka dipertimbangkan kombinasi OAE 8). Bila memungkinkan dilakukan pemantauan kadar obat sesuai indikasi (Kustiowati dkk, 2003). b. Pediatrik Pediatrik bukan merupakan miniatur dari orang dewasa. Hal ini karena pada pediatrik masih terjadi pertumbuhan dan perkembangan dalam profil farmakologinya yang berbeda dengan populasi dewasa (US. Department of Health and Human Service, 2014). Menurut Europe Medicine Agency (EMA) (2001) populasi pediatrik dapat diklasifikasikan 16 menjadi 4 kelompok berdasarkan usia seperti berikut ini: 1). Neonatus (0 - 27 hari) 2). Infant (28 hari - 23 bulan) 3). Anak (2 - 11 tahun) 4). Remaja (12 - 18 tahun) c. Memulai Terapi Antiepilepsi pada Pasien Anak Sebagian besar kasus epilepsi dimulai sejak masa bayi dan anak. Penderita epilepsi anak, merupakan segmen pasien tertentu, yang dalam beberapa hal, berbeda dengan pasien dewasa. Manajemen terapi yang optimal diperlukan pengetahuan tentang kondisi anak, perkembanganya, status penyakitnya, dan tentu juga pengetahuan farmakologi OAE. Terapi epilepsi anak memerlukan perhatian khusus yang perlu dicermati, seperti misalnya pertumbuhan organ pasien, metabolisme hepar, eliminasi ginjal, profil farmakokinetik OAE, toleransi terhadap OAE, serta ketaatan mengkonsumsi obat. Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap penyesuaian dosis OAE yang akan diberikan (Wibowo dan Gofir, 2006). d. Pengobatan OAE secara Monoterapi pada Pasien Epilepsi Anak OAE monoterapi menjadi pilihan dalam memulai pengobatan epilepsi, karena sebagian besar pasien berhasil dikontrol dengan obat monoterapi pertama atau kedua yang diberikan. Penggunaan monoterapi dapat mengurangi potensial interaksi obat dan efek toksik yang 17 merugikan (Louis dkk, 2009). Sebagian besar pasien epilepsi merespon pengobatan dengan monoterapi, 47% pasien menjadi bebas kejang dengan percobaan OAE pertama, dan 13% mencapai bebasan kejang dengan percobaan monoterapi kedua (Kwan & Brodie, 2000). Pengobatan pada pasien epilepsi anak sedapat mungkin dengan monoterapi. Cara memilih OAE pertama adalah menentukan jenis epilepsinya. (Wibowo & Gofir, 2006). Tabel I. Pilihan Terapi Untuk Berbagai Tipe Bangkitan Epilepsi Anak Tipe seizure First-line drugs Second-line drugs Generalized tonic-clonic Karbamazepina, Lamotigrin, Valproat, Topiramata,b Klobazam, Levitirasetam, Okskarbazepina Absence Etosuksimid, Lamotigrinb, Valproat, Klobazam, Klonazepam, Topiramata Myoclonic Valproat, Topiramata Klobazam, Klonazepam, Lamotigrin, Levetirasetam, Pirasetam Tonic Lamotigrinb, Valproat, Klobazam, Klonazepam, Levetirasetam, Topiramata Atonic Lamotigrinb, Valproat Klobazam, Klonazepam, Levetirasetam, Topiramata Klobazam, Klonazepam, Valproat, Topiramata Steroida, Vigabatrinb Karbamazepina, Focal with/without Lamotigrina, Klobazam, Gabapentin, secondary Okskarbazepina,b, Levetirasetam, Fenitoina, generalisation Valproat, Tiagabin Topiramata,b Infantile Spasme Alternatif/obat lain Obat yang harus yang dapat dihindari (mungkin dipertimbangkan memperburuk kejang) Asetazolamida, Klonazepam, Fenobarbitala, Tiagabin, Vigabatrin Fenitoina, Primidona,c Kabarmazepina, Gabapentin, Okskarbazepina, Tiagabin, Vigabatrin Kabarmazepina, Gabapentin, Okskarbazepina, Tiagabin, Vigabatrin Asetazolamida, Fenobarbitala, Kabarmazepina, a Fenitoin , Okskarbazepina, Primidona,c Asetazolamida, Kabarmazepina, a Fenobarbital , Okskarbazepina, Primidona,c Fenitoina Kabarmazepina, Nitrazepam Okskarbazepina Asetazolamidac, Klonazepam, Fenobarbitala, Primidona,c Keterangan: a. Enzim hati menginduksi OAE b. Harus digunakan sebagai pilihan pertama dalam keadaan seperti diuraikan dalam NICE Technology Appraisal of Newer AEDs for Children c. Jarang dan perlu inisiasi, jika barbiturat yang digunakan lebih disukai (NICE Guideline, 2012) Edukasi yang dapat diberikan pada pasien anak : 18 1). Pasien dan orang tua diharapkan mengetahui permasalahan dan terapi epilepsi 2). Botol berisi obat epilepsi sebaiknya ditandai 3). Berusaha untuk hidup senormal mungkin 4). Anak-anak sebaiknya banyak melakukan kegiatan fisik yang sesuai dengan umur mereka 5). Tidur yang cukup, hindari kekurangan tidur (Shih, 2007) Pembagian dosis OAE untuk terapi pasien anak dapat dilihat pada Tabel II berikut. Obat Fenitoin Karbamazepin Okskarbazepin Lamotrigin Zonisamid Etosuksimid Felbamat Topiramat Clobazam Clonazepam Fenobarbital Pirimidon Vigabatrin Gabapentin Valproat Levetiracetam Tiagabin Tabel II. Dosis Obat Antiepilepsi untuk Pediatrik Dosis awal (mg/kg/hari) Dosis maintenance Frekuensi pemberian (mg/kg/hari) (kali/hari) 5 5-15 1-2 5 10-25 2-4 5 10-50 2-3 0,5 2-8 1-2 2-4 4-8 2 10 15-30 1-2 15 30-45 3-4 0,5-1 5-9 2 0,25 0,5-1 1-2 0,025 0,025-0,1 2-3 4 4-8 1-2 10 20-30 1-2 40 50-150 1-2 20 20-40 3 10 15-40 2-3 10 20-60 2 Tidak disarankan untuk anak di bawah usia 12 tahun (Brodie dkk., 2005) e. Penggolongan dan Mekanisme Kerja Antiepilepsi Wibowo & Gofir (2006) membagi mekanisme kerja obat antiepilepsi menjadi 2 bagian besar, yaitu : efek langsung pada 19 membran yang eksitabel dan efek melalui perubahan meurotransmitter. Berikut penggolongan OAE berdasarkan pada mekanisme tersebut: 1). Efek langsung pada membran yang eksitabel. Perubahan pada permeabilitas membran serta mencegah aliran frekuensi tinggi dan neuron-neuron pada keadaan lepas muatan listrik epilepsi (Wibowo & Gofir, 2006). OAE dengan mekanisme ini antara lain: a). Fenitoin : Ikaphen®, Dilantin®, Kutoin® Fenitoin diindikasikan sebagai terapi awal atau terapi tambahan pada serangan parsial kompleks atau serangan tonik klonik. Efek sampingnya dapat menimbulkan hiperplasia gingival yang reversibel dan efek samping kosmetik lainnya (Browne dan Holmes, 2000). Mekanisme aksinya dengan memblokade kanal natrium dan beraksi dengan konduktansi pada klorida dan kalsium, serta neurotransmisi voltage-dependent (Shorvon, 2000). Fenitoin memiliki kinetika eliminasi tergantung dosis dan dihidroksilasi di hati oleh sistem enzim. Peningkatan dosis yang kecil dapat meningkatkan waktu paruh dan kadar dalam serum yang besar. Peningkatan kadar tunak mungkin tidak proporsional dengan toksisitas yang dihasilkan dari peningkatan dosis 10% atau lebih (Porter dan Meldrum, 2012). 20 b). Karbamazepin : Tegretol® Derivat anti depresan trisiklik ini efektif untuk serangan parsial dan general tonik klonik, dapat diberikan secara tunggal atau kombinasi. Mekanisme kerja obat ini dengan menghambat kanal Na selama pelepasan dan mengalirnya muatan listrik sel-sel saraf serta mencegah potensial post tetanik (Wibowo & Gofir, 2006). c). Etosuksimid Etosuksimid sebagai obat pilihan untuk serangan absence pada anak-anak yang tidak disertai serangan tonik-klonik atau mioklonik (Wibowo & Gofir, 2006). Mekanisme kerja obat ini menghambat kanall Ca tipe T. Etosuksimid mempunyai efek penting pada arus Ca2+, menurunkan arus nilai ambang rendah (tipe T). Arus kalsium tipe T diperkirakan merupakan arus yang menimbulkan pemacu pada saraf talamus sehingga terjadi gelombang korteks yang ritmis dari serangan absence. Penghambat arus tersebut karenanya merupakan kerja terapeutik dari etosuksimid (Katzung, 2002). d). Valproat : asam dipropilasetat, Depakene®, Depakote®, Ikalep® Valproat diindikasikan sebagai drug of choice untuk epilepsi general idiopatik, epilepsi fokal, epilepsi mioklonik, 21 epilepsi fotosensitif, sindrom lennox dan second-line pada terapi spasme infantil (Wibowo & Gofir, 2006). Valproat memiliki mekanisme aksi yang multipel, yaitu mengahambat kanal Ca tipe T dan meningkatkan fungsi GABA tetapi hanya terlihat pada konsentrasi tinggi. Obat ini meningkatkan sintesa GABA dengan menstimulasi Glutamic Acid Dekarboksilasi (GAD). Obat ini menghasilkan modulasi selektif pada arus Na selama pelepasan muatan (Wibowo dan Gofir, 2006). Valproat menghambat metabolisme beberapa obat termasuk fenobarbital, fenitoin dan karbamazepin, menyebabkan konsentrasi obat-obat tersebut dalam darah menjadi meningkat. Penghambatan metabolisme fenobarbital menyebabkan kadar barbiturat meningkat secara tajam hingga menimbulkan stupor atau koma (Katzung, 2002). e). Okskarbazepin : Trileptal® Okskarbazepin karbamazepin, merupakan dikembangkan 10-keto dalam analog upaya dari untuk menghindari autoinduksi dan potensi interaksi sebagaimana terdapat pada karbamazepin. OAE ini telah memperoleh lisensi di seluruh dunia, lebih dari 50 negara. Beberapa negara telah menggunakan okskarbamazepin sebagai obat pilihan pertama (Harsono, 2007b). 22 Okskarbamazepin digunakan sebagai monoterapi atau terapi tambahan pada serangan parsial (sederhana, kompleks, umum sekunder) pada dewasa dan anak-anak, termasuk pasien yang baru terdiagnosa (Browne dan Holmes, 2000). Mekanisme aksinya dengan menghambat kanal Na dan berdampak pada konduktansi kalium dan memodulasi tegangan tinggi sehingga mengaktivasi kanal Ca (Shorvon, 2000). f). Lamotrigin : Lamictal® Lamotrigin diindikasikan sebagai terapi tambahan pada pasien dewasa dengan serangan parsial yang tidak terkontrol dengan obat-obat pilihan pertama seperti fenitoin dan karbamazepin. Lamotrigin memiliki toksisitas tergantung dosis yang minimal dan tidak memerlukan monitoring hasil laboratorium (Browne dan Holmes, 2000). 2). Efek melalui perubahan neurotransmitter a). Penghambatan aksi glutamat Obat-obat dengan aksi ini antara lain: (1). Felbamat Mekanisme kerja obat dengan memperkuat aktivitas GABA. Felbamat terbukti efektif baik pada monoterapi maupun terapi tambahan pada serangan parsial pada pasien dengan usia ≥14 tahun, obat ini juga 23 bermanfaat untuk sindrom lennox-gastaut yang tidak berespon terhadap terapi lain (Wibowo dan Gofir, 2006). (2). Topiramat : Topamax® Topiramat diindikasikan sebagai terapi tambahan untuk serangan parsial dan untuk serangan umum tonik-klonik primer pada pasien dewasa dan anak-anak berusia 2 hingga 16 tahun. Topiramat dilaporkan memiliki sedikit interaksi dan diberikan sebanyak 2 kali sehari (Browne dan Holmes, 2000). Mekanisme aksinya dengan menghambat kanal Na, memulai influx GABA-mediated chloride dan memodulasi efek dari reseptor GABAA dan bereaksi pada reseptor AMP (Shorvon, 2000). b). Mendorong aksi inhibisi Gamma Amino Butyruc Acid (GABA) pada membran pasca-sinaptik dan neuron Obat-obat dengan aksi ini antara lain: (1). Klonazepam : Riklona 2® Klonazepam sebagai agonis reseptor GABA, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap reseptor GABAA. Efektif untuk serangan mioklonik, serangan umum dan sedikit berperan pada serangan parsial. Obat ini digunakan sebagai terapi adjuvan untuk epilepsi refrakter. Klonazepam juga digunakan sebagai terapi 24 emergensi pada status epileptikus seperti diazepam (Wibowo dan Gofir, 2006). (2). Fenobarbital : fenobarbiton, Luminal® Fenobarbital beraksi langsung pada reseptor GABA dengan berikatan pada tempat ikatan barbiturat sehingga memperpanjang durasi pembukaan kanal Cl, mengurangi aliran Na dan K, mengurangi influks Ca dan menurunkan eksitabilitas glutamat. Fenobarbital merupakan OAE dengan spektrum luas, digunakan pada terapi serangan parsial dan serangan umum sekunder. Obat ini digunakan sebagai second drug karena memberikan efek buruk seperti sedasi dan penurunan daya kognitif, namun pada status epileptikus, obat ini masih digunakan sebagai first drug (Wibowo dan Gofir, 2006). (3). Klobazam : Frisium® Klobazam merupakan derivat 1,5-benzodazepin (1982) yang memiliki khasiat antikonvulsi yang sama kuatnya dengan diazepam. Klobazam digunakan sebagai obat tambahan pada absence yang resisten terhadap klonazepam. Tidak dapat dikombinasi dengan valproat (Tan dan Rahardja, 2000). Klobazam merupakan terapi tambahan pada serangan parsial, umum, terapi 25 intermittent, terapi one-off profilaktik, dan non-konvulsif status epileptikus (Shorvon, 2000). (4). Gabapentin : Neurontin® Gabapentin mempunyai hubungan struktural yang sangat dekat dengan GABA. Walaupun dirancang sebagai agonis GABA, pengalaman dan bukti klinis menunjukan bahwa gabapentin tidak beraksi atau sedikit beraksi terhadap reseptor GABAA maupun GABAB. Sementara itu, gabapentin juga tidak berpengaruh terhadap sintesis GABA. Awalnya gabapentin diteliti manfaatnya sebagai antispasmodik dan sebagai analgetik. Kemudian gabapentin diteliti manfaatnya sebagai OAE. Saat ini gabapentin sudah memperoleh lisensi untuk dipakai sebagai OAE di Inggris, Amerika Serikat, Eropa daratan dan berbagai negara lainnya, namun demikian ada yang menggunakan gabapentin sebagai analgetik walaupun tanpa lisensi. Gabapentin dipakai sebagai adjuvan untuk serangan parsial atau serangan umum sekunder pada terapi epilepsi (Harsono, 2007b). 3). Obat dengan mekanisme lain a). Levetiracetam : Keppra® Levetiracetam diterima oleh FDA untuk mengatasi serangan parsial. Obat ini dapat digunakan bersama dengan 26 obat lain pada orang berusia 4 tahun ke atas. Keppra juga diterima oleh FDA untuk mengatasi mioklonik pada orang dewasa dan epilepsi mioklonik juvenil untuk orang berusia 12 tahun ke atas. Obat ini diekskresi di ginjal, dan dosisnya dapat mengalami perbedaan pada orang yang mengalami gangguan ginjal. 3. Efek Terapi Efek terapi merupakan hasil yang diharapkan setelah pemberian terapi yaitu meningkatnya outcome. Penilaian outcome pada pasien epilepsi selain pengurangan keparahan kejang, pengukuran kualitas hidup pasien juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana aspek psikososial pasien. Pengurangan kejang akan berdampak langsung pada fungsi psikososial pasien (Sabaz dkk, 2001). Penurunan jumlah kejang merupakan penilaian outcome yang paling mudah dilakukan. Pasien datang kontrol ke poliklinik secara rutin, akan mudah menanyakan jumlah kejang yang terjadi setelah kontrol sebelumnya, ataupun jumlah kejang yang sesuai periode yang diinginkan, misalnya sebulan, seminggu, ataupun sehari. Pasien dikatakan berespon terhadap pengobatan jika pengurangan frekuensi kejang lebih dari 50%. Selain penurunan jumlah kejang, pengukuran keparahan kejang juga merupakan parameter efek terapi Obat Anti Epilepsi (Bachtera, 2007). Cramer dan French (2001) meyebutkan, penilaian kuantitatif keparahan kejang dapat dilakukan dengan berbagai sistem, seperti : 27 a. Veterans Administration (VA) Scale Sistem ini menilai frekuensi kejang yang terjadi pada kejang tipe parsial (secondarily generalized tonic–clonic, complex partial seizure dan simple partial seizure) maupun keparahan kejangnya. VA Scale diselesaikan oleh dokter berdasarkan pertanyaan spesifik tentang komponen kejang yang dilakukan dengan pemeriksaan dan wawancara. VA Scale dikritik karena merupakan sistem skoring yang kompleks, meskipun penilaian terhadap beberapa kejang dapat dihitung. b. Chalfont-National Hospital Seizure Severity Scale (NHS3) Chalfont Seizure Severity Scale merupakan penyederhanaan dari VA Scale yang kemudian diperbaharui dan berganti nama menjadi National Hospital Seizure Severity Scale (NHS3). Skala ini digunakan untuk pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Kuesioner diberikan oleh dokter yang mewawancarai pasien dan orang-orang yang menyaksikan tipe kejangnya. Penilaian ini terhadap 3 jenis kejang ( kejang umum, complex partial seizure dan simple partial seizure). c. Occupational Hazard Scale Sistem ini menggambarkan tingkat bahaya berdasarkan frekuensi dan keparahan kejang. Gangguan sosial yang mungkin disebabkan oleh kejang (seperti, risiko kecelakaan) merupakan suatu hal yang penting. Skala ini memberikan contoh jenis kejang dan status pengobatan, digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pemilihan pekerjaan pasien berdasarkan tingkat keparahan kejang. 28 d. Liverpool Seizure Severity Scale (LSSS) LSSS dikembangkan untuk menilai keparahan kejang pasien yang dirasakan oleh pasien. Kuesioner dijawab oleh pasien tanpa adanya interpretasi dari penyedia layanan kesehatan untuk menilai aktivitas kejang selama 4 minggu sebelumnya. Item skala berfungsi untuk mendiskripsikan persepsi pasien dari dampak kejang pada fungsi sehari-hari tanpa menetapkan poin disetiap pertanyaan. Kuesioner ini tidak memberikan informasi tentang frekuensi yang tepat dari kejang dan juga tidak menggambarkan klasifikasi kejang secara spesifik. e. Hague Seizure Severity Scale (HASSS) HASSS merupakan pengembangan skala keparahan kejang untuk anak-anak yang didasarkan pada persepsi orang tua pasien. Sebagian besar konten HASSS berdasarkan LSSS dan didesain ulang menjadi kuesioner yang diisi oleh orang tua, bukan pasien. Komponen dari beberapa kuesioner diatas hampir sama, yaitu : frekuensi kejang, jenis kejang, durasi kejang, kejadian postictal, durasi postictal, automatisme, pola yang diketahui, tanda-tanda, menggigit lidah dan gangguan fungsional (Cramer dan French, 2001) Kuesioner yang digunakan adalah Hague Seizure Severity Scale (HASSS) merupakan bentuk kuesioner yang dikembangkan oleh Carpay, dkk. (1996) untuk mengukur keparahan kejadian kejang yang terjadi selama 3 bulan terakhir berdasarkan persepsi orang tua. Nilai HASSS berkisar antara 13-54 (Carpay dkk.,1996). 29 F. Keterangan Empirik Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pengobatan dan efek terapi OAE secara monoterapi dilihat dari frekuensi dan keparahan kejang pada pengobatan pasien epilepsi pediatrik rawat jalan dengan umur 4-16 tahun di Instalasi Kesehatan Anak Sub. Bagian Neurologi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada periode Januari-Maret 2015. Evaluasi efek terapi dinilai dalam suatu kuesioner yang diberikan kepada subyek penelitian yang bersedia. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan jumlah kejang sebulan terakhir dan pertanyaan-pertanyaan terjemahan dari Hague Seizures Severity Scale (HASSS). HASSS ditujukan untuk mengukur keparahan kejang. 30