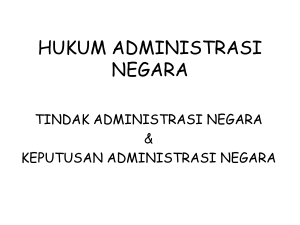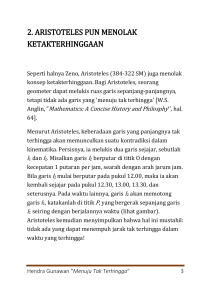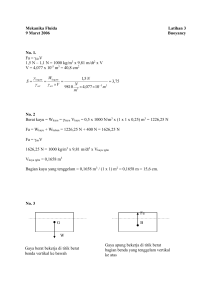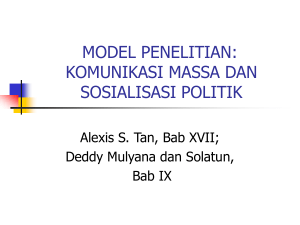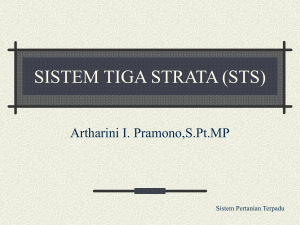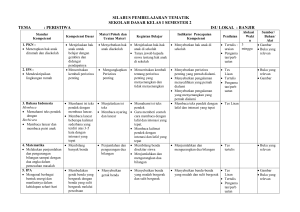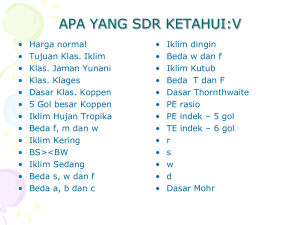bangkitnya budaya intelektualitas jawa di kediri 1915
advertisement

1 BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Pada awal abad ke-20, Gemeente Kediri1 diramaikan dengan mulai dibukanya toko buku Tan Khoen Swie pada tahun 1905. Sepuluh tahun kemudian (1915), pemilik toko membuka penerbitan yang kemudian diberi nama Boekhandel Tan Khoen Swie. Ramainya kegiatan transaksi selama kurun waktu tahun 19201926 dapat dibaca dalam sepuluh surat pembaca dari berbagai kota di Jawa Timur yang dilayangkan kepada redaksi Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri. Surat Ik Tie Tjoe dari Banyuwangi dengan gembira dan bersyukur atas kiriman dan diterbitkannya Buku Sioe Lian, demikian pula ucapan senada Ik Tjong Tjoe dari Jember, Ik Kan Tjoe Probolinggo, Boen Sim Tjoe Pasuruan, selain Buku Sioe Lian khususnya Boen Sim Tjoe meminta Tan Khoen Swie untuk menerbitkan ilmu theosofi.2 Demikian pula Soe Pin Kie Soe beralamat Surabaya mendatangi langsung ke dapur redaksi Boekhandel Tan Khoen Swie setelah membaca Buku Sioe Lian Sejarah status kota Kediri dimulai Sejak 1 April 1906, dengan ditetapkan sebagai Gemeente. Sifat pemerintahan otonom terbatas, dan memiliki Gemeente Raad sebanyak 13 orang, yang terdiri atas 8 orang golongan Eropa dan yang disamakan, 4 orang Pribumi (Inlander) dan 1 orang bangsa Timur Asing. Dalam perkembangannya, kota Kediri pada 1 Nopember 1928 menjadi Zelfstanding Gemeenteschap (menjadi otonom penuh) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Lihat Staatsblad no. 148 tertanggal 1 maret 1906, dan berdasarkan Staatsblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906. Lihat juga Staatsblad No. 498 Tahun 1928. 1 2 Surat-surat para pembaca dapat dibaca pada buku Kitab Sioe Lian. Lihat Ien Sie Tjoe, Kitab Sioe Lian (Samadhi), cetakan ke-2, (Kediri : Boekhandel Tan Khoen Swie, 1926), hlm. 7, 28, 30, 32. 2 dan banyak memujinya. Tjing Tjaij Tjoe Djien dari Kertosono, Siauw Jauw Loo Djien dari Kediri, Boen Iet Ong Tulungagung, Kwan Liam Tjoe Blitar, dan Boe Bing Tjoe dari Malang, mereka memuji dan berterima kasih atas kiriman buku-buku Tan Khoen Swie.3 Pada periode berikutnya kota itu menjadi dikenal di seluruh Jawa dan luar Jawa berkat buku-buku produk penerbitan tersebut. Aktivitas penting penerbitan yang dikendalikan oleh Tan Khoen Swie itu menjadi perhatian M.C. Ricklefs. Dalam Bagian sub bab karyanya, Ricklefs membahas tiga buku produk Boekhandel Tan Khoen Swie, Babad Kadhiri, Suluk Gatholoco dan Serat Darmogandhul yang dinilai mengandung unsur ajaran penyebab munculnya konflik-konflik horisontal yang berujung pada terbentuknya polarisasi pada masyarakat Jawa pada awal abad ke-20.4 Menurut Subardi, munculnya konflik-konflik tersebut dinilai juga terkait dengan kondisi masyarakat yang semakin melek huruf dan berkembang intelektualitasnya setelah naskah-naskah klasik itu diubah dari bentuk macapat menjadi bacaan bebas oleh Tan Khoen Swie.5 3 Ien Sie Tjoe, Kitab Sioe Lian (Samadhi), cetakan ke-2, (Kediri : Boekhandel Tan Khoen Swie, 1926), hlm. 34, 36, 38, 40, 41, dan 45. 4 M.C. Ricklefs, Polarising Javanese Society Islamic and Other Visions (Singapore: NUS Press, 2007), hlm.181. 5 Subardi, “Transformasi Teks Macapat Terbitan Boerkhandel Tan Khoen Swie”, Disertasi, Universitas Negeri Malang, Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Oktober 2012. 3 Perbincangan tentang Tan Khoen Swie tidak hanya marak di dunia akademik,6 di kalangan jurnalis, pembicaraan itu menjadi tema yang menarik. Beberapa penulis media massa,7 memaparkan dengan tema bervariasi. Hal yang menarik dari perbincangan itu memberi kata sepakat bahwa Tan Khoen Swie sebagai seorang perubah (man of change) yang telah melakukan upaya merubah kondisi masyarakat yang berbudaya tutur menjadi budaya baca. Pembicaraan tentang Tan Khoen Swie tidak terlepas dengan tempat usahanya, yaitu kota Kediri. Secara historis, Kediri menyimpan kenangan sebagai kerajaan pusat sastra yang telah menerbitkan buku-buku kakawin. Buku-buku itu pada abad ke-18 dan ke-19 telah disusun dan ditulis kembali oleh Yasadipura.8 Oleh Pigeaud, periode itu disebut sebagai renaisance Sastra Jawa di Surakarta.9 Apakah kemudian kota itu akan dibangkitkan kembali sebagai pusat sastra oleh Tan Khoen Swie ? Sebuah pertanyaan menarik. Terlepas dari pandangan yang menggoda itu, Kediri juga mengalami imbas dari berakhirnya masa kapujanggan di keraton Surakarta. 6 Belly Isayoga Kristowidi, “Boekhandel Tan Khoen Swie 1915-1950-an: Nilai Kultural dalam Terbitan TKS”. Skripsi S-1 Sejarah Unair Surabaya, 2012. 7 Seperti antara lain Djulianto Susantio, “Mengenang Boekhandel Tan Khoen Swie”, dalam Jurnal Ilmu Arkeologi, Minggu, 24 Mei 2009. Sawega A.M, “Peran Kebudayaan Tan Khoen Swie”, Kompas, Sabtu, 6 April 2002. Seno Joko Suyono, dkk., “Harta Karun Boekhandel Tan Khoen Swie”, Tempo Interaktif, 21 Oktober 2002. 8 S. Margana, Pujuangga Jawa dan Bayang-bayang Kolonial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 21, 47-48. 9 hlm. 7. Th. Pigeaud, The Literature of Java, Vol.I, (The Hague : M. Nijhoff, 1967), 4 Setelah berakhirnya periode kapujanggan, atau saat kematian10 Pujangga Ranggawarsita pada tahun 1873, tidak ada lagi naskah-naskah yang dihasilkan dari keraton, sementara masyarakat memerlukan sumber baca. Faktor yang lain, ditunjang suasana kondusif di luar keraton terutama di wilayah-wilayah pedalaman, keseragaman budaya pada golongan terpelajar semakin menguat. Oleh karena itu budaya kapujanggan di keraton Surakarta yang dianggap sebagai satu-satunya peradaban asli Jawa keluar dan menyebar, berkembang di berbagai wilayah. Perkembangan budaya kapunjanggan (budaya menulis) atau kepengarangan di berbagai wilayah diikuti pula dengan munculnya berbagai penerbitan. Penulis-penulis lokal di luar keraton bermunculan di berbagai wilayah Jawa Timur (Ngawi, Lumajang, Bjonegoro, Blitar, Tulungagung, Surabaya, dan Kediri), di Jawa Tengah (Cilacap, Semarang, Surakarta, dan Karanganyar).11 Kemunculan penulis-penulis lokal tersebut diiringi dengan munculnya penerbit-penerbit baru di berbagai kota di Jawa. Dalam catatan Leo Suryadinata,12 pada akhir abad ke-19, 10 Menurut Andjar Any, kematian Ranggawarsita diduga karena dihukum mati, sehingga ia bisa mengetahui dengan persis kapan hari kematiannya, terbukti tanggal kematiannya 24 Desember 1873 tertulis dalam karya terakhirnya, Serat Sabdajati yang ia tulis sendiri. Andjar Any, Raden Ngabehi Ronggowarsito, Apa yang Terjadi? (Semarang: Aneka Ilmu, 1980). 11 Data didasarkan pada naskah-naskah tulisan pengarang yang masuk ke redaksi dan telah diterbitkan Boekhandel Tan Khoen Swie, seperti yang ditulis Boedihardjo dari Lumajang pada naskah Boedihardjo, R., Tjinta Kebaktian pada Tanah Air, (Kediri : Boekhandel Tan Khoen Swie, 1941). Demikian halnya tulisan Soedjonoredjo dari Karanganyar, Soedjonoredjo, R., Wedatama Winardi, (Kediri: Boekhandel Tan Khoen Swie, 1953). 12 Leo Suryadinata, Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia, (Jakarta: Grasindo,1996), hlm. 62. 5 penerbitan-penerbitan milik orang-orang Tionghoa bermunculan, di Jakarta (4), Bogor (1), Semarang (2). Antara 1900-1923 jumlah penerbitan mereka berkembang pesat, di Jakarta (19), Bogor (1), Sukabumi (2), Bandung (4), Cirebon (1), Pekalongan (1), Cilacap (1), Semarang (2), Surakarta (2), Surabaya (2), Malang (2), Jombang dan Kediri masing-masing satu penerbit. Tahun-tahun berikutnya, di Tegal dan Kudus (3), Gresik (1), Bangil (1), Bondowoso (1), Blitar (3), Madiun (1), dan Kebumen (1).13 Di Kediri, Tan Khoen Swie memanfaatkan suasana kondusif untuk membuka usaha penerbitan. Langkahnya memberi pengaruh pada munculnya usaha penerbitan dan media masa di kota itu.14 Beberapa media masa yang terbit di Kediri seperti, Sri Djojobojo (1920), Hindia Timoer (1926), Padang Boelan (1924), Sekartadji (1934), Mardi Hardjo (1922), Heroe Tjokro (1923), dan De Kedirische Courant (1922). Beberapa majalah dan Surat kabar yang terbit sesudah kemerdekaan : Djojobojo (1945), Soeara Rakjat (1945), Pelajar Merdeka (1946), Menara Merdeka (1946), Hari Warta (1947), Berita Rakjat (1947), Tinjauan (1948).15 13 Leo Suryadinata, Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia, (Jakarta: Grasindo,1996), hlm. 62. 14 Media Massa yang secara langsung dikendalikan Tan Khoen Swie, Soeara Sam Kauw Hwee Kediri yang terbit pertama kali bulan Januari 1935 dan berakhir Pebruari 1936. Harian Oetoesan, terbit di Kediri tahun 1930-an, Tan Khoen Swie sebagai penasehat. Lihat Oetoesan, 13 Desember 1934. Setelah 20 Desember 1934, Harian Oetoesan tersebut berganti nama Neratja Timoer. Ucapan selamat berpisah dari Redaktur Chen, dalam Oetoesan, 20 Desember 1934. 15 Suripan Sadi Hutomo, Teraju Ombak, Masalah Sosiologi Sastra Indonesia, (Surabaya: Gayamasa, 1995), hlm.115. 6 Semaraknya aktivitas penerbitan dan media masa di Kediri menarik untuk dicermati, karena melalui penerbitan dan media masa, perkembangan sejarah intelektual dan budaya penulisan dapat diketahui. Penelitian ini akan mencoba menganalisa bagaimana Tan Khoen Swie sebagai pemilik penerbitan menjalankan usahanya menghadapi situasi dan kondisi dua jaman yang berbeda; masa kolonial dan masa kemerdekaan. Dalam historiografi Indonesia, kiprah Tan Khoen Swie tidak pernah disinggung. Sepak terjangnya jarang mendapat perhatian, padahal ia memiliki kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan intelektualitas Jawa. Dia kelahiran Gunung Legong, Duren Siwo, Wonogiri pada tahun 1884,16 dan meninggal di Kediri tahun 1953.17 Semasa hidupnya, ia menggeluti kebatinan Jawa, fasih berbahasa Jawa, menulis dan membaca aksara Jawa. Ia lebih dikenal sebagai seorang Tionghoa yang berbudaya Jawa. Pengalaman di dunia penerbitan, ia peroleh ketika bekerja di Drukkerijk Sie Dhian Ho Surakarta.18 Pekerjaannya itu 16 Tan Hoen Boen, Orang-orang Tionghoa yang Terkemoeka di Jawa (Surakarta: The Biographical Publishing Center, 1935), hlm. 89. 17 Jasadnya disemayamkan di Bong (pemakaman) Tionghoa di lereng Gunung Klotok, Kota Kediri. “Tan Khoen Swie: Penerbit dan Penulis Meninggal Dunia”, dalam Jawa Pos, 5 Mei 1953. 18 Sie Dhian Ho Surakarta, di samping memiliki kegiatan di dunia pernerbitan juga usaha sampingan berupa firma dagang, terutama memperdagangkan kain batik. Lihat Benny G. Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm.339. 7 yang mengenalkan dia dengan Ki Padmosusastra, 19 seorang sastrawan dari keraton Surakarta. Tan Khoen Swie membuka usaha penerbitan di Kediri diduga karena situasi kehidupan sosial ekonomi di Surakarta kurang kondusif. Kerusuhan rasial20 antara pedagang Jawa dan Tionghoa yang dikelola oleh Firma Sie Dhian Ho, menyebabkan aktivitas penerbitan di Surakarta terganggu. Hal ini yang mendorongnya untuk membuka usaha penerbitan di kota Kediri, yang kemudian dikenal dengan nama Boekhandel Tan Khoen Swie. Boekhandel Tan Khoen Swie mengawali usaha penerbitan buku sejak tahun 1915-an, dari sebuah kompleks bangunan pertokoan di Jalan Dhoho Kota Kediri.21 Beberapa buku berhasil dicetak kembali, baik naskah aslinya maupun salinan yang secara langsung diperoleh dari para penulis naskah-naskah lisan.22 19 Padmosusastro memelopori cara bercerita modern (gagrak anyar) dalam sastra Jawa. Padmosusastro juga dikenal sebagai jurnalis. Ia pernah memimpin koran Jawa Bramartani dan majalah berbahasa Jawa Jawi Kandha. Tahun 1911 ia penulis aneka tata bahasa Jawa, seperti Paramabasa, Layang Basa Jawa. Lihat Imam Supardi, Ki Padmosusastro (Surabaya: Penyebar Semangat, 1961), hlm. 5-11. 20 Kerusuhan itu merupakan pengaruh dari boikot pasar pedagang Tionghoa di Surabaya pada 1912. Firma Sie Dhian Ho berusaha menekan kain batik yang mereka beli dari Lawean. Sebagai balasannya, para pedagang di bawah pimpinan Martodharsono melakukan boikot terhadap firma Sie Dhian Ho, yang menyebabkan perkelahian masal antara anggota-anggota SI dengan orang-orang Tionghoa di jalanan Surakarta. G. Beny Setyono, loc. cit. 21 Pada foto tahun 1920-an itu terpampang sebuah tulisan : “Toko Tan Khoen Swie, Sedia Boekoe Djawa, Melajoe dan Ollanda”. Gambar foto Toko Surabaya, tahun 1920 berada di ruang tamu drg. Jojo Soetjahjo Gani Jl. Doho, 165 Kediri. 22 Ungkapan-ungkapan para guru ditulis sendiri oleh Tan Khoen Swie dan disusun dalam Kitab Ilmoe Wedjangan Goeroe-goeroe. Lihat Kitab Ilmoe Wedjangan Goeroe-goeroe (Kediri: Boekhandel Tan Khoen Swie, 1935). 8 Upaya Boekhandel Tan Khoen Swie untuk menggali naskah-naskah yang telah tersimpan dalam memori masyarakat dan menyajikannya kembali dalam bentuk buku-buku yang secara bebas dapat dibaca oleh semua lapisan masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Tidak ada lagi sesuatu yang bersifat rahasia dari ilmu kebatinan, ilmu para guru dan pengetahuan kehidupan formal dari dunia keraton.23 Hal tersebut diungkapkan Boekhandel Tan Khoen Swie dengan tulisan yang lebih bebas untuk diketahui secara umum. Tan Khoen Swie banyak menerbitkan buku-buku berbahasa Jawa berkat bantuan Padmosusastro, R. Tanoyo, dan Mangoenwidjaja dari Kartasura. Apakah latar belakang asal Tan Khoen Swie dari Wonogiri itu menjadi alasan untuk menerbitkan buku-buku berbahasa Jawa, di samping alasan prospek pasar konsumennya terbanyak adalah orang-orang Jawa di berbagai wilayah, baik di pedesaan maupun di kota, menjadi pentanyaan menarik. Di samping ketiga penulis di atas, Tan Khoen Swie juga berhasil memanfaatkan jaringan penulis pribumi dari berbagai daerah dalam membantu usaha penerbitannya. Beberapa penulis yang diundang untuk membicarakan ide-ide yang akan ditulis antara lain berasal dari Yogyakarta, Surakarta, Bojonegoro, Surabaya, dan Lumajang.24 Demikian halnya beberapa penulis dari Cilacap dan 23 Tema-tema tentang kehidupan keraton diperoleh dari Padmosusastro pujangga keraton Surakarta, Kepala Perpustakaan Radya Pustaka. Wawancara dengan drg, Jojo Soetjahjo Gani, (Cicit Tan Khoen Swie), 24 April 2012. 24 Naskah yang disumbangkan dari penulis Lumajang buku Atoeran dari Hal Melakoeken Hak Perkoempoelan dan Persidangan Dalem Hindia-Nederland, yang dikarang oleh R. Boedihardjo, Patih Lumajang, cetakan 1932. Juga buku Tjinta Kebaktian pada Tanah Air, terbitan 1941. Dari kedua buku yang dicetak ini terlihat jiwa nasionalisme Tan. 9 Ngawi seringkali datang untuk bergabung.25 Tan Khoen Swie juga didukung oleh warga Tionghoa, di antaranya Tjoa Boe Sing, Tan Tik Sioe, Sioe Lian, Tjoa Hien Tjioe, Tan Soe Djwan. Mereka adalah para penulis, jurnalis, redaktur, dan pengusaha penerbitan Tionghoa. Fasilitas untuk keperluan penulis menjadi perhatian utama Tan Khoen Swie. Tan Khoen Swie menyediakan rumahnya menjadi semacam artist residence. Ia membangun kamar-kamar khusus untuk persinggahan jaringan penulis. Upaya ini dimaksudkan untuk menarik para penulis. Dari tangan Padmosusastro, R. Tanojo, dan Mangoenwidjaja, ketiganya berperan besar membawa naskah-naskah keraton untuk diterbitkan Boekhandel Tan Khoen Swie. Seperti Ardjunawiwaha (Pakubuwono III), Bawa Sagerongipoen (K.G.P.A.A. Mangkoenegara IV), Weda Tama (K.G.P.A. Mangkoenegara IV), Nitik Kraton (Pakubuwono IV), Pati Tjentini (Pakoebuwono V), Pramanasidi (Pakoebuwono X), Sendon Langen Swara (Kanjeng Gusti Adipati Arja MangkoenagaraIV), Woelangreh (Pakoebuwono IV), Sasmita Rahardja (Pakubuwono IV), Widijakirana (Pakubuwono IV).26 Di samping itu ketiganya juga menulis naskah-naskahnya sendiri untuk diterbitkan. Pada awal tahun 1916, pencetakan buku telah dilakukan, antara lain 25 Wawancara dengan drg. Jojo Soetjahjo Gani, (Cucu Tan Khoen Swie), 24 April 2012. 26 Catalog Kitab-kitab Pengetahuan Lahir-Batin terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri, 1941. 10 Kawruh Kasukman, Serat Babad Surakarta.27 Serat Madoe Wasito diterbitkan 1918.28 Disusul Serat Hasmorolojo dan Kridosastro oleh R.Ng. Mangoenwidjaja, tahun 1919.29 Perkembangan tahun 1920-1930-an semakin bertambah naskahnaskah diterbitkan sampai kematian Tan Khoen Swie tahun 1953. Michael Tanzil, putra ketiga Tan Khoen Swie, melanjutkan usaha Boekhandel Tan Khoen Swie. Ia menerbitkan beberapa buku baru dan mencetak ulang beberapa buku lama. 30 Beberapa cetakan ulang, yang dilakukan Michael Tanzil, antara lain buku Primbon Jayabaya tahun 1958, Bagawadgita, tahun 1959. Pada akhir tahun 1950-an, Michael Tanzil mencetak ulang buku Aji Asmaragama, buku tentang seni hubungan suami-istri untuk mendapat keturunan. Dalam edisi cetak, buku itu dilengkapi dengan foto ilustrasi adegan suami-istri. Buku-buku tersebut tidak sempat beredar, karena terlebih dahulu disita pemerintah. Buku terakhir yang diterbitkan Michael Tanzil dengan menggunakan nama penerbit Boekhandel Tan Khoen Swie adalah “Flowers of Leisure : an exhibition of Oil 27 Naskah Kawruh Kasukman diterbitkan Boekhadel Tan Khoen Swie Kediri tahun 1916, pada saat yang sama, Penerbit De Bliksem Surakarta, juga menerbitkan judul naskah yang sama. Serat Babad Surakarta disebut juga Babad Giyanti, diterbitkan dalam bentuk tembang mocopat pada tahun 1916 oleh Boekhandel Tan Khoen Swie. 28 Serat Madoe Wasito selesai ditulis Ki Padmosusastro tahun 1916, dan diterbitkan Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri tahun 1918. 29 Pada tahun yang sama oleh Boekhandel Tan Khoen Swie juga diterbitkan beberapa buku untuk konsumsi masyarakat Tionghoa, antara lain : Kitab Samadhi Sioe Lian. 30 Buku baru karya Michael Tanzil, “Pembatasan Penduduk dan Pengendalian Kelahiran” yang menggunakan nama penerbit Interstar. Lihat Michael Tan B.S., Pembatasan Penduduk dan Pengendalian Kelahiran, (Kediri: Interstar, 1959). 11 Paintings”,31 tahun 1963. Setelah itu tidak ada lagi buku-buku yang diterbitkan bahkan aktivitas Boekhandel Tan Khoen Swie tidak berjalan lagi. Boekhandel Tan Khoen Swie mulai tidak terurus sekitar 1963, ketika ditinggal Michael Tanzil pindah ke Jakarta. Penelitian ini membatasi buku-buku terbitan sebelum tahun tersebut. Karakter naskah-naskah terbitan Tan Khoen Swie berbeda dengan naskahnaskah terbitan Balai Pustaka. Produk terbitan Tan Khoen Swie menurut pandangan Sri Widati dikategorikan sastra Jawa non Balai Pustaka yang cenderung lebih berpihak pada kultur pribumi, praktis, mudah dimengerti pembaca umum, kendati yang diterjemahkan karya klasik.32 Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Modern,33 efisien, dan efektif. Bahasanya tidak banyak pengulangan, padat, dan tanpa kata-kata mubazir. Cetakannya tipis-tipis, dengan bahan dari kertas merang. Hal ini dimungkinkan agar dapat terjangkau dan terbeli oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Beberapa buku Tan Khoen Swie yang mengandung nilai-nilai budaya pemikiran Jawa seperti tentang teosofi, misalnya, seperti Serat Wuninga ing Gaib, Skandha Karma, Pejah Saksampuni lajeng kados pundi, Wawarah Samadi, Warni Pitu jejer dumadosipun manungso, Kawruh Kasukaman, Kawruh Teosofi, 31 Buku itu terbit dalam edisi berbahasa Inggris. Menguraikan tentang keindahan lukisan bunga-bunga luang. Keterangan Yuriah Tanzil, pada 26 April 2014 di Jakarta. 32 Sri Widati, dkk., Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Pra Kemerdekaan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 162. 33 Istilah Bahasa Jawa Modern dipakai untuk menunjukkan bahasa yang dipakai dalam sastra Jawa pada jaman para pujangga (akhir abad ke-18 awal abad ke-19, di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Lihat P.J. Zoetmulder, Kalangwan : Sastra Jawa Kuno Selayang pandang (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 34. 12 Swaraning Asepi. Tema pendidikan dan budi pekerti, Wulangreh, Wedatama Wiradi. Mengandung ilmu pengetahuan, misalnya Adji Jopomontro, Kridohatmoko, Patak Modin, Pastikowarno, Hidajat Djati, Nitiprana, Soponolojo, Bauwarna, Kabutuhan, Kapratjajan, Prasidodjati, Poerwo Karono,Sukanda Karmo.34 Selain buku-buku dengan tema di atas terdapat pula buku-buku tentang primbon Jawa yang menjelaskan tentang rahasia numerologi, misalnya Primbon Djampi Djawi, Primbon Hadu Djago, Primbon Ngimpi,35 Primbon Djajabaja, Achli Noedjoem, Kitab Ramalan, dan Illaduni.36 Buku-buku Primbon tersebut memuat berbagai hal, tentang persoalan hidup. 37 Buku-buku itu diterbitkan tahun 1919 hingga 1956. Pada masa itu, buku-buku demikian paling banyak diminati masyarakat. Bagaimana Tan memahami peluang pasar terhadap buku-bukunya, menjadi perhatian penting dalam kajian ini. Naskah-naskah terbitan Tan Khoen Swie beredar di hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya buku kebatinan, ramalan, primbon, legenda dapat dijumpai di setiap rumah, baik di desa maupun di kota. Menurut Sardono, Tan Khoen Swie 34 Lihat klasifikasi tema-tema buku terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie dalam Daftar Kitab-kitab Kawedalaken Saka Kasade Dening Toko Buku Tan Khoen Swie Kediri, 1 Februari 1953, hlm. 23-25. 35 Catalogus Kitab-kitab Lahir Bathin, terbitan dari Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri, 1941. 36 Daftar Kitab-kitab Kawedalaken Saka Kasade Dening Toko Buku Tan Khoen Swie Kediri, 1 Februari 1953, hlm. 23. 37 Primbon disebut juga sebagai gudang ilmu pengetahuan (pangawikan Jawa). Memunculkan paham primbonisme, termasuk di dalamnya mistikawan. Lihat Suwardi Endraswara, Falsafah Hidup Jawa, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 118-119. 13 menawarkan buku-bukunya door to door.38 Itu membuat komunitas pergaulannya meluas. Buku-buku terbitan Tan Khoen Swie tidak hanya menjadi konsumsi para pembaca dari kalangan terbatas di Kediri, Surakarta,39 Yogyakarta, Cilacap, Ngawi, Bojonegoro, Surabaya, dan Lumajang (Jawa) namun juga dibaca secara luas oleh masyarakat di luar Jawa. Hal ini dapat dilihat pada buku register pengiriman tahun 1958-1959, Boekhandel Tan Khoen Swie telah melakukan pengiriman pesanan kitab-kitab kepada pembaca, toko buku, dan penerbit ke seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua.40 Dalam memasarkan produk terbitannya Boekhandel Tan Khoen Swie memanfaatkan jaringan penulis, penerbit, dan toko buku. Hubungan simbiose dengan penulis, sangat menarik, karena ternyata hubungan itu memunculkan para penulis baru.41 Tan Khoen Swie juga memberikan daya tarik kepada penerbit dan toko-toko buku. Sambutan yang cukup bersemangat untuk menjalin kerja sama adalah toko-toko buku. Tidak hanya toko buku yang ada di Jawa, akan tetapi menyebar hampir di seluruh pulau-pulau di luar Jawa. Proses perkembangan itu 38 Majalah Tempointeraktif, 2 April 2011. 39 Penyebaran buku-buku Tan di Surakarta tahun 1920-an melalui beberapa agen, salah satunya Boekhandel Sitti Sjamsijah Surakarta. Lihat Suripan Sadi Hutomo, “Sumbangane “Boekhandel Siti Sjamsijah”, Marang Kasusastraan Jawa”, dalam Jaya Baya, 28 Nopember 1982, hlm. 37 dan 43. 40 Lihat Buku Register pengiriman tahun 1958-1959, Boekhandel Tan Khoen Swie. 41 Kemunculan penulis baru itu semakin gencar ketika Michael Tanzil memasang iklan di Majalah Terang Bulan No.23 Th.XI, 1 Desember 1957, “Kirimkanlah Naskah-naskah Ilmu Pengetahuan dan Primbon dalam Bahasa Indonesia, untuk kita periksa dan kita terbitkan bilatjotjok”. 14 mencapai puncaknya ketika Boekhandel Tan Khoen Swie dipegang oleh Michael Tanzil tahun 1957-1960.42 Ketertarikan para penulis, penerbit dan toko buku untuk menjalin hubungan bisnis, terutama setelah mengetahui semakin berkembangnya usaha penerbitan Tan Khoen Swie. Di samping itu daya tarik buku terbitannya sangat digemari dan banyak diminati pembaca. Walau disadari kiprah Tan Khoen Swie tidak dapat menapak sepanjang masa setelah meninggalnya tahun 1953. Berbagai persoalan muncul, mulai dari bagaimana mengelola Boekhandel itu selanjutnya, pemikiran penggantian nama, menghadapi situasi politik ideologi pemerintah Orde Lama. Michael Tansil mengendalikan Boekhandel banyak menghadapi tantangan. Terutama ketika beberapa naskah Boekhandel Tan Khoen Swie dilarang terbit. Michael Tansil mengalami kesulitan ketika harus mengedepankan antara politik, dan menggeluti bidang ekonomi. Sebuah keputusan untuk tidak lagi mengoperasikan Boekhandel Tan Khoen Swie menjadi pilihannya di tahun 1963. Perjalanan Boekhandel Tan Khoen Swie menjadi menarik untuk dikaji. B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Eksistensi kelompok penerbit kurang mendapat perhatian dalam tradisi penulisan sejarah di Indonesia. Kelompok eksklusif ini jarang dimunculkan sebagai aktor perubahan sosial budaya. Padahal kiprah mereka tidak dapat dipandang remeh 42 Data-data mengenai hubungan khususnya penerbit dan toko buku dapat dilihat pada Buku Pesanan dan Pembayaran Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri tahun 1958. Dan lihat juga Buku Kiriman dan Penerimaan Pos Wesel Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri tahun 1958. 15 dalam membentuk mentalitas suatu bangsa. Munculnya tradisi baca dari naskahnaskah yang telah ditulis dan dicetak oleh penerbit memberi kontribusi terhadap perkembangan identitas bangsa yang sedang menggeliat pada awal abad ke-20.43 Menurut Sartono Kartodirdjo, untuk memahami pergerakan nasional kiranya sejarah mentalitas tidak dapat ditinggalkan, lebih-lebih apabila masalah kesadaran yang dipandang sebagai awal dari segala perubahan.44 Secara garis besar penelitian ini hendak mengkaji bagaimana Tan Khoen Swie menerbitkan buku-buku dan sebagai agent cultural menyebarkan budaya baca kepada masyarakat Jawa dan luar Jawa, selama kurun waktu 1915-1963. Beberapa pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kebijakan perbukuan dan penerbitan pemerintah kolonial dan poskolonial Indonesia ? 2. Bagaimana gambaran eksistensi dan aktivitas agen pengarang, agen penerbit swasta, dan kelompok pembaca sastra Jawa ? 3. Mengapa Tan Khoen Swie memilih ide atau gagasan menyebarkan buku-buku budaya Jawa ? 4. Bagaimana Tan Khoen Swie melalui kemampuan dan kekuatannya merajut jaringan agen penulis, penerbit, dan pedagang buku ? 43 Lihat terutama pada Bab XXI, “Kebangkitan Nasional 1900-1927”, dalam Benny G. Setiono, op. cit.,hlm. 323-361. 44 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm.172-173. 16 Skope temporal studi ini dibagi dua bagian; pertama, periode dimulai sejak Tan Khoen Swie membuka penerbitan tahun 1915 sampai meninggalnya tahun 1953. Kedua, periode Michael Tanzil, 1954 sampai 1963. Walaupun sebenarnya batasan ini tidaklah mutlak, karena persoalan kausalitas sebelum dan sesudahnya juga dipandang penting diuraikan. Tempat penelitian di wilayah Kediri (Jawa) dan luar Jawa terutama yang terkait dan mendapat pengaruh terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie. Kediri, sebagai lokasi aktivitas Boekhandel Tan Khoen Swie terletak di Jalan Doho No.165 Kota Kediri. Dalam catatan historis, Kediri (Mamenang) disebut-sebut sebagai pusat sastra di Jawa terutama pada masa Kerajaan Kediri (1045-1222) di samping Medhangkamulan.45 Babad Kadiri, Serat Darmogandul, dan Suluk Gatoloco ditulis di kota ini pada tahun 1830-an. Alasan lainnya, bahwa kebiasaan penulisan karya sastra berbahasa Jawa di Kediri bertahan hingga sekarang. Terbukti di Kediri terdapat organisasi pengarang Triwida. Organisasi ini menghimpun para pengarang kesusastraan Jawa Modern yang bertebaran di Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar.46 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Studi ini mencoba mengungkap bagaimana aktivitas Boekhandel Tan Khoen Swie dan pengaruh produk terbitannya pada masyarakat di Jawa dan luar Jawa. Secara khusus studi ini bertujuan: (1) menjelaskan bagaimana kebijakan perbukuan 45 46 S. Margana, op. cit., hlm. 21. Suripan Sadi Hutomo, op. cit., hlm. 114. 17 dan penerbitan pemerintah kolonial dan poskolonial; (2) menjelaskan gambaran agen pengarang, agen penerbit swasta, dan kelompok pembaca sastra Jawa; (3) mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi Tan Khoen Swie memilih ide atau gagasan menyebarkan buku-buku budaya Jawa; (4) mendiskripsikan bagaimana Tan Khoen Swie melalui kemampuan dan kekuatannya merajut jaringan agen penulis, penerbit, dan pedagang buku. Temuan studi ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi masyarakat umum, temuan studi ini dapat membuka dan menambah wawasan masyarakat tentang pemahaman perkembangan penerbitan buku-buku budaya Jawa di Kediri yang terjadi sejak awal abad ke-20. Temuan studi ini juga dapat menumbuhkan kesadaran sejarah di kalangan masyarakat, bahwa proses penerbitan buku yang ada sekarang ini tidak terlepas dari penerbitan sebelumnya. Bagi dunia akademis, temuan studi ini memperkaya kajian tentang sejarah penerbitan di Indonesia yang pernah diteliti. Temuan studi ini dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai kemajuan tingkat konsumsi bacaan komunitas sosial tertentu. Adakah pelajaran yang bisa diambil dari studi perkembangan penerbitan buku di Kediri sejak masa kolonial hingga Orde Lama memiliki keterkaitan dengan kebijakan masa kini. Temuan studi ini memperkaya pemahaman tentang perkembangan sejarah penerbitan di Indonesia yang sedang berlangsung sejak masa kolonial. Bagi pembelajaran sejarah, temuan studi ini dapat dimanfaatkan untuk substansi pembelajaran sejarah pada berbagai jenjang pendidikan. Tidak hanya untuk mata pelajaran sejarah akan tetapi dapat juga memperkaya substansi mata pelajaran IPS dan Antropologi Budaya, serta kajian sejarah sastra. 18 Bagi Pemerintah Daerah, temuan studi ini dapat dipakai sebagai bahan untuk melengkapi penulisan sejarah lokal, dan bahkan mungkin untuk bahan rujukan bagi pemerintah daerah yang ingin menulis kembali sejarah penerbitan di daerahnya. D. Tinjauan Pustaka Literatur yang membahas tentang Tan Khoen Swie dan aktivitas usahanya sangat terbatas. Beberapa penulis seperti, M.C.Ricklefs,47 dalam Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions, 1830-1930 memberi penilaian yang menarik. Menurutnya, Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri (1882-1953) memainkan peranan penting dalam mendukung kepustakaan Jawa. Tan Khoen Swie pemilik usaha itu menguasai bahasa Jawa seperti halnya banyak orang Tionghoa lain di Jawa dan menjadi kekuatan intelektual Jawa yang penting. Dia mensponsori dan menerbitkan tulisan-tulisan terkenal dari orang-orang Jawa seperti Raden Tanaya, Ki Mangunwijaya dan Ki Padmasusastra. Karya-karyanya kebanyakan bergaya tradisional, tidak dipengaruhi oleh pembaharuan Islam dan satu bentuk yang menarik pembaca untuk cenderung pada sitesa mistik Jawa. Ricklefs berusaha mencari keterkaitan antara konsep ‘budi dan buda’ terhadap munculnya polarisasi politik yang terjadi pada awal abad ke-20. Tiga naskah yang kemudian menjadi rujukan Ricklefs, Serat Babad Kediri, Serat Darmogandul, dan Suluk Gatoloco yang pada akhir abad XIX menjadi bacaan kontroversi di masyarakat Jawa dipandangnya menjadi pemicu munculnya polarisasi. Ketika awal abad ke-20 Tan Khoen Swie menerbitkan kembali ketiga 47 Lihat M.C. Ricklefs, op. cit., hlm.238-239. 19 naskah tersebut, pertentangan sosial antara golongan Islam dan non Islam semakin meninggi. Tan Khoen Swie, terkena dampak dari konflik sosial yang muncul. Salah satu dari ketiga naskah di atas, (Serat Darmogandul), yang dipandang kontroversi itu berasal dari tulisan Drewes yang mendapat protes tahun 1923.48 Menurut penjelasan Ricklefs, Drewes tidak mengira kalau tulisannya itu berdampak luas. Penjelasan Ricklefs pada persoalan di atas menarik untuk dijadikan bahan analisa terhadap naskah-naskah Boekhandel Tan Khoen Swie, terutama dikaitkan dengan naskah-naskah yang bersifat kontroversial. Tulisan Sri Widati dan kawan-kawan, mengenai perkembangan sastra Jawa modern masa prakemerdekaan sangat membantu dalam memahami aspek historisnya.49 Menurutnya, pada rentang waktu antara tahun 1917 sampai dengan 1942, sastra Jawa tumbuh dan berkembang melalui dua jalur penerbitan, yaitu jalur Balai Pustaka dan non Balai Pustaka. Boekhandel Tan Khoen Swie, menurut Sri Widati, termasuk penerbit non Balai Pustaka (swasta), untuk membedakan dengan Balai Pustaka (pemerintah). Menurutnya, penerbit non Balai Pustaka dinilai sebagai penerbit tak resmi. Sebagai penerbitan swasta, Boekhandel Tan Khoen Swie memiliki jalan berlawanan dengan Balai Pustaka dan menekuni jalur bebas, sehingga karya-karyanya tidak sepenuhnya patuh pada kekuasaan. Alasan yang dikemukakan, karena penerbit itu : (1) bukan bagian dari alat kolonial; (2) tidak bertujuan menciptakan mode dan corak yang seragam baik bentuk maupun isi, 48 Drewes, G.W.J., “The Struggle Between Javanism and Islam as Illustrated by The Serat Darmogandul”, Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie (BKI),122 309-365, 1966. 49 Lihat Sri Widati, dkk., op. cit., hlm.69. 20 karena sistem sosial (pengarang, penerbit, dan pembacanya) tidak berasal dari kekuasaan atau produk kolonial; (3) tidak didukung oleh dana pemerintah, tetapi oleh swadaya penuh, sehingga lebih bersifat mencari untung.50 Sebagai penerbit non Balai Pustaka, Boekhandel Tan Khoen Swie memberi kebebasan kepada setiap pengarang untuk berkarya. Artinya penerbit itu cenderung tidak mengelola sistem redaksionalnya seperti balai Pustaka. Bebas mengisi celahcelah komersial yang tidak dapat diisi oleh balai Pustaka. Menurut Sri Widati, Boekhandel Tan Khoen Swie menerbitkan karya-karya klasik, dan sedikit karyakarya yang bernuansa nasionalisme.51 Penjelasan tersebut penting untuk memahami karakteristik dan status sebuah penerbitan. Uraian yang tidak kalah penting dari tulisan Sri Widati adalah informasi tentang struktur masyarakat pendukungnya. Posisi pengarang, penerbit, pembaca, dan pengayom dijelaskan beriringan dengan perkembangan sastra Jawa modern. Walaupun dalam tulisan itu, sepak terjang Tan Khoen Swie disajikan sepotongpotong, namun uraiannya sangat membantu memahami eksistensi dan perkembangan Boekhandel Tan Khoen Swie. Disertasi Zubaidah Isa, berjudul Printing and Publishing in Indonesia, 1902-1970, menjelaskan bahwa pembentukan Volkslectuur pada tahun 1910 merupakan langkah maju yang signifikan di bidang penerbitan, pendidikan, dan 50 51 Ibid.,hlm. 162. Sri Widati dkk., Ikhtisar Perkembangan sastra Jawa Modern Periode Prakemerdekaan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm.168. 21 perpustakaan pemerintah di Hindia.52 Kritik kebijakan pemerintah tentang pendidikan menyebabkan dibentuknya Commissie voor de Inlands che School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Sekolah dan Bacaan Rakyat) pada 14 September, 1908. Fungsi utama komisi adalah untuk membangun sekolah-sekolah desa, untuk memberikan buku bacaan dalam bahasa asli untuk siswa-siswa sekolah, dan untuk membangun perpustakaan di sekolah-sekolah. Kegiatan penerbitan Volkslectuur termasuk menerjemahkan, dan mencetak ulang cerita rakyat. Uraian Zubaidah yang cukup menarik adalah tentang pembangunan usaha penerbitan di tahun 1950-an. Menurutnya, pembangunan usaha penerbitan pemerintah dilakukan dengan mengimpor barang-barang untuk keperluan penerbitan. Data-data yang dituangkan memberikan pemahaman tentang bagaimana usaha penerbitan pemerintah pasca kemerdekaan dimulai. Bandingkan dengan ketika masa kolonial dengan balai Pustakanya. Bahan-bahan tulisan ini cukup bermanfaat untuk pengembangan eksplanasi tulisan ini. Sayangnya beberapa ulasan mengenai seba-sebab menurunnya usaha penerbitan nasional di akhir tahun 1950-an tidak ada penjelasan yang detail. Disertasi Subardi, berjudul “Transformasi Teks Macapat Terbitan Boerkhandel Tan Khoen Swie” lebih menekankan tinjauan sisi bahasa pada tiga buku terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie.53 Subardi melakukan eksperimen transformasi teks terhadap Serat Wulangreh, Wedatama Wiradi, dan Sariwarsita. Tulisan itu dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami 52 Zubaidah Isa, “Printing and Publishing in Indonesia, 1902-1970”, Tesis Ph. D. Indiana University, 1972. 53 Lihat Subardi, loc. cit. 22 ketiga naskah tersebut. Tulisan ini memberi pemahaman tentang bagaimana naskah tembang macapat ditransformasikan ke dalam sebuah karya bebas atau gancaran (prosa).54 Menurut Subardi, alasan penerbitan buku-buku oleh Tan Khoen Swie adalah untuk menyebarluaskan karya-karya pujangga yang semula terbatas di kalangan istana sehingga lebih mudah diapresiasi oleh masyarakat. Inisiatif tersebut lebih didasari motivasi penyebaran gagasan dan nilai-nilai daripada motivasi ekonomi. Indikatornya menurut Subardi, harga buku dijual dengan harga murah sehingga terjangkau untuk dibeli masyarakat.55 Karya S. Margana berjudul Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial, berisi tentang tradisi pemikiran para intelektual Jawa tradisional, tentang sastra, dan kesejarahan sangat penting untuk memahami persoalan psikologis, sosial, kultural, dan politik selama abad ke-18 dan 19 di Surakarta.56 Walaupun Boekhandel Tan Khoen Swie hanya disinggung sangat terbatas terutama mengenai komparasi naskah penelitian Sasatya Darnawi, “Serat Wicara Keras Karangan Yasadipura II”, dengan naskah koleksi Netherland Bible Society Leiden sangat menarik. Uraian yang sangat bermanfaat dari buku S. Margana terutama pada bab IV mengenai dunia akademis kolonial dan intelektual Jawa abad ke-19 dan pada 54 Upaya itu dimaksudkan untuk mengubah motip dari sastra Jawa tradisional ke sastra Jawa modern. Motif sastra modern ini digagas oleh Padmosusastro yang berusaha melepaskan diri dari literer sastra Jawa tradisional, yaitu bentuk tembang ke arah bentuk naratif atau gancaran. Lihat Edi Sedyawati, dkk., (Ed.), Sastra Jawa Suatu Tinjauan Umum, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.170-171. 55 56 Subardi, op. cit., hlm. 171. Buku ini membahas tradisi pemikiran para intelektual Jawa tradisional tentang sastra dan kesejarahan. Lihat S. Margana, op. cit., hlm. VII. 23 penjelasan bab V tentang dunia kapujanggan Surakarta dan tradisi pemikiran intelektual Jawa abad ke-18 dan 19. Analisa tulisan itu membantu untuk melihat gambaran struktur masyarakat sastra Jawa yang menjadi fokus penelitian ini. Tulisan sejenis, yang menguraikan perkembangan sastra Jawa Modern periode kemerdekaan, dapat dibaca pada tulisan Tim Penyusun Sejarah Sastra Jawa Modern.57 Kedua tulisan itu memberi pemahaman mengenai sejarah perkembangan Sastra Jawa Modern masa prakemerdekaan sampai periode kemerdekaan. Tulisan Mikihiro Moriyama, “Ketika sastra dicetak: perbandingan tradisi tulisan tangan dan cetakan dalam Bahasa Sunda pada paruh abad ke-19”, penting untuk dicermati. Dalam penjelasannya, tradisi membaca naskah tidak hilang seketika setelah munculnya buku-buku cetakan mekanis, tetapi terjadi perubahan dalam aktivitas membaca. Reproduksi mekanis memiliki sifat baru, masing-masing buku memiliki bentuk yang sama dalam penampilan. Keseragaman yang timbul karena percetakan memperkuat kecenderungan ke arah penguatan kesatuan atau komunitas bahasa. Kondisi tersebut memunculkan praktek-praktek budaya yang baru dalam membaca dan menulis yang menciptakan pola-pola solidaritas dan rasa kebersatuan yang kuat bersamaan dengan saat budaya naskah mulai melemah.58 57 Tim Peneliti Balai Bahasa Yogyakarta, Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Kemerdekaan, (Yogyakarta: Kalika, 2001). 58 Mikihiro Moriyama, “Ketika Sastra dicetak: perbandingan tradisi tulisan tangan dan cetakan dalam bahasa Sunda pada paruh kedua abad ke-19”, Makalah terjemahan Dr. Mikihiro Moriyama Profesor of Indonesian Studies Faculty of Foreign Studies Nanzan University, hlm. 4. 24 Melalui percetakan, kesusastraan di Nusantara mengalami perubahan besar, tulis Hilmar Farid.59 Lanjutnya, naskah-naskah yang semula ditulis tangan hanya memiliki jangkauan peredaran yang terbatas. Ketika karya-karya yang terbit dalam masa perkembangan kapitalisme cetak dapat diterbitkan secara massal dan menjangkau jumlah pembaca yang lebih besar, sastra (teks dalam bentuk tercetak) memasuki dunia komoditi yang dapat diperjualbelikan dan memiliki makna yang berbeda dengan karya-karya yang ditulis tangan. Dalam perkembangan sejarah, terlihat bagaimana produksi naskah tulisan tangan digeser oleh barang cetakan. Secara konseptual proses produksi kapitalis tersebut dijelaskan secara detail dalam buku Frederick Engels, “Tentang Das Kapital Marx”. Dijelaskan bahwa, dalam kekayaan masyarakat berlaku produksi kapitalis yang meliputi atas barangbarang dagangan. Setiap barang dagangan mempunyai nilai pakai dan nilai tukar yang berlaku bagi semua masyarakat. Aktivitas di dalamnya ditentukan secara rangkap, di satu pihak, sebagai aktivitas produktif tertentu, di pihak lain, sebagai pengerahan tenaga kerja manusia. Yang pertama memproduksi nilai pakai, dan yang kedua memproduksi nilai tukar. Konsep dasar tersebut belakangan secara kuantitatif dapat diperbandingkan mengenai perbedaan atau selisih antara kerja ahli dan tidak ahli, kerja gabungan dan dalam lingkup sederhana. Oleh karenanya substansi nilai tukar adalah kerja abstrak, termasuk besaran dan ukurannya.60 Tinjauan pustaka di atas secara umum menyiratkan beberapa hal. Pertama, Kediri merupakan pusat sastra yang utama yang mewariskan budaya menulis, 59 Hilmar Farid, “ Kolonialisme dan Budaya : Balai Poestaka di Hindia Belanda”, dalam Prisma, Edisi Oktober 1991. 60 Sinopsis Capital K. Marx. Capital Jilid I. Buku I. Proses Produksi Kapitalis, dalam Frederick Engels, Tentang Das Kapital Marx, (Alih Bahasa Oey Hay Djoen), (T.T.: Geys, Renaissance, 2007), hlm. 40. 25 membaca, dan mencetak yang melahirkan budaya intelektual Jawa yang lepas dari perhatian para peneliti. Kedua, munculnya Boekhandel Tan Khoen Swie telah membuka cakrawala perubahan untuk menuju budaya baca, dari budaya tutur berkembang menjadi budaya tulis. Ketiga, produk terbitan Tan Khoen Swie tidak hanya sebuah teks semata, melainkan telah menginformasikan sebuah konteks peristiwa historis yang menyertainya. Sepengetahuan peneliti belum ada satupun tulisan yang membahas tema sejarah bisnis penerbitan yang bernilai historis. E. Kerangka Konseptual dan Analisis Selama ini tema sejarah penerbitan kurang mendapat minat dari para peneliti. Alasan utamanya, karena di samping tren tulisan yang sering dipilih adalah tema-tema yang dinilai lebih mudah penggarapannya dari sisi penggunaan pendekatan, juga pertimbangan lain disebabkan persoalan keterbatasan sumber. Bahan-bahan penggunaan untuk menulis naskah-naskah sejarah produk penerbitan terbitan mengharuskan mengandung fakta formulasi kejiwaan (mentifact).61 Penggunaan mentifact dimaksudkan untuk menganalisis apa dasar seseorang atau kelompok sosial/etnis bersikap dan bertindak. Dalam kaitan penelitian ini obyek yang akan dikaji mencakup : ide, gagasan, ideologi, orientasi nilai, mitos, pandangan hidup, latar belakang Tan Khoen Swie. 61 Fakta-fakta yang terjadi dalam jiwa, pikiran, atau kesadaran manusia. Lihat Sartono Kartodirdjo, op. cit., hlm. 176. 26 Dalam memahami persoalan tersebut, teori strukturasi Anthony Giddens digunakan untuk memperjelas eksplanasi. Teori strukturasi terfokus pada praktik sosial, yang melibatkan hubungan antara agen dengan struktur. Praktek sosial diartikan sebagai praktek dalam bidang kehidupan dan kegiatan nyata keseharian manusia. Dalam suatu praktek sosial, Giddens melihat terdapat interaksi antara agen dan struktur, yang selanjutnya menjadi sebuah kebiasaan dalam suatu rutinitas yang direproduksi dalam kehidupan sosial.62 Inti teori strukturasi Giddens adalah praktek sosial yang berulang.63 Praktek sosial tersebut dipandang sebagai dasar eksistensi agen dan masyarakat.64 Teori strukturasi Giddens tidak terlepas dari konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu tersebut melekat pada konsep ‘struktur-(asi)’ yang memberi pengertian kelangsungan atau proses. Ruang dan waktu merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam mengkaji peristiwa atau gejala sosial.65 Bagaimana peran agen dalam suatu praktek sosial ? Agen adalah orangorang yang terlibat dalam arus kontinu tindakan.66 Pengertian agen menurut Oxford English Dictionary sebagai seseorang yang mengeluarkan kekuasaan atau 62 Anthony Giddens, The Constitution of Society : Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial, (Terj. Adi Loka Sujono), (Pasuruan : Pedati, 1984), hlm. 131. 63 Ibid., hlm. 2. 64 Peter Beilharz, (Ed.), Teori-teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka, (Terj. Sigit Jatmiko), (Yogyakarta: Pustaka Pekerja, 2003), hlm.193. 65 66 B. Herri Priyono, op. cit., hlm.20. B.Herry Priyono, Anthony Giddens : Suatu Pengantar, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm.19. 27 menghasilkan efek. Itulah sebabnya Giddens memberi pengertian agensi hanya pada orang yang memiliki kemampuan terhadap hal-hal yang menyiratkan kekuasaan.67 Agen sebagai pelaku dalam praktek sosial, dan dapat dilihat sebagai individu atau kelompok. Dalam penelitian ini Boekhandel Tan Khoen Swie dan pengarang yang mensuport naskah-naskah hasil karangannya dipandang sebagai agen. Menurut Giddens, ‘semua manusia’ adalah agen, memiliki tujuan yang tidak hanya memiliki alasan logis bagi tindakannya, tetapi juga mampu melakukan elaborasi diskursif atas alasan-alasan tersebut. Lebih jauh, Giddens menyebut bahwa knowledgeability memiliki bentuk reflektif yang merupakan bagian penting dari praktik sosial yang berulang.68 Dalam melakukan tindakan sosial, agen selalu melakukan pemantauan reflektif (reflexive monitoring). Giddens menyebutnya sebagai karakter purposif dari tindak-tanduk manusia. Melalui pemantauan reflektif, agen tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga mempengaruhi struktur. Dalam pemantauan reflektif, action bukanlah untaian tindakan (acts) yang memiliki cirinya masingmasing atau agregat dari tujuan, tetapi sebuah proses yang terus berlanjut. Tindakan manusia dikerangkai oleh beberapa elemen yang disebut Giddens sebagai stratification model. Model tersebut diajukan sebagai usaha konseptualisasi human agency. Dalam model tersebut ditekankan tiga lapis kognisi/motivasi. Pertama, kesadaran diskursif atau kapasitas agen untuk merasionalisasi dan memberikan alasan atas tingkah lakunya. Kedua, kesadaran praktikal atau apa yang dipahami agen sebagai kondisi sosial dan tidak bisa disampaikan oleh agen secara 67 Anthony Gidden, op. cit., hlm. 11. Anthony Giddens, The Constitution of Society : Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial, (Terj. Adi Loka Sujono), (Pasuruan : Pedati, 1984), hlm. 2-3. 68 28 diskursif. Kesadaran praktikal digunakan agen untuk menyesuaikan diri dengan terhadap situasi tertentu dan menfsirkan tingkah laku aktor lainnya. Namun, tindakan manusia tidak hanya dipandu oleh elemen sadar, tetapi juga elemen tidak sadar yang dikategorikan Giddens sebagai lapis motivasi. Lapis ini terkait dengan kepercayaan bahwa apa yang berlangsung di dunia ini terjadi apa adanya (are as they appear to be). Elemen tidak sadar ini dianggap sebagai kebutuhan agen atas keamanan ontologis yang timbul dari kebutuhan akan sebentuk kepercayaan. Tanpa elemen ini, manusia akan mengalami kegelisahan akut karena mereka tidak memiliki identitas sosial. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa elemen ini merupakan hasil dari regionalisasi dan rutinisasi struktur yang merupakan hasil dari penggunaan aturan dan sumber daya di masa lalu. Teori strukturasi meletakkan hubungan agen dan struktur dalam sebuah hubungan “mutually constitutive”. Agen dan struktur saling jalin menjalin menyatu dalam praktek sosial. Struktur yang dimaksud dalam kerangka pemikiran Gidden adalah bersifat maya ‘virtually’, artinya hanya hadir melalui aktivitas agen, serta ada dalam pikiran manusia yang digunakan hanya ketika bertindak. 69 Struktur dikonsepsikan sebagai aturan ‘rules’ dan sumber daya ‘resources’ yang memungkinkan praktek sosial terjadi di sepanjang ruang dan waktu.70 Artinya struktur hanya akan terwujud dengan adanya aturan dan sumber daya. Menurut Giddens, struktur adalah aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan memediasi perulangan praktek sosial. Dualitas struktur terletak pada proses 69 H. Andersen and L.B. Kaspersen, (Ed.), Classical and Modern Sosial Theory,(Oxford: Blackwell, 2000), hlm. 381. 70 Anthony Giddens, op. cit., hlm. 17. 29 outcome dan menjadi sarana medium parktek sosial. Artinya dualitas agen dan struktur terletak dalam fakta bahwa suatu struktur yang menjadi prinsip praktekpraktek sosial di berbagai tempat dan waktu merupakan suatu hasil perulangan dan terus menerus dari praktek sosial, dan struktur menjadi medium bagi berlangsungnya praktek sosial.71 Melalui dualitas struktur, hubungan antara agen dan struktur dapat terlihat. Agen dengan jangkauan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadikan struktur sebagai acuan dalam bertindak dan mengubah serta memproduksi struktur melalui praktek sosial. Agen dan struktur melakukan interaksi saling mempengaruhi satu sama lain. Struktur dalam kehidupan sosial diidentifikasikan ke dalam dua aspek yakni, sebagai aturan dan sumber daya. Aspek pertama, sebagai aturan, struktur adalah suatu prosedur yang dijadikan sebagai pedoman oleh agen dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Terkadang interpretasi aturan dituliskan dalam bentuk hukum atau aturan birokratis. Demikian pula, aturan structural dapat direproduksi oleh agen dalam suatu masyarakat, atau dapat diubah melalui perkembangan pola baru dari suatu interaksi. Aspek kedua dari struktur adalah sumber daya, yang juga terjadi melalui praktek sosial, dan dapat diubah atau dipertahankan oleh agen. Struktur sebagai sumber daya dibedakan sumber daya alokatif (allocative) dan sumber daya kewenangan (authoritative). Sumber daya alokatif (allocative) adalah kegunaan gambaran materi dan benda-benda untuk mengontrol serta menggerakkan pola interaksi, mencakup bahan mentah, tanah, teknologi, alat-alat produksi, pendapatan, dan harta benda. Sumber daya kewenangan (authoritative) adalah 71 B. Herri Priyono, op. cit., hlm 22. 30 kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan pola-pola interaksi, mencakup ketrampilan, pengetahuan/keahlian, posisi di lembaga atau organisasi, dominasi dan legitimasi. Dengan kata lain, mereka menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membuat orang lain menuruti dan melakukan keinginan atau perintahnya. Berdasarkan konsep Gidden tiga gugus struktur dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Pertama struktur signifikansi yang menyangkut skemata simbolik atau pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Dalam hal ini nama boekhandel atau penerbitan menunjuk pada sebuah bisnis gagasan, bisnis ide-ide, dan wacana pemikiran melalui buku-buku oleh Tan Khoen Swie. Kedua struktur dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi), dalam hal ini seperti kebijakan perbukuan (pemerintah Belanda, Jepang, dan Indonesia), kebijakan di bidang pendidikan dan bahasa yang merupakan bentuk dominasi pemerintah. Ketiga struktur legitimasi yang menyangkut skemata normatif yang terungkap dalam undang-undang. Dalam hal ini seperti undang-undang pers dan undang-undang penerbitan yang mengatur kehidupan pers, dan penerbitan bukubuku bacaan. Ketiga gugus tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam perjalanan aktivitas Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri. Tindakan Tan Khoen Swie dipengaruhi oleh karakteristik struktural masyarakat Tionghoa, pada saat yang sama ia mencoba untuk menciptakan (dan juga sampai batas tertentu mengubah) karakteristik struktural dalam tindakannya. Dalam hal ini tindakan Tan Khoen Swie dalam menerbitkan buku-buku tidak dapat terlepas dari masyarakat tempat ia berada yaitu di Jawa (Indonesia), namun disisi lain tindakannya tersebut merupakan suatu bentuk kesadaran yang tercipta dari dalam dirinya sendiri. 31 Dalam konteks aktivitas Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri, tindakan individu yang dalam hal ini adalah pembaca/pembeli buku-buku Tan Khoen Swie mempengaruhi tindakan sosial agen dalam paraktik sosialnya, sementara agen (penerbit/pengarang) memiliki kemampuan dalam menciptakan perbedaan sosial di dunia sosialnya. Agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah, karena keduanya diibaratkan dua sisi mata uang.72 Teori strukturasi mengintegrasikan agen dan struktur, serta menjelaskan dualitas dan hubungan dialektika antara agen dan struktur. Struktur tidak menentukan agen, dan sebaliknya agen juga tidak menentukan struktur, namun sesungguhnya baik struktur maupun agen tidak akan ada tanpa kehadiran pihak lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya harus dilihat sebagai sebuah sejarah, proses, dan dinamis. Teori strukturasi terpusat pada cara agen memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakan mereka sendiri. Aktivitas-aktivitas manusia yang teratur tidak diwujudkan oleh actor-aktor individual, melainkan terus menerus diciptakan dan diulang oleh mereka melalui cara mereka mengekspresikan diri sebagai actor. Melalui aktivitasnya, agen mereproduksi sejumlah kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitasnya. Ia bertindak sesuai aturan dan mereproduksi aturan itu. Aturan yang mengikat tersebut menjadikan masyarakat di sekitarnya turut melembagakan kekangan, walaupun pada akhirnya ia mampu menembus peraturan yang mereka buat sendiri. 72 Paul Bagguley, “Reflexivity Contra Structuration”, dalam The Canadian Journal of Sociology, Vol. 28, No.2, 2003, hlm. 133-152. 32 F. Metode dan Sumber Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat kegiatan pokok, yaitu (1) heuristik, kegiatan mengimpun jejak-jejak masa lampau, (2) kritik, menyelidiki apakah jejak-jejak tersebut asli, baik bentuk maupun isinya, (3) Interpretasi, menetapkan saling hubungan antarfakta yang diperoleh, (4) Penyajian, menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam satu bentuk kisah sejarah.73 Kegiatan pertama penelitian ini yaitu penelusuran dan mengumpulkan sumber-sumber tertulis. Perhatian utama dalam tahapan ini ialah mendasarkan pada sumber-sumber tertulis dalam spasial wilayah Kediri Jawa Timur. Sumbersumber yang berupa naskah-naskah terbitan Tan Khoen Swie dapat diperoleh dari ruang penerbitan Tan Khoen Swie di Jalan Dhoho Kediri. Kekurangannya dapat ditelusuri pada lembaga-lembaga penyimpanan naskah baik di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Beberapa koleksi juga diperoleh dari beberapa perpustakaan di Yogyakarta, seperti Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Sono Budoyo, dan beberapa perpustakaan di Surakarta, seperti Radyo Pustoko dan Rekso Pustoko. Beberapa sumber berupa surat-surat penting diperoleh dari Ahli Waris (Yuriah Tanzil) Boekhandel Tan Khoen Swie di Jakarta. Dalam konteks pemahaman institusional, terbitan resmi pemerintah kolonial Belanda berupa staatsblad, verslag, besluit, dan keputusan-keputusan rapat sangat membantu memahami peran institusi dalam struktur. Sumber-sumber historis itu 73 G.J. Garraghan, A Guide to Historical Method, (New York: Fordam University Press, 1957). 33 ditelusuri di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Badan Arsip Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Arsip Kota Surabaya, dan Arsip-arsip kota-kota di wilayah Jawa Timur, perpustakaan-perpustakaan di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kediri. Tanpa memahami persoalan yang paling mendasar dan yang dialami individu atau masyarakat pribumi di kampung, gejolak yang muncul dan berpengaruh pada perkembangan budaya intelektual Jawa tidak dapat terdeteksi. Oleh karenanya, Sartono Kartodirdjo sangat berharap tinjauan terhadap golongangolongan pada lokasi sosial politiknya, orientasi tujuan, dasar loyalitas, afiliasi, orientasi normatif, nilai-nilai, ide-ide atau ideologi, sebagai produk budaya politik,74 itu semua merupakan fakta-fakta yang harus dipertimbangkan.75 Implikasinya faktafakta itu harus dicari di luar struktur, berupa koran-koran, pamphlet, karikatur,76 biografi, catatan harian, pengakuan, bahkan cerita rakyat. Lokasi pencarian di samping di perpustakaan milik pemerintah, juga perpustakaan-perpustakaan pribadi, berupa buku-buku, dokumen, catatan warisan para orang-orang tua terdahulu. Sumber-sumber ini akan dilacak di berbagai wilayah di Jawa Timur dan khususnya di Kediri. 74 Seseorang yang mengkaji kekuasaan harus menganalisa tidak hanya struktur politik tapi juga budaya politik. Lihat Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 114-115. 75 76 Sartono Kartodirdjo, op. cit., hlm. 168. Lihat penjelasan Frank Palmeri," The Cartoon: The image as criticue", dalam Sarah Barber and Corinna M.Peniston (Ed.), History Beyond The Text A student's Guide to Apparoaching Alternative Sources (London: Routledge, 2009), hlm.32. 34 Tahap kedua, hanya melakukan penilaian terhadap kredibilitas sumber. Penilaian terutama terhadap beberapa surat-surat penting dalam tulisan tangan dan juga terhadap beberapa keaslian atau otentisitas buku terbitan Tan Khoen Swie. Langkah-langkah yang dilakukan dengan mengamati bahan kertas dan tinta yang dipakai dalam mencetak buku. Pada tahap ketiga, yaitu interpretasi. Sumber-sumber yang sudah selesai diverifikasi, selanjutnya menjadi fakta pendukung yang kemudian diinterpretasi. Fakta-fakta atau kekuatan-kekuatan serta institusi yang berperan di masa lampau dicoba untuk diekstrapolasikan guna menghasilkan deskripsi analitis yang tepat.77 Implikasi metodologinya mengharuskan penggunaan multidimensional approach.78 Penggunaan pendekatan tersebut dalam studi ini guna mendapatkan akurasi pemecahan persoalan yang lebih terfokus dalam suatu deskripsi yang berdimensi, sehingga menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Walaupun disadari bahwa tidak ada suatu restorasi menghasilkan kembali suatu keadaan seperti aslinya.79 Oleh karena itu, fakta-fakta itu perlu diolah dengan meminjam teori-teori, konsep-konsep ilmu sosial. Upaya ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang ilmiah belaka. Manusia, baik secara individual maupun secara kolektif, adalah kompleks. Studi mengenai manusia sebagai 77 Lihat Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), him. 87. 78 79 Sartono Kartodirdjo, op. cit.,hlm. 35. Henri Pirenne, "What Are Historians Trying to do ?", dalam Hans Meyerhoff, The Philosophy of History in Our Time (New York: Doubleday Anchor Books 8s Company, 1959), him. 90. 35 makhluk sosial mengharuskan penggunaan konsep-konsep dan teori ilmu sosial, agar dapat dikaji secara entitas analitik.80 Tahapan terakhir adalah penulisan laporan, yang merupakan sintesis dalam bentuk kisah sejarah. Sumber-sumber untuk kepentingan penelitian ini banyak menggunakan sumber tertulis baik primer maupun sumber sekunder. Sumber tertulis yang terpenting, diperoleh dari dua tempat. Pertama, arsip Boekhandel Tan Khoen Swie di Kediri, berupa Buku Kiriman dan Penerimaan 1958, Buku Pesanan dan Pembayaran, 1958, Buku Pesanan dan Pengiriman, 1958, Buku Register Tahun 1959, Daftar Buku Toko Tan Khoen Swie Kediri Tahun 1957, Daftar Buku/Barang, per 31 Desember 1958, Daftar Kitab-kitab Kawedalaken Saha Kasade dening : Toko Buku Tan Khoen Swie, 1941 dan 1953, Daftar Persekot Penerbit Tan Khoen Swie Kediri per 31 Desember 1958, buku-buku dan majalah terbitan Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri, dan dokumen foto-foto keluarga. Kedua, arsip Yuriah Tanzil di Jakarta, berupa surat-surat pembaca dan tawaran naskah dari masyarakat, surat-surat penyerahan hak pengarang, dan beberapa dokumen foto-foto keluarga. Informasi tentang Tan Khoen Swie juga dapat dibaca dari beberapa surat kabar antara lain : De Indische courant, Soerabaijasch handelsblad, Nieuws en advertentieblad, Staat en letterkundig nieuwsblad, Bataviaasch nieuwsblad, De Sumatra Post. 80 Baca Robert F. Berkhofer, Jr, A Behavioral Approach to Historical Analysis, 1971. 36 G. Sistematika Penulisan Mengacu pada masalah yang hendak dicari jawabnya, maka sajian pembahasan mengikuti sistematika sebagai berikut. Bab satu merupakan pengantar. Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan analisis, metode dan sumber penelitian, serta sistematika penulisan. Bab dua, membahas kebijakan perbukuan dan penerbitan pemerintah, dunia pengarang, penerbit swasta, dan pembaca sastra Jawa. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebijakan perbukuan dan penerbitan pemerintah, sejak masa kolonial Belanda, masa Jepang, dan pemerintah RI, kemudian diuraikan mengenai dunia pengarang sastra Jawa abad ke-19 dan 20, penerbit swasta, dan pembaca sastra Jawa. Selanjutnya dalam bab tiga, secara khusus akan membahas Tan Khoen Swie : dari pedagang buku hingga usaha penerbitan. Bagian ini meliputi pembahasan Tan Khoen Swie : masa pembelajaran di Surakarta, membuka toko buku : menjadi agen buku pemerintah Hindia Belanda, Tan Khoen Swie dan pemikirannya di bidang agama, sosial dan budaya, Tan Khoen Swie dan dunia organisasi ormas Tionghoa. Bab empat, membahas aktivitas penerbitan Tan Khoen Swie periode 19151963. Pada bagian ini akan dibahas mengenai motif pendirian penerbitan dan langkah-langkah memulainya, upaya menggaet pengarang, sistem pembayaran naskah, karakter buku dan bentuk sampul, perkembangan penggunaan bahasa, pembaca buku-buku Tan Khoen Swie, perkembangan penerbitan buku-buku, dan penyebaran buku-buku Boekhandel Tan Khoen Swie. 37 Bab lima, sistem management baru pada periode Michael Tanzil (19531963), yang terdiri dari pembahasan, pembaharuan sistem administrasi masa Michael Tanzil, terdiri dari pembahasan : penggunaan nama penerbit Interstars, perubahan bentuk cetakan, pembukuan dan pencatatan. Selanjutnya pelarangan buku Aji Asmaragama, dan berakhirnya sebuah penerbitan besar. Pada bab enam dibahas tentang merajut jaringan agen penulis, penerbit, dan pedagang buku. Pembahasan pada bagian ini meliputi, terbentuknya kelompok pembaca sebagai penulis baru, jaringan penulis, jaringan penerbit : kerjasama saling menguntungkan di antara penerbit, jaringan pedagang buku : peran pedagang buku dan penyebaran buku-buku Boekhandel Tan Khoen Swie. Bab tujuh merupakan kesimpulan. Pada bagian ini diberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan secara ringkas dan saran-saran.