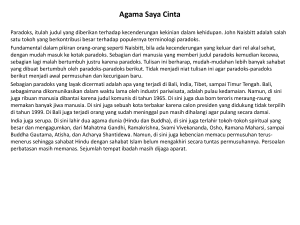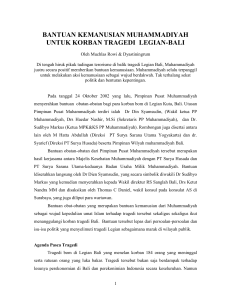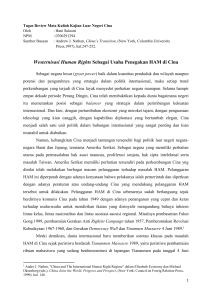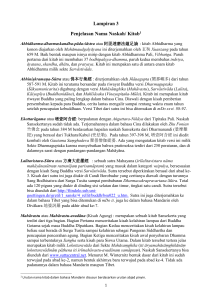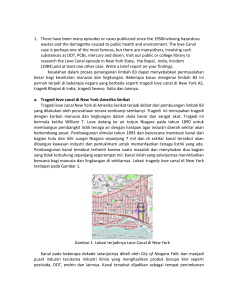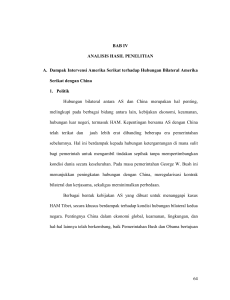Indonesia dan Tragedi Kemanusiaan di Tibet
advertisement
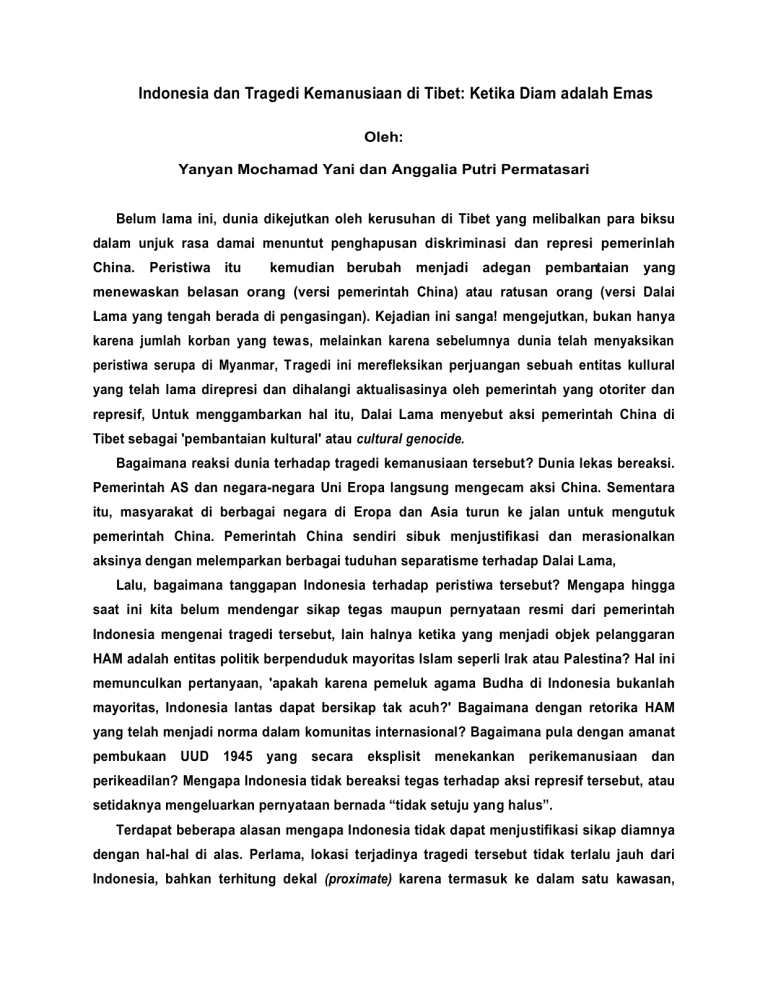
Indonesia dan Tragedi Kemanusiaan di Tibet: Ketika Diam adalah Emas Oleh: Yanyan Mochamad Yani dan Anggalia Putri Permatasari Belum lama ini, dunia dikejutkan oleh kerusuhan di Tibet yang melibalkan para biksu dalam unjuk rasa damai menuntut penghapusan diskriminasi dan represi pemerinlah China. Peristiwa itu kemudian berubah menjadi adegan pembantaian yang menewaskan belasan orang (versi pemerintah China) atau ratusan orang (versi Dalai Lama yang tengah berada di pengasingan). Kejadian ini sanga! mengejutkan, bukan hanya karena jumlah korban yang tewas, melainkan karena sebelumnya dunia telah menyaksikan peristiwa serupa di Myanmar, Tragedi ini merefleksikan perjuangan sebuah entitas kullural yang telah lama direpresi dan dihalangi aktualisasinya oleh pemerintah yang otoriter dan represif, Untuk menggambarkan hal itu, Dalai Lama menyebut aksi pemerintah China di Tibet sebagai 'pembantaian kultural' atau cultural genocide. Bagaimana reaksi dunia terhadap tragedi kemanusiaan tersebut? Dunia lekas bereaksi. Pemerintah AS dan negara-negara Uni Eropa langsung mengecam aksi China. Sementara itu, masyarakat di berbagai negara di Eropa dan Asia turun ke jalan untuk mengutuk pemerintah China. Pemerintah China sendiri sibuk menjustifikasi dan merasionalkan aksinya dengan melemparkan berbagai tuduhan separatisme terhadap Dalai Lama, Lalu, bagaimana tanggapan Indonesia terhadap peristiwa tersebut? Mengapa hingga saat ini kita belum mendengar sikap tegas maupun pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai tragedi tersebut, lain halnya ketika yang menjadi objek pelanggaran HAM adalah entitas politik berpenduduk mayoritas Islam seperli Irak atau Palestina? Hal ini memunculkan pertanyaan, 'apakah karena pemeluk agama Budha di Indonesia bukanlah mayoritas, Indonesia lantas dapat bersikap tak acuh?' Bagaimana dengan retorika HAM yang telah menjadi norma dalam komunitas internasional? Bagaimana pula dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang secara eksplisit menekankan perikemanusiaan dan perikeadilan? Mengapa Indonesia tidak bereaksi tegas terhadap aksi represif tersebut, atau setidaknya mengeluarkan pernyataan bernada “tidak setuju yang halus”. Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia tidak dapat menjustifikasi sikap diamnya dengan hal-hal di alas. Perlama, lokasi terjadinya tragedi tersebut tidak terlalu jauh dari Indonesia, bahkan terhitung dekal (proximate) karena termasuk ke dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Pasifik yang semakin diperhitungkan sebagai sebuah kompleks keamanan regional (regional security complex) tersendiri di mana keamanan dan stabilitas satu negara terkait erat dengan keamanan dan stabilitas negara-negara lain di dalam kawasan tersebut. Kedua, isu HAM telah menjadi isu global yang tidak lagi mengenal batasbatas negara dan nasionalitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa tragedi kerusuhan di Tibet berdampak pada dan bertalian erat dengan prinsip dan preferensi negara dan bangsa lndonesia. Saat ini, kerusuhan di Tibet mungkin dianggap tidak berdampak secara langsung pada kedaulalan dan vitalitas ekonomi Indonesia. Namun, sebenarnya hal itu justru mengancam nilai-nilai inti bangsa Indonesia yang sedang dibangun kembali, yakni nilai-nilai HAM dan demokrasi. Selain itu, aksi pemerintah China juga tidak sejalan dengan tujuan nasional indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang antara lain didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan tetapi, pertimbangan ada atau tidak adanya kepentingan Indonesia saja belum memadai untuk menjelaskan sikap diam Indonesia dalam kasus ini. Saat ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia tengah mengalami kesulitan dalam penyusunan prioritas tujuan karena terdapat kepentingan dan tujuan nasional yang tidak kompatibel satu sarna lain. Tujuan nasional lndonesia untuk mempromosikan HAM berkonflik dengan tujuan lain yang tidak kalah penting, yaitu untuk memelihara hubungan baik dengan China yang posisinya dalam sistem internasional dewasa ini semakin menguat serta hubungan multilateral (dalam konteks ASEAN plus 3), Tentunya, Indonesia yang memiliki kepentingan ekstensif dalam bidang ekonomi (terutama ketika AS tengah dilanda resesi) tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merusak hubungan bilateralnya dengan China, misalnya dengan mengeluarkan pernyataan yang bernada mengecam (mungkin sehalus apapun). Selaln itu, segala pertimbangan mengenai tujuan nasional yang dilandaskan pada nilainilai fundamental bangsa Indonesia seperti kemanusiaan, HAM, dan demokrasi siasia saja jika lidak ditopang oleh kepemilikan kapabilitas dan power yang diperlukan unluk merealisasikannya. Sementara itu, kapabilitas Indonesia yang terdirl dari faktor geografi, sumber daya alam, dan sosial-kultural belum dapat ditranslasikan menjadi power karena manajemen yang kurang baik. Mungkin satu-satunya 'keunggulan' relatif Indonesia dibandingkan China, yaitu sistem pemerintahan demokratis yang sedang dibangun di tanah air. Jadi, secara relatif, dapat dikatakan bahwa dari segi power, Indonesia kalah jauh dari China. Oleh karena itu, dari perspektif ini, adalah rasional bagi pemerintah Indonesia untuk lidak mengeluarkan pernyataan yang bernada mengecam terhadap China atas aksinya di Tibet, meskipun hal tersebut seakan memperkuat anggapan bahwa Indonesia tidak berani mengambil sikap yang mencerminkan identitasnya. Pada titik ini tampaknya yang perlu diperhatikan oieh pemerintah Indonesia adaiah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada publik yang berminat dan bersikap kritis terhadap tragedy kemuaniaan di Tibet. Pemerintah kiranya dapat mendayagunakan berbagai saluran komunikasi polilik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, misalnya meialui diplomasi publik, diskusi-diskusi akademik di berbagai universitas, hingga komunikasi melalui situs resmi Deplu. Dengan cara ini, pemerintah dapat menghadirkan dirinya dalam ranah masyarakat sipil sembari mengimbangi debat kusir mengenai kebijakan luar negeri RI yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap pemerintah. Pada gilirannya, pemerinlah dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mengedukasi publik mengenai kompleksitas kebijakan luar negeri. Semua ini menjadi semakin penling di era globalisasi informasi dan komunikasi yang di salu sisi berpotensi mengancam legitimasi pemerinlah, namun di sisi lain menghadirkan peluang yang sangat baik untuk menciptakan masyarakat sipil yang berdaya, atentif, dan partisipatif baik dalam kebijakan luar negeri negeri tercinta ini.*** ________________________________________________________________________________ Yanyan Mochamad Yani dan Anggalia Putri Permatasari adalah Dosen dan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.