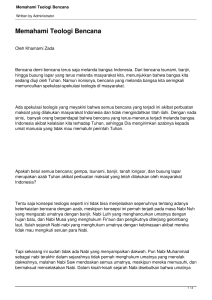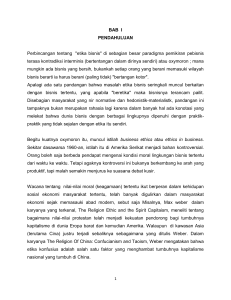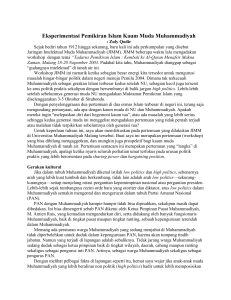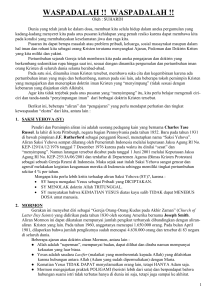Tanggung Jawab Politik GPIB Dalam Perspektif Teologi Politik
advertisement

B A B II TEOLOGI POLITIK: LANDASAN TEORI Indonesia sebagai negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir dengan sendirinya orang berasumsi bahwa agama dan negara itu satu. Dalam dokrin Islam dikenal yang disebut din wa dawla, yaitu bahwa Islam bukan sekedar agama melainkan juga negara. Pemahaman ini begitu melekat dalam diri orang Indonesia, sehingga orang menjadi heran apabila ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya konsep negara Islam tidak terdapat dalam Al Qur‟an. Yewangoe1 sebagaimana mengutip Gus Dur dalam buku Ilusi Negara Islam mengemukakan bahwa sistem negara Islam baru terjadi di era para khafila, yaitu para pengganti nabi Muhamad. Dalam sejarah lahirnya UUD 1945 partai Islam mencoba untuk mencantumkan syariat sebagai dasar Negara, tetapi hal tersebut mendapat tantangan dari masyarakat di Indonesia bagian timur. Ucapan Bung Karno di dalam pidato lahirnya pancasila, mengatakan bahwa Indonesia hendaknya menjadi Negara yang ber-Tuhan.2 Masing-masing agama mengamalkan ajarannya untuk dapat menciptakan hidup rukun dan sejahtera serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sehingga kemerdekaan yang dicapai dapat berarti dan bermakna bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu berkaitan dengan inti pembahasan tesis ini, penulis akan memberikan penjelasan teoritik menyangkut 3 [tiga] pokok bahasan, yaitu: 1 Andreas A. Yewangoe Teologi Politik, (Makasar: Yayasan Oase Intim, 2013),125. Panitia Persiapan Kemerdekaan IndonesiaSekretariat, Risalah Sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Jakarta: Sekretariat Negara republik Indonesia 1998), 101 . 2 10 [a]. Hubungan Gereja dan Negara, [b]. Teologi politik dan faktor-faktor pendukung. [c]. Peranan dan Fungsi Gereja di Indonesia. 1. Hubungan Gereja dan Negara Di kalangan gereja-gereja lebih santer dikemukakan pendapat bahwa relasi agama (gereja) dan negara mestinya dipisahkan (de scheding van kerk en staat). Artinya urusan-urusan agama sebaiknya diselesaikan oleh agama itu sendiri tanpa campur tangan negara. Tetapi dilain pihak perlu dipahami bahwa pluralisme agama-agama di Indonesia menyebabkan negara harus ikut berperan dalam menciptakan hidup rukun antar pemeluk agama. Agama mayoritas tidak boleh menekan yang minoritas tetapi sebaliknya mereka saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan bersama. Di sinilah akan diuji sampai sejauh mana kenetralan negara dalam menyelesaikan persoalan agama dalam suatu negara demokasi seperti Indonesia. Dalam pandangan Wogaman gereja mula-mula menunjukan sikap yang ambivalen terhadap pemerintahan. Disatu pihak pemerintah dianggap berasal dari Allah (jika ia melakukan kebaikan), dan dipihak lain pemerintah dianggap sebagai iblis (jika melakukan ketidakbenaran/jahat).3 Terhadap masalah ini Wogaman mencoba menawarkan beberapa pikiran dasar yang merupakan “theological entry points” untuk membangun etika politik Kristen. Pertama, Allah merupakan pemerintahan tertinggi, di mana kekuatan dan kekuasaan yang paling tinggi hanya pada Allah, maka dalam konteks kemanusiaan dan kekuasaan/kekuatan dunia tidak ada yang disebut dengan kekuasan/kekuasaan absolute. Sebab bagi Wogaman dalam kehidupan ini kita perlu memiliki kekuasaan tertinggi namun semua kekuasaan itu harus tunduk pada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan Allah (Roma 13). Kedua, Transendensi Allah. 3 J Philip Wogaman, Christian Prespectives on Politics, (Louisville John Knox Press 2000), 36. 11 Maksud pokok ini adalah bahwa dengan keberadaan Allah yang transenden itu, maka setinggi apapun manusia itu berkuasa ia tetap tidak sama dengan Allah. Ketiga, keterbatasan manusia. Sama dengan halnya Alkitab, dari sudut pandang antropologi juga memperlihatkan dengan jelas bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas. Hidup manusia sama singkat di dunia ini, kepandaian manusiapun sangat terbatas bahkan kekuasaan yang diraihpun akan lenyap. Dalam keterbatasan seperti itu, seharusnya manusia mempunyai kesadaran akan keterbatasannya untuk tidak saling menghakimi dan menjahtuhkan satu sama lain dengan mengatasnamakan kehendak Tuhan untuk memperoleh kekuasaan. Keempat, dokrin tentang penciptaan alam semesta dan manusia menjadi sangat melekat di hati orang Yahudi agar bersikap takut, tunduk dan taat pada Allah. Dalam teologi Yahudi, pemerintah haruslah dilihat dari konteks perjanjian antara Yehweh dan umat-Nya di mana Ia sendiri menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Kelima, dokrin tentang dosa, salib dan anugerah. Dokrin tentang dosa mula-mula telah menempatkan manusia di dalam ketidakberdayaan. Dalam konteks ini Thomas Bobbes mempertanyakan apakah ada kemungkinan manusia mencapai kemajuan melalui proses politis untuk mencapai kekuasaan. Apakah tidak berbahaya bila manusia dalam kondisi kejahatannya diberi kekusaan apalagi kekuasaan absolute bila ia sendiri tidak dapat mengendalikan dirinya. Keenam, eskatologi dan ekklesiologi. Dokrin eskatologi dalam prespektif Kristen merujuk pada keyakinan akan berakhirnya sejarah yang dalam istilah teologis disebut sebagai penggenapan, di mana semua kekuasaan manusia akan berakhir oleh kekuasaan yang tertinggi yaitu kekuasaan Allah. Namun orang-orang Kristen masih berada di tengah dunia dan selaku gereja di tengah dunia, dirinya melakukan perjumpaan dengan segala konsekuensi-konsekuensi politis yang mengitarinya. Namun justru disinilah letak 12 panggilan orang Kristen selaku komunitas iman bersama dengan saudara-saudaranya yang lain (yang tidak seiman) tetap melaksanakan panggilan politisnya tanpa harus menarik diri hanya karena semata-mata ia orang beriman.4 Hubungan gereja dan pemerintah (politik) bagi Wogaman memiliki beberapa model antara lain: Model Teokrasi Model Erasionisme “Pemisahan” secara Damai Pemisahan yang tidak bersahabat yang mengakibatkan Permusuhan 1.1. Model Teokrasi Pada model teokrasi menurut Wogaman, Negara berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin atau lembaga-lembaga agama guna kepentingan keagamaan contohnya dapat kita lihat sebagian besar pada masyarakat primitife, dalam masyarakat Ibrani zaman dahulu dan pada wilayah-wilayah muslim pada masa yang berbeda (contohnya Iran). Bentuk ini dapat juga ditemukan dalam bentuk katolisisme modern seperti dibebarapa kota zaman Vatikan II5. Ia selanjutnya menjelaskan bahwa teokrasi telah merupakan komitmen orang atas usaha yang tidak biasa terhadap pandangan politik tertentu. Jika salah satu pandangan agama benar, maka mengapa tidak memasukkan kekuasaan negara untuk mendukungnya? Sedikit para teolog yang berpikir bahwa mungkin dengan cara demikian mengusahakan orang lain untuk beriman. Tetapi kekuasaan negara sedikitnya dapat menghambat kompetensi dan menciptakan kondisi nyata yang lebih menolong. Inilah yang terjadi di Eropa post-constantinian, di mana kekristenan berubah dari status 4 5 J. Philip Wogaman ...., 163-177. Ibid., 250. 13 minoritas menjadi suatu dominasi kebudayaan yang mendukung kekaisaran Romawi. Kekuasaan Negara tak pasti menjamin penyebaran suatu agama, tetapi siapa yang dapat membantah bahwa hal tersebut dapat sangat memfasilitasi penyebaran agama? Hanya sedikit orang pada masa itu yang menyarankan keutuhan teokrasi dari penyatuan gereja dan negara, tetapi aspek-aspek tertentu dan model teokrasi sangat mendukung. Di Amerika Serikat berbagai usaha dilakukan oleh para penginjil yang cemburu, menginginkan negara secara konstitusional menandatangani pengesahan “Negara Kristen” dan memperkenalkan kembali pengenalan agama-agama di sekolahsekolah publik. Tetapi hal ini merupakan suatu bahaya yang harus diambil oleh orang Kristen ini merupakan suatu cara mencapai ilusi. Beberapa ilusi tersebut bersifat praktis dan politis. Mereka yang berusaha mengontrol negara bagi tujuan agama, kadang pada akhirnya menemukan bahwa pada akhirnya gerejalah yang digunakan untuk kepentingan politik. Terdapat juga masalah praktis tentang bagaimana membedakan antara kebaikan dan ketidak-baikan iman dalam suatu masyarakat di mana badan-badan keagamaan berkuasa. Kekuasaan memiliki penghargaan atas dirinya bagaimana gereja dapat mengatakan perbedaan antara mereka yang mengakui iman sebagai wujud ketaatan yang murni pada agama dengan mereka yang hanya mencari penghargaan. Sebuah negara teokrasi dapat saja berilusi bahwa apa yang mereka lakukan akan di dukung oleh publik, tetapi dapat saja pada kenyataannya tidak demikian. Teokrasi hadir dalam penempatan bahwa kebenaran dapat dikenal baik untuk membuat sesuatu perbedaan utama antara mereka yang dalam kebenaran dan mereka yang tidak. Mereka yang dalam kebenaran diizinkan untuk memerintah, sementara mereka yang tidak secara hukum tidak bisa memerintah. Ilusi yang terjadi di sini tidak 14 hanya bahwa mereka yang tampaknya dalam kebenaran dapat saja merupakan oportunis yang mengambil keutungan dari hak istimewa mereka untuk dapat memerintah. Konsep akan Tuhan lebih terbuka semacam itu merupakan suatu kekuasaan yang mendukung demokrasi, dan dapat juga menjadi alasan terkuat menolak teokrasi, karena teokrasi telah menentukan siapa orang yang dapat dipakaioleh Tuhan dan siapa yang tidak dapat di pakai oleh Tuhan.6 1.2. Model Erastianisme Menurut Wogaman, untuk mengindentifikasi teokrasi secara tepat sangatlah sukar, ini dikarenakan apa yang dianggap bahwa pemimpin agama mengontrol negara bagi kepentingan agama, pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, pemimpin politik mengontrol agama bagi kepentingan negara. Agama sangat dieksploitasi bagi kepentingan-kepentingan politik, yakni digunakan untuk mengusahakan persatuan dalam suatu komunitas masyarakat, memberi kekuasaan bagi negara, memberi suatu sanksi atas kebijakan politik lainnya. Sebagian besar kaisar Romawi yang memerintahkan adanya penyembahan atas diri mereka ini tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan dari jabatan mereka. Penolakan orang Kristen untuk menyembah Kaisar telah dilihat sebagai suatu ketidak-taatan terhadap kekuasaan, dan bukan sebagai suatu ketegasan atas kekuatan-kekuatan keagaman. Perlu di pahami bahwa Erastianisme adalah agama yang digunakan bagi kepentingan negara (setelah abad enam belas Erastus Thomas asal Swiss). Pendekatan Erastian terhadap negara berusaha untukm mengotrol gereja telah diikuti oleh para politikus dalam tujuan agama. Hal ini terbukti dalam negara yang dikontrol baik legal maupun institusional Penyembahan Shinto di Jepang adalah lebih bersifat Erastian 6 Ibid., 253-254. 15 dibanding Teokrasi, dan dapat dianggap benar oleh sebagian besar masyarakat Budha di Asia Tenggara.7 Menurut Wogaman, tujuan politik zaman itu diabsolutkan penguasaan lembagalembaga agama oleh negara semuanya demi kepentingan politik, sampai penolakan formal akan Tuhan yang transenden. Menurutnya, agama sipil dapat konsisten dalam pemahaman akan Tuhan yang transenden-sebagaimana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, dimana negara dipahami berada di bawah pengadilan Tuhan. Juga Robert Bellah mengatakan, mengusahakan suatu agama sipil yang lebih baik bukanlah suatu erastian. Walaupun kita menaruh perhatian bahwa terdapat suatu sumber dari legitimasi transenden agama bagi negara demokrasi.8 Menurutnya juga, bahwa memahami negara berada di bawah pengawasan Tuhan dan bukanlah manipulator dari lembaga keagamaan guna suatu tujuan temporere yang murni: simbolisasi semacam itu dapat lebih dari penyembahan atas negara sebagai kebaikan tertinggi, atau dapat saja menjadi, seperti Amerika, penyembahan kepada realitas yang lebih tinggi yang mengatasi standar-standar yang berusaha dibangun oleh republik. Ketika negara itu sendiri diperlakukan sebagai kebaikan tertinggi maka integritas dan lembaga keagamaan itu secara fatal ditanyakan. Mereka tidak lagi dianggap serius, di atas landasan iman yang mereka bangun. Mereka hanya menjadi penting bagi kepentingan politis mereka. Beberapa tingkatan Erastianisme pada kenyataan dapat dihindari, bagi gerejagereja yang ada dalam masyarakat dan pada tingkatan tertentu diperintah oleh negara. Kenyataan tersebut berarti bahwa integritas gereja harus selalu menjadi usaha dalam 7 8 Ibid., 250. Ibid., 255. 16 perjuangan-perjuangan teologis. Tetapi erastianisme yang sempurna, dimana negara mengontrol gereja secara penuh, pada prinsipnya merupakan suatu pengidolaan.9 1.3. Pemisahan secara Damai Pada model ini, Wogaman mengemukakan bahwa di beberapa negara, lembagalembaga agama dan politik secara hukum terpisah, tetapi tanpa kebencian atau permusuhan. Bentuk inilah yang secara esensial terjadi di Amerika Serikat. Dengan mengabaikan panggilan untuk suatu hubungan yang lebih erat, prinsip akan tidak dibangunnya agama dalam lembaga-lembaga negara di AS dipahami bukan sebagai suatu yang negatif, tetapi tidak adanya keterlibatan agama dalam negara dapat dilihat sebagai suatu usaha yang positif bagi integritas dan kemandirian badan-badan keagamaan.10 Versi yang bersahabat dari gereja dan negara ditemukan di beberapa negara Barat yang demokrstis. Ini merupakan bagian penting dari hukum dan tradisi di AS, di mana kunci institusional yang dihasilkan dalam amandemen Pertama adalah “Kongres tidak membuat hukum apapun menyangkut keberadaan agama, atau melarang kebebasan beragama,” pernyataan ini yang merupakan landasan dan tradisi Amerika” pemisahan agama dan negara”, yang kadang diterjemahkan dengan cara yang berbeda.11 Interpretasi Thomas Jefferson (yang dikutip Wogaman) akan pernyataan ini dapat ditemukan dalam surat terkenal kepada Asosiasi Babtis Danburry. Sama seperti yang anda yakin bahwa agama hanya merupakan suatu permasalahan tentang manusia dan tuhannya, yang mana ia tidak bertanggungjawab terhadap orang lain atas keyakinan dan ibadahnya, demikian juga kekuasaan legislatif dari pemerintah dapat melakukan tindakan dan bukan pendapat. Mengacu kepada penyataan masyarakat Amerika sebelumnya yang menyatakan bahwa legislatif harus “tidak membuat aturan apapun menyangkut 9 Ibid., 255-256. Ibid. 11 Ibid., 256. 10 17 keberadaan agama atau melarang bebebasan beragama”, karenanya hal itu membangun suatu dinding pemisahan antara gereja dan negara.12 Beberapa pemimpin agama dan teolog tidak senang disebut “religius”. Teolog Karl Barth dan Hendrik Kraemer, membedakan antara “iman Kristen” dan “agama”, bagi mereka agama merupakan usaha manusia untuk mengenal Tuhan, sedangkan iman merupakan respon manusia akan pemberian iman yang dihasilkan dari usaha Tuhan menjangkau manusia lewat Yesus Kristus. Bagaimanapun bagi Barth dan Kraemer menginginkan mereka mengatakan iman mereka sebagai orang Kristen berada di bawah perlindungan Amandemen pertama. Tetapi negara harus berhati-hati untuk mendefenisikan agama dalam cara untuk menciptakan peluang bagi mereka yang menyebut diri mereka religius akan mendapatkan keuntungan dari hak istimewa dari agama.13 1.4. Pemisahan Yang Tidak Bersahabat Dalam dua abad terakhir ini, sering dikembangkannya pemisahan yang tidak bersahabat antara gereja dan negara. Sebagian besar negara-negara Marxisme (contohnya Perancis) melembagakan suatu kebencian atau prasangka terhadap lembagalembaga agama. Pada kenyataan di sebagian besar negara-negara seperti itu, lembaga-lembaga agama, penginjil-penginjil dan lainnya disediakan beberapa pendanaan publik yang juga disertai pula dengan kontrol publik. Tetapi sikap yang jelas dalam negara-negara semacam ini adalah agama di toleransi hingga masyarakat menjadi dewasa menuju suatu pandangan yang ilmiah. Pada akhir abad, 19 kelompok-kelompok agama masih menemui kesulitan untuk menembus negara-negara Marxis. 12 13 Ibid. Ibid., 258. 18 Mengenai beberapa tradisi nasional adalah penting untuk mengingat bahwa praktek yang sebenarnya dapat sangat berbeda dengan teori konstitusional. Lebih jauh lagi, apa yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan sejarah tradisinya yang unik-unik bisa saja tidak berlaku di negara lainnya dan bahkan di situasi yang sangat berbeda, orang kristen dapat terus mengingat bahwa martir itu telah menjadi benih bagi gereja. Akhirnya pemisahan yang tidak bersahabat adalah berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh orang Kristen atas Civil society. Tingkat yang bagaimana negara harus mendukung lembaga dan praktek-praktek agama dapat diperdebatkan. Tetapi secara teologis dan berdasarkan prinsip demokrasi sebaiknya tidak harus ditentang.14 Mengenai hubungan gereja dan negara, Robert N. Bellah dan Phillip E, Hammond mengemukakan bahwa hampir seluruh rentang sejarah Barat, terjadi ketegangan antara gereja dan negara yang sangat dalam. Dalam banyak peristiwa sejarah, negara mendominasi gereja dan mengekploitasinya, dan suatu waktu, negara dapat dikuasai oleh gereja, bahkan menggunakannya bagi kepentingan dirinya dan menduniawikan loyalitas spiritualitasnya ke dalam suatu bentuk nasionalisme keagamaan.15 Menurut mereka “hingga saat ini belum ada pemecahan yang pernah menghilangkan keteganganketegangan mendasar. Kecenderungan yang telah terjadi bagi setiap pemecahan persoalan ketegangan itu adalah memposisikan agama sebagai pelayan negara atau negara sebagai pelayan agama”16. Sebagai reaksi atas permasalahan tersebut, kemudian muncullah gagasan tentang pemisahan gereja dan negara disertai dengan Undang- 14 Ibid., 251-252. Robert N. Bellah dan Philip E, Hammond, Varieties of Civil Religion, penerjemah, Imam Khoiri, dkk, (Jogja: IRGiSoD), 26-28. 16 Ibid. 15 19 undang yang melarang suatu pembentukan agama melindungi kebebasan menjalankan (ajaran) agama. Hal tersebut dilanjutkan dengan ide tentang kebebasan beragama. Kekebasan agama akhirnya hanya menjadi sebuah hak untuk menyembah Tuhan apapun yang disukai atau tidak sama sekali. Dengan implikasi bahwa agama adalah sematamata urusan pribadi yang tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan masyarakat politik (political society)17. Di Perancis awal hingga sekarang, liberalisme mencapai salah satu tujuannya, yaitu pemisahan total gereja dan negara, yang berarti gereja sangat bebas dari tekanan politik. Sebenarnya hubungan seperti ini mau menggambarkan adanya kecenderungan orang untuk memisahkan gereja sama sekali dari negara dan memisahkan negara sama sekali dari agama/gereja sehingga tidak ada lagi saling mempengaruhi dan kerjasama antara gereja dan negara. Meskipun demikian, kebebasan mereka untuk melakukan kegiatan sangat terbatas karena keuangan mereka sangat tergantung pada dukungan perorangan. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Jerman, hubungan gereja dan negara di Jerman sangat dekat sehingga gereja-gereja diperbolehkan menarik pajak gereja yang dibayar oleh semua anggota. Pajak itu mulai dikumpulkan melalui struktur administrasi negara, meskipun gereja-gereja harus membayar biaya andministrasi. Bahkan gereja-gereja diberi dukungan keaungan oleh negara untuk menunjang pelayanan gereja di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.18 17 Ibid., 29-30. Wolfgang Schmidt, Agama Negara dan Bangsa: Suatu Perdebatan Baru Beberapa Permasalahan dalam Perdebatan Eropa, dalam Soegeng Hardiyanto et al (dewan Redaksi), Agama dalam Dialog Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan. Punjung tulis 60 Tahun Prof Dr Olaf Schumann (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 330-331. 18 20 2. Teologia Politik Dan Faktor-Faktor Pendukung19 Istilah “teologi politik” digunakan secara luas sejak 1960-an dan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh para teolog Katolik dan Protestan untuk mengatasi krisis kebudayaan dengan dasar-dasar Kekristenan dalam terang abad XX. Setelah Perang Dunia I, teologi mencapai semacam ekuilibrium, dimana ada tiga tokoh teolog Protestan seperti K.Barth (1968); R.Bultmann (1976) dan P.Tillich (1965) mengembang sayap-sayap refleksi teologis hingga mencapai ketinggian sekaligus kedalaman yang menakjubkan. Sementara itu orang-orang Katolik masih mengembangkan rona skolastisisme yang digaungkan kembali oleh Leo XIII (1879), yang menyeru agar diadakan pembaruan teologi-filosofis Thomisme.20 Dapat jadi, orang yang mendengar untuk pertama kalinya istilah “teologi politik” merasa bingung dengan arti dan maknanya. Kebingungan ini bukan karena istilah “teologi politik” memberikan sebuah fenomena yang tidak familier, melainkan karena terminologi itu mengesankan berupaya menggabungkan 2 (dua) hal yang tidak kompatibel, bagaikan air dan minyak. Dikalangan para teolog, teologi politik yang dicetuskan oleh Johann Babtist Metz 21 sering dikualifikasikan dengan ungkapan Teologi Politik Baru. Kualifikasi ini dibutuhkan, sebab memang sudah ada teologi politik lama sejak zaman Yunani Kuno. Pada Stoa kita telah menemukan pembagian teologi ke dalam tiga kelompok: teologi mitis, teologi naturalis, dan teologi politik. Di dalam era Romawi kuno teologi politik dipakai sebagai legitimasi kekuasaan negara. Teologi politik adalah teologi publik yang mendasarkan kekuasaan absolut dan infalibel negara. Pandangan tentang legitimasi 19 John B. Cobb,Jr, Process Theology as Political Theology, (Philadelphia: Manchester University, 1982), 8-25. 20 A.Eddy Kristiyanto, Teologi Politik, (Jakarta: Yayasan Bumi Karsa 2003), 1-2. 21 Dikutip oleh Paulus Budi Kleden, dalam buku yang berjudul Teologi Terlibat, 67. 21 teologis atas politik negara masih diwakili oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, yang berangkat dari anggapan bahwa manusia dari alamnya memiliki kecenderungan untuk menghancurkan orang lain, sebab itu dibutuhkan dominasi negara yang mesti dilegitimasikan secara teologis demi terciptanya sebuah kondisi yang baik di dalam kehidupan bersama. Kleden mengutip pendapat Metz dengan menyebut teologia politik adalah keseluruhan konstruksi pengetahuan, sistem nilai dan tatanan masyarakat yang menentukan kehidupan bersama manusia.22 Teologi politik tidak mempunyai maksud lain selain mengungkapkan relefansi politis dari iman. Yang dimaksudkan ialah, bukanlah iman itu mempunyai satu dimensi politis, yang mesti dibedakan dari dimensi personal. Seluruh iman itu bersifat politis, juga aspek personal dari iman adalah sebuah ungkapan dari ciri politis iman. Yang personal, yang bersifat individual senantiasa mengungkapkan dirinya dalam kebersamaan dan membutuhkan perlindungan dan pengakuan dari dunia politik. Karena itu teologi sebagai pembicaraan tentang iman mesti menyadari tendensitendensi dan mengungkapkan kekuatan-kekuatan masyarakat, untuk dapat mempertahankan aspek personal dari iman. Teologi seperti ini hendak menjawab tantangan yang dilemparkan oleh kritik agama sebegai kritik idiologi dari sudut marxisme. Untuk itu teologi politik harus menyadari implikasi-implikasi sosial politis dari pengertian-pengertiannya. Metz mengingatkan setiap teologi untuk bertanya “siapa berbicara, kapan dan dimana, untuk siapa dan dengan maksud apa Allah?” berbicara.23 Teologi perlu membongkar kesadaran akan kepentingan yang melatarinya dan mempertanggungjawabannya. Bagi Metz semua yang mungkin secara teknis dapat 22 23 Ibid., 69. Paulus Budi Kleden, mengutip artikel JB.Metz yang berjudul Politische Theologie, 394 22 diperbolehkan secara etis. Dengan demikian tidak ada lagi ruang untuk segala kemungkinan lain, untuk semua ideal dan alternatif lainnya. Karena itu tugas pertama dari teologi politik yang hendak memantau dan mendampingi secara kritis sebuah masyarakat adalah menunjukan keterbukaan manusia kepada masa depan dan serentak menyingkapkan ketakmestian dan keterbatasan dunia nyata. Teologi mesti menjadi teologi yang berorientasi ke masa depan, namun oreintasi ini sekaligus bersifat kritis terhadap diktator pada masa sekarang. Di sini teologi mesti menjadi sebuah eskatologi, menjadi sebuah teologi harapan. Dimensi eskatologi dari teologi bukannya hendak mengembalikan teologi kepada pembicaraan tentang dunia akhirat, melainkan menanamkan kesaradan bahwa yang ada ini belum yang semestinya. Pada latar kesadaran akan status “belum” dari yang ada, yang ada sekarang akan tampil sebagai yang mesti di ubah. Di bawah cahaya dari “yang masih akan datang”, yang ada sekarang akan kehilangan kemutlakannya. Kritik atas yang ada dan penghadiran diri “yang akan datang” itu dilakukan dalam praktek perubahan itu sendiri. Dengan demikian maka tidak ada sesuatu yang mutlak tetapi semuanya berada dalam proses untuk mencapai kesempurnaan.24 Tiga tokoh dalam teologi politik Jerman yakni Johann Baptist Metz, Jurgen Moltmann dan Dorothe Solle menyampaikan pemikirannya tentang teologi politik yang di kutip oleh John B.Cobb,Jr mengungkapkan bahwa pada pertengahan tahun enampuluhan Metz berkonsentrasi pada bagaimana hubungan manusia dalam dunia, karena manusia menyatu dengan dunia maka ia tidak bisa dipisahkan dari keberadaannya di tengah lingkungan dan masyarakat. Setiap pengalaman dunia 24 Ibid.,71. 23 berlangsung dalam cakrawala eksistensi manusia bersama, bukan hanya dalam masalah “pribadi” tetapi dalam “politik” menyangkut eksistensi sosial di masyarakat. Jadi setiap pengalaman tentang sejarah manusia terjadi dalam konteks dunia dimana manusia itu berada. Sehingga berbicara tentang teologi, harus dimuali dari dunia. Teologia dunia harus dimualai dari kreatifitas, harapan, militan, yang berbasis kepada dunia dan masyarakat untuk mengalami perubahan. Metz pada tahun 1961-1967 menulis sekumpulan esei yang berjudul “Teologia Dunia” dan artikel yang berjudul “Gereja dan Dunia dalam terang teologi politik”. Tulisannya itu menimbulkan banyak diskusi dan perdebatan. Sesuadah tahun 1969 ia menerbitkan sebuah buku untuk menjawab perdebatan. Dalam pikirannya itu ia mengidentisikasikan tiga hal yang berkaitan dengan teologi politik. Yang pertama, adalah tugas seorang „hermeneutik‟ teologis dalam konteks sosial kontemporer. Ini disebut juga hermeneutika politik. Kedua, teologi politik baru harus menjadi „kritis korektif terhadap kecenderungan prifatisasi tertentu dalam teologi terkini, ketiga, karena teologi dan gereja benar-benar memiliki kepentingan politik yang sangat besar maka teologi politik harus memiliki fungsi penting dalam gereja‟. Jurgen Moltmann pada tahun 1971 menerbitkan sebuah esei tentang „teologi politik‟ dimana dia mengungkapkan pikirannya bahwa orang kristen dewasa ini harus mengungkapkan kebebasannya berdasarkan tradisi mereka sendiri, tetapi itu belum tercapai dalam hubungannya dengan dunia politik. Disamping itu ia melihat teologia politik sebagai teologia untuk mengkritik diri sendiri (hermeneutis), kritik itu akan membuat kita sadar akan lingkungan sosial dan konteks dimana kita berada. Ketika kita menyadari akan setting sosial dimana kita berada maka kita akan mengembangkan suatu hermeneutik politik. Kita akan berpindah 24 dari eksistensialisme dan interpretasi teks tradisionil ke hermeneutik politik tradisi yakni pemahaman kepada sebuah eksegesis representasi keagamaan tradisional dalam arti praktis. Solle tidak memberikan kepada kita suatu penjelasan yang penting tentang telogi politik tetapi dia menawarkan sesuatu yang sangat eksplesit yang berfokus kepada hermeneutik. Dia menyatakan bahwa teologi politik paling baik dipahami sebagai „interpretasi politik injil‟. Solle, seperti Metz dan Bultmann, menyatakan bahwa dasar dari teologi politik adalah kritis baik dalam gereja maupun struktur dalam masyarakat. Akhirnya akan melibatkan otokritik, dan pengakuan tentang bagaimana seseorang terikat dalam dosa masyarakat dan memiliki kecenderungan yang mengarah pada tindakan yang jahat. Dari ketiga tokoh teologi politik di atas menurut John B.Cobb.Jr mereka juga mempunyai kesamaan. Ketiganya melihat teologi politik sebagai suatu hermeneutik, yaitu kritik terhadap gereja dan teologi serta realitas sosial dalam masyarakat. Beberapa pertanyaan yang perlu dilontarkan adalah apakah semua teologi harus menjadi teologi politik? dan apakah politik menjadi satu-satunya sumber bagi pekerjaan teologis? serta apakah hanya ada keselamatan pribadi tanpa keselamatan sosial. Menurut Solle bahwa sudah waktunya sekarang seluruh teologi harus menjadi teologi politik. Sebab tidak ada keselamatan pribadi. Melalui prinsip hermeneutis dapat membimbing kita memahami arti kehidupan bagi semua orang. Ini bukan berarti bahwa persoalan individu di abaikan atau dikesampingkan, tetapi pertanyaannya bagaimana persoalan individu berkaitan dengan kondisi sosial dalam konteks dimana kita berada. Sebab pada prinsipnya manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dan berkaitan dengan manusia yang lain. 25 Jadi tidak ada keselamatan sendiri-sendiri. Subjektivitas dimasukkan ke dalam proses sosial dengan tujuan bukan untuk mencari pemahaman diri sendiri saja, melainkan percaya dan memahami bahwa keselamatan itu berada dalam dunia. Pandangan keutuhan keselamatan bagi semua secara konsisten berakar pada keyakinan bahwa semua realitas dunia yang ada adalah kenyataan sosial. 2.1. Teologia Politik dan Kritik Atas Ketidakadilan Pertanyaan tentang kebutuhan masyarakat akan pentingnya agama muncul kembali selama jaman Renaisance dan Pencerahan. Klem kekiristenan sebagai agama negara dianggap sebagai salah satu hambatan pada abad XVII. Masyarakat pada saat itu menginginkan adanya suatu agama yang memenuhi kebutuhan komunitas manusia akan suatu agama politis, atau yang disebut Russeau agama sipil. Para pemimpin dari Restorasi Katolik menekankan pentingnya agama bagi masyarakat untuk menghadapi arus sekularisasi di jaman Pencerahan dan Renaisace. Walaupun pada mulanya argumen ini digunakan untuk mendukung suatu bentuk aliran konservatif gereja katolik namun bagi mereka yang memilki aliran sosial yang positif yang dapat diterima oleh masyarakat. Pada abad ke-20, pembahasan tentang teologia politik dikemukakan oleh Carl Schmitt yang menggunakan istilah tersebut sebagai suatu judul buku tahun 1922. Ia mengemukakan pendapat dengan melihat monarki sebagai sesuatu yang berhubungan dengan konsep ketuhanan yakni pemerintahan teokrasi yang bertentangan dengan demokrasi. Thesis Scmitt menghasilkan perdebatan yang membawa koreksi bagi gereja dan orang Kristen. Gereja harus dapat melihat masalah-masalah sosial dan politik sebagai tanggung jawabnya, dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara 26 saja. Hal tersebut menjadi koreksi gereja karena kekuasaan Hitler menjadi sesuatu yang menakutkan bagi keberadaan umat manusia di masa mendatang. Kekejaman dan ketidak adilan meraja lela tanpa ada perlawanan. Seakan-akan Hitler menjadi Allah di dunia ini bagi sesamanya. Solle menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Di balik Ketaatan Semata”. Pemikirannya tentang teologia politik dituangkan dalam buku ini. Ia menunjukkan bagaimana hubungan yang erat dari iman dengan ketaatan yang buta terhadap Tuhan, yang dipicu oleh ketaatan teologia Kristen kepada peraturan-peraturan yang dimanifestasikan pada Hitler di Jerman.25 Solle tidak menyediakan suatu daftar yang memadai dari bentuk-bentuk asli dari teologi politik, tetapi dia lebih menekankan kepada hermeneutik politik. Artinya teologi politik harus dipahami sebagai „interpretasi politik dari Injil‟. Bagi Solle, seperti juga Metz dan Molmann, teologi politis pada dasarnya merupakan teologi kritis. Kritik terhadap teologi dan gereja dalam menyikapi struktur masyarakat yang tidak adil. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana seseorang terikat dengan dosa masyarakat yang kecenderungannya melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Sebuah tindakan kritik terhadap masyarakat yang membiarkan kaum kapitalis atau para penjaga kamp konsentrasi yang selalu ada di sekitar kita. Metz melihat bahwa penderitaan Yesus adalah bagian dari tindakan politik. Dan gereja harus benar-benar kritis terhadap situasi politik yang terjadi. Ia mengambil contoh penindasan Israel kepada bangsa Palestina. Dalam hal ini penilaian kita bukan pada masalah aktualnya namun pada implikasinya terhadap peran dan fungsi gereja dalam menegakskan keadilan. Banyak dari mereka yang kehilangan, harta benda, 25 Ibid.,17-19. 27 tempat tinggal dan keluarga. Gereja harus bertindak atas sebuah komitmen tanpa syarat untuk mencapai keadilan, kebebasan dan kedamain bagi semua. Satu hal yang sangat penting dari teologi politik menurut Whitehead sebagai seorang pemikir kristen adalah „kebebasan‟ merupakan suatu keharusan. Jika tidak ada kebebasan, keberanian tidak ada gunanya. Ia mengemukakan bahwa kebebasan dan persamaan menjadi satu karena hal yang terpenting dari „persamaan‟ adalah kebebasan. Dengan kebebasan setiap orang akan memperjuangkan haknya tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Dan sebaliknya tidak ada gunanya kalau seseorang itu bebas tapi masih ada perbedaan, dalam hubungannya dengan hak wanita, ras, atau agama.26 Metz ingin semua orang memahami sepenuhnya tentang diri mereka sebagai subyek yang bebas. Sama halnya dengan Whitehead yang berfokus pada kesadaran akan kebebasan. Komitmen Whitehead memperjuangkan kebebasan dengan mengatakan bahwa Allah ada bersama orang-orang yang tertindas, dan kita dipanggil untuk bersolidaritas dengan mereka. Ia mengambil contoh tentang struktur pendidikan yang memihak kepada orang kaya menyebabkan orang miskin akan terus tergusur dan tidak memperoleh tempat untuk menikmati pendidikan yang lebih baik. Ada juga penindasan dan perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat kulit hitam di Amerika Latin. Oleh karena itu gereja dan orang kristen harus terpanggil dengan sepenuh hati untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Allah menuju kepada keselamatan seluruh dunia, dengan melibatkan semua dimensi, publik dan sosial. Semua orang harus dipanggil untuk membagi tugas dan perannya masing-masing. Mereka harus diyakinkan tentang pengampunan Allah melalui penderitaan Yesus Kristus. Untuk memahami iman kristen dengan cara ini merupakan suatu kemajuan yang sangat besar. Namun itu baru 26 Ibid.,146. 28 permulaan. Orang-orang Kristen setuju bahwa keselamatan mencakup seluruh dunia, meliputi aspek manusia dan alam, semuanya berada dalam kerangka rencana keselamatan Allah. Untuk itu Ia akan tetap menjaga dan melestarikan alam untuk kelangsungan dan kesejahteraan bersama. Begitu pula dalam hubungan dengan sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pintu harus terbuka terhadap pluralitas. Bagaimana pengalaman penderitaan orang kulit hitam di amerika Serikat dan di Amerika Latin, bahkan para wanita di Atlantis Utara. Selain itu juga kita tidak boleh melupakan pengalaman orang Yahudi yang telah menderita oleh tangan orang-orang Kristen pada abad 19. Dan masih banyak lagi yang kita lihat penindasan terhadap kaum minoritas. Kebanyakan orang di dunia dibentuk dalam presepsi dan harapan oleh tradisi religius dari Yudaisme dan Kekristenan. Apa yang mereka lihat sangat berbeda dengan apa yang kita lihat, semuanya sangat berbeda dengan ajaran dan pemahaman iman Kristen itu sendiri. Dewan gereja-gereja sedunia telah menyediakan sebuah forum untuk menampung semua suara-suara yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Karena selama ini mereka tidak didengarkan serta tidak mendapatkan tempat untuk mengungkapkan segala penderitaan yang mereka alami. Semuanya ini dilakukan dengan visi akan masyarakat yang adil, berpartisipasi dan berkelanjutan untuk dunia yang diselamatkan.27 2.2. Dimensi Politik Manusia Moltmann membagi dimensi politik menjadi empat sebagaimana dikutip oleh John B, Cobb Jr, antara lain:28 27 28 Ibid.,154. Ibid., 90-91. 29 1. Dalam dimensi kehidupan ekonomi, kebebasan berarti kepuasan kebutuhan material manusia akan kesehatan, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Lebih jauh dari ini adalah keadilan sosial yang dapat memberikan semua anggota masyarakat berbagi kepuasan dan keadilan dari produk yang mereka hasilkan. Sejauh lingkaran setan kemiskinan dihasilkan oleh eksploitasi dan dominasi kelas, keadilan sosial hanya dapat dicapai dengan redistribusi kekuatan ekonomi. Jika dan sejauh sosialisme, berarti kepuasan dan kebutuhan material dan keadilan sosial dalam demokrasi material, sosialisme adalah simbol pembebasan manusia dari lingkaran setan kemiskinan. 2. Dalam dimensi kehidupan politik, demokarasi adalah pembebasan dari lingkaran setan penindasan. Dengan ini, dapat dimengerti bahwa martabat manusia akan menjadi penting apabila dia dapat menerima tanggung jawab politik. Ini termasuk partisipasi dalam hal pengendalian dan pelaksanaan kekuasaan ekonomi dan politik. Pada tingkatan ini demokrasi berarti penghapusan hak istimewa dan pembentukan hak asasi manusia. Demokrasi adalah simbol pembebasan manusia dari lingkaran setan kekerasan. 3. Dalam dimensi kehidupan budaya, pembebasan dari lingkaran setan keterasingan berarti identitas dalam pengakuan terhadap orang lain. Dengan ini kita mengartikan 'emansipasi manusia dari manusia' (Marx), di mana manusia mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan diri dalam pengakuannya terhadap orang lain dan dalam persekutuan dengan mereka. Jika dan sejauh emansipasi berarti personalisasi dalam sosialisasi dan menemukan identitas seseorang dalam pengakuan terhadap orang lain. Emansipasi adalah simbol pembebasan dari lingkaran setan keterasingan. 30 4. Dalam hubungan masyarakat dengan alam, pembebasan dari lingkaran setan polusi industri menandakan bahwa manusia telah berdamai dengan alam. Tidak ada pembebasan orang dari kesulitan ekonomi, penindasan politik dan keterasingan manusia akan berhasil yang tidak bebas dari eksploitasi alam yang tidak manusiawi dan yang tidak memenuhi/memuaskan alam. Oleh karena itu tahap panjang pembebasan manusia dari alam dalam 'perjuangan untuk bertahan hidup harus diganti oleh fase pembebasan alam dari kebiadaban demi 'perdamaian yang eksis'. Pada tingkat bahwa transisi orientasi meningkat dalam kuantitas hidup untuk menghargai kualitas hidup, dan dengan demikian dari kepemilikan alam dengan sukacita yang ada di dalamnya dapat mengatasi krisis ekologi. Perdamaian dengan alam adalah simbol pembebasan manusi dari lingkaran setan ini. Semuanya itu terjadi karena keserakahan manusia. 2.3. Metodologi Teologia Politik Teologi politik harus memiliki karakter atau ciri khas baik itu metode maupun dokrin-dokrin yang tepat maupun sesuai dengan konteks dan persoalan gereja di tengah kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan ini kita akan melihat metodologi Teologi politik yang di jelaskan oleh John B Cobb Jr,29 dengan membandingkan pemikiran beberapa ahli teologi politik diantaranya Metz, Moltmann dan Solle. a). Hermeneutik Teologi.30 Ketiga teolog ini menekankan bahwa hermeneutik sebagai pusat dari teologi politik. Sehingga lewat kajian-kajian hermeneutik politik, gereja akan memahami tanggung jawabnya di tengah dunia yang modern dalam kerangka menjawab tantangan iman dalam konteks di mana gereja dan orang percaya itu berada. Semua itu harus 29 30 Ibid., 44-61. Hermeneutik Teologi berarti interpretasi atau penafsiran tentang Alkitab. 31 membutuhkan teologis proses yakni penafsiran atau interpretasi terhadap Alkitab. Karena pembacaan Alkitab saja tidaklah cukup menjawab persoalan yang ada, harus dilakukan penafsiran dari teks ke konteks serta aplikasinya. Masalahnya adalah bahwa banyak orang Kristen menganggap bahwa apa yang telah di tulis dalam teks Alkitab tidak bisa dirubah sama sekali. Itu harus diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu harus ada beberapa proses untuk dapat memahami teks Alkitab sehingga teks-teks tersebut dapat dimengerti dan dipahami isinya serta relefan dengan kehidupan yang terjadi. Bultman dan Solle sebagaimana dikutip oleh John B, Cobb Jr, menawarkan studi kritis yang menekankan konteks “sosio-historis”. Hal ini lebih menekankan kepada fungsi publik dari teks itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan kritik teks, sebab pemahaman dari ketiga tokoh tersebut bahwa tidak ada dokrin yang tidak bisa dikritik, semuanya berada dalam proses. Dalam pemahaman seperti itu kita dapat melihat seluruh kehidupan iman berada dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk masa depan. Tidak ada bagian dari kehidupan itu sendiri yang kebal terhadap perubahan. Beberapa bagian dari kehidupan ini mungkin tidak berubah sementara yang lain berubah dengan drastis, dan tidak ada takdir yang menentukan apa yang akan berubah dan berapa banyak perubahannya. Persoalannya adalah bukan apakah akan ada perubahan? Tetapi apakah perubahan itu merupakan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menjawab tantangan dan persoalan baru. Dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan di atas, para ahli mengatakan bahwa sudah saatnya gereja harus merubah para digma dalam mengahadapi dunia yang terus berubah. Solle mengambil contoh tentang bagaiman Yesus menghadapai dan mengatasi realitas sosial pada saat itu. Tidak ada sesuatu yang 32 mutlak, bagaimana kita menghadapi sistem yang menindas, dan tidak adil. Yesus mengadakan trasformasi teologis terhadap struktur sosial, dalam kerangka Ia berpikir dan bertindak. Cara bagaimana Yesus berpikir dan bertindak secara de facto membuka dan mengubah struktur sosial di mana Ia berada. Jadi melalui pemahaman ini yang mau dikatakan bahwa orang Kristen harus terlibat dalam meluruskan kesalahan-kesalahan sosial yang menurunkan derajat kemanusiaan. Kalau pemahaman kita berakar dari Alkitab maka kita juga harus mengikuti apa yang Yesus lakukan yaitu keprihatinannya kepada orang yang miskin dan tertindas. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bukan apakah Yesus seorang revolusioner? Tetapi bagaimana Ia berdiri dan melawan kekerasan, ketidak adilan dan diskriminasi. Yang terpenting disini adalah bukan perkataan tetapi bagaimana perbuatan dan tindakan. Semuanya ini terjadi dalam konteks dan perjalan sejarah. Oleh karena itu kita harus memahami secara sosial historis. Berdasarkan prespektif ini kita tidak akan meremehkan pentingnya penafsiran kitab suci, tetapi melalui hermeneutik kitab suci, kita dapat memahami dan mengerti bahwa ada bagian-bagian yang berbeda dari Alkitab yang di tulis dengan kepentingan-kepentingan dan maksud tertentu. Yesus, Paulus dan Yohanes serta para nabi lain yang terdapat dalam Perjanjian Lama maupun Baru mempunyai perjalanan sejarah tersendiri dalam konteks budaya dan masyarakat tertentu dengan problem sosial dan masalah tersendiri. Oleh karena itu tugas teologi bukan hanya bisa menafsirkan teks yang tertulis, tetapi harus juga dapat menemukan teks yang relevan dalam waktu dan tempat yang berbeda serta dapat menjawab problem dan masalah yang timbul dalam masyarakat, sesuai tantangan saman.31 b). Pendekatan Memori dan Narasi. 31 Ibid., 51. 33 H.Richard Niebuhr mengembangkan pendekatan terhadap pengakuan beberapa cerita sebagai cara menerima dan memahami pluralisme. Ia menunjukan bahwa tidak gampang dua masyarakat hidup bersama dan saling menerima satu sama lain. Misalnya Protestan dan Katolik dapat tumbuh dan hidup bersama dengan benar apabila mereka memiliki pengalaman hidup yang sama dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Konsili Trent harus menjadi bagian dari sejarah Protestan, dan Luther dan Anababtis harus menjadi bagian dari Katolik.32 Jika demikian maka apapun yang terjadi dalam persoalan kelembagaan mereka tetap mempunyai pengalaman yang sama tentang kekristenan secara umum. Menurut Metz yang dikutip oleh John Cobb, Jr bahwa hanya dengan proses sejarah semua orang dapat menemukan makna kehidupan. Semua orang mempunyai arti dan makna pengalaman hidup. Menurut Metz masalah utama yang ada pada orang Kristen ialah bukan pada dokrin dan ajaran tetapi pada tindakan terhadap komitmen kesetiaan. Ia lebih menekankan kepada tindakan praksis. Bagaimana kita dapat meniru Kristus dalam sikap dan tindakan serta perbuatan. Kristus yang menderita, mati dan bangkit semuanya terjadi dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Manusia menjadi pusat karya dan penyelamatan Allah. Semua orang dipanggil untuk menjadi subyek dalam hadirat Allah. Model praksis atau tindakan dilihat lebih baik dalam hubungan interaksi dengan masyarakat. Kita punya pengalaman yang berbeda, teori yang berbeda, pandangan dan makna yang berbeda. Melalui semuanya itu dapat menjadi kesempatan yang berharga untuk bertumbuh dalam kebenaran. Pertumbuhan dalam kebenaran tidak bisa merubah keyakinan yang lama atau menambahkan keyakinan yang baru, tetapi semuanya itu dapat terjadi apabila ada 32 Ibid., 54. 34 kompromi atau kesepakatan bersama. Pertumbuhan terjadi ketika keyakinan yang bertentangan di ubah oleh pikiran kresatif ke dalam apa yang disebut Whitehead kontras. Artinya, integritas dan kekuatan yang berbeda di pertahankan pada hubungan yang saling menguntungkan. Tapi pemahaman atau perspektif baru dapat dicapai apabila kebenaran dari masing-masing dapat direalisasikan bersama dalam keterbatasan masing-masing. Dalam kaitan ini masing-masing kemudian diubah oleh hubungan baru satu sama lain tersebut, dan keseluruhan pengalaman itu akhirnya menjadi luas dan diperkaya oleh satu dengan yang lain demi mencapai tujuan dan kepentingan bersama. 2.4. Ruang Lingkup Teologia Politik 2.4.1. Teologia Politik adalah Sebuah Koreksi Kritis. Teologi Politik adalah sebuah koreksi kritis atas tendensi untuk membatasi teologi pada wilayah pribadi dan personal, seperti dalam bentuk-bentuk transendental, eksistensial dan personalis. Ada kecenderungan untuk mereduksi “inti” warta Kristen dan praksis iman pada keputusan individu yang terpisah dari dunia, suatu rekasi terhadap separasi antara agama dam masyarakat. Disini Teologi Politik ikut campur, bukan dalam arti suatu identitas yang berbeda dari agama dan masyarakat, melainkan suatu usaha sengaja untuk membangun relasi agama dan masyarakat. Dalam usaha ini, Teologi Politik bertujuan “nationalization” sambil memperhatikan konsep teologis, bahasa pewartaan dan spiritualitas. Teologi ini berupaya mengatasi esoterisme yang berlebikan berkenaan dengan diskursus mengenai Allah, oposisi yang sulit didamaikan antara kehidupan rohani pribadi dan kebebasan sosial, yang dengan jelas memperluas jurang antara teologi dan pewartaan serta apa yang dalam kenyataan dihayati orang Kristen. 2.4.2. Teologia Politik Sebagai Warta Eskatologis Kristen. 35 Teologi Politik merupakan usaha memformulasikan warta eskatologis Kristen dalam kondisi masyarakat dewasa ini, seraya memperhitungkan perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan publik. Dengan kata lain teologi politik merupakan usaha “keluar dari” hermeneutika yang semata-mata “pasif” dan “buta” terhadap konteks masyarakat dewasa ini. Masyarakat dipandang sebagai sasaran sekunder aktivitas Krsiten. Dalam teologi politik masyarakat pertama-tama diyakini sebagai medium hakiki bagi penemuan kebenaran teologis dan pewartaan Kristen pada umumnya.33 Dengan demikian “Teologi Politik” bukan semata-mata suatu jenis “teologi tarapan”. Ia juga tak dapat diidentikan begitu saja dengan “etika politik” atau “teologi sosial”. Teologi politik mengklem menjadi unsur dasariah dalam keseluruhan struktur pemikiran teologis-kritis, terdorong oleh suatu paham baru tentang relasi antara teori dan praktek, dengan itu maka semua teologi harus menjadi “praksis” dari dirinya sendiri. Jadi teologi politik berorientasi pada aksi. Tidakan dan sikap gereja terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakat dalam menyikapim isu-isu politik. 3. Peranan dan Fungsi Gereja dalam Politik Sejak awal bangsa Indonesia menyadari, bahwa keberadaannya dimungkinkan oleh campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga dari Pembukaan UUD 1945 menyatakan, bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemerdekaan yang diproklamasikan oleh bangsa Indonesia itu disadari sebagai terjadi atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut John Titaley, ini adalah pernyataan religiusitas karena dalam kenyataan kemerdekaan itu diperjuangkan oleh bangsa 33 A.Eddy Kristiyanto, Teologi Politik, (Jakarta: Yayasan Bumi Karsa, 2003), 2-3. 36 Indonesia dengan korban jiwa. Dengan mengatakan hal yang demikian, bangsa Indonesia mau menunjukan rasa keagamaan dirinya, bahwa selain perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukannya, apa yang dicapainya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari adanya campur tangan Tuhan yang diyakini itu.34 Gereja sebagai warga masyarakat Indonesia yang ikut berjuang mempertahankan dan merebut kemerdekaan, tidak akan menyaia-nyiakan arti kemerdekaan itu, tetapi harus berperan aktif dalam menciptakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi yang dialami bangsa kita seharusnya dilihat sebagai suatu loncatan baru menuju kepada Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Pertanyaannya bagaimana gereja menunjukan perannya di tengah situasi bangsa yang sedang bergejolak karena arus reformasi yang begitu deras mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara? Albert Patty35 menjelaskan ada [4] empat, peran utama agama (gereja) dalam situasi politik di Indonesia. 1. Agama (gereja) berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Pendidikan politik itu berguna agar rakyat mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Berpartisipasi secara aktif berarti memiliki kemampuan untuk bersikap kritis baik terhadap pemerintah, terhadap sikap keberagaman maupun terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Berpartisipasi secara aktif juga berarti memiliki kemampuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap fungsi negara, terhadap kecenderungan demonisme agama yang mempersetankan kemanusiaan diri sendiri maupun kemanusiaan sesama yang berbeda. Berpartisipasi secara aktif berarti memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi terhadap 34 John Titaley, Religiusitas Di Alinea Tiga (Salatiga: Satya Wacana University 2013), 50. Albertus Patty, Kristen dan Situasi Politik Indonesia Kontemporer, (Editor: Einar M.Sitompul, 2004), 19-20. 35 37 negara, sikap keberagamaannya dan terhadap berbagai kondisi sosial yang berlenggu dan menderitakan rakyat. 2. Agama (gereja) berperan dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin politik masa depan yang memiliki intelektualitas tinggi, berwawasan luas, memiliki integritas dan spiritualitas yang tangguh. Pemimpin yang dibutuhkan pada masa sekarang dan di masa depan adalah mereka yang bisa mengubah kultur konflik dan kekerasan menjadi kultur persaudaraan. Pemimpin yang bangsa ini butuhkan adalah pemimpin yang mampu mengtransenden dirinya dari ikatan-ikatan primordialisme baik agama maupun suku bangsa. Persoalan kita sekarang adalah bahwa kita memiliki terlalu banyak pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan diri maupun kepentingan kelompoknya saja. 3. Agama (gereja) berperan dalam meletakan landasan etik dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan berpolitik bangsa. Landasan etik dalam kehidupan sosial mengatur relasi horisontal yang menghargai kemajemukan bangsa. Dalam konteks ini agen itu sendiri memainkan peranan penting dalam mempererat relasi para aktor demokrasi baik yang berada di tengah masyarakat maupun para elit. Dalam konteks ini agama justru harus belajar dari rakyat. Di tengah situasi konflik, rakyat telah berhasil menciptakan suatu kultur akternatif yaitu kultur persaudaraan. 4. Agama (gereja) bisa berperan dalam tataran spiritual. Yang dimaksud tataran spiritual adalah kemampuan mentransenden diri. Transisi demokrasi hanya bisa berhasil bila kita berhasil mentransenden diri kita, dan sesama kita melampawi mentalitas korban.Transisi demokrasi bisa berhasil bila “korban-korban” saling bekerja dan saling menyembuhkan. 38 Dengan demikian maka apabila kekristenan hanya memperhatikan kesalehan pribadinya sendiri tanpa peduli terhadap perubahan yang terjadi maka, tindakannya itu bisa menjadi bumerang untuk membahayakan dirinya. Reformasi yang terjadi di Indonesia karena rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Dan gereja merasa nyaman dengan keadaan demikian tanpa ada tindakan kritis dan koreksi terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru. Ada anggapan bahwa lebih baik kita hidup dalam pemerintahan orde baru dengan kepemimpinan Soeharto dari gereja akan berhadapan dengan pemikian Islam yang fundamental dan radikal. Untuk menyikapi masalah ini ada tiga sikap politik orang Kristen antara lain:36 Pertama, mereka yang apolitik, yang menganggap politik sebagai urusan duniawi yang kotor yang tidak perlu dicampuri gereja yang dianggap sebagai lembaga yang mengurusi sorga saja. Bagi mereka doa dan ibadah akan menyelesaikan segala sesuatu. (contoh: aliran pietisme) Kedua, adalah kelompok yang ingin merebut kekuasaan politik (paling sedikit mempunyai kekuatan signifikan dalam struktur pemerintahan) agar dapat mementukan jalannya negeri ini. (Contoh: PDS). Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa orang Kristen di Indonesia terpanggil sebagai garam dan terang dunia yang melalui iman Kristianinya dapat melakukan transformasi politik secara positif, kritis, kreatif, dan realistis. (Contoh: PGI). 4. Kesimpulan : 1. Wogaman membagi hubungan gereja dan negara menjadi empat model: a).Teokrasi. b).Erasionisme. c).“Pemisahan” secara Damai. d). Pemisahan yang tidak bersahabat yang mengakibatkan Permusuhan. 36 Richard Daulay, Kekristenan Dan Politik, (Jakarta: Waskita Publishing, 2013), 15-16. 39 2. Teologi politik adalah teologi publik yang mengoreksi secara kritis dominasi negara dan struktur masyarakat yang menindas. 3. Inti teologi politik adalah kritik terhadap gereja, teologi dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. 4. Teologia Politik mendasari pemikirannya kepada teologia proses, dengan pemahaman bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak terjadi dalam dunia ini, semuanya melewati proses menuju kepada suatu tujuan yang dikehendaki Allah. Dan gereja sebagai tubuh Kristus harus dapat menjawab tantangan dan pergumulannya sesuai dengan konteks dimana gereja itu berada. 5. Ketidakadilan, diskriminasi, kehancuran alam semesta, disebabkan karena egoisme manuisa dan struktur masyarakat yang tidak memihak kepada kaum miskin dan minoritas. 6. Keselamatan yang diperjuangkan bukan keselamatan “pribadi” tetapi keselatan seluruh alam ciptaan. 40 41