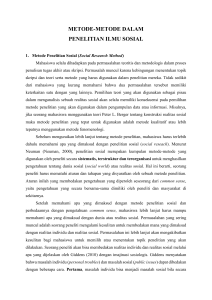PKS, PARTAI POLITIK YANG UNIK, JUGA MENARIK
advertisement
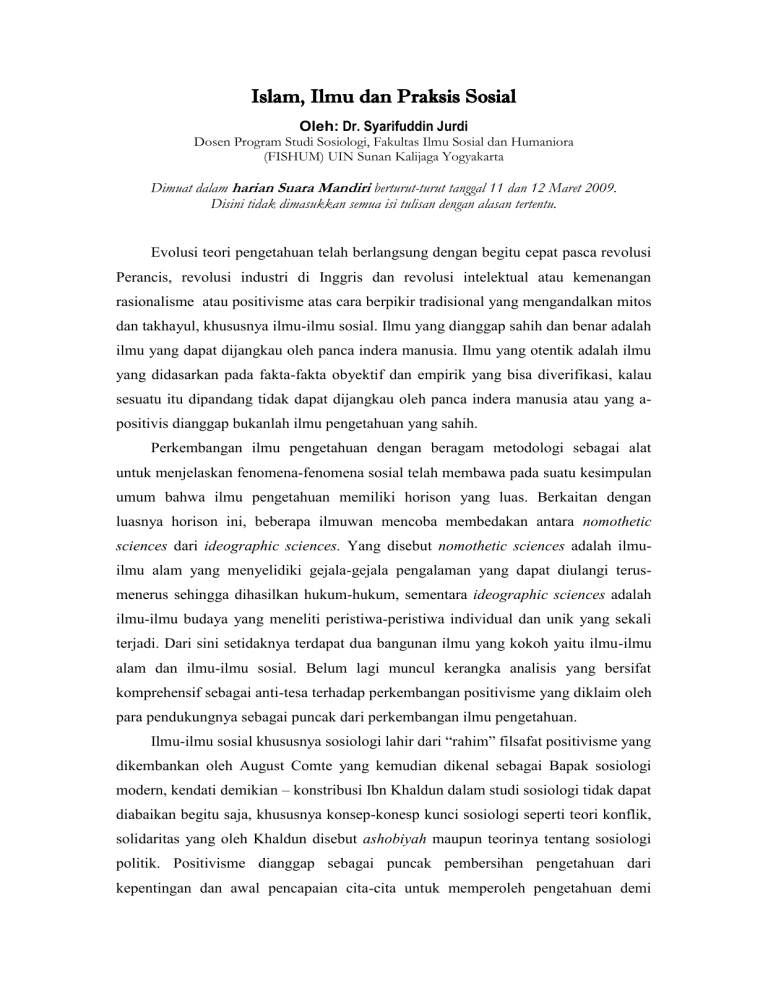
Islam, Ilmu dan Praksis Sosial Oleh: Dr. Syarifuddin Jurdi Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dimuat dalam harian Suara Mandiri berturut-turut tanggal 11 dan 12 Maret 2009. Disini tidak dimasukkan semua isi tulisan dengan alasan tertentu. Evolusi teori pengetahuan telah berlangsung dengan begitu cepat pasca revolusi Perancis, revolusi industri di Inggris dan revolusi intelektual atau kemenangan rasionalisme atau positivisme atas cara berpikir tradisional yang mengandalkan mitos dan takhayul, khususnya ilmu-ilmu sosial. Ilmu yang dianggap sahih dan benar adalah ilmu yang dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Ilmu yang otentik adalah ilmu yang didasarkan pada fakta-fakta obyektif dan empirik yang bisa diverifikasi, kalau sesuatu itu dipandang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia atau yang apositivis dianggap bukanlah ilmu pengetahuan yang sahih. Perkembangan ilmu pengetahuan dengan beragam metodologi sebagai alat untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial telah membawa pada suatu kesimpulan umum bahwa ilmu pengetahuan memiliki horison yang luas. Berkaitan dengan luasnya horison ini, beberapa ilmuwan mencoba membedakan antara nomothetic sciences dari ideographic sciences. Yang disebut nomothetic sciences adalah ilmuilmu alam yang menyelidiki gejala-gejala pengalaman yang dapat diulangi terusmenerus sehingga dihasilkan hukum-hukum, sementara ideographic sciences adalah ilmu-ilmu budaya yang meneliti peristiwa-peristiwa individual dan unik yang sekali terjadi. Dari sini setidaknya terdapat dua bangunan ilmu yang kokoh yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Belum lagi muncul kerangka analisis yang bersifat komprehensif sebagai anti-tesa terhadap perkembangan positivisme yang diklaim oleh para pendukungnya sebagai puncak dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi lahir dari “rahim” filsafat positivisme yang dikembankan oleh August Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak sosiologi modern, kendati demikian – konstribusi Ibn Khaldun dalam studi sosiologi tidak dapat diabaikan begitu saja, khususnya konsep-konesp kunci sosiologi seperti teori konflik, solidaritas yang oleh Khaldun disebut ashobiyah maupun teorinya tentang sosiologi politik. Positivisme dianggap sebagai puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari praxis hidup manusia. Positivisme menganggap pengatahuan mengenai fakta obyektif sebagai pengetahuan yang murni dan otentik, walaupun begitu, dalam positivisme masih mengalir darah ontologis. Poatulat dasar kaum positivis meletakkan apa yang disebut pengetahuan ilmiah yang sahih harus bersumber dari bekerjanya rasio dalam memahami dan menjelaskan fakta-fakta empiris, artinya kaum positivis dengan tegas mengatakan bahwa pengetahuan murni dapat diperoleh melalui rasio manusia, dan corak berpikir yang mengatakan bahwa pengalaman empiris menjadi sumber dari pengetahuan yang sahih. Dengan mengikuti alur atau corak berpikir kaum positivis dalam menemukan suatu pengetahuan ilmiah yang bebas kepentingan sebenarnya mengandung makna bahwa semua pengetahuan yang melampaui fakta obyektif atau melampaui fakta inderawi bukanlah suatu pengetahuan yang murni, ini mengakhiri riwayat ontologi dan metafisika. August Comte menganggap bahwa sosiologi merupakan puncak dari kulminasi perkembangan berbagai disiplin ilmiah, puncak dari perkembangan positivisme sendiri. ***** Perkembangan ilmu pengetahuan dengan perangkat metodologi telah membuka ruang bagi beragamnya perspektif dalam memandang kehidupan sosial, khususnya perkembangan social science. Karena begitu beragamnya perspektif yang dapat dipergunakan, maka ilmu pengetahuan memiliki kepentingan sendiri seperti disebut oleh Jurgen Habermas dalam Human and Interest bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat netral, tetapi memiliki kepentingan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, ilmu pngetahuan dalam roh ontologisnya tetap memiliki kepentingan-kepentingan moral, praktis dan pragmatis. Ilmu pengetahuan akan tetap bermain pada ranah ontologis, epistemologi dan aksiologi, karena itu ilmu akan mengabdi untuk ilmu itu sendiri. Dalam paradigma ilmu sosial kritis atau mereka yang menjadi penganut aliran kritis memandang bahwa ilmu pengetahuan harus mampu merefleksikan diri agar dapat membebaskan manusia bila pengetahuan itu jatuh dan membeku pada salah kutub, entah transendental, entah empiris. Paradigma kritis yang diwakili oleh mazhab Frankfurt School menggabungkan dua entitas yang dianggap berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu transendensi dan yang empirik, yang positivis dan apositivis. Perkembangan pemikiran ini sebagai upaya untuk membersihkan pengetahuan dari kecendrungan positivistik yang dianggap oleh kaum moralis sebagai sesuatu yang a-historis dari proses kemunculan pengetahuan itu sendiri dan perkembangan peradaban manusia. Tugas ilmu adalah menjelaskan persoalan-persoalan empirik yang menjadi kenyataan hidup manusia sehari-hari yang terus mengalami perkembangan dan perubahan, tetapi juga mengembang tugas untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang sama – didalamnya mengandung nilai-nilai, normanorma dan hukum yang bersifat transendensi, dimana kekuatannya terletak pada yang adikodrati. Argumen kuatnya adalah rasio manusia terbatas dalam kapasitas dan kemampuannya untuk menangkap seluruh realitas eksistensi. Dalam soal ini kita dapat mengambil contoh dari kasus kaum Ad dan kaum Tsamud yang telah diberitakan oleh Allah melalui wahyunya, berita mengenai kehidupan manusia yang membangkang terhadap perintah Tuhan-Nya, mereka mendustakan adanya hari kiamat (Kadzabat tsamudu waadum bilqaari’ati), akibat kedustaan itu, kaum Ad dan Tsamud ditimpa angin selama tujuh malam delapan hari terus-menerus dan mereka semua mati bergelimpangan. Memahami peristiwa kemanusiaan yang diberitakan agama tersebut, dapat kita kembangkan menjadi suatu pengetahuan yang dapat dikonstruksi untuk memahami konteks yang sama pada masa kini dan masa datang, peristiwa-peristiwa seperti itu akan terus-menerus berulang hingga akhir zaman. Untuk itulah, Ilmu yang bersumber dari yang adikodrati itu dapat dipergunakan untuk memahami fenomena-fenomena alam dan fenomena sosial yang kita alami sehari-hari. ***** Dalam tradisi Islam, berkembang cara berpikir untuk membangun kerangka epistemologi Islam, bagaimana proses integrasi Islam dengan ilmu, mana yang lebih penting antara Islamisasi ilmu dengan meng-Ilmu-kan Islam? Pada sebagian ilmuwan Muslim ada yang lebih condong pada model Islamisasi ilmu seperti yang dilakukan oleh Osman Bakar (Classification of Knowledge in Islam, 1992) dan ilmuwan lain dengan gigih mengutamakan atau mengedepankan usaha meng-ilmu-kan Islam seperti yang dilakukan oleh Kuntowijoyo (Islam sebagai Ilmu, 2004). Saya sendiri tidak terlalu mempersoalkan apakah Islamisasi ilmu atau meng-ilmu-kan Islam yang lebih penting, dua istilah itu dapat dipergunakan secara bergantian, apakah kita berangkat dari konteks untuk memahami teks atau berangkat dari teks untuk memahami konteks, keduanya sama penting dan strategisnya bagi dunia Islam. Paradigma Islam berusaha menawarkan alternatif penjelasan tentang fenomena sosial yang terjadi dengan pendekatan yang bersifat integratif, memadukan antara yang empirik dan yang ghaib. Perkembangan pemikiran ini mengalami transformasi yang sangat dominan pada abad pertengahan, lalu mengalami “kevakuman” dalam dunia Islam setelah Barat bangkit dan menguasai peradaban dunia dengan berbagai perangkat teori dan metodologinya, belakangan sebagian kalangan Islam menggelorakan “Islamisasi ilmu” atau “meng-ilmu-kan Islam” dalam rangka memahami realitas sosial, tentu dengan bantuan teori dan metodologi Barat. Mari kita coba memahami sumber pengetahuan yang begitu banyak yang tersebar dalam sejumlah ayat dalam al-Qur’an, kita akan menemukan bahwa sistem pengetahuan yang bersumber dalam Islam mencerminkan pengetahuan itu bersifat positivis dan apositivis, untuk hal itu dapat dirujuk dalam Qur’an Surat al-Baqarah ayat 2-5. Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, Dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya,dan merekalah orang-orang yang beruntung (lihat Syarifuddin Jurdi [ed.al], Sosiologi Profetik, 2009). Dari ayat tersebut karakteristik orang yang siap mendapat petunjuk merupakan simbol dari keilmuan yang bisa memberi arah transformasi sosial, yaitu bersifat: pertama, apositivistik (Beriman kepada yang ghaib); kedua, transenden (Mendirikan shalat); ketiga, mengusung Kolektivisme (Menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka); keempat, spiritualisme-Dialetik (Beriman kepada Kitab [al-Qur'an] yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya [kehidupan] akhirat) (Ibid.). Wallahu a’lam bi shawab



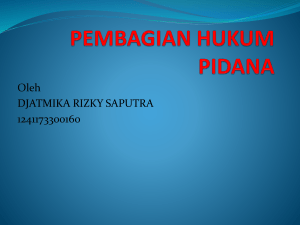

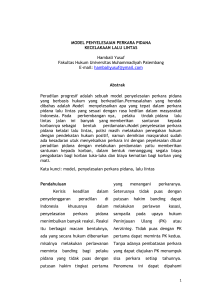

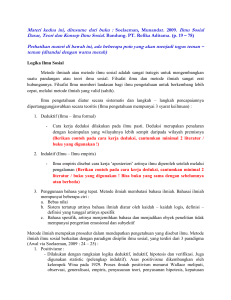

![Modul Metode Penelitian Kualitatif [TM2].](http://s1.studylibid.com/store/data/000151223_1-9caf017675d8ca6e4e27dd48466eb9ac-300x300.png)