Gaya Hidup dan Komoditi Ilusi
advertisement

MODUL PERKULIAHAN NEW MEDIA & SOCIETY Life Style dan Social Media Fakultas Program Studi Ilmu Komunikasi Broadcasting Tatap Muka 08 Abstract Kode MK Disusun Oleh 41021 Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Kompetensi Dalam dunia modern, gaya hidup Dengan memperoleh membantu individu mendefinisikan mahasiswa diharapkan materi ini, mengerti sikap, nilai, identitas serta posisi dan memahami tentang Life Style sosialnya Pengetahuan dalam masyarakat. dan Social Media. gaya hidup termuktahir ini tak lepas dari era globalisasi informasi yang mengacu pada eksistensi media baru. Gaya hidup. Life Style. Suatu istilah yang sudah marak kita dengar saat ini. Berbagai media mulai dari majalah hingga portal berita online menyajikan satu kolom spesial dengan frase—Life Style yang jika kita mengkliknya, maka mucul setumpuk gambar yang sedang ‘mengantri’ dilirik dalam bentuk fashion terbaru, potongan baju teranyar, model rambut masa kini, tempat ‘bergaul’ ala sosialita atau selebriti, serta pelbagai pilihan lainnya. Kurang lebih begitulah media khususnya jurnalis mengasosiasikan makna sebuah Life Style ke dalam bentuk-bentuk kegiatan konsumtif. David Chaney dalam Lifestyle menyebut gaya hidup sebagai ciri sebuah dunia modern. Namun apakah benar gaya hidup cukup dimaknai hanya sebatas pada tampilan-tampilan pada rubrik yang ditampilkan oleh media di atas? Dalam bahasan ini, kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan gaya hidup dan bentuk-bentuknya yang diakibatkan oleh new media saat ini. Namun sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu, kita perlu memahami definisi Life Style menurut pakar budaya. Gaya Hidup (Life Style): Pengertian dan BentukBentuknya Seperti yang telah disebut sebelumnya, Chaney mengungkapkan bahwa dalam tatanan masyarakat modern saat ini, gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern, atau juga yang biasa disebut modernitas. Siapa pun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Menurutnya, gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Gaya hidup membantu memahami apa yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya maupun orang lain. Gaya hidup (menurut Kotler, 2002:192) adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup juga menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu dalam kehidupannya, juga dapat dilihat dari aktivitas sehari-seharinya dan minat apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam pengertian yang lebih umun, Yasraf Amir Piliang, mendefinisikan gaya hidup sebagai karakteristik seseorang yang dapat diamati, yang menandai sistem nilai serta sikap ‘13 2 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id diri sendiri dan lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan pola penggunaan waktu, uang, ruang, dan objek yang berkaitan dengan semuanya (cara berpakaian, cara makan, cara berbicara, kebiasaan di rumah, pilihan teman, pilihan restoran, tata rambut, tata busana, dsb). Dengan demikian, gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas dari cara, tata, kebiasaan, pilihan serta objek-objek yang mendukungnya, yang pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Arti gaya hidup sendiri mengalami peningkatan yang dianggap berasal dari evaluasi kembali budaya material, jauh dari nilai uang yang dekat dengan objek dan ke arah sosial kulturalnya. Tak heran jika terjadi perubahan dalam masyarakat saat ini. Jika dahulu dengan status seseorang mencari uang, kini, bisa jadi seseorang justru mencari uang demi status. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gaya hidup membantu individu mendefinisikan sikap, nilai, identitas serta posisi sosialnya dalam masyarakat. Di tanah air, globalisasi industri media dari mancanegara dengan modal besar mulai masuk sejak awal 1990-an. Media membentuk opsi-opsi bagi masyarakat menyoal mode dan gaya hidup. Saat itu bermunculan beragam slogan—yang disebut Idi Subandi menawarkan fantasi hidup. Pada waktu yang sama, muncul pula gaya hidup alternatif yang seakan menjadi antitesis dari glamour fashion yang sudah tidak lagi malu-malu dipamerkan oleh kaum borjuis. Rupanya, gaya hidup tidak sesederhana seperti halnya potret kehidupan kelas menengah di kolom gaya hidup media populer. Gaya hidup bukan melulu monopoli orang berduit. Bukankah orang miskin sekalipun masih bisa mencomot model gaya hidup tertentu. Meskipun mungkin hanya bersandiwara, meniru-niru. Seperti halnya orang berduit juga bisa berlagak sok miskin. Bukan karena penganut ideologi hemat tapi lebih karena pilihan gaya (mengutip Johan Huizinga (1938), “Bukankah dalam pengertian ‘gaya’ itu sendiri sudah terkandung pengakuan tentang adanya suatu unsur permainan tertentu?”). Idi menambahkan, dalam masyarakat mutakhir seringkali soal cita rasa dan gaya hidup sudah tidak jelas lagi batas-batasnya. Gaya hidup kini bukan lagi monopoli suatu kelas, tapi sudah lintaskelas. Mana yang kelas atas/menengah/bawah sudah bercampur baur dan terkadang dipakai berganti-ganti. Gaya hidup yang ditawarkan lewat iklan, misalnya, menjadi lebih beraneka ragam dan cenderung mengambang bebas, sehingga ia tidak lagi menjadi milik eksklusif kelas tertentu dalam masyarakat. Ia menjadi citra netral yang mudah ditiru, dijiplak, dipakai sesuka hati oleh setiap orang. Di sinilah terlihat betapa tidak sederhananya istilah atau konsep gaya hidup. ‘13 3 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id Selanjutnya, Gaya hidup dipahami sebagai proyek refleksif dan penggunaan fasilitas konsumen secara sangat kreatif. Anthony Giddens menyebutkan bahwa dalam tatanan postradisional, diri (self) menjadi suatu proyek refleksif. Perlu keterbukaan yang terbatas terhadap makna-makna gaya hidup dalam konteks apa pun. “...makna praktik gaya hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh ‘kekuatan-kekuatan dalam masyarakat’ yang lebih luas (dari jenis apa pun). Ia menunjukkan bahwa dalam negosiasi praktis dari dunia kehidupan tertentu, makna dari cara menggunakan sumber daya simbolik konsumsi massa diubah menjadi objek-objek atau praktik-praktik yang kasat mata yang merupakan metafor bagi diri mereka sendiri.” Chaney menambahkan bahwa perkembangan gaya hidup dan perubahan struktural modernitas saling terhubung melalui reflektivitas institusional: “karena keterbukaan (openness) kehidupan sosial masa kini, pluralisasi konteks tindakan dan aneka ragam ‘otoritas’, pilihan gaya hidup semakin penting dalam penyusunan identitas diri dan aktivitas keseharian.” Maka penting untuk menyadari bahwa identitas diri adalah satu proyek yang diwujudkan oleh para individu dengan cara-cara pendirian mereka sendiri. Cara khusus yang dipilih seseorang untuk mengekspresikan diri, tak disangsikan merupakan bagian dari usahanya mencari gaya hidup pribadinya. Dalam perburuan akan gaya, kita senantiasa mencari “pahlawan-pahlawan” untuk ditokohkan dan ditiru. Dalam menyoroti gaya hidup, setidaknya ada dua pendekatan yang menonjol yaitu: 1) pendekatan ideologis (yang mengingatkan kita pada analisis sosial Marxisme). Gaya hidup dilandasi oleh satu ideologi tertentu yang menentukan bentuk dan arahnya. Cara berpakaian, gaya makan, jenis bacaan dikatakan merupakan ekspresi dari cara kelompok masyarakat mengaitkan hidup mereka dengan kondisi eksistensi mereka. Gaya hidup merefleksikan kesadaran kelas kelompok masyarakat tetentu, dan dengan demikian ia merupakan satu bentuk ideologi kelas. 2) pendekatan sosiokultural yang melihat gaya hidup sebagai satu bentuk pengungkapan makna sosial dan kultural. Setiap bentuk penggunaan waktu, ruang, dan objek mengandung di dalamnya aspek-aspek pertandaan dan semiotik yang mengungkapkan maknsa sosial dan kultural tertentu. Menurut para kulturalis, gaya visual merupakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup dan yang berperan besar dalam membentuk Life Style kini adalah iklan. Di era globalisasi ekonomi dan transformasi kapitalisme konsumsi kini, kita sedang kedapatan ratusan mall baru yang menjamur di kota-kota besar, industri kecantikan, industri kuliner, industri gosip, kawasan huni mewah, apartemen, real estate, gencarnya iklan barang-barang supermewah dan liburan wisata ke luar negeri, berdirinya sekolah-sekolah mahal (dengan label “plus”), kegandrungan terhadap merk asing, makanan serba instan ‘13 4 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id (fast food), telepon seluler, dan tentu saja serbuan gaya hidup lewat industri iklan dan televisi yang sudah sampai ke ruang-ruang kita yang paling pribadi, dan bahkan mungkin ke relung-relung jiwa kita yang paling dalam. Dalam menyoroti gaya hidup di Indonesia, khususnya yang berkembang sebagai akibat globalisasi ekonomi dan informasi sejak dua dasawarsa ini, setidaknya ada empat pengaruh ideologi yang melandasi gaya-gaya hidup, yaitu: 1) gerakan etnik dan subkultur, 2) gerakan pecinta lingkungan dan ekologis, 3) gerakan spiritual dan keagamaan, dan 4) kegiatan ekonomi kapitalisme global sebagai satu bentuk ideologi. Menurut Chaney (dalam Idi Subandy, 1997) ada beberapa bentuk gaya hidup antara lain, pertama, Industri Gaya Hidup. Di dalam abad gaya hidup, penampilan adalah segalanya. Penampilan diri mengalami estetisasi, “estetisasi kehidupan sehari-sehari.” Dan, bahkan tubuh/diri (body/self) pun justru mengalami estetisasi tubuh. Tubuh/diri dan kehidupan sehari-hari pun menjadi sebuah proyek, benih penyemaian gaya hidup. “Kamu bergaya maka kamu ada!” dirasa menjadi jargon yang cukup representatif untuk melukiskan kegandrungan manusia modern akan gaya. Maka tak heran jika sebagian besar orang menganggap industri penampilan sebagai sinonim dari industri gaya hidup. “Penampakan luar” menjadi salah satu situs yang penting bagi gaya hidup. Hal-hal permukaan akan menjadi lebih penting daripada substansi. Gaya dan desain lebih penting daripada fungsi. Gaya menggantikan substansi. Kulit akan mengalahkan isi. Pemasaran, penampakan luar, penampilan, hal-hal yang bersifat permukaan atau kulit akan menjadi bisnis besar gaya hidup. Chaney juga mengatakan bahwa pad akhir modernitas semua yang kita miliki akan menjadi budaya tontonan ( a culture of spectacle). Semua orang ingin menjadi penonton dan sekaligus ditonton. Ingin melihat tapi sekaligus juga dilihat. Di sinilah gaya mulai menjadi modus keberadaan manusia modern: Kamu bergaya maka kamu ada! Kalu kamu tidak bergaya, siap-siaplah untuk dianggap “tidak ada”: diremehkan, diabaikan, atau mungkin dilecehkan. Itulah sebabnya mungkin orang sekarang perlu bersolek atau berias diri. Jadilah kita menjadi “masyarakat pesolek” (dandy society). Kedua, Iklan Gaya Hidup. Dalam masyarakat mutakhir, berbagai perusahaan (korporasi), para politisi, individu-individu semuanya terobsesi dengan citra. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, yang berperan besar dalam membentuk budaya citra (image culture) dan budaya cita rasa (taste culture) adalah gempuran iklan yang menawarkan gaya visual yang kadang-kadang mempesona dan memabukkan. Iklan merepresentasikan gaya hidup dengan menanamkan secara halus (subtle) arti pentingnya ‘13 5 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id citra diri untuk tampil di muka publik. Iklan juga perlahan tapi pasti mempengaruhi pilihan cita rasa yang kita buat. Kritikus media terkemuka, Marshal McLuhan, menyebut iklan sebagai karya seni terbesar abad ke-20. Iklan sering dianggap sebagai penentu kecenderungan, tren, mode, dan bahkan dianggap sebagai pembentuk kesadaran manusia modern. Tentu saja tidak semua orang atau konsumen bisa terpengaruh begitu saja oleh bujuk rayu iklan. Tidak setiap orang akan membeli setiap barang yang diiklankan dengan menawan sekalipun. Ketiga, Public Relations dan Jurnalisme Gaya Hidup. Pemikiran dalam dunia promosi sampai pada kesimpulan bahwa dalam budaya berbasis-selebriti (celebrity based-culture), para selebriti membantu dalam pembentukan identitas dari para konsumen kontemporer. Dalam budaya konsumen, identitas menjadi suatu sandaran “aksesori fashion”. Wajah generasi baru yang dikenal sebagai anak-anak E-Generation, menjadi seperti sekarang ini dianggap terbentuk melalui identitas yang diilhami selebriti (celebrity-inspired identity)—cara mereka berselancar di dunia maya (Internet), cara mereka gonta-ganti busana untuk jalanjalan. Ini berarti bahwa selebriti dan citra mereka digunakan momen demi momen untuk membantu konsumen dalam parade identitas. Sedangkan Yasraf melihat setidaknya ada empat gaya hidup, antara lain: 1) Gaya hidup etnik dan subkultur. Paruh kedua abad ke-20 ditandai oleh pergerakan-pergerakan politik, sosial, dan kultural ke arah heterogenitas lokal, regional, dan isolasionisme. Ketersediaan informasi, hiburan, makanan, bahasa, dan gaya hidup dari berbagai suku, kebudayaan, dan kebangsaan semakin terbuka untuk setiap individu, memberikan lebih banyak kemungkinan bagi heterogenisasi diri. Seseorang dapat menikmati McDonald sambil menonton Wayang Golek di sebuah hotel, lalu pulang ke rumah sederhana menggunakan taksi President. 2) Gaya hidup konsumerisme. Konsumsi tidak lagi diartikan semata sebagai satu lalu lintas kebudayaan benda, akan tetapi menjadi sebuah panggung sosial, yang di dalamnya makna-makna sosial diperebutkan, yang di dalamnya terjadi perang posisi di antara anggota-anggota masyarakat yang terlibat. Relasi sosial sehari-hari tidak lagi berhenti sebagai relasi di antara sesama manusia, melainkan sebagai fungsi dari pemilikan dan penggunaan benda-benda dan gaya hidup. Jam tangan emas, pulpen, dasi, ikat pinggang, mobil luks, dan rumah mewah, semuanya merupakan kata-kata yang bercerita mengenai gaya hidup dan posisi kelas menengah baru. ‘13 6 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id Kecenderungan ini menimbulkan semacam fetisisme komoditi, yaitu simbol, yang sebenarnya tidak merupakan substansi dari komoditi, yang dianggap suatu kebenaran. Kecenderungan ini menciptakan istilah-istalah baru seperti hyper commodity dan ekstrimisme pasar, seperti Mall yang berkembang menjadi pusat pembentukan gaya hidup. 3) Gaya hidup spiritualisme dan neospiritualisme. Kini tengah terjadi perkembangan masyarakat kontemporer Indonesia yang ditandai meningkatnya tempo kehidupan sosial akibat globalisasi ekonomi dan informasi. Dalam kondisi ini, fungsi adat, tabu, ideolgi, bahkan agama sebagai perekat sosial mulai digeser oleh fungsi-fungsi simbol status, prestise, dan citraan yang disampaikan berbagai media massa. Sehingga tercipta satu kesan seolah-olah masyarakat dan kebudayaan kontemporer telah memudar perekat moral dan spiritual. Akan tetapi ada beberapa kecenderungan gaya hidup lain yang hidup di masyarakat, yang arahnya justru bersebrangan dengan ideologi konsumerisme, misalnya berkembangnya kelompok-kelompok keagamaan (seperti Darul Arqam). Kelompok ini menjadikan kepercayaan keagamaan sebagai landasan kehidupan sosial. 4) Gaya hidup hijau. Dampak pemanasan global sebagai akibat dari produksi dan konsumsi yang melampaui kemampuan sumberdaya alam yang ada, mengharuskan dilakukannya perubahan-perubahan pada setiap tingkat masyarakat dan kebudayaan. Maka muncul tuntutan untuk menciptakan bentuk kehidupan dan gaya hidup yang lebih hijau, tidak berarti harus kembali ke alam, dan juga tidak berarti menentang sains dan teknologi. Ada tuntutan lingkungan global untuk mengembangkan semacam eco-estate atau kampung hijau alternatif. Oleh karena itu peran media massa juga perlu diarahkan untuk mencapai masyarakat yang berkeseimbangan. Media massa harus digunakan dalam rangka membangun kesadaran baru ke arah etika, moral, lingkungan, dan spiritual yang berkeseimbangan bukan lagi terprogam untuk tujuan komersial, sebagai bagian dari komoditi, yang mengikuti logika pasar, logika hasrat, dan logika libido. Semakin banyak gaya hidup yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi, informasi, dan kebidayaan di satu pihak telah membuka cakrawala yang tak terbatas dan kreatif bagi setiap individu untuk menentukan pilihan dan seleranya; namun di pihak lain telah menggiring masyarakat kontemporer kita ke arah krisis identitas, krisis kebudayaan, bahkan ‘13 7 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id krisis kepercayaan. Semua ini adalah beberapa alternatif pilihan sekaligus tantangan kebudayaan dalam menjalani abad ke-21 ini. Gaya Hidup, Hasrat, dan Masyarakat Konsumer Dalam wacana gaya hidup, sulit untuk memisahkan frase tersebut dengan kata konsumerisme yang merupakan produk dari hasrat. Maka, dalam tulisan ini, kita perlu menggambarkan relasi antar ketiganya atau bahkan menilik lebih jauh mengenai definisi (atau mungkin esensi) dari ketiga hal di atas. Berangkat dari penjabaran mengenai pengertian dan bentuk-bentuk gaya hidup sebelumnya, kita akan melaju pada pemahaman mengapa manusia berpotensi mengalami fenomena kebaruan (bentuk-bentuk gaya hidup) dalam era posmodern saat ini. Menurut Yasraf Amir Piliang, manusia mempunyai hasrat (desire) yang memerlukan sesuatu di luar dirinya sebagai sumber pemenuhan hasrat dikarenakan adanya rasa kurang (lack), dan ia tidak dapat memenuhi sendiri hasrat tersebut. Upaya pemenuhan itulah yang menggerakkan. Hal ini tampaknya bisa menjadi alasan mengapa manusia selalu mendapati dirinya pada sesuatu yang baru, berubah. Di dalam psikiatri, hasrat dipandang sebagai lawan dari ego. Kesenjangan sosial dan berbagai bentuk muslihat yang berujung pada eksploitasi dapat berhasil karena bekerjanya hasrat. Hasrat kemudian dianggap sesuatu yang harus dikurung, dibatasi, dan dipasung demi terwujudnya impian utopis manusia. Konsumerisme sendiri merupakan suatu pola pikir dan tindakan di mana orang membeli barang bukan karena ia membutuhkan barang itu, melainkan karena tindakan membeli itu sendiri memberikan kepuasan kepadanya. Istilah Konsumerisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai paham/gaya hidup yang beranggapan barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, gaya hidup tidak hemat, dsb. Wiliamson berpandangan positif terhadap konsumerisme, yang melihatnya sebagai media representasi kekuasaan, khususnya dalam mengontrol objek-objek. Kita mengkkonsumsi objek-objek bukan sekadar menghabiskan nilai guna dan nilai utilitasnya, akan tetapi juga untuk mengkomunikasikan makna-makna tertentu. Kita menggunakan objek-objek untuk mengkomunikasikan/merepresentasikan/menandai/mengirim pesan. Kita menggunakan perhiasan mahal untuk menandai kekayaan dan status sosial kita. Dalam relasi semcam ini, kita mengontrol objek dalam proses pertandaan dan komunikasi sosial. Akan tetapi benarkah kita mengontrol objek dalam tindakan konsumsi? Baudrillard melihat ‘13 8 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id kekuasaan ini sebagai bersifat semu belaka. Kita tidak lagi mengontrol objek, akan tetapi dikontrol oleh objek-objek ini. kita “....hidup sesuai dengan iramanya, sesuai dengan siklus perputarannya yang tak putus-putusnya.” Konsumsi terkait erat dengan pembentukan diri yang menekankan keunikan pada makna. Sedangkan Charles Revlon, pendiri Revlon, seperti dikutip The Jakarta Post mengatakan bahwa “di dalam perusahaan kami membuat kosmetik, di dalam toko kami menjual harapan.” Harapan yang ditanamkan melalui imaji ideal sebagai konsumen, yang tidak pernah dapat dipuaskan, itulah salah satu unsur dalam konsumerisme. Dengan begitu, konsumerisme telah menjadi cara hidup bagi masyarakat kontemporer. Bagi masyarakat tertentu yang memiliki budaya konsumsi berlebihan (conspicuous consumption), seperti kaum selebriti, jet set, remaja menengah ke atas perkotaan, yang sudah mencapai tahap belanja gaya hidup (life style-shopping), apa yang dicari bukan lagi makna-makna ideologis melalui tindakan sublasi, melainkan kegairahan ekstasi dalam pergantian objek-objek konsumsi; yang dicari dalam komunikasi bukan pesan-pesan dan informasi, melainkan kegairahan dalam berkomunikasi itu sendiri, dalam bermain dengan tanda, citraan, dan medianya. Di dalam konsumsi yang dilandasi oleh nilai tanda dan citraan ketimbang nilai utilitas, logika yang mendasarinya bukan lagi logika kebutuhan (need) melainkan logika hasrat (desire). Di Indonesia sendiri, kecenderungan umum ke arah pembentukan simbol sosial dan identitas kultural melalui gaya pakaian, mobil, atau produk lainnya sebagai komunikasi simbolik dan makna-makna sosial telah mewabahi masyarakat Indonesia lima tahun terakhir ini. Yasraf mengatakan bahwa manusia masa kini tidak lagi dikelilingi oleh manusia-manusia lain seperti pada masa lalu, melainkan oleh objek-objek. Relasi sosial mereka tidak lagi berhenti sebagai relasi di antara sesama manusia, melainkan sebagai fungsi dari kepemilikan dan penggunaan benda-benda dan gaya hidup. Kecenderungan ini menimbulkan semacam fetisisme komoditi, yaitu simbol, yang sebenarnya tidak merupakan substansi dari komoditi, dianggap sebagai satu kebenaran. Pada awal abad ke-20, kapitalisme konsumsi benar-benar telah telah ikut berperan penting dalam memoles gaya hidup dan membentuk masyarakat konsumen. Konsumsi sebagai bentuk gaya hidup. Konsumsi mengekspresikan posisi sosial dan identitas kultural seseorang di dalam masyarakat. Jika sebelumnya gaya hidup ditampilkan lewat penampilan, berikut ini kita juga akan melihat gaya hidup yang dimunculkan lewat wujud kebudayaan lain, salah satunya yaitu aktivitas makan (culinary culture). Yasraf menambahkan, aktivitas makan tidak hanya melibatkan unsur budaya fisik (material culture), yaitu makanan, ‘13 9 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id peralatan makan, dan tempat makan, akan tetapi unsur-unsur budaya nonfisik (nonmaterial culture), yaitu: 1) selera (taste), tidak saja selera terhadap makanan itu sendiri secara psikologis (selera makan), tetapi selera dalam dalam pengertian sosialnya, yaitu klasifikasi dan hierarki sosial selera; 2) makna, yaitu bagaimana makanan, tata cara makan dan teknologi makanan mengandung berbagai makna di baliknya; 3) nilai (cultural value), yaitu bagaimana makan dan aktivitas makan bermakna secara sosial, politik, ekonomi, sosial, kultural, dan spiritual. Gaya Hidup dan Komoditi Ilusi Seperti yang telah dijelaskan pada modul sebelumnya, bahwasanya kita telah sampai pada kondisi dimana masyarakat telah dijejali banyak media. Lebih jelas lagi, Yasraf menyebut era ini sebagai era yang melampai—hyper. Baudrillard melihat apa yang sebenarnya terjadi terhadap kencenderungan pada kondisi hyper, adalah berkembangnya wacana sosial-kebudayaan menuju apa yang disebut sebagai hipermodernitas (hypermodernity), yaitu kondisi ketika segala sesuatu bertumbuh lebih cepat, ketika tempo kehidupan menjadi semakin tinggi, ketika setiap wacana (ekonomi, seni, seksual) bertumbuh ke arah ekstrim, sebagai meningkat dan diumbarnya setiap potensi, sebagai logika proses ekstrimitas, dan percepatan proses kehancuran. Akan tetapi kini, di dalam ekonomi pasar bebas, energi kemajuan tersebut lebih banyak digunakan untuk menciptakan kebutuhan semu bagi konsumer, semata agar ekonomi (kapitalisme) dapat terus berputar, yang pada gilirannya menghasilkan kesejahteraan semu. Kecenderungan hyper juga terlihat pada fenomena perkembangan media. Perkembangan teknologi mutakhir (seperti televisi, komputer, multimedia, internet) telah memungkinkan diciptakannya satu rekayasa realitas, yaitu satu realitas yang tampak seperti nyata, padahal semuanya hanyalah simulasi image yang tercipta lewat teknologi elektronik. Di dalamnya antara realitas dan halusinasi atau antara kebenaran dan rekayasa kebenaran bercampur aduk di dalam media. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada perkembangan komoditi dan pasar dalam kapitalisme mutakhir menjelang abad ke-21. Di dalam kapitalisme mutakhir, komoditi tidak lagi berfungsi sekadar objek utilitas, akan tetapi telah berkembang menjadi virtualcommodity, yaitu komoditi yang menjadi ajang permainan semiotika, status, prestise, dan ‘13 10 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id sensualitas komunikasi pemasaran. Apa pun kini dijadikan komoditi, mulai gosip, skandal, tubuh, kebugaran, sampai kematian. Daftar Pustaka Piliang, Yasraf Amir. 2004. Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melalui Batas-Batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra Chaney, David. 2003. Life Style: Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: Jalasutra ‘13 11 New Media & Society Rahmadya Putra Nugraha, M.Si Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id
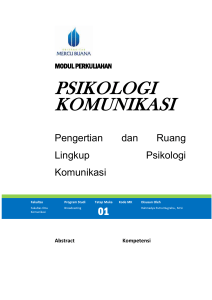
![Modul Psikologi Komunikasi [TM15]](http://s1.studylibid.com/store/data/000334434_1-9654ca616690d353b5a643859290004d-300x300.png)
![Modul Sosiologi Komunikasi [TM13]](http://s1.studylibid.com/store/data/000184546_1-2b81e1eb35bbbe7dd73629d7ab5d50ec-300x300.png)
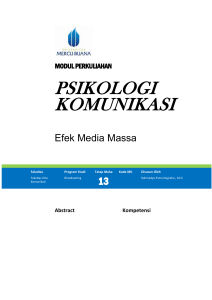
![Modul Psikologi Komunikasi [TM7]](http://s1.studylibid.com/store/data/000184456_1-d32b50ddff61f4446a8fb81ddfcca7b8-300x300.png)
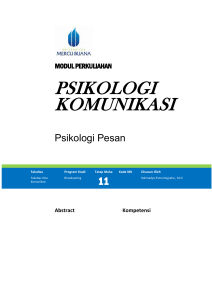
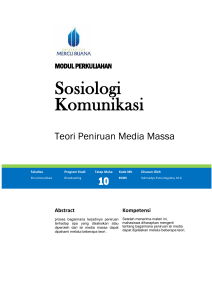
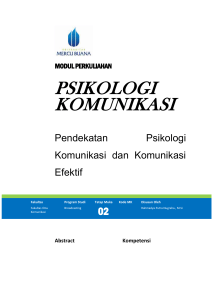
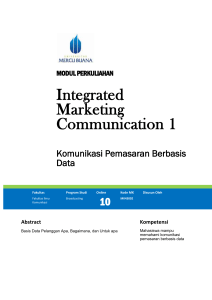
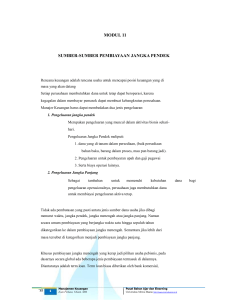
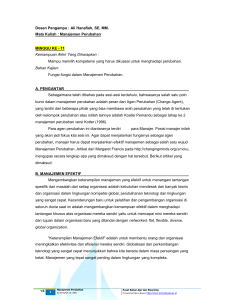
![Modul Riset Advertising dan Marcomm [TM10]](http://s1.studylibid.com/store/data/000142912_1-88be32367fda1f7012482a2ad163e17b-300x300.png)