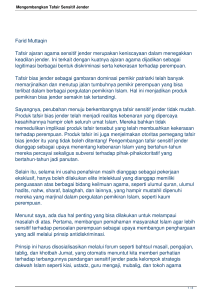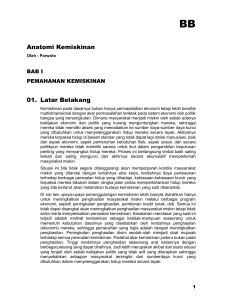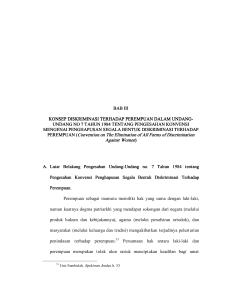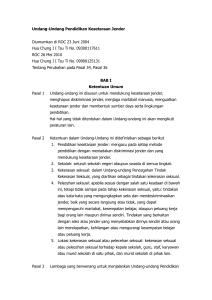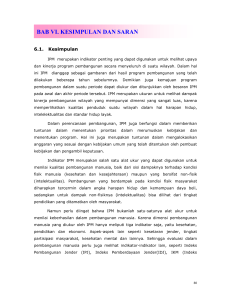BIAS JENDER DALAM BAHASA ARAB
advertisement

BIAS JENDER DALAM BAHASA ARAB Sebagai sebuah bagian dari bahasa-bahasa kuno dalam rumpun bahasa Semitik, bias jender dalam bahasa Arab sangatlah kental. Setiap kata dalam bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari jenis kelamin yang menjadi bagian kategorisnya: mudzakkar (maskulin) atau muannats (feminin). Persoalan tentang konstruksi jender dalam bahasa ini mengemuka ketika bahasa Arab menjadi bahasa induk yang dipakai di hampir semua sumber-sumber klasik dalam kajian keislaman. Dalam hal ini sumber utama hukum Islam: al-Qur’an dan Hadits, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW guna menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Arab ketika itu. Argumen teologis yang menjawab persoalan mengapa al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab dapat dicerna melalui QS. Ibrahim 14:4, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi... “ “Dan sekali-sekali Kami tidak mengutus salah seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya....” Akan tetapi, watak utama peradaban Arab yang lekat dengan budaya patriarakhis menjadikan beberapa konsep yang diusung oleh para mujtahid dalam agama Islam melalui penelaahan terhadap al-Qur’an dan Hadis yang menggunakan bahasa Arab, serta kreatifitas ijtihadi mereka dalam menggunakan sumber-sumber hukum Islam yang lain pada setiap masanya sebagian besar tidak bisa dilepaskan dari bias jender yang timbul dari upaya penafsiran dan istinbat hukum yang berlatar belakang budaya masyarakat Arab yang cenderung patriarkhis. Oleh karena itu, persoalan bias jender bukan saja menyangkut aspek utama secara lingusitik, di mana bahasa Arab sebagai bahasa induk kajian Islam memang bertumpu pada pemilahan jender; tetapi juga terkait dengan aspek penafsiran di mana konsep-konsep yang diturunkan dari al-Qur’an dan Hadis turut pula diwarnai oleh latar belakang budaya yang didominasi oleh peradaban partriarkhis yang bias sebagai akibatnya. Kenyataan ini membawa sebuah persoalan pelik dalam kajian Islam ketika pada hakikatnya semangat dan keberadaan pesan yang dibawa oleh Islam itu sendiri menjunjung tinggi asas kesetaraan jender, di mana semua manusia secara ontologis setara kedudukannya di sisi Allah SWT. Makalah ini akan membahas persoalan-persoalan apa sajakah yang membawa dampak pada terjadinya bias jender dalam bahasa Arab sebagai bahasa induk kajian Islam. Dalam hal ini, uraian akan dibagi dalam tiga kategori utama: bias jender dalam kosa kata (mufradat) bahasa Arab, struktur bahasa yang didominasi bentuk jender maskulin, dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ambigu yang berakibat timbulnya ketidaksetaraan jender dalam aspek penafsiran. Sebelum memulai ketiga pembahasan utama tersebut, akan diuraikan pula sekilas tentang kedudukan penting bahasa Arab sebagai bahasa induk dalam kajian keislaman. A. Pentingnya Kedudukan Bahasa Arab dalam Kajian Islam Bahasa Arab memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Islam, ketika alQur’an sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertuang dalam bahasa Arab yang jelas (bilisani arabiyyin mubin).1 Dalam perkembangan bahasa Arab, bahasa al-Qur’an dapat digolongkan ke dalam apa 1 Lihat QS. 16:103; 26:195; dan 46:12. yang dinamakan dengan bahasa Arab klasik, yaitu bahasa al-Qur’an yang berkembang pula menjadi bahasa susastra sejak abad ke-7 masehi. Berkat ketinggian bahasa al-Qur’an pulalah maka kemudian para ahli bahasa membuat standarisasi bahasa Arab secara akademik pada abad ke-3 H (9 M) dan 4 H (10 M). Dalam proses standarisasi inilah ditentukan sistematika grammatikal, sintaksis, kosa kata, serta pemakaian susastra melalui berbagai aktivitas penelitian yang mendalam.2 Dari sini, kita mendapati sebuah kenyataan bahwa keberadaan teks al-Qur’an ber[eran besar bagi terciptanya kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab secara umum. Bila kita telusuri sejarah perkembangan bahasa Arab dari asal muasal sejarahnya, maka akan didapati sebuah kenyataan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari rumpun bahasa semitik. Dalam hal ini, pada masa pra-klasik bahasa Arab tergabung dalam rumpun cabang bahasa semit selatan (south semitic) atau semit barat daya (south-west semitic) yang tediri dari dua kelompok besar: (1) Arab selatan (meliputi bahasa suku Sabean kuno, Minean, Katabanian, dan Hadramitik di Yaman dan Hadramaut Selatan, serta bahasa Mehri di Hadramaut Utara, dan bahasa penduduk pulau Sokotra); (2) Bahasa Ethiopia (yang meliputi bahasa Ethiopia kuno atau Ge’ez, Tigre, Tigrinya, Amharik, Hurari, dan Gurage. Dalam proses pembentukannya, bahasa Arab juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Semit Barat Laut (bahasa Ibrani, bahasa Lihat C. Rabin, “Arabiyya” dalam Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill, 1999 (CD ROM Edition) i, 564a. 2 Ugaritik dan bahasa Aramaik).3 Oleh karena itu, secara keseluruhan bahasa Arab berdiri diantara bahasa Semit Selatan dan Semit Barat Laut, serta menjalin hubungan yang kuat dengan kedua cabang bahasa semitik tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika sebagian besar kelompok-kelompok bahasa semitik dalam rumpun bahasa semit selatan tidak ditemukan lagi penggunaannya kini kecuali bahasa Arab, maka faktor utama yang membuat bahasa Arab tetap terjaga hingga kini adalah karena bahasa Arab menjadi bahasa al-Qur’an, bahasa kitab suci umat Islam dan bahasa resmi yang dipakai dalam beberapa ritual ibadat umat Islam. Dalam ritual ibadat salat, misalnya, pengucapan bacaan-bacaan salat dilakukan dalam bahasa Arabnya yang asli, begitu juga dalam beberapa even dalam ritual ibadah Haji. Selain itu, secara sosiologis, bahasa Arab kini menjadi bahasa ibu yang dipakai oleh masyarakat di Asia Barat dan Afrika Utara. Bahkan, bahasa Arab juga memiliki pengaruh besar terhadap bahasa-bahasa lain seperti Persia, Turki, Urdu, Swahili, Melayu dan Husa. Dengan kata lain, bahasa Arab sudah menjadi bahasa kebudayaan Islam yang diajarkan pada ribuan sekolah di luar dunia Arab, termasuk negeri kita Indonesia dan kantong-kantong umat Islam lainnya di seluruh dunia.4 Sehingga, kenyataan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur’an dan bahasa kebudayaan Islam menjadikan bahasa ini semakin terasa penting keberadaannya sebagai bahasa yang tidak saja harus dikenal oleh umat Islam guna bisa membaca al-Qur’an, dan melaksanakan beberapa ritual ibadah Seperti akhiran –in yang menandai bentuk jamak maskulin ataupun bentuk pasif dan bentuk pengecilan (diminutive) melalui wazan fu’ayl yang kesemuanya tidak didapatkan dalam bahasa Arab selatan dan bahasa Ethiopia. (Lihat, C. Rabin, ibid., 564b.) 3 Lihat Nasaruddin Umar, Teologi Jender Antara Miitos dan Teks Kitab Suci. Jakarta: Pustaka Cicero, 2003, 113. 4 penting, tetapi juga menjadi elemen penting yang harus dipelajari guna dapat memahami al-Qur’an dan sumberr-sumber ajaran Islam lainnya dalam kerangka upaya pengkajian terhadap Islam secara umum. Al-Qur’an menjadi sumber pokok ajaran Islam, dan bahkan ayat-ayat al-Qur’an yang berfungsi sebagai penjelasan bagi ayat-ayat dalam bahagian lain al-Qur’an yang masih samar menempati hirarkhi tertinggi dalam sumber-sumber penafsiran kitab suci ini. Bila tidak ditemukan penjelasan tentang makna sebuah ayat dalam bahagian lain ayat-ayat al-Qur’an, maka barulah penafsiran dilakukan melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam bentuk hadis. Begitu seterusnya sampai kemudian penafsiran didasarkan pada ijtihad masing-masing mufassir, mulai dari kalangan sahabat, tabiin, tabiit-tabiin, dan sampai kepada para ulama mujtahidin dan mufassirin periode mutakhir. Bila kita kemudian menyebut hierarkhi tata urutan sumber penafsiran al-Qur’an seperti itu dengan istilah hermeneutika al-Qur’an,5 maka penguasaan yang paripurna terhadap bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an menempati urutan tertinggi dalam prasyarat penafsiran al-Qur’an,6 di samping penguasaan terhadap disiplin cabang ilmu keislaman yang lain seperti qira’at, teologi, usul fiqh, fiqh, asbab al-nuzul, nasikh mansukh, serta penguasaan terhadap ilmu hadis merupakan hal yang juga memegang peranan penting. Lihat Jane Dammen Mc Auliffe, Qur’anic Christians An Analysis of Classical and Modern Exegesis. Cambridge: Cambridge Univ Press, 1991, 17. 5 Lihat al-Suyuti, al-Itqan, ii, 180-1. Dalam hal ini, dari 15 cabang ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir, penguasaan bahasa Arab mencakup sedikitnya 7 aspek bahasa: lughat, nahw, saraf, isytiqaq, ma’ani, badi’ dan bayan. Lihat juga, Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bidaya fi al-tafsir al-mawdu’i, Kairo: Matba’ah al-hadarat al-arabiyya, 1977, 19-20. 6 Dalam mencermati kesemua sumber-sumber dalam hirarkhi penafsiran dan bahkan juga berlaku sebagai prosedur penetapan istinbat hukum yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ijtihad, kedudukan dan fungsi bahasa Arab memegang peranan sangat penting. Dalam hal ini, pemilahan jender yang diterapkan dalam bahasa Arab kerap mengakibatkan terjadinya pemahaman yang timpang bila ditinjau dari sisi keadilan jender antara status dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek yang diatur oleh Syariat Islam. Sebuah persoalan yang memerlukan upaya penafsiran ulang, atau reinterpretasi, di mana pemahaman yang semestinya tetap harus mengedepankan semangat kesetaraan jender yang tidak membedakan status dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah uraian yang mengupas aspek-aspek mana saja yang kerap dapat menimbulkan pemahaman yang bias jender dalam bahasa Arab. Dalam hal ini, pemahaman terhadap bahasa Arab, baik tentang makna kosa kata (mufradat), struktur, maupun kaidah yang berlaku di dalamnya merupakan keniscayaaan untuk dapat memahami kajian Islam dengan baik ketika umumnya generasi awal Islam menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam karya-karya yang berbahasa Arab, dan hanya dalam waktu akhir-akhir ini saja karya-karya itu giat diterjemahkan dalam berbagai bahasa lain di dunia Islam. B. Bias Jender dalam Kosa Kata (mufradat) Melalui pendekatan semantik, pemahaman tentang makna kosa kata dalam sebuah bahasa merupakan pondasi kuat yang akan bisa mengantar seseorang pada pemahaman yang tepat, tidak saja agar bisa sesuai dengan semangat yang dibawa oleh teks yang dihendak difahami, tetapi juga agar seorang penafsir dapat tepat sasaran dalam memilih makna yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penuturnya. Dalam hal ini, pemahaman yang baik terhadap makna kosa kata bahasa Arab menjadi prasyarat utama yang harus dilakukan dalam memahami teks kitab suci. Beberapa contoh pemahaman terhadap teks kitab suci al-Qur’an yang terkesan menimbulkan bias jender dapat disebutkan dalam memahami kosa kata bahasa Arab seperti quru’, lamasa, dan kalala yang dipahami secara berbeda oleh para ahli hukum Islam.7 1. Quru’ Kata quru’ merupakan bentuk jamak dari kata benda qar’ yang secara leksikal berarti “waktu” yang berlaku baik untuk masa haid maupun masa suci.8 Oleh karena itu, kata ini dapat dikategorikan sebagai kata yang musytarak, yaitu kosa kata yang maknanya tidak tunggal, bahkan saling bertentangan satu sama lain.9 Terkait dengan proses pengambilan ketetapan hukum tentang lamanya periode menunggu (iddah) yang diberikan kepada kaum perempuan yang dijatuhi talak oleh suaminya, seperti yang tertuang dalam QS. 2:228, Wal mutallaqatu yatarabbashna bi anfusihinna tsalatata quru’, “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga kali quru’....” Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang makna apa yang paling tepat diambil dari kosa kata quru’ ini, periode haidkah atau masa suci? Sebagian ulama menetapkan makna quru’ sebagai masa haid, seperti yang dipilih oleh Ibn Qayyim sesuai dengan 7 Lihat Nasaruddin Umar, op.cit, 218-219. 8 Lihat pendapat Abu Ubayd dalam Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, i, 130. 9 Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Semarang: Toha Putra, tt, II, 279. hadis yang memerintahkan kaum perempuan untuk meninggalkan salat di masa haid mereka, “da’i al-salata ayyama aqra’iki...” Kata aqra’ yang menjadi padanan jamak kata quru’ dalam hadis ini mengindikasikan kepada masa haid. Pengambilan makna yang sama juga berlaku bila kita mempertimbangkan kelanjutan QS. 2:228 yang menegaskan larangan bagi kaum wanita untuk menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka, yang menurut umumnya para ahli tafsir berarti haid dan kehamilan.10 Penafsiran berbeda dikemukakan para hali hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi‘i. Imam Syafi’i sendiri menegaskan bahwa kata quru’ boleh dipakai baik untuk masa haid maupun masa suci. Akan tetapi, menurutnya kata quru’ dalam QS. 2:228 hendaklah dipahami sebagai masa suci. Pemilihan makna suci ini didasarkan pada argumen bahwa ketika Ibn Umar mentalak isterinya yang tengah haid, maka Umar kemudian meminta pendapat Nabi mengenai apa yang harus dilakukannya. Nabi kemudian bersabda, “Suruhlah dia (Ibn Umar) untuk merujuk isterinya, dan apabila tiba waktu sucinya maka barulah ia jatuhkan talaknya; itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk mentalak kaum wanita.”11 Kedua penafsiran yang berbeda dalam menyikapi kosa kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna ganda (musytarak), bahkan yang berlawanan antara satu makna dengan lainnya, pada gilirannya mengakibatkan munculnya ketetapan hukum yang berbeda tentang berapa lama seorang wanita mesti menunggu dan 10 Menurut pada ulama, makhluk di dalam rahim adalah mamsa datang bulan yang nyata ( haidh wujudi). 11 Lihat Lisan al-Arab, i, 131. menahan diri dari keinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Pilihan terhadap kata quru’ yang berarti masa haid, seperti pendapat yang dipegangi oleh Abu Hanifah memberi akibat pada lamanya waktu menunggu yang diperlukan oleh kaum wanita dalam menjalani masa iddah mereka bisa mencapai minimal sekitar 60 hari dengan perhitungan: masa haid pertama maksimal 10 hari, lalu suci 15 hari, haid lagi 10 hari, suci lagi 15 hari, dan terakhir haid lagi 10 hari. Hitungan yang lebih pendek diberikan oleh pengikut (ashab ) madzhab Hanafi yang lain bahwa masa iddahnya berlangsung minimal 39 hari dengan menghitung masa haid minimal 3 hari. Oleh karena itu, dalam rentang waktu tiga kali masa haid dihitung terdapat dua kali masa suci masingmasing 15 hari, sehingga jumlah total lama iddah minimal 39 hari (3+15+3+15+3=39).12 Rentang waktu masa menunggu (iddah) minimal yang direkomendasikan oleh para ulama Hanafiah tersebut masih terhitung lebih lama jika dibandingkan dengan perhitungan rentang waktu iddah minimal yang dipahami kelompok madzhab Syafi’i yang mengambil arti kata quru’ sebagai masa suci. Menurut mereka, masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan yang tertalak oleh suaminya berlangsung minimal 32 hari ditambah satu jam. Logikanya, jika seorang wanita tertalak dalam keadaan suci dan satu jam kemudian dia mendapatkan masa haid, maka masa satu jam tadi sudah bisa dianggap sebagai satu kali suci, kemudian ia mesti menunggu masa haid pertama yang minimal berlangsung 1 hari, kemudian masa suci 15 hari, haid lagi 1 hari, dan suci lagi 15 hari. Pada waktu ia menjalai masa haid yang ketiga, 12 Sayyid Sabiq, op.cit., 279-80. maka berakhirlah masa menunggu yang dijalaninya.13 Walhasil, masa menunggu yang lebih pendek, sebagaimana dipegangi oleh pendapat Imam Syafi‘i, dianggap lebih memperhatikan hak-hak kaum perempuan yang sedikit banyak mampu memupus bias jender yang terjadi di dalam bahasa Arab yang terlalu banyak membela kepentingan kaum lakilaki akibat budaya patriarkhis masyarakat Arabia. 2. Lamasa Kata kerja lamasa juga merupakan lafazh yang musytarak dalam penggunaan bahasa Arab, sehingga perbedaan makna yang diambil terhadap makna kata itu berimplikasi pada perbedaan ketetapan hukum yang lahir dari pemakaian kata itu dalam teks al-Qur’an. Dalam QS. 5:6 yang menerangkan aturan berwudu’ dan hal-hal yang membatalkan wudu terdapat kalimat yang berbunyi aw lamastumun nisa’. Kalimat ini dipahami secara berbeda olah para ahli hukum Islam sebagai akibat perbedaan mereka dalam mengambil makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut dari penggunaan kata lamasa dalam kebiasaan masyarakat Arab yang mengindikasikan pemakaian yang majemuk. Dalam hal ini, ungkapan dalam ayat tersebut ditafsirkan secara tidak sama sebagai akibat perbedaan makna yang bisa diambil dari kata tersebut. Sebagian mengatakan bahwa kata lamasa diartikan sebagai aktivitas menyentuh yang dilakuan dengan tangan, sehingga menyentuh kulit perempuan bukan muhrim tanpa penghalang dianggap sebagai tindakan yang membatalkan wudu’. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memandang kalimat tersebut sebagai sebuah ungkapan 13 Ibid., 279. konotatif yang sebenarnya menjurus pada aktivitas persetubuhan, sehingga persentuhan kulit semata-mata tidaklah berakibat pada batalnya wudu’ seseorang. Pendapat pertama dipegangi umumnya oleh kalangan madzhab Syafi‘i dan Maliki, meski ada perbedaan diantara keduanya;14 sedangkan pandangan kedua dipegangi oleh kelompok madzhab Hanafi. Dari dua pendapat ini, pendapat Abu Hanifa kali ini nampak lebih moderat dibandingkan dengan pendapat dalam madzhab lain seperti Syafi’i dan Maliki yang mengesankan adanya sesuatu hal dalam tubuh perempuan yang begitu mudah bisa membatalkan wudu bagi laki-laki yang menyentuhnya.15 3. Kalala Kosa kata lain dalam bahasa Arab yang memiliki makna ganda, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai penetapan hukum yang terkait dengan masalah itu dapat pula dicontohkan dalam makna yang dikandung oleh lafazh kalala. Dalam ayat pembagian waris QS. 4:12, “Jika seorang laki-laki atau perempuan (meninggal dalam keadaan) tidak memiliki ayah ataupun anak, dan ia memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka masing-masing keduanya memperoleh bagian seperenam. Jika jumlah mereka ternyata lebih banyak dari itu, maka mereka bersekutu untuk (mendapatkan) bagian sepertiga....” Dalam hal ini, makna kalala didefinisikan sebagai Perbedaan antara kedua madzhab ini dipaparkan oleh Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid sebagai akibat hukum yang didasarkan pada asas pengambilan keputusan hukum yang berbeda. Kelompok madzhab Maliki memandang persoalan tersebut dari sudut pandangan yang umum dengan menghendaki sesuatu yang bersifat khusus (bab al-‘am urida bihi al-khash), oleh karena itu mereka mensyaratkan terjadinya batal wudu’ jika akibat persentuhan tersebut menimbulkan syahwat. Sementara kelompok Syafiiyah menganggapnya dari sudut pandangan umum dengan menghendaki keumumannya (bab al-‘am urida bihi al-‘am) sehingga tidak ada syarat apakah persentuhan tersebut menimbulkan syahwat atidak, tetap saja hal tersebut dianggap telah membatalkan wudu. Lihat Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. Singapura: Sulaiman Mara’i, tt, i, 38. 14 15 Lihat Nasaruddin Umar, op.cit., 219. “seseorang yang tidak memiliki anak maupun orang tua.”16 Perbedaan pendapat menyeruak ketika timbul pertanyaan kepada siapa status kalala itu dikenakan, apakah kepada si mayit yang tidak meninggalkan anak dan orang tua, ataukah kepada kaum kerabat terdekatnya yang ditinggalkan yang bukan merupakan ayah ataupun anak dari yang meninggal? Kedua makna tersebut sama-sama diakui keberadaannya oleh ahli bahasa Arab. Perbedaan pandangan mengenai makna mana yang boleh diambil untuk lafazh kalala menyebabkan lahirnya perbedaan dalam hal penetapan hukum, apakah berlaku bagian yang sama-sama seperenam untuk saudara baik laki-laki maupun perempuan, ataukah melalui cara pembagian lain yang terkesan bias jender seperti yang ditunjukkan dalam hadis Jabir bin Abdillah di mana kaum laki-laki memperoleh porsi dua kali lebih besar dibandingkan dengan bahagian perempuan.17 Dari ketiga contoh kosa kata bahasa Arab yang memiliki makna ganda (musyarak) sebagimana diuraikan di atas nampak bahwa perbedaan makna menyebabkan terjadinya perbedaan keputusan hukum yang berimplikasi pada munculnya bias jender, ketika masing-masing pendapat yang dikemukakan memunculkan perbedaan perlakuan yang didasarkan atas nama perbedaan jenis kelamin. Dalam hal ini, dominasi budaya patriarkhis memojokkan kaum perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, atau bahkan minimal tidak diperlakukan setara dengan kaum laki-laki. Ketiga contoh di atas cukup memberikan gambaran betapa kaum perempuan diharuskan untuk menjalani waktu iddah yang lama, atau bahkan lebih lama lagi akibat perbedaan 16 Lisan al-Arab, xi, 592. 17 Lihat Nasaruddin Umar, op.cit. 219. parameter quru’; tubuh perempuan menjadi sebab yang membatalkan wudu bagi laki-laki yang menyentuhnya, serta pembagian waris yang tidak seimbang dengan bagian waris laki-laki. Kesemua perlakuan yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan jender tersebut berakar pada perbedaan ketetapan hukum sebagai akibat dari perbedaan makna yang dikandung dalam kosa kata (mufradat) bahasa Arab yang memiliki makna ganda. Dalam hal ini, sebenarnya bukanlah teks al-Qur’an yang mengandung bias jender, tetapi perbedaan istinbat hukum yang didasarkan pada perbedaan makna dalam penggunaan lafazh tertentu dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan penuturnya menjadikan proses interpretasi yang dilakukan seorang mujtahid kerap menghasilkan keputusan hukum yang jatuh terjerembab dalam bias jender, di mana kepentingan kaum perempuan dinomorduakan dibandingkan dengan kepentingan laki-laki. C. Struktur Bahasa Arab yang didominansi Bentuk Maskulin Selain aspek kosa katanya yang memberikan makna yang bias jender, bahasa Arab memiliki beberapa struktur yang bentuk maskulinnya terkesan mendominasi, sehingga penyebutan sebuah bentuk maskulin mencakup pula di dalamnya masuknya jenis jender feminin, dan bahkan beberapa bentuk maskulin terkesan begitu dominan sehingga tidak memiliki bentuk feminin yang menjadi padanan katanya. Dalam dua kasus ini, pokok persoalan yang bermuara pada dominasi bentuk jender maskulin dalam struktur bahasa Arab nampak sebagai akibat domain sosiologis yang bias ketika peran sosial laki-laki lebih ditonjolkan dibandingkan dengan peran perempuan, bahkan cenderung terdapat kesan bila kaum perempuan berada di bawah sub-ordinas laki-laki. 1. Pemakaian Khitab Maskulin Struktur bahasa Arab yang kerap menimbulkan bias jender berasal dari kenyataan bahwa bahasa Arab merupakan bagian dari rumpun bahasa Semitik yang lebih dominan memakai bentuk maskulin dibandingkan dengan bentuk feminin. Contoh yang paling gamblang dalam hal ini adalah pemakaian khitab laki-laki yang dianggap pula mencakup pula jender feminin di dalamnya, bila keduanya berkumpul dalam sebuah tempat yang sama. Dengan kata lain, selain berarti khusus laki-laki khitab maskulin juga bisa diartikan sebagai khitab universal yang tidak saja mencakup jender laki-laki, tetapi juga mencakup jender perempuan pada tempat yang sama. Kondisi semacam ini dipandang memiliki kaitan dengan konsepsi kosmologi bangsa Semit yang menganggap perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki, sehingga jika laki-laki dan perempuan berkumpul di tempat yang sama, maka menyebutkan laki-laki dirasakan sudah mencakup pula kaum perempuan di dalamnya.18 Beberapa sebutan yang menggunakan khitab laki-laki untuk maksud universal di dalam teks al-Qur’an dapat disebutkan seperti penyebutan khitab panggilan Ya ayyuha alladzina amanu (wahai orang-orang yang beriman); ya ayyuha alkafirun (wahai orang-orang kafir), dan lain sebagainya, dengan jelas mengindikasikan pemakaian bentuk maskulin untuk tujuan universal. Di 18 Lihat Nasaruddin Umar, ibid., 227. samping itu, untuk hampir semua khitab universal al-Qur’an juga menyebutnya dengan bentuk maskulin, seperti aqimu al-salat, atimmu al-hajja, dst. Bentuk lain dominasi budaya patriakhis dalam struktur bahasa Arab tercermin dalam urut-urutan penyebutan yang mendahulukan laki-laki baru kemudian perempuan dalam urutan kata dalam sebuah kalimat seperti QS. 4:1, ...wa batstsa minhuma rijalan katsiran wa nisa’a..., QS. 4:7, lirrijali nasibun...wa lin nisa’i..., QS. 4:12, ...wa in kana rajulun yuratsu kalalatan aw imra’atun..., QS. 5:38, Al-sariqu was sariqatu faqta’u..., dsb. Tata urutan penyebutan semacam itu yang mendahulukan sebutan bagi laki-laki dibandingkan perempuan merupakan bentuk normal, karena ketika penyebutannya dibalik seperti dalam kasus yang menyangkut hukuman pidana bagi pezina dalam QS. 24:2, al- zaniyatu wa al-zani fajlidu..., maka hal ini dianggap sebagai kasus khusus yang memerlukan penjelasan. Sebagian mufassir menafsirkan didahulukannya penyebutan pelaku zinah perempuan (zaniyah) dalam ayat ini sebagai sebuah peringatan (warning) yang kuat atas dasar alasan bahwa karena syahwat dalam diri kaum perempuan dianggap lebih besar, sehingga perlu didahulukan penyebutannya.19 Walhasil, struktur bahasa Arab yang lebih banyak didominasi oleh pemakaian khitab maskulin, penggunaan kata ganti (dhamir) mudzakkar dalam lingkup yang juga mencakup perempuan di dalamnya sebagai sebuah kesatuan, dan penyebutan urutan laki-laki yang didahulukan dari perempuan merupakan beberapa contoh yang mencerminkan adanya bias jender dalam bahasa Arab 19 Tafsir al-Baghawi, xii, 160. yang terjadi akibat produk budaya masyarakat yang patriarkhis. Kenyataan ini menjadi keniscayaan yang tidak mungkin hilang, mengingat budaya patriarkhis dalam masyarakat Arab memang telah menciptakan dominasi laki-laki dan memojokkan posisi kaum perempuan dalam peran dan relasi sosial dan keagamaan mereka, yang pada gilirannya juga menciptakan konsep-konsep agama yang lebih dominan memberikan bentuk-bentuk dan hak-hak khusus bagi kaum laki-laki dan cenderung menafikan peran kaum perempuan di dalamnya, sebagaimana sudah diuraikan dalam pertemuan-pertemuan terdahulu. 2. Beberapa Bentuk Khusus Maskulin Beberapa ungkapan dalam bahasa Arab ada yang cenderung memiliki struktur dalam bentuk laki-laki saja, dan tidak memiliki struktur dalam bentuk feminin. Dalam hal ini, kata imam dan khalifah dengan jelas menunjukkan bahwa dua kata tersebut merupakan bentuk kata benda maskulin yang tidak memiliki bentuknya dalam jender feminin. Kenyataan yang sangat bias jender dan cenderung patriarkhis ini pada gilirannya menyumbang amat besar bagi lahirnya konsep-konsep keagamaan yang kemudian hanya diperuntukkan sebagai hak bagi kaum laki-laki. Kata imam yang tidak memiliki bentuk nomina feminin pada gilirannya selalu ditonjolkan sebagai sesuatu yang berkonotasi laki-laki, seperti predikat imam sebagai pemimpin dalam salat berjamaah, pemimpin agama, atau bahkan pemuka masyarakat. Struktur bahasa Arab yang didominasi bentuk maskulin kemudian memberi kesan lebih jauh bahwa konsep imam melulu menjadi otoritas yang dimiliki kaum laki-laki,20 dan sebaliknya meminggirkan atau bahkan meniadakan peran perempuan di dalamnya. Sementara itu, kata khalifah meskipun memiliki ciri feminin dengan tambahan ta’ marbutah di akhir dianggap sebagai sebuah kata yang digolongkan ke dalam bentuk mudzakkar dengan dua buah bentuk jamak khulafa’ dan khala’if. Bentuk jamak yang pertama selalu menampilkan bentuk mudzakar, sementara bentuk jamak yang kedua bisa pula dianggap sebagai mu’annats. Di sini, berkait dengan makna kata ini, bentuk yang selalu mudzakkar diberikan untuk kata benda tunggal khalifah maupun bentuk jamaknya yang membawa arti “pemimpin (imam) tertinggi yang tidak ada lagi imam di atasnya”.21 Walhasil, kekhususan bentuk mudzakar dalam contoh dua kata imam dan khalifah menjadi dasar bagi lahirnya konsepsi-konsepsi sosial dan politik yang kemudian turut pula menyeret dominasi hak-hak khusus dan peran yang diperuntukkan hanya untuk kaum laki-laki. Dalam hal ini, struktur bahasa Arab yang cenderung didominasi laki-laki menyumbang peranan yang sangat besar bagi bias jender yang asalnya sangat bersifat liguistik ini, ketika kemudian dominasi budaya patriarkhis yang mendasari penafsiran terhadap al- Qur’an,misalnya, tidak jarang pula memberikan sokongan bagi lahirnya legitimasi secara keagamaan. Stempel keagamaan untuk konsep-konsep yang bias jender ini merupakan dampak langsung dari aktivitas interpretasi dalam bentuk ijtihad yang dilandasi pemakaian bahasa yang didominasi oleh budaya, 20 Lihat Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, xii, 22-27. Lihat pula Nasaruddin Umar, op.cit., 229. Lihat L. Ma’louf, al-Munjid, Beirut: Dar el-Masyriq, 1986, 192. Dukungan terhadap dominasi mudzakkar bagi makna tersebut diberikan pula oleh Sibawaih dan Ibn Sayyidih. Lihat Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, ix, 84. 21 pemikiran, dan ideologi masyarakat Arab secara umum yang masih patriarkhis dan meninggikan peran laki-laki. D. Kaidah Bahasa yang Bersifat Ambigu Bias jender dalam bahasa Arab juga dapat dilihat dalam penerapan beberapa kaidah kebahasaan yang terkesan bersifat ambigu. Kaidah-kaidah yang ambigu ini terdapat dalam beberapa macam kasus seperti tentang fungsi dan makna huruf waw, apakah huruf itu berfungsi sebagai huruf ‘athaf, ataukah sebagai hal, dan fungsi-fungsi gramatikal yang lain; begitu juga dengan kasus ketidakjelasan mengenai ruang lingkup batas pengecualian (istitsna); dan penetapan rujukan kata ganti (dhamir). Ketiga macam kasus di atas merupakan persoalan konkrit yang ditemukan di dalam teks al-Qur’an yang berbahasa Arab, ketika tidak ada kaidah yang jelas mengatur bagaimana seharusnya fungsi dan makna elemen-elemen kebahasaan tadi bisa diterapkan secara standar, dan dengan begitu bisa diberikan makna secara lebih pasti menurut tata kaidah bahasa Arab yang dianggap benar. 1. Fungsi dan Makna Huruf Waw Huruf waw yang terletak di tengah-tengah kalimat dalam bahasa Arab seringkali dipahami secara berbeda menyangkut status dan fungsi gratikalnya. Perbedaan ini pada gilirannya menimbulkan perbedaan makna yang dikandung oleh kalimat dimaksud. Berbeda dengan waw yang terletak di muka kalimat yang sering dirujuk dalam status qasam, di mana fungsi huruf ini menjadi kata pembuka sumpah yang mengiringi penyebutan nama Tuhan atau tempat dan objek yang dianggap sakral, huruf waw yang berada di tengah kalimat lazimnya dirujuk sebagai huruf athaf (kata sambung atau conjunction) dan hal (circumstantial expression). Huruf waw yang berfungsi sebagai kata sambung yang dipahami secara berbeda maknanya oleh para ulama dapat dilihat dalam contoh QS. 4:3, wa in khiftum an la tuqsitu fi al-yatama, fankihu ma thaba lakum min al-nisa’i matsna wa tsulatsa wa ruba’, fa in khiftum an la ta’dilu fa wahidah... ‘Dan jikalau kamu khawatir tidak akan bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kemudian kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja...” Terjemahan seperti di muka merupakan pendapat jumhur ulama yang cenderung memaknai huruf waw dalam kalimat matsna wa tsulatsa wa ruba’ sebagai huruf athaf yang mewakili lambang “koma” dalam aksara latin dan bermakna “atau”22 yang dalam bahasa Arab menempati fungsi sebagai “pengganti” (badal).23 Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi laki-laki muslim menikahi wanita lebih dari empat orang. Bila kemudian Nabi SAW sendiri menikahi sembilan isteri, maka hal itu merupakan pengecualian yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Akan tetapi, ada pendapat di kalangan sekte Syi’ah dan sebagian penganut aliran Zhahiri yang membolehkan seorang lelaki muslim untuk menikahi wanita lebih dari empat orang. Untuk itu mereka menafsirkan huruf athaf waw dalam fungsi makna penjumlahan (lil jam’i), sehingga ungkapan matsna wa tsulatsa wa ruba’ dimaknai sebagai 2+3+4=9. Jumlah ini, menurut kaum Syi’ah sesuai 22 Nasaruddin Umar, Teologi Jender, 227. 23 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, II, 97. dengan jumlah isteri yang boleh dimiliki oleh Nabi SAW. Bahkan, pendapat yang lebih buruk lagi diungkapkan oleh sebagian kelompok Zhahiri yang menafsirkan matsna sebagai dua-dua, dst. Sehingga, jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah 18 orang dari hasil penjumlahan 2+2+3+3+4+4=18.24 Beberapa penafsiran yang berbeda menyangkut status, fungsi dan makna waw sebagai huruf athaf dilatarbelakangi oleh perbedaan masing-masing penafsir dalam memberikan makna bagi status dan fungsi waw sendiri yang memang tidak saja bersifat multi-tafsir. Dalam tradisi pemakaian bahasa Arab, waw yang berfungsi sebagai athaf dengan makna penjumlahan memang lazim dipakai oleh penutur bahasa Arab, sehingga untuk mengatakan jumlah total sembilan, orang Arab biasa mengatakan: “dua, tiga, dan empat”. Begitu juga dengan ungkapan matsna untuk menunjuk "kelompok dua", seperti ungkapan “mereka datang berdua-dua” maksudnya dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari dua orang dua orang. Sementara itu, jumhur membatasi jumlah wanita yang dinikahi sebatas empat sebagaimana mereka menggunakan pertimbangan dalil lain yang berasal dari hadis yang menegaskan kembali batasan itu.25 Walhasil, perbedaan cara istinbat hukum, utamanya ketika menyertakan pengambilan argumentasi menurut pemakaian bahasa Arab secara umum turut memberikan kontribusi dalam penafsiran teks al-Qur’an menyangkut makna apa yang mesti dikenakan terhadap huruf athaf yang ambigu maknanya dan disimbolkan dengan huruf waw tersebut. Kesemua penafsiran tentang makna waw sebagai huruf athaf di atas sangat jelas mencerminkan bagaimana bahasa Arab dipahami 24 Ibid. 25 Ibid., 96-98. dan dibentuk dalam kultur yang sangat bias jender. Akibat ketimpangan jender ini, nasib kaum perempuan terkesan sangat dirugikan secara kultural. 2. Penetapan Batas Pengecualian (istisna) Makna yang ambigu dalam kaidah bahasa Arab juga tercermin dalam kaidah dalam menetapkan batas pengecualian (istisna) apakah hanya kalimat yang berada dalam urutan terdekat saja, ataukah bisa menjangkau sebagian atau keseluruhan kalimat yang sudah disebutkan. Contoh yang cukup gamblang dapat dilihat dalam contoh kasus QS. 24:4-5, walladzina yarmuna al- muhshanati tsumma lam ya’tu bia rba’ati syuhada’a fajliduhum tsamanina jaldah, wa la taqbalu lahum syahadatan abada, wa ula’ika hum al-fasiqun (4). Illa alladzina tabu min ba’di dzalika...(5) “Dan orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) wanita-wanita yang baik, kemudian tidak mendatangkan orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Penyayang.” Terdapat perbedaan pandangan terhadap aspek mana sajakah yang termasuk dalam pengecualian yang disebutkan di dalam ayat kelima dari surat al-Nur ini. Ada tiga hal yang menjadi elemen hukuman bagi mereka yang melakukan tuduhan palsu terhadap perbuatan zina: (1) hukuman 80 cambuk, (2) ditolak kesaksiannya, (3) digolongkan ke dalam kelompok fasik. Abu Hanifa mengatakan bahwa pengecualian hanya berlaku bagi penggolongan terhadap kelompok fasik. Oleh karena itu, jika si pelaku bertaubat maka dia dikeluarkan dari kategori fasik di hadapan Allah. Sementara penolakan terhadap kesaksian dan hukuman cambuk tetap berlaku. Akan tetapi, ulama lain secara umum memandang bahwa selain dikeluarkan dari kategori fasik, maka pelaku tuduhan palsu yang sudah bertaubat juga dikeluarkan dari kelompok yang ditolak kesaksiannya. Dengan demikian, istisna juga diberlakukan terhadap elemen yang kedua, sehingga penolakan terhadap kesaksian digugurkan oleh taubat yang dilakukannya. Meskipun demikian mereka tetap sepakat bahwa taubat tidak bisa menggugurkan hukuman dera yang termaktub dalam elemen pertama.26 Perbedaan penerapa hukuman akibat perbedaan pandangan mengenai penetapan batas pengecualian ini tentu saja menimbulkan dampak yang bias jender, karena pandangan jumhur ulama yang membebaskan penolakan terhadap kesaksian dengan taubat terkesan memberikan keringanan hukuman kepada para pelaku tuduhan palsu yang umumnya merupakan kaum laki-laki.27 3. Penetapan Rujukan Kata Ganti (dhamir) Kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang mengesankan terjadinya bias jender akibat ambiguitas yang ditunjuk dalam pemakaian istisna juga didapati dalam penetapan rujukan kata ganti (dhamir). Dalam hal ini, di dalam al-Qur’an juga terdapat pemakaian kata ganti yang tidak jelas ke mana rujukan yang sebenarnya. Salah satu contoh yang kalau kita analisis lebih jauh akan menimbulkan bias jender yang menjadi akar pemahaman yang juga bias jender Lihat Tafsir al-Qurtubi, xii, 179. Lihat pula Ali al-Sabuni, Tafsir ayat ahkam, II, 76 dalam Nasaruddin Umar, Teologi Jender, 225. 26 27 Nasarudin Umar, ibid. dalam teologi penciptaan manusia, sebagaimana tertuang dalam QS. 4:1, Ya ayyuha al-nas (i)ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha... “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (nafs wahida), dan dari padanya (minha) Allah menciptakan pasangannya (zawjaha)...” Terdapat dua buah kata ganti (dhamir) ha’ yang diperselisihkan ke mana kembalinya. Umumnya mufassir mengembalikan rujukan dhamir ha tersebut kepada kata nafsin wahida yang dimaknai sebagai Adam, sehingga dhamir ha’ dalam kata zawjaha dimaknai sebagai pasangan Adam, yaitu Hawa. Bias jender yang cenderung berpangkal dari keyakinan Israiliyat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok yang kemudian dikuatkan pula oleh sebuah hadis Nabi menjadikan penafsiran ayat ini menjadi penguat bagi lahirnya kultur dan budaya yang menempatkan kedudukan wanita secara ontologis sebagai makhluk yang tersubordinasi oleh kedudukan dan kekuasaan laki-laki. Penafsiran yang berbeda terhadap ayat ini diungkapkan oleh Abduh. Mengikuti pendapat Abu Muslim al-Isfahani, Abduh mengembalikan kata ganti dhamir ha hanya kepada kata nafsin yang bermakna diri yang satu yang menjadi unsur pembentuk Adam. Sementara dhamir kedua ha dimaknai sebagai pasangan genetik dari diri yang satu.28 Penetapan rujukan kata ganti dhamir ha dalam ayat di atas, sebagaimana ditunjukkan dalam perbedaan penafsiran ayat tersebut menunjukkan dengan jelas, bagaimana budaya patriarkhis masyarakat Arab yang ditunjukkan dalam penggunaan bahasa Arab memberikan kontribusi 28 Lihat Nasaruddin Umar, Teologi Jender, 219-224. yang sangat besar bagi terjadinya ketimpangan jender dalam memahami ayatayat al-Qur’an yang seyogianya paralel dengan semangat al-Qur’an yang menjunjung tinggi kesamaan derajat semua manusia di hadapan Allah, tidak peduli apa jenis kelamin dan peran sosialnya yang tercipta dari perbedaan jenis kelamin itu. Bias jender yang terjadi dalam memahami teks-teks al-Qur’an, sebagaimana tercermin dalam pandangan-pandangan yang tertuang dalam kitab-kitab tafsir yang mu’tabar secara umum berpangkal dari penggunaan bahasa Arab yang bias jender. Kasus-kasus yang memberi ruang bagi kemungkinan mufradat yang memiliki makna ganda, struktur bahasa yang didominasi jender maskulin, ataupun kaidah-kaidah yang terkadang bersifat ambigu akibat kurang jelasnya batasan pengecualian maupun rujukan kata ganti dhamir yang disebut menjadikan pemahaman terhadap teks-teks berbahasa Arab kerapkali dibarengi dengan lahirnya penafsiran yang bias pula dan menempatkan laki-laki setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Penafsiran semacam ini tidak sejalan dengan semangat persamaan jender yang diusung oleh al-Qur’an, sehingga sudah selayaknya untuk mulai ditinjau kembali. Wallahu a’lam Daftar Pustaka Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Rabin, C. “Arabiyya” dalam Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill, 1999 (CD ROM Edition) i, 564a. Umar, Nasaruddin. Teologi Jender Antara Miitos dan Teks Kitab Suci. Jakarta: Pustaka Cicero, 2003. Mc Auliffe, J.D. Qur’anic Christians An Analysis of Classical and Modern Exegesis. Cambridge: Cambridge Univ Press, 1991, Suyuti, al-Itqan, Beirut: Dar el Fikr, 1979, 2 vols. Farmawi, Abd al-Hayy. al-Bidaya fi al-tafsir al-mawdu’i, Kairo: Matba’ah alhadarat al-arabiyya, 1977. Ma’louf, L. al-Munjid, Beirut: Dar el-Masyriq, 1986. Ibn Mandzur, Lisan al-Arab. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Semarang: Toha Putra, tt, II, 279. Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. Singapura: Sulaiman Mara’i, tt, i, 38. Tafsir al-Baghawi. Tafsir al-Qurtubi. Sabuni, Ali al-. Tafsir ayat ahkam, 2 vols.