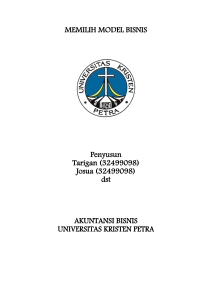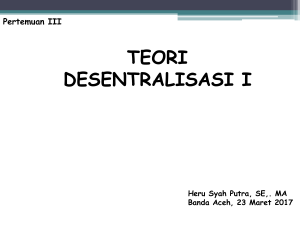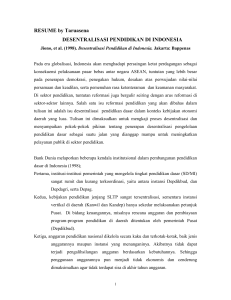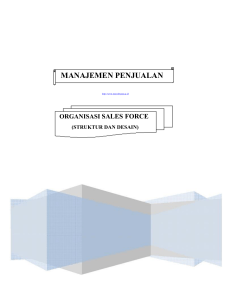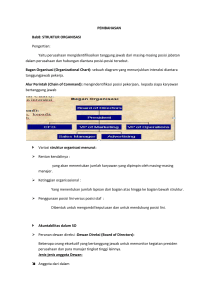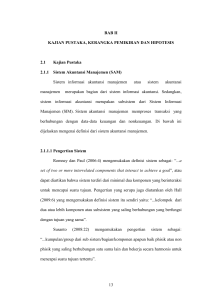Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam
advertisement

Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pada bulan Ramadhan kemarin ramai perbincangan mengenai tindakan Satuan Petugas Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Serang yang menyita barang dagangan salah satu warung makan karena berjualan di siang hari. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Purwakarta justru mempersilahkan pemilik rumah makan untuk beroperasi selama 24 jam. Fenomena tersebut adalah gambaran bagaimana sistem desentralisasi melahirkan keragaman kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah. Meskipun beragam, kepemimpinan demokrasi mengharuskan pemerintah melindungi hak warga, termasuk melalui produk hukum. Mirisnya, hingga kini masih banyak ditemui peraturan daerah diskriminatif bahkan melanggar hak asasi manusia. Bagaimana norma hukum masih dibutuhkan untuk mewujudkan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial? Dalam logika kepemimpinan demokrasi, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia bahkan telah menjadi kewajiban konstitusi penyelenggaraan negara di berbagai tingkat, baik dalam lingkup pusat dan daerah. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 4 dan 5 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; dan untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap penyel-enggaraan pemerintah memiliki kewajiban konstitusi untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia termasuk dalam upaya pemenuhannya. Herlambang Perdana, akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya menyebutkan pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah merupakan bagian dari kewajiban konstitusi. Sehingga konsekuensi bagi setiap pelanggaran pemenuhan hak rakyat merupakan pelanggaran konstitusi. “Secara tertulis kewajiban pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusional bagi penyelanggara pemerintahan di berbagai level, nasional maupun daerah. Hal ini disebutkan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap penyelenggara pemerintahan yang mengabaikan dan bahkan melanggar pemenuhan hak rakyat, bukan hanya melanggar hukum, melainkan melanggar konstitusi,” jelas Herlambang. Meskipun memiliki legitimasi konstitusional, kenyataannya pemenuhan hak asasi bagi warga negara belum menjadi agenda utama pemerintahan Indonesia. Hal ini juga diakui Herlambang, seiring perkembangan waktu, hak-hak rakyat menjadi begitu abstrak sehingga pemerintah daerah lebih menitikberatkan pemenuhan kebutuhan investor atau lajur kapital. Alhasil pemenuhan hak warga dikesampingkan. “Ibarat salesman atau dealer, pemerintah daerah menggadaikan hak rakyat demi kepentingan investasi. Pemenuhan keadilan sosial kerap kali diucapkan, namun diputarbalikkan untuk kepentingan politik lokal guna melitigimasi bisnis-bisnis yang sebenarnya berdampak mengesampingkan hak-hak dasar rakyat,” jelas Herlambang yang merupakan koordinator Asosiasi Dosen Hak Asasi Manusia se Indonesia (SEPAHAM). Deretan kasus tambang di Pulau Jawa merupakan bukti bagaimana ketidakberpihakan pemerintah daerah kepada pemenuhan hak rakyat. Sebagai contoh adalah kasus tambang semen di Rembang dan Pati (Jawa Tengah), pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi dan ekspolitasi eksesif tambang, perkebunan kelapa sawit dan sejumlah industri yang mulai merajalela di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun secara analisis lingkungan pendirian industri tersebut melanggar hukum, serta banyak penolakan dari penduduk lokal yang kelangsungan hidupnya terancam, pemerintah daerah lokasi-lokasi industri tersebut tetap berupaya untuk melangsungkan pembangunan. Dampaknya konflik warga tidak lagi terbendung. Pembiaran sikap diskriminatif yang dilakukan kelompok intoleran juga memperparah situasi dan melanggengkan abainya negara untuk memberikan keamanan bagi warga yang hidup di tanahnya sendiri. Situasi demikian menurut Herlambang disebabkan karena minimnya pengetahuan pemerintah daerah terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. “Pemerintah daerah kerap kali belum mengenal konsep pemenuhan hak-hak seperti hak ekonomi, sosial dan budaya. Terutama mengenai realisasi progresif dan pemenuhannya,” jelas Herlambang. Fokus kerja pemerintah dan birokrasi hanya berorientasi pada kebijakan khususnya mengenai penganggaran. Adapun penganggaran tersebut belum sepenuhnya mendorong strategi pro-poor budget atau penganggaran yang berbasis kebutuhan dasar rakyat miskin. Karakteristik Desentralisasi dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Pasca runtuhnya era otoritarianisme, sistem pemerintahan Indonesia berubah cukup signifikan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah di tingkat daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sistem desentralisasi secara langsung memberikan otoritas dari pusat ke daerah. Jakarta tidak lagi menjadi pusat untuk menentukan proses politik dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Beberapa daerah diberikan sistem desentralisasi asimetris dengan kewenangan khusus, seperti Aceh dan Papua, karena peristiwa konflik yang berkepanjangan. Selain itu, kedua daerah tersebut juga dianggap memiliki keunikan secara budaya dan politik. Sederhananya, otonomi daerah melegitimasi kewenangan pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta anggaran guna kepentingan kemajuan daerahnya masing-masing. Dalam makalah Hasrul Hanif, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berjudul ‘Daulat Rakyat atau Daulat Pasar’, yang disampaikan dalam Konferensi “Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” pada tahun 2008 lalu, menegaskan bahwa sistem desentralisasi adalah hasil resultante dari adanya perubahan struktur ekonomi politik baik di ranah global, nasional maupun lokal. Selain itu, arsitektur devolusi tergantung dengan dominasi dalam pertarungan ideologis yang ada. Dengan demikian desentralisasi harus dipandang lebih luas. Sistem desentralisasi tidak hanya sebatas pelimpahan kewenangan, melainkan distribusi akumulasi modal dari pusat ke daerah. Hal ini memiliki dampak yang lebih besar karena berimplikasi pada konstelasi politik. “Persebaran model demikian telah mengubah konstelasi politik yang tadinya sentralistik dalam setiap kebijakan menjadi harus lebih mempertimbangkan konteks politik kepentingan di tingkat lokal,” ujar Herlambang melalui surat elektronik pada bulan Juli 2016. Hal senada diungkapkan Vedi R Hadiz dalam bukunya yang berjudul “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective.” Ia mengunkapkan distribusi kekuasaan ke tingkat lokal sangat terkait erat dengan ekonomi-politik di tingkat global. Hal ini merupakan upaya dari pengintegrasian negara kepada pasar global. Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) mendorong adanya perubahan sifat dan fungsi negara karena kekuasaan politik tersentral di pemerintahan pusat dianggap kurang efisien bagi beroperasinya pasar. Perubahan sifat dan fungsi negara tersebut mendorong adanya de-statisation (upaya mereduksi fungsi negara ke pasar) dan de-nationalisation (upaya rekonfigurasi kekuasaan negara ke tingkatan regional dan lokal). Agenda tersebut tidak hanya dijalankan di Indonesia saja, namun di negara-negara pasca otoritarian di kawasan Asia, seperti Thailand dan Filipina. Hadiz mendefinisikan kerangka perubahan sifat dan fungsi negara untuk memfasilitasi berjalannya logika pasar tersebut sebagai neo-institusionalisme. Salah satu bentuk bentuknya adalah desentralisasi, yang merupakan manifestasi dari lokalisasi kekuasaan. Situasi yang demikian membutuhkan kondisi kemitraan kerja sejajar antara eksekutif dan legilatif daerah. Dalam konteks itulah dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2003 yang sejatinya ditujukan untuk membatasi kekuasaan legislatif sebagai aktor politik lokal untuk meminimalisir ruang gerak ‘raja-raja kecil’ yang kerap kali menjadikan eksekutif daerah sangat lemah. Di sisi lain, sistem desentralisasi membutuhkan perombakan mentalitas kerja birokrat yang selama ini berorientasi atasan dan kekuasaan sehingga tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Walaupun regulasi sudah dilahirkan, otonomi daerah ideal masih membutuhkan jalan panjang. Menurut Hasrul Hanif, ide pemenuhan hak asasi manusia jangan hanya terjebak pada implementasi ke produk hukum, melainkan pada tingkatan budaya hukumnya. Hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintahan demokrasi baru, pasalnya konsep pelayanan publik dan pemenuhan hak warga belum sepenuhnya melekat dalam birokrasi di era otonomi daerah. “Kondisi riilnya adalah konsep hak asasi manusia belum menjadi norma sosial. Cara pandang terhadap pemenuhan HAM masih sangat formalistik dalam bentuk produk hukum nyata, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut implementasi nyata,” ujar Hanif. Padahal desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan penghormatan serta pemenuhan hak warga negara. Menurut United Nations Development Program (UNDP), desentralisasi seharusnya mampu menstimulasi pencarian program dan inovasi kebijakan yang dilakukan secara independen oleh pemerintah daerah. Meskipun variasi kebijakan sangat dimungkinkan, tetapi ide pemenuhan belum banyak diimplementasikan di berbagai daerah. Bagi Hanif, hal ini disebabkan karena cara pandang pemenuhan HAM masih sangat populis dan tergantung dengan individu serta kondisi politik kepala daerah, tanpa secara menyeluruh dimaknai sebagai sistem kerja birokrasi di Indonesia. Dampaknya pemenuhan HAM menjadi tidak merata sekalipun sudah dimandatkan dalam RPJMN dan RPJMD. Hal yang lain dari kekuasaan yang makin terlokalisasi, menurut Hadiz, adalah membuat jaringan oligarki lama yang merupakan Orde Baru memanfaatkan ruang politik lokal. Karakter mereka tetap sama, yaitu merampok sumber daya ekonomi politik publik melalui kekuasaan. Dalam bahasa lain, elemen-elemen itu tetap hidup dengan bentuk jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain. Kekuatan ini yang kemudian membajak agenda desentralisasi sehingga terbentuk problem-problem lain, seperti politik uang (money politics), tumbuhnya kekuatan koersi preman dan KKN semakin tumbuh subur. Marajalelanya praktek korupsi di tingkat lokal akibat pembajakan elemen-elemen tersebut dapat terlihat dari penanganan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika melihat data KPK tentang penanganan korupsi berdasarkan instansi tahun 2004-2016 menunjukkan bahwa peringkat 1 masih diduduki oleh Kementerian/Lembaga dengan 225 kasus. Namun kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten/pemerintah kota menempati urutan kedua dengan 109 kasus, sementara pemerintah provinsi menempati urutan ketiga dengan 82 kasus. Sedangkan DPR dan DPRD menempati peringkat keempat dengan 46 kasus dan BUMN/BUMD menempat urutan kelima dengan 32 kasus. Norma Hukum dan Partisipasi Masyarakat Masih Relevan Untuk Menagih Janji Meskipun secara substansial dan implementasi suatu kebijakan masih semerawut, tetapi legitimasi secara hukum jelas masih diperlukan. Terutama dalam konteks pemenuhan hak asasi warga, hal ini tidak hanya memberikan patokan jelas terkait posisi kekuatan di mata hukum, tetapi hal ini juga dalam rangka menciptakan suasana demokratis bagi masyarakat untuk terus melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Kejelasan secara hukum ini diuraikan Herlambang sebagai sebuah penegasan posisi klaim hukum. Mengimplementasikan setiap pemenuhan hak asasi dalam bentuk hukum dapat mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah. “Misalnya APBD yang dituangkan dalam Perda, dapat diuji publik dalam proses perancangannya hingga produk hukum tersebut disahkan. Atau Perda yang bertentangan dengan kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia, maka sangat potensial untuk diuji publik dan dibatalkan,” jelas Herlambang. Dengan demikian implementasi pemenuhan hak warga dalam bentuk norma hukum masih dibutuhkan dengan tujuan mendorong pemerintah dalam melaksanakan kewajiban evaluasi. “Oleh sebab itu bentuk hukum untuk pemenuhan hak warga masih diperlukan dalam rangka menegaskan kewajiban evaluasi dan pertanggungjawaban, agar bisa ditingkatkan kemajuan di masa depan,” tambahnya Ruang uji publik tersebut menjadi efektif dalam suasana yang demokratis. Desentralisasi secara prinsipil tidak dapat dipisahkan dari karakteristik demokrasi partisipatoris yang bersanding dengan akuntabilitas, edukasi, dan obligasi. Tujuannya tidak lain adalah menerapkan sebuah strategi yang mengandung unsur keadilan sosial bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan kembali oleh Hasrul Hanif, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurutnya desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari dari ruang publik yang besar untuk mengontrol kebijakan pemerintahan. “Desentralisasi membutuhkan kontrol publik yang besar. Dalam artian pemerintah harus menciptakan suasana demokratik yang kondusif yaitu membuka aksesibilitas bagi masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah,” jelas Hanif yang dihubungi melalui telepon bulan Juni 2016 lalu. Fungsi legislasi dan pengawasan yang dimiliki DPRD seharusnya mampu menjadi karpet merah menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat. Mulai dari kewenangan menciptakan kebijakan yang melegitimasi pemenuhan hak rakyat hingga implementasinya melalui anggaran daerah. Secara khusus, UU Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengakui dan melegitimasi peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dalam Pasal 354 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pemerintah daerah harus mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan keterlibatan publik secara efektif. Partisipasi publik tersebut dapat mencakup penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang membebani masyarakat, proses perencanaan hinga pengevaluasian daerah, hingga pengelolaan aset dan penyelenggaraan publik. Meskipun secara hukum sudah memiliki legalitas, partisipasi publik untuk terlibat dalam kinerja pemerintah belum populer. Dampaknya kebijakan yang inkonstitusional dan tidak berpihak pada rakyat terus dilahirkan. Dalam konteks itulah perspektif pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak warga menjadi penting termasuk bagi publik. Menurut Hasrul Hanif, konsep hak asasi manusia belum menjadi public concern. Cara pandang yang sangat populis dan parsial sebatas tokoh kepala daerah merupakan langkah lambat untuk menjadikan hak asasi sebagai norma sosial. “Publik sesungguhnya punya peran untuk mendorong pemerintah. Publik harus mulai menjadikan HAM sebagai dasar memilih wakil rakyat. Dalam artian HAM harus menjadi indikator bagi masyarakat. Hanya saja hal ini belum menjadi kesadaran bagi kebanyakan masyarakat,” jelas Hanif. Kesadaran warga akan haknya dapat melahirkan suasana yang lebih demokratis dan mampu memberikan dorongan lebih besar bagi kinerja pemerintah. Dengan demikian publik bisa melakukan kontrol dan membuka relasi antara negara dan masyarakat. Sementara bagi Hadiz, walaupun desentralisasi telah dibajak, namun kontestasi politik di tingkat lokal juga memberikan peluang bagi gerakan rakyat untuk mulai bereksperimen menjajal arena kontestasi tersebut. Selain sebagai upaya untuk memutus kekuatan oligarki di tingkat lokal dan memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia, eksperimen tersebut juga dimanfaatkan untuk belajar memahami seluk beluk sistem pemerintahan itu sendiri.