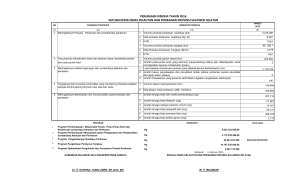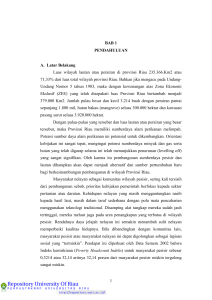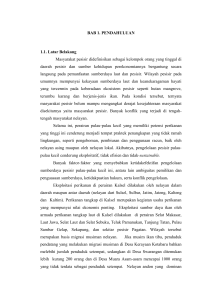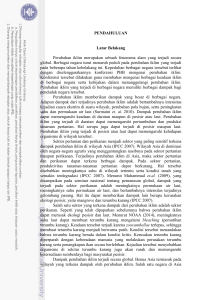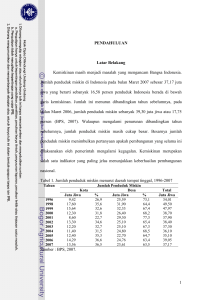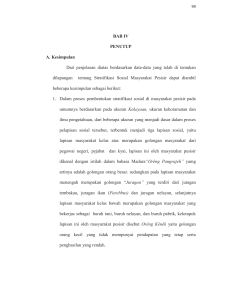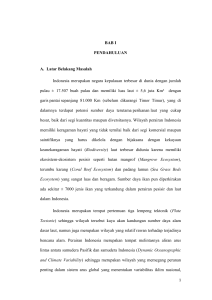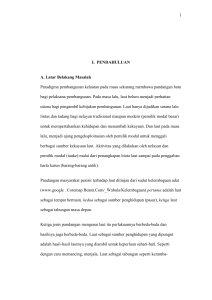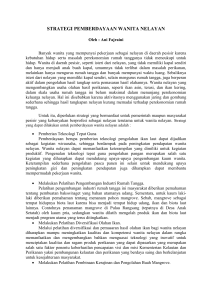Seharusnya Laut Memerdekakan
advertisement
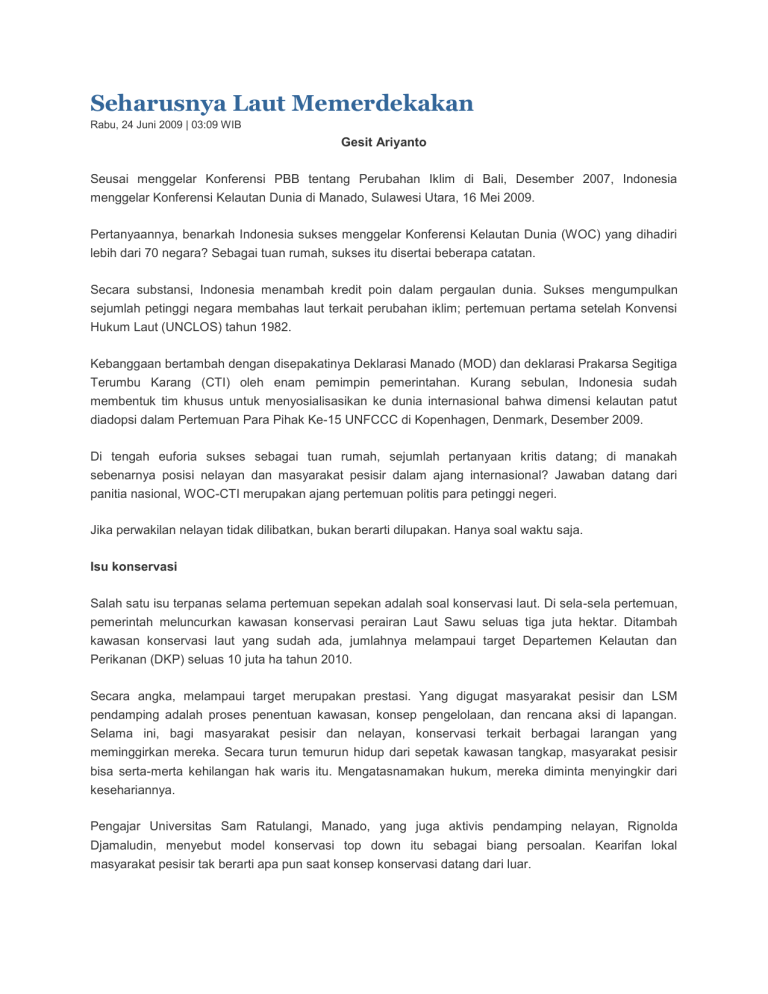
Seharusnya Laut Memerdekakan Rabu, 24 Juni 2009 | 03:09 WIB Gesit Ariyanto Seusai menggelar Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali, Desember 2007, Indonesia menggelar Konferensi Kelautan Dunia di Manado, Sulawesi Utara, 16 Mei 2009. Pertanyaannya, benarkah Indonesia sukses menggelar Konferensi Kelautan Dunia (WOC) yang dihadiri lebih dari 70 negara? Sebagai tuan rumah, sukses itu disertai beberapa catatan. Secara substansi, Indonesia menambah kredit poin dalam pergaulan dunia. Sukses mengumpulkan sejumlah petinggi negara membahas laut terkait perubahan iklim; pertemuan pertama setelah Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Kebanggaan bertambah dengan disepakatinya Deklarasi Manado (MOD) dan deklarasi Prakarsa Segitiga Terumbu Karang (CTI) oleh enam pemimpin pemerintahan. Kurang sebulan, Indonesia sudah membentuk tim khusus untuk menyosialisasikan ke dunia internasional bahwa dimensi kelautan patut diadopsi dalam Pertemuan Para Pihak Ke-15 UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, Desember 2009. Di tengah euforia sukses sebagai tuan rumah, sejumlah pertanyaan kritis datang; di manakah sebenarnya posisi nelayan dan masyarakat pesisir dalam ajang internasional? Jawaban datang dari panitia nasional, WOC-CTI merupakan ajang pertemuan politis para petinggi negeri. Jika perwakilan nelayan tidak dilibatkan, bukan berarti dilupakan. Hanya soal waktu saja. Isu konservasi Salah satu isu terpanas selama pertemuan sepekan adalah soal konservasi laut. Di sela-sela pertemuan, pemerintah meluncurkan kawasan konservasi perairan Laut Sawu seluas tiga juta hektar. Ditambah kawasan konservasi laut yang sudah ada, jumlahnya melampaui target Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) seluas 10 juta ha tahun 2010. Secara angka, melampaui target merupakan prestasi. Yang digugat masyarakat pesisir dan LSM pendamping adalah proses penentuan kawasan, konsep pengelolaan, dan rencana aksi di lapangan. Selama ini, bagi masyarakat pesisir dan nelayan, konservasi terkait berbagai larangan yang meminggirkan mereka. Secara turun temurun hidup dari sepetak kawasan tangkap, masyarakat pesisir bisa serta-merta kehilangan hak waris itu. Mengatasnamakan hukum, mereka diminta menyingkir dari kesehariannya. Pengajar Universitas Sam Ratulangi, Manado, yang juga aktivis pendamping nelayan, Rignolda Djamaludin, menyebut model konservasi top down itu sebagai biang persoalan. Kearifan lokal masyarakat pesisir tak berarti apa pun saat konsep konservasi datang dari luar. Keanehan yang sering muncul, kawasan konservasi (yang identik pelarangan aktivitas) ada di bekas kawasan tangkap nelayan tradisional. Artinya, mereka dipaksa pergi dan mencari lokasi lain. Ketika nelayan-nelayan tradisional kembali menangkap di kawasan lama itu, serta-merta mereka dicap pelanggar kawasan. ”Pada saat itulah mereka dikriminalkan,” kata Rignolda. Sebaliknya, proses pengambilalihan hak masyarakat pesisir oleh pemerintah atau rekanan resmi pemerintah tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Bila ditelaah, cara-cara penetapan kawasan dan pengelolaan kawasan konservasi semacam itu justru melanggengkan kemiskinan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Di tengah kondisi itu, masyarakat Lamalera di Pulau Lembata, NTT, memilih menolak rencana pemerintah memasukkan kawasan lautnya ke dalam kawasan konservasi. Bila mereka setuju, luas kawasan konservasi Laut Sawu menjadi lebih luas lagi. Juru Bicara Forum Masyarakat Peduli Tradisi Penangkapan Ikan Paus Lamalera Bona Beding mengatakan, masyarakat tahu risiko yang akan dihadapi. Maka, mereka mengirim surat resmi penolakan kepada pemerintah. Suara dari bawah Seperti harapan wajar masyarakat pesisir, pesan penolakan warga Lamalera jelas; dengarkan suara dari bawah. Mereka tak menolak konsep konservasi, tetapi meminta negara mendengarkan dan mencerna konsep konservasi tradisional mereka. Apa yang terjadi di sela-sela WOC semoga tidak mewakili sikap negara, yakni menolak suara masyarakat pesisir. Seperti diberitakan, polisi membubarkan aksi massa Aliansi Manado dan menangkap dua tokohnya. Sebanyak 15 peserta kongres dari Filipina juga digiring ke Kantor Imigrasi dan diusir dari Manado. Di persidangan, kedua tokoh aktivis Aliansi Manado dituding melawan perintah petugas yang bekerja di bawah undang-undang. Perlu dicerna pernyataan anggota Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim dan Penasihat Khusus Presiden Seychelles Rolph Payet, pembahasan kelautan tanpa menyinggung keseharian nelayan adalah sia-sia. Nelayan tak hidup bagi diri sendiri. Kepada mereka, gizi keluarga, yang berguna bagi kecerdasan manusia, disandarkan. Sayang, justru mereka tergolong paling rentan dalam persoalan laut sekaligus luput dari perhatian soal kesejahteraan. Tak hanya di negara kepulauan kecil seperti Seychelles, nasib nelayan dalam kerentanan. Di Indonesia, enam kali pergantian presiden, nasib nelayan tak bergerak; sebatas jadi obyek perhatian musim kampanye. Laut yang luar biasa kaya, tak cukup memerdekakan nelayan dan masyarakat pesisir dari ketergantungan dan kemiskinan. Sebaliknya, laut menjadi semacam kutukan hidup. Sah-sah saja Indonesia bangga karena sukses menjadi tuan rumah ajang kelautan besar dunia. Namun, itu saja tidak cukup. Ada masyarakat pesisir, yang entah harus bersuara seperti apalagi agar benar-benar diperhatikan.