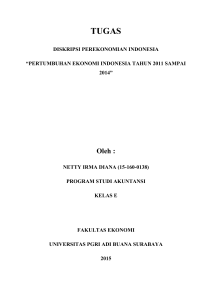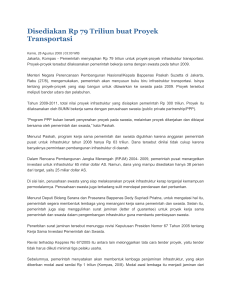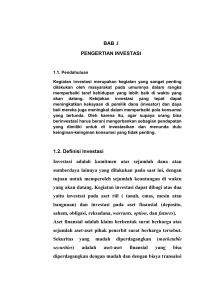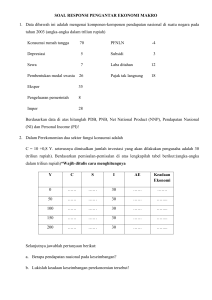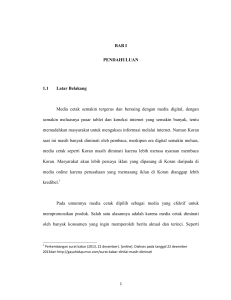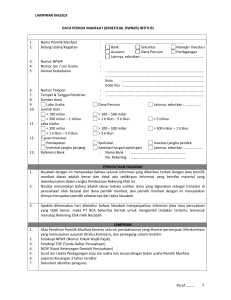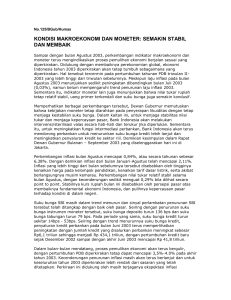Kualitas Belanja, Kinerja, dan Daya Saing Indonesia
advertisement

Kualitas Belanja, Kinerja, dan Daya Saing Indonesia Oleh Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan* Berdasarkan Global Competitiveness Report 2014-2015 yang disampaikan oleh World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 di posisi 38. Kondisi ini tentu menjadi modalitas yang positif bagi pemerintahan yang baru, khususnya menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompetitif. Dilihat dari sejarahnya, posisi Indonesia pada tahun 2009 masih tercatat di peringkat 54 dari 133 negara, meningkat ke posisi 44 dari 139 negara di tahun 2010. Sayangnya, posisi tersebut sedikit mengalami kemerosotan di tahun 2011 menjadi posisi 46 serta 50 di tahun 2012. Dengan beberapa perbaikan yang gencar dilakukan pemerintah, tahun 2013 posisi Indonesia kembali melesat ke peringkat 38. Dicapainya posisi tersebut tak pelak menjadikan Indonesia kembali diperhitungkan dalam percaturan ekonomi dunia, sebagaimana yang telah dipidatokan mantan Presiden SBY dalam pidato Nota Keuangan 2015, dimana secara tegas Bank Dunia sudah memasukkan Indonesia dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan metode perhitungan Purchasing Power Parity (PPP). Dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,8% dalam periode 10 tahun terakhir, pengelolaan ekonomi makro yang makin prudent, ditambah kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, pencapaian tersebut memang sudah selayaknya. Namun demikian pemerintah tetap wajib memperhatikan beberapa aspek yang masih menjadi catatan, khususnya terkait dengan persoalan kesenjangan dan ketimpangan beberapa faktor dan indikator daya saing tersebut. Secara umum, penilaian terhadap indikator infrastruktur dan konektivitas mengalami perbaikan di posisi 56, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator lainnya yang menunjukkan kriteria positif adalah indikator kualitas hubungan antara pemerintah dan swasta, melompat hingga 14 peringkat di posisi 53, begitupula indikator efisiensi pemerintahan yang berada di ranking 36. Sayangnya, untuk beberapa indikator lainnya, justru memperlihatkan fakta yang berkebalikan. Tingkat korupsi di Indonesia dinyatakan masih dalam kondisi yang membahayakan, berada di peringkat 87. Meskipun pemerintah sudah mengupayakan pemberantasan korupsi di berbagai tingkatan, dampak yang ditimbulkan ternyata masih sangat minim khususnya bagi upaya mendongkrak daya saing. Persoalan defisit anggaran juga masih membebani indikator makro ekonomi. Sebagai sebuah indikator, kemampuan mengelola defisit anggaran ini memang sering dijadikan tolak ukur kinerja utama pemerintah. Defisit yang terkendali, tentu memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi pemerintah. Sebaliknya defisit yang bergejolak, selain membahayakan kondisi stabilitas fiskal, juga menimbulkan potensi penarikan pembiayaan hutang luar negeri. Mengutip data pemerintah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kemampuan mengendalikan defisit anggaran sebetulnya relatif memuaskan. Tahun 2007 misalnya, defisit anggaran dapat dijaga di level 1,3% PDB atau senilai Rp50,1 triliun, sementara tahun 2009 stabil di level 1,6% PDB atau Rp88,6 triliun. APBN-P 2011 pun mencatat realisasi defisit anggaran 2,1% PDB, sementara tahun 2013 sebesar 2,38% dan 2014 sebesar 1,69% PDB. Problem besar lainnya terkait persoalan ketenagakerjaan, dimana indikator pasar tenaga kerja Indonesia turun sampai 7 peringkat di posisi 110, dengan tingkat partisipasi pekerja wanita menempati peringkat 112. Sektor lain yang juga mendapat perhatian serius adalah masalah kesehatan publik. Mudahnya penyebaran wabah penyakit, ditambah infant mortality yang masih tinggi, menjadikan Indonesia berada di level yang sama dengan kawasan Sub–Sahara Afrika, di ranking 99. Indikator kesiapan teknologi juga tergolong rendah, menempati peringkat 77, aspek penggunaan teknologi informasi di posisi 94. Jika disimpulkan, rekomendasi WEF menyebutkan bahwa indikator daya saing global Indonesia belum memperlihatkan hasil yang merata. Sejumlah indikator menunjukkan perbaikan yang cukup mengesankan, sejumlah indikator lain justru mengkhawatirkan. Beberapa indikator justru memperlihatkan kesan berkebalikan, misalnya indikator efisiensi pemerintah dengan indikator korupsi. Korupsi juga tercatat sebagai hambatan tertinggi dalam berbisnis di Indonesia, bersama dengan instabilitas kebijakan, persoalan hukum serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Problematika Berbagai uraian di atas tentu membutuhkan perhatian yang serius. Dan secara tidak langsung, ada hal yang cukup menarik ketika menyimak pidato kerakyatan Presiden tepilih Joko Widodo. Selain himbauan untuk saling bekerjasama dan sapaan untuk seluruh profesi, jargon kerja, kerja dan kerja sekiranya menjadi solusi yang ampuh bagi upaya memperbaiki berbagai indikator daya saing Indonesia yang masih memprihatinkan. Ditambah dengan kecepatan dan ketegasan Presiden, ke depannya daya saing Indonesia akan meningkat. Persoalannya, Presiden seorang tentu tidak mampu mewujudkan semua impian tersebut. Dibutuhkan kerjasama yang seimbang dari seluruh Menteri dan jajaran pembantu Presiden serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam jangka pendek, APBN 2015 dapat dijadikan dukungan yang utama. Pemerintah harus dapat menjadikan APBN sebagai enginee of growth melalui berbagai belanja yang berkualitas. Sayangnya, beberapa pihak justru mempertanyakan hal ini. Berdasarkan data pemerintah, hingga 29 Agustus 2014, realisasi belanja negara mencapai 55,9% atau sekitar Rp1.049 triliun dari pagu 1.876,9 triliun APBN-P 2014. Dari besaran tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 53,4% atau Rp683,9 triliun sementara transfer ke daerah 61,2% atau sekitar Rp365,3 triliun. Di dalam komponen belanja pemerintah pusat, realisasi pembayaran kewajiban utang mencapai 63,6% atau Rp86,2 triliun dari pagu Rp135,5 triliun. Disusul realisasi belanja subsidi 61,7% atau Rp248,5 triliun, belanja pegawai sebesar Rp164,8 triliun atau 63,8%, belanja bantuan sosial 53,1% atau Rp51,4 triliun dan belanja barang Rp82,6 triliun atau 42,3%. Fakta realisasi belanja modal yang baru mencapai 30,2% atau Rp48,6 triliun, mungkin patut menjadi keprihatinan bersama. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tersebut relatif hampir sama. Hingga 30 Agustus 2013, realisasi belanja negara mencapai 54,8% atau sekitar Rp945,8 triliun dari pagu Rp1.726,2 triliun dalam APBN-P 2013. Realisasi belanja pemerintah pusat sendiri mencapai Rp615,6 triliun atau 51,4% sementara transfer ke daerah mencapai Rp330,1 triliun atau 62,4%. Dalam komponen belanja pemerintah pusat, realisasi pembayaran kewajiban utang mencapai 64,8% atau Rp72,9 triliun, disusul belanja subsidi 61,1% atau Rp212,8 triliun, belanja pegawai Rp152,6 triliun atau 65,5%, belanja bantuan sosial Rp45,7 triliun atau 55,4% serta belanja barang Rp70,0 triliun atau 33,9%. Realisasi belanja modal kembali yang paling rendah sekitar Rp60,6 triliun atau 31,4%. Jika ditarik data 5 tahun ke belakang pun, sepertinya pola realisasi belanja negara masih akan tetap sama. Pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja barang selalu mendominasi, sementara belanja modal selalu tertinggal. Fakta ini tentu menyiratkan adanya persoalan serius serta wajib dicermati oleh pemerintahan baru, mengingat secara teori, di beberapa negara berkembang, peran dari belanja modal pemerintah masih menjadi penggerak utama. Hal ini jelas berkaitan dengan minimnya peran swasta serta lembaga perbankan yang seharusnya menjadi penggerak utama laju modernisasi di negara tersebut. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran pemerintah tentu bukan menjadi bentuk dukungan yang memadai bagi upaya mendongkrak posisi daya saing bangsa. Begitupula kinerja aparat pemerintah yang masih melestarikan budaya birokrasi dan administrasi yang ”serba sulit”. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Presiden di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanyalah satu dari serangkaian niat tulus pemerintah untuk terus memperbaiki iklim usaha yang pro investasi demi mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, juga harus terus dievaluasi, khususnya yang terkait dengan misi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Reformasi juga perlu dilakukan di dalam sistem penganggaran, dimana asumsi ”anggaran yang besar akan mendorong kinerja yang lebih baik" adalah tidak 100% tepat. Untuk K/L yang sudah mendapatkan alokasi anggaran besar, tapi ternyata kinerjanya masih jalan di tempat, Pemerintah harus berani untuk memberikan hukuman meski harus berhadapan dengan regulasi hukum demi tercapainya asas keadilan dan pemerataan. Ingat kegagalan dalam menciptakan kinerja pelayanan publik yang handal, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakberhasilan pemerintah mengemban amanat masyarakat. *) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja