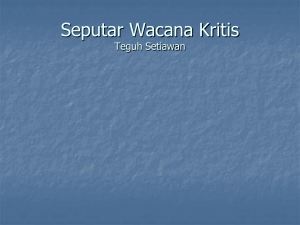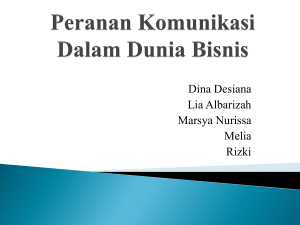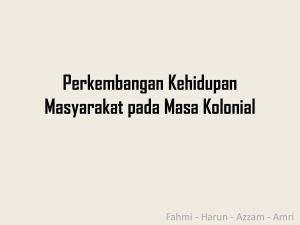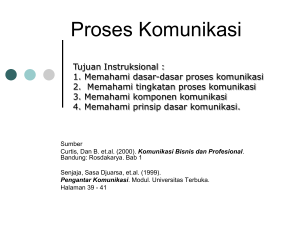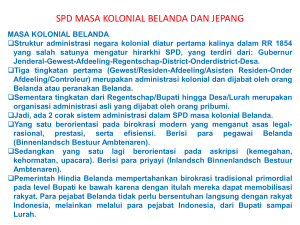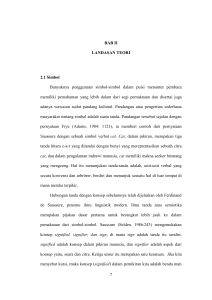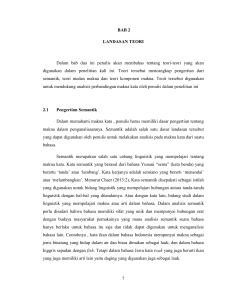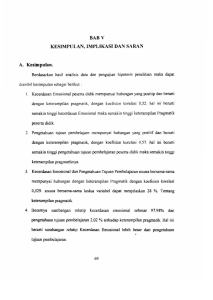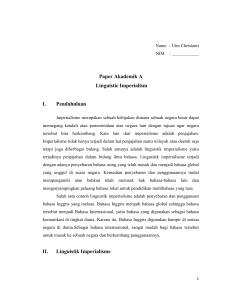View/Open - Repository | UNHAS
advertisement

Usulan Penelitian ANALISIS SEMANTIK TEKS-TEKS KOLONIAL DI INDONESIA THE SEMANTIC ANALYSIS OF THE COLONIAL TEXTS IN INDONESIA Disusun dan Diajukan oleh Ade Yolanda Latjuba PO 300309002 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2011 1 BAB I PENDAHULUAN A. Konteks Penelitian Penelitian yang memfokuskan perhatian pada kebermaknaan teks-teks kolonial ini bermula pada keingintahuan akan realitas sosial yang ada di balik teks-teks yang diproduksi. Teks sebagaimana diketahui umum dapat berarti verbal, tetapi dapat juga nonverbal, seperti pertunjukkan suatu tarian. Dari awal tarian itu mulai hingga berakhirnya tarian tersebut dapat dianggap sebagai satu teks, namun itu berarti kita membicarakan teks dengan pengertian khusus. Adapun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, adalah pengertian teks sebagaimana yang umum dipahami. Secara umum teks dipahami lewat bentuknya, yaitu teks tertulis (written text) dan teks ujaran (spoken text), namun ujaran akan menjadi teks tertulis bila ia telah didokumentasikan secara tertulis. Dokumen tertulis oleh sebagian ahli digunakan untuk merujuk pada hal yang sama sebagaimana yang dirujuk oleh wacana (discourse). Kedua istilah ini, teks dan wacana tidak lain merujuk pada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di sini dapat diidentifikasi mulai dari tahap (level) kata hingga kalimat dan klausa –kalimat yang lebih rumit-. Namun, tidak tertutup 2 kemungkinan adanya pemahaman lain mengenai teks dan wacana. Ini terjadi karena ada yang beranggapan bahwa teks yang merupakan fakta material dari gagasan (notion) yang ingin disuarakan, mengambil bentuknya yang konkret dalam wujud bahasa di atas kalimat dan klausa. Wacana, dalam wujudnya yang abstrak dapat berupa ide, gagasan, pemikiran, yang bila diaktualisasikan dalam bentuk teks, dapat muncul dalam bermacam-macam bentuk (discursive forms). Jadi, bila ingin menganalisis suatu wacana tertentu, sudah selayaknya kita menaruh perhatian pada berbagai bentuk teks agar dapat diperoleh pemahaman menyeluruh akan wacana yang dimaksud. Karena analisis wacana merujuk pada penggunaan bahasa maka unit linguistik terkecil yang dapat dianalisis adalah kata. Kata, dalam pandangan strukturalis, merupakan pertautan antara satu tanda (sign) dengan tandatanda lain (other signs) yang membentuk satu tanda yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari citraan bunyi (sound images). Pemahaman penganut aliran rationalisme mengatakan bahwa bahasa yang merupakan manifestasi dari citraan bunyi, keterkaitannya dengan tanda yang diwakili bersifat semena-mena (arbitrary). Tidak ada satu alasan pun yang mampu menjelaskan mengapa penutur bahasa Indonesia memilih perlambangan yang diwakili oleh alfabet Latin m e r a h untuk sesuatu konsep yang merupakan hasil persepsi inderawi terhadap keadaan nyata yang berbeda dari keadaan lainnya, misalnya k u n i n g atau p u t i h. Sementara penuturpenutur bahasa lain lebih suka memilih perlambangan dengan huruf Latin 3 r o o d atau r e d untuk konsep atau ide yang sama. Semua ini menunjukkan bahwa sumber pengetahuan primer manusia tidak terletak pada empiri atau pengalaman yang diserap lewat indera, tetapi sudah ada disediakan oleh rede atau akal / pikiran, yang dalam bahasa masa kini sering dirujuk dengan kata kognisi. Kesadaran akan pemahaman ini, dapat dijelaskan dengan merujuk pada hasil pemikiran Ferdinand de Saussure (1857-1913), penggagas Strukturalisme modern, yang mengaitkan citraan bunyi dengan tanda yang arbitrer tanpa harus keluar dari lingkungan mind tiap-tiap penutur. Gagasan De Saussure ini menjelaskan pula bahwa citraan bunyi yang terbentuk dari suatu tanda bahasa sebenarnya merujuk pada konsep atau gambaran pikiran yang ada di kepala tiap-tiap penutur, dan tidak merujuk pada objek atau referen yang berada di luar, dalam dunia realitas. Kedekatan antara tanda bahasa dan gambaran pikiran ini seolaholah menyatu, berhimpitan, sampai-sampai sukar untuk dipisahkan. Sementara keberadaan gambaran pikiran atau konsep ini hanyalah merupakan hasil kesepakatan bersama (convention) masyarakat penutur suatu bahasa. Dengan memahami konsep De Saussure akan kearbitreran hubungan satu tanda dengan apa yang diwakilinya, maka dapat diturunkan pemahaman bahwa tanda (baca: kata) pada hakikatnya tidak memiliki beban atau content yang mengandung muatan-muatan positif ataupun negatif, karena ia 4 diturunkan dari suatu pemikiran murni yang dibawa manusia sejak lahir. Keadaan ini berlaku bila kedekatan antara tanda dan apa yang diwakilinya berdiam hanya dalam pikiran penuturnya. Keadaan sebaliknya terjadi bila tanda (baca: kata) telah keluar dari ‘tempat persembunyiannya’ yaitu pikiran dan digunakan oleh pemiliknya. Kedekatan antara tanda bahasa dan gambaran pikiran - antara signifiant dan signifié - dapat disetarakan dengan kedekatan antara kata dan makna (meaning), sehingga dengan ini dapat diduga bahwa hubungan antara kata dan makna seyogianya juga bersifat tanpa beban, artinya tidak mengandung muatan-muatan penilaian. Kenyataan yang ditemui menyajikan banyak kata yang dituturkan atau yang diungkapkan dalam bentuk tulisan menimbulkan ketersinggungan pendengar atau pembacanya. Hal ini mengindikasikan bahwa kata-kata itu telah aktif digunakan dan tidak hanya berdiam di dalam kepala penutur. Bukan hanya itu, banyak faktor yang dapat menjadikan kata dimaknai lebih meluas. Menurut Roeffaers (2004: 30), De Saussure pun mengakui adanya penyatuan antara bentuk tanda dengan maknanya, namun ia tidak membahas masalah signification, ia justru berbicara mengenai nilai (valeur) yang dikandung oleh suatu tanda, yang merupakan bagian dari sistem bahasa (langue). Kata, ketika digunakan akan terkait dengan kata-kata lain, yang kemudian akan memunculkan makna (meaning). Begitu pula yang dipahami 5 wacana analitis (analitical discourse), ketika kata telah digunakan, baik secara tertulis ataupun tertutur, maka ia akan menunjuk, merefleksikan, atau mengasosiasi sesuatu kenyataan di luar dirinya. Pada ruang inilah penggunaan kata tidak akan bebas dari pemaknaan. Sebagai contoh, pada permulaan tahun 2011 lalu, medio bulan Januari, media massa luar negeri dan Indonesia banyak memberitakan ketersinggungan pihak-pihak tertentu akibat penggunaan kata-kata tertentu. Kata-kata itu adalah blood libel (“fitnah darah”) yang digunakan Sarah Palin, politisi dari Partai Republik AS, dalam pernyataannya menanggapi ditembaknya politisi dari Partai Demokrat AS yang berketurunan Yahudi, Gabrielle Giffords, oleh seseorang di Tucson, Arizona, AS, ketika sedang mengadakan pertemuan dengan para konstituennya di pelataran sebuah Mall (Kompas, 10 dan 15 Januari 2011). Pernyataann Palin yang menggunakan kata “fitnah darah” ini, telah menimbulkan ketersinggungan banyak orang, terutama mereka yang memiliki darah keturunan bangsa Yahudi. Ini terjadi karena ketika kata tersebut digunakan, ia tidak bebas dari pemaknaan; dengan melihat konteks yang ada, maka ia dapat menunjuk, mengasosiasi pada suatu kenyataan yang ada atau yang pernah ada. Bagi yang memahami sejarah bangsa Yahudi, kata ini mengingatkan mereka pada peristiwa kelam di Abad Pertengahan, saat bangsa Yahudi pernah mengalami fitnah yang dilakukan oleh Kristen Eropa. Fitnah yang disebarkan berupa rumor ini, mengisukan bahwa orang-orang 6 Yahudi masih melakukan ritual pengorbanan manusia. Karena itu, mereka dituduh menculik anak-anak Kristen guna dijadikan korban persembahan. Sebagai akibat dari fitnah tersebut, banyak orang Yahudi ketika itu ditindas, disiksa, bahkan dibunuh. Peristiwa kelam ini rupanya telah menjadi beban yang dimuat oleh kata blood libel itu sendiri, terutama bagi masyarakat yang telah menyimpannya dalam ingatan mereka. Sebenarnya, faktanya kata itu biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris yang merujuk pada orang yang difitnah (Kompas, 15 Januari 2011 “Fitnah Darah” Jejak Sejarah Kelam Anti-Semitisme di Eropa, 9), tetapi bila digunakan pada konteks tertentu ia akan memiliki dampak karena dimaknai berbeda dari makna yang sudah ada sebelumnya. Pemaknaan kata sebagaimana contoh di atas, merupakan pandangan poststrukturalis. Poststrukturalis memiliki pandangan yang bertitik tolak dari pandangan strukturalis, tetapi dengan sedikit modifikasi. Poststrukturalis mengambil ide strukturalis, bahwa tanda menurunkan (derive) maknanya tidak melalui relasinya terhadap kenyataan (reality) tetapi melalui relasi intern dalam jaringan tanda itu sendiri, namun ia menolak pandangan strukturalis terhadap bahasa sebagai suatu struktur yang stabil (stable), tidak dapat diubah (unchangeable), dan total (totalising). Bagi poststrukturalis, tanda tetap memperoleh (acquire) maknanya lewat pembedaan dari tanda lain, tetapi tanda yang membedakannya dari yang lain itu dapat berubah menurut 7 konteksnya (Phillips, L and Jorgensen, M.W., 2004:9-11). Jadi, bahasa bukan hanya merupakan saluran di mana informasi mengenai pernyataan mental dan perilaku atau fakta mengenai dunia dikomunikasikan, melainkan juga merupakan ‘mesin’ yang menggeneralisasi, dan sebagai hasilnya bahasa juga menetapkan dunia sosial. Contoh lain yang menjelaskan bahwa hubungan antara bahasa dan realita juga bersifat arbitrer, satu poin yang dikembangkan oleh teori strukturalisme yang datang kemudian dan juga poststrukturalisme. Teori strukturalisme menerima pandangan bahwa makna tanda individual dideterminasi (determined) oleh relasinya terhadap tanda-tanda lain, atau suatu tanda memperoleh maknanya karena berbeda dari tanda lain. Sebagai contoh kata berbahasa Belanda aap ‘monyet’, kata ini bermakna karena ia berbeda dari kata-kata lain misalnya geit ‘kambing’, buffel ‘kerbau’, muis ‘tikus’, kat ‘kucing’ dst. Kata aap ini merupakan bagian dari jaringan (network) atau struktur kata yang menjadikannya berbeda dari struktur kata lain yang tidak memberikannya makna ‘aap’ sebagai hewan berkaki empat yang ‘terampil’. Tidak hanya itu, ia juga menampakkan bentuk yang berbeda dalam bahasa-bahasa yang berbeda, misalnya: monyet dalam bahasa Indonesia, monkey atau apes, la signe, der affe dalam bahasa-bahasa lain. Penjelasan ini berimplikasi pada hubungan antara bahasa dan kenyataan; bukan dunia yang mendikte kata yang dengan ini dunia digambarkan, 8 sebagaimana sudah dikatakan, ini hanyalah hasil kesepakatan masyarakat pemakai bahasa. Meski demikian, muatan tanda itu selalu berubah bila diterapkan pada situasi lain, contohnya ketika dikatakan pada seseorang bahwa dia “als een klein nietswaardig aapmenschje”1, maka reaksinya tentu tidak sekedar memahami sebagai makna biasa, yang arbitrer, yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan, tetapi sudah mengandung muatan mendeskriditkan, ‘mengecilkan’: aapmenschje adalah manusia yang dipersamakan dengan monyet. Bahasa adalah istilah yang paling umum digunakan untuk merujuk pada apa yang disebut sebagai ‘bahasa-bahasa alamiah’, yakni bentuk komunikasi yang digunakan makhluk manusia. Dalam linguistik istilah ini diperluas dengan mengacu pada proses berpikir manusia dalam menciptakan dan menggunakan bahasa. Sesungguhnya, proses berpikir manusia tidak selalu harus menggunakan bahasa (Callow, 1998:8), karena dalam keadaan normal sehari-hari, tak jarang manusia pun berpikir secara non-verbal, misalnya ketika kita tengah menggumam beberapa baris nada 1 Kutipan ini diambil dari salah satu teks kolonial yang menjadi bahan penelitian dan dikutip sesuai aslinya dengan masih menggunakan ejaan lama. Kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut: …Dan tasten zijn handen naar de sarong en zwaait hij haar open en draait haar weer in nieuwe wrongen om het magere lijf. Teeken van eerbied voor de meerderen, en hij gaat hurken midden op ‘wegje en zit daar nu als een klein nietswaardig aapmenschje,omhangen met zijn djimats…(Zeggelen, M. van, 1920, Onderworpenen, Schetsen uit Celebes, p. 22-23) Terjemahannya: Kemudian tangannya menyentuh sarong dan dia membuka dengan mengibaskannya dan kembali melingkarkan dengan lipatan baru di sekeliling tubuhnya yang kurus. Tanda rasa hormat pada orang yang dianggap lebih, dan dia akan membungkuk di tengah jalan dan duduk di sana sekarang layaknya seorang manusia monyek, kecil, tidak berharga, dengan jimat menggantung. 9 lagu, lalu baris berikutnya kita lupa, maka beberapa saat kita akan berkonsentrasi mengingat nada yang tepat untuk ditampilkan ke permukaan dalam pikiran. Begitu pula, ketika kita sedang berpikir tentang warna tas yang cocok dengan gaun yang akan kita kenakan, kita akan berkonsentrasi sejenak, sebelum sampai pada keputusan. Semua kegiatan berpikir itu tidak menggunakan kata-kata, demikian juga bila kita mempelajari masalah geometri atau persamaan (equation) dalam matematika, pemikiran kita secara total terserap dalam relasi spasial dan numerik. Meskipun demikian, dalam pikiran kita tersedia sarana petanda yang memudahkan kita mengingat atau memunculkan kembali nada melodi yang terlupakan tadi, misalnya dengan melihat angka atau simbol yang tertera pada partitur. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa cara lain manusia berpikir adalah dengan mengeksploitasi tanda-tanda semiotik. Dalam menciptakan dan menggunakan sistem tanda secara sistematis, terutama dalam berbahasa, manusia secara mendasar perlu memperhatikan konsep linguistik tentang makna (semantik), struktur kalimat, dan tata bahasa, agar produk bahasa yang dihasilkan dapat dipahami. Konsep linguistik tentang makna dapat diklasifikasi dalam beberapa pengertian, yaitu konsep tentang makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Setiap kata memiliki medan semantik yang mencakup seluruh kemungkinan pemanfaatannya secara kontekstual dalam batas-batas 10 normal (sebagaimana dikutip dari Cruse, 2004: 199). Dari makna kontekstual diperoleh pengertian akan makna pragmatik, yaitu makna yang lebih memperhitungkan makna bahasa dalam penggunaannya (language in use) daripada makna leksikal kata secara terisolasi. Karena itu, dalam menganalisis wacana yang ada dalam teks, konteks mendapat porsi perhatian yang cukup besar. Chilton (2004:154, dalam: Blackledge, A., 2005:9) menunjukkan bahwa makna suatu teks tidak dimuat dalam teks itu sendiri, lebih dari itu pembaca atau pendengar membuat pengertian terhadap teks dengan jalan mengaitkannya dengan pengetahuan dan harapan-harapan mereka sebelumnya. Chilton memberi istilah konteks ini dengan ‘backstage knowledge’ pengetahuan di balik panggung yang pada dasarnya tidak terbatas, dan ditentukan tidak hanya lewat pengetahuan tetapi juga lewat ketertarikan (interest) dan anggapan (presumption) atau keyakinan pembaca. Bagi Van Dijk (2004) konteks wacana seharusnya tidak hanya didefinisikan dalam istilah situasi sosial tempat wacana itu terjadi, tetapi lebih dari itu sebagai representasi mental atau model mental. Model mental adalah interpretasi personal terhadap wacana oleh pengguna-pengguna bahasa individual, yang boleh digeneralisasikan sebagai pengetahuan umum tentang dunia. 11 Memahami keterkaitan bahasa yang ada dalam wacana dengan pikiran (kognisi) penggunanya, tentu tidak akan lepas dari memahami keterkaitan antara kata dan makna yang juga dianalogikan dengan kedekatan antara tanda bahasa dan gambaran pikiran (konsep). Kedekatan antara tanda bahasa dan gambaran pikiran membentuk satu kesatuan yang melahirkan makna literal, sedangkan gabungan dua kata atau lebih melahirkan makna figuratif, yang belum tentu merupakan gabungan makna literal dari masing-masing kata, karena bisa saja makna yang tercipta adalah sesuatu yang baru. Untuk mengetahui bagaimana hal tersebut dapat terjadi, pertama-tama harus disadari bahwa ilmu bahasa kognisi mengakui sebagian bahasa manusia kapasitas sudah dibawa sejak manusia lahir (ingeboren / innate), sebagaimana juga diakui oleh teori gramatika generatif Chomsky dengan konsep LAD (Language Acquisition Device) nya. Akan tetapi, menurut ilmu ini juga, sisa kapasitas bahasa lainnya diperoleh melalui serapan kenyataan dari luar dengan memberdayakan pengamatan indera dengan baik, sehingga diperoleh pengalaman yang menjadi pengetahuan. Keadaan ini memiliki kesamaan cara perolehan dengan pengetahuan lain selain bahasa, yang juga dimiliki manusia. Jadi, menurut ahli bahasa kognisi, bahasa merupakan proses perolehan (acquisition) sekaligus juga proses penyituasian dalam lingkungan khusus (gesitueerd in specifiek milieu). 12 Penelitian-penelitian bahasa yang berkenaan dengan kognisi manusia, telah banyak dilakukan orang, bahkan telah melahirkan teori-teori yang kerap dijadikan rujukan oleh peneliti lain, seperti misalnya proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan kognisi ini merupakan pengembangan dari pendekatan-pendekatan lama yang mungkin dirasa sudah tidak efektif lagi, misalnya pendekatan behaviorisme. Tidak hanya itu, pendekatan kognisi juga digunakan dalam ilmu pengetahuan bahasa (linguistik) dalam mengembangkan temuan-temuannya di bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik satu bahasa yang dahulu sesungguhnya telah ada, namun kini dirasa telah mencapai titik kejenuhan, sehingga pendekatan kognisi dilihat sebagai jalan keluar yang membawa kebaruan temuan. Untuk mencari tahu representasi mental pengguna bahasa dalam memahami dan mengekspresikan wacana yang diproduksi lewat teks, perlu memperhitungkan ketiga elemen yaitu wacana, bahasa, dan kognisi. Wacana didefinisikan secara luas berarti ide, gagasan yang bersemayam di benak, pikiran pemilik bahasa, yang dalam bentuknya yang konkret diwujudkan berupa ekspresi bahasa lisan (talk) atau bahasa tulisan berupa teks. Meskipun ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai batasan wacana, intinya memberikan pemahaman bahwa bahasa yang digunakan dalam wacana selalu memiliki intensi, maksud tertentu, apakah bentuknya berada di 13 “atas” klausa atau kalimat ataukah bisa hanya diwakili oleh kata atau kelompok kata, sebagaimana yang diyakini oleh Widdowson (2004). Dari batasan yang dikenakan pada wacana, dapat dilihat bahwa analisis yang dapat dilakukan padanya, meliputi analisis pada tataran kata hingga kalimat. Dalam wujudnya sebagai teks, wacana diorganisasi dari unit-unit linguistik yang memiliki makna khusus, karena essensi wacana adalah maksud atau intensi yang dikandungnya yang ingin dipersuasikan pada resipien agar dapat diproduksi ulang oleh penerima dalam bentuknya yang bermacammacam. Bentuk yang bermacam-macam (discursive forms) ini berimplikasi pada penggunaan kata yang memiliki makna ekuivalen, yang tujuannya adalah maksud semula tetap dapat disampaikan, atau dengan kata lain wacana berhasil direproduksi secara berantai. Tidak hanya itu, discursive forms juga dapat menampilkan diri dalam bentuknya yang total berlawanan. Semua ini merefleksikan bahwa bahasa dalam wacana memiliki keterkaitan dengan situasi sosio-historis dan sosio-kultural yang melatarbelakangi kemunculannya. Hal yang sama dapat dilihat pada wacana kolonial, khususnya wacana kolonial di Indonesia yang ditulis oleh pengarang-pengarang Belanda, yang eksis beberapa abad lalu. Teks-teks yang memproduksi dan mereproduksi wacana ini tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi dan keadaan ketika ia diproduksi. Karena keadaan ketika itu memperlihatkan situasi bahasa 14 multilingual, maka tidak heran bila kondisi itu tercermin di dalamnya: katakata dan kalimat-kalimat singkat berbahasa Perancis, Inggris, Jerman, bahkan terutama berbahasa Indonesia lama dan bahasa lokal setempat seperti bahasa Makassar turut menghiasi penggunaan bahasa Belanda yang boleh dibilang agak ouderwets dan telah ‘mengindonesia’ (verindisch) menurut pendengaran kebanyakan orang-orang Belanda masa kini. Situasi politik ketika itu juga turut mewarnai wacana yang ada, dan yang paling mudah diserap pembaca adalah gambaran kondisi sosio-historis yang mewakili zamannya. Gambaran yang ditampilkan adalah kehidupan dan aktivitas orang-orang Belanda yang kala itu dikenal dengan sebutan Hollander, di berbagai tempat di pedalaman hingga hutan-hutan di Hindia; suka duka menjalani kehidupan dengan sesama orang Belanda Totok (volbloed Hollander), dengan orang-orang Indisch, yakni orang-orang Belanda yang berdarah campuran pribumi yang biasa dikenal dengan nama orang Indo, hingga tantangan yang harus dihadapi karena perbedaan iklim dengan negara asal, terutama bagi Hollander yang baru tiba di koloni ini. Kehidupan yang eksklusif, megah di zamannya, terpisah dari kehidupan rakyat kebanyakan yang berlawanan bagaikan bumi dan langit dalam hal kemewahan; sketsa kehidupan yang menampilkan pemilik asli negeri ini, yang di mata para pendatang atau mereka biasa menyebut diri sebagai Indische gasten (tamu-tamu Hindia), hanya sebagai pelengkap penderita yang melayani, mempermudah berbagai aktivitas para tuan besar, sehingga 15 dengan demikian kehadiran para inlander, begitu mereka biasa disebut oleh para tamu Hindia ini, semakin memperkuat wacana kuasa yang dipertontonkan oleh orang-orang Holland yang berdarah asli Belanda. Mereka tidak hanya menguasai kehidupan penduduk asli bumi pertiwi, tetapi juga menguasai tanah negeri dan segala kekayaan yang dimiliki. Kehadiran mereka yang hanya sedikit dalam ukuran kuantitas namun mampu menyuarakan eksistensi kebesaran kuasa yang dimiliki lewat strategi yang digunakan. Karena itu wacana kolonial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wacana kuasa; kata kuasa atau macht dalam bahasa Belanda akan dijadikan titik pusat yang mengikat dan mengaitkan kata-kata lain yang memperkuat dan mendukung eksistensi keberadaan kekuasaan itu sendiri. Latar pemikiran atau background pengetahuan pengguna bahasa diduga ada kaitannya dengan kata-kata yang dipilih, struktur yang dibangun, serta strategi yang digunakan untuk menanamkan pemahaman dalam pikiran pembaca akan wacana kuasa yang sedang disebarluaskan. Karena teks masa kolonial yang berbahasa Belanda, terutama teks literer banyak mencerminkan kehidupan dan pemikiran penguasa, maka penelitian ini pun diarahkan padanya. Mengungkap wacana kuasa dibalik penggunaan katakata tertentu menarik untuk menelisik lebih jauh konteks pemikiran penggunanya, yang kadang pilihan katanya cukup menggores rasa kesantunan berbahasa orang yang dikuasai. Mengaitkan penggunaan 16 bahasa dengan konteks pemikiran merupakan usaha lebih lanjut dalam memaknai teks. Penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, memang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti Belanda, namun hal ini hanya menyentuh sebagian kecil dari yang ingin diungkap, sebagai contoh yang dapat diutarakan di sini adalah penelitian Van Dijk2 pada tahun 1990-an yang dilakukan terhadap cara berbahasa masyarakat Belanda bila berbicara mengenai kalangan minoritas yang ada di sana. Hasilnya menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif secara bahasa, terhadap kalangan yang dipersepsi sebagai pembuat masalah di masyarakat ini, seperti masalah ekonomi, sosial, yang berupa kerusuhan, kekerasan, kriminalitas, dan sebagainya. Pada tahun 2000-an pernah pula dilakukan penelitian terhadap orang asing pencari suaka (asielzoeker) di Belanda. Penelitian ini dilakukan oleh Ivo Nieuwenhuis, dengan bertitik tolak pada dua teks sastra Belanda masa kini, yang diberi judul: Vreemd Besoek. De koloniale representatie van de asielzoeker in twee hedendaagse Nederlandse teksten. 3 Penelitian ini menerapkan pendekatan postkolonial dalam menganalisis teks, yaitu peneliti pertama-tama mengkritisi dan mendiskusikan pandangan Edward Said yang 2 Hasil penelitian ini dipublikasikan sebagai artikel berjudul: Discourse, Ethnicity, Culture, and Rasism oleh Teun van dijk , dkk, dan dimuat dalam Discourse As Social Interaction. Discourse Studies 2. A Multidiciplinairy Introduction yang dicetak ulang tahun 2004. 3 Sumber informasi diperoleh lewat layanan online google.nl yang diakses 16-8-2011. 17 sudah dikenal umum tentang Orientalism. Pandangan ini mengonfrontasikan Barat dengan Timur, bagaimana sikap berpikir Barat telah mendasari cara bertindak memperlakukan ‘Yang Lain” Timur (de Oosterse Ander) sebagai kutub yang berbeda dan berlawanan dengan Barat itu sendiri (Westerse Zelf). Hal ini berdampak pada cara kolonisator bertindak pada orang-orang yang dikolonisasi (dijajah). Walau ada perbedaan essensial antara wacana kolonial dan representasi pencari suaka, tetapi peneliti melihat adanya kesamaan yang dapat diperbandingkan di antara keduanya. Pertama, keduanya dibicarakan dari sudut pandang Barat, dengan konteks dan sumber-sumber penunjang yang juga berasal dari Barat. Kedua, yang menarik dari penelitian ini, adalah sikap peneliti yang mengaitkan antara pencari suaka yang notabene adalah permasalahan masa kini dan sikap kolonial dari kolonisator-kolonisator yang seharusnya sudah menjadi bagian dari masa lalu. Dari permasalahan yang mencuat dalam penelitian Ivo Nieuwenhuis ini dapat dimaknai bahwa sesungguhnya permasalahan laten kolonialisme masih tetap ada tersembunyi di bawah permukaan, dan masih akan tetap penting untuk diteliti demi memberi solusi bagi permasalahan relasi ras yang akhir-akhir ini menghangat kembali dibicarakan di Eropa. Pertanyaannya sekarang apakah penelitian yang tengah dirancang ini akan bermuara pada hasil yang sama seperti yang dilakukan peneliti-peneliti 18 Belanda? Tentu saja jawabannya tidak, karena apa yang akan dilakukan adalah memberikan makna secara komprihensip pada teks kolonial. Memang tidak dimungkiri bahwa penelitian ini juga akan menyentuh penggunaan bahasa secara khusus yang diduga mengandung muatan intensi tertentu, namun di sisi lain kebermaknaan juga ada dalam aspek-aspek bahasa yang berlaku secara umum. Teks kolonial yang diduga mengandung muatan wacana kuasa ini tentunya menggunakan bahasa tertentu yang merepresentasikan pemikiran penggunanya. Oleh karena itu, pemaknaan wacana kuasa akan mendapat porsi perhatian tersendiri. Ujung dari pemaknaan secara semantik maupun pragmatik diharapkan dapat menguak kognisi (pemikiran) sang kolonisator dan memberikan gambaran realita ketika itu Fokus Penelitian Penelitian ini bertitiktolak dari teks-teks masa penjajahan dulu. Dalam hal ini, peneliti mencurahkan banyak perhatian pada produksi bahasa (wacana) yang digunakan oleh pemroduksi bahasa, yang berdampak pada pemaknaan oleh penerima; semua ini berkaitan dengan pikiran manusia penggunanya. Langkah awal yang akan dilakukan adalah membongkar teksteks yang telah dipilih secara selektif (eclectic) dari sejumlah teks yang masuk kategori teks kolonial untuk mendapatkan data bahasa yang dimaksud. Untuk itu, pertanyaan mula-mula yang dapat diajukan adalah: 19 1. Bagaimanakah kata-kata dan ungkapan kalimat di seputar wacana kuasa yang teridentifikasi dalam teks-teks kolonial dapat ditampilkan dan dianalisis dengan teori wacana? 2. Bagaimana menginterpretasi dan menganalisis konteks dalam wacana teks kolonial 3. Bagaimanakah menjelaskan keterkaitan kata-kata yang dipilih untuk digunakan dalam wacana kolonial ini dengan representasi makna dan kognisi penggunanya (konteks)? B. Tujuan Penelitian Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk menjawab rasa ingin tahu peneliti akan fenomena bahasa masa lalu yang pernah ada di Indonesia. Bahasa ini bahkan pernah menjadi salah satu pilihan bahasa bergengsi kaum intelektual Indonesia. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, bahasa ini lambat laun tersingkir dari perbincangan dan hanya menyisakan lembaran-lembaran dokumen yang sarat dengan data dan fakta-fakta sejarah. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada sub-bab Fokus Masalah di atas, sebagai berikut: 1. Menampilkan dan menjelaskan data bahasa berupa kata, frasa, dan kalimat yang diidentifikasi mengandung muatan wacana kolonial 20 2. Menginterpretasi dan menganalisis makna konteks dalam wacana teks kolonial 3. Menjelaskan keterkaitan penggunaan kata-kata dalam wacana kolonial dengan representasi makna dan kognisi penggunanya (konteks) D. Kegunaan Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pengembangan teori analisis wacana kritis, yang selama ini sudah menunjukkan keragaman pemikiran dalam menjawab berbagai fenomena wacana yang ada di masyarakat masa kini, seperti fenomena yang ada pada konversasi (percakapan) sehari-hari, berita lewat media komunikasi, pengajaran (hubungan guru dan murid) dalam bidang pendidikan, dan masih banyak yang lainnya, termasuk wacana rasisme. Dan kini peneliti mencoba menyumbangkan pemikiran lewat wacana kolonialisme. Selain itu, diharapkan penelitian ini memberikan perluasan pengetahuan akan makna kosakata yang digunakan pada peristiwa (event) khusus, yang dalam hal ini peristiwa yang bersituasikan masa lalu di Indonesia. Dalam bidang ilmu bahasa penelitian dengan objek bahasa masa lalu ini, kiranya dapat memberikan warna berbeda untuk hasil-hasil penelitian yang di Eropa dan di Amerika telah dihimpun di bawah satu nama historical 21 discourse analysis, yang merupakan bidang ilmu yang berada di bawah historical pragmatics, suatu bidang ilmu yang relatif masih baru dari linguistik historis. 22 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.TINJAUAN TEORI dan KONSEP Untuk menunjang penelitian ini, pertama-tama akan diulas pengetahuan yang berkaitan dengan fokus perhatian peneliti dan juga teori yang akan dijadikan landasan berpikir. Tinjauan pustaka dan perspektif teoretis ini diharapkan dapat membingkai arah penelitian agar tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Walau disadari bahwa formasi teori bukanlah proses yang bertujuan mereproduksi kebenaran abadi, setidaktidaknya ia merupakan alat yang didesain untuk membantu memahami dunia. 1. Analisis wacana Analisis wacana sekarang ini sering dilihat sebagai suatu cara yang dilokalisasi dalam disiplin ilmu linguistik, walau sesungguhnya ia merupakan suatu bidang yang mengusik rasa ingin tahu yang bersifat antardisiplin. Dalam waktu kurang dari setengah abad analisis wacana telah memiliki status, stabilitas , signifikansi, dan integritas sebagai disiplin yang memiliki penilaian baik, dan ia merupakan perluasan batasan linguistik konvensional. Bila merujuk ke belakang ke tahun 1960an, ia didefinisikan sebagai analisis 23 perilaku linguistik (Bhatia, V.K. et al. 2008) dan fokus utamanya pada konstruksi dan interpretasi makna bahasa yang digunakan pada konteks sosial khusus. Pendekatan yang lebih kontemporer terhadap bahasa dalam penggunaannya, berakar dari sejumlah perkembangan pada Abad 20 dalam bidang filsafat, antropologi, sosiologi, dan linguistik. Akar dari pandangan terhadap bahasa ini, mungkin bersumber dari karya Wittgenstein (1951/1972) yang melihat bahasa sebagai suatu seri ‘permainan’ yang dengannya orang mengonstruksi apa yang disebut ‘bentuk kehidupan’, cara khusus berinteraksi dengan orang lain dan sekelilingnya. Kemudian diikuti oleh kemunculan publikasi karya klasik Austin pada tahun 1962, How to Do Things with Words, suatu kajian yang menyarankan bahwa pengkajian bahasa tidak hanya melibatkan strukturnya, tetapi yang penting bagaimana cara ia digunakan, dibentuk, dan dimunculkan hingga menjadi lebih menonjol, sekurangkurangnya di lingkungan filsafat. Menyusul pemikir-pemikir seperti Foucault dan Derrida, meskipun apa yang dilakukan mereka bukanlah cara yang menguatkan apa yang menjadi tradisi Austin, tetapi perlu untuk dicatat bahwa cara mereka justru memperluas cara menganalisis bahasa, yaitu apa yang mereka lakukan lebih bersifat divergence daripada convergence terhadap karya Austin, juga telah membuat bahasa khususnya ‘wacana’ menjadi sentra untuk memahami praktik sosial. 24 Kegiatan menganalisis wacana bahasa telah banyak dilakukan oleh para ahli bahasa, sebut saja Harris (1952), Stubbs (1983), yang banyak dirujuk oleh Widdowson (2004) dalam menganalisis isu-isu kritis dalam analisis wacana. Widdowson sesungguhnya mengelompokkan dua cara dalam menghadapi bahasa, pertama analisis, bila yang dihadapai adalah unit-unit linguistik, terutama dalam memahami maknanya, sedangkan, bila yang ingin diketahui adalah apa yang dimaksud penulis / penutur lewat penggunaan bahasa tertentu, maka alat yang digunakan adalah interpretasi. Interpretasi berarti mempertimbangkan segi pragmatik dalam penggunaan bahasa, dan tidak semata-mata hanya masalah semantik. Penggunaan istilah wacana oleh Nelson Phillips dan Cynthia Hardy (2002) lebih bersifat khusus; mereka mendefinisikan wacana sebagai seperangkat teks yang terhubungkan satu sama lain, di mana praktik produksi, diseminasi, dan resepsi telah menjadikannya objek yang mengada. Mereka memberikan contoh koleksi teks dari berbagai jenis, yang telah membuat wacana psychiatry menjadi populer dengan gagasannya mengenai ketaksadaran yang eksis pada Abad 19 (sebagaimana hasil penelitian Foucault, 1965). Dengan kata lain, realita sosial diproduksi dan dibuat nyata melalui wacana, interaksi sosial tidak dapat dipahami penuh, jika tidak merujuk pada wacana yang telah memberinya makna. Karena itu, tugas 25 seorang analis wacana menurut mereka adalah mengeksplorasi relasi antara wacana dan realita. Wacana juga dipandang sebagai konstruksi sosial (Phillips, L. and Jorgensen, M.W., 2004; Phillips, N. and Hardy,C., 2002), paham konstruksi sosial sesungguhnya merupakan istilah yang memayungi teori-teori baru mengenai budaya dan masyarakat ( Phillips, L and Jorgensen, M.W., 2004: 4). Akan tetapi analisis wacana hanyalah salah satu di antara beberapa pendekatan yang biasa digunakan para konstruksionis, walau demikian penggunaannya paling meluas di antara pendekatan yang lain. Bila dilihat asal muasalnya, paham ini memiliki akarnya dalam teori poststrukturalisme Prancis dan penolakannya terhadap totalisasi dan universalisasi teori-teori seperti Marxisme dan psychoanalysis (Ibid: 6). a. Wacana bahasa dan konteks budaya. Di Amerika, munculnya perhatian yang mengaitkan bahasa dengan kebudayaan sudah dimulai pada tahun-tahun pertama Abad Kedua Puluh, dengan kehadiran karya Edward Sapir dan Benyamin Lee-Whorf, seperti juga sebelumnya telah dirintis oleh tradisi Boasian dalam antropologi linguistik. Adapun di Eropa, pendekatan yang mengaitkan bahasa dengan lingkungan sosial dan budaya dapat dilihat pada karya Michael Halliday. Konsep Halliday bertitik tolak dari paradigma strukturalis, dan kognisi dalam 26 gramatika, yang melihat sistem bahasa sebagai suatu sistem yang otonom dan independen dalam penggunaannya. Namun dalam perkembangannya ia kemudian mengaitkannya dengan linguistik sosiologi, yaitu suatu disiplin yang membuka ruang bagi bahasa untuk dikenali struktur sosial, nilai-nilai, sistem pengetahuan serta pola-pola budaya yang terdapat dan yang menyatu di dalamnya. Kemudian konsep ini menggabungkan kedua tataran, yakni tataran makro sosiologi (Halliday, 1978:65) dan juga tataran mikro sosiologis, yang padanya makna bahasa dilihat secara spesifik dalam konteks dan situasi. Hipotesis relativitas Whorf (1956) terhadap bahasa, menurut Dirven (2001:176-178) dapat diinterpretasi dengan dua cara. Versi aliran keras mengatakan bahwa sistem bahasa menentukan atau ‘mendeterminasi’ pemikiran. Tesis ini telah dikesampingkan oleh sebagian orang, karena manusia nyatanya tanpa bahasa masih dapat mengonstruksi pikirannya panjang lebar, seperti misalnya pada penciptaan karya seni lukis, tari, dsb. Adapun versi lemah mengatakan bahwa bahasa mengarahkan pemikiran dan pengamatan kita. Jika masih tetap berpikir dengan bahasa, ide-ide Whorf senantiasa masih merupakan tantangan untuk dipikirkan. Karena masyarakat berevolusi, kategori-kategori pemahaman ini pun dapat disesuaikan dengan perkembangan atau bahkan dihilangkan. Dalam pengertian ini, gambaran dunia suatu masyarakat ternyata tidak pernah statis dan tidak pernah 27 ‘dideterminasi ‘ secara penuh oleh alat-alat yang ada dimiliki oleh kategorikategori pemahaman, meskipun memang ia dipengaruhi oleh ketegorikategori tersebut. Demikian juga dengan pandangan individu tertentu terhadap dunia, sama sekali tidak dideterminasi oleh bahasanya, tetapi ia memang sangat dipengaruhi oleh bahasanya. Semua berlaku mutatis mutandis karena satu dan lain hal perlu perubahan, ini juga berlaku untuk perilaku komunikasi dalam budaya tertentu. Gaya komunikasi individu sama sekali tidak pernah dideterminasi oleh budaya yang ia serap di mana ia tumbuh dan dibesarkan. Tetapi memang selalu ada ruang untuk variasi dan pembaharuan yang bersifat sosial dan individual. Secara historis, satu alasan mengapa kajian mengenai sosial budaya begitu disukai dalam bahasa, adalah karena keduanya, bahasa dan budaya, tampaknya memiliki properti yang sama. Keduanya dapat diperlakukan sebagai sistem yang mengandung identitas diri yang didefinisikan dari aturan-aturan yang digunakan untuk mengombinasikan elemen-elemen masing-masing. Pada masa poststrukturalisme sekarang ini, menurut Kress, sebagaimana dikutip dari Wetherell (2005: 284), pendekatan strukturalis tidak lagi memberikan kepuasan, akibatnya, ia berargumentasi bahwa lebih 28 banyak pandangan yang tertarik dan menaruh perhatian terhadap relasi antara bahasa dan konteks sosialnya. Ini terjadi bila peneliti mulai lebih mengkaji praktik berbahasanya daripada strukturnya. Fokus berbalik ke tindakan sosial dan realita yang hidup secara aktual. Tulisan Bakhtin dan Volosinov (dalam Wetherell, 2005) merupakan contoh yang bagus sekali karena bagi Bakhtin dan Volosinov makna kata tidak diturunkan dari tempatnya dalam struktur, tetapi dari akumulasi dan dinamisasi penggunaannya secara sosial. b. Wacana kritis terhadap interaksi sosial. Dengan meningkatnya isu-isu sosial dan politik mengenai imigran dan relasi etnis di Eropa dan Amerika Serikat pada sekitar tahun 1990 membuat analisis wacana mendapat perhatian ketika itu. T. van Dijk (1997/2004) salah satu di antara analis-analis Critical Discourse Analysis yang melakukan pengujian terhadap cara anggota kelompok mayoritas di Belanda dan di Amerika Serikat dalam bercakap (talk) dan menulis (written) mengenai kelompok minoritas, juga bagaimana relasi etnis menampakkan diri dalam percakapan sehari-hari, buku teks, bahasa pers, parlemen, korporasi bisnis dan ilmu pengetahuan. Dalam kajiannya, ia menunjukkan bagaimana pendekatan multi-disiplin bekerja untuk menampilkan reproduksi rasisme dalam masyarakat, yang melibatkan relasi yang kompleks antara struktur 29 wacana, representasi kognisi, dan strukrur sosial. Analisis wacana yang dilibatkan dalam penelitiannya itu terutama difokuskan pada tipe topik yang lebih disukai, seperti topik perbedaan, penyimpangan, dan ancaman, juga riwayat perkembangannya, struktur berita, argumentasi, gerakan pemaknaan secara lokal, seperti stilistika dan properti retorika yang digunakan. Paradigma yang sama juga digunakan Jӓger dan teman-temannya di Duisburg (Jerman) (van Dijk, 1997/2004:167) dalam menguji secara mendetail cara orang Jerman berbicara dan menulis mengenai minoritas dan pengungsi pada tahun sekitar 1990, yang menjadikan mereka tiba pada kesimpulan yang secara esensial sama. Ini memberi ide bahwa model percakapan dan teks di sana menampakkan diri hampir sama bila berbicara mengenai ‘orang lain’ (the others). Cara yang hampir sama juga dilakukan Wodak dkk di Austria. Keingintahuan akan wacana anti Semit di Austria, didasarkan pada kasus the Waldheim affair, pemilihan presiden yang presidennya diduga terlibat kejahatan perang Nazi selama Perang Dunia II. Sebagai tambahan untuk analisis wacana secara mendetail, Wodak mengkaji berita di media, talk show di TV, percakapan sehari-hari di jalan. Wodak juga menguji dimensi kognisi, sosial, politik, dan histori. Dalam kerangka yang lebih luas pada pragmatik dan wacana nasional, Blommaert dan Verschueren (1992) melakukan pengujian terhadap orang kulit putih di Belgia, bagaimana mereka berbicara mengenai minoritas dan imigran di sana. 30 Dalam menganalisis texts dan talks, van Dijk memfokuskan pada properti wacana dan kondisi kontekstual serta konsekuensinya. Beberapa struktur diskursi dan strategi yang lebih khusus ternyata berpengaruh dalam mereproduksi rasisme. Struktur wacana berperan dalam mengekpresikan dan mempersuasi perilaku dan ideologi yang dipolarisasi sebagaimana “kami” yang baik dan “mereka” yang buruk. Makna semacam ini boleh jadi ditekankan lewat intonasi khusus dalam percakapan, sebagaimana juga dalam headline berita atau gambar dalam buku teks. Properti wacana yang jelas-jelas paling masuk akal adalah topik. Bila anggota kelompok dominan atau institusi berbicara atau menulis mengenai kelompok minoritas, maka akan tampak pada topik apa yang mereka gunakan. Analisis mengenai topik-topik semacam ini penting, karena mereka sebagain besar mendeterminasi cara orang memahami dan mereproduksi teks dan percakapan semacam itu. Jadi, topik umum dalam media akan memengaruhi agenda, yakni apa yang publik pikirkan dan perbincangkan. Dari analisis mengenai wacana anggota kelompok mayoritas dan institusi ini diperoleh hasil, bahwa mereka sebagian besar mereproduksi dan mengekspresikan stereotip dominan, seperti topik-topik berbau etnik: imigran, kejahatan, perbedaan budaya, penyimpangan, dan masalah sosial ekonomi. Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa kelompok minoritas sering menimbulkan dampak negatif. Jadi, imigran tidak pernah dijadikan topik 31 netral atau sebagai kontributor dalam bidang ekonomi, tetapi sebagai pembawa masalah, apakah itu masalah penipuan, atau ancaman bagi berbagai masalah kejahatan yang khas secara etnis, seperti perampokan, drugs, kekerasan (kerusuhan). Pada sisi lain kejahatan yang dilakukan terhadap golongan minoritas, seperti diskriminasi, cenderung dinilai kecil atau diasosiasikan dengan perbuatan individual yang menyimpang atau perbuatan kelompok radikal. 2. Teori dan metode analisis wacana Banyak teori dan kerangka kerja terhadap analisis wacana telah diperkenalkan oleh para ahli, di antaranya Fairclough menawarkan kerangka kerja “tiga dimensi” yang bertujuan memetakan tiga bentuk terpisah dari analisis wacana: pertama, analisis teks bahasa (tuturan atau tulisan), kedua, analisis praktik wacana (berupa proses produksi teks, distribusi dan pengonsumsiannya), dan ketiga, analisis terhadap peristiwa diskursi sebagai bagian dari praktik sosiokultural (Fairclough, 1995:2; Bhatia, et al. (ed), 2008:11). Dalam pengertiannya yang paling abstrak, wacana merujuk pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Wacana juga dipahami sebagai jenis bahasa yang digunakan dalam satu bidang khusus, seperti wacana ilmu politik. Dan yang paling konkret, wacana dilihat sebagai kata benda (noun) 32 yang dapat dihitung, contohnya: a discourse, the discourse, the discourses, discouses, (Phillips, L and Jorgensen, M.W., 2004: 66), yang merujuk pada cara berbicara yang memberi makna pada pengalaman yang diperoleh dari perspektif khusus. Fairclough membatasi istilah wacana menjadi sistem semiotik seperti bahasa (dalam bentuk ujaran maupun tulisan) dan imaji, berlawanan dengan apa yang dilakukan Laclau dan Mouffe yang memperlakukan semua praktik sosial sebagai wacana (Ibid: 67). a.Teori tentang konteks menurut van Dijk. Van Dijk (2009) memperkenalkan teori tentang konteks yang menjelaskan bagaimana text dan talk diproduksi, disesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Ini merupakan hubungan tidak langsung yang ditetapkan antara wacana dan masyarakat, karena penyesuaian yang dilakukan tergantung pada pengguna bahasa itu sendiri, bagaimana ia atau mereka mendefinisikan situasi komunikasi. Model-model konteks Van Dijk ini mengontrol semua produksi bahasa dan pemahamannya dan menjelaskan bagaimana wacana dibuat cocok untuk setiap situasi. Dengan pendekatan multidisiplin, dia mengembangkan teori tentang konteks dan melakukan pengujian pada struktur situasi sosial dengan memperhatikan dimensi psikologi sosial, sosiologi, dan variasi-variasi budaya. 33 Dalam disiplin psikologi sosial perhatian lebih dicurahkan pada ‘social cognition’, yakni representasi dan proses kognitif, masyarakat dipahami lewat cara bagaimana mereka dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Juga dilanjutkan menganalisis masyarakat dengan jalan memahami situasi sosial individu atau anggota dari satu kelompok komunitas yang berpartispasi dalam suatu interaksi sosial. Konteks situasi sosial dari suatu interaksi sosial dalam setting khusus ini, melibatkan partisipan yang berhadapan satu lawan satu, sedangkan ‘konteks budaya’ didefinisikan lebih global, yang melibatkan anggota seluruh komunitas, sebagaimana juga beberapa properti yang mereka miliki, seperti pengetahuan, norma-norma, dan nilai-nilai (Ibid: 154). Teori tentang konteks ini diklaim sebagai perantara interface yang bersifat teoretis dan empiris, yang menjadi jembatan penghubung antara aktor sosial dengan struktur sosial. Lain halnya dengan teori wacana Laclau dan Mouffe (1985), yang dikonstruksi dengan jalan mengombinasikan dua tradisi mayor teoretis, tradisi Marxisme dan Strukturalisme. Marxisme memberikan jalan untuk berpikir mengenai masyarakat, sedangkan Strukturalisme memberi jalan bagi teoriteori tentang makna. Laclau dan Mouffe memfusikan kedua tradisi ini ke dalam satu teori poststrukturalis tunggal, yakni keseluruhan bidang kemasyarakatan dipahami sebagai jaringan proses yang di dalamnya makna diciptakan. Untuk memahami seperti apa teori wacana yang diperkenalkan 34 Laclau dan Mouffe, di bawah ini akan disarikan teori tersebut sebagaimana digambarkan oleh Louise Phillips and M.W. Jorgensen b.Teori wacana Laclau dan Mouffe. Laclau dan Mouffe mendefinisikan 4 konsep yang telah diuji oleh Louise Phillips and Marianne W. Jorgensen, di samping itu dua orang yang disebut terakhir ini juga memperkenalkan sejumlah konsep yang terkait, yaitu ‘nodal point’ poin persetujuan, ‘the fields of discursivity,’ dan ‘closure’ pengakhiran / penutupan. Bagaimana pemahaman mereka mengenai teori Laclau dan Mouffe, akan dipaparkan di bawah, sebagaimana disarikan dari uraian mereka pada halaman 26-30 (2004). Wacana dipahami sebagai pemastian makna dalam suatu domain khusus. Semua tanda dalam wacana adalah moment-moment. Mereka adalah simpul seperti yang ada pada jaring / jala ikan, makna mereka dipastikan melalui perbedaannya dengan yang lain (differential positions). Sebagai contoh, misalnya pada wacana medikal: tubuh, penyakit, dan pengobatan direpresentasikan dengan cara khusus. Semua penelitian medikal membagi tubuh, penyakit, dan pengobatan menjadi bagian-bagian, yang digambarkan memiliki relasi dengan cara yang tidak ambigu. Secara khusus tubuh dilihat seperti terbagi dalam bagian-bagian yang akan diobati secara terpisah dan penyebab penyakit sering dilihat sebagai bersifat lokal. 35 Misalnya, infeksi diterima sebagai disebabkan oleh serangan lokal dari mikro organisme yang harus dieliminasi dengan obat. Wacana medikal, membentangkan suatu jaringan makna antarrelasi, yang mengaitkan tubuh dengan penyakit. Dalam pengertian ini, kita berbicara mengenai wacana bahwa semua tanda adalah moment dalam suatu sistem, dan makna setiap tanda dideterminasi lewat relasinya dengan tanda-tanda lain. Wacana dibentuk lewat pemastian makna sebagian di sekitar nodal point tertentu (Phillips, L. and Jorgensen, M.W., 2004:26; lihat juga Laclau and Mouffe, 1985:112). Nodal point adalah tanda yang memperoleh hak istimewa (privileged), di sekitarnya tanda-tanda lain ditata. Tanda-tanda lain ini memperoleh maknanya dari relasi dengan nodal point. medikal misalnya, Pada wacana tubuh merupakan nodal point, yang di sekitarnya beberapa makna lain terkristalisasi. Tanda-tanda seperti ‘symptoms’ gejala, ‘tissue’ jaringan, dan ‘scalpel’ pisau bedah memperoleh maknanya dengan jalan menghubungkannya dengan ‘body’ tubuh secara khusus. Nodal point dalam wacana politik, misalnya, adalah ‘demokrasi’, sedangkan dalam wacana kebangsaan adalah ‘rakyat’. Nodal point untuk wacana kolonial diduga adalah ‘kekuasaan’, namun itu pun masih harus dibuktikan dalam penelitian ini. Wacana ditetapkan sebagai suatu totalitas, yaitu setiap tanda dipastikan sebagai moment melalui relasinya terhadap tanda-tanda lain 36 sebagaimana dalam metafora jala ikan tadi. Ini dilakukan dengan jalan penyingkiran (exclution) semua makna yang mungkin yang dapat dimiliki oleh tanda-tanda itu, atau penyingkiran semua cara yang mungkin yang dapat digunakan menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, wacana merupakan pereduksian semua kemungkinan. Ini merupakan usaha untuk menghentikan tanda yang menggelinding / meluncur / menyasar dalam hubunganya dengan tanda lain dan juga karena ingin menciptakan sistem makna yang menyatu. Semua kemungkinan yang wacana singkirkan, oleh Laclau dan Mouffe disebut the field of discursivity (Phillips, L. and Jorgensen, M.W., 2004:27; lihat juga Laclau and Mouffe, 1985:111). The field of discursivity ini merupakan tempat penampungan bagi ‘makna yang berlebih’ (‘surplus of meaning’) yang diproduksi lewat praktik artikulasi, Ini adalah makna yang dimiliki oleh suatu tanda atau pernah dimiliki di wacana-wacana lain, tetapi yang disingkirkan oleh satu wacana khusus demi untuk menciptakan kesatuan makna. Misalnya, wacana medikal ditetapkan (constituted) dengan jalan menyingkirkan wacana mengenai pengobatan alternatif, dalam wacana ini tubuh dilihat sebagai entitas secara holistik yang menyerap energi lewat jalan yang berbeda. The field of discursivity dalam definisi konsep Laclau dan Mouffe, dipahami sebagai segala sesuatu yang berada di luar satu wacana, segala yang wacana itu singkirkan. Namun, karena satu wacana selalu ditetapkan 37 dalam hubungannya dengan wacana di luarnya, maka ia selalu berada dalam bahaya dikurangpentingkan (undermined), yakni kesatuan maknanya berada dalam bahaya dikacaukan (disrupted) oleh cara penetapan makna yang lain tandanya. Di sini konsep element menjadi relevan. Element adalah tanda yang maknanya belum dipastikan, tanda yang memiliki potensi makna multi (tanda-tanda yang polisemi). Jadi, dengan menggunakan konsep ini, definisi wacana dapat direformulasi sebagai suatu usaha untuk mentransformasi elemen-elemen ke dalam momen-momen dengan jalan mereduksi poliseminya menjadi makna yang pasti. Dalam teori wacana Laclau dan Mouffe diistilahkan bahwa wacana tersebut telah menetapkan makna tanda akhir, a closure, suatu penghentian sejenak fluktuasi makna dalam tanda. Akan tetapi a closure, makna akhir, tidak pernah definitif. Sebagaimana dikutip perkataan Laclau dan Mouffe oleh Louise Phillips dan Marianne Jorgensen (hal. 28): ‘The transition from the “elements” to the “moments” is never entirely fullfilled.’ Wacana tidak pernah dapat dipastikan dengan sempurna karena ia dapat dikacaukan dan diubah dengan berbagai makna multi yang ada dalam tanda. Misalnya, dalam wacana pengobatan Barat, masuknya akupuntur telah menyebabkan terjadinya modifikasi dalam pemahaman pengobatan yang dominan cara Barat. Dalam istilah Laclau dan Mouffe ‘tubuh’ adalah elemen sebagaimana di dalamnya ada beberapa cara pemahaman yang bersaing, Dalam wacana 38 pengobatan Barat yang dominan, tubuh dapat direduksi menjadi moment yang dapat didefinisikan wacana pengobatan secara khusus dan tidak ambigu, dan dalam alternatif, tubuh dapat didefinisikan dengan dikorespondesikan dengan ketidakambiguan, tetapi dengan cara yang berbeda dari wacana medikal. Namun, wacana Kristen memiliki cara lain memahami tubuh, yakni mengaitkannya dengan tanda ‘soul’ jiwa. Jadi, kata ‘body’, tidak terlalu berbicara banyak mengenai dirinya, ia harus diposisikan dalam hubungannya dengan tanda lain untuk memberikan makna, ini terjadi lewat articulation. Laclau dan Mouffe mendefinisikan artikulasi sebagai setiap praktik yang menetapkan relasi antar elemen-elemen, seperti halnya identitas dari elemen yang dimodifikasi. Kata ‘body’ dalam dirinya sendiri bersifat polisemi dan identitasnya, oleh karena itu, diputuskan melalui hubungannya dengan kata lain dalam artikulasi. Misalnya, ujaran ‘body and soul’ menempatkan ‘body’ dalam wacana religius, beberapa makna kata tetap lanjut digunakan dan yang lain diabaikan. Nodal point adalah tanda-tanda yang memiliki privilege di mana di sekelilingnya wacana diorganisasi, tetapi tanda-tanda ini dalam dirinya kosong. Sebagaimana telah disebutkan, tanda ‘body’ tidak memperoleh makna yang mendetail sampai ia masuk dalam wacana khusus. Oleh karena itu, tanda ‘body’ juga merupakan elemen. Sesungguhnya teori wacana memiliki istilah untuk elemen yang terbuka untuk perbedaan makna, dan itu 39 adalah floating signifier penanda mengambang. Floating signifier adalah tanda yang berbagai wacana berbeda berusaha miliki dengan makna yang sesuai dengan yang mereka ingini. Nodal point adalah floating signifier, tetapi karena istilah ‘nodal point’ mengacu kepada poin pengkristalisasian dalam wacana khusus, maka istilah ‘floating signifier’ menjadi bagian dari pergulatan yang sedang terjadi antara wacana berbeda untuk memastikan makna tanda yang penting. Dengan menghubungkan semua istilah satu sama lain, wacana bertujuan memindahkan ambiguitas dengan jalan mengubah element menjadi moment sampai menjadi makna akhir atau closure. Tetapi tujuan ini tidak pernah berhasil dengan sempurna sebagaimana kemungkinankemungkinan makna yang wacana pindahkan (displaces) ke field of discursivity yang selalu mengancam untuk membuat tidak stabil makna yang pasti (fixed). Oleh karena itu, semua moment berada dalam polisemi yang berpotensi, yang berarti bahwa moment selalu merupakan element potensial. Artikulasi-artikulasi khusus mereproduksi atau menolak wacana yang telah eksis lewat penetapan makna dengan cara khusus. Oleh karena polisemi yang terus menerus berpotensi, maka setiap ekspresi verbal atau tertulis (bahkan setiap tindakan sosial) juga merupakan artikulasi atau inovasi; meskipun ekspresi itu digambarkan berdasarkan kepastian makna sebelumnya – ia digambarkan berdasarkan wacana-wacana yang telah 40 menjadikan tanda sebagai moment – namun ia tidak pernah merupakan repetisi dari sesuatu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ekspresi merupakan reduksi aktif dari kemungkinan-kemungkinan makna karena ia memosisikan tanda dalam hubungannya satu terhadap yang lain dengan melalui hanya satu cara, menyingkirkan bentuk-bentuk organisasi alternatif. Wacana, dalam pengertian Saussurean adalah satu tipe struktur yang makna tandanya dalam satu jaringan relasional sudah pasti. Atau dengan kata lain struktur dalam tradisi Saussurean meliputi semua tanda akhir (closure) yang permanen, sedangkan bagi Laclau dan Mouffe, wacana tidak pernah secara total berada dalam pengertian Saussurean ini. Selalu ada makna potensial lain, yang ketika diartikulasi dengan cara khusus, boleh jadi ia menolak dan mentransformasi struktur wacana. Jadi, wacana dalam pandangan Laclau dan Mouffe merupakan (closure) makna tanda akhir temporer: ia memastikan makna dengan cara khusus, tetapi ia tidak mendikte makna itu pasti menjadi tetap dengan cara itu untuk selamanya. c.Teori relativisme dan universalisme bahasa. Ketika peneliti-peneliti Barat mulai mencurahkan perhatian mereka pada bahasa-bahasa lain di luar bahasanya sendiri, maka muncullah dua pendapat yang saling bertentangan dalam melihat hubungan bahasa dengan budaya. Pendapat pertama yang setuju dengan pernyataan yang 41 mengatakan bahwa bahasa yang dimiliki seseorang mendeterminasi cara pandang dan berpikirnya, di mana dengan ini akan berdampak pada cara ia memperlakukan dunia, melahirkan teori yang disebut sebagai teori relativisme bahasa. Teori ini beranggapan bahwa konsep setiap bahasa berbeda-beda, baik dalam bidang leksikologi, morfologi, maupun dalam bidang sintaksis. Bahkan dalam bidang fonologi pun demikian pula, perbedaan tekanan dan intonasi sering memberikan perbedaan makna pada satu bahasa tertentu yang belum tentu sama pada bahasa yang lain. Begitu juga dengan bangun fisik kata yang tampak dari luar (overt) suatu bahasa, kata bahasa Belanda rijst misalnya, padanannya dalam bahasa Indonesia bisa beras,nasi, padi, gabah, dst. Hal ini disebabkan kata rijst dalam bahasa Belanda tidak memiliki hubungan budaya dengan masyarakat bahasanya, kata ini diadopsi ke dalam bahasa Belanda hanya karena adanya ikatan dengan Indonesia, oleh karena itu kata ini dalam beberapa teks tampil sebagaimana asalnya, seperti kata nasi goreng, paddi, dst. Pandangan kedua melihat bahwa dalam bahasa terdapat ciri-ciri yang bersifat universal, karena itu lahirlah teori universalisme bahasa. Bila kita ingin mengadopsi kedua pandangan ini maka apa yang dilakukan tidaklah terlalu salah. Karena bila dicermati dengan seksama, memang dalam setiap bahasa selalu terdapat ciri atau karakter yang memperlihat kesamaan dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia, terutama dalam hal konsep, 42 klasifikasi, dan kategorisasi. Ikhwal konsep suatu kata, akan memperlihatkan ciri keuniversalan bila yang dianalisis adalah fitur makna yang dikandung oleh kata tersebut. Contohnya kata bahasa Belanda paard memiliki fitur-fitur makna [+bernyawa], [+ binatang], [+piaraan], [+warna: hitam, coklat, putih, dan belang-belang], [+kaki empat], [+ekor satu]..dst; fitur-fitur ini dapat diperluas sesuai dengan kemampuan pengetahuan orang yang memaknainya, seperti [+nomina], [+tunggal], [+jamak], [+referen], dst. Banyak pemikir-pemikir besar dunia yang mengakui keberadaan konsep makna universal ini. Filosof seperti Pascal, Arnauld, dan Leibniz (Dirven, 2001: 161) menyebut konsep semacam ini sebagai “pengertian sederhana’ (“eenvoudige begrippen”). Dalam linguistik modern pengertian semacam ini umum disebut sebagai semantik primitif, sebagaimana istilah yang digunakan René Dirven semantische primitiven dan juga Anna Wierzbicka dan Cliff Goddard ketika mengulas mengenai Semantics and Lexical Universal (1994) juga menggunakan istilah yang senada semantic primitives, namun dalam tulisan-tulisan mereka yang muncul kemudian istilah yang sama telah diubah menjadi semantic primes (semantik prima). Sebagai peneliti yang berkepentingan menggunakan istilah ini, saya cenderung lebih memilih istilah semantik prima, karena menurut representasi mental saya kata ini lebih mengandung muatan fitur netral dibandingkan kata primitif. Kata primitif pernah pula digunakan oleh sosiolog 43 Prancis pada permulaan Abad Kedua Puluh, Lucien Lévy Bruhl (Wierzbiecka, pada opening statementnya dalam Semantics and Lexical Universal, 1994: 1). Lévy Bruhl menggunakan kata ini ketika ia membedakan cara berpikir masyarakat Barat yang menurutnya logis dan non-Barat yang primitif. Cara ini tentu saja tidak mencerminkan cara berpikir yang universal. Semantik prima merupakan konsep-konsep universal yang dimiliki semua bahasa di dunia, yang keberadaanya relatif kecil dalam jumlahnya. Menurut Driven (2001) ada sekitar 60-an kata bahasa Belanda yang dapat diidentifikasi memiliki konsep makna prima. Semantik prima adalah pemaknaan yang sudah jelas untuk dirinya sendiri dan tidak dapat lagi dijelaskan dengan pengertian sederhana lain. Umumnya dari pengertian sederhana ini dapat dikembangkan lagi pendekatan baru yang bersifat antar bahasa dan lintas budaya, serta dapat digunakan untuk memparafrasekan pengertian-pengertian yang khas secara budaya. Diyakini dalam konsep semantik prima ini pasti terdapat kerumitankerumitan lain yang masih perlu dibuktikan dalam penelitian ini, apalagi bila yang diteliti adalah kata-kata yang mengandung intensi tertentu seperti wacana kolonial. Sebagai contoh dapat disebutkan beberapa di antaranya, seperti alloleksen (allolexen): satu konsep makna (covert) yang diwujudkan 44 dalam dua bentuk fisik kata (overt) yang berbeda, seperti je / u , iemand / een persoon, zich voelen / voelen, dst. Makna figuratif, yakni makna assosiatif yang terbentuk dari gabungan dua makna prima, seperti kata majemuk aapmens. Kompleksitas atau kerumitan lain yang perlu dijelaskan lebih jauh adalah kata yang memiliki makna ganda atau polisemi. 3. Pandangan terhadap makna kata Berlawanan dengan pandangan strukturalis yang memiliki pandangan bahwa kata yang biasanya diwakili oleh tanda memiliki kedekatan dengan makna yang hampir tidak dapat dipisahkan darinya, maka Callow (1998: 19) justru melihat bahwa keberadaan makna lebih dulu hadir dari pada kata. Orang yang sedang berkomunikasi tahu apa makna yang hendak dikomunikasikan, kemudian baru ia memilih kata-kata terbaik untuk mengekspresikan maksud (makna) tersebut. Jadi, sesungguhnya bukan kata yang memaknai sesuatu, tetapi manusialah yang memaknai sesuatu ketika ia menggunakan kata-kata. Bagi Callow, kata tidak memiliki makna, tetapi kata hanya memberi sinyal mengenai makna. Pikiran orang yang sedang berkomunikasi tidak kosong (blank), tetapi ada dipenuhi muatan-muatan. Kata-kata tidak berada di otak kita sebagaimana abstraksi logis, tetapi keberadaan kata lebih dekat pada penggunaannya. Di sini tampak, pandangan terhadap makna berpusat pada 45 penutur (speaker). Mereka yang menerima pandangan tentang makna yang terpusat pada kata, melihat satu kata yang sama bisa memiliki makna-makna yang berbeda di konteks kalimat yang berbeda. Sedangkan mereka yang memandang makna terpusat pada penutur, melihat makna yang sama dapat diekspresikan lewat kata-kata yang berbeda (dan melalui sejumlah cara yang berbeda). Dapat juga makna yang sama diekspresikan dalam bahasa yang berbeda. Jadi, jika makna dipertimbangkan inheren dalam kata, maka tidak mungkin mengekspresikan makna berbeda bila konteks kalimat tidak berbeda. Apa yang dijelaskan di atas, secara singkat dapat memberikan pengertian mengenai definisi makna dalam pandangan strukturalis, yang kemudian mendapat tentangan dari pandangan poststrukturalis. Dalam pandangan strukturalis, makna adalah relasi yang setiap elemen linguistik miliki dengan elemen lain, juga dipahami sebagai penyatuan signifier (signifiant) dan signified (signifié), expression dan content. Makna juga didefinisikan sebagai konsep atau mental image yang ekspresi atau tanda kaitkan dalam pikiran kita. Selain itu, masih ada pandangan lain yang mendefinisikan makna sebagai ‘sesuatu’ atau entitas yang dirujuk oleh tanda atau ekspresi. Pandangan-pandangan lain yang tengah mencari jawaban untuk pertanyaan “apa itu makna?” secara fundamental dapat dibedakan menurut 46 seberapa besar penekanan mereka pada sisi berbeda dari segitiga semiotik, semiotic triangle (lihat Violi, 2001): linguistik dan psikolinguistik menekankan perhatian pada expression dan content, sedangkan filsafat pada content dan referent. Dalam tradisi filsafat, misalnya, dapat digambarkan perbedaan antara mereka yang mempertimbangkan relasi langsung antara ekspresi dan referen (menyingkirkan puncak dari semiotic triangle atau dalam hal ini content), dan mereka yang melihatnya sebagai relasi yang dimediasi oleh entitas penengah yang disebut sense atau intension. Linguistik juga menginterpretasi content dengan cara berbeda, baik sebagai bagian integral dari ekspresi, petanda linguistik (signified) yang tidak dapat dipisah dari penandanya (signifier) atau sebagai sesuatu yang memiliki substansi konseptual yang otonom. a. Semantik kognitif. Semantik kognitif yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengkaji leksikal merupakan bagian dari linguistik kognitif. Sebagai pendekatan, semantik kognitif ini rupanya menolak pembagian linguistik secara tradisional ke dalam bagian-bagian seperti fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dsb. Sebagai gantinya, semantik (makna) justru dibagi menjadi konstruksi makna (meaning construction) dan representasi pengetahuan (knowledge representation). Dari situ dapat dilihat bahwa semantik kognitif menaruh perhatian pada kajian makna secara keseluruhan. 47 Oleh karena itu kajian semantik kognitif mempersembahkan perhatian tidak hanya pada makna leksikal (semantik) tetapi juga pada pragmatik atau makna kalimat dalam penggunaannya. Sebagai teori, semantik kognitif membangun argumentasi bahwa makna leksikal bersifat konseptual. Makna leksem (lexeme) tidak merujuk pada entitas atau relasinya dengan dunia nyata, tetapi merujuk pada konsep yang ada di kepala berdasarkan pengetahuan dan relasinya dengan dunia nyata. Lebih dari itu, semantik kognitif menerima proses mental yang terjadi sebagai pengetahuan yang bersifat ensiklopedis (bersifat meluas), dan karenanya melibatkan beberapa teori dari psikologi kognitif. Ciri lain dari semantik kognitif adalah mengakui bahwa makna leksikal bersifat tidak tetap dan merupakan masalah penafsiran (construal) serta konvensionalisasi (conventionalization). Proses penafsiran secara linguistik diyakini sebagai proses yang sama seperti pada pengetahuan lain yang secara psikologis melibatkan proses mempersepsi, mengassosiasi, dan mengingat. (1). Konsep makna Konsep makna yang paling sederhana yang dapat dibentuk oleh seorang anak yang baru pertama kali memperoleh bahasa ibu adalah dengan jalan membangun ciri-ciri fisik benda yang diperkenalkan padanya. Ciri-ciri itu diperoleh dengan memaksimalkan pengamatan inderawi, seperti 48 penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dst. Kemudian menghubungkannya dengan apa yang didengar dari ibu atau pengasuhnya tentang benda itu. Semua ini nantinya akan direkam dalam memori anak tersebut, untuk nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk ujaran bila ia melihat benda yang sama atau hampir sama dengan ciri-ciri yang sudah direkamnya. Teori ini menurut psikolinguistik disebut sebagai teori fitur (meminjam istilah Dardjowidjojo, 2005) Teori fitur hakekatnya menyatakan bahwa kata memiliki seperangkat fitur atau ciri yang menjadi bagian integral dari kata itu. Seperti kata kucing, memliki fitur [+bernyawa], [+binatang], [+warna: hitam, coklat, putih, abu-abu, atau belang-belang], [+berbulu halus], dst. Fitur-fitur ini secara keseluruhan membentuk konsep untuk kucing. Teori ini dalam praktiknya ternyata memiliki banyak kelemahan, seperti, ciri-ciri yang dibangun sering merupakan ciri yang prototipe, sehingga dengan demikian benda yang dirujuk kadang keliru dengan benda lain yang memiliki ciri yang sama. Karena itu muncul teori lain yang dinamakan Teori Berdasarkan-Pengetahuan (Knowledge-Based Theory) (Dardjowidjojo, 2005: 91). Teori ini masih bersandar pada teori fitur, tetapi diperluas. Dalam teori ini tidak hanya fitur yang dilihat tetapi juga esensi dan konteksnya. Di sini tidak hanya pengetahuan yang dapat memperluas ciri makna suatu kata tetapi juga pengalaman yang telah menjadi pengetahuan, misalnya untuk kata 49 kucing dapat diperluas dengan fitur [+bersuara: meong], [+pemakan ikan], dst. Pandangan yang senada juga dikemukan oleh Katz dan koleganya (Katz dan Fodor, 1963; Katz dan Postal, 1964; Katz, 1972 dalam: Evans, 2006: ?) yang mengidentifikasi elemen makna sebagai analisis komponen. Pandangan mereka ini dilandasi pemikiran bahwa kata sesungguhnya terdiri dari elemen-elemen atau komponen-komponen atomik khusus. Sehingga analisis yang dikembangkan oleh mereka ini dikenal sebagai gaya komponensial (style-componential). Dalam perhitungan mereka makna kata terdiri dari penanda (marker) semantik dan pembeda semantik (distinguisher). Penanda semantik terdiri dari informasi yang dimiliki oleh kata, sementara pembeda menetapkan informasi idiosinkratik untuk makna kata yang ada. Misalnya, menurut Katz dan Postal (1964) makna polisemi untuk kata bachelor dapat dihadirkan sebagai berikut: a. (manusia) (laki-laki) [ yang tidak pernah menikah] b. (manusia) ( laki-laki) [satria muda yang melayani dibawah perintah orang lain] c. (manusia) [penerima gelar akademik terendah] d. (bukan manusia) (laki-laki / jantan) [anjing laut berbulu yang masih muda tanpa pasangan]. 50 Keterangan: penanda semantik (marker) diberikan dalam parantheses (tanda kurung) dan pembeda semantik (distinguisher) diberikan dalam tanda kurung siku-siku ( [ ] ). (2). Makna ujaran atau tuturan Makna tuturan langsung dapat diartikan secara harafiah (letterlijk), sebagai ungkapan perpaduan makna kata dari tiap kata yang ada dalam kalimat. Namun ada kalanya makna dari satu kata yang dijejerkan dengan kata lain, bukan merupakan perpaduan dari kedua makna kata tersebut atau dengan kata lain ia menunjuk pada makna figuratif. Begitu pula makna tuturan dapat bersifat metaforis, artinya ungkapan kalimat yang terdiri dari jejeran kata-kata itu dipersamakan dengan sesuatu yang lain, meskipun sebenarnya mereka tidak sama. Ungkapan ini biasanya ditandai dengan pemakaian kata pembanding bagaikan, seperti, dan sejenisnya. Contohnya ungkapan wajah kedua anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Di sini wajah anak-anak itu dipersamakan dengan buah pinang yang terbelah dua, sama persis, padahal faktanya wajah seorang anak dengan buah pinang tidak ada kemiripannya sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari sering pula dijumpai dalam percakapan atau tulisan dalam suatu teks, ungkapan-ungkapan kalimat yang bermakna ambigu, seperti ungkapan panas ya hari ini, yang diucapkan seorang dosen 51 ketika memasuki ruang kuliah. Makna tuturan ini sebenarnya tidak hanya sekedar memberikan informasi bahwa suhu udara hari ini panas, tetapi lebih dari itu si penutur mengingatkan bahwa AC atau pendingin udara di ruangan itu belum dinyalakan dan meminta atau menyuruh secara tidak langsung kepada siapa pun yang ada dalam ruangan itu untuk menyalakan AC. Ilustrasi di atas memperlihatkan bahwa makna tuturan sangat tergantung pada konteks. Suatu bidang linguistik dan kajian wacana yang secara sistematis mengkaji relasi antara konteks dan bahasa adalah pragmatik. Pragmatik lebih terkait dengan penggunaan bahasa dan tindakannya daripada dengan tata bahasa formal atau struktur wacana abstrak. Akan tetapi pragmatik juga dapat digunakan dalam psikolinguistik, sosiolinguistik, dan analisis konversasi. Di antara arah penelitian terhadap penggunaan bahasa, pragmatik lebih fokus pada isu-isu filosofis. Jadi, pragmatik menjadi label yang umum untuk berbagai kajian seperti analisis speech act (Austin, 1962; Searle, 1969), maksim konversasi (Grice, 1989), kesantunan (Brown and Levinson, 1989), presupposisi dan indeksikal (Stalnaker, 1999) dan beberapa pendekatan yang lain (Van Dijk, 2009:13). Tindak tutur John R. Searle (dalam: Rahardi, R.K., 2005) menyatakan dalam bukunya Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, bahwa 52 dalam praktik penggunaan bahasa terdapat sedikitnya tiga macam tindak tutur, yaitu: (1) tindak lokusioner (locutionary acts), (2) tindak ilokusioner (illocutionary acts), dan (3) tindak perlokusioner (perlocutionary acts) Dalam menuturkan sesuatu, seseorang secara khusus memerankan beberapa tindakan (acts). Sebagaimana disampaikan Searle (1969), ketiga tindakan itu adalah (a) an utterance act (the bringing forth of certain speech sound, word, and sentence), (b) a propositional act (referring to something or someone and pradicating some properties of that thing or person), (c) an illocutionary act (investing the utterence with a communicative force of promise, statement of fact, and so on). Tindak lokusioner adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, kalimat yang maknanya sesuai dengan apa yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat tersebut, walau kadang dalam maknanya tersembunyi tujuan dan maksud tertentu. Contoh tuturan di atas, panas ya hari ini, dapat menjelaskan hal itu. Tuturan ini memiliki makna informatif sesungguhnya bagi pendengarnya, yakni menyampaikan pernyataan yang sebenarnya akan cuaca hari itu kepada yang mendengarkan. Kalimat proposisi atau pernyataan seperti ini oleh Searle dimasukkan dalam kategori tindak tutur representatif. 53 Namun tidak tertutup kemungkinan, penyataan dari tindak tutur ini dimaknai lebih jauh oleh pendengarnya, misalnya dengan melakukan tindakan menyalakan AC bila dalam ruangan tersebut terdapat AC atau alat pendingin lain, atau dapat juga seseorang melakukan tindakan membuka jendela. Bahkan dapat saja terjadi bahwa pendengar dari tindak tutur tersebut tidak melakukan suatu tindakan apapun, pernyataan ini hanya dimaknai sebagai informasi umum sebagaimana kategori tindak tutur representatif. Pernyataan tindak tutur yang dimaknai dengan suatu tindakan oleh pendengarnya dikategorikan sebagai tindak tutur direktif. Tindak tutur lokusioner, dalam hal perwujudannya oleh Searle (1969) (lihat Dardjowidjojo,2005 dan Rahardi, R. K., 2005) dikategorikan ke dalam lima bentuk, yakni: (a) representatif, (b) direktif, (c) komisif, (d) ekspresif, dan (e) deklaratif. Sama seperti pernyataan tidak tutur direktif yang dimaknai tersirat sebagai “perintah”, tindak tutur komisif pun demikian, hanya saja pada tindak tutur komisif pemaknaannya diarahkan pada diri sendiri dan lebih bersifat tersurat dengan menggunakan kata-kata seperti berjanji, bersumpah, bertekad, dan sejenisnya. Contohnya adalah kalimat: saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini secepatnya. 54 Tindak tutur ekspresif dimaknai pendengar sebagai bentuk ungkapan yang bersifat psikologis sekaitan dengan apa yang dirasakan oleh penutur. Dalam bentuk perwujudannya, ungkapan ini sering digunakan mengekspresikan rasa terima kasih, rasa bahagia dalam bentuk ucapan selamat, rasa kagum seperti contoh dalam bahasa Belanda berikut: Wat een prinsesje, de vrouw van dien sul (padanannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini: alangkah cantiknya istri sultan itu). Dapat juga mengekpresikan rasa keterkejutan, seperti contoh: “God, wat ‘n ellende” Ungkapan ini dituturkan ketika pendengar mendengar penderitaan seorang yang tengah menjadi bahan obrolan, seorang laki-laki setelah beberapa hari sakit dan setelah diperiksa dokter ternyata menderita penyakit lepra. Tidak hanya itu ia juga sudah dikeluarkan dari pekerjaannya, sementara istrinya pun sedang berada di Holland untuk urusan kesehatannya sendiri. Ungkapan itu mengekspresikan perasaan pendengar setelah mendengar cerita tersebut: “Ya Tuhan, betapa menderitanya (orang itu).” Tindak tutur deklaratif dimaknai sebagai pernyataan yang mengungkapkan adanya suatu keadaan baru yang timbul setelah pernyataan ini diungkapkan. Biasanya orang yang mendeklarasikan sesuatu adalah orang yang memiliki wewenang untuk itu, misalnya hakim yang membacakan putusan terhadap terdakwa: “Dus drie jaar dwang-arbeid buiten den 55 ketting en driehonderd gulden boete, subsidiair zes weken dwangarbeid…..” (De Wit, A., 1903: 95). Maksim konversasi Dalam berkomunikasi orang biasanya akan mengikuti prinsip kerjasama (cooperative principle) yang akan menjadikan percakapan itu berjalan dengan baik. Prinsipel Kooperatif ini pertama kali dikenalkan oleh filsuf H. Paul Grice, pada kuliahnya di tahun 1967 (Dardjowidjojo, 2005: 108113). Prinsipel ini memberikan landasan dalam berkomunikasi yang dikenal dengan sebutan maksim (maxims). Grice memperkenalkan empat macam maksim, yaitu: (a) maksim kuantitas, (b) maksim kualitas, (c) maksim relasi, (d) maksim cara (manner). Maksim kuantitas dimaknai sebagai landasan dari tuturan yang memberikan informasi yang tepat kepada pendengar. Ukuran tepat untuk tuturan ini berarti informasi yang diberikan tidak berlebih tetapi juga bukan kurang. Namun informasi yang disampaikan harus sesuai dengan yang diperlukan. Bila informasi yang disampaikan kurang, maka pendengar akan salah memahami ungkapan tersebut, sebaliknya bila berlebihan maka pendengar akan dibuat bingung, karena tuturan akan menjadi tidak fokus. 56 Maksim kualitas dimaknai sebagai landasan bagi tuturan untuk memberikan informasi yang benar. Komunikasi biasanya akan terganggu bila informasi yang disampaikan tidak benar. Sedangkan pada maksim relasi dimaknai bahwa pendengar seharusnya mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan percakapan. Bila tidak, maka komunikasi akan terganggu. Untuk maksim cara, diharapkan pendengar mendapatkan informasi yang jelas mengenai ungkapan pemikiran penutur. Pemikiran yang diungkapkan dengan cara ambigu akan mengganggu pemaknaan pendengar terhadap apa yang disampaikan. Dalam kenyataannya, prinsipel kooperatif tidak selamanya diterapkan dalam kehidupan berbahasa. Karena apa yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan bahwa sering orang menyatakan apa yang dimaksud tidak secara rinci dan eksplisit, bahkan ujaran yang disampaikan pun tidak dengan pemikiran yang runtun atau pemberian informasi kadang tidak jelas. Teori kesantunan Brown dan Levinson Komunikasi, dalam pandangan Brown dan Levinson, dilihat sebagai bahaya berpotensi dan antagonistis. Kekuatan dari pendekatan mereka 57 menurut Gabriel BĂRBULEŢ dalam artikelnya yang berjudul The Politeness Principle – A Fundamental Pragmatic Dimension, melebihi teori Geoff Leech, karena mereka menjelaskan kesantunan dengan jalan menurunkannya dari gagasan yang lebih fundamental tentang kemanusiaan. Gagasan dasar dari model ini adalah “face” wajah yang didefinisikan sebagai citra (image) diri publik yang setiap anggota masyarakat ingin miliki untuk dirinya. The public self-image that every member (of society) wants to claim for himself. Dalam kerangka kerja mereka, wajah terdiri dari dua aspek terkait. Pertama, negative face wajah negatif, yakni hak atas teritori diri, yang menyebabkan orang bebas bertindak dan bebas dari paksaan. Kedua, positive face wajah positif adalah citra diri yang konsisten dimiliki orang, yakni merupakan keinginan untuk dihargai dan setidak-tidaknya disetujui oleh sejumlah orang. Kedua aspek wajah ini dimiliki oleh setiap manusia, namun dalam suatu interaksi komunikasi kadang aspek wajah negatif lebih menonjol sehingga menyebabkan dampak tidak menyenangkan pada mitra tutur. Orang yang bertindak rasional berusaha menjaga kedua jenis wajah ini untuk dirinya dan orang yang berinteraksi dengannya. Brown dan Levinson juga berargumentasi bahwa dalam komunikasi manusia, baik tuturan maupun tulisan, orang cenderung menjaga wajah seseorang dari orang lain secara terus menerus. Namun adakalanya orang lain dibuat tidak nyaman atau dipermalukan lewat tuturan yang disampaikan atau tulisan yang dibuat. Tindakan demikian disebut sebagai tindakan 58 mengancam wajah (face threatening act – FTA). FTA adalah tindakan yang melanggar kebutuhan pendengar (mitra tutur) untuk menjaga harga dirinya dan dihargai. Untuk mengurangi dampak tidak menyenangkan dari FTA ini, Brown dan Levinson mengidentifikasi 4 strategi kesantunan yang biasa dilakukan orang dalam berinteraksi, yaitu: bald on-record, positive politeness, negative politeness, dan off-record-indirect. Keempat strategi itu dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan disertai contoh-cotoh (yang berbahasa Inggris dikutip dari artikel Bărbulet yang telah disebut di atas). Bald on-record strategy (strategi gundul / polos terekam). Dengan menggunakan strategi ini tidak satu pun ancaman terhadap wajah pendengar yang diminimalisasi. Tuturan atau tulisan ditampilkan apa adanya; sejauh hal itu masuk kategori tertentu, seperti yang disebutkan di bawah ini, maka itu masih dapat dikategorikan santun. Di luar dari kriteria ini, maka tuturan atau tulisan tersebut berpotensi mengancam wajah pendengar atau pembaca. Tuturan yang masih dapat dikategorikan santun, bila ia memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Pemberituhuan keadaan darurat (an emergency): help! 2) Berorientasi tugas (task-oriented): give me those! 3) Merupakan permohonan (request): put your jacket away! 59 4) Meminta kewaspadaan (alerting): turn your lights on! (while driving). Positive politeness strategy (strategi kesantunan positif). Strategi ini menunjukkan pengakuan penutur akan keinginan pendengar untuk dihargai. Strategi ini sekaligus juga mengkonfirmasikan bahwa hubungan ini adalah hubungan persahabatan dan mengekspresikan rasa kelompok yang sama. Tuturan atau tulisan yang menggunakan strategi kesantuan positif menampilkan ciri-ciri, seperti: 1) Menunjukkan perhatian pada pendengar: you must be hungry. It’s a long time since breakfast. How about some lunch? 2) Menghindari ketidaksetujuan dengan jalan tidak mengatakan secara langsung tetapi sedikit berputar-putar : A: What is she, small? B : Yes, yes, She’s small, smallish, um, not really small but certainly not very big. 3) Mengasumsi persetujuan dengan suatu penegasan: so when are you coming to see us? 4) Mengelak memberikan opini: you really should sort of try harder. Negative politeness strategy (strategi kesantunan negatif). Strategi ini mengakui wajah positif pendengar atau mitra tutur, tetapi di sisi lain strategi 60 ini juga mengakui bahwa penutur dengan beberapa cara memaksakan sesuatu pada pendengar. Ada beberapa contoh dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang bisa ditampilkan, seperti: 1) Penggunaan kata-kata: I don’t want to bother you but……. atau … I was wondering if ……. 2) Mengutarakan secara tidak langsung, misalnya dengan mengatakan: “saya mencari bolpoin”, padahal yang dimaksud adalah “saya membutuhkan sebuah bolpoin”. 3) Mengutarakan permintaan maaf yang diikuti permintaan yang sedikit memaksa : you must forgive me, but……. 4) Menggunakan kata yang memberi kesan meminimalisasi pemaksaan: I just want to ask you if I could use your computer. 5) Melipatgandakan tanggungjawab personal: we forgot to tell you that you needed to buy your plane ticket yesterday. Off-record indirect strategy (Strategi tidak langsung tidak terekam). Cara ini menanggalkan beberapa tekanan terhadap pendengar atau mitra tutur, dengan mencoba menghindari FTA secara langsung. Strategi ini diyakini merupakan cara yang paling santun untuk menghindari ancaman terhadap wajah. Untuk itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti: 61 1) Memberi isyarat dengan meminta pendapat mitra tutur sebelum permintaan sesungguhnya diajukan padanya, seperti: “Sedikit berangin di sini, bagaimana kalau jendela itu ditutup.” 2) Bertutur secara samar-samar: “Barangkali seseorang harus dapat lebih bertanggungjawab.” 3) Dengan cara bercanda atau bertutur dengan humor. Strategi ini setelah diuji pada beberapa bahasa yang ada di dunia ternyata tidak menunjukkan sifat keuniversalannya yang menonjol. Kesantunan berbahasa untuk sebagian besar bahasa-bahasa di dunia, sangat dipengaruhi oleh budaya yang melingkupi masyarakat penuturnya. Dilihat dari kecendrungan yang dilakukan masyarakat penutur InggrisAmerika, dapat disimpulkan bahwa mereka banyak menggunakan strategi kesantunan positif, sedangkan masyarakat Jepang lebih menggunakan strategi kesantunan negatif (lihat artikel Langcope mengenai The Universality of Face in Brown and Levinson’s Politeness Theory: A Japanese Perspective, dalam: longscope.pdf). 4. Bagaimana pikiran mengorganisasi bahasa Manusia memiliki kemampuan mengekpresikan berbagai hal. Untuk itu pertanyaan yang dapat diajukan adalah innerfaculties dan kemampuan 62 macam apa yang dimiliki manusia yang membuatnya dapat mengirim dan menerima pesan dalam berkomunikasi? Untuk memulainya, pertama-tama harus disadari bahwa manusia secara genetik telah dibekali Language Acquisition Devices (LAD), sarana penunjang manusia agar dapat berbahasa, sebagaimana teori yang diyakini Chomsky. Alat ini juga, diyakini banyak ahli (Dardjowidjojo, 2003:5) sebagai pembeda manusia dari hewan dalam hal kemampuan berbahasa. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan menyimpan semua impresi yang diperoleh lewat inderanya, dari dulu hingga sekarang, ke dalam gudang penyimpanan yang disebut mind, minda (dipinjam dari istilah Soenjono Dardjowidjojo). Minda ini dapat menampung semua memori yang sifatnya individual dan subjektif, karena mereka merupakan pengalaman dan aktivitas milik seseorang dan bukan milik orang lain. Bila harus memahami bagaimana orang berkomunikasi, kita harus memahami kecendrungan terhadap apa yang disebut mental furniture, karena itu adalah apa yang ada dalam batin seseorang (inwardy) yang ia ekspresikan ke luar (outwardy). Cara kita mengorganisasi ujaran kita merefleksikan bentuk dan lekuk (contour) pikiran kita. Bagaimana konfigurasi mental kita, mencirikan bagaimana kandungan minda kita; kandungan minda diorganisasi dan diatur dapat diakses ketika kita membutuhkannya tetapi tidak menonjol ketika kita tidak membutuhkannya. 63 Manusia memiliki kapasitas untuk menggeneralisasi dan mengidentifikasi. Ia dapat mengidentifikasi pengalaman baru dengan beberapa cara sebagai “hal yang sama” yang pernah ia alami sebelumnya, dan ia menyimpan kedua pengalaman ini pada tempat yang sama. Ia juga sepanjang hidupnya membandingkan dan mengkategorisasi, bahkan ketika aktivitas ini telah menjadi kebiasaan (habitual) yang terlatih di luar kesadaran. Menurut Callow (1998), kandungan mental manusia diorganisasi sebagai unit-unit sarang, suatu gambaran multidimensional yang terdiri dari blok-blok atau area atau bidang-bidang materi terkait, masing-masing merupakan area yang lebih kecil. Jadi seorang anak kecil memiliki area keluarga dalam mindanya, dengan sub area terpisah untuk ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain, dan untuk semua jenis peristiwa dan kejadian yang berbasis pada rumah, seperti bermain, makan, membantu ibu. Ketika ia besar ia menambah satu area di luar rumah, dan ini nantinya akan beraneka, ada area sekolah, hobby, dst. Sampai ia dewasa area-area ini akan terus bertambah sesuai dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuannya. Secara teknis, para ahli lain ada yang menggunakan istilah the faculties of mind (Chomsky), frame (Fillmore), mental space (Fouconnier) ataukah image schema (Lakoff). Namun intinya menggambarkan, bahwa muatan mental manusia seperti kotak dalam kotak atau ruangan-ruangan dalam satu bangunan, yang batasannya tidak begitu solid, karena kemampuan mental manusia untuk menyimpan beberapa detail dalam 64 pikirannya berada di bawah satu payung besar, di mana tiap-tiap kotak atau ruangan-ruangan kecil di bawahnya menyimpan pengalaman / pengetahuan yang telah dipisah-pisahkan berdasarkan kategori-kategori, bisa berdasarkan waktu kejadian, jenis peristiwa, relasi peristiwa, apakah penting, atau kurang penting, dsb. Ketika berbahasa, pikiran akan menampilkan ke permukaan simpanan yang ada pada satu area kemudian dengan cepat akan beralih pada area lain dan begitu seterusnya, sehingga nampak seolah-olah batas antara satu area dengan area lain tidak begitu jelas. Pengalaman masa lalu manusia disimpan di area-area di dalam minda, dan disimpan dalam bentuk unit-unit dalam unit besar. Manusia juga memiliki kemampuan untuk melihat peristiwa yang paling rumit sebagai satu kesatuan dengan beberapa cara. Pada saat yang sama ia juga memiliki kapasitas untuk melihat konstituen bagian sebagaimana mereka unit-unit tersendiri. Tanpa kapasitas ini, memori sebagaimana kita tahu, tidak dapat eksis dan pemikiran yang koheren tidak dapat terjadi. Namun demikian, tidaklah sesederhana itu, kadang pikiran kita dapat dikacaukan dan terjadi disorganisasi, lebih dari itu, bahkan berpikir sebagaimana kita tahu, dapat tidak terjadi sama sekali. Satu dari kapasitas-kapasitas esensial manusia yang membuat berpikir menjadi mungkin adalah mengenali kesatuan yang berhubungan dengan variasi-variasi bersama, dan variasi bergabung membentuk satu kesatuan. Namun kebanyakan dunia pikiran (the realm of the mind) tetap tersembunyi dari kita., jadi survey ini tidak dapat sempurna. 65 B. Kerangka Pikir Teks yang diasumsikan mengandung muatan “wacana kolonial”, secara empiris kehadirannya dapat diuji lewat pilihan kata-kata yang digunakan yang sifatnya tidak terbatas dan menyebar di sepanjang teks. Pilihan kata yang dimaksud dapat tampil dalam bentuknya sebagai kata lepas, frasa, klausa, dan rangkaian beberapa kalimat. Kehadiran kata-kata dan rangkaian kata ini secara teoretis tidaklah mungkin terlepas dari makna, apakah itu makna leksikal ataukah makna gramatikal. Makna bahasa, intinya, adalah titik berangkat yang akan dieksplorasi untuk sampai pada akhir dari tujuan penelitian ini. Untuk dapat mengeksplorasi makna leksikal dan gramatikal, diperlukan data kata-kata dan kalimat yang diasumsikan mengandung muatan “wacana kuasa kolonial” yang kehadirannya akan dimunculkan lewat pembedahan dengan menggunakan pisau teori analisis wacana yang diadopsi dari Laclau dan Mouffe. Dalam pembedahan ini, istilah nodal point (NP) akan digunakan ketika mengidentifikasi kata lepas dan frasa yang diduga mengandung muatan makna ‘kolonial’. Seperti pemahaman Laclau dan Mouffe, di sekitar NP ini juga dapat diidentifikasi kata-kata lain yang juga tidak terbatas, di mana penetapan maknanya sangat tergantung pada NP yakni makna istimewa 66 yang sejak awal akan ditetapkan lebih dulu. Kata-kata lain yang berada di sekitar NP ini, oleh Laclau dan mouffe disebut moments. Moment adalah makna sementara yang kepastian maknanya baru diperoleh ketika ia berada dalam suatu wacana khusus. Jadi moment adalah penanda wacana (kata) yang teridentifikasi berada di seputar penanda wacana istimewa yang akan ditetapkan lebih awal. Keberadaan moment di sekitar nodal point (NP) tidak terlepas dari keberadaan elements yang merupakan elemen bahasa atau tanda yang berpotensi memiliki makna multi. Untuk sampai menjadi moment, element direduksi makna lainnya, hingga tinggal menjadi satu makna akhir yang pasti. Satu makna pasti dari moment baru menjadi makna akhir, apabila tanda tersebut menjadi bagian dari satu wacana khusus. Data-data bahasa yang teridentifikasi ini dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi kelompok kata, frasa, dan kalimat yang mengandung muatan makna kolonial, yang nantinya akan menjadi sumber rujukan bila akan menganalisis makna ungkapan kolonial. Kemudian, melalui metode observasi akan dilakukan interpretasi makna terhadap wacana teks, yang pada akhirnya akan sampai pada menganalisis konteks yang terdapat dalam wacana teks kolonial. Dalam menganalisis makna semantik data-data kebahasaan akan diklasifikasi berdasarkan aspek-aspek pemaknaan teks bila dilihat secara 67 keseluruhan dan aspek-aspek makna khusus yang berkaitan dengan teori dan konsep semantik, juga akan didiskusikan pengelompokkan kata berdasarkan pandangan sosio-historis dan sosio-kultural. Secara singkat kerangka pikir ini dapat dihadirkan sebagaimana gambar berikut ini: Wacana Teks Kata, Frasa, Kalimat Makna Leksikal Konteks Kebermaknaan Teks Kolonial Gambar 1. Skema kerangka pikir Gramatikal 68 BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Untuk mendapatkan data-data bahasa yang bersifat kolonial yang diduga ada tersembunyi di balik praktik-praktik diskursif, pertama-tama dilakukan adalah membongkar seperangkat teks yang yang teridentifikasi mengandung muatan-muatan itu. Hal ini dilakukan dengan alasan karena analisis wacana sesungguhnya mengeksplorasi ide-ide dan objek-objek yang diproduksi atau dikonstruksi secara sosial, yang disebarkan ke seluruh teks, dipelihara, dan dipertahankan dari waktu ke waktu. Karena itu cara yang paling cocok untuk mendapatkan data kebahasaan ini adalah dengan menggunakan konsep teori yang telah dikembangkan oleh para analis wacana. Ada banyak teori dan konsep yang dikenal, namun penelitian ini sedikit banyak mengadopsi pemikiran analisis wacana Laclau dan Mouffe untuk mendapatkan data kebahasaan Analisis wacana tidak hanya sekedar metode, tetapi ia mewakili suatu metodologi yang mewujudkan suatu pandangan konstruksi sosial yang kuat (Gergen, 1999, sebagaimana dikutip oleh Philips dan Cynthia Hardy, 2002: 5). 69 Analisis wacana ini tidak sama dengan bentuk metodologi penelitian kualitatif lain, seperti pendekatan analisis naratif atau analisis konversasi yang khas kajian teks atau kajian konversasi. Kedua pendekatan kualitatif yang disebut terakhir ini memang memperhitungkan juga konteks untuk memastikan makna, tetapi biasanya tanpa referensi yang lebih luas atau tanpa memperhitungkan akumulasi bentuk-bentuk teks yang biasanya juga menentukan makna. Meskipun tertarik pada pengonstruksian naratif atau konversasi, pendekatan ini kurang secara eksplisit mempersembahkan perhatian pada konstruksi realitas sosial yang lebih luas. Sama halnya seperti pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui metodologi etnografi. Etnografi sering bertujuan membongkar makna realitas sosial dengan metode partisipasi, tetapi sering kurang memperhatikan bagaimana suatu realitas sosial bisa sampai menjadi eksis, yang biasanya terkonstruksi sebagai akibat dari berbagai wacana dan dari berbagai teks yang diasosiasikan padanya (Ibid: 6). Metodologi etno fokus pada aturan-aturan generatif yang memungkinkan hubungan antar relasi sosial, tetapi perhatiannya ini lebih kepada mengobservasi tindakan dari pada mengkaji teks. Analisis content, dalam bentuknya yang lebih interpretatif dapat digunakan dalam penelitian ini, untuk menghubungkan isi teks dengan konteks diskursif yang lebih luas. Misalnya mengidentifikasi tema atau topik, 70 strategi retorika yang digunakan, kemudian mengaitkannya dengan siapa yang berbicara dan siapa pendengar yang dituju. Penelitian ini juga akan memberdayakan teknik interpretatif, yakni pemaknaan secara pragmatik ujaran-ujaran individual dalam teks dan analisis semantik kata (leksikal) digunakan untuk memaknai lebih jauh kata-kata yang dipilih secara khusus. Perlu ditekankan kembali di sini, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian purposif-kualitatif, artinya data yang telah diidentifikasi hanya akan dianalisispemaknaannya sesuai kebutuhan, untuk memperlihatkan konsepkonsep yang sesuai dengan pemahaman teori analisis semantik. B. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh teks yang diproduksi pada masa penjajahan dulu di Hindia, dalam rentang waktu yang dibatasi mulai Abad 19 hingga paruh awal Abad 20, oleh Belanda sebagai pihak yang menjajah ketika itu, dan diaktualisasikan dalam dengan menggunakan bahasa Belanda. bentuk teks tertulis Teks ini merupakan perspektif mereka tentang Hindia dengan segala permasalahannya, terutama yang berkaitan dengan peran mereka sebagai penguasa dalam mengelola tanah jajahan. Khusus penelitian ini, sumber data sebagai sample dibatasi pada teksteks yang telah ditetapkan secara eclectic yang berada pada rentang waktu 71 yang telah diputuskan, dan memiliki bentuk khusus berupa novel, roman, cerpen, laporan-laporan atau dokumen-dokumen pemerintahan. Sedangkan data yang dikumpulkan dari nya berupa kata-kata lepas, frasa, dan kalimat-kalimat yang sesuai dengan arah tujuan penelitian. Katakata dan kalimat-kalimat ini diambil dari sumber data yang telah ditetapkan sebagai sample dan diterima sebagai data primer, sehingga dengan demikian keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan sumber data sekunder juga kadang diperlukan, bila harus menjelaskan konteks yang melatari penjelasan akan kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut. C. Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberdayakan teori Laclau dan Mouffe dalam menghimpun data kata-kata, rangkaian kata, yang menyimpan karakteristik kolonial, di samping juga mengidentifikasi ungkapan-ungkapan bahasa dalam bentuk tuturan langsung, dan tidak langsung yang terdapat dalam beberapa teks kolonial yang menjadi sumber data penelitian. Mengikuti konsep dan teori Laclau dan Mouffe, pertama-tama akan ditetapkan nodal point (tanda/kata yg diberi hak istimewa) 72 Langkah berikut di sekitar nodal point diidentifikasi moments (tanda/ kata yg maknanya telah ditetapkan sebagian) yang mendukung wacana yang sedang dibentuk. Untuk mendapatkan tanda/kata yang dimaksud akan dirancang suatu metode di mana dengan cara ini akan ditetapkan lebih dulu beberapa pertanyaan penuntun yang dipastikan akan dapat mengarahkan pemikiran dan perhatian dalam mengidentifikasi moments. Cara ini bersifat filosofis, dalam pengertian bahwa cara berpikir yang dilakukan dapat dimulai secara rasional baru kemudian menemukan data secara empiris dalam teksteks yang dimaksud. Namun dapat juga dilakukan dengan cara sebaliknya, menemukan data secara empiris, yakni semua tanda/kata yang telah teridentifikasi lewat pembacaan akan dicatat dan dikumpulkan untuk selanjutnya akan diklasifikasi dan dikategorisasi sesuai prinsip-prinsip rasionalisme wacana yang telah ditetapkan. C. Teknik Analisis Data Data-data yang terkumpul, diklasifikasi berdasarkan kelompok kata lepas, frasa, mengandung pemaknaannya dan kalimat. muatan Ungkapan-ungkapan ‘wacana berdasarkan kuasa aspek-aspek yang kolonial’ pemaknaan akan diidentifikasi dianalisis negatif secara langsung dan tidak langsung. Mengeksplorasi pemaknaan negatif ini tentu 73 dengan mempertimbangkan konteks pengetahuan, nilai-nilai, dan moral yang dianut penutur bahasa. Untuk itu, data kata yang akan dianalisis ditentukan lebih dulu makna leksikalnya sebagaimana yang tertera dalam kamus, namun dalam penulisan di sini akan diekspresikan dalam bentuk padanannya dalam bahasa Indonesia atau diparafrasekan untuk makna leksikal yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Kemudian, dilakukan analisis makna gramatikal yang berkaitan dengan lingkungan fisik kalimat di mana kata itu ditempatkan. Dari situ dapat dijabarkan konsep makna kata sebagaimana diperkenalkan oleh teori tentang makna. Agar diperoleh ciri-ciri yang lebih rinci mengenai konsep suatu kata, maka perlu dieksplorasi pengetahuan dan hal-hal lain yang menjadi latar belakang untuk memahami kata tersebut. Konteks dalam pengertian luas akan ditelusuri dan dicoba untuk diinterpretasi agar kebermaknaan wacana kolonial dapat dimunculkan. 74 DAFTAR PUSTAKA Adinda, 1892, Vrouwen Lief en Leed Onder de Tropen (roman), Schrool – Conserve [Indische Letterenreeks: 4], Eerder verschenen: Utrecht: Beijers. Allwood, J. and Gӓrdenfors, P. (eds), 1999, Cognitive Semantics: Meaning and Cognition, John Benjamin B.V., USA. Beaugrande, R. De, 1991, Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works, Longman, London and New York. Bărbulet, Gabriel, tanpa tahun, The politeness Principle – A Fundamental Dimension (online), diakses 6-11-2011. Bhatia, V.K., et al. 2008, Advances in Discourse Studies, Routledge, USA a…….and Canada. Blackledge, A., 2005, Discourse and Power in a Multilingual World (Discourse Approaches to Politics,Society and Culture), John Benjamin, B.V., USA. Boas, F., 1966, Introduction to Handbook of American Indian Languages, The University of Nebraska Press, United States of America. Bourdieu, P. (edited and introduced by John B. Thompson), 1991, Language and Symbolic Power (translated by Gino Raymond and Matthew Adamson), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. Brugge, Carry van, 1909, Goenong-Djatti (roman), Schoorl – Conserve [Indische Letterenreeks: 1], Eerder verschenen Amsterdam. Brugge, Carry van, 1921, Een Indisch Huwelijk (novelle), Schrool – Conserve [Indische Letterenreeks: 2], Eerder verschenen Amsterdam. Caldas-Coulthard, C.R. and Coulthard, M. (eds.), 2003, Texts and Practices. Readings in Critical Discourse Analysis, Roudledge, New Yorlk. 75 Callow, K., 1998, Man and Message. A Guide to Meaning-Based Text Analysis, Summer Institute of Linguistics, Inc., Lanham-New YorkOxford. Campen, C. van, De Verwarring der Zintuigen. Artistieke en Psychologische Experimenten met Synesthesie (online), http://www.synesthesie.nl/pub/synp&m96.htm (diakses 14-9-2010). Cobley, P., 2001, “Introduction” dalam: The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics, Routledge, London and New York. Croft, W. and Cruse, D. A. 2004, Cognitive Linguistics, Cambridge Press, United Kingdom. Cruse, A., 2004, Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford University Press, New York. Cummings, L., 2007, Pragmatik. Sebuah Perspektif Multidisipliner, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Dardjowidjojo, S., 2010, “Bahasa dan Pola Berpikir Bangsa Kita,” dalam: Jurnal Linguistik Indonesia tahun ke 28, nomor 2, Masyarakat Linguistik Indonesia, Jakarta. Dardjowidjojo, S. 2003, Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Daum, P.A., 1895/1989, Batavia-Amsterdam Reisschets, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam. Daum, P.A., 1890/1982, H. van Brakel, Ing. B.O.W. (Salamander), Em. Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam. Daum, P.A., 1895/1987, Goena-Goena (Salamander), Em. Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam. De Jong, G. F., 1975, The Dutch In Amerika 1609-1974, Twayne Publishers a Division of G.K. Hall & Co, Boston. Djajasudarma, T. F., 2012, Wacana & Pragmatik, Refika Aditama, Bandung. Douglas, P.A., 2009, “Unveiling Dutch America. The New Netherland Project”, 76 Dalam: The Low Countries, The Flemish-Netherlands Association Ons Erfdeel vxw. Driven, R. en Verspoor, M. (reds), 2001, Cognitieve Inleiding tot Taal en Taalwetenschap, Uitgeverij Acco, Leuven. Drooglever, P.J., 1991, Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam. Eriyanto, 2001, Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media, LKiS, Yogyakarta: Evans, V. and Green, M., 2006, Cognitive Linguistics An Introduction, Lawrence Ertbaum Associates Inc.Publishers, New Jersey. Fairclough, N., 1995, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Longman, London and New York. Fouconnier, G., 1985, Mental Space: Aspects of Meaning Construction in Natural Language, MIT Press/Bradford, Cambridge, MA/London. Goddard, Cliff (ed), 2008, Cross Linguistic Semantics, Jhon Publishing, Amsterdam/Philadelphia. Benjamin Guevara, E., 2006, Lexical Semantics Book Review. Corpora in Cognitive Linguistics: Corpus Based Approaches to Syntax and Lexis. Stefan Gries and Anatol Stefanowitsch (eds), Mouton de Gruyter (online). Guevara-corpora-in-cognitive-linguistics.pdf-Adobe Reader (diakses 6-112010). Halliday, M.A.K., 1978, Interpretation of Australia/USA: Language as Social Semiotic. The Language and Meaning, Edward Social Arnold, Hymes, D., 1986, Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, Eight Paperback Printing, USA. Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973), masalah pendidikan, no reg.48-49, 91-92. Inventaris Arsip Selayar (1823-1973), masalah pendidikan, no reg. 369, 370, 373, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 388. 77 Jackendoff, R., 2001, “Language in the Ecology of the Mind”, dalam: The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics edited by Paul Cobley, Routledge, London and New York. Jansma, K. en Schroor, M. (red), 1987, Onze Vaderlandse Geschiedenis, Uitgeverij Inter-Combi van Seijen, Leeuwarden. JSTOR, Ethnophaulisms and Ethnocentrism. American Journal of Sociology (online), Vol 67, No 4 (Jan, 1962) (http://www.jstor.org/pss/2775144, diakses 26-11-2011). Kompas, 10 Januari 2011, Anggota Kongres Kritis. Si Penembak Diduga Tidak Sendirian, 8. Kompas, 15 Januari 2011, Palin Terus Diserang, 9. Kompas, 15 Januari 2011, “Fitnah Darah” Semitisme di Eropa, 9. Jejak Sejarah Kelam Anti- Kompas (Liputan Khusus: Ekspedisi Cincin Api), 28 Juli 2012, New York Pun Ditukar dengan Pulau Run, 36. Knaap, G.J., 1991, Inleidende opmerkingen over de geschiedenis van Indonesië tot circa 1870, dalam Drooglever, P.J., 1991, Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam. Kramsch, C., 1998, Language and Culture, Oxford University Press, UK. Laclau, E. and Mouffe, C., Hegemony and Socialist Strategy. Towards Radical Democratic Politics, Verso, London. a Longcope, P. The Universality of Face in Brown and Levinson’s Politeness Theory: A Japanese Perspective (online), langscope.pdf (diakses 6-112011). LuMing, Robert Mao, 1994, Beyond politeness theory: “Face” revisited and renewed. Journal of Pragmatics 21: 451-486. Matthes, B.F., “Verslag van een Verblijf in de Binnenlanden van Celebes, van 24 April tot 24 October 1856”, dalam: Van den Brink, H., 1943, Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn Leven en Arbeid in Dienst van het Nederlandch Bijbelgenootschap, Nederlandsch Bijbelgenootschap, 78 Amsterdam. Matthes, B.F., “Beknopte Verslag van een Paar Tochten in de Binnenlanden van Celebes, Gedurende de Jaren 1857 en 1861”, dalam: Van den Brink, H., 1943, Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn Leven en Arbeid in Dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. McGilvray, J. (ed), 2005, The Cambridge Companion Cambridge University Press, Cambridge. to Chomsky, Nieuwenhuys, R., 1972, Oost-Indische Spiegel, E.M. Querido’s N. V., Amsterdam. Uitgeverij Nieuwenhuiys, R., 1988, “Kartini” dalam: Orientatie, Literair-cultureel tijdschrift in Indonesië [1947-1953] (onder red.van Peter van Zonneveld), Schoorl-Conserve, Peeters, B. (ed.) 2006, Semantic Primes and Universal Grammar: Empirical Evidence from Romance Languages, John Benyamin B.V., The Nederland / Philadelphia. Philips, N. and Hardy, C 2002, Discourse Analysis. Investigating Processes of social construction (Qualitative Research Methods Series 50), Sage Publication International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks London, New Delhi. Phillips, L. and Jorgensen, M. W. 2004, Discourse Analysis as Theory and Methods, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi. Riemer, Nick, 2010, Introducing Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, UK. Roeffaers, H., 2004, Taal Woordkunst. Een Filosofische Garant-Uitgevers n.v., Antwerpen-Apeldoorn. Verkenning, Rutten, G.J.E., 2004, Wittgenstein’s Tractatus Logico Philosophicus (online), wittgensteinstractatus.pdf-Adobe Reader (diakses 19-10-2010). Samuel, J., 2008, Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta. Saussure, F. de. translated and annotated by Roy Harris, Course in General 79 Linguistics, Duckworth, Britain. Shimp, T.A. and Sharma, S., Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the Cetscale. Journal of Marketing Research, Vol. XXIV (August, 1987), hal 280-289. (online), consumer ethnocentrism construction and validation of the CETSCALE.pdf (diakses 26-112011). Siauw, F. Y., 2012, Muhammad Al- Fatih 1453, Khalifah Press, Jakarta. Sternberg, R. J., 2008, Psikologi Kognitif, Pustaka Pelajar, Jogyakarta. Talmy, L., Cognitive Semantics: An Overview (online), http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/talmy/talmyweb/recent/overview.ht ml. (diakses 30-9-2010). Titscher, S., et al., 2005, Methods of Text and Discourse Analysis, Sage Publications Ltd., London: Urmson, J.O. and Sblsa, M. (ed), 1962/1975, How to Do Things with Words. J.L. Austin. Van den Brink, H., 1943, Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn Leven en Arbeid in Dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Van Dijk, T.A. (ed), 2004, Discource As Social Interaction. Discourse Studies 2, A Multidisciplinary Introduction, Sage Publication Ltd., London. Van Dijk, T.A., 2009, Society and Discourse. How Social Contexts Influence Text and Talk, Cambridge University Press, UK. Verhaar, J.W.M., 2008, Asas-Asas Linguistik Umum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Verschuren, J. and Östman, J-O, 2009, Key Notions for Pragmatic, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam / Philadelphia. Violi, P. (Translated by Jeremy Carden), 2001, Meaning and Experience, Indiana University Press, USA. Walraven, W., 1988, “Ngawi” dalam: Orientatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesië [1947-1953], Schrool-Conserve. 80 Wetherell, M., et al., 2005, Discourse Theory and Practice: A Reader, Sage Publication Ltd., London. Widdowson, H.C., 2004, Text, Context, Pretext. Critical Issues in Discourse Analysis, Blackwell Publishing, USA. Wierzbicka, A. and Goddard, C.(ed), 1994, Semantic and Lexical Universal, John Benyamin Publishing Company, The Netherland / USA. Wit, A. de, 1903, De Godin die Wacht (roman), Schrool – Conserve [Indische Letterenreeks: 6], Oorspr. Uitg. Amsterdam: Van Kampen. Wit, A. de, 1920, De Drie Vrouwen in Het Heilige Woud [Indische Letterenreeks No.: 7], Meulenhoff, Amsterdam. Wodak, R. and Meyer, M. (eds), 2009, Methods of Critical Discourse Analysis, Sage Publications Ltd., London. Wodak, R. and Chilton, P. (eds), 2005, A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity (Discourse Approaches to Politics, Society and Culture), John Benjamin Publishing Company, USA. Yule, G., 2006, Pragmatik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Zeggelen, M. van, 1920 / 1909, Onderworpenen. Schetsen uit Celebes, Schrool - Conserve (Indische Letteren-reeks; nr.8), Oorspr. Uitg. Semarang: Masman & Stroink; Amsterdam: Meulenhoff. Zonneveld, P. van (red), 1988, Oriëntatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesië [1947-1853], Schoorl-Conserve. 81 Kamus: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Elfde herziene druk, 1984, Van Dale lexicografie: Utrect / Antwerpen. Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Vermeerderde Druk, 1913, J.B. Wolters: Groningen. Taal, Tiende, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal, Zeventwintigste Druk, 1975, H.D. Tjeenk Willink BV: Groningen. 82 83