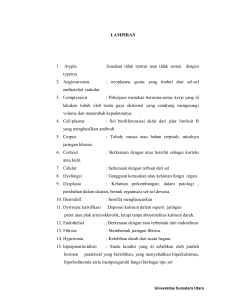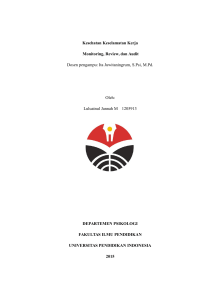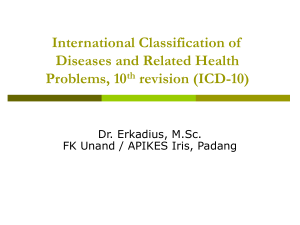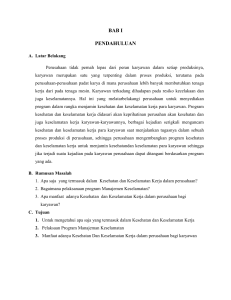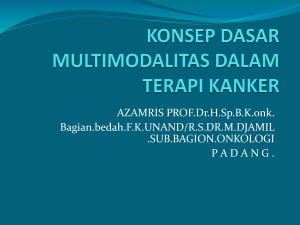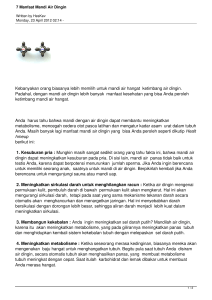Laporan Penelitian Korelasi antara Rentang Waktu
advertisement

Daftar Isi Laporan Penelitian Korelasi antara Rentang Waktu Cedera Otak Traumatik dengan Dimulainya Terapi Pembedahan Kraniotomi terhadap Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) Radian Ahmad Halimi, Iwan Fuadi, Tatang Bisri .................................................................. 141–48 Laporan Kasus Penatalaksanaan Anestesi dengan TIVA Propofol-Dexmedetomidine-Fentanyl untuk Operasi Meningioma Frontalis Sinistra Rebecca S. Mangastuti, Himendra Wargahadibrata, Nazaruddin Umar................................. 149–56 Tehnik Proteksi Otak pada Pembedahan Non Neurosurgery (Radical Neck Dissection) dengan Premorbid Space Occupying Lesion (SOL) dan Infark Serebri Buyung Hartiyo Laksono, Siti Chasnak Saleh........................................................................ 157‒63 Anestesi untuk Malformasi Arnold Chiari Ardana Tri Arianto, MH Soedjito........................................................................................... 164–72 Awake Craniotomy pada Biopsi Steriotaktik Tumor Supratentorial di daerah Thalamus Dextra et causa Suspect Thalamic Glioma Muhammad Dwi Satriyanto, Siti Chasnak Saleh .................................................................. 173–79 Pemantauan Neurofisiologis Intraoperatif selama Anestesia untuk Operasi Meningioma Foramen Magnum Riyadh Firdaus, Bambang Suryono, Siti Chasnak Saleh.......................................................... 180–88 Tinjauan Pustaka Terapi Hipotermi setelah Cedera Otak Traumatik Dewi Yulianti Bisri, Tatang Bisri........................................................................................... 189–98 Disseminated Intravascular Coagulation pada Cedera Otak Traumatik Agus Baratha Suyasa, Sudadi, Bambang Suryono ................................................................ 199–205 Korelasi antara Rentang Waktu Cedera Otak Traumatik dengan Dimulainya Terapi Pembedahan Kraniotomi terhadap Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) Radian Ahmad Halimi, Iwan Fuadi, Tatang Bisri Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung Abstrak Latar Belakang dan Tujuan: Keluhan nyeri kepala setelah terjadinya Cedera Otak Traumatik (COT) dikenal sebagai Post Traumatic Headache (PTH) yang dapat terjadi setelah cedera kepala ringan, sedang, atau berat. Tujuan penelitian ini adalah mencari apakah ada korelasi antara rentang waktu kejadian COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi terhadap angka kejadian dan beratnya PTH. Subjek dan Metode: Penelitian observasional kohort prospektif pada 33 orang pasien COT derajat ringan atau sedang dengan pengambilan data secara consequetif sampling. Parameter yang dicatat dalam penelitian ini antara lain usia, jenis kelamin, berat badan, GCS, rentang waktu dari kejadian COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi, angka kejadian PTH, derajat berat nyeri dengan menggunakan sistem penilaian Numeric Rating Scale (NRS). Analisis korelasi linear dua variabel dihitung berdasarkan analisis korelasi Spearman. Hubungan korelasi bermakna bila koefisien korelasi (R) >0,4 dan nilai p<0,05. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara rentang waktu terhadap kejadian PTH (r = 0,75) dengan korelasi searah dan bermakna (p<0,05). Terdapat korelasi yang kuat antara rentang waktu terhadap derajat beratnya PTH (r = 0,82) dengan korelasi searah dan bermakna (p<0,05). Simpulan: semakin lama rentang waktu dari kejadian COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi maka akan semakin banyak angka kejadian dan semakin berat PTH. Kata kunci: cedera otak traumatik, post traumatic headache, numeric rating scale JNI 2014;3 (3): 141‒48 The Correlation between The Interval of Traumatic Brain Injury with Craniotomy Surgery Start on The Incidence and Severity of Post Traumatic Headache (PTH) Abstract Background and Objective: Complaints of headache in the aftermath of Traumatic Brain Injury (TBI) is known as Post Traumatic Headache (PTH), which can occur after mild, moderate, or severe head injury. The purpose of this study is to find a correlation between the time span from the TBI events until the craniotomy surgical therapy was performed with the incidence and severity of PTH. Subject and Method: Prospective observational cohort study in 33 patients with mild or moderate TBI with data retrieval consequetif sampling. The parameters recorded in this study including age, gender, weight, GCS, time interval between the events of TBI until the craniotomy surgical therapy was performed, the incidence of PTH, severity of pain using NRS score. Analysis of linear correlation of two variables calculated by Spearman correlation analysis. Significant correlation when the correlation coefficient (R) > 0.4 and p < 0.05. Result: The results showed a strong correlation between the interval of the incidence with the incidence of PTH (r = 0.75) with unidirectional and significant correlation (p< 0.05). There is a strong correlation between the time span from TBI events until the craniotomy surgical therapy with the severity of PTH (r = 0.82) with unidirectional and significant correlation ( p< 0.05). Conclusions: the longer of interval between the TBI events to craniotomy surgical treatment, the more of the incidence and severity of PTH. Key words: traumatic brain injury, post traumatic headache, numeric rating scale JNI 2014;3 (3): 141‒48 141 142 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Cedera otak traumatik (COT) merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan pada masyarakat Barat.1 Kejadian COT memiliki insidensi yang tinggi terutama pada usia muda.2 The Center for Disease Control (CDC) melaporkan bahwa pada pasien dengan COT terhitung sekitar 1,4 juta pasien perlu dirujuk ke ruang gawat darurat, 275.000 ribu pasien perlu dilakukan rawat inap di rumah sakit, dan 52.000 pasien meninggal setiap tahunnya.3 Angka kejadian keseluruhan COT di Amerika Serikat terhitung 538,2 per 100.000 populasi atau sekitar 1,5 juta kasus baru di tahun 2003. Telah dilaporkan angka kejadian yang lebih rendah di negara Eropa (235 per 100.000) dan Australia (322 per 100.000).4 Pada daerah industri seperti Amerika, sebanyak 45% mekanisme penyebab COT adalah akibat kecelakaan kendaraan bermotor, 30% karena mekanisme jatuh, 10% akibat kecelakaan kerja, 10% kecelakaan rekreasi, dan 3% karena kecelakaan akibat kekerasan.5 Berdasarkan tingkat keparahannya COT dibagi menjadi derajat ringan, sedang, dan berat. Tingkat keparahan COT ini tentu mempengaruhi beratnya gangguan neurologis dan fungsionalnya. Di Amerika Serikat angka kejadian kecacatan jangka panjang akibat COT berkisar antara 3,2– 5,2 juta penduduk atau 1–2% dari total populasi, dengan insidensi terjadinya cedera kepala berat adalah 10%, 10% mengalami cedera kepala sedang, dan 80% mengalami cedera kepala derajat ringan.6 Saat ini penatalaksanaan COT dilakukan berdasarkan konsep COT primer atau sekunder. Terapi pembedahan karena adanya lesi pada otak merupakan terapi inisial pada COT primer. Identifikasi, pencegahan, dan penatalaksanaan terhadap COT sekunder merupakan fokus prinsip pada manajemen neurointensif.4 Pada pasien COT primer dengan lesi intrakranial, dapat dilakukan terapi konservatif atau terapi pembedahan, tergantung pada jumlah volume perdarahannya. Adanya hematoma dan edema pada COT dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Selain itu adanya mekanisme kaskade cedera molekuler saat awal terjadinya trauma yang kemudian berkembang hingga beberapa hari, dan diikuti oleh edema otak, peningkatan tekanan intrakranial dapat menyebabkan terjadinya kematian pada sel dan mengeksaserbasi cedera kepala.4 Suatu studi prospektif menunjukkan bahwa pada satu tahun setelah terjadinya COT terdapat 72,6% pasien mengeluh nyeri kepala dimana 47,2% pasien mengeluh nyeri ringan, dan 25,4% pasien mengeluh nyeri derajat sedang hingga berat.7 Keluhan nyeri kepala yang paling sering timbul setelah terjadinya COT dikenal sebagai Post Traumatic Headache (PTH) yang dapat terjadi setelah cedera kepala ringan, sedang, atau berat. Gejala PTH biasanya hilang dalam 3 bulan, namun telah dilaporkan gejala yang menetap pada beberapa kejadian.8 Secara keseluruhan angka kejadian PTH terjadi sekitar 4% dari seluruh nyeri kepala simptomatis. Suatu penelitian menyatakan bahwa 31,3–90% pasien mengalami nyeri kepala hingga 1 bulan, 47–78% hingga 3 bulan, 8,4–35% hingga 1 tahun, dan 25% pasien hingga 4 tahun.5 Didapatkan beberapa jenis nyeri kepala yang terjadi setelah COT antara lain; nyeri kepala tipe migraine, nyeri kepala tipe tension, nyeri kepala tipe cervicogenic dan nyeri kepala tipe rebound. Pada kebanyakan pasien, PTH dapat sembuh spontan dalam beberapa bulan, akan tetapi, ada sebagian kasus PTH yang menetap.9 Suatu penelitian melaporkan bahwa 87,3% pasien dengan PTH mengeluh nyeri kepala tipe tension, 10% yang terjadi setiap harinya dengan intensitas nyeri derajat sedang (verbal rating scale adalah 6).1 Kriteria diagnostik PTH tidak memerlukan fenotip nyeri kepala secara spesifik. Kualitas nyeri kepala dalam bentuk apapun dapat diterima untuk dilakukannya diagnosis, karena tidak terdapat karakteristik PTH dengan bentuk yang khusus.1 Post Traumatic Headache merupakan suatu permasalahan medis dan sosioekonomi serius, yang perlu penanganan yang tepat dan adekuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya nyeri kepala yang kronis.1 Suatu penelitian menunjukkan bahwa ketika PTH dapat terdiagnosa dengan cepat dan penatalaksanaan PTH dilakukan secara adekuat, maka pada kebanyakan pasien dengan gejala PTH dapat disembuhkan. Apabila PTH tidak dapat disembuhkan maka akan dimodulasi dan menetap Korelasi antara Rentang Waktu Cedera Otak Traumatik dengan Dimulainya Terapi Pembedahan Kraniotomi terhadap Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) hingga waktu yang lama.10 Antara kejadian trauma dan dimulainya nyeri kepala akan berkorelasi dengan waktu dilakukannya terapi.11 Berdasarkan data-data diatas maka rentang waktu dari mulai terjadinya hematoma, edema, iskemia hingga dimulainya terapi, akan sangat berperan dalam menentukan hasil luaran pasien, yang biasanya dinilai dengan Glasgow Outcome Scale (GOS) atau GOSE (extended GOS), dengan salah satu parameter dari GOSE adalah gangguan fungsi kognitif dan PTH.9 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara rentang waktu cedera otak traumatik dengan dimulainya terapi evakuasi hematoma intrakranial terhadap kejadian dan beratnya PTH. II. Subjek dan Metode Penelitian Penelitian observasional kohort prospektif dilakukan pada 33 pasien yang menjalani operasi kraniotomi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dengan kriteria inklusi adalah pasien pria atau wanita dengan cedera kepala derajat ringan atau sedang yang dilakukan terapi pembedahan kraniotomi, umur antara 13 hingga 59 tahun, pada pemeriksaan CT-scan kepala didapatkan hematoma intrakranial, hematoma ekstra aksial, atau fraktura terdepresi, dan pasien yang mendapatkan kembali kesadarannya setelah terapi pembedahan kraniotomi. Kriteria ekslusi adalah pasien yang memiliki cedera servikal, pasien yang memiliki riwayat nyeri kepala berulang sebelum terjadinya trauma, dan pasien yang sedang dalam pengaruh alkohol atau intoksikasi obat-obatan. Kriteria pengeluaran adalah pasien yang tidak mendapatkan kembali kesadarannya setelah lebih dari 2 minggu pasca kraniotomi, pasien yang meninggal selama masa penelitian, dan pasien yang dengan gangguan fungsi kognitif yang dinilai dengan menggunakan skoring Mini Mental State Examination (MMSE). Parameter yang dicatat pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, berat badan, GCS, rentang waktu dari mulai terjadinya COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi, angka kejadian PTH yang dinilai setelah pasien sadar penuh dan dinilai hingga 1 minggu, Derajat beratnya PTH dengan menggunakan skor NRS. 143 Dilakukan analisis korelasi linear dua variabel yang dihitung berdasarkan analisis korelasi Spearman. Hubungan korelasi bermakna bila koefisien korelasi (R) >0,4 dan nilai p<0,05. III. Hasil Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata usia pasien dalam penelitian ini adalah 26,96 tahun dengan usia termuda 14 tahun dan usia tertua 52 tahun. Rata-rata berat badan pada pasien ini adalah 60,77 kg dengan berat badan terendah adalah 48 kg dan berat badan tertinggi adalah 80 kg. Sebagian besar jenis kelamin pada penelitian ini adalah laki-laki, rentang GCS pada penelitian ini adalah 9 pada rentang bawah dan 15 pada rentang atas. Selain itu rentang waktu kejadian pada penelitian ini adalah 6 jam hingga 12 hari, dengan rentang penilaian NRS berkisar antara 0 hingga 8, dan sebagian besar pasien mengalami PTH. Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian Variabel Umur Pasien (tahun) Berat Badan (Kg) Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Rentang Waktu (jam) NRS Score GCS Pasien n(%) Rerata (SD) 26,96 (12,06) 60,77 (7,92) Median 13,09 (5,78) 12,00 25 60 22 (71,0%) 9 (29,0%) 11,32 (1,97) 5,00 11,00 Keterangan: NRS: Numeric Rating Scale; GCS: Glasgow Coma Scale; PTH: Post Traumatic Headache Tabel 2 menunjukkan analisis korelasi yang digunakan untuk menganalisis korelasi antara antara variabel numeric dengan nominal yaitu dengan menggunakan analisis korelasi point biserial. Berdasarkan dari analisis statistika diperoleh p value sebesar <0,0001 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 (p<0,05) maka hal ini menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistika maka dapat disimpulkan 144 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Tabel 2. Korelasi antara Rentang Waktu dengan Kejadian PTH Variabel PTH PTH R Nilai p (+) (-) Rentang 0,75 <0,0001** Waktu 15.31 7,66 Mean (SD) (5.38) (1.65) 14,00 8,00 Median 18,00 5,00 Range Keterangan: Analisis Korelasi Point Biserial; nilai kemaknaan p<0,05. Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistika. r: koefisien korelasi. PTH: Post Traumatic Headache terdapat korelasi antara Rentang Waktu kejadian COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi dengan kejadian PTH. Dari nilai koefisien korelasi (R) diperoleh informasi bahwa arah korelasi positif dengan kekuatan korelasi kuat antara Rentang Waktu kejadian COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi dengan kejadian PTH. Dengan menggunakan analisis statistik point biserial, maka didapatkan nilai r: 0.75; nilai p=0.0001 (p<0,05). Setelah melalui pengujian hipotesis dan hasilnya signifikan, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan Kriteria Guilford (1956), yaitu: 1. ≥0,00→<0.20=> Korelasi yang sangat kecil dan bisa diabaikan 2. ≥0,20→<0,40=> Korelasi yang kecil (tidak erat) 3. ≥0,40→<0,70=> Korelasi yang moderat 4. ≥0,70→<0,90=> Korelasi yang kuat 5. ≥0,90→<1,00=> Korelasi yang sangat kuat Dari kriteria diatas maka keeratan hubungan atau korelasi pada tabel diatas untuk variabel Rentang Waktu dengan PTH, memiliki hubungan atau korelasi yang kuat menurut kriteria Guillford. Tabel 3 menunjukkan bahwa data pada penelitian tidak berdistribusi normal berdasarkan uji kenormalan data dengan uji Shapiro Wilks Test maka analisis selanjutnya dengan analisis korelasi antara variabel numeric dengan numeric yaitu dengan analisis korelasi Spearman. Berdasarkan dari analisis statistika diperoleh p value sebesar Tabel 3. Koefisien Korelasi antara Rentang Waktu terhadap Berat PTH yang diukur dengan menggunakan skor NRS Variabel Rentang Waktu Skor NRS R 0.82* Nilai p <0.0001** Keterangan: Analisis Korelasi Pearson apabila data normal, alternatif Spearman apabila data tidak berdistribusi normal ; nilai kemaknaan p <0,05.Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistika. r: koefisien korelasi. NRS: Numeric Rating Scale <0,0001 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 (p<0,05) maka hal ini menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistika maka dapat disimpulkan terdapat korelasi antara rentang waktu dengan NRS Score. Dari nilai koefisien korelasi (R) diperoleh informasi bahwa arah korelasi positif dengan kekuatan korelasi kuat antara rentang waktu dengan NRS Score. Dengan menggunakan analisis statistik korelasi Spearman, maka didapatkan nilai r:0.82; nilai p=0.0001 (p<0,05). Setelah melalui pengujian hipotesis dan hasilnya signifikan, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan Kriteria Guilford (1956), yaitu: 1. ≥0,00→<0,20=> Korelasi yang sangat kecil dan bisa diabaikan 2. ≥0,20→<0,40=> Korelasi yang kecil 3. ≥0,40→<0,70=> Korelasi yang moderat 4. ≥0,70→<0,90=> Korelasi yang kuat 5. ≥0,90→<1,00=> Korelasi yang sangat kuat Dari kriteria diatas maka keeratan hubungan atau korelasi pada tabel diatas untuk variabel Rentang Waktu dengan NRS Score, memiliki hubungan atau korelasi yang kuat menurut kriteria Guillford. IV. Pembahasan Keluhan nyeri kepala yang paling sering timbul setelah terjadinya COT dikenal sebagai Post Traumatic Headache (PTH) yang dapat terjadi setelah cedera kepala ringan, sedang, atau berat.8 Kriteria diagnostik PTH tidak memerlukan fenotip nyeri kepala secara spesifik. Kualitas nyeri kepala dalam bentuk apapun dapat diterima untuk dilakukannya diagnosis, karena tidak Korelasi antara Rentang Waktu Cedera Otak Traumatik dengan Dimulainya Terapi Pembedahan Kraniotomi terhadap Kejadian dan Beratnya Postt Taumatic Headache (PTH) terdapat karakteristik PTH dengan bentuk yang khusus.1 Pada satu penelitian dinyatakan bahwa hasil luaran dari PTH ditentukan oleh faktor usia, jenis kelamin dan tingkat depresi seseorang. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan pada 33 subyek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dengan usia rata-rata 26,96 tahun, berat badan rata-rata 60,77 kg, jumlah pasien dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 71% dan jenis kelamin wanita sebanyak 29%. Subjek penelitian memiliki rentang waktu dari terjadinya COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi rata-rata sebesar 13,09 jam, penilaian NRS rata-rata sebesar 4,03 dan angka kejadian PTH sebesar 71%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama rentang waktu dari kejadian COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi maka akan semakin sering kejadian PTH dan meningkatnya derajat berat PTH. Ketika COT terjadi, autoregulasi akan menjadi terganggu sehingga akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke otak, dan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial (TIK).6 Peningkatan TIK akan mengakibatkan berkurangnya perfusi dan aliran darah ke otak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kondisi iskemia yang akan mengakibatkan terjadinya cedera otak iskemik sekunder.12 Semakin meningkatnya TIK maka akan mengakibatkan semakin meluasnya daerah yang mengalami iskemia hingga menyebabkan kerusakan sel yang menetap dan gangguan fungsi otak. Rentang waktu untuk dilakukannya penurunan terhadap TIK akan menentukan besarnya kerusakan pada otak.13 Salah satu penyebab terjadinya peningkatan TIK adalah karena terjadinya edema pada otak. Saat terjadinya cedera dan iskemia pada sistem saraf pusat (SSP), mediator seperti glutamat, free fatty acid, atau campuran potassium ekstraselular yang tinggi akan dilepaskan atau diaktivasi, hal tersebut akan menyebabkan pembengkakan sekunder dan cedera dari sel saraf. Substansi lain seperti histamin, asam arakhidonat dan radikal bebas meliputi NO merupakan mediator untuk terjadinya edema otak.13 Kerusakan pada sel dan pembuluh darah akan mengaktivasi suatu kaskade 145 dari COT. Kaskade ini dimulai dengan pelepasan glutamat ke kompartemen ekstraselular. Gerbang kalsium dan sodium akan terbuka dengan terstimulasinya glutamat. Pompa pada membran ATPase akan menyebabkan terjadinya pertukaran satu ion kalsium dengan tiga ion sodium. Sodium banyak masuk ke dalam sel dan menyebabkan peningkatan gradien osmotik sehingga akan meningkatkan volume sel dengan masuknya air kedalam sel.13 Pembengkakkan otak kongestif setelah COT berhubungan dengan peningkatan volume darah otak pada kondisi segera setelah terjadinya trauma. Penyebabnya diakibatkan karena suatu respon vasodilatasi yang merupakan respon otak untuk menjaga aliran darah otak yang optimal pada jaringan otak yang rusak. Edema otak merupakan akibat dari meningkatnya kandungan cairan di dalam otak. Edema otak luas dapat terjadi secara tidak terduga pada pasien dengan COT derajat berat.6 Diklasifikasikan bahwa terdapat 2 kategori edema pada otak, yakni edema vasogenik dan sitotoksik. Edema vasogenik adalah edema pada otak yang diakibatkan karena masuknya cairan kedalam otak melalui sawar darah otak. Edema sitotoksik diakibatkan karena terjadinya pembengkakkan pada glia, neuron, sel endotel yang akan dimulai segera setelah terjadinya trauma. Edema sitotoksik biasa ditemukan pada kondisi pasien dengan cedera kepala dan hipoksia.13 Suatu penelitian mengatakan bahwa edema otak yang bukan diakibatkan oleh meningkatnya aliran darah ke otak merupakan penyebab yang paling sering terjadi pada edema otak pada pasien dengan COT. Sedangkan edema sitotoksik merupakan penyebab untuk terjadinya edema otak pada kondisi cedera kepala sekunder.12 Mekanisme edema pada otak terjadi karena pompa pada membran ATPase akan menyebabkan terjadinya pertukaran satu ion kalsium dengan tiga ion sodium. Sodium banyak masuk ke dalam sel dan menyebabkan peningkatan gradien osmotik sehingga akan meningkatkan volume sel dengan masuknya air kedalam sel.13 Edema pada otak tidak akan menyebabkan terjadinya iskemia lokal apabila nilai TIK belum mencapai titik tertentu. Edema otak apabila tidak 146 Jurnal Neuroanestesi Indonesia disertai dengan peningkatan TIK (berdiri sendiri) maka tidak akan menyebabkan abnormalitas pada pemeriksaan neurologis.13 Edema otak iskemik pada tahap inisial merupakan bentuk edema otak yang sitotoksik, pada tahap selanjutnya diikuti oleh edema otak vasogenik yang dikarenakan oleh terjadinya gangguan pada sawar darah otak. Edema otak biasanya terjadi segera setelah onset dari proses iskemia dan dengan fase tertingginya 24–96 jam. Ketika proses dari zona iskemia menyebabkan penekanan terhadap otak maka dapat menyebabkan perburukan dari kondisi neurologis.13 Sehingga kombinasi dari peningkatan TIK, edema otak, dan iskemia dapat menimbulkan kerusakan sel-sel neuron dan mengaktifasi suatu kaskade cedera kepala.6 Pada saat terjadinya suatu trauma kepala, serangkaian proses patologis berupa kerusakan pada intraselular dan ekstraselular mulai terjadi, meliputi neurokimia, neuroanatomi, dan perubahan neurofisiologi. Cedera otak sekunder sangat mempengaruhi proses patologis tersebut.6 Kaskade cedera kepala sekunder terjadi akibat suatu proses yang kompleks, yang mengikuti dan menyebabkan komplikasi dari suatu cedera kepala primer yang terjadi dalam hitungan jam hingga hari.14 Cedera kepala sekunder terjadi meliputi kaskade selular dan molekular yang menyebabkan terjadinya kematian sel, yang akan menyebabkan terjadinya edema otak dan iskemia.15 Mekanisme ini diawali dengan terjadinya pelepasan neurotransmiter glutamat dan radikal bebas ke membran sel, gangguan elektrolit, disfungsi mitokondria, respon inflamasi, apoptosis, iskemi sekunder akibat vasospasme, oklusi pembuluh darah mikro, dan cedera pembuluh darah.6 Suatu penelitian menyatakan bahwa gangguan pada perfusi di otak setelah COT sedang atau berat telah diteliti dengan menggunakan Perfussion Weighted Imagin (PWI) dan pada penelitian ini ditemukan bahwa gangguan perfusi paling banyak ditemukan pada daerah lobus frontalis.16 Dikatakan bahwa operasi kraniotomi dilakukan untuk menurunkan TIK pada pasien dengan COT. Pada penelitian lain mengatakan bahwa terapi operasi kraniotomi dekompresi pada pasien COT dengan lesi intrakranial bertujuan untuk meminimalisir terjadinya cedera otak sekunder.17 Pengendalian dari TIK merupakan salah satu prinsip utama dari manajemen COT.15 Manfaat dari dilakukannya terapi evakuasi hematoma adalah untuk mengurangi kondisi edema pada otak.13 Ketepatan waktu untuk dilakukannya dekompresi merupakan hal yang krusial untuk menentukan suatu hasil luaran. Sasaran dari operasi kraniotomi ini adalah untuk mengoptimalkan daerah otak yang sehat sebelum terjadinya penurunan aliran darah otak yang diakibatkan oleh terjadinya penurunan tekanan perfusi otak, penekanan pada otak, dan distorsi pada pembuluh darah.18 Tindakan operasi dengan rentang waktu dari kejadian trauma hingga dilakukannya kraniotomi lebih dari 12 jam dianggap penatalaksanaan yang terlambat.19 Berdasarkan analisis dari beberapa jurnal artikel, disimpulkan bahwa serotonin sangat berpengaruh pada patogenesis nyeri kepala. Abnormalitas pembuluh darah juga berimplikasi terhadap terjadinya nyeri kepala tipe migren, dan kontraksi otot yang berlebihan dapat menyebabkan nyeri kepala tipe tension. Diduga perubahan pada kadar serotonin dapat menyebabkan terjadinya hal diatas.20 Menurut data diatas, menunjukkan bahwa bagian otak bukanlah merupakan sumber penyebab nyeri. Pada bagian dalam dari tulang tengkorak kepala, struktur utama yang merupakan sumber penyebab terjadinya nyeri adalah lapisan pelindung yang melapisi otak (duramater), sinus venosus, pembuluh darah, dan beberapa syaraf kranialis.5 Nyeri kepala biasanya disebabkan karena cedera pada daerah tulang kepala, daerah servikal dan struktur intrakranial. Biasanya sulit untuk menentukan bahwa PTH disebabkan oleh faktor organik atau psikogenik, karena kedua faktor tersebut sangat berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya PTH dan derajat beratnya PTH.11 Pada suatu penelitian menyatakan bahwa PTH merupakan hal yang langka dan hanya dapat disebabkan karena kondisi lesi intrakranial yang organik. Beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa PTH merupakan manifestasi disfungsi otak yang diakibatkan oleh cedera otot skeletal. Nyeri akut dapat pula diakibatkan oleh lesi pada daerah kepala. Stimulus pada jaringan otot skeletal dapat mencetuskan terjadinya perubahan Korelasi antara Rentang Waktu Cedera Otak Traumatik dengan Dimulainya Terapi Pembedahan Kraniotomi terhadap Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) neuroplastik pada neuron di caudalis trigeminal nucleus yang menyebabkan terjadinya fenomena sensititasi. Dengan stimulus yang terus menerus dapat menyebabkan peningkatan sensititasi pada neuron dorsal, mencetuskan peningkatan aktifitas spontan, menurunnya ambang batas nyeri dan berubahnya proses stimulus aferen yang dapat menjelaskan sebagai salah satu sumber terjadinya PTH.11 Secara definisi, nyeri kepala yang terjadi dalam 1 minggu setelah terjadinya nyeri kepala (atau 1 minggu setelah pasien mendapatkan kembali kesadarannya) disebut juga dengan PTH.11 Nyeri kepala merupakan akibat dari 6 fenomena fisiologis, yakni; perubahan struktur pada daerah intrakranial, peradangan, iskemia atau perubahan metabolik, myodystonia (meningkatnya tonus otot), iritasi meningen, dan meningkatnya tekanan intrakranial.5 Pada edisi pertama dari klasifikasi IHS, waktu interval antara terjadinya trauma hingga terjadinya nyeri kepala terjadi dalam 14 hari.11 Pada penelitian ini digunakan klasifikasi ICHD yakni kejadian PTH terjadi dalam 1 minggu seelah terjadinya trauma, ditemukan sebanyak 71% pasien mengeluhkan timbulnya gejala nyeri kepala dalam 7 hari setelah terjadinya trauma. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menjawab pertanyaan dari penelitian-penelitian lain, yakni terdapatnya pengaruh dari kecepatan dilakukannya tindakan kraniotomi dalam meminimalisir kerusakan otak yang terjadi akibat COT. V. Simpulan Semakin lama rentang waktu terjadinya COT hingga dimulainya terapi pembedahan kraniotomi maka akan semakin tinggi kejadian PTH dan derajat beratnya PTH. Mengacu pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis yang bermanfaat mengenai rentang waktu yang diperlukan hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi terhadap kejadian PTH, sehingga karena dapat dibuktikan bahwa semakin lama rentang waktu dari terjadinya COT hingga dilakukan terapi dapat menyebabkan semakin berat dan seringnya terjadi PTH, akan membuka kesadaran pada tenaga medis 147 untuk tidak memperlambat dilakukannya terapi. Daftar Pustaka 1. Obermann M, Keidel M, Diener HC. Post traumatic headache: is it for real? Crossfire debates on headache: pro. Headache Currents 2010; 710–15. 2. Bullock MR, Chestnut R, Ghajaar J, Gordon D, Harti R, Newell DW, dkk. Introduction. Neurosurgery 2006; 58 (suppl3):S1–3. 3. Bullock MR, Chestnut R, Ghajaar J, Gordon D, Harti R, Newell DW, dkk. Surgical management of acute epidural hematomas. Neuro Surgery 2006; 58 (Suppl3): S2:7–15. 4. Finkel AG. Concussion and post traumatic headache. Information For Health Care Professionals. (www. AmericanHeadacheSociety.org). Diunduh pada tanggal 28 juli 2014. 5. Seifert TD, Evans RW. Post traumatic headache: a review. Curr Pain Headache Rep 2010. 6. Heegaard W, Biros M. Traumatic brain injury. Emerg Med Clin N Am 2007; 25:655–78. 7. Sherman KB, Bell KR. Traumatic brain injury and pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 17 (2006); hlm 473–490. 8. Lew HL, Lin PH, Fuh JL, Wang SJ, Clark DJ, Walker WC. Characteristic and treatment of headache after traumatic brain injury. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006; hlm: 619–27. 9. DeGuise E, LeBlanc J, Feyz M, Meyer K, Duplantie J, Thomas H, dkk. Long term outcome after severe traumatic brain injury: the McGill interdisciplinary prospective study. J Head Trauma Rehabil 2008; (5): 294–303. 10. Zasler N. Post traumatic headache: Clinical 148 Jurnal Neuroanestesi Indonesia caveats. Rev Cubana Neurol Neuroar 2014; 4(2):105–8. 11. Martins HAL, Ribas VR, Martins BBM, Ribas RMG, Valenca MM. Post traumatic headache. Arq Neuropsiquiatr 2009; 67(1):43–45. 12. Smith M. Monitoring intracranial pressure in traumatic brain injury. Anest Analg 2008;106:240–8). 13. Puri SK, Patna, Bihar. Cerebral edema and its management. MJAFI 2003; 59: 326–31. 14. Haddad SH, Arabi YM. Critical care management of severe traumatic brain injury in adults. Emergency medicine 2012;20:1–15. 15. Levine JM, Kumar MA. Traumatic brain injury. Neurocritical Care Society Practice Update 2013; 1–28. 16. Wilson MC, Krolczyk SJ. Pediatric posttraumatic headache. Current Pain and Headache Reports 2006;10:387–90. 17. Syed AB, Ahmad IH, Hussain M, AlBya F, Solaiman A. Outcome following decompressive craniectomy in severe head injury: Rashid hospital experience. Pan Arab Journal of Neurosurgery 2009;13:29–33. 18. Mathai KI, Sudumbrekar SM, Shashivadhanan MS, Sengupta SK, Rappai TJ. Decompressive craniectomy in traumatic brain injury rationale and practice. Indian Journal of Neurotrauma 2010;7:9–12. 19. Khan MB, Riaz M, Javed G, Hashmi FA, Sanaullah M, Ahmed SI. Surgical management of traumatic extra dural hematoma in children: experiences and analysis from 24 consecutively treated patients in a developing country. Surg Neurol Int 2013;4:103. 20. Gray LC, Matta BF. Acute and chronic pain following craniotomy: a review. Anesthesia 2005; 60:693–704. Penatalaksanaan Anestesi dengan TIVA Propofol-Dexmedetomidine-Fentanyl untuk Operasi Meningioma Frontalis Sinistra Rebecca S. Mangastuti*), Himendra Wargahadibrata**), Nazaruddin Umar***) *)Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan, **)Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif – Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran – Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, ***)Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara – Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan Abstrak Meningioma merupakan tumor intrakranial jinak yang sering ditemukan. Berasal dari jaringan meningen dan medulla spinalis, tidak tumbuh dari jaringan otak. Pada kasus ini, pasien laki-laki, 46 tahun, 80 kg, datang ke rumah sakit dengan keluhan kejang berulang dan sakit kepala yang hilang timbul sejak 5 bulan yang lalu. Kesadaran composmentis, GCS 15, pupil isokor bilateral 2 mm, hemodinamik stabil, jantung dan paru tidak ada kelainan dan tidak ada kelumpuhan atau kelemahan pada ke empat ekstremitas. Magnetic Resonance Imaging (MRI) brain ditemukan masa hipointens yang melekat dengan meningen di frontal kiri ukuran 52x48x43 mm, kesan convexitas meningioma disertai perifokal edema dengan midline shift ke kanan sekitar 7 mm. Disimpulkan meningioma frontal sinistra dan dianjurkan kraniotomi pengangkatan tumor. Operasi dilakukan dengan anestesi umum. Tehnik anestesi menggunakan Total Intra Venous Anesthesia (TIVA) dengan syringe pump. Operasi berlangsung selama 7 jam dan tumor dapat terangkat semua. Jumlah perdarahan 1000 mL. Pasien mendapat 300 ml Fresh Frozen Plasma (FFP) dan 500 ml Packed Red Cell (PRC) intraoperasi. Untuk mengurangi tekanan intrakranial, diberikan manitol 0,5 gram/kgBB dan drainase cairan serebrospinal 10–20 mL langsung ke ventrikel lateral oleh operator. Pascaoperasi, pasien diekstubasi dan rawat diruang ICU. Dengan data five year survival rate untuk meningioma jinak 70%, meningioma ganas 55%, diharapkan prognosis pasien pascaoperasi adalah dubia ad bonam. Kata kunci: anestesi, meningioma, total intra venous anesthesia JNI 2014;3 (3): 149‒56 Management Anesthesia with TIVA Propofol-Dexmedetomidine-Fentanyl for Meningioma Frontalis Sinistra Operation Abstract Meningiomas are the most common benign intracranial tumors. These tumors originate from the meninges and spinal cord, not from the brain tissue. A 46 year old 80 kgs male patient, was admited to the hospital with recurrent seizures and intermittent headaches that occured since five months ago. He was fully alert, GCS 15, both pupils were isokor (2 mm), with stable hemodynamic, no parese in all extremities and normal heart and lung. Magnectic Resonance Imaging (MRI) result showed a 52x48x43 mm mass attached to the meninges at the left frontal with perifocal tumour edema and midline shifted to the right about 7 mm. The patients was diagnosed with the left frontal meningioma and suggested for craniotomy tumour removal. The surgery was performed under general anesthesia using. Total Intra Venous Anesthesia (TIVA) with syringe pump. The 7 hours surgery performed uneventfully with total bleeding of 1000 mL and the patient was received 300 mL Fresh Frozen Plasma (FFP) and 500 ml Packed Red Cell (PRC) intraoperatively. To reduce intracranial pressure, a 0.5gr/kg mannitol was and a 10–20 cc of cerebrospinal liquor drainage through the lateral ventricle was performed by the operator. The patient was extubated after the operation and admitted the ICU for futher management. With the five year survival rate of 70% for benign meningioma and 55% for malignant meningiomas, the prognosis of this patient is dubia ad bonam. Key words: anesthesia, meningiomas, total intra venous anesthesia JNI 2014;3 (3): 149‒56 149 150 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Meningioma merupakan tumor otak jinak yang banyak ditemukan. Tumor ini berasal dari jaringan meningen dan medulla spinalis, tidak tumbuh dari jaringan otak. Pertumbuhan tumor yang lambat, menyebabkan gejala klinis baru terlihat setelah otak atau jaringan sekitar terdesak oleh tumor. Sedikitnya 6500 orang di Amerika Serikat di diagnosis meningioma setiap tahunnya. Umumnya ditemukan pada usia 40–70 tahun, lebih banyak wanita dibandingkan pria dengan rasio wanita banding pria kira-kira 3 banding 1. Diduga faktor predisposisi meningioma adalah terpapar gelombang radiasi, trauma, virus atau herediter yang disebut neurofibromatosis tipe 2 (NF-2).1–4 Meningioma dibagi menjadi 3 kategori, yakni meningioma jinak, meningioma atipikal dan meningioma maligna (anaplastik). Tujuh puluh sampai 80% meningioma umumnya jinak, 2–3% meningioma maligna, sisanya meningioma atipikal yaitu meningioma yang tumbuhnya lebih cepat dibanding meningioma jinak dan dapat tumbuh kembali walaupun tumor sudah diangkat.1,5,6 Diagnosa ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan diperkuat dengan hasil CT-scan kepala atau Magnetic Resonance Imaging (MRI) kepala. Terapi yang dianjurkan, umumnya kraniotomi pengangkatan tumor, atau radiasi jika tumor tidak dapat terangkat semua. Tehnik anestesi yang digunakan adalah anestesi umum dengan tujuan menghindari terjadinya hipertensi intrakranial dan pembengkakan otak (brain bulging). 2,3,6 Usia penderita, besar masa tumor, lokasi tumor, kecepatan tumbuh tumor dan data five year survival rate untuk meningioma jinak 70%, meningioma ganas 55% turut menentukan prognosis penderita meningioma.1,2,6 II. Kasus Laki-laki berusia 46 tahun dengan berat badan 80 kg. Anamnesis: Pasien kejang berulang sejak 5 bulan sebelum masuk rumah sakit. Lama kejang 5 menit. Dalam 1 hari, pasien mengalami kejang sampai 7 kali. Saat kejang, pasien tampak tidak sadarkan diri, tangan dan kaki tampak kaku. Pasien juga mengeluh sakit kepala yang hilang timbul, mual dan muntah. Pandangan mata kabur dan gangguan pendengaran disangkal. Tidak didapatkan perubahan perilaku, memori dan fungsi intelektual. Riwayat kejang demam disangkal. Riwayat penyakit hipertensi, diabetes melitus disangkal. Pemeriksaan Fisik Kesadaran composmentis, GCS 15, pupil isokor, diameter 2 mm kanan dan kiri, reflek cahaya kedua mata positip, papil edema negatif. Tekanan darah 120/70 mmHg, laju nadi 90 x/menit, laju nafas 12 x/menit, suhu 36,5 0C. Bunyi jantung I, II reguler, tidak didapatkan murmur dan gallop. Gambar 1. MRI Otak: Tumor Meningioma Frontalis Sinistra Penatalaksanaan Anestesi dengan TIVA Propofol-Dexmedetomidine-Fentanyl untuk Operasi Meningioma Frontalis Sinistra Paru vesikuler, tidak didapatkan ronchi dan wheezing dikedua lapang paru. Abdomen lemas, soepel, nyeri tekan tidak ada, tidak membuncit, hepar dan lien tidak membesar. Ekstremitas hangat, tidak didapatkan edema, sianosis dan ikterik. Kekuatan motorik ke empat ekstremitas sama, tidak ada kelemahan atau kelumpuhan pada ke empat ekstremitas. Tidak didapatkan gangguan sensorik pada ke empat ekstremitas. Pemeriksaan Laboratorium Hemoglobin 15,2 g/dl, Hematokrit 45 %, Leukosit 6500 /mm3, Trombosit 179.000 /mm3, Ureum 21 mg/dl, Creatinin 0,8 mg/dl, Gula darah sewaktu 143 mg/dl. Albumin 3,1 g/dl, Globulin 3 g/dl. Natrium 140 mEq/L, Kalium 3,6 mEq/L, Chlorida 109 mEq/L. Foto thorax tidak didapatkan kelainan, CTR <50%. EKG sinus ritme, laju jantung 75–85 x/menit. MRI kepala, didapatkan masa hipointens yang melekat dengan meningen di frontal kiri ukuran 52x48x3 mm, kesan convexitas meningioma disertai perifokal edema dengan midline shift ke kanan sekitar 7 mm. Pasien dirawat inap dan mendapat terapi manitol 250 mg dalam waktu 6 jam dilanjutkan manitol 4x125 mgiv, methyl prednisolon 2x125 mg, phenitoin 3x100 mgiv, ketofrozen HCL 1x1 ampul iv. Diagnosa kerja, tumor meningioma frontalis sinistra. Direncanakan operasi kraniotomi elektif pro eksisi tumor. Penatalaksanaan Anestesi Saat masuk kamar operasi, kesadaran pasien composmentis, GCS 15, tekanan darah 140/94 mmHg, laju nadi 90 x/menit, laju nafas 12 x/menit, suhu 36,5 0C. Diberikan premedikasi midazolam 5 mg iv dilanjutkan dengan fentanyl 50 mcg iv, induksi dengan propofol 160 mg iv, fentanil 100 mcg iv, lidokain 120 mg iv, vecuronium 8 mg iv, intubasi dengan ETT non kinking no 8, cuff (+). Saat akan dilakukan pemasangan head-pin diberikan fentanil 50 mcg iv dan propofol 20 mg. Pada saat akan insisi kulit diberikan fentanil 50 mcg iv. Pemeliharaan anestesi dengan Total Intra Venous Anesthesia (TIVA) menggunakan syringe pump, propofol 2–3 mg/kg BB/jam, vecuronium 0,06 mg/kg BB/jam, fentanyl 1 mcg/kg BB/ jam, dexmedetomidine 0,1–0,2 mcg/kg BB/jam. 151 Inhalasi dengan gas O2 : udara = 1 : 1, tanpa gas anestesi. Cairan masuk intraoperatif, kristaloid 2500 ml, manitol 500 ml, Fresh Frozen Plasma (FFP) 300 ml, Packed Red Cell (PRC) 500 ml. Cairan keluar intraoperatif, urine 1500 ml, perdarahan 1000 ml. Diusahakan balans imbang selama operasi berlangsung. Hemodinamik, Grafik 1. Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik selama Operasi Berlangsung Grafik 2. Laju Nadi dan Laju Nafas selama Operasi Berlangsung Grafik 3. Saturasi O2 dan End Tidal CO2 selama Operasi Berlangsung 152 Jurnal Neuroanestesi Indonesia saturasi O2 dan end tidal CO2 stabil selama intraoperatif. Operasi berjalan selama 7 jam. Tumor berhasil terangkat semua. Pascaoperasi, pasien diekstubasi dan rawat di ICU. III. Pembahasan Meningioma umumnya terdeteksi pada usia 40– 70 tahun. Umumnya lebih banyak dijumpai pada wanita, hal ini diduga karena faktor hormonal estrogen, progesteron dan androgen yang terkait dengan pola menstruasi dan kehamilan.2,3,8,9 Namum meningioma pada kasus ini ditemukan pada pasien laki-laki berusia 46 tahun. Meningioma merupakan tumor jinak intracranial dan cenderung mudah berdarah. Tumor ini berasal dari lapisan meningen dan medulla spinalis, tidak tumbuh dari jaringan otak. Umumnya tumbuh ke dalam otak yang menyebabkan tekanan pada otak dan medulla spinalis, tetapi juga dapat tumbuh keluar ke arah tulang tengkorak. Pertumbuhan tumor ini lambat sehingga pasien tidak merasakan gejala klinis. Gejala klinis baru terasa saat telah terjadi penekanan pada otak atau jaringan sekitar akibat desakan tumor.1,2,7 Meningioma pada kasus ini terletak pada lobus frontalis. Fungsi lobus frontalis adalah mengatur gerakan voluntari, fungsi intelektual, proses berpikir, memori dan perilaku. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau terdapat tumor pada lobus ini, akan didapatkan gejala klinis sakit kepala, mual, muntah, drowsiness, pingsan, kejang, kelemahan atau kelumpuhan pada ekstremitas, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan perubahan perilaku (personality atau behavior), emosi dan intelektual. Pada kasus ini, tidak didapatkan papil edema, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, perubahan perilaku, emosi, intelektukal, kelemahan atau kelumpuhan pada ke empat ekstremitas, serta tidak terdapat gangguan sensorik pada keempat ekstremitas. Hal ini diduga karena belum atau tidak terdesaknya area tersebut oleh masa tumor. Adanya kenaikan tekanan intrakranial pada pasien ini ditandai dengan gejala sakit kepala yang hilang timbul, mual dan muntah. Gejala lain seperti penurunan kesadaran, pandangan kabur, papil edema, depresi nafas tidak didapatkan. Pada CT scan atau MRI, peningkatan tekanan intrakranial terlihat dengan adanya midline shift ke kanan sekitar 7 mm disertai dengan perifokal edema. Peningkatan tekanan intrakranial dapat dijelaskan dengan hipotesis Monro-Kellie, dengan mengingat tulang tengkorak merupakan bagian yang keras, dimana rongganya terdiri dari 3 komponen, yaitu jaringan otak 80% (1400 ml), darah 10% (150 ml) dan cairan serebrospinal 10% (150 ml). Dalam keadaaan normal, komponenkomponen ini dalam keseimbangan yang dinamis yakni jika terjadi kenaikan volume dari salah satu komponen maka akan dikompensasi dengan penurunan volume komponen yang lain supaya tidak terjadi kenaikan tekanan intrakranial. Mekanisme kompensasi tersebut berupa perpindahan cairan serebrospinal kearah rongga spinal, peningkatan reabsorbsi cairan serebrospinal, dan kompresi sinusvenosus. Hasil dari mekanisme ini akan menurunkan volume cairan intrakranial. Hipotesis MonroKellie dapat diperjelas dengan kurva hubungan tekanan intrakranial dan kenaikan masa/volume komponen otak.1,10,11 Derajat 1–2: fase kompensasi, dimana bila ada kenaikan volume salah satu komponen maka volume komponen yang lain akan menurun sehingga tekanan intrakranial tetap konstan. Derajat 3–4: fase dekompensasi, yaitu ketika fase kompensasi terlampui dengan sedikit kenaikan komponen intrakranial akan menyebabkan kenaikan yang tinggi dari tekanan intrakranial. 1,10 Kemiringan kurva tergantung pada komponen yang volumenya meningkat. Peningkatan volume darah, cairan serebrospinalis atau keduanya Gambar 3. Kurva Hubungan Tekanan Intrakranial dan Volume3 Penatalaksanaan Anestesi dengan TIVA Propofol-Dexmedetomidine-Fentanyl untuk Operasi Meningioma Frontalis Sinistra maka daya kompresinya kurang bagus dan kemiringannya lebih tajam. Peningkatan volume jaringan otak, misal tumor, kemiringannya kurve lebih landai dan lebih dapat dikompresi.1,10 Bila tekanan intrakranial meningkat dengan cepat, terjadi perubahan sistemik seperti hipertensi, takikardia, bradikardia, perubahan irama jantung, perubahan EKG, gangguan elektrolit, hipoksia dan Neurogenic Pulmonary Edema (NPE). Cushing menuliskan adanya Trias Cushing pada pasien dengan kenaikan tekanan intrakranial. Trias ini terdiri atas hipertensi, bradikardia dan melambatnya respirasi. Peningkatan tekanan darah ini merupakan mekanisme untuk mempertahankan tekanan darah otak yang terjadi akibat peningkatan kadar adrenalin, nor adrenalin, dopamin dalam sirkulasi. Bradikardia tidak selalu terjadi pada setiap pasien. Bradikardia dapat juga terjadi selintas, yang paling sering terjadi yaitu takikardia dan atau aritmia ventrikel.10-12 Kejang dan peningkatan tekanan intrakranial pada pasien ini, merupakan masalah yang harus diperhatikan saat penatalaksanaan preoperasi, intraoperasi dan pascaoperasi. Preoperatif, telah diberikan terapi manitol 250 mg dalam waktu 6 jam dilanjutkan manitol 4x125 mg iv, methylprednisolon 2x125 mg, phenitoin 3x100 mg iv selama perawatan untuk mengatasi masalah ini. Intraoperasi, penatalaksanaan anestesi yang dilakukan bertujuan menghindari terjadinya intrakranial hipertensi dan pembengkakan otak melalui tindakan preventif dan terapi dengan cara memberikan sedasi, analgetik dan ansiolitis yang adekuat dengan midazolam iv (dosis tidak melebihi 0,25 mg/kgBB), propofol 2–2,5 mg/kg BB iv, fentanil 1–3 mcg/kgBB, vecuronium 0,1–0,15 mg/kgBB. Lidokain 1–1,5 mg/kgBB diberikan 3 menit sebelum intubasi dilakukan untuk menghindari terjadinya lonjakan hemodimanik saat intubasi berlangsung. Saat akan dilakukan pemasangan head-pin diberikan fentanil 50 mcg iv dan propofol 20 mg, dan saat akan insisi kulit diberikan fentanil 50 mcg iv. Teknik TIVA yaitu tehnik anestesi umum dengan menggunakan obat anestesi secara intra vena yang dilakukan saat induksi maupun rumatan anestesi tanpa menggunakan gas anestesi. Keuntungan 153 TIVA adalah hemodinamik lebih stabil, dalamnya anestesi lebih stabil, lebih dapat diprediksi, pemulihan lebih cepat, mual dan muntah post operasi menurun, tidak ada polusi di kamar operasi, tidak toksis terhadap organ, tidak iritasi pada jalan nafas, tidak delirium pascaoperasi, laju jantung lebih rendah, menurunkan tingkat stres hormon, memelihara reaktifitas cerebrovaskular.1 Mekanisme kerja propofol yaitu memfasilitasi inhibisi neurotransmisi yang dimediasi oleh GABA. Efek terhadap serebral, pada pasien dengan tekanan intrakranial normal (ICP = intracanial pressure), propofol akan menurunkan Cerebral Metabolic Rate (CMR) 36%, ICP 30%, dan Cerebral Perfussion Pressure (CPP) 10%. Reaktivitas cerebral terhadap CO2 dan auroregulasi dipelihara selama infus propofol berjalan. Sesudah injeksi bolus propofol iv, tekanan darah menurun sehingga CPP menurun. Propofol sebagai proteksi otak terbatas pada iskemik ringan. Untuk iskemik sedang dan berat, propofol tidak sebaik barbiturat dalam hal efek proteksi otak.1,13 Dosis kecil narkotik mempunyai efek minimal pada cerebral blood flow (CBF) dan cerebral metabolic rate for oxygen (CMRO2), sedangkan dosis besar secara progresif akan menurunkan CBF dan CMRO2. Autoregulasi dan reaktivitas terhadap CO2 tetap dipertahankan. Pada umumnya, sedikit sekali efeknya pada CBF dan CMRO2, tetapi opioid sintetis termasuk fentanil, sufentanil dan alfentanil dapat menyebabkan kenaikan ICP pada pasien tumor otak dan cedera kepala.1,13 Pengaruh pada dinamika CBF terlihat pada tabel 1 dibawah ini Pada dosis kecil, fentanil, alfentanil dan sufentanil menyebabkan tidak ada perubahan pada Vf dan ada penurunan pada Ra dengan prediksi terjadi penurunan ICP. Pada dosis tinggi, fentanil menurunkan Vf, tidak ada perubahan atau ada peningkatan Ra dengan prediksi akan menurunkan ICP atau efeknya pada ICP tidak menentu. Pada dosis besar, alfentanil tidak menimbulkan perubahan pada Vf dan tidak ada perubahan atau peningkatan pada Ra, dan diprediksi pengaruhnya pada ICP tidak berubah atau meningkat. Pada kebanyakan keadaan, narkotik tidak menimbulkan perubahan atau sedikit menurunkan 154 Jurnal Neuroanestesi Indonesia ICP. Akan tetapi, pada keadaan tertentu narkotik dapat menimbulkan peningkatan ICP, misalnya pemberian bolus sufentanil dapat menimbulkan peningkatan ICP yang selintas tapi besar pada pasien dengan cedera kepala berat. Demikian pula, pemberian bolus sufentanil dan alfentanil akan meningkatkan tekanan CSF pada pasien dengan tumor supratentorial, hal ini karena autoregulasi yang menimbulkan vasodilatasi pembuluh darah serebral akibat penurunan MAP. Jadi, bila narkotik diberikan pada pasien bedah saraf, harus diberikan dengan syarat jangan terjadi penurunan tekanan darah yang tiba-tiba.1,10,13 Dexmedetomidin adalah selektif α2 agonis, sedatif lebih selektif terhadap reseptor α2 dibanding klonidin. Pada dosis yang lebih tinggi akan hilang selektifitasnya dan stimulasinya pada reseptor α adrenergik. Dexmedetomidin dapat menyebabkan sedasi, ansiolitis, analgesia dan kurangnya respon simpatik terhadap pembedahan dan stres. Efek utama adalah menurunkan kebutuhan opioid, tidak menyebabkan depresi respirasi secara signifikan, tetapi dapat menyebabkan obstruksi jalan nafas. Digunakan untuk waktu yang pendek (<24 jam) untuk sedasi intravena pada pasien dengan ventilasi mekanik. Pada penghentian sesudah pemakaian lama, potensial menyebabkan fenomena withdrawal sama seperti klonidin. Manifestasinya dapat terjadi krisis hipertensi. Tabel 1. Pengaruh Narkotik pada Laju Pembentukan, CSF, Resistensi CSF dan ICP Narkotik Vf Rs Prediksi efek pada ICP Dosis rendah: Fentanyl 0 Alfentanil 0 Sufentanil 0 Dosis tinggi: Fentanyl - 0,+,* -,?,* Alfentanil 0 0 0 Sufentanil 0 +,0,* +,0,* Keterangan: Vf = Kecepatan pembentukan cerebrospinal fluid/ CSF, RS = Resistensi terhadap absorpsi CSF, ICP= intracranial pressure (tekanan intrakranial), 0 = tidak ada perubahan, - = menurun, + = meningkat,* = efek bergantung pada dosis. Dikutip dari: Newfield P, Cottrell JE., ed. Handbook of neuroanesthesia, 4th, ed; 2007 Dexmedetomidin juga digunakan sebagai sedasi untuk tambahan pada anestesi umum. Efek sampingnya berupa bradikardi, blok jantung dan hipotensi. Dosis, untuk permulaan diberikan 1 ug/kgBB iv selama lebih dari 10 menit, kecepatan infus untuk pemeliharaan 0,2–0,7 ug/kgBB/jam. Mula kerja cepat, waktu paruh terminal 2 jam. Metabolisme di hepar, metabolit akan dieliminasi lewat urine. Dosis diturunkan pada gangguan fungsi ginjal atau perburukan hepar.1,10,13 Tindakan lain untuk menurunkan peningkatan tekanan intrakranial, adalah posisi head-up. Posisi head-up untuk menurunkan ICP harus hati-hati, karena MAP lebih menurun daripada ICP saat posisi head-up. Posisi head-up yang dianjurkan 10–20% atau 15–300. Posisi pasien terlentang dengan kepala miring ke kanan dan dipastikan tidak terdapat penekanan pada vena jugularis. Steroid (methylprednisolon) telah diberikan selama perawatan. Manitol diberikan 0,5 gr/kgBB selama 20 menit iv sebelum dura dibuka. Dilakukan drainase langsung ke ventrikel lateralis 10–20 ml oleh operator.10,11 Kortikosteroid akan mengurangi edema sekeliling tumor otak. Penurunan tekanan intrakranial baru terlihat beberapa jam atau hari pada terapi kortikosteroid. Pemberian kortikosteroid sebelum reseksi tumor sering menimbulkan perbaikan neurologis mendahului pengurangan tekanan intrakranial. Kortikosteroid dapat memperbaiki kerusakan Blood Brain Barier (BBB), mengurangi edema otak, dehidrasi otak, pencegahan aktivitas lisosom, mempertinggi transport elektrolit serebral, merangsang ekresi air dan elektrolit, menghambat aktivitas fosfolipase A2. Efek pemberian kortikosteroid dalam jangka panjang adalah hiperglikemia, ulkus peptikum, peningkatan kejadian infeksi.10-12 Penurunan tekanan intrakranial yang cepat, dapat dicapai dengan pemberian diuretik. Dua macam diuretik yang umum digunakan yaitu osmotik diuretik (manitol) dan loop diuretik (furosemide). Manitol diberikan secara bolus intravena dengan dosis 0,25–1 gram/kg BB, diberikan secara perlahan selama 10–20 menit. Bekerja dalam waktu 10–15 menit dan efektif kira-kira selama 2 jam. Manitol tidak menembus sawar darah otak yang intak. Manitol akan meningkatkan Penatalaksanaan Anestesi dengan TIVA Propofol-Dexmedetomidine-Fentanyl untuk Operasi Meningioma Frontalis Sinistra osmolalitas darah relatif terhadap otak dan menarik air dari otak ke dalam pembuluh darah. Bila sawar darah otak rusak, manitol dapat memasuki otak dan menyebabkan rebound fenomena, yaitu kenaikan tekanan intrakranial sebab ada suatu reversal perbedaan osmotik. Manitol dapat menyebabkan vasodilatasi yang tergantung dari besarnya dosis dan kecepatan pemberian. Vasodilatasi akibat manitol dapat menyebabkan peningkatan volume darah otak dan tekanan intrakranial secara selintas yang simultan dengan penurunan tekanan darah sistemik. Penggunaan manitol jangka panjang dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, hiperosmolalitas dan gangguan fungsi ginjal. Hal ini terutama bila serum osmolalitas meningkat diatas 320 mOsm/kg.10-12 Furosemide mengurangi tekanan intrakranial dengan menimbulkan diuresis, menurunkan produksi cairan serebrospinal, dan memperbaiki edema serebral dengan memperbaiki transport air seluler. Furosemide menurunkan tekanan intrakranial tanpa meningkatkan volume darah otak atau osmolalitas darah, tetapi tidak seefektif manitol dalam menurunkan tekanan intrakranial. Furosemide dapat diberikan sendiri dengan dosis 0,5–1 mg/kg BB atau dengan manitol dengan dosis yang lebih rendah 0,15–0,3 mg/ kg BB. Kombinasi manitol dan furosemide lebih efektif daripada manitol saja dalam mengurangi brain bulk dan tekanan intrakranial, tetapi lebih menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit, sehingga diperlukan pemantauan serum elektrolit dan osmolalitas dan penggantian kalium bila ada indikasi.10,11 Pola pernafasan normoventilasi dengan target PaO2 100 mmHg dan PaCO2 29–34 mmHg yang setara dengan endtidal CO2 25–30 mmHg. Intraoperasi, tidak menggunakan PEEP saat operasi berlangsung, untuk menghindari terjadinya peningkatan tekanan intratorakal yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial intraoperatif. Perdarahan 1000 ml dan urine 1500 ml intraopratif digantikan dengan kristaloid 2500 ml, FFP 300 ml dan PRC 500 ml. Diusahakan balans imbang selama operasi berlangsung.Operasi berlangsung selama 7 jam. Tumor berhasil terangkat semua. Pasca operasi, diberikan reverse dengan 4 ampul 155 Sulfas Atropin iv dan 4 ampul prostigmin iv, setelah diyakini hemodimanik stabil, laju nafas 10–12 x/menit, tidak takikardi, tidal volume mencukupi, dilakukan ekstubasi diatas meja operasi dan pasien di rawat di ruang ICU. IV. Simpulan Meningioma merupakan tumor otak jinak, berasal dari lapisan meningen dan medulla spinalis. Dapat tumbuh ke dalam otak dan keluar ke arah tulang tengkorak. Gejala klinis baru dirasakan setelah tumor membesar dan terjadi desakan pada otak atau jaringan sekitar tumor. Terapi meningioma meliputi terapi simptomatis, operatif dan radiasi (atas indikasi). Penatalaksanan anestesi pada meningioma bertujuan mencegah terjadinya hipertensi intrakranial dan pembengkakan otak (brain bulging). Indikator yang berperan adalah posisi pasien, elevasi kepala, kedalaman anestesi yang adekuat, PaCO2, end tidal CO2 dan balans imbang. Daftar Pustaka 1. Roosiati B, Rahardjo Sri. TIVA pada kraniotomi pengangkatan meningioma residif. JNI Oktober 2012; 1 (4): 269–77 2. Meningioma. American Association of Neurological Surgeons Jurnal, Juni 2012. http: //www. brainsciencefoundation.org/ 3. Smith WOHG. Supratentorial masses: anesthetic consideration. Dalam: Anesthesia and neurosurgery, 4th ed; Philadelphia:Mosby, 297–313 4. Park JK. Meningioma (beyond the basics). Wolters Kluwer Health Journal. Juli 2013 5. Laura J, Martin MD. WebMD Medical Reference. June 22, 2012. 6. Gonzales N. Meningioma brain tumor. UCLA Neurosurgery journal, February 2013. 7. Haddad G. Meningioma treatment and management. Medscape Jurnal. May 2013. 156 Jurnal Neuroanestesi Indonesia 8. Wen P. Meningioma treatment options. Brain science foundation Journal. April 2012 9. Kaal ECA, Vecht CJ. The management of brain edema in brain tumors. Current Opinion in Oncology 2004, 593–9 10. Bruder N, Ravussin P. Supratentorial masses; anesthetic considerations. Dalam: Cottrell and Young’s Neuroanesthesia. 5th ed; Philadelphia: Mosby, 184–191 11. Bisri T. Neurofisiologi. Dalam: Penanganan Neuroanestesia dan Critical Care: Cedera Otak Traumatik. Bandung: Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 2012, 10–12 12. Hill L, Gwinnutt C. Cerebral blood flow and intracranial pressure. Medscape Journal. Oktober 2012 13. Morgan GE, Jr, Mikhail MS, Murray MJ, Nonvolatile anesthetic agents. Dalam: Clinical Anesthesiology. 4 th ed: New York: The Mc Grow Hill Companies: 2006. 192–202. Tehnik Proteksi Otak pada Pembedahan Non Neurosurgery (Radical Neck Dissection) dengan Premorbid Space Occupying Lesion (SOL) dan Infark Serebri Buyung Hartiyo Laksono*), Siti Chasnak Saleh**) *)Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya – Rumah Sakit Daerah Dr Saiful Anwar Malang, **)Departemen Anestesiologi dan Reanimasi – Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Abstrak Insidensi kasus tumor dengan metastase otak berkisar antara 100.000 sampai 170.000 pertahun. Metastase otak bersifat multiple dengan 80% terletak pada hemis ferserebri. Pendesakan akibat lesi tersebut mengakibatkan gangguan neurologis dan peningkatan tekanan intrakranial (TIK). Seorang laki-laki, 62 tahun dengan tumor sub mandibula direncanakan radical neck dissection. Pada pasien didapatkan proses metastase pada serebri dan cerebropontine angle disertai infark serebri daerah pons dan otak tengah. Defisit neurologis berupa kelemahan ekstremitas kanan dan disartria. Preoperatif diberikan kortikosteroid untuk menurunkan edema perifokal. Tatalaksana anestesi dengan prinsip tehnik proteksi otak, dilakukan induksi kombinasi dengan midazolam, fentanyl, lidokain, propofol dan rocuronium. Kontrol ventilasi target paCO2 30–35 mmHg. Pemeliharaan anestesi dengan kombinasi sevofluran dan propofol. Pembedahan berjalan 7 jam, temperature selama pembedahan 35–36 °C dan MAP dijaga >70 mmHg. Dilakukan ekstubasi, setelah menilai status neurologis dan hemodinamik, difasilitasi dengan lidokain. Pascabedah tidak didapatkan perburukan defisit neurologis. Pasien dirawat di ICU selama 2 hari kemudian ke ruangan dengan perbaikan status neurologis. Tehnik proteksi otak bertujuan mencegah cedera sekunder dari SOL dan iskemia. Tindakan anestesi dan pembedahan dapat menambah perburukan cedera sekunder. Penatalaksanaan anestesi yang baik dengan prinsip proteksi otak akan menghasilkan outcome pembedahan sesuai yang diharapkan. Kata kunci: tehnik proteksiotak, prosedur non neurosurgery, space occupying lession, infark serebri JNI 2014;3 (3): 157‒63 Brain Protection Technique in Non Neurosurgical Procedure (Radical Neck Dissection) on a Patient with Space Occupying Lession (SOL) and Cerebral Infarction Abstract The incidence of tumors with brain metastases ranged from 100,000 to 170,000 per year. Brain metastases are multiple with 80% of lesion located on the cerebral hemispheres. These lesions could cause neurological disorders and increase intracranial pressure (ICP). A 62 years old male, diagnosed with sub mandibular tumour was scheduled for radical neck dissection. From preoperative evaluation he hadcerebral metastasis at the cerebrum and cerebro-pontine angle with cerebral infarction at pons and middle brain regions. Neurological deficits were weakness of the right limband dysarthria. The patient received corticosteroids pre-operatively to reduce perifocal edema. Anesthesia management was given using brain protection principles. Induction was done by using midazolam, fentanyl, lidocaine, propofol and rocuronium. Ventilation was controlled with a target PaCO2 of 30–35 mmHg. Sevoflurane and propofol was given as anesthesia maintenance. Surgery was done for 7 hrs, temperature was 35–36 °C during surgery and MAP was maintained >70 mmHg. Extubation was done after assessing the neurologic and hemodynamic status,facilitated with lidocaine. There was no worsening of neurologic deficits post surgery. Patients was managed in the ICU for 2 days and transferred to ward with increased neurological state. The technique of brain protection aims to prevent further process of secondary injury from SOL and ischemia. Anesthesia and surgery itself could increase the progression of secondary injury. Anesthesia management usingbrain protection principles will provide better outcomes as expected. Key words: brain protection techniques, non neurosurgical procedure, space occupying lesion, cerebral infarction JNI 2014;3 (3): 157‒63 157 158 I. Jurnal Neuroanestesi Indonesia Pendahuluan Insidensi kasus tumor dengan metastase otak berkisar antara 100.000 sampai 170.000 pertahun. Lesi metastase otak 80% berupa metastase multipel pada otak besar.1,2 Pendesakan akibat lesi tersebut mengakibatkan gangguan neurologis dan peningkatan tekanan intrakranial (TIK). Banyak kasus memerlukan pembedahan pada tumor primer dengan premorbid SOL. Manajemen anestesi bukan hanya memperhatikan pembedahan tumor primer tetapi juga memperhatikan tatalaksana proteksi otak akibat adanya SOL. Salah satu komplikasi yang ditakuti akibat dari anestesi dan pembedahan adalah kejadian iskemia pada otak dan kerusakan neuron. Meskipun angka kejadian stroke selama pembedahan masih rendah, tetapi pada beberapa kondisi dapat menjadi tinggi. Pada kasus pembedahan jantung insiden komplikasi neurologis berkisar antara 2–6%. Sebagian besar terjadi selama pembedahan berlangsung. Risiko kejadian stroke pasca pembedahan pada kasus carotid endarterectomy berkisar 15%. Pada kondisi tertentu risiko tersebut dapat lebih tinggi.3,4 Proteksi otak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan sel-sel otak yang diakibatkan oleh keadaan iskemia sehingga didapatkan outcome Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan Keterangan Hemoglobin Hematokrit Leukosit Trombosit Natrium Kalium Clorida Ureum Creatinin SGOT 11,3 g/dl 32% 14.700/mm3 230.000//mm3 138 mEq/L 3,51 mEq/L 105 mEq/L 27,0 mg/dl 0,84 mg/dl 15 u/L SGPT 13 u/L neurologis yang sesuai dengan harapan. Setelah terjadi cedera iskemia, kemampuan regenerasi otak sangat terbatas. Maka dari itu untuk tatakelola anestesi pada kasus dengan SOL dan infark serebri diperlukan tehnik proteksi otak yang baik. II. Kasus Pasien laki-laki usia 62 tahun dengan diagnosis tumor submandibula yang sudah metastase kelenjar leher dan jaringan otak. Anamnesis didapatkan keluhan benjolan dileher yang membesar cepat dalam 1 tahun terakhir. Tidak didapatkan kesulitan menelan ataupun mudah tersedak. Dari pernafasan juga tidak didapatkan adanya keluhan. Pada pemeriksaan neurologis didapatkan keluhan sering nyeri kepala, 1 bulan terakhir pasien mengalami gangguan bicara (pelo) dan tangan kaki dirasakan melemah pada sebelah kanan. Pemeriksaan Fisik Dari pemeriksaan fisik prabedah didapatkan nafas spontan dengan udara ruangan saturasi pulse oxymetri (SpO2) 97%, buka mulut 3 jari, Mallampati I, tidak ada gigi palsu, pergerakan sendi temporomandibular baik, fleksi ekstensi leher baik, didapatkan benjolan submandibulla dengan kosistensi kenyal, tidak melekat pada Pemeriksaan PT APTT Albumin GDS Keterangan 11 ( kontrol 12) detik 31 (kontrol 26) detik 3.43 u/L 107 u/L Tehnik Proteksi Otak pada Pembedahan Non Neurosurgery (Radical Neck Dissection) dengan Premorbid Space Occupying Lesion (SOL) dan Infark Serebri dasar, disertai benjolan lain berbagai ukuran disekitar leher, auskultasi tidak didapatkan wheezing dan ronkhi. Akral hangat, suhu aksila 36,30C, nadi 88x/m, tekanan darah 120/70 mmHg dan CRT <2 detik. Auskultasi suara jantung S12 single, tidak ada suara tambahan. Kesadaran baik, GCS 4x (dysarthria) 6, paralisis N. cranialis tidak didapatkan, didapatkan kelemahan pada ektremitas atas dan bawah sebelah kanan dengan nilai 3, sensoris dalam batas normal, reflek patologis tidak ditemukan dan otonom dalam batas normal. Pupil 3 mm/3mm, reflek cahaya normal/ normal. Miksi spontan tidak terpasang kateter. Bising usus (+) normal. Tulang ekstremitas dan tulang belakang dalam batas normal. Pasien termasuk status fisik ASA 3 geritari, SOL dengan risiko TIK meningkat, infark dan defisit neurologis. Direncanakan pembedahan radical neck dissection bilateral dengan anestesi umum intubasi. Pengobatan steroid tetap diberikan hingga pagi hari menjelang operasi yaitu dexametason 5 mg. Kebutuhan cairan disesuaikan dengan kebutuhan rumatan selama puasa (50 cc/ jam) dengan isoosmolar kristaloid. Pengelolaan Anestesi Dilakukan induksi dengan pemberian midazolam 2,5 mg, fentanyl 100 uq titrasi, lidokain 80 mg, propofol 90 mg titrasi, rocuronium 50mg, satu menit sebelum tindakan intubasi diberikan tambahan propofol 30 mg. Intubasi dilakukan menggunakan laringoskopi Macintosh dengan 159 pipa endotrakeal (ETT) non kinking nomor 7.5, kedalaman ETT 20 cm pada tepi bibir. Pemeliharaan anestesi menggunakan sevoflurane kurang dari 1 MAC dengan aliran oksigen dan N20 (3:1) kombinasi propofol TIVA, fentanyl kontinyu 1–2 μg/KgBB/jam dan vecuronium kontinyu 0,06 mg/KgBB/jam. Ventilasi terkontrol dengan evaluasi end tidal CO2 dan BGA. Target paCO2 30–35 mmHg. Setelah intubasi dilakukan pemasangan CVC subclavia kanan dan arterial line pada arteri radialis kanan. Diberikan mannitol 0,5 mg/kgbb dan dexamethason 10 mg iv sebelum incisi kulit. Monitoring selama operasi berupa evaluasi tekanan darah sistolik, diastolik, arteri rerata, tekanan CVC, end tidal CO2, saturasi oksigen, gelombang EKG, pemasangan stetoskop prekordial, produksi urine melalui kateter urine, insersi NGT, analisa gas darah. Gula darah diperiksa setelah operasi berjalan 2 jam dengan hasil 145. Hasil analisis gas darah selama operasi dengan pH 7,45, PCO2 33, PaO2 210, HCO3 24, BE –0.1, Sat 99%. Pembedahan berlangsung selama 7 jam dengan insisi daerah dekat tumor dan diperlebar pada daerah leher bilateral. Tumor beserta kelenjar limfe diangkat total. Setelah pembedahan selesai dan dilakukan jahitan primer pada luka, dilakukan evaluasi jalan nafas terhadap risiko kemungkinan obstruksi. Dipastikan drain lancar dan perdarahan minimal. Pasien mulai dibangunkan. Evaluasi nafas adekuat dan dapat merespon perintah, dilakukan early emergence dengan difasilitasi lidokain. Pascaekstubasi Foto torak AP normal tidak didapatkan metastasis pada paru. EKG irama sinus 89x/m, axis normal, intraventrikular corda defesiensi inferior borderline. Hasil CT Scan (gambar 1) menunjukkan metastase cerebrum dan cerebello pontin angle, infark pada pons dan otak tengah. 160 Jurnal Neuroanestesi Indonesia 140 120 100 80 60 40 20 0 Sistolik Diastolik HR CVP ET ET CO CO2 2 1 2 3 4 5 6 7 Gambar 2. Grafik Profil Tanda Vital dan Monitoring selama Operasi dinilai lagi status neurologis pasien tidak ada perburukan dari status neurologis dibandingkan preoperatif. Pengelolaan Pascabedah Pasca tindakan bedah, pasien dirawat di Unit Perawatan Intensif (Intensive Care Unit/ICU) selama 2 hari sebelum pindah ruangan untuk observasi patensi jalan nafas, kemungkinan perdarahan dan penurunan derajat status neurologis. Hari kedua di ICU, pasien bernafas spontan, kondisi hemodinamik stabil, sudah bisa diet lunak dan status neurologis tidak ada penurunan bahkan ada kecenderungan kenaikan pada motoris ekstremitas 1 poin, pasien kemudian dipindahkan ke ruangan. regio serebri dan sisanya pada cerebellum. Diketemukannya kasus tersebut bisa sebelum diagnosa dari tumor primer. Pemeriksaan radiologis baik CT scan atau MRI dilakukan karena keluhan dan klinis dari pasien. Rentang usia 45–64 tahun insidensi kasus tersebut III. Pembahasan Insidensi metastase tumor ke otak 80% multipel pada beberapa regio otak. Sekitar 85% pada Gambar 3. Kondisi Pembedahan dan Pascabedah Tabel 2. Balans Cairan Selama Operasi Cairan output Urine 1800 cc Pendarahan 600 cc NS Mannitol Koloid Rumatan NS Cairan operasi NS Keterangan: NS = normal salin Cairan input 500 cc 150 cc 500 cc (50 cc/jam) 400 cc (2 cc/Kg/jam) 500 cc + Ringerfundin 250 cc Balans cairan Defisit 500 cc Tehnik Proteksi Otak pada Pembedahan Non Neurosurgery (Radical Neck Dissection) dengan Premorbid Space Occupying Lesion (SOL) dan Infark Serebri meningkat dan puncaknya pada usia 65 tahun. Pasien ini berusia 63 tahun, masuk pada rentang usia risiko kejadian kasus tersebut. Diagnosa didapatkan setelah diagnosa tumor primer.1,2 Pada pasien ini juga didapatkan stroke iskemia infark pada pons dan otak tengah. Angka kejadian stroke perioperatif 1 dalam 1000 kasus pembedahan, meningkat menjadi 6 dalam 1000 kasus pada kasus-kasus pembedahan vaskular.2-4 Untuk mengantipasi perburukan dari kondisi tersebut maka optimalisasi tekanan perfusi otak (cerebral perfusion pressure/CPP) dengan tehnik proteksi otak sangat diperlukan. Pasien mempunyai risiko terjadinya iskemia selama pembedahan karena beberapa kondisi preoperatif yang mendukung kondisi tersebut. Usia tua dengan adanya SOL dan stroke iskemia, besar kemungkinan risiko kejadian iskemia selama pembedahan tinggi. Manipulasi selama pembedahan pada daerah leher akan mengganggu perfusi otak dengan adanya penekanan pada curah balik atau sirkulasi arteri menuju otak. Posisi kepala yang hiperekstensi berisiko peningkatan TIK. Manipulasi sinus caroticus juga berpengaruh pada stabilitas hemodinamik. Stabilitas hemodinamik yang terganggu akan mengganggu perfusi otak. Anestesiolog harus mewaspadai faktor-faktor tersebut. Monitoring ketat dan melihat lapang pembedahan penting untuk mengantisipasinya. Target tatalaksana anestesi dengan proteksi otak pada pasien ini adalah mencegah perburukan dari kondisi iskemia dan cedera otak sekunder untuk menghasilkan luaran neurologis yang diharapkan. Daerah penumbra akibat pendesakan SOL ataupun infark dapat dijaga perfusinya secara optimal dan memperpanjang kemampuan kompensasinya. Berdasarkan postulat Monro Kellie bahwa isi otak adalah konstan, meliputi 80% massa otak, 10% darah dan 10% cairan serebro spinal, maka peningkatan TIK yang tidak terkompensasi dapat meningkatkan TIK melebihi batas regulasi. Ini besar terjadi pada kasus ini, karena tidak dilakukan dekompresi.5-7 Obat-obatan anestesi yang dipilih adalah obatobat yang termasuk golongan obat neuroanastesi. 161 Untuk induksi anestesi pada kasus ini dipilih obat-obatan yang mempunyai efek proteksi otak. Midazolam digunakan sebagai koinduksi dengan dosis 30 µg/kgbb untuk mengurangi kebutuhan obat anestesi lain dan memperdalam induksi. Propofol digunakan sebagai obat induksi karena memiliki efek proteksi otak. Tekanan intrakranial, aliran darah otak dan metabolism otak turun pada penggunaan propofol.8 Propofol diberikan titrasi 80 mg untuk induksi untuk menghindari penurunan tekanan darah yang dapat menurunkan CPP, terutama pada kasus geriatri. Lidokain berdasarkan literatur digunakan sebagai adjuvant proteksi otak. Pemberian lidokain menurunkan CMRO2 15–20%. Dosis yang direkomendasikan 1,5 mg/kgbb. Tujuan lain penggunaan lidokain untuk menurunkan respon hemodinamik sewaktu dilakukan tindakan intubasi.9 Pada kasus ini digunakan lidokain 80 mg intravena saat induksi dengan harapan tidak terjadi gejolak hemodinamik yang dapat meningkatkan tekanan darah rerata dan lidokain mempunyai efek proteksi otak. Mekanisme lidokain dalam proteksi otak adalah menurunkan perpindahan ion transmembran, menurunkan laju metabolisme otak (cerebral metabolit rate/CMR), modulator aktifitas leukosit dan menurunkan pelepasan excitotoxin karena iskemia.7 Anestesi inhalasi yang digunakan dalam prosedur ini adalah sevoflurane dengan menggunakan aliran gas O2 dan N2O dengan perbandingan (60:40). Penggunaan aliran oksigen 60% dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tekanan PaO2 diatas 200 mmHg dan dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan analisis gas darah. Penggunaan N2O dipilih karena tidak tersedianya fasilitas udara bertekanan. Penggunaan N2O dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah otak secara langsung dan meningkatkan aliran darah otak, akan tetapi efek tersebut dapat dikurangi dengan tindakan hiperventilasi (PaCO2 30–35). Pada beberapa penelitian penggunaan N2O tidak memiliki efek protektif terhadap neuron otak dan dapat menyebabkan vakuolisasi endoplasmik retikulum serta mitokondria. N2O juga dapat menyebabkan disinhibisi pada reseptor GABA secara menyeluruh. Pada pasien 162 Jurnal Neuroanestesi Indonesia dengan defisiensi asam folat, penggunaan N2O dapat menyebabkan degenerasi medulla spinalis serta manghambat pemulihan elektrofisiologis sel. Akan tetapi pengaruh negatif tersebut bervariasi bila N2O digunakan bersama anestesi inhalasi lain, dengan atau tanpa hipokapnia.6,10 Sevolurane digunakan dalam kasus ini karena efek dari vasodilatasi serebral serta peningkatan CBF yang paling kecil diantara semua gas anestesi. Sevoflurane juga memiliki efek neuroprotektif berupa anti apoptosis.11 Penurunan curah jantung oleh sevoflurane juga lebih kecil dibandingkan isoflurane ataupun halothane sehingga menghindari pemberian cairan berlebih atau penggunaan vasokonstriktor. Ekstubasi dini setelah pemakaian sevofluran memfasilitasi dilakukan pemeriksaan neurologis dini.8 Pelumpuh otot yang digunakan adalah vecuronium dengan dosis bolus 0,1 mg/kgBB dan dosis rumatan 0,06 mg/kg/jam. Vecuronium dipilih pada kasus ini karena tidak menyebabkan pelepasan histamin yang dapat menimbulkan gejolak hemodinamik dan tidak meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan edema. Vecuronium juga mempunyai efek minimal atau tidak ada efeknya pada ICP, tekanan darah, denyut jantung dan efektif pada pasien dengan SOL ataupun iskemia. Rocuronium merupakan alternatif terbaik karena mula kerja cepat dan sedikit pengaruhnya pada dinamika intrakranial.12 Pemberian kortikosteroid pada kasus tumor otak untuk mengurangi edema disekeliling tumor. Pemberian steroid sebelum reseksi tumor sering memberikan perbaikan neurologis mendahului pengurangan tekanan intrakranial. Steroid dapat memperbaiki kerusakan barier darah-otak. Pada kasus ini, steroid sudah diberikan sejak sebelum pembedahan. Banyak literatur menuliskan pemberian steroid menurunkan edema vasogenic peritumoral. Efek steroid melalui mekanisme stabilisasi membran, mencegah pelepasan lipid peroxidase dan antiinflamasi sehingga dapat sebagai proteksi kondisi iskemia otak. Selain steroid diberikan juga mannitol dengan dosis 0,5–1 gr/kgbb dengan tujuan menurunkan tekanan intrakranial (TIK), meningkatkan CPP dan memperbaiki aliran darah otak terutama pada daerah iskemia.6,7 Suhu tubuh dijaga pada rentang 35–36 0C dengan tujuan mempertahankan kondisi low normothermia. Terdapat bukti-bukti dari kondisi tersebut sebagai upaya proteksi otak. Keuntungan low normothermia terbatas pada mencegah kejadian hipertermia yang sangat tidak menguntungkan dan menghindari efek samping dari kondisi hipothermia. Literatur menyarankan suhu tubuh di kamar operasi 34–35 0C dan pascabedah di ICU 36 0C.6 Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan intakranial adalah dengan mengatur posisi pasien elevasi 15–30 derajat. Mencegah penekanan pada vena-vena leher karena posisi leher yang tertekan dapat menyebabkan penurunan drainase vena jugularis sehingga menyebabkan peningkatan TIK. Mencegah PEEP dengan mengawasi penekanan pada daerah abdomen dan toraks yang dapat meningkatkan tekanan inspirasi puncak dan mempengaruhi aliran darah ke jantung.6 Pengelolaan cairan selama pembedahan dengan memperhitungkan kebutuhan rumatan dan penggantian cairan yang keluar melalui urin akibat penggunaan diuretika osmotik dan perdarahan. Target dari hematokrit optimal dengan kondisi iskemia pada otak adalah 30%–32%. Penting untuk mencapai kondisi tekanan perfusi serebral (CPP) yang optimal.13 Pembatasan cairan yang berlebihan akan menurunkan CPP sehingga akibat kondisi iskemia makin besar.14 Pada kasus ini perdarahan 600 cc dan digantikan dengan koloid. Urin digantikan dengan kristaloid. Balans cairan selama operasi tercapai defisit 500 cc. Dengan kondisi defisit ringan tersebut diharapkan tercapai target hematokrit dan CPP yang optimal. Kondisi normovolemia adalah hal yang sementara ini diterima paling luas oleh para ahli, kontroversi penggunaan jenis cairan masih dalam perdebatan.14 Pascabedah dilakukan rapid emergence dengan mempertimbangkan lama operasi tidak lebih 7 jam, perdarahan tidak banyak, airway aman, nafas spontan adekuat dan tidak ada tanda-tanda kejadian penurunan status neurologis. Untuk menghindari batuk dan perubahan hemodinamik mendadak selama ekstubasi difasilitasi dengan pemberian lidokain. Evaluasi status neurologis Tehnik Proteksi Otak pada Pembedahan Non Neurosurgery (Radical Neck Dissection) dengan Premorbid Space Occupying Lesion (SOL) dan Infark Serebri dini dilakukan pascabedah dengan tujuan untuk menilai outcome pembedahan dan jika ada komplikasi dapat segera terdeteksi. Pada pasien ini status neurologis dinilai tidak didapatkan penurunan. Penilaian kembali ke kondisi semula tanpa adanya tambahan defisit neurologis yang lain. V. Simpulan Tehnik proteksi otak bertujuan mencegah cedera sekunder dari SOL dan iskemia. Beban anestesi dan pembedahan akan menambah perburukan cedera sekunder. Penatalaksanaan anestesi yang baik dengan prinsip proteksi otak akan menghasilkan luaran pembedahan sesuai yang diharapkan. Daftar Pustaka 1. Lassman AB, DeAngelis LM. Brain metastases. Neurol Clin N Am 2003; 21:1–23. 2. Anonimus. Metastasic brain tumors. American Brain Tumors Association (ABTA) 2012. 3. Mashour GA, Moore LE, Lele AV, Robicsek R, Gelb WA. Perioperative care of patients at high risk for stroke during or after noncardiac, non-neurologic surgery: Consensus statement from the society for neuroscience in anesthesiology and critical care. J Neurosurg Anesthesiology 2014;00:000–000. 4. Patel P. Brain protection – The clinical reality. Revista Mexicana de Anestesiologia 2007; 30(1): 101–06. 5. Hans P, Bonhomme V. The rationale for perioperative brain protection. EJA 2004; 21(1): 1–5. 163 6. Bisri T. Dasar-Dasar Neuroanestesi. Edisi ke-2. Bandung: Saga Olah Citra; 2008, 1–74. 7. Menon G, Nair S, Bhattacharya RN. Cerebral protection – Current concepts. IJNT 2005; 2(2):67–79. 8. Rao GSU. Anaesthetic management of supratentorial intracranial tumors. ISSN 2005; 311(2): 4. 9. Lalenoh D, Bisri T, Yusuf I. Brain protection effect of lidocaine measured by interleukin-6 and phospholipase A2 concentration in epidural haematoma with moderate head injury patient. J Anesth Clin Res 2014;5(3):1–3. 10. Ansgar MB, Jeffresy RK. Essentials of Neurosurgical Anesthesia & Critical Care. Springer; 2012: 78–80. 11. Ravussin PA, Smith W. Supratentorial mass: anesthetic considerations. Dalam: Cottrell JE, Smith DS, eds. Anesthesia and Neurosurgery. 4th ed. St.Louis: Mosby 2001; 297–313. 12. William F, Chandler. Management of suprasellar meningioma. J NeuroOphthalmology 2003; 23(1): 1–2. 13. Ramachandra PT, Sheth RN, Heros RC. Hemodilution and fluid management in neurosurgery. Clinical Neurosurgery 2006;53:249–50. 14. Lindroos AC, Niiya T, Lundell M, Randell T, Hernesniemi J, Niemi T. Stroke volumedirected administration of hydroxyethyl starch (HES 130/0.4) or ringer´s acetate in sitting position during craniotomy: a randomised controlled trial. Acta Anaesthesiol Scand 2013;57(6):729–36. Anestesi untuk Malformasi Arnold Chiari Ardana Tri Arianto, MH Soedjito Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Solo Abstrak Malformasi Arnold-Chiari, merupakan suatu bentuk malformasi pada otak. Pada malformasi ini terjadi pergeseran (displasi) tonsila serebelum ke arah bawah melalui foramen magnum (lubang di basis kranii), yang terkadang menyebabkan hidrosefalus non-komunikans sebagai akibat terjadinya obstruksi aliran keluar dari cairan serebrospinal. Seorang wanita 23 tahun datang dengan keluhan sering pusing, nyeri tengkuk, serta kelemahan pada lengan kanan. CT Scan dan MRI didapatkan gambaran cerebellar tonsil yang mendukung Arnold Chiari Malformation. Dilakukan operasi osteotomi suboccipital dengan posisi prone. Rumatan anestesi dengan sevoflurane 1 vol% dan O2: udara 1,5: 1,5, analgetik fentanyl 25 mcg tiap 30 menit, pelumpuh otot vecuronium 3 mg/jam. Operasi berlangsung selama 2 jam 45 menit. Hemodinamik selama operasi stabil. Dilakukan ekstubasi segera di kamar operasi. Pascaoperasi pasien dirawat di unit intensif selama sehari. Hemodinamik selama di ICU stabil. Tidak ada keluhan selama di ICU. Kata kunci: fossa posterior, malformasi arnold chiari, posisi prone JNI 2014;3 (3): 164‒72 Anesthesia for Arnold Chiari Malformation Abstract Arnold-Chiari's malformation, is a brain malformation caused by the displacement of the cerebellar tonsil caudally into the foramen magnum, which in some cases will cause obstruction of the cerebrospinal fluid flow, resulting in a communicating hydrocephalus condition. A 23 years old female patient with a chief complaint of having frequent dizzines, painful neck, and weakness of the right arm. CT scan and MRI reveal cerebellar tonsil imaging that support the diagnosis of Arnold-Chiari's malformation. Surgical procedure was performed using suboccipital osteotomy approach in a prone position. Maintenance anesthesia with sevoflurane 1 vol% and O2: air 1,5: 1,5, analgetic fentanyl 25 mcg every 30 minute, muscle relaxant vecuronium 3 mg/hour. The time of surgery was 2 hours and 45 minutes. Hemodynamics were stable during the procedure. Patient was extubated early after surgery at operating room, and admitted to the ICU for 24 hours. Hemodynamics parameter were stable, without any remarkable events. Key words: posterior fossa, Arnold-Chiari's malformation, prone position JNI 2014;3 (3): 164‒72 164 Anestesi untuk Malformasi Arnold Chiari I. Pendahuluan Malformasi Chiari menunjukan turunnya cerebellar tonsils melalui celah terbesar di dasar tengkorak (foramen magnum) ke bagian atas cervical (leher). Secara normal cerebellar tonsils terletak didalam tengkorak. Seorang dengan Malformasi Chiari, tonsilnya turun ke bawah sampai vertebra cervical pertama atau terkadang bahkan sampai vertebra cervical kedua. Istilah "malformasi" mungkin tidak sepenuhnya sesuai. Istilah ini tentu saja tidak digunakan dalam cara yang sama seperti saat kita memikirkan malformasi jantung pada bayi baru lahir, bibir sumbing, clubfoot atau spina bifida. Ketika Profesor Hans Chiari pertama kali menjelaskan Malformasi Chiari lebih dari 100 tahun yang lalu, perbedaan ini tidak jelas. Saat ini kita meyakini pada sebagian besar orang, turunnya tonsils terjadi karena adanya rongga di tengkorak dimana terdapat cerebellum dengan kedua tonsilnya (kanan dan kiri), rongga tersebut terlalu kecil untuk berkembangnya otak; dengan demikian, tonsil "keluar" melalui foramen magnum. Pada tahun 1890 Profesor Chiari pertama kali mendiskripsikan kelainan yang saat ini kita kenal sebagai Malformasi Chiari. Semua penelitiannya dilakukan pada bayi yang lahir mati atau bayi yang baru lahir, dan kelainan yang dia teliti diklasifikasikan sesuai dengan tingkat keparahan tonsillar and cerebellar descent, tipe I menjadi tipe yang parah, tipe IV adalah tipe yang terparah. Saat ini ada terdapat banyak pemahaman yang lebih mengenai kondisi ini, tidak ada ukuran yang kecil berdasarkan hasil MRI. Kita menyadari adanya fakta bahwa Malformasi Chiari III and IV benar-benar merupakan malformasi otak yang parah dan bayi dengan masalah ini pada umumnya tidak dapat bertahan lama setelah kelahirannya. Fossa posterior atau ruangan infratentorial berisi pons, medulla (brainstem) dan serebellum. Dalam medulla terdapat serabut motoris dan sensoris utama, nervus cranial, pusat-pusat vital yang mengendalikan fungsi respirasi dan kardiovaskuler, sistem aktivasi retikuler dan jalan keluar cairan serebrospinal (cerebrospinal fluid/ CSF) dari sistem ventrikuler serebri.1,2 Tumor di daerah ini akan menekan dan menyebabkan 165 obstruksi CSF atau penekanan pada batang otak pada stadium pertumbuhan tumor. Disebabkan karena kecilnya ruangan fossa posterior, suatu space occupying lesion (SOL) atau sedikit edema akan menimbulkan gejala neurologis.2 Masalah selama pembedahan adalah adanya pengaruh pada fungsi pernafasan dan kardiovaskuler atau saraf kranial dimana efek ini kadang-kadang menetap sampai ke periode pascabedah, sehingga memerlukan perawatan ICU. Operasi pada fossa posterior mungkin tumor, aneurisma, dekompresi saraf kranial. Obstruksi tumor pada aliran CSF di ventrikel IV bisa menyebabkan hidrosefalus.1,3 Masalah anestesi pada operasi fossa posterior adalah adanya bahaya emboli udara, stimulasi batang otak dengan kemungkinan kerusakan pusat-pusat vital dan saraf kranial, dan bahaya yang dihubungkan dengan posisi pasien.1-3 Operasi fossa posterior terkadang membutuhkan posisi pasien yang tidak umum, banyak digunakan posisi prone, lateral, park bench, dan posisi duduk. Pada posisi prone, ulserasi kulit wajah dapat terjadi karena tekanan saat menggunakan head rest, dan kebutaan dapat terjadi oleh karena tekanan pada bola mata. Faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan posisi ini termasuk kehilangan darah yang signifikan, anemia, dan hipotensi.4 II. Kasus Anamnesa Seorang wanita, Nn. U, usia 23 tahun datang ke RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan keluhan sering pusing dan nyeri tengkuk. Kondisi ini sudah dirasakan sejak beberapa tahun terakhir namun memberat dalam 3 bulan terakhir. Nyeri yang dirasakan hilang timbul, kadang menetap. Ketika nyeri tersebut timbul dapat mengganggu aktivitas. Pada bulan Januari 2014 pasien memeriksakan diri di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Setelah berkonsultasi dengan dokter saraf, sempat diberi obat penghilang rasa sakit, tapi tetap mengganggu aktivitas. Keluhan lain yang dirasakan pasien adalah perkembangan ruas jari kanan pasien sedikit lebih kecil dibanding kiri, dan agak kesulitan mengangkat beban yang terlalu berat, sehingga dilakukan pemeriksaan CTscan dan akhirnya MRI. Didapatkan kesimpulan hasil berupa: Gambaran tonsil cerebelli dibawah 166 Jurnal Neuroanestesi Indonesia foramen magnum sejauh 25,5 mm sesuai dengan gambaran “Malformasi Arnold–Chiari”. Syrinx setinggi vertebra C2 s/d vertebra Th 1-12. Tidak ada keluhan kejang/batuk/muntah/ gangguan pendengaran/gangguan menelan.Tidak didapatkan riwayat penyakit lain (asma, alergi, hipertensi, diabetes melitus, sesak/biru sejak kecil). Riwayat penyakit keluarga disangkal. Riwayat operasi sebelumnya disangkal. Di RSUD Dr. Soetomo disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter bedah saraf. Karena tempat tinggal pasien di Cepu sehingga memutuskan berobat di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta yang lebih dekat dengan tempat tinggal pasien. Pemeriksaan Fisik Pada pemeriksaan praoperasi (7 Februari 2014), didapatkan: Pasien dengan berat badan 50 kg, tinggi badan 156 cm, kesan status gizi cukup, keadaan umum baik dan tidak tampak sesak, kesadaran komposmentis, GCS E4V5M6, pupil isokor diameter 3 mm/ 3 mm, reflek cahaya (+/+), tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 x/menit, laju napas 15 x/ menit, suhu afebril. Konjungtiva anemis (-), sklera ikterik (-), napas cuping hidung (-), tekanan vena jugularis tidak meningkat, limfonodi leher tidak membesar. Gigi palsu dan gigi goyah (-) dengan skor Mallampati 1. Abdomen Inspeksi : Dinding perut sejajar dengan dinding dada Auskultasi : Bising usus (+) normal Perkusi : Timpani Palpasi : Supel, nyeri tekan (-) Ekstremitas : CRT <2 detik Oedem : Superior (-/-); Inferior (-/-) Akral dingin ; Superior (-/-); Inferior (-/-) Lengan dan tangan kanan lebih kecil 20% dibandingkan lengan dan tangan kiri Sensorik : Kanan sama dengan kiri Motorik : Lengan kanan 4 vs Lengan kiri 5, Tungkai kanan 5 = tungkai kiri 5 Thorax : Bentuk dan ukuran normal, retraksi intercostal (-) Cor Inspeksi Palpasi Perkusi Auskultasi Pulmo Inspeksi Palpasi Perkusi Auskultasi : : : : Tidak dilakukan Tidak dilakukan Tidak dilakukan Bunyi jantung I – II normal, intensitas normal, reguler, bising (-). : Pengembangan dada kanan = dada kiri : Fremitus dada kanan = dada kiri : Sonor – sonor : SD vesikuler (+/+); ST Ronkhi (-/-); ST Wheezing (-/-) Pemeriksaan Laboratorium Laboratorium darah (13 Februari 2012) Hemoglobin : 12,5 g/dl Hematokrit : 39% Leukosit : 8.000/ul Trombosit : 305.000/ul Eritrosit : 4,70 juta/ul Gula darah sewaktu : 148 mg/dl Natrium : 138 mmol/L Kalium : 3,9 mmol/L Chloride : 105 mmol/L Golongan Darah : AB PT : 11,4 detik APTT : 20,7 detik INR : 0,880 Albumin : 4,8 g/dl SGOT : 19 u/l SGPT : 12 u/l Ureum : 16 mg/dl Creatinin : 0,5 mg/dl MRI tanpa kontras (16 Januari 2014) • Tampak tonsil cerebelli dibawah foramen magnum sejauh 25,5 mm • Tampak lesi fuiform beaded appearance di myelum setinggi VC2 s/d Vth 11–12 yang Anestesi untuk Malformasi Arnold Chiari • • • • • • yang hipodens pada T1W1 dan hiperintens pada T2W1 Alignment baik, curve normal. Tak tampak listesis ataupun kompresi Tak tampak perubahan intensitas bone marrow Tak tampak loss of intense pada discus intervertebralis Conu medularis berakhir pada L1 – L2 Tak tampak gambaran abses soft tissue MR myelografi: Tak tampak hambatan aliran liquor cerebrospinalis Simpulan: • Sesuai “Malformasi Arnold–Chiari” dengan gambaran tonsil cerebelli dibawah foramen magnum sejauh 25,5 mm. • Syrinx setinggi VC2 s/d VTh 1-12. kg) perlahan, lalu lidocaine 80 mg (1,5 mg/kg), lalu propofol 50 mg (1mg/kgBB). Pelumpuh otot menggunakan vecuronium 5 mg (0,1 mg/ kg BB). Dilakukan pemasangan ETT 7,0 non kingking. Memastikan kedalaman ETT (level 21) dan dilakukan fiksasi. Rumatan anestesi dengan sevoflurane 1 vol% dan O2: udara 1,5: 1,5. Analgetik fentanyl 25 mcg tiap 30 menit, pelumpuh otot vecuronium 3 mg/jam. Setelah terintubasi dilakukan pemasangan jalur infus intravena di dorsum manus sinistra dengan kanul intravena 18G terhubung dengan infus NaCl 500 ml (untuk mengantisipasi bila terjadi perdarahan) dan pemasangan kateter urin. Lalu tanda vital sementara dicopot untuk dilakukan pemindahan dari brankar ke meja operasi. Pasien diposisikan tengkurap (prone). Pemasangan kembali bedside monitor. Setelah dilakukan pemasangan doek steril diberikan fentanyl 25 Konsul Anestesi Setuju penatalaksaan anestesi atas pasien Nn U dengan “Malformasi Arnold– Chiari”, yang akan dilakukan kraniotomi/osteotomi dekompresi dengan status fisik ASA II. Pengelolaan Anestesi Perencanaan anestesi dilakukan dengan anestesi umum dengan ETT respirasi kontrol dengan teknik neuroanestesi dan dilakukan proteksi otak, sedia darah sesuai operator, pascabedah di ICU, disiapkan ventilator jika diperlukan, lakukan informed consent, puasa 6 jam pre op, disertai pemasangan IVFD RL 20 tetes per menit. Pasien masuk ruang operasi pada jam 08.10, dilakukan pemasangan EKG, saturasi oksigen dan tekanan darah (pasien tetap di brankar). Didapatkan data tanda vital: Tekanan darah: 108/ 67 mmHg Denyut jantung: 85 x/ menit, Saturasi: O2 100%,E K G : S i n u s rhythm Pembiusan tetap dilakukan di kereta pendorong/ brankar pada jam 08.15. Kemudian pasien diberikan sedasi dengan midazolam 0,05 mg/ kg (2,5 mg). Sambil diberikan loading NaCl 300cc. Mulai diberikan fentanyl 150 mcg (3 mcg/ 167 Gambar 6. CT Scan Pasien Gambar 7. Posisi Prone Pasien 168 Jurnal Neuroanestesi Indonesia mcg. Operasi dimulai pada pukul 09.00. Obat– obatan yang diberikan selama operasi berupa Fentanyl 25 mcg/30 menit sebanyak 3x, asam tranexamat 1000 mg, dexketoprofen 50 mg dan ondansetron 4 mg. Operasi dimulai pada pukul 08.30. Operasi berjalan selama 2 jam dan 45 menit, selesai pada pukul 11.15. Selama operasi, kisaran tekanan darah 89/58 mmHg–108/67 (MAP 60–80) mmHg; denyut jantung 65–98 x/ menit; saturasi O2 99–100%. Perdarahan kira-kira 200 cc. Produksi urin 30cc/jam. Pasien dilakukan prosedur osteotomi suboccipital. Diambilnya tulang kurang lebih 1,5 cm untuk dekompresi. Kemudian dilakukan observasi duramater kurang lebih 30 menit. Prosedur operasi selesai pukul 11.15. Pascaoperasi pasien dilakukan early extubation (Fast track), dengan extubasi dalam dengan lidocaine 60 mg. Jam II = (100 + 300) mL = 400 mL Jam III = (100 + 300) mL = 400 mL Ditambah keluaran urin dan perdarahan yang terjadi selama operasi. Perhitungan kebutuhan transfusi (BB 50 kg) 1. Estimated blood volume (EBV) EBV= 65 ml/ kgBB x 50 kg = 3.250 mL 2. ABL = 20% x EBV= 650 mL Perdarahan yang terjadi selama operasi < ABL, tidak perlu transfusi. Pada pukul 11.45 pasien selesai operasi lalu dilakukan extubasi kemudian di bawa ke ICU dengan instruksi pascabedah: periksa laboratorium darah rutin pascabedah, analgetik pascabedah dexketoprofen/8 jam dan paracetamol/8jam. Bila bising usus (+), Pengelolaan Pascabedah Perawatan pascabedah dilakukan di ruang ICU. Kesadaran composmentis. Tanda vital stabil. Suplementasi oksigen dengan nasal kanul 3 liter/menit. Analgetik pascabedah dengan menggunakan dexketoprofen 50 mg/8 jam dan paracetamol infus 1000mg/8jam. Fungsi motorik dan sensorik kembali seperti sebelum operasi. Perhitungan kebutuhan cairan perioperatif (BB 50 kg) Pengganti puasa Pasien mendapatkan asupan oral terakhir 8 jam sebelum operasi dimulai dan infus intravena telah terpasang. Pengganti puasa= 2 mL/ kgBB/ jam x 50 kg x 8 jam = 800 mL Dari ruangan, kebutuhan pengganti puasa telah diberikan sebanyak 1 kantung infus malam sebelumnya, dan infus diganti pagi hari jam 5, tersisa sekitar 200 mL. Sehingga diasumsikan kehilangan cairan karena puasa preoperasi sudah tergantikan. Pemeliharaan Pemeliharaan = 2 mL/ kgBB/ jam x 50 kg = 100 mL/ jam Stres operasi besar = 6 mL/ kgBB/ jam x 50 kg = 30 mL/ jam Sehingga rencana pemberian cairan: Jam I = (100 + 300) mL = 400 mL Gambar 8. Medan Operasi 1 Gambar 9. Medan Operasi 2 Anestesi untuk Malformasi Arnold Chiari maka boleh minum sedikit demi sedikit. III. Pembahasan Gejala Arnold Chiari Malformation antara lain nyeri kepala, kelelahan, kelemahan otot (kelemahan dimulai dari lengan tangan kemudian berjalan sesuai dengan arah jarum jam), kesulitan menelan, pusing, mual, gangguan koordinasi, dan pada kasus-kasus yang berat, juga dapat menyebabkan paralisis. Pada pasien ini hanya didapatkan nyeri kepala disertai atrofi pada ruas jari kanan dan kelemahan lengan kanan dibandingkan kiri. Dari pemeriksaan CT Scan dan MRI didapatkan kesimpulan hasil berupa: Gambaran tonsil cerebelli dibawah foramen magnum sejauh 25,5 mm sesuai dengan gambaran “Malformasi Arnold–Chiari”. Syrinx setinggi C2 s/d Th 1–12. Arnold Chiari malformasi sendiri terdiri dari 4 tipe. Klasifikasi pada pasien ini termasuk Arnold Chiari Malformasi tipe I. Arnold Chiari malformasi merupakan kelainan di fossa posterior. Hasil pemeriksaan darah pascaoperasi: Laboratorium darah pasca operasi (07 Februari 2014 jam 15.00) Hemoglobin : 12,1 g/dl Hematokrit : 38% : 11.200/ul Leukosit : 282.000/ul Trombosit : 4,55 juta/ul Eritrosit : 138 mmol/L Natrium : 3,9 mmol/L Kalium : 110 mmol/L Chloride : 7,383 PH : - 3,6 BE : 35,3 PCO2 : 238 PO2 : 21,4 HCO3 : 99,4 Saturasi Follow Up hari ke -1 di ICU : Tidak ada Kel : Baik, Kes: CM, GCS 15 KU : tensi 110/70, HR 82 x/menit VS RR VAS 169 : spontan 18x/menit, Nasal kanul O2 2 lpm : 2 Pemeriksaan fisik : anemis (-) Mata : cor dan pulmo dbn Thoraks : BU(+) normal, supel Abdomen Ekstremitas : edema (-) Pasien dapat pindah perawatan di ruangan Masalah anestesi pada operasi fossa posterior adalah adanya: bahaya emboli udara, stimulasi batang otak, kemungkinan kerusakan pusat-pusat vital dan saraf kranial, bahaya yang dihubungkan dengan posisi pasien. Untuk prosedur pada pasien ini dilakukan posisi prone. Prosedur untuk Chiari Malformation dapat dikelompokkan menjadi 4 Group antara lain: dekompresi, drainase syrinx, terminal ventrikulostomi, aspirasi perkutaneous syrinx. Pada pasien ini dilakukan dekompresi dengan cara osteotomi suboccipital. Pengelolaan Anestesia Tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan premedikasi. Premedikasi yang berat harus dihindari pada pasien dengan hidrocephalus dan peningkatan tekanan intrakranial. Selama membuka tulang tengkorak dan hindari pemakaian N2O, gunakan ventilasi kendali.2,3,9 Harus ada monitor untuk mendeteksi emboli udara dan mendeteksi kerusakan pusat-pusat vital dan nervus cranialis. Pemakaian Doppler dan ET CO2 dipertimbangkan untuk pemakaian minimum.10 Teknik anestesi yang baik untuk operasi otak: mempertahankan CPP yang baik, relaksasi otak yang baik, stabilisasi kardiovaskuler baik tekanan darah atau irama.2,3 Hipotermia ringan (34–36 o C) harus selalu dijaga selama operasi. Teknik hipotermia ringan ini bisa memberikan dampak yang bagus bagi perkembangan otaknya selama operasi.9 Penempatan retraktor dekat batang otak dapat menimbulkan perubahan irama dan tekanan darah.1 Stimulasi batang otak dan nervus kranialis mempunyai efek yang dramatis. Hipertensi hebat terjadi akibat stimulasi nervus kranialis V, daerah 170 Jurnal Neuroanestesi Indonesia periventrikuler substansia grisea, formasio retikularis, nukleus traktus solitarius. Bradikardia terjadi akibat stimulasi nervus vagus. Hipotensi terjadi akibat penekanan medulla oblongata dan pontin. Ventrikuler dan supra ventrikuler aritmia terjadi akibat stimulasi struktur batang otak. Persiapan dengan atropin atau glikopirolat kadang diperlukan.1,9 Bangun dari anestesi harus tenang, batuk dan mengejan karena adanya pipa endotrakeal dapat menyebabkan perdarahan intrakranial. Untuk mencegah mengejan dan batuk dapat diberikan lidokain 1,5 mg iv.4,9 Pemeriksaan Prabedah Biasanya pasien dengan SOL pada fossa posterior sensitif terhadap depresi respirasi karena narkotik, juga sensitif terhadap sedatif dan tranquilizer, maka premedikasi dengan sedatif harus minimal. Obat-obat sedasi dan depresi respirasi lebih baik dihindari sebelum pasien betul-betul diawasi oleh anesthesiologist.1,3,9 Kontrol jalan nafas dan sistem respirasi harus dikaji. Pasien mungkin akan merasa disfagi, disfungsi laringeal, ketidakteraturan pola napas. Pada beberapa kasus sering terjadi aspirasi.9 Pasien pada umumnya menderita sakit kepala, muntah tapi gejala tersebut sering berkurang dengan penggunaan steroid. Mungkin diperlukan premedikasi dengan antiemetik.1 Untuk menentukan apakah pasien dapat diekstubasi atau tidak, tidak selalu mudah. Pada umumnya, jika pasien komposmentis pada periode prabedah dan operasinya superfisial dan tanpa banyak traksi pada batang otak, maka ekstubasi diperkirakan aman bila dilakukan di kamar operasi. Tetapi bila sebaliknya, operasinya dalam, banyak traksi pada batang otak, ada bahaya terjadi apnea dan penurunan sensorium dengan penurunan refleks jalan nafas, pasien harus diintubasi dan diventilasi sampai bahaya terlewati.1 Manajemen anestesi pada pasien di atas pada prinsipnya sama dengan kasus neuroanestesi yang lain. Hal ini disebutkan sebagai ABCDE Neuroanestesi, yaitu1: Airway Jalan napas harus bebas sepanjang waktu, karena bila terjadi hipoksia dan atau hiperkarbia, maka aliran darah akan meningkat. Sebaiknya dipilih pipa endorakheal non kinking dengan ukuran terbesar yang bisa masuk. Breathing Ventilasi kendali dengan target PaCO2 30–35 mmHg untuk operasi tumor dan normokapnea (PaCO2 35–45 mmHg) pada kasus trauma, PaO2 100–200 mmHg. Hindari PaCO2 <20 mmHg karena: (1) sedikit pengaruhnya pada aliran darah (2) untuk mencapai PaCO2 <20 mmHg dibutuhkan ventilasi semenit yang tinggi, sehingga tekanan vena sentral meningkat yang akan menyebabkan peningkatan volume darah dan tekanan di dalam sistem saraf pusat (3) vasokonstriksi sehingga dapat terjadi iskemia. Circulation Pengendalian tekanan darah merupakan faktor yang penting karena saat induksi dapat terjadi hipotensi. Pada pasien yang sebelumnya tekanan darahnya normal, lebih disukai sistolik sekitar 90-100 mmHg. Drugs Pemilihan obat dan keterampilan dokter anestesi sangat penting karena cedera sekunder dapat terjadi sebagai akibat tindakan anestesi. Sebaiknya dipakai obat yang punya efek proteksi otak/sistem saraf pusat. Environment Pengaturan suhu dengan cara mengatur suhu inti 35 0C saat operasi dan menjadi 36 0C pascabedah. Monitoring Dikarenakan komplikasi dari operasi posterior sangatlah besar terutama emboli maka sebaiknya invasif monitor dan ET CO2 terpasang tetapi tidak dilakukan karena masalah fasilitas namun anestesi tetap meminimalisir kejadian tersebut dengan terus memonitor hemodinamik dan dilakukan pemeriksaan analisa gas darah. Perhatian posisi prone pada pasien ini tidak kalah penting antara lain dengan meminimalkan cedera pasien yaitu pemakaian benda lunak untuk melindungi wajah, lengan, lutut. Serta pemantauan hemodinamik akibat perubahan posisi ini. Untuk menghindari cedera akibat tekanan, maka digunakan penahan kepala khusus dan bagian wajah dialasi dengan Anestesi untuk Malformasi Arnold Chiari balon berisi air. ETT dipastikan tidak kinking dan guedel tetap terpasang. Karena kami tidak memberikan antisialogogue maka diinsersikan kasa lembab untuk meresap lendir dari kavitas oral. Pascaoperasi dan ketika pasien sudah bisa diajak berkomunikasi, pasien tidak mengeluhkan adanya perubahan atau gangguan penglihatan pascaoperasi. Juga tidak didapatkan adanya injuri tekan pada tubuh pasien. Posisi prone menyebabkan sisi bedah terletak lebih tinggi daripada jantung, hal ini menyebabkan mudah masuknya udara ke sistem sirkulasi. Deteksi emboli udara ini secara legeartis dapat dideteksi dengan alat Doppler Precordial. Alat ini mampu mendeteksi gelembung udara di sirkulasi bahkan pada volume hanya 1 cc. Selain precordial Doppler, bisa juga digunakan kapnograf. Jika terjadi penurunan end tidal CO2 menunjukkan udara yang memasuki sirkulasi paru. Namun penurunan et CO2 ini tidak spesifik karena bisa juga disebabkan oleh hal lain. Masuknya udara ke sirkulasi paru akan meningkatkan tekanan arteri pulmonalis yang sesuai dengan ukuran emboli yang terjadi. Cara yang paling sensitif adalah menggunakan transesofageal ekokardiografi. 171 fentanyl 25 mcg intermiten tiap 30 menit. Perdarahan durante operasi kurang lebih 200 cc, hemodinamik stabil. Tidak dilakukan tranfusi pada pasien ini. Kami kesulitan mengambil sampel untuk analisa gas darah durante operasi dikarenakan posisi pasien prone. Terapi dari malformasi pada pasien ini dilakukan osteotomi dekompresi untuk mengurangi sempitnya ruangan dari foramen magnum. Setelah tulang terangkat, dilakukan observasi kondisi parenkim otak dan duramater. Operator mengobservasi kurang lebih selama setengah jam, dan diputuskan tidak dilakukan sayatan pada duramater. Emergens Pada pasien ini dilakukan ekstubasi segera karena memenuhi syarat antara lain: kesadaran prabedah adekuat, operasi otak terbatas, tidak ada laserasi otak yang luas, bukan operasi fossa posterior yang mengenai syaraf IX dan XII, bukan reseksi AVM yang besar, temperatur normal, oksigenasi normal, kardiovaskuler stabil. Perawatan pascaoperasi di ICU, hemodinamik stabil dengan hasil analisa gas darah baik. Dirawat di ICU selama 24 jam, dan dipindah ke ruangan. Prainduksi dan Induksi Prainduksi diberikan midazolam 2,5 mg untuk mengurangi kecemasan pasien, sambil dilakukan preoksigenasi. Sebelum pasien diintubasi, diberikan fentanyl 150mcg secara pelan-pelan dan lidocain 80 mg untuk meredam gejolak hemodinamik. Digunakan pelumpuh otot vecuronium 0,1 mg/kg. Intubasi dilakukan setelah tekanan darah menurun kira-kira 20% dari tekanan awal, relaksasi otot adekuat, dan dengan kombinasi obat-obat tersebut diatas pada umumnya tekanan darah tidak terlalu turun (asal sebelumnya normovolemia) dan tidak naik saat intubasi Pascabedah Komplikasi yang dihubungkan dengan operasi fossa posterior: perdarahan atau pembengkakan akut dari struktur struktur fossa posterior harus dipikirkan bila pasien tidak bangun dari anestesi. Adanya vasospasme atau hidrosephalus akibat obstruksi akut perlu dipertimbangkan setelah operasi aneurisma serebral atau ventrikel IV. Bisa juga terjadi epidural atau subdural hematom akibat bridging vena di dura akibat dekompresi yang cepat dari hidrosefalus pada tumor fossa posterior. Burr hole dan fiksasi pin bisa menyebabkan sumber dari perdarahan supratentorial. Pneumocephalus sering terjadi setelah operasi dengan posisi duduk.1 Rumatan Pemilihan obat sebaiknya yang punya efek paling kecil atau tidak mempengaruhi autoregulasi dan respon terhadap CO2, mempertahankan kestabilan kardiovaskuler. Rumatan anestesi dengan inhalasi sevoflurane 1–1,5%, oksigen + udara: 1,5+1,5, tanpa pemakaian N2O. Durante operasi diberikan Pasien yang manifest dengan gejala disfungsi n. Cranialis umumnya karena pembengkakan dan retraksi selama operasi. Kerusakan N. IX dan X dapat dilihat dari kehilangan kemampuan menelan dan batuk yang efektif selama pascabedah, sehingga bisa terjadi aspirasi.9 Bila selama operasi ada retraksi batang otak 172 Jurnal Neuroanestesi Indonesia atau diseksi dekat n. cranialis, maka pada periode pascabedah pipa endotrakeal tetap dipertahankan sampai pasien benar-benar sadar dan mampu menunjukkan refleks jalan nafas yang adekuat.1,4,9 Meningitis aseptis, terlihat dengan adanya peningkatan suhu tubuh, nuchal rigidity ringan, leosyntesis CSF, lebih sering terjadi setelah operasi fossa posterior daripada operasi intrakranial yang lain.1 Simpulan Operasi pada fossa posterior harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati mengingat komplikasi yang terjadi lebih besar yang berkaitan dengan emboli udara, kerusakan saraf, dan bahaya posisi pasien selama operasi. Maka dari itu prinsipprinsip neuroanestesia harus dilakukan dengan baik. Pemantauan fungsi motorik dan sensorik pasien sebelum dan setelah dilakukan prosedur dekompresi harus selalu diamati. Daftar Pustaka 1. Bisri T. Dasar-dasar neuroanestesi. Bandung: Olah Saga Citra; 2011 2. Porter SS, Sanan A, Rengachary SS. Surgery and anesthesia of the posterior fossa. Dalam: Albin MS, ed. Textbook of Anesthesia with Neurosurgical and Neuroscience Pespective. New York: The McGraw-Hill Companie; 1997, 971–1008 3. Cottrell JE, Smith DS. Anesthesi and Neurosurgery. Fourth Edition. Philadelphia: Mosby; 2001, 319–35 4. Pederson DS, Petefreund RA. Anesthesia for posterior fossa surgery. Dalam: Newfield P, Cotrell JE, eds. Handbook of Neuroanesthesia. Fifth edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;2012, 136–47. 5. Batzdorf U, Benzel EC, Ellenbogen RG, Ferrante FM, Green BA, Menezes AH, et al. Chiari malformation and Syringomyelia a Handbook for Patients and their Families; 2008, 5–33 6. Yassari R, Frim D. Evaluation and management of the Chiari. Pediatr Clin N Am 2004;51: 477– 90 7. Longnecker DE. Anesthesiology. New York: The McGraw-Hill Companies;2008, 470–2 8. Edgcombe H, Carter K, Yarrow S. Anesthesia in prone position. Br J Anesth 2008; 100(2): 165–83 9. Duffy C. Anesthesia for posterior fossa surgery. Dalam: Matta BF, Menon DK, Turner JM, eds. Textbook of Neuroanesthesia and Critical Care. London: Greenwich Medical Media Ltd. 2000, 267–80 10. Feldstein N. Pediatric neurosurgery chiari malformation, diakses http: // cpmcnet.columbia.edu/dept/nsg/PNS/ ChiariMalformation.html (1 of 2) [5/24/1999 4:44:18 PM] Awake Craniotomy pada Biopsi Steriotaktik Tumor Supratentorial di daerah Thalamus Dextra et causa Suspect Thalamic Glioma Muhammad Dwi Satriyanto*), Siti Chasnak Saleh**) *)Departement Anestesi dan Terapi Intensif, Eka Hospital Pekanbaru Riau, **)Departemen Anestesiologi dan Reanimasi – Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Abstrak Awake craniotomy merupakan suatu prosedur yang banyak digunakan pada kasus-kasus intrakranial dengan berbagai tujuan, yang memungkinkan dapat menentukan lokasi kelainan di otak yang akurat dan meminimalkan risiko cedera neurologis selama tindakan. Peran anaesthesiologist adalah untuk memberikan analgesia dan sedasi yang memadai sambil mempertahankan ventilasi dan stabilitas hemodinamik pada pasien yang sadar dan harus kooperatif selama tindakan berlangsung. Seorang wanita berusia 32 tahun dengan tumor supratentorial at region thalamus dextra et causa suspek thalamic glioma untuk dilakukan tindakan steriotaktik biopsi dengan Awake craniotomy. Pada pemeriksaan ditemukan keluhan sulit berjalan sejak 4 tahun karena sisi tubuh bagian kiri lemah, bicara cedal, mulut mencong ke kanan, kejang pada kepala dan mata sebelah kiri. Pasien dirujuk karena muntah hebat dan sakit kepala hebat 1 minggu terakhir, kesadaran komposmentis, GCS E4M6V5. Paresenerves VI kanan-kiri, parese nerves VII sinistra sentral. Pemeriksaan laboratorium, ECG dan foto thorak tidak didapatkan kelainan, sedangkan pada MSCT kepala didapat kan adanya massa berbatas tidak tegas, dinding tidak teratur dengan kalsifikasi minimal di thalamus kanan disertai edema perifokal kemungkinan suatu low grade astrocytoma dan hydrocephalus obstruksi. Tindakan biopsi steriotaktik terhadap tumor supratentorial ini dilakukan dengan tehnik anestesi awake craniotomy dengan obat dexmedetomidin, propofol dan fentanyl. Pengawasan pasien di ruang pemulihan selama 4 jam.Setelah Modified Aldrete score 9–10, pasien dipindahkan ke ruangan. Kata Kunci: tumor supratentorial, awake craniotomy, dexmedetomidin, propofol, fentanyl JNI 2014;3 (3): 173‒79 Awake Craniotomy in Stereotactic Biopsy for Supratentorial Tumors at Thalamus Dextra Region et causa Suspect Thalamic Glioma Abstract Awake craniotomy is a procedure that is widely used in intracranial procedures with a variety purposes, which also allows an accurate localization of abnormalities in the brain, and to minimize the risk of neurological injury. Anaesthesiologist role is to provide adequateanalgesia and sedation while maintaining ventilation and hemodynamic stability in patients that still conscious and cooperative during the surgery. A 32years old woman with supratentorial tumor at theright thalamus with suspected thalamic glioma. Stereotactic biopsy was performed under awake craniotomy.She was sufferedwith difficulty in walking for 4 years due to weakness of the left side of the body,slurred talking, and lopsided mouth to the right, withspastic on the head and left eye. She was referred because of severe vomiting and headaches since 1 week, but still fully alert withGCS E4M6V5. She had bilateral nerve VI and central of left nerve VIIpareses. Her laboratory examinations, ECG and thoracic images were normal, whereas MSCT showeda mass with not firm verge, irregular wall with minimal calcification in the right thalamus and perifocaledema, suggested as a low grade astrocytoma and hydrocephalus obstruction. Stereotactic biopsy of supratentorial tumors was performed under awake craniotomy with dexmedetomidine, propofol and fentanyl. The patient was observed at the PACU for 4 hours, and after Modified Aldrete score reached 9–10, the patient was transferred to the ward. Key words: supratentorial tumors, awake craniotomy, dexmedetomidine, propofol, fentanyl JNI 2014;3 (3): 173‒79 173 174 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Sejarah mencatat bahwa operasi untuk intractable epilepsi dilakukan pada pasien yang sadar atau terjaga dibeberapa bagian dari prosedur tindakan, hal ini dilakukan untuk memfasilitasi pemetaan kortikal dan dapat melakukan tindakan eksisi pada focus epileptogenik dengan aman. Walaupun awake craniotomy untuk tindakan pengangkatan tumor otak masih kurang umum dilakukan namun saat ini semakin sering dilakukan. Sementara itu dengan ketersediaan alat modern yaitu dengan paduan system frameless stereotactic dan neuronavigation telah dapat melokalisasi tumor intraoperatif menjadi lebih tepat, namun hal ini juga masih tidak dapat menggantikan pengujian neurologis intraoperatif dengan pasien yang sadar.1-2 Teknik anestesi untuk awake craniotomy telah berkembang selama bertahun-tahun dan saat ini dilakukan dengan anestesi lokal dan sedasi atau anestesi umum dengan pasien bangun saat intraoperatif. Tantangan manajemen anestesi pada awake craniotomy adalah dengan membuat pasien agar cukup nyaman untuk tetap bergerak selama prosedur dan belum cukup mengetahui dan kooperatifnya pasien saat dilakukan pengujian neurologis selama tindakan pembedahan. Ketersediaan obat anestesi dengan kerja singkat telah meningkatkan penggunaannya oleh dokter spesialis neuroanestesi dalam manajemen perioperatif untuk tindakan ini.3-4 II. Kasus Wanita berusia 32 tahun dengan dengan tumor supratentorial at region thalamus dextra et causa suspect thalamic glioma akan dilakukan tindakan stereotaktik biopsi dengan awake craniotomy. Anamnesis Pasien dirawat di rumah sakit dengan keluhan sulit berjalan sejak 4 tahun. Sulit berjalan ini terjadi perlahan, awalnya kaki kiri diseret, namun saat ini pasien tidak bisa berjalan sama sekali disertai dengan kelemahan lengan kiri, bicara cedal, mulut mencong ke kanan, pasien juga pernah mengalami kejang, rasa baal tidak ada. Sejak 7 hari sebelum masuk rumah sakit pasien mengeluh muntah hebat dan sakit kepala sehingga pasien dibawa kerumah sakit. Saat pemeriksaan prabedah pasien tidak mengeluh sakit kepala lagi, tidak ada kejang selama perawatan, tetapi masih mengeluh lemah pada sisi tubuh bagian kiri. Tidak ada riwayat trauma. Tidak didapatkan riwayat penyakit sistemik lainnya dan tidak ada riwayat operasi sebelumnya. Pemeriksaan Fisik Didapatkan pasien tampak sakit sedang, dengan berat badan 50 kg, kesadaran composmentis dengan kontak baik, GCS E4M6V5, pada pemeriksaan mata pupil isokor dengan diameter pupil kanan 4mm dan pupil kiri 4mm dan reflek cahaya baik pada kedua mata, namun didapatkan kesan adanya parese nervus VI mata kanan dan kiri, parese nervus VII sinistra central. Pada respirasi didapatkan suara nafas vesikuler kanan kiri, tidak ditemukan adanya ronki dan mengi, laju nafas 20 kali permenit, pulse saturasi oksigen 99% dengan udara ruangan. Pemeriksaan pada jantung didapatkan S1–2 normal, murmur dan gallop tidak ada, tekanan darah 130/80 mmHg, laju nadi 76 kali permenit. Pemeriksaan ekstremitas didapatkan motorik atas kanan 4 dan kiri 3, sedangkan pada pemeriksaan motorik bawah kanan 4 dan kiri 3, pemeriksaan tonus dalam batas normal, sedangkan pada pemeriksaan sensibilitas dalam batas normal. Pemeriksaan Penunjang Pada pemeriksaan darah didapatkan kadar hemoglobin 13,7g/dL, hematokrit 41%, hitung leukosit 6.400/mm3 dan trombosit 187.000/mm3, Na 138mEq/L, Kalium 3,2 mEq/L, Chlorida 106 mEq/L, Calsium 8,91 mg/dL, Magnesium 1,81mg/dL, Glukosa 137 mg/dL, PT 14,2 detik, INR 1,14 detik, aPTT 24,9 detik, Ureum 19, Creatinin 0,51, Albumin 3,7. Pemeriksaan penunjang foto thorak didapatkan kesan jantung dan paru dalam batas normal tidak tampak metastase intrapulmonal. Pemeriksaan EKG didapatkan irama sinus dengan laju jantung 82 kali permenit. Kesimpulan hasil MSCt kepala didapatkan adanya massa berbatas tidak tegas, dinding tidak teratur dengan kalsifikasi minimal di thalamus disertai dengan edema perifokal, kesimpulan sugestif suatu low grade astrocytoma Awake Craniotomy pada Biopsi Steriotaktik Tumor Supratentorial di daerah Thalamus Dextra et causa Suspect Thalamic Glioma dan hidrocephalus obstruksi. Pengelolaan Anestesia Pada praanestesi, pasien disiapkan untuk tindakan awake craniotomy dengan obat dexmedetomidin, propofol, fentanyl, obat dan alat untuk persiapan anestesi umum bila awake craniotomy mengalami hambatan dan obat-obat darurat. Sebelum dipasang head frame, pasien diberikan midazolam 1mg intravena dan infiltrasi lidokain pada tempat pemasangan pin dari head frame. Pasien tiba di kamar bedah 10.40 wib, pasien diposisikan supine dengan slight head-up, pasien telah terpasang infus dengan cairan NaCl 0,9% pada tangan kiri, kemudian dipasang monitor standar yaitu EKG, tensimeter kontinyu setiap 5 menit, pulse oksimetri, oksigen kanul 2 liter permenit, tidak dipasang kateter urine. Dilakukan pemeriksaan tanda vital awal dengan tekanan darah 125/85 mmHg, nadi 80 kali permenit, pulse saturasi O2 didapatkan 99%, pada gambaran EKG irama sinus. Disiapkan syringe pump yang digunakan untuk dexmedetomidin (konsentrasi 4µg/cc) dengan syringe 25 cc, dihubungkan dengan three way stopcock ke infus. Kemudian diberikan loading dose dexmedetomidine 1µ/kgbb (12mL) selama 15 menit hingga pasien tampak tertidur (Ramsay 2–3), kemudian dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 0,2–0,7 µg/kgbb/jam. Selama pemberian dexmedetomidine ini dilakukan pemantauan ketat hemodinamik. Setelah dilakukan loading dexmedetomidine, 175 diberikan dosis rumatan 0,7 µg/kgbb/ jam, namun setelah 5 menit berjalan didapatkan tekanan darah dan laju jantung turun menjadi 66 kali permenit, lalu dosis dexmedetomidin diturunkan menjadi 0,4 µg/kgbb/jam, namun dalam 5 menit pemantauan didapat laju jantung cenderung tetap turun sampai 57 kali permenit dan kembali dosis dexmedetomidin diturunkan kembali sampai 0,15 µg/kgbb/jam, dan setelah dosis ini laju jantung kembali stabil normal menjadi. Jam 11.15 wib, dilakukan infiltrasi lokal anestesi dengan bupivacain 0,25% ditambah adrenalin 1/200,000 unit, diinfiltrasikan pada daerah yang akan dilakukan insisi. Saat dilakukan insisi kulit kepala, penderita masih mengeluh nyeri, maka ditambahkan fentanyl 1 µg/kgBB perlahan. Jam 11.35 wib dilakukan bor tulang kepala, pasien merasa tidak nyaman dan agak kesakitan, maka diberikan propofol 20 mg iv perlahan dan fentanyl 1µg/kgBB iv perlahan, dosis dexmedetomidin 0,2 µg/kgBB/jam, didapatkan hemodinamik stabil dengan tekanan darah 120/80 mmHg, dan laju jantung 64 x/mnt, saturasi oksigen 99%. Pada jam 12.00 wib, saat dilakukan penusukan trocath melalui lubang yang telah dibuat tadi, pasien gelisah dan mengeluh kesakitan, maka diberikan kembali propofol 20 mg iv perlahan, didapatkan hemodinamik yang stabil dengan tekanan darah 115/75 mmHg, laju jantung 70 x/menit, saturasi oksigen 99%, Ramsay 2. Selama prosedur berlangsung kesadaran dan hemodinamik dipantau secara berkala. Jam 12.10 wib, sebagian Gambar 1. MSCt Kepala dari Tumor 176 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Gambar 2. Pemantauan Tekanan Darah, Saturasi selama Tindakan Berlangsung Gambar 3. Saat tindakan berlangsung (stereotactic biopsy) tumor telah selesai diaspirasi untuk biopsi. Hemodinamik stabil dan infus dexmedetomidine 0,6 µg/kgBB/jam. Dilakukan jahit duramater, evaluasi perdarahan, dosis dexmedetomidin di turunkan bertahap sampai 0,15/kgbb/jam. Jam 12.25 wib operasi selesai, dimana kondisi pasien sadar, tidak ada gangguan anggota gerak, nyeri dengan VAS 2, lalu pasien diberikan metamizol 1 gram iv. Hemodinamik stabil dengan tekanan darah 110/62 mmHg, laju jantung 75x/ menit dan saturasi oksigen pulse 100% dengan binasal kanul 2 liter permenit.Total pemakaian dexmedetomidin 104 µg atau 26 cc, fentanyl 100 µg, propofol 40 mg. Operasi berlangsung selama 2 jam 40 menit, kemudian pasien dipindahkan ke ruang pemulihan dan diobservasi selama 4 jam, setelah modified Aldrete score tercapai 10, kemudian dipindahkan ke ruangan. III. Pembahasan Awake craniotomy pada operasi tumor saat ini menjadi lebih popular, hal ini memungkinkan dilakukan pemetaan otak dan memfasilitasi untuk dilakukanya pengangkatan tumor secara maksimal dengan penurunan risiko morbiditas neurologis. Pada pengangkatan tumor otak yang agresif menawarkan banyak keuntungan, termasuk peningkatan diagnose yang akurat, mengurangai tekanan intrakranial, mengurangi besarnya tumor sebagai awal untuk tambahan terapi dan penurunan differensiasi ke kelas yang lebih rendah. Ada data yang menunjukkan adanya peningkatan lama bertahan hidup rata-rata dan Awake Craniotomy pada Biopsi Steriotaktik Tumor Supratentorial di daerah Thalamus Dextra et causa Suspect Thalamic Glioma timbulnya kekambuhan dikemudian hari, namun hal ini harus pikirkan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan defisit neurologis. Pengangkatan tumor dekat dengan daerah korteks yang penting dapat sangat aman dikerjakan pada pasien yang sadar, karena hal ini memberikan umpan balik terus menerus pada ahli bedah saraf mengenai integritas fungsi neurologis. Penilaian terhadap fungsi neurologis ini juga memfasilitasi dilakukannya tindakan eksisi tumor.1-2 Tindakan anestesi pada awake craniotomy memberikan suatu tantangan tersendiri dan pemilihan pasien merupakan hal yang sangat penting karena tidak semua pasien dapat menjalani tindakan awake craniotomy, kebingungan, penurunan tingkat kesadaran dan komunikasi yang sulit (misalnya disfasia atau hambatan bahasa) serta kecemasan yang ekstrim merupakan kontraindikasi terhadap tindakan awake craniotomy. Lama tindakan sekitar 4 jam dan karenanya kemampuan pasien untuk berbaring diam dalam jangka waktu yang lama harus dipertimbangkan.2-3 Stereotaktik biopsi merupakan suatu prosedur invasif minimal bedah saraf yang dilakukan untuk mengetahui diagnosis dari lesi tumor atau hal lain di dalam otak atau yang diatasnya diliputi otak. Hal ini hanya dimaksudkan sebagai prosedur diagnostik. Modalitas lainnya termasuk pengangkatan bedah penuh, radiasi dan/atau kemoterapi mungkin juga tindakan awake craniotomy ini.1,4 Pasien yang mengalami sleep apnea obstruktif terjadi pada pasien sangat gemuk dan pasien dengan tumor pembuluh darah yang besar atau tumor yang melibatkan duramater secara signifikan dapat memberikan tantangan tambahan bagi dokter sepsialis anestesi. Setiap adanya defisit neurologis dan masalah medis harus diidentifikasikan selama kunjungan prabedah. Pasien juga harus diberitahu tentang kerumitan dan tuntutan dari awake craniotomy. Perlu dibentuk suatu hubungan yang baik antara dokter spesialis anestesi dengan pasien. Tanda-tanda dan gejala yang mungkin menunjukkan bahwa pasien mengalami kejang harus diperhatikan dan obat-obatan seperti steroid dan antikonvulsan harus tetap dilanjutkan Tindakan awake craniotomy menambah stres tambahan bagi 177 pasien dan seluruh tim operasi sehingga semua persiapan harus diselesaikan sebelum pasien tiba di ruang operasi. Semua team harus menyadari kehadiran pasien yang sadar dengan beri tanda pada semua pintu masuk diruang dan kebisingan harus hindari. Gerakan team operasi harus dibatasi dan suasana yang tenang dipertahankan. Jika perlu bantal ekstra, headrest dengan kasur yang empuk dan lembut harus tersedia untuk menjamin kenyamanan pasien selama operasi. Pemantauan rutin tekanan darah tidak invasif, elektrokardiogram dan pulse oksimetri sangat penting. Pemantauan kapnograf juga berguna, terutama sebagai memantau tingkat pernapasan dan kecukupan ventilasi, karena bila terjadi apnea atau obstruksi saluran napas dapat dideteksi oleh hilangnya jejak pada kapnografi. Kehilangan darah umumnya tidak signifikan dan pemasangan kateter vena sentral tidak perlu, Sedangkan pemasangan kateter urin juga tidak rutin dilakukan guna meminimalkan ketidaknyamanan pasien, namun harus dipertimbangkan juga untuk dipasang jika diperkirakan operasi akan terjadi lebih lama atau jika ada kemungkinan besar penggunaan diuretic selama operasi. Penggunaan neuronavigation memerlukan penempatan kepala pasien dalam sistem tengkorak yang kaku dengan pemasangan pin fiksasi sehingga pemberian anestesi lokal harus dilakukan sebelum pin tersebut di pasang. Tambahan analgesia intravena dan sedasi kadang-kadang diperlukan selama pemberian anestesi lokal infiltrasi, karena hal ini dapat sangat menyakitkan pasien, biasanya tindakan anestesi lokal infiltrasi pada kulit kepala ini dilakukan oleh ahli bedah saraf. Obat anestesi lokal kerja lama seperti bupivakain dan ditambah adrenalin sering digunakan. Lignocaine/lidokain dapat diberikan pada daerah yang masih menimbulkan sakit selama prosedur berlangsung seperti pada duramater. Banyak teknik sedasi telah dijelaskan untuk tindakan awake craniotomy, pemberian dan dosis obat sangat bervariasi dan harus diberikan secara titrasi dan sesuai kebutuhan masing-masing pasien. Obat anestesi yang kerja singkat sangat disukai karena dapat memberikan kondisi yang baik dimana pasien masih tetap sadar saat dilakukan penilaian neurologis. 178 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Dahulu digunakan bolus intermiten fentanyl dan droperidol namun saat ini kombinasi propofol dan fentanil atau remifentanil ini sering digunakan. Dexmedetomidine adalah agonis adrenoreseptor α2 selektif. Tidak seperti opioid dan propofol, dexmedetomidine telah terbukti mempunyai sifat sebagai obat penenang dan analgesia tanpa menyebabkan depresi pernafasan yang signifikan. Pemberian dexmedetomidine juga dapat mengurangi penggunaan obat anestesi lain. Pasien yang dianestesi dengan dexmedetomidine mengamali sedasi yang nyaman dan mudah dibangunkan dengan rangsang verbal. Hal inilah yang membuat dexmedetomidine sering digunakan pada tindakan awake craniotomy. Namun efek samping yang umum terjadi adalah hipotensi dan bradikardia.6-10 Pasien yang menjalani kraniotomi sering mengalami mual dan muntah, hal ini terjadi karena adanya rangsangan pada saat manipulasi duramater, lobus temporal dan pembuluh meningeal. Suatu penelitian melaporkan insiden terjadinya mual muntah pascabedah setelah awake craniotomy selama operasi tumor kurang terjadi dibandingkan dengan tindakan anestesi umum, mereka mengatakan juga bahwa penggunaan propofol juga efektif untuk digunakan sebagai antiemetik, selain itu hindari dosis tinggi penggunaan opioid. Pada kasus ini, pasien telah dilakukan awake craniotomy dengan pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan hanya untuk menentukan jenis tumor atau sebagai prosedur diagnostik dengan durasi operasi 2–4 jam. Selama operasi, pasien cukup tenang dan kooperatif. Evaluasi jalan nafas menjadi perhatian utama karena lokasi yang akan sulit untuk dijangkau. Dengan manipulasi alat dan sarana diupayakan agar muka dan jalan nafas pasien tetap lapang dan secara visual tidak ada halangan. Suasana kamar operasi yang dingin juga menjadi perhatian sehingga dilakukan pemberian selimut dan meningkatkan suhu kamar operasi. Pemberian midazolam sebelum pemasangan frame dimaksudkan sebagai ansilolitik atau penenang dan pasien masih tetap sadar serta lebih kooperatif, dosis yang diberikan merupakan dosis premedikasi untuk ansiolitik sehingga tidak menyebabkan hipoventilasi yang dapat mengakibatkan terjadinya hiperkapnia. Dexmedetomidin digunakan pada tindakan ini karena beberapa alasan seperti dijelaskan sebelumnya, dan pada kasus ini dexmedetomidine dipakai sebagai obat utama dengan fentanyl sebagai rescue analgesia, ternyata cukup memberikan hasil yang baik. Respon bradikardi tampak beberapa kali terjadi pada pasien ini, tetapi pasien masih tetap bernafas spontan, tekanan darah relatif stabil, saturasi oksigen baik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dosis dexmedetomidine sampai tercapai denyut jantung yang diharapkan.9,10 Pemakaian analgetik opioid tidak dilakukan secara kontinyu untuk mengurangi efek mual-muntah yang mungkin terjadi. Pemakaian anestesi lokal pehacaine saat sebelum pemasangan pin, berguna untuk mengurangi nyeri dan kandungan epinefrin bertujuan untuk vasokonstriksi lokal sebagai hemostasis lokal. Pemakaian bupivacaine 0,25% untuk insisi kulit kepala untuk membantu penanganan nyeri dengan durasi kurang lebih 4 jam dan ditambahkan lagi sesaat akan menutup kulit untuk penanganan nyeri pascabedah. Pada saat prosedur berlangsung, propofol beberapa kali digunakan seperti saat tindakan berlangsung, seperti saat dilakukan bor dan penusukan dura dengan trochart. Pemberian propofol bertujuan untuk menambah kedalam sedasi, namun pemberian propofol ini harus dilakukan perlahan atau titrasi sampai tercapai Ramsay 2, tujuan pemberian titrasi ini adalah mencegah jangan sampai pasien apnoe. Pascabedah pasien diobservasi di ruangan pemulihan dan selama di ruang pemulihan pasien tetap sadar baik, orientasi baik, nyeri minimal dengan nilai Visual Analog Scale/ VAS 2 dan tidak ada mual dan muntah. IV. Simpulan Awake craniotomy merupakan salah satu prosedur anestesi yang telah berkembang pesat sejak awal diperkenalkan seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, keterampilan dokter bedah saraf dan dokter spesialis anestesi. Prosedur ini memerlukan kerjasama dari pasien, karena dilakukan suatu test selama pembedahaan Awake Craniotomy pada Biopsi Steriotaktik Tumor Supratentorial di daerah Thalamus Dextra et causa Suspect Thalamic Glioma berlangsung. Awake craniotomy menjamin masa pemulihan yang cepat dengan evaluasi secara dini fungsi neurologis pasien. Dengan masa pemulihan yang cepat, rawat inap di rumah sakit juga singkat sehingga dapat mengurangi beban biaya maupun mengurangi risiko infeksi yang didapat di rumah sakit. Pemakaian kombinasi dexmedetomidine, fentanyl, propofol dan anestesi lokal memberikan hasil yang cukup baik dengan sedikit komplikasi. Daftar Pustaka 1. Koenig HM. Anesthesia for awake intracranial procedures. Dalam: Lake CL, Johnson JO, McLoughin TM, editor. Advances in Anesthesia. Philadelphia: Mosby Elsevier, Inc; 2006, 127–48 2. Schubert A, Lotto M. Awake craniotomy, epilepsy, minimal invasive, and robotic surgery. Dalam: Cottrell JE, Young WL, editor. Neuroanesthesia, 5th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, Inc; 2010, 296–302. 3. Bisri T, Wargahadibrata AH, Surahman E. Neuroanestesi. Bandung; Bagian Anestesiologi dan Reanimasi FK UNPAD/ RS Hasan Sadikin: 1997. 4. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Anesthesia for neurosurgery. Dalam: Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, editor. Clinical 179 Anesthesiology, 4th ed. New York: A Lange Medical Books; 2006, 631–40. 5. Sarang A, Dinsmore J. Anaesthesia for awake craniotomy-evolution of technique that facilitates awake neurological testing. Br J. Anaesth 2003; 90(2): 161–65. 6. Ard JL, Bekker AY, Doyle WK. Dexmedetomidine in awake craniotomy: a technical note. Surgical Neurology 2003; 63: 114–17. 7. Skucas AP, Artru AA. Anesthetic complications of awake craniotomies for epilepsy surgery. Anesth Analg 2006; 102: 882–7. 8. Blanshard HJ. Awake craniotomy for removal of intracranial tumor: considerations for early discharge. Anesth Analg 2001;92: 89 –94. 9. Bhana N, Goa KL, Mc Clellan KJ. Dexmedetomidine. Drugs. Adis International 2000;59(2): 263–68. 10. Villela NR, Nascimento P. Dexmedetomidin in anesthesiology. Rev Bras Anestesiol 2003;53(1): 97–113. Pemantauan Neurofisiologis Intraoperatif selama Anestesia untuk Operasi Meningioma Foramen Magnum Riyadh Firdaus*), Bambang Suryono**), Siti Chasnak Saleh***) *)Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, **)Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta, ***)Departemen Anestesiologi dan Reanimasi – Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Abstrak Pemantauan neurofisiologis intraoperatif (Intraoperative neurophysiological monitoring/IONM) pada operasi yang rentan mencederai saraf sangat penting untuk menunjang proses keputusan medis intraoperatif dan pada akhirnya mengurangi angka morbiditas. Operasi meningioma foramen magnum sangat berisiko cedera saraf dan morbiditas sehingga menjadi kandidat yang cocok untuk penggunaan IONM. Cakupan manajemen anesthesia pada operasi yang menggunakan IONM adalah pertimbangan tentang pilihan dan dosis obat anestesia yang digunakan serta perhatian terhadap kestabilan homeostasis pasien. Pemahaman yang baik oleh dokter bedah, anestesi dan neurologi akan membuat tindakan operasi berjalan dengan lancar dan mencegah terjadinya komplikasi intra dan pascaoperasi. Seorang wanita umur 39 tahun dengan keluhan utama nyeri kepala belakang sejak 2 bulan yang lalu. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang pasien di diagnosis tumor meningioma pada regio foramen magnum. Pasien dilakukan operasi kraniotomi removal tumor dengan panduan IONM dalam posisi park bench. Lama operasi kurang lebih 14 jam. Pascaoperasi pasien tidak dilakukan ekstubasi dan dirawat di ICU sehari. Kata kunci: anatomi foramen magnum, IONM, posisi park bench, bispectral index JNI 2014;3 (3): 180‒88 Intraoperative Neurophysiological Monitoring (IONM) during Anesthesia for Meningioma Foramen Magnum Surgery Abstract Intraoperative neurophysiological monitoring (IONM) in a surgery that is prone to neuronal injury is very useful to guide intraoperative decision makings and to reduce morbidity. Foramen magnum tumor surgerycarries a very high risk for neuronal injury, and thereforeapplication of IONM would be advantageous. The termsof anesthetic management in IONM-guided-surgery are the selection of anesthetic agents with limitation of the dosageswhileremain focusingon stability of patient’s homeostasis. A thorough understanding and communication among surgeon, neurologist and anesthesiologist are important to createan uneventful procedure and to reduce intra and postoperative complications.A 39 years old female with severe headache for 2 months was diagnosed with meningioma at foramen magnum based on history, physical examination, and advanced examination procedures. The patient was underwent tumor removal guided by IONM on park bench position. The duration of surgery was 14 hours. The patient was not extubatedpostoperatively and admitted to ICU for a day. Key words: foramen Magnum, IONM, park bench position, bispectral index JNI 2014;3 (3): 180‒88 180 Pemantauan Neurofisiologis Intraoperatif selama Anestesia untuk Operasi Meningioma Foramen Magnum I. Pendahuluan Monitoring neurofisiologis intraoperatif (intraoperative neurophysiological monitoring/ IONM) merupakan metode yang digunakan untuk memonitor integritas fungsional dari sebuah struktur neural tertentu (saraf, spinal cord dan bagian dari otak) selama pembedahan.1 Manfaat monitoring ini sangat penting untuk menunjang proses keputusan medis intraoperatif dan pada akhirnya mengurangi angka morbiditas.2 Tumor foramen magnum merupakan tumor yang sangat unik dan membutuhkan manajemen serta tatalaksana yang khusus.3 Hal tersebut disebabkan oleh letak foramen magnum yang secara anatomis berada dekat dengan medula oblongata, persarafan kranial bawah dan arteri vertebralis. Sesuai dengan keunikan tersebut, maka tatalaksana tumor foramen magnum memerlukan perhatian khusus antara lain dengan penggunaan monitoring neurofisiologis intraoperatif.4 Meningioma merupakan tumor ekstra-aksial dari sistem saraf pusat yang berasal dari sel arakhnoid duramater. Jumlah insiden per tahun tumor ini adalah 6 per 100.000 orang, sebagian besar terjadi pada populasi berusia 50 hingga 60 tahun dan sangat jarang terjadi pada anak-anak.5 Sebagian besar meningioma bersifat jinak, memiliki kecepatan pertumbuhan yang lambat, sering terjadi pada wanita dan keturunan Afrika. Perbandingan penderita tumor ini antara pria dan wanita sebanding dengan peningkatan insiden meningioma pada wanita postmenopause yang mendapatkan terapi sulih hormon. Meningioma merupakan salah satu keganasan yang cukup sering terjadi dan memiliki prevalensi 14,3%– 19% dari semua tumor intrakranial. Dari sebagian besar meningioma, hanya 1,8% hingga 3,2% yang merupakan tumor foramen magnum. Meningioma merupakan tumor yang paling sering diobservasi yang merupakan 70% dari semua tumor jinak.Hampir sepanjang waktu meningioma hanya melibatkan bagian intradural. Sebanyak 10% tumor ini dapat mencapai ekstradural, sedangkan sebagian besar adalah tumor intra dan ekstradural dan hanya sebagian kecil yang meliputi keseluruhan ekstradural.6 Lesi 181 pada meningioma ini sering ditemukan dengan ukuran yang besar, kecepatan pertumbuhan yang sangat lambat, tingkat kesulitan diagnosis mengakibatkan jangka waktu yang cukup panjang antara diagnosis dan gejala awal yang timbul pada pasien. Metode diagnosis yang sering digunakan untuk meningioma adalah dengan menggunakan contrast–enhanced computerized tomography (CT-scan) dan magnetic resonance imaging (MRI). Imaging dengan menggunakan MRI lebih diunggulkan dibandingkan dengan CT-scan karena resolusi yang lebih tajam, tidak adanya artefak tulang dan penguatan kontras yang intens pada tumor.3,6 Berdasarkan letak tumor, risiko pada pasien dengan meningioma serta gejala neurologis yang timbul, reseksi dengan pembedahan tumor pada sebagian besar kasus merupakan tindakan kuratif. Pada kasus yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pembedahan sehingga reseksi yang dilakukan tidak lengkap, maka angka kekambuhan dan agresivitas tumor menjadi lebih tinggi, selain itu juga diperlukan radioterapi sebagai bagian dari manajemen.4-6 Tindakan anestesi pada operasi tumor foramen magnum memiliki hal yang khusus. Beberapa tindakan tersebut adalah pengaturan posisi pasien, pemasangan alatalat (central venous catheter, arterial line, dan pressure monitoring kit), penggunaan bispectral index (BIS) untuk monitoring kedalaman anestesia dan tidak digunakannya relaksan kontinyu seperti pembedahan bedah saraf pada umumnya dikarenakan penggunaan alat IONM untuk mencegah terjadinya cidera saraf kranial. II. Kasus Ny S, perempuan, 39 tahun dengan keluhan utama nyeri pada kepala sejak kurang lebih 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. Nyeri terutama dibagian belakang kepala, dirasakan berdenyut dan hilang timbul. Keluhan tersebut diatas tidak berkurang walaupun penderita telah minum obat penghilang rasa sakit. Mual muntah tidak ada, kejang tidak ada dan gangguan menelan tidak ada. Riwayat operasi sebelumnya tidak ada. Riwayat alergi obat ada yaitu griseofulvin, membuat gatal dan merah-merah seluruh badan. Riwayat 182 Jurnal Neuroanestesi Indonesia sakit asma, diabetes mellitus tidak ada, riwayat hipertensi ada sejak 2 tahun yang lalu, tekanan darah tertinggi 160/90 mmHg, saat ini sekitar 140/90 mmHg terkontrol dengan obat amlodipin 1 x 5mg per oral. Riwayat penyakit jantung, paru, kuning, kejang, dan pingsan tidak ada. Riwayat nyeri dada dan sesak nafas tidak ada, New York Functional Class I. Saat ini demam, batuk, dan pilek tidak ada. Gigi goyang dan palsu tidak ada. Pemeriksaaan Fisik Pada pemeriksaan fisik tampak kesadaran komposmentis, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 95 x/mnt, laju napas 18kali/mnt, suhu 36,8 o C, berat badan 75 kg, tinggi badan 147 cm, BMI 34,7 kg/m2. Periksaan mata didapatkan pupil isokor 4 mm: 4 mm, reflek cahaya +/+, lain-lain dalam batas normal. Disimpulkan pasien dengan status fisik ASA II dengan peningkatan tekanan intrakranial kronis, hipertensi terkontrol TD/140/90 mmHg, Terapi Amlodipin 1x 5mg P, dan obesitas BMI 34,7 kg/ m2. Rencana anestesia dengan anestesia umum inhalasi dengan kombinasi anestesia intravena. Pemeriksaan Laboratorium Pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil pemeriksaan darah seperti dibawah ini. WBC HGB HCT PLT Albumin : : : : : 8740K/µL 12,4gr% 37,3% 503K/µL 4,5gr/dL Pengelolaan Anestesi Persiapan di kamar operasi dilakukan dengan memposisikan pasien tidur telentang diatas meja operasi, kemudian dilakukan pemasangan elektrode EKG dan manset tekanan darah serta pulse oksimeter. Tekanan darah praoperasi 150/90 mmHg, nadi 95 x/menit. Premedikasi midazolam 2 mg dan fentany l200µg intravena. Anestesia dimulai pukul 06:00 WIB dengan induksi anestesia dengan propofol 100mg secara intravena, pelumpuh otot untuk intubasi dengan atrakurium 50 mg intravena. Laringoskopi intubasi dengan pipa endotrakea tipe non kinking ukuran ID7, 5, cuff (+) dan pemasangan selang nasogastrik. Pemeliharaan anestesia dengan isoflurane 0,8 vol%, dengan O2 dan udara FiO2 40%, drip propofol 2,5 mg/kg/jam, dan fentanyl 5 mcg/kg/jam. Arterial line dan CVC dipasang, diikuti dengan pemasangan IONM oleh dokter neurologi. Pengaturan posisi park bench dilakukan bersama-sama antara dokter anestesiologi, operator dan neurologi. BIS dipasang setelah posisi stabil dan nilai BIS dipertahankan antara 50–60 untuk memfasilitasi kualitas IONM yang diharapkan tanpa mengganggu jalannya anestesia dan operasi. Operasi mulai pukul 09.27 sampai pukul 20:30 WIB. Durante operasi tekanan darah berkisar antara 90–120 mmHg sistolik dan 85–50 mmHg diastolik, nadi antara 80–60x/menit. BT : ’30” Ureum CT : 9’00” Creat PT/APPT : 1/1,1x SGOT SGPT : : : : 24mg/dL 1,1mg/dL 19 IU/L 6 IU/L Na+ : 145mmol/L K+ : 4,23 mmol/L Cl: 103,4 mmol/L Rontgen thorak : cor dan pulmo dalam batas normal MRI kepala dengan kontras: massa ekstraaksial hipervaskular di region foramen magnum– medulla oblongata ukuran 2,5x1,93x1,72 cm. Pemantauan Neurofisiologis Intraoperatif selama Anestesia untuk Operasi Meningioma Foramen Magnum 183 Pada pukul 10:45 WIB manitol diberikan 75 gram drip IV sebelum duramater dibuka. Pada pukul 13:30WIB, tekanan darah turun 90/50 mmHg, dilakukan pemasangan dopamin 5µg/kg/menit dan pemberian darah PRC satu kantong (216 ml). Dopamine distop setelah satu jam pemberian, tekanan darah saat itu 120/80 mmHg. Pada pukul 16:15 WIB relaksan atrakurium diberikan 10 mg setelah IONM tidak dibutuhkan lagi. Total perdarahan adalah ±1000 ml. Total produksi urin adalah ±2500 ml. Total cairan: koloid 1000ml, kristaloid 2500ml, transfusi PRC 2 kantong (419 ml). Operasi selesai pukul 20:30 WIB dan pasien ditransport ke ICU tanpa dilakukan ekstubasi. Pasien diesktubasi keesokan harinya dan pindah ke ruangan setelah hari perawatan ICU kedua. Pasien dirawat di ruangan selama seminggu untuk pemulihan luka dan rehabilitas medik. Setelah beristirahat selama sebulan di rumah pasien kembali bekerja seperti biasa. III. Pembahasan Penatalaksanaan pada tumor foramen magnum merupakan tindakan yang sangat menantang baik dari segi pembedahan maupun pengelolaan anestesinya. Foramen magnum yang merupakan suatu ruang yang menghubungkan medula oblongata dan medula spinalis mempunyai struktur yang vital bagi otak yaitu beberapa saraf kranialis dan arteri vertebralis. Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman mengenai anatomi foramen magnum, peralatan monitoring yang digunakan, serta manajemen anestesia pada tumor foramen magnum. Anatomi Batasan Foramen Magnum Meningioma foramen magnum didefinisikan sebagai meningioma yang tumbuh berasal dari duramater. Sehingga tidak termasuk tumor yang berasal dari luar duramater yang meluas menuju duramater.7 Batasan anatomis foramen magnum adalah sebagai berikut dari sisi anterior, batasannya yaitu sepertiga clivus dan batas atas C2, dari bagian lateral batasannya adalah tuberkel jugular dan batas atas lamina C2, dari arah posterior Gambar 1. Foramen Magnum batasannya merupakan bagian tepi anterior dari tulang occipital squamosal dan prosesus spinalis. Lower Cranial Nerves Empat saraf kranial/cranial nerves (CN) bagian bawah yang melintasi foramen magnum merupakan persarafan yang harus dilindungi dan dipertahankan tetap utuh selama pembedahan sehingga morbiditas neurologis akibat pembedahan dapat dihindari.6,7 Empat saraf tersebut adalah saraf glossofaringeal (CN IX), vagus (CN X), aksesorius (CNXI) yang berasal dari akar dari sulkus postolivari dan akan bergabung dengan foramen jugular, melewati bagian ventral ke plexus choroidales dan keluar dari foramen Luschka dan bagian dorsal menuju ke arteri vertebralis. Saraf hipoglosus (CN XII) yang berasal dari akar dari sulkus preolivari. Saraf tersebut akan berjalan secara anterolateral pada ruang subarakhnoid dan melewati bagian belakang arteri vertebralis hingga mencapai kanal hipoglosus. Sangat jarang terjadi, arteri vertebralis akan memisahkan akar dari CN XII. Persarafan saraf aksesorius terdiri dari akar yang berasal dari medula dan spinal cord. Akar persarafan medula bagian atas akan berjalan secara langsung menuju ke foramen jugular. Bagian utama dibentuk dari akar tulang belakang yang akan bergabung ke atas melalui foramen magnum berjalan di belakang ligament dentata dan bersatu dengan akar dari medulla bagian 184 Jurnal Neuroanestesi Indonesia atas. Anastomosis dengan akar dorsal dari saraf servikal bagian atas sering terjadi yang dengan C1 akan menjadi akar saraf yang terbesar. Segmen Arteri Vertebra (VA), V3 dan V4 Pembedahan pada kasus meningioma di daerah foramen magnum tidak terpisahkan dengan pembedahan arteri vertebralis. Bahkan pendekatan pembedahan sangat terkait dengan arteri vertebra, segmen V3 dan reseksi dari lesi itu sendiri berhubungan dengan arteri vertebra dan segmen V4.6,7 Segmen VA V3 juga dikenal dengan segmen suboksipital yang berasal dari prosesus transversus C2 menuju duramater foramen magnum dimana kemudian akan berubah menjadi segmen V4 ketika melewatinya. Pendarahan Duramater Foramen Magnum Terdapat empat pembuluh darah meningeal yang memperdarahi duramater foramen magnum, bagian anterior dan posterior dari arteri meningeal VA dan cabang meningeal dari arteri faringeal ascending dan oksipital. Jarang sekali, percabangan meningeal berasal dari posterior inferior cerebellar artery (PICA), arteri spinal posterior dan segmen VA V4. Percabangan meningeal anterior yang merupakan cabang paling utama, berasal dari VA pada level C2–C3. Arteri meningeal posterior berasal dari aspek posterosuperior VA ketika berputar mengelilingi masa lateral dari atlas, diatas arkus posterior atlas, tepat sebelum melakukan penetrasi ke dura, atau tepat pada permulaan segmen V4.6,7 Arteri faringeal asending merupakan cabang dari arteri karotis eksternal, yang mengakibatkan cabang meningeal melakukan penetrasi ke kanal hipoglosus dan foramen jugular. Percabangan meningeal dari arteri oksipital inkonsisten dan melewati foramen emissary mastoid.6,7 Teknik pembedahan Pada dasarnya terdapat tiga pendekatan pembedahan yang umumnya digunakan dalam melakukan reseksi meningioma foramen magnum. Pendekatan tersebut antara lain dengan pendekatan midline posterior, pendekatan posterolateral dan pendekatan anterolateral.6,8 Seperti yang dijelaskan oleh Rhoton, pendekatan postero-lateral atau far lateral approach merupakan pendekatan subocipital lateral yang ditujukan di belakang otot sternokleidomastoideus dan VA serta medial terhadap occipital dan kondilus Atlanta serta sendi atlanto-ocipital.9 Pendekatan anterolateral atau pendekatan ekstrim lateral merupakan pendekatan lateral ke dalam bagian anterior otot sternokleidomastoideus dan di belakang vena jugularis interna sepanjang bagian depan dari VA. Pada kenyataannya, kedua pendekatan memungkinkan pengeboran kondilus occipital namun menyediakan tampilan yang berbeda karena terdapat perbedaan arah pendekatan. Gambar 2. Sistem Klasifikasi Meningioma Foramen Magnum Pemantauan Neurofisiologis Intraoperatif selama Anestesia untuk Operasi Meningioma Foramen Magnum Gambar 3. Posisi Park Bench Posisi Pembedahan (Park Bench Position ) Posisi dalam pembedahan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur reseksi meningioma foramen magnum.10 Pada pembedahan reseksi meningioma foramen magnum terdapat dua posisi pembedahan yang sering digunakan yaitu posisi duduk dan Park Bench. Pada posisi duduk, segmen sefalik dari meja operasi ditinggikan. Kepala pasien dalam posisi fleksi dan diputar kearah sisi lesi agar memungkinkan visualisasi langsung dan akses terhadap lesi. Aliran balik vena dijaga dengan cara kaki dibalut dengan elastic bandage, panggul dan lutut dalam keadaan fleksi dengan meja ditempatkan pada posisi trendelenburg. Posisi pasien dan mikroskop harus diuji terlebih dahulu sebelum dilakukan draping sehingga ahli bedah lebih nyaman dalam melakukan operasi. Sedangkan pada posisi Park Bench, pasien diposisikan secara lateral dengan sebuah roll dibawah axilla. Kepala sedikit fleksi dan diputar menuju kearah lantai. Bahu dijaga agar tetap berada diluar lapangan operasi dengan strapping. Meja operasi dapat diputar sedikit bila diperlukan untuk menjaga kesejajaran dengan tumor. Intraoperative Neurophysiological Monitoring (IONM) Tujuan dari IONM adalah mengurangi risiko pasien untuk terkena kerusakan iatrogenik pada sistem saraf pusat serta menyediakan acuan fungsional kepada ahli bedah pada saat pembedahan.1,2 185 Gambar 4. Intraoperative Neurophysiological Monitoring (IONM) Neuromonitoring meliputi berbagai modalitas elektrofisiologis seperti extracellular single unit dan local field recordings, somatosensory evoked potentials (SSEP), transcranial electrical motor evoked potentials (TCeMEP), electro encephalography (EEG), electro miography (EMG) dan Auditory brainstem response (ABR).1,11 Teknik IONM ini secara signifikan mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas tanpa meningkatkan risiko, sehingga secara keseluruhan dapat mengurangi pembiayaan kesehatan.1 Seorang neurofisiologis akan menghubungkan sistem komputer dengan pasien dengan menggunakan stimulasi dan elektroda perekam. Program komputer interaktif akan bekerja dalam sistem yang melakukan dua tugas yaitu mengaktifkan elektroda stimulasi dengan waktu yang tepat dan memproses dan menampilkan sinyal elektrofisiologis pada saat bersamaan dengan sinyal tersebut diterima oleh elektrode perekam. Operator sistem ini dapat mengawasi dan merekam sinyal elektrofisiologis secara realtime pada area operasi selama pembedahan. Sinyal elektrofisiologis ini akan berubah atau dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain zat anestesia, suhu jaringan, tahapan pembedahan dan stres pada jaringan. Beberapa contoh alat IONM adalah EEG dan EMG. Pengukuran EEG dilakukan selama dilakukan anestesia akibat adanya perubahan pola pada EEG seiring dengan bertambah dalamnya anestesia.11 Perubahan 186 Jurnal Neuroanestesi Indonesia ini tampak pada pola gelombang dengan perlambatan frekuensi yang diikuti dengan peningkatan amplitude sehingga akan mencapai puncaknya saat pasien kehilangan kesadaran. Saat kedalaman anestesia bertambah, EEG akan menunjukkan gelombang ritmik yang terputus, amplitude yang tinggi, amplitude isoelektrik yang rendah atau aktivitas flat line. Berbagai pendekatan analisis sinyal telah dilakukan untuk menerjemahkan perubahan pola gelombang sehingga dapat menunjukkan hilangnya loss of recall, loss of consciousness dan kedalaman anestesia.12 Monitor telah dikembangkan dengan berbagai algoritma untuk analisis sinyal, namun hingga saat ini belum ada yang terbukti akurat. EMG digunakan untuk monitoring persarafan kranial pada dasar otak dan monitoring pada akar persarafan serta untuk pembedahan di daerah spinal. Bispectral Index (BIS) Monitor bispectral index menunjukkan penilaian secara real time pada electroencephalography (EEG), yang dihasilkan dari gelombang frontotemporal. Monitor akan mengeluarkan angka dengan skala kontinu dari 0–100, dengan 100 menunjukkan aktivitas elektrik kortikal yang normal dan 0 mengindikasikan ketiadaan aktivitas listrik kortikal.13 Pengaruh adanya neuropatologi sebelumnya pada nilai BIS hingga kini masih belum diketahui. Sedangkan Gambar 5. Bispectral Index (BIS) dengan adanya sinyal EEG, dapat mengganggu penilaian dan mempengaruhi nilai BIS. Mengingat tidak terdapat baku emas yang dapat dibandingkan dengan BIS maka berbagai studi yang dilakukan terhadap nilai BIS memiliki variasi intepretasi yang sangat beragam. Studi yang telah dilakukan menghasilkan panduan yang menyatakan nilai BIS pada pasien yang dilakukan anestesia umum berkisar 45–60. Nilai BIS <60 intraoperasi menunjukkan kemungkinan recall post operasi sangat rendah.13 Fase hubungan antara komponen gelombang dari berbagai frekuensi yang berbeda yang merupakan komponen dari EEG tidak turut diperhitungkan dengan penghitungan analisis power spektral tradisional. Analisis Bispectral menggabungkan antara analisis daya secara tradisional dengan pemeriksaan dari fase hubungan ini. Sejumlah subparameter EEG lain untuk menghasilkan kombinasi pelengkap yang diturunkan dari EEG yang tidak terkoordinasi. BIS dikembangkan dengan merekam data EEG dari manusia dewasa yang sehat yang mengalami transisi berulang antara kesadaran dan ketidaksadaran, menggunakan beberapa regimen anestesia yang berbeda. Data mentah EEG ditandai berdasarkan berbagai nilai akhir yang bervariasi.13 Manajemen Anestesia Anestesia pada tumor foramen magnum mempunyai beberapa hal khusus yang harus diperhatikan. Beberapa hal tersebut berkaitan dengan posisi operasi, obat-obat yang digunakan, pemantauan intraoperasi, serta komplikasi yang dapat terjadi. Pembedahan pada tumor foramen magnum memerlukan posisi pasien yang tidak umum dilakukan. Pada laporan kasus diatas, operasi dilakukan dengan posisi park bench. Posisi lain yang dapat digunakan adalah posisi duduk, namun posisi duduk mempunyai komplikasi yang sering terjadi yaitu emboli udara vena. Penggunaan obat anestesia pada tumor foramen magnum untuk premedikasi dan induksi anestesia memiliki kesamaan pada operasi bedah saraf pada umumnya. Namun penggunaan obat anestesia pada pemeliharaan intraoperasi memiliki hal yang khusus. Obat pelumpuh otot hanya digunakan untuk fasilitasi intubasi dan selama pemeliharaan obat pelumpuh otot tidak digunakan. Hal ini Pemantauan Neurofisiologis Intraoperatif selama Anestesia untuk Operasi Meningioma Foramen Magnum berkaitan dengan digunakannya alat intraoperatif neurofisiologi monitoring (IONM) oleh dokter neurologi agar mencegah cidera saraf kranialis yang berada disekitar foramen magnum. Obat yang digunakan untuk menjaga kedalaman anestesia adalah dengan menggunakan kombinasi gas sevofluran dan propofol intravena serta penggunaan fentanyl drip. Pemantauan intraoperasi untuk memantau kedalaman anestesia dengan menggunakan bispectral index (BIS). BIS dipertahankan nilainya sekitar 50– 60 membuat kedalaman anestesia yang cukup namun tidak mengganggu pemantauan IONM selama intraoperasi. Komplikasi yang dapat timbul dari operasi foramen magnum antara lain cidera saraf kranialis, trauma medula oblongata dan spinalis serta perdarahan arteri vertebralis. Disfungsi saraf kranialis umumnya karena pembengkakan dan retraksi selama operasi. Kerusakan nervus IX dan X dapat dilihat dari kehilangan kemampuan menelan dan batuk yang efektif selama pascabedah. Post operasi untuk menentukan pasien dilakukan ekstubasi atau tidak bukan perkara yang mudah. Pada umumnya, jika pasien komposmentis pada periode prabedah dan intraoperasinya tidak banyak traksi pada batang otak, maka pasien diperkirakan bisa untuk dilakukan ekstubasi. Akan tetapi jika intraoperasi banyak traksi pada batang otak akan membuat terjadinya apneu dan penurunan sensorium dengan penurunan reflek jalan nafas, sehingga pasien tersebut harus diintubasi sampai bahaya tersebut dilewati. Pada pasien ini tidak dilakukan ekstubasi untuk memastikan benar-benar kondisi pasien aman untuk dilakukan ekstubasi. Pada pasien didapatkan oedem pada tangan kanan, wajah dan mata dikarenakan posisi operasi yang ekstrim (park bench). Postoperasi pasien dirawat di ICU dan diberikan sedasi dengan propofol intravena 100mg/jam sampai dipastikan aman untuk dilakukan ekstubasi. Hasil lab post operasi DPL:13,4/39/19550/442000, SGOT/SGPT: 41/29, Ur/Cr: 22/0, 5, Pt/Aptt: 1/1, 1x, Na/K/Cl: 142/3,8/101, GDS: 250. Pasien diberikan terapi clear fluid 30 cc/jam sampai makan cair 70cc/jam, ringerfundin 20 cc/jam, propofol 100mg/jam, cefazolin 2x2 gram (P1), OMZ 2x40mg, deksametason 4x5 mg, tramadol 187 3x100mg, ondansetron 2x8 mg, ketorolak 3x30 mg. Keesokan harinya pasien dilakukan ekstubasi dengan sebelumnya dilakukan leak test untuk memastikan tidak terjadinya sumbatan jalan nafas akibat oedem pada laring. IV. Simpulan Monitoring neurofisiologis intraoperatif sangat berguna untuk meningkatkan presisi pembedahan dan menghindari kerusakan saraf kranial serta medula spinalis pada operasi meningioma foramen magnum. Teknis anestesia yang memperhatikan efek obat-obat anestesia dan perubahan homeostasis pasien terhadap monitoring neurofisiologis turut menyertai faktor-faktor lain yang terkait dengan kekhususan operasi ini. Beberapa faktor tersebut adalah posisi operasi, obat-obat yang digunakan, pemantauan intraoperasi (selain IONM), serta komplikasi yang dapat terjadi. Posisi operasi yang bisa digunakan dalam operasi tumor foramen magnum adalah posisi duduk dan posisi park bench. Posisi park bench lebih sering digunakan operator dibandingkan posisi duduk karena posisi duduk memiliki komplikasi yang sering terjadi yaitu emboli udara vena. Alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman anestesia selama operasi berlangsung ialah dengan menggunakan Bispectral Index (BIS). Dibutuhkan kerjasama dokter bedah saraf, neurologi dan anestesia agar operasi berjalan lancar serta mengurangi morbiditas dan mortalitas terhadap pasien yang memiliki tumor foramen magnum. Daftar Pustaka 1. Sabbagh AJ, Al Yamany M, Bunyan RF, Takrouri MSM, Radwan SM. Neuroanesthesia management of neurosurgery of brain stem tumor requiring neurophysiology monitoring in an IMRI OT setting. Saudi Journal of Anaesthesia 2009; 3:91–3. 2. Sloan TB, Jameson L, Janik D. Evoked potentials. Dalam: Cottrell and Young’s Neuroanesthesia. 5th ed. Philadelphia. 2010; 7: 115–130. 188 Jurnal Neuroanestesi Indonesia 3. Boulton MF, Cusimano MD. Foramen magnum meningioma: concepts, classifications and nuances. Neurosurg Focus. 2004;14;1–8. 4. Tsao GJ, Tsang MW, Mobley CB, Cheng WW. Foramen magnum meningioma: dysphagia of atypical etiology. JGIM. 2007; 206–9. 5. Geetha L, Radhakrishan M, Raghavendra BS, Rao U, Devi BI. Anesthetic management for foramen magnum decompression in a patient with morquio syndrome: a case report. J Anesth. 2010;24; 594–7. 6. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, Burger PC, Jouvet A, Scheithauer BW, et al The 2007 WHO classification of tumours of central nervous system. Acta Neurophatol. 2007;114; 97–109. 7. Bruneau M, George B. Foramen Magnum Menangiomas: detailed surgical approaches and technical aspects at Lariboisiere Hospital and review of the literature. Neurosurg. 2008;31;19–33. 8. Bruneau M, George B. Classification system of foramen magnum meningiomas. Journal of Craniovertebral Junction and Spine. 2010; 1; 10–17. 9. Koizumi H, Utsuki S, Inukai M, Oka H. Osawa S, Fujii K. An Operation in the park bench position complicated by massive tongue swelling: case report. Neurological Medicine Journal. 2012; 1–4. 10. Chan Y, Data NN, Chan KY, Chan K, Ur Rehman S, Poon CY, et al. Outcome analysis of 40 cases of vestibular schwanoma: A comparison of sitting and park bench surgical position. Ann CollSurg HK. 2003;7; 83–7. 11. Kauff DW, Koch KP, Somerlit KH, Heimann A, Hoffmann KP, Lang H, et al. Online signal processing of internal anal sphincter activity during pelvic autonomic nerve stimulation: a new method to improve the reliability of intra-operative neuromonitoring Signals. The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland Journal. 2011;13; 1422-7. 12. Nazzi V, Cordella R, Messina G, Dones I, Franzini A. Role of inta-operative neurophysiologic monitoring during decompression and neurolysis after peripheral nerve injury: case report. Somatosensory and Motor Research. 2012; 29(4): 117–121. 13. Russel IF. The ability of bispectral index to detect intra-operative wakefulness during total intravenous anaesthesia compared with the isolated forearm technique. Anaesthesia Journal. 2013; 68; 502–11. Terapi Hipotermi setelah Cedera Otak Traumatik Dewi Yulianti Bisri, Tatang Bisri Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin – Bandung Abstrak Mekanisme proteksi otak hipotermi adalah mengurangi kebutuhan metabolik, cerebral metabolic rate for oxygen (CMRO2), eksitotoksisitas, menurunkan pelepasan glutamat, menurunkan pembentukan radikal bebas, mengurangi pembentukan edema, stabilisasi membran, memelihara adenosine triphosphate (ATP), menurunkan influx Ca, dan tekanan intrakranial. Sedangkan komplikasi hipotermi berat adalah pneumonia, sepsis, disritmia jantung, hipotensi, masalah perdarahan dan menggigil. Temperatur ideal untuk hipotermia terapeutik adalah 35 0 C. Pertanyaan untuk terapi hipotermik (HT) adalah bagaimana mekanisme terapi hipotermi sebagai protektor otak? Berapa derajat C penurunan suhu tubuhnya? Bagaimana cara melakukan penurunan suhu? Berapa cepat hipotermia harus dicapai? Berapa lama hipotermi dipertahankan? Bagaimana memulihkan ke normotermi (rewarming)? Bagaimana hasilnya? Apakah ada penelitian yang sedang berlangsung? Untuk menggunakan hipotermia sebagai neuroprotektor, diperlukan mencapai keadaan hipotermi secepat mungkin setelah cedera dan pertahankan pada level aman. Metode hipotermi terapeutik adalah pendinginan permukaan tubuh, pendinginan endovaskuler, pendinginan kepala. Selama penghangatan kembali pasien dengan hipertensi intrakranial telah diketahui bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial selama pemanasan yang cepat. Dianjurkan pemanasan lambat lebih dari 12 jam dengan kecepatan 0,1 0C/jam. Sebagai simpulan, hipotermi terapeutik masih kontroversi, tapi dalam situasi klinik pertahankan suhu pasien 35 0C dan harus dihindari temperatur lebih dari 37 0C. Untuk mencapai suhu inti 35 0C dianjurkan digunakan metode pendinginan permukaan tubuh. Kata kunci: cedera otak traumatik, terapi hipotermia, proteksi otak, resusitasi otak JNI 2014;3 (3): 189‒98 Hypothermia Therapy after Traumatic Brain Injury Abstract The mechanism of hypothermia as neuro protector are by reducing metabolic demand of the brain, cerebral metabolic rate of oxygen (CMRO2), excitotoxicity, decrease the glutamate release, reduction of free radical formation, edema formation, membrane stabilization, maintains adenosine triphosphate (ATP), decrease in Ca influx, and intracranial pressure. In the order hand, complication of deep hypothermia are pneumonia, sepsis, cardiac dysrrhythmia, hypotension, bleeding problem and shivering. The ideal temperature for therapeutic hypothermia is 35 0C. Question arised for hypothermic therapy (HT) are what is the therapeutic mechanism of HT as neuroprotective? What is the proper degree for hypothermia? What can we do to induce hypothermia? How soon should we do the HT? How long hypothermia should be maintain? How to restore normothermia (rewarming)? What is the result? Is there any ongoing research?. For the use hypothermia as one of neuroprotective therapy, it is necessary to implement it as soon as possible after the insult and to maintain it at the lowest safe level. Methods of therapeutic hypothermia are surface cooling, endovascular cooling, as well as selective head cooling. During rewarming, patients with intracranial hypertension are known to have reflex that would increase ICP during rapid rewarming. Slow rewarming over a period of 12 hrs at the rate of 0.1 0C/hr is desirable. As conclusion, therapeutic hypothermia still controversial, but in clinical situation keep the patient 35 0C is desirable and temperature more than 37 0C should be avoided. To reach core temperature 35 0C, surface cooling is recommended. Key words: brain protection, brain resuscitation, hypothermia therapy, traumatic brain injury JNI 2014;3 (3): 189‒98 189 190 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Cedera otak traumatik (COT) merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada usia muda. Di Amerika Serikat kejadian COT kira-kira 1,5 juta orang setiap tahunnya dengan 50.000 orang meninggal dan 70 ribu sampai 90 ribu pasien yang selamat dari cedera otak berat akan berkembang kearah terjadinya defisit fungsional serius yang memerlukan pengobatan dan perawatan terus menerus.1 Pengelolaan pasien COT harus komprehensif, dimulai dari tempat kecelakaan, selama transportasi, kamar operasi, dan pengelolaan pascabedah (pengelolaan perioperatif).1 Pasien dengan risiko hipertensi intrakranial, seperti pasien COT, secara nyata dipengaruhi oleh perubahan suhu tubuh karena aliran darah otak (cerebral blood flow/CBF) akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu tubuh. Peningkatan volume darah otak yang dihubungkan dengan kenaikan suhu tubuh akan meningkatkan tekanan intrakranial (intracranial pressure/ICP) dan menyebabkan otak berisiko terkena cedera lain. Karena itu, hipertermia meningkatkan resiko kerusakan sel neuron dan menempatkan pasien beresiko terjadinya cedera otak sekunder melalui adanya peningkatan ICP.1 Hipertermia postiskemik dihubungkan dengan peningkatan ukuran infark dan outcome yang lebih buruk. Walaupun pengendalian yang ketat kearah suhu tubuh yang normal telah dicatat sebagai strategi terapi yang penting pada Guideline for Management Severe Head Injury, akan tetapi, strategi managemen terapi klinis untuk praktisi sering tidak efektif dan mungkin merupakan kontraindikasi pada pasien COT.2 Pengendalian normotermia (pencegahan panas dengan pendinginan intravaskuler) efektif dalam mengurangi panas dan beratnya cedera otak sekunder setelah cedera kepala berat akibat dari penurunan tekanan intrakranial dan panas.3 Telah lama diketahui dari beberapa penelitian eksperimental bahwa hipotermia adalah neuroprotektif setelah iskemia otak. Mekanisme bagaimana hipotermia mempunyai efek proteksi otak, belum jelas. Kemungkinan karena menurunkan metabolisme otak, mencegah apoptosis, mengurangi disfungsi mitokhondria, mengurangi produksi radikal bebas dan juga mengurangi kerusakan oksidatif DNA, menurunkan influks Ca2+, menurunkan pelepasan exitatory amino acids (EAA) glutamat, mencegah peroksidasi lipid, menurunkan pembentukan edema. Pada umumnya diterima efek neuroproteksi hipotermia pada iskemia global dan pada iskemia fokal seperti setelah COT. Hipotermia juga dipercaya dapat digunakan untuk mengendalikan peningkatan ICP dan memotong kaskade biokimia dalam proses terjadinya cedera otak sekunder.4 Ada 4 konsekuensi negatif dari hipotermia pada pasien COT berdasarkan patofisiologi serebral spesifik pasien-pasien ini, yang menerangkan kenapa hipotermia belum menunjukkan efektivitasnya untuk outcome atau memperburuk outcome pada pasien COT yaitu: 1) efek hipotermia memicu stres pada mikrosirkulasi zona penumbra, 2) efek samping dari penggunaan vasokonstriktor disebabkan penurunan tekanan darah setelah cooling, 3) risiko perdarahan karena hipotermi memicu koagulopati, 4) bahaya akibat peningkatan ICP selama rewarming pada pasien dengan peningkatan ICP.4 Satu penelitian meta-analysis RCT mendukung bahwa hipotermia tidak menguntungkan dalam pengelolaan cedera otak traumatika berat, akan tetapi, karena hipotermia terus digunakan untuk terapi cedera otak, maka diperlukan penelitian segera untuk memastikan tentang kegunaan dan kerugian terapi hipotermi pada pengelolaan cedera otak traumatika berat. II. Apakah yang disebut terapi hipotermi? Pendinginan (cooling) setelah cedera otak traumatik pertama kali disampaikan pada tahun 1945. Akhir tahun 50-an dilakukan pendinginan setelah henti jantung dan akhir tahun 1990 ketertarikan akan terapi hipotermi muncul kembali. Terapi hipotermia adalah kondisi dimana suhu tubuh menurun dibawah temperatur tubuh yang normal yang diperlukan untuk berlangsungnya metabolisme yang normal. Dengan demikian, ada 8 pertanyaan untuk terapi hipotermi yaitu5: 1. Bagaimana mekanisme terapi hipotermi sebagai protektor otak? 2. Berapa derajat Celcius penurunan suhu Terapi Hipotermi setelah Cedera Otak Traumatik tubuhnya? Bagaimana cara melakukan penurunan suhu? Berapa cepat hipotermia harus dicapai? Berapa lama hipotermi dipertahankan? Bagaimana memulihkan ke normotermi (rewarming)? 7. Bagaimana hasilnya? 8. Apakah ada penelitian yang sedang berlangsung? 3. 4. 5. 6. Penelitian cedera otak traumatik pada model hewan coba menunjukkan bahwa penggunaan hipotermi dalam (profound hypothermia) memberikan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa hipotermi sedang (moderate hypothermia) memperlihatkan efek neuroproteksi pada tikus dengan model cedera otak traumatik.6 Penelitian cedera otak traumatik pada manusia menunjukkan bahwa terapi hipotermi mempunyai pengaruh memulihkan autoregulasi serebral, memperbaiki neuro-electrofisiologi dan oksigenasi otak, mengurangi kadar lipid dan kolesterol pasien TBI di area perikontusio,7 serta mengurangi tekanan intrakranial sebesar 3–10 mmHg.8 Penggunaan hipotermia selalu terlambat pada saat resusitasi awal, optimalisasi CPP/CBF, evakuasi bedah, pemantauan ICP, pengendalian perdarahan pasien cedera otak traumatik. Padahal cedera otak sekunder dapat terjadi akibat temperatur, diperberat oleh demam, dan dihambat oleh hipotermi. Panas setelah cedera otak traumatik dapat menimbulkan hipertensi intrakranial dan memperburuk prognosis.3 Pada cedera otak traumatik dapat terjadi cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Kekuatan mekanis dari luar dapat menimbulkan gangguan menetap atau temporer berupa perubahan kesadaran, gangguan fungsi kognitif, fisikal, psikososial. Penyebabnya adalah kontusio otak, epidural hematoma, perdarahan subarakhnoid, perdarahan intraventrikuler, cedera robekan. Insult sekunder dapat berupa hipotensi arterial, hipoxemia/hiperoxemia, hiperkapnia, hipokapnia, hiperglikemia, hipoglikemia, hipertermia, gangguan keseimbangan air dan elektrolit, anemia, seizure. Cedera sekunder dapat menyebabkan terjadinya iskemia seluler, 191 pembengkakkan neuron, edema vasogenik, dan pembengkakkan otak dapat meningkatkan tekanan intrakranial dan menurunkan tekanan perfudi otak (cerebral perfusion pressure/CPP).9 Terapi hipotermi telah digunakan pada pasien dengan henti jantung, asfiksia perinatal, cedera otak traumatik, oprasi jantung, bedah saraf, bedah vaskuler.9 Komplikasi dari hipotermia dalam (profound/deep hypothermia) adalah pneumonia, sepsis, disritmia jantung, hipotensi, masalah perdarahan karena adanya koagulopati. Komplikasi kardiovaskuler adalah depresi miokardial, disritmia termasuk ventricular fibrilasi, hipotensi, perfusi jaringan tidak adequat, iskemia. Gangguan koagulasi berupa thrombositopenia, fibrinolisis, disfungsi platelet, peningkatan perdarahan. Gangguan metabolisme berupa melambatnya metabolisme anestetika, memanjangnya blokade neuromuskuler, meningkatnya katabolisme protein. Adanya komplikasi menggigil akan meningkatkan konsumsi oksigen, meningkatkan produksi CO2, desaturasi O2 arterial, ketidakstabilan hemodinamik. III. Bagaimana mekanisme terapi hipotermi sebagai protektor otak? Hipotermia menurunkan aktivitas metabolik dan fungsional dari otak. Koefisien temperatur (Q10) menunjukkan faktor dengan mana CMRO2 berubah setiap perbedaan temperatur 10 derajat. Untuk kebanyakan reaksi biologis, Q10 nilainya kira-kira 2 (penurunan 50% CMRO2 untuk setiap penurunan temperatur 10 0C). Jadi otak yang normotermik (37 0C) dapat mentolerir iskemia komplit yang berlangsung selama 5 menit, pada suhu 27 0C otak dapat mentolerir iskemia yang berlangsung selama 10 menit.5,10 Walaupun hipotermi mengurangi CMRO2 sekitar 7% setiap derajat C, mekanismenya tidak linier. Aktual Q10 adalah 2,2 sampai 2,4 antara 37 0C dan 27 0 C menyebabkan penurunan 50% CMRO2 pada suhu 27 0C. Antara 27 0C dan 17 0C, Q10 kira-kira 5. Hal ini berkorelasi dengan kehilangan fungsi neuron secara bertahap, seperti ditunjukkan dengan EEG isoelektrik (yang terjadi antara 18 0C dan 17 0C) dan kemampuan otak untuk mentolerir iskemia otak yang lebih berat daripada 192 Jurnal Neuroanestesi Indonesia yang diprediksi dengan model linier. Dibawah 17 0 C, Q10 kembali ke 2,2 sampai 2,4 lagi.5,10 Proteksi otak dari hipotermi ringan sampai sedang telah ditunjukkan dalam model laboratorium COT yang berbeda. Mekanismenya multifaktorial dan berhubungan dengan penurunan metabolisme, penurunan Ca influx, penurunan pelepasan excitatory amino acids (EAA), preservasi sintesa protein dan sawar darah otak, mencegah peroksidasi lipid, menurunkan pembentukan edema, protein substansia alba, modulasi respons inflamasi dan kematian sel apoptotik.5,10 Secara klinis penggunaan hipotermi pada pasien pascacedera otak traumatik, stroke, aneurisma serebral mungkin mempunyai efek menguntungkan dalam hal penurunan ICP dan kemungkinan proteksi otak. Akan tetapi, sampai saat ini penelitian klinis belum membenarkan penggunaan hipotermi untuk proteksi otak pada keadaan-keadaaan tersebut.10 Untuk mencapai keuntungan maksimum, terapi hipotermi harus diberikan sesegera mungkin, langsung ke target suhu yang diinginkan dan diberikan dalam jangka waktu lama. Pasien yang menunjukkan respons terhadap teurapetik hipotermia adalah pasien usia muda (<15 tahun) dan yang mengalami cedera kepala berat dengan GCS 4 sampai 7 saat masuk ke rumah sakit. Pada kasus stroke ikemik, hipotermia harus dikombinasi dengan perfusi otak yang adekuat. Bukti keuntungan hipotermi ringan tidak ada untuk carotid endarterectomy (CEA) dan clipping aneurisma serebral.10 Walaupun riset klinis tidak menunjukkan perbaikan pada outcome, hipotermi ringan (32– 35 0C), dan hipotermi sedang (26–31 0C) telah digunakan untuk prosedur jantung. Hal yang sama, hipotermia dalam (deep hypothermia, suhu 18-25 0C) selama henti sirkulasi juga digunakan pada repair penyakit jantung kongenital, aorta torakalis pada dewasa, dan giant atau serebral aneurisma kompleks.10 Ada beberapa komplikasi serius dari hipotermia yang membatasi efek menguntungkan dalam memelihara fungsi neuron. Keadaan ini kebanyakan terjadi pada hipotermia berat dan sedang. Komplikasi yang terjadi dapat mengenai sistem kardiovaskuler, gangguan koagulasi, perlambatan metabolisme obat, dan menggigil. Komplikasi kardiovaskuler antara lain depresi miokardium, disritmia, hipotensi, dan perfusi jaringan yang tidak adekuat. Gangguan koagulasi antara lain trombositopenia, fibrinolisis, dan disfungsi platelet. Menggigil dapat menyebabkan desaturasi oksigen, ketidakstabilan hemodinamik, peningkatan kebutuhan oksigen dan produksi CO2.10 Dalam dekade yang lalu penelitian menunjukkan bahwa hipotermi ringan secara nyata menurunkan cedera pada pasien dengan iskemia serebral. Ada resiko sistemik yang nyata dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan teknik hipotermi. Hipotermi ringan (sampai suhu 34 oC) mempunyai efek proteksi otak. Terdapat sejumlah laporan penelitian model binatang percobaan pada iskemi serebral global untuk melihat efek proteksi dengan penurunan temperatur 1–4 oC. Untuk penurunan 3 oC, ada penurunan cerebral metabolic rate for oxygen (CMRO2) sebanyak 20%. Akan tetapi, efek proteksi otak dengan hipotermia ringan bukan primer pada efeknya menurunkan CMRO2, tetapi juga pada mediator cedera iskemik (misalnya dengan menurunkan pelepasan EAA). Hipotermia ringan untuk beberapa hari setelah kliping aneurisma, subarachnoid hemorrhage (SAH) atau cedera kepala secara nyata mengurangi konsentrasi glutamat pada cairan serebrospinal. Hipotermia ringan juga mempunyai keuntungan lain dengan bekerja pada sintesa ubiqitin dan aktivasi protein C-kinase atau dengan stabilisasi membran dan mengurangi konsentrasi kalsium intraseluler.10 Peningkatan suhu tubuh akan meningkatkan CMRO2 yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan oksigen. Beberapa penelitian klinis hipotermia ringan selama 24–48 jam setelah cedera kepala berat memperbaiki outcome neurologis. Beberapa pusat pendidikan anestesi menggunakan teknik hipotermia ringan (33–35 0C) pada operasi dimana jelas ada resiko cedera iskemi susunan saraf pusat, misal cliping aneurisma serebral. Pengaturan temperatur pasien yang dirawat di ICU adalah konsep “low normothermia” yaitu pasien dipertahankan dalam temperatur 36 oC. Pada penelitian invitro menunjukkan bahwa hipotermia akan memelihara ATP, mengurangi Ca influks, memperbaiki pemulihan elektrofisiologis dari hipoksia sedangkan hipertermi akan menghabiskan ATP, meningkatkan Ca influks dan Terapi Hipotermi setelah Cedera Otak Traumatik mengganggu pemulihan. Adanya demam pada pasien neuro dan jantung akan memperburuk outcome, sebagai contoh 90% pasien SAH akan mengalami hipertemi selama perawatan di ICU dan dihubungkan dengan buruknya outcome.5,10 Penelitian pada pasien yang diberikan moderat hipotermi (33 0C) 11 dari 24 pasien meninggal akibat herniasi yang disebabkan peningkatan ICP sekunder setelah rewarming dan 10 dari 25 pasien (40%) menderita pneumonia. Kalau keuntungan hipotermi ringan terbatas pada mencegah hipertermi, keuntungan yang lebih baik adalah mempertahankan pasien dalam low normothermia.5,10 Terdapat buktibukti neuroproteksi dari profilaksis hipotermi ringan. Data yang baru yang membandingkan normotermi dengan hipotermi (35,5–36,5 lawan 28–30 0C) pasien bypass kardiopulmonal, gagal menunjukkan keuntungan dari hipotermi. Akan tetapi sampai bukti-bukti empiris ada, dianjurkan untuk melakukan hipotermi ringan intraoperatif. Mekanisme proteksi otak dengan hipotermi adalah menurunkan metabolisme otak, memperlambat depolarisasi anoksik/iskemik, memelihara homeostasis ion, menurunkan eksitatori neurotransmisi, mencegah atau mengurangi kerusakan sekunder terhadap perubahan biokimia. Efek proteksi serebral dari hipotermia telah diketahui dengan baik. Teknik yang aman dan efektif untuk melakukan hipotermi, masih sulit ditentukan. Untuk mencapai hipotermi ringan dengan pendinginan permukaan tubuh berlangsung lambat karena adanya vasokontriksi perifer dan pada umumnya gagal untuk mendinginkan otak mencapai temperatur inti. Selain itu, prosedur pendinginan permukaan tubuh sulit dengan adanya fenomena rewarming afterdrop dan dapat menyebabkan pembengkakan otak selama periode rewarming. Hal ini ditambah dengan adanya efek buruk akibat hipotermi pada seluruh tubuh, termasuk terjadinya aritmia jantung, koagulopati, hemolisis, disfungsi hepar dan renal dan penekanan fungsi imun. Untuk menghindari komplikasi sistemik akibat pendinginan seluruh tubuh (total body cooling) peneliti-peneliti mencoba melakukan pendinginan secara selektif hanya pada serebralnya saja. Alat-alat pendinginan eksternal telah terbukti efektif dalam mendinginkan secara selektif pada 193 otak saja pada binatang kecil. Sayangnya, tidak berhasil dilakukan pada binatang yang lebih besar. Penelitian lain menunjukkan kelambatan teknik ini yaitu ketidak mampuan mencapai bagian otak yang dalam. Sebaliknya, extracorporeal cerebral bypass hypothermia efektif untuk melakukan pendinginan otak secara selektif, akan tetapi, teknik ini memerlukan heparin yang menjadi sulit pada pasien trauma pembuluh darah, embolisasai, edema serebral idiopatik dan telah ditinggalkan karena tidak praktis dan tidak aman. Satu penelitian dengan melakukan pendinginan intravaskuler dikarenakan kegagalan mencapai hipotermia ringan pada pasien cedera kepala berat. Penelitian ini ditekankan pada kebutuhan mendapatkan cara yang lebih aman, efektif untuk mencapai keadaan serebral hipotermia. Mack melakukan katerisasi vena no 10 F melalui vena femoralis dan ujungnya mencapai vena cava inferior. Dilakukan pendinginan dengan kecepatan 6,3(0,8) 0C, dan temperatur otak 32,2(0,2) 0C dicapai dalam waktu 47,7 (6,32) menit.5 Cedera otak akibat cedera merupakan penyebab penting dari kematian dan disabilitas pada personil sipil maupun militer. Dengan sistem pengorganisasian trauma care dan critical care yang baik dan adekuat, mortalitas dari cedera kepala berat telah menurun dari kira-kira 50% pada tahun 70-an menjadi 30% pada tahun 2001. Lebih penting, penurunan mortalitas ini dihubungkan dengan peningkatan proporsi yang hidup dengan fungsi otak yang relatif normal. Bagaimanapun, pencapaian yang luar biasa ini tidak diketahui secara luas. Perbaikan ini dianggap disebabkan karena lebih cepatnya transportasi pasien ke UGD, menghindari terjadinya hipotensi dan hipoksia, metode resusitasi yang lebih efektif, brain imaging yang segera, intervensi bedah yang segera, ICU yang baik, dan pemantauan serta pengelolaan tekanan intrakranial. Beberapa dari cedera neurologis dapat terjadi pada saat terjadinya kecelakaan dan mungkin bersifat ireversibel. Tetapi, kemudian terjadi proses biokimia yang memperburuk outcome. Menghambat atau melawan proses ini menjadi target neuroscientist dalam banyak tahun. Sebagai data, terdapat lusinan penelitian klinis dari obat seperti free radical scavenger, 194 Jurnal Neuroanestesi Indonesia antagonis glutamat, Ca chanel blocker yang mungkin mengurangi cedera pada otak pasien dengan cedera kepala. Walaupun telah dipelajari tentang patofisiologi cedera otak dan faktor-faktor yang mempengaruhi outcome, tidak ada satupun obat yang terbukti efektif. Pendekatan non-farmakologi untuk pengobatan pasien dengan cedera otak trauma difokuskan pada pencegahan hipertensi intrakranial dan mempertahankan perfusi otak yang adekuat. Penelitian klinis multisenter dari hipotermia pada pasien dengan cedera kepala berat telah dilaporkan oleh Clifton dkk, walaupun mengecewakan, menggambarkan hasil yang penting. Penelitian Clifton dimulai tahun 1994 dengan harapan ada bukti definitif keuntungan hipotermi pada pasien cedera kepala. Akan tetapi, pada bulan Mei 1998, penelitian tersebut dihentikan oleh Patient Safety and Monitoring Board setelah dilakukan pada 392 pasien dari 500 pasien yang direncanakan, karena ternyata terapi hipotermi tidak efektif. Pendinginan pasien dengan target suhu kandung kencing 33 0C dalam 8 jam setelah cedera dan dipertahankan hipotermi selama 48 jam tidak efektif dalam memperbaiki outcome klinik pada 6 bulan kemudian. Dalam kenyataannya, pasien yang berumur >45 tahun. Mild hypothermia-core temperatur tubuh 32–34 0 C dapat memproteksi tubuh efek inflamasi setelah cedera otak, henti jantung, atau infark miokardial acut. Tujuan terapi hipotermi pada keadaan– keadaan tersebut adalah untuk mengurangi cedera iskemi yang disebabkan karena proses biokimia. Mekanisme proteksi dari hipotermi belum dimengerti dengan jelas. Pada iskemi serebral akibat stroke atau henti jantung, hipotermi mengurangi metabolisme otak dan kebutuhan oksigen dan menurunkan kadar EAA. Hipotermi juga menghambat infark miokard pada AMI, kemungkinan dengan mekanisme yang sama. Hipotermia ringan mungkin rentang terapi yang paling aman dan paling efektif, bahkan bila diberikan dalam jangka waktu lama, hipotermia ringan tidak menimbulkan komplikasi seperti hipotermi moderat (28–32 0 C). Sebaliknya, hipotermi moderat dapat menimbulkan terjadinya aritmia jantung, fibrilasi ventrikel, koagulopati, dan infeksi. Terapi hipotermia mempunyai efek dalam menurunkan metabolisme otak, menurunkan pelepasan excitatory amino acids (EAA), pencegahan apoptosis, mengurangi disfungsi mitokhondria, mengurangi produksi radikal bebas, mengurangi oksidatif DNA, mempertahankan ATP, menurunkan Ca influx, memelihara sintesa protein dan sawar darah otak, mencegah peroksidasi lipid, mengurangi pembentukan edema, memodulasi respons inflamasi dan kematian sel secara apptotik. Terapi hipotermi dapat mengendalikan tekanan intrakranial.11 IV. Berapa derajat celcius penurunan suhu tubuhnya? Banyak definisi tentang hipotermia dan tidak semuanya sama. Sebagai contoh, ada yang menyebut hipotermia ringan bila suhu 32-34 0 C, hipotermia sedang 28–32 0C. Hipotermia ringan: 32–33 0C. Hipotermia sedang: 33–34 0C. Hipotermia dalam (deep hypothermia): 27 0C atau lebih rendah. Hipotermia ringan 33–35 0C. Hipotermia ringan 34–360 C, sedang 32–34 0C, berat <32 0C . Yang lainnya mengatakan bahwa disebut ringan bila suhu 32–35 0C, sedang 28– 32 0C, berat 20–28 0C, profound <20 0C. Lebih rendah temperatur, lebih dalam proteksi otak dengan hipotermia, tapi dengan lebih rendahnya temperatur, efek samping akan meningkat. Kedalaman optimal dari hipotermia terapeutik harus seimbang antara proteksi otak maksimal dan efek samping yang minimal. Dari data eksperimental dan pengalaman klinis, temperatur optimal adalah dalam rentang 340 dan 350C.5 V. Bagaimana cara melakukan penurunan suhu? Pengelolaan tradisional hipertermi setelah COT adalah dengan memberikan antipiretik, selimut pendingin, ice packs, dan beberapa kasus blokade neuromuskuler. Ada kekurangan dari evaluasi literatur tentang efektivitas antipiretik tradisional seperti asetaminofen, paracetamol, aspirin, dan nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) untuk hipertermia akibat COT. Data terbatas mendukung bahwa walaupun sering diberikan antipiretik untuk mengobati hipertermi setelah COT, ternyata tidak mampu (insufficient) Terapi Hipotermi setelah Cedera Otak Traumatik mengobati pireksia. Satu penelitian menunjukkan bahwa paracetamol tidak bisa menurunkan suhu pada 20% anak untuk mengobati hipertermia setelah COT. Acetaminophen juga jarang berhasil dalam mengobati hipertermia pada pediatrik COT. Antipiretik hanya efektif hanya pada 7% pasien dewasa yang panas pada COT. Induksi hipotermi dapat dilakukan dengan pendinginan permukaan (surface cooling), endovascular cooling, selective head cooling. Surface cooling dapat dilakukan dengan kantong es, helm, vests, mattresses, intravenous cooling, intravascular cooling devices, selective brain cooling (pharyngeal).12 Pendinginan intravena dilakukan dengan memberikan 20–30 mL/kg larutan kristaloid (4 0C), diberikan lebih dari 30 menit dan dengan teknik ini risiko terjadinya pneumonia kecil. Surface cooling dilakukan dengan selimut dingin dan kantong es merupakan metode yang sangat sederhana, dan butuh 3 jam untuk mencapai target suhu, kebutuhan obat pelumpuh otot dan intubasi untuk melawan vasokonstriksi dan menggigil. Endovascular cooling membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mencapai temperatur target, tidak diperlukan pelumpuh otot dan intubasi dan pengendalian menggigil. Head cooling adalah selective head cooling dengan hipotermia sistemik ringan dan diberikan pada neonatal ensephalopati.12 195 dengan kecepatan 0,5 0C setiap 2 jam. Penelitian ini tidak mengkonfirmasikan kegunaan hipotermia sebagai strategi neuroprokteksi yang utama pada pasien dengan cedera otak traumatik berat.4 VII. Berapa lama hipotermi dipertahankan? Pendinginan harus dimulai sesegera mungkin dengan temperatur extracorporeal 30 0C dan dipertahankan pada temperatur otak 32 0C untuk 48 jam kemudian dilakukan rewarming secara bertahap untuk 24 jam. Delapan pasien, GCS 4–5 dan hasilnya adalah 5 pasien meninggal akibat kelainan intrakranial (n=4) atau akibat septik syok setelah pneumonia (n=1). Sebagai simpulannya adalah tidak ada keuntungan terapeutik hipotermia pada outcome. Satu penelitian melakukan hipotermia untuk mencapai temperatur tubuh 33 0C, yang dimulai 6 jam setelah cedera dan dipertahankan selama 48 jam dengan surface cooling. Hasilnya adalah tidak efektip. Peneliti lain melakukan hipotermi ringan (33–35 0C) dalam jangka lama (long-term cooling) dan ternyata secara nyata memperbaiki outcome pasien cedera kepala berat dengan kontusio serebral dan hipertensi intrakranial tanpa komplikasi yang nyata. Pendinginan selama 5 hari lebih manjur daripada 2 hari (short-term cooling).13 VI. Berapa cepat hipotermia harus dicapai? VIII. Bagaimana memulihkan ke normotermi (Rewarming)? Untuk penggunaan hipotermia sebagai neuroprotektif dalam pencegahan kerusakan iskemik, itu diperlukan untuk melakukan hipotermi sesegera mungkin setelah insult dan mempertahankannya pada level terendah yang aman. Induksi hipotermi sangat segera pada pasien dengan cedera otak traumatik berat (Very early hypothermia induction in patient with severe brain injury/the NABIS: Hypothermia II). RCT, penelitian klinis multisenter, menyertakan 232 pasien cedera otak traumatik berat (119 pasien dilakukan hipotermia terapeutik dalam 2,5 jam setelah cedera, 113 pasien lagi normotermia), umur 16–45 tahun, segera didinginkan sampai 33 0 C, dipertahankan untuk 48 jam dan dihangatkan Pasien dengan hipertensi intrakranial diketahui mempunyai refleks meningkatkan ICP selama rewarming yang cepat. Menggigil selama rewarming akan meningkatkan konsumsi oksigen dan harus dihentikan dengan pemberian sedasi dan pelumpuh otot. Alat penghangat adalah pemanas cairan, sikuit humidifier, selimut air panas, forced air warming blankets (paling cepat), lampu pemanas infrared. Rewarming dilakukan bila ICP <20 mmHg (stabil untuk 48 jam). Dianjurkan rewarming yang lambat lebih dari 12 jam dengan kecepatan 0,1 0C/ jam, ada yang menyarankan rewarming dengan kecepatan 1 0C setiap 3–4 jam, 1 0C/hari, 0,5 0C dalam 2 jam. Rewarming yang lambat 0,25 0C/ jam memberikan proteksi yang maksimal.14 196 Jurnal Neuroanestesi Indonesia IX. Bagaimana hasilnya? Bukti klinis tentang hasil dari terapi hipotermia masih kontroversial. Limabelas persen perbaikan outcome 6 bulan pada 46 pasien yang mana temperatur tubuhnya diturunkan sampai 32 0C selama 48 jam yang dimulai dalam 6 jam setelah cedera. Penelitian lain menunjukkan perbaikan outcome yang signifikan secara statistik sebanyak 38% pada 46 pasien dengan GCS 5–7 diantara 82 pasien yang didinginkan sampai 32 0C. Walaupun terbatas, bukti terbaik yang tersedia mendukung bahwa terapeutik hipotermi dapat mengurangi risiko mortalitas dan memperbaiki neurologik outcome, terutama bila dipertahankan dalam waktu lebih dari 48 jam dan bila digunakan pada pasien yang berespon baik terhadap tindakan standar untuk mengendalikan ICP tanpa menggunakan dosis tinggi barbiturat.5,15 Satu sistematik review dari 18 penelitian yang terdiri dari 13 RCT dan 5 penelitian observasional. Terapeutik hipotermia 32–4 0C, efektip dalam mengendalikan hipertensi intrakranial. Sebagai kesimpulannya adalah tangguhkan menunggu hasil penelitian multisenter yang besar yang mengevaluasi efek terapeutik hipotermia pada hipertensi intrakranial dan outcome, terapeutik hipotermia harus dimasukkan sebagai opsi terapi untuk mengendalikan hipertensi intrakranial pada pasien dengan cedera otak traumatik yang berat.16 Sebaliknya, terapi dengan hipotermia dengan suhu tubuh mencapai 33 0C dalam 8 jam setelah cedera, tidak efektif untuk memperbaiki outcome pada pasien dengan cedera kepala berat. Penelitian Clifton dkk., dimulai pada tahun 1994, akan tetapi pada bulan Mei 1998, penelitiannya dihentikan oleh Patient Safety and Monitoring Board, setelah melakukan penelitian pada 392 dari 500 pasien yang direncanakan, disebabkan terapinya tidak efektip. Satu Cochrane Database Systematic Review tahun 2009 dengan kriteria seleksi: penelitian RCT dengam hipotermia maksimal sampai 35 0C dan dilakukan minimal 12 jam. Dilakukan pada 23 penelitian dengan total 1614 pasien. Tidak ada bukti bahwa hipotermia menguntungkan untuk terapi cedera kepala.17 Tidak konsistennya efek hipotermia terapi pada cedera kepala berat pada penelitian-penelitian sebelumnya mungkin disebabkan karena induksi hipotermi terlalu terlambat setelah cedera. Satu penelitian melakukan pendinginan segera (early cooling) dalam 2–2,5 jam setelah cedera dengan suhu 33 0C dan dipertahankan selama 48 jam dan dibandingkan dengan normotermia sebagai kontrol. Penelitian ini tidak mengkonfirmasikan kegunaan hipotermia sebagai suatu strategi neuroproteksi utama pada pasien dengan cedera otak traumatika berat.11 Untuk dapat melakukan terapi hipotermia diperlukan unit khusus, personil yang berpengalaman dan protokol pelaksanaannya. X. Apakah ada penelitian yang sedang berlangsung? Ada bebeapa penelitian besar yang sedang berlangsung yaitu di Jepang (clinical trials: NCT00134472), Australia-New Zealand (Polar RCT), dan Eropa (Eurotherm Trial). Japanese trial (clinical trials: NCT00134472).18 Peneltian RCT tentang terapi hipotermia untuk pasien cedera kepala berat di Jepang. Mereka membagi sampel dalam dua kelompok yaitu kelompok normotermia 35–37 0C dan hipotermia ringan 32–34 0C dan dipertahankan selama 72 jam. Pengambilan sampelnya sudah selesai tapi belum dipublikasikan. Polar RCT 19 Prophylactic Hypothermia Trial to Lessen TBI (POLAR-RCT) dilakukan di Australian and New Zealand Intensive Care Research Centre. Penelitian dilakukan pada 500 pasien dan sampai saat ini masih mengumpulkan pasien. Suhu tubuh diturunkan sampai 33 0C selama 3 hari. Rewarming dilakukan dengan kecepatan 0,17 0C/jam. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah propilaksis early hypothermia memperbaiki outcome pada 6 bulan setelah cedera otak traumatik? The Eurotherm3235Trial 20 European Society of Intensive Care Medicine study of HT (32-35°C) for ICP reduction after TBI (the Eurotherm3235Trial). Ini adalah penelitian pragmatis, internasional, Terapi Hipotermi setelah Cedera Otak Traumatik multisenter RCT yang menguji efek hipotermia 32–35 0C, untuk mengurangi ICP <20 mmHg, dalam morbiditas dan mortalitas 6 bulan setelah cedera otak raumatik. Pendinginan dilakukan dalam 72 jam setelah cedera otak traumatika dan dipertahankan selama 48 jam, untuk melihat efek terhadap penurunan tekanan intrakranial. Jumlah pasiennya direncanakan 1800 pasien dan penelitian dimulai bulan April 2010. X. Simpulan Hipotermi terapeutik masih kontroversi, akan tetapi, dalam situasi klinik pertahankan suhu pasien 35 0C dan hindari suhu tubuh pasien lebih dari 37 0C, lakukan terapeutik hipotermi minimal 5 hari, untuk mencapai suhu 35 0C dianjurkan memakai metode surface cooling, tentang outcome masih dipertanyakan, dan belum diketahui, dan sekarang penelitian yang lebih besar sedang dilakukan. Daftar Pustaka 1. Bendo AA. Perioperative management of adult patient with severe head injury. Dalam: Cottrell JE, Young WL, eds. Cottrell and Young’s neuroanesthesia; 2011, 317–25. 2. Bullock RM, Povlishock JT. Guideline for the management severe traumatic brain injury, Brain Trauma Foundation. J Neurotrauma 2007;24, S21 3. Puccio AM, Fischer MR, Jankowitz BT, Yonas H, Darby JM, Okonkwo D. Induce normothermia attenuate intracranial hypertension and reduces fever burden after severe traumatic brain injury. Neurocrit Care 2009;11(1):82–87 4. Grande PO, Reinstrup P, Romner B. Active cooling in traumatic brain-injured patients: a questionable therapy? Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:1233–38 5. Bisri DY, Oetoro B, Harahap S, Siti Chasnak Saleh SC. Hipotermia untuk proteksi otak. JNI 197 6. Sinclair HL, Andrews PJ. Bench-to-bed side review: hypothermia in traumatic brain injury. Crit Care 2010;14(1): 204 7. Masaoka H. Cerebral blood flow and metabolism during mild hypothermia in patient with severe traumatic brain injury. J Med Sci Den 2010;57(2):133–8 8. Schreckinger M, Marion DW. Contemporary management of traumatic intracranial hypertension: is there a role for therapeutic hypothermia? Neurocrit Care 2009;11(3):427–36. 9. Oddo M, Ribordy V, Feihl F, Rosetti AO, Schaller MD, Chiolero R, et al. Early predictors of outcome in comatose survivors of ventricular fibrillation and non-ventricular fibrillation cardiac arrest trated with hypothermia: a prospective study. Crit Care Med 2008;36(8):2296–301 10. Hou YJ, Cottrell JE, Lei B, Kass IS. Improving neurologic recovery from cerebral ischemia. Dalam: Newfield P, Cottrell JE, eds. Handbook of Neuroanesthesia, 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012, 50–69 11. Clifton GL, Valadka A, Zygun D, Coffey CS, Drever P, Fourwinds S, et al. Very early hypothermia induction in patients with severe brain injury (the National Acute Brain Injury Study: hypothermia II): a randomised trial. Lancet Neurol 2011;10(2):131–39 12. Hoedemaekers CW, Ezzahti M, Gerritsen A, van der Hoeven JG. Comparison of cooling method to induce and maintain normo and hypothermia in intensive care unit patients: a prospective intervention study. Crit Care 2007;11(4):R–91 13. Jiang JY, Xu W, Li WP, Gao GY, Bau YH, Liang YM, et al. Effect of long-term mild hypothermia or short-term mild hypothermia on outcome of patients with severe traumatic brain injury. Journal of Cerebral Blood Flow 198 Jurnal Neuroanestesi Indonesia & Metabolism 2006;26:771–6 14. Povlishock JT, Wei EP. Posthypothermic rewarning consideration following traumatic brain injury. J Neurotrauma 2009;26:333–40 15. Patterson K, Carson S, Carney N. Hypothermic treatment for traumatic brain injury: a systematic review and metaanalysis. J Neurotrauma 2008;25(1):62–71 16. Sadaka F, Veremakis C. Therapeutic hypothermia for the management of intracranial hypertension in severe traumatic brain injury: a systematic review. Brain injury 2012;26(7-8):899–908 17. Sydenham E, Robert L, Anderson P. Hypothermia for traumatic head injury. Cochrane Database Syst Rev 2009, issue 2. 18. Maekawa T, Yamashita S. Therapeutic hypothermia for severe traumatic brain injury in Japan. Japanese trial (clinical trials: NCT00134472) cloud.golgbamboo.com/ topic-t10163–a1 19. Cooper D, Myburgh J, Cameron P, Presneill J, Bernard S, Nichol A. The Polar RCT. http:// researchdata.ands.org.au/polar-rct 20. Andrews PJD, Sinclair HL, Battison CG, Polderman KH, Citerio G, Mascia L, et al. European society of intensive care medicine study of therapeutic hypothermia (32-350C) for intracranial pressure reduction after traumatic brain injury (the Eurotherm3235Trial). Trial 2011,12:8 http:// www.trialsjournal.com/content/12/1/8 Disseminated Intravascular Coagulation pada Cedera Otak Traumatik Agus Baratha Suyasa*, Sudadi**, Bambang Suryono** *)Departemen Anestesi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Kasih Ibu, Denpasar – Bali **)Departemen Anestesi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Sardjito – Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta Abstrak Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) merupakan konsekuensi yang sering dan penting pada cedera otak traumatik (Traumatic Brain Injury/TBI) dan menyebabkan cedera otak sekunder. Walaupun perkembangan proses ini belum dapat dijelaskan secara keseluruhan, namun abnormalitas koagulasi darah adalah bukti yang ditemukan pascatrauma. DIC adalah proses patofisiologi dan bukan merupakan suatu penyakit tersendiri. Gangguan yang terjadi meliputi ketidaktepatan, berlebihan dan aktivasi proses hemostasis yang tidak terkontrol. Karakteristik DIC adalah konsumsi faktor pembekuan darah dan trombosit dalam sirkulasi yang menimbulkan berbagai derajat obstruksi pembuluh darah mikro sehubungan dengan deposisi fibrin. Masalah dan gambaran utama akut DIC adalah perdarahan. Gangguan mekanisme hemostatik sangat penting dalam TBI. Perdarahan mikro sering terjadi di parenkim otak dan status koagulasi normal adalah penting untuk mencegah perkembangannya menjadi hematom yang lebih besar. Abnormalitas koagulasi tidak hanya hasil dari cedera, tetapi juga menyebabkan cedera sekunder. Gangguan koagulasi dalam TBI sangat kompleks dan dapat disertai dengan koagulopati dan hiperkoagulabilitas. Di temukan bukti bahwa luasnya trauma jaringan otak memiliki peran penting terhadap gangguan koagulasi dibandingkan syok traumatik maupun hipoksia. Adanya koagulopati pada TBI mengindikasikan prognosis yang buruk, sehingga pemeriksaan rutin terhadap status koagulasi harus selalu dilakukan pada semua pasien TBI. Kata kunci: koagulopati, disseminated intravascular coagulation, cedera otak traumatik JNI 2014;3 (3): 199‒205 Disseminated Intravascular Coagulation on Traumatic Brain Injury Abstract Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) is a frequent and important consequence of traumatic brain injury and may cause secondary brain injury. Although the mechanism of this process cannot be explained as a whole, but abnormalities of blood coagulation after trauma is the evidence. DIC in brain trauma is a pathophysiological process and is not due to a disease in itself. Disturbance includes inaccuracy, excessive and activation of uncontrolled hemostasis process. Characteristic of DIC is the consumption of blood clotting factors and platelets in the circulation that cause various degrees of micro vascular obstruction in conjunction with the deposition of fibrin. The main problem features of acute DIC are bleeding. Impaired hemostatic mechanism plays an important role in traumatic brain injury (TBI). Micro bleeding often occurs in the brain parenchyma and normal coagulation status is important to prevent its development into a larger hematoma. Coagulation abnormality is not the only discouraging factor of injury, but also lead to secondary injury. Coagulation disorders in TBI are very complex and can be accompanied by coagulopathy and hypercoagulability. Found evidence ofextented trauma in the brain tissue plays more important role to coagulation disorder than traumatic shock and hypoxia. The presence of coagulopathy in TBI indicates a poor prognosis, so the routine inspection of the coagulation status should always be performed in all patients with TBI. Key words: coagulopathy, disseminated intravascular coagulation, traumatic brain injury JNI 2014;3 (3): 199‒205 199 200 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I.Pendahuluan Abnormalitas pada koagulasi darah cukup sering terjadi pada cedera otak traumatik (traumatic brain injury/TBI). Beberapa penulis meneliti gambaran klinis dan patofisiologi dari fenomena tersebut dan menemukan bahwa abnormalitas koagulasi darah merupakan awal terjadinya disseminated intravascular coagulation (DIC). Hubungan ini dapat menjelaskan terjadinya iskemia serebral yang menyertai cedera otak traumatik, yang disebut mikrotrombosis intravaskular. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DIC merupakan konsekuensi yang sering dan penting pada cedera otak traumatik dan menyebabkan cedera otak sekunder. Walaupun perkembangan proses ini belum dapat dijelaskan secara keseluruhan, namun abnormalitas koagulasi darah adalah bukti yang ditemukan pascatrauma. Abnormalitas hemostasis berhubungan dengan banyak komplikasi pada trauma dan berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas.1-6 Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) DIC adalah proses patofisiologi dan bukan merupakan suatu penyakit tersendiri. Gangguan yang terjadi meliputi ketidaktepatan, berlebihan dan aktivasi proses hemostasis yang tidak terkontrol. Manifestasi klinis DIC berhubungan dengan sumbatan pembuluh darah kecil (microvessel) selama fase obstruksi dan perdarahan karena konsumsi plasma dan komponen seluler pada sistem hemostasis. Proses DIC kemungkinan karena berlanjutnya stimulus dan atau konsumsi inhibitor alami hemostasis. Pada awalnya DIC muncul dengan kompensasi yang adekuat, namun jika proses berlanjut menjadi berat, maka gejala klinis akan muncul sebagai perdarahan sistemik dan biasanya berkaitan dengan kerusakan organ. Kompensasi sekunder DIC adalah fibrinolisis, dimana pada beberapa kasus justru meningkatkan perdarahan.7,8 Patofisiologi Karakteristik DIC adalah konsumsi faktor pembekuan darah dan trombosit dalam sirkulasi yang menimbulkan berbagai derajat obstruksi pembuluh darah mikro sehubungan dengan deposisi fibrin. Pada saat konsumsi faktor pembekuan darah dan trombosit menjadi signifikan, maka gejala utama yang terjadi adalah perdarahan.7,8 Beberapa mekanisme yang secara tidak langsung mengaktifkan sistem hemostasis diantaranya: 1. Aktivasi jalur koagulasi dengan melepaskan tromboplastin jaringan kedalam sirkulasi sistemik (pada trauma jaringan, operasi, keganasan, dan hemolisis intravaskuler akut). 2. Kerusakan dinding endotel pembuluh darah menyebabkan aktivasi trombosit yang diikuti aktivasi sistem hemostasis, melalui jalur intrinsik; misalnya (sepsis karena pelepasan endotoksin gram negatif, infeksi virus, luka bakar luas, hipertensi, hipoksia dan asidosis). 3. Induksi aktivasi trombosit, contohnya (septikemia, viraemia, komplek antigenantibodi dan aktivasi trombosit). Gambaran klinis Gambaran klinis DIC bervariasi, dapat berupa trombosis, perdarahan, atau manifestasi campuran pada berbagai sistem organ. Masalah dan gambaran utama akut DIC adalah perdarahan. Manifestasinya dapat sebagai bercak menyeluruh, perdarahan pada tempat trauma seperti (penusukan vena dan luka operasi). DIC juga dapat muncul berkaitan dengan berbagai macam gangguan klinis (tabel 2). Jika DIC muncul pada penderita dengan penyakit berat dan kerusakan organ multipel, maka prognosisnya menjadi buruk.7,8 Gambaran Laboratorium DIC yang signifikan ditandai dengan pemeriksaan standar koagulasi (Prothrombintime/PT, Activated partial thromboplastin time/APTT, dan Thrombin clotting time/TCT). Kunci pemeriksaan dalam mendiagnosis adalah menemukan bukti konversi fibrinogen menjadi fibrin yang berlebihan dalam sirkulasi dan kemudian lisis. Gumpalan fibrintrombosit (platelet-fibrin clots) membentuk jaring (mesh) pada mikrosirkulasi yang menimbulkan trauma pada sel darah merah yang lewat sehingga menyebabkan fragmentasi dan hemolisis. Pemeriksaan hapusan darah (blood film) menunjukkan fragmentasi sel darah merah (microangiopatic haemolytic anemia).7,8 Disseminated Intravascular Coagulation pada Cedera Otak Traumatik 201 Gambar 1. Patofisiologi dan Manajemen DIC7 Diagnosis DIC biasanya berdasarkan kombinasi gambaran klinis yang sesuai dan gambaran laboratorium sistem hemostasis yang mendukung (tabel 1) Trombosiopenia, hipofibrinogenemia dengan pemanjangan PT, APTT, dan TCT serta peningkatan produk degradasi fibrin (fibrinogen degradation product/FDP dan D-Dimer) merupakan bukti pendukung untuk menegakan diagnosis. D-Dimer merupakan pemeriksaan spesifik untuk pemecahan fibrin dibandingkan fibrinogenolisis primer. Pemeriksaan yang lebih spesifik adalah peningkatan fibrinopeptide A dan penurunan antitrombin III (ATIII) juga dapat mempertegas diagnosis.7-9 II. DIC pada Cedera Otak Traumatik (TBI) Pada tahun 1960, Penick dan McLendon melaporkan beberapa kasus abnormalitas koagulasi darah karena berbagai penyebab, diantaranya terdapat kasus neonatus yang mengalami cedera otak traumatik selama persalinan dan mengalami koagulopati yang berat. Beberapa tahun kemudian dilaporkan serial kasus gangguan pembekuan darah pasca cedera otak taumatik dan cedera kepala lainnya. Kejadian abnormalitas pembekuan darah pada cedera otak traumatik bervariasi antara 15–100%.1 Gangguan mekanisme hemostatik sangat relevan dalam TBI). Perdarahan mikro sering 202 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Tabel 1. Kondisi yang Berhubungan dengan DIC7 Infeksi Trauma Keganasan Gangguan Imunologi Bakterial sepsis Panas karena virus hemoragik Protozoa (malaria) Kerusakan jaringan luas Cedera kepala Emboli Lemak Karsinoma Leukemia (terutama promielositik) Penolakan transplantasi Reaksi transfusiincompatible haemolytic blood Reaksi alergi berat Reaksi obat Sirkulasi ekstra korporeal Gigitan ular tanpa antidotum Gangguan vaskuler Hemangioma besar Aneurisma aorta Gangguan kehamilan Aborsi septik Plasenta abrupsi/ablatio Eklampsia Emboli air ketuban Plasenta previa Luka bakar Hipertermia Penyakit hati dan nekrosis hati akut terjadi di parenkim otak dan status koagulasi normal adalah penting untuk mencegah perkembangannya menjadi hematom yang lebih besar. Abnormalitas koagulasi tidak hanya hasil dari cedera, tetapi juga menyebabkan cedera sekunder. Gangguan koagulasi dalam TBI sangat kompleks dan dapat disertai dengan koagulopati dan hiperkoagulabilitas. Hiperkoagulabilitas adalah meningkatnya kapasitas pembentukan fibrin dalam pembuluh darah. Suatu keadaan hiperkoagulasi dapat digeneralisasikan pada kasus disseminated intravascular coagulation (DIC) atau lokal dengan perkembangan microthrombi dalam daerah kontusio penumbra. DIC ditandai dengan meluasnya aktivasi koagulasi, yang menghasilkan pembentukan fibrin intravaskular dan akhirnya trombotik oklusi pembuluh darah kecil dan sedang.3,9,10 III. Patogenesis Gangguan Koagulasi pada TBI Pada individu sehat, koagulasi dan fibrinolisis adalah seimbang untuk mencegah perdarahan yang berlebihan atau trombosis. Pasien dengan TBI berisiko terjadi kelainan koagulasi dan fibrinolisis. Abnormalitas koagulasi berbeda antara pasien dengan cedera otak terisolasi (isolated brain injury) dan pasien dengan cedera multipel. Di temukan bukti bahwa luasnya trauma jaringan otak memiliki peran penting terhadap gangguan koagulasi dibandingkan syok traumatik maupun hipoksia. Pada awal tahun tujuh puluhan, pelepasan faktor jaringan (Tissue factor/TF), sebelumnya disebut tromboplastin atau thrombokinase dari cedera jaringan otak telah dinyatakan sebagai penyebab. Faktor jaringan adalah protein, hadir dalam jaringan subendothelial, trombosit, dan leukosit diperlukan untuk memulai kaskade koagulasi yang akhirnya mengarah ke pembentukan trombin dari zymogen protrombin. TF adalah inisiator fisiologis utama koagulasi dan karena pelepasanya juga dapat mengaktifkan sistem koagulasi yang berlebihan pada pasien dengan trauma kepala.3,10 Hal ini menunjukkan bahwa aktivasi ini tergantung pada jumlah TF yang dilepaskan dari kerusakan jaringan otak. Penelitian Gando dan rekan-rekan menunjukkan kadar TF yang lebih tinggi pada pasien dengan cedera kepala dibandingkan pasien yang bukan cedera kepala. Namun ditegaskan kadar plasma antigen terlarut faktor jaringan belum dapat dijelaskan dan apakah kadar ini memiliki arti serta apa fungsinya belum diketahui.3 Paparan awal TF terhadap faktor VII dan VIIA menghasilkan FVIIa /TF kompleks. Bentuk kompleks ini menghasilkan sejumlah kecil faktor Xa dan faktor IXa. Faktor Xa bersama dengan permukaan membran mengaktifkan sejumlah kecil protrombin menjadi trombin. Generasi kecil trombin akan mengaktifkan Disseminated Intravascular Coagulation pada Cedera Otak Traumatik 203 Tabel 1. Pemeriksaan Laboratorium untuk Diagnosis 7 Analisis Jumlah Platelet Activated partial thromboplastin (APTT) Prothrombin time (PT) Thrombin clotting time (TCT) Fibrin degradation time (TCT) Hypofibrinogen Other coagulation factors II, VII, X, VIII Coagulation inhibitors-antithrombin III, protein C Blood film Supplementary and research test-prothrombin fragment 1+2 thrombin-antithrombin complex (TAT-complex), procalcitonin (PCT) Plasmin-antiplasmin complexes (PAP-complex) Early Late ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ Usually normal in early stages ↑ Fragmented red cells+in subacute or chronic cases ↑ Traumatic Brain Injury Brain tissue damage Local release tissue factor Activation of haemostasis system Fibrin deposition Depletion coagulation factors and platelets Multi organ-failure Haemorrhagic 10 diathesis Gambar 2. Diagram Skematik TBI dan Koagulopati trombosit dan faktor V dan VIII, dimana akan menyediakan permukaan yang sesuai untuk membentuk prothrombinase yang akan membutuhkan lebih banyak generasi trombin untuk konversi fibrinogen menjadi fibrin.3,9,11 Aktivasi faktor jaringan-dependen dari koagulasi, yang kemudian dikenal sebagai jalur ekstrinsik, menyebabkan pembentukan thrombus fibrin mikro dan makrovaskular. Mekanisme kontrol, termasuk inhibitor jalur faktor jaringan (TFPI), sistem protein C, dan antitrombin glycosamine glycans aktif untuk melawan pembentukan fibrin 204 Jurnal Neuroanestesi Indonesia dan melokalisir pembentukan fibrin ke tempat cedera, tetapi sering tidak cukup setelah terpapar TF yang luas. DIC yang dicetuskan oleh aktivasi TF, menghambat mekanisme antitrombotik melalui pelepasan sitokin dan upregulation menyebabkan gangguan jalur antikoagulasi fisiologis. Hal ini dapat menyebabkan nekrosis dan perdarahan di banyak organ, akhirnya menyebabkan kegagalan multi organ (multiple organ failure/MOF).10 Beberapa penelitian telah memastikan hubungan antara abnormalitas koagulasi dengan outcome yang buruk. Keterkaitan antara abnormalitas koagulasi dengan perdarahan intraserebral lambat juga telah dibuktikan. Diagnosis dan penanganan koagulopati pada TBI masih menjadi kontroversi, walaupun penangangan awal yang telah diberikan pada fase awal hiperkoagulasi dapat mencegah progresi lesi dan meningkatkan outcome.10 secara signifikan waktu koagulopati. Obat anti fibrinolitik seperti aprotinin, asam tranexamat dan asam aminokaproat sering digunakan pada operasi jantung. Peran obat antifibrinolitik pada pasien trauma dengan perdarahan yang banyak, belum diketahui secara jelas. Data awal penelitian menunjukkan factor rekombinan VIIa (rF VIIa) mampu memperbaiki koagulopati pada trauma kepala dengan baik dan cepat yang dapat menjadi terapi alternatif. Hal yang menarik adalah terapi dengan rFVIIa dalam waktu empat jam setelah onset perdarahan intrakranial mampu menghambat perkembangan hematoma, menurunkan mortalitas dan meningkatkan outcome fungsional dalam waktu 90 hari. Namun demikian rFVIIa harus diberikan secara hati-hati karena resiko tromboemboli.8,10,12,13 IV. Manajemen Koagulopati pada TBI V. Simpulan dan Rekomendasi Guidelines yang pasti untuk penanganan koagulopati pasca TBI belum ada. Juga belum ada penelitian acak dengan intervensi pemberian Fresh Frozen Plasma (FFP), obat antitrombosis atau konsentrat factor koagulasi antitrombosis setelah TBI. Secara umum terapi gangguan koagulasi ditujukan untuk menghilangkan penyebab primernya. Tujuan terapi seharusnya mengatasi koagulasi, melisiskan bekuan yang ada, mengganti faktor koagulasi serta mengembalikan hiperfibrinolisis.1 FFP dan trombosit concentrate (TC) direkomendasikan untuk perdarahan aktif. Satu penelitian bahkan merekomendasikan FFP sebagai cairan resusitasi pada pasien dengan GSC ≤7.12 Koagulopati sering terjadi padaTBI. Koagulopati lebih berat pada trauma yang berat. Taruma otak yang progresif terjadi lebih sering pada pasien dengan koagulopati. Adanya koagulopati pada TBI mengindikasikan prognosis yang buruk, sehingga pemeriksaan rutin terhadap status koagulasi harus selalu dilakukan pada semua pasien TBI. Secara spesifik status koagulasi yang dimaksud adalah hiperkoagulopati dan DIC. Guidelines terhadap skor DIC yang direkomendasikan adalah D-Dimer atau FDP, jumlah trombosit, protrombin time (PTT) dan fibrinogen. Data-data ini memiliki implikasi yang penting dalam penanganan pasien. Namun banyak yang tidak setuju dengan pendapatnya. Pemberian heparin sebagai antikoagulan yang diikuti dengan penggantian agresif dengan trombosit dan FFP dapat menjadi indikasi terapi pada DIC secara umum.13 Sebagian besar klinisi yang menangani TBI takut untuk memberikan heparin karena peningkatan resiko perdarahan intrakranial dan sedikit bukti klinis yang mendukung. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk memperbaiki koagulopati pada TBI. Pemberian dini antitrombin III (AT III) pada pasien TBI dapat mengurangi 1. Stein SC, Smith DH. Coagulopathy in traumatic brain injury. Neurocritical Care 2004; 1 (4) : 479 -88. Daftar Pustaka 2. Takahashi H, Urano T, Nagai N, Takada Y, Takada A. Neutrophil elastase may play a key role in developing symptomatic disseminated intravascular coagulation and multipel organ failure in patient with head injury. Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care. July 2000; 49 (1): 86–91. Disseminated Intravascular Coagulation pada Cedera Otak Traumatik 3. Talving P, Benfield R, Hadjizacharia P, Inaba K, Chan LS, Demetriades D. Coagulopathyin severe traumatic brain injury: A Prospective Study. Journal of Trauma–Injury Infection & Critical Care. January 2009; 66 (1): 55–62. 4. Hess JR, Brohi K, Dutton RP, Hauser CJ, Holcomb JB, Kluger Y, et al. The coagulopathy of trauma: a review mechanism. Journal of Trauma–Injury Infection & Critical Care. October 2008; 65 (4) : 748–54. 5. Jacoby RC, Owings JT, Holmes J, Battistella FD, Gosselin RC, Paglieroni TG. Platelet Activation and function after trauma. Journal of Trauma–Injury Infection & Critical Care. October 2001; 51 (4): 639–47. 6. Vavilala MS, Dunbar PJ, Rivara FP, Lam AM. Coagulopathy predicts poor outcome following head injury in children less than 16 years of age. Journal of Neurosurgical Anesthesiology. January 2001; 13 (1): 13–8. 7. Tan CW, Ward CM, Isbister JP. Haemostatic failure. Dalam: Bersten AD, Soni, N, eds. OH's Intensive Care Manual, 7th, China: Elsevier 2014, 1003–16. 8. Marcel L, Evert DJ, Tom VDP, Hugo TC. Novel aproach to the management of 205 disseminated intravascular coagulation. Crtical Care Medicine. September 2000; 28(9): 20–4. 9. Nekludov M, Antovic J, Bredbacka S, Blomback M. Coagulation abnormalities asscociated with severe isolated traumatic brain injury: cerebral arterio-venous differences in coagulation and inflamatory markers. Journal of Neurotrauma. January 2007; 24 (1) : 174–80. 10. Harhangi BS, Kompanje EJO, Leebeek FWG, Maas ALR. Review article: coagulation disorders after traumatic brain injury. Acta Neurochir 2008; 150: 165–75. 11. Gando S. Disseminated intravascular coagulation in trauma patient. Semin thromb haemost 2001; 27 (6): 585–92. 12. May AK, Young JS, Butler K, Bassam D, Brondy W. Coagulopathy in severe closed head injury: is empiric therapy warranted. Am.Surg 1997; 63(3): 233–36; discussion 236–37. 13. Rubin RN, Colman RW. Disseminated intravascular coagulation. Approach to treatment. Drugs1992; 44(6): 963–71. Indeks Penulis A Agus Baratha Suyasa, 199 Ardana Tri Arianto, 164 B Bambang Suryono, 180, 199 Buyung Hartiyo Laksono, 157 D Dewi Yulianti Bisri, 189 H Himendra Wargahadibrata, 149 I Iwan Fuadi, 141 M MH Soedjito, 164 N Nazaruddin Umar, 149 R Rebecca S. Mangastuti, 149 Radian Ahmad Halimi, 141 Riyadh Firdaus, 180 S Siti Chasnak Saleh, 157, 173, 180 Sudadi, 199 T Tatang Bisri, 141, 189 Indeks Subjek A Anestesi, 149 Anatomi foramen magnum, 180 Awake craniotomy, 173 B Bispectral index, 180 C Cedera otak traumatik, 141, 199 D Dexmedetomidine, 173 Disseminated intravascular coagulation, 199 F Fentanyl, 173 Fossa posterior, 164 I Infark serebri, 157 IONM, 180 K Koagulopati, 199 M Malformasi Arnold Chiari, 164 Meningioma, 149 N Numeric rating scale, 141 Non neurosurgery, 157 P Post traumatic headache, 141 Posisi prone, 164 Posisi park bench, 180 Propofol, 173 Proteksi otak, 189 Prosedur non neurosurgery, 157 R Resusitasi otak, 189 S Space occupying lession, 157 T Terapi hipotermia, 189 Tehnik proteksi otak, 157 Tumor supratentorial, 173 Total intra venous anesthesia, 149 Pedoman Bagi Penulis 1. Ketentuan Umum Redaksi majalah Jurnal Neuroanestesi Indonesia menerima tulisan Neurosains dalam bentuk Laporan Penelitian, Laporan Kasus, Tinjauan Pustaka, serta surat ke editor. Naskah yang dipertimbangkan dapat dimuat adalah naskah lengkap yang belum dipublikasikan dalam majalah nasional lainnya. Naskah yang telah dimuat dalam proceeding pertemuan ilmiah masih dapat diterima asalkan mendapat izin tertulis dari panitia penyelenggara. 2. Judul Bahasa Indonesia tidak melebihi 12 kata, judul bahasa Inggris tidak melebihi10 kata. 3. Abstrak Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta tidak boleh lebih dari 250 kata. Abstrak Penelitian: Terdiri dari IMRAD (Introduction, Method, Result, and Discussion). Dalam introduction mengandung latar belakang dan tujuan penelitian. Dalam Discussion diakhiri oleh Simpulan. Contoh Penulisan Abstrak Penelitian: Latar Belakang dan Tujuan: Disfungsi kognitif pascaoperasi (DKPO) sering terjadi dan menjadi masalah serius karena dapat menurunkan kualitas hidup pasien yang menjalani pembedahan dan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui angka kejadian DKPO pada pasien yang menjalani operasi elektif di GBPT RSU dr. Sutomo dan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Subjek dan Metode: Penelitian ini melibatkan 50 orang sampel berusia 40 tahun atau lebih yang menjalani pembedahan lebih dari dua jam. Dilakukan serangkaian pemeriksaan fungsi kognitif praoperasi dan tujuh hari pascaoperasi. Domain kognitif yang diukur adalah atensi dan memori. Faktor yang diduga mempengaruhi kejadian DKPO dalam penelitian ini adalah usia, tingkat pendidikan dan durasi operasi. Hasil: Tujuh hari pascaoperasi 30% sampel mengalami gangguan atensi, 36% sampel mengalami gangguan memori dan 52% sampel mengalami disfungsi kognitif pascaoperasi. Pemeriksaan kognitif yang mengalami penurunan bermakna adalah digit repetition test, immediate recall, dan paired associate learning. Analisa logistik regresi variabel usia (p=0,798), tingkat pendidikan (p=0,921) dan durasi operasi (p=0,811) terhadap kejadian DKPO menunjukkan hubungan yang tidak bermakna. Namun bila dianalisa pada masing masing kelompok usia tampak bahwa persentase pasien yang mengalami DKPO konsisten lebih tinggi pada usia ≥50 tahun, tingkat pendidikan ≤6 tahun dan durasi operasi ≥180 menit Simpulan: Kejadian disfungsi kognitif pada pasien yang menjalani operasi elektif di GBPT RSU dr. Sutomo cukup tinggi. Faktor usia, tingkat pendidikan dan durasi operasi tampaknya mempengaruhi kejadian DKPO meskipun secara statistik tidak signifikan. Kata kunci: anestesi umum, atensi, kognitif pascaoperasi, memori Abstrak Laporan Kasus: Terdiri dari Pendahuluan, Kasus, Pembahasan, simpulan Contoh Penulisan Abstrak Laporan Kasus: Abstract Meningoencephaloceles are very rare congenital malformations in the world that have a high incidence in the population of Southeast Asia, include in Indonesia. Children with anterior meningoencephaloceles should have surgical correction as early as possible because of the facial dysmorphia, impairment of binocular vision, increasing size of the meningoencephalocele caused by increasing brainprolapse, and risk of infection of the central nervous system. In the report, we presented a case of a 9 monthsold baby girl with naso-frontal encephalocele and hydrocepahalus non communicant, posted for VP shunt (ventriculo-peritoneal shunt) and cele excision. Becaused of the mass, nasofrontal or frontoethmoidal and occipital meningoencephalocele leads the anaesthetist to problems since the anaesthesia during the operation until post operative care. Anaesthetic challenges in management of meningoencephalocele, which most of the patients are children, include securing the airway with intubation with the mass in nasofrontal or nasoethmoidal with its associated complications and accurate assessment of blood loss and prevention of hypothermia pengelolaan hemodinamik dan jantung, 2) jalan nafas dan ventilasi, 3) evaluasi fungsi neurologic dan kebutuhan pemantauan tekanan intracranial atau drainase ventrikel atau keduanya. Key words: Anaesthesia, difficult ventilation, difficult intubation, naso-frontal, meningoencephalocele, padiatrics Contoh cara penulisannya: Abstrak Tinjauan Pustaka: Terdiri dari Pendahuluan, Isi, dan Simpulan Abstrak Stroke hemoragik merupakan penyakit yang mengerikan dan hanya 30% pasien bertahan hidup dalam 6 bulan setelah kejadian. Penyebab umum dari perdarahan intracranial adalah subarachnoid haemorrhage (SAH) dari aneurisma, perdarahan dari arteriovenous malformation (AVM), atau perdarahan intraserebral. Perdarahan intraserebral sering dihubungkan dengan hipertensi, terapi antikoagulan atau koagulopati lainnya, kecanduan obat dan alcohol, neoplasma, atau angiopati amyloid. Mortalitas dalam 30 hari sebesar 50%. Outcome untuk stroke hemoragik lebih buruk bila dibandingkan dengan stroke iskemik dimana mortalitas hanya sekitar 10-30%. Stroke hemoragik khas dengan danya sakit kepala, mual muntah, kejang dan defist neurologic fokal yang lebih besar. Hematoma dapat menyebabkan letargi, stupor dan koma. Disfungsi neurologic dapat terjadi dari rentang sakit kepala sampai koma. Pengelolaan dini difokuskan pada: 1) Kata kunci: perdarahan intracranial, stroke perdarahan Diakhir abstrak dibuat kata kunci yang ditulis berurutan secara alphabet, 3–5 buah. 4. Cara Penulisan Makalah Penulisan Daftar Pustaka: • Nomor Kepustakaan berdasarkan urutan datang”di dalam teks, Vancouver style. Jumlah kepustakaan minimal 10 dan maksimal 20 buah. • Dari Jurnal: 1. Powers WJ. Intracerebral haemorrhage and head trauma. Common effect and common mechanism of injury. Stroke 2010;41(suppl 1):S107–S110. 2. Qureshi A, Tuhrim S, Broderick JP, Batjer HH, Hondo H, Hanley DF. Spontaneus intracerebral haemorrhage. N Engl J Med 2001; 344(19):1450–58. Dari Buku: 1. Ryan S, Kopelnik A, Zaroff J. Intracranial hemorrhage: intensive care management. Dalam: Gupta AK, Gelb AW, eds. Essentials of Neuroanesthesia and Neurointensive Care. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008, 229–36. 2. Rost N, Rosand J. Intracerebral hemorrhage. Dalam: Torbey MT, ed. Neuro Critical Care. New York: Cambridge University Press;2010,143-56. Materi Elektronik Artikel Jurnal dalam Format Elektronik Lipton B, Fosha D. Attachment as a transformative process in AEDP: operationalizing the intersection of attachment theory and affective neuroscience. Journal of Psychotherapy Integration [Online Journal] 2011 [diunduh 25 November 2011]. Tersedia dari: http://www.sciencedirect.com 5. Jumlah halaman Laporan Kasus Laporan Penelitian : 10-12 halaman : 15 halaman Tinjauan Pustaka : 15-20 halaman Surat Pembaca : 1 halaman Ditik 1,5 spasi, Times New Roman, 11 font. Penanggungjawab, pemimpin, dan segenap redaksi Jurnal Neuroanestesi Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada mitra bebestari: Prof. Siti Chasnak Saleh, dr., SpAnKIC, KNA (Universitas Airlangga ‒ Surabaya) Dr. Sri Rahardjo, dr., SpAnKNA, KAO (Universitas Gadjah Mada ‒ Yogyakarta) Bambang Suryono, dr., SpAnKNA, KAO (Universitas Gadjah Mada ‒ Yogyakarta) Dr. Bambang J. Oetoro, dr., SpAnKNA (Universitas Atmajaya Khatolik – Jakarta) Dr. Sudadi, dr., SpAnKNA (Universitas Gadjah Mada ‒ Yogyakarta) Dr. M. Sofyan Harahap, dr., SpAnKNA (Universitas Diponegoro ‒ Semarang) Abdul Lian, dr., SpAnKNA (Universitas Diponegoro ‒ Semarang) MH. Sudjito, dr., SpAnKNA (Universitas Sebelas Maret ‒ Surakarta) Atas kerjasama yang terjalin selama ini, dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Neuroanestesi Indonesia, semoga kerjasama ini dapat berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang Redaksi FORMULIR PESANAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : ………………………………………………………………... Alamat Rumah : ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ……………….. Kode pos…………………………................. Telepon …………………………Faks …………………......... HP ………………………………E-mail…………................... Alamat Praktik : ………………………………………………………………... Telepon …………………………Faks ………………............. Alamat Kantor : ………………………………………………………................ ……………………….. Kode pos…………………………….. Telepon …………………………Faks ……………………...... Mulai berlangganan : ………………………………. s.d ……………………………... Saya bermaksud untuk berlangganan JNI secara teratur dengan mengirimkan biaya berlangganan sebesar Rp. 250.000,00 per tahun** Pembayaran melalui : □ Langsung ke Sekretariat Redaksi Jl. Prof. Dr. Eijkman No. 38 – Bandung 40161 Mobile: 087722631615 JNI dikirimkan ke* : Alamat Rumah Alamat praktik Alamat Kantor □ □ □ Bandung, ………………………………… Hormat Saya ( * pilih salah satu ** foto kopi bukti transfer mohon segera dikirimkan/faks ke Sekretariat Redaksi *** termasuk ongkos kirim untuk wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten )