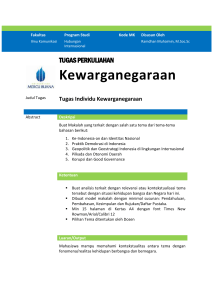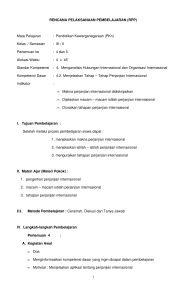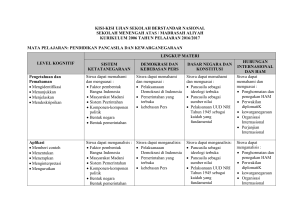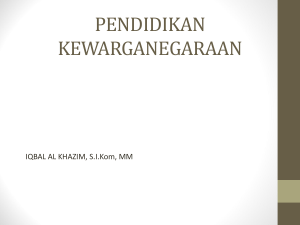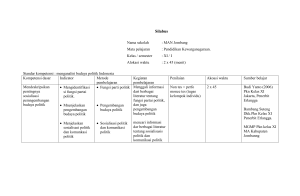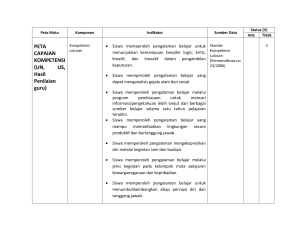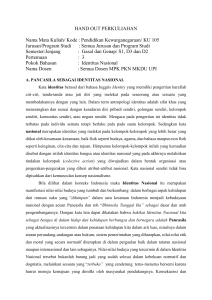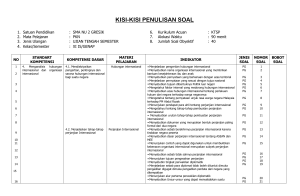Jurnal HPI Revisi Final Per_Pages
advertisement

Volume 01 ● Oktober 2009 ARTIKEL The Law of the Sea and Ethical Maritime Order in South East Asia Statement by the H.E. Dr. N. Hassan Wirajuda At the University of Virginia School of Law, Charlotsville, 30 September 2009 Sengketa Perbatasan Antar ASEAN Arif Havas Oegroseno Keutuhan Wilayah RI : Persepsi Ancaman dan Ancaman Nyata Haris Nugroho Pulau Miangas : Perlukah Kekhawatiran Itu ? Irma D. Rismayati Manusia Perahu Rohingya : Tantangan Penegakan HAM di ASEAN Irma D. Rismayati Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Investasi Syahda Guruh LS Implementasi UU No.12/2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Perlindungan WNI di Luar Negeri Clemens Bektikusuma Mandatory Consular Notification Sahadatun Donatirin Praktek Pergeseran Doktrin Kekebalan Perwakilan Diplomatik Dihadapan Yurisdiksi Pengadilan Negara Penerima : Sengketa & Kontrak Kerja Soeharyo Tri Sasongko Statuta International Criminal Court : Perlukah Indonesia Meratifikasinya? Adhi Kawidastra Responsibility to Protect dalam Perspektif Hukum Bebeb A.K. Djundjunan dan Rizal Wirakara BEDAH BUKU Beyond Terror and Martyrdom: The Future of the Middle East Gilles Kepel, Harvard University Press PRESS BRIEFING Deklarasi Solo, Upaya Penjagaan dan Perlindungan Warisan Budaya Volume 01 ● Oktober 2009 DAFTAR ISI i PENGANTAR REDAKSI ii ARTIKEL The Law of the Sea and Ethical Maritime Order in South East Asia Statement by the H.E. Dr. N. Hassan Wirajuda At the University of Virginia School of Law, Charlotsville, 30 September 2009 Sengketa Perbatasan Antar ASEAN Arif Havas Oegroseno Keutuhan Wilayah RI : Persepsi Ancaman dan Ancaman Nyata Haris Nugroho Pulau Miangas : Perlukah Kekhawatiran Itu ? Irma D. Rismayati Manusia Perahu Rohingya : Tantangan Penegakan HAM di ASEAN Irma D. Rismayati Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Investasi Syahda Guruh LS Implementasi UU No.12/2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Perlindungan WNI di Luar Negeri Clemens Bektikusuma Mandatory Consular Notification Sahadatun Donatirin Praktek Pergeseran Doktrin Kekebalan Perwakilan Diplomatik Dihadapan Yurisdiksi Pengadilan Negara Penerima : Sengketa & Kontrak Kerja Soeharyo Tri Sasongko Statuta International Criminal Court : Perlukah Indonesia Meratifikasinya? Adhi Kawidastra Responsibility to Protect dalam Perspektif Hukum Bebeb A.K. Djundjunan dan Rizal Wirakara 1-5 6-9 10 - 11 12 - 15 16 - 23 24 - 26 27 - 30 31 - 32 33 - 39 40 - 43 44 - 53 BEDAH BUKU Beyond Terror and Martyrdom: The Future of the Middle East Gilles Kepel, Harvard University Press 54 - 57 PRESS BRIEFING Deklarasi Solo, Upaya Penjagaan dan Perlindungan Warisan Budaya 58 i Volume 01 ● Oktober 2009 Opinio Juris ini diterbitkan untuk menyebarluaskan berbagai informasi, wacana dan perspektif hukum dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri. Dalam edisi perdana ini, seluruh penulis berasal dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, namun demikian tidak tertutup kemungkinan kami akan memuat tulisan dari rekanrekan sejawat Deplu atau mitra kerja dari luar lingkungan Deplu. Dari berbagai tulisan yang dimuat pada edisi perdana ini, kami berusaha untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus perhatian pada saat ini. OPINIO JURIS Hal ini terlihat dari adanya artikel yang membahas, mulai dari soal integritas wilayah dan keamanan, kekebalan diplomatik, perlindungan WNI di luar negeri hingga menyentuh juga masalah yang memiliki dimensi regional seperti masalah Rohingya dan sengketa Candi Preah Vihear serta doktrin kemanusiaan, Responsibility to Protect. Harapan kami, semoga Opinio Juris ini dapat menjadi wahana diseminasi isu-isu hukum dan perjanjian internasional, sekaligus menjadi rujukan dalam mengembangkan wacana tentang peningkatan pemahaman berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Kecuali dinyatakan sebaliknya, pandangan-pandangan dalam artikel yang termuat dalam Opinio Juris merupakan pendapat pribadi dan akademik. ii OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 THE LAW OF THE SEA AND ETHICAL MARITIME ORDER IN SOUTH EAST ASIA STATEMENT BY THE H.E. DR. N. HASSAN WIRAJUDA AT THE UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF LAW CHARLOTSVILLE, 30 SEPTEMBER 2009 with me not only pleasant memories of the University of Virginia and Charlotsville but also a fine sense of anticipation that much can and should be done for the cause of law and order in a world that is mostly oceans, seas, and waterways. Distinguished Members of the Faculty, Members of the Student Body, Ladies and Gentlemen, I am honoured and delighted to be here again in the Center for Oceans Law and Policy of the University of Virginia School of Law and mingling with eminent academicians and their bright-eyed students. From where I stand, I can see familiar faces among the members of the Center’s Board of Directors. I do recognize Prof. John Norton Moore and Prof. Myron Nordquist who, through their writings, have contributed tremendously to the promotion of law and order at sea. My being here today gives me a sense of déjàvu: the time I spent on this campus was filled with intellectual excitement and remains a very important part of my life. When I left after completing my studies in 1988, I brought The world has radically changed since then – it has become so much more complex. New issues, new ideas and new realities are now prevailing in international affairs. A very much welcome reality has been the coming into force of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. This “Constitution of the Ocean” enjoys almost universal ratification, as 159 states are parties to it, making it the single legal framework for ocean governance. Because of the Convention, all maritime spaces on the planet are now regulated. The UNCLOS is a codification of longstanding customary laws as well as new legal principles in matters relating to oceans applicable to all states regardless of their geographical situation. Thus, the Convention represents a breakthrough in transnational rule-making on the rights and responsibilities of states with regards to the world’s oceans. Consequently, the Convention has brought about a great deal of legal certainty in interstate relations. Indonesia is proud of the fact it was actively involved in the nine-year negotiations that led to the concluding of the Convention in 1982. 1 Volume 01 ● Oktober 2009 Of course, the tremendous advances in science and technology have also changed the world in the meantime: they have shrunk the world into a virtual village. But they have not diminished the importance of the oceans and seas. They still have a vital role in food security, energy security, climate stability, human security and socioeconomic activities. The oceans provide the only feasible means of transporting strategic materials -be the food or energy- in gigantic quantities in relatively short time. Without the oceans so much less commerce would be taking place. Sea-borne trade accounts for nearly 85 percent of world trade. And this is estimated to increase at a steady rate of ten percent a year. We in Indonesia are very much aware of this. As the largest archipelagic state in the world, we have a special regard for our maritime territory and resources; they are life-giving and they are a force for national unity and identity. That is why we refer to our country as tanah airku, meaning my land and waters. We are aware of the strategic importance of our archipelago. Four of the ten straits vital to international navigation involve Indonesia waters: the Strait of Malacca, the Strait of Singapore, the Strait of Sunda and the Strait of Lombok. One third of all sea-borne trade and the energy supply from the Middle East to China, the Republic of Korea and Japan pass through the Straits of Malacca and Singapore. 2 OPINIO JURIS Over 60,000 vessels pass through these straits every year, and the number is expected to increase by ten percent annually. Any disruption in this maritime traffic because of a collision of vessels, in this matter of piracy, would have an adverse impact on global trade and on the economies of the littoral states. The other countries of Southeast Asia share Indonesia’s marine and maritime concerns. The region as a whole boasts a mega diversity of marine flora and fauna and other resources that can be exploited for economic purposes. Hence, all the countries of the region are seized with the task of integrated coastal management and environmental protection. And because the seas of the region are semi-enclosed seas, the bordering states are mandated to cooperate closely with one another in the exercise of their rights and in the performance of their duties under the Convention. That is the idea behind the establishment of the Sulu-Sulawesi Seas Marine Eco-region in February 2004 and the Coral Triangle Initiative (CTI) in May this year. We also hosted the World Ocean Conference back to back with the Coral Triangle Initiative in May this year. There is a great deal of cooperation on maritime matters among the countries of Southeast Asia today, not only because it is mandated by the Convention but also because they learned several decades ago that cooperation was the only way to achieve prosperity and stability in a region that was until 1975 ravaged by proxy wars and civil wars. OPINIO JURIS It was the best strategy for survival in an uncertain world. That was why the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN was established in 1967; to promote cooperation in political, economic and socio-cultural fields so that there would be peace and progress in the region. Today ASEAN is no longer just a loose association of nations in a given geographical area; it has new Charter that gives it legal entity and imparts momentum to its efforts to become an ASEAN Community by 2015. As such, ASEAN will also be a Security Community, an Economic Community and a Socio-cultural Community. When I speak of a Political Security Community, I do not refer to a military alliance. It means that we take responsibility for our own national and regional security so that we take every measure possible to ensure peace and stability. It also means that we attend to our political development by promoting democracy, human rights and good governance among ASEAN members through sharing norms and shaping of values – values that are conducive to peace and cooperation among ourselves the regional nations and between us and external powers. This shaping and sharing of values has been going on for some time. Once significant process began in 1990 when Indonesia launched an annual informal workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea. The workshop was launched at the time when it was feared that the next flashpoints would be Volume 01 ● Oktober 2009 in the South China Sea, as there are many unresolved maritime boundaries and sovereignty disputes in an area so important to international navigation. China was locked with several ASEAN Countries that were also engaged with one another in such disputes. Not being one of the rival claimants to all or parts of the South China Sea, Indonesia was able to organize the workshop as a confidence building measure and as a venue for Track Two Diplomacy. Experts and analysts from all over the region participated in this process – in their individual capacities and not as representatives of governments. Over the years in the 1990s, a body of ideas and project plans grew out of the workshop, all of them aimed at promoting cooperation among the rival claimants. Several of these projects were carried out, benefiting those involved and enhancing mutual trust among the nations of the region. The ideas developed in the workshop led to the adoption in 1992 of the ASEAN Declaration on the South China Sea, which not only committed the regional countries to peaceful resolution of their maritime boundary and sovereignty disputes but also to work together for the common good of all stakeholders. This was followed by negotiations and the eventual conclusion, in 2002, of an ASEAN – China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. By virtue of the Code, China and the ASEAN countries committed themselves to the peaceful resolution of their maritime territorial disputes. 3 Volume 01 ● Oktober 2009 Another process of shaping and sharing of norms was launched in Bangkok in 1994 – The ASEAN Regional Forum, a vehicle for political and security dialogue and cooperation on political security matters that involves all countries that have significant influence and interest in the security of the larger Asia-Pacific region. The ASEAN Regional Forum now has 27 states members including all the major powers. The work of the Forum would cover progressively the fields of confidence building, preventive diplomacy and practical cooperation. Since then, the Forum has proven to be greatly effective in confidence building and has additionally begun to undertake preventive diplomacy activities. It has also opened up a Track Two process, involving non-governmental entities in the promotion of security in the Asia-Pacific region. As a matter of course, since a large part of the Asia-Pacific is made up of an ocean and many seas, much of the work of the Forum has been directed at maritime safety and security. Last June, the ARF met in Surabaya, Indonesia to consider exclusively maritime security matters. Taking a cue from the success of the ASEAN Regional Forum, we in the region are launching by the end of this year the ASEAN Maritime Forum (AMF) which will provide us a venue for developing common perceptions on threats to maritime security and enhance inter-govern-mental cooperation in fighting perpetrators of crimes at sea. These processes involving the sharing and shaping of norms were built on the solid 4 OPINIO JURIS foundation of the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia, which was concluded in 1976. The TAC is essentially ASEAN’s code of conduct committing its signatories to five principles of peaceful coexistence, mutual respect, non- interference, peaceful settlement of disputes, renunciation of the threat or use of force and cooperation for socioeconomic development. As of today 17 states have acceded to the Treaty, I mean non ASEAN countries, including major maritime powers like Russia, China, India, Japan and recently the United States and the European Union. As a code of conduct it has worked so well that for more that three decades, in spite of many maritime boundary disputes in the Asia-Pacific region, no armed conflict has broken out among the signatories and those who acceded to the Treaty. And it is quite obvious to me that these processes of sharing and shaping of norms leading to good behaviour between and among states have promoted faithful compliance to the mandates and stipulations of the UN Convention of the Law of the Sea. To my mind, this brings up an important point, the law is always vital because we must have an ordered society of individuals as well as of nations, but the law will never be strong enough until and unless it is supported by human values. Ethics and a striving for virtue must complement the law that is what we have been proving in the ASEAN region over the years that we have been growing and evolving OPINIO JURIS to become a true community. On the other hand, the existence of law encourages and validates ethical behaviour. I believe there is a synergy rather than conflict between law and ethics. Knowing this, I do not think that we in ASEAN will ever become a litigious group of nations. A few years ago, a territorial dispute between Malaysia and Indonesia over the islands of Sipadan and Ligitan was decided by the International Court of Justice in favor of Malaysia. More recently a territorial dispute over the little rock of Pedra Branca between Malaysia and Singapore was decided in favour of Singapore. I do not believe there will be many more adjudications like that in the near future. That is because we have seen that adjudication, although it has the major virtue of being a peaceful process, almost inevitably leads to a winner-take –all situations. There is always something more to be desired from a situation where one party must accept the role of loser. The more prudent choice therefore is to sustain the various processes of dialogue, norms setting and promoting ethical behaviour while we settle our maritime and other disputes through consultation and negotiation. Negotiations, of course, take a great deal of time and patience. I please to tell you that it took 32 years for Indonesia and Vietnam to settle their continental shelf agreement. But as long as the parties involved are committed to peace and cooperation, time is not of the Volume 01 ● Oktober 2009 essence. An accumulation of wisdom over the years, even decades, could eventually lead to a win-win solution to any dispute no matter how intractable it appears to be. Meanwhile all parties benefit from the maintenance of peace and from the results of their cooperation. We do have something right and good taking place in the ASEAN region, a processes of sharing and shaping norms that lead to nations becoming well behaved and law abiding. It occurs to me that there is no similar process going among the Indian Ocean rim nations – at a time when the Indian Ocean is becoming more than ever before an important strategic theater. I think it would be worth the time of policy-makers, think tanks and thoughtful individuals to explore the potential of the ASEAN led forums and processes as models for the promotion of peace and cooperation in other part of the world that ate not carrying out similar undertakings. In sum, let me just say that one of the greatest achievements of the international community has been the virtual universal ratification of the UN Convention on the Law of the Sea. It has served humankind very well and imparted additional order to international relations. It deserves our support and we need to support it. And the best way to support it is to develop the values, the sense of ethics that make human beings law-abiding. That is what we have been doing in the ASEAN region. I thank you very much. 5 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS SENGKETA PERBATASAN ANTAR ASEAN Oleh : Arif Havas Oegroseno * Berita media beberapa waktu terakhir menyoroti sengketa antara Kamboja dan Thailand tentang status Candi Preah Vihear yang dinilai membahayakan keutuhan ASEAN. Ketegangan yang meningkat dan ditunjukan dengan siaga tentara kedua belah pihak di daerah perbatasan telah meningkatkan tensi hubungan bilateral diantara kedua negara. Seluruh Negara anggota ASEAN layak prihatin dan berharap para pihak dapat menyelesaikan permasalahan secara damai sesuai semangat solidaritas ASEAN dan good neighbourliness. Keprihatinan tersebut tercermin dari pernyataan Menlu Singapura George Yeo selaku Ketua ASEAN pada penutupan AMM ke-10 pada 20 Juli 2008. Di awal terbentuknya ASEAN Charter, sengketa atas Candi Preah Vihear seakan menyentak kesadaran publik. Lebih jauh, eskalasi konflik perbatasan ini juga telah menimbulkan keraguan sejumlah kalangan tentang efektifitas kerjasama ASEAN. Beberapa pengamat internasional bahkan menilainya sebagai ketidakberdayaan atau kegagalan ASEAN menyelesaikan masalah diantara negara anggota. Sengketa perbatasan sebagai konflik hukum. Sulit dipungkiri bahwa delimitasi batas internasional memiliki konsekuensi politis. Pakar pemetaan Ron Adler menyebutkan tiga aspek politis dari delimitasi batas Negara, yakni: mengakhiri konflik jika menjadi bagian dari peace treaty; memberikan keamanan yang berbeda dengan pengaturan militer, atau penyelesaian politis; dan reafirmasi eksistensi suatu negara yang berdaulat (Adler : 2001). Karena itu, sengketa wilayah dan/atau perbatasan memang memiliki potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik melalui dialog dan kesediaan bersikap terbuka untuk melanjutkan negosiasi. Pembentukan general/joint border committee dalam konteks bilateral, umumnya dibentuk guna membahas berbagai kerjasama perbatasan antarnegara. Namun komite bersama umumnya tidak memiliki kewenangan memutuskan status kepemilikan atas suatu wilayah di daerah perbatasan atau penetapan batas internasional. Pertimbangannya wajar karena sengketa wilayah perbatasan merupakan isu hukum. * Penulis dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI 6 OPINIO JURIS Ia berhubungan erat dengan aspek wilayah yang merupakan salah satu elemen objektif eksistensi sebuah entitas negara. Dalam batas-batas wilayahnya, Negara memiliki kedaulatan yang bersifat eksklusif dan mutlak serta terhadap penduduk yang bermukim di wilayah tersebut. Konvensi Montevideo 1933 menegaskan elemen wilayah, kedaulatan dan penduduk sebagai prasyarat bagi berdirinya Negara. Mudah dipahami jika sengketa perbatasan senantiasa menjadi isu sentral setiap negara dan secara emosional memancing sentimen publik para pihak yang bersengketa. Karena sengketa perbatasan merupakan isu yuridis maka efektifitas penyelesaiannya juga harus dikembalikan kepada mekanisme hukum. Volume 01 ● Oktober 2009 Di belahan Amerika Selatan, Guatemala juga memiliki masalah perbatasan dengan Belize. Atau Peru yang memiliki sengketa perbatasan laut dengan tetangganya, Bolivia. Dalam sejumlah kasus tersebut, seluruh Negara tersebut menjadi anggota organisasi regional yang sama. Terlepas dari sengketa yang ada di tingkat bilateral, sengketa dimaksud tidak mempengaruhi kerjasama di tingkat regional. Harus akurat Namun hal ini tidak berkaitan dengan fakta bahwa Negara-negara yang bersengketa menjadi anggota dari satu organisasi regional yang sama. Spanyol, misalnya memiliki sengketa kewilayahan dengan Inggris dalam masalah Gibraltar. Upaya penyelesaian di antara sesama anggota mapan Uni Eropa juga belum menuai hasil yang disepakati bersama. Perlu dipahami bahwa delimitasi perbatasan harus dilakukan secara lengkap dan akurat. Sifat komprehensif delimitasi batas Negara ini mengharuskan keterwakilan elemen dari berbagai keahlian teknis selain pakar hukum internasional. Ahli survei pemetaan dan ahli hidrographi dasar laut umumnya menjadi bagian dari tim negosiasi. Hal ini penting mengingat garis batas antar negara sekali disepakati bersifat final. Sesuai Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional 1969, perubahan fundamental (rebus sinc stantibus) - yang dalam situasi umum dapat diajukan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tidak berlaku dalam perjanjian perbatasan. Ketiadaan solusi atau kegagalan mencapai penyelesaian sengketa ini tidak berarti kegagalan Uni Eropa. Sebaliknya, kerjasama diantara Negara Uni Eropa anggota tetap solid dan dibuktikan antara lain dengan adanya common foreign policy. AS dan Kanada juga memilih pendekatan hukum melalui ICJ untuk menyelesaikan batas maritim di Gulf Maine. Ramifikasinya karena dalam banyak kasus, sengketa perbatasan cenderung merupakan konflik warisan kolonial. Sengketa atas Candi Preah Vihear yang berusia 900 tahun menjadi ilustrasi yang tepat. Intinya ketidakcocokan hasil survei tentang lokasi kuil dengan narasi konvensi yang menggunakan batas alamiah atau bukit/watershed. 7 Volume 01 ● Oktober 2009 Hasil survei Perancis di dalam Mixed Commission yang dibentuk pada 1904 menggambarkan Candi Preah Vihear sebagai bagian dari Kamboja. Sementara itu, Thailand berpegang kepada hasil pemetaan ahli Amerika yang memasukkannya sebagai bagian dari wilayahnya. Akses termudah mencapai candi memang berada di Thailand. Namun ICJ pada 1959 menetapkan bahwa pihak Siam telah memberikan persetujuannya secara diam-diam (aquiesence) terhadap peta hasil survei pihak Perancis karena tidak pernah mengajukan protes. OPINIO JURIS Salah satu ketentuan Treaty of Amity and Cooperation (TAC-1976) mensyaratkan pembentukan high council untuk menyelesaikan isu politik yang muncul diantara Negara anggota. Namun sejak awal telah dipahami bahwa wewenang high council tidak mencakup penyelesaian sengketa hukum terkait dengan klaim kedaulatan. Terlalu kompleks kiranya menyerahkan sengketa hukum kepada Dewan Tinggi ASEAN. Terlebih dalam kasus ultrasensitif yang berhubungan dengan klaim kepemilikan atas suatu wilayah. Solusi hukum Legalisasi politik international merupakan keniscayaan. Arus kuat globalisasi dan pemanfaatan ekonomis sumber daya alam yang terdapat dalam batas-batas wilayah Negara telah mendorong pragmatisme untuk mendahulukan proses judisial dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Opsi ini merupakan pendekatan realistis guna menjamin kepastian hukum. Robert Keohane mencatat bahwa kecenderungan yang sama juga terjadi dalam kerjasama Negara di berbagai organisasi internasional (Keohane : 2001). Hal ini berlaku untuk ASEAN. Meski awalnya ASEAN dikenal dengan ciri penyelesaian sengketa melalui musyawarah (consultation) dan mufakat (concensus), pengesahan ASEAN Charter mencerminkan kecenderungan ke arah legalisasi politis kerjasama diantara Negaranegara kawasan Asia Tenggara. 8 Fakta bahwa sejumlah Negara anggota ASEAN memiliki sengketa perbatasan sudah menjelaskan kearifan untuk tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada para anggota Dewan Tinggi. Hal ini pada gilirannya mencerminkan kedewasaan ASEAN untuk menghindari penyelesaian politis terhadap isu yuridis tentang overlapping claim of sovereignty. Karena itu, ASEAN tetap membuka opsi mekanisme penyelesaian damai atas sengketa kewilayahan secara hukum, baik yang prosedurnya longgar (arbitrasi) hingga cenderung ketat (ICJ dan ITLOS). Di antara berbagai lembaga judisial antarnegara tersebut, Mahkamah Internasional menempati posisi khusus. Tidak saja karena pengalamannya namun juga karena status hukumnya yang menjadi bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 Sepanjang periode pembentukannya, Mahkamah telah memutuskan 16 sengketa perbatasan. Sembilan kasus merupakan sengketa perbatasan (delimitasi batas maritim) dan tujuh sisanya menyoal status kepemilikan atas suatu wilayah/daratan, yakni: Sovereignty over certain frontier land (Belgia v. Belanda, 1957); Temple of Preah Vihear, 1959 (Thailand v. Kamboja); Land, Island and maritime frontier dispute, 1986 (El Salvador v. Honduras); Territorial dispute (Libya v. Chad) 1990; Kasikili/ Sedudu (Botswana v. Namibia, 1996); SipadanLigitan (Indonesia v. Malaysia, 1998). Terakhir pada Mei 2008, Mahkamah juga memutuskan sengketa antara Singapura dan Malaysia tentang status kepemilikan atas Pulau Pedra Branca. mengedepankan prinsip rule of law dalam hubungan antarnegara dengan pengajuan sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional. Langkah yang sama juga ditunjukkan Malaysia dan Singapura dengan membawa kasus Pedra Branca yang baru saja diputuskan Mahkamah, Mei 2008. Pilihan penyelesaian sengketa hukum melalui sistem hukum pada gilirannya menjadi bukti kedewasaan politik dalam menyikapi isu yang potensial menjadi sumber konflik terbuka dalam hubungan antarnegara. Sikap masyarakat internasional yang menghormati putusan Mahkamah Reputasi ICJ pada gilirannya memperkuat reputasinya sebagai lembaga judisial antarnegara yang independen dari aspek politis dalam penanganan perkara. Dengan telah disahkannya Piagam ASEAN, maka Negara-Negara ASEAN telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Piagam ASEAN. Pihak-pihak yang terkait dalam sengketa dapat meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN untuk bertindak ex-officio dalam rangka memberikan jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan, maka perkara ini akan diajukan ke level KTT ASEAN. Bersama-sama dengan Malaysia, kita pernah memberikan contoh positif untuk Komitmen kesediaan melaksanakan apapun hasil putusan Mahkamah pada gilirannya merefleksikan kedewasaan dalam mencari penyelesaian komprehensif yang bermartabat melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dipercaya dan kredibel. 9 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS KEUTUHAN WILAYAH NEGARA RI: PERSEPSI ANCAMAN DAN ANCAMAN NYATA Oleh: Haris Nugroho* I. PENDAHULUAN Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia yang merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 telah mengalami perjalanan dalam rentang waktu yang cukup panjang dalam menata dan terus membenahi kehidupan kenegaraannya. Setelah kemerdekaan tersebut bangsa Indonesia misalnya masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap wilayahnya yang sebagian besar merupakan perairan, setelah mencabut TZKMO (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) tahun 1939 produk penjajah Belanda yang membagi pulau-pulau Indonesia menjadi kantong-kantong wilayah yang dipisahkan oleh perairan internasional. Pada tanggal 13 Desember 1957 dalam menyatukan wilayah kepulauan Nusantara para pimpinan Negara kemudian sepakat untuk mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 4 Prp/Tahun 1960 yang mencakup titik-titik dasar, garis pangkal kepulauan wilayah RI sekaligus pulau-pulau kecil terluar. Namun demikian pengaturan sepihak tersebut tidak serta merta diakui oleh dunia internasional dan memerlukan perjuangan panjang di dunia diplomasi internasional sehingga pada akhirnya konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) mendapat * Penulis adalah Koordinator Fungsi Politik, KBRI London 10 pengakuan masyarakat dunia dengan dimasukkan dalam Bab IV, UNCLOS 1982. Dengan demikian Negara kepulauan sekarang ini telah menjadi suatu prinsip hukum internasional baru yang diperkenalkan oleh Indonesia. II. PERMASALAHAN 1. PERSEPSI ANCAMAN WILAYAH (the perceived threats and/or “fabricated threats”?) Apabila diamati secara mendalam, keberatan dunia internasional terhadap konsepsi negara kepulauan tidak terkait sama sekali dengan kepemilikan pulau-pulau di wilayah Nusantara oleh Indonesia yang tercantum dalam UU No.4 Prp/Tahun 1960, pada waktu itu, lebih kepada kekhawatiran negara-negara maritim besar, seperti AS, Inggris. Soviet serta negara-negara lainnya terhadap akses navigasi di perairan Nusantara yang menjadi perairan kepulauan yang tunduk sepenuhnya pada kedaulatan Indonesia. Namun demikian ada gejala di sekelompok tertentu di masyarakat Indonesia yang mempunyai perasaan ketakutan yang tidak mendasar akan diduduki atau dikuasainya pulau-pulau tertentu atau bagian wilayah Indonesia oleh negara tetangga. Berdasarkan fakta dan pengalaman sejarah belum pernah ada satu-pun negara asing OPINIO JURIS (external threats) yang ingin untuk menduduki, menguasai pulau, wilayah atau bagian dari wilayah NKRI yang berada dalam NKRI berdasarkan Deklarasi Djuanda dan UU No.4 Prp/Tahun 1960. Tidak ada satu negarapun dari tahun 1960 sampai sekarang ini yang pernah mengklaim kepemilikan RI atas pulaupulau yang ada dalam UU No. 4 Prp/Tahun 1960. Pulau Sipadan dan P. Ligitan misalnya tidak pernah masuk dalam deklarasi dan UU tersebut. Sehingga sulit bagi RI untuk memperkuat klaimnya. Demikian juga wilayah Timor Timur yang tidak pernah masuk dalam UU dimaksud. Masyarakat awam, yang tidak memahami hukum, biasanya akan sulit membedakan kasus-kasus diatas dengan pulau-pulau lain yang sudah jelas berada dalam kedaulatan RI dan mereka masih saja dibayang-bayangi rasa takut dan kekhawatiran yang tidak berdasar bahwa ada 12 pulau terluar yang rawan effectiveoccupation tanpa memahami arti dan makna prinsip hukum internasional tersebut. 2. ANCAMAN NYATA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA (the real-threats) Namun demikian apabila dikaji lebih jauh, terdapat ancaman nyata yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, yaitu ancaman separatisme dan dis-integrasi wilayah (internal threats). Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ancaman tersebut masih ada. Kita masih ingat perjuangan pengembalian Papua yang kita rebut dari tangan penjajah Belanda dan pemberontakan yang bersifat kedaerahan seperti PRRI/Permesta. Saat ini ancaman pemisahan wilayah dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu: Volume 01 ● Oktober 2009 1) Gerakan ilegal yang secara terangterangan melawan hukum (OPM, Aceh Merdeka, RMS); 2) Penyalahgunaan otonomi daerah yang akhirnya sulit dikontrol dan dikendalikan. Bahkan akhir-akhir ini ada sementara pihak yang menginginkan untuk membentuk provinsi kepulauan yang jelas-jelas tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dan apabila tidak ditangani secara hati-hati dapat mengarah kepada disintegrasi wilayah. Tindakan lain yang perlu diatur dan dikontrol adalah perusakan/penambangan pulau-pulau di perbatasan yang terdapat Titik Dasar untuk penetapan wilayah maritim dengan negara lain yang membahayakan integritas wilayah NKRI. S e b ag a i co n toh ad ala h h a mp ir tenggelamnya P. Nipa sehingga sampai saat ini memerlukan biaya yang amat besar untuk mereklamasi pulau tersebut. Di pulau tersebut terdapat titik dasar untuk penarikan batas maritim dengan Singapura, sehingga apabila tidak dilakukan reklamasi akan sangat merugikan posisi Indonesia dalam perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan Singapura. Selain itu penggunaan wilayah darat ataupun perairan Indonesia untuk latihan perang angkatan bersenjata negara lain juga merupakan tantangan lain kedaulatan dan integritas wilayah NKRI serta perlu untuk diatur sebagaimana mestinya sehingga Pemerintah RI bisa dengan tegas menegakkan segala peraturan perundangundangan yang terkait dengan wilayahnya. 11 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS PULAU MIANGAS: PERLUKAH KEKHAWATIRAN ITU? Oleh Irma D. Rismayati 1 melakukan beberapa pembangunan pos dan fasilitas pengamanan di Pulau Miangas. Sementara itu, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah mengupayakan pengembangan infrastruktur pulau tersebut, seperti pembangunan lapangan terbang, dan mengupayakan pelayaran yang dilakukan oleh PT. Pelni secara rutin. Beberapa waktu terakhir ini, surat kabarsurat kabar nasional memberitakan “klaim” Filipina yang mencantumkan Pulau Miangas (Las Palmas) sebagai salah satu tujuan wisata negara tersebut. Tak urung “klaim” ini membuat masyarakat “gerah” dan khawatir akan kehilangan Pulau Miangas. Menanggapi gencarnya ungkapan kekhawatiran masyarakat, beberapa instansi pemerintah terkait berupaya meredam kemungkinan meluasnya dampak berlebihan tersebut dan meyakinkan masyarakat bahwa “effective occupation” telah dilakukan di Pulau Miangas. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko menyatakan bahwa TNI telah 1. Penulis adalah Kasubag Dokumentasi, Setditjen HPI. 12 Gencarnya pembangunan infrastruktur di pulau tersebut dan penegasan kepemilikan Indonesia atas Pulau Miangas ditenggarai oleh kekhawatiran akan kehilangan satu lagi pulau dalam gugusan kepulauan nusantara ke tangan negara lain. Tampaknya trauma Sipadan Ligitan cukup membuat semua pihak merasa berkepentingan dalam mempertahankan pulau Miangas ini. Pulau Miangas terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanao Filipina. Pulau ini pernah menjadi sengketa antara Pemerintah Belanda (sebagai penjajah Indonesia) dengan Amerika Serikat (sebagai OPINIO JURIS penjajah Filipina). Secara geografis, posisi Pulau Miangas berada di 5° 34' 02'' Lintang Utara dan 126° 34' 54'' Bujur Timur terdapat pada TD No. 056 dan TR No. 056, telah terdaftar di Perserikatan BangsaBangsa sebagai pulau terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan milik sah Pemerintah Republik Indonesia.2 Oleh karena itu, masih perlukah kekhawatiran itu? Volume 01 ● Oktober 2009 kepemilikan sah pulau Miangas. Keputusan ini pulalah yang menjadi dasar hukum bahwa Miangas adalah milik Indonesia, sebagai penerus dari penguasaan Belanda di wilayah nusantara. Dengan adanya dasar hukum internasional yang kuat ini maka tindakan fisik negara lain seperti kunjungan, aktivitas bisnis, memasukkan dalam peta dan sejenisnya, tidak akan berarti apa-apa terhadap status kedaulatan Indonesia atas Pulau Miangas. Legalitas Kepemilikan Pulau Miangas Ada beberapa hal yang memperkuat kepemilikan Indonesia atas Pulau Miangas, baik legalitas maupun realitas. Pertama, dalam hukum internasional dikenal istilah “uti possidetis juris” atau wilayah suatu negara mengikuti wilayah kekuasaan penjajah atau pendahulunya. Berdasarkan prinsip hukum internasional tersebut maka Indonesia mewarisi wilayah nusantara yang sama dengan yang dikuasai oleh Belanda. Ini berarti termasuk Pulau Miangas. Kepemilikan Belanda atas pulau Miangas ditetapkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada tanggal 4 April 1928. Keputusan tersebut mengakhiri sengketa antara Belanda dengan Amerika Serikat terkait Kedua, klaim kepemilikan Indonesia atas Miangas telah tercantum dalam UndangUndang No. 4/Prp/1960, dan klaim tersebut tidak pernah mendapatkan protes dari negara manapun, termasuk Filipina. Ketiga, penegasan kepemilikan atas Miangas lebih lanjut dinyatakan dalam Protokol Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Filipina mengenai Definisi Wilayah Indonesia.3 Protokol perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Filipina, Carlos P. Romulo pada tanggal 10 Februari 1976 tersebut menegaskan bahwa “Indonesia adalah pemilik tunggal dari pulau yang dikenal dengan nama Pulau Miangas atau Las Palmas sebagai hasil putusan 2. Bakorsurtanal, Daftar Pulau-pulau Kecil Terluar, http://wwwbakorsutanal.go.id/upl_document/pucil/list% 20tabel.html, diakses 25 Februari 2009 3. Arif Havas Oegroseno, “Ada Apa dengan Miangas?”, Gatra, 25 Februari 2009. 13 Volume 01 ● Oktober 2009 Mahkamah Arbitrase Internasional pada tanggal 4 April 1928”.4 Keempat, secara fisik, Indonesia telah menguasai Pulau Miangas. Hukum dan administrasi pemerintahan Indonesialah yang berlaku di pulau tersebut. Penduduknya adalah warganegara Indonesia yang sehariharinya berbahasa Sanger. Hal ini berbeda dengan Sipadan dan Ligitan yang tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari wilayah, baik Belanda dan juga Inggris (sebagai penjajah Malaysia). Oleh karena itulah kasus Sipadan dan Ligitan berbeda dengan Miangas. Sipadan dan Ligitan awalnya adalah dua pulau ‘tak bertuan’, yang kemudian di klaim oleh Indonesia dan Malaysia. Atas sengketa tersebut, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia dinyatakan berhak atas kedua pulau itu, berdasarkan penguasaan efektif yang dilakukan Inggris terhadap kedua pulau tersebut melalui pemberlakuan hukum dan pemeliharaan. Mahkamah Internasional mendasarkan keputusannya kepada tindakan penguasaan efektif yang dilakukan sebelum tahun 1969. Sehingga tidak benar jika kemenangan Malaysia atas kasus ini dikarenakan pembangunan resort wisata di pulau-pulau tersebut, karena resort 4. Ibid 14 OPINIO JURIS di kedua pulau tersebut baru dibangun setelah tahun 1969. Namun demikian, pendirian resort tersebut telah menyalahi hukum karena pembangunannya dilakukan di pulau yang masih dalam sengketa. Pada kasus Sipadan-Ligitan, Indonesia memang kalah, tetapi bukan kehilangan pulau-pulaunya, karena sejak awal Sipadan-Ligitan memang bukan milik Indonesia. Potensi dan Tantangan Secara hukum, kekhawatiran akan kehilangan kedaulatan atas Pulau Miangas tidak beralasan. Lalu apakah yang perlu kita khawatirkan? Ancaman disintegrasi sebagai dampak dari pembangunan yang tidak merata. Kita perlu memahami bahwa pulau-pulau terluar nusantara tersebut memiliki aspek strategis terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus memunculkan tantangan disintegrasi apabila tidak dikelola secara baik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi mengingat sampai saat ini pembangunan di pulau-pulau terluar masih sangat terbatas bahkan beberapa diantaranya hampir tidak tersentuh. Sampai saat ini, pembangunan fisik dan non-fisik di pulau- OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 pulau terluar Indonesia ini pun masih sangat minim dan masih jauh dari harapan. Pembangunan dan pengembangan di pulaupulau terluar ini, terutama pada aspek ekonomi dan sosial akan berdampak terhadap nasionalisme masyarakat. Karena sekalipun tidak terkait dengan adanya kemungkinan kehilangan pulau-pulau tersebut, namun rapuhnya nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan akan berdampak negatif bagi keutuhan bangsa.5 Selain itu, dalam aspek keamanan berkaitan dengan maraknya kejahatan lintas negara, maka pembangunan, pengelolaan dan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar, termasuk Pulau Miangas ini menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara, seperti penyeludupan barang, manusia, dan narkoba, illegal logging dan illegal fishing serta jalur lintas kejahatan transnasional lainnya. Aspek strategis lainnya dari keberadaan pulau-pulau terluar ini adalah bahwa berdasarkan pulau-pulau inilah batas negara kita ditentukan. Sehingga merupakan suatu keharusan/mutlak bahwa pulau-pulau tersebut mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu menegaskan dan merealisasikan komitmen untuk mempercepat pengembangan pulaupulau terluarnya secara komprehensif, melalui berbagai pembangunan fisik dan non fisik, perbaikan infrastruktur dan menjadikan pulau-pulau terluar sebagai beranda nusantara. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik kepada penduduk Miangas, akan semakin menegaskan dan mengokohkan klaim atau okupasi kedaulatan negara Indonesia atas Pulau Miangas. 5. I Made Andi Arsana, “Miangas Island? No worries!”, The Jakarta Post, 3 Maret 2009, diakses melalui http:// www.thejakartapost.com/news/2009/03/03/miangas-island-no-worries.html tanggal 4 Maret 2009 15 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS MANUSIA PERAHU ROHINGYA: TANTANGAN PENEGAKAN HAM DI ASEAN Oleh Irma D. Rismayati 1 Pemberitaan terkait pengungsi suku minoritas Rohingya Myanmar mengundang perhatian masyarakat internasional, setelah ratusan manusia perahu yang melarikan diri dari Myanmar terdampar di Aceh dan mengungkapkan perlakuan buruk yang mereka terima selama berada di Thailand. Pada awal tahun 2009 lalu, Angkatan Laut Thailand telah menangkap manusia perahu Rohingya di perairan Andaman dan kemudian memaksa sekitar 1000 manusia perahu kembali ke laut dalam perahu-perahu tanpa mesin serta tanpa perbekalan air dan makanan yang memadai. International Organization for Migration (IOM) juga menemukan bukti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer Thailand tersebut. Tidak heran apabila kemudian Thailand menuai kritik dan kecaman dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Perlakuan militer Thailand tersebut tergolong tindakan tidak manusiawi bahkan untuk alasan penerapan hukum terhadap para pelanggar batas atau illegal entry sekalipun. Organization of the Islamic Conference (OIC) juga telah meminta Pemerintah Thailand untuk memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap manusia perahu sebagaimana yang tercantum dalam the 1951 UN Convention on Refugees. 1. Penulis adalah Kasubag Dokumentasi Setditjen HPI. 16 Kasus manusia perahu tersebut muncul ditengah-tengah kentalnya isu-isu HAM dan memunculkan pertanyaan mengenai kesungguhan negara-negara ASEAN dalam penegakan HAM dan pembentukan ASEAN Human Right Body. Penanganan kasus manusia perahu juga diwarnai berbagai perbedaan kepentingan negara-negara di kawasan. Bagi Thailand keberadaan manusia perahu Rohingya di wilayahnya adalah illegal dan merupakan bagian dari kejahatan penyeludupan dan perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan Thailand, Indonesia juga berpendapat bahwa gelombang pengungsian tersebut merupakan kegiatan human trafficking dan people smuggling. Namun, Pemerintah Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap penderitaan etnis Rohingya dan berupaya untuk mencari solusi terbaik sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. Myanmar sebagai negara asal, mengambil sikap tidak peduli terhadap nasib etnis minoritas tersebut dan bersikeras bahwa Rohingya bukanlah warganya. Sementara itu, Bangladesh sebagai negara miskin di kawasan Asia Selatan merasa terbebani dengan besarnya arus pengungsian dari Myanmar tersebut. Australia yang menjadi OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 salah satu negara tujuan berkepentingan dalam mencegah masuknya pengungsi dikarenakan alasan kepentingan keamanan nasionalnya. lebih mendekati bangsa Asia Selatan, dan sebagian dari mereka adalah keturunan Arab, Persia dan Pathan. Muncul pertanyaan bagaimana kasus ini akan ditangani, mekanisme apa yang dapat digunakan dalam penyelesaiannya? Bagaimana instrumen hukum dapat memberikan perlindungan terhadap manusia perahu ini? Baik Thailand maupun Indonesia menyadari bahwa manusia perahu ini memerlukan penanganan komprehensif yang melibatkan hampir semua negara di kawasan karena merupakan cross border issues. Selama bertahun-tahun mereka mendapatkan perlakuan buruk dan diskriminatif dari Pemerintah Myanmar, terlebih lagi paska operasi Militer King Dragon,2 yang telah memaksa mereka mengungsi ke Bangladesh. Menurut data Amnesti Internasional pada periode 1991-1992, kurang lebih 250 ribu orang Rohingya mengungsi dan memasuki wilayah Bangladesh. Sedangkan menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 28 ribu orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Ironisnya etnis muslim Rohingya tersebut tidak diakui baik oleh Myanmar maupun Bangladesh sebagai warg an ya. P e mer in tah Myan ma r menganggap orang Rohingya sebagai orang Bengali (Bangladesh) yang tinggal di Myanmar. Pemerintah Junta Militer Myanmar menyatakan bahwa sekalipun mereka tinggal di Arakan, Myanmar, tetapi etnis Rohingya bukanlah rakyat Myanmar dan tidak termasuk dalam salah satu dari 135 kelompok etnis yang tergabung dalam Uni Etnis Rohingya dan Perlakuan Diskriminatif Siapa etnis Rohingya ini? Bagaimana gelombang pengungsian etnis Rohingya bermula? Etnis Rohingya telah mendiami dua kota di Utara Negara Bagian Rakhine, yang dulu dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myamar. Etnis Rohingya secara fisik, bahasa dan budaya 2. Pada tahun 1978 Pemerintah Myanmar dibawah kepemimpinan Jenderal Ne Win melakukan operasi militer King Dragon di Negara bagian Rakhine (Arakan) dalam upaya memberantas para mujahidin di wilayah tersebut. Namun, operasi militer tersebut juga berdampak pada masyarakat muslim lainnya, terutama dari etnis Rohingya. 17 Volume 01 ● Oktober 2009 Myanmar.3 Pemerintah Myanmar juga tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya ini adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan atau stateless. Menurut Amnesti Internasional, orang Rohingya telah mengalami pende-ritaan yang cukup panjang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Junta Myanmar. Kebebasan orang Rohingya sangat dibatasi, mayoritas dari mereka tidak diakui kewarga-negaraannya. Mereka hanya sedikit dan bahkan tidak diberikan hak kepemilikan atas tanah dan rumah serta diperkerja paksakan pada sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur di Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan dan penghidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain adalah Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia dan Australia. Hingga pada awal tahun 2009 perhatian dunia internasional kembali tertuju pada etnis Rohingya ketika sekitar 1000 manusia perahu tersebut ditangkap pada saat akan memasuki wilayah Thailand. OPINIO JURIS Namun, menurut perwakilan UNHCR di Bangkok, meskipun tidak diketahui jumlah pastinya, setidaknya masih terdapat sekitar 78 orang Rohingya yang ditahan di Ranong, di bagian selatan Thailand dan belum dapat diketahui keadaannya apakah mereka juga memerlukan perlindungan internasional. Manusia Perahu Rohingya Perspektif Hukum Internasional dalam Pemerintah Thailand menyatakan bahwa manusia perahu Rohingya sebagai pelintas batas illegal dan dikategorikan sebagai migran ekonomi, bukan pencari suaka yang berhak mendapatkan status pengungsi. Namun, bagaimana kedudukan manusia perahu Rohingya ditinjau dari pandangan hukum? Ada 2 perangkat hukum internasional yang mengatur masalah pengungsi yaitu the 1951 UN Convention on Refugees dan the 1967 Protocol on Status of Refugees. Konvensi tersebut dalam artikel 1 butir A (2) mendefinisikan pengungsi4 sebagai: "A person who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to 3. Pernyataan dikeluarkan pada Press Realese Kemlu Myanmar pada 26/02/1992. Pernyataan tersebut ditegaskan lagi dalam Political Situation of Myanmar and its Role in the Region, Col. Hla Min, Office of Strategic Studies, Ministy of Defense of Myanmar, February 2001, p. 95-99. Pemberitaan Media Indonesia, 12/02/2009, hal 6, bahwa Perwakilan Pemerintah Myanmar di Hongkong melalui surat kabar setempat yang meminta agar masyarakat internasional, khususnya media untuk tidak menyebut etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. 4. The 1951 UN Convention on Refugees yang diamandemen dalam Protokol 1967. 18 OPINIO JURIS such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.." Menurut hukum internasional, pengungsi adalah orang yang berada di luar negara atau tempat tinggal asalnya, mengalami ketakutan terhadap penuntutan dikarenakan oleh ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau memiliki pandangan politik yang berbeda, dan tidak memiliki kewarganegaran dan tidak mampu atau tidak bersedia untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya dikarenakan adanya ketakutan tersebut. Sedangkan definisi migran menurut Pedoman Penetapan Prosedur dan Kriteria Pengungsi sesuai Konvensi tahun 1951 adalah orang yang, selain dari alasan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu dan perbedaan pandangan politik, secara sukarela meninggalkan negaranya untuk menetap di negara lain.5 Sedangkan motivasinya untuk berpindah tempat tinggal, adalah karena menginginkan perubahan atau petualangan, atau karena alasan keluarga maupun pribadi. Volume 01 ● Oktober 2009 Apabila secara khusus motivasinya adalah pertimbangan ekonomi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, maka orang tersebut adalah seorang migran ekonomi dan bukan termasuk kategori pengungsi.6 Namun, perbedaan antara migran ekonomi dengan pengungsi seringkali rancu dan tidak jelas. Memang bukanlah perkara yang mudah untuk menetapkan standar ukuran apakah ekonomi atau politik yang menjadi latar belakang atau motif dari perpindahan seseorang, karena bukan tidak mungkin apabila motif ekonomi tersebut dipengaruhi oleh isu rasial, agama atau politik yang dihadapi oleh satu kelompok tertentu di negara asalnya.7 Disamping itu, pada prakteknya, penentuan apakah orang tersebut adalah pengungsi atau bukan, seringkali diserahkan pada lembaga-lembaga atau badan-badan Pemerintah dari negara penerima, negara transit atau negara kedua. Akibatnya adalah terjadinya kecenderungan untuk menolak memberikan status pengungsi dan bahkan para pencari suaka tersebut seringkali diperlakukan sebagai pendatang illegal. Sehingga sulit untuk dapat menggaransi adanya suatu perlindungan bagi para pencari suaka tersebut. 5. Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protokol relating to the Status of Refugees paragraph 62, UNHCR document, Geneva, Januari 1992 6. Ibid 7. The distinction between an economic migrant and a refugee is, however, sometimes blurred in the same way as the distinction between economic and political measures in an applicant’s country of origin is not always clear...” Dikutip dari Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967Protokol relating to the Status of Refugees, UNHCR Publication, Jenewa, 1992 19 Volume 01 ● Oktober 2009 Seperti halnya manusia perahu Rohingya, lalu apakah dengan demikian mereka dapat dikategorikan sebagai pengungsi? Ada berapa fakta terkait manusia perahu tersebut, yaitu: pertama, etnis Rohingya jelas tidak diakui sebagai rakyat Myanmar (stateless). Pengertian stateless ini dinyatakan dalam artikel 1 the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons adalah “a person who is not considered as a national by any state under the operation of its law”. Kedua, mereka mengalami perlakuan diskriminatif dan rasis baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Secara ekonomi diskriminasi tersebut meliputi tidak diberikannya hak kepemilikan atas tanah dan rumah, pemberlakuan perbedaan dalam pengenaan pajak, dll. Secara sosial, Rohingya terdiskriminasi dengan adanya pembatasan ijin pernikahan dan akses pendidikan, serta terbatasnya ruang gerak mereka di Myanmar. Sedangkan secara politik mereka tidak diberikan status kewarganegaraan Myanmar. Ketiga, etnis Rohingya mengalami berbagai penyiksaan dan pelanggaran HAM dengan diperkerja paksakan, diberi upah minim dan bahkan tanpa upah diberbagai proyek pembangunan infrastruktur di Myanmar.8 Fakta lain mengatakan bahwa, Pemerintah Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan karena etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang tergabung dalam Uni Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap orang Rohingya sebagai bangsa pendatang dari Bengali-Bangladesh yang tinggal di Myanmar. OPINIO JURIS Secara hukum, orang Rohingya tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga Myanmar lainnya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Myanmar memberlakukan berbagai pembatasan di bidang ekonomi, sosial dan politik bagi etnis Rohingya. Fakta lainnya adalah dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka meninggalkan Myanmar untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik di negara lain atau dengan kata lain faktor ekonomilah yang menjadi motif pendorong utama. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut, di balik motif ekonomi dapat dikatakan etnis Rohingya di Myanmar mengalami berbagai tekanan sebagaimana yang tercantum pada artikel 1 Konvensi tentang Pengungsi atau dengan kata lain mereka mengalami perlakuan-perlakuan diskriminatif sehingga secara ekonomi etnis Rohingya tertekan. Berdasarkan ketentuan Konvensi tersebut, manusia perahu Rohingya berhak mendapat status pengungsi. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees paragraph 63, bahwa: …Behind economic measures affecting a person’s livelihood there may be racial, religious or political aims or intentions directed against a particular group. Where economic measures destroy the economic existence of a particular section of the population 8. Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Right Denied, Amnesty International, May 2004, AI Index: ASA 16/005/2004 http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/005/2004/en/dom-ASA160052004en.pdf. 20 OPINIO JURIS (e.g. withdrawal of trading rights from, or discriminatory or excessive taxation of, a specific ethnics or religious group), the victims may according to the circumstances become refugees on leaving the country. Konsekuensi dari butir diatas terhadap negaranegara yang menjadi tempat transit (negara kedua) atau negara tujuan (negara ketiga) sebagaimana tercantum dalam artikel 31 butir (1) adalah bahwa: The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, on refugees who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of article 1, enter or are present in their territory without authorization, provided they present themselves without delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or presence.9 Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah Thailand melanggar ketentuan tentang kewajiban suatu negara terhadap pengungsi. Selain itu, tindakan mendeportasi manusia perahu, khususnya Rohingya juga akan bertentangan dengan artikel 33 butir 1 Konvensi tentang Pengungsi yaitu: No Contracting States shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner Volume 01 ● Oktober 2009 where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.10 Sebagaimana ketentuan dalam hukum internasional lainnya, ketentuan tersebut mengikat seluruh negara yang menjadi pihak pada Konvensi tersebut. Sedangkan, kepada negaranegara non pihak, kewajiban-kewajiban perlindungan dan penanganan pengungsi lebih tergantung pada willingness dari negara non pihak tersebut. Sekalipun demikian, prinisip non legally binding untuk negara-negara non pihak pada Konvensi tersebut tidak serta merta menghapuskan kewajiban universal lainnya dalam memberikan perlindungan dan penegakan HAM. Indonesia dalam Upaya Penanganan Pengungsi Rohingya Sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk ikut menciptakan perdamaian dunia, menjaga ketertiban dunia, dan menghapus segala tindak penindasan, maka terlepas dari apakah manusia perahu tersebut adalah pengungsi yang berhak mendapatkan perlindungan atau pencari suaka bermotif ekonomi, secara moral, Indonesia sebagai negara kedua/transit wajib memberikan perlindungan kepada mereka, sampai statusnya jelas. Hal ini tercantum dalam UU Dasar 1945, Keputusan MPR. No.XVII/ MPR/1998, UU No. 39/1999 mengenai HAM, 9. Artikel 31 butir 1, Refugees Unlawfully in the Country of Refugeee, the 1951 UN Convention on Refugees, http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/o c ref.htm diakses pada tanggal 23 Februari 2009. 10. Artikel 33 butir 1 Prohibition of Expulsion or Return (“refoulement”), the 1951 UN Convention on Refugees, http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm, diakses pada tanggal 23 Februari 2009 21 Volume 01 ● Oktober 2009 dan UU No. 37/1999 mengenai Hubungan Luar Negeri yang menyiratkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan suaka dan perlindungan HAM. Keterlibatan Indonesia dan Thailand dalam penanganan manusia perahu Rohingya didasari oleh pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan rakyat Rohingya, perlindungan HAM dan solidaritas kesatuan ASEAN. Disamping itu, didasari oleh tekad untuk mengurangi, apabila dapat, menghentikan praktek kejahatan perdagangan dan penyeludupan manusia, khususnya dikawasan Asia Pasifik. Kebijakan Pemri jelas bahwa penanganan masalah Rohingya harus tuntas namun tidak mencederai hubungan bilateral dan regional (ASEAN). Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penanganan manusia perahu tersebut akan melibatkan negara asal, negara transit, negara tujuan negara-negara lain di kawasan serta lembaga internasional terkait (seperti antara lain UNHCR dan IOM). Mempertimbangkan latar belakang permasalahannya, kasus manusia perahu Rohingya tersebut sangat kompleks dan merupakan cross border issues, dan bukan semata-mata isu ekonomi. Sehingga dalam penanganannya tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua negara saja. Ada beberapa opsi pilihan dalam penanganan sekitar 400 manusia perahu yang terdampar di Aceh, antara lain adalah pertama, Indonesia segera mengembalikan (mendeportasi) manusia perahu tersebut, apabila dipandang negara asal akan menerima dan menjamin adanya perlindungan bagi mereka. Untuk itu, Indonesia perlu meng-engage Myanmar secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN dalam 22 OPINIO JURIS menjamin perlindungan HAM bagi etnis Rohingya. Mengkaitkan kasus pengungsian Rohingya dengan upaya penegakan HAM di ASEAN menjadi sangat krusial dan kemungkinan tidak akan terselesaikan dengan mudah. Myanmar menganggap HAM adalah isu sensitif dalam negerinya dan track record penegakan HAM Myanmar juga masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya, sementara pengungsian tersebut ditenggarai karena terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, Indonesia sebagai negara transit menetapkan status manusia perahu tersebut sebagai pengungsi. Dalam kaitan ini, Indonesia dapat meminta bantuan dan bekerjasama dengan IOM, UNCHR dan OCHA untuk mencarikan negara ketiga/tujuan. IOM dipandang sebagai lembaga internasional yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. IOM menangani isu-isu migrasi, termasuk people smuggling atau trafficking in person. Disamping itu, kerja IOM dalam menangani migrasi dinilai lebih cepat dan efektif, apalagi mengingat bahwa motif manusia perahu Rohingya diduga kuat adalah pencari suaka ekonomi. Namun, Pemri hendaknya tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan UNHCR dan OCHA dalam mencari pemecahan terbaik bagi penyelesaian kasus ini. Kasus Rohingya ini memperlihatkan masih lemahnya upaya penegakan HAM di ASEAN. Terkait upaya penegakan HAM, dalam konteks regional, mekanisme konsultasi ASEAN diharapkan dapat menjadi pilihan dalam menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap tindak pelanggaran HAM dan sekaligus menghentikan akar penyebab gelombang pengungsian tersebut. Pada tingkat OPINIO JURIS yang lebih luas, Indonesia, Thailand dan negaranegara ASEAN lainnya telah sepakat menggunakan pertemuan Bali Process, yaitu suatu forum tingkat menteri yang bertujuan untuk menetapkan dan mengambil langkahlangkah yang dibutuhkan dalam mengatasi isu-isu perdagangan manusia dan kejahatankejahatan antar negara lainnya di wilayah Asia-Pasifik, guna mencari penyelesaian terbaik dalam menangani kasus manusia perahu ini. Perbedaan tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang tajam di kawasan Asia Pasifik membuat gelombang migrasi irreguler sangat rentan terkait dengan tindak perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya. Untuk itu, melalui kerangka Bali Process diharapkan kasus-kasus yang timbul, baik itu perdagangan dan penyeludupan manusia maupun kejahatan transnasional lainnya dapat diselesaikan secara komprehensif sampai ke akar permasalahannya. Kesimpulan Migrasi etnis Rohingya ditenggarai bermotif ekonomi dan sarat akan isu pelanggaran Volume 01 ● Oktober 2009 HAM. Apapun motif dibalik migrasi tersebut, pelanggaran HAM yang terjadi maupun eksploitasi ekonomi harus diakhiri. Upaya menyelesaikan kasus pengungsian secara komprehensif harus melibat berbagai pihak, yaitu negara asal, negara transit dan negara penerima serta organisasi internasional terkait dan dilakukan melalui mekanisme yang ada, baik dalam kerangka ASEAN maupun Bali Process. Selain itu, dalam menghadapi perdagangan bebas, kasuskasus migrasi seperti Rohingya akan memunculkan tantangan bagi Indonesia, ASEAN dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Perdagangan bebas ASEAN akan semakin mendorong terjadinya migrasi penduduk di kawasan, dan apabila isu migrasi tidak ditangani dengan baik, maka akan rentan terhadap terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia, tindak kejahatan penyeludupan dan perdagangan manusia. Untuk itu, diperlukan upaya secepatnya dari negara-negara di kawasan untuk membenahi mekanisme dan instrumen hukumnya terkait mengenai pengaturan migrasi penduduk. 23 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI oleh: Syahda Guruh LS A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara dimana investasi dilakukan (host state) adalah kunci dari sistem perlindungan investasi yang ada di dalam perjanjian internasional di bidang investasi (International Investment Agreements (IIAs)) atau dikenal juga sebagai Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau Investment Guarantee Agreement (IGA). Oleh karena itu keberadaan klausula penyelesaian sengketa di dalam suatu IIAs telah menjadi inti dari kebijakan investasi khususnya di negara berkembang di bidang investasi dalam menjamin kepentingan investor. Keberadaan klausula penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Investasi membuka pilihan mekanisme dan forum bagi investor untuk menyelesaikan sengketa dengan pemerintah negara penerima investasi (host government). Mekanisme sebagaimana dimaksud dapat mengambil bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan atau pengajuan penyelesaian sengketa di pengadilan. Pilihan mekanisme dan forum sebagaimana dimaksud lazimnya secara eksplisit akan disebutkan dan diatur dalam perjanjian. B. Arbitrase Arbitrase adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution : 24 ADR) yang secara teknis dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pada forum arbitrase ini, para pihak yang bersengketa akan memilih satu orang atau lebih yang bertindak sebagai ”wasit” (disebut sebagai arbitrators atau arbiters atau arbitral tribunal) yang akan memberikan putusan yang disebut ”award”. Untuk dapat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa harus mengaturnya dalam perjanjian tertulis atau dalam klausula khusus tentang arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan melalui forum arbitrase ad-hoc atau diajukan ke lembaga arbitrase. Dalam konteks lembaga arbitrase, selain arbitrase nasional (contoh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)), penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada badan arbitrase international seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang dimiliki oleh Bank Dunia dan atau melalui United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Selain dua forum arbitrase dimaksud, dapat pula ditemukan penyelesaian sengketa investasi yang menggunakan forum arbitrase di luar organisasi internasional seperti Singapore International Arbitration Center (SIAC), Hongkong International Arbitration Center dan atau Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration. Selanjutnya, OPINIO JURIS apabila pihak yang bersengketa memilih salah satu forum arbitrase tersebut maka ketentuan dan aturan yang berlaku pada lembaga arbitrase dimaksud akan diterapkan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase pada dasarnya sangat menarik karena secara relatif terjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dapat dihindari adanya keterlambatan karena hal prosedural dan administratif; para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan; pengalaman serta latar belakang yang cukup me ngenai ma salah yang disengketakan, jujur dan adil; para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atau langsung dapat dilaksanakan. Namun demikian terdapat pula beberapa kelemahan arbitrase antara lain bila suatu arbitrase bersifat mandatory dan binding, maka para pihak yang bersengketa melepaskan hak untuk membawa sengketa ke Pengadilan. Selanjutnya, walaupun arbitrase seringkali dianggap lebih cepat, namun dengan adanya arbitrators yang beragam dan lebih dari satu dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan jadwal hearing yang berakibat pada kelambatan penyelesaian. Selain itu, pengaturan tentang hukum yang berlaku Volume 01 ● Oktober 2009 tidak selalu bersifat binding kepada arbitrator walaupun arbitrator tidak dapat mengabaikan hukum. walaupun terdapat kelemahan demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. C. Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Investasi melalui Arbitrase Sebagai negara yang berupaya menarik investasi asing, Indonesia setidaknya telah memiliki komitmen perlindungan investasi dalam kerangka Persetujuan P4M dengan 61 negara. Perlindungan investasi sebagaimana dimaksud salah satunya diwujudkan dalam rumusan klausula penyelesaian sengketa. Pada perjanjian-perjanjian tersebut, memang dibuka berbagai cara penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga klausula penyelesaian sengketa sedapat mungkin dapat terbuka, efisien dan mengakomodasi kemungkinan sengketa yang terjadi baik antara Investor vs Negara atau Negara vs Negara. Indonesia tercatat beberapa kali pernah melaksanakan penyelesaian sengketa terkait dengan investasi melalui forum arbitrase. Sebagai contoh dalam kerangka ICSID tercatat dua kali Indonesia melakukan penyelesaian sengketa di forum dimaksud, yaitu: Cemex Asia Holdings Ltd v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/04/3) tahun 2004 dan Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1) tahun 1981 – 1991. 25 Volume 01 ● Oktober 2009 Sesuai contoh tersebut, nampak bahwa penyelesaian sengketa investasi yang dibawa ke forum arbitrase internasional tidak selalu dapat menyelesaikan suatu sengketa secara singkat dan cost efficient. Bahkan kadangkala karena salah satu pihak dalam arbitrase merasa tidak puas terhadap award yang diberikan panel atau kesulitan dalam melakukan eksekusi award menyebabkan suatu sengketa akan berlangsung berlarut-larut. Dalam konteks hukum Indonesia, Arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui arbitrase nasional atau internasional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa dan diatur pula bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada ketentuan dan peraturan (rules and regulations) pada lembaga arbitrase yang disepakati para pihak yang bersengketa. Apabila suatu forum arbitrase telah memutuskan “award” kepada pihak yang bersengketa, maka sesuai hukum Indonesia award tersebut harus di daftarkan di Pengadilan untuk pelaksanaanya. Untuk award yang dikeluarkan oleh arbitrase nasional, award harus di daftarkan pada OPINIO JURIS pengadilan dimana tergugat berdomisili atau tempat dimana obyek sengketa berada. Apabila dalam penyelesaian sengketa investasi para pihak memilih forum arbitrasi internasional, maka pelaksanaan award dari arbitrase hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal pemerintah Indonesia menjadi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian melalui arbitrase, maka persetujuan Mahkamah Agung wajib dimintakan sebelum pelaksanaan award. Selanjutnya, keputusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia apabila lembaga arbitrase yang memutuskan suatu sengketa berada di salah satu negara pihak pada New York Convention. Dalam prakteknya terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan award dari arbitrase internasional dapat memperoleh perlawanan melalui pengadilan di Indonesia. Adanya kemungkinan tersebut pada satu sisi dapat dipahami sebagai upaya hukum lanjutan, namun disatu sisi dapat dinilai sebagai mengabaikan arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang. Syahda Guruh Langkah Samudra Kepala Seksi Perjanjian Perdagangan Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Sumber : Treaty Room Deplu 26 OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI Oleh : Clemens T. Bektikusuma1 Latar Belakang Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (RI)2 telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006 sebagai pengganti UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yang secara filosofis, yuridis dan sosiologis dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia. UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI secara filosofis dinilai masih mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan kurang memberikan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dan anak-anak.3 Ditinjau dari aspek yuridis, landasan konstitusional yang digunakan dalam pembentukan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sendiri dalam perkembangannya telah mengalami amandemen sebanyak empat kali, dimana di dalam perubahan-perubahan tersebut perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lebih dijamin.4 Secara sosiologis, UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dinilai juga tidak sesuai dengan perubahan jaman dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang lebih menghendaki adanya persamaan di depan hukum (equality before the law) serta kesetaraan gender. UU Kewarganegaraan hadir sebagai sebuah karya monumental yang dipandang telah merubah paradigma hukum kewarganegaraan di Indonesia. Melalui UU ini diharapkan sifat diskriminasi sebagaimana banyak terdapat dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dapat dihilangkan dan perlindungan maksimal dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada. Implementasi UU Kewarganegaraan di Luar Negeri Pengundangan dan pemberlakuan UU Kewarga- 1. Staf Dit. Perlindungan WNI/BHI 2. Selanjutnya disebut sebagai UU Kewarganegaraan. 3. Bdk. Pasal 1 UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, dalam pasal ini sifat patrilineal kental terasa dimana kewarganegaraan untuk anak-anak didasarkan pada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya (Pasal 1 huruf b). Hal ini menimbulkan suatu permasalahan tersendiri bagi wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan berkewarganegaraan asing, atau apabila anak yang bersangkutan ingin memiliki kewarganegaraan RI maka harus melalui proses naturalisasi yang relatif memiliki birokrasi rumit dan memakan waktu lama. 4. Bdk. Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk dan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. 27 Volume 01 ● Oktober 2009 negaraan di Indonesia di dalam negeri disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Antusiasme terutama dirasakan di kalangan wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Hal ini dinilai wajar mengingat anak hasil pernikahan beda kewarganegaraan ini bisa mendapatkan fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas.5 Dengan adanya fasilitas ini, wanita Indonesia yang melakukan pernikahan beda kewarganegaraan tidak perlu khawatir akan status kewarganegaraan RI anaknya. Bagi anak-anak hasil pernikahan beda kewarganegaraan yang lahir sebelum diundangkannya UU Kewarganegaraan, mereka juga dapat memanfaatkan fasilitas ini hingga 31 Juli 2010 sesuai dengan Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Pasca diundangkan dan diberlakukannya UU Kewarganegaraan, implementasi UU Kewarganegaraan di dalam negeri berjalan dengan lancar, namun sayangnya hal yang sama tidak terjadi pada implementasi UU Kewarganegaraan di luar negeri. Dalam prakteknya terdapat banyak permasalahan yang ditemui dalam implementasi UU Kewarganegaraan, termasuk di dalamnya kesulitan dalam implementasi fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil pernikahan beda kewarganegaraan. Selain fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas, UU Kewarganegaraan juga memberikan fasilitas lain, yakni fasilitas perolehan kembali kewarganegaraan OPINIO JURIS RI bagi warganegara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan RI-nya dengan batas waktu hingga 31 Juli 2009.6 Namun demikian, seperti halnya implementasi faslitas kewarganegaraan ganda terbatas, pelaksanaan fasilitas ini juga menemui hambatan dalam pelaksanaannya di luar negeri. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagai institusi yang menjadi ujung tombak implementasi UU Kewarganegaraan di luar negeri, ternyata dalam prakteknya di lapangan menemukan banyak hambatan, mulai dari intepretasi pasal-pasal di dalam UU Kewarganegaraan, sulitnya pemenuhan syarat-syarat formil oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, lambatnya respon Departemen Hukum & HAM (Depkumham) dalam menangani masalah kewarganegaraan di luar negeri, hingga muatan politis dalam masalah kewarganegaraan di luar negeri.7 Peran Ditjen HPI dalam Optimalisasi Implementasi UU Kewarganegaraan Mengingat banyaknya hambatan dalam implementasi UU Kewarganegaraan di luar negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) melalui Direktorat Hukum, melaksanakan beberapa langkah guna optimalisasi pelaksanaan UU Kewarganegaraan. 5. Lihat Pasal 6 UU Kewarganegaraan. Fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas adalah fasilitas yang diberikan kepada anak-anak hasil dari pernikahan wanita yang berkewarganegaraan Indonesia dengan suami berkewarganegaraan asing hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Setelah anak tersebut berumur 18 tahun, yang bersangkutan memiliki waktu tiga tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan, apakah kewarganegaraan ibu atau ayah, yang akan disandangnya. 6. Pasal 42 UU Kewarganegaraan 7. Beberapa masalah kewarganegaraan di luar negeri yang mengandung muatan politis antara lain masalah perolehan kembali kewarganegaraan RI oleh mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid). Khusus untuk kasus-kasus tersebut, seringkali proses perolehan kembali kewarganegaraan RI tidak segera direspon oleh Depkumham, sehingga menjadi berlarutlarut. Selain itu, dalam beberapa kasus, para mantan anggota gerakan seperatis maupun Mahid seringkali menolak untuk memenuhi persyaratan pendaftaran perolehan kembali kewarganegaraan RI dengan alasan mereka tidak pernah merasa kehilangan kewarganegaraan RI-nya, padahal secara hukum, berdasarkan Pasal 17 huruf k UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, yang bersangkutan telah kehilangan kewarganegaraan RI-nya. 28 OPINIO JURIS Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi: (1) melakukan kajian terkait dengan kasus-kasus kewarganegaraan yang dihadapi Perwakilan RI; (2) melakukan koordinasi dengan Depkumham serta; (3) bersama dengan Depkumham melaksanakan evaluasi serta diseminasi informasi secara intensif dan ekstensif langsung ke beberapa negara. Dalam praktek di lapangan, Perwakilan RI banyak menemukan kesulitan dalam melaksanakan fasilitas kewarganegaraan ganda serta perolehan kembali kewarganegaraan RI, khususnya dalam intepretasi pasal-pasal UU Kewarganegaraan untuk diimplementasikan dalam kasus-kasus tertentu. Guna menanggulangi hal ini, Direktorat Hukum selalu memberikan kajian terhadap kasus-kasus kewarganegaraan yang dihadapi oleh Perwakilan RI. Kajian-kajian tersebut kemudian disampaikan kembali kepada Perwakilan RI terkait dan dijadikan dasar untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang berkembang, sehingga tidak ada kasus kewarganegaraan yang diproses secara berlarut-larut. Hambatan lain yang dihadapi di dalam memproses masalah-masalah kewarganegaraan di luar negeri adalah lambatnya respon Departemen Hukum dan HAM di dalam memproses pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas dan perolehan kembali kewarganegaraan RI sehingga pengurusan masalah kewarga-negaraan menjadi memakan waktu yang lama.8 Untuk menanggulangi permasalahan ini, Direktorat Hukum mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan Depkumham secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil yang dicapai Volume 01 ● Oktober 2009 sangat positif, proses pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas dan perolehan kembali kewarganegaraan RI yang pada awalnya memakan waktu lebih dari enam bulan, saat ini dapat diproses dalam waktu kurang dari tiga bulan. Guna lebih meningkatkan pemahaman Perwakilan RI di luar negeri terhadap implementasi UU Kewarganegaraan, Tim Ditjen HPI beserta Depkumham juga melakukan evaluasi serta diseminasi informasi secara intensif dan ekstensif langsung ke beberapa negara; yang meliputi: (1) Amerika Serikat pada tanggal 12 Juli 2008 yang mencakup seluruh Perwakilan RI di Amerika Utara, Tengah dan Selatan; (2) Belanda pada tanggal 19-20 September 2008 yang mencakup seluruh wilayah di Eropa Barat; dan; (3) Jepang pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2008 yang meliputi wilayah Asia Pasifik dan Australia. Tim ini langsung dipimpin sendiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Bapak Andi Mattalata untuk memberikan kebijakan-kebijakan teknis sekaligus menyelesaikan secara langsung kasus-kasus kewarganegaraan RI di luar negeri. Kehadiran Tim ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan UU Kewarganegaraan di luar negeri, penyelesaian permasalahan-permasalahan kewarganegaraan, sekaligus melakukan diseminasi informasi secara langsung ke beberapa negara terkait dengan kebijakankebijakan terbaru UU Kewarganegaraan. Kehadiran Tim di beberapa negara ini mendapat tanggapan positif dari PerwakilanPerwakilan RI di luar negeri, khususnya para Pelaksana Fungsi Konsuler, dan dimanfaatkan sebagai ajang untuk menggali informasi 8. Masalah kewarganegaraan di Depkumham ditangani oleh Direktorat Tata Negara, termasuk di dalamnya pemrosesan kewarganegaraan ganda terbatas dan perolehan kembali kewarganegaraan RI. 29 Volume 01 ● Oktober 2009 mengenai hukum kewarganegaraan dan kesempatan untuk mendapat arahan dan kebijakan secara langsung dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan masalahmasalah kewarganegaraan di luar negeri. Permasalahan kewarganegaraan di luar negeri hingga saat ini tetap menjadi salah satu perhatian utama. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dalam beberapa waktu dekat Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Kewarganegaraan merupakan syarat mutlak bagi masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi ini, tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Kewarganegaraan juga erat kaitannya dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Perwakilan RI untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Tanpa status kewarganegaraan RI yang jelas, Perwakilan RI di luar negeri tentu akan sulit menjalankan fungsi perlindungannya. Meskipun UU Kewarganegaraan ini dapat dinilai sebagai sebuah karya monumental, namun UU ini juga tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan yang terdapat di dalam UU ini adalah tidak ditekankannya kewajiban masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri untuk berhubungan dengan Perwakilan RI di luar negeri.9 Keadaan ini, tentu akan mempersulit Perwakilan RI untuk melaksanakan fungsi OPINIO JURIS pemantauan dan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Pengamatan Direktorat Hukum Implementasi UU Kewarganegaraan di luar negeri merupakan salah satu wujud perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. UU Kewarganegaraan memang banyak merefleksikan perubahan yang bersifat positif dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Persamaan di depan hukum (equality before the law) serta kesetaraan gender, merupakan dua hal yang sangat ditonjolkan di dalam UU ini. Walaupun banyak hal positif yang dapat digali dari UU Kewarganegaraan, namun tidak dapat disangkal bahwa terdapat pula kekurangan-kekurangan di dalamnya, khususnya dalam pelaksanaannya di luar negeri. Untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan yang ada, Departemen Luar Negeri, khususnya Ditjen HPI dan Perwakilan RI di luar negeri akan senantiasa mengembangkan kemampuan dalam menghadapi setiap permasalahan kewarganegaraan di luar negeri. Koordinasi antar departemen, khususnya dengan Departemen Hukum dan HAM sebagai focal point dari pelaksanaan UU Kewarga-negaraan di Indonesia, juga akan terus ditingkatkan. Seluruh upaya ini dilakukan guna meningkatkan upaya perlindungan Departemen Luar Negeri kepada warga negara Indonesia di luar negeri. 9. Bdk. Ketentuan Pasal 23 huruf i UU Kewarganegaraan, di dalam pasal tersebut tidak ada sanksi tegas bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak melaksanakan lapor diri kepada Perwakilan RI. 30 OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION Oleh: Sahadatun Donatirin* Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (VCCR) menyebutkan bahwa petugas konsuler dari suatu perwakilan konsuler memiliki kebebasan berkomunikasi dengan warga negaranya serta memiliki akses terhadap mereka, demikian pula sebaliknya bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan yang sama untuk berkomunikasi dan memiliki akses kepada petugas konsuler negaranya. Apabila ia menghendaki, maka otoritas yang berwenang dari negara penerima harus menginformasikan perwakilan konsuler negara pengirim tanpa ditunda jika warga negara dari negara pengirim tersebut ditangkap atau ditahan atau dalam proses persidangan atau ditahan atas dasar lainnya (consular notification). Sehubungan dengan hal tersebut, petugas konsuler berhak untuk mengunjungi warga negaranya yang berada di tahanan, untuk melakukan komunikasi atau korespondensi untuk mengatur pemberian bantuan hukum (consular assistance), namun petugas konsuler tidak dibenarkan bertindak untuk dan atas nama warga negaranya, jika warga negara tersebut tidak menginginkannya. Kerahasiaan pribadi adalah hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui di dalam UN Declaration of Human Rights, the International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan juga di perjanjian internasional maupun regional lainnya. Kerahasiaan pribadi merupakan pendukung bagi martabat manusia dan nilai lainnya seperti kebebasan berorganisasi dan kebebasan berpendapat, yang telah menjadi isu hak asasi manusia di zaman modern ini. Hampir di setiap negara mencantumkan ketentuan mengenai kerahasiaan pribadi di dalam Konstitusinya. Bagi negara yang tidak mencantumkan kerahasiaan pribadi secara eksplisit dalam Konstitusinya, misalnya Amerika Serikat, Irlandia dan India, ketentuan mengenai kerahasiaan pribadi biasanya diatur dalam pengaturan yang lain (Privacy Act), atau sudah banyak negara yang menerima dan menjadi pihak dalam ICCPR. Sedangkan untuk kawasan Eropa telah memilki European Convention on Human Rights yang telah diadopsi menjadi hukum nasional bagi negaranegara di Eropa. Negara yang memiliki Privacy Act ataupun yang mencantumkan perlindungan kerahasiaan pribadi di dalam Konstitusinya memberikan perlindungan yang ketat akan kerahasiaan pribadi sesorang. Kerahasiaan pribadi ini tidak hanya berarti bahwa informasi pribadi sesorang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi juga memberikan perlindungan bahwa seseorang memiliki kontrol terhadap informasi pribadinya, baik kuantitas maupun kualitas dari informasi tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, petugas konsuler kerap kali tidak memperoleh informasi (consular notification) mengenai warga negaranya yang memiliki masalah hukum (ditahan, dalam proses persidangan * Penulis adalah Kasi Ketenagakerjaan pada Direktorat Perjanjian Ekososbud, Ditjen HPI, Deplu 31 Volume 01 ● Oktober 2009 atau alasan lainnya) di wilayah akreditasinya, jika warga negaranya tersebut tidak menginginkan keberadaannya diketahui oleh orang lain, termasuk perwakilan diplomatik/konsuler negaranya. Hal ini dimungkinkan dengan adanya ketentuan VCCR pasal 36 ayat (1b) dan dapat diperkuat bila negara tersebut memiliki pengaturan mengenai Privacy Act. Dalam praktek Hukum Internasional, consular notification dapat menjadi bersifat wajib/mandatory apabila terdapat perjanjian bilateral antara negara pengirim dan penerima, sehingga ‘right of privacy’ orang tersebut berdasarkan Pasal 36 VCCR dapat dikesampingkan. Mandatory Consular Notification (MCN) bertujuan agar seseorang dapat memperoleh bantuan kekonsuleran dari perwakilan diplomatik/ konsuler negaranya jika yang bersangkutan mengalami permasalahan hukum di negara penerima. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemri mulai mengadakan penjajagan dengan negara sahabat untuk mengadakan perjanjian bilateral di bidang MCN yang bertujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, dimana hal ini merupakan amanat dari UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Bab V mengenai Perlindungan WNI. Saat ini, konsentrasi pemerintah ditujukan pada negara-negara yang konsentrasi WNI terdapat dalam jumlah besar, misalnya Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, 32 OPINIO JURIS Australia dan lainnya. Namun demikian, tidak semua negara mitra memberikan respon positif atas proposal kerjasama MCN ini. Sejauh ini, baru Brunei Darussalam yang memberikan tanggapan atas draft yang diajukan oleh Pemri. Pada umumnya, keengganan negara mitra untuk memberikan tanggapan atas draft yang diajukan Pemri karena dalam hukum kebiasaan internasional, consular notification adalah praktek yang telah dilaksanakan secara universal berdasarkan VCCR, bahkan bagi warga negara dari negara yang bukan merupakan pihak VCCR. Disamping itu, prinsip perlindungan atas kerahasiaan pribadi (privacy) haruslah dijunjung tinggi sesuai dengan UN Declaration of Human Rights, ICCPR serta perjanjian internasional dan regional sejenis lainnya. Pengungkapan informasi pribadi seseorang (disclosure of personal information) tanpa seizin yang bersangkutan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia sesorang. Dan bagi negara yang memiliki Privacy Act, dengan adanya perjanjian bilateral MCN, dimana rights of privacy seseorang dapat dikesampingkan demi consular notification, hal ini dirasa sebagai hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional negaranya. Untuk itu, upaya Pemri untuk mengadakan perjanjian bilateral di bidang MCN masih menghadapi ujian dimana Pemri harus dapat meyakinkan negara mitra untuk bersedia mengadakan kerjasama di bidang MCN yang bertujuan meningkatkan upaya perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 PRAKTEK PERGESERAN DOKTRIN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DIHADAPAN YURISDIKSI PENGADILAN NEGARA PENERIMA : SENGKETA & KONTRAK KERJA Oleh : Soeharyo Tri Sasongko1 Pendahuluan Pada dekade belakangan ini, beberapa Perwakilan RI kembali disibukkan oleh gugatan sengketa ketenagakerjaan yang diajukan pada Pengadilan domestik Negara Penerima. Tak hanya muncul di Perwakilan Diplomatik dengan wilayah akreditasi negara-negara dengan perlindungan buruh yang tergolong maju seperti kawasan Eropa Barat, kasus sengketa ketenagakerjaan juga terjadi pada Perwakilan Diplomatik dengan wilayah akreditasi negara berkembang seperti di Kenya dan Brazil. Munculnya kasus-kasus gugatan kepada Perwakilan RI pada Pengadilan domestik Negara Penerima ini tak urung menimbulkan pertanyaan mendasar, sampai sejauh mana hukum internasional dan praktek negara-negara memberikan kekebalan kepada Perwakilan Diplomatik atas yurisdiksi Pengadilan domestik Negara Penerima dalam konteks sengketa ketenagakerjaan. Konsepsi Dasar Kekebalan Perwakilan Diplomatik Berbicara pemberian kekebalan dan hak istimewa (Privileges and Immunities) suatu Perwakilan Diplomatik dan Konsuler tentu saja tidak terlepas dari imunitas suatu Negara berdaulat yang menjadi dasar dari legal reasoning pemberian keistimewaan-keistimewaan tersebut. Dasar-dasar pemberian Privileges and Immunities terhadap Perwakilan Diplomatik suatu negara berdaulat terbagi dalam 3 (tiga) teori: a. Teori Eksteritorialitas; Berdasarkan teori eksteritorialitas ini, maka pemberian Privileges and Immunities ini didasarkan pada pandangan bahwa Pejabat Diplomatik maupun Perwakilan Diplomatik seolah-olah tidak pernah meninggalkan negaranya. b. Teori Representatif; Berdasarkan teori ini, maka pemberian Privileges and Immunities didasarkan pada pandangan bahwa Pejabat dan Perwakilan Diplomatik asing berada pada wilayah Negara Penerima dalam kapasitas sebagai wakil Negara Pengirim dan Kepala Negaranya. c. Teori Kebutuhan Fungsional. Teori ini berpandangan bahwa pemberian Privileges and Immunities semata-mata hanya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para Pejabat dan Perwakilan Diplomatik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan lancar. Dari ketiga teori tersebut, maka teori yang terakhir merupakan teori yang diadopsi dalam The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations sebagaimana termaktub dalam Paragraf 4 bagian Pembukaan sebagai berikut: 1. Penulis adalah Staf Direktorat Hukum. 2. Dr. Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Penerbit PT. Alumni. Hlm 547-548. 33 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing states. 3. No measures of execution to be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs 1 of this Article and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability his or of his residence. Sebagai pedoman utama hubungan diplomatik antar negara di dunia, The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, khususnya Pasal 31, mengatur pemberian kekebalan (pejabat) diplomatik atas yurisdiksi Pengadilan Negara Penerima sebagai berikut: 4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving state does not exempt him from the jurisdiction of the sending state. Article 31 Immunity From Jurisdiction 1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of: (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving state, unless he holds it on behalf of the sending state for the purposes of the mission; (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending state; (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving state outside his official functions. 2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness. 34 Mencermati rumusan Pasal 31 The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations tersebut, tampak bahwa pada eranya para perumus Konvensi ini belum menyadari potensi conflict of laws yang menimbulkan urgensi pengaturan lebih detil masalah ketenagakerjaan sebagai bagian “rumah tangga” suatu Perwakilan Diplomatik. Terlepas dari kekebalan atas yurisdiksi Pengadilan Negara Penerima, para perumus Konvensi juga menyadari bahwa setiap pejabat diplomatik asing wajib menghormati hukum dan peraturan negara setempat sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 Konvensi tersebut. Pergeseran Doktrin Kekebalan Perwakilan Diplomatik Dalam memahami doktrin kekebalan Perwakilan Diplomatik perlu dipahami bahwa Kekebalan suatu Perwakilan Diplomatik bersumber dari konsep imunitas suatu negara berdaulat. Dalam konteks hukum internasional, Kekebalan itu sendiri perlu dibedakan antara “kekebalan atas yurisdiksi” (Immunity from Jurisdiction) dan “kekebalan atas kekuatan eksekutorial” (Immunity from Enforcement Measures). Pembedaan tersebut menjadi menonjol ketika pada pertengahan abad ke XX ketika negara-negara di dunia OPINIO JURIS khususnya pada kawasan Eropa Barat mulai beralih dari mainstream Absolute Privileges and Immunities (Imunitas Mutlak) menjadi Restrictive Privileges and Immunities (Imunitas Terbatas) dalam konteks kekebalan atas yurisidksi, namun belum sepenuhnya beralih dalam konteks kekebalan atas kekuatan eksekutorial. Ketidak-konsistenan pada peralihan mainstream tersebut disebut sebagai “the last bastion of state immunity.3 Berdasarkan praktek pergeseran mainstream tersebut, kini dalam konteks Hukum Internasional dikenal adanya 2 (dua) doktrin dalam pemberian Privileges and Immunities terhadap Perwakilan Diplomatik, yaitu: a. Absolute Privileges and Immunities (Imunitas Mutlak) yang merupakan hak istimewa dan kekebalan yang melekat pada negara untuk melaksanakan tugas terkait dengan fungsinya (fungsi pelayanan publik). Dengan demikian hak istimewa dan kekebalan diberikan dalam rangka menjalankan foreign state’s public functions atau acts performed in the interest of a public service; dan b. Restrictive Privileges and Immunities merupakan hak istimewa dan kekebalan yang melekat pada negara namun dibatasi atas dasar perbuatan hukum di luar dari pelaksanaan fungsi pelayanan publiknya, karena terkait dengan transaksi komersial (commercial transaction) seperti transaksi (kontrak) keuangan, transaksi (kontrak) jual-beli, transaksi (kontrak) sewamenyewa. Volume 01 ● Oktober 2009 Kedua doktrin sebagaimana tersebut dalam uraian di atas pada dasarnya merupakan cerminan dari dua azas Hukum internasional tentang Foreign Sovereign Immunity, yaitu acta iure imperii yaitu aktivitas Publik yang dilaksanakan oleh suatu negara/institusi ketatanegaraannya, dan acta iure gestionis yaitu aktivitas komersial yang dilaksanakan oleh suatu negara/institusi ketatanegaraannya.4 Terjadinya perbedaan penerapan doktrin Immunity terhadap Perwakilan Diplomatik oleh beberapa Negara Penerima di wilayah Eropa Barat mulai menimbulkan konsekuensi conflict of laws. Beberapa Perwakilan Diplomatik asing masih berpedoman pada doktrin imunitas mutlak (absolute immunity) dan acta iure imperii berkaitan dengan masalah sengketa ketenagakerjaan termasuk masalah kontrak kerja. Sedangkan saat ini terdapat kecenderungan negara-negara di wilayah Eropa Barat, yang menganggap masalah sengketa ketenagakerjaan dan kontrak kerja termasuk dalam ranah doktrin imunitas terbatas (restrictive immunity) dan acta iure gestionis. Berdasar doktrin imunitas terbatas ini, apabila terjadi sengketa ketenagakerjaan dan kontrak kerja yang berkaitan dengan Warga Negara setempat ataupun Warga Negara Asing yang memiliki territorial nexus dengan Negara Penerima, Perwakilan Diplomatik harus menerima dan mengakui hukum ketenagakerjaan dan yurisdiksi pengadilan setempat. Praktek yang terjadi, ketika tuntutan Warga Negara setempat ataupun Warga Negara Asing 3. August Reinisch, 2006, European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures, The European Journal of International Law Vol. 17 No. 4, Hlm. 804. 4. Hazel Fox QC, 2002, The Law of State Immunity, New York, The Oxford International Law Library, Hlm. 272. 35 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS yang memiliki territorial nexus dengan Negara Penerima sampai ke pengadilan setempat dan Perwakilan Diplomatik konsisten untuk tidak hadir/ikut dalam proses litigasi, Pengadilan Negara Penerima yang menganut doktrin imunitas terbatas cenderung untuk memenangkan tuntutan tersebut melalui putusan in absentia. Apabila Perwakilan Diplomatik tetap tidak mengindahkan putusan tersebut, pengadilan akan melakukan upaya paksa eksekusi dengan cara membekukan / memblokir rekening Perwakilan Diplomatik yang terdapat pada negara tersebut. Pada beberapa negara Eropa, saat ini terdapat kecenderungan munculnya peraturanperaturan perburuhan yang lebih melindungi tenaga kerja setempat. Terhadap pola hubungan kerja pegawai setempat dengan Perwakilan Diplomatik asing, baik yang berkewarganegaran asing maupun yang berkewarganegaraan setempat, Kementrian Luar Negeri setempat telah menyebarkan edaran yang menyatakan bahwa kontrak kerja antara Perwakilan Diplomatik asing dengan pegawai setempat harus sesuai dengan standar dan peraturan perburuhan setempat. Penyebaran edaran sejenis tersebut terjadi di Italia dan Spanyol. Dengan adanya edaran tersebut, maka doktrin imunitas terbatas (restrictive immunity) dan acta iure gestionis semakin nyata dipraktekkan negara-negara tersebut. Praktek Penerapan Kekebalan Yurisdiksi Pengadilan di Eropa atas Pada dasarnya sebagian besar Pengadilan domestik negara Eropa menerapkan restrictive immunity sebagai dasar dalam menerapkan prinsip nonimmunity dalam hal sengketa ketenagakerjaan dan kontrak kerja dengan Perwakilan Diplomatik asing. Hal tersebut tercermin dalam beberapa putusan sebagai berikut5: putusan Spanish Supreme Court (Tribunal Supremo) pada “Emilio MB (individual) v. Embassy of Guinea Equatorial (State)”, tanggal 10 Februari 1986; putusan Austrian Supreme Court (Oberster Gerichtshof) dalam French Consular Employee (individual) v. France (state), tanggal 14 Juni 1989; putusan Tribunal de Relacao de Lisboa-Appeal pada Maria Aparecida Pereira de Melo Cunha Brazao (individual) v. Brazilian Embassy and Republic of Brazil (State), tanggal 13 Desember 2000; dan putusan Cour du Travail de Bruxelles pada Queiros Magalhaes Abrantes v. Portugal (State) tanggal 22 September 1992. Namun demikian, dalam pengimplementasiannya, beberapa Pengadilan domestik negara Eropa tetap berusaha mencari keseimbangan dari penerapan restrictive immunity dengan status Privileges and Immunities yang dimiliki oleh Pejabat dan Perwakilan Diplomatik. Penerapan konsep absolute immunity pada perkara sengketa ketenagakerjaan tersebut diantaranya terlihat pada beberapa putusan Pengadilan domestik negara Eropa sebagai berikut6: putusan the United Kingdom Court of Appeal’ pada “Ahmed v. Government of the Kingdom of Saudi Arabia”, tanggal 6 Juli 1995; Putusan Irish Supreme Court’s pada “the Government of Canada v. Brian Burke”, tanggal 12 March 1992; Putusan Italian Supreme Court of Cassation’s pada “Malta (state) v. Dalli (natural person), tanggal 15 5. Ulrike Kohler, State Immunity regarding Employment Contracts on State Practice Regarding State Immunities, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, Hlm. 78-80. 6. Ibid, Hlm. 81-83. 36 OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 March 1989; dan Putusan Finnish Supreme Court’s pada “Hanna Heusala (individual) v. Republic of Turkey (state)”, tanggal 30 September 1993.7 Sebagaimana tergambar dalam contoh-contoh yurisprudensi di atas, berkaitan masalah sengketa ketenagakerjaan dan kontrak kerja, putusan pengadilan di Eropa masih tetap bervariasi. Hakim pada pengadilan di Eropa masih mempertimbangkan variabel-variabel di sekitar hubungan kerja yang terjadi. Variabel tersebut antara lain: lokasi Perwakilan Diplomatik / Konsuler; bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan; status dari pekerja; obyek tuntutan; unsur security; kewarganegaraan dan tempat tinggal pekerja itu sendiri. Perkembangan Kontemporer Hukum Internasional terkait Instrumen Pada dasarnya hukum internasional yang mengatur tentang Imunitas Negara (State Immunity) bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang mengkodifikasikan praktek-praktek yang menonjol pada negaranegara di dunia. Perjanjian multilateral pertama yang khusus mengatur masalah State Immunity secara komprehensif adalah the European Convention on State Immunity yang diadopsi pada tahun 1972 dan mulai entry in to force pada tanggal 11 Juni 1976. Konvensi ini diinisiasi oleh Council of Europe dan walaupun hanya beranggotakan 8 negara pihak (Austria, Belgia, Siprus, Jerman, Luxemburg, Belanda, Swiss dan Inggris), namun konvensi dianggap sebagai kodifikasi awal prinsip-prinsip hukum internasional tentang state immunity yang berkembang mulai pada dekade 1970-an8. Walaupun hanya memiliki 8 negara pihak, the European Convention on State Immunity tersebut menjadi salah satu instrumen hukum yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan di negara-negara Eropa dalam menerapkan doktrin imunitas terbatas (restrictive immunity) dan acta iure gestionis dalam sengketa ketenagakerjaan dan kontrak kerja dengan Perwakilan Diplomatik Asing. Pasal yang dijadikan dasar yurisdiksi Pengadilan Negara Penerima atas masalah sengketa ketenagakerjaan dan kontrak kerja adalah Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : 1. A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court of another Contracting State if the proceedings relate to a contract of employment between the State and an individual where the work has to be performed on the territory of the State of the forum. Praktek negara-negara di kawasan Eropa tersebut hanyalah sebagian dari keberagaman praktek penerapan state immunity antar negara di dunia. Adanya keberagaman praktek antar negara tersebut mulai menjadi perhatian PBB hingga akhirnya Majelis Umum PBB tahun 1977 memutuskan untuk memasukkan topik State Immunity sebagai bagian program kerja International Law Commission (ILC). Diskusi mendalam antar para pakar hukum dalam forum ILC serta perwakilan negara pada UNGA sixth Committee menunjukkan sangat beragamnya praktek antar negara. Pada tahun 1991 ILC sempat memunculkan Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property, namun baru pada tanggal 2 Desember 2004, 7. Ibid, Hlm. 96. 8. Joanne Foakes & Elizabeth Wilmshurst, 2005, State Immunity: the United Nations Convention and its effect, Chatham House International Law Programme, Hlm. 4. 37 Volume 01 ● Oktober 2009 Sidang Majelis Umum PBB berhasil mengadopsi United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property melalui resolusi No. A/59/38 pada 65th plenary meeting. Hingga bulan Januari 2009 tercatat baru 28 negara yang menandatangani United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, dan dari ke 28 negara tersebut, terdapat 6 negara yang secara resmi telah meratifikasinya9. Walaupun berdasarkan Pasal 30 ayat (1), Konvensi ini memerlukan 30 negara pihak agar entry in to force, menilik prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral tentang state immunity paling anyar yang mengkodifikasikan praktek negara-negara di dunia. Berkaitan dengan sengketa ketenagakerjaan antara Perwakilan Diplomatik pada Pengadilan Negara Setempat, khususnya masalah kontrak kerja, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, menjabarkan pengecualian Absolute State Immunity (Restrictive Immunity) dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi : 1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to a contract of employment between the State and an individual for work performed or to be performed, in whole or in part, in the territory of that other State. OPINIO JURIS Namun sebagaimana praktek yang dijalankan pada pengadilan Eropa, Konvensi ini juga memberikan pengecualian atas berlakunya doktrin Restrictive Immunity di atas sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: 2. Paragraph 1 does not apply if: (a) the employee has been recruited to perform particular functions in the exercise of governmental authority; (b) the employee is: (i) a diplomatic agent, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961; (ii) a consular officer, as defined in the Vienna Convention on Consular Relations of 1963; (iii) a member of the diplomatic staff of a permanent mission to an international organization or of a special mission, or is recruited to Represent a State at an international conference; or (iv) any other person enjoying diplomatic immunity; (c) the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an individual; (d) the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an individual and, as determined by the head of State, the head of Government or the Minister for Foreign Affairs of the employer State, such a proceeding would interfere with the security interests of that State; (e) the employee is a national of the employer State at the time when the proceeding is instituted, unless this person has the permanent residence in the State of the forum; or 9. Status of Ratification of the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=284&chapter=3&lang=en 38 OPINIO JURIS (f) the employer State and the employee have otherwise agreed in writing, subject to any considerations of public policy conferring on the courts of the State of the forum exclusive jurisdiction by reason of the subject-matter of the proceeding. Singkatnya, dari rumusan Pasal 11 ayat (2) tersebut, tergambar bahwa dalam mengecualikan doktrin Restrictive Immunity, Konvensi ini menerapkan variabel yang hampir sama seperti praktek pengadilan negara-negara Eropa, yaitu10: a. b. c. d. e. status pekerja; bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan; obyek sengketa; security interest; dan hubungan wilayah (territorial nexus) antara pekerja dengan Negara Penerima. Selain mengatur mengenai pengecualian doktrin Absolute Immunity dalam konteks sengketa ketenagakerjaan dan kontrak kerja, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property juga mengatur mengenai pembatasan State Immunity pada perbuatan Negara/Perwakilan Diplomatik berkaitan dengan Commercial Transaction, Arbitration Agreements, Immovable Property, dan Enforcement of Judgement. Penutup Praktek pengadilan domestik di banyak negara, terutama di kawasan Eropa menunjukkan bahwa mulai pertengahan abad XX hingga saat Volume 01 ● Oktober 2009 Ini terjadi perubahan mainstream Absolute Immunities (Imunitas Mutlak) menjadi Restrictive Immunities (Imunitas Terbatas). Walaupun implementasi doktrin Restrictive Immunities tersebut masih mempertimbangkan beberapa faktor seperti: lokasi Perwakilan Diplomatik; bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan; status pekerja; obyek tuntutan; unsur security interest; kewarganegaraan dan faktor territorial nexus; namun tak pelak adanya putusan sengketa ketenagakerjaan terhadap Perwakilan Diplomatik yang masih menganut Absolute Immunities berpotensi menimbulkan conflict of laws yang tak jarang akan mengganggu kinerja Perwakilan Diplomatik atau bahkan hubungan persahabatan antar kedua negara. PBB melalui United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property mencoba mengkodifikasikan dan mengkompromikan beragamnya praktek negara-negara di dunia mengenai penerapan yurisdiksi Pengadilan domestik Negara Penerima atas Perwakilan Diplomatik. Munculnya konvensi ini merupakan kemajuan bagi perkembangan hukum internasional. Negara seperti Indonesia yang belum memilki model peraturan perundangan nasional mengenai pembatasan State Immunities, baik yang berkenaan dengan Perwakilan RI di luar negeri ataupun Perwakilan Diplomatik asing di Jakarta, sudah saatnya menjadikan model Konvensi ini sebagai bahan rujukan, atau bahkan mulai melakukan penjajagan untuk menjadi negara pihak pada konvensi ini dengan mengaksesi Konvensi ini. 10. Ulrike Kohler, Op. Cit., Hlm. 73. 39 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS Statuta International Criminal Court: Perlukah Indonesia Meratifikasinya? Oleh: Adhi Kawidastra * Beberapa waktu yang lalu terdapat perdebatan dari berbagai pihak berkaitan dengan perlu tidaknya Indonesia meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Perdebatan tersebut terkait dengan kekhawatiran bahwa nantinya banyak Jenderal kawakan kita yang akan diseret ke meja hijau di Den Haag untuk diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, atas keterlibatan mereka di beberapa operasi militer di Indonesia dan wilayah yang saat ini menjadi Timor Leste. Secara singkat dapat dijawab bahwa kekhawatiran tersebut sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar, mengingat di dalam Statuta Roma (pasal 24) jelas disebutkan bahwa ICC hanya dapat menangani perkara yang terjadi setelah masa berlaku resminya Statuta Roma. Namun demikian, pertanyaan apakah Indonesia perlu untuk meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak dari ICC masih memerlukan jawaban yang berdasarkan analisa cost and benefit. Untuk dapat membuat analisa tersebut, perlu diidentifikasi terlebih dahulu seperti apakah ICC tersebut dan apa kepentingan Indonesia terhadap keberadaannya? Berbicara mengenai ICC tentunya tidak bisa terlepas dari embrio yang kemudian membesarkan Mahkamah Pidana Inter40 nasional tersebut, yaitu Statuta Roma. Statuta International Criminal Court atau yang lebih dikenal sebagai Statuta Roma, merupakan traktat yang mengawali langkah pendirian ICC. Langkah perjalanan penetapan Statuta Roma sudah dimulai sejak tahun 1952, ketika Komisi Hukum Internasional akhirnya berhasil menyepakati draft final mengenai Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind. Draft tersebut merupakan suatu milestone dalam proses penyiapan Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Sebagai tindak lanjutnya, melalui resolusi Majelis Umum PBB tahun 1996 dan 1997, sebuah Konferensi Diplomatik untuk membahas p e mb e n tu k a n Ma h k a ma h P id a n a Internasional diadakan di Roma pada tanggal 15 Juni sampai dengan 17 juli 1998. Tercatat 160 negara telah mengirimkan delegasinya untuk mengikuti konferensi tersebut, termasuk Indonesia. Konferensi tersebut menghasilkan suatu traktat yang kemudian dikenal sebagai Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 juli 1998 dan telah berlaku efektif mulai tahun 2002, ketika 60 negara telah meratifikasinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa negara, termasuk diantaranya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina yang tidak meratifikasinya dengan berbagai pertimbangan kepentingan nasional dan Internasional yang dihadapi sekarang maupun yang akan datang. OPINIO JURIS Dalam Statuta Roma disebutkan bahwa wilayah yurisdiksi ICC meliputi empat isu pidana utama yang menjadi perhatian utama m a s ya r a k a t i n t e r n a s i o n a l s e c a r a keseluruhan. Empat isu utama tersebut meliputi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan masalah agresi (pasal 5). Namun dari keempat isu pidana utama tersebut, ICC masih belum dapat sepenuhnya menerapkan fungsinya untuk menangangi kejahatan yang berkaitan dengan masalah agresi, mengingat belum jelasnya definisi agresi itu sendiri di dalam berbagai forum ICC dan bagi para negara pihaknya. Sementara itu, banyak negara yang berusaha untuk menambahkan beberapa isu yang menurut mereka cukup merepotkan dan membutuhkan perhatian masyarakat internasional, seperti masalah terorisme dan penyelundupan obat-obatan terlarang. Namun usaha tersebut harus berhenti di tengah jalan, karena sama halnya dengan masalah agresi, banyak pihak yang belum dapat menyepakati definisi terorisme itu sendiri seperti apa. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh ICC juga harus membuat isu tentang penyelundupan obat-obatan terlarang tidak dapat dimasukkan dalam Statuta. Prinsip dasar yang terdapat di dalam Statuta tersebut adalah bahwa ICC merupakan suatu instrumen pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional (pasal 1), yang berarti bahwa sistem peradilan nasional harus didahulukan dalam setiap upaya penyelesain setiap kasus pidana. Prioritas tersebut dapat berubah ketika sistem peradilan nasional sudah tidak mampu (unable) atau Volume 01 ● Oktober 2009 tidak bersedia (unwilling) untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan. Pada tingkatan ini, status penanganan kasus kejahatan tersebut dapat diambil alih oleh ICC (pasal 17). Walaupun begitu, dalam ketentuan yang termuat di dalam statuta, ditetapkan standar yang tinggi untuk mendefinisikan “ketidakmampuan” dan “ketidakmauan” tersebut. Salah satu contoh kondisi yang menyatakan “ketidakmauan” adalah ketika keputusan nasional diambil dengan tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab kriminal (Pasal 17 ayat 2.a). Sementara itu, untuk menentukan “ketidakmampuan” memerlukan apa yang disebut sebagai “keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasionalnya” (Pasal 17 ayat 3). Selain itu, pihak yang menjadi tertuduh ataupun negara yang bersangkutan dapat mengungkapkan keberatan atas campur tangan ICC (pasal 18 dan 19). Fungsi ICC sebagai instrumen pelengkap memiliki arti bahwa keberadaan ICC bukanlah sebagai pengganti sistem peradilan nasional yang masih berfungsi, melainkan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah impunity, yang disebabkan nihilnya sistem peradilan nasional yang independen dan efektif. Sejalan dengan fungsi tersebut, Pemerintah Indonesia juga yakin bahwa Statuta Roma telah menambah arti positif pada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB yang meliputi persepakatan, imparsialitas, nondiskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah. Melalui premis tersebut, Indonesia berusaha untuk menekankan bahwa keberadaan ICC adalah untuk melengkapi dan bukan menggantikan mekanisme hukum nasional. 41 Volume 01 ● Oktober 2009 Pemerintah Indonesia pada dasarnya menyambut positif keberadaan ICC, melalui apresiasi positifnya ketika I n d o n e s ia s e c a r a k h u s u s t e la h mengirimkan delegasinya untuk mengikuti Konferensi Diplomatik di Roma pada bulan Juli 1998. Sambutan positif Indonesia tersebut juga disampaikan kepada Komite ke-6 Majelis Umum PBB dan menyatakan bahwa partisipasi universal harus menjadi ujung tombak dari ICC dan bahwa ICC menjadi bentuk hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu di dalam negeri, Presiden Indonesia telah mengesahkan Rencana Aksi nasional tentang Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang didalamnya juga mengungkapkan maksud Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Presiden juga telah membentuk sebuah Komite Nasional yang mempelajari Statuta Roma mendorong perlunya penyusunan legislasi nasional demi kelancaran proses kerjasama dengan Pengadilan Nasional sebelum ratifikasi dilaksanakan. Dukungan positif tersebut tampaknya juga terlihat dari para anggota parlemen, melalui partisipasi perwakilan anggota parlemen dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentang ICC. Tindak lanjut dari hasil konferensi tersebut kemudian adalah upaya dan janji untuk mempercepat proses ratifikasi atau aksesi Statuta Roma pada tahun 2008 atau lebih cepat. Lebih jauh, Indonesia pada dasarnya telah me milik i b eb erap a p roduk leg islasi 42 OPINIO JURIS nasional yang mengatur masalah HAM. Isu mengenai HAM terutama diatur dalam RANHAM tahun 2004–2009 dan sebelumnya pun telah disahkan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dengan demikian, produk-produk legislasi nasional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya untuk memajukan isu penegakan HAM dengan tetap berpedoman pada kepentingan nasional dan situasi kemasyarakatan di Indonesia. Sementara itu di dalam forum ICC sendiri, Indonesia yang saat ini statusnya masih sebagai observer, mengedepankan kebijakan untuk memajukan penegakan HAM di tingkat nasional, regional, dan global. Sejalan dengan prioritas kebijakan tersebut, isu yang paling relevan untuk dijadikan perhatian bagi Indonesia adalah pandangan umum yang disampaikan oleh delegasi Jepang pada Sesi Ketujuh Sidang Negara-negara Pihak pada Statuta Roma yang berlangsung pada bulan November 2008 yang lalu. Delegasi Jepang pada saat itu mengungkapkan bahwa Jepang sebagai salah satu negara di wilayah Asia yang telah meratifikasi Statuta Roma, merasa prihatin bahwa sampai saat ini baru 14 negara di kawasan Asia yang meratifikasi statuta tersebut. Oleh karena itu, Indonesia dan negaranegara di kawasan Asia lainnya yang belum meratifikasi statuta tersebut untuk dapat segera mempercepat kemungkinan ratifikasi, untuk menghindari terjadinya kebijakan ICC yang sifatnya Eropa-sentris, mengingat hampir seluruh negara-negara di kawasan Eropa telah meratifikasi statuta tersebut. OPINIO JURIS Dalam skala global, mekanisme penegakan HAM, termasuk didalamnya mekanisme penjatuhan hukuman bagi para pelaku pelanggaran HAM berat telah banyak dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional di bidang HAM seperti Universal Declaration of Human Rights 1948, UN Charter 1945, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights maupun International Covenant on Civil and Political Rights. Idealnya, dengan kehadiran beberapa instrumen penegak HAM internasional tersebut, seharusnya dapat memicu timbulnya suatu kewajiban moral bagi setiap entitas yang memiliki kepentingan terhadapnya, namun apa dikata bahwa pada kenyataannya masih saja banyak terdapat praktik-praktik pelanggaran HAM berat yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, disamping kehadiran beberapa instrumen HAM internasional tersebut, diperlukan suatu upaya keras secara menyeluruh dari masyarakat internasional untuk mencegah meluasnya pelanggaran HAM berat yang terus berkembang. Disinilah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional dapat memainkan peranannya dan memberikan kontribusinya dalam upaya mengatasi dan mencegah meluasnya pelanggaran HAM dengan cara meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak di dalam forum ICC. Pada skala regional, dengan wilayah geografis yang sangat luas dan jumlah negara yang banyak, menjadikan Asia sebagai lini inti dalam setiap upaya penegakan HAM melalui ICC. Oleh karena itu, melihat positifnya kedudukan Indonesia di mata negara-negara Asia dalam bidang penegakan HAM, maka keterlibatan dan partisipasi aktif Indonesia jika meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak ICC, merupakan langkah Volume 01 ● Oktober 2009 positif untuk semakin meningkatkan citra positif Indonesia dalam bidang HAM di tingkat regional. Pada skala nasional, keterlibatan Indonesia di dalam upaya global penanggulangan pelanggaran Hak Azasi Manusi merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia: “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Pada era reformasi, setelah pasal-pasal di dalam UUD 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan, isu mengenai HAM justru makin dikedepankan melalui penambahan klausul mengenai HAM yang terdapat di dalam pasal 28 A – 28 J. Selain instrumen legislasi nasional, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen dasar pengaturan HAM internasional, seperti International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights melalui UU No. 11 tahun 2005 dan International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU No. 12 tahun 2005. Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mendukung kinerja ICC untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan atau pelanggaran HAM pada tingkat global diperlukan kerjasama internasional dengan berbagai pihak, baik itu negara pihak, observer, organisasi internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Oleh karena itu, partisipasi aktif Indonesia, jika meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak International Criminal Court, merupakan salah satu langkah positif dalam mengemban amanah nasional dan global untuk mengkampanyekan upaya penegakan HAM pada skala global. 43 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS THE RESPONSIBILITY TO PROTECT DALAM PERSPEKTIF HUKUM1 Oleh : Bebeb A.K. Djundjunan2 dan Rizal Wirakara3 Pendahuluan Pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2005, para Kepala Negara/Pemerintahan menegaskan kembali komitmen politik dan moral berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajiban setiap negara serta masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindak kejahatan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komitmen tersebut tertuang dalam the Summit Outcome Document, khususnya pasal 138 dan 139 mengenai the Responsibility to Protect (R2P).4 Komitmen ini dapat dikategorikan sebagai suatu terobosan bersejarah, mengingat sejak inisiasi konsep tersebut pada tahun 2001, pembahasannya dalam berbagai forum selalu ditandai dengan perdebatan hangat pro dan kontra terhadap doktrin R2P. Sejak awal sebagian besar negara berkembang mencurigai konsep ini sebagai cover baru dari intervensi kemanusiaan yang telah banyak menuai kritik. Disamping itu, timbul kekhawatiran bahwa R2P akan digunakan oleh negaranegara besar untuk melegalisasi intervensi, yang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip non-interference dan nonintervention. Apabila ditelusuri kembali, konsep R2P lahir sebagai respon terhadap realitas dan permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, terkait dengan berbagai tindak kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, yang membutuhkan reaksi yang harus cepat namun efektif untuk menghindarkan dan menghentikan meluasnya petaka kemanusiaan tersebut. Humanitarian intervention tidak dipandang sebagai solusi, karena dalam prakteknya sangat kental diwarnai oleh kepentingan-kepentingan negara 1. Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Roundtable Discussion: Responsibility to Protect: Tinjauan Konsep dan Implementasinya yang diselenggarakan oleh BPPK Deplu, pada tanggal 18 Februari 2009. 2. Penulis adalah Kepala Subdit Perjanjian Kelautan, Direktorat Perjanjian Polkamwil 3. Penulis adalah Kepala Seksi Hukum Politik dan Keamanan, Direktorat Perjanjian Polkamwil 4. The Summit Outcome diadopsi oleh para Pemimpin Negara melalui Resolusi General Assembly No. A/60/1 pada tanggal 24 Oktober 2005. 44 OPINIO JURIS negara tertentu, sehingga seringkali gagal mendapatkan dukungan dan legalitas dari dunia internasional. Di satu sisi, dunia internasional harus dapat merespon tindak pelanggaran terhadap kemanusian tersebut dengan tepat tanpa berbenturan dengan prinsip-prinsip state sovereignty, non intervention dan non interference. Pada tahun 2001, ICISS mengeluarkan suatu rekomendasi yang cukup cerdas dan lugas yang menyatakan bahwa pada setiap negara berdaulat terdapat tanggung jawab memberikan perlindungan kepada seluruh warganya, termasuk dari berbagai tindak kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis, yang diakibatkan oleh terjadinya perang saudara, pemberontakan, penindasan atau kekacauan didalam negara. Namun, apabila negara tersebut dianggap dan atau tidak mampu melaksanakan perlindungan kepada warganya, maka masyarakat inter-nasional berkewajiban memberikan bantuannya dalam kerangka the responsibility to protect untuk menghindarkan atau menghentikan berbagai tindak kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis. Pada intinya, konsep R2P ini menggaris bawahi kewajiban negara dan masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan tersebut. Menindaklanjuti konsep R2P yang diadopsi Volume 01 ● Oktober 2009 dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. A/60/1, Sekretaris Jenderal PBB berupaya untuk mempercepat implementasi R2P sebagai salah satu instrumen dalam pencapaian keadilan dan perdamaian dunia. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa menyadari bahwa menerapkan R2P tidak mudah, mengingat masih rendahnya komitmen politik yang disebabkan adanya keragu-raguan dari beberapa negara terhadap efektifitas dan ketidak berpihakan pengimplementasian doktrin R2P dalam mengakhiri berbagai tindak kejahatan kemanusiaan termaksud. Di lain pihak, adanya upaya dari negara-negara tertentu untuk memperluas cakupan R2P, sehingga tidak terbatas hanya pada kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis. Muncul pertanyaan, apakah kemudian R2P dapat menjamin tegaknya keadilan tanpa mencederai prinsip kedaulatan, tidak campur tangan dan tidak intervensi terhadap suatu negara, apabila instrumen penyokongnya, seperti Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hak veto, tidak berubah? Bagaimana implikasi dan dampaknya terhadap negara yang tidak mampu memberikan perlindungan sebagaimana yang dituntut dalam R2P? Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Indonesia memang perlu mengkaji lebih dalam mengenai prinsip R2P dalam pandangan hokum inter45 Volume 01 ● Oktober 2009 nasional dan nasional serta bagaimana konsekuensi penerapannya. Konsep dan Prinsip the Responsibility to Protect Konsep R2P muncul sebagai respon terhadap kegagalan humanitarian intervention menyelesaikan konflik kemanusiaan dan ketidak mampuannya untuk menggalang dukungan internasional. Permasalahan yang mendasar adalah karena dalam pelaksanaan humanitarian intervention selalu diwarnai berbagai konflik kepentingan dari negara-negara tertentu, sehingga kerap kali dilakukan tanpa mandat dan legalitas. Akibatnya humanitarian intervention selalu memunculkan kontroversi, baik ketika intervensi dilakukan maupun ketika intervensi tidak dilakukan. Sejarah mencatat bahwa intervensi kemanusiaan yang terjadi seperti intervensi India di Pakistan Timur, Vietnam di Kamboja dan NATO di Kosovo, selain tidak mendapat mandat dari DK PBB, juga mencederai prinsip non-intervention dalam pasal 2 (4) Piagam PBB. Oleh karena itu, intervensiintevensi tersebut dipandang sebagai illegal dan hanya menunjukkan arogansi kekuatan negara-negara besar yang menginjak kedaulatan negara-negara yang lemah.5 Tidak berbeda dengan humanitarian intervention, R2P tidak memandang kedaulatan sebagai suatu yang absolut dalam dunia OPINIO JURIS yang interdependen. Kedua doktrin tersebut membenarkan atau memandang perlu adanya campur tangan asing, apabila negara tertentu dianggap tidak mampu atau gagal menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. R2P menggeser doktrin “hak” menjadi “kewajiban” negara dan masyarakat internasional menjamin suatu perlindungan terhadap setiap individu. Namun, berbeda dengan konsep humanitarian intervention, R2P mengedepankan kewajiban negara, baik secara nasional maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam me mberikan perlindungan dasar terhadap setiap individu yaitu sovereignty as responsibility. Berdasarkan prinsip tersebut, dalam praktek bernegara, suatu pemerintahan nasional yang berkedaulatan mengemban setidaknya tiga tanggung jawab penting, yaitu pertama bertanggung jawab melaksanakan fungsi fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan dari warganegaranya dan menjamin kesejahteraan warganya. Kedua, pemerintah nasional bertanggung jawab terhadap warganegaranya dan masyarakat internasional melalui keanggotaannya di PBB. Ketiga, bahwa pelaksana pemerintahan bertanggung jawab terhadap tindakan dan kebijakan yang diambilnya.6 Terakomodasinya R2P dalam the 2005 Summit Outcome menunjukkan peran krusial PBB 5. Thomas M. Frank, “Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention”, in J.L. Holzgrefe and Robert O. Keohane (eds), Humanitarian Intervention: Ethical, Legal dan Political Dillemas, Cambridge University Press, 2007, pp. 204-31. 6. ICISS, report of the International Commission on Intervention and State Sovreignty, 2001, p. 13 46 OPINIO JURIS dalam mendukung realisasi doktrin tersebut. Konsep R2P yang tertuang didalamnya mencakup tiga pilar yaitu: 7 The protection responsibility of state atau kewajiban negara untuk menjamin perlindungan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah kedaulatannya dari pembunuhan massal (genocide), kejahatan perang (war crime), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan pembersihan etnis (ethnic cleansing). The international assistance and capacity building, yaitu komitmen masyarakat internasional untuk membantu negaranegara yang membutuhkan dalam melaksanakan kewajibannya. Timely and decisive resonse atau respon kolektif masyarakat internasional in timely dan decisive manner terhadap ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan tersebut. Kewajiban setiap negara sebagaimana yang disebutkan dalam pilar satu bahwa : Each individual state has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means... Volume 01 ● Oktober 2009 bukanlah kewajiban baru dari suatu negara, dan perlindungan terhadap genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan termasuk dalam international customary law yang sifatnya compelling. International Human Rights law mencantumkan kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warganegara dan setiap individu yang berada dalam yuridiksinya dari tindak pelanggaran HAM dan berbagai ancaman terhadap hak-hak hidup dan keamanan. Pilar kedua R2P menggarisbawahi respon dan peran aktif masyarakat internasional mendukung dan mendorong upaya negara tertentu dalam memenuhi kewajibannya tersebut melalui kerangka peningkatan kapasitas dan berbagai bantuan lainnya. Disamping itu, pilar kedua merupakan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan. ...The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the UN in establishing an early warning capacity... also intended to commit ourselves, as necessary and appropriate to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity and assisting those which are under stress before crises and conflicts break out. Pilar ketiga menggarisbawahi bahwa respon kolektif masyarakat internasional melalui 7. Paragraf 138 dan 139, The 2005 Summit Outcome, UN General Assembly No. A/60/1, 2005 47 Volume 01 ● Oktober 2009 penggunaan kekuatan militer/intervensi dapat dilakukan apabila negara tersebut dipandang gagal melindungi warganya dan apabila cara-cara damai yang ditempuh juga mengalami kegagalan. ... to take collective action, in timely and decisive manner, through the Security Council, ... on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organisations as appropriate, ...[if only] peaceful means [are] inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. Perspektif dan Payung Hukum the Responsibility to Protect Konsep R2P diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/1, khususnya paragraf 138 dan 139, dan sifatnya adalah “rekomendasi”. Dalam perspektif hukum internasional, suatu rekomendasi, komitmen atau deklarasi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB mempunyai konsekuensi yang berbeda dibandingkan resolusi DK PBB, dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sekalipun tidak mengikat, namun the outcome document tersebut mempunyai muatan “politik dan moral” yang signifikan dalam menciptakan suatu norma internasional yang baru. Konsep R2P sebagaimana yang dijelaskan diatas, tidak menciptakan kewajiban baru bagi negara maupun membuat doktrin dan instrumen hukum internasional yang baru, tetapi mengacu pada kewajiban-kewajiban 48 OPINIO JURIS negara yang telah diatur dalam hukum internasional yang telah ada, yaitu antara lain international humanitarian law dan international human right law. Disamping itu, kewajiban dan tanggung jawab negara sesuai pilar satu tersebut juga tertuang dalam berbagai macam perjanjian HAM dan ketentuan, seperti Human Rights Covenants of 1966: International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) serta berbagai produk hukum internasional lainnya yang lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia dan telah diratifikasi oleh sejumlah besar negara, termasuk didalamnya adalah Konvensi tentang Genosida, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan lainnya yang tidak Manusiawi atau Merendahkan (CAT), Konvensi tentang Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CEDR) dan ratifikasi universal terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949, dimana negara-negara pihak diwajibkan untuk menerapkan perlindungan tersebut secara konkrit. Sedangkan Statuta Roma 1998 menegaskan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelanggar HAM berat tersebut. R2P mewajibkan setiap negara untuk mencegah dan menghukum para pelaku genocide, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusian. Kewajiban negara terkait kejahatan genocide dan kejahatan perang terdefinisikan secara jelas dan telah memiliki dasar hukum tersendiri, sekalipun cakupannya terus mengalami penyesuaian. OPINIO JURIS Perjanjian internasional mengenai kejahatan kemanusiaan masih banyak yang belum terkodifikasi, namun perkembangan sejumlah kasus hukum dari berbagai pengadilan inter-nasional dan tribunal telah dapat mengelabora-sikan dasar dan batasan kejahatan kemanusiaan tersebut. Sedangkan perlindungan terhadap tindak kejahatan keempat yaitu pemusnahan/ pembersihan etnis sampai saat ini belum dimasukkan dalam hukum internasional yang ada. Lebih lanjut pemahaman hukum atas genocide, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusian yang telah berkembang sejak Nuremberg Tribunal terefleksikan dalam Statuta Roma, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Statuta Roma mempertegas kewajiban negara untuk secara efektif menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tindak kejahatan kriminal termaksud.8 Statuta Roma menghapuskan kekebalan hukum para pelaku kejahatan sehingga menjadikan ICC dan tribunal-tribunal regional sejalan dengan prinsip R2P. Di satu sisi, R2P secara politis dapat memperkuat tuntutan terhadap akuntabilitas kasus-kasus yang ditangani oleh ICC, melalui penuntutan kriminal atau bentuk penanganan lainnya. Kejahatan yang tercantum dalam butir-butir the World Summit Outcome Document, masuk dalam yuridiksi International Criminal Court (ICC) yang dibentuk untuk menangani kejahatan kriminal berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional seperti pemusnahan massal Volume 01 ● Oktober 2009 (Article 6), kejahatan kemanusiaan (artikel 7) dan kejahatan perang (article 8). Pada prinsipnya R2P dan ICC dapat berfungsi saling melengkapi dan memperkuat upayaupaya internasional dalam mencegah terjadinya kejahatan HAM berat di masa yang akan datang. Sedangkan pilar kedua R2P menuntut keterlibatan aktif masyarakat internasional dan PBB dalam mencegah, menghentikan dan menyelesaikan berbagai tindak pelanggaran HAM berat sebagaimana yang disebutkan pada pilar 1. Adapun keterlibatan aktif tersebut dilakukan melalui saluran-saluran diplomatik, bantuan kemanusiaan, bantuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan instrumen hukum dan institusi dari negaranegara yang membutuhkan bantuan tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Piagam PBB, khususnya Chapter VI dan VII. Pilar ketiga R2P juga tidak secara sendirinya menerapkan kewajiban-kewajiban hukum baru kepada masyarakat internasional pada kasus-kasus genocide, kejahatan perang, kejahatan kemanusian, atau pembersihan etnis, tetapi konsisten dan sejalan dengan hukum internasional yang berkembang dalam praktek dan pengaturan hubungan antar negara. Terlepas dari the Summit Outcome, hukum internasional telah mengatur pelarangan terhadap genocide dan mempertimbangkan sejumlah peraturan khusus yang memuat kejahatan perang atau 8. Hanya negara pihak pada Statuta Roma yang terikat untuk bekerjasama dalam ICC, sedangkan semua negara terikat untuk bekerjasama dalam dua tribunal khusus, tribunal Yugoslavia dan Rwanda, yang dibentuk oleh Resolusi DK PBB. 49 Volume 01 ● Oktober 2009 kejahatan kemanusiaan sebagai peremptory norms dari hukum internasional.9 Apabila terindikasi bahwa suatu negara melakukan pelanggaran serius terhadap peremptory norms, maka masyarakat internasional harus bekerjasama untuk mengakhiri pelanggaran tersebut dengan menggunakan perangkat hukum yang ada. Hal ini termuat dalam Artikel 41 International Law Commission’s (ILC) yang secara hati-hati mengelaborasi pasal mengenai Tanggung Jawab Negara terhadap Tindak-tindak Pelanggaran Internasional. Selain Konvensi tentang Genosida, tidak ada doktrin yang memformulasikan mengenai tanggungjawab negara/pihak ketiga apabila gagal mencegah kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan serta pembersihan etnis. Dimana satu doktrin R2P meletakkan kewajiban hukum internasional dalam pencegahan dan pemberian hukuman atas tindak kejahatan genosida. Pasal 1, Konvensi tentang Prevention and Punishment of the Crime of Genocide menyatakan bahwa genocide whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish. Lalu apakah kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan genosida dalam hukum internasional menyebabkan adanya kewajiban untuk mengintervensi dalam keadaaan khusus dari masing-masing kasus? Doktrin R2P dalam OPINIO JURIS paragraf 138 dan 139 tidak menyebabkan kewajiban intervensi militer, tetapi menekankan pada upaya pencegahan, penghentian dan penyelesaian isu-isu pelanggaran HAM berat tersebut. Intervensi militer hanya merupakan pilihan terakhir, apabila semua pilihan damai tidak berhasil menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi, dan hanya dapat dipilih sebagai opsi terakhir dengan justifikasi dan legitimasi PBB. Prospek Implementasi R2P: Tantangan Legalitas dan State Sovereignty Negara-negara berkembang memandang bahwa konsep R2P memiliki kesamaan dengan humanitarian intervention, dan dikhawatirkan pengimplentasian konsep tersebut akan berdampak terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip non interference dan non intervention, penghormatan terhadap territorial integrity dan national sovereignty yang selama ini menjadi prinsip-prinsip utama hubungan antar negara dan forum kerjasama di berbagai kawasan di dunia. Sehingga, tidak salah apabila perhatian masyarakat internasional dalam pembahasan R2P terfokus pada pilar ketiga, yang menyediakan “jalan” untuk keterlibatan pihak asing, mengambil alih tanggung jawab suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Kekhawatiran yang muncul adalah manipulasi dan politisasi yang akan dilakukan negaranegara besar untuk melegalisasi tindakan intervensi yang dilakukannya. Di lain pihak, beberapa negara besar mengkritik 9. Dapat diartikan bahwa peremptory norms diterima oleh masyarakat internasional seutuhnya, dan hanya dapat diubah apabila adanya perubahan pada norma-norma yang bertentangan namun memiliki kekuatan hukum yang sama. 50 OPINIO JURIS cakupan R2P yang terbatas hanya pada empat jenis tindak kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Mereka beranggapan bahwa dalam menciptakan suatu perdamaian dan ketertiban dunia, cakupan tanggung jawab tersebut harus diperluas. R2P juga menghadapi tantangan, terutama dalam menyamakan persepsi atau mengkategorikan bahwa ‘national authority is manifestly failing to protect...’ berdasarkan standar nilai dan ukuran yang universal tanpa politisasi dari negara-negara tertentu. Bagaimana doktrin R2P menjawab kekhawatiran sebagian negara tersebut? Sebagaimana tercantum pada paragraf 139 diatas, bahwa pada prinsipnya R2P memberikan prioritas utama kepada negara untuk menjamin perlindungan warganya dari berbagai pelanggaran HAM. Jika menurut doktrin hukum internasional suatu negara dipandang telah melanggar kewajibannya, maka diharapkan negara tersebut dapat/ mampu menghentikan pelanggaran tersebut (jika pelanggaran tersebut masih berlanjut), menawarkan kepastian penyelesaian hukum (appropriate assurances of nonrepetition), dan melakukan perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkannya. Namun, apabila negara dipandang tidak mampu atau gagal menghentikan tindak pelanggaran genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis, maka negara tersebut harus mengijinkan masuknya bantuan asing (...appropriate diplomatic humantiarian and other peaceful means... bahkan juga intervensi militer (...collective use of force authorized by the Security Council under Chapter VII...) hanya jika berbagai upaya damai yang Volume 01 ● Oktober 2009 ditawarkan masyarakat internasional dan juga negara tersebut benar-benar tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi. Doktrin R2P memang tidak mengikat, namun karena R2P mengacu pada hukum inter-nasional dan hukum kebiasaan internasional yang ada, dimana negaranegara terikat didalamnya, maka negaranegara menjadi ‘berkewajiban’ memenuhi segala konsekuensi, termasuk menerapkan prinsip-prinsip R2P tersebut. Artinya, bahwa setiap negara harus menyesuaikan seluruh instrumen dan perangkat hukumnya, termasuk menghapuskan immunity dan impunity sehingga doktrin R2P dapat terakomodir dalam hukum nasionalnya. Konsekuensi lainnya adalah negara harus mau menerima adanya campur tangan asing, apabila negara tersebut dipandang tidak mampu menyelesaikan isu-isu kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis. Untuk menghindarkan perbenturan doktrin R2P dengan prinsip state sovereignty dan non interference, maka pemahaman konseptual dan doktrinal haruslah ada pada tataran yang sama. Perspektif Indonesia terhadap Prinsip R2P Pada umumnya prinsip the Responsibility to Protect tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Hukum nasional Indonesia berpandangan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warganya. Kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut tercantum dalam UUD 51 Volume 01 ● Oktober 2009 1945 bahwa “...pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa .. dan tumpah darah Indonesia ... ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ... “ dan TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional yang merupakan implementasi dari instrumen dasar HAM internasional, antara lain UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dapat mendukung pelaksanaan R2P. Disamping itu, UU No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU No. 5 tahun 1998 yang Menentang Penyiksaan, UU No. 29 tahun 1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Indonesia juga merencanakan untuk aksesi Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang sejalan dengan semangat R2P. Apakah the Responsiblity to Protect bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang dianut oleh Indonesia? Konsep kedaulatan suatu negara tercermin dari kemampuan negara tersebut dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada warga negaranya. Dalam menjabarkan kedaulatannya tersebut, suatu pemerintahan negara harus mengupayakan, dengan segala cara, untuk menjamin perlindungan mendasar bagi seluruh warganya, termasuk dengan menerima “bantuan asing” bukan “campur tangan asing” 52 OPINIO JURIS apabila negaranya tidak mampu mengupayakannya sendiri. Kedaulatan suatu negara tidak hilang/berakhir dengan masuknya suatu bantuan asing, selama bantuan tersebut merupakan consent negara yang bersangkutan. Selama bantuan tersebut tidak bertentangan dengan yurisdiksinya dimana negara penerima bantuan masih tetap memiliki kewenangan dalam membuat dan menegakkan hukumnya tanpa campur tangan asing. Pada kasus Timor Timur paska referendum, Indonesia telah dapat menerima masuknya bantuan internasional melalui mekanisme dan instrumen yang tersedia pada hukum nasional sehingga tidak lagi menghadapi isu pelanggaran kedaulatan nasional. Disamping itu, Indonesia juga memiliki pengalaman yang dapat dibagi dengan negara lain terkait dengan upaya perlindungan dalam kerangka pemajuan HAM di tanah air. Namun, implementasi doktrin R2P tanpa diikuti dengan reformasi DK-PBB dan institusi lainnya memang akan berbenturan dengan prinsip-prinsip tidak intervensi dan tidak campur tangan serta melanggar kedaulatan negara dan integritas kewilayahan suatu negara. Untuk menjamin ketidak berpihakan dan politisasi doktrin R2P diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pemerintah dan harus didukung dengan sistem internasional yang bebas dari berbagai konflik kepentingan. Saat ini sistem kerja dan struktur keanggotaan DK PBB belum memungkinkan diterapkannya konsep R2P secara adil. Oleh karena itu, implementasi R2P di masa yang akan datang tidak akan terlepas dari hasil reformasi OPINIO JURIS Volume 01 ● Oktober 2009 DK PBB dimana penggunaan veto perlu dilarang, sekiranya DK PBB membahas definisi crime of genocide, war crimes, ethnic cleansing dan crime against humanity. instrumen-instrumen yang digunakan R2P lebih luas karena mencakup juga upayaupaya pencegahan, perlindungan, pengembangan kapasitas dan pembangunan kembali. Kesimpulan Penggunaan kekuatan militer atau tindakan coercive dalam R2P merupakan last resort dalam merespon pelanggaran yang terjadi, yaitu hanya dilakukan apabila terindikasi kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan kepada warganya, dimana langkah-langkah damai tidak dapat diterapkan, dan juga adanya otorisasi Dewan Keamanan PBB. Konsep R2P berangkat dari kewajiban negara dan masyarakat internasional membantu pembangunan kapasitas dalam menjamin perlindungan dasar bagi setiap individu dan bertindak dalam kerangka Chapter VII Piagam PBB sekiranya suatu pemerintah nasional dinilai tidak memiliki komitmen politik atau bahkan dinilai turut terlibat dalam berbagai kejahatan tersebut. Sehingga ketika negara dianggap tidak mampu atau tidak mau melaksanakan kewajiban perlindungan maka kewajiban tersebut diserahkan kepada organisasi internasional, seperti antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep R2P berbeda dan dapat dibedakan dari humanitarian intervention dan human security ditinjau dari dasar, cakupan dan instrumennya. R2P mencantumkan kewajiban masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kepada suatu negara melalui kerangka capacity building, sehingga memungkinkan negara tersebut memenuhi kewajibannya dalam menjamin perlindungan bagi penduduknya. Selain itu, Menerapkan konsep R2P secara adil memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pemerintah dan harus didukung dengan sistem internasional yang bebas dari berbagai konflik kepentingan. Saat ini sistem kerja dan struktur keanggotaan DK PBB belum memungkinkan diterapkannya konsep R2P secara adil. Disamping itu, mengimplementasikan R2P secara efektif memerlukan adanya pemahaman doktrinal dan konseptual yang sama, serta penyelarasan antara institusi, kebijakan dan perangkat hukum. Terpenuhinya unsurunsur tersebut diatas memungkinkan ‘kapan dan bagaimana’ keterlibatan masyarakat internasional dalam krisis internal suatu negara dapat dijustifikasi dan dilegalkan. 53 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS Beyond Terror and Martyrdom: The Future of the Middle East Penulis: Gilles Kepel. Penerbit: Harvard University Press. 328 halaman. ISBN 978-0-674-03138-8 Sejak 9/11, dua kubu bentrok di kancah global: aliran neokonservatif yang berpikir bahwa teroris yang berasal dari kaum fundamentalis Islam merupakan ancaman bagi kehidupan beradab, dan aliran jihadis yang meyakini mitos tentang syuhada yang menghalalkan darah mereka yang dianggap kafir (infidels). Layar televisi di seantero dunia disuguhi tontonan yang menggiriskan, persembahan dari kedua kubu. Berbagai gambar hidup yang mengerikan seolah berebut tempat untuk saling mengancam kubu lawan. Kita disuguhi adegan pemenggalan kepala seorang sandera “Barat” ditayangkan nyaris berbarengan dengan adegan penyiksaan “teroris Islam” di Abu Ghraib. Adegan bom bunuh diri di Bali, London dan Madrid ditampilkan seolah “super-imposed” dengan adegan pembunuhan massal rakyat sipil tak berdosa oleh serdadu Amerika Serikat dan sekutunya di Iraq. Dan dunia pun seolah terpolarisasi oleh kedua kekuatan dominan ini. Dalam konteks inilah, Gilles Kepel, Professor dan Ketua Pusat Studi Timur Tengah di Institute of Political Studies, 54 Paris, menyodorkan pandangan kritis yang tajam dan cerdas melalui bukunya: “Beyond Terror and Martyrdom: The Future of the Middle East.” Kepel menegaskan bahwa khotbah dan kebencian global yang dicanangkan mantan Presiden George W. Bush dan Usamah Bin Ladin terbukti gagal dan gulung tikar. OPINIO JURIS Bush yang menggali kapak peperangan terhadap teror global yang diyakininya telah dilancarkan oleh kalangan jihadis Islam akhirnya terperosok kedalam “the fiasco in Iraq” yang sudah tak jelas lagi ujung pangkalnya. Sementara rakyat sipil hampir setiap hari tewas bergelimpangan ditangan tentara pendudukan yang dimotori serdadu Amerika Serikat. Agenda perang Irak yang dilancarkan Bush, oleh Kepel dinilai sudah tidak jelas lagi. Apakah maunya memaksakan demokrasi a la Barat di Irak, atau menguasai ladang minyak Irak, mengamankan posisi Israel atau hanya sekadar menggulingkan rejim Saddam Hussein dan mungkin juga merembet pada penggulingan rejim yang kini berkuasa di negeri tetangga: Iran? Yang pasti, semakin lama Amerika Serikat bercokol di Iraq, semakin besar juga harga politik, ekonomi dan militer, terutama jiwa para serdadunya, yang harus dibayar. Menurut Kepel, konsep Bush tentang “global war on terror” bukan hanya berujung pada invasi Irak dan Afghanistan, tetapi juga membawa misi proyek “suci” untuk menyebarkan benih demokrasi ke jazirah Arab, sekaligus menata kembali kawasan Timur Tengah yang carut marut menurut pandangan Bush. Kepel menyebutnya sebagai: “a vision of global rectification through violent means!” Volume 01 ● Oktober 2009 Situasi ini, menurut Kepel, persis sama dengan apa yang dilakukan bin Ladin. Khotbah bin Ladin tentang jihad dan syuhada untuk menghabisi kaum kafir dan menyingkirkan para pemimpin di negara Islam yang dianggap murtad (apostade), seperti Saudi Arabia terkendala oleh kenyataan kekuatan dunia Islam yang tercerai berai dan tak memiliki kesatuan pandangan yang utuh. Aksi kekerasan bin Ladin yang konon wajib dilancarkan demi menyongsong fajar baru negara Islam universal, kerapkali justru memicu bentrokan berdarah diantara kaum Muslim sendiri. Kepel menyimpulkan bahwa kedua kubu terbukti telah “crashed against a wall of reality within the Muslim world”. Alih-alih memberangus gerakan jihadis, pendudukan dan kekejaman Amerika Serikat di Iraq justru menyuburkan ladang penyemaian martir martir baru yang semakin memusingkan, bukan hanya Amerika Serikat dan sekutunya, tetapi juga dunia Islam. Bagi Al Qaeda, kondisi ini tidak serta merta selalu menguntungkan. Kendati kekuatan Islam radikal semakin kukuh, ternyata bukan kalangan Sunni fanatik Al Qaeda saja yang mengeruk keuntungan, melainkan rival bebuyutan mereka dalam merebut kepemimpinan dunia Islam, golongan Shiah, yang justru lebih memantapkan kekuatan mereka. Hal ini terlihat dengan semakin berkibarnya pengaruh para pemimpin Shiah di Iran, dan selepas perang 33 hari dengan Israel tahun 2006, 55 Volume 01 ● Oktober 2009 kelompok Hizbullah Lebanon yang di dukung Iran juga semakin Mencorong. Ketajaman lain dari pisau analisa Kepel, adalah pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang Islam dan Timur Tengah. Buku ini memberikan gambaran yang tajam, sekaligus jernih dan mudah difahami, tentang berbagai friksi, intrik dan persaingan berdarah diantara kelompok nasionalis Arab dan diantara kelompok sektarian Muslim, atau bentrokan antara nasionalis dan fundamentalis Muslim. Buku ini menyajikan suguhan tentang latar belakang dan konteks sejarah dan budaya yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang kurang difahami oleh Amerika Serikat, sehingga sering kebijakan Amerika Serikat macet di tengah jalan, atau bahkan keluar jalur. Hal yang layak direnungkan adalah ajakan Kepel agar kita meninggalkan jauh-jauh belantara persaingan ideologis antara terorisme dan martyrdom, dan mulai menapaki ranah dialog yang konstruktif antara Islam dan Barat. Kepel mengambil contoh matra Eropa, dimana populasi dan ajaran Islam berkembang pesat. Di Inggris dan Perancis, Kepel melihat adanya kebijakan tentang integrasi sosial dan upaya menyuburkan multikulturalisme, dapat dijadikan ladang percontohan untuk mendorong proses marjinalisasi pemikiran sektarian sekaligus memperkecil ruang gerak terorisme dan radikalisme di kalangan 56 OPINIO JURIS Islam di Eropa. Meminjam kalimat Kepel, upaya bersama yang sekarang sedang digalakkan di Inggris dan Perancis ini adalah “to transcend terror and martyrdom and to ensure the decisive marginalization of jihadist radicalism.” Kepel nampaknya cukup yakin bahwa apa yang sekarang sedang berlangsung di Eropa merupakan “a unique deterrent to the logic of terrorism”. Tentu saja, kita boleh bersilat lidah. Konklusi yang disodorkan Kepel dapat saja kita hadapkan dengan fakta masih adanya bom bunuh diri para pemuda Muslim Inggris di London’s underground, protes penuh kekerasan atas karikatur Nabi Muhammad SAW yang dilansir koran Denmark, pelarangan jilbab di sekolah Perancis, atau pembunuhan terhadap sutradara muda Belanda, Theo van Gogh yang dianggap menghina Islam. Masih segar di ingatan kita peristiwa “Paris Membara” tahun 2005, dimana kelompok muda Muslim Paris melakukan aksi pembakaran dan perusakan massal sebagai protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan menghina kaum pendatang. Untuk ini, Kepel berkilah. Menurutnya Inggris dan Belanda, misalnya, terkadang terlalu memaksakan multikulturalisme terlalu jauh dan menafikkan adanya keperluan untuk membangun identitas bersama, dimana kaum Muslim dapat merasa nyaman hidup berdampingan secara damai dengan penduduk “asli” Eropa. Dalam kasus aksi pembakaran di Paris, OPINIO JURIS Kepel menegaskan bahwa kemarahan para pemuda Muslim di picu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap diskrimantif sebagai upaya marjinalisasi kaum pendatang, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan jihad atau terorisme. Kepel malah menegaskan bahwa dengan menyuarakan sikap frustasi dengan protes yang keras, para pemuda Muslim itu justru: “inadvertently pointed out the promise of a society that rejects ideologies of separatism and embraces the ideology of inclusion.” Dan kondisi ini dapat digarap menjadi ajang rekonsiliasi sosial yang baik untuk mematikan benih radikalisme sektarian. Volume 01 ● Oktober 2009 Sebagai bagian dari upaya untuk lebih memahami situasi dan kondisi “Perang Terhadap Teror” yang kini seolah menjadi mantra dalam hubungan internasional, ada baiknya kita membaca buku ini. Resep-resep yang disodorkan Kepel, mencerminkan pemahamannya yang mendalam atas berbagai anasir yang membentuk konstelasi politik dan budaya di kawasan Timur Tengah. Kritik yang dilontarkan Kepel terbilang tajam dan cerdas. Hal ini tentunya menjadikan buku ini sebagai rujukan berharga, bukan hanya untuk memahami Timur Tengah, tetapi juga memberikan berbagai pandangan umum tentang hubungan internasional kontemporer.[a] 57 Volume 01 ● Oktober 2009 OPINIO JURIS Deklarasi Solo, Upaya Penjagaan dan Perlindungan Warisan Budaya Pada tanggal 25-28 Oktober 2008 di Solo telah berlangsung International Conference of World Heritage Cities of Euro-Asia. Konperensi ini dihadiri oleh 143 walikota dari berbagai kota di Asia dan Eropa yang berasal dari 29 negara, para pakar dari UNESCO, WIPO, WTO, serta kalangan akademisi dan profesional di bidang preservasi arsitektur dan pelestarian kota. Konferensi merupakan salah satu sarana untuk mendiskusikan berbagai masalah dan saling tukar pengalaman dalam masalah perlindungan warisan budaya. Konferensi menghasilkan Solo Declaration on the Safeguarding and Protection of Heritage yang pada pokoknya menekankan pentingnya penjagaan dan perlindungan warisan budaya benda dan takbenda dalam pembangunan kota berkelanjutan yang dilaksanakan secara seimbang dengan pelestarian budaya sehinga mampu membentuk citra kota yang khas, termasuk pula pentingnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. Konferensi WHC di Solo ini, memiliki nilai strategis, sekaligus sebagai perjuangan awal dalam upaya melindungi, melestarikan dan mengembangkan warisan pusaka budaya. Seluruh peserta Konferensi ini sepakat untuk mengakui keragaman budaya dan pemahaman multi-budaya yang merupakan landasan untuk menciptakan dunia yang harmonis, dan secara signifikan akan memberikan kontribusi guna mengurangi ketegangan serta menyelesaikan konflik di seluruh dunia. Disamping itu, konferensi juga menyepakati bahwa warisan budaya dunia harus dicatat dalam daftar representatif UNESCO guna memperoleh pengakuan internasional atas hak paten/kepatenan atas warisan budaya tertentu. 58 Berkaitan dengan perlindungan warisan budaya, sesuai dengan permintaan RI, UNESCO telah memasukkan batik, keris dan gamelan ke dalam daftar warisan dunia yang perlu untuk dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan. Terkait dengan substansi Deklarasi Solo, Indonesia telah memasukkan satu butir tentang perlunya mempercepat dibuatnya instrumen internasional yang saat ini sedang dibahas dalam kerangka Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) guna mencegah penyalahgunan, misappropriation dan misexploitation terhadap aset budaya. HAKI tersebut akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap orginalitas warisan budaya yang dapat dipahami oleh masyarakat dunia. Upaya perlindungan, pelestarian dan pengembangan warisan pusaka budaya memang harus dilakukan secara simultan, dimulai dari tinggkan nasional, regional dan internasional. Untuk itu, peserta konferensi WHC juga merekomendasikan pejajagan kemungkinan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan budaya melalui pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, diharapkan pemerintah juga terus mendorong dan memfasilitasi inisiatif masyarakat terkait gerakan pelestarian warisan budaya. Rangkaian kegiatan konferensi ini meliputi pembukaan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, expo dan workshop yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri serta cultural event dan carnival. Sementara itu, konferensi ditutup oleh Walikota Surakarta yang sebelumnya membacakan Solo Declaration on the Safeguarding and Protection of Heritage. Pemimpin Umum Arif Havas Oegroseno Pemimpin Redaksi Mulya Wirana Redaktur Eksekutif Iswayudha Sidang Redaksi Moh. Zahir S. Soedajat Lefiana H. Ferdinandus Irma Dewi Rismayati Syahda Guruh L. S. Rheinhard Sinaga Rama Kurniawan Adhi Kawidastra Desain Visual Abdul Hayyi Bendahara Neneng Nur Farida Distribusi Uki Subki DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN LUAR NEGERI - REPUBLIK INDONESIA Jln. Taman Pejambon No.6 - Jakarta Telp. : (021) 384 6633 - 344 1508 Ext. 4212; Fax. : (021) 385 8044; Email : [email protected]