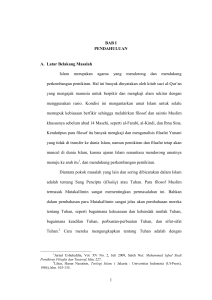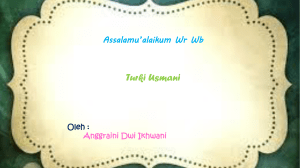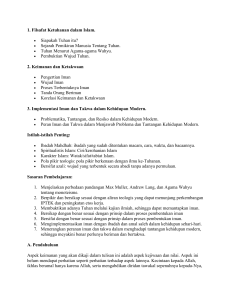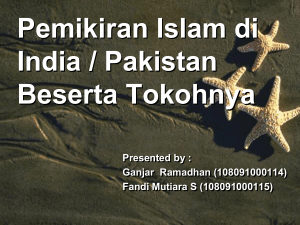Filsafat sebagai Mata Kunci
advertisement
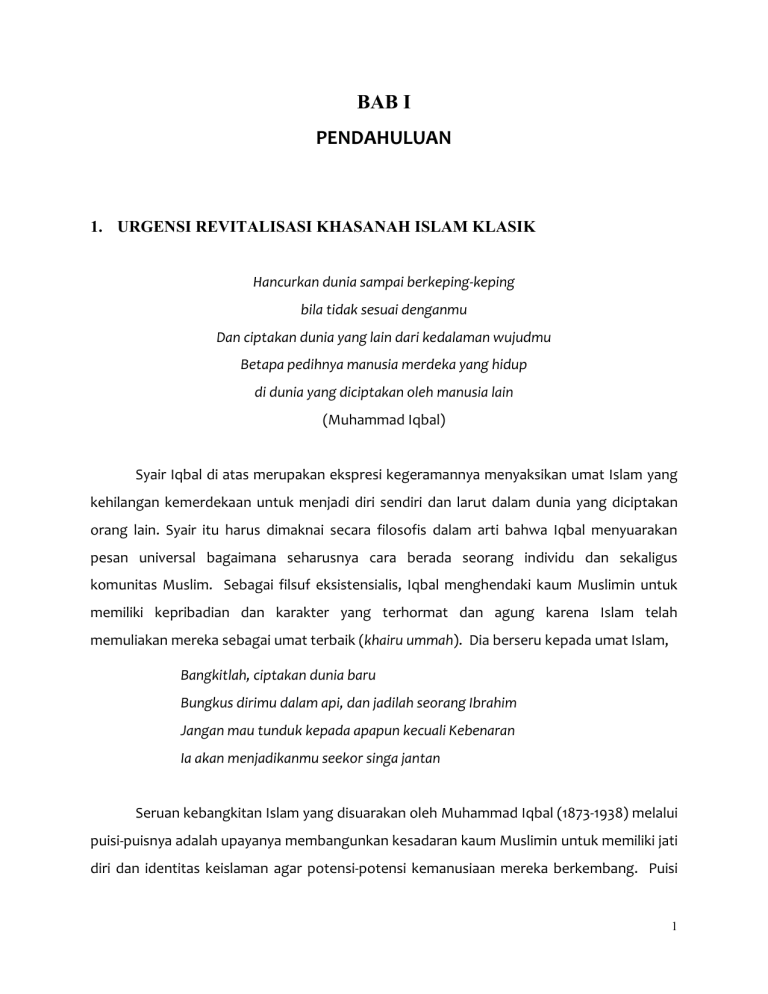
BAB I PENDAHULUAN 1. URGENSI REVITALISASI KHASANAH ISLAM KLASIK Hancurkan dunia sampai berkeping-keping bila tidak sesuai denganmu Dan ciptakan dunia yang lain dari kedalaman wujudmu Betapa pedihnya manusia merdeka yang hidup di dunia yang diciptakan oleh manusia lain (Muhammad Iqbal) Syair Iqbal di atas merupakan ekspresi kegeramannya menyaksikan umat Islam yang kehilangan kemerdekaan untuk menjadi diri sendiri dan larut dalam dunia yang diciptakan orang lain. Syair itu harus dimaknai secara filosofis dalam arti bahwa Iqbal menyuarakan pesan universal bagaimana seharusnya cara berada seorang individu dan sekaligus komunitas Muslim. Sebagai filsuf eksistensialis, Iqbal menghendaki kaum Muslimin untuk memiliki kepribadian dan karakter yang terhormat dan agung karena Islam telah memuliakan mereka sebagai umat terbaik (khairu ummah). Dia berseru kepada umat Islam, Bangkitlah, ciptakan dunia baru Bungkus dirimu dalam api, dan jadilah seorang Ibrahim Jangan mau tunduk kepada apapun kecuali Kebenaran Ia akan menjadikanmu seekor singa jantan Seruan kebangkitan Islam yang disuarakan oleh Muhammad Iqbal (1873-1938) melalui puisi-puisnya adalah upayanya membangunkan kesadaran kaum Muslimin untuk memiliki jati diri dan identitas keislaman agar potensi-potensi kemanusiaan mereka berkembang. Puisi 1 Iqbal merupakan manifestasi pemikiran filosofisnya yang mendesak individu-individu Muslim untuk merekonstruksi diri agar sejalan dengan amanah Tuhan sebagai khalifahNya di muka bumi. Murtadha Muthahhari (1919-1979) menyebutkan bahwa inti pemikiran Iqbal adalah ‘penyadaran diri’. Tetapi konsep ‘diri’ yang disasar iqbal tak terbatas hanya pada level individu tetapi juga meliputi diri umat karena sebuah komunitas serupa dengan individu yang memiliki ruh dan kepribadian. Menurut Iqbal, kaum Muslimin terlarang untuk menjadi umat pembeo, pengekor, peniru yang tak kreatif, dan lemah tak berdaya menghadapi gempuran sistem nilai-nilai asing yang menggerogoti keislaman dan kemanusiaan mereka. Dengan lantang Iqbal berseru, Jangan hinakan pribadimu dengan imitasi Bangunlah, hai kau yang asing terhadap rahasia kehidupan Nyalakan api yang tersembunyi dalam debumu sendiri Wujudkan dalam dirimu sifat-sifat Tuhan (Sumber: Miss Luce-Claude Maitre, Pengantar ke Pemikiran Iqbal, yang diterjemahkan oleh Djohan Effendi, Mizan, Bandung, 1981) Salah seorang Muslim merdeka yang menyambut imbauan Iqbal tersebut adalah Hassan Hanafī, pemikir asal Mesir (1934- ... ). Dia menolak imperialisme Barat yang telah membelenggu dan menghipnotis kaum Muslimin dan membuat mereka rela berada dalam penindasan dan penjajahan mental, pikiran, budaya, politik, dan ekonomi. Dia memaparkan bagaimana Barat sejak era kolonialisme hingga kini selalu berusaha mendistorsi ajaran dan citra Islam agar tercipta citra negatif terhadap dunia Islam dengan maksud Barat lebih mudah menundukkan dunia Islam. Jika pada era kolonialisme, melalui agenda Orientalisme, Barat menjuluki Islam sebagai pangkal kejumudan (kebodohan), maka hari ini Barat sesuai dengan kepentingannya mencitrakan Islam sebagai agama kekerasan dan agama yang tak toleran. Dan ironisnya, pencitraan yang mereka ciptakan berhasil memengaruhi mentalitas dan sikap sebagian umat Islam sehingga mereka pun ikut latah mewacanakan tema-tema seperti ‘Islam dan kekerasan’, ‘Pluralisme Agama’ atau ‘Islam Pluralis’ dalam seminar- 2 seminar, mengalahkan tema-tema yang lebih penting dan aktual untuk umat. Ini adalah sebuah contoh penjajahan mental pikiran. Dalam konteks itulah, Hassan Hanafi tergerak untuk melawan imperialisme kultural Barat yang telah begitu menghegemoni dunia Islam. Terinspirasi oleh Revolusi Islam Iran 1979 yang menurutnya berkarakter spiritual Islam, Hassan Hanafi berkesimpulan bahwa membangkitkan semangat Tauhid (Tawhīd) merupakan sebuah keniscayaan. Semangat Tauhid adalah inti dari revolusi dan kebangkitan Islam. Namun, pengertian semangat Tauhid yang dimaksudkan Hanafi bukan dalam pengertian literal yang dangkal dan antirasional sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum fundamentalis-skripturalistik seperti yang diekspresikan oleh kaum Wahabi. Tak seperti kaum salafi fundamentalis, pemahaman Tauhid yang hendak diusung bersifat rasional, filosofis, dan humanis dalam arti bersesuaian dengan fitrah manusia itu sendiri (realitas-fenomenologis manusia). Karena Hassan Hanafi merujuk Revolusi Islam Iran, ada baiknya kita mengutip pandangan Muthahhari, salah seorang arsitek revolusi tersebut. Menurut Muthahhari, pandangan-dunia Tauhid (the world view of Tauhid) bermakna bahwa alam semesta itu unipolar dan uniaksial; bahwa alam semesta pada esensinya berasal dari Allah (inna lillah) dan kembali kepadaNya (inna ilaihy raji’un). Pandangan-dunia Tauhid memahami bahwa alam raya dapat maujud melalui suatu kehendak bijak dan bahwa tatanan kemaujudan itu berdiri di atas dasar kebaikan dan rahmat sedemikian sehingga maujud-maujud memperoleh kesempurnaan mereka. (Muthahhari, Fundamentals of Islamic Thought, Mizan Press, Berkeley, 1985, hal. 74). Revolusi Tauhid, menurut Hassan Hanafī, memiliki tiga pilar, yaitu: (1) revitalisasi khazanah Islam klasik; (2) menentang imperialisme kultural dan peradaban barat; dan (3) analisis atas dunia Islam. Sasaran yang ingin dituju Hassan Hanafī adalah bagaimana kaum Muslim diperhitungkan kembali dalam sejarah peradaban dunia. Itu bisa dilihat dari sikapnya yang tertuang di dalam bukunya yang terbit dua tahun setelah Revolusi Islam Iran 1979, Kiri Islam (al-Yasār al-Islāmī), di mana dia mengatakan bahwa, “…kaum Muslim masuk kembali dalam gerak sejarah setelah Revolusi Islam akbar Iran pada permulaan abad 15 H”. (Hassan Hanafi, Kiri Islam, LKiS, Yogyakarta, 1993). 3 Pada dasarnya, visi dan harapan tersebut sesuai dengan misi dan tanggung jawab yang diemban kaum Muslim, sebagaimana yang dinyatakan Allah Swt., Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah (QS Āli Imrān [3]: 110). Entah kebetulan atau tidak, respons Hanafi terhadap seruan Iqbal di muka memiliki padanannya dengan apa yang dikemukakan oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Spiritual Iran sekarang. Sebagai peneliti puisi dan filsafat Iqbal, Khamenei menulis, “Kebijakan kita berdasarkan prinsip “tidak Timur tidak pula Barat” bersesuaian dengan apa yang Iqbal sarankan dan kehendaki. Kebijakan mandiri kita identik dengan pandangan Iqbal. Dan di dalam keyakinan kita bahwa Quran dan Islam dijadikan sebagai dasar dari revolusi dan pergerakan kita, kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Iqbal kepada kita.” (Sayyid Ali Khamenei, Iqbal: Penyair-Filsuf Pembaru Islam, Al-Huda, Jakarta, 2002) Dari Mana Kita Mesti Mulai? Mengikuti saran Hassan Hanafi, kita perlu melakukan analisis terhadap realitas objektif dunia eksternal sebagaimana juga realitas internal umat Islam sebagai langkah awal untuk menentukan langkah-langkah pencerahan dan kebangkitan umat. Dalam hal inilah kita menghadapi dua keadaan yang perlu dicermati. Di satu sisi, peradaban modern yang serba teknokratis-mekanistik dan pragmatis-materialistik kini telah sampai pada titik balik pemikiran yang cenderung bergerak menuju chaos, ambiguitas, relativisme, dan nihilisme sebagaimana yang ditunjukkan oleh postmodernisme. Optimisme Aufklarung abad 18 M telah berubah menjadi pesimisme abad 21. Kita menyaksikan bahwa jika modernisme ditandai dengan pemberhalaan kepada hal-hal yang terukur secara kuantitatif, bendawi, serba terkontrol dan mekanis seperti mesin, maka posmodernisme justru mengkhutbahkan hal-hal yang tak terukur, tak terkontrol, serba acak dan tak beraturan. Namun di lain sisi, keterbelakangan kaum Muslim dalam sosial-ekonomi-politik dan tradisi keilmuan, bahkan krisis moral, membuat sebagian besar kaum Muslim tergagap untuk mengantisipasi tantangan dan perubahan zaman yang sedemikian deras. Masih dalam periode merangkak memahami dan mengatasi modernisme, tiba-tiba kita sudah diterjang 4 oleh angin posmodernisme yang meniupkan gagasan-gagasan penuh kontradiktif. Ketika sebagian anak-anak muda Muslim bergairah mengusung rasionalisme dan humanisme modern, tiba-tiba mereka dihadapkan pada provokasi posmodernis yang menolak logika dan rasionalitas. Sebagian di antara mereka terpancing untuk turut merayakan gagasan posmodernisme dengan anggapan bahwa pemahaman itu memberi ruang bagi ‘iman’ yang mereka anggap di luar wilayah akal. Sebagian lain tidak memedulikan perkembangan arus pemikiran itu karena mereka sudah membulatkan tekad untuk meniru mentah-mentah rasionalisme dan humanisme modern dengan segenap konsekuensinya termasuk pengikisan keimanan dan identitas keislaman mereka. Sementara itu, dalam banalitas keseharian, kecendrungan titik balik zaman seperti itu bisa kita saksikan bagaimana hiruk pikuk teknologi audiovisual, TV dan internet telah membunuh budaya membaca yang baru tumbuh pada kalangan Muslim sedemikian sehingga mentalitas pasif dalam budaya menonton hidup kembali. Irasionalitas dan keengganan berpikir mendalam seakan mendapat tempat kembali dalam banalitas teknologi terkini. Jika pun mereka membaca, idola mereka adalah buku-buku fiksi ringan populer yang tidak menuntut imajinasi tinggi. Sinetron-sinetron klenik dan cerita-cerita yang tak masuk akal, yang kerap dibumbui oleh ekspresi religi –lantaran agama itu dianggap sesuatu yang irasional-, mendapat rating tinggi. Pesan-pesan agama pun banjir melimpah ruah melalui budaya banal yang tak menuntut pendayagunaan akal dan nurani itu. Poin yang hendak disampaikan di sini adalah apapun keadaan eksternal yang berkembang dan apapun pilihan sikap internal kita, umumnya hal itu secara de facto tidak keluar dari pilihan-pilihan yang disodorkan oleh pihak lain ke diri kita. Baik modernisme maupun posmodernisme lahir dan berkembang di Barat. Kita hanya mengunyah dan menelan paham-paham ini. Liberalisme dan pluralisme juga disuguhkan ke umat Islam untuk memamahnya mentah-mentah tanpa sikap kritis. Isu-isu feminisme dalam agama dipasok dari pengalaman dunia Barat. Wacana fundamentalisme agama dan kekerasan pun meruyak setelah Barat ketakutan menghadapi respons ekstrem kaum radikal baik lokal maupun global. Walhasil, dunia hari ini seakan memaksa kita untuk menuruti skenario dan paham- 5 paham yang datang dari Barat. Agaknya suara Iqbal yang menghendaki kita untuk berkemandirian dalam berpikir dan bersikap masih jauh dari harapan. Sebuah contoh konkrit bagaimana kejumudan berpikir umat kita perlu disebutkan di sini. Seorang rektor IAIN asal kota tertentu pada kesempatan Ceramah Isra’ Mi’raj di Istana Negara tahun 2007 lalu dengan bangga mengutip filsuf Kant dengan mengatakan, “Menurut Kant, ada realitas yang disebut noumena yang tak bisa kita ketahui. Akal kita tak mampu memahaminya. Namun, realitas inilah yang membuka ruang bagi iman kita. Iman adalah sesuatu yang kita yakini dan percayai karena di luar pengetahuan kita.” Sungguh ironis dan menggelikan. Kita bisa bayangkan seorang rektor perguruan tinggi negeri Islam saja jatuh ke dalam kekeliruan fatal seperti itu, bagaimana halnya dengan sarjana, mahasiswa, pelajar dan anak-anak muda Islam yang lain. Sang rektor itu lupa atau tak tahu bahwa Kant telah membunuh metafisika dan teologi. Alih-alih memberi ruang iman – yang amat sempit jika memang ada – Kant justru telah melapangkan jalan menuju agnostisisme, selangkah sebelum ateisme. Bahwa Kant adalah seorang yang religius secara praktis, itu adalah wilayah kajian lain semisal psiko-fenomenologis. Hal ini sama persis dengan fenomena Iblis yang sesungguhnya religius karena berkomunikasi dengan Tuhan tetapi dia justru menciptakan keraguan dalam pikiran manusia kepada wujud Tuhan dan mengingkariNya. Kita bagaikan kafilah tersesat yang tidak mengenal medan gurun pasir. Akan tetapi karena kita harus tetap berjalan untuk mempertahankan hidup maka apapun yang disampaikan oleh penjelajah lain –yang sesungguhnya juga tak mengenal medan - kita ikuti dan gunakan sebagai petunjuk jalan. Sementara kita tak mampu menggunakan petunjuk kompas yang sesungguhnya kita bawa dan warisi dari pendahulu kita. Dalam situasi sulit yang diilustrasikan seperti inilah status eksistensi umat Islam sekarang. Ada beberapa bentuk respons yang dilakukan. Sebagian kaum Muslim mengambil sikap pasrah terhadap peradaban Barat, bahkan beranggapan bahwa dunia Barat telah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dunia. Mereka beranggapan bahwa keimanan adalah urusan individu semata yang tak terkait dengan ideologi apapun. Bukankah pengalaman religius termasuk wilayah privat (private sphere of religious experience), demikian argumen 6 mereka. Oleh karena itu, mereka mengadaptasi total sistem nilai budaya yang asing dengan ruh Islam sedemikian rupa sehingga identitas dan eksistensi mereka sebagai Muslim luntur dan larut. Sebagian kaum Muslim lain berespons reaktif, ada yang berbentuk defensif dan ada yang mengambil sikap ofensif. Kaum Muslim yang bereaksi defensif berusaha mengisolasi diri dari pemikiran Barat seraya mempertahankan tradisi secara ketat. Meski mereka berhasil menjaga warisan tradisi Islam, mereka terjebak ke dalam apa yang disebut Mohammed Arkoun sebagai proses “taqdīs al-afkār al-dīnī” (pensakralan pemikiran keagamaan). Proses itu terjadi lantaran tradisi keilmuan yang melatih sikap kritis-komparatif telah hilang sehingga tidak mampu membedakan aspek normatif yang universal dengan aspek historis kemanusiaan yang relatif. Di Indonesia, kalangan Nahdlatul Ulama (NU) mematok empat mazhab fiqih (Hanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, dan Hanbalī), dan secara teologis berpegang pada Asy‘āriyah, sebagai ajaranajaran suci yang tidak boleh diinterprestasi ulang, apalagi dikritik. Sikap fatalis-nonkreatif ini pada gilirannya membuat mereka justru tidak mampu membendung pengaruh pemikiran dan budaya Barat, hal yang awalnya hendak mereka hindari. Mengapa demikian? Rupanya, mereka tidak menyadari akan hadirnya nilai-nilai peradaban dan kebudayaan Barat yang telah terkristalisasi dan terstruktur (built-in) dalam sistem pendidikan, teknologi, ekonomi, politik, dan komunikasi global yang menguasai dunia. Meski pun secara retoris mereka bersikeras mengklaim kemurnian Islamnya, kenyataannya mereka telah hidup dengan etika, epistemologi, kosmologi, kapitalisme, dan pandangan-dunia (world-view) Barat dalam kesehariannya. Pemimpin kaum ortodoks—meminjam istilah Fazlur Rahman—tersebut akhirnya mengidap penyakit inferiority complex (penyakit mental rendah diri), sehingga kadang mereka mencoba “sok kritis” (malah sampai membingungkan umat), tetapi pada saat yang sama mereka amat ramah dan membebek kepada Barat dan pihak asing. Ada pula analisis kultural yang menyebutkan bahwa hal itu terjadi juga lantaran masih belum hilangnya watak inlander (kaum terjajah, budak)—akibat praktik kolonialisme selama tiga setengah abad—pada kaum Muslim Indonesia. 7 Sementara itu, bentuk respons defensif lain ditunjukkan oleh kaum fundamentalisskripturalistik, seperti Wahabī, yang telah menetapkan ajaran Ibn Taimiyyah dan tradisi salafiyah sebagai standar baku pengajaran agama seraya mengharamkan pemahaman lain untuk berkembang. Kelompok Al-Qaeda, sebuah varian ekstrem salafi, bahkan menyerang siapapun di luar kelompoknya. Alih-alih pembebasan dari hegemoni asing, kelompok ekstrem ini justru membuka ruang intervensi kekuatan-kekuatan asing secara budaya, sosial politik dan bahkan militer seperti yang terjadi di Afghanistan dan sebagian wilayah Pakistan. Sedangkan negara-negara Arab yang menganut ajaran resmi Wahabi, yang berpegang teguh pada tradisi ritual agama versi mereka, malah telah menjadi satelit imperalisme sosial budaya dan militer Barat, khususnya Amerika Serikat. Seruan puisi-puisi eksistensialis Iqbal dan teriakan revolusi Tauhid Hassan Hanafi sama sekali tak terdengar di jazirah tempat lahirnya Islam ini, setidaknya untuk saat ini. Terkait dengan respons kaum ekstrem yang kerap terkait dengan aksi kekerasan dan teror, menarik untuk mengutip apa yang ditulis oleh Karen Armstrong. Dalam bukunya yang bestseller, The Battle for God: A History of Fundamentalism (New York, 2001), Armstrong mengisahkan bahwa fundamentalisme radikal agama, yang sering dituding sebagai salah satu akar kekerasan, lahir di penghujung era modern (sekarang post-modern) sebagai sebuah respons irasional terhadap sekulerisme dan krisis spiritual dunia modern. Mereka dihadapkan pada situasi yang sulit mereka pahami bagaimana hidup yang bermakna sebagai seorang yang beriman dalam dunia modern yang sekuler atau bagaimana mengakomodasi tantangan-tantangan modern dalam horizon keimanan mereka. Bertali-temali dengan isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan global, marjinalisasi, perasaan terasing dari peradaban dunia (the other) maka lahirlah paham fundamentalisme agama sebagai respons yang paling mudah dan instan. Dalam kutub respons yang lain, kaum Muslim yang bereaksi ofensif berusaha bersikap proaktif terhadap peradaban Barat modern dengan menyerap nilai budaya Barat yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam, misalnya ilmiah-rasionalitas, kritis, progresif, disiplin, seraya membuang nilai Barat modern yang bertentangan dengan Islam, seperti individualisme, materialisme, sekularisme. Mereka juga membuka kembali pintu ijtihad 8 sebagaimana yang diserukan oleh Iqbal sejak awal abad ke-20. Dalam banyak hal, mereka memang berhasil membangun sistem pendidikan dan ekonomi modern yang tidak begitu kalah jauh dibanding dengan sistem Barat. Kalangan Muhammadiyah beserta kerabat dekat mereka seperti kalangan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Hizbut Tahrir di Indonesia, Jamī‘at al-Islāmī di Pakistan, Ikhwan al-Muslimin di Mesir–Suriah, atau FIS (Front Penyelamatan Islam) di Aljazair, telah melahirkan banyak sarjana dan cendekiawan kritis yang mampu berkomunikasi secara elegan pada level global. Akankah mereka dapat menjadi lokomotif kebangkitan Islam sebagaimana yang kita harapkan? Tidak juga! Mengapa demikian? Mengapa kita tidak dapat menggantungkan harapan proyek kebangkitan Islam sepenuhnya pada mereka yang notabene telah berhasil membangun dunia pendidikan dan jaringan ekonomi jauh lumayan bagus daripada kaum tradisionalis? Dalam hal ini, ada satu hal terpenting yang tidak dapat kita lupakan, yaitu fenomena dissemination of culture (penyebaran, penaburan budaya). Kebudayaan bukanlah benda mati yang dapat kita preteli bagian-bagiannya, lalu kita pasang kembali untuk membangun kebudayaan baru. Kebudayaan bukanlah mobil. Kebudayaan dari suatu world-view atau ideologi merupakan kesatuan organis yang satu sama lainnya tak terpisahkan. Kebudayaan adalah sesuatu yang hidup dan dinamis. Suatu kebudayaan dan peradaban juga tidak lahir dari kevakuman. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa bahwa kebangkitan Barat modern sejak abad ke-17 dalam ranah sains dan teknologi tidaklah jatuh dari langit. Sains dan teknologi Barat berkembang secara revolusioner melalui apa yang disebut dengan Revolusi Copernicus. Kosmologi modern ini ditafsirkan secara filosofis sebagai kebangkitan subjektivitas manusia. Gerakan Renaisans dan antroposentrisme merupakan gerbang utama menuju peradaban Barat modern. Bapak filsafat Barat modern, René Descartes (1596–1650), mengumandangkan suatu doktrin yang menggambarkan semangat awal peradaban Barat modern, yaitu: cogito ergo sum (aku berpikir, maka aku ada). Filsafat dan sains Barat modern lahir dari semangat dan suasana pemberontakan terhadap tradisi teologi, metafisika, moral, dan nilai agama seraya memproklamirkan manusia sebagai pengganti Tuhan dalam menguasai alam semesta. Humanisme sekular merupakan pandangan-dunia yang inheren dalam peradaban modern. 9 Lalu, bagaimana cara bekerjanya diseminasi kultur tersebut? Modus Operandi Diseminasi Kultur Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kebudayaan bukanlah benda mati, melainkan kesatuan organis. Suatu kebudayaan asing akan tumbuh dan berkembang biak dalam tubuh umat kita secara alamiah tanpa kita sadari, jika kita tidak memiliki falsafah dan pandangan-dunia sendiri. Oleh karena itu, kebudayaan Islam atau peradaban Islam hanya dapat dibentuk dengan filsafat, paradigma, dan nilai Islam itu sendiri. Berikut akan dikisahkan proses diseminasi kultur (penaburan budaya) Barat yang terjadi secara alamiah tanpa dapat dielakkan lagi oleh masyarakat Islam Turki. Proses sekularisasi atau bahkan sekularisme yang melanda Turki tanpa disengaja sejak awal itu, bermula dari keinginan Turki ‘Utsmānī untuk meminta bantuan militer Barat. Sejarawan ternama, Arnold J. Toynbee (1889–1975), mengisahkan peristiwa permintaan Turki ‘Utsmānī akan ahli-ahli militer Barat untuk memperkuat Angkatan Laut Turki guna menghadapi Eropa yang di luar dugaan telah memiliki armada tangguh. Penasihat dan teknisi militer yang dibayar mahal tersebut bersedia untuk memenuhi permintaan itu, dengan konsesi mereka diperbolehkan mengajak keluarga mereka ke Turki. (jika mungkin, tolong Dian cari referensinya ya, saya lupa dari buku mana saya kutip) Konsesi ini pada gilirannya juga memaksa Kerajaan ‘Utsmānī membolehkan kehadiran dokter-dokter Eropa guna merawat kesehatan keluarga teknisi militer Eropa tersebut. Dokter-dokter Eropa ini sering menggunakan waktu senggangnya untuk menyelidiki kesehatan masyarakat Turki, dan beberapa kali sempat menyelamatkan warga dari penyakit akut. Suatu ketika, dokter Eropa yang semuanya laki-laki tersebut menyelamatkan seorang wanita hamil, dan ini berarti melanggar tradisi pergaulan laki-laki dan wanita yang begitu ketat diterapkan di Turki ‘Utsmānī ketika itu. Sebuah diseminasi budaya baru dimulai. Masyarakat Turki segera menyadari keterbelakangannya dalam sains dan teknologi dibanding dengan musuhnya, Eropa. Sementara kaum ulama dan inteletual mereka, karena sibuk dengan urusan politik, tidak 10 membangun fundasi filosofis dan paradigma peradaban Islam yang menopang kekhalifahan Usmani ketika itu. Krisis jati diri dan kebudayaan Islam ini memuncak dengan tumbangnya Kekhalifahan Turki ‘Utsmānī dan berdirinya Republik Turki sekular yang dipimpin Kemal Mustafa Ataturk (1881–1938). Pemimpin sekularistik Turki ini tidak sekadar mengundang teknisi Barat, melainkan turut mengimpor seluruh bangunan pemikiran Barat, termasuk penggantian huruf Arab menjadi huruf Latin. Itulah sebuah kisah diseminasi budaya Barat yang terjadi pada Turki yang kehilangan kepercayaan diri pada tradisi khazanah Islam. Alih-alih menjadi negara kuat yang mampu menyaingi Barat, Turki justru jatuh menjadi negeri sekular yang mengemis-ngemis kepada Barat untuk diterima sebagai anggota Uni Eropa. Nasib tragis yang dialami Turki tersebut, pada level yang lebih rendah, juga terjadi pada negara-negara Muslim yang terlena dengan proyek modernisasi Islam tanpa apresiasi terhadap kekayaan khazanah intelektual Muslim sebagai latar belakang budaya mereka. Pakistan, Mesir, Aljazair, dan Indonesia adalah negeri Muslim yang secara politis, ekonomi, dan pendidikan bergantung pada Barat. Lebih jauh lagi, nilai-nilai budaya dan peradaban mereka lebih berfungsi sebagai satelit-satelit kepentingan peradaban dunia global Barat. Satu contoh konkrit adalah misalnya bagaimana negara kita telah menyerahkan sepenuhnya kekayaan alam kita kepada perusahaan-perusahaan Barat seperti Exxon, Freeport, Newmont dan sebagainya untuk mereka eksplorasi habis-habisan sedemikian rupa sehingga tak jarang instansi pemerintah terkait tidak tahu menahu kandungan mineral apa yang telah mereka kuras dari perut bumi Indonesia. Padahal, kita tahu Pertamina dan BUMN lain sudah puluhan tahun aktif dan tiap tahun kita meluluskan ribuan insinyur dan teknisi pertambangan. Ini bukanlah persoalan teknis-ekonomis semata tapi juga kalkulasi politik yaitu ketergantungan politik luar begeri kita. Semisal, pemerintah kita tidak berani mengusik eksplorasi tambang di Papua oleh Freeport karena takut terhadap sikap Amerika Serikat yang mengancam akan menarik dukungannya terhadap integrasi Papua dalam NKRI. 11 2. PERAN FILSAFAT DAN PEMIKIRAN ISLAM Uraian di muka menggambarkan pentingnya suprasistem nilai budaya sebagai basis pengembangan sistem-sistem ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan iptek yang bermuatan nilai-nilai Islam. Suprasistem adalah sistem nilai budaya primer yang melandasi segenap sistem sosial sebuah kebudayaan dan peradaban. Dalam istilah sejarawan antropolog Fernand Braudel, suprasistem itu disebut sebagai ‘mentalite’, sebuah struktur/lapisan kesadaran terdalam sebuah masyarakat (A History of Civilizations, Penguin Books, London, 2001). Sedang kebudayaan itu sendiri disebut Clifford Geertz sebagai sistem simbolik signifikansi, yaitu “pola-pola makna yang melekat dalam simbol-simbol yang diwariskan secara historis yang dengannya manusia mengkomunikasikan, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap hidup” (Geertz, The interpretation of Cultures, Basic Book, New York, 1973. hal. 89). Mengacu kepada tiga wilayah/struktur kebudayaan yang dirumuskan oleh Koentjaraningrat (Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1985) , suprasistem adalah sistem ideofak yang terdapat pada lingkaran paling dalam wilayah kebudayaan (lihat gambar berikut). 3 2 1 1. ideofak : sistem gagasan, nilai, asumsi-asumsi dasar 2. sosiofak: sistem sosial, perilaku, kebahasaan (ekspresi ide) 3. artefak: bentuk material Tanpa latar belakang kesadaran budaya dan pandangan-dunia Islam yang kukuh sebagai ideofak (sistem gagasan), program Islamisasi apa pun akan menemui kebuntuan. Nilai-nilai 12 Islam bukanlah sebuah produk manufaktur yang instan sehingga dapat diamalkan begitu saja tanpa basis diskursus intelektual-epistemologis yang matang. Sebagai contoh, program Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikumandangkan sesuai Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Islam pada 1977, sampai kini belum berjalan seperti yang diharapkan. Konsep Islamisasi sains yang ditawarkan Isma‘il Raji al-Faruqi dengan mensintesiskan ilmu-ilmu tradisional Islam ke dalam buku-buku daras sains modern mendapat kritikan tajam dari sarjana Muslim sendiri. Hal yang dilakukan al-Faruqi tidak lebih sekadar mencangkokkan kepingan-kepingan ilmu Islam ke dalam kultur organis sains modern, tanpa menawarkan paradigma sains baru yang Islami. Paradigma positivisme yang merupakan fondasi sains (epistemologi) Barat modern sama sekali tidak digubris, padahal pokok persoalan Islamisasi sains justru terletak pada bagaimana kita memanfaatkan sains sebagai salah satu unsur dalam stuktur pengetahuan Islam untuk menyingkap realitas yang berdimensi ilahiah. Dengan demikian, program Islamisasi sains tidak akan berjalan tanpa didahului pengkajian epistemologi (filsafat pengetahuan) Islam. Studi epistemologi Islam pada gilirannya juga menuntut studi ontologi-metafisika Islam, yaitu pandangan Islam ihwal realitas dari prinsip-prinsip kemaujudan. Oleh karena itu, Munawar A. Anees menyambut gembira usaha Seyyed Hossein Nasr yang memperkenalkan citra baru sains Islam yang ditopang dengan elaborasi khazanah filsafat Islam klasik. Nasr, dalam bukunya Man and Nature : The Spiritual Crisis of Modern Man (Chicago, 1997) berhasil menelanjangi argumenargumen yang memandang sains Barat modern sebagai bebas nilai. Sains modern seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, terlebih ilmu-ilmu humaniora, ternyata sarat dengan bias ideologi dan nilai Barat. Urgensi menghidupkan kembali filsafat Islam kian terasa jika disadari bahwa pelbagai nilai materialisme, agnostisisme, pragmatisme, dan positivisme peradaban Barat telah menggurita dalam struktur kehidupan modern. Nilai-nilai yang mengikis fitrah kita sebagai manusia hanīf (gandrung kepada kebenaran) itu, bukan saja telah memasuki ruang personal kita—seperti kamar tidur—melalui TV, internet, ruang-ruang kelas, perkantoran, pasar, kampus, dan masjid, tetapi juga telah membentuk pola berpikir kita memandang dunia.. 13 Kebiasaan menonton film action tentang kehebatan kekuatan fisik dan militer, misalnya, akan membangun mentalitas yang mengutamakan kekuasaan fisik (hardpower) dalam menyelesaikan setiap persoalan. Fenomena ini mungkin bisa dijelaskan dengan bantuan teori “praktek” (practice) yang dikemukakan oleh Piere Bourdieu. Menurut Bourdieu, manusia sebagai agen juga turut mengkonstruksi simbol dan nilai budaya yang dia adopsi melalui interaksi dengan kondisi sosial sebagai wahana cara dia berada (habitus). Nilai-nilai asing yang meracuni Tauhid dan fitrah kemanusiaan kita memang subtil (halus), hal yang mengingatkan kita pada sabda Nabi Saw. bahwa “Kemusyrikan itu halus dan tidak tampak, bagaikan semut hitam berjalan di atas batu pada kegelapan malam”. Jika kita mengatakan bahwa hanya orang yang memiliki pandangan Tauhid mendalam yang dapat melihat kemusyrikan itu, maka kita bisa pula mengatakan bahwa orang yang memahami filsafat Islam dan Barat yang dapat melihat penjajahan mental kaum Muslim oleh nilai-nilai Barat. Sebuah contoh yang menunjukkan keterjajahan kaum Muslim secara mental pikiran adalah keberhasilan Barat menanamkan pandangan bahwa semua negara Barat adalah Dunia Pertama (negara maju), sedangkan negara-negara Islam adalah Dunia Ketiga (negara berkembang). Penggunaan istilah “Dunia Ketiga” mengesankan bahwa kita hanyalah ibarat penumpang dalam kapal yang dinahkodai Barat. Dunia ini milik Barat, kita harus ikut bersamanya jika ingin selamat mengarungi lautan dunia. Semua negara Barat adalah negara maju yang menjadi model, standard, dan referensi kita dalam segala tujuan ekonomi, demokrasi, pendidikan, iptek, dan peradaban. Oleh karena itu, pembangunan negara kita, yang dikategorikan sebagai negara berkembang, harus mengacu pada segala ukuran, kriteria, dan indikator yang diterapkan Barat melalui lembaga-lembaga internasional yang mereka bentuk, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, Amnesti International, dan sebagainya. Pada akhirnya, pranata sosial, ekonomi, politik, dan hukum negara kita terpaksa dikonstruksi sedemikian rupa agar sesuai dengan struktur pranata induk semang Barat. Oleh sebab itulah, nasib ekonomi kita, misalnya, menjadi sangat bergantung pada pasar internasional kapitalistik yang setiap saat membutuhkan tumbal agar roda ekonomi dunia berjalan. Krisis moneter dan ekonomi yang kita alami hampir satu dekade merupakan 14 sebuah contoh betapa lembaran-lembaran kertas dolar perekonomian dan menguras kekayaan alam kita. dapat mengobrak-abrik Betapa berkuasanya sistem perekonomian dunia kapitalistik sehingga dapat mengendalikan harga barang-barang negara “Dunia Ketiga” hanya melalui permainan valuta asing. Pada saat yang sama, miliaran dolar kekayaan negeri kita mengalir deras ke Amerika Serikat dan Eropa melalui royalti berbagai produk mereka, seperti merek barang/jasa, periklanan, film, musik, dunia hiburan, dan produk budaya Barat lainnya yang diimpor. Penjajahan ekonomi ini bersumber dari penjajahan budaya, penjajahan mental pikiran, penjajahan pandangan hidup, di samping kejumudan dan terpasungnya daya nalar dan kreatif umat Islam itu sendiri secara internal. Revitalisasi Membutuhkan Reinterpretasi Tradisi Menyimak nasib dua bentuk respons (defensif dan ofensif) kelompok kaum Muslim yang katakanlah gagal merespons tantangan zaman seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa tidak ada jalan lain yang mesti kita tempuh selain merintis jalan ketiga (The Third Way). Jalan yang kita pilih ini bermaksud mengambil sisi positif dari respons pertama yang mewarisi tradisi dan khazanah klasik Islam, dan membuang sisi negatifnya, yaitu matinya proses kreatif dalam memahami dan menyingkap kekayaan intelektual Islam. Jalan ketiga ini juga mengambil semangat dinamis dan pembaharuan (tajdīd) pemikiran Islam dengan mengapresiasi kekayaan khazanah klasik Islam. Kedua bentuk respons yang selama ini dipraktikkan kaum Muslim lahir dari cara berpikir yang sama, yaitu memandang tradisi keilmuan Islam sebagai produk sejarah, bukan sebagai proses interpretasi (penafsiran) yang selalu menyingkap makna ajaran Islam yang tak habis-habisnya digali itu. Mereka sama-sama menganggap khazanah Islam klasik sebagai tradisi yang taken for granted atau museum kebanggaan identitas umat, bukan sebagai sarana yang inheren dalam penerapan dan pembaharuan makna kandungan ajaran Islam yang membutuhkan kreativitas dan perluasan horizon umat. Akibatnya, mereka memusatkan perhatian pada satu pilihan dari dua alternatif: bersikap apologi terhadap Barat dengan mensakralkan tradisi atau bersikap progresif dengan meninggalkan tradisi. Kedua 15 bentuk respons ini telah terbukti tidak berhasil membangun kembali kepercayaan diri (self esteem) dan kesadaran kolektif umat untuk bangkit kembali menjadi pelaku sejarah, sebagai saksi, atau menurut istilah al-Qur’ān sebagai ummatan wasathan (wasit terhadap perbuatan umat manusia). Jalan ketiga mendukung gerakan tajdīd (pembaharuan) yang tiada henti sebagaimana kehidupan itu sendiri merupakan perubahan dan gerak evolusi menuju kesempurnaan. Namun, tajdīd yang dilakukan haruslah berangkat dari tradisi yang telah kita miliki dan ikut membentuk diri kita sekarang. Tanpa tradisi, tidak mungkin tajdīd yang sesungguhnya dilakukan. Tradisi merupakan kekayaan sejarah yang sarat nilai dan mampu memandu dan memotori gerak umat menuju pencerahan dan kebangkitan kembali (Renaisans Kedua). Oleh karena itu, menurut Hassan Hanafī, tradisi adalah sumber dan inti gerak untuk menjaga keberlangsungan umat, dan mendorongnya ke arah kemajuan dan mengantisipasi perubahan sosial. Bagi Nurcholish Madjid, biasa disapa Cak Nur, tradisi keilmuan Islam berguna untuk membangun keautentikan peradaban Muslim itu sendiri. Menurut Cak Nur, tanpa apresiasi akan tradisi Islam, kita tidak mungkin menghidupkan dan mengembangkan kembali etos keilmuan Muslim yang amat tinggi (Kaki Langit Peradaban Islam, Paramadina, Jakarta, 1997 Kita bisa lihat bagaimana kisah gerakan tajdīd yang dulu bergema di seantero Dunia Islam, termasuk Indonesia, kini kehilangan momentum. Sudah seratus tahun lebih api pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamāl al-Dīn al-Afghāni, namun tampaknya kaum pembaharu Islam menjadi mandek dan kehabisan nafas. Hal ini terjadi lantaran mereka hanya mengambil api pembaharuan al-Afghāni, tetapi gagal menguasai sumber api itu sendiri, yaitu tradisi intelektual dan hikmah (filsafat). Padahal, seperti dikatakan al-Afghāni, ketiadaan filsafat dan tradisi keilmuan di kalangan kaum Muslim menjadi sumber kemunduran mereka. Ketiadaan filsafat, selama ini, menjadikan kaum Muslim tidak seperti pendahulu mereka, konsumen-konsumen yang tidak kritis bagi segala sesuatu yang datang dari kebudayaan lain dan menjadi kaum yang tersubordinasikan terhadap kelompok lain. Walhasil, mereka menemui kebuntuan dalam meneruskan gerakan tajdīd itu sendiri. Hal itu menambah daftar kejumudan umat. 16 Oleh karena itu, tajdīd mesti kita pahami sebagai proses reinterpretasi terhadap tradisi sesuai dengan kebutuhan zaman. Tradisi merupakan sarana pembaharuan. Menurut Hanafī, nilai tradisi bukan pada dirinya, melainkan pada elaborasi terus-menerus untuk menafsirkan realitas dan mentransformasi fakta-fakta menjadi nilai-nilai. Untuk itu, tak syak lagi, kita membutuhkan proses reinterpretasi yang melibatkan kajian-kajian hermeneutik dan fenomenologi. Hermeneutik diterapkan untuk melangsungkan proses dialektika pemahaman dan penafsiran terus menerus untuk selalu menyingkap makna-makna teks tradisi historis, sedangkan fenomenologi berguna untuk menganalisis realitas-realitas: masyarakat, politik, ekonomi, khazanah Islam, dan tantangan Barat. 3. URGENSI STUDI FILSAFAT DI DUNIA ISLAM1 Sub-bab ini menguraikan secara kontekstual tentang perlunya dunia Islam menghidupkan kembali filsafat agar pembaca setidaknya dapat memahami mengapa studi filsafat dan khususnya filsafat Islam sangat penting dan mendesak kita lakukan khususnya di tanah air Indonesia. Selain sebagai pembentuk dasar pandangan dunia Islam yang mengisi ruh kebudayaan dan peradaban Islam sebagaimana panjang lebar telah dipaparkan sebelumnya, filsafat sebagai sebuah metode berpikir dalam menganalisis persoalan secara radikal (mengakar, mendasar) dan menyeluruh juga turut berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku keseharian kita baik sebagai individu maupun warga masyarakat. Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sudah cukup lama umat Islam di Indonesia terjebak ke dalam pola pikir pragmatis, legalistik, dan product oriented yang selalu mengukur manfaat suatu wacana dan aktivitas dari nilai guna seketika (instantly), formalitas yang tertera secara verbal linguistik, dan kasat mata yang dapat dihitung dengan angka. Dalam pemilu legislatif dan presiden atau gubernur misalnya, umat kita mudah sekali 1 Tulisan sub-bab 3 ini awalnya adalah esai yang disusun bersama dengan Pak Haidar Bagir, dan penah dimuat oleh Harian Republika pada tanggal 7-8 November 2001, yang kemudian dimodifikasi sekitar 20 persen untuk disesuaikan dengan konteks dan isi bab buku ini (penulis) 17 dibujuk oleh sesuatu yang bermanfaat dalam jangka pendek, katakanlah uang dan sembako, tetapi melupakan efek jangka panjangnya kepada bangsa dan diri mereka sendiri. Praktek money politics tentu saja akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang culas dan tak bertanggugjawab kepada bangsa karena mereka harus mengejar ‘setoran’ membayar kembali biaya kampanyenya hingga ratusan milyar rupiah. Pola pikir seperti inilah yang menjerumuskan kita untuk selalu bertindak kasuistik (ad hoc), yaitu tindakan-tindakan yang merupakan respons parsial terhadap situasi sesaat sehingga cenderung bersifat atomistik, terpisah-pisah (segregated), dan reaktif. Paradigma berpikir yang tertawan oleh situasi kekinian dan kesinian ini (spasio temporal) justru bertentangan dengan keunggulan manusia sebagai mahkluk transendental, yakni kemampuan kreatif dan nalar insani untuk mampu melampaui batasan-batasan spasio temporal. Menurut Cak Nur, krisis bangsa yang kita alami sekarang ini tidak terlepas dari kesalahan kebijakan kita di masa lalu, yaitu memprioritaskan pembangunan ekonomi, tetapi mengabaikan pengembangan sumber daya manusia. Cak Nur mengatakan sekiranya sejak dulu kita menomorsatukan pendidikan ketimbang ekonomi, mungkin krisis kita tidak separah seperti sekarang—dia seraya mencontohkan Korea Selatan yang cepat bangkit dari krisis karena tingkat pendidikan masyarakatnya yang relatif lebih tinggi. Filsafat sebagai Mata Kunci Mungkin di luar dugaan perkiraan banyak orang jika disebutkan bahwa filsafat dapat berguna membantu penyelesaian problem-problem konkret seperti sosial politik, penegakan supremasi hukum, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, dan sebagainya. Berbagai krisis yang tengah kita hadapi sekarang (krisis-krisis ekonomi, politik, kepemimpinan, disintegrasi, moral, kepercayaan, budaya, lingkungan, dan sebagainya), jika tidak dikatakan bermula dari, setidaknya, berkorelasi erat dengan krisis persepsi yang terjadi di benak kita baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang masing-masing telah memiliki kesadaran/memori kolektif (collective memory). Salah satu bentuk krisis persepsi yang kerap terjadi adalah ketidakmampuan kita menangkap substansi suatu persoalan, termasuk hal ihwal persoalan kebangsaan kita hari 18 ini. Betapa banyak perdebatan-perdebatan ilmiah, terlebih lagi yang populer seperti yang dipertontonkan oleh media elektronik, hanya mengupas permukaan persoalan. Pembahasan dan diskusi yang terjadi kerap bersifat superfisial (dangkal), atomistik, terpilahpilah, monokausal, dan simplistik (terlalu menyederhanakan). Perdebatan wacana tentang isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, gender, pluralisme, dan sebagainya tidak jarang malah kontraproduktif lantaran tidak tergalinya muatan-muatan filosofis yang menjadi asumsi dasar dari isu-isu tersebut, demokrasi, misalnya. Sebagai contoh, jika kita memerhatikan saksama perdebatan politik antara eksekutif dengan legislatif, hal itu kentara sekali mementaskan bahwa para petinggi politik kita lebih disibukkan oleh soal-soal yang berkaitan dengan perasaan, emosi, dan harga diri. Perang statement antara petinggi politik kita lebih merepresentasikan ledakan emosi dan respons ketersinggungan perasaan pribadi mereka daripada sebagai debat wacana yang memasuki substansi persoalan. Pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan cenderung provokatif dan sentimental, dan sangat jarang mengemukakan argumentasi-argumentasi yang dapat diverifikasi secara rasional. Praksis politik negara kita masih primitif karena menganggap kekuasaan politik formal menjelmakan kekuasaan negara itu sendiri, bukan sebagai pentas bagaimana mengelola negara ini secara dewasa, rasional, dan beradab. Sudah saatnya para pengambil kebijakan negara, termasuk kaum intelektual bangsa, mempelajari logika, etika, filsafat manusia, filsafat politik, dan hal senada lainnya. Keterlatihan berpikir filosofis yang rasional, kritis, refleksif, radikal (mendasar, mendalam), sistematis, dan menyeluruh secara epistemologis akan mengonstruksi pemikiran dan mental kita untuk lebih rendah hati, bijak, rasional (tidak sentimental), transparan, dan membuka ruang dalam diri untuk siap dikritik dan berdiskusi secara argumentatif. Sebuah penerapan praktis dari epistemologi untuk pendekatan ilmu-ilmu sosial telah digunakan sejak 1990-an, yaitu apa yang disebut sebagai analisis wacana (discourse analysis). Analisis wacana ini menyoroti bagaimana suatu perspektif dapat terbentuk pada diri seseorang atau sekelompok orang dalam memersepsi realitas. Analisis ini meneliti, mendiskusikan, dan menguji kesahihan dan akuntabilitas keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 19 mengacu kepada prinsip-prinsip politik, baik pada tingkat empiris (matter of fact) maupun pada tingkat normatif (matter of principle). Dengan demikian, setiap keputusan politik dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Usulan pencabutan atau pengesahan suatu undang-undang, misalnya, mesti diuji dulu pada tingkat empiris dan tingkat normatif. Usulan pencabutan UU Penodaan Agama misalnya, mungkin secara normatif usulan tersebut ada peluang untuk dapat dipertimbangakn karena sesuai dengan prinsip kesetaraan hukum warga negara, namun apakah pada tataran realitas empiris usulan tersebut diterima oleh rakyat kebanyakan sehingga menjamin tercapainya tujuan usulan pencabutan tersebut, kalau malah bukan menambah runyam persoalan. Kecuali itu, realitas sosio-kultural-historis kita sebagai bangsa pun perlu dipertimbangkan; semisal ideologi negara Pancasila yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama dengan segenap aturan perundangan di bawahnya. Walhasil, boleh dikatakan studi filsafat dapat berperan mengasah dan mempertajam penalaran kita, dan juga membongkar kejumudan pola pikir yang kita warisi begitu saja yang seakan turun dari langit (taken for granted). Filsafat ibarat obat mujarab bagi krisis persepsi yang berkorelasi erat dengan problem-problem konkret. Filsafat bagaikan mata kunci yang membuka hijab-hijab formalisme dan irasionalisme untuk menembus dan menangkap substansi persoalan. Antisipasi Krisis Modernisme Evolusi ilmu pengetahuan dan kebudayaan manusia telah sampai kepada zaman yang memaksa kita untuk berpikir holistik, sistemik dan refleksif-mendalam dalam memahami realitas. Berpikir holistik maksudnya adalah suatu bentuk kognisi yang memahami realitas sebagai suatu sistem keseluruhan yang utuh. Tak seperti berpikir parsial yang memulai dari bagian untuk memahami keseluruhan, berpikir holistik memulainya dari pemahaman keseluruhan sebelum memasuki bagian-bagiannya. Persoalan pemanasan global (global warming), misalnya, harus dipandang sebagai suatu fakta keseluruhan menyangkut atmosfir Bumi kita, yang tidak bisa ditangani parsial oleh beberapa negara. Karena itu, penyelesaiannya harus ditangani bersama yang menuntut keutuhan dalam sikap dan 20 bertindak. Efek pemenasan global hanyalah salah satu isu penting dalam apa yang disebut sebagai krisis ekologis. Krisis yang hangat dibicarakan sekarang ini sesungguhnya telah mengentakkan kesadaran manusia modern untuk menggugat pandangan kosmologi modern yang positivistik-antroposentris yang mereka anut hampir tiga abad. Krisis ini menggugah seorang filsuf analitik dari Norwegia, Arne Naess, yang melakukan hijrah intelektual untuk menjadi pelopor apa yang disebut sebagai Gerakan Ekologi Dalam (Deep Ecology Movement) pada pertengahan 1970-an. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat dan telah mengarah kepada ancaman eksistensi dan kemuliaan martabat manusia juga mendorong kaum pemikir dan cendekiawan untuk menoleh kembali etika dan moral. Perkembangan bioteknologi semisal kemungkinan praktek pengklonan manusia, misalnya, mendorong ilmuwan, filsuf dan agamawan merumuskan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah bioetika. Pada saat yang sama, pada tataran internal ilmiah, kemajuan revolusioner sains secara tak terduga merubuhkan positivisme sebagai paradigma standar epistemologi modern. Banyak ilmuwan yang tiba-tiba beralih menjadi filsuf. Fisikawan Thomas Kuhn, misalnya, mencoba memahami gerak laju ilmu pengetahuan--yang menurutnya diskontinu—dengan mengembangkan konsep “paradigma” sains yang berkorelasi erat dengan metafisika dan nilai (The Structure of Scientific Revolutions). Fritjof Capra, bahkan, terpaksa menoleh hikmah Timur, khususnya Taoisme, untuk membingkai kembali bangunan ilmu pengetahuan dari puing-puing relativime dan skeptisisme (The Tao of Physics). Tampaknya, sejarah telah menuntut kita bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak boleh melupakan induknya, yakni filsafat. Namun, krisis modernisme tidak berhenti pada krisis epistemologis dan ekologis saja. Krisis yang lebih akut lagi adalah krisis-krisis eksistensial yang menyangkut hakikat dan makna kehidupan itu sendiri. Manusia modern mengalami kehampaan spiritual, krisis makna dan legitimasi hidup, kehilangan visi untuk apa hidup, dan keterasingan (alienasi) terhadap dirinya sendiri. Menurut Syed Hossein Nasr, dalam The Plight of Modern Man (London, 1976), krisis-krisis eksistensial ini bermula dari pemberontakan manusia modern kepada Allah. Mereka telah kehilangan harapan terhadap kebahagiaan masa depan seperti 21 yang dijanjikan oleh Renaisans, Abad Pencerahan, sekularisme, sains, dan teknologi. Di sinilah peran kedua kajian filsafat khususnya filsafat Islam, yaitu mendekonstruksi paradigma modernisme yang telah memberhalakan materialisme, ateisme, dan sekularisme. Rekonstruksi Filsafat Pasca-Modernisme Peran ketiga filsafat saat ini adalah melanjutkan semacam proyek dekonstruksi, yaitu merekonstruksi filsafat yang dapat memberi jalan keluar dari kebuntuan (deadlock) filsafat Barat modern dan krisis-krisis eksistensial manusia modern. Dalam momen ini, filsafat Islam dapat mengambil peran penting untuk memberikan kontribusi bagi proyek “penyelamatan” peradaban manusia di masa depan. Salah satu manifestasi Islam sebagai rahmātan lil ‘ālamīn, dalam hal ini secara filosofis, adalah menawarkan pandangan-dunia yang utuh, holistik, dan penuh makna kepada manusia modern dalam memersepsi realitas. Khazanah filsafat Islam klasik dan kontemporer sesungguhnya sangat kaya. Sayangnya, sampai sekarang kekayaan intelektual itu masih tersimpan dalam perpustakaanperpustakaan Islam dan Barat, misalnya, belum banyak digali. Pemikiran filsuf jenius Ibn Sīnā, masih banyak yang belum terungkap, terutama perkembangan akhir pemikirannya seperti pada karya-karya Isyārāt wa Tanbīhāt, (Logika Timur). al-Manthiq al-Masyriqiyyah Belum banyak orang tahu bagaimana Ibn Sīnā memecahkan persoalan- persoalan ilmiah dan filosofis juga menggunakan metode iluminasionis melalui renungan dan shalat, jauh sebelum Quantum Learning itu heboh. Mungkin akan lebih terasa asing bagi kebanyakan manusia modern jika disebutkan bahwa Suhrawardī mencetuskan aliran filsafat isyrāqiyyah (Pencerahan) atau menyebutkan bahwa pemikiran Mullā Shadrā menjadi semacam puncak perkembangan filsafat Islam pada abad ke-17, sezaman dengan Bapak Filsafat Modern René Descartes. Sebagai perbandingan saja, seorang filsuf Prancis Henry Corbin yang sejak muda berminat mencari filsafat yang serius-mendalam, suatu kali pernah menyebut, “filsafat eksistensialis Heidegger sebagai catatan kaki bagi filsafat eksistensialis (Falsafah Wujūd) Mullā Shadrā”. Padahal, Heidegger adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai tokoh eksistensialis terkemuka Barat sampai saat ini. 22 Kekhasan cara berpikir filsafat Islam adalah pandangannya yang utuh dan terpadu terhadap kajian metafisika, epistemologi, etika, kosmologi, dan psikologi. Hal itu merupakan manifestasi nilai Tauhid. Pemahaman yang benar tentang eksistensi/wujud (metafisika) akan berimplikasi kepada pemahaman yang tepat tentang pengetahuan (yaitu sebagai modus eksistensi), dan pada gilirannya berimplikasi pada pemahaman yang eksistensial tentang nilai-nilai moral. Bermula dari refleksi mendalam terhadap makna Wujud, filsafat wujud atau filsafat eksistensialis Islam berbeda dengan eksistensialisme Barat, karena memiliki landasan metafisika yang kukuh, epistemologi realis-konstruktif, dan bersifat teleologis. Sifat-sifat seperti inilah yang diharapkan dapat memperoleh-kembali pegangan hidup bagi manusia modern, selain hal itu turut dapat memuasi tuntutan-intelektual manusia modern guna mengobati krisis-krisis eksistensial modernitas. Jika Islam memang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem-sistem alternatif di berbagai bidang kehidupan, maka semuanya itu hanya mungkin terwujud dengan baik dan genuine (orisinal, otentik) bila terlebih dahulu dibangun fondasi filosofis sedemikian. Oleh karena itu, bukan merupakan suatu hal yang kontroversial jika mengatakan bahwa berbagai sistem kehidupan itu—entah ekonomi, politik, sosial, budaya, apalagi keagamaan—tak pernah bisa dilepaskan dari persoalanpersoalan filosofis yang menjadi fondasinya. Termasuk di dalamnya, makna-sejati kemanusiaan, keadilan, persamaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sebagai tujuan semua solusi. Filsafat sebagai Pendewasaan Umat Salah satu sumber keprihatinan kita terhadap kondisi psikososial kita (umat Islam) sekarang adalah kelambatan kita untuk bisa keluar dari “masa kanak-kanak” dalam banyak hal. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: terobsesinya umat dengan simbol-simbol formalisme-legalistik, pemahaman keagamaan yang superfisial dan skripturalistik, mudahnya kita terpesona dengan retorika dan orasi emosional yang sering kurang penalaran, dan pada saat yang sama, gamang menghadapi tantangan realitas zaman yang menuntut kemampuan 23 apropriasi, yaitu kemampuan memahami orang lain tanpa terlebur ke dalamnya tapi justru memperkaya pemahaman tentang diri sendiri. Sikap penentangan membabi buta terhadap teori evolusi misalnya, telah menghabiskan energi dan dana umat yang sangat banyak, padahal ternyata teori itu tidak harus dikaitkan dengan Darwinisme atau ateisme. Ini hanya persoalan bagaimana kita menafsirkan temuan-temuan ilmiah dalam perkembangan spesies secara benar dan dalam hal ini, filsafat Islam bisa menawarkan jalan keluar penyelesaian antara konsep evolusi dengan prinsip Tauhid. Ulama-filsuf Muthahhari pernah membahas relasi teori evolusi dengan pandangan-dunia Tauhid (baca bukunya Ruh dan Materi, Yayasan Muthahhari, Bandung, 1991). Kita, biasanya, mengambil jalan pintas nan mudah, yakni menutup diri dari ideologiideologi/ajaran-ajaran asing seraya mencap mereka sesat dan berbahaya. Padahal, dalam zaman yang semakin plural dan kompleks seperti sekarang ini, kemampuan apropriasi seperti itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di sinilah peran keempat filsafat, yaitu membuka wawasan berpikir umat untuk menyadari fenomena perkembangan wacana keagamaan kontemporer yang menyuarakan nilai-nilai keterbukaan, pluralitas, dan inklusivitas. Studi filsafat sebagai pilar utama rekonstruksi pemikiran dapat membongkar formalisme agama dan kekakuan pemahaman agama—atau dalam istilah M. Arkoun sebagai taqdīs al afkār al-dīniyyah (penyakralan pemikiran keagamaan)—sebagai salah satu sumber eksklusivisme agama dan kejumudan umat. Salah satu problem krusial pemikiran dan pemahaman keagamaan sekarang ini, misalnya, adalah perumusan pemahaman agama yang dapat mengintegrasikan secara utuh visi ilahi dan visi manusiawi tanpa dikotomi sedikitpun. Karena itu, kembali kepada diagnosa al-Afghāni, gerakan pembaharuan Islam harus menampilkan Islam sebagai suatu peradaban dan pandangan-dunia yang utuh dan menyeluruh. Gerakan pembaharuan Islam harus dapat mengelaborasi pandangan-dunia Islam ke dalam berbagai bidang kehidupan. Elaborasi ini merupakan proses terus menerus untuk mentranfosmasi fakta-fakta menjadi nilai-nilai, aksi-aksi menjadi tujuan-tujuan, dan harapan-harapan menjadi kenyataan-kenyataan. Proses elaborasi ini tak syak lagi 24 membutuhkan kajian epistemologi Islam, hal yang merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat Islam. Dengan demikian, kajian filsafat merupakan keniscayaan bagi para pemerhati dan pelaku upaya rekonstruksi peradaban Islam. Oleh karena itu, untuk mengentaskan masa kanak-kanak (mendewasakan) umat Islam, mungkin sudah saatnya filsafat harus dianggap sebagai anak sah dari peradaban Islam, bukan lagi anak haram sebagaimana yang dipahami oleh kaum ortodoks seperti kaum salafi, Wahabi atau Asy’ariyyin. Sikap seperti itu mengandaikan bahwa seseorang tidak mengenal sejarah keemasan peradaban Islam. Dari Revitalisasi Khasanah Ke Revitalisasi Filsafat Islam Api yang berkobar pada jiwa eksistensialis Iqbal seperti yang terbaca pada kutipan syairnya pada pembuka tulisan ini (sub-bab 1) dapat ditranformasikan ke dalam bentuk gerakan kebangkitan kebudayaan dan peradaban Islam. Kita memiliki kekayaan khazanah pengetahuan filsafat Islam yang belum banyak digali-kembangkan. Karya-karya besar saintis, filsuf, dan sufi seperti al-Kindī, al-Farābī, Ikhwān al-Shafā’, Ibn Sīnā, al-Haitsam, alBīrūnī, al-Khawārizmī, ‘Umar Khayyām, Ibn Nafīs, al-Thūsī, Farīd al-Dīn al-‘Aththār, Jalāl al-Dīn Rūmī, Quthb al-Dīn Syīrāzī, Ibn ‘Arabī, Suhrawardī, dan Mullā Shadrā masih tersimpan rapi dan belum dikaji secara menyeluruh. Pengenalan terhadap tokoh-tokoh ilmuwan, pemikir, dan filsuf/sufi Muslim ini diharapkan dapat menumbuhkan self esteem (harga diri) umat bahwa kita adalah umat yang terdepan dalam menyumbang kemajuan peradaban dunia. Agar revitalisasi filsafat Islam dapat berkomunikasi dan berdialog dengan wacana kontemporer, maka kita juga membutuhkan filsuf Muslim yang menguasai pemikiran, kebudayaan, dan filsafat Barat (modern/postmodern). Sarjana-sarjana seperti Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, Seyyed Hossein Nasr, Murtadhā Muthahharī, ‘Alī Syari‘ati, Muhammad Arkoun, Mehdi Ha’iri Yazdī, William Chittick, Akbar Ahmad, Alparslan Acikgenk, Naquib Alatas, Osman Bakar, Nurcholish Madjid, dan Hassan Hanafī adalah sejumlah kecil pemikir dan filsuf Muslim yang dapat menjadi lokomotif diskursus filsafat dan pemikiran Islam kontemporer sebagai fondasi rumah peradaban Islam; sekaligus dapat memperkaya khazanah Islam klasik itu sendiri.[] 25