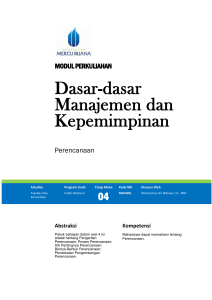BaB V hubungan antara manusia dengan tuhan menurut martin buber
advertisement
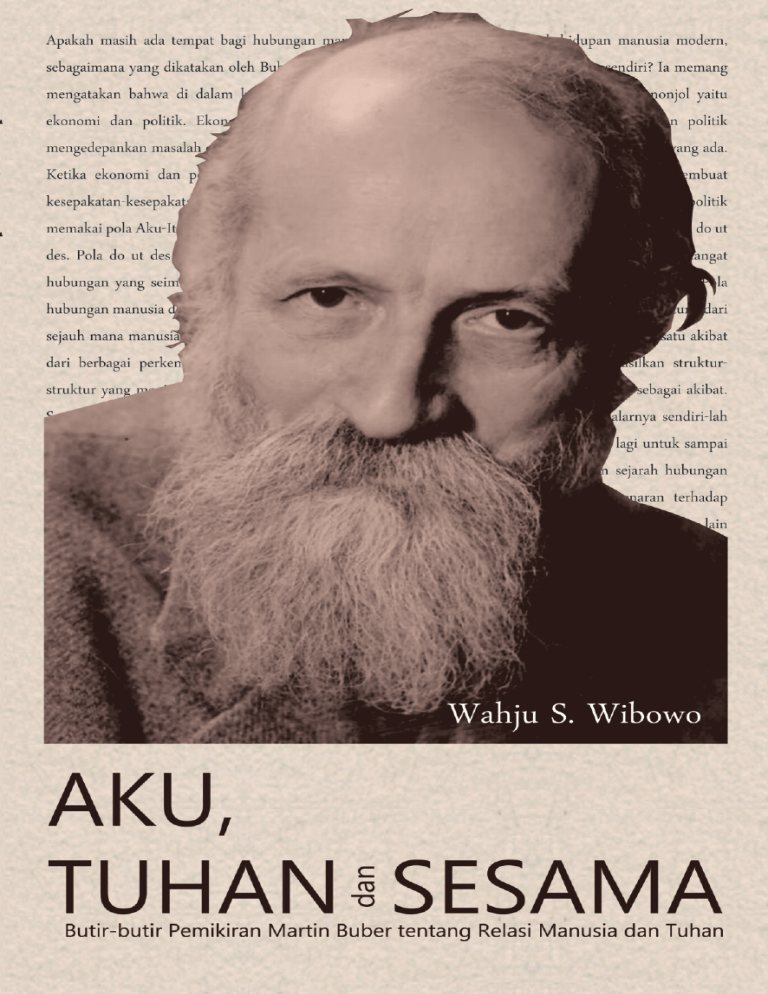
Aku, Tuhan dan Sesama: Butir-butir Pemikiran Martin Buber tentang Relasi Manusia dan Tuhan Wahju S. Wibowo Kata Pengantar Manusia sehari-hari berada dalam relasi dengan orang lain sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia ‘ada’ dan menjadi dirinya sendiri, justru karena dibentuk bersama dengan orang lain. Namun tidak selalu relasi itu berjalan dengan mulus, seringkali yang terjadi adalah pertikaian bahkan saling melukai satu dengan yang lainnya. Dalam situasi seperti itu orang lain justru dilihat sebagai ancaman. Akhirnya banyak orang merasa lebih membahagiakan hidup sendiri tanpa orang lain. Hidup sendiri berarti meminimalkan masalah yang mungkin ada karena relasi dengan orang lain. Ketika penulis menyelesaikan tugas akhir di S-1, tema yang diambil adalah tentang kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles, kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi manusia. Siapapun orangnya mesti mendambakan kebahagiaan. Namun apa yang dimaksud dan bagaimana meraih kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Bagi Aristoteles kebahagiaan adalah ketika seorang manusia memaksimalkan keutamaan yang ada di dalam dirinya. Bagi penulis, salah satu keutamaan itu adalah relasi dengan orang lain sehingga dengan bantuan pemikiran Thomas Aquinas, kemudian penulis mendapatkan pemikiran bahwa kebahagiaan manusia ada pada relasinya dengan iii iv Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama orang lain. Jika demikian maka relasi itu menjadi penting. Namun yang penting itu tidak berarti mudah. Manusia jatuh bangun untuk mewujudkan relasi yang baik dengan sesamanya. Sejarah manusia penuh dengan intrik dan pengkhiatan, namun juga dengan ketulusan dan cinta. Semua memotret soal relasi. Pergulatan itu terus berlanjut. Sampai kemudian penulis berkenalan dengan berbagai pemikiran filosofis tentang relasi antar manusia,, dan akhirnya memilih Martin Buber sebagai teman berdialog. Dalam pemikiran Buber bagaimana relasi itu dilakukan dan dihidupi menjadi lebih kongkret lagi. Martin Buber menjadi teman dialog untuk merenungkan relasi antara manusia, yang di dalamnya manusia mendamba ada Tuhan yang berkenan hadir. Bagi penulis, pemikiran Buber mempunyai bobot bukan hanya karena kedalaman berpikirnya, namun juga karena pengalaman pribadi yang mendasari tulisan Buber. Buber sempat mengalami pahitnya relasi antar manusia ketika ia, sebagai orang Yahudi, dikejar-kejar oleh tentara Nazi Jerman. Namun ia juga dibukakan oleh pengalaman ketulusan dan cinta dalam relasi ketika ia diselamatkan dan dibantu justru oleh orang Palestina, yang seperti kita ketahui bersama, berada dalam situasi hubungan yang sulit dan konfrontatif dengan Israel. Pengalaman itulah yang menjadi ‘daya dorong’ pemikiran Buber. Dalam konteks itulah buku kecil ini hadir. Semoga buku kecil ini dapat menjadi teman berdialog, khususnya tentang pemikiran Martin Buber, dan tentang relasi manusia dengan sesame dan dengan Tuhan. Buku kecil diperuntukkan bagi Ike, istri penulis, yang menyediakan diri untuk berjalan bersama dengan hidup penulis dalam segala suka-duka dan dinamika relasi antar manusia. Jogjakarta, Mei 2015 Daftar Isi Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v BAB I–Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1. Kebingungan Menempatkan Relasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. Tuhan dan Manusia di Tengah Dunia Modern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3. Struktur Tulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 BAB II–Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber . . . . . . . . . . . . . . .11 1. Riwayat Hidup Martin Buber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 2. Karya-karya Martin Buber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3. Perkembangan Pemikiran Martin Buber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 4. Pengaruh Hasidisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 5. Pengaruh Pemikir-pemikir Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 6. Pengaruh Eksistensialisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 7.Kesimpulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 BAB III–Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 1. Realitas (Wirklichkeit) dan Proses Pengetahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 2.Pribadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 3. Hubungan Aku-Itu dan Aku-Engkau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 v vi Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama 3.1. Hubungan Aku-Itu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3.2. Hubungan Aku-Engkau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 3.2.1. Cinta dalam Hubungan “Aku-Engkau” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 3.2.2. Kebebasan dalam Hubungan “Aku-Engkau” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 3.2.3. Tiga Bidang Kehidupan dalam Hubungan “Aku-Engkau”. . . . . . . . .46 4.Kesimpulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 BAB IV–Tuhan Menurut Martin Buber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 1. Beberapa Pemikiran Modern Tentang Tuhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 1.1. Jean-Paul Sartre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 1.1.1. Pemikiran Jean-Paul Sartre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 1.1.2. Tanggapan Martin Buber terhadap Jean-Paul Sartre . . . . . . . . . . . .60 1.2. Martin Heidegger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 1.2.1. Pemikiran Martin Heidegger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.2.2. Tanggapan Martin Buber terhadap Heidegger . . . . . . . . . . . . . . . . .64 1.3. Carl-Gustav Jung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 1.3.1. Pemikiran Jung tentang Tuhan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 1.3.2. Tanggapan Martin Buber terhadap Pemikiran Jung. . . . . . . . . . . . .67 2. Tuhan sebagai Pribadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 2.1. Pribadi yang Menyejarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 2.2. Pribadi yang Membentuk Manusia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 3. Tuhan sebagai “Engkau Absolut” yang Aktif Terlibat dalam Hubungan . . . . . . .81 4.Kesimpulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 BAB V–Hubungan antara Manusia dengan Tuhan Menurut Martin Buber . . . . . . . . .87 1. Dinamika Hubungan “Aku-Itu”, “Aku-Engkau” dan “Aku-Engkau Absolut” . . . . .88 1.1. Peralihan dari “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 1.2. Peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Itu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 1.3. Peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Engkau Absolut” . . . . . . . . . . . . . . . .94 2. Aspek-aspek Hubungan Manusia dengan Tuhan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 2.1. Aspek Perjumpaan (Encounter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Daftar Isi 2.2. Aspek Kebebasan (Freedom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 2.3. Aspek Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 3.Kesimpulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 BAB VI–Penutup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 1.Kesimpulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 2. Beberapa Catatan Kritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 2.1. Pengaruh Pemikiran Mistisisme : Penolakan Gambaran Tuhan sebagai Objek Rasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 2.2. Dasar Ontologis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 2.3. Mengenal Aku dan Mengenal Engkau: Sisi Epistemologis . . . . . . . . . . . . .125 2.4. Kondisi “Aku” yang Menjalin Hubungan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 vii BAB I Pendahuluan 1. Kebingungan Menempatkan Relasi Martin Buber membuka buku Eclipse of God dengan sebuah cerita mengenai peristiwa yang dialaminya.1 Pada suatu saat ia diundang untuk memberikan kuliah umum di hadapan para pekerja industri di Jerman selama tiga hari. Tema kuliah umum yang ia berikan adalah “Agama sebagai Realitas”. Setelah tiga hari ia menyampaikan kuliah, Buber merasa heran karena peserta kuliah umum kebanyakan sangat tidak antusias untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Keheranannya berubah menjadi sesuatu yang mengejutkan ketika pada hari keempat, seorang pekerja muda mengajaknya berdiskusi dan memulai dengan satu pernyataan “pengalaman saya menunjukkan bahwa selama ini saya tidak memerlukan hipotesis tentang Tuhan untuk membuat dunia ini sungguh-sungguh sebagai tempat tinggal saya ”. Ia bertanya dalam hatinya terhadap pernyataan pekerja itu, bagaimana mungkin seseorang merasa dunia ini sebagai tempat ting1 Martin Buber, Eclipse of God, 1979, Humanities Press:New Jersey, h.3-6; selanjutnya dalam seluruh tesis akan disingkat dengan EoG. 1 2 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama gal yang nyaman, sementara ada banyak sekali pertanyaan di dunia yang tidak bisa ia jawab? Apa itu warna merah? Apakah warna merah ada pada dirinya sendiri sebagai benda? Atau menyatu di dalam jiwa seseorang? Atau hanya merupakan persepsi mata saja? Sikap seperti apa yang harus ia lakukan terhadap sesamanya manusia? Apa “ada” (being) yang telah memberikan dasar pada dunia yang penuh dengan pertanyaan itu? Keheranan Buber terhadap pernyataan pekerja muda itu berkaitan dengan makna hidup manusia. Bagaimana mungkin seseorang bisa menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman, sementara dirinya tidak berusaha menjawab berbagai pertanyaan yang akan membuka pemahamannya mengenai makna dunia ini sekaligus makna dirinya di dunia ini. Untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang nyaman, seseorang harus mempunyai dorongan untuk mengetahui jawaban dari berbagai pertanyaan mengenai dunia. Jawaban-jawaban itu akan membawanya pada pengertian mengenai makna dunia ini, dan sekaligus makna dirinya sebagai manusia yang hidup di dunia. Buber kemudian membawa masalah itu pada tataran pemikiran religius. Ia mengatakan bahwa pemikiran pada jaman modern ditandai dengan dua tujuan yang berbeda. Tujuan yang pertama yaitu untuk mempertahankan idea tentang Tuhan sebagai perhatian utama agama. Di pihak lain ada tujuan lain yaitu menghancurkan realitas idea Tuhan dan dengan cara itu sekaligus menghancurkan realitas hubungan kita dengan-Nya.2 Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara, baik melalui pemahaman metafisis, psikologi ataupun pemahaman mengenai kemajuan teknologi manusia. Untuk itu tidaklah heran jika kemudian muncul pemikiran yang mengatakan bahwa “Tuhan mati” (death of God) seperti yang dilontarkan oleh Sartre dan Nietzsche. Bagi Buber masalah sebenarnya tidak terletak pada 2 Martin Buber, EoG, h.17. BAB I Pendahuluan Tuhan, sehingga harus dikatakan bahwa “Tuhan mati”. Masalahnya terletak pada hubungan antara manusia dengan Tuhan, untuk itu ia memunculkan istilah Eclipse of God 3. Ada sesuatu yang tidak “pas” dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Padahal menurutnya hubungan manusia dengan Tuhan merupakan salah satu komponen penting bagi manusia untuk membentuk makna hidupnya. Memang permasalahan yang dimunculkan Buber menjadi perdebatan hangat dalam kehidupan manusia modern. Misalnya tentang hubungan iman, agama dan ilmu. Benarkah pencapaian sains dan teknologi menjauhkan manusia dari Tuhan atau justru membawanya semakin dekat dengan Tuhan? Seperti apa makna diri manusia dan hubungan dengan dunia, sesama dan “Ada” yang memberikan dasar kepada dunia, dalam perkembangan teknologi? Lewis Mumford mengatakan bahwa dengan teknologi manusia membentuk sang “aku”.4 Salah satu simbol pembentukan sang “aku” adalah pencapaian manusia dalam menghasilkan mesin-mesin sebagai produk teknologi yang dianggap sebagai pencapaian tingkat kemajuan berpikir manusia. Sang “aku” dilihat dari kemajuan berpikir yang berhasil dicapai. Mesin sebagai simbol pencapaian sang “aku” yang berpikir memerankan hubungan yang fungsional dengan manusia. Mesin dihargai sejauh dirinya berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan keinginan manusia yang menjalankannya. Pada titik inilah hubungan pribadi antar manusia pun dapat berubah. Hubungan antar pribadi dapat berubah menjadi hubungan “fungsional”. 5 Hubungan 3 Maurice Friedman, Martin Buber’s Life and Work, The Later Years 1945-1965, 1983, EP.Dutton : New York, h.138. 4 Bdk. Lewis Mumford, The Myth of The Machine, bag. Prologue dan Epilogue yang diterjemahkan dalam kumpulan tulisan Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, Vol.2. Ed. YB. Mangunwijaya, 1985, YOI, h.33-48. 5 Istilah “fungsional” dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam dunia modern sikap manusia terhadap sesamanya, seringkali sama dengan sikap manusia terhadap mesin. Padahal sikap manusia terhadap mesin memakai hubungan “fungsional”, dalam arti ketika mesin kehilangan fungsinya seperti yang diinginkan oleh ang operator, 3 4 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama hanya dilihat sebatas “fungsi”, yaitu sejauh mana seseorang “berfungsi” bagiku, dan tidak lagi dilihat dari segi “adanya” manusia, yaitu sejauh mana seluruh eksistensinya ternyata berharga bagiku. Dengan demikian pemahaman akan makna hidup manusia, baik “aku” maupun “sesama” sudah berubah. Lalu bagaimana dengan pemahaman tentang Tuhan? Ketika “aku” mulai memutlakkan diri dengan pencapaianpencapaian teknologi yang dihasilkannya, maka “ruang” untuk Tuhan sebagai yang “benar-benar Mutlak” mulai disingkirkan. Pemahaman manusia pun mengenai Tuhan dapat berubah. Banyak filsuf kemudian mencoba mengemukakan pikirannya untuk menguraikan sekaligus mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Mereka mencari makna hidup manusia dalam hubungan dengan orang lain dan Tuhan. Fenomena hubungan antar manusia dilihat dalam kaitan hubungan dengan Tuhan. Gabriel Marcel, misalnya, mengemukakan bahwa refleksi filosofis tentang kehadiran orang lain akan membawa manusia pada kehadiran “Yang Lain” secara istimewa, yaitu Tuhan. Himbauan Marcel untuk “mencintai” sebagai sarana menyatukan aku dengan engkau, diharapkan membawa manusia pada kehadiran “cinta” Tuhan. Dalam setiap perkembangan kebudayaan, ketika himbauan “mencintai” engkau tetap dilakukan, keinginan untuk mengalami kehadiran Tuhan bukanlah hal yang tidak mungkin. Sedangkan Emanuel Levinas mengatakan bahwa manusia maka mesin menjadi tidak bernilai lagi. C.A. van Peursen mengungkapkan secara lebih luas pemahaman mengenai pemikiran fungsional yang menandakan dunia modern. Gejala pemikiran fungsional dalam dunia modern dikemukakan oleh van Peursen sebagai bagian terakhir dari perkembangana manusia setelah tahap mitis dan tahap ontologis. van Peursen mengemukakan pemikiran fungsional sebagai pembebasan dari tahap ontologis yang bercirikan substansialisme, yaitu adanya “pengasingan” terhadap benda-benda atau gejala-gejala tertentu. “Pengasingan” menyebabkan kurangnya relasi yang terjadi antara manusia dengan dunianya. Pemikiran fungsional menandakan adanya hubungan yang lebih hangat dan eksistensial antara manusia dengan dunianya. Itulah hubungan fungsional (Lih. C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, 1988, Kanisius:Yogyakarta, h.85-118.) BAB I Pendahuluan bertanggung jawab terhadap orang lain. Tuhan tampil melalui “muka”, yaitu muka orang lain yang kepadanya seorang manusia memberikan tanggung jawabnya. Dengan demikian pengalaman berhadapan muka dengan “muka” Tuhan, dicapai dengan bertanggung jawab terhadap “muka” orang lain. Demikian juga dengan Martin Buber, yang mencoba mengemukakan pemikirannya mengenai bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan sebagai jawaban dari permasalahan yang ia munculkan. Pemikiran Martin Buber inilah yang akan menjadi isi tesis ini. Mengapa Buber, bukan pemikir yang lain? Pertama, Buber meletakkan dasar pemikiran yang kuat mengenai hubungan antar personal, dan bagaimana dari hubungan antar personal tersebut manusia dapat membina relasi dengan Tuhan. Kedua, Buber mengemukakan pemikirannya dengan meraciknya bukan hanya dari bahan-bahan filsofis sebelumnya, tetapi juga dari tradisi religius yang dihidupinya. Menurut Martin Buber, hubungan manusia dengan Tuhan tidak dapat dipahami tanpa memahami pola hubungan Aku-Itu dan Aku-Engkau. Yang dimaksud dengan hubungan Aku-Engkau dan Aku-Itu adalah : 1. Hubungan Aku-Itu. Hubungan Aku-itu adalah hubungan yang sepihak, Aku menjadikan Itu sebagai obyek semata-mata. Tidak ada hubungan timbal balik. Segala sesuatu mengalir dari Aku dan Itu hanya menerima, tanpa bisa mengungkapkan keinginan, perasaan dan kehendaknya secara seimbang terhadap Aku. Aku mengkategorikan, memperalat, menyusun, memasukkan Itu ke dalam kode-kode tertentu. Ketika Aku berhadapan dengan pohon, misalnya, Aku dapat segera memasukkan pohon itu ke dalam berbagai kategori, dari segi bentuknya, unsur kimia atau mekanisnya. Namun Aku tidak mempunyai kesan-kesan mendalam mengenai pohon itu. Pohon itu tidak berperan lebih lanjut dalam seluruh 5 6 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama gambaran dan imajinasi yang ada di dalam diriku. “Itu” tidak mempengaruhi Aku. 2. Hubungan Aku-Engkau. Hubungan Aku-Engkau merupakan hubungan timbal balik yang seimbang. Bagi Buber arti mendasar dari suatu hubungan adalah adanya aspek timbal balik. Hanya Engkau yang dapat membalas apa yang Aku sampaikan dan hanya Engkau yang dapat memberikan masukkan kepada Aku sehingga Aku dapat survive dan mengembangkan diri. Mengapa? Karena Aku dan Engkau adalah pribadi dan hanya pribadi yang dapat berhubungan timbal balik. Dalam Aku-Engkau, Aku adalah pribadi yang sadar akan subyektivitas, yaitu subyektivitas Aku sendiri dan subyektivitas Engkau. Dengan demikian pribadi muncul dan membangun diri dengan memasuki hubungan dengan pribadi lainnya. Dengan memahami dua pola hubungan itu, maka manusia dapat memahami hubungan dengan Tuhan. Bagi Buber hubungan AkuEngkau memuncak dalam hubungan Aku dengan Tuhan. Hubungan Aku dengan Tuhan memuncak ketika manusia mengaktualisasikan hubungan itu dengan kegiatan yang efektif, yang penuh dengan kekuatan dan kedalaman pengertian terhadap yang suci. Kekuatan dan kedalaman itu hanya didapat ketika manusia masuk ke dalam aktivitas seluruh umat manusia. Dengan demikian baginya, hubungan manusia dengan Tuhan dapat dialami ketika manusia sadar dan melakukan pola hubungan Aku-Engkau. Namun apakah hubungan Aku-Itu juga terdapat dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan? Buber mengatakan bisa saja terjadi manusia terjatuh pada pola hubungan Aku-Itu ketika berhubungan dengan Tuhan. Ia memberi contoh, ketika manusia mengatakan bahwa “Aku memiliki Tuhan”, maka ia terjatuh dalam pola hubungan Aku-Itu. Mengapa? Karena sebutan kepunyaan merupakan ciri dari pola hubungan Aku-Itu. Padahal BAB I Pendahuluan sikap seperti itu seringkali pakai manusia justru untuk menunjukkan hubungannya dengan Tuhan. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog protestan, memberikan sebuah contoh lain bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan bisa jatuh ke dalam hubungan Aku-itu sebagaimana dijelaskan Buber. Bonhoeffer mengatakan bahwa ketika manusia hanya “memanggil” Tuhan manakala nalar, kemampuan dan kekuatannya sudah berada di batas akhir, maka ia menjadikan Tuhan hanya sebagai alat, yang kalau perlu baru dipakai. Deus ex machina-lah yang dipakai manusia untuk menunjukkan hubungannya dengan Tuhan.6 2. Tuhan dan Manusia di Tengah Dunia Modern Apakah masih ada tempat bagi hubungan manusia dengan Tuhan di tengah kehidupan manusia modern, sebagaimana yang dikatakan oleh Buber? Dan apakah maknanya bagi hidup manusia itu sendiri? Ia memang mengatakan bahwa di dalam kehidupan masyarakat modern ada dua aspek yang sangat menonjol yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi mengedepankan barang kebuTuhan dan pelayanan, sedangkan politik mengedepankan masalah opini dan aspirasi. Dua aspek ini bisa masuk ke dalam dua pola hubungan yang ada. Ketika ekonomi dan politik memakai rumusan bahwa semua manusia yang dengannya Aku membuat kesepakatan-kesepakatan adalah obyek di mana aku mengambil keuntungan, maka ekonomi dan politik memakai pola Aku-Itu. Salah satu imbas dalam hubungan manusia dengan Tuhan adalah dipakainya pola do ut des. Pola do ut des persis seperti sebuah hubungan ekonomi. Namun ketika ia mengedepankan semangat hubungan yang seimbang untuk pengembangan bersama, ia mengedepankan hubungan Aku-Engkau. Pola hubungan manusia dengan Tuhan dalam situasi masyarakat ekonomi dan politik modern, 6 Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, surat 30 April dan 29 Mei 1944, seperti dikutip oleh John de Gruchy, Saksi Bagi Kristus : Kumpulan Cuplikan Karya Dietrich Bonhoeffer, 1993, BPK Gunung Mulia : Jakarta, h. 345 &349. 7 8 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama akan tergantung dari sejauh mana manusia mengembangkan dua pola hubungan itu. Ateisme, kemudian menjadi salah satu akibat dari berbagai perkembangan peradaban manusia. Ketika sistem ekonomipolitik menghasilkan struktur-struktur yang menindas, sementara agama seolah melegalkan hal itu, ateisme-marxis muncul sebagai akibat. Sementara itu ketika kemajuan teknologi membawa manusia pada pemahaman bahwa nalarnya sendiri-lah yang mampu menjawab berbagai permasalahan manusia, maka manusia tinggal selangkah lagi untuk sampai pada pemahaman bahwa manusia-lah sang penyelamat dan pencipta kehidupan. Dalam sejarah hubungan antara agama, termasuk di Indonesia, hubungan Aku-Tuhan seringkali menjadi pembenaran terhadap hubungan antar manusia yang berdasarkan pola Aku-Itu. Aku mengobjekkan dan memperlakukan orang lain dengan semena-mena, sebagai bentuk pemenuhan terhadap hubungan Aku-Tuhan. Dengan tidak bermaksud menyederhanakan masalah karena bisa jadi factor ekonomi dan politik ikut menentukan, fenomena fundamentalisme yang melahirkan gerakan teroris bisa menjadi contoh. Dasar keyakinan tertentu tentang Tuhan dipandang sebagai legitimasi untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Jadi basis legitimasinya pada sesuatu yang justru ‘tidak kelihatan’. Oleh Buber hal itu dibalik. Justru dengan memperlakukan yang kelihatan dengan baik, maka yang tidak kelihatan akan ‘menampakkan’ diri sebagai legitimasi terhadap tindakan itu. Dengan demikian sebenarnya Aku bukan hanya mengobjekkan orang lain dengan semena-mena sesuai dengan keinginanku, namun sekaligus mengobjekkan Tuhan sesuai dengan keinginanku. Di tengah situasi seperti itu, pokok-pokok pemikiran Buber menjadi sangat relevan untuk mengembalikan manusia akan pengalaman berhubungan dengan Tuhan. BAB I Pendahuluan 3. Struktur Tulisan Setelah pendahuluan maka akan diuraikan latar belakang Martin Buber Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang kehidupan Martin Buber, dan karya-karya Martin Buber. Karya-karya Martin Buber akan disusun secara historis, sehingga terlihat alur perkembangan pemikirannya. Bagian berikutnya adalah pemahaman Buber mengenai hubungan Aku-Itu dan Aku-Engkau. Sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pemahaman Buber tentang proses mengetahui realitas dan pemahamannya tentang pribadi. Bagi Buber yang senantiasa masuk dan berada dalam hubungan, mampu menerima dan memberi hubungan adalah pribadi. Dengan demikian manusia tersebut sadar dakan subyektivitasnya. Dengan sadar akan subyektivitasnya sekaligus ia sadar bahwa eksistensinya bukan hanya didasarkan akan keberadaan dirinya sendiri, melainkan keberadaan orang lain. Orang lain ikut menentukan pengembangan diriku dan itu dilakukan dalam suatu hubungan. Setelah itu kemudian diuraikan mengenai konsep Buber tentang Tuhan. Buber, dalam Eclipse of God, menguraikan beberapa pemikiran modern tentang Tuhan, di antaranya adalah Tuhan sebagai Obyek dan Tuhan sebagai Rasio. Bagi Buber pemikiran itu tidaklah mencukupi. Pengalaman manusia mengatakan bahwa Tuhan melebihi daripada sekedar obyek maupun rasio. Lewat dialog dengan pemikiran-pemikiran modern tentang Tuhan, Buber mengemukakan pemahamannya. Beberapa pemikir modern yang akan ditanggapi olehnya antara lain adalah Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger dan seorang ahli psikologi terkenal, Carl-Gustav Jung. Bagian berikutnya membahas Hubungan Aku-Tuhan menurut Buber. Bagi Buber Tuhan adalah tujuan diri dan hidup manusia. Sebuah 9 10 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama Pribadi, yang di dalam diri-Nya manusia berada dalam proses menjadi, yaitu menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Menjadi manusia, dalam pemikiran Buber, adalah untuk memenuhi tujuan mengapa manusia diciptakan. Lewat proses “menjadi manusia” seseorang menemukan makna hidupnya di dunia ini. Pemenuhan akan tujuan itu hanya mungkin dengan adanya hubungan yang benar dengan Tuhan. Inilah yang disebut Buber dengan religiusitas yang berpusat pada pengalaman. Pengalaman menjadi sesuatu yang berlangsung setiap hari, di mana Tuhan “berhadap-hadapan muka” dengan manusi. Situasi “berhadapan” membuat manusia bisa selalu berada dalam peralihan tertentu: dari “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau” dan sebaliknya, dan dari “Aku-Engkau” menjadi “Aku-Engkau Absolut” dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya. Bagian terakhir akan menguraikan kesimpulan dari pemikiran Buber dan berbagai relevansinya. Buber memberikan sebuah dasar pemahaman yang kuat bahwa manusia akan senantiasa berada dalam hubungan dengan orang lain. Untuk itu sangat penting bagi manusia untuk melakukan pola hubungan yang tepat. Lewat hubungan itu, seseorang dapat mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun demikian pemikirannya bukan tanpa kelemahan. Beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh lainnya akan digunakan untuk menanggapi pemikiran Buber. BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber 1. Riwayat Hidup Martin Buber Martin Buber lahir di Wina pada tahun 1878, dengan nama Mordecai Martin Buber. Ketika ia berumur tiga tahun orang tuanya bercerai dan ia dibesarkan oleh kakeknya, Solomon Buber, di Lemberg, Polandia. Sang kakek merupakan seorang yang terpelajar, bekerja dalam bidang perbankan dan ahli dalam kebudayaan dan sastra Yahudi. Buber menggambarkan sang kakek sebagai “pribadi yang bijaksana dalam menggunakan kata-kata, secara khusus, senantiasa cocok dan mendukung semua orang”.7 Pribadi sang kakek-lah yang kemudian mempengaruhi Buber, terutama dalam sastra Yahudi. Sang kakek menjadi orang tua sekaligus guru bagi Buber. Buber menggambarkan sang kakek sebagai “lover of the word”.8 Namun kecintaan Buber terhadap kata-kata justru mendapatkan tempatnya lewat sang nenek, 7 Maurice Friedman, Martin Buber’s Life and Work, The Early Years 1878-1923, 1982, London:Search Press, h.4. 8 Paul Arthur Schilpp (ed), The Philosophy of Martin Buber, 1967, London : Cambridge Univ.Press, h.5 11 12 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama Adele. Adele sangat piawai dalam memilih kata-kata dalam setiap kalimat yang diucapkannya. Sang Nenek pula yang mendorong Buber untuk mempelajari berbagai bahasa. Buber kemudian bergulat dengan struktur dan makna yang dihasilkan oleh berbagai bahasa. Jerman, Perancis, Yunani, Ibrani dan Latin merupakan bahasa yang dikuasainya dengan baik sejak ia masih remaja. Buber mengatakan bahwa dirinya senang berada dalam perubahan dari satu pikiran bahasa ke pikiran bahasa lainya. Selama tinggal di rumah kakek dan neneknya, Buber sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi tentang kedua orang tuanya. Kakek dan neneknya selalu menghindar untuk berbicara tentang kedua orang tua Buber. Sebagai seorang anak yang masih kecil, Buber tentu merindukan kehadiran kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Namun kerinduan itu hanya dapat disimpannya dalam hati. Ia terus menunggu perjumpaan kembali dengan sang ibu. Penantian Buber akhirnya kandas setelah seorang gadis, dalam suatu pembicaraan di balkon rumah neneknya, memberitahukan bahwa ia tidak akan bertemu kembali dengan ibunya. Sang ibu tidak akan kembali. Pada saat itu usianya baru empat tahun. Sebagai anak usia empat tahun, Buber tentu mengalami situasi yang amat pahit mengetahui ibu yang dirindukannya tidak akan kembali. Lama kelamaan Buber dapat menerima kebenaran apa yang dikatakan sang gadis kepadanya. Dari pengalaman ini Buber mengambil suatu pelajaran bahwa setiap orang pasti akan mengalami suatu pengalaman gagal berjumpa dengan orang yang dikasihinya. Buber merasa menderita karena ketidakhadiran sang ibu. Pengalaman tersebt mendorong Buber menemukan suatu kata untuk menggambarkanya, yaitu Vergegnung yang berarti ketiadaan perjumpaan.9 Kata Vergegnung menggambarkan 9 Pamela Vermes, Buber on God and The Perfect Man, 1980, Scholar Press : USA, h. 11. Vermes menterjemahkan Vergegnung dengan mis-encounter. Sementara Maurice Friedman menerjemahkannya dengan mis-meeting. BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber suatu perjumpaan yang seharusnya terjadi antara seorang pribadi dengan pribadi lainnya, namun tidak terjadi. Buber menilai bahwa pengalamannya di balkon itu merupakan pengalaman yang paling dasariah mengenai suatu perjumpaan. Walaupun pada kenyataannya perjumpaan itu tidak pernah terjadi. Buber sendiri pada usia 14 tahun tinggal kembali bersama dengan ayahnya yang telah menikah kembali. Perkenalan awal Buber dengan filsafat dimulai ketika ia membaca karya-karya Plato dalam bahasa Yunani. Ketertarikan dan keterlibatan lebih dalam ia dapatkan setelah membaca buku Immanuel Kant, Prolegomena, pada usia 15 tahun. Dua tahun kemudian ia berkenalan dengan Nietzsche lewat, Thus Spake Zarathustra. Buber menggambarkan bahwa kedua buku ini membawa dirinya pada “kebebasan filosofis”. Masalah ruang dan waktu, dan eksistensi manusia berhadapan dengan ruang dan waktu yang hanya merupakan persepsi, seperti yang dikatakan Kant, merupakan pergumulan awal Buber dalam kebebasan filosofisnya. Lewat tulisan Kant ini Buber kemudian membuka pemahaman bahwa ketidakterbatasan ruang dan waktu sama tidak mungkinnya dengan keterbatasan ruang dan waktu. Pada kurun waktu 1897-1899, Buber belajar di dua universitas yaitu Universitas Leipzig dan Universitas Zurich. Setelah kurun waktu itu, ia masih melanjutkan kuliah di universitas Berlin dan Wina. Buber meraih gelar ‘doktor’ di Universitas Wina. Ia mengikuti hampir semua mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat, filologi, psikiatri, ekonomi dan sastra. Psikiatri amat menarik minat dari Buber, sehingga ia hampir mengikuti seluruh mata kuliah psikiatri yang disampaikan oleh Erns Mach, Wilhelm Wund dan Carl Stumpf. Sewaktu Buber belajar di Universitas Leipzig, ia berkenalan dengan gerakan zionis yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Semangat dalam mengikuti gerakan zionis ditunjukkan Buber dengan mempelajari hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan keyahudian, 13 14 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama seperti sejarah, sastra, religiusitas, dan kesenian. Lewat mempelajari berbagai aspek keyahudian itu, Buber melihat Yudaisme lebih pada religiusitas dan kesalehannya, bukan pada permasalahan politiknya. Inilah yang kemudian membedakan Buber dengan pendiri gerakan zionis Theodor Herzl. Karena perbedaan inilah beberapa tahun kemudian Buber menarik diri dari gerakan zionis Theodor Herzl, yang bertujuan melakukan gerakan politik agar bangsa Yahudi mendapatkan tempatnya kembali. Zionisme bagi Buber adalah zionisme kultural. Untuk mewujudkan gagasanya itu Buber menerbitkan majalah zionis Die Welt (Dunia). Kemudian 1916 ia mendirikan majalah Der Jude (Orang Yahudi). Buber kemudian mengajar dan diangkat menjadi profesor di Universitas Frankfurt pada 1923. Bersama sahabatnya, Franz Rosenzweig, ia memulai menerjemahkan Alkitab Yahudi ke dalam bahasa Jerman. Seiring dengan mulai berkuasanya Hitler, pada 1938 Buber pindah ke Yerusalem dan menjadi profesor di Universitas Ibrani. Di Yerusalem ia memimpin gerakan Yikkhud, suatu gerakan untuk mempertebal saling pengertian antara Yahudi dengan Arab di Palestina. Buber menikah 1899 pada usia 21 dengan seorang gadis yang berasal dari Munich bernama Paula Winkler. Paula adalah seorang penulis. Lewat pernikahannya Buber dikaruniai dua orang anak yaitu Eva dan Rafael. Buber meninggal di Yerusalem pada 1965, dalam usia 65 tahun. 2. Karya-karya Martin Buber Buber menulis banyak tulisan, baik buku maupun artikel-artikel. Buku yang termasuk dalam tulisan awalnya adalah The Tales of Rabbi Nahman. Buku ini bercorak Hasidisme. Hasidisme adalah aliran Yahudi yang mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab dalam BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber kehidupannya, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Untuk itu dituntut suatu perilaku yang benar, yang memungkinkan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan. Karya-karyanya dikumpulkan menjadi tiga jilid dengan judul Martin Buber, Werke. (1962-1964). Karya-karyanya mencakup bidang Alkitab dan agama Yahudi, bidang Hasidisme dan bidang filsafat. Dalam bidang Alkitab dan agama Yahudi Buber menulis diantaranya Kingship of God (Kerajaan Tuhan) (1932), Moses : The Revelation and The Covenant (Musa : Wahyu dan Perjanjian) (1945); The Prophetic Faith (Iman Kenabian) (1960). Dalam bidang Hasidisme Buber juga menulis diantaranya The Legend of BaalShem (Legenda Baal-Shem) (1906), The Tales of Hasidism (Kisah-kisah Hasidisme) (1947), Hasidism and The Modern Man (Hasidisme dan Manusia Modern) (1958). Dalam bidang filafat Buber termashur dengan karyanya Ich und Du (1923) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, I and Thou (Aku dan Engkau). Karya lainnya dalam bidang filsafat adalah Eclipse of God (Gerhana Tuhan) (1953) dan Between Man and Man (Antara Manusia dan Manusia) (1961). 3. Perkembangan Pemikiran Martin Buber Karya-karya awal Martin Buber didominasi oleh pemikiran Hasidisme. The Tales of Rabbi Nahman, The Legend of The Baal Shem, dan Daniel merupakan karya awal Buber yang kental bercorak Hasidisme. Pengaruh Hasidisme terhadap Buber dibawa oleh kakeknya, Solomon Buber. Buber sering diajak kakeknya untuk hadir di dalam pertemuan anggota Zaddikim (kelompok dari kaum Hasidisme, dengan pemimpinnya yang disebut Zaddik). Perkenalannya dengan Hasidisme memberi dampak besar terhadap perkembangan spiritualnya. Lewat pemahaman Hasidisme, Buber melihat bahwa kesalahan merupakan esensi dasar dari keyahudian.10 Kekentalan pemahaman Buber akan masalah ini kemudian membawanya pada titik yang berseberangan 10 Pamela Vermes, ibid, h. 15. 15 16 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dengan tokoh Zionis, Theodor Herzl. Tulisan Buber The Legend of Baal Shem diawali dari pendalamannya terhadap tulisan Rabi Yahudi Baal Shem yang berjudul Zevaat Ribesh. Namun Buber sendiri bukan tanpa kritik terhadap Hasidisme. Beberapa tulisannya setelah Perang Dunia pertama memberikan kritik tajam terhadap Hasidisme. Dalam My Way to Hasidisme dan The Holy Way Buber menggariskan pemahaman bahwa kehidupan religius tidak dapat dipisahkan dari dunia dimana dirinya berada. Dan dunia itu bukan hanya dunia komunitas itu sendiri, tetapi juga dunia sekular. Untuk itu religiusitas tidak dapat menutup diri terhadap dunia sekitar, yang dihidupinya sehari-hari. Pemahaman ini merupakan kritiknya terhadap Hasidisme yang menutup diri dan menganggap agama sebagai bidang khusus yang terpisah dari kehidupan sekitarnya. Kritik Buber berlanjut dalam tulisan Hasidism and The Modern Man. Rupanya pengalaman menyaksikan Perang Dunia pertama membuka mata Buber terhadap makna baru dari religiusitas keagamaan. Tulisannya yang memberikan kritik terhadap Hasidisme seolah mempersiapkan Buber untuk bukunya yang terkenal, Ich und Du (1923). Walau pengaruh Hasidisme tidak dapat dihilangkan, lewat Ich und Du, Buber menampakkan kedewasaan intelektualnya.11 Buber berhasil menjernihkan pemikirannya dari pengaruh mistisisme. Dalam Ich und Du, Buber dengan nuansa bahasa yang sangat halus dan pemilihan istilah yang ketat dan dalam, menjernihkan apa yang disebut sebagai “hidup relasional” (relational-life). Penjelajahan pemikiran Buber berhasil menjangkau secara dalam ke arah kehidupan spiritual, intelektual dan psikologi dari manusia. Lewat Ich und Du, Buber memasukkan kehidupan masa depan, dalam keberlangsungan aktual kehidupan manusia saat ini dan seluruh alam semesta. 11 Pamela Vermes, ibid, h. 31. BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber Karya-karya berikutnya dari Buber berisi pengembangan pemahaman yang terdapat dalam Ich und Du. Kingship of God (1932) dan The Question to The Single One (1936), mengembangkan gagasan tentang Tuhan, sebagai yang memperkenalkan diri dengan sebutan “ehyeh asyer ehyeh” (Aku adalah Aku yang ada sebagaimana Aku ada). Lewat kajian eksegetis dari kitab Keluaran Buber memberikan pemahaman bahwa Tuhan ada dalam kehadiran-Nya secara personal yang tidak dapat direduksikan dalam sebutan “dia” atau bentuk orang ke tiga. Buber mengatakan “dia yang hadir kepada mereka, ada bersama mereka – itulah Dia; dia yang hadir kepada Aku, ada bersama aku – itulah Engkau; dia yang hadir kepada engkau, ada bersama engkau – itulah Aku”.12 Tuhan tidak dapat “diikat” dalam bagian sebagai orang ketiga. Ia hadir sebagai Engkau yang menyapa Aku. Tuhan menyatakan kehadiran-Nya kepada manusia dan manusia menyambut kehadiran Tuhan tersebut. Dengan demikian menurut Buber Tuhan bukan hanya “ada” melainkan “hadir saat ini” (present). Hadir dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Tuhan yang hadir menyatakan diri secara personal kepada Musa dalam kitab Keluaran sangat memukau bagi Buber. Bagi Buber, ke –Aku-an Tuhan, itulah yang menjadi the Eternal Thou bagi Aku, sang manusia. Dalam pemikiran-pemikiran berikutnya, Buber mempertegas penolakannya terhadap mistisisme. Bagi Buber praktek mistisisme bertolak belakang dengan pemenuhan personalitas diri sebagai manusia. Tujuan hidup manusia di dunia ini, yaitu untuk memberikan cinta kepada dunia ciptaan Tuhan, tidak akan mungkin tercapai dengan praktek mistisisme yang justru menjauhkan diri dari dunia ciptaan. Tujuan hidup yang digariskan Buber sebenarnya sangat kental 12 “so: he who present to them,, is there with them – HE. He who is present to the I, is there with me – YOU. He who is present to you, is there with you – I”. (Buber, Werke II, Kleinere Schriften , h.189. seperti dikutip Pamela Vermes, ibid, h.94.) 17 18 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama memperlihatkan adanya pengaruh Hasidisme.13 Walaupun dalam praktek yang dilakukan, Buber menolaknya. Penolakan Buber tersebut dapat terlihat dalam pola hubungan yang dikembangkannya. Mistisisme memulai melalui hubungan dengan Tuhan, kemudian peduli dan memperhatikan dunia untuk kepentingan Tuhan dan diakhiri dengan kesempurnaan realisasi hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan bagi Buber, hubungan dimulai dengan pola Aku-Engkau (I and Thou). Kemudian dilanjutkan dengan adanya realisasi dan unifikasi dari Aku. Artinya dalam hubungan Aku-engkau, Aku merealisasikan diri sekaligus menyambut personalitas engkau sehingga terjadi unifikasi. Dan akhirnya pada tahap akhir terdapat hubungan Aku-Engkau Abadi (I and Eternal Thou). Jika mistisisme memulai dengan hubungan Aku dengan Tuhan, maka Buber memulai dengan hubungan Aku dengan “engkau” (sesama). Bagi Buber realitas kongkret yang dialami manusia sehari-hari adalah “engkau”.14 Pemahaman inilah yang menandai puncak pemikiran dari Buber. 4. Pengaruh Hasidisme Hasidisme adalah aliran mistis umat Yahudi di Eropa Timur, yang muncul abad 18 di Polandia. Pemimpinnya di sebut Zaddik (jamak: Zaddikim).15 Inti ajaran Hasidisme adalah pentingnya menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, mencintai Tuhan dan sesama, peka terhadap wahyu Tuhan dan menekankan doa sebagai unsur terpenting untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Buber sendiri mengakui bahwa dirinya sangat dipengaruhi oleh Hasidisme. Ia mengatakan bahwa Hasidisme awal sangat mempengaruhinya dibanding Hadisisme 13 Pamela Vermes, ibid, h.159. Pemikiran Buber mengenai hal ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam Bab V. 15 Maurice Friedman, Martin Buber’s Life and Work, The Early Years 1878-1923, h.94. Pamela Vermes menyebutnya Zaddikim sebagai “orang suci kaum Hasidim” (Lih. Pamela Vermes, h.11). 14 BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber dalam perkembangan berikutnya. Penggagas-penggagas awal Hasidisme begitu memikat hatinya.16 Memang dalam perkembangan pemikiran berikutnya, ia secara keras melontarkan kritik terhadap Hasidisme terutama perkembangan Hasidisme setelah Perang Dunia I. Salah satu pemikiran yang paling mempengaruhinya adalah tulisan seorang tokoh Hasidisme, yaitu Baal Shem. Baal Shem mengemukakan bahwa di antara Tuhan dan manusia ada hubungan timbal balik. Lewat hubungan itulah makna hidup manusia dijalankan sepanjang hidupnya.17 Manusia menerima segala sesuatu dari Tuhan dan apa yang manusia lakukan, dilakukan untuk Tuhan. Hanya manusia yang mau dan mampu mengarahkan dirinya menuju pada “kesempurnaan” selaku manusia, ia dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Apa yang dikemukakan oleh Baal Shem menjadi titik tolak pemikiran Buber mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Makna hidup manusia dibentuk melalui tindakannya dalam menjalankan hubungan dengan Tuhan, sesama dan dunia. Pengaruh Hasidisme membentuk pemikiran Buber menjadi religius. Titik tolak pemikirannya adalah sikap religius yang ada di dalam dirinya. Ia sendiri mengatakan bahwa seluruh pemikirannya harus dilihat sebagai satu kesatuan berupa pemikiran religius, seperti yang dikemukakan oleh Walter Kaufmann. Baginya sikap religius mencakup seluruh hidup manusia. 5. Pengaruh Pemikir-pemikir Lain Di samping Yudaisme dan Hasidisme, pemikiran Buber juga dipengaruhi oleh pemikir-pemikir lainnya. Ketika ia masih berusia belasan tahun, ia sudah membaca buku Prolegomena dari Immanuel 16 Martin Buber, Replies to My Critics, dlm Martin Buber’s Philosophy, 1967, (Ed) Paul A. Schillp & Maurice Fieldman, h.734. 17 Martin Buber, ibid, h. 735. 19 20 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama Kant dan Thus Spake Zarathustra dari Friedrich Nietzsche. Melalui kedua pemikir tersebut ia memahami bahwa “waktu” tidaklah menentukan hidup manusia, justru manusia yang menentukan hidupnya sendiri. Manusia mengatur waktu dengan demikian manusia yang akan menentukan makna hidupnya melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ia mengatakan dengan pemahaman seperti itu dirinya seolah-olah dibebaskan dari kungkungan waktu yang terus mendesaknya tanpa ampun. Seorang pemikir lainnya, yang sangat mempengaruhi jalan pemikiran Buber, tidak lain adalah sahabatnya sendiri yaitu Franz Rosenzweig. Bersama Rosenzweig, ia membuat terjemahan kitab suci Yahudi ke dalam bahasa Jerman. Rosenzweig mempunyai pemikiran bahwa Tuhan, manusia dan dunia masing-masing bersifat independen, tetapi tetap mempunyai hubungan satu dengan yang lain yang diwujudkan sepanjang waktu. Tuhan menurutnya adalah “Tuhanbagi-yang-lain”. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa berada di dalam hubungan. Tuhan berada dalam hubungan dengan manusia dan dunia, dan Tuhan pun ada manakala sesama manusia menjalin hubungan. Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia mempunyai kebebasan. Walaupun manusia adalah ciptaan Tuhan, namun manusia berdiri di depan Tuhan dengan kebebasannya dan dalam posisi yang “setara”. Rosenzweig menolak idealisme yang hendak menggabungkan Tuhan, manusia dan dunia sebagai satu substansi. 18 Pemikiran Rosenzweig sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran Buber selanjutnya. Selanjutnya bukan hanya pemikiran Rosenzweig, tetapi caranya berfilsafat juga sangat mempengaruhi Buber. Rosenzweig berfilsafat dengan cara eksistensial, yaitu melibatkan seluruh kepribadiannya.19 18 Maurice Friedman, Martin Buber’s Life and Work, The Early Years 1878-1923, 1982, h.286-287. 19 Kees Bertens, Filsafat Barat Abad XX, Inggris-Jerman, 1983, h. 157. BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber 6. Pengaruh Eksistensialisme Apakah yang dimaksud dengan eksistensialisme? John Macquarrie mengatakan bahwa eksistensialisme merupakah salah satu cara berfilsafat dengan ciri utama mendasarkan diri pada manusia dibanding dari alam. Berfilsafat dengan pendasaran pada subyek dari pada obyek.20 Namun berbeda dengan idealisme, yang juga mendasarkan diri pada subyek, eksistensialisme mendasarkan diri pada subyek dengan seluruh cara beradanya sebagai persona, bukan hanya sebagai subyek yang berpikir seperti pada idealisme. Manusia berada di dunia, namun ia bukan hanya berada karena benda-benda pun berada di dunia. Manusia sekaligus “menghadapi dunia”, yaitu dengan mengerti berbagai hal yang dihadapinya. Manusia mengerti benda-benda, hewan, alam semesta bahkan dirinya sendiri dengan harapan, ketakutan, kegelisahan, kematian, hubungannya dengan orang lain dan hubungannya dengan yang Ilahi. Dengan mengerti, manusia menyadari bahwa hidupnya berarti. Hidup bukan hanya berada namun juga mempunyai arti.21 Manusia sebagai subyek seperti itulah yang akan menjadi titik tolak bahasan eksistensialisme. John Macquarrie sendiri mengatakan bahwa dalam kaitan dengan pemikiran eksistensialisme, Buber tidak dapat dikategorikan sebagai pemikir eksistensialis seperti halnya Kierkegaard, Sartre atau Camus. Namun dalam pemikiran Buber, jejak eksistensialisme sebagai sebuah pola berpikir terlihat secara jelas. Macquarrie menyebut Buber sebagai near-existentialist atau berkecenderungan eksistensialis (existentialist tendency).22 Berbeda dengan Sartre atau Camus yang menolak segala klaim religius dan benar-benar menekankan tanggung jawab 20 John Macquarrie, Existensialism, 1972, Pelican Book:New York, h.2. Driyarkara, Percikan Filsafat, 1989, PT. Pembangunan Jaya:Jakarta, h.56. 22 John Macquarrie, op.cit, h.4,6. 21 21 22 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dan otonomi individu, Buber justru sangat menekankan religiusitas, sebagai bagian dari pengaruh Hasidisme yang ia terima. Ada beberapa kekhasan eksistensialisme yang dapat terlihat dalam pemikiran Buber, yaitu : 1. Ada bersama yang lain, sebagai karakteristik dasar dari manusia. Eksistensialisme melihat bahwa salah satu karakteristik dasar dari manusia adalah “ada bersama yang lain”. “Ada bersama yang lain” berarti membina hubungan dengan yang lain. Yang lain adalah benda-benda, hewan, alam sekitar dan manusia. Manusia menyadari bahwa dirinya membina hubungan dengan yang lain. Dalam pemahaman Buber, tidak ada “Aku” yang berdiri sendiri. Aku senantiasa berada dalam relasi dengan orang lain. “Aku” hanya ada dengan dua kata, yaitu “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. Dengan demikian Buber menggariskan bahwa “Aku” hanya ada sebagai “Aku-ada-bersama-yang lain” dan “Aku-ada-didunia” (being-with-others and being-in-the- world). Dengan demikian kekhasan cara berpikir eksistensialis terlihat dalam pemahaman Buber. ‘Aku-Engkau” merupakan realitas sosial yang membuat adanya “diri” dan personalitas individu menjadi mungkin. Pemahaman bahwa “aku” dapat mengasingkan diri dari yang lain dan hidup sendiri (soliter) merupakan khayalan belaka. Manusia tidak dapat menjadi penonton dalam dunia ini. Dengan kesadaran dan kemampuannya melakukan persepsi (perception) manusia terlibat, baik di dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya bersama yang lain.23 2. Hubungan antar pribadi Di dalam dunia, manusia bertemu dengan manusia lainnya. Manusia yang lain bukanlah obyek yang ada di dalam dunia atau bukan sebagai “alat” yang disediakan dunia untuk “aku”. Keberadaan 23 Martin Buber, Replies to My Critics, dlm. Paul Althur Schilpp, op.cit., h.695. BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber mereka di dalam dunia, sama seperti keberadaan “aku” di dalam dunia.24 Merekapun membentuk dunia. Inilah pemahaman eksistensialis mengenai keberadaan “orang lain” di dalam dunia. Sebagai sesama subyek, mana hubungan antar pribadi merupakan keharusan yang tak terhindarkan. Justru “aku” membentu diri dalam hubungan dengan “orang lain”. “Aku” menaruh perhatian (concern) terhadap lingkungan dunia, tetapi “aku” mencemaskan (solicitude) keberadaan orang lain. Bagi Buber, pola hubungan “Aku-Engkau” mempunyai aspek timbal balik antar pribadi. “Aku” dalam pola hubungan “Aku-Engkau” bukanlah “aku” yang menjadikan yang lain sebagai obyek, tetapi “aku” yang menghargai keberadaan yang lain sebagai yang sama dengan “aku”. “Engkau” adalah yang lain, yang mempunyai harapan, kecemasan atau ketakutan yang sama dengan aku. Dengan “Aku-Engkau” , manusia dihubungan secara total dengan orang lain. Orang lain bukan sebagai “yang ada” untuk aku, apalagi sebagai alat pelampiasan kesenangan dari sang “aku”. Buber nampak dengan jelas menempatkan hubungan antar pribadi sebagai hubungan yang bersifat primordial bagi manusia. Dialog menjadi hal yang sangat penting dalam pola hubungan seperti itu. Mengatakan bahwa hubungan interpersonal bersifat timbal balik secara setara, sama dengan mengatakan bahwa dialog merupakan bagian tak terpisahkan dalam hubungan antar pribadi. 3. Bahasa Pemikiran manusia diartikulasikan melalui bahasa. Bahasa menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Pemaknaan dan referensi yang dituju oleh makna itu ditandakan melalui bahasa. Dalam pemahaman eksistensialis bahasa merupakan fenomena eksistensial manusia yang diperoleh melalui berbagai struktur internal yang ada di dalam dirinya dan referensinya. Bahasa tidak pernah tanpa 24 John Macquarrie, op.cit,h. 79. 23 24 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama manusia yang membahasakannya. Semua bahasa merupakan “bahasa seseorang”. Artinya semua bahasa pastilah dipakai oleh seseorang. Bahasa juga senantiasa mengarahkan diri pada seseorang. Bahkan ketika ia berbicara seorang diri, bahasa tetap terarah pada seseorang, yaitu –paling tidak- pada dirinya sendiri. Itu berarti bahwa dalam studi mengenai bahasa, pemahaman eksistensialis senantiasa mengaitkannya dengan “ada-bersama-orang-lain” (being-with-others). Sartre, misalnya, mengatakan bahwa seseorang harus menjadikan dirinya menarik bagi orang lain. Dan itu dilakukan lewat berbahasa. Bahasa menjadi sumber bagi “aku” untuk berada bersama orang lain. Demikian juga dengan Buber.25 Buber membuka buku I and Thou dengan ide utama mengenai “kata-kata dasar” (primary words), yaitu “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. Kombinasi kata tersebut tidak ingin menunjukkan suatu hal yang tertutup pada dirinya sendiri, melainkan terbuka dalam relasi. Kata “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” berada dalam konteks “ada-bersama-yang-lain-di-dunia” (being-with-others-inthe-world). Jika “Aku” berkata, maka “Aku” berkata dalam kombinasi “Aku-Itu” atau “Aku-Engkau”. Demikian juga ketika “Engkau” berkata, ia berkata dalam hubungan dengan “Aku”. Dalam pemikiran Buber ini terlihat penekanan pada dimensi pribadi dari bahasa yaitu komunikasi. Kata-kata dasar bukan menunjuk pada benda, melainkan pada relasi yang intim. Bagi Buber relasi eksistensial dari bahasa ditunjukkan dengan kata “Aku-Engkau”. Relasi eksistensial inilah yang menyebabkan bahasa menjadi mungkin. Pada pihak lain, bahasa-lah yang menyebabkan hubungan eksistensial menjadi mungkin. Dengan demikian pemikiran Buber mengandung analisa eksistensialis mengenai bahasa. 25 John Macquarrie, ibid, h.111. BAB II Hidup, Karya dan Perkembangan Pemikiran Martin Buber 7. Kesimpulan Perkenalan dengan Hasidisme yang dibawa oleh kakek maupun ayahnya sangat berkesan dalam hidup Buber. Pemikiran tokoh-tokoh Hasidisme awal memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadapnya, terutama pemikiranya mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama dan makna hidup manusia yang ditandai dengan tindakan kongret untuk mencintai Tuhan dan sesama. Pengaruh Hasidisme membuat pemikiran-pemikiran Buber harus dilihat dalam kerangka sikap religius. Kritiknya terhadap Hasidisme terutama ditujukan kepada Hasidisme pasca Perang Dunia I, yang cenderung eksklusif. Sementara itu pemikiran Buber juga memperlihatkan jejak-jejak gaya berpikir eksistensialisme, walaupun seperti yang dikatakan oleh John Macquarrie, Buber tidaklah dapat dikategorikan sebagai filosof eksistensialis. Latar belakang masa kecilnya yang harus menanggung akibat perceraian kedua orang tuanya, didikan kakek dan neneknya dalam bidang sastra, perjumpaannya dengan Hasidisme dan perkenalannya dengan tokoh-tokoh eksistensialis yang tulisannya ia baca sewaktu berumur belasan tahun, membentuk pemikiran Buber. Setelah kita memahami riwayat hidup dan latar belakang pemikiran Buber, maka pada bab selanjutnya akan diungkapkan pemikirannya mengenai dua hubungan yang dijalani manusia, yaitu hubungan “AkuItu” dan “Aku-Engkau”. Dengan bekal sikap religius yang ia miliki, Buber mencoba menstrukturisasikan hubungan antar manusia sebagai pribadi, yang akan dijadikannya sebagai dasar untuk menguraikan hubungan manusia dengan Tuhan. 25 26 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” Pada bagian ini akan diuraikan pemikiran Buber mengenai hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. Namun akan diuraikan terlebih dahulu pemikirannya tentang proses mengetahui realitas dan pemikirannya mengenai pribadi. Pemikirannya tentang proses mengetahui realitas akan memberikan pemahaman yang lebih jelas untuk masuk ke dalam pemikirannya tentang hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. Melalui “hubungan” seseorang mengetahui adanya realitas. Namun pertanyannya adalah apakah yang dimaksud dengan “realitas” oleh Buber? Dan bagaimana seseorang dapat mengetahuinya? Demikian juga halnya dengan pemikirannya mengenai pribadi. Salah satu aspek yang membedakan hubungan “Aku-Itu” dengan “Aku-Engkau” adalah aspek “pribadi”. Hubungan “Aku-Engkau” merupakan hubungan antar pribadi yang mempunyai dimensi timbal-balik, sedangkan hubungan “Aku-Itu” bukanlah hubungan antar pribadi. Karena itu menjadi sangat penting memahami terlebih dahulu bagaimana pemikirannya mengenai pribadi. 27 28 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama 1. Realitas (Wirklichkeit) dan Proses Pengetahuan Buber mengemukakan manusia selalu berhubungan dengan tiga pihak dalam dunia ini, yaitu berhubungan dengan alam (termasuk benda-benda), berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan “Ada yang Transenden” yang disebut sebagai “Yang Absolut” atau yang oleh kaum beragama disebut “Tuhan”.26 Ketiga arah ke mana manusia melakukan hubungan tersebut, berkaitan dengan pemahamannya mengenai realitas. Ketiga hal tersebut bukanlah realitas. Bahkan “Aku” pun bukanlah realitas. Bagi Buber realitas adalah “ruang antara” (in between) yang terbuka ketika aku berhubungan dengan ketiganya. Hubungan tersebut dibangun di atas dasar hubungan timbal balik. Ia menyebut juga realitas sebagai “aktualitas”, dasar di mana seseorang membangun kehidupan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana manusia dapat mempunyai pengetahuan mengenai alam, orang lain dan Tuhan? Ia mengatakan bahwa jika pikiran manusia tidak menyatu alam, orang lain dan Tuhan, maka ia tidak akan mempunyai pengetahuan tentangnya.27 Pikiran manusia mengobjektivasi berbagai macam hal tersebut dan menyatukannya. Sarana yang dipakai untuk melakukan hal itu adalah perangkat filosofis yang dimiliki manusia. Perangkat filosofis merupakan kemampuan pikiran untuk mempersepsi dan memahami setiap hal yang dijumpainya. Menurutnya semua manusia yang “berpikir” mempunyai dan menjalankan perangkat ini. Lewat perangkat filosofis pikiran mempunyai kemampuan untuk memikirkan hubungannya yang kongkret dengan “ada”. Buber mengungkapkan bahwa ada dua macam proses pengetahuan yang berlangsung di dalam diri manusia. Proses yang pertama 26 Robert E. Wood, Martin Buber’s Ontology, 1969, Northwestern Univ. Press:Northwestern, h.44-45. 27 Martin Buber, EoG,, h.42 BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” berlangsung antara subjek dengan objek. Dalam proses ini seseorang mengategorikan, memilah-milah dan memberikan berbagai label pada objek pengetahuannya. Suatu objek menjadi objek pengalaman dan objek penggunaan. Objek tersebut menjadi objek pengalaman karena subjek mengalami langsung hubungannya dengan objek tersebut. Buber menyebutnya sebagai objek yang “dialami”.28 Sementara itu objek juga sekaligus menjadi objek penggunaan, karena subjeklah yang akan menggunakannya untuk keperluan subjek. Dengan demikian objek menjadi objek yang “dialami” dan “digunakan”, sedangkan subjek menjadi subjek yang “mengalami” dan “menggunakan”. Proses ini berlaku sepihak. Buber memberi contoh mengenai orang yang melihat pohon. Ketika orang melihat pohon maka pikirannya akan mengonstruksi pohon tersebut. Pikirannya akan memilah, mengategori atau dapat terjadi ia membiarkannya. Namun menurutnya justru lewat proses ini seseorang mengembangkan pengetahuannya mengenai sesuatu. Karena itu proses ini biasanya menjadi dasar bagi pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan.29 Proses yang kedua berlangsung antara subjek dengan subjek. Dalam proses ini subjek menganggap dan memperlakukan baik alam, manusia maupun Tuhan bukan sebagai objek, melainkan sebagai sesama subjek. Jika dalam proses pengetahuan yang pertama berlangsung hubungan sepihak, maka dalam proses kedua berlangsung hubungan timbal balik. Subjek membiarkan diri dibentuk pemahamannya oleh subjek yang lain. Tidak ada lagi objek yang “dialami”. Objek 28 Martin Buber, I and Thou, 1970, Charles Scribner’s Son:New York, h. 56. (selanjutnya disingkat IT) Walter Kaufmann menterjemahkan demikian: “The World does not participate in experience. It allows itself to be experienced….” 29 Pemahaman ini sekaligus menjadi dasar epistemologi Buber mengenai pengetahuan konseptual. Distingsi yang tajam antara subyek dengan obyek membuat pengetahuan menjadi mungkin. Hubungan Aku-Itu pada Buber mengungkapkan hubungan antara pikiran dengan objek yang berada di luar diri. (Lih. Brendan Sweetman, Martin Buber’s Epistemology, dlm. International Philosophical Quarterly, Vol. XLI, No.2 Issue No. 162, h.145-160. (Juni 2001). 29 30 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama berubah menjadi subjek sebagaimana “aku” sebagai subjek. Ia berdiri sebagai subjek yang melakukan hubungan dengan “aku”. Buber mengistilahkannya dengan “perjumpaan”. Inilah proses pengetahuan di mana manusia berjumpa dan mengenal dengan subjek lainnya dalam dunia ini. Ia mengatakan bahwa proses kedua berada dalam sebuah pengetahuan religius. Kemudian ia mengambil contoh dari Alkitab, yaitu peristiwa perkenalan Adam dengan Hawa. Pengenalan tersebut merupakan suatu pengetahuan religius.30 Adam melakukan perjumpaan dengan Hawa sebagai sesama subjek. Hawa bukanlah objek yang sedang dipersepsi oleh Adam, atau sebaliknya. Di antara keduanya ada intimitas dalam hubungan timbal balik sebagai pasangan. Adam memperhatikan kepentingan dan keinginan Hawa. Dengan berbuat seperti itu keberadaan diri Hawa membentuk diri Adam. Demikian juga sebaliknya. Inilah pengetahuan yang muncul dari hubungan yang setara antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang sama juga terdapat dalam kitab Hosea, yaitu hubungan Tuhan dengan umat-Nya. Ada intimitas dalam hubungan timbal balik yang sama antara Tuhan dengan umat-Nya. Tuhan adalah pasangan bagi umat-Nya. Realitas terdapat dalam proses pengetahuan yang kedua. Melalui proses pengetahuan yang berlangsung antara subjek dengan subjek, realitas hadir. Ketika seseorang melakukan proses pengetahuan subjek dengan subjek, ia akan menyadari adanya realitas, yaitu ruang antara antara dirinya dengan subjek lainnya. Dalam proses pengetahuan seperti itulah seseorang menjalankan aktualitas hidupnya di dunia ini. 31 30 Pedro Sevilla, God as Person in The Writing’s of Martin Buber, 1970, Loyola House:Manila, h.18 31 Martin Buber, IT, h.136-137. BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” 2. Pribadi Buber memisahkan antara ego (ego, Eigenwensen,) dengan Aku pribadi (person, Ich). Ego muncul dengan cara memisahkan dirinya dari hubungan dengan yang lain.32 Sedangkan pribadi justru muncul dengan memasuki hubungan dengan yang lain. Tujuan ego memisahkan diri dari hubungan dengan yang lain adalah untuk “mengalami” yang lain dan “menggunakan” yang lain. Untuk itu bahasa yang dipakai adalah bahasa kepemilikan, seperti duniaku, pohonku, bajuku, kekasihku dan sebagainya. Ego adalah manusia menyadari bahwa dirinya adalah subjek yang “mengalami” dan “menggunakan”. Menurutnya ego tidak mempunyai aktualitas karena ego menarik diri dari hubungan. Aktualitas seseorang justru didapatkan ketika dirinya berada dalam hubungan dengan orang lain. Ego menjadikan dirinya sebagai pusat dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Untuk itu ego bisa mendapatkan dirinya berada dalam dua bentuk yaitu menjadi penyombong (egotist), yaitu “Aku” yang selalu merasa lebih unggul dari orang lain atau selalu mementingkan dirinya sendiri (selfish man)33, yaitu “Aku” yang selalu menganggap keberadaan orang lain sebagai alat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Sebaliknya pribadi sadar akan subjektivitasnya. Kesadaran akan subjektivitasnya menunjukkan bahwa ia mempunyai keterbukaan, yaitu keterbukaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam kesadaran akan subjektivitasnya “Aku” menjalani hubungan dengan orang lain. “Aku” menerima, mengenal dan mengakui orang lain. Dan dengan itu “Aku” dapat menerima, mengenal dan mengakui dirinya sendiri. “Aku” sadar bahwa dirinya tidak bisa dilepaskan dari hubungan dengan 32 Martin Buber, IT, h.62. Walter Kaufmann dalam terjemahannya mengatakan bahwa istilah Eigenwesen yang menunjuk pada ego, berarti ada untuk dirinya sendiri. Istilah ini oleh Buber dipakai untuk menyebut manusia yang hanya mengurudi hubungan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. (Lih. Walter Kaufmann, h. 112) 33 Robert E. Wood, op.cit, h.81. 31 32 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama orang lain, dan sadar bahwa dirinya dibentuk dan dibina oleh orang lain dalam hubungan tersebut. Ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan orang lain. Pribadi adalah manusia yang masuk ke dalam hubungan dengan orang lain dan hidup di dalam hubungan dengan orang lain. Lewat hubungan dengan orang lain, hubungan dirinya dengan realitas dan sejarah serta masa depan dibangun. Dengan demikian aktualitas dari pribadi ditentukan melalui partisipasinya dalam hubungan dengan orang lain. Di dalam hubungan terdapat satu aspek penting yang juga dijalani oleh “Aku”, yaitu dialog. Perjumpaan antara “Aku” dengan orang lain dimungkinkan dengan adanya dialog di antara keduanya. Dialog mewujudkan transformasi yang terjadi di antara dua pribadi. Dalam dialog “Aku” mengakui yang lain sebagai yang setara dengan dirinya, sebagai subjek yang memberi sekaligus yang menerima sama seperti dirinya. Transformasi ini menghilangkan sikap mengobjekkan antara yang satu dengan yang lain. Dialog yang ada adalah dialog yang setara antara subjek dengan subjek. Atau dengan kata lain, dialog antara pribadi dengan pribadi, karena pribadi-lah yang dapat berdialog. Menurut Buber penjelmaan dari dialog di antara kedua pribadi menunjukkan bergesernya komunikasi (communication) menjadi persekutuan (communion).34 Peran orang lain dalam membantu “Aku” yang sedang berada dalam proses “mempribadi” terjadi di dalam komunitas. Komunitas dibangun diatas dasar perjumpaan timbal balik. Dengan demikian menurutnya tempat yang paling real bagi aktualisasi diri manusia terdapat dalam komunitas. Dengan demikian menurut Buber “Aku” senantiasa berada dalam proses “mempribadi”. Proses tersebut hanya terdapat dalam hubungan “Aku-Engkau”. Bersama dengan “Engkau”, “Aku” menjalin persekutuan dan masing-masing saling membentuk dalam proses “mempribadi”. 34 Martin Buber, Between Man and Man, 1971, h.21. (selanjutnya disebut BMM) BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” Dalam proses “mempribadi”, perjumpaan dengan “Engkau” menjadikan “Aku” dapat menghargai perbedaan dan kebebasan orang lain. Hadirnya “Engkau” dalam perjumpaan dengan “Aku” menyebabkan “Aku” sadar akan diriku, duniaku dan apa yang harus aku lakukan untuk menjadikan hidupku dan orang lain bermakna; sekaligus kehadiran “Engkau” menyebabkan “Aku” sadar bahwa diriku tidak dapat hidup tanpa orang lain. Apakah ego dan pribadi merupakan dua entitas terpisah dalam diri manusia? Buber mengatakan tidaklah demikian. Ego dan pribadi merupakan dua kutub yang ada di dalam diri seorang manusia. Tidak ada manusia yang menjadi pribadi sempurna atau sejati, demikian juga dengan ego. Setiap manusia hidup dalam dua kutub tersebut. Yang ada adalah manusia yang kadang-kadang menjelmakan ego di dalam dirinya, dan manusia yang kadang-kadang menjelmakan pribadi di dalam dirinya. Keduanya ada dalam kehidupan manusia. Namun ia memperingatkan bahwa semakin banyak ego mendominasi dalam kehidupan manusia, semakin dirinya kehilangan aktualitas kehidupan. Aktualitas ada pada pribadi, yaitu “Aku” yang berhubungan timbal balik dengan orang lain. 3. Hubungan Aku-Itu dan Aku-Engkau 3.1. Hubungan Aku-Itu Hubungan Aku-Itu adalah hubungan yang sepihak dan bersifat posesif. Dalam hubungan itu, “Aku” mengategorikan, menyusun, memperalat segala sesuatu yang dialami. Ketika Aku berhadapan dengan pohon, aku mengategorikannya berdasarkan bentuk, unsur kimia atau unsur mekanisnya. Namun aku sendiri tidak mempunyai kesan yang mendalam tertuju kepada pohon tersebut. Pohon itu tidak berperan lebih lanjut dalam seluruh imajinasi dan gambaran yang ada di dalam diriku. Bagi Buber hubungan seperti ini tidak menampakkan suatu 33 34 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama arti yang mendasar. “Itu” sama sekali tidak mempengaruhi aku dan tidak berperan untukku. Aku yang berada dalam hubungan “AkuItu “ adalah aku yang tidak membiarkan “Itu” mempengarui “Aku”. Hubungan Aku-Itu menandakan adanya pemisahan karena “Itu” tidak dapat mempengaruhi “Aku”. Ia mengatakan bahwa pemisahan itu adalah pemisahan antara subjek dan objek. Dalam hubungan ini, “Itu” tidak lebih dari sekedar apa yang dialami dan yang digunakan oleh subjek. Menurutnya, “Aku” yang berada dalam hubungan “Aku-Itu” adalah Aku yang hanya mempunyai masa lampau, tetapi tidak mempunyai masa kini. Masa lampau dipahami sebagai sesuatu yang “mati”, tidak bergerak dan tidak menampakkan dinamika gerakan timbal balik. Sedangkan masa kini dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, aktif bergerak dan menampakkan gerakan yang dinamis. Karena itu ia mengatakan bahwa melalui konteks perjumpaan hadirlah masa kini. Kekinian dirasakan dalam satu hubungan timbal balik yang setara. Sedangkan yang terjadi dalam hubungan “Aku-Itu” adalah bagaimana Aku “mengalami” dan “menggunakan” apa yang sudah tersedia, tanpa adanya hubungan timbal balik yang setara. Apa yang aku alami dan aku gunakan tidak lebih dari objek semata. Baginya “Itu” tidaklah menyatakan kehadirannya (presence) kepada “Aku”. “Itu” ada secara pasif. Sifat ini merupakan simbolisasi masa lampau. Kehadiran selalu menunjukkan proses yang berlangsung terus, yaitu aspek kekinian. Apa yang menjadi objek senantiasa tidak dapat menyatakan kehadirannya. Objek berada pada masa lampau.35 Secara tegas ia mengatakan bahwa di dalam hubungan “Aku-Itu” tidak ada aspek perjumpaan. Menurutnya hal itu terjadi karena tidak adanya keterlibatan pribadi yang menyeluruh. Aku menahan diri dan menjaga jarak terhadap Itu. Aku menganggap Itu sebagai sesuatu yang 35 Martin Buber, IT, h. 64. BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” asing dan melihatnya hanya dari segi kuantitas. “Aku” menutup diri kepada “Itu” dengan tidak membiarkan “Itu” ada pada dirinya sendiri melainkan ada menurut pemikiran “Aku”. Proses seperti itu menutup kemungkinan terjadinya suatu perjumpaan. Apakah dengan demikian Buber mau mengatakan bahwa hubungan “Aku-Itu merupakan hubungan antara manusia dengan benda? Ia menolak pemahaman itu. Ruang lingkup “Itu” tidaklah terbatas pada benda-benda mati, tetapi juga mencakup manusia, bahkan Tuhan. Ia mengemukakan hubungan “Aku-Itu” sebagai sebuah pola hubungan yang dipakai manusia. Dan pola ini dapat dipakai seseorang kepada apa saja dalam kehidupannya. Ketika “Aku” mengobjekkan yang lain, baik benda-benda, alam sekitar, manusia maupun Tuhan, maka pada saat itu “Aku” menerapkan pola hubungan “Aku-Itu”. Baginya ruang lingkup “Itu” adalah dunia pengalaman (Erfahrung).36 Ia memaksudkan “pengalaman” sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk berbagai tujuan demi kepentingan “Aku” termasuk kepentingan pengetahuan teoretis. Lewat pengalaman “Aku” memasukkan segala yang lain ke dalam diriku sendiri. “Yang lain” tidak berada di “ruang antara” (in between) Aku dan dunia. Karena itu tidak ada realitas di antara “Aku” dengan “Itu”. Bagi Buber, ketika yang lain berada pada posisi di “ruang antara” (in between), maka ia hadir dengan seluruh keberadaannya yang tidak dapat ditentukan oleh Aku karena dalam posisi di “ruang antara”, berarti ada suatu hubungan yang setara dan timbal balik. Sementara itu dalam pengalaman, Aku hadir sebagai diri yang egois, yang mengobjektivasi yang lain demi kepentinganku. Dunia pengalaman adalah dunia untuk kepentingan dan pemuasan diri “Aku” belaka dengan memperalat yang lain. Ia memang mengakui bahwa ada pengalaman batiniah disamping pengalaman lahiriah, 36 Martin Buber, IT, h.56, 88. 35 36 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama namun pengalaman batiniah baginya tidak berbeda dengan pengalaman lahiriah, yaitu berada dalam dunia Itu. Di samping dunia pengalaman, ia juga mengatakan bahwa dunia filsafat sebagai bagian dari ilmu pengetahuan berada dalam hubungan “Aku-Itu”. Menurutnya dalam ilmu pengetahuan, yang lain (objek) menjadi tertutup terhadap Aku. Seperti telah dikemukakan pada bagian pemahaman Buber mengenai proses pengetahuan, ia mengatakan bahwa dunia filsafat berada dalam proses mengetahui dengan pola subjek-objek. Pola subjek-objek merupakan pola khas yang menampakkan hubungan “Aku-Itu”. Lewat filsafat seseorang mencoba memalingkan dirinya dari situasi kongkret dan membuat pemilahan dan pengategorian dengan berbagai konsep. Dalam dunia filsafat, sebagaimana ilmu pengatahuan lainnya, hanya ada dua pihak yang berperan, yaitu subjek yang melakukan observasi, mengalami dan menggunakan yang lain demi kepentingan dirinya sendiri dan objek yang diobservasi, dialami dan kemudian digunakan subjek demi kepentingan subjek. Dunia filsafat merupakan dunia di mana hubungan “Aku-Itu” mendapatkan puncak perhatian. 37 Dalam filsafat terjadi transformasi sempurna “Itu” sebagai objek. Aku mentranformasikan “Itu” menjadi objek yang terpisah dari essensinya. Dengan demikian jelaslah bahwa bagi Buber, “pengalaman” dan “ilmu pengetahuan” merupakan dunia di mana Aku dan objek berada dalam keadaan terpisah. Objek dalam dunia pengalaman dan ilmu pengetahuan sama sekali tidak mempunyai peran kecuali sebagai alat eksploitasi belaka.38 “Aku” yang mengeksploitasi objek tidak mempunyai tempat dalam dunia objek. Ia memberi contoh melalui tingkah laku seorang bayi. Seorang bayi yang tidak memanggil ibunya, baik melalui tangisan maupun kata-kata, dan hanya memandang 37 Martin Buber, EoG, h.45 Shmuel Bergman, Dialogical Philosophy from Kierkergaard to Buber, 1991, State Univ. Press:New York, h.227. 38 BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” acuh-tak-acuk kepada ibunya, tidak akan menyebabkan ibunya datang menghampirinya. Pada saat itu bayi tersebut memperlakukan ibunya sebagai objek, karena itu ia tidak berperan bagi ibunya.39 Secara tegas ia mengatakan bahwa manusia yang hanya melakukan pola hubungan “Aku-Itu” bukanlah manusia.40 Mengapa? Karena hidup melalui pola hubungan seperti itu, dirinya akan terpisahkan dari komunitas dan sekaligus terjauhkan dari hubungan dengan sesama. Ia tidak menyangkal bahwa hubungan “Aku-Itu” juga merupakan “cara berada” bagi manusia. Hubungan “Aku-Itu” penting dalam upaya pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Tanpa pola hubungan “Aku-Itu” seseorang tidak akan dapat hidup. Namun jika hanya melakukan hubungan “Aku-Itu” seseorang kehilangan jati dirinya. Ia hidup terasing dan terpisah dari dunia sekitarnya. Padahal jati dirinya sebagai “ada” (being) hanya dapat diwujudkan bila berada dalam perjumpaan (encounter). Hubungan membentuk suatu komunitas, di mana setiap orang yang hidup di dalamnya bergerak ke arah pengembangan dirinya dan orang lain. Aspek ini yang tidak terdapat dalam hubungan “Aku-Itu”. Buber mengatakan bahwa dalam kehidupan modern, hubungan “Aku-Itu” dibentuk melalui institusi (institutions).41 Institusi menampakkan dunia “Itu” yang penuh dengan objek. Lewat institusi seseorang mengatur segala sesuatu, berkompetisi, mempengaruhi, bernegosiasi, mengajar dan sebagainya. Insitusi menyebabkan orang hidup dalam keterpisahan dengan orang lain. Si A dikategorikan sebagai B dan berada dalam kelompok B, dengan demikian ia akan terpisah dengan si C yang dikategorikan sebagai D dan berada dalam kelompok D. Seringkali situasi seperti itu menekan hidup orang-orang yang ada di 39 Shmuel Bergman, ibid, 1991, h.227. Martin Buber, IT, h, 85. 41 I and Thou, 1970, h.93 40 37 38 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dalamnya. Sementara itu di dalam diri setiap orang selalu ada aspek privat, yaitu kehidupan pribadi yang diisi dengan berbagai perasaan subjektif yang ada di dalam dirinya. Kehidupan institusi, yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam pengelompokkan dengan banyak orang, bisa jadi menekan aspek privat tersebut dan yang ada hanyalah perasaan komunal atau publik. Situasi ini mengakibatkan perasaan subjektif “Aku” yang seharusnya berisi keterbukaan terhadap orang lain, akhirnya mengikuti struktur institusi. Perasaan subjektif yang ada di dalam “Aku” ikut melihat orang lain sebagai objek pengelompokan, pemisahan dan kompetisi. Jika situasi ini menjadi semakin menyesak, seseorang akan menjadi jenuh hidup dalam institusi. Ia membutuhkan untuk keluar dari suasana institusi dan melakukan relaksasi dari suasana pengelompokan, pemisahan dan kompetisi yang tajam. Untuk itu ia akan masuk ke dalam aspek privat yaitu kehidupan pribadi yang ada di dalam dirinya dan mencoba menutup hubungan dengan orang lain sebagai cara untuk meminimalisasi pengaruh institusi. Namun pada saat itu ia justru kehilangan perjumpaan dengan sesama. Buber kemudian melihat bahwa sejarah perkembangan manusia justru menunjukkan peningkatan yang progresif pola hubungan “AkuItu. 42 Akibatnya adalah manusia modern kehilangan perjumpaan dengan sesama. Sesama justru dipandang sebagai “objek” kepentinganku. “Aku” menjadi terasing dari sesama, karena sesama hanyalah sekedar objekku belaka, bukan subjek yang berdiri setara denganku. Manusia modern hidup dari satu keterasingan ke keterasingan lainnya. Bahkan dalam hubungan dengan Tuhan pun manusia mengalami hal demikian. Tuhan hanya menjadi objek pemikiran manusia sehingga mengalami Tuhan hanya dipahami sebagai idea saja. Makna hidup seperti apa yang dapat didapat manusia dalam situasi seperti itu? Buber mengatakan ini untuk menanggapi konsep Hermann Cohen tentang 42 I and Thou, 1970, h.87. BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” Tuhan sebagai idea.43 Cohen mengatakan bahwa Tuhan adalah idea, bahkan pusat segala idea, termasuk idea kebenaran. Tuhan adalah ide yang utama. Ide Tuhan berada dalam struktur pikiran manusia. Sebagai ide, Tuhan tidak mempunyai realitas dalam dunia. Tuhan juga tidak mempunyai eksistensi, sebagaimana ide tidak mempunyai eksistensi. Menurutnya seseorang mungkin saja mencintai Tuhan sebagai ide. Cohen mengatakan pemahaman bahwa Tuhan merupakan idea adalah religiusitas yang benar. Menurut Buber pemahaman ini mempunyai konsekwensi bahwa dualitas antara Tuhan dengan manusia menjadi tidak ada. Tuhan identik dengan pikiran manusia, padahal pikiran manusia merupakan bagian dari diri manusia itu sendiri. Berpikir tentang Tuhan tidaklah sama dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian menurutnya dengan pemahaman seperti itu, maka manusia dengan Tuhan berada pada pola hubungan “Aku-Itu”, yang tidak memungkinkan terjadinya perjumpaan antara Tuhan dengan manusia. Baginya Tuhan adalah pribadi yang menjumpai manusia dan Tuhan bukanlah objek dalam pola hubungan “Aku-Itu”. Tuhan adalah pribadi, bukan ide belaka yang ada dalam pemikiran manusia. Cinta manusia kepada Tuhan bukanlah cinta kepada idea, melainkan cinta kepada satu Pribadi. 3.2. Hubungan Aku-Engkau Kemudian Buber juga mengemukakan adanya pola hubungan kedua yang juga dilakukan manusia, yaitu hubungan “Aku-Engkau”. Menurutnya hubungan ini merupakan hubungan timbal balik. Hanya “Engkau” yang dapat membalas apa yang aku sampaikan dan hanya “Engkau” yang dapat memberi kepadaku masukkan sehingga aku bisa mengembangkan diri. Ia mengatakan bahwa hubungan “AkuEngkau” merupakan peningkatan progresif dari hubungan “Aku-Itu”. 43 Martin Buber, EoG, h.54. 39 40 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama Pengembangan progresif merupakan tanda adanya “kehidupan roh” (progressive development of the life of the spirit). 44 Pengembangan itu harus terjadi terus menerus di dalam diri manusia. Menurut Buber, roh yang memanifestasi dalam diri manusia adalah roh untuk membina hubungan perjumpaan dengan orang lain. Roh memanifestasi dalam sambutan “Aku” terhadap “Engkau . Bagi Buber kehidupan roh tidak terdapat di dalam “Aku”, melainkan berada di dalam perjumpaan antara “Aku” dengan “Engkau”. Kehidupan roh ada di “ruang antara” (in between) “Aku” dan “Engkau”. Dengan demikian Buber hendak mengatakan “Aku” bisa berada dalam kehidupan roh, jika “Aku” dapat menanggapi perjumpaan dengan “Engkau” sebagai subjek yang setara dan membangun “Aku”. Hubungan “Aku-Engkau” seperti udara yang diperlukan agar manusia dapat bernafas dan hidup. “Roh tidak ada di dalam aku tetapi antara Aku dan Engkau. Roh tersebut tidaklah seperti darah yang mengalir di dalam tubuhmu, tetapi seperti udara yang kamu hirup. Manusia hidup di dalam roh ketika ia mampu menanggapi Engkau…”45 “Ruang antara” (in between, das Zwischen) merupakan ruang yang tercipta dalam hubungan “Aku-Engkau”. “Ruang antara” menjadi pusat dimana “ada” (being) menjadi “ada yang disadari” (being is being realized). “Aku” yang berada di “ruang antara”, menjadi sadar akan diriku sendiri, sekaligus sadar akan keberadaan orang lain. “Ada-ku” dan 44 Martin Buber, I T, h.88. Robert E. Wood mengatakan bahwa istilah “perkembangan progresif kehidupan roh” yang dipakai Buber, merupakan pengaruh pemikiran Hegel. Namun Buber memberikan pengertian yang lain dengan menempatkan istilah itu dalam hubungan antar manusia, yaitu “Aku-Engkau”. (Lih. Robert E. Wood, op.cit, h.73) 45 “spirit is not in the I but between I and You. It is not like the blood that circulates in you but like the air in which you breathe. Man lives in the spirit when he is able to respond to his You.” (Martin Buber, I T, h. 89) BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” “Ada-orang lain” menjadi disadari. Adanya “ruang antara” membuka kemungkinan Aku berjumpa dengan Engkau. Perjumpaan tersebut tidak berada di dalam diri subjek, tetapi berada dalam “ruang antara” tersebut. “Ruang antara” menyebabkan Aku dan Engkau “terpisah” untuk berhadapan muka sebagai yang setara, namun sekaligus ada jarak yang sama menyatukan “Aku” dan “Engkau”. Buber ingin menunjukkan bahwa, baik Aku maupun Engkau mempunyai subjektivitas masing-masing. Lewat “ruang antara” tersebut keduanya menjadi sadar akan subjektivitas dirinya sendiri, sekaligus sadar akan subjektivitas orang lain. Dan dalam “ruang antara” itu pula kedua subjektivitas tersebut dibangun dan dikembangkan. Lebih lanjut Buber mengatakan bahwa bahasa merupakan simbol sederhana bagaimana hubungan tersebut dapat dijalankan. Dalam berbahasa manusia saling menanggapi. Ada hubungan yang jelas ketika manusia berbahasa. Namun menurutnya isi bahasa sendiri tidak membuktikan apa-apa. Mengapa? Bisa saja terjadi seseorang mengucapkan kalimat yang mencerminkan hubungan “Aku-Itu”, padahal yang dimaksudkannya bukanlah hubungan tersebut. Demikian juga sebaliknya. Hubungan “Aku-Engkau” membentuk kehidupan komunitas. Setiap orang membutuhkan tempat berpijak untuk hidup dalam hubungan timbal balik yang setara. Komunitas memberi kesempatan kepada manusia untuk berdialog dan membina hubungan. Inilah komunitas otentik yang dibangun di atas dasar hubungan timbal balik antar manusia. Dalam komunitas muncul manusia-manusia yang terbuka satu sama lain. Menurut Buber, komunitas dibangun berdasarkan dua hal, pertama hubungan timbal balik yang dijalankan di atas dasar satu “pusat kehidupan”. Artinya semua orang yang berada dalam komunitas tersebut terikat pada satu pusat kehidupan, yaitu dialog dalam 41 42 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama kebebasan.46 Komunitas yang otentik tidak mungkin dibangun tanpa dialog di antara setiap orang yang terlibat di dalamnya dengan penuh kebebasan. Dalam dialog tersebut hubungan timbal balik dijalankan. Yang kedua, komunitas dibangun berdasarkan hubungan timbal balik Dialog menyediakan dasar agar aspek kedua dapat di jalankan. Adanya hubungan timbal balik mengikatkan satu orang dengan yang lainnya. Buber kemudian mengambil contoh bagaimana hubungan “Aku-Engkau” dapat dibangun dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan komunitas. Contoh yang diambilnya berkaitan dengan komunitas masyarakat modern. Ia mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat modern ada dua aspek yang sangat menonjol yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi mengedepankan barang kebuTuhan dan pelayanan, sedangkan politik mengedepankan masalah opini dan aspirasi. Bagi Buber komunitas masyarakat modern dengan aspek ekonomi dan politik dapat menjadi komunitas dengan pola hubungan “Aku-Engkau”. Hal ini tergantung pada cara bagaimana mereka memandang manusia lainnya, dengan siapa mereka membuat kesepakatan-kesepakatan. Jika dalam kehidupan ekonomi, “rumus” yang dipakai adalah “Engkau + Engkau + Engkau = Itu” , maka dunia ekonomi adalah dunia ‘Itu”. Keadaan yang dihasilkan adalah keadaan di mana “Aku” mengobjekkan orang lain dan hanya menjadikannya alat pemuas kepentinganku. Demikian juga dengan dunia politik. Namun bila dalam kehidupan ekonomi “rumus” yang dipakai adalah “Engkau + Engkau + Engkau = Engkau”, maka dunia ekonomi menjadi komunitas di mana pola hubungan “Aku-Engkau” dipakai. Bahwa kita menjalankan pola hubungan “Aku-Engkau” dalam dunia ekonomi dan politik bukan berarti menghilangkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau keinginan untuk berkuasa. Keinginan-keinginan itu merupakan hal yang alamiah. Namun keinginan-keinginan itu 46 Martin Buber , I T, h.94. BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” harus didasarkan pada hubungan “Aku-Engkau”. Baginya, struktur kehidupan komunitas muncul dari daya hubungan “Aku-Engkau”, yang menyatukan segenap anggota komunitas. Lewat hal tersebut ada “Aku” menerima kehadiran orang lain sebagaimana dirinya ada. Ketika manusia terjatuh pada pola “Aku-Itu”, maka ia harus bisa kembali mempunyai kemampuan untuk menghadirkan hubungan “Aku-Engkau”. Manusia harus kembali mampu untuk berkata : “Engkau. Dalam Engkaulah Aku memperoleh kepenuhanku”. Lalu apakah dengan demikian Buber memaksudkan bahwa Aku dan Engkau merupakan dua hal yang lebur menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan? Nampaknya tidak demikian. Ia tetap mengakui bahwa dalam hubungan “Aku-Engkau” dualitas di antara Aku dan Engkau tetap terjaga. Aku dan Engkau tidaklah lebur menjadi satu. Mengapa? Ketika keduanya lebur menjadi satu, bagaimana perkembangan “Aku” yang objektif dalam perjumpaan itu dapat ditengarai? Subjektivitas baik “Aku” maupun “Engkau” tetap terjaga ketika pola hubungan itu dijalankan. Terjaganya subjektivitas tersebut memungkinkan “Aku” dan “Engkau” berkembang bersama. 3.2.1. Cinta dalam Hubungan “Aku-Engkau” Cinta merupakan aspek dalam hubungan “Aku-Engkau” yang memungkinkan seseorang bertanggung jawab kepada yang lainnya. Menurut Buber Aku dalam pola hubungan “Aku-Engkau”, adalah Aku yang mampu mencintai. Cinta merupakan bentuk tanggung jawab “Aku” terhadap “Engkau”, yang tidak terdapat dalam pola hubungan “Aku-Itu”.47 Cinta merupakan pengarahan “Aku” kepada “Engkau”. Lewat cinta seseorang dimampukan untuk hidup dalam keterlibatan yang utuh dengan sesamanya. Tidak ada pemisahan, pengategorian atau pengotakan. Dalam cinta “Aku” menghilangkan kecenderungkan 47 Martin Buber, I T, h.66. 43 44 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama pengotakan sesama dalam kategori seperti pintar, kaya, miskin, bodoh dan sebagainya. “Aku” menerima “Engkau” dengan utuh sebagaimana “Engkau” ada dan “Aku” ikut mengambil bagian di dalam diri ‘Engkau. “Aku” tidak menerima “Engkau” dengan berbagai syarat, seperti “Engkau” harus sesuai dengan keinginanku atau “Engkau” harus bisa menjadi pemuas keinginanku. Lewat cinta, Aku menerima dengan utuh keberadaan orang lain. Contoh paling nyata menurutnya ada dalam perkawinan. Dua orang yang berbeda justru meneguhkan diri bersama-sama. Menurut Buber, cinta memungkinkan hal itu terjadi karena di dalam cinta ada pengakuan akan kesetaraan. Aku yang mencintai Engkau, adalah Aku yang memperlakukan Engkau setara. Dan dalam kesetaraan itulah, “Aku” mewujudkan tanggung jawab. “ Cinta adalah tanggung jawab Aku terhadap Engkau : dalam cinta terkandung apa-apa yang tidak terdapat dalam perasaan, yaitu kesetaraan di antara semua yang mencintai….” 48 Dengan demikian secara jelas Buber mengatakan bahwa pengakuan bahwa Engkau setara dengan Aku muncul dari cinta yang ada di dalam diriku. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa cinta bukanlah perasaan subjektif. Perasaan ada di dalam Aku, sedangkan Aku ada di dalam cinta. Hal ini untuk membedakan dengan apa yang ada di dalam Aku dalam hubungan “Aku-Itu”. Dalam hubungan “Aku-Itu” seperti telah disebutkan, aspek yang terdapat dalam “Aku” adalah perasaan. “Aku” yang senantiasa melarikan diri untuk masuk ke dalam diriku sendiri karena jenuh dengan dunia “institusi”, yaitu dunia “Itu” dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam hubungan “Aku-Engkau”, yang ada di dalam “Aku” adalah cinta. Cinta yang mengalir “keluar” 48 “Love is responsibility of an I for a You: in this consists what cannot consist in any feeling – the equality of all lovers…”(Martin Buber, I T, h.66.) BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” untuk berjumpa dengan orang lain. Di sinilah letak perbedaan antara cinta dengan perasaan. Cinta mengalir keluar ke arah orang lain, sedangkan perasaan mengalir ke dalam ke arah diri sendiri. 3.2.2. Kebebasan dalam Hubungan “Aku-Engkau” Buber kemudian menunjukkan bahwa hubungan “Aku-Engkau” mempunyai aspek kebebasan. Hal ini berbeda dengan hubungan “Aku-Itu”. Menurutnya hubungan “Aku-Itu” menunjukkan hubungan kausalitas tanpa batas. Artinya “Aku” memperlakukan “Itu” disebabkan karena keinginanku atau kepentinganku. Aku mengobjekkan Itu, karena keinginanku atau kepentinganku. Tidak ada kebebasan di dalamnya. Namun dalam hubungan “Aku-Engkau” yang menentukan adalah keputusan bebas dalam hubungan timbal balik. “Aku” mengadakan perjumpaan dengan “Engkau”, bukan karena Engkau telah melakukan sesuatu terhadapku, namun “Aku” menanggapi “Engkau” berdasarkan atas keputusan bebasku untuk mengadakan hubungan dengan “Engkau”. “Aku” menjalankan hubungan dengan “Engkau”, juga bukan karena keinginan atau kepentinganku belaka. Jadi “Aku” dalam pola hubungan “Aku-Engkau” bukanlah “Aku” yang dikendalikan oleh keinginan dan kepentinganku sehingga memperalat orang lain. Dengan demikian kebebasan menjadi syarat untuk hubungan timbal balik itu. Menurut Buber pemahaman mengenai kausalitas dapat membawa manusia pada pemahaman mengenai nasib. Namun nasib bukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Nasib dapat diubah dengan mengaktualisasikan kebebasan. Dalam kaitan dengan kebebasan, Buber menyebutkan bahwa manusia bebas adalah seseorang yang berkehendak tanpa selalu berubah pikiran dengan tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas. Ia percaya pada suatu kondisi aktual, yaitu hubungan yang nyata dari dualitas yang real, “Aku” dan “Engkau”. Kondisi aktual ini diaktualisasikan dalam 45 46 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama perbuatan “Aku”. “Aku” yang berada dalam kebebasan adalah “Aku” yang mempunyai alasan kuat dalam melakukan sesuatu dan alasan tersebut menyebabkan “Aku” tidak mudah berubah. Menurutnya hal ini penting dilakukan agar dalam hubungan “Aku-Engkau” seseorang tidak mudah berubah. Hal ini berbeda dengan seseorang yang selalu berubah pikiran dengan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Ia tidak percaya pada kondisi aktual “Aku” dan “Engkau” dan ia tidak berada dalam realitas. Ketika ia menyebut “Engkau”, maka yang ia maksud bukanlah “Engkau” sebagai sesama dalam perjumpaan, melainkan alat belaka, alat yang digunakan oleh “Aku”. 3.2.3. Tiga Bidang Kehidupan dalam Hubungan “Aku-Engkau” Lebih lanjut, Buber kemudian menggambarkan bahwa hubungan “Aku-Engkau” dapat dilakukan dalam tiga bidang kehidupan, yaitu hidup dengan alam, hidup dengan sesama dan hidup dengan “berbagai yang ada yang (bersifat) rohani” (spiritual beings).49 Dalam bidang yang pertama, hidup dengan alam, Buber memberi contoh mengenai pohon. Manusia dapat menjadikan pohon sebagai “Itu”. Ketika seorang ahli biologi memperlakukan pohon, ia memperlakukannya sebagai objek dengan mengkategorikan, memilah-milah dan membaginya dalam unsur-unsur kimia tertentu. Namun dapat terjadi bahwa “Aku” masuk ke dalam perenungan akan pohon tersebut dalam sebuah perjumpaan. Artinya “Aku” membiarkan pohon itu “berbicara” dan ada sebagaimana dirinya ada sehingga terjadi “dialog” dengan “Aku”. Aku membiarkan pohon menjadi ‘Engkau” dan menjadikannya sebagai subjek yang setara dengan Aku. Aku memandang pohon bukan lagi semata-mata untuk kepentinganku. Aku memandang dan membiarkan pohon itu menjadi “dirinya sendiri”. Buber mengatakan : 49 I and Thou, 1970 h. 56-57. BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” “Dapat terjadi, jika kehendak dan rasa hormat bersatu, begitu aku merenungkan pohon, maka aku masuk ke dalam hubungan (Aku-Engkau) dan pohon berhenti menjadi “Itu”.50 Namun demikian, apakah pohon kemudian mempunyai kesadaran sama seperti “Aku”? Ia mengatakan dengan jujur bahwa ia tidak mengetahuinya. Dengan membiarkan pohon ada sebagaimana dirinya, manusia menempatkan pohon sebagai subjek yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian pohon dan lingkungan alam secara luas bukan hanya menjadi bagian dari masa lalu yang dapat diperlakukan sekehendak subjek, tetapi merupakan bagian dari masa kini dan masa depan kehidupan seseorang. Ketika memberikan contoh mengenai perjumpaan dengan kucing, Buber mengatakan bahwa kucing itu dapat bertanya demikian : “Dapatkah terjadi bahwa engkau menjadi alat bagiku? Apakah engkau sungguh-sungguh tidak menginginkan aku mengecohmu? Apakah aku menaruh perhatian kepadamu? Apakah aku ada untukmu? Apakah aku ada seperti itu? Apa yang datang darimu?…”51 Kucing memang tidak mungkin bertanya demikian. Namun untuk menjalankan hubungan yang setara antara “Aku” dengan “Engkau”, “Aku” yang harus mencoba bertanya seperti itu. Dengan demikian “Aku” mencoba untuk membiarkan kucing untuk 50 “But it can also happen, if will and grace are joined, that as I contemplate the tree I am drawn into relation, and the tree ceases to be an It” ( I and Thou,1970, h.58.) 51 “can it be that you mean me? Do you actually want that I should not merely do trick for you?Do I concern you? Am I there for you? Am I there? What is that coming from you?….” (I and Thou, 1970, h.145.) 47 48 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama “berbicara” kepadaku. Aku tidak menjadikannya sebagai masa lampau yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun aku mulai mempertanyakan hubunganku dengan lingkungan alam dalam kekinian dan jangkauan masa depan. Dalam bagian ini Buber mengemukakan satu hal penting yaitu bahwa Aku memasuki hubungan “Aku-Engkau” karena “kehendak” dan “anugerah” bersatu. Kehendak menunjuk pada sikap aktif Aku yang mengarahkan diri kepada Engkau. Aku datang menghampiri dan berjumpa dengan Engkau. Ia secara tegas mengatakan bahwa kehendak yang ada di dalam diri manusia, bukanlah kehendak untuk berkuasa, sebagaimana dikatakan oleh Nietzsche, melainkan kehendak untuk merealisasikan kehidupan “roh” yaitu kehidupan yang mendorong manusia untuk mengadakan perjumpaan dengan orang lain. Kehidupan mewujud dalam hubungan Aku dengan Engkau.52 Sedangkan “anugerah” menunjuk pada adanya Engkau yang memberikan diri kepada Aku. Ketika Engkau memberikan diri kepada Aku, Aku menjadi pasif dan bersifat menanti dan menerima. Dengan demikian sikap aktif dan pasif bersatu dalam satu tindakan hubungan perjumpaan antara Aku dengan Engkau, di mana Aku menerima dari Engkau dan memberi kepada Engkau.53 Dalam bidang yang kedua, yaitu hidup dengan sesama, Buber mengatakan bahwa ketika Aku berjumpa dengan Engkau, Engkau tidak lagi menjadi “benda” (thing). Memang bisa terjadi bahwa Aku hanya melihat warna rambutnya saja, atau hanya melihat warna matanya saja, namun ketika Aku melakukan hal itu orang tersebut tidak lagi menjadi Engkau, melainkan berubah menjadi “Itu”. 54 Menurutnya hal ini masih merupakan hal yang wajar. Manusia tidak mungkin meninggalkan pengetahuan yang dimilikinya, manakala ia berhadapan 52 Martin Buber, BMM, h.184. Robert E. Wood, op.cit, 1969, h.51. 54 Martin Buber, I T, h.59. 53 BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” dengan orang lain. Pengetahuan mengenai ras atau warna kulit pasti akan menyertainya. Namun yang penting baginya adalah bagaimana Aku tidak terus menerus memperlakukan Engkau sebagai “Itu”. Karena dengan demikian Aku menjadikannya hanya sebagai alat untuk dialami. Bagi Buber sesama, yang kepadanya Aku menyapa Engkau, tidak dapat aku alami. Aku tidak mengalaminya, melainkan Aku melakukan perjumpaan dengannya. Dalam perjumpaan itu “Aku” tidak lagi menjadikan”Engkau” sebagai alat. “Mengalami” berarti Aku berjauhan dari Engkau. 55 Dalam bidang yang ketiga, yaitu hidup bersama dengan “yang ada yang bersifat rohani”56, Buber mengatakan bahwa manusia bersifat terbuka terhadap dimensi rohani. Yang dimaksud dengan “yang ada yang (bersifat) rohani” adalah bentuk-bentuk yang bersifat nonmaterial seperti cinta dan seni. Walaupun bersifat non-material, tetap membutuhkan perwujudan dalam bentuk material. Buber memberikan contoh dalam bidang seni, bukan dalam bidang rohani dalam arti religius-keagamaan. Baginya seni menunjukkan suatu sifat timbal balik, seperti yang diandaikan di dalam pola hubungan “Aku-Engkau”. Dalam seni, yang dibutuhkan adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan seluruh keberadaan dirinya. Ketika ia menjalankan hal itu dan berdialog dengan dirinya sendiri, maka akan muncul kekuatan kreatif yang menghasilkan karya seni. Kekuatan kreatif dihasilkan oleh aspek rohani yang ada di dalam diri seseorang, manakala dirinya “berdialog” dengan dirinya sendiri untuk menghasilkan suatu karya 55 Buber dengan tegas mengatakan, “experience is remoteness from You’. (Lih. Martin Buber, I T, h. 60) 56 “yang ada yang (bersifat) rohani” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Walter Kaufmann menjadi “spiritual beings” terjemahan yang sama juga dipakai oleh Ronald Gregor Smith. Terjemahan ini berasal dari tulisan Buber dalam bahasa Jerman geistige Wesenheiten. Robert E. Wood mengusulkan dari pada memakai terjemahan spiritual beings yang cenderung membingungkan, lebih baik dipakai forms of the spirit. Istilah itu lebih menunjuk pada aspek-aspek non-material (bersifat rohani) seperti cinta dan seni. (Lih. Robert E. Wood, op.cit, h. 43). 49 50 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama seni. Ia mengatakan bahwa manusia mempunyai aspek rohani, sehingga memungkinkan Aku berdialog dengan diriku sendiri. Lewat pemahaman ini Buber memasuki pemikiran psikologis tentang diri manusia. 57 Baginya manusia memang bisa “mengalami” sesuatu yang bersifat rohani, yang terdapat di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian ia berada dalam dunia “Itu”, karena aspek mengalami ada dalam dunia “Itu”. Seseorang mampu “mengalami” (yaitu berada dalam pola hubungan “Aku-Itu”) hal yang bersifat rohani, maka ia pun diharapkan mampu untuk menyapa aspek spiritual itu dengan sebutan “Engkau” (yaitu berada dalam pola hubungan “Aku-Engkau”). Ia menjadikan yang rohani itu sebagai “Engkau”. Dengan pemahaman ini Buber menunjukkan bahwa setiap “Itu” dapat berubah menjadi “Engkau” dan sebaliknya. Lewat contoh dalam bidang seni, Buber kemudian mengatakan bahwa aspek spiritual dalam kehidupan religius-keagamaan pun tidak jauh berbeda.. Aspek rohani itu sudah ada di dalam diri seseorang. Ia kemudian menegaskan adanya “Ada yang bersifat rohani” (spiritual Being), yang berada di luar seseorang. Namun “Ada yang bersifat rohani” yang di luar seseorang itu, justru akan meneguhkan aspek rohani yang telah ada di dalam dirinya. Jika seseorang bisa mengalami aspek rohani yang ada di dalam dirinya sendiri, maka ia pasti bisa mengalami aspek rohani yang berada di luar dirinya Bagi Buber siapapun yang menjalankan hubungan “Aku-Engkau”, ia berada dalam aktualitas atau realitas. Atau dengan kata lain aktualitas diri ditunjukkan melalui hubungan “Aku-Engkau”. Semakin sempurna Aku berpartisipasi, semakin aktual Aku menjadi. Semakin Aku memberikan Engkau ruang gerak, semakin Aku memberikan diriku sendiri ruang gerak. Buber mengatakan : 57 Martin Buber, I T,, h. 60. BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” “Aku memerlukan Engkau untuk menjadi; dalam menjadi Aku, Aku mengatakan Engkau”.58 Dengan demikian menurutnya kepenuhan diri manusia hanya bisa diperoleh ketika dirinya terus menerus merealisasikan diri dalam hubungan “Aku-Engkau. Seseorang menjadi Aku hanya lewat Engkau. Menurut Buber, hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” merupakan pola hubungan yang secara berganti-ganti akan ada di dalam diri manusia. Pada satu sisi, hubungan “Aku-Itu” dapat ditingkatkan menjadi “Aku-Engkau”. Pada saat seseorang mengabdikan hidup sungguh-sungguh demi “Itu” dan membina hubungan timbal balik dengan “Itu”, saat itulah “Itu” berubah menjadi “Engkau”. Namun pada pihak lain, hubungan “Aku-Engkau” justru dapat mengalami degradasi menjadi “Aku-Itu. Tatkala “Engkau” mulai dikategorikan, dianalisis, dikelompokan, dan dijadikan sebagai alat, saat itu hubungan berubah menjadi “Aku-Itu”. 4. Kesimpulan Seseorang senantiasa menjalankan dua hubungan, yaitu “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. Hubungan “Aku-Itu” merupakan hubungan subjek-objek, sedangkan hubungan “Aku-Engkau” merupakan hubungan subjek-subjek. Hal ini sejajar dengan pola pengetahuan yang terdapat di dalam diri manusia, yaitu pola pengetahuan subjek-objek dan pola pengetahuan subjek-subjek. Dalam hubungan “Aku-Itu”, Aku sebagai subjek mengobjekkan yang lain. Aku mengotak-ngotakkan, memisahkan dan menggunakan yang lain sebagai pemuas keinginanku. Aku adalah yang “mengalami” dan “menggunakan”, sedangkan yang lain adalah yang “dialami” dan 58 “I require a You to become; becoming I, I say You”. (Martin Buber, I T, h. 62.) 51 52 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama “digunakan”. Engkau ada sebagai bahan “persediaan” yang dapat aku gunakan sesuai dengan kebuTuhanku. “Aku-Itu” menampakkan pola hubungan yang sepihak. “Aku” sendiri tidak melibatkan diri sepenuhnya dalam hubungan ini. “Aku” melakukan hubungan hanya sejauh “kepentingan” dan “keinginan-ku saja. Untuk itu Aku yang ada dalam hubungan ini memperlihatkan Aku yang egois, dalam kaitan dengan perlakuan terhadap Itu. Hubungan “Aku-Engkau” merupakan hubungan yang dibangun di atas dasar kesetaraan. Syarat-syarat dari hubungan ini menyangkut sikap terhadap orang lain, yaitu memberikan kebebasan, menghargai, menghormati dan kesetaraan. “Aku” menyapa “Engkau” sebagai yang setara dengan “Aku”, sebagai sesama subjek. Hubungan ini memperlihatkan perjumpaan kedua subjek. Perjumpaan itu diliputi oleh suasana dialogis. “Aku” menyapa “Engkau” di dalam kebebasanku. Demikian juga sebaliknya. Dalam hubungan ini, cinta menguasai baik “Aku” maupun “Engkau”. Cinta menyebabkan “Aku” bertanggung-jawab terhadap “Engkau”. Dan dalam tanggung jawab itu “Aku” memberikan diri kepada “Engkau” dan menerima sesuatu dari “Engkau”. Demikian juga sebaliknya. Aspek timbal balik inilah yang akan membentuk identitas. Aku tidak mungkin mendapatkan identitas yang sesungguhnya tanpa “Engkau”. Aktualitas diriku sebagai “ada” (being), hanya bisa dicapai dengan hubungan timbal balik dengan “Engkau”. Karena itu menurut Buber realitas sesungguhnya ada di “ruang antara”, yaitu ruang yang terbentuk melalui hubungan timbal balik. Hubungan “Aku-Itu” tidak menunjuk pada hubungan antara manusia dengan benda. Manakala manusia berhubungan, baik dengan benda, hewan, manusia lainnya atau bahkan dengan Tuhan, kemudian manusia memperalatnya hanya untuk kepentingan diri sendiri maka hubungan yang terjadi adalah “Aku-Itu”. Demikian juga sebaliknya, manakala manusia berhubungan termasuk dengan benda-benda, BAB III Hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” kemudian manusia memperlakukannya dengan hormat sebagai yang setara dengan dirinya, melihatnya sebagai sesama subjek, maka hubungan yang dibangun adalah “Aku-Engkau. Setelah kita membahas pemikiran Buber mengenai hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”, pada bab berikutnya kita akan melihat pemikirannya mengenai Tuhan. Ia mengemukakan pemikirannya tentang Tuhan dengan mendasarkan diri pada aspek-aspek yang terdapat dalam hubungan “Aku-Engkau”. Ia juga mengemukakan pemahamannya mengenai Tuhan dalam kerangka berdialog dengan beberapa pemikir lainnya. 53 BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber Bagi Buber setiap individu merupakan pribadi yang unik. Masingmasing mempunyai cara yang unik pula dalam berhubungan dengan Tuhan. Karena beragamnya cara, maka hasil yang dicapai pun bisa sangat beragam dan belum tentu dapat dimengerti oleh orang lain. Buber mempertanyakan, “Bagaimana caranya setiap individu membawa dirinya untuk dapat berkata tentang ‘Tuhan’ dari waktu ke waktu? Bagaimana caranya kita dapat berharap bahwa orang lain dapat mengerti tentang itu, persis seperti yang kita mengerti?…………”59 Pertanyaan Buber ini terus bergema sampai dengan abad XX. Seorang teolog bernama William Hamilton mengatakan bahwa manusia modern hidup pada jaman “Tuhan yang Mati”. Maksudnya bukan 59 “How can you bring yourself to say “God” time after time? How can you expect that your readers will take the word in the sense in which you wish it to be taken?” (Martin Buber, EoG, h. 7) 55 56 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama untuk mengatakan bahwa Tuhan tiada, melainkan untuk mengatakan bahwa gambaran Tuhan yang dikemukakan pada abad pertengahan, seperti oleh Agustinus atau oleh kaum reformatoris semakin sukar untuk dipahami manusia modern, dan semakin tidak berarti dalam diri manusia modern.60 Untuk itulah dalam diri manusia modern Tuhan menjadi mati. Pernyataan Hamilton seolah menegaskan kembali secara lebih halus atas apa yang pernah diungkapkan Nietzsche bahwa Tuhan (terutama dalam tradisi kekristenan) hanya berada sebagai idea di luar kehendak manusia. Tuhan yang justru membelenggu manusia dan menyebabkan manusia tidak dapat mengembangkan diri. Tuhan seperti itu harus “dimatikan”. Berhadapan dengan pemahaman ini Buber mengatakan bahwa memproklamirkan Tuhan mati hanya merupakan satu petunjuk ketidakmampuan dalam memahami sang “realitas absolut independen” dan sekaligus kegagalan dalam membina hubungan dengan dia.61 Ketidakmampuan dan kegagalan seperti itu tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak ada atau mati malahan seharusnya mendorong seseorang untuk terus menemukan berbagai cara untuk berhubungan dengan Tuhan. Baginya masalahnya bukan pada Tuhan ada atau tidak ada, tetapi apakah manusia merasakan pengalaman berdialog dengan Tuhan. Untuk itu bagi Buber istilah “Tuhan mati” tidaklah tepat. Menurutnya yang lebih tepat adalah “Eclipse of God” (Gerhana Tuhan). Dengan istilah ini ia mau menggambarkan bahwa permasalahan terjadi bukan karena Tuhan tidak ada atau Tuhan mati, melainkan karena adanya hubungan yang tidak tepat antara manusia dengan Tuhan. 60 William Hamilton, The New Essence of Christianity, seperti dikutip Harun Hadiwijono, Teologi Reformatoris Abad XX, 1993, BPK Gunung Mulia:Jakarta, h. 156-157. 61 Martin Buber, EoG, h. 14. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber Bagi Buber setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk mencari jalan bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Menurutnya, cara berhubungan dengan Tuhan harus dilakukan melalui suatu perbuatan yang terus menerus dipelihara oleh manusia. Pemeliharaan itu mengambil tempat dalam perjumpaan antar manusia dan komunitas yang dihasilkannya. Lewat sapaan Aku terhadap Engkau, manusia menemukan Tuhan. Dengan demikian orang lain pun dapat memahami pemahaman kita mengenai Tuhan. Sebab, ketika kita mengemukakan perjumpaan dengan Tuhan, kita mengemukakannya dalam konteks perjumpaan dengan orang lain. Namun pertanyaannya adalah “Tuhan seperti apa yang “dialami” manusia dalam perjumpaannya dengan Engkau?”. Bab ini akan mengemukakan pemikiran Buber mengenai Tuhan. Terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pemikiran modern berkaitan dengan pemahaman tentang Tuhan dan bagaimana Buber menanggapinya, kemudian pemikiran Buber mengenai Tuhan sebagai pribadi dan Tuhan yang berada dalam perjumpaan dengan manusia. 1. Beberapa Pemikiran Modern Tentang Tuhan Kegagalan untuk dapat melihat hubungan antara manusia dengan Tuhan terlihat dalam pemikiran beberapa filosof. Salah satu penyebabnya menurut Buber adalah seringnya Tuhan dilihat hanya objek yang berada dalam pikiran manusia. Atau dengan kata lain Tuhan adalah objek pengetahuan manusia. Manusia tidak secara sungguh-sungguh terlibat secara eksistensial dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sebagai objek pengetahuan, maka Tuhan hanya dipahami sebagai ide. Berikut ini beberapa pemikiran modern tentang Tuhan yang ditanggapi oleh Buber 62: 62 Ada tiga pemikir yang akan dibahas, yaitu Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger dan Carl-Gustav Jung. Buber juga mengulas secara cukup luas beberapa pemikir lainnya seperti Spinoza, Hermann Cohen, dan Immanuel Kant, namun ketiganya telah 57 58 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama 1.1. Jean-Paul Sartre 1.1.1. Pemikiran Jean-Paul Sartre Sartre menyatakan dirinya sebagai seorang ateis. Menurut Sartre, ateisme merupakan konsekuensi logis dari filsafat eksistensialisme. Pemikiran Sartre sangat dipengaruhi pengalaman masa kecilnya, di mana ia dididik oleh kakeknya yang cenderung menertawakan tradisi religius, walaupun Sartre sendiri dibaptis secara katolik. Pengalaman itu ia ungkapkan dalam satu tulisan sinis : “Dididik dalam ajaran Katolik, aku diberitahu bahwa Tuhan yang Maha Esa telah menciptakanku demi kebesaran-Nya. Harapanku tidaklah pernah setinggi itu. Di kemudian hari aku tidak mengenali Tuhan yang serba ‘modis’ itu sebagai yang dinanti-nantikan jiwaku. Kubutuhkan seorang pencipta, tahu-tahu yang ditawarkan seorang Majikan Agung…”63 Pemikiran Sartre tentang Tuhan dipengaruhi oleh pemikirannya tentang diri dan orang lain. Bagi Sartre, kesadaran manusia sebagai “Aku” selalu bersifat “menidak” terhadap yang lain.64 Kesadaran memproyeksikan diri pada lingkungan di sekitarnya dan menegasikan atau menyangkal sesuatu di luar diri sebagai “bukan diri” atau tidak sama dengan diri. Penegasian ini menghasilkan penolakan Aku terhadap orang lain dan sebaliknya. Dengan demikian kesadaran yang “menidak” selalu menimbulkan konflik dalam relasi antar individu. Konflik adalah dibahas dalam skripsi sdr. Kasdin Sihotang dengan judul “Tuhan sebagai Pribadi dalam Hubungannya dengan Manusia menurut Martin Buber: Sebuah Refleksi Teologis”, STF 1993. 63 Jean-Paul Sartre, Kata-kata, 2000, Gramedia:Jakarta, h.129. 64 David West, An Introduction to Continental Philosophy, 1996, Blackwell:Cambridge, h. 140. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber inti setiap relasi. Bagi Sartre orang lain senantiasa ada untuk menjadikan “Aku” sebagai objek. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan adalah “Orang Lain Mutlak” (The Absolute Other). Mengakui adanya Tuhan berarti mengakui “Aku” atau diri sendiri diobjekkan oleh orang lain.65 Dengan demikian subjektivitas manusia akan terampas. Tuhan harus tidak ada supaya subjektivitas manusia dapat muncul dan berkembang. Lalu bagaimana Sartre sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada? Menurut Buber masalah yang mengganggu bagi Sartre dan kaum eksistensialis atheis lainnya adalah pemahaman bahwa Tuhan pada jaman modern telah “diam” (silence). Manusia modern sesungguhnya mempunyai kebuTuhan untuk berhubungan dengan Tuhan. Namun ternyata Tuhan diam. Karena itu Sartre dan kaum eksistensialis lainnya mengatakan bahwa sebaiknya orang melupakan Tuhan dan menghentikan usaha pencarian Tuhan. Tuhan adalah tidak ada. Manusia harus mulai mengenali dirinya sendiri sebagai penyebab yang menyebabkan dunia ini ada. Tidak ada eksistensi lain di dunia ini selain manusia. Dalam pemikiran Sartre, bisa jadi memang Tuhan pernah ada dan berbicara pada manusia di masa silam. Itu adalah Tuhan sebagai “being for Itself ”. Namun begitu manusia menjadikan Tuhan sebagai identitas atau esensi yang mutlak-sempurna, dan dengan demikian berhenti berproses (being in Itself ), maka manusia menjadikan Tuhan diam dan mati. Yang dirasakan manusia jaman modern adalah mayat dari Tuhan. Hal lain yang menyebabkan Sartre mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada adalah pemikirannya mengenai kebebasan manusia untuk menentukan esensinya. Bagi Sartre eksistensi mendahului esensi. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa manusia bebas menentukan esensinya (being for itself ). Individu berada dalam kebebasan mutlak dan bertanggung jawab hanya pada dirinya sendiri. Kebebasan tidak 65 Martin Buber, EoG, h.67. 59 60 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dapat dipisahkan dari realitas diri manusia. Di dalam kebebasannya, manusia menentukan nilai-nilai untuk mengembangkan subjektivitasnya Buber mengutip apa yang dikatakan Sartre demikian : “seorang manusia memerlukan diri untuk menemukan nilai-nilai…hidup tidak punya nilai apriori…terserah pada setiap individu untuk mencari maknanya, dan nilai tidak lebih dari pada makna yang kamu pilih….”66 Identitas atau esensi suatu individu berhenti bila individu tersebut mati. Dengan pemahaman seperti ini, menurut Sartre Tuhan yang disembah manusia seharusnya merupakan pribadi yang bebas mutlak dalam menentukan esensinya (being for Itself ), namun di pihak lain Tuhan juga harus sekaligus merupakan pribadi yang sudah “berhenti” esensinya karena Tuhan pastilah pribadi yang identitasnya sudah sempurna (being in Itself ). Namun pribadi yang sekaligus being for Itself dan being in Itself adalah tidak mungkin. Untuk itu Sartre mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada untuk itu manusia tidak perlu bersusah payah mencari Tuhan. 1.1.2. Tanggapan Martin Buber terhadap Jean-Paul Sartre Secara tegas Buber mengatakan bahwa manusia mendapatkan subjektivitasnya bukan dengan meniadakan Tuhan untuk selanjutnya menciptakan nilai-nilai yang memberi makna dalam hidupnya. Terhadap pemikiran Sartre yang mengatakan bahwa Tuhan adalah “Orang Lain Mutlak” (The Absolute Other) yang menjadikan manusia sebagai objek, karena itu manusia harus melupakan dan menganggap 66 “someone is needed to invent values….Life has no meaning a priori….it is up to you to give it a meaning…and value is nothing else than this meaning which you choose.” (Martin Buber, EoG, h. 70). BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber bahwa Tuhan tidak ada untuk pengembangan subjektivitasnya, Buber mengatakan bahwa Tuhan yang menjadikan manusia sebagai objek bukanlah Tuhan. Tuhan yang berada dalam hubungan dengan manusia adalah Tuhan yang melakukan hubungan timbal balik. Tuhan tidak akan pernah menjadikan manusia sebagai objek dan manusia pun tidak mungkin berhubungan dengan Tuhan, jika menganggap Tuhan hanya sebagai objek. Menurutnya Sartre mempertahankan kondisi hubungan subjek-objek, sehingga wajar kalau ia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Hubungan manusia dengan Tuhan yang dipaparkan Sartre adalah hubungan “Aku-Itu”. Tidak ada Tuhan di dalam hubungan “Aku-Itu”, sehingga wajar jika seseorang tidak berjumpa dengan Tuhan dalam hubungan itu. Kalau pun manusia tidak dapat merasakan Tuhan dan Tuhan “diam” terhadap manusia, maka bagi Buber hal itu tidak terdapat di dalam subjektivitas manusia, melainkan pada “Ada” itu sendiri (Being itself ). Jika memang manusia tidak dapat lagi merasakan dan mendengar suara Tuhan, maka lebih baik bagi dirinya untuk menanggung saja peristiwa tersebut, dari pada mengambil kesimpulan atau mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Setelah itu manusia berusaha bergerak secara eksistensial melampaui peristiwa tersebut sehingga pengalaman baru dapat dijumpainya, yaitu mendengar suara Tuhan dan dengan demikian hubungannya dengan Tuhan terjalin kembali. Buber agaknya tidak menafikan kenyataan adanya kenyataan bahwa Tuhan “diam” bagi manusia modern. Namun hal itu tidaklah berarti bahwa Tuhan tidak ada. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika Sartre mengakui bahwa di dalam diri manusia modern ada kebuTuhan religius, maka Sartre harus menjawab terlebih dahulu apakah kebuTuhan tersebut mengindikasikan adanya “sesuatu” di dalam diri manusia? 61 62 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama 1.2. Martin Heidegger 1.2.1. Pemikiran Martin Heidegger. Menurut Buber, Heidegger mendasarkan pemikirannya mengenai Tuhan pada penolakan segala bentuk pemahaman metafisika. Bagi Heidegger pemikiran metafisika mulai dari Plato sampai Hegel dan Nietzsche mengalami “lupa-akan-Ada”. “Ada” diperlakukan dan dipahami sama sebagai “adaan”. “Ada” dianggap sama seperti manusia, batu, Tuhan dan sebagainya. Untuk memahami “Ada” dengan benar kita harus kembali memperhatikan istilah atau konsep yang digunakan. Heidegger mengemukakan bahwa dalam pemikiran metafisika bahasa yang dipakai adalah bahasa “memperhitungkan”, yaitu dengan mengasalkan suatu adaan kepada adaan lainnya, mengkalkulasikan, mengatur dan memanipulasi. Untuk sampai pada pemikiran mengenai “Ada” kita harus menggunakan pemikiran yang “memperhatikan”, yaitu pemikiran yang memperhatikan perbedaan ontologis. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang melampaui bahasa metafisika. Heidegger kemudian mengatakan bahwa bahasa puisi merupakan bahasa yang bisa melampaui bahasa metafisika dalam pemikirkan tentang “Ada”. Demikian pula dengan tentang Tuhan. Menurut Heidegger Tuhan harus dikemukakan dengan konsep pemikiran yang tepat dan benar. Menjernihkan atau mengklarifikasi kembali pengertian tentang Tuhan merupakan dasar apakah manusia dapat mengalami Tuhan atau tidak. Apabila manusia dengan benar dapat melakukan klarifikasi pengertian tentang Tuhan dan mendapatkan konsep yang benar, maka manusia akan mengalami Tuhan. Pemahaman metafisika selama ini telah mengubur konsep Tuhan. Bagi Heidegger yang memungkinkan manusia mengalami Tuhan adalah apakah manusia mempunyai konsep yang benar mengenai Tuhan atau tidak. Jika manusia tidak mempunyai suatu bahasa yang tepat dalam menunjukkan pengertian yang benar tentang Tuhan, maka Tuhan haruslah dikatakan tidak ada (God is BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber Absent).67 Kata (word) dan Tuhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika manusia tidak dapat menghadirkan atau memunculkan kata yang tepat dan benar mengenai Tuhan, maka Tuhan pun tidak hadir. Dengan mengemukakan secara tepat mengenai sesuatu, maka akan ada keterbukaan dari “Ada”. Heidegger mengatakan seperti dikutip oleh Buber bahwa “para allah hanya dapat mengemuka dalam kata jika mereka sendiri menyapa kita dan menempatkan tuntutannya terhadap kita. Kata-kata yang menunjukkan nama para allah itu selalu merupakan jawaban dari tuntutan itu”68 Heidegger menyangkal kalau disebutkan bahwa pemikirannya sebagai pemikiran ateis. Pemikirannya memang tidak dimaksudkan untuk menyangkal atau mengafirmasi adanya Tuhan. Heidegger ingin menjernihkan konsep tentang Tuhan agar konsep itu membawa seseorang pada pengalaman akan Tuhan. Lalu bagaimana dengan konsep Tuhan menurut Heidegger sendiri? Buber mengatakan bahwa nampaknya Heidegger sendiri kesulitan mengemukakan konsepnya tentang Tuhan. Ia hanya mengemukakan bagaimana kemungkinan mengenai kemunculan (appearance) Tuhan. Tuhan bukanlah “Ada” (Being), dan dari konsep tentang “Ada”-lah muncul Tuhan.69 Senada dengan Buber, Michael Inwood mengatakan bahwa konsep Heidegger tentang Tuhan sangat kabur. Bagi Heidegger Tuhan bukanlah “non-eksistensi” (nonexistent, unseiend), maupun “eksistensi” (existent, seiend). 70 67 Mengutip perkataan Heidegger, Buber mengatakan, “This is the age in which God is Absent; the Word and God are absent together” (Martin Buber, EoG, h. 72). 68 “The gods can only enter the Word if they themselves address us and place their demand upon us. The Word that names the gods is always an answer to this demand” (Martin Buber, EoG, h. 76). 69 “Being-that is not God and it is not ground of the world….be it, an angel or God” (Martin Buber, EoG, h.74). 70 Martin Inwood, Heidegger Dictionary, 2000, Blackwell:UK, h.82. 63 64 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama 1.2.2. Tanggapan Martin Buber terhadap Heidegger Buber melihat bahwa ada sesuatu yang kosong dan tak teratasi ketika Heidegger mengatakan bahwa di dalam “konsep” terkandung seluruh fakta inheren dari “eksistensinya”. Artinya sebelum konsep itu terwujud dan dapat dibahasakan dengan benar, ketuhanan merupakan sesuatu yang bersifat kosong. Ada bidang yang tidak terjembatani di antara konsep yang benar dengan pengalaman akan Tuhan itu sendiri. Bagi Buber aspek “ketuhanan” (Godhead), mendahului (prior) segala konsep yang dapat dibuat manusia mengenai aspek ketuhanan itu. Demikian juga dengan pengalaman akan aspek ketuhanan tersebut. Justru konsep yang dibentuk manusia lewat bahasa berasal dari pengalaman seseorang akan adanya aspek keTuhanan. Bagi Buber tiadanya konsep atau bahasa yang mengatasi bahasa metafisika tidaklah menghilangkan pengalaman akan Tuhan. Namun Buber melihat sisi positif pemikiran Heidegger bahwa ia mengajak manusia modern untuk memikirkan kembali konsep mengenai Tuhan. Dengan pemikiran seperti itu masih ada kemungkinan Tuhan “bangkit” dari “kematian-Nya”. Pemikirannya menyisakan kemungkinan bahwa pengalaman akan Tuhan bukan sesuatu yang mustahil untuk dapat dirasakan kembali oleh seseorang pada jaman modern, walaupun bentuk dan jenis hubungan itu mungkin akan berbeda dengan apa yang dipahami selama ini. Buber dengan tegas mengatakan bahwa pada titik inilah Tuhan “membuka” diri kepada manusia sehingga secara terus menerus seseorang dapat memperbaiki konsepnya mengenai Dia. Tuhan memerlukan manusia, yang secara mandiri menjadi rekan Tuhan di dalam dialog. Buber mengambil contoh sejarah pengalaman Israel, yaitu bagaimana Tuhan membuka diri terus menerus kepada Israel sehingga Israel mempunyai konsep tentang Tuhan yang kuat dan terjalin dalam pengalaman mereka. Israel di hadapan Tuhan adalah rekan dialog yang berdiri secara mandiri. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber 1.3. Carl-Gustav Jung 1.3.1. Pemikiran Jung tentang Tuhan. Jung melihat bahwa Tuhan hanyalah merupakah fenomen psikologis seseorang. Ia mendefinisikan Tuhan sebagai “muatan psikis yang bersifat otonom” (autonomous psychic content).71 Dengan mendefinisikan Tuhan seperti itu maka menurutnya Tuhan tidaklah dipahami sebagai “Ada” atau “Realitas” yang terhadapnya aspek psikis seseorang menjalin hubungan. Tuhan adalah bagian dari kondisi psikis seseorang. Tuhan berada pada wilayah ketidaksadaran seseorang. Tuhan merupakan bagian integral dari diri manusia itu sendiri. Baginya pernyataan-pernyataan metafisis merupakan ekspresi jiwa dan konsekwensinya adalah pernyataan itu bersifat psikologis. Demikian juga dengan pernyataan metafisis mengenai Tuhan merupakan ekspresi jiwa sehingga pernyataan itu harus dilihat bersifat psikologis. Memang Jung mengemukakan pemahamannya ini dengan maksud untuk menolak pemahaman ortodoks yang mengatakan bahwa Tuhan “Ada untuk dirinya sendiri”. Dengan mengatakan bahwa Tuhan “Ada untuk diri-Nya sendiri”, maka Tuhan merupakan subyek yang berada di luar diri seseorang. Baginya jika seseorang mengatakan seperti itu maka ia tidak sadar pada fakta bahwa tindakan penyembahan kepada Tuhan dan obyek penyembahan itu sendiri (Tuhan) sebenarnya muncul dari kedalaman dirinya sendiri. Jika Tuhan memang “Ada untuk diri-Nya sendiri” dan jika yang berhubungan dengan-Nya adalah sisi kerohanian atau kejiwaan seseorang, maka Tuhan seharusnya sama seperti manusia sehingga ada hubungan yang setara. Bagi Jung hal ini tidaklah mungkin, karena Tuhan mestilah tidak sama seperti manusia. Satu-satunya yang mungkin adalah bahwa Tuhan merupakan fenomen psikis seseorang. Bagian dari “sisi gelap” (dark side) kejiwaan seseorang. Yang dimaksudkan “sisi gelap” olehnya adalah bagian dari diri seseorang yang paling dalam dan tidak disadari. 71 Martin Buber, Eclipse of God, 1971, h. 80. 65 66 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama Dengan demikian bagi Jung Tuhan merupakan proyeksi dari sisi psikis ketidaksadaran seseorang. Dalam konsep pemikiran psikologis Jung, alam ketidaksadaran manusia mengandung khayalan ideal sebagai pengalihan dari hambatan atau ketidakmampuan diri. Sedangkan alam sadar, yaitu “diri” (person, self ) akan menuntut penyesuaian-penyesuaian dengan kemampuan seseorang dan keadaan lingkungan sosial. Apa yang ideal pada alam bawah sadar pada akhirnya berbenturan dengan kesadaran akan keterbatasan pada alam sadar. Tuhan merupakan “bayangan” ideal alam ketidaksadaran seseorang, namun orang tersebut tidak menyadarinya. Apa yang dikatakan oleh Jung mirip dengan pemikiran Feuerbach. Feuerbach mengatakan bahwa Tuhan merupakan proyeksi ideal manusia belaka. Agama sebagai wadah yang memuat hubungan dengan muatan psikis seseorang yang bersifat otonom , berada di daerah “pedalaman” (hinterland) kejiwaan seseorang. Agama bukanlah wadah yang memuat hubungan seseorang dengan aspek Ilahi yang berada di luar dirinya sendiri. Agama hanya merupakan suatu peristiwa kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang, yang kemudian keluar membentuk diri dalam lingkungan sosial tertentu. Agama adalah fenomena sosial sebagai hasil dari peristiwa kejiwaan yang dialami bersama-sama dalam komunitas tertentu. Namun Jung sendiri tidak menolak keberadaan agama. Agama diperlukan untuk memelihara dan menjalankan proses “individuasi” (individuation). Proses individuasi dilakukan untuk memulihkan kondisi psikis seseorang dari kesibukan (bustle) hidup sehari-hari dan mengarahkan seseorang pada perkembangan personalitas yang utuh.72 Agama mengajak seseorang melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. “Diri” (person, self ) hanya mungkin melepaskan diri dari khayalan ideal bila ia melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Proses ini dilakukan di dalam kesadaran. 72 Martin Buber, EoG, h.84. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber Lewat proses ini pula seseorang “memasukkan” kembali muatan psikisnya, yaitu Tuhan yang berada dalam ketidaksadaran, ke dalam dirinya sendiri untuk kemudian muncul dalam kesadaran. “Muatan psikis” itu, yaitu Tuhan, “bersatu” kembali dengan diri dan membentuk diri. Lewat agama seseorang menjadikan dunia sebagai bagian dari dirinya untuk perkembangan “diri” yang utuh. Lewat proses itu ia mulai mengatur, mengategorikan dan memilah-milah setiap aspek yang ada di dalam dunia sesuai dengan kepercayaan agamanya. Agama apapun, baik Kristen, Islam, Hindu atau Budha, mempunyai nilai-nilai religius yang penting untuk kesehatan psikis seseorang, tetapi bukan mengenai pemahaman akan Tuhan. 1.3.2. Tanggapan Martin Buber terhadap Pemikiran Jung Buber mengatakan bahwa pemikiran Jung bahwa Tuhan merupakan bagian dari kondisi psikis seseorang boleh jadi merupakan sisi dari diri seseorang yang dapat ketahui. Namun ia mempertanyakan bukankah masih sangat banyak sisi lain yang tidak dapat diketahui, yang tidak bisa begitu saja diintegrasikan dengan apa yang sudah diketahui. Baginya suatu “jiwa atau psikis” yang secara individu bersifat real atau nyata, pastilah bukan merupakan pemikiran metafisis belaka.73 “Jiwa” itu mestilah merupakan individu yang real dan mempunyai kehidupan esensial sendiri. Bagi Buber bukanlah tugas seorang ahli psikologis untuk menentukan apa yang real dan apa yang tidak berkenaan dengan sesuatu yang jauh melebihi manusia.74 Terlalu dini bagi Jung untuk bisa mengatakan Tuhan tidak real dan Tuhan hanya merupakan muatan psikis seseorang belaka berdasarkan kondisi ketidaksadaran yang belum dapat dipahami seluruhnya. Demikian juga dengan dirinya. Ia tidak hendak membantah Jung untuk kemudian membuktikan bahwa Tuhan 73 Martin Buber, EoG, h.82. Martin Buber, EoG, h. 134. 74 67 68 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama itu ada. Ia hanya ingin mengemukakan bahwa jika Tuhan dipahami berada dalam alam ketidaksadaran manusia dan seorang ahli psikologi sekalipun tidak akan dapat memahaminya dengan sempurna sehingga ada jurang yang sangat dalam dengan alam ketidaksadaran itu, maka betapa luasnya alam ketidaksadaran itu. Padahal Tuhan bukanlah alam ketidaksadaran itu, melainkan pencipta alam ketidaksadaran itu. Lebih lanjut Buber kemudian kembali menggunakan pemikirannya mengenai hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. untuk menanggapi Jung, khususnya pemikirannya mengenai agama. Buber mengatakan, jika Jung memahami agama penting untuk proses individuasi, maka hubungan yang terjadi dalam agama, termasuk dengan “Tuhan”, bukanlah hubungan “Aku-Engkau”. Dalam hubungan seperti yang dipahami Jung yang terjalin adalah hubungan “Aku-Itu”. Mengapa Buber menanggapi seperti itu? Karena dalam pemikiran Jung, lewat agama seseorang menjadikan dunia sebagai bagian dari dirinya dan membuat pengategorian dan pemilahan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, termasuk Tuhan dan orang lain. Dalam kaca matanya menjadikan dunia sebagai bagian dari dirinya, berarti menjadikan dunia sebagai objek bagi dirinya sendiri. Hal ini sudah cukup untuk menilai bahwa hubungan itu merupakan hubungan “Aku-Itu”. 2. Tuhan sebagai Pribadi Siapakah Tuhan dalam pemahaman Buber? Tuhan adalah Dia yang memasuki hubungan langsung dengan manusia. Tuhan seperti itu mestilah seorang Pribadi.75 Sebagai Pribadi Tuhan berada dalam 75 Pedro Sevilla mengemukakan bahwa Buber mengungkapkan pemahaman Tuhan sebagai Pribadi untuk menolak, pandangan adanya Tuhan kaum filosof yang mereduksikannya menjadi sekedar idea belaka dan pandangan adanya Tuhan kaum teolog. Menurut Sevilla bagi Buber Tuhan adalah Dia – siapapun Dia, karena Dia tidak mungkin dikonsepkan dan digambarkan – yang berada dalam hubungan langsung dengan manusia. (Pedro Sevilla, 1970, h.72). Memang agak sulit memahami Tuhan sebagai Pribadi, karena pasti yang kita bayangkan adalah “seorang pribadi”, yang BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber hubungan dengan pribadi yang lain, yaitu manusia. Untuk itu baginya Tuhan adalah Pribadi yang real ada dalam pengalaman manusia. Secara real Tuhan adalah Pribadi yang ada dan terlibat dalam sejarah dunia dan Pribadi yang membentuk manusia dalam hubungan “AkuEngkau Absolut” sehingga manusia dapat menjadi pribadi yang sejati dan memberikan makna bagi dunia. 2.1. Pribadi yang Menyejarah Terlebih dahulu akan diungkapkan pemahaman Buber mengenai sejarah. Ia mengemukakan pemahamannya mengenai sejarah untuk menanggapi pemikiran sejarah dari Hegel.76 Bagi Hegel sejarah merupakan proses perwujudan “Roh”. Sejarah dunia adalah proses perwujudan dari “Roh” mutlak. Bagi Hegel “Roh” itu merupakan Tuhan, namun bukan sebagai persona. Tuhan dalam pemikiran Hegel adalah Tuhan yang benar-benar imanen dan real. Alam dan manusia adalah salah satu “tahap” dalam perjalanan Tuhan mewujudkan dirinya secara sempurna. Filsafat sejarah Hegel sendiri kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh para pengikutnya. Penyebabnya adalah adanya perbedaan dalam menjawab pertanyaan : apakah sejarah dialektika Hegel secara substansial lengkap/sempurna atau tidak. Kelompok pertama disebut “Old Hegelians” (atau sering juga disebut Hegelian Kanan), yang pemikiran politik dan filsafatnya lebih konservatif. Mereka mengatakan bahwa filsafat Hegel merupakan pendamaian yang jenius antara agama dan filsafat, yang mengatasi skeptisisme yang merusak dari jaman pastilah merujuk kepada manusia. Barangkali istilah metafisika “Pengada Personal” dapat dipakai untuk memahami Tuhan sebagai substansi yang tidak terbatas, memiliki kepenuhan mutlak dan berada dalam korelasi dengan manusia (Bdk. Anton Bakker, 1992, h.40-41). 76 Jacob Tauber, Buber and Philosophy of History, The Philosophy of Martin Buber, Ed. Paul A. Schilpp, 1967, h.453. 69 70 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama pencerahan, sekaligus memberikan dasar baru bagi keyakinan (faith). Mereka melihat bahwa pemerintahan politik Prussia di bawah Frederic William III dan ekspresi intelektualnya idealisme Hegel merupakan puncak dari perkembangan dialektika “roh”, dan karena itu merupakan momen bagi “Roh Mutlak”. Untuk itu mereka menyarankan kepaTuhan setiap individu kepada komunitas dan negara.77 Masa depan bagi “Old Hegelians” merupakan masa depan yang tertutup. Kelompok kedua disebut “Young Hegelians” (atau sering disebut Hegelian Kiri), yang mempunyai pengaruh lebih besar, baik dalam perkembangan filsafat kontinental berikutnya maupun secara umum di seluruh dunia. Mereka menafsirkan filsafat dengan berbeda dan menegaskan bahwa proses sejarah belumlah lengkap/sempurna dan spiral dialektika perlu untuk melakukan perubahan/peralihan lebih lanjut.78 Baik kekuasaan politik yang tengah memerintah maupun pemahaman filosofis dan agama yang tengah berlaku harus ditransformasi, bahkan diakhiri. Melalui perubahan sosial yang radikal dan kekritisan intelektual, filosof harus membawa revolusi politik dan intelektual. Masa depan dalam kaca mata kaum “Young Hegelians” merupakan masa depan yang terbuka. 77 Salah satu pernyataan Hegel yang sangat terkenal adalah “segala sesuatu yang real adalah rasional, dan segala sesuatu yang rasional adalah real”. Pernyataan ini menjadi “senjata” kaum “Old Hegelians” untuk mengatakan bahwa pemerintahan politik saat itu adalah real, maka rasional, dan harus dipatuhi. Dan ini diterapkan juga pada pajak, polisi dsb. (Lih. F. Engels, Ludwig Feuerbach and The End of Classical German Philosophy, Moscow:Progress Publisher, 1969, h.10). 78 Menurut “Young Hegelians” negara yang dimaksud Hegel adalah negara dalam konteks Revolusi Prancis. Negara pasca Revolusi Prancis ini menjamin penghormatan terhadap hak individu, martabat dan kebebasan manusia menentukan sikap batin dan keyakinan moralnya. Sikap negara yang mau memaksakan kehendak terhadap kebebasan manusia ini merupakan sikap tidak rasional, dan yang tidak rasional adalah tidak real. Dan yang tidak real tidak berhak menuntut ketaataan! Sikap ini menjadi pedoman “mesianis” bagi kaum “Young Hegelians”. (Jacob Taubes, Buber and Philosophy of History, 1967, h.456) BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber Dalam menanggapi filsafat sejarah Hegel, Buber mengatakan bahwa sejarah senantiasa mempunyai unsur dialogis. Jika, dalam pemikiran Hegel, sejarah dipahami hanya sebagai perwujudan “Roh Mutlak” saja, maka sejarah dalam pemikiran Hegel adalah sejarah yang monologis. Segala sesuatu berjalan karena “sudah semestinya” sebagai wujud perjalanan “Roh Mutlak”.79 Dalam sejarah tersebut yang berperan hanyalah “Roh Mutlak yang terus menerus mewujudkan diri. Kalaupun ada unsur dialektika dalam pemikiran Hegel, dialektika itu tidak lebih dari “Roh” yang sedang berproses mewujudkan kesempurnaannya itu sendiri. Memang dalam pemikiran sejarah Hegel kesadaran manusia mengungkapkan diri. Namun di baliknya, ada “Roh Mutlak” yang sedang berproses mencapai tujuannya. Sejarah mempunyai makna justru dari unsur dialogis yang terdapat di dalamnya. Tatkala manusia menjawab satu situasi khusus yang dialaminya, di sanalah sejarah menorehkan makna yang mendalam bagi dunia. Buber memang tidak menyangkal pemahaman Hegel bahwa ada peran “Roh Mutlak” dalam proses perwujudan sejarah. Namun menurutnya sejarah dibentuk dari dialektika hubungan antara Tuhan dengan manusia, bukan sematamata “kemauan” dari “Roh Mutlak” itu. Tuhan memang ada di dalam sejarah bahkan Ia mewujudkan diri di dalam sejarah, namun Tuhan tidaklah “memproduksi” sejarah sebagaimana yang dipikirkan Hegel.80 Masa depan bukanlah sesuatu yang bersifat pasti dan mutlak karena sudah ditentukan melalui perwujudan “Roh Mutlak” seperti yang dikatakan oleh Hegel. Bagi Buber masa depan ditentukan oleh dialog yang terjadi antara Tuhan dengan manusia. Dalam proses pembentukan sejarah, kebebasan manusia menjadi hal yang sangat penting. Melalui kebebasannya manusia memilih berbagai keputusan dari beberapa 79 Bdk. Franz Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Gramedia:Jakarta, 1999, h.58. 80 Martin Buber, Prophetic Faith, Harper & Row:NY, 1949, h.94. (selanjutnya disebut PF). 71 72 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama alternatif yang ada. Lewat hal itulah dialog antara Tuhan dengan manusia terjadi, dan sejarah pun dibentuk. Buber menulis : “hanya makhluk yang mempunyai kekuatan untuk memilih di antara berbagai alternatif, yang dipilih untuk menjadi mitra Tuhan dalam sejarah yang dialogis. Masa depan bukanlah sesuatu yang sudah pasti, selama Tuhan menginginkan manusia datang kepada-Nya dengan kebebasan……”81 Masa depan bersifat terbuka dan pada akhirnya diisi dan ditentukan lewat keputusan manusia. Dengan demikian bagi Buber, manusia adalah pusat sejarah. Lewat sejarah, manusia mencapai “kesadaran” akan dirinya sendiri. Sementara bagi Hegel yang menjadi pusat sejarah adalah “Roh Mutlak” itu sendiri. Sejarah dunia merupakan proses absolut di mana “Roh Mutlak” mencapai kesadaran sempurna akan dirinya sendiri. Dengan pemahaman seperti ini, kritikan Buber di samping ditujukan kepada pemikiran Hegel itu sendiri, juga nampaknya ditujukan kepada kaum “Old Hegelians” dari pada untuk kaum “Young Hegelians”. Keterbukaan terhadap sejarah masa depan seperti yang dipahami kaum “Young Hegelians” lebih sesuai dengan pemikiran Buber mengenai unsur dialogis antar manusia yang akan membuka ruang bagi masa depan manusia. Buber memahami sejarah dengan kaca mata konsep Tuhan sebagai pribadi. Sebagai pribadi Tuhan akan senantiasa berada di dalam hubungan dengan manusia. Dalam hubungan itulah “ruang antara” terbentuk”. “Ruang antara” merupakan realitas di mana manusia menunjukkan mengembangkan diri dan menunjukkan aktualitasnya. Hanya di dalam “ruang antara”, realitas dan aktualitas diri manusia itu ada. Dengan kata lain, “ruang antara” bagi Buber merupakan sejarah 81 Martin Buber, Pointing The Way, 1957, h. 192. (selanjutnya disebut PW) BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber yang sedang berlangsung. “Tuhan yang menyejarah” bagi Buber tidak lain dari pada Tuhan yang senantiasa berada di dalam hubungan. Baginya sejarah tidak lain merupakan hubungan-hubungan yang di dalamnya terdapat keputusan-keputusan manusia terhadap berbagai situasi. Dalam sejarah dunia, manusia dapat “bertemu” dengan Tuhan. Namun muncul sebuah pertanyaan, bagaimana Tuhan dipahami di dalam sejarah dunia? Dan bagaimana seseorang dapat melihat keberadaan Tuhan dalam sejarah dunia? Buber menjawab dengan mengatakan bahwa memang seseorang dapat bertemu dengan Tuhan melalui segala sesuatu yang ada di dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah medium di mana seseorang dapat bertemu dengan Tuhan.82 Mengapa? Karena Tuhan berbicara melalui segala sesuatu yang ada di dunia. Kemudian ia mengambil contoh penampakan Tuhan melalui semak belukar, api atau angin dalam Kitab Suci. Semua dipakai Tuhan untuk bertemu manusia. Namun fenomena tersebut harus di lihat sebagai simbol, bukan Tuhan itu sendiri. Semak yang menyala bukanlah Tuhan, melainkan simbol penampakan Tuhan. Buber dengan hati-hati mengatakan bahwa walaupun Tuhan menampakan diri namun Tuhan tidak dapat dicari, seperti manusia mencari barang yang hilang. Tuhan bersifat transenden terhadap dunia. Seseorang memang dapat “berpaling” dari dunia dengan bertarak atau semadi untuk mendapat kebijaksanaan atau religiositas tertentu. Namun pada akhirnya hanya perjumpaan dengan “Engkau”, yaitu sesama manusia, yang dapat membawa seseorang untuk berjumpa dengan “The Eternal Thou”. Sebagai orang Israel, Buber mengambil contoh kehidupan bangsa Israel dalam kitab suci untuk menunjukkan bahwa sejarah dibentuk oleh dialog antara Tuhan dan manusia. Israel mengenal Tuhan sebagai pribadi. Sebagai Pribadi, Tuhan berjumpa dengan Israel, termasuk 82 Robert E. Wood, op.cit, h.91. 73 74 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama perjumpaan di gunung Sinai lewat sepuluh perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa, proses tersebut merupakan proses sejarah yang sangat dalam. Mengapa disebut proses sejarah yang sangat dalam? Karena dalam kaca mata Buber, proses tersebut menunjukkan adanya koneksitas sejarah, yaitu dialog yang dibangun oleh Tuhan dengan manusia. Baginya tidaklah penting untuk mengetahui apakah gunung Sinai benar-benar sebuah gunung atau hanya tempat yang agak tinggi, walaupun untuk sebuah data historis hal itu penting. 83 Perjanjian yang dibangun di atas dasar hubungan Tuhan dengan Israel, mengandaikan adanya kebebasan Israel. Israel dapat memasuki perjanjian itu, hanya jika dirinya mempunyai kebebasan. Dan kebebasan itu diperoleh melalui perjumpaan dengan Tuhan sebagai pribadi.84 Demikian juga dengan pengalaman nabi-nabi dalam kitab suci. Mereka senantiasa mempunyai hubungan dialogis dengan Tuhan. Tuhan membuka hubungan lewat ruang dialog yang tercipta, dan para nabi menjawab di tengah berbagai alternatif jawaban. Bahwa nabi Elia sempat mengambil pilihan untuk mati dalam proses berdialog dengan Tuhan, hal itu merupakan wujud kebebasan atas berbagai pilihan yang ada. Dalam kehidupan para nabi Israel, proses ini menorehkan garis-garis sejarah yang kuat dalam kehidupan Israel. 2.2. Pribadi yang Membentuk Manusia Menurut Buber, hanya dengan menjalankan hubungan “AkuEngkau” seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan sebagai Pribadi. Lewat hubungan “Aku-Engkau”, “Aku” berada dalam proses “mempribadi” atau menjadi pribadi yang sejati. “Aku” bukan hanya menjadi “ada pada dirinya sendiri” (being itself ) melainkan sekaligus berada dalam proses “mengada”. Jika proses pembentukan “Aku” sebagai pribadi yang 83 Martin Buber, Moses, The Revelation and The Covenant, Harper & Row:NY, 1958, h.16. (selanjutnya disebut MRC. 84 Martin Buber, PF, h.26. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber sejati terdapat dalam hubungan “Aku-Engkau”, sementara itu anugerah Tuhan senantiasa berada pada “ruang antara” yang terjalin dalam hubungan itu, maka ia memastikan bahwa Tuhan mestilah Pribadi yang membentuk manusia. Tuhan membentuk manusia ketika manusia ada pada “ruang antara”. Bagi Buber hubungan seseorang dengan Tuhan tidak mungkin dilakukan dengan pola “Aku-Itu. Tuhan sebagai Pribadi tidak dapat dijadikan “Itu” oleh seseorang. Hubungan antara Tuhan dengan manusia haruslah merupakan hubungan “Aku-Engkau”. Ini berarti ada hubungan yang setara dan timbal balik antara Tuhan dengan manusia. “Aku” menerima “Engkau” sebagai sesama yang setara dan “Aku” membentuk diri bersama dengan “Engkau”. Jika pemahaman ini diterapkan pada hubungan antara manusia, tentu tidak menjadi masalah. Namun jika pemahaman ini diterapkan dalam hubungan Tuhan dengan manusia, muncul satu pertanyaan yaitu apakah di dalam hubungan “Aku-Tuhan”, “Aku” ikut membentuk Tuhan? Jika “Aku” membentuk Tuhan, bukankah Tuhan menjadi pribadi yang “kurang” sempurna? Dan jika hanya Tuhan yang membentuk “Aku”, pola hubungan akan menjadi tidak setara dan bergeser pada hubungan “Aku-Itu”?. Ia mengatakan bahwa “setara” tidaklah berarti mempunyai kualitas yang sama. Jika dua orang berada dalam hubungan yang “setara”, tidaklah berarti keduanya mempunyai kualitas yang sama. Begitu juga jika seseorang melakukan pola hubungan “Aku-Engkau” dengan lingkungan hutan yang memberinya oksigen dan resapan air, itu tidak berarti kualitas orang tersebut sama dengan kualitas hutan. “Setara” dalam pengertian Buber adalah bahwa yang satu tidak mengobjekkan yang lain demi kepentingan atau keinginannya semata. Demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan. Jika dikatakan bahwa Tuhan senantiasa berada dalam hubungan “Aku-Engkau”, dan karenanya Tuhan menjalin hubungan setara dan timbal balik dengan seseorang, maka 75 76 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama tidaklah berarti bahwa Tuhan secara kualitas setara atau sama seperti manusia. Bagi Buber hubungan timbal balik yang setara antara Tuhan dengan manusia terlihat ketika manusia mengambil keputusan secara bebas atas berbagai situasi yang dihadapainya. Pada dasarnya “ruang antara” yang terbentuk dalam hubungan “Aku-Engkau” merupakan ruang di mana seseorang memberikan tanggapan atau respon terhadap “Engkau”. Di sanalah ada kebebasan dan sekaligus menampakkan kesetaraan. “Aku” dibentuk dan memperoleh perkembangannya di dalam “ruang antara”. Untuk itu Buber mengatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang sempurna atau dengan kata lain Tuhan adalah Pribadi yang mutlak atau absolut. Ia berbeda dengan pribadi manusia. Tuhan menjadi “Pribadi Absolut” karena Tuhan tidak dapat dibatasai. Dalam kesempurnaan dan kemutlakkannya Tuhan tidak sama dengan pribadi manusia, yang harus berada dalam komunitas dan bertemu dengan pribadi yang lain untuk pembentukkan dirinya. “Engkau” terbatas dalam melakukan aktualitasnya, karena walaupun ia adalah makhluk mandiri, tetapi ia terikat pembentukan dirinya pada manusia lain, sedangkan “Engkau Absolut” tidaklah demikian. Namun jika dikatakan bahwa Tuhan bersifat sempurna dan tidak terbatas, tidak berarti Tuhan berada pada posisi diam dan tidak berproses apa-apa. Tuhan tetap melakukan proses dan proses itulah yang terlihat di dalam hubungan “Aku-Engkau Absolut”. Bagi Buber alam semesta berada dalam proses “menjadi” (becoming). Tuhan hadir dalam proses “menjadi” lewat hubungan “AkuEngkau Absolut”. Kehadiran Tuhan membentuk dunia dan manusia. Pribadi Absolut itu, yaitu Tuhan masuk ke dalam hubungan langsung dengan manusia. Buber mengambil contoh saat Tuhan memberikan “nama-Nya” kepada Musa. Tuhan mengatakan bahwa diri-Nya adalah “Aku akan hadir sebagaimana aku akan terus hadir” (I shall be present as which I shall be present).85 Menurutnya dengan mengemukakan seperti 85 Terjemahan ini merupakan terjemahan Buber bersama dengan Rosenzweig terhadap Keluaran 3:14. Dalam terjemahan Alkitab TB-LAI dikatakan “Aku adalah Aku”, BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber itu Tuhan harus dipahami sebagai Tuhan yang selalu hadir, sedangkan kehadiran adalah makna dari kehidupan. Dengan demikian Tuhan hadir dalam rangka meneguhkan bahwa ada suatu makna dalam kehidupan di dunia ini. Proses inilah yang dilalui Tuhan di dalam dunia ini. Dalam proses memberikan arti bagi dunia, Tuhan membentuk seseorang. Sebagai pribadi yang berada dalam hubungan “Aku-Engkau”, Tuhan “mengalirkan” sesuatu di dalam perjumpaan dengan “Aku”. Apa yang “dialirkan” Tuhan di dalam perjumpaan itu? Buber mengatakan hal itu sebagai “anugerah” (grace). “Anugerah” ada pada “ruang antara”. Di dalam perjumpaan seseorang merasakan anugerah itu dan sekaligus “menyambut” anugerah tersebut dalam bentuk “kehendak” (will). “Kehendak” merupakan keputusan atau tanggapan seseorang terhadap “anugerah” yang dialirkan Tuhan. Proses kesetaraan dan dialogis dalam hubungan Tuhan dengan seseorang terjadi ketika Tuhan “mengalirkan” sesuatu kepadanya, dan ia memberikan keputusan sebagai tanggapan. Namun keputusan dan tanggapan tersebut bukanlah untuk “membentuk Tuhan”, sebagaimana yang biasa terjadi dalam hubungan antar manusia. Keputusan dan tanggapan tersebut dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan dunia, di mana Tuhan sendiri terlibat dalam proses di dalamnya. Inilah hubungan setara dan timbal balik yang terjadi antara “Aku-Tuhan”. Lalu apakah dalam proses hubungan tersebut hanya manusia yang membutuhkan Tuhan? Ternyata tidak. Menurut Buber, bukan hanya manusia yang membutuhkan Tuhan untuk pembentukan dirinya, Tuhan juga memerlukan manusia agar sedangkan dalam bahasa Inggris dikatakan “I Am Who I Am”. Lewat terjemahan ini Buber ini menekankan aspek “Tuhan yang ada bersama”, “Tuhan yang hadir bersama”, “Tuhan yang berjalan bersama”. Penerjemahan seperti ini bukan tanpa reaksi. Erns Simon, salah seorang tokoh intelektual Yahudi yang ikut mendirikan Brit Shalom (lembaga Yahudi untuk membina iklim persahabatan dengan dunia Arab), memprotes terjemahan seperti itu dengan mengatakan bahwa Buber mengubah identitas Tuhan. Buber kemudian menjawab “Tuhan tidak pernah memberikan pernyataan filosofis mengenai siapa dirinya” (Lih. Maurice Friedman, Martin Buber’s Life and Work, The Middle Years, 1923-1945, 1983, EP Dutton : New York, h.65) 77 78 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama manusia dapat menjadi mitra dialog bagi Tuhan.86 Untuk itu Tuhan mengarahkan manusia agar tetap berada dalam proses menjadi pribadi. Tuhan yang memerlukan manusia sebagai mitra dialog menggariskan makna yang sangat dalam bagi hidup manusia. Hidup manusia menjadi bermakna karena Tuhan membutuhkan manusia. Jika Tuhan tidak membutuhkan manusia, apa makna hidup manusia? Dan apakah manusia dapat ada dalam dunia ini? Menurut Buber Tuhan membentuk seseorang terutama dalam bidang etika dan moral. Manakala seseorang melakukan hubungan “Aku-Engkau”, maka ia harus menjalankan nilai-nilai etika tertentu. Dalam kebebasannya menghadapi satu situasi tertentu, seseorang juga mempunyai kebebasan untuk mengambil satu keputusan etis untuk menjawab situasi tersebut. Menurutnya setiap situasi adalah unik dan membutuhkan keputusan-keputusan yang berbeda pula. Seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang ia lihat, dengar dan rasakan.87 Pada titik ini Buber nampak hati-hati agar tidak terjatuh pada pemahaman bahwa keputusan etis akhirnya tergantung dari situasi yang dihadapinya. Di satu pihak Buber menyadari bahwa seseorang mengambil keputusan etis dipengaruhi oleh situasi yang terjadi. Namun di pihak lain, pembenaran keputusan etis berdasarkan situasi tidaklah 86 Martin Buber, IT, h. 130. Pernyataan Buber bahwa Tuhan membutuhkan manusia menentang pemahaman keTuhanan kontemporer bahwa ciptaan termasuk manusia tidak menambah sesuatu pun pada Ada. Tuhan sempurna dan tidak terbatas untuk itu manusia tidak menambahkan sesuatu pun pada kaulitas Tuhan. Namun dari kenyataan itu tidak dapat disimpulkan bahwa ciptaan tidak berarti apa-apa bagi-Nya. Karena ciptaan hanya ada dan hanya dapat ada dengan mengambil bagian dalam kesempurnaan-kesempurnaan ilahi lewat sebuah tindakan dengan mana dalam arti tertentu Tuhan telah melibatkan Diri, maka Ia mendapati diri dalam ciptaan itu dan oleh sebab itu ciptaan itu bukan tanpa arti (Lih. Louis Leahy, Filsafat KeTuhanan Kontemporer, 1993, Kanisius:Jakarta, h. 222). Buber nampaknya juga mendasarkan diri pada pemahaman Perjanjian Lama bahwa Tuhan mengadakan perjanjian, khususnya di Sinai, dengan Israel. Tuhan mengikatkan diri dengan manusia dalam perjanjian itu. Dengan perjanjian itu, terlihat Tuhan “memerlukan” manusia. 87 Martin Buber, BMM, h.34. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber benar. Untuk itu menurutnya harus ada satu nilai “absolut” yang mempunyai keterkaitan dengan “Ada” yang Absolut. Ia mengatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara moral dalam hubungan “Aku-Engkau” ketika dirinya terbuka terhadap yang absolut.88 Apa maksudnya ia mengatakan seperti itu? Maksudnya adalah nilai absolut terdapat pada Tuhan sebagai yang Ada yang Absolut. Nilai absolut itu sekaligus menjadi rujukan bagi nilai-nilai moral manusia. Tatkala seseorang berada dalam hubungan “Aku-Engkau”, ia sekaligus berada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membawanya untuk menemukan nilai absolut dari Tuhan. Nilai absolut inilah yang akan menjadi rujukan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Inilah tanggung jawab yang harus diambil seseorang dalam setiap hubungan “Aku-Engkau”. Dengan tegas Buber mengatakan bahwa keterkaitan nilai “absolut” itu ada pada Tuhan. Tuhan melakukan hal itu melalui proses “pewahyuan” (revelation). Di sinilah agama memegang peranan untuk mengembangkan nilai-nilai etika dan moral yang diwahyukan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang keputusannya mengandung nilai etika dan moral yang tinggi, tanpa sekalipun “berbicara tentang Tuhan”? Apakah keputusannya menjadi tidak berarti? Buber mengatakan bahwa dirinya sangat mengagumi orang yang mampu mengambil keputusan dengan nilai etika dan moral yang tinggi tanpa berpikir tentang Tuhan.89 Baginya, berpikir atau tidak berpikir tentang Tuhan ketika dalam hubungan “Aku-Engkau” seseorang memberikan keputusan dengan moralitas yang tinggi “pewahyuan” itu tetap ada. Di sini Buber sama sekali tidak mengatakan bahwa proses pembentukan seseorang dalam hubungan “Aku-Engkau Absolut” adalah untuk 88 Martin Buber, BMM, 1971, h.35. Buber mengatakan, “…I find it glorious when the pious man does the good with his whole soul ‘without thinking of God’”. (Martin Buber, Replies to My Critics, dlm. The Philosophy of Martin Buber, Ed. Arthur Schillp, 1967, h. 719. 89 79 80 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama membawa dirinya pada pengakuan akan adanya Tuhan. Bagaimanapun ada kebebasan yang diberikan kepada manusia dalam perjumpaan dengan Tuhan. Melalui kebebasan itu, seseorang bisa mengambil keputusan “ya” atau “tidak” terhadap Tuhan. Bagi Buber keputusan (Entscheidung) menjadi satu aspek penting ketika seseorang membentuk diri dalam hubungan “Aku-Engkau”. Keputusan merupakan tindakan fundamental yang dilakukan seseorang manakala dirinya memasuki suatu hubungan.90 Lewat keputusan, seseorang secara sadar memilih apa yang dianggapnya baik dan apa yang tidak. Hanya orang yang sadar akan adanya hubungan dan mengetahui kehadiran “Engkau”, ia dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. “Engkau Absolut” hadir dalam hubungan dengan seseorang sekaligus memberikan “jalan” kepada seseorang dalam mengambil keputusan. Lewat itulah “Engkau Absolut” membentuk seseorang. Buber di sini mengambil paham tradisional bahwa Tuhan mengajarkan “jalan-jalan-Nya” kepada manusia dan manusia mengambil keputusan atasnya. “Jalan-jalan” yang ditunjukkan oleh Tuhan, ditunjukkan melalui pengalaman akan hubungan “AkuEngkau Absolut”. Lewat pengalaman itu, keputusan seseorang untuk mengarahkan diri pada “jalan-jalan” yang diberikan Tuhan dihasilkan lewat konfrontasi yang dihasilkan dengan pengalaman real sehari-hari. Keputusan bagi Buber senantiasa merupakan “keputusan eksistensial” di mana seseorang menyatakan aktualitas dirinya. 90 Alexander Kohanski, Martin Buber’s Philosophy of Interhuman Relation, 1982, h.87. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber 3. Tuhan sebagai “Engkau Absolut” yang Aktif Terlibat dalam Hubungan Buber mengatakan bahwa hubungan “Aku-Engkau” terjalin hanya melalui hubungan antar pribadi. Jika demikian maka Tuhan yang melakukan hubungan “Aku-Engkau” dengan manusia juga merupakan pribadi. Tuhan menjadikan dirinya sebagai pribadi agar senantiasa berada di dalam hubungan dengan manusia, yang adalah pribadi. Ia melihat bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam hubungan “AkuEngkau” dapat diterapkan dalam hubungan “Aku-Engkau Absolut”. Prinsip-prinsip yang ditemukan dalam hubungan “Aku-Engkau” dapat pula ditemukan dalam hubungan “Aku-Engkau Absolut”. Hubungan antar manusia merupakan metafor untuk menggambarkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Sebagai Pribadi, Tuhan mencintai manusia dan “berharap” untuk dicintai oleh manusia pula. Apa yang mengindikasikan bahwa Tuhan merupakan “Engkau Absolut” yang senantiasa berada di dalam hubungan? Ada dua indikasi, indikasi pertama adalah seperti telah diungkapkan bahwa dalam hubungan “Aku-Engkau”, Tuhan hadir “mengalirkan” anugerah di dalam hubungan itu dan disambut dengan kehendak manusia. Dalam hubungan terdapat dua aspek penting, yaitu anugerah Tuhan dan kehendak manusia. Dengan demikian dalam hubungan “Aku-Engkau” terdapat satu aspek yang akan tetap ada, yaitu “anugerah” Tuhan. Namun Buber nampaknya tidak memaksudkan anugerah itu sebagai “alat” bagi Tuhan untuk berhubungan dengan manusia, melainkan anugerah Tuhan sebagai pribadi Tuhan yang terungkap dan dapat dialami manusia dalam “ruang antara” hubungan “Aku-Engkau”. Hubungan tersebut menampakan dimensi transenden. Apa yang dikatakan Buber bermakna ganda, makna pertama adalah lewat anugerah-Nya yang terungkap dalam hubungan “Aku-Engkau”, Tuhan menjadi “faktor” yang tidak bisa tidak ada dalam hubungan itu. Hubungan “Aku-Engkau” 81 82 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama yang dilandasi oleh cinta kasih menjadi cerminan anugerah Tuhan. Sedangkan makna kedua adalah dengan adanya “faktor yang tidak bisa tidak ada” dalam hubungan “Aku-Engkau”, seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Seseorang dapat merasakan peralihan menuju pada yang transenden, ketika ia sungguh-sungguh melakukan hubungan “Aku-Engkau”. Indikasi kedua terlihat melalui pengalaman tokoh-tokoh dalam kitab Suci. Tokoh-tokoh dalam kitab suci berhubungan dengan Tuhan karena inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang memulai hubungan sebagai pribadi dengan manusia, menandakan bahwa Tuhan merupakan Pribadi yang berada di dalam hubungan. Di dalam hubungan itu Tuhan menyapa seseorang sebagai pribadi. Adanya inisiatif Tuhan untuk memasuki hubungan secara pribadi dengan manusia, memungkinkan manusia untuk masuk ke dalam hubungan itu. Buber kemudian mengambil contoh dari Kitab Suci. Kenyataan bahwa Tuhan senantiasa berada di dalam hubungan ditunjukkan dengan inisiatif Tuhan untuk memulai dialog dengan manusia. Ketika Abraham berhubungan dengan Tuhan, Tuhan yang terlebih dahulu memulai dialog dengan Abraham. Tuhan membuka hubungan dengan Abraham, dan hal ini memungkinkan Abraham untuk memasuki hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang Tuhan lakukan dengan Abraham adalah hubungan personal. Tuhan “memisahkan” Abraham dari kaum keluarganya untuk menghadakan hubungan pribadi dengannya. Menurut Buber dalam hubungan pribadi ini terdapat aspek pewahyuan (revelation) dan keputusan (decision).91 Dalam pewahyuan ada dua aspek, yaitu “pemanggilan” (summon) dan “pengutusan” (send). Tuhan memanggil dan mengutus Abraham. Abraham menjawab panggilan tersebut melalui keputusannya untuk menerima tawaran hubungan dari Tuhan atau tidak. Lewat pengalaman itulah Abraham 91 Martin Buber, PT, h.36. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber mulai mengenal Tuhan. Lewat setiap pengalaman yang dijumpainya, Abraham terus menerus membaharui pengenalannya akan Tuhan. Dengan demikian hubungan Tuhan dengan manusia tidak berada pada “kebenaran-kebenaran” teologis yang statis (“static” theological truths).92 Baginya hubungan Tuhan dengan manusia berada dalam kebenaran teologis yang statis, jika Tuhan, melalui agama, secara mutlak memberikan pewahyuan mengenai siapa dirinya dan apa makna kehidupan tanpa manusia diberi kesempatan untuk menjawab berdasarkan realitas kongkret hidupnya. Dilihat dari sudut manusia, hubungan dirinya dengan Tuhan tidak dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan hubungan itu dilakukan untuk meneguhkan satu hal, yaitu bahwa ada sesuatu yang bermakna di dalam dunia dan lewat keputusan yang ia ambil, ia turut meneguhkan makna itu. Buber menunjukkan bahwa dengan melakukan hubungan dengan Tuhan, Abraham menyadari bahwa Tuhan memerlukan dirinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hidupnya bermakna. Hidup Abraham yang bermakna ada di dalam dunia dan sekaligus untuk memberi makna kepada dunia. Dengan demikian dunia pun menjadi bermakna. Dalam dunia yang bermakna itulah, Tuhan menjadi pribadi yang selalu hadir dan berjalan bersama manusia. Bagi Buber, Tuhan yang senantiasa berada dalam hubungan, bukanlah Tuhan kaum filosof. Ia mengemukakan ini untuk menanggapi Blaise Pascal yang mengatakan bahwa Tuhan kaum teolog berbeda dengan Tuhan kaum filosof.93 Menurutnya sejauh Tuhan hanya dipahami se92 Maurice Friedman, Martin Buber’s Life and Work, The Early Years 1878-1923, 1982, h.354. 93 Martin Buber, EoG, h.62. Juga lihat, Pedro Sevilla, God as Person in The Writings of Martin Buber, 1970, h. 76-dst. Dalam buku harian Pascal sebelum ia meninggal, orang menemukan doa Pascal yang membedakan antara Tuhan Abraham, Isaak dan Yakub dan Tuhan para filsuf. Pembedaan ini menimbulkan dua penafsiran. Penafsiran pertama pembedaan ini merupakan dikotomi antara paham Tuhan yang dikenal dan diimani dalam agama dan dipelajari dalam filsafat dengan suatu sikap kritis. Penafsiran kedua melihat pembedaan ini dalam keseluruhan konteks filsafat 83 84 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama bagai ide belaka dan hanya diakui melalui argumentasi-argumentasi rasional akan selalu ada pembedaan. Namun jika perangkat filosofis dipakai sekaligus untuk merasakan keberadaan dan kehadiran Tuhan lewat pengalaman kongkret, seharusnya tidak ada pembedaan seperti itu. Demikian juga sebaliknya jika kaum teolog mendasarkan pemahamannya mengenai Tuhan hanya lewat apa yang terungkap dalam kitab suci, tanpa mendialogkan dengan pengalaman kongkret situasi masa kini, itupun berarti mereduksikan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang hadir dalam hubungan manusia, baik dulu, sekarang maupun masa yang akan datang. Penghalaman terhadap hubungan itulah yang akan membawa manusia untuk “memahami” Tuhan dan memberikan makna dalam kehidupan ini. Ia juga memuji Pascal dengan mengatakan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh Pascal justru menampakkan perbedaan yang jelas antara Tuhan yang hidup dalam hubungan dialogis dengan manusia, dengan Tuhan yang hanya merupakan objek pemikiran semata. Tuhan kaum filosof adalah Tuhan hasil objektifikasi akal budi yang berwujud idea, sedangkan Tuhan yang hidup adalah Tuhan dari Abraham, Isak dan Yakub.94 Memang bagi Pascal kepercayaan dan perjumpaan manusia dengan Tuhan bukanlah soal akal budi atau rasio melainkan soal hati (coeur). Manusia bertemu Tuhan di dalam hatinya, dan keputusan terpenting manusia adalah untuk menerima dan mengikuti Tuhan. Ketika hati sudah bertemu dengan Tuhan melalui keputusan eksistensial seseorang, hati itulah yang akan mengarahkan akal budi untuk memberikan pemahaman mengenai Tuhan. Pascal yaitu pembedaan antara ‘hati” dan “akal”. Pascal mengatakan bahwa manusia bertemu dengan Tuhan di dalam hatinya dan keputusan ini jauh melampaui rasio. (lih. Louis Leahy, Filsafat KeTuhanan Kontemporer, 1991, Yogyakarta, h.18-21. Leahy cenderung mengikuti penafsiran pertama; Harry Hamersma, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern, 1991, Jakarta, h.16-18. Hamersma cenderung mengikuti penafsiran kedua). 94 Martin Buber, EoG, h.49. BAB IV Tuhan Menurut Martin Buber 4. Kesimpulan Tuhan tidak dapat ditemukan oleh manusia. Tuhan hanya dapat dirasakan oleh manusia melalui pengalaman hubungan “Aku-Engkau Absolut”. Untuk itu segala pemikiran tentang Tuhan yang hanya mendasarkan diri pada penelahaan akal budi atau rasio, tidak akan dapat membawa manusia pada pengalaman yang sesungguhnya dengan Tuhan. Tuhan bukanlah ide semata. Untuk itu Tuhan bukanlah objek akal budi. Tuhan yang hanya sekedar menjadi objek akal budi tidak akan hadir dalam pengalaman eksistensial manusia dalam menghadapi situasi real sehari-hari. Tuhan seperti itu adalah Tuhan yang terpisah dari realitas kehidupan manusia. Dia tidak dapat berkomunikasi dengan manusia dan sebaliknya manusia pun tidak dapat berkomunikasi dengan-Nya. Tidak ada makna bagi dunia yang dapat ditambahkan jika Tuhan hanya sekedar menjadi objek akal budi. Tuhan membutuhkan manusia untuk menjadi mitra dialognya. Itulah makna hidup manusia yang sangat dalam. Untuk meneguhkan makna hidup manusia itu Tuhan menjadikan dirinya sebagai pribadi untuk berhubungan dan membentuk manusia. Hanya seorang pribadi yang dapat membina hubungan setara dan timbal balik. Namun kepribadian Tuhan berbeda dengan kepribadian manusia. Tuhan adalah Pribadi mutlak. Jika manusia membutuhkan sesama dan lingkungannya dalam proses mempribadi, maka Tuhan tidak membutuhkan siapapun. Manusia membutuhkan Tuhan dalam proses mempribadi dan Tuhan membutuhkan manusia untuk mengaktualkan pribadi yang sesungguhnya sebagai rekan dalam dialog dengan Tuhan. Dalam hubungannya dengan manusia itulah, Tuhan membentuk diri manusia untuk menjadi pribadi sejati. Pembentukan itu terjadi ketika manusia mengkonfrontasikan situasi aktual hidup sehari-hari dengan “jalan” yang Tuhan tunjukkan lewat dialog yang terjadi. Hasil dari proses itu disebut sebagai keputusan manusia. Keputusan demi keputusan 85 86 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama akan mewarnai eksistensi manusia di dunia ini sekaligus meneguhkan makna dirinya. Sebagai pribadi Tuhan akan senantiasa berada dalam hubungan dengan manusia. Tuhan “menjadikan” dirinya sebagai pribadi justru supaya dapat berhubungan dengan pribadi “lainnya’, yaitu manusia. Untuk itu proses pembentukan manusia sebagai pribadi yang sejati dalam hubungan “Aku-Engkau Absolut” pun akan terus berlangsung. Perjumpaan manusia dengan Tuhan dalam hubungan “Aku-Engkau Absolut” juga dapat terjadi melalui sesama, yaitu melalui hubungan “Aku-Engkau”. Dalam hubungan “Aku-Engkau” ada dua aspek yang bertemu, yaitu anugerah dari Tuhan, dan kehendak dari manusia yang diwujudkan dalam keputusan-keputusan. Ketika hubungan “AkuEngkau” dilakukan dengan sungguh-sungguh maka aspek anugerah akan senantiasa hadir. Lewat perjumpaan dengan sesama, seseorang dapat menghayati perjumpaan dengan Tuhan. Namun demikian pemikiran Buber mengundang satu pertanyaan, apakah seseorang yang menghayati pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dalam hubungan “Aku-Engkau” akan mempunyai kualitas perlakuan lebih baik terhadap orang lain dibanding yang tidak menghayatinya? Apakah makna “lebih” yang dapat dibawa orang yang menghayati perjumpaannya dengan Tuhan dibandingkan dengan orang yang tidak menghayati perjumpaan itu, sementara itu keduanya menjalankan hubungan “Aku-Engkau” dengan orang lain? Setelah kita mengetahui pemikiran Buber mengenai Tuhan, maka pada bab berikutnya akan dibahas pemikirannya mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Pemikirannya mengenai hubungan “AkuEngkau” dan mengenai Tuhan akan mendasari pemikirannya tentang hubungan manusia dengan Tuhan. BAB V Hubungan antara Manusia dengan Tuhan Menurut Martin Buber Bagian ini akan membahas Hubungan antara manusia dengan Tuhan menurut Buber. Bagi Buber Tuhan adalah tujuan diri dan hidup manusia. Tuhan adalah Pribadi, yang di dalam diri-Nya manusia berada dalam proses menjadi, yaitu menjadi manusia dan bukan menjadi Tuhan. Menjadi manusia, dalam pemikirannya, adalah untuk memenuhi tujuan mengapa manusia diciptakan yaitu agar manusia dapat menjadi pribadi yang sejati. Pemenuhan akan tujuan itu hanya mungkin dengan adanya hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan inilah yang disebut Buber dengan religiusitas. Pengalaman religius menjadi sesuatu yang berlangsung setiap hari, di mana Tuhan “berhadap-hadapan muka” dengan manusia dalam pengalaman hidup sehari-hari. Pada bab IV telah digambarkan bagaimana Buber menolak pemahaman yang mereduksikan Tuhan menjadi hanya sekedar idea dan objek pemikiran belaka. Tuhan haruslah Tuhan yang senantiasa berada dalam hubungan dengan manusia. Namun pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara Tuhan dengan manusia dapat 87 88 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama berlangsung? Aspek-aspek apa saja yang menyertai hubungan tersebut? Pemikiran Buber mengenai hubungan manusia dengan Tuhan didasari oleh pemikirannya mengenai dua hubungan dasar yang selalu dijalani oleh manusia, yaitu “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. Hubungan “AkuEngkau” akan mengantar manusia untuk berjumpa dengan “Engkau Absolut”. “Engkau Absolut” diyakini Buber adalah Tuhan. Untuk itu menjadi sangat penting untuk mengemukakan peralihan-peralihan yang dialami manusia dalam pola-pola hubungan itu. Bab ini akan dimulai dengan membahas peralihan-peralihan dari “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau”; dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Itu”; dan akhirnya dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Engkau Absolut”. Kemudian akan dibahas juga mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam hubungan “Aku-Engkau Absolut”, yaitu aspek pertemuan, aspek kebebasan dan aspek dialog. Pada bagian berikutnya akan diuraikan pemikiran Buber mengenai bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dipahami dalam agama, khususnya dalam kehidupan manusia modern. Bagian ini merupakan salah satu pokok penting karena pemikirannya mengenai hubungan manusia dengan Tuhan didasari oleh keprihatinannya terhadap pola hubungan manusia dengan Tuhan dalam kehidupan manusia modern. Bab ini akan ditutup dengan kesimpulan. 1. Dinamika Hubungan “Aku-Itu”, “Aku-Engkau” dan “AkuEngkau Absolut” Telah diungkapkan dalam Bab IV bahwa bagi Buber “Engkau Absolut” adalah Tuhan. Perjumpaan manusia dengan “Engkau Absolut” didasari oleh hubungan “Aku-Engkau”. Sedangkan hubungan “Aku-Engkau” terkait erat dengan hubungan “Aku-Itu”. Pola hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” merupakan dua pola hubungan yang selalu dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Hubungan “Aku-Itu” pada titik tertentu bisa berubah menjadi “Aku-Engkau”. Demikian juga dengan sebaliknya, hubungan BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber “Aku-Engkau” dapat berubah menjadi “Aku-Itu”. Lalu bagaimana dengan hubungan “Aku-Engkau Absolut”? Menurut Buber di dalam hubungan “Aku-Engkau” seseorang dapat berjumpa dan mengadakan hubungan dengan “Engkau Absolut”. Untuk itu pada bagian berikut ini akan dikemukakan peralihan-peralihan yang terjadi dari satu pola hubungan ke pola hubungan yang lainnya. 1.1. Peralihan dari “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau” Pada bab III telah dikemukakan bahwa hubungan “Aku-Itu” didasarkan pada pola subjek-objek. Subjek memperlakukan objek semata-mata untuk tujuan atau kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan hubungan “Aku-Engkau” didasarkan pada pola subjek-subjek, di mana ada kesetaraan dan timbal balik. “Aku” memperhatikan “Engkau” sebagaimana “Engkau” ada dengan berbagai keinginan dan harapan yang ada pada “Engkau”. Menurut Buber hubungan “Aku-Itu” dapat beralih menjadi hubungan “Aku-Engkau”. Jika itu dilakukan maka ada “peningkatan” dalam pola hubungan yang dilakukan oleh seseorang. Pada saat seseorang melakukan pola hubungan “Aku-Itu”, maka keberadaan “Itu” adalah untuk “Aku”. “Itu” ada semata-mata untuk mengabdi pada kepentingan dan keinginanku. “Itu” tidak dapat berbuat apa-apa. Harapan dan keinginannya tidak berarti bagiku. Ia hanyalah sebuah objek. Peralihan dari pola hubungan “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau” terjadi jika seseorang mengabdikan dirinya bagi “Itu”. “Aku” mengadakan hubungan timbal balik dengan “Itu”, di mana harapan dan keinginan “Itu” menjadi penting bagiku. “Aku” berhenti menjadikan “Itu” sebagai objek untuk kepentingan dan keinginanku belaka. Pada saat itu “Itu” tidak lagi menjadi “Itu” melainkan berubah menjadi “Engkau”. Menurut Buber, peralihan dari “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau” ada dalam tindakan, bukan bahasa atau perkataan karena bahasa atau perkataan belum mencerminkan apakah seseorang 89 90 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama menjalani pola hubungan “Aku-Itu” atau “Aku-Engkau”. Bisa terjadi lewat bahasa seseorang menyapa orang lain dengan “Itu” tetapi tindakannya terhadap orang itu menunjukkan sikap terhadap “Engkau”. Tindakan seseorang menunjukkan keputusan yang ia ambil berkaitan dengan sikapnya terhadap sesuatu atau suatu kondisi, dalam hal ini terhadap “Itu. Keputusan itulah yang mencerminkan sikap dan pola pikirnya terhadap “Itu”. Lewat keputusannya, “Aku” memperlakukan “Itu” atau “Engkau”. Dan lewat keputusan itu pula “Aku” mengubah perlakuanku terhadap “Itu” menjadi “Engkau”. Menurut Buber peralihan dari “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau” menunjukkan adanya peralihan menuju apa yang baik. Apakah yang dimaksud “yang baik” oleh Buber? Baginya “yang baik” adalah gerakan untuk mengarahkan diri memasuki hubungan “Aku-Engkau”.95 “Arah” yang dituju hanyalah satu, yaitu “Engkau”. Ia mengatakan manusiapun tidaklah “baik” atau “jahat”. Manusia mempunyai perasaan dan pendirian yang ulung terhadap “yang baik” dan “yang jahat”.96 Gerakan dari diri seseorang untuk mengarah pada hubungan yang setara dan timbal balik bersama dengan “Engkau”, merupakan gerakan yang akan mewujudkan “yang baik”. Dengan berkata seperti itu berarti setiap usaha peralihan dari hubungan “Aku-Itu” menuju ke hubungan “Aku-Engkau” merupakan gerakan diri seseorang untuk menuju kepada “yang baik”. Lalu jika Buber mengatakan bahwa gerakan seseorang untuk beralih dari “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau” adalah untuk mewujudkan “yang baik”, maka apakah menurutnya hubungan “Aku-Itu” adalah jahat? Buber sama sekali tidak mengatakan bahwa “Aku-Itu” adalah jahat. Juga ia tidak mengatakan bahwa dunia “Itu” adalah jahat.97 Apa yang 95 Alexander Kohanski, op.cit, h.85. Buber mengatakan “Man is not good, man is not evil; he is in a pre-eminent sense good and evil together”.(Martin Buber, BMM, h.103). 97 Martin Buber, I T, h.95 96 BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber dikatakan Buber tidak meniadakan kenyataan bahwa dalam hubungan “Aku-Itu” ada masalah mengenai kejahatan dan kebaikan. Ia menyadari bahwa dalam dunia “Itu” terdapat potensi menuju arah “yang jahat”. Namun hubungan “Aku-Itu” dan dunia “Itu” bukanlah sesuatu yang “jahat”. Konflik mengenai bagaimana “Aku” memperlakukan orang lain sebagai objek atau memilih untuk memasuki hubungan setara dan timbal balik dengannya akan senantiasa ada. Manakala seorang ilmuwan memperlakukan seorang manusia yang rela menjadikan dirinya sebagai objek penelitian untuk menemukan obat terhadap suatu penyakit, apakah ilmuwan itu jahat karena telah memperlakukan seseorang sebagai “Itu”? Buber menjawab bahwa hal itu tidaklah jahat. Bahkan tidak mungkin dihindari dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal itu justru penting untuk memajukan ilmu pengetahuan. Namun Buber mendorong manusia untuk mengontrol dirinya dalam pola hubungan “Aku-Itu”. Apabila manusia tidak dapat mengontrol dirinya, maka ia akan menjadi penentu “takdir” sesamanya. Yang diperlukan oleh ilmuwan dan dunia teknologi adalah “arah” (direction), yaitu ketika seorang ilmuwan melakukan gerakan untuk memasuki hubungan “Aku-Engkau”, setelah ia mencapai keberhasilan dalam penelitiannya. Tanpa melakukan gerakan untuk mengubah “arah”, ia justru akan semakin kehilangan arah hubungan yang benar, yaitu hubungan “Aku-Engkau”. 1.2. Peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Itu”. Peralihan dari pola hubungan “Aku-Engkau” ke “Aku-Itu” berjalan berbalikan dengan peralihan “Aku-Itu” ke “Aku-Engkau”. Jika “Aku” tidak lagi memperlakukan “Engkau” sebagai sesama yang setara dalam hubungan timbal balik, melainkan memperlakukan “Engkau” sebagai objek pemikiran, pengamatan dan penggunaan bagi “Aku”, maka pada saat itu “Engkau” berubah menjadi “Itu”. Menurut Buber peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Itu” merupakan peralihan dari sistem 91 92 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama penyatuan (association) ke sistem yang berdiri sendiri (discreteness) oleh karena ia merasa berbeda dengan yang lain. Hubungan “AkuEngkau” menampakkan asosiasi antara “Aku” dengan “Engkau”. “Aku” menggabungkan dan menyatukan diri dengan “Engkau” dalam suatu hubungan yang setara. Ketika seseorang menjadikan “Engkau” sebagai “Itu”, maka asosiasi berubah menjadi pemisahan. “Aku” menyadari bahwa diriku berbeda dengan orang lain dan aku menolak orang lain. Buber memberikan contoh tentang bayi.98 Ketika bayi masih dalam kandungan, hubungan antara dia dengan ibunya dapat diandaikan seperti hubungan penyatuan yang alamiah (natural association). Ia menggabungkan diri dengan ibunya, merasa bersatu dan merasa aman dengan kehadiran ibunya. Ada keterbukaan di dalam dirinya. Keterbukaan ini membawa ia untuk mempercayakan diri kepada sang ibu. Semakin erat cinta kasih dan kehangatan yang ia rasakan dari ibunya, semakin dirinya erat persekutuan ia dengan ibunya. Namun ketika ia lahir dan beranjak menjadi besar, ia mulai mengenali bahwa ia berbeda dengan ibunya. Ia mulai mengenali lingkungannya dan mempergunakan segala sesuatu yang ada di dalam lingkungannya untuk meneguhkan dirinya. Proses untuk menjauhkan diri dari ibu mulai terjadi sebagai bagian dari keinginannya untuk menunjukkan bahwa ia berdikari dan berbeda dengan ibunya. Berbagai hal yang ada di sekitarnya, ia jadikan objek untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Bukan hanya itu ia juga menjadikan apa yang ada di sekitarnya sebagai objek untuk kesenangan dirinya, termasuk ibunya sendiri. Ketika objek tersebut memuaskan keinginannya, ia akan tertawa dan merasa senang. Namun ketika objek tersebut membuatnya jengkel, ia akan menangis. Hubungan asosiasi yang alamiah telah berubah menjadi keadaan berdiri sendiri yang alamiah (natural discreteness). Penerimaan total telah berubah menjadi penolakan total. Terjadi peralihan dari “Engkau” menjadi “Itu”. 98 Martin Buber, I T, h.76-77. BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber Tatkala seseorang menjalankan peralihan “Aku-Engkau” ke “AkuItu”, ia tidak melakukan gerakan untuk “terarah” kepada “Engkau”, melainkan terperangkap di dalam dirinya sendiri. “Aku” terperangkap di dalam diriku sendiri dan menjadikan “Engkau” sebagai “Itu”, manakala “Aku” mengobjektivasi “Engkau” yang tadinya aku cintai, mengelompokkan “Engkau” sesuai dengan pemikiranku, mendekripsikan, mensistematisasi dan menganalisis “Engkau” sesuai dengan akal budiku belaka. “Aku” terperangkap di dalam diriku sendiri karena melihat “Engkau” melulu dari kaca mata “Aku”. Hubungan itu tidak melibatkan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. “Aku” menjadi tertutup terhadap “Engkau”. Menurut Buber, “Aku” yang mengalami peralihan dari “AkuEngkau” ke “Aku-Itu” adalah “Aku” yang sudah berubah. “Aku” yang berada dalam hubungan “Aku-Engkau” adalah “Aku” yang bersifat terbuka dan toleran terhadap “Engkau”. Ketika “Engkau” berubah menjadi “Itu”, maka “Aku” pun berubah menjadi “Aku” yang tertutup, tidak toleran dan mementingkan kepuasan diri dengan mengobjekkan orang lain. “Aku” tidak lagi membutuhkan keberadaan “Engkau”. Padahal kondisi saling membutuhkan harus ada di dalam hubungan “Aku-Engkau”. “Aku”, yang tadinya merupakan pribadi ketika menjalin hubungan dengan “Engkau”, berubah menjadi “ego”. Pada bab III telah dikemukakan bahwa ego merupakan sisi manusiawi yang mementingkan diri sendiri dan menjadikan diri sebagai pusat. Ia merasa unggul dibanding orang lain, untuk itu ia menutup diri. Ia merasa lebih penting dibanding orang lain, untuk itu selalu menganggap orang lain tidak penting dan orang lain ada hanya sebagai alat pemenuhan diri sendiri. Ia dengan tegas mengatakan bahwa peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Itu” menyebabkan “Aku” kehilangan aktualisasinya. Aktualisasi diri seseorang hanya terjadi di dalam hubungan “Aku-Engkau”. Di 93 94 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dalam hubungan itu, perjumpaam membawa “Aku” untuk senantiasa “hadir” (presence) secara aktual. Kehadiran “Aku” secara aktual membuka masa depan “Aku”. “Aku” yang berada dalam proses mempribadi adalah “Aku” yang bergerak menuju ke masa depan. Dengan demikian “Aku” yang berada dalam hubungan “Aku-Engkau” adalah “Aku” yang terbuka ke masa depan. Peralihan ke “Aku-Itu” menjadikan “Aku” tertutup. “Aku” bukan hanya menutup diri bagi orang lain, sekaligus “Aku” menutup diri bagi masa depanku. Mengapa itu terjadi? Karena aktualitas “Aku” telah hilang. Begitu peralihan terjadi, aktualitasku hilang dan masa depanku tertutup. “Engkau” yang membentuk “Aku” menjadi sirna, padahal “Aku” menjadi “Aku” hanya karena “Engkau”. 1.3. Peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Engkau Absolut” Peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Engkau Absolut” berbeda dengan proses peralihan “Aku-Engkau” ke “Aku-Itu” atau sebaliknya. Peralihan ini bersifat lebih transendental dibandingkan dua peralihan sebelumnya. Jika dikatakan bahwa ada peralihan dari “Aku-Engkau” ke “Aku-Engkau Absolut”, maka itu tidak berarti bahwa hubungan “Aku-Engkau” ditinggalkan sebagaimana seseorang beralih dari “AkuItu” ke “Aku-Engkau” atau sebaliknya. Yang dimaksudkan dengan peralihan pada bagian ke tiga ini adalah terlibatnya “Engkau Absolut” manakala seseorang menjalankan hubungan “Aku-Engkau” dengan sungguh-sungguh. Hubungan “Aku-Engkau Absolut” didapat melalui hubungan “Aku-Engkau”. Jadi “Engkau” tidaklah berubah menjadi “Engkau Absolut”. “Engkau” tetap menjadi “Engkau”. Namun di dalam perjumpaan dengan “Engkau”, “Engkau Absolut” hadir. Bagaimana Buber menjelaskan hal itu? Buber mengatakan bahwa manusia mempunyai sifat transenden di dalam dirinya. Sifat ini ada secara apriori dan menyebabkan manusia mampu mentransendensikan, baik pengalaman atau apa pun yang ada BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber di dalam dunia ini, yang bersifat terbatas (finite). Manusia mampu mentransendensikan perjumpaan secara fisik-material di antara dua orang. Namun kemampuan mentransendensikan apa yang bersifat terbatas tidak muncul secara otomatis dan serta merta. Seseorang harus mengakui dan menghargai terlebih dahulu kenyataan bahwa orang lain bersifat unik dan setara dengan dirinya. Keterbukaan terhadap orang lain akan membawa dirinya terbuka terhadap sifat transenden tersebut. Akses menuju pada yang transenden hanya terjadi jika “Engkau” hadir dan menjelma secara utuh terhadap “Aku”.99 Melalui perjumpaan dengan setiap “Engkau”, seseorang dapat melangkah untuk memulai mengenal “Suara” Tuhan yang berbicara kepadanya lewat berbagai peristiwa. Buber di sini memberikan kesaksian melalui pengalaman hidupnya. Perjumpaan dan hubungannya dengan berbagai orang, termasuk dengan orang-orang Palestina yang sering dianggap “musuh” oleh bangsa Yahudi, membawanya masuk ke dalam satu pengalaman puncak, yaitu pengalaman beriman kepada Tuhan. Lewat pengalaman itu dirinya memahami bahwa dunia adalah “dunia hubungan-hubungan”. “Ada” yang berada di dunia seharusnya merupakan “Ada” yang selalu berada di dalam hubugan dialogis. Inilah yang secara fundamental mendasari pemahaman Buber bahwa setiap “Engkau” yang terbatas (finite Thou) mencerminkan keberadaan Tuhan. Lewat “Engkau” yang terbatas, secara sekilas pandangan seseorang dapat menuju kepada Tuhan. Menurut Buber setiap “Engkau” berbicara sebagai “Engkau Absolut”. Namun tidak berarti bahwa “Engkau” (sebagai manusia) identik dengan “Engkau Absolut” (yang dimengerti sebagai Tuhan). “Engkau” hanya menunjukkan pantulan dari “Engkau Absolut”. “Engkau” tidak mungkin identik dan menjadi “Engkau Absolut” karena “Engkau” bisa berubah menjadi “Itu” sedangkan “Engkau Absolut” 99 Robert E. Wood, op.cit, h. 88. 95 96 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama tidak demikian.100 Menurutnya setiap hal yang bersifat terbatas di dunia ini dapat menjadi “Engkau”, namun dapat pula berubah menjadi “Itu”. Sedangkan “Engkau Absolut” karena sifat mutlaknya, tidak dapat berubah menjadi “Itu”. Secara apriori orientasi diri dari “Aku” bisa didapatkan lewat setiap hubungan dengan “Engkau”, namun pemenuhan orientasi diri itu hanya mungkin bila ada relasi khusus dengan Tuhan sebagai “Engkau Absolut”. Maksud Buber adalah bahwa “Aku” dapat melihat sisi transenden yang ada pada “Engkau” dan pada saat yang bersamaan sekaligus “Aku” dapat melihat sisi transenden yang ada pada diriku sendiri. Pada titik inilah “Aku” membuka orientasi diriku sendiri. “Aku” sadar bahwa diriku berbeda dengan “Engkau”, namun sekaligus “Aku” merasa diriku menyatu dengan “Engkau”. “Aku” sedang berada dalam orientasi untuk menjadi keseluruhan “Aku-Engkau”. Jika melalui “Engkau” seseorang dapat berjumpa dengan “Engkau Absolut”, akankah perjalanan seseorang untuk mengaktualisasikan diri berhenti? Buber menjawabnya dengan mengatakan bahwa dalam setiap perjumpaan dengan “Engkau” seseorang memang dapat berjumpa dengan “Engkau Absolut”, namun tidak berarti proses mengaktualisasikan dirinya berhenti. Di sini seseorang hanya menemukan “Pusat” Absolut. Lewat “Pusat” Absolut absolut inilah segala sesuatu mengalir pada keseluruhan.101 Orang yang telah menemukan “Pusat” Absolut ini kemudian di minta menelusuri jalan-jalan yang mengalir lewat “Pusat” Absolut tersebut. Bagi Buber “Pusat” Absolut itulah Tuhan dengan segala misterinya. Dengan mengatakan bahwa dari “Pusat” Absolut mengalir segala sesuatu menuju pada keseluruhan, ia menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pusat dari segala sesuatu dan di dalam diri Tuhan-lah keseluruhan itu ada termasuk di dalamnya nilai-nilai Absolut. Setelah berjumpa dengan Tuhan, seseorang diminta untuk mengikuti “jejak-jejak” Tuhan yang mengalir ke luar dari 100 Martin Buber, I T, h.69. Robert E. Wood, op.cit, h. 92. 101 BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber “Pusat” tersebut. Ia mendialogkan kembali perjumpaan itu dengan realitas pengalaman yang ia dapatkan. Perjumpaan dengan Tuhan bukanlah akhir dari pencarian manusia terhadap makna kehidupan secara keseluruhan, melainkan awal dari pencarian itu. Secara terus menerus pengalaman perjumpaan dengan Tuhan akan terlihat melalui berbagai keputusan yang dihasilkan seseorang. Lewat itu, manusia menghasilkan “ada-nya di dunia”, yaitu “ada” yang mengatualisasikan dirinya lewat perjumpaan dan hubungan. Peralihan “Aku-Engkau” menjadi “Aku-Engkau Absolut” menghasilkan panggilan dan misi. Perjumpaan dengan Tuhan melibatkan misi yang harus dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini. Setiap perjumpaan dengan Tuhan, di mana ada “pewahyuan”, senantiasa mempunyai dimensi misi dan panggilan. Misi dan panggilannya adalah memberikan makna hidup di dunia. Misi dan panggilan itu berwujud nilai-nilai yang bersifat absolut, yang diwahyukan Tuhan sendiri. Makna hidup itu dibuktikan dengan perbuatan seseorang dalam dunia.102 Manusia diminta untuk setia melakukan misi memberikan makna hidup di dunia. Kesetiaannya menunjukkan bahwa dirinya terus berada dalam hubungan dengan Tuhan. Semakin tekun misi yang ia bawakan, semakin dekat perjumpaannya dengan Tuhan. Dengan demikian baginya, pelaksanaan nilai absolut sebagai wujud misi dan panggilan untuk memberi makna bagi dunia, tidak mungkin tanpa pewahyuan dari Tuhan.103 Namun Buber mengingatkan bahwa mungkin saja seseorang kembali “ke belakang”, yaitu melakukan kembali hubungan “Aku-Itu”. Boleh jadi ia tetap berbicara tentang Tuhan, tetapi ketika tindakannya sudah tidak mewujudkan misi dan panggilan Tuhan, ia sebenarnya berada di dalam dunia “Itu”. Seseorang yang merasa melakukan nilai-nilai dari Tuhan, padahal 102 Martin Buber, I T, h. 164. Sylvain Boni, The Self and The Other In the Ontologies of Sartre and Buber, 1982, Univ Press of America:Washington, h.160. 103 97 98 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama tidak demikian, disebutnya sebagai dikendalikan oleh “False absolutes”. Apa yang dimaksudkan dengan “absoluditas palsu”? Absoluditas palsu menurutnya adalah sesuatu yang dianggap seseorang sebagai absolut, sehingga nilai-nilainya diikuti, padahal sesuatu itu bukanlah Tuhan, karena satu-satunya yang absolut adalah Tuhan. Ada ketergantungan pada “absoluditas palsu”. Dan “absoluditas palsu” itu mengendalikan dirinya. Buber memang tidak memastikan dengan jelas kemungkinan apa dan siapa yang bisa menjadi “absoluditas palsu” itu. Bisa saja berupa delusi, atau nabi-nabi palsu seperti dalam Kitab Suci atau dorongan lingkungan di mana seseorang hidup.104 2. Aspek-aspek Hubungan Manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan mempunyai berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah pribadi dan Tuhan adalah pribadi mutlak. Kenyataan ini membawa hubungan manusia dengan Tuhan pada hubungan timbal balik. Manusia bisa berjumpa dan menyapa Tuhan karena Tuhan adalah pribadi. Demikian juga sebaliknya. Ada beberapa aspek yang melandasi hubungan tersebut, yaitu : 2.1. Aspek Perjumpaan (Encounter) Seperti telah dijelaskan pada bab III, bagi Buber yang real dan aktual adalah “ruang antara” yang ada di antara dua orang yang saling berjumpa dalam suatu hubungan timbal balik. “Ruang antara” itulah yang menjadi “jembatan’ agar dua pribadi dapat berjumpa. Lewat perjumpaan seseorang dapat mengenal Tuhan. Baginya pengenalan 104 Nampaknya pemikiran ini dipakai Buber untuk membalikkan apa yang dikatakan oleh Feuerbach bahwa Tuhan hanyalah proyeksi manusia belaka; Tuhan adalah absoluditas palsu yang disembah oleh manusia. Tuhan adalah angan-angan manusia tentang hakikatnya sendiri. Angan-angan itu sedemikian sempurna sehingga dianggap absolut dan akhirnya disembah manusia. Lewat pemikirannya Buber mau mengatakan bahwa manusialah yang seringkali menjadi absoluditas palsu. BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber akan Tuhan tidak didapatkan dari pengajaran-pengajaran dogmatis tentang Tuhan atau konsep-konsep yang dirumuskan semata oleh akal budi, melainkan dari perjumpaan dengan Tuhan. Berangkat dari konsep Buber bahwa yang real dan aktual adalah “ruang antara”, maka perjumpaan menjadi pengalaman yang real. Pengalaman tersebut tidaklah mungkin diterangkan secara memuaskan melalui akal budi. Pengalaman tersebut jauh lebih kaya dibandingkan apa yang dapat ditangkap oleh akal budi Namun dalam perjumpaan dengan Tuhan, Buber mengemukakan bahwa ada dua posisi yang bisa mereduksikan atau meleburkan satu pihak kepada yang lain. Posisi pertama adalah pihak “diri” (self ) direduksikan oleh perasaan ketergantungan kepada Tuhan.105 Ia memang tidak menampik bahwa perasaan ini akan ada sebagai elemen dasar dari perjumpaan dengan Tuhan karena bagaimanapun manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Perasaan sebagai mahkluk ciptaan yang bergantung kepada Penciptanya, merupakan sesuatu yang wajar. Ia mempertanyakan, manusia memang membutuhkan Tuhan setiap saat, namun apakah Tuhan tidak membutuhkan manusia? Tuhan membutuhkan manusia untuk memberikan makna bagi kehidupan ini, sekaligus menunjukkan bahwa di dunia ini ada sifat “Ilahi” yang sedang bekerja. Perasaan ketergantungan hanya akan mereduksikan satu pihak kepada yang lainnya, dan sekaligus mereduksikan nilai dari hubungan itu sendiri. Ucapan Yesus yang mengatakan “Aku dan Bapa adalah satu” mencerminkan posisi yang pertama ini. Kesatuan antara Yesus dengan Bapa adalah kesatuan oleh karena ketergantungan Yesus kepada Bapa. Hubungan tersebut tidak didasarkan pada posisi yang setara. Perjumpaan tersebut mewakili posisi “atas” dan “bawah”. Yang satu memberikan perintah, dan yang lainnya melakukan tanpa syarat. Posisi kedua adalah kebalikan dari posisi pertama. Tuhan, atau 105 Martin Buber, I T, h. 129-131. 99 100 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama “Yang Ilahi” direduksikan menjadi “diri”. “Diri” bukan lagi sebagai cerminan atau pantulan dari Yang Ilahi, melainkan “diri” itu sendiri adalah representasi dari Tuhan. Posisi ini secara jelas dapat ditemukan dalam mistik India. Dalam agama Buddha, gelar Buddha diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan pencerahan sempurna. Tuhan menjadi dirinya. Buber secara tegas menolak apabila perjumpaan antara manusia dengan Tuhan didasarkan pada dua posisi tersebut. Baginya kedua posisi itu sangat menyesatkan. Ia menyebutkan dua alasan. Alasan pertama adalah kedua posisi tersebut merusak prinsip dasar bahwa realitas terletak hanya pada perjumpaan yang dibangun di atas dasar dua identitas yang berbeda dan bersifat timbal balik. Alasan kedua adalah kedua posisi itu memisahkan hidup manusia menjadi dua bagian, ada manusia “tinggi”, yang sudah mendapatkan pencerahan sempurna (bersatu dengan Tuhan) dan manusia “rendah” yang belum mendapatkan pencerahan sempurna.106 Sesuatu yang real akhirnya menjadi hilang. Bagaimana mungkin masih akan ada perjumpaan jika Tuhan direduksikan atau melebur menjadi “Aku” dan sebaliknya? Padahal yang real adalah “ruang antara” yang ada dalam perjumpaan itu. Bagi Buber hubungan yang didasarkan pada perasaan ketergantungan akan mendeaktualisasikan salah satu pihak. Demikian juga dengan praktek religiusitas yang dijalankan oleh aliran mistisisme tertentu yang bersifat magis, terutama lewat tradisi pengorbanan. Baginya mistisisme yang diisi dengan hal-hal yang bersifat magis tidak pernah benar-benar mewujudkan perjumpaan dengan Tuhan. Yang ada justru adalah dunia “Itu”. Ketika seseorang memberikan pengorbanan, maka yang ada di dalam benaknya adalah pengorbanan itu diberikan agar Tuhan tidak mendatangkan hukuman dan memberikan kelimpahan. Yang tersirat dalam pengalaman 106 Robert E. Wood, op.cit, h. 94. BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber itu adalah bahwa manusia “memperalat” Tuhan dengan memberikan pengorbanan agar tidak mendatangkan hukuman, dan Tuhan memperalat manusia dengan menakut-nakuti lewat hukuman agar manusia memenuhi permintaannya untuk mengorbankan sesuatu. Tidak ada aspek perjumpaan di dalamnya. Yang ada adalah unsur ketakutan. Manusia melakukan ritual pengorbanan karena manusia takut akan dihukum atau dihancurkan oleh Tuhan jika tidak melakukannya. Atau sebaliknya, manusia melakukan ritual pengorbanan untuk memuaskan hati Tuhan sehingga Tuhan mau memberikan apa saja yang diminta manusia. Di samping menolak mistisisme seperti itu, Buber juga menolak praktek mistisisme yang hanya diisi dengan praktek-praktek meditasi. Baginya manusia tidak perlu mempelajari cara berdoa dan praktek meditasi untuk berjumpa dengan Tuhan. Ajaran-ajaran agama mengenai cara berdoa dan meditasi pada akhirnya dapat menjadi “dogma” yang membelenggu seseorang, seolah-olah tanpa praktek seperti itu ia tidak akan dapat berjumpa dengan Tuhan. Apalagi mistisisme yang mengajarkan untuk memalingkan diri dari dunia agar dapat berjumpa dengan Tuhan. Menurutnya Tuhan tidak dapat dijumpai dengan memalingkan diri dari dunia. Justru dengan “masuk” ke dalam dunia, dalam arti melakukan hubungan “Aku-Engkau” seseorang dapat berjumpa dengan Tuhan. Di sini ia mengingatkan umat beragama agar tidak terjebak pada ritual agama tanpa pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan hanya bersifat real jika berada dalam hubungan dialogis “Aku-Engkau”. Dalam perjumpaan dengan “Engkau” seseorang dapat melihat dan merasakan cahaya anugerah Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam perjumpaan tersebut bersifat pasti. 101 102 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama 2.2. Aspek Kebebasan (Freedom) Menurut Buber, Tuhan dan manusia berhadap-hadapan dalam perjumpaan dalam kebebasan. Tuhan mengakui kebebasan manusia dihadapannya. Pemahaman ini sekaligus menambah kritik Buber terhadap perasaan ketergantungan mutlak manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan. Perasaan ketergantungan menghambat kebebasan yang seharusnya ada dalam suatu hubungan dialogis. Manusia diberikan kebebasan untuk menjawab kepada Tuhan. Tanpa kebebasan, secara dasariah manusia tidak akan dapat menjawab keterbukaan Tuhan terhadap dirinya. Lewat jawaban itulah manusia membentuk diri dan menunjukkan eksistensinya. Bagi Buber ada sisi eksistensial dalam setiap jawaban seseorang terhadap keterbukaan Tuhan. Apakah kebebasan itu mencakup masalah bagaimana manusia memahami Tuhan? Ia menjawab dengan mengatakan bahwa pemahaman tentang Tuhan pun merupakan bagian dari kebebasan manusia. Lewat kebebasannya itu manusia mengembangkan pemahaman tentang Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memahami dirinya. Tuhan membuka diri-Nya dan membiarkan manusia mengembangkan pemahaman itu secara bebas. Tuhan tidak memberikan pemahaman yang sudah baku dan kaku. Buber kembali mengambil contoh saat Tuhan membuka siapa dirinya kepada Musa. Ketika Tuhan mengatakan bahwa diri-Nya adalah “Aku yang akan hadir dan terus akan hadir”107, terdapat makna implisit bahwa ada suatu proses bagi manusia untuk memahami Tuhan. Nama Tuhan itu lebih menunjukkan suatu proses keterbukaan yang Tuhan berikan kepada manusia, dari pada satu nama baku yang statis. Ada kekuatan, suara dan senTuhan Tuhan yang mengalir terus dalam pengalaman keseharian manusia. Dalam proses ini manusia diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban melalui apa yang dialaminya sehari-hari. 107 Martin Buber, I T, h.160. BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber Sisi eksistensialis Buber terlihat lewat aspek kebebasan ini. Berhadapan dengan Tuhan manusia tetap mempunyai kebebasan. Dalam kebebasan untuk menjawab keterbukaan itu, manusia menyatakan makna yang diperolehnya dalam perjumpaan dengan Tuhan. Makna itu hanya dapat dinyatakan dalam keunikan “adanya” masingmasing individu. Dalam tindakan masing-masing tersimpul jawaban terhadap keterbukaan Tuhan. 108 Makna itu bukan untuk “dunia yang akan datang” atau kehidupan “yang lain” yang bukan di dunia ini, sebagaimana seringkali dipahami secara salah oleh kaum beragama, melainkan untuk “dunia saat ini”. Menurutnya, manusia menjalani kehidupan di dunia ini; kalau pun ada makna yang ia rajut makna itu seharusnya untuk kehidupannya di dunia ini. Dalam kehidupan yang fana inilah manusia merajut makna hidupnya. Makna itu berarti bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga berarti bagi dunia yang fana ini. Untuk itu Buber tidak setuju jika dikatakan bahwa makna hidup yang dirajut manusia hanya diperuntukkan bagi dunia yang baka, seperti yang banyak dipahami umat beragama. Mengapa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia? Tidakkah kebebasan tersebut justru akan disalahgunakan oleh manusia untuk menjauhi Tuhan? Buber menjawab dengan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia agar manusia dapat menjadi pribadi yang dapat menyambut uluran tangan Tuhan dalam suatu dialog. Mitra Tuhan dalam dialog sejati dengan dirinya, mestilah merupakan mitra yang berlandaskan kebebasan sehingga dengan kebebasannya ia dapat memilih dari berbagai alternatif keputusan yang ada. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, Tuhan adalah Pribadi Mutlak yang senantiasa menempatkan diri dalam hubungan. Hubungan itu dijalin dengan pribadi yang lain, yang walaupun tidak bersifat mutlak namun dapat menyambut dialog itu, yaitu manusia. Sedangkan pribadi 108 Martin Buber, I T, h.159. 103 104 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama yang berada di dalam hubungan “Aku-Engkau” adalah pribadi yang bebas. Dengan demikian tentunya manusia pun sebagai pribadi yang melakukan hubungan dengan Tuhan mempunyai kebebasan. Manusia tidak mendapati dirinya sebagai objek Tuhan, melainkan sebagai mitra dialog. Sebagai mitra dialog, manusia bebas untuk mengaktualisasikan siapa dirinya, termasuk jika manusia “menjauh” dari Tuhan atau menutup telinganya sehingga tidak dapat mendengar suara Tuhan. Itu adalah konsekwensi kebebasan. Kebebasan adalah suatu kebaikan yang hakiki, yang memungkinkan manusia berhubungan dengan manusia lain dalam situasi saling menghormati sebagai pribadi. Dan hidup berdampingan seperti itu tidak tanpa resiko kegagalan dan penolakan. Termasuk terhadap Tuhan. Namun bagaimanapun manusia bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambilnya, termasuk penolakan terhadap Tuhan. Buber cenderung melihat hal ini sebagai bagian dari proses siklis dialog manusia dengan Tuhan. 2.3. Aspek Dialog Buber membuka buku I and Thou dengan tulisan : “Bagi manusia, dunia berada dalam keadaan berlipat ganda, merujuk kepada dua sikap dasar yang dimiliki manusia…dan dua sikap dasar itu berhubungan dengan dua jenis kata-kata dasar yang digunakan”109 Pernyataan pembuka ini menggariskan bahwa eksistensi manusia dibangun di atas dasar hubungan yang bersifat komunikatif. “Sikap dasar” yang dimaksud olehnya bukan hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana 109 ”The world is twofold for man in accordance with his twofold atitude. The attitude of man is twofold in accordance with two basic words he can speak” (Martin Buber, I T, h.50. BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber seseorang berkomunikasi. Lewat komunikasi seseorang memasuki hubungan dengan orang lain. Komunikasi menjadi pembuka bagi suasana dialogis diantara dua pribadi. Dengan komunikasi yang dibangun seseorang mempersekutukan diri dengan orang lain.110 Lalu bagaimana dengan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan dirinya sendiri? Buber mengatakan bisa saja komunikasi seperti itu terjadi, namun itu bukanlah dialog yang sesungguhnya. Dialog yang sesungguhnya terjadi melalui komunikasi di antara dua pribadi. Dengan mengutip apa yang dikatakan Feuerbach, ia mengatakan bahwa dialektika yang benar bukanlah komunikasi monolog antara seseorang dengan dirinya sendiri, melainkan dialog antara “Aku-Engkau”.111 Setelah manusia berjumpa dengan Tuhan dan manusia diberikan kebebasan di dalam perjumpaan itu, maka aspek selanjutnya adalah manusia berdialog dengan Tuhan. Bagi Buber, perjumpaan antara Tuhan dengan manusia adalah perjumpaan yang bersifat dialogis. Tuhan “mewahyukan” diri dan manusia menjawab keterbukaan Tuhan yang diterimanya melalui pewahyuan tersebut. Atau dengan kata lain keterbukaan Tuhan di jawab manusia dengan keterbukaan juga. Manusia membuka diri terhadap Tuhan. Buber mengatakan bahwa : 110 Dalam catatan kaki terhadap kalimat pembuka Buber, Alexander Kohanski berpendapat bahwa kata“attitude” lebih tepat bila dimengerti pertama kali sebagai komunikasi (communication) dari pada sebagai suatu sikap yang berasal dari reaksi psikologis ketika berhadapan dengan orang lain. Dengan mengemukakan kata ini, Buber mencari landasan ontologis pertemuan seseorang dengan dunia, sesama dan Tuhan. Kata yang dipakai Buber adalah Haltung dan kata ini sekaligus menunjuk pada komunikasi.(Lih. Alexander Kohanski, Martin Buber’s Philosophy of Interhuman relation, 1982, h.224). Salah seorang filsuf paling terkemuka Jerman abad 20, Jürgen Habermas, juga mengatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan dasar manusia dengan sesamanya sebagai sesama subyek. Tindakan komunikatif bersifat dialogal di antara dua subyek. Di samping itu tindakan dasar lain yang terdapat pada manusia adalah tindakan rasional bertujuan, yaitu tindakan manipulatif yang biasa dilakukan terhadap alam dan mengambil bentuk subyek-obyek (lih. F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi, 1990, Kanisius:Yogyakarta, h. 89). 111 Martin Buber, BMM, h.46. 105 106 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama “Dialog yang sejati (mempunyai) kemampuan berbicara dari kepastian ke kepastian, tetapi juga dari pribadi yang berhati terbuka ke pribadi yang lain, yang juga berhati terbuka.”112 Di sini Buber menegaskan bahwa proses komunikasi yang terjadi, bukan hanya melibatkan bahasa verbal, melainkan melibatkan hati. Melalui dialog seseorang melakukan “pembalikan” (turning, Kehre), untuk mulai mendengarkan dan memperhatikan semata-mata hanya orang lain, seolah-olah tidak ada momen lain pada saat itu. Untuk itu aspek “melibatkan hati” menjadi sangat penting tatkala dua orang melakukan dialog. Demikian juga dengan dialog antara manusia dengan Tuhan. Tuhan berbicara dan menyapa manusia bukan hanya secara verbal belaka, tetapi melibatkan hati manusia. Manusia menjawab sapaan Tuhan dengan segenap hati. Dalam keseluruhan hidup manusia, Tuhan melakukan dialog. Jawaban manusiapun mencakup keseluruhan hidupnya, bukan hanya sebagian saja. Buber memberikan contoh mengenai Abraham dan Musa. Tuhan berbicara baik kepada Abraham maupun Musa. Dan keduanya menjawab bukan hanya dengan bahasa verbal, melainkan dengan keterlibatan hati dan seluruh kepribadiannya. Totalitas itulah yang seharusnya ada di dalam diri seseorang yang menjalankan dialog dengan Tuhan. Ia mengatakan bahwa dialog bersifat aktual dan kongkret bila berada dalam rangkaian waktu.113 Dengan demikian totalitas yang ada di dalam diri seseorang yang menjalin dialog dengan Tuhan harus terlihat dalam kehidupan kongkret dirinya sepanjang waktu. Perwujudan hal 112 “…genuine dialogue speech from certainty to certainty, but also from one open-hearted person to another open-hearted person”. (Martin Buber, BMM, h. 24.) 113 Martin Buber, BMM , h.19. BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber itu adalah persekutuan (communion).114 Persekutuan antara manusia dengan Tuhan berarti adanya dialog trus menerus. Dan persekutuan itu, menurut Buber, bukan hanya persekutuan mistik belaka, di mana dengan mengasingkan diri seseorang merasa sudah mencapai persekutuan dengan Tuhan melainkan dengan persekutuan dengan sesama dalam rangkaian waktu sehari-hari yang dilaluinya. Dalam salah satu contohnya ia mengemukakan 115 : andaikan bahwa ada dua orang yang saling bertemu. Namun keduanya tidak saling berdialog. Perhatian orang yang satu tidak ditujukan kepada orang yang lainnya. Apakah dengan demikian yang satu akan memahami kehendak dan keinginan yang lain? Memang “komunikasi” dapat terjadi. Tetapi hanya di dalam “keheningan”. Yang satu “menahan” diri terhadap yang lain. Dengan memberikan contoh seperti itu, Buber mau mengatakan bahwa memang komunikasi dapat terjadi secara mistis (dalam keheningan), namun komunikasi seperti itu tidak dapat secara utuh menangkap dan “mengetahui” keberadaan mitra dialognya. Tatkala manusia berdialog dengan Tuhan dalam kehidupan kongkret sehari-hari, maka manusia akan mengerti kehendak dan keinginan Tuhan. Menurutnya, dialog dengan Tuhan tidak dapat didasarkan pada pewahyuan yang “tiba-tiba”, seperti seseorang yang sebelumnya lupa akan sesuatu, kemudian tiba-tiba memperoleh ilham sehingga yang lupa itu dapat diingat kembali. Dengan “ilham yang tiba-tiba” itu, orang kemudian berharap mendapatkan teofani dan dengan teofani itu ia merasa sudah berdialog dengan Tuhan. Dialog dengan Tuhan tidak mungkin didasarkan pada situasi seperti itu. Kalau pun dipahami Musa mendapatkan “pewahyuan tiba-tiba” karena Tuhan yang mendadak menemuinya, maka itu harus dipahami sebagai awal dari proses terjadinya dialog. Teofani Tuhan yang sesungguhnya mengambil tempat dalam komunitas dengan persekutuan yang berangkat dari 114 Martin Buber, BMM, h.21. Martin Buber, BMM, h. 20. 115 107 108 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama suatu dialog yang sungguh-sungguh. Dan Musa melakukan hal itu ketika ia berangkat untuk melanjutkan proses dialog dengan Tuhan dalam kehidupan komunitasnya. Dialog antara Tuhan dengan Musa berlangsung dengan latar belakang kehidupan religius komunitas Israel. Namun Buber tidak mau mengajarkan doktrin pewahyuan dengan mengkritik “pewahyuan tiba-tiba” seperti itu. Ia hanya mau menyodorkan hubungan “Aku-Engkau”sebagai tempat di mana Tuhan mewahyukan dirinya. Menurut Buber hal inilah yang seringkali menyebabkan orang modern tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dipahami hanya mungkin melalui “pewahyuan tiba-tiba”. Manusia berharap Tuhan tiba-tiba muncul di hadapan dirinya, sehingga dengan peristiwa itu ia bisa segera percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada. Hal ini seperti orang yang menatap ke langit dalam kabut awan yang gelap dan tebal dan berharap tiba-tiba ada cahaya meteor yang bersinar. Hubungan dengan Tuhan tidak dapat dipahami dalam kaca mata seperti itu. Menurutnya satu-satunya cara untuk berhubungan dan berdialog dengan Tuhan adalah dengan “mengalami”, mengalami langsung hubungan itu. 116 Dan pengalaman itu diperoleh dengan keterlibatan dirinya dalam dialog dengan sesama. Dalam hubungan “Aku-Engkau” ada tanda kehadiran Tuhan. Tanda itu menunjukkan keterbukaan dan sapaan Tuhan untuk berdialog dengan manusia. Seseorang harus berusaha keras agar hubungan “Aku-Engkau” dapat terwujud dengan sungguh-sungguh. Dan ia pun harus berusaha agar pengalaman “Aku-Engkau” menjelma menjadi dialog dengan Tuhan. 116 Ada pertanyaan dasar yang mengemuka berkaitan dengan pemahaman Buber bahwa orang harus mengalami sendiri hubungan dengan Tuhan, yaitu : apakah hubungan itu dapat dibuktikan? Buber tidak menjawab pertanyaan itu, namun Brendan Sweetman mengatakan bahwa hal itu tidak akan dapat dibuktikan oleh Buber dan bukan hanya Buber, tetapi setiap orang tidak akan dapat membuktikan itu. Buber, atau orang yang menjalani hubungan itu, hanya dapat mengalami dan menjadikannya sebagai jaminan bagi kehidupannya. (Lih. Brendan Sweetman, op.cit, h. 157). BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber Adanya Tuhan yang berdialog dengan manusia tidaklah perlu dibuktikan, hanya perlu“dialami”. Demikian pula dengan adanya “sesuatu” di antara manusia dengan Tuhan yang menjadikan “gerhana Tuhan”.117 “Gerhana Tuhan” dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tegas Buber mengatakan bahwa dalam setiap hubungan “Aku-Engkau” sebenarnya manusia dengan “mengalami” hubungan dengan Tuhan, termasuk mereka yang menamakan diri ateis. Setiap orang yang melangkah memasuki “ruang antara”, ia sekaligus berhubungan dengan Tuhan. Hanya dengan menjalin hubungan “Aku-Engkau” seseorang berada dalam proses mewujudkan dirinya sebagai pribadi. Dan hal itulah yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa manusia memberi makna pada dirinya sebagai “ada” yang berada di dunia. Dalam proses seperti itulah Tuhan hadir. Dialog merupakan perwujudan pewahyuan Tuhan di dalam dunia. Dalam dialog senantiasa ada semangat baru dan pembaharuan bagi manusia untuk memberi makna bagi kehidupan yang dijalaninya. Namun sejarah dunia, yang di dalamnya terdapat pewahyuan dan jawaban manusia, bukanlah sejarah yang bergerak secara linear melainkan spiral. Maksudnya adalah dalam menjalankan dialog dengan Tuhan, seseorang tidak mungkin berada pada garis lurus yang menanjak. Tatkala hubungan itu kembali pada titik “Aku-Itu”, dibutuhkan titik balik atau perputaran agar kembali pada hubungan “Aku-Engkau”. 118 Untuk itu walaupun dunia modern mengalami gerhana Tuhan, Buber yakin bahwa akan ada titik balik, di mana dorongan untuk menyatukan diri dengan Tuhan muncul. 117 118 Martin Buber, EoG, h. 127. Robert E. Wood, op.cit, h.109. 109 110 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama 3. Kesimpulan Hubungan “Aku-Engkau” membawa manusia pada hubungan “Aku-Engkau Absolut”. “Engkau Absolut” adalah merupakan “Ada” yang tidak terbatas, yang kehadirannya melampaui dua orang yang menjalin hubungan “Aku-Engkau”. Kehadiran “Ada” sebagai “Engkau Absolut” dalam hubungan “Aku-Engkau” tidak terpisahkan. Buber mengatakan bahwa “Engkau Absolut” adalah Tuhan. Tuhan adalah “Ada” yang tidak terpisahkan ketika manusia menjalin hubungan “AkuEngkau” dengan sesamanya. Untuk itu pengalaman seseorang dalam hubungan “Aku-Engkau” dapat membawa dirinya pada pengalaman menjalin hubungan dengan Tuhan. Unsur apiori yang ada di dalam diri manusia, memampukan dirinya untuk “mentransendensikan” pengalaman akan yang terbatas menuju pada yang tidak terbatas. Namun pemahaman ini sekaligus membuka satu pertanyaan, tidakkah unsur a priori yang mentransendensikan itu hanya merupakan proses proyeksi dari diri manusia, seperti yang dikatakan oleh Feuerbach bahwa manusia memproyeksikan adanya Tuhan melalui sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam dirinya?. Tuhan membuka diri kepada manusia dalam hubungan “AkuEngkau” sehingga dalam hubungan “Aku-Engkau”, “Engkau Absolut” dapat dijumpai. Keterbukaan diri Tuhan tersebut membuka peluang bagi manusia untuk “menjawabnya”. Dengan demikian dialog kemudian dapat berlangsung. Jawaban manusia ditunjukkan dengan keputusan-keputusan yang diambilnya. Dan keputusan itu berkaitan dengan masalah-masalah yang berada di dalam dunia ini. Lewat keputusan itulah manusia memberikan makna kepada dunia. Dengan demikian hubungan manusia dengan Tuhan terjadi agar manusia dapat merealisasikan diri dalam memberi makna kepada dunia. Perealisasian diri merupakan misi dan panggilan Tuhan yang harus dilakukan seseorang. Sebagaimana dua pribadi bertemu, maka keinginan dan kehendak masing-masing pribadi harus diperhatikan. Kehendak dan keinginan BAB V Hubungan antara Manusia dengan TuhanMenurut Martin Buber Tuhan diwujudkan dalam panggilan agar manusia merealisasikan diri sebagai pribadi yang sejati. Perealisasian diri itu diwujudkan dengan perbuatan-perbuatannya di dunia ini, baik terhadap sesama maupun alas semesta. Jejak-jejak realisasi diri manusia dalam memberi makna bagi dunia terlihat dari keputusan, sikap dan tanggapan manusia terhadap sesamanya dan lingkungan hidup. Namun adakah perbedaan bagi Buber ketika ada orang yang memberikan keputusan, sikap dan tanggapan yang tepat terhadap orang lain dan lingkungan, tanpa sedikitpun ia merasa tengah berhubungan dengan Tuhan? Manusia berjumpa dengan Tuhan. Dalam perjumpaan itu manusia mempunyai kebebasan untuk melanjutkan hubungan atau menolaknya. Ketika manusia memutuskan untuk melanjutkan hubungan maka kebebasan menjadi dasar bagi dialog yang akan terjadi antara manusia dengan Tuhan. Lewat proses itulah persekutuan antara manusia dengan Tuhan dibangun. Dan hal itu hanya dapat “dialami”. Seseorang tidak mungkin menggambarkan Tuhan hanya dengan rasionya. Pengalamanlah yang akan berbicara mengenai masalah itu. Dalam pengalaman itu, “hati” (heart) menjadi jembatan yang penting dalam menyatukan keduanya, sehingga komunikasi beralih menjadi persekutuan. Dua pribadi yang berdialog haruslah membuka hatinya. Hanya dialog yang dilandasi oleh keterbukaan hati yang akan menghasilkan persekutuan. Demikian juga dalam hal berdialog dengan Tuhan. Keterbukaan Tuhan menunjukkan keterbukaan “hati” Tuhan. Untuk itu, manusia pun diminta untuk menunjukkan keterbukaan yang sama. Hati yang terbuka terhadap Tuhan dalam seluruh pengalaman hidup, diwujudkan dengan keterbukaan terhadap sesama. Setelah kita memahami pemikiran Buber mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, maka pada bagian berikutnya sebagai bagian terakhir dari tesis ini, akan ditarik beberapa kesimpulan, yang akan disertai dengan beberapa catatan kritis. 111 BAB VI Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian pemikiran Buber sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Kenyataan bahwa Buber mendapatkan pendidikan religius yang cukup dalam dari kakek neneknya dan pengalamannya berhubungan dengan hasidisme sangat mempengaruhi pemikiran Buber. Didikan kakek-nenek dan orang tuanya, serta hubungannya dengan tokoh Hasidisme membentuk Buber menjadi pribadi yang religius. Untuk itu pemikiran Buber pertama kali harus dilihat sebagai pemikiran religius. Pengalaman-pengalaman dan penelahaan kitab suci membawanya pada keyakinan yang kuat mengenai keberadaan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Berangkat kenyataan seperti itu Buber mencoba untuk bertanya bagaimana keyakinan tersebut ditempatkan dalam struktur hubungan manusia dengan Tuhan. Uraian-uraian Buber mengenai hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” merupakan pijakan dasar yang dipakainya untuk menguraikan struktur hubungan manusia 113 114 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dengan Tuhan. Pemahamannya mengenai sisi transenden manusia, berangkat dari pengalaman iman yang dimilikinya. 2. Ada dua hubungan dasar yang dijalani manusia, yaitu “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”. “Aku-Itu” adalah hubungan sepihak, di mana “Aku” memperalat, mengobjekkan dan memperlakukan “Itu” semata-mata hanya untuk keinginan dan kehendakku saja. “Aku” tidak memperhatikan “Itu” sebagai sesama yang setara dengan “Aku”. Sedangkan hubungan “Aku-Engkau” dibangun di atas dasar kesetaraan, dialogis dan timbal balik, yang diliputi oleh cinta. Masing-masing pihak saling memperhatikan harapan, keinginan dan kehendak sesamanya. Dialog yang terjadi di antara “Aku” dan “Engkau” memungkinkan bergesernya komunikasi menjadi persekutuan. “Aku-Engkau” adalah hubungan antara subjek dengan subjek, karena itu dialog yang terjadi pun adalah dialog subjeksubjek. Pribadi yang satu membuka dirinya terhadap pribadi yang lain. Tanda utama yang terdapat dalam hubungan “Aku-Engkau” adalah cinta. Cinta merupakan pengarahan diri terus menerus kepada orang lain. Lewat cinta seseorang ingin memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya bagi orang lain dan mau menerima keberadaan orang lain. Cinta diwujudkan lewat tanggung jawab seseorang terhadap sesamanya yang lain. 3. Hubungan “Aku-Engkau” dapat merupakan salah satu dasar untuk berjumpa dengan Tuhan. Lewat perjumpaan dengan sesama, seseorang dapat mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan hadir melalui “ruang antara” yang ada di dalam hubungan “Aku-Engkau. Memang bisa saja seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lewat aspek mistik. Namun perjumpaan itu belumlah lengkap. Tanpa pijakan dari hubungan dengan sesama maka perjumpaan dan dialog antara manusia dengan Tuhan akan menjadi dialog yang kosong. Aspek “panggilan” dan BAB VI Penutup “pengutusan” senantiasa meminta agar manusia terbuka terhadap sesama. Dalam keterbukaan itu terdapat kesetaraan, subjek dengan subjek. “Aku” tidak mengobjekkan “Engkau” semata-mata demi pemuasan keinginan dan nafsuku. Melainkan menerima “Engkau” dengan segala keberadaannya termasuk harapan dan keinginnya. Dengan demikian bersama dengan sesama manusia, seseorang bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Namun hubungan manusia dengan Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Mengapa? Karena dasar hubungan ini, yaitu “Aku-Engkau” dapat tergelincir menjadi “Aku-Itu”. Dalam hubungan “Aku-Itu” tidak ada “Engkau Absolut” yang dapat dijumpai oleh seseorang. 4. Dalam hubungan “Aku-Engkau” terdapat “ruang antara” yang menghubungkan “Aku” dengan “Engkau”. “Ruang antara” merupakan realitas sesungguhnya, di mana aktualitas manusia nampak. Aktualitas yang menunjukkan adanya aktivitas intensif, di mana “Aku” berdialog dan menyapa “Engkau”. Pada “ruang antara” inilah, seseorang menyadari keberadaan dirinya karena adanya hubungan dialogis. Adanya tanggapan yang setara dari “Engkau” menyadarkan seseorang akan keberadaannya. Di sinilah anugerah Tuhan hadir. Adanya anugerah Tuhan pada ruang antara ini, menyebabkan seseorang dapat merasakan dan menjumpai Tuhan dalam hubungan “Aku-Engkau”. Dalam setiap hubungan “AkuEngkau” ada anugerah Tuhan. Kehadiran Tuhan dapat dirasakan karena manusia mempunyai sisi transenden. Hal ini memungkinkan manusia untuk mentransendensikan pengalamannya kepada yang “Tak Terbatas”, sehingga perjumpaan dengan Tuhan melalui pengalaman hidup sehari-hari bukan sesuatu yang tidak mungkin. 5. Untuk itu Tuhan tidak dapat direduksi hanya menjadi objek akal budi dan rasio semata. Menentukan keberadaan Tuhan atau hubungan Tuhan dengan manusia hanya melalui rasio tidak dapat 115 116 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dilakukan. Tuhan yang hanya sekedar dipikirkan manusia melalui rasio, adalah objek bagi manusia. Dengan pola itu manusia menjalankan hubungan “Aku-Itu” dengan Tuhan. Manusia menjadikan Tuhan sebagai “Itu”, padahal Tuhan tidak akan pernah dapat menjadi “Itu. Manusia menganggap dengan menjalankan pola seperti itu, ia sudah berjumpa dengan Tuhan, padahal kenyataannya tidak demikian. Tuhan tidak dapat “ditemukan” melalui konsep-konsep hasil rasio manusia, Tuhan hanya dapat “dijumpai” dalam pengalaman kongkret manusia. Sebelum berbicara mengenai konsep, manusia selayaknya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dunia “Itu” adalah dunia objek, dan di dalamnya tidak ada perjumpaan. Tuhan tidak dapat dijumpai dalam pola hubungan “Aku-Itu”. Gambaran-gambaran Tuhan yang dirumuskan oleh rasio hanya mereduksikan kekayaan pengalaman yang sesungguhnya. Hanya melalui pengalaman kongkret seseorang dapat berjumpa dan berhubungan dengan Tuhan. Pengalaman ini melebihi rasio manusia. Tuhan yang hanya sekedar diperoleh lewat olah rasio bukanlah Tuhan yang hadir dalam pengalaman eksistensial manusia. Tuhan seperti itu adalah Tuhan yang terpisah dari realitas kehidupan sehari-hari. Perjumpaan manusia dengan Tuhan adalah perjumpaan dialogis, di mana manusia dapat menyapa Tuhan sebagai “Engkau”, demikian juga Tuhan memperlakukan manusia sebagai “Engkau”. Dalam keadaan seperti itulah komunikasi dapat berlangsung. 6. Perjumpaan manusia dengan Tuhan adalah dialog antara pribadi dengan pribadi. Tuhan haruslah seorang pribadi agar dapat menjalin hubungan dengan manusia. Hanya pribadi yang bisa berada dalam hubungan “Aku-Engkau”. Hubungan “Aku-Engkau” yang dialami diantara sesama manusia menjadi analogi bagi hubungan manusia dengan Tuhan. Jika dalam hubungan “Aku-Engkau” manusia berhubungan dengan pribadi lain, maka dalam hubungan BAB VI Penutup “Aku-Engkau Absolut”, Tuhan juga merupakan pribadi. Namun pribadi Tuhan berbeda dengan manusia. Jika manusia adalah pribadi yang masih dalam proses menjadi pribadi yang sejati dalam perjumpaannya dengan sesama dan Tuhan, maka Tuhan adalah Pribadi yang tidak membutuhkan apapun lagi untuk membuat diri-Nya menjadi Pribadi Sejati. Tuhan adalah Pribadi Mutlak. Dalam perjumpaan dengan “Aku”, Pribadi Mutlak membentuk “Aku” lewat keinginan dan kehendak-Nya yang diwahyukan melalui pengalaman perjumpaan itu sendiri. Tuhan membuka diri-Nya kepada manusia dan dengan keterbukaan itu, terbuka pula kesempatan bagi manusia untuk menjawabnya. Di sinilah kemudian nampak kebebasan manusia. Manusia bebas untuk memberikan jawaban dan memilih di antara berbagai alternatif pilihan, termasuk jika ternyata manusa menolak kehadiran Tuhan. Keputusan manusia terhadap masalah itu akan memberi makna bagi dunia ini, sekaligus menunjukkan proses perealisasian dirinya. Perealisasian diri untuk menjadi pribadi merupakan proses bagaimana seseorang “memanusiakan dirinya sendiri”. Tatkala seseorang berada dalam proses “memanusiakan diri”, Tuhan berjumpa dengan membentuknya. Lewat proses itulah seseorang memberi makna terhadap kehidupannya dan dunia tempat ia hidup. 2. Beberapa Catatan Kritis Apa yang dipikirkan Buber tentu memberikan beberapa sumbangan penting dalam membentuk kerangka hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhan. Dengan menjelaskan struktur hubungan “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”, Buber memberikan dasar penting mengenai hubungan sehari-hari yang dijalani oleh manusia. Bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari keduanya, itu merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Namun hal itu bukanlah dasar 117 118 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama agar manusia dapat mempertahankan pola hubungan “Aku-Itu” dalam setiap situasi dan terhadap apapun. Aktualitas manusia ditentukan oleh hubungan “Aku-Engkau”. Di sanalah realitas diri seseorang menunjukkan artinya. Hal penting berikutnya yang disampaikannya adalah bahwa perjumpaan manusia dengan Tuhan adalah perjumpaan antara pribadi. Manusia sebagai pribadi, berjumpa dengan Tuhan sebagai Pribadi Mutlak. Gambaran perjumpaan yang disampaikannya menunjukkan bahwa Tuhan sebagai Pribadi Mutlak adalah Tuhan yang dekat dengan manusia, yaitu Tuhan yang dapat disapa sebagai “Engkau”, Tuhan yang membentuk manusia untuk mengaktualisasikan dirinya dan Tuhan yang memberikan kebebasan terhadap manusia. Tuhan seperti ini adalah Tuhan yang melebihi apa yang mampu dimengerti dan dirumuskan oleh rasio. Dalam perjumpaan sehari-hari dengan sesama manusia melalui hubungan “Aku-Engkau”, Tuhan pun turut hadir. Anugerah Tuhan hadir dalam setiap “ruang antara” yang tejalin di antara dua pribadi. Walaupun Buber memberikan sumbangan pemikiran yang cukup besar dalam struktur hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhan, namun ada beberapa catatan kritis yang patut ditujukan kepadanya. 2.1. Pengaruh Pemikiran Mistisisme : Penolakan Gambaran Tuhan sebagai Objek Rasio Buber memang memberikan kritik yang tajam terhadap dunia mistisisme, khususnya yang terdapat dalam Hasidisme. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, inti ajaran Hasidisme adalah pentingnya menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, mencintai Tuhan dan sesama, peka terhadap wahyu Tuhan dan menekankan doa sebagai unsur terpenting untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Namun dalam BAB VI Penutup perjalanannya Hasidisme hanya mementingkan aspek asketis dan bersifat ekslusif. Menurutnya mistisisme tidak dapat memulai perjumpaan dengan Tuhan hanya melalui askese atau perjumpaan secara pribadi, tetapi melalui hubungan “Aku-Engkau” yang melibatkan pengalaman keseharian manusia dengan sesamanya. Namun walau Buber memberikan kritik terhadap mistisisme, pikirannya sendiri sangat dipengaruhi oleh mistisisme. Pengaruh mistisisme Yahudi menyebabkan pemikiran Buber berangkat dari keyakinan imannya bahwa Tuhan sungguhsungguh hadir dan berjumpa dengan manusia. Dengan keyakinan seperti itu ia berusaha untuk menjelaskan struktur hubungan manusia dengan Tuhan. Persekutuan antara manusia dengan Tuhan yang diidentifikasi oleh Buber melalui hubungan “Aku-Engkau Absolut” lebih mengarah pada persekutuan mistis. Persekutuan ini memang terejawantah dalam hubungan kongkret manusia dengan sesamanya, namun bagaimanapun seringkali pengalaman satu orang dengan yang lainnya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan bersifat sangat pribadi. Setiap orang dapat mengambil kesimpulan yang berbedabeda terhadap pengalaman perjumpaan tersebut. Untuk itu ia menolak segala bentuk penggambaran Tuhan melalui konsep dan rumusan hasil pemikiran atau rasio. Pengalaman yang sangat personal belum tentu dapat dirumuskan dan dikonsepkan secara sempurna dengan memakai bahasa. Bahasa belum dapat mengungkapkan kekayaan pengalaman seseorang, sehingga perumusan dan pengonsepan atas pengalaman akan Tuhan, justru dapat mengurangi kekayaan pengalaman itu sendiri. Yang dapat dilakukan seseorang adalah “menunjukkan” bahwa pengalaman itulah wujud “penggambaran” Tuhan, yang melebihi konsep manusia. Pengaruh mistisisme ini membawa Buber menolak pengonsepan Tuhan.119 119 Di samping mempelajari mistisisme Yahudi, Buber juga pernah mempelajari mistisisme Hindu dan Buddha. Dalam mistisisme Hindu, misalnya, ideal moral yang mengarahkan seseorang pada Yang Ilahi dipahami sebagai sebuah transendensi. Devosi terhadap Yang Ilahi mampu membawa jiwa seseorang melampaui kebaikan 119 120 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama Jika demikian apa akibatnya bagi setiap pemahaman manusia tentang Tuhan? Oleh karena perjumpaan dengan Tuhan bersifat sangat pribadi maka penggambaran tentang Tuhan pun akan bersifat relatif. Dalam memahami Tuhan, setiap orang akan mendasarkan diri pada pengalaman dirinya, yaitu pengalaman yang menunjuk pada perjumpaan dirinya dengan Tuhan. Sementara itu, bagi Buber pengalaman melebihi rasio dan bersifat tidak terbantahkan. Dengan demikian pemahaman setiap orang akan Tuhan yang didasarkan pada pengalaman dirinya bersifat tidak terbantahkan. Akibatnya adalah menutup kemungkinan akan setiap perdebatan dan diskusi mengenai pemahaman tentang Tuhan. Setiap perdebatan dan pembicaraan tentang Tuhan tidak akan berjalan dengan baik, karena setiap orang akan cenderung untuk membenarkan pemahamannya sendiri (yang bersifat relatif tersebut). Lalu bagaimana menjelaskan hal ini, jika dikaitkan dengan pemahaman Buber mengenai absoluditas Tuhan. Charles Hartshorne mengatakan bahwa Buber melupakan satu kenyataan bahwa apa yang aku pahami mengenai Tuhan, itulah yang aku lakukan dalam pengalaman sehari-hari. Apa yang aku pahami mengenai Tuhan terungkap dalam bentuk konsep dan penggambaranpenggambaran tertentu. Bahwa pengalaman kemudian memberikan pemahaman lebih lanjut, pemahaman ini yang akan menjadi dasar bagi tindakanku kemudian.120 Menurut Hartshorne, Tuhan yang disapa dan kejahatan yang ada di dunia. Upaya eksistensial ini pada akhirnya tetaplah sebuah misteri, sebab segala kepintaran manusia tidak akan mampu memberikan pembenaran yang memuaskan. (Lih. John McKenzie, Hindu Ethics, A Historical and Critical Essay, 1922, Oxford Univ. Press:Oxford, khususnya hal 203-216.). Namun penolakan Buber terhadap pengonsepan Tuhan dapat pula dilihat sebagai pengaruh Kierkergaard. Buber sejak masih muda sudah membaca Kierkergard. Kierkergaard sendiri berpendapat bahwa kredo dan doktrin tentang Tuhan seringkali menjadi berhala bagi manusia, bertujuan pada dirinya sendiri bahkan membatasi dan menggantikan realitas Tuhan yang tidak mungkin tergambarkan. (Lih. Martin Buber, EoG, 1971, h. 115) 120 Charles Hartshorne, Martin Buber’s Metaphysics, dlm. The Philosophy of Martin Buber, ed. Paul A. Schillp, 1967, h.50. BAB VI Penutup oleh seseorang dalam pemikiran Buber adalah Tuhan hasil transendensi. Proses transendensi hanya bisa terjadi melalui kejadian-kejadian atau benda-benda yang bersifat “terbatas” dan “biasa”. Hasil dari proses transendental itu kemudian dirumuskan oleh seseorang walaupun hanya dalam bentuk perenungan dan hasilnya adalah sebutan “Tuhan”, kepada Realitas Transenden Absolut. Masalahnya adalah bukankah setiap hasil perumusan akan bersifat mereduksi setiap pengalaman yang sesungguhnya? Keberatan berikutnya dari Hartshorne adalah soal pengetahuan tentang Tuhan. Ketika seseorang menjalin hubungan dengan Tuhan, maka ia harus mengenal Tuhan dibandingkan orang lain. Seseorang hanya dapat mengenal Tuhan sejauh pengetahuannya mencukupi atau memadai untuk mengenal Tuhan. Tanpa itu pengenalan seperti apa yang dapat dilakukannya? Untuk itu mengutamakan pengalaman dengan mengecilkan arti pengetahuan seseorang tentang Tuhan tidaklah tepat. Berkaitan dengan peran akal budi dalam menggambarkan Tuhan, Louis Leahy berpendapat bahwa akal budi dipakai untuk mengungkap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Pendapatnya itu dirumuskan dengan beberapa argumen, pertama bahwa tujuan akal budi adalah “Totalitas Ada” yang dapat dimengerti.121 Artinya dalam setiap pernyataan akal budi ada tendensi menuju pada pemahaman akan “Totalitas Ada”. Namun dengan sebutan “dapat dimengerti” bukan berarti “Totalitas Ada” tersebut bersifat terbatas. “Totalitas Ada” bersifat tidak terbatas. Mengapa disebut tidak terbatas? Karena tidak mungkin totalitas inteligibel yang berupa objek penalaran tersebut bersifat terbatas. Kalau saja diandaikan akal budi tahu bahwa ia bersifat terbatas, tentu akal budi manusia sudah melampauinya. Totalitas seperti itu pasti tidak akan memuaskan akal budi. Kedua bahwa “Totalitas ada” yang dapat dipahami tersebut bersifat transenden. Maksudnya adalah bahwa 121 Louis Leahy, Filsafat KeTuhanan Kontemporer, 1991, h.92. 121 122 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama “Totalitas ada” itu tidak sama seperti kumpulan “ada-ada” terbatas yang menjadi satu. Jika seluruh yang terbatas dijadikan satu, tetap saja sifatnya akan terbatas dan tidak akan bisa menjadi tidak terbatas. Orang masih akan tetap memikirkan sesuatu yang bersifat tidak terbatas. Ketiga Totalitas ada itu mestilah bereksistensi. Mengapa? Karena jika ia tidak bereksistensi maka ia berada dalam wilayah ketidakmungkinan. Atau jika tidak ada “ada” (yang terbatas) yang dapat membuatnya bereksistensi (karena ia totalitas ada yang tidak terbatas), maka ia juga termasuk wilayah ketidakmungkinan. Totalitas ada itu adalah Tuhan, sebagai tujuan tertinggi dan objek yang memadai dari pemahaman akal budi manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi Leahy Tuhan memang dapat dijadikan objek akal budi manusia. Sebagai objek akal budi upaya manusia untuk memahami Tuhan dapat didiskusikan, diperdebatkan dan dikembangkan oleh manusia. Apa yang dikatakan oleh Leahy secara tidak langsung membantah pendapat Buber. Penggambaran dan pengonsepan Tuhan dengan memakai akal budi tidak mengurangi pengalaman eksistensial seseorang berhubungan dengan Tuhan, kecuali kalau konsep itu dimutlakkan dan dianggap sebagai kebenaran satu-satunya tentang Tuhan. Akal budi tidak mungkin memikirkan Tuhan tanpa menjadikannya sebagai objek pemikiran. Jika Tuhan mewahyukan dirinya kepada manusia, maka mestilah pewahyuan itu dapat pula ditangkap oleh akal budi atau rasio. Bagaimana pengalaman itu dimengerti, tentunya menggunakan akal budi. Rudolf Otto mengatakan bahwa jika seseorang mengonsepsikan Tuhan, maka Tuhan bagi dirinya merupakan Tuhan yang bisa digapai dan dipikirkan melalui akal budi dan sekaligus diperdebatkan. Baginya, bahasa dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan setiap pengalaman religius.122 Seseorang membutuhkan bahasa untuk meng122 Rudolf Otto, The Rational dan The Non-Rational, dlm. The Problem of Religious Language, ed. MJ. Charlesworth,1974, Prentice Hall-New Jersey BAB VI Penutup ungkapkan pengalaman religiusnya.123 Tanpa itu tidak mungkin ia dapat mengungkapkan pengalaman religiusnya. 2.2. Dasar Ontologis Buber menarik satu dasar ontologis hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu pada hubungan atau relasi, yang di dalamnya terdapat “ruang antara” sebagai wujud hubungan itu. Baginya apa yang termuat dalam realitas, yaitu “ruang antara” itu, adalah “Aku” dan “Engkau”. Jika hubungan merupakan sesuatu yang real, maka “Aku” dan “Engkau” yang terdapat dalam hubungan itu mestilah merupakan sesuatu yang real pula, termasuk Tuhan. Tentu merupakan sesuatu yang sangat menarik jika ia meletakkan “hubungan” sebagai dasar ontologis untuk menjelaskan struktur hubungan manusia dengan Tuhan. Namun dasar ontologis ini tidak didukung dengan penjelasan sistemik dan terstruktur mengenai Tuhan dan manusia. Ia bisa saja menghindari penjelasan ontologis mengenai Tuhan, untuk menghindari “pengonsepan” yang telah ditolaknya terlebih dahulu. Namun ia tidak menjelaskan secara kongkret bagaimana seseorang mampu untuk mengatakan “Aku” pada dirinya sendiri terlebih dahulu, untuk memasuki misteri hubungan dengan “Engkau”. Dasar ontologis, yaitu “ruang antara” yang terdapat dalam hubungan, tercipta di antara “Aku” dan “Engkau”. Memang ia kemudian mengatakan bahwa “Aku” menjadi “Aku” dalam hubungan 123 Untuk mengurangi kritik yang ditujukan kepadanya berkaitan dengan penolakannya mengenai konsep dan penggambaran Tuhan, Buber mengemukakan kepada Malcolm Diamond, seorang profesor filsafat agama di Princeton Universiy bahwa pengalaman religius manusia jauh lebih kaya dibandingkan dengan kemampuan bahasa untuk mengungkapkannya. Namun bukan berarti penggambaran dan pengonsepan tidak perlu. Ketika seseorang hendak mengungkapkan pengalaman itu kepada orang lain, mau tidak mau ia harus mengonsepkan dan menggambarkannya supaya orang lain mengerti. Namun hendaknya penggambaran itu dalam bentuk paradoks. Karena itu satu-satunya cara untuk menggambarkan Tuhan. (Lih. Maurice Friedman (III), op.cit, h.256) 123 124 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama dengan “Engkau”. Namun pertanyaannya adalah “Aku” seperti apa yang dipahami, ketika pertama kali memulai hubungan dengan “Engkau”? Alexander Kohanski mengatakan bahwa dasar ontologis hubungan manusia dengan Tuhan, menurut Buber, diletakkan pada “ruang antara” yang terletak dalam hubungan “Aku-Engkau”. Lewat hubungan “Aku-Engkau”, seseorang menjumpai dan berhubungan dengan Tuhan dan mengidentifikasikannya sebagai “Engkau”. Namun dasar ontologis ini justru melemahkan posisi Buber yang sejak awal menolak penggambaran dan pengonsepan Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana mungkin seseorang bisa membedakan “Engkau” dari “Itu” tanpa menggambarkannya atau mengkonsepkannya?124 Jika seseorang mampu membedakan “Engkau” dari “Itu”, tentu karena ia telah mempunyai suatu gambaran atau deskripsi terlebih dahulu. Ketika seseorang kembali pada hubungan “Aku-Itu”, akankah dasar ontologis itu menjadi hilang? Dan jika dasar ontologis itu hilang, maka akan banyak fase di mana perjumpaan dengan Tuhan tidak terjadi. Apa yang dikatakan Kohanski memberikan suatu gambaran bahwa ketika seseorang melakukan hubungan “Aku-Itu” dengan orang lain, belum tentu Tuhan tidak dapat ia jumpai oleh dirinya. Buber mengatakan bahwa hubungan “Aku-Itu” tidak mungkin manusia hindari. Dengan demikian suatu fase di mana manusia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan, memang tidak mungkin dihindari. Namun Buber sendiri mengatakan bahwa hubungan “Aku-Itu” berguna bagi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Lalu, apakah dalam ilmu pengetahuan dan filsafat Tuhan tidak dapat menjumpai manusia? Apakah pembentukan Tuhan terhadap diri manusia tidak dapat dijumpai dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat? Dengan mengatakan bahwa hubungan “Aku-Itu” dalam ilmu pengetahuan dan filsafat berguna bagi manusia untuk mengembangkan diri, maka ada 124 Alexander Kohanski, Martin Buber’s Philosophy of Interhuman Relation, 1982, h.107. BAB VI Penutup suatu “fase” hubungan “Aku-Itu” yang terarah pada “Aku-Engkau”. Apakah Tuhan mutlak tetap tidak dapat dijumpai dalam fase ini? Emil L. Fackenheim mengatakan bahwa seharusnya “Aku-Itu” dilihat juga dalam hubungan dialektik dengan “Aku-Engkau”. Dengan konsep dialektika “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau”, Tuhan tetap dapat hadir melalui “Aku-Itu”, yang terarah pada “Aku-Engkau”.125 Jadi “Aku-Itu” tetap dapat dilihat sebagai bagian dari proses “Aku” yang sedang membentuk diri menjadi “manusia”. 2.3. Mengenal Aku dan Mengenal Engkau: Sisi Epistemologis Relasi ‘Aku-Itu’ potensial memunculkan kekerasan kepada orang lain, yang akhirnya menghancurkan relasi di antara keduanya. Ada struktur epistemologis dalam pemikiran Buber, yaitu bahwa pengenalan akan orang lain membawa sikap positif. Mari kita lihat: pertama, berkaitan dengan aspek epistemologis. Proses pengenalan yang gagal dalam diri seseorang terhadap sesamanya menjadi salah satu akar munculnya masalah kekerasan. Jika seseorang menganggap orang lain sebagai “itu” berarti ada proses yang gagal dalam pengenalannya terhadap orang itu. “Engkau” dalam proses pengenalan itu merupakan rekonstruksi dari “Aku”. Kemudian muncul satu pertanyaan : dari mana aku memperoleh isi pengenalan yang aku konstruksikan terhadap orang lain? Apakah isi pengenalan itu merupakan sesuatu yang diberikan sistem atau struktur sosial yang ada di sekitar kita?Jika benar maka, relasi “Aku-Itu” dan “Aku-Engkau” juga berada dalam konteks konstruksi social sekitar. Apabila mengikuti alur pemikiran Behaviorisme, misalnya F.B. Skinner126, seseorang mendapatkan pengenalan atas 125 Emil F. Fackenheim, Buber’s Concept of Revelation, dlm. Martin Buber’s Philosophy, ed. Paul A. Schillp, 1967, h. 295 126 Lih. Uraian Franz Magnis-Suseno tentang F.B. Skinner dalam buku Tokohtokoh Etika Abad 20, Gramedia:Jakarta. 125 126 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama orang lain oleh karena bentukan sistem atau lingkungan yang ada. Jika demikian maka struktur epistemologis yang ada adalah struktur epistemologis suatu sistem atau lingkungan. Itu permasalahan pertama berkaitan dengan aspek epistemologis. Permasalahan kedua adalah adanya kekerasan sebaga kegagalan aku dalam pengenalan terhadap orang lain, membawaku pada keterikatan dalam satu struktur yang lebih besar, yaitu struktur massa tertentu yang pada akhirnya besifat destruktif. Nah, sekarang kalau yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu aku berusaha keluar dan menolak massa tersebut, apakah tidak akan terjadi kekerasan. Hegel mengemukakan bahwa masalah kekerasan, sebagai akibat pola “Aku-Itu” merupakan masalah human conflict. Human conflict ini terjadi karena proses pengenalan yang ada di dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk komunal, tetapi mereka mereka justru menemukan essensinya hanya dengan melepaskan diri dari komunalitas itu. Being for Itself hanya dapat ditemukan dengan menolak lingkungan komunal. Kekerasan bisa terjadi tatkala proses penolakan ini terjadi. Kekerasan dari aku terhadap orang lain sebagai akibat pola “Aku-Itu” yang berada dalam lingkungan komunal itu.. Bagi Hegel penolakan atas komunalitas itulah yang potensial memunculkan kekerasan. Barangkali aspek kekerasan di sini sudah agak bergeser, bisa ke arah kekerasan individu. Dari pertanyaan ini sebenarnya bisa muncul pertanyaan lain, yaitu kita sedang berada dalam proses mengenali orang lain, tetapi bagaimana mungkin dalam proses mengenali orang lain, orang yang kita kenali itu dihancurkan. Proses pengenalan itu sendiri kemudian dihancurkan dengan tindakan menghancurkan orang lain! Akhirnya yang terjadi adalah langkah mundur, termasuk pengenalan diri. Padahal siapapun yang memposisikan diri berada dalam relasi Aku-Engkau, ia berada dalam aktualitas. Atau dengan kata lain aktualitas dari Aku ditunjukkan dengan berpartisipasi dalam hubungan BAB VI Penutup Aku-Engkau. Semakin sempurna Aku berpartisipasi, semakin aktual Aku menjadi. Semakin memberikan Engkau ruang gerak, semakin memberikan Aku ruang gerak. Aku membutuhkan Engkau untuk menjadi; dalam menjadi Aku, Aku mengatakan Engkau.127 Bagaimana kepenuhan manusia sebagai manusia tergantung dari sejauh mana relasi Aku-Engkau. 2.4. Kondisi “Aku” yang Menjalin Hubungan Buber tidak mengemukakan “Aku” seperti apa yang bisa mengadakan hubungan yang ideal dengan “Engkau”. Kalaupun ia mengemukakan syarat-syarat dalam berhubungan dengan “Engkau”, yaitu “Aku” yang tidak memperalat, mengobjekkan atau menjadikan “Engkau” hanya sebagai pemuas keinginan, maka syarat itu adalah syarat yang berupa “tindakan apa apa yang seharusnya “Aku” lakukan dalam hubungan itu”. Ia tidak mengemukakan syarat, “Aku” seperti apa yang memungkinkan hubungan ideal itu. Adalah faktor ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi? Dalam menjalankan hubungan dengan orang lain maupun dengan Tuhan, setiap manusia akan dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi dan politik. Bagaimana hubungan ideal “Aku-Engkau” dapat terjadi jika faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial diperhitungkan? Bukankah latar belakang ekonomi, politik dan sosial dapat memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap hubungan itu? Latar belakang Buber adalah keluarga yang mapan dan berada. Walaupun ia diasuh beberapa tahun oleh kakek dan neneknya karena kedua orang tuanya bercerai, namun ia dibesarkan dengan pendidikan yang baik dan kecukupan materi. Belum lagi lingkungan sosial komunitasnya Yahudi yang cukup ideal membentuk diri Buber. Walaupun sebagai orang Yahudi Buber sempat mengalami “ketakutan” menghadapai kekejaman Nazi, namun 127 “I require a You to become; becoming I, I say You”. P.62. 127 128 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama ia berhasil lolos dan mendapatkan perlindungan. Semua faktor itu memungkinkan Buber mencari formula ideal dalam struktur hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama. Lalu bagaimana dengan orang miskin dan tak berpendidikan yang harus berjuang memeras keringat dan tenaga untuk sekedar mencari sesuap nasi? Mampukah ia menjalankan hubungan “Aku-Engkau” dengan sebaik-baiknya, sementara dalam pikirannya yang ada hanyalah mencari sesuap nasi? Buber melupakan suatu kecenderungan bahwa dalam keadaan miskin, teraniaya dan tertindas oleh seseorang bisa menjadi brutal. Beberapa catatan kritis di atas menunjukkan bahwa pemikiran Buber masih menantang untuk dikembangkan dan dilengkapi. Dengan keyakinan imannya, ia mencoba menjelaskan struktur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ia menekankan bagaimana lewat perjumpaan dengan sesama, seseorang dapat berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan sesama lewat hubungan “Aku-Engkau” mempertegas prinsip humanisme Buber bahwa orang lain bukanlah objek kepentingan semata, melainkan sesama manusia yang setara dan mempunyai makna bagi pembentukan diriku. Dalam pemikiran Buber ada penghargaan terhadap sesama manusia. Namun sekaligus Buber mengingatkan bahwa tindakan semena-mena terhadap sesama manusia, tidaklah mencerminkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Daftar Pustaka Buber, Martin, I and Thou, trans. Walter Kaufmann, 1970, Charles Scribner’s Son:New York. ------------------, 1979, Eclipse of God, Humanities Press:New Jersey. ------------------, 1947, Between Man and Man, Fontana Library : London ------------------, 1949, The Prophetic Faith, Harper and Row : New York. -----------------, 1958, Moses, The Revelation dan The Covenant, Harper and Row : New York. -----------------, 1974, Pointing The Way, Shocken Book:New York. Bergman, Shmuel Hugo, 1991, Dialogical Philosophy From Kierkergaard to Buber, State University New York Press:New York. Bertens, Kees, 1983, Filsafat Barat Abad XX, Inggris-Jerman, Gramedia:Jakarta. Boni, Slyvain, 1982, The Self and The Other in The Ontologies of Sartre and Buber, University Press of America:Washington. 129 130 Wahju S. Wibowo ✴ Aku, Tuhan dan Sesama Drijarkara, 1989, Percikan Filsafat, PT. Pembangunan Jaya:Jakarta. Engels, Friedrich, 1969, Feuerbach and The End of Classical German Philosophy, Progress Publisher:Moscow. Friedman, Maurice, 1982, Martin Buber’s Life and Work 1878-1923, Search Press : London. ------------------------, 1983, Martin Buber’s Life and Work 19231945, E.P Dutton: New York. -----------------------, 1983, Martin Buber’s Life and Work 19451965, E.P. Dutton: New York. Hadiwijono, Harun, 1993, Teologi Reformatoris abad XX, BPK GM: Jakarta. Hamersma, Harry, 1991, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, Gramedia:Jakarta. Inwood, Martin, 2000, Heidegger Dictionary, Blackwell: United Kingdom Kohanski, Alexander, 1982, Martin Buber’s Philosophy of Interhuman Relation, Assosiated Univ. Press:New Jersey. Leahy, Louis, 1993, Filsafat KeTuhanan Kontemporer, Kanisius:Yogyakarta. McKenzie, John, Hindu Ethics, A Historical and Critical Essay, 1922, Oxford Univ. Press:Oxford, Macquarrie, John, 1972, Existentialism, Pelican Book:New York. Magnis-Suseno, Franz, 1999, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Gramedia:Jakarta. Mumford, Lewis, 1985, The Myth of The Machine, dlm. Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, YOI : Jakarta Daftar Pustaka Otto, Rudolf, 1974, The Rational dan The Non-Rational, dlm. The Problem of Religious Language, ed. MJ. Charlesworth, Prentice Hall-New Jersey Sartre, Jean-Paul, 2000, Kata-kata, Gramedia;Jakarta. Schilpp, Arthur; Paul/Maurice Friedman (ed), 1967, The Philosophy of Martin Buber, Cambridge Univ. Press : Cambridge. Sevilla, Pedro, 1970, God as Person in the Writings of Martin Buber, Loyola House:Manila. Sweetman, Brendan, Martin Buber’s Epistemology, dlm. International Philosophical Quarterly, Vol.XLI, No.2, Issue No.162 ( June 2001) van Peursen, C.A, 1988, Strategi Kebudayaan, Kanisius:Yogyakarta. Vermes, Pamela, 1980, Buber on God and the Perfect Man, Scholar Press:California. West, David, 1996, An Introduction to Continental Philosophy, Blackwell:Cambridge Wood, Robert E, 1969, Martin Buber’s Ontology, Northwestern University Press:Evanston. 131

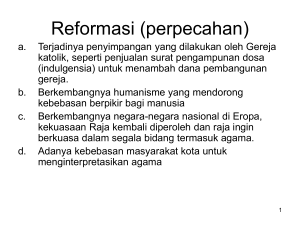
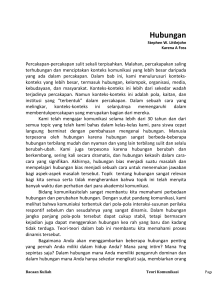

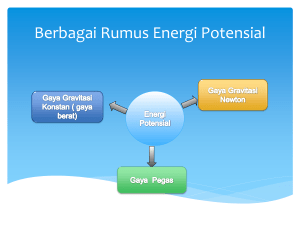
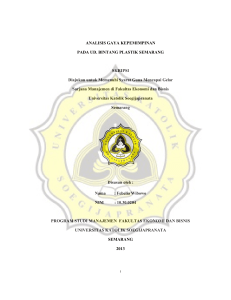
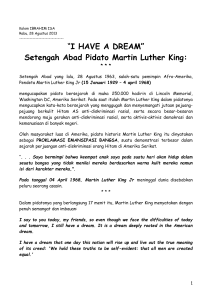
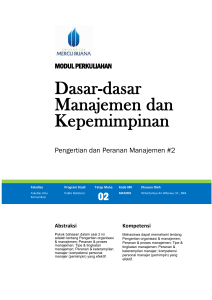
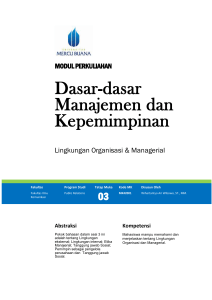
![Modul Statistika Sosial [TM2]](http://s1.studylibid.com/store/data/000443912_1-6728616ae6fc3879714e07e0f0c68e32-300x300.png)