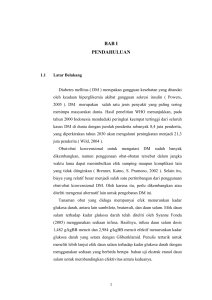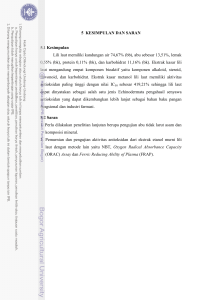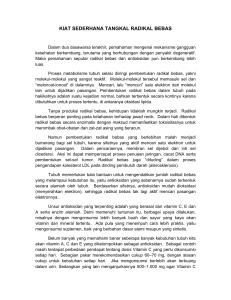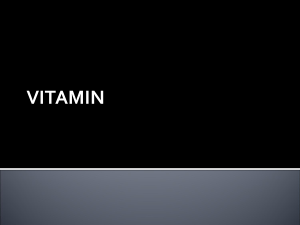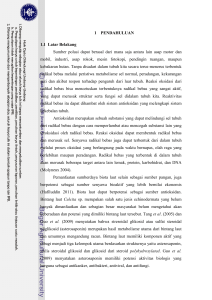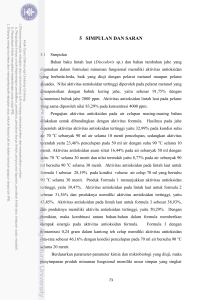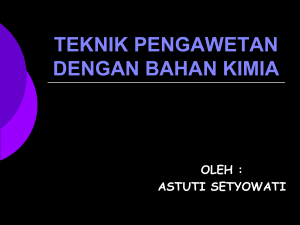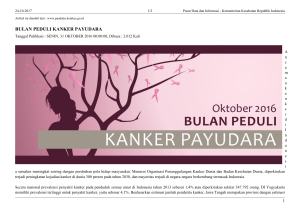Uploaded by
ShaniaAs
Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksik Ekstrak Kulit Buah Mangga Kasturi
advertisement

AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN SITOTOKSIK EKSTRAK KULIT BUAH MANGGA KASTURI (Mangifera casturi) TERHADAP SEL KANKER PAYUDARA MCF7 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Proposal Skripsi Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Mar’atus Sholihah 1643050085 FAKULTAS FARMASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI KIMIA BAHAN ALAM JAKARTA NOVEMBER 2019 HALAMAN PENGESAHAN Proposal Skripsi AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN SITOTOKSIK EKSTRAK KULIT BUAH MANGGA KASTURI (Mangifera casturi) TERHADAP SEL KANKER PAYUDARA MCF7 Disusun Oleh Mar’atus Sholihah 1643050085 Telah disetujui, Pembimbing Utama (Rabima, M. Farm, Apt) Tanggal: 14 November 2019 ii Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Kata Pengantar Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karna atas segala nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga proposal skripsi yang berjudul ”Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksik Ekstrak Kulit Buah Mangga Kasturi (Mangifera casturi) Terhadap Sel Kanker Payudara MCF7” dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu. Proposal skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 1 Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selain itu proposal skripsi ini juga sebagai bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengenyam pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dalam penulisan proposal skripsi ini banyak sekali pihak yang membantu ataupun membimbing, sehingga dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Ibu Dr. Diana Laila Ramatillah, M. Farm., Apt. selaku dekan Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta . 2. Bapak Drs. Wahidin, M.Si., Apt. selaku kepala Program Studi Sarjana Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 3. Ibu Rabima, M.Farm, Apt Selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 4. Ibu Rabima, M.Farm, Apt dan Bapak Sogandi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan, motivasi serta saran-saran yang sangat bermanfaat bagi penulis. 5. Kedua Orang tua, kakak yang senantiasa memberikan dorongan semangat, materi, dan doa sehingga menjadikan motivasi untuk penulis. 6. Kepada Ariq Ramadhan tersayang yang telah banyak membantu dan selalu sabar menemani dalam penyusunan proposal skripsi ini I Love You. iii Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 7. Teman- teman seperjuangan skripsi Andi Ristiawan Sholih, Joni Suryo, Ka Sella, Ka Dora. Squad IND (Dewi, Nelly Deana, Silvia) yang telah banyak memberikan masukan serta saran selama penyusunan proposal skripsi. Serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terimakasih. Saya telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini untuk mencapai hasil yang terbaik. Saya menyadari skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Jakarta, November 2019 Penulis iv Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................ i LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................... ii KATA PENGANTAR .............................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................. V BAB I : PENDAHULUAN........................................................................ 1 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ..................................................................... 2 1.3 Tujuan Penelitan........................................................................ 3 1.4 Manfaat Penelitian .................................................................... 3 1.5 Hipotesis.................................................................................... 3 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 4 2.1 Tumbuhan Kasturi (Magnifera Casturi) ................................... 4 2.1.1 Klasifikasi Tumbuhan Kasturi ........................................ 4 2.1.2 Morfologi Tanaman ........................................................ 5 2.1.3 Kandungan Kimia ........................................................... 6 2.2 Ekstrasi dan Fraksinasi .............................................................. 8 2.2.1 Metode Ekstrasi Dingin .................................................. 8 2.2.2 Metode Ekstrasi Panas .................................................... 9 2.2.3 Fraksinasi ........................................................................ 10 2.3 Kandungan Total Flavonoid ...................................................... 11 2.4 Kandungan Total Fenol ............................................................. 10 2.5 Antioksidan ............................................................................... 12 2.5.1 Macam-macam Antioksidan (Sayuti et al, 2015) ........... 12 2.5.2 Vitamin C ........................................................................ 13 2.5.3 Uji Antioksidan ............................................................... 14 2.6 Antikanker ................................................................................. 16 2.6.1 Pengertian Kanker Payudara ........................................... 17 2.6.2 Sel Kanker MCF7 ........................................................... 17 v Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 2.6.3 Etiologi Kanker Payudara ............................................... 18 2.6.4 Patofisiologi Kanker payudara......................................... 18 2.6.5 Pengobatan Kanker (Radji, 2016) ................................... 19 2.6.6 Mekanisme Antikanker (Radji, 2016) ............................. 21 2.6.7 Doxorubisin...................................................................... 22 2.6.8 Uji Aktivitas Antikanker ................................................. 23 2.6.9 Apoptosis ........................................................................ 24 2.6.10 Anti Proliferasi .............................................................. 24 2.5 GC-MS (Gass Chomatography – Mass Spectrocopy) .............. 24 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN ............................................. 26 3.1 Metode Penelitian ..................................................................... 26 3.2 Tempat dan Waktu .................................................................. 26 3.3 Sampel .................................................................................... 26 3.4 Alat dan Bahan .......................................................................... 26 3.4.1 Alat ................................................................................... 26 3.4.2 Bahan ............................................................................... 27 3.5 Prosedur Kerja ........................................................................... 27 3.5.1 Determinasi Simplisia ...................................................... 27 3.5.2 Ekstraksi ........................................................................... 27 3.5.3 Fraksinasi ......................................................................... 28 3.5.4 Skrining Fitokimia ........................................................... 28 3.5.5 Uji Total Kandungan Flavonoid....................................... 31 3.5.6 Uji Total Kandungan Fenolik........................................... 32 3.5.7 Uji Antioksidan ................................................................ 33 3.5.8 Uji Antikanker.................................................................. 35 3.5.8.1 Persiapan Larutan Uji ........................................... 35 3.5.8.2 Persiapan Kultur Sel MCF7 ................................. 35 3.5.8.3 Uji Proliferasi dengan MTT ................................. 36 3.5.8.4 Apoptosis ............................................................. 36 3.5.8.5 Perhitungan Persen Inhibisi.................................. 37 vi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 3.5.8.6 Analisa Data ......................................................... 37 3.4.8 Identifikasi Kandungan Senyawa Fraksi Kulit Buah Kasturi (Mangifera casturi) dengan menggunakkan Gass Chomatography – Mass Spectrocopy (GC-MS) .................................................... 38 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 39 LAMPIRAN ............................................................................................... 46 vii Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian khusus di bidang kedokteran dan kesehatan, hal ini disebabkan karena belum ditemukan cara efektif untuk mengobatinya. Kanker dapat diartikan sebagai suatu kelompok besar penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel abnormal yang bertumbuh di luar batas wajarnya, kemudian melakukan penyebaran ke organ lain dan menyerang bagian-bagian tubuh yang berdekatan (Sunaryanti, 2011). Penyakit kanker dengan presentase tertinggi di Indonesia adalah kanker payudara sebesar 0,5% dan kanker serviks sebesar 0,8% (Kemenkes RI, 2015). Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kanker seperti merokok, terpapar radiasi, terinfeksi virus, terpapar hormon dengan kadar tinggi, memiliki riwayat penyakit kanker dan radikal bebas . Radikal bebas mempunyai sifat sangat labil dan reaktif sehingga menimbulkan kerusakan sel seperti DNA, lipid, protein dan karbohidrat. Radikal bebas merupakan suatu molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbit terluarnya (Septiana et al, 2017). Dapat diartikan bahwa radikal bebas memiliki sifat toksik terhadap sel-sel dan molekul biologis di dalam tubuh karena radikal bebas berusaha mengambil elektron dari molekul sekitarnya. Radikal bebas yang mengambil elektron dari DNA dapat menyebabkan gangguan lipid pada dinding sel, pembuluh darah, produksi prostaglandin dan protein lain nya sehingga struktur DNA berubah dan menimbulkan sel mutan. Bila mutasi ini terjadi berlangsung lama dapat menjadi kanker (Werdhasari, 2014). Terdapat beberapa jenis pengobatan terhadap kanker salah satunya adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah penggunaan obat-obatan baik dalam bentuk injeksi, ataupun tablet minum untuk mematikan sel-sel kanker (Yudissanta, 2012). Selain menggunakkan pengobatan secara klinis dengan 1 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 2 menggunakkan bahan kimia, pengobatan secara tradisional menggunakan bahan alam juga sering dilakukan. Pengobatan tradisional biasanya menggunakkan ramuan ramuan yang berasal dari akar, kulit batang, kayu, daun, buah, kulit buah, biji, dan bunga (Sukandar, 2008). Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengobatan kanker adalah buah mangga (Mangifera indica L.). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lauricella (2019) menyatakan bahwa buah mangga (Mangifera indica L.) memiliki aktivitas sebagai antikanker (Lauricella et al, 2019). Indonesia kaya akan sumber daya alam nabati maupun hewani yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Banyak jenis tumbuhan Indonesia yang dapat digunakan sebagai obat, salah satunya dengan tumbuhan kasturi (Mangifera casturi). Mangifera casturi merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan dan termasuk dalam tumbuhan langka. Pada kulit batang kasturi (Mangifera casturi) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri S.aureus dan E.coli. (Rosyidah, 2012) .Penelitian terdahulu menyatakan bahwa daun tumbuhan kasturi (Mangifera casturi Kosterm.) juga memiliki aktivitas antioksidan (Khairiah, 2018). Sedangkan pada kulit buahnya mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, triterpenoid, saponin, tanin, glikosida, dan fenolik (Sogandi, 2018) Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder dari tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antikanker (Sirait, 2019 ) Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji aktivitas antioksidan dan antikanker dari fraksi kulit buah kasturi (Mangifera Casturi) 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Apakah kulit buah mangga kasturi (Mangifera Casturi) memiliki aktivitas antioksidan dan antikanker terhadap sel kanker payudara MCF7? 1.2.2 Senyawa bioaktif apakah yang terdapat dalam kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) yang berperan sebagai antioksidan dan antikanker ? Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 3 1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Mengetahui aktivitas antioksidan dan antikanker kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) terhadap sel kanker payudara MCF7. 1.3.2 Mengetahui jenis senyawa bioaktif dalam fraksi kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) yang berperan sebagai antioksidan dan antikanker. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Dapat digunakan sebagai referensi mengenai uji aktivitas antioksidan kulit buah kasturi (Mangifera casturi) untuk penelitian lanjutan. 1.4.2 Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk uji aktivitas antikanker dari kulit buah kasturi (Mangifera casturi). 1.4.3 Menambah wawasan untuk berfikir kritis dalam memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai efek kulit buah kasturi (Mangifera casturi) sebagai agen terapi kanker payudara MCF7. 1.5 Hipotesis Kulit buah mangga kasturi (Mangifera Casturi) memiliki aktivitas antioksidan dan antikanker terhadap sel kanker payudara MCF Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tumbuhan Kasturi ( Mangifera Casturi ) Gambar 2.1 Tumbuhan Kasturi (Mangifera Casturi) Sumber : wikimedia commons 2.1.1 Klasifikasi Tumbuhan Kasturi Kingdom : Plantae (tumbuhan) Subkingdom : Thracheobionta (tumbuhan berpembuluh) Super divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) Divisi : Angiospermae/Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) Kelas : Dicotyledoneae/Magnoliopsida (berkeping dua) Subkelas : Rosidae Ordo : Sapindales Family : Anacardiaceae Genus : Mangifera Spesies : Mangifera Casturi (Andriyani, 2013) 4 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 5 2.1.2 Morfologi Tanaman Tanaman mangga kasturi (Mangifera casturi) merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimatan. Tumbuhan ini memiliki umur puluhan tahun dan memiliki habitat di hutan ataupun pekarangan rumah. Jenis akar yang dimiliki tanaman mangga kasturi (Mangifera casturi) merupakan perakaran tunggang yang memiliki warna coklat keabu-abuan. Bentuk batang tanaman ini silindris dengan tinggi hingga 25m dan diameter yang dimilikinya kurang lebih 1m. Kulit batang bagian luar berwarna coklat tua dan kulit batang yang telah mati memiliki retakan berwarna keabu-abuan. Sedangkan kulit batang bagian dalam memiliki warna coklat muda. Tanaman bisa mencapai tinggi 25-50 m atau bahkan lebih, dengan diameter batang ±40-115 cm. (Sutomo, 2017). Daun tanaman mangga kasturi (Mangifera casturi) berwarna hijau muda sampai dengan hijau tua dengan bentuk daun lancet. Panjang daunnya berkisar ± 20 samapi dengan 27 cm dan lebar ± 5,5 samapi dengan 8,5 cm. Tanaman ini memiliki permukaan daun kasar, ujung daun berbentuk runcing dengan tepi rata. Tulang daunnya menyirip dengan jumlah 17 sampai dengan 23 pasang. (Sutomo, 2017) Bunga mangga kasturi (Mangifera casturi) termasuk bunga atinomorf atau bunga berbentuk bintang dan memiliki rambut rapat. Tanamn ini juga memiliki bunga berbentuk karang dalam malai dengan banyak yang berukuran cukup kecil. Bunga ini tergolong dalam bunga majemuk berkelamin ganda. Panjang tangkai bunga berkisar ±28 cm .Daun kelopak berbentuk bulat telur memanjang dengan panjang 2-3 mm. Daun mahkota berbentuk bulat telur memanjang dan bunga berbau harum. Benang sari sama panjang dengan mahkota, staminodia sangat pendek seperti benang sari yang tertancap pada tonjolan dasar bunga (Rashedy, 2014). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 6 Tanaman mangga kasturi (Mangifera casturi) memiliki bentuk buah yang bulat sampai elips dengan berat berkisar antara 6084 g, panjang antara 4,5-5,5 cm, dan lebar 3,5-3,9 cm. Saat matang buah mangga kasturi (Mangifera casturi) memiliki bintik-bintik berbentuk bulat kecil kehijauan. Warna buah ini saat matang adalah coklat keunguan.Buah ini memiliki getah pada permukaan kulitnya yang licin (Sutomo, 2107) .Daging buahnya cenderung tipis dan mengandung kadar air yang cukup tinggi air, berwarna orange kekunginan serta memiliki serabut, tekstur daging buah sedikit kasar, memiliki rasa yang manis keasaman dengan bau yang khas. Buah ini memiliki biji berdinding tebal. Biji nya bertekstur keras sehingga tergolong dalam biji batu. Saat memasuki musim penghujan, tanaman ini akan mulai berbuah (Shaban, 2009). 2.1.3 Kandungan Kimia Batang pohon mangga kasturi (Mangifera casturi) memiliki kandungan senyawa terpenoid, steroid, dan saponin (Mustikasari, 2008). Penelitian yang di lakukan oleh Soetomo, dkk menyatakan bahwa ekstrak metanol buah mangga kasturi mengandung senyawa golongan terpenoid, steroid, dan fenolik. Berdasarkan penelitian sebelumnya menggunakkan pengujian fitokimia fraksi etil asetat, menyatakan bahwa daun mangga kasturi mengandung flavonoid, tanin, serta triterpenoid. (Tanaya et al, 2015) Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan sering dikaitkan dengan pengobatan penyakit kanker diabetes, dan lainnya. Flavonoid termasuk ke dalam kelas polifenol dan memiliki fungsi sebagai modulator komunikasi intraseluler. Flavonoid dikenal memiliki sifat terapeutik seperti antioksidatif, anti mutagenik, dan anti karsinogenik (Yadavalli, 2019). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 7 Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang mampu mengikat protein, sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap degradasi oleh enzim protease didalam silo. Selain itu tanin juga bersifat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba (Oliveira et al, 2009) . Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyatakan bahwa senyawa flavonoid, steroid, dan tannin dalam bentuk bebas dan kompleks tannin-protein berkhasiat sebagai antiinflamasi. (Simon, 2000) Triterpenoid adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang tersusun dari kerangka karbon dan enam satuan isoprena yang di sebut skualena. Skualena terbentuk dari turunan hidrokarbon C 30 asiklik. Senyawa ini mengandung gugus alkohol, aldehida, atau asam karboksilat. Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan triterpenoid dapat digunakkan sebagai obat seperti untuk pengobatan diabetes, gangguan menstruasi, gangguan pada kulit, kerusakan hati dan juga pengobatan `malaria. Triterpenoid ini juga dapat bermanfaat bagi tumbuhan, karena senyawa ini memiliki aktivitas sebagai anti jamur, membunuh serangga (insektisida), anti pemangsa, pembunuh bakteri & antivirus. (Widiyati, 2006) Saponin adalah senyawa yang terdapat disebagian besar tanaman tingkat tinggi serta pada beberapa hewan laut. Senyawa glikosida ini merupakan sekumpulan senyawa yang memiliki berbagai macam sifat fisikokimia, struktur dan efek biologisnya (Patra, 2009). Menurut penilitian yang telah dilakukan saponin mempunyai aktivitas hemolitik, antibakterial, aktivitas sitotoksik atau antikanker, efek hipokolesterolemia (Singh, 2012). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 8 2.2 Ekstraksi dan Fraksinasi Ekstraksi dapat di artikan sebagai pemisahan suatu senyawa atau bahan dari campurannya dengan menggunakkan cairan pelarut yang cocok atau sesuai. Pada proses ektraksi ini akan tercapai kesetimbangan konsentrasi suatu senyawa didalam pelarut dengan konsentrasi didalam sel tanaman. Saat terjadi kesetimbangan proses ekstraksi ini akan dihentikan. Menurut Hamdani (2009) terdapat 2 jenis metode ekstraksi berdasarkan ada tidak nya proses pemanasan, yaitu ekstraksi dingin dan panas. 2.2.1 Metode Ekstraksi Dingin : 2.2.1.1 Maserasi Maserasi adalah cara penyarian yang sangat sederhana dibandingkan proses ekstraksi lainnya. Proses maserari dilakukan dengan cara menggunakkan cairan penyari yang cocok untuk merendam serbuk simplisia. Saat proses perendaman ini terjadi, cairan penyari akan memasuki dinding sel dan perlahan akan masuk kedalam rongga sel. Di dalam rongga sel terdapat zat aktif, sehingga saat cairan penyari masuk maka akan melarutkan zat aktif di dalam nya. Larutan terpekat di dalam sel akan keluar karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dan di luar sel. Proses ini akan terjadi berulang kali sampai didapatkan konsentrasi yang seimbang antara larutan di dalam dan di luar sel. 2.2.2.2 Perkolasi Perkolasi adalah proses penyarian dengan cara mengalirkan cairan penyari melalui bahan yang telah dibasahi . Proses perkolasi umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Prosedur metode ini yaitu bahan direndam dengan pelarut, kemudian pelarut baru dialirkan secara terus menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening yang artinya sudah tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Kelebihan dari metode ini yaitu tidak diperlukan proses tambahan untuk Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 9 memisahkan padatan dengan ekstrak, sedangkan kelemahan metode ini adalah jumlah pelarut yang dibutuhkan cukup banyak dan proses juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta tidak meratanya kontak antara padatan dengan pelarut (Sarker et al, 2006). 2.2.2 Metode Ekstraksi Panas : 2.2.2.1 Sokhlet Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ektraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. (Mukhriani, 2011). 2.2.2.2 Refluk Ekstraksi refluks merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut, selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik (kondensor). Pada umumnya dilakukan tiga sampai lima kali pengulangan proses pada rafinat pertama. Kelebihan metode refluks adalah padatan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat diekstrak dengan metode ini. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang banyak ( Irawan, 2010). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 10 2.2.2.3 Infusa Infusa adalah cara ekstraksi dengan menggunakan pelarut air pada suhu 98-98˚C selama 15-20 menit. Bejana infusa teredup dalam dalam tangas air (Hanani, 2015). 2.2.2.4 Destilasi Uap Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006). 2.2.2.5 Dekokta Dekok merupakan cara ekstraksi yang mirip dengan infusa, akan tetapi pada dekok proses ekstraksinya membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu 30 menit dan suhunya mencapai titik didih air (Hanani, 2015). 2.2.3 Fraksinasi Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawasenyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari, 2012). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 11 2.3 Kandungan Total Flavonoid Total kandungan flavonoid diukur dengan prinsip 𝐴𝑙𝐶𝑙3 yang akan membentuk kompleks karena memiliki C-4 gugus keto lalu dengan C-3 atau C-5 gugus hidroksil yang bertetangga sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah visible (nampak) yang terlihat dari warna kuning pada larutan .Pada pengukuran total flavonoid dilakukan pembuatan standar kuersetin sebagai pembanding. Pada penelitian ini untuk menentukan kadar flavonoid total pada sampel digunakan kuarsetin sebagai larutan standar dengan deret konsentrasi 6, 8, 10, 12 dan 14 ppm. Digunakan deret konsentrasi karena metode yang di pakai dalam menentukan kadar adalah metode yang menggunakan persamaan kurva baku untuk membuat kurva baku terlebih dahulu dibuat beberapa deret konsentrasi untuk mendapatkan persamaan linear yang dapat digunakan untuk menghitung persen kadar. Pengukuran serapan panjang gelombang maksimum dilakukan running dari panjang gelombang 400 – 450 nm. Kuersetin dipilih karena merupakan salah satu golongan flavonoid/flovanol Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 435 nm. Ekstrak dengan kandungan total flavonoid tertinggi kemudian dilanjutkan padat tahap pengujian nilai antioksidan (IC50) (Senet et al, 2018) 2.4 Kandungan Total Fenol Kandungan fenolik total pada ekstrak dinyatakan sebagai ekuivalen asam galat atau Gallic Acid Equivalent (GAE). GAE merupakan acuan umum untuk mengukur sejumlah senyawa fenolik yang terdapat dalam suatu bahan (Mongkolsilp et al, 2004). Total kandungan fenolik dapat dilakukan dengan menggunakkan reagen Folin-Ciocalteu. Penentuan kandungan total fenol merupakan uji kuantitatif yang didasarkan pada kemampuan sampel untuk mereduksi reagen Folin-Ciocalteu membentuk Kompleks Molybdenum-Blue. Timbang ekstrak sebanyak 100mg, larutkan dengan aquadest 10ml (konsentrasi 10mg/ml). Lalu Pipet 1ml dan encerkan dengan aquadest 10ml, sehingga diperoleh konsentrasi 1mg/ml. Kemudian Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 12 pipet 0,2 ekstrak dan tambahkan aqadest sebanyak 15,8 ml. Tambah 1 ml reagen Folin-Ciocalteu lalu di kocok. Diamkan selama 8menit, lalu tambahkan Na2CO3 10%. Kemudian diamkan lagi selama 2 jam pada suhu kamar. Ukur serapan dengan spektrometer UV-Vis . Lakukan tiga kali pengulangan (Triplo) (Orak, 2006). 2.5 Antioksidan Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkap atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Dalam pengertian kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (electron donors). Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa dihambat (Winarsi, 2007). Antioksidan bersifat sangat mudah dioksidasi, sehingga radikal bebas akan mengoksidasi antioksidan dan melindungi molekul lain dalam sel dari kerusakan akibat oksidasi oleh radikal bebas atau oksigen reaktif.Radikal bebas merupakan molekul yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbital luarnya sehingga dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh dengan cara mengikat elektron molekul sel tersebut (Nurdin et al, 2008). Radikal bebas yang dihasilkan secara terus menerus selama proses metabolisme normal, dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusakan fungsi sel-sel tubuh yang akhirnya menjadi pemicu timbulnya penyakit degeneratif (Juniarti, 2009) 2.5.1 Macam-macam Antioksidan (Sayuti et al, 2015): 2.5.1.1 Antioksidan Primer Antioksidan primer merupakan antioksidan yang bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 13 rantai reaksi radikal dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal, produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk awal. Contoh antioksidan primer adalah superoksida dismutase (SOD), glutation peroksidase (GPx), katalase dan protein pengikat logam. 2.5.1.2 Antioksidan Sekunder Antioksidan sekunder bekerja dengan cara megkelat logam yang bertindak sebagai pro oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Antioksidan seunder berperan sebagai pengikat ion-ion logam, penangkap oksigen, pengurai hidroperoksida menjadi senyawa non radikal, penyerap radiasi UV atau deaktivasi singlet oksigen. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, C, , β-karoten, isoflavon, bilirubin dan albumin. 2.5.1.3 Antioksidan Tersier Antioksidan tersier bekerja dengan cara memperbaiki kerusakanbiomolekul yang disebabkan radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim yang memperbaiki DNA yaitu metionin sulfida reduktase. 2.5.2 Vitamin C Pembanding yang digunakkan dalam pengujian antioksidan ini adalah vitamin C. (Farmakope, 1995) Sinonim : 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone; Acidum ascorbicum Rumus Kimia : C6H8O6 Berat Molekul : 176,15 Deskripsi : Kristal atau serbuk putih atau agak kuning. Bila terpapar udara, warnanya perlahan-lahan menjadi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 14 lebih gelap. Dalam keadaaan kering, stabil di udara, tetapi dalam larutan akan teroksidasi dengan cepat. Kelarutan : Larut 1 bagian dalam 3 bagian air dan 1 bagian dalam 40 bagian alkohol, tidak larut dalam kloroform, eter, dan benzena. Penyimpanan : dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya matahari. Stabilitas : Secara bertahap menjadi gelap lewat paparan terhadap cahaya, namun sedikit perubahan warna tidak berpengaruh pada efek terapinya. Asam askorbat teroksidasi dengan cepat pada udara atau suasana basa.Pada konsentrasi > 100 mg/ml, vitamin C mengalami dekomposisi melalui produksi kabon dioksida. Vitamin C juga disebut sebagai elektron donor (pemberi elektron) sehinggatermasukdalam senyawa anti-oksidan. Vitamin C sebagai pemberi elektron, juga ini berarti sebagai agen reduktor, berasal dari sifat ikatan ganda antara C-2 dan C-3 dari cincin lakton 6karbontersebut. Vitamin C dapat mencegah senyawa-senyawa lain mengalami oksidasi. Secara alamiah vitamin C itu sendiri yang mengalami oksidasi (Wijaya, 2014). 2.5.3 Uji Antioksidan 2.5.3.1 Metode DPPH (1, 1-diphenyl-2picrylhydrazyl radical) DPPH (2,2-difenil-1-pikril-hidrazil) Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dilakukan untuk menentukan seberapa besar aktivitas suatu sampel untuk menghambat radikal stabil DPPH dengan cara mendonorkan atom hidrogen. Sampel yang memiliki aktivitas antioksidan akan mereduksi DPPH menjadi DPPH-H (Molyneux, 2005). Prinsip DPPH adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat antioksidan. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 15 Senyawa DPPH akan bereaksi dengan atom Hidrogen yang berasal dari suatu antioksidan membentuk senyawa dihenylpicrylhydrazine berwarna kuning pucat ( Molyneux, 2004). Parameter yang dipakai untuk menentukan aktivitas antioksidan adalah harga konsentrasi efesien atau efficient concentration 50 ( EC50) atau inhibition concentration 50 (IC50) , yaitu konsentrasi suatu zat antioksidan yang dapat menyebabkan 50% DPPH kehilangan karakter radikal atau konsentrasi suatu zat antioksidan yang memberikan % penghambatan sebesar 50%. Zat yang mempunyai antioksidan tinggi akan mempunya nilai EC50 atau IC50 yang rendah (Molyneux, 2004). Aktivitas antioksidan dikatakan sangat kuat jika nilai IC50 < 50 µg/mL, kuat jika IC50 < 100 µg/mL, sedang jika IC50 < 150 µg/mL, lemah jika IC50 < 200 µg/mL, dan sangat lemah jika IC50 > 200 µg/mL (Blois, 1958). Selain itu aktivitas suatu antioksidan juga di pengaruhi oleh kandungan total fenol, semakin besar kandungan total fenol maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidan nya. (Chung and Woo, 2001). 2.5.3.2 Metode Cupric Ion Reducing Antioxidant (CUPRAC) Pada metode CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant capacity), kompleks bis- neokuproin-tembaga(II) akan mengoksidasi senyawaan antioksidan dalam ekstrak tanaman dan mengalami reduksi membentuk kompleks bis-neokuprointembaga(I). Secara visual hal ini dapat dilihat dari perubahan warna kompleks larutan dari biru toska menjadi kuning. Pereaksi CUPRAC merupakan pereaksi yang selektif karena memiliki nilai potensial reduksi yang rendah, yaitu sebesar 0,17 V (Apak et al. 2007). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 16 2.5.3.3 Metode Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) Hasil pengujian dengan metode FRAP dipengaruhi oleh banyaknya reduksi dari ferri-tripyridyl triazine (Fe (III)-TPTZ) berubah menjadi ferrotripyridyl-triazine (Fe (II)-TPTZ) oleh pereduksi atau reduktan (Benzie,1996). 2.5.3.4 Metode uji kapasitas radikal oksigen (ORAC) Prosedur analisis ini mengukur kemampuan antioksidan dari makanan, vitamin, suplemen nutrisi atau bahan kimia lainya terhadap radikal bebas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan trolox (analog vitamin E ) sebagai standar untuk menentukan trolox ekuvalen (TE). Nilai ORAC kemudian dihitung dari TE dan ditunjukan sebagai satuan atau nilai ORAC. Semakin tinggi nilai ORAC, semakin besar kekuatan antioksidanya (Amelia, 2011). 2.6 Antikanker Upaya pengobatan kanker dapat dilakukan dengan pembedahan, radiasi, kemoterapi, dan pemberian hormon-hormon terapi (Di Piro et al., 2009). Kemoterapi bekerja berdasarkan gangguan pada salah satu proses sel yang essensial, karena tidak ada perbedaan kualitatif antara sel kanker dengan sel normal, maka semua obat anti kanker bersifat mengganggu sel normal, bersifat sitotoksik, dan bukan kankerosid atau kankerotoksik yang selektif (Nafrialdi & Gan, 2008) . Berdasarkan penelitian tanaman obat sebagai antikanker, alkaloid merupakan senyawa kimia yang berpotensi memiliki aktivitas tersebut dengan mekanisme menginduksi apoptosis (Macabeo et al., 2008). Apoptosis adalah tipe kematian sel yang terprogram melalui serangkaian perubahan struktural sebagai hasil dari rangsang fisiologis atau patologis. Ciri morfologi apoptosis adalah pengkerutan sel, penonjolan membran (membrane blebbing), mitokondria bersegregasi, ribosom bersegregasi, sitoplasma berkondensasi, kondensi kromatin, dan fragmentasi inti sel (De Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 17 Vita et al., 1997 cit Sudarmawan, 2006; Rahmawati, 2006) Alkaloid yang telah digunakan untuk pengobatan kanker adalah alkaloid vinkristin dan vinblastin dari tanaman tapak dara. 2.6.1 Pengertian Kanker Payudara Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang mempunyai prevalensi cukup tinggi. Kanker ini dapat menyerang pria ataupun wanita, namun prevalensi terhadap wanita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Kemungkinan laki-laki terkena kanker payudara adalah 1: 100 dari wanita. Frekuensi kejadian kanker payudara relatif tinggi, terutama pada wanita usia 40 tahun ke atas (Wijayakusuma, 2008). Sampai usia 80 tahun, risiko seumur hidup seseorang wanita untuk terkena kanker payudara adalah 1 dari 9 (Davey, 2005). Kanker juga merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak antara 3-14 tahun di Amerika Serikat (Nafrialdi & Gan, 2008). Kanker payudara pada umumnya berupa ductal breast cancer yang invasif dengan pertumbuhan yang tidak terlalu cepat. Sebagian besar kanker payudara ditandai dengan adanya gumpalan yang biasanya terasa sakit pada payudara. Adapun gejala yang jarang ditemui berupa sakit pada payudara, erosi, retraksi, pembesaran dan rasa gatal pada bagian puting, timbul kemerahan, pemesaran atau penyusutan payudara. (Tambunan, 2003) 2.6.2 Sel Kanker MCF7 Sel MCF7 merupakan sel kanker payudara yang diperoleh dari pleural effusion breast adenocarcinoma seorang pasien wanita Kaukasian berubur 69 tahun, golongn darah , dengan Rh Positif. Sel tersebut menunjukkan adanya deferensiasi pada jaringan epitel mammae termasuk deferensiasi pada sintesis estradiol. Media dasar penumbuh sel MCF7 adalah media EMEM terformulasi. Untuk Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 18 memperoleh media kompleks , maka ditambahkan 0,01 mg/ml bovine insulin dan FBS hingga konsentrasi akhir FBS dalam media menjadi 10%. Sel ditumbuhkan pada suhu 37°C dan dengan kadar CO2 5%. Sel MCF7 tergolong Cell line adherent (Zampieri et al, 2002 ) Sel MCF-7 digunakan di mana-mana dalam penelitian untuk percobaan sel kanker payudara ER-positif, dengan sebagian besar investigasi terhadap resistensi obat anti-estrogen yang didapat telah menggunakannya. Sel MCF-7 sangat cocok untuk studi resistensi terapi anti-hormon karena mereka mudah dikultur dan mempertahankan ekspresi ER ketika mereka diperlakukan dengan terapi yang ditargetkan tersebut. Untuk menyelidiki sifat-sifat sel kanker payudara yang kebal antihormon yang diperoleh, populasi sel MCF-7 - yang diadaptasi ke berbagai lingkungan anti-hormon - telah dibuat (Comsa, 2015). 2.6.3 Etiologi Kanker Payudara Faktor etiologi kanker payudara sampai saat ini belum di ketahui pasti. Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kanker payudara. Faktor reproduksi (usia menache dini, kehamilan pertama pada usia lanjut, paritas yang rendah, masa laktasi), faktor endokrin ( kontrasepsi oral, terapi sulih hormon, usia >75 tahun denan densitas payudara 75%, hiperplasi atipik), adapun faktor genetik yang dapat menyebabkan kanker payudara (riwayat keluarga dengan kanker payudara, kanker ovarium). Namun faktor resiko utama yang berhubungan dengan kanker payudara adalah keadaan hormonal dan genetik (Rasajidi, 2010). 2.6.4 Patofisiologi Kanker Payudara Kanker payudara yang invasif disebabkan oleh pertumbuhan selsel epitel payudara yang berlebih dan tidak terkendali (Stopeck et al, 2014). Proliferasi sel yang berlebih dapat disebabkan oleh mutasi gen, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 19 tidak aktifnya gen supresor tumor, gangguan apoptosis, dan gangguan perbaikan DNA sehingga terjadi aktivasi onkogen yang pada akhirnya menjadi sel kanker invasif. Selain itu, reseptor estrogen dan progesteron yang berada di inti sel yang terdapat pada beberapa kanker payudara dapat mendorong replikasi DNA, pembelahan sel dan pertumbuhan sel kanker ketika hormon yang sesuai berikatan pada reseptor (Kosir, 2013). Pertumbuhan sel ini dapat muncul pertama kali di duktus maupun lobulus payudara yang kemudian menyebar ke jaringan sekitar infiltrasi, invasi, dan penetrasi progresif. Sel kanker dapat menyebar melalui aliran limfe dan sirkulasi darah yang mengakibatkan metastasis ke organ tubuh lain (Kosir, 2013) 2.6.5 Pengobatan Kanker Pengobatan kanker sangat bervariasi dan tergantung pada berbagai faktor, antara lain jenis kanker, lokasi kanker pada tubuh, stadiumnya dan status kesehatan pasien. Pada umumnya, pengobatan kanker ditujukan untuk membunuh sel kanker, mengangkat sel kanker melalui tindakan operasi, atau mencegah agar sel kanker tidak mendapatkan sinyal yang dibutuhkan untuk proses pembelahan sel. Selain itu, upaya pengobatan kanker juga dilakukan dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien sehingga tubuh mampu mempertahankan diri dari serangan sel kanker. Beberapa jenis pengobatan kanker (Radji, 2016) : 2.6.5.1 Operasi Tindakan operasi merupakan pengobatan lini pertama untuk kanker atau tumor padat. Pada kasus kanker yang terdiagnosis pada stadium dini, tindakan operasi merupakan cara yang cukup efektif untuk menanggulangi kanker. Pada umumnya, tindakan operasi hanya dapat mengatasi kanker jinak atau tumor yang terlokalisasi. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 20 2.6.5.2 Radiasi Radiasi ditujukan untuk membunuh sel kanker dengan energi sinar, biasanya merupakan terapi setelah pengangkatan sel tumor. Radiasi juga dapat dikombinasi dengan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker yang kemungkinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dengan cara operasi. 2.6.5.3 Kemoterapi Kemoterapi merupakan pengobatan yang menggunakan suatu senyawa kimia untuk membunuh sel kanker yang sedang membelah dan mencegah perkembangan sel selanjutnya. 2.6.5.4 Terapi hormonal Obat ini diberikan untuk mencegah pertumbuhan sel kanker dengan mencegah sel kanker menerima sinyal penting untuk pembelahan dan proliferasi sel kanker. 2.6.5.5 Terapi tepat sasaran Terapi tepat sasaran (targeted therapy) merupakan golongan obat yang relatif baru untuk pengobatan kanker. Obat ini bekerja secara spesifik dan terarah untuk menghalangi peran protein atau enzim tertentu yang spesifik hanya terdapat atau banyak terdapat pada sel kanker. Penghambatan terhadap peran protein spesifik tersebut akan mencegah pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. 2.6.5.6 Antibodi monoklonal Antibodi digunakan dalam terapi kanker merupakan antibodi monoklonal yang diproduksi tidak hanya untuk menghantarkan senyawa kemoterapi, tetapi juga digunakan sebagai obat. Antibodi monoklonal sebagai terapi antikanker bekerja dalam berbagai mekanisme, baik secara langsung dapat membunuh sel kanker maupun dengan menghambat Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 21 sinyal penting yang dibutuhkan untuk proliferasi sel. Karena antibodi bersifat sangat spesifik, antibodi monoklonal dapat dikatakan sebagai inhibitor spesifik untuk sel kanker. 2.6.5.7 Biological response modifier Terapi ini menggunakan protein yang secara alami tedapat dalam tubuh untuk menstimulasi pertahanan tubuh dalam mengatasi sel kanker. 2.6.5.8 Vaksin kanker Tujuan penggunaan vaksin kanker adalah untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh melawan kanker. Vaksin kanker umumnya mengandung protein yang terdapat pada sel kanker atau yang diproduksi oleh sel kanker. Pemberian protein tersebut sebagai vaksin akan merangsang respons tubuh terhadap sel kanker. 2.6.5.9 Terapi alternatif dan komplementer Terapi ini menggunakan senyawa alami dari herbal atau hewan yang digunakan untuk pengobatan kanker disamping obat konvensional. 2.6.6 Mekanisme Antikanker Obat antikanker merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh sel kanker. Antikanker umumnya bekerja dengan cara membunuh sel yang sedang berkembang. Dengan begitu, sel kanker lebih rentan terhadap senyawa yang bersifat sitotoksik tersebut karena sel kanker umumnya terus membelah dengan cepat dibandingkan dengan sel yang normal. Antikanker biasanya ditujukan untuk menghambat langsung sistem metabolisme esensial pada replikasi sel kanker, antara lain penghambatan terhadap biosintesis purin dan pirimidin yang merupakan senyawa penting untuk sintesis RNA dan DNA. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 22 Beberapa jenis antikanker yang umum digunakan pada terapi kanker adalah (Radji, 2016) 2.6.6.1 Senyawa antimetabolit Senyawa ini dapat menghambat sintesis purin atau pirimidin yang merupakan precursor nukleotida sehinga dapat menghambat sintesis RNA dan DNA sel dan menyebabkan kematian sel kanker. 2.6.6.2 Senyawa genotoksik Senyawa genotoksik menyebabkan kelainan pada DNA sehingga mempengaruhi replikasi DNA dan pembelahan sel kanker. 2.6.6.3 Inhibitor spindel mitosis sel Senyawa ini dapat menghambat pembelahan sel dengan menghambat pembentukan spindel sel yang merupakan komponen sitoskeletal sel sehingga sel tidak mampu membelah diri. 2.6.6.4 Senyawa antikanker lain Senyawa dalam golongan ini merupakan senyawa yang dapat menghambat pembelahan sel kanker yang tidak termaduk dalam kategori senyawa yang telah disebutkan sebelumnya. 2.6.7 Doxorubisin Doxorubicin adalah obat yang sering digunakan dalam terapi kanker dan memiliki nama dagang adryamicin. Obat ini tidak diserap oleh saluran cerna, karena obat ini sangat mengiritasi saluran lambung. Ikatan doxorubicin dengan protein plasma adalah 75% (Kumar et al, 2014) Doxorubisin merupakan antibiotik golongan antrasiklin yang banyak digunakan untuk pengobatan kanker serviks, ovarium, endometrium, dan karsinoma mama. Antibiotik antrasiklin seperti Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 23 doxorubisin berinterkalasi dengan DNA, sehingga fungsi DNA sebagai template dan pertukaran sister chromatid terganggu dan pita DNA putus. Antrasiklin juga bereaksi dengan sitokrom P450 reduktase yang dengan adanya MADPH membentuk zat perantara, yang kemudian bereaksi dengan oksigen menghasilkan radikal bebas yang menghancurkan sel (Nafrialdi & Gan, 2008). 2.6.8 Uji Aktivitas Antikanker 2.6.8.1 Uji 3-[4,5-dimetilthiazol-2yl]-2,5-difeniltetrazolium bromide (MTT) Uji MTT adalah uji yang sensitif, kuantitatif dan terpercaya. Reaksi MTT merupakan reaksi reduksi selular yang didasarkan pada pemecahan garam tetrazolium MTT berwarna kuning menjadi kristal formazan berwarna biru keunguan. Metode perubahan warna tersebut digunakan untuk mendeteksi adanya proliferasi sel. Sel yang mengalami proliferase, mitokondrianya akan menyerap MTT sehingga sel-sel tersebut akan berwarna ungu akibat terbentuknya kristal tetrazolium (formazan) (Depamede et al, 2009). 2.6.8.2 Metode Perhitungan Langsung Metode perhitungan langsung dilakukan dengan pengecatan menggunakan larutan biru tripan. Sel yang mati akan menyerap warna biru tripan, sedangkan yang hidup tidak. Hal ini disebabkan karena sel yang mati mengalami kerusakan pada membrane selnya, mengakibatkan protein di dalam sel keluar dan berikatan dengan biru tripan. Pemberian biru tripan dilakukan secara bertahap untuk menghindari kemungkinan kematian sel yang disebabkan oleh biru tripan dan hasilnya sel yang mati akan tampak keruh tidak bercahaya (Freshney, 2010). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 24 2.6.9 Apoptosis Apoptosis merupakan mekanisme kematian sel penting yang telah terprogram dalam berbagai proses biologi. Proses apoptosis yang kurang atau tidaak sempurna dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Apoptosis yang terlalu banyak dapat menyebabkan kekacauan sel, sedangkan apoptosis yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan poliferasi sel yang tidak terkontrol atau dapat disebut dengan kanker (CRCC, 2009). 2.6.10 Anti Proliferasi Uji penghambatan pertumbuhan proliferasi dilakukan setelah diketahui nilai IC50. Tujuan pengujian antiproliferasi ini adalah untuk mengetahui bahwa suatu senyawa dapat menghambat pertumbuhan sel. Pada uji antiproliferasi sel dipuasakan (starvasi) selama 24 jam dalam media kultur yang mengandung FBS dimana FBS kaya akan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan sel, sehingga dengan mengurangi kadar FBS dalam media berarti terjadi pengurangan pertumbuhan. Tujuan dari starvasi adalah mengurangi kecepatan pertumbuhan sel, menyebabkan sel berada dalam standart awal yang sama yaitu G0 (fase istirahat). Sel yang berada pada fase M akan cepat berhenti dan mencapai fase G0, sedangkan pada fase G1 akan meneruskan daur sel sehingga pada G0 akan berhenti. Sel kanker merupakan sel yang tidak terkontrol pertumbuhannya karena dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan signal pertumbuhan (Muhammad, 2018) 2.7 GC-MS (Gass Chomatography – Mass Spectrocopy) Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) merupakan instrumen yang mendukung untuk menganalisis suatu senyawa dalam konsentrasi yang kecil salah satu instrument yang dapat mendeteksi suatu senyawa hingga < 1 ng/g . GC adalah suatu teknik kromatografi yang hanya Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 25 dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap. Cara kerja mesin ini adalah suatu fase gerak yang berbentuk gas mengalir di bawah tekanan melewati pipa yang dipanaskan dan disalut dengan fase diam cair atau dikemas dengan fase diam cair yang disalut pada suatu penyangga padat. Seiring dengan berkembang nya zaman dan kemajuan teknologi, instrument GC di gunakkan bersamaan dengan instrument lain seperti Mass-Spectrometer. Mass-Spectrometer atau yang biasa disebut spektrometer masa dapat digunakkan untuk menentukan bobot molekul dan juga menentukan rumus molekul. Prinsipnya adalah pengionan senyawa-senyawa kimia untuk menghasilkan molekul bermuatan dan mengukur rasio massa atau muatan (Ari, 2016). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta BAB III Metodologi Penelitian 3.1 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorik. 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian di lakukan di Laboratorium Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara; Pusat Studi satwa Primata yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat; Pusat Studi Biofarmaka Propika IPB di Kampus IPB Taman Kencana, Bogor. Penelitian ini berlangsung dalam waktu 5 bulan terhitung dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 3.3 Sampel Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) 3.4 Alat dan Bahan 3.4.1 Alat Alat yang digunakkan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometer UV-Vis , peralatan maserasi, Rotary Evaporator, erlenmeyer, labu ukur, botol penampung berbagai ukuran, batang pengaduk, cawan uap, blender, kertas saring, corong pisah, alumunium foil, pipet, timbangan, penjepit kayu, lemari pendingin, microplate 96 sumuran , haemocytometer, microplate reader, tissue cultur flack, tabung falcon, hot plate, GC-MS, Lampu UV, Elisa reader, 26 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 27 3.4.2 Bahan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) matang, etanol 70%, etil asetat, nheksan, NaOH,𝐻2 𝑆𝑂4 pekat, dan serbuk Mg-HCl pekat, kloroform, amoniak, pereaksi mayer, pereaksi dragendorff, pereaksi wagner, asam sulfat, metanol, anhidra asetat, larutan besi (III) klorida 10%, plat KLT, n-butanol, DPPH, DMSO, larutan metanol proanalisa, vitamin C, aquadest, sel kanker payudara (MCF7), MTT [3-(4,5- dimetiltiazolil-2)-2,5- difeniltetrazolium bromida] (Sigma), media penumbuh RPMI (Rossewell Park Memorial Institute), PBS (Phosphate buffer Saline) pH 7,4 Sodium Dodesil Sulfat (SDS) 10%, Fetal bovine serum (FBS) 10%, Natrium subkarbonat (NaHCO3) 2 g/l, HCl 0,1 N, trypan blue dan trypsin EDTA 0,5%, doxorubisin, kuersetin, asam galat, 𝐴𝑙𝐶𝑙3, 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3, Fenol Folin-Ciocalteu, Working Solution etidium bromida-akridin oranye, 3.5 Prosedur Kerja 3.5.1 Determinasi Simplisia Mangifera casturi yang akan digunakan diambil dari kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan dilakukan determinasi di Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kebun Raya Bogor. 3.5.2 Ekstraksi Pertama, dilakukan pemisahan antara daging dan kulit buah mangga kasturi. Kemudian kulitnya dikeringkan dan di haluskan sebanyak 600g. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% (1:1). Maserasi dilakukan 3 x 24 jam (3 kali pengulangan). Maserat yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan Rotary Evaporator. Setelah itu diuapkan di atas Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 28 waterbath. Sehingga dihasilkan ekstrak kental etanol 70% dan dilakukan perhitungan rendemen. 3.5.3 Fraksinasi Ekstrak etanol difraksinasi menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, dan metanol. Fraksinasi dilakukan dengan cara 30 g ekstrak kental kulit buah kasturi dilarutkan dalam 100 mL metanol-air (4:1) kemudian difraksinasi menggunakan 100 mL n-heksan (Tanaya et al, 2015), kocok campuran tersebut sampai terbentuk dua lapisan. Pisahkan lapisan n-heksan dan metanol-air dengan cara dituang dari corong pisah ke erlenmayer. Lakukan perlakuan tersebut sebanyak 6 kali sampai jernih. Selanjutnya fraksi n-heksan dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Fase metanol-air difraksinasi menggunakan etil asetat 100 mL, kocok campuran tersebut sampai terbentuk dua lapisan. Pisahkan fraksi etil asetat dan metanol dengan cara dituang dari corong pisah ke erlenmeyer. Lakukan perlakuan tersebut sebanyak 5 kali sampai jernih. kemudian fraksi yang didapat, dipekatkan dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Fraksi nheksan, etil asetat dan metanol-air yang diperoleh ditimbang dan dihitung rendemen (Munawaroh et al, 2018) 3.5.4 Skrining Fitokimia Skrining atau pengujian fitokimia yang dilakukan adalah uji flavonoid, alkaloid, terpenoid, triterpenoid dan steroid, glikosida, tanin, saponin, dan fenolik. Tabel 1. Skringing Fitokimia No 1. Identifikasi Alkoloid Cara Identifikasi Senyawa Teori 1.Ekstrak kental 0,1g + Senyawa alkaloid 10ml kloroform amoniakal ditunjukkan oleh : (kocok lalu saring) -Tabung pertama (adanya Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 29 2. Tambah asam sulfat 2N, pisah kan menjadi dua lapisan 3. Lapisan bagian atas (asam) dimasukkan kedalam masing-masing endapan putih) -Tabung kedua (adanya endapan coklat kemerahan) -Tabung ketiga (adanya endapan coklat kemerahan) (Kristianti et al, 2008) tiga tabung reaksi. - Tabung peratama (+3 tetes pereaksi Mayer) - Tabung kedua (+3 tetes pereaksi Dragendorff) - Tabung ketigas (+3 tetes pereaksi Wagner) 2. Flavonoid 1. Ekstrak kental 0,1 g + 10 Senyawa flavonoid di mL metanol tunjukkan oleh perubahan 2. Bagi menjadi empat warna yang terjadi pada tabung ( kontrol, masing-masing tabung NaOH,𝐻2 𝑆𝑂4 pekat, dan (Tapas, 2008) serbuk Mg-HCl pekat) 3. Masing-masing tabung di bandingkan dengan tabung kontrol. 1. Ekstrak kental yang telah Senyawa saponin 3. Saponin diencerkan 1:1 dengan air ditunjukkan dengan adanya 2. Dikocok secara vertikal busa yang dihasilkan stabil (±15menit) setelah didiamkan selama 15 menit (Marliana, 2005) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 30 4 Triterpenoid 4. 5. & Steroid Tanin 1.0,1 g sampel dilarutkan a.Senyawa terpenoid dengan metanol, uapkan di ditunjukkan dengan atas waterbath terbentuk cincin kecoklatan 2. Filtrat digerus, larutkan atau violet. dengan 2 mL kloroform b. Senyawa sterois 3. Tambah anhidra asetat ditunjukkan dengan 10 tetes terbentuk cincin yang 4. Tetesi dengan ,𝐻2 𝑆𝑂4 3 berwarna hijau. (Nugrahani, tetes 2016) Larutan uji sebanyak 1ml Senyawa tanin ditunjukkan direaksikan dengan larutan dengan adanya warna biru besi (III) klorida 10% tua atau hitam kehijauan. ( Halimah, 2010) 6. Glikosida 1.Ekstrak kental 1g Senyawa glikosida 2. Tambahkan dengan 5ml ditunjukkan dengan adanya asam asetat anhidrat P cincin berwarna ungu 3. Tambahkan dengan asam kemerahan (Sawhney,2005) sulfat P (10tetes) 7. Fenolik 1.Larutan ekstrak Senyawa fenolik ditunjukkan ditotolkan pada plat KLT dengan adanya noda warna dan dielusi dengan hijau, merah, hitam yang menggunakan pelarut n- kuat (Aktsar,2015) butanol : asam asetat : air (4:1:5) 2. amati bercak pada lampu UV dan disemprot dengan reagen besi (III) klorida (𝐹𝑒𝐶𝑙3) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 31 3.5.5 Uji Total Kandungan Flavonoid 1. Penentuan panjang gelombang maksimum kuersetin Penentuan panjang gelombang kuersetin dilakukan dengan running larutan kuersetin pada range 400-450nm. Hasilnya menunjukan panjang gelombang maksimum kuersitin adalah 435nm. Panjang gelombang ini dibunakkan untuk mengukur serapan dari sampel uj. 2. Pembuatan kurva standart kuersetin Timbang 25 mg kuersetin, larutkan dalam 25 mL etanol. Larutan dipipet sebanyak 1mL lalu ditambahkan etanol hinggal 10 mL (100 ppm). Lalu buat pengenceran konsentrasi 6 ppm, 8 ppm, 10ppm, 12 ppm, dan 14 ppm. Dari masing-masing konsentrasi dipipet 1 mL. Kemudian di tambahkan 1 mL 𝐴𝑙𝐶𝑙3 2% dan 1 mL kalium asetat 120 mM. Sampel diinkubasi selama satu jam pada suhu kamar. Absorbansi ditentukan menggunakan metode spektrofotometri UVVis pada panjang gelombang maksimum 435 nm 3. Penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) Timbang 15 mg ekstrak, dilarutkan dalam 10 mL etanol, sehingga diperoleh konsentrasi 1500 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 1mL kemudian ditambahkan 1 mL larutan 𝐴𝑙𝐶𝑙3 2% dan 1 mL kalium asetat 120 mM. Sampel diinkubasi selama satu jam pada suhu kamar. Absorbansi ditentukan menggunakkan metode spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 435 nm. Sampel dibuat dalam 3 replika untuk setiap analisis dan diperoleh nilai rata-rata absorbansi (Stankoviv, 2011). 4. Analisis kandungan flavonoid total : %= 𝐶𝑝 (𝐴𝑢 − 𝐴𝑏𝑢 ) 100 𝑥 1,25 𝑥 𝐴𝑝 − 𝐴𝑏𝑝 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 % = Falvonoid total 𝐶𝑝 = konsentrasi larutan pembanding 𝐴𝑢 = Absorbansi larutan uji dengan alumunium klorida Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 32 Abu= Absorbansi larutan uji tanpa alumunium klorida Ap = Absorbansi larutan pembanding dengan alumunium klorida Abp= Absorbansi larutan pembanding tanpa alumunium klorida 1,25 = Faktor konstan 3.5.6 Uji Total Kandungan Fenolik 1. Pembuatan reagen a. Pembutan larutan induk asam galat Timabng 50 mg asam galat, tambahkan 1mL etanol 96%. Kemudian tambahkan dengan aquadst hingga volume akhir 50mL. b. Pembuatan larutan 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 10% Timbang 10g 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 , tambahkan aquadest sampai 20mL. Diamkan selama 24 jam. 2. Pembuatan kurva kalibrasi asam galat dengan reagen Fenol FolinCiocalteu Larutan induk asam galat 50 ml (1mg/mL) di pipet 1 mL; 1,25 mL; 1,5 mL; 1,75 mL; dan 2 mL secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan aquadest dengan volume akhir 10mL sehingga dihasilkan konsentrasi 100, 125, 150, 175, 200µg/ml asam galat. Dari masing-masing konsentrasi dipipet 0,2 mL lalu ditambahkan 15,8 mL aquadest dan 1 mL Reagen Folin-Ciocalteu kemudian kocok sampai homogen (diamkan selama 8 menit). Ditambahkan 3 mL larutan 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 10% lalu kocok sampai homogen dan diamkan selama 2 jam pada suhu kamar. Ukur serapan geombang pada serapan maksimum 765 nm dengan spektrofotometer UV-Vis (DeBeer, 2004) 3. Penetapan kandungan fenol total dengan metode Folin-Ciocalteu (Orak, 2006) Timbang 100 mg ekstrak kemudian dilarutkan sampai 10 mL dengan aquades sehingga diperoleh konsentrasi 10 mg/mL. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 33 Kemudian pipet 1 mL dan ditambahkan dengn aquadest hingga 10 mL (1 mg/mL). Pipet 0,2 mL ekstrak, tambahkan 15,8 mL aquadest dan 1 mL regaen Folin-Ciocalteu lalu dikocok. Didiamkan selama 8 menit kemudian ditambahkan 3 mL 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 10%. Setelah itu diamkan selama 2 jam pada suhu kamar. Ukur serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 765. Dilakukan tiga kali pengulangan (triplo). 4. Analisis kandungan total fenolik menggunakan rumus : %= 𝐶𝑝 𝑥 𝐴𝑢−𝐴𝑏 𝑥𝑓𝑥𝑣 𝐴𝑝−𝐴𝑏 𝑊 𝑥 100% Au = Absorbansi larutan uji Ap = Absorbansi larutan standart Ab = Absorbansi larutan kosong Cp = Konsentrasi larutan standart V = Volume larutan uji sebelum pengenceran W = Bobot ekstrak (gram) F = Faktor pengenceran larutan uji 3.5.7 Uji Antioksidan 1. Pembuatan larutan DPPH ( 100 ppm) Ditimbang 10 mg DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) (BM=394,33) dilarutkan dalam 100 mL methanol proanalisis lalu dihomogenkan dan ditempatkan dalam botol berwarna gelap. 2. Penentuan kurva serapan larutan DPPH Diukur serapan dan panjang gelombang maksimum larutan DPPH pada panjang gelombang 400-800 nm dengan blanko metanol (Pro analisa). 3. Penyiapan seri larutan uji fraksi kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 34 Sampel ditimbang 250 mg kemudian di tambahkan methanol pro analisa sampai 500 ml (500 ppm). Buat konsentrasi pengenceran fraksi kulit buah mangga kasturi (Mangifera casturi) , fraksi nheksana, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol dengan konsentrasi 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,625 ppm yang dibuat dalam pelarut metanol pro analisa. 4. Pembuatan larutan pembanding vitamin C Sejumlah 2,5 mg Vitamin C ditimbang, lalu dilarutkan menggunakan metanol proanalisis sampai 25 mL (100 ppm). Kemudian dibuat dengan konsentrasi 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 ppm. 5. Pengukuran serapan perendaman radikal bebas DPPH Pada tabung reaksi dimasukkan 1,5 ml larutan uji. Kemudian ditambah 0,5 ml larutan pereaksi DPPH dikocok sampai homogen, disimpan selama 30 menit ditempat gelap. Kemudian ukur serapan larutan blanko, larutan uji, dan kontrol positif pada panjang gelombang maksimum 517 nm. 6. Analisis antioksidan Presentasi peredaman radikal bebas DPPH dihitung dengan rumus : 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 % inhibisi = ( 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 ) 𝑥 100% Aktivitas penangkapan radikal bebas dari ekstrak dan fraksi ditentukan dengan nilai IC50 yaitu konsentrasi efektif yang dibutuhkan untuk menurunkan 50% intensitas serapan dibandingkan larutan pereaksi DPPH. IC50 dihitung dari persen (%) peredaman serapan berbagai konsentrasi dengan menggunakan regresi linier. Pengujian antioksidan dilakukan triplo dengan menggunakkan microplate 96 well. Dengan menggunakkan larutan DPPH konsentrasi 100 ppm. Dan dihitung serapan nya dengan spektrofotometri UV-Vis. Serapan dihitung pada panjang gelombang 517 nm. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 35 3.5.8 Uji Antikanker 3.5.8.1 Persiapan Larutan Uji 1. Larutan Uji Fraksi Sebanyak 1 mg sampel uji ditimbang dan dilarutkan dengan 50 μl DMSO 0,1%, lalu ditambahkan DMSO 0,1% ad 1000 μl sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Selanjutnya dibuat larutan uji dengan seri konsentrasi 500; 250; 125; 62,5; 31,25; dan 15,625 ppm dari larutan stok 2. Persiapan Kontrol Positif Doxorubisin dipakai sebagai kontrol positif, dibuat larutan dengan mempipet sebnyak 3,75 μl dari larutan induk 2000 ppm, dan ditambahkan 1496,25 μl media DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) sehingga diperoleh konsentrasi doxorubisin 5 ppm. 3. Kontrol DMSO (Kontrol Negatif) Buat pengenceran DMSO 99,5% dengan DMSO pro analisis menjadi konsentrasi 0,1%. Kemudian saring dengan menggunakkan Syiringe filter membrane non pyrogenic. 3.5.8.2 Persiapan Kultur Sel MCF7 Dari koleksi Pusat Studi Primata Bogor, didaptkan sel kanker MCf7 yang disimpan dalam cyro vial dari nitrogen cair dihangatkan dengan water bath dengan suhu 370C beberapa saat lalu di sentrifuse. Setelah itu pindahkan sel ke T-flash yang sudah berisi 5-10 ml medium kultur DMEM,. Kemudian diinkubasi pada inkubator CO2 5 % dengan suhu 37ºC, sampai sel tumbuh dan menempel (±24 jam) (diamati dengan mikroskop apakah sel sudah tumbuh dan menempel). Kemudian media dibuang dan masukan PBS untuk membilas. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 36 3.5.8.3 Uji Proliferasi Sel MCF7 dengan Metode MTT Kemudian sel yang telah dikultur diberi perlakuan sampel dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu : Kelompok Perlakuan 1 (KE1) : dosis 500 ppm Kelompok Perlakuan 2 (KE2) : dosis 250 ppm Kelompok Perlakuan 3 (KE3) : dosis 125 ppm Kelompok Perlakuan 4 (KE4) : dosis 62,5 ppm Kelompok Perlakuan 5 (KE5) : dosis 31,25 ppm Kelompok Perlakuan 6 (KKN) : Sel tanpa perlakuan Kelompok Perlakuan 7 (KN) : DMSO 0,1% Kelompok Perlakuan 8 (KKP) : Doxorubisin 5 ppm Dilakukan pengulangan masing-masing triplo untuk berbagai konsentrasi, termasuk kontrol negatif (kontrol pelarut) dan kontrol positif, dengan volume akhir 100 μL/well. Mikroplate diinkubasi kembali selama 48 jam pada 37°C dalam inkubator dengan kelembabkan 5% CO2. , masing-masing well ditambahkan 10 μL reagen MTT (5 mg /mL). Diinkubasi pada suhu 37°C selama 4 jam. Terjadi perubahan warna kuning menjadi ungu terbantuk kristal formazan. Jika sudah terbentuk kristal formazan tambahkan dengan SDS 10%. Plate dibungkus dan diinkubasi selama 24 jam. Kristal formazon dilarutkan dengan etanol 96% dan kamudian di ukur dengan ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) reader pada panjang gelombang 595 nm. Setelah itu lakukan perhitungan hasil dan menghitung penghambatan sampel ( % inhibisi) dengan rumus : % 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 = 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 100% 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 3.5.8.4 Apoptosis Sel MCF-7 ditanam pada coverslips yang dimasukan dalam microplate 24 sumuran sehingga diperoleh kepadatan 3 X Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 37 104 sel/sumuran dan diinkubasi sampai 50-60% konfluen. Setelah itu diinkubasi dengan senyawa uji selama 24, 48, 72 jam. Medium diambil, dicuci dengan PBS. Cover slip yang memuat sel diangkat, diletakan di atas object glass dan ditambahkan 10 μL 1 X Working Solution etidium bromidaakridin oranye kemudian didiamkan selama 5 menit. Sel segera diamati di bawah mikroskop flouresens (Zeiss MC 80). Sel hidup berfluoresensi hijau (dengan akridin orange) dan sel mati berfluoresensi orange (dengan etidium bromida). (Gow-Chin Yen, 2017). 3.5.8.5 Perhitungan Persen Inhibisi Dengan metode MTT 3-[4,5-dimetilthiazol-2yl]-2,5- difeniltetrazolium bromide , selisih absorbansi kontrol negatif dengan absorbansi sampel uji dibagi absorbansi kontrol negatif dikali dengan 100% merupakan perhitungan untuk mendapatkan presentasi kematian sel. Perhitungan kematian sel (Zakaria, 2011) % Penghambatan Proliferasi = ( 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝑠𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑢𝑗𝑖 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 ) 𝑥 100% 3.5.8.6 Analisa Data Hasil yang diperoleh dari pengukuran serapan sampel dianalisis menggunakan persamaan regresi linier. Persamaan regresi linier (y=a+bx) menggunakan hubungan antara konsentrasi dengan % inhibisi. Kemudian dari hasil regresi linier yang diperoleh dihitung IC50. Untuk mengetahui harga IC50 (Konsentrasi daya hambat 50%) ditentukan dengan menggunakan persamaan regresi linier. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 38 3.5.9 Identifikasi Kandungan Senyawa Fraksi Kulit Buah Kasturi (Mangifera casturi) dengan menggunakkan Gass Chomatography – Mass Spectrocopy (GC-MS) Fraksi aktif antioksidan kulit buah kasturi (Mangifera casturi) dianalisis menggunakan Gas Chromatograpy–Mass Spectroscopy (GC-MS) Shimadzu QP 5000. Sampel sebanyak 1 μL diinjeksikan ke GC-MS yang dioperasikan menggunakan kolom kaca panjang 25 m, diameter 0,25 mm dan ketebalan 0,25 μm dengan fasa diam CP-Sil 5CB dengan temperatur oven diprogram antara 70-270 °C dengan laju kenaikan temperatur 10 °C/menit, gas pembawa Helium bertekanan 12 kPa, total laju 30 mL/menit dan split ratio sebesar 1:50. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta DAFTAR PUSTAKA Amelia, P. (2011). Isolasi , elusidasi struktur dan uji aktivitas antioksidan senyawa kimia dari daun Garcinia benthami Pierre. 2–3. Andriyani S. 2013. Upaya konservasi kasturi (Mangifera casturi), Badan penelitian dan pengembangan kehutanan, bogor, http://forplan.or.id/images/File/Apforgen/flyer/2010/kasturi.pdf[3desember 2017]. Apak R, Kubilai GI, Zyrek M, Karademir SE. 2013. “Novel total antioxidant capacity index for dietary poliphenols and vitamin C ang E, using their cupric ion reducing in the presence neocuproine: cuprac method”. J Agric Food Ari, K., & Darmapatni, G. (2016). Pengembangan Metode Gc-Ms Untuk Penetapan Kadar Acetaminophen Pada Spesimen Rambut Manusia. Jurnal Biosains Pascasarjana Vol. 18 (2016) Pp ©, 18(3), 1–13. Benzie IFF, Strain JJ. 1996. “The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of Antioxidant Power: the FRAP assay”. Analitical Biochemistry 239. Academic in Pr Chung, H.S. dan Woo, W.S., 2001. A quinolone alkaloid with antioxidant activity from the aleurone layer of anthocyanin-pigmented rice. Journal of natural products, 64: 1579–1580. Comşa, Ş., Cîmpean, A. M., & Raica, M. (2015). The story of MCF-7 breast cancer cell line: 40 Years of experience in research. Anticancer Research, 35(6), 3147–3154. CRCC (Community College Research Center). 2009. Prosedur Tetap Uji Sitotoksik Metode MTT. Yogyakarta: Fakultas Farmasi, UGM. Davey, Patrick. (2005). At A Glance Medicine. Jakarta: Erlangga De Beer, D., Harbertson, J. F., Kilmartin, P. A., Roginsky, V., Barsukova, T., Adams, D. O., & Waterhouse, A. L. (2004). Phenolics: A comparison of diverse analytical methods. American Journal of Enology and Viticulture, 55(4), 389– 400. 39 40 Depamede, S.N Rosyidi, A. 2009. Penghambatan Proliferasi Limfosit Mencit Balb/C oleh Ekstrak Testis Sapi Bali : Peran TGF-β. Media Peternaka. 32(2): 95-103 DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. 2009. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach 7th Ed. United States (US): McGraw-Hill Companies Farmakope Indonesia edisi IV tahun (1995). Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Freshney, R.I. 2010. Culture of Animal Cells a Manual of Basic Technique and Specialized Application 6th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons Gawlik-Dziki, U., Świeca, M., Sułkowski, M., Dziki, D., Baraniak, B., & Czyz, J. (2013). Antioxidant and anticancer activities of Chenopodium quinoa leaves extracts - In vitro study. Food and Chemical Toxicology, 57, 154–160. https://doi.org/10.1016/j.fct.2013.03.023 Hamdani., R. A. Seprima., Suranto dan D. Wiranda. 2009. Laporan Praktek Kerja Lapangan Pengolahan Teh. Universitas Sumatera Utara Press. Medan. Hanani, E. 2015. Analisis Fitokimia. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. Hery Winarsi. 2007. Antioksidan Alami dan Radikal Bebas. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 189-90 Irawan, B., 2010. Peningkatan Mutu Minyak Nilam dengan Ekstraksi dan Destilasi pada Berbagai Komposisi Pelarut, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Khairiah, K., Taufiqurrahman, I., & Putri, D. K. T. (2018). Antioxidant activity test of ethyl acetate fraction of binjai (Mangifera Caesia) leaf ethanol extract. Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi), 51(4), 164. https://doi.org/10.20473/j.djmkg.v51.i4.p164-168 Kosir, M.A. 2015. Breast Cancer, USA: Merck. Diakses melalui : http://www.merckmanuals.com/professional/gynecologyandobstetrics/breast disorders/breastcancer (Accessed 12 November 2018) Kumar, M. K., Nagaraju, K., Satyabrata, B., & Sudhakar, M. (2014). Formulation and Evaluation of Sublingual Tablets of Terazosin Hydro- Chloride. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 41 International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 5(10), 4117–4128. https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.5(10).4117-28 Kristanti, A. N., N. S. Aminah, M. Tanjung, dan B. Kurniadi. 2008. Buku Ajar Fitokimia. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 23, 47. Lauricella, M., Galbo, V. Lo, Cernigliaro, C., Maggio, A., Piccionello, A. P., Calvaruso, G., … D’Anneo, A. (2019). The anti-cancer effect of mangifera indica L. Peel extract is associated to γH2Ax-mediated apoptosis in colon cancer cells. Antioxidants, 8(10). https://doi.org/10.3390/antiox8100422 Macabeo, A. P. G., Krohn, K., Gehle, D., Read, R. W., Brophy, J. J., Franzblau, S. G., & Aguinaldo, M. A. M. (2008). Activity of the extracts and indole alkaloids from Alstonia scholaris against Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Philippine Agricultural Scientist, 91(3), 348–351. Ministry of Health Republic of Indonesia. (2015). Data and information on cancer situation (Data dan Informasi Kesehatan Situasi Penyakit Kanker). Buletin Kanker, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 Molyneux P. (2004). The use of the stable free radical diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for estimating anti-oxidant activity. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 26(May), 211–219. Mongkolsilp, S., Pongbupakit, I., Sae-lee, N., Sitthithaworn, W. 2004. Radical Scavenging activity and total phenolic content of medical plants used in primary health care. Jurnal of Pharmacy and Science. 9(1) :32-35. Mukhriani. 2011 “Ekstraksi, pemisahan senyawa, dan identifikasi senyawa aktif,” UIN Allaudin Press. Medan. Munawaroh, R., Siswadi, S., Setyowati, E. P., Murwanti, R., & Hertiani, T. (2018). Correlation Between Total Flavonoid Contents and Macrophage Phagocytosis Activity of Fractions From Faloak (Sterculia quadrifida R.Br.) Barks Ethanolic Extract In Vitro. Majalah Obat Tradisional, 23(1), 47. https://doi.org/10.22146/mot.30882 Mutiasari, IR. 2012. Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Fraksi Aktif, Journal. Jakarta: FMIPA-UI Ningsih, D. R. (2017). EKSTRAK DAUN MANGGA (Mangifera indica L.) SEBAGAI ANTIJAMUR TERHADAP JAMUR Candida albicans DAN IDENTIFIKASI GOLONGAN SENYAWANYA. Jurnal Kimia Riset, 2(1), 61. https://doi.org/10.20473/jkr.v2i1.3690 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 42 Nugrahani, R., Andayani, Y., & Hakim, A. (2016). SKRINING FITOKIMIA DARI EKSTRAK BUAH BUNCIS (Phaseolus vulgaris L) DALAM SEDIAAN SERBUK. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 2(1). https://doi.org/10.29303/jppipa.v2i1.38 Oliveira, L. M. B., Bevilaqua, C. M. L., Costa, C. T. C., Macedo, I. T. F., Barros, R. S., Rodrigues, A. C. M., … Navarro, A. M. C. (2009). Anthelmintic activity of Cocos nucifera L. against sheep gastrointestinal nematodes. Veterinary Parasitology, 159(1), 55–59. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2008.10.018 Patra, A. K., & Saxena, J. (2009). The effect and mode of action of saponins on the microbial populations and fermentation in the rumen and ruminant production. Nutrition Research Reviews, 22(2), 204–219. https://doi.org/10.1017/S0954422409990163 Radji, Maksum. 2016. Mekanisme Aksi Molekuler Antibiotik dan Kemoterapi. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC Rahman, N., Bahriul, P., & Diah, A. (2014). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Salam (Syzygium Polyanthum) Dengan Menggunanakan 1,1-Difenil2-Pikrilhidrazil. Jurnal Akademika Kimia, 3(3), 143–149. Rashedy, A. A., Kheshin, M. A. El, Allatif, A. M. A., & Besinnara, H. (2014). Histological Parameters Related to Dwarfism in Some Mango Cultivars. World Journal of Agricultural Sciences, 10(5), 216–222. https://doi.org/10.5829/idosi.wjas.2014.10.5.1826 Rasjidi, I. 2010. Epiemiologi Kanker Pada Wanita. Jakarta: Sagung Seto Rosyidah, K., Nurmuhaimina, S. A., Komari, N., & Astuti, M. D. (2012). AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI SAPONIN DARI KULIT BATANG TUMBUHAN KASTURI (Mangifera casturi). Alchemy, 1(2), 65–69. https://doi.org/10.18860/al.v0i0.1674 Ryan, M., Rahardhian, R., Utami, D., Farmasi, P. S., Farmasi, F., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (1999). UJI SITOTOKSIK DAN ANTIPROLIFERASI EKSTRAK ETER DAUN BINAHONG ( A ndredera cordifolia ( Tenore ) Steen .) TERHADAP SEL HeLa. 13(1), 1284–1292. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 43 Sarker SD, Latif Z, & Gray AI. 2006. Natural products isolation. In: Sarker SD, Latif Z, & Gray AI, editors. Natural Products Isolation. 2nd ed. Totowa (New Jersey). Humana Press Inc. hal. 6-10, 18. Sayuti, K. (n.d.). Antioksidan, Alami dan Sintetik, 2015;(1)7-29. Seidel V. Initial and ulkextraction. In: Sarker SD, Latif Z & Gray Al, editors. 2006. Natural product Isolation, 2nd ed. Totowa (Ney Jersey). Humana Press Inc. hal. 31-5 Senet, M. R. M., Raharja, I. G. M. A. P., Darma, I. K. T., Prastakarini, K. T., Dewi, N. M. A., & Parwata, I. M. O. A. (2018). PENENTUAN KANDUNGAN TOTAL FLAVONOID DAN TOTAL FENOL DARI AKAR KERSEN (Mutingia calabura) SERTA AKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIOKSIDAN. Jurnal Kimia, 13. https://doi.org/10.24843/jchem.2018.v12.i01.p03 Septiana, E., Bustanussalam, B., Rachman, F., Hapsari, Y., & Simanjuntak, P. (2017). Potensi Ekstrak Kapang Endofit Asal Rimpang Kunyit Sebagai Antimalaria dan Antioksidan. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 7(1). https://doi.org/10.22435/jki.v7i1.5669.1-9 Shaban, A. E. A. (2009). Vegetative Growth Cycles of Some Mango Cultivars in Relation to Flowering and Fruiting. 5(6), 751–759. Simon K, Kerry B.(2000) Principles and Pracice of Phytotheraphy. Modern Herbal Medicine. New York: Churchill Livingstone Singh, J., & Basu, P. S. (2012). Non-Nutritive Bioactive Compounds in Pulses and Their Impact on Human Health: An Overview. Food and Nutrition Sciences, 03(12), 1664–1672. https://doi.org/10.4236/fns.2012.312218 Sirait, P. S., & Setyaningsih, I. (2019). Aktivitas Antikanker Ekstrak Sprirulina yang Dikultur Pada Media Walne dan Media Organik. Jphpi, 22, 50–59. Sogandi, S. & Klustiana, D. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Fraksi Kulit Buah Mangga Kasturi (Mangifera casturi Kosterm) Terhadap bakteri Listeria monocytogenes DNA Salmonella typhi. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Sukandar, D., Hermanto, S., & Lestari, E. (2008). Uji Toksisitas Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Jurnal Kimia VALENSI, 1(2). https://doi.org/10.15408/jkv.v1i2.217 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 44 Sunaryati, S.S. 2011. 14 Penyakit Paling Sering Menyerang dan Mematikan. Jogjakarta: Flash Books Stanković, M. (2011). Total phenolic content, flavonoid concentration and antioxidant activity of Marrubium peregrinum L. extracts. Kragujevac Journal of Science, (33), 63–72. Stopeck AT. 2014. Breast Cancer Risk Factors. Arizona. Medscape. Tersedia dari http://emedicine,medscape.com. Sutomo, S., Azhari, H., Arnida, A., Fadlilaturrahmah, F., & Yunus, R. (2017). Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Antioksidan Dari Buah Kasturi (Mangifera casturi Kosterm.). Jurnal Pharmascience, 4(2). https://doi.org/10.20527/jps.v4i2.5778 Syafni, N., Putra, D. P., & Arbain, D. (2012). 3,4-dihydroxybenzoic acid and 3,4dihydroxybenzaldehyde from the fern Trichomanes chinense L.; isolation, antimicrobial and antioxidant properties. Indonesian Journal of Chemistry, 12(3), 273–278. https://doi.org/10.22146/ijc.21342 Tanaya, V., Retnowati, R., & Suratmo. (2015). Fraksi semi polar dari daun mangga kasturi (Mangifera casturi Kosterm). Kimia Journal, 1(1), 778–784. Tulus Tambunan, 2003. Perkembangan Sektor Pertanian di Indoneisa, Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia Jakarta. Vincken JP, Heng L, de Groot A, Gruppen H (2007) Saponins, classification and occurrence in the plant kingdom. Phytochemistry 68:275–297 Werdhasari, A. (2014). Peran Antioksidan Bagi Kesehatan. Indonesian Journal of Biotechnology Medicine, 3(2), 59–68. https://doi.org/10.22435/jbmi.v3i2.4203.59-68 Widiyati, E. (2006). Penentuan Adanya Senyawa Triterpenoid Dan Uji Aktivitas Biologis Pada Beberapa Spesies Tanaman Obat Tradisional Masyarakat Pedesaan Bengkulu. Jurnal Gradien, 2(1), 116–122. Widjaya, C. H. (2014). Peran Antioksidan Terhadap Kesehatan Tubuh. Healty Choice: Edisi IV Wijayakusuma, H. 2008. Atasi Kanker dengan Tanaman Obat. Jakarta : puspa Swara. Yadavalli, R., Ratnapuram, H., Motamarry, S., & Fathima, M. N. (2019). Department of Biotechnology. The Grants Register 2019, 284–284. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 45 https://doi.org/10.1007/978-1-349-95810-8_400 Yen, G. C., Chen, C. S., Chang, W. T., Wu, M. F., Cheng, F. T., Shiau, D. K., & Hsu, C. L. (2018). Antioxidant activity and anticancer effect of ethanolic and aqueous extracts of the roots of Ficus beecheyana and their phenolic components. Journal of Food and Drug Analysis, 26(1), 182–192. https://doi.org/10.1016/j.jfda.2017.02.002 Yudissanta, A., & Ratna, M. (2012). Analisis Pemakaian Kemoterapi pada Kasus Kanker Payudara dengan Menggunakan Metode. Sains Dan Seni Its, 1(1). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/15866-IDanalisis-pemakaian-kemoterapi-pada-kasus-kanker-payudara-denganmenggunakan-meto.pdf Zakaria, Z. A., Mohamed, A. M., Jamil, N. S. M., Somchit, M. N., Zuraini, A., Rofiee, M. S., … Sulaiman, M. R. (2011). In vitro cytotoxic and antioxidant properties of the aqueous, chloroform and methanol extracts of dicranopteris linearis leaves. African Journal of Biotechnology, 10(2), 273–282. https://doi.org/10.5897/AJB10.423 Zempieri, L., et al. 2002, Differential Modulation by Estradiol of P-glycoprotein Drug Resistance Protein Expression in Cultured MCF7 dan T47D Breast Cancer Cells. Anticancer Res. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 46 Lampiran 1. Skema Prosedur Kerja Determinasi Ekstraksi Kulit Buah Mangga Kasturi (Mangifera casturi) Fraksinasi (Metanol, n-heksan, etil asetat) Skrining Fitokimia Total Kandungan Fenol & Total Kandungan Flavonoid Uji aktivitas Antioksidan (DPPH) Proliferasi dengan metode MTT Assay (3[4,5-dimetilthiazol-2yl]2,5-difeniltetrazolium bromide. Uji sitotoksisitas Terhadap Sel Kanker Payudara (MCF7) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 47 Uji Apoptosis Identifikasi Senyawa menggunakkan Gass Chomatography-Mass Spectrocopys Lampiran 2. Skema Uji Antioksidan Fraksi Kulit Buah Mangga Kasturi (Mangifera casturi) Pembuatan Larutan DPPH (10 mg DPPH dilarutkan dalam 100 mL methanol p.a) Uji Antioksidan dilakukan dengan metode DPPH Penetapan Panjang Gelombang Maksimum DPPH Pembuatan Larutan Kontrol Positif Vitamin C Penyiapan Seri Larutan Uji ( 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,625 ppm) Fraksi n-heksan Fraksi etil asetat Pembuatan Larutan Blanko (0,5 mL DPPH + 1,5 mL Methanol p.a) Fraksi metanol Ukur serapan larutan kontrol positif, larutan uji, dan larutan blanko pada panjang gelombang maksimum DPPH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 48 Analisis data % inhibisi Nilai IC50 Lampiran 3. Skema Uji Proliferasi dengan MTT Sel Kanker Payudara MCF7 koleksi Pusat Studi Primata, Bogor Dihangatkan dengan waterbath suhu 37°C Kultur pada medium DMEM. Inkubasi pada inkubator CO2 5%. Dengan suhu 37°C selama 24 jam. Amati dengan mikroskop pertumbuhan kultur sel Buang media kemudian bilas plat dengan menggunakan PBS Beri larutan uji dengan konsentreasi (500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,625 ppm) Kontrol Negatif (DMSO 0,1%) Kontrol Positif (Doxorubicin) Sel Normal Dilakukan 3 kali pengulangan (triplo) Inkubasi kembali selama 48 jam pada suhu 37°C dalam inkubator . Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 49 Diinkubasi selama 4 jam pada suhu 37°C Ditambah 10µL reagen MTT pada masing masing well Terbentuk kristal formazon. Tambah SDS 10% Pembacaan Absorbansi pada Elisa Reader Persen Inhibisi Larutkan kristal dengan etanol 96% IC50 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta