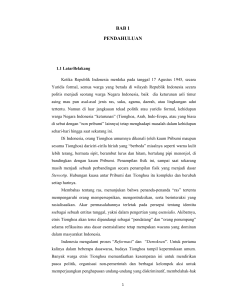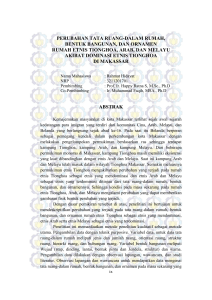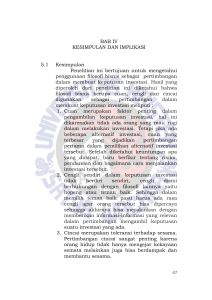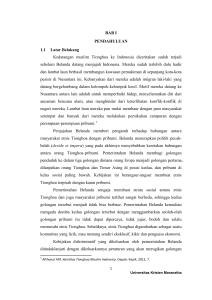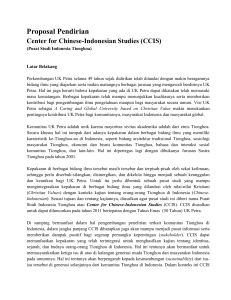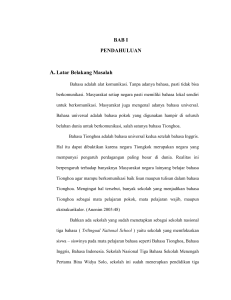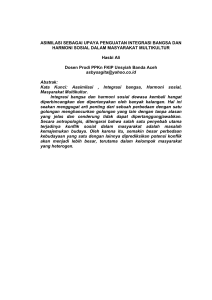BAB 1 PENDAHULUAN
advertisement

BAB 1 PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Masalah: Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatua Republik Indonesia memiliki beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai pusat aktivitas perkembangan negara terdapat berbagai etnis atau suku bangsa yang datang ke kota ini. Beberapa etnis atau suku bangsa seperti: Melayu, Arab, China, serta India, yang merupakan bagian dari warga Jakarta saat ini yang telah tinggal di kota ini sejak dulu. Salah satu etnis yang paling menonjol perannya dalam perkembangan di Jakarta, khususnya dibidang ekonomi dan industri, adalah etnis China atau yang biasa kita sebut sebagai keturunan Tionghoa. Gelombang migrasi orang-orang Tionghoa secara Individual dari daratan China ke berbagai pelosok wilayah di seluruh Indonesia, telah berlangsung lama dan itu terjadi jauh sebelum zaman Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) datang. Kaum Belanda dan priayayi menjadi penguasa, masyarakat Tionghoa menjadi masyarakat menengah yang bergerak di bidang perdagangan saja, sementara bagian terbesar rakyat jelata menjadi kaum yang senantiasa ditindas. Kesenjangan ekonomi dan politik menjadi nyata dalam situasi tersebut. Sebagai masyarakat perantauan, mereka memiliki kekuatan yang cukup besar, dari segi jumlah maupun dari segi peran. Hanya sayangnya, mereka selalu di tempatkan dalam posisi mengembang baik dari segi hokum maupun kehidupan social. Mereka menjadi masyarakat yang identitasnya selalu dibuat 1 2 tidak mengakar. Sejak zaman penjajahan Belanda, Tionghoa selalu dijadikan “target operasi” konflik politik. Bahkan, ketika bangsa ini sudah merdeka dan merumuskan cita-cita perjuangannya dalam wadah Pancasila yang egaliter dan jauh sentiment etnis itu, Tionghoa masih menjadi tumbal kekuasaan. Warga keturunan Tionghoa selalu dijadikan kambing hitam. Minoritas Tionghoa dicap eksklusif, tidak mau berbaur, tahunya hanya berdagang, tidak punya nasionalisme, tidak peduli nasib bangsa, dan seterusnya. Labellisasi itu tentu tidak sepenuhnya tepat. Ketika Indonesia sudah merdeka, diskriminasi terhadap warga Tionghoa tidak mengalami perubahan. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, melarang hampir semua bentuk perdagangan eceran daerah pedalaman yang berada di tangan orang-orang Tionghoa. Dengan demikian Pemerintah Indonesia tidak saja membatasi pembauran, tetapi juga mengesampingkan kedudukan masyarakat tionghoa dalam kehidupan social desa.(Suparlan, 1979) Sama halnya ketika Indonesia memasuki era Orde Baru, Presiden Soeharto juga melakukan pembatasan melalui Intruksi Presiden No.14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Inpres ini yang kemudian menjadi dasar bagi dilarangnya bentuk-bentuk ekspresi keagamaan, kepercayaan dan adat-istiadat masyarakat Tionghoa di depan umum (黄昆章, 2005). Kaum Tionghoa hanya bisa bergerak di bidang ekonomi, sementara pribumi mendominanasi bidang politik dan pemerintahan. Akhirnya terjadilah 3 kolusi antara penguasa dan pengusaha. Ketergantungan etnis Tionghoa semakin dinintensifkan dalam lingkaran kekuasaan, terutama menyangkut jaminan keamanan, perlindungan, dan proteksi ekonomi. Bila akhirnya munculah budaya suap, kelompok minoritas inilah yang dipersalahkan oleh masyarakat. Mereka, yang menurut pendapat umum warga Tionghoa terbiasa dengan main sogok, seakan-akan dituduh atau dicap sebagai biang keladi budaya korupsi. Hal ini jarang sekali dipandang secara objektif, bahwa sesungguhnya dipihak lain para aparat dan pegawai borokrasi juga yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, sehingga memeras kelompok minoritas ini yang tengah terjepit kepentingannya. Dari sinilah, mitos-mitos yang salah tentang orang-orang Tionghoa itu semakin terkukuhkan lagi. Pengusaha keturunan Tionghoa yang melakukan bisnis melalui jalan KKN mungkin hanya beberapa pengusaha, tetapi menyebapkan hampir semua pengusaha Tionghoa dicap Tionghoa KKN. Stempel ini bahkan sudah ada sejak zaman colonial Belanda dulu. Kiprah segelintir pengusaha Tionghoa yang menikmati hasil pembangunan itulah, yang membuat jurang pemisah dan rasa kebencian bagi masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa. Salah satu peristiwa yang merupakan contoh nyata perihal telah berkembangnya rasa sentiment masyarakat umum terhadap eksistensi warga minoritas ini kerusuhan Mei tahun 1998 silam (Suparlan, 1979) Memasuki era reformasi eksistensi masyarakat Tionghoa mulai diakui. Presiden abduraahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden Nomer 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 (dalam Latar belakang meihwa-flim, 2006). Dan pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri, 4 beliau menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa adalah bagian dari bangsa ini, dan kedudukannya harus disamaratakan. Seperti suami beliau Taufik Kemas, Mega Wati selalu memberi perlakuan yang sama terhadap warga Tionghoa, di dalam suatu kabinetpun paling sedikit ada seorang warga keturunan Tionghoa memegang jabatan mentri. Mega Wati juga menetapkan hari Raya Imlek dalam daftar tanggal merah almanak Indonesia, melengkapi pengakuan identitas yang selama ini dibatasi oleh penguasa (李卓辉,2004). Hal ini memang cukup mengembirakan, namun sampai hari ini, yang terjadi baru wilayah permukaan dan simbolik. Sebab, dalam praktek kehidupan warga Tionghoa sehari-hari, apabila dibeberapa tempat tertentu, mereka tetap memperoleh perlakuan berbeda. Etnis Tionghoa kini masih kerap mengalami diskriminasi seperti diminta Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) yang secara resmi tidak dibutuhkan lagi. Salah satu bentuk perlakuan yang membedakan terhadap warga Tionghoa yang terungkap adalah wawancara Wimar kepada beberapa nara sumber dalam acara Wimars World pada tanggal 14 februari 2007 di Jak TV. Berdasarkan wawancara dari nara sumber Lucky krompis, Hendrawan, dan Anton J Supit, sebagai etnis Tionghoa, terungkap bahwa mereka masih harus menggunakan SBKRI untuk pembuatan surat-surat penting seperti KTP, akte kelahiran, paspor, dan sebagainya. Hal tersebut seperti belum sepenuhnya menunjukan tercapainya persamaan hak sipil. Selain itu narasumber Toni dan Hendrawan (keturunan Tionghoa) mengatakan bahwa mereka harus dimintau uang oleh petugas untuk mempelancar pembuatan paspor. 5 Hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi penulis, sudahkah diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa benar-benar lepas? Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, dimana terdapat keragaman etnik, kultur, bahasa, agama, dan keyakinan ini, peluang masyarakat untuk berprasangka negatif terhadap orang lain cukup besar. Prasangka social inilah yang dapat membawa masyarakat di suatu daerah untuk bertindak diskriminatif, dalam hal ini terhadap warga keturunan Tionghoa. Tindakan-tindakan diskriminatif atau berbeda diartikan sebagai tindakantindakan yang bercorak menghambat, merugikan perkembangan, bahkan mengecam kehidupan pribadi orang-orang hanya karena mereka kebetulan termasuk golongan yang diprasangkai itu. (Gerungan, 2004). Melalui pernyataan ini dapat dikatakan bahwa munculnya diskriminasi terhadap golongan tertentu dapat diawali dengan munculnya prasangka. Prasangka yang terjadi terhadap golongan etnis Tionghoa merupakan fenomena prasangka social. Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang berbeda dengan golongan orang yang berprasangka itu. Prasangka sosial terdiri dari sikap-sikap sosial yang negatif terhadap golongan lain dan tidak mempengaruhi tingkah lakunya terhadap golongan manusia lain tadi. Prasangka sosial yang pada umumnya hanya merupakan sikap-sikap persaan negatif itu lambat laun menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap orangorang yang termasuk golongan-golongan yang diprasangkai itu tanpa terdapat alasan-alasan yang objektif pada pribadi orang yang dikenai tindakan-tindakan diskriminatif. 6 Prasangka itu datang bisa dikarnakan adanya pengaruh-pengaruh sejarah, dari lingkungan, dan bisa juga dari pengalaman yang mereka alami, yang menjadikan prasangka itu ada dan ditujukan kepada golongan yang sama, dan sebenarnya mereka belum tentu mempunyai sifat yang sama. Prasangka bisa terjadi kepada siapapun, termasuk para mahasiswa dengan latar belakang yang sudah cukup tinggi mahasiswa adalah intelektual, yaitu berfikir logis. Berpikir logis, artinya berpikir dengan yang jernih dan sehat. Tindakan logis, artinya tidak melakukan sebuah tindakan terlebih dahulu, sebelumnya tindakan itu dipertimbangan matang-matang melalui pikiran, nalar yang sehat, mempunyai pemikiran yang sangat luas, dan bisa memilih mana yang baik dan buruk. Maka penulis memilih mahasiswa untuk dijadikan objek penelitian. 1. 2. Perumusan Masalah: Analisa Gambaran prasangka sosial mahasiswa pribumi terhadap warga Tionghoa (dari segi psikologi sosial). 1. 3. Ruang Lingkup Masalah: Ruang lingkup pada penelitian ini mencangkup mahasiswa pribumi di beberapa Universitas di Jakarta, yaitu: Universitas Al-azhar (Jakarta selatan), Universitas Bina Nusantara (Jakarta barat), Universitas Darma Persada (Jakarta timur), Universitas Kedokteran Iarsi (Jakarta pusat), Universitas Bunda Mulia (Jakarta Utara) dan Universitas Indonesia (Depok). 1. 4. Tujuan dan Manfaat Penulisan: Tujuan penulisan peneliti adalah mengetahui masih adakah sikap prasangka sosial oleh mahasiswa pribumi terhadap warga Tionghoa di Jakarta. 7 1. 5. Metodologi Penulitian: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif (dengan instrument kuesioner), kualitatif (dengan wawancara beberapa sumber) dan studi kepustakaan untuk memeperkuat data dan informasi yang berhubungan skripsi ini, baik dari buku, maupun internet. 1. 6. Sistematika penulisan: BAB 1 Pendahuluan Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. BAB 2 Landasan Teori Membahas tentang ada dan tidak adanya prasangka dari sisi teori “Psikologi Sosial”. BAB 3 Analisa Data Akan menbahas gambaran prasangka sosial mahasiswa pribumi terhadap warga Tionghoa dari hasil penelitian. BAB 4 Kesimpulan dan Saran Bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran. BAB 5 Ringkasan Bab ini akan membahas ringkasan isi skripsi dari bab 1-4.