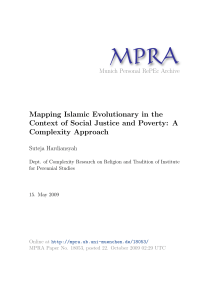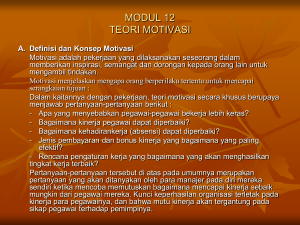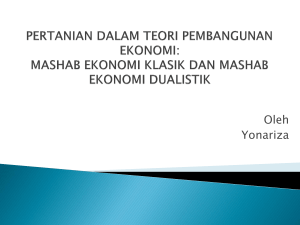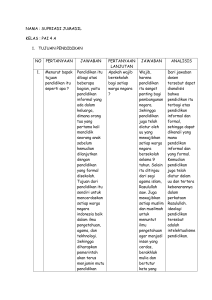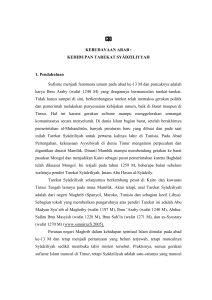MERUMUSKAN KEBERISLAMAN SECARA BARU Audith M
advertisement
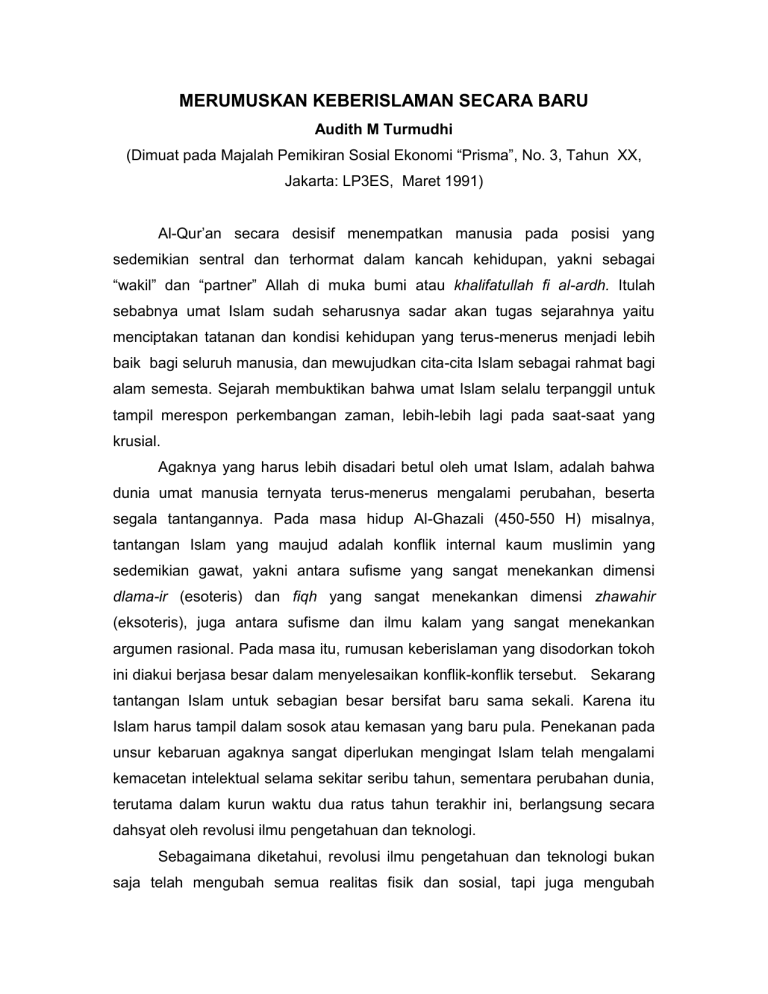
MERUMUSKAN KEBERISLAMAN SECARA BARU Audith M Turmudhi (Dimuat pada Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi “Prisma”, No. 3, Tahun XX, Jakarta: LP3ES, Maret 1991) Al-Qur’an secara desisif menempatkan manusia pada posisi yang sedemikian sentral dan terhormat dalam kancah kehidupan, yakni sebagai “wakil” dan “partner” Allah di muka bumi atau khalifatullah fi al-ardh. Itulah sebabnya umat Islam sudah seharusnya sadar akan tugas sejarahnya yaitu menciptakan tatanan dan kondisi kehidupan yang terus-menerus menjadi lebih baik bagi seluruh manusia, dan mewujudkan cita-cita Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Sejarah membuktikan bahwa umat Islam selalu terpanggil untuk tampil merespon perkembangan zaman, lebih-lebih lagi pada saat-saat yang krusial. Agaknya yang harus lebih disadari betul oleh umat Islam, adalah bahwa dunia umat manusia ternyata terus-menerus mengalami perubahan, beserta segala tantangannya. Pada masa hidup Al-Ghazali (450-550 H) misalnya, tantangan Islam yang maujud adalah konflik internal kaum muslimin yang sedemikian gawat, yakni antara sufisme yang sangat menekankan dimensi dlama-ir (esoteris) dan fiqh yang sangat menekankan dimensi zhawahir (eksoteris), juga antara sufisme dan ilmu kalam yang sangat menekankan argumen rasional. Pada masa itu, rumusan keberislaman yang disodorkan tokoh ini diakui berjasa besar dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Sekarang tantangan Islam untuk sebagian besar bersifat baru sama sekali. Karena itu Islam harus tampil dalam sosok atau kemasan yang baru pula. Penekanan pada unsur kebaruan agaknya sangat diperlukan mengingat Islam telah mengalami kemacetan intelektual selama sekitar seribu tahun, sementara perubahan dunia, terutama dalam kurun waktu dua ratus tahun terakhir ini, berlangsung secara dahsyat oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana diketahui, revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja telah mengubah semua realitas fisik dan sosial, tapi juga mengubah persepsi dan pandangan kita tentang kehidupan. Kuatnya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengubah pandangan tentang kehidupan, telah menjadikannya mencapai posisi ideologi. Ilmu dan teknologi, kata Habermas, kini telah menjadi ideologi tersendiri yang mempunyai kekuatan untuk mendikte sejarah dan mentransformasikannya untuk kepentingannya sendiri. Islam adalah karunia dan rahmat Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia (dan bukan sebaliknya), untuk membimbing umat manusia sepanjang zaman. Itu sebabnya Islam sangat berkepentingan terhadap seluruh realitas hidup umat manusia , baik dalam realitas subjektif (kesadaran, motif-motif dan sikap-sikap jiwa), realitas simbolis (ilmu dan seluruh konsep-konsep intelektual), maupun dalam realitas objektif (seluruh karya atau hasil pemikiran, baik berupa sistem-sistem sosial-ekonomi-politik-budaya yang kita bangun atau kita afirmasi, maupun berwujud barang-barang atau benda-benda yang kita hasilkan). Karena ketiga realitas tersebut senantiasa dalam perubahan, maka pembaruan keberislaman adalah keharusan sejarah yang terus-menerus. Berkaitan dengan itu, Al-Qur’an memberikan dua macam petunjuk: pertama, petunjuk tentang nilai-nilai kebenaran yang bersifat mutlak-eternal; kedua, petunjuk tentang bagaimana mengeksteriorisasikan nilai-nilai kebenaran tersebut dalam konteks ruang, waktu dan peristiwa tertentu, melalui contoh respon kongkret Qur’ani terhadap realitas sejarah. Jadi ada kebenaran yang eternal dan ada pula kebenaran yang temporal. Sedangkan tindakan nyata Nabi Muhammad SAW., dapat kita pandang sebagai contoh-contoh lebih detil lagi mengenai bagaimana eksteriorisasi atau penerjemahan nilai-nilai kebenaran eternal dalam konteks ruang dan waktu; sekaligus sebagai contoh sebaik-baiknya setelah Al-Qur’an sendiri. Dari situ sebenarnya umat Islam dapat merumuskan metodologi eksteriorisasi setelah terlebih dahulu merumuskan nilai-nilai kebenaran eternal Al-Qur’an dan memahami dengan baik struktur dan kondisi sosio-kultural masyarakat pada masa hidup Rasulullah. Dengan metodologi tersebut, proses eksteriorisasi di masa sekarang dan di masa mendatang akan berlangsung secara lebih terbimbing. Adapun hasil pemikiran para ulama, terutama karya-karya intelektual klasik yang merupakan hasil perumusan gemilang pada periode formatif Islam, yakni pada kurun waktu sekitar dua setengah abad setelah wafatnya Rasulullah, harus kita pandang sebagai warisan kultural Islam yang luar biasa berharga untuk kita dialogi, namun tidak untuk mendikte. Kita harus terus-menerus membangkitkan intelektualisme kita sendiri, karena hidup harus kita orientasikan ke masa kini dan ke masa depan, bukan ke masa lalu. Semangat atau nilai kebenaran eternal Al-Qur’an harus terus-menerus kita terjemahkan di dalam konteks zaman yang terus berkembang. Maka pembaruan, bukan saja diperlukan karena Islam telah mengalami degenerasi pada pasca periode formatif sebagai akibat pergaulan Islam dengan pelbagai budaya lokal dan pelbagai faham non-Islam, tetapi juga karena maturitas umat manusia secara keseluruhan oleh akumulasi pengalaman sejarahnya tentunya terus berkembang, juga karena perkembangan kompleksitas zaman. Dan umat Islam, sebagai umat yang meyakini kebenaran Al-Qur’an, tentulah harus selalu dapat menegakkan suatu leading Islamic civilization, sebagaimana telah terbukti pada masa-masa kejayaan umat Islam dahulu, bukan seperti kenyataan sekarang. Lemahnya posisi Islam di tengah peradaban dunia saat ini pastilah akibat kecelakaan sejarah atau pada dasarnya karena kesalahan umat Islam sendiri. Jadi seluruh produk historical Islam, harus sungguh-sungguh kita kritisi, karena status kebenarannya relatif. Bahkan juga terhadap apa yang kita persepsikan sebagai nilai-nilai kebenaran mutlak-eternal itu pun tetap harus kita buka kemungkinan kekeliruan dan kekuranglengkapannya. Problematika Global Dewasa ini umat manusia dihadapkan pada berbagai masalah global mondial yang luar biasa serius. Kondisi lingkungan hidup kita sudah sedemikian gawat mengancam keselamatan seluruh umat manusia – dengan jebolnya lapisan ozon di atas kutub selatan, naiknya permukaan air laut, turunnya hujan asam, memanasnya suhu udara dan mulai kacaunya iklim, dan lain-lain. Semua itu tidak lain sebagai akibat ulah manusia sendiri, yakni oleh filsafat materialisme dan ateisme yang menuntun pandangan masyarakat dunia, yang mendasari dan menyemangati ilmu, teknologi, industri, praktik bisnis dan seluruh pola hubungan eksploitatif, baik antar manusia maupun manusia dengan alam. Peradaban kita dewasa ini digerakkan oleh jiwa dan semangat yang penuh keserakarahan, kesombongan, egoisme, hedonisme dan ketidakpedulian akan kebutuhan dan kesusahan sesama manusia, alam dan kehidupan di masa depan. Disebutkan olah Erich Fromm, bahwa masyarakat moderen adalah masyarakat yang acquisitive, yakni masyarakat yang berorientasi dan bermodus eksistensi to have, penuh nafsu untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi, tak puas-puasnya. Dalam masyarakat demikian, mendemonstrasikan kekuasaan dan kesuksesan material, merampas kesempatan dan hak-hak orang lain, menjadi pola-pola perilaku umum. Filsafat dan sikap jiwa tersebut adalah sumber dari pelbagai-bagai krisis: ekologi, sosial-budaya dan kemanusiaan. Alhasil, dalam zaman yang oleh Tillich disebut sebagai the age of anxiety ini, kebahagiaan makin jauh dari batin umat manusia. Padahal semangat yang sakit itu menebar ke mana-mana, berpusar keras di seluruh atmosfer kehidupan, tak terkecuali ke tengah-tengah masyarakat kita. Dengan demikian problematika keindonesiaan saat ini, untuk sebagian utamanya, dapat dilihat dalam perspektif problematika global umat manusia sebagaimana diterangkan di atas. Marjinalisasi dan penggusuran masyarakat kecil oleh kekuatan-kekuatan industrial, ketimpangan penguasaan sumbersumber ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan sehingga terjadi keberlimpahan pada sekelompok anggota masyarakat di satu pihak dan kemiskinan rakyat banyak di pihak lain, tidak terlepas dari globalisasi semangat materialisme-individualisme. Kuatnya pemihakan kekuasaan pada kepentingan industrial, dan lemahnya pembelaan pada kebutuhan rakyat-kecilbanyak, yakni kaum tani, pedagang kecil, buruh, kaum pencari kerja – yang semua itu seakan-akan menjadi beyond help oleh sebab lemahnya kekuatan sipil dalam mengontrol kebijakan-kebijakan penguasa, akibat belum cukup dikembangkannya demokrasi politik di negeri ini – adalah buah yang wajar dari sistem ekonomi kapitalistik yang kita terapkan. Suatu sistem kapitalistik yang bukan saja dalam dirinya tidak berintikan moralitas kemanusiaan dan kebertuhanan, tetapi juga yang praktik-praktiknya belum cukup mengalami revisi sehingga masih sarat mengidap ciri-ciri kapitalisme dekaden abad lalu. Dalam istilah Yoshihara Kunio, kapitalisme kita adalah suatu ersatz capitalism, yaitu bertumbuhkembangnya kaum kapitalis bukan melalui mekanisme wajar, melainkan melalui patronase, perlindungan atau koneksi dengan kekuasaan. Keberislaman dalam Konteks Indonesia Kini Dengan konteks persoalan tersebut kiranya dinamika keberislaman yang sangat menggairahkan saat ini, arus utamanya harus kita arahkan pada hal-hal berikut: Pertama, umat Islam harus menghadapkan kesadarannya tidak semata kepada problem keindonesiaan saja, tetapi harus memperluas concern-nya kepada masalah global-mondial, dan tentu saja keterkaitan antara keduanya. Dengan begitu jawaban lokal kita pun, tetap berwawasan global. Berkaitan dengan ini, intelektualisme Islam Indonesia harus aktif menggabungkan diri dengan arus intelektualisme Islam Internasional. Kedua, upaya pencerdasan kehidupan umat Islam, haruslah lebih dipersungguh-sungguh. Umat Islam harus didorong untuk berjuang menguasai ilmu dan teknologi, serta menerjuni segala sektor kehidupan moderen, agar terkuasai seluruh idiomnya. Hanya dengan cara demikian umat Islam dapat memiliki power untuk memimpin peradaban. Tetapi berbarengan dengan ini, upaya Islamisasi dan atau penggalian ilmu-ilmu yang orisinal Islami haruslah dilakukan. Pembahasan mengenai rumusan sistem-sistem sosial, ekonomi dan politik yang Islami perlu dipertajam. Ini dikarenakan kita tidak hendak mengafirmasi dan melarutkan diri dengan semua idiom-modernitas, lebih-lebih lagi terhadap sistem sosial yang eksploitatif. Berbarengan dengan itu pula perlu dikembangkan kritisisme atas faham dan praktik keberislaman warisan masa lalu, dalam seluruh seginya. Dalam hal ini, kiranya pemikiran Islam kaum mu’tazilah sangat baik diintroduksikan di tengah-tengah masyarakat kita, untuk mendorong keberanian berpikir umat Islam. Begitulah, berpikir kritis sistematis, harus diarahkan sekaligus kepada kedua sumber ayat-ayat Allah, yakni kepada diri manusia dan alam semesta (ayat-ayat kauniyah) dan kepada Al-Qur’an (ayat-ayat kauliyah) dan dengan mendialogkan keduanya. Untuk itu semua, sungguhlah besar manfaat filsafat. Ketiga, pelaksanaan prinsip amar ma’ruf nahi munkar mutlak diperlukan untuk mendorong terciptanya masyarakat etis dan egaliter. Mengingat problem-problem sosial yang menyertai pembangunan dan perubahan sosial, maka amat penting para intelektual Islam lebih mempervokal advokasinya atas kelompok masyarakat lemah yang terkorbankan dalam proses pembangunan dengan memperkeras suara kritik terhadap budaya yang mendemoralisasi masyarakat dan bertentangan dengan hati nurani rakyat, dan dengan lebih memperkeras dorongan terhadap proses demokratisasi politik dan ekonomi, terutama dalam politik distribusi hasil-hasil pembangunan. Jika kepentingan masyarakat bawah dan aspirasi umat Islam dapat diartikulasikan secara vokal oleh para intelektual muslim yang berintegritas, maka pikiran tentang perlunya umat Islam kembali berpolitik formal atau kembali berpartai politik (misalnya dikaitkan dengan kemungkinan telah dekatnya kedatangan periode “pasca Orde Baru”) akan makin kehilangan relevansinya. Ini penting mengingat pada masa sekarang ini, berpartai-politik-Islam agaknya tetap lebih banyak menghasilkan kemudaratan daripada kemanfaatan bagi umat Islam. Dengan tidak berpartai politik, umat Islam dapat lebih cair memasuki berbagai kotak sosial karena Islam tidak tereduksi seakan identik dengan partai Islam, dan dapat lebih berkonsentrasi menggarap masalah-masalah yang lebih strategis, sehingga dapat lebih produktif untuk jangka panjang. Keempat, perlu dikembangkan teologi Islam yang memandang pentingnya dimensi tasawuf. Ini sangat penting, karena dua hal. Pertama, betapa berbahayanya akal kecerdasan, ilmu dan teknologi jika dinamikanya tidak didorong dan dibimbing oleh motif-motif rohani yang bersih. Kedua, pemikiran keagamaan kaum fuqaha yang memperlakukan agama lebih sebagai ‘hukum’ dan pemikiran kaum modernis yang mengembangkannya menjadi semacam ‘ideologi’, ternyata sama-sama kurang memperhatikan dimensi batin atau kedalaman, yang sesungguhnya menjadi inti keberagamaan. ---- &&&----