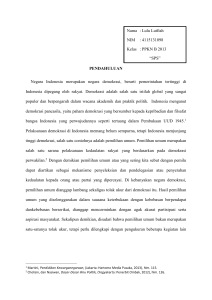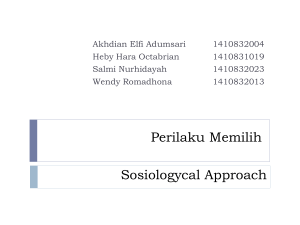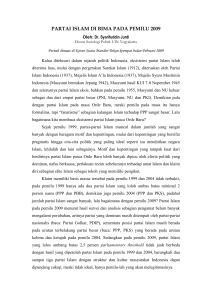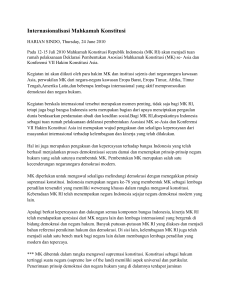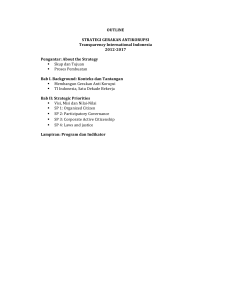TOR Diskusi Kafe di Zoe, Depok (13/2)
advertisement
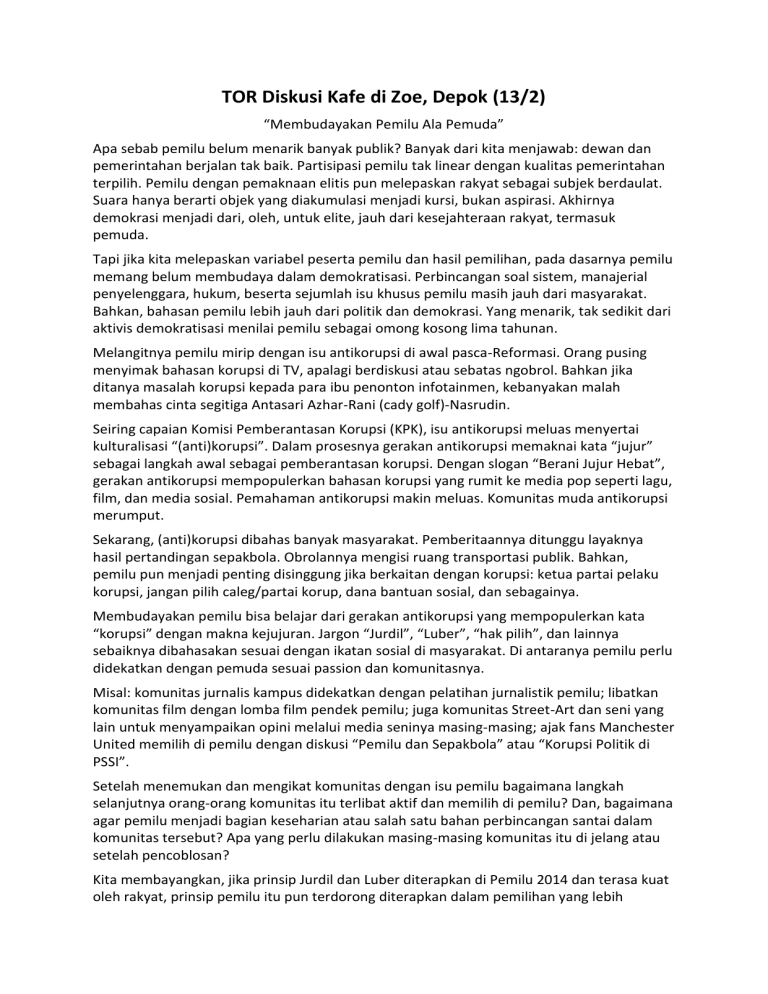
TOR Diskusi Kafe di Zoe, Depok (13/2) “Membudayakan Pemilu Ala Pemuda” Apa sebab pemilu belum menarik banyak publik? Banyak dari kita menjawab: dewan dan pemerintahan berjalan tak baik. Partisipasi pemilu tak linear dengan kualitas pemerintahan terpilih. Pemilu dengan pemaknaan elitis pun melepaskan rakyat sebagai subjek berdaulat. Suara hanya berarti objek yang diakumulasi menjadi kursi, bukan aspirasi. Akhirnya demokrasi menjadi dari, oleh, untuk elite, jauh dari kesejahteraan rakyat, termasuk pemuda. Tapi jika kita melepaskan variabel peserta pemilu dan hasil pemilihan, pada dasarnya pemilu memang belum membudaya dalam demokratisasi. Perbincangan soal sistem, manajerial penyelenggara, hukum, beserta sejumlah isu khusus pemilu masih jauh dari masyarakat. Bahkan, bahasan pemilu lebih jauh dari politik dan demokrasi. Yang menarik, tak sedikit dari aktivis demokratisasi menilai pemilu sebagai omong kosong lima tahunan. Melangitnya pemilu mirip dengan isu antikorupsi di awal pasca-Reformasi. Orang pusing menyimak bahasan korupsi di TV, apalagi berdiskusi atau sebatas ngobrol. Bahkan jika ditanya masalah korupsi kepada para ibu penonton infotainmen, kebanyakan malah membahas cinta segitiga Antasari Azhar-Rani (cady golf)-Nasrudin. Seiring capaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isu antikorupsi meluas menyertai kulturalisasi “(anti)korupsi”. Dalam prosesnya gerakan antikorupsi memaknai kata “jujur” sebagai langkah awal sebagai pemberantasan korupsi. Dengan slogan “Berani Jujur Hebat”, gerakan antikorupsi mempopulerkan bahasan korupsi yang rumit ke media pop seperti lagu, film, dan media sosial. Pemahaman antikorupsi makin meluas. Komunitas muda antikorupsi merumput. Sekarang, (anti)korupsi dibahas banyak masyarakat. Pemberitaannya ditunggu layaknya hasil pertandingan sepakbola. Obrolannya mengisi ruang transportasi publik. Bahkan, pemilu pun menjadi penting disinggung jika berkaitan dengan korupsi: ketua partai pelaku korupsi, jangan pilih caleg/partai korup, dana bantuan sosial, dan sebagainya. Membudayakan pemilu bisa belajar dari gerakan antikorupsi yang mempopulerkan kata “korupsi” dengan makna kejujuran. Jargon “Jurdil”, “Luber”, “hak pilih”, dan lainnya sebaiknya dibahasakan sesuai dengan ikatan sosial di masyarakat. Di antaranya pemilu perlu didekatkan dengan pemuda sesuai passion dan komunitasnya. Misal: komunitas jurnalis kampus didekatkan dengan pelatihan jurnalistik pemilu; libatkan komunitas film dengan lomba film pendek pemilu; juga komunitas Street-Art dan seni yang lain untuk menyampaikan opini melalui media seninya masing-masing; ajak fans Manchester United memilih di pemilu dengan diskusi “Pemilu dan Sepakbola” atau “Korupsi Politik di PSSI”. Setelah menemukan dan mengikat komunitas dengan isu pemilu bagaimana langkah selanjutnya orang-orang komunitas itu terlibat aktif dan memilih di pemilu? Dan, bagaimana agar pemilu menjadi bagian keseharian atau salah satu bahan perbincangan santai dalam komunitas tersebut? Apa yang perlu dilakukan masing-masing komunitas itu di jelang atau setelah pencoblosan? Kita membayangkan, jika prinsip Jurdil dan Luber diterapkan di Pemilu 2014 dan terasa kuat oleh rakyat, prinsip pemilu itu pun terdorong diterapkan dalam pemilihan yang lebih bersifat keseharian: memilih kepala keluarga, memilih ketua kelas, memilih ketua RT, memilih forum penasehat sekolah, dan sebagainya. Mungkin semua upaya pembudayaan pemilu tersebut jika disimpulkan dengan slogan, bunyinya: “Men-Jurdil-Luber-kan Masyarakat, dan Memasyarakatkan Jurdil-Luber”. []