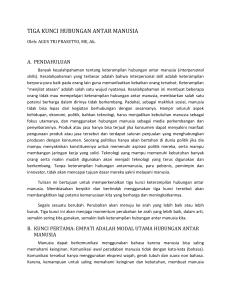dana aspirasi dan birokrasi.
advertisement
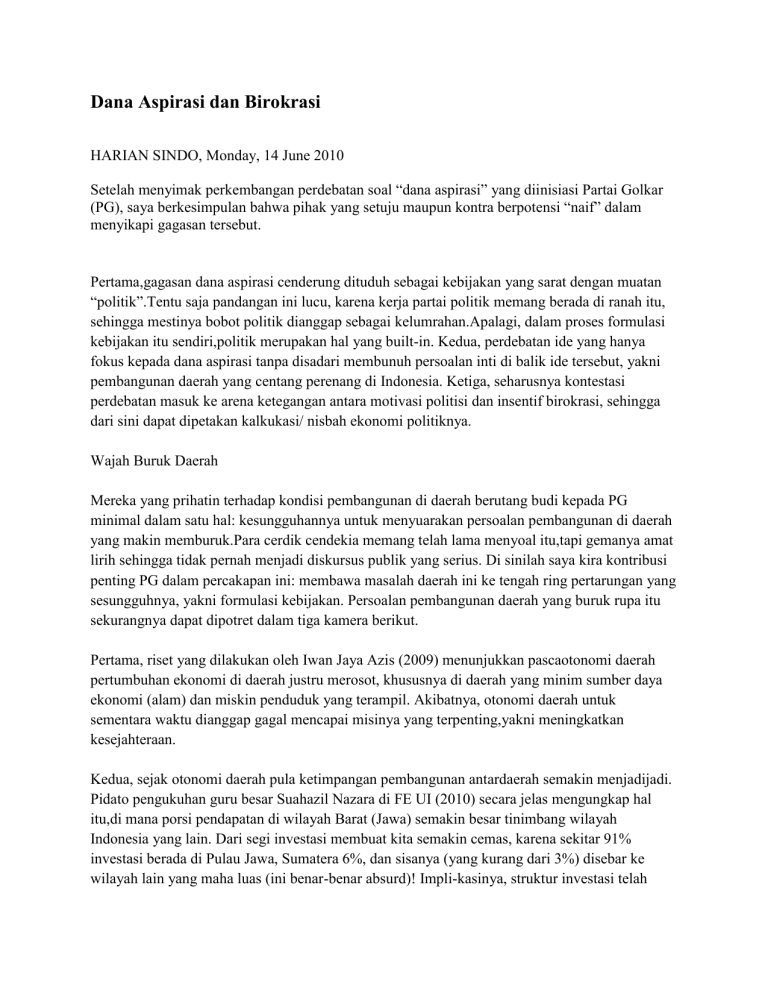
Dana Aspirasi dan Birokrasi HARIAN SINDO, Monday, 14 June 2010 Setelah menyimak perkembangan perdebatan soal “dana aspirasi” yang diinisiasi Partai Golkar (PG), saya berkesimpulan bahwa pihak yang setuju maupun kontra berpotensi “naif” dalam menyikapi gagasan tersebut. Pertama,gagasan dana aspirasi cenderung dituduh sebagai kebijakan yang sarat dengan muatan “politik”.Tentu saja pandangan ini lucu, karena kerja partai politik memang berada di ranah itu, sehingga mestinya bobot politik dianggap sebagai kelumrahan.Apalagi, dalam proses formulasi kebijakan itu sendiri,politik merupakan hal yang built-in. Kedua, perdebatan ide yang hanya fokus kepada dana aspirasi tanpa disadari membunuh persoalan inti di balik ide tersebut, yakni pembangunan daerah yang centang perenang di Indonesia. Ketiga, seharusnya kontestasi perdebatan masuk ke arena ketegangan antara motivasi politisi dan insentif birokrasi, sehingga dari sini dapat dipetakan kalkukasi/ nisbah ekonomi politiknya. Wajah Buruk Daerah Mereka yang prihatin terhadap kondisi pembangunan di daerah berutang budi kepada PG minimal dalam satu hal: kesungguhannya untuk menyuarakan persoalan pembangunan di daerah yang makin memburuk.Para cerdik cendekia memang telah lama menyoal itu,tapi gemanya amat lirih sehingga tidak pernah menjadi diskursus publik yang serius. Di sinilah saya kira kontribusi penting PG dalam percakapan ini: membawa masalah daerah ini ke tengah ring pertarungan yang sesungguhnya, yakni formulasi kebijakan. Persoalan pembangunan daerah yang buruk rupa itu sekurangnya dapat dipotret dalam tiga kamera berikut. Pertama, riset yang dilakukan oleh Iwan Jaya Azis (2009) menunjukkan pascaotonomi daerah pertumbuhan ekonomi di daerah justru merosot, khususnya di daerah yang minim sumber daya ekonomi (alam) dan miskin penduduk yang terampil. Akibatnya, otonomi daerah untuk sementara waktu dianggap gagal mencapai misinya yang terpenting,yakni meningkatkan kesejahteraan. Kedua, sejak otonomi daerah pula ketimpangan pembangunan antardaerah semakin menjadijadi. Pidato pengukuhan guru besar Suahazil Nazara di FE UI (2010) secara jelas mengungkap hal itu,di mana porsi pendapatan di wilayah Barat (Jawa) semakin besar tinimbang wilayah Indonesia yang lain. Dari segi investasi membuat kita semakin cemas, karena sekitar 91% investasi berada di Pulau Jawa, Sumatera 6%, dan sisanya (yang kurang dari 3%) disebar ke wilayah lain yang maha luas (ini benar-benar absurd)! Impli-kasinya, struktur investasi telah membuat pembangunan daerah kian timpang. Pulau Jawa semakin digdaya dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi (walaupun sebetulnya juga hanya ter-konsentrasi di Jabodetabek, Gerbangkertasusila, dan sekitar Bandung), sedangkan pulau lain terpinggirkan di sudut pembangunan ekonomi. Dengan data itu pula kita tidak bisa berkata lain, kecuali menyatakan bahwa pembangunan di daerah telah berada dalam zona darurat. Ketiga, prosedur perencanaan pembangunan di daerah memang telah berjalan cukup bagus lewat mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) meskipun masih jauh dari sempurna. Namun,kerap kali proses yang bagus tersebut dipenggal di tengah jalan ketika masuk ke DPRD. Dokumen perencanaan teknokratik dan partisipatif tersebut sebagian hasilnya dipelintir begitu terjadi pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD (kota,kabupaten, provinsi).Inilah yang menyebabkan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) menjadi tidak sesuai dengan prioritas masalah. Persoalan ini masih ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian besar APBD habis untuk membiayai anggaran rutin dan gaji pegawai, setidaknya memakan 50–60% dari porsi anggaran daerah.Akumulasi dari dana yang terbatas dan program yang ditelikung membuat pembangunan di daerah makin jauh dari kebutuhan masyarakat. Monopoli “Penjarahan” Deskripsi di atas dengan gamblang menunjukkan bahwa latar belakang munculnya dana aspirasi sangat sahih sehingga setting masalah itu tidak boleh diaborsi sejak dini. Sungguh pun begitu, gagasan dana aspirasi sebagai instrumen untuk menyelesaikan soal pembangunan daerah memang berpotensi menimbulkan masalah baru yang tidak kalah rumit. Untuk mengupasnya, sebaiknya dimulai dengan sebuah postulat populer yang menyatakan setiap kebijakan selalu memiliki dua sisi: motivasi dari politisi yang terpilih (pengambil kebijakan) dan insentif birokrat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (Przeworski, 2003). Dalam banyak hal,politisi memang selalu disiplin untuk menafkahi kepentingan partisannya (pribadi maupun partai), tapi dalam banyak hal pula mereka memiliki sikap agung untuk menyantuni problem serius yang benar-benar terjadi (nilainilai universal). Kisah pahit di daerah itulah yang saya kira membuat PG tergerak untuk menata pembangunan daerah. Seterusnya,PG tentu berhitung secara ekonomi politik menyangkut instrumen yang digunakan untuk membasmi masalah itu. Di sinilah kita akan ketemu dengan rumusan kedua, di mana Aliran Chicago (Chicago School) berpendapat para politikus pasti memiliki hasrat untuk terpilih kembali (re-elected), atau sekurangnya Mazhab Virginia (Virginia School) beropini para politikus mengharapkan benefit pribadi atas kebijakan yang diambil. Kedua aliran tersebut secara baik menyampaikan adanya hasrat partisan yang membonceng di balik usulan mulia yang dilontarkan oleh para politikus. Munculnya opsi dana aspirasi itu secara cerdik bisa dikatakan sebagai manifestasi atas gabungan dari idealisme untuk membangun daerah (universal) sambil meraup keuntungan pribadi/ partai (partisan).Masalahnya, mengapapartai-partaidiluarPartai Demokrat(PD) engganmendukung ini? Apakah mereka lebih bajik dari para politikus PG? Silakan saja semua pihak mengembangkan imajinasi untuk mengupas soal ini. Saya hanya akan fokus menjawab keterkaitan berikutnya,mengapa birokrasi tidak memiliki insentif menyetujui gagasan tersebut? Inilah skemanya: bila usulan PG diadopsi sebagai kebijakan, secara teoretis PD yang paling dirugikan. Kenapa? Sebab,anggaran negara tidak bisa lagi dimonopoli partai pemerintah untuk merebut hati konstituen.Setiap keberhasilan pembangunan daerah (jika kebijakan itu diluncurkan) merupakan agregasi dari “keringat” semua partai politik. Seterusnya, birokrasi bukanlah organ bebas yang independen,sehingga tindak tanduknya merupakan derivasi dari partai yang berkuasa (di sini dis/insentif birokrasi paralel dengan dis/insentif partai politik penguasa). Inilah yang menyebabkan mengapa presiden mengapresiasi usulan dana aspirasi tersebut, sambil tidak lupa menambahkan implementasinya harus dilembagakan dalam skema perencanaan pembangunan. Singkat kata, jika skema presiden itu yang diadopsi, insentif birokrasi menjadi maksimal, tetapi monopoli “penjarahan” anggaran tetap awet seperti sediakala.(*) Ahmad Erani Yustika Direktur Eksekutif Indef, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Unibraw
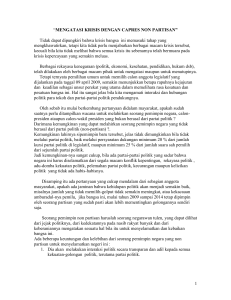


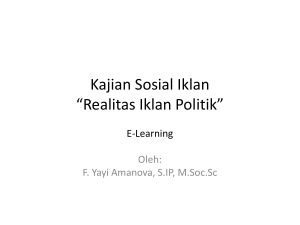


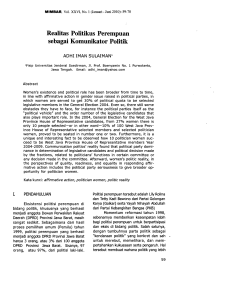


![Modul Komunikasi Politik [TM3]](http://s1.studylibid.com/store/data/000116295_1-3b54447b5d2446c13bf2a6d4b31873ca-300x300.png)