fikrah - stain kudus
advertisement

fikrah Vol. 1 N0. 1. Januari - Juni 2013 ISSN : 2354-6174 Page: 1-206 Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan fikrah Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol. 1 N0.1. Januari- Juni 2013 MEWUJUDKAN TRADISI ISLAM DALAM MANIFESTASI HARMONI KEBERAGAMAAN UMAT Mas'udi KRITIK WACANA PLURALISME AGAMA Andi Hartoyo RELATIVITAS AJARAN AGAMA: MENUJU PLURALISME KEBERAGAMAAN YANG HARMONIS Ahmad Atabik ISSN :2354-6174 AMBIVALENSI KOTA DEMOKRASI DALAM FILSAFAT POLITIK AL‐FARABI STUDI KRITIS MADINAH AL FADHILAH AL FARABI Moh. Yasin TEOLOGI ISLAM KONTEKSTUAL‐TRANSFORMATIF Nur Said STRUKTUR NALAR DI BALIK POLEMIK TEOLOGI DAN FILSAFAT ISLAM Tahir Sapsuha Diterbitkan oleh: Jurusan Ushuluddin Program Studi Ilmu Aqidah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Telp. (0291) 432677 fax. (441613) Kudus 59322 Jurusan Ushuluddin Program Studi Ilmu Aqidah SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS JAWA TENGAH ‐ INDONESIA FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 1 Januari-Juni 2013 ISSN: 2354-6174 Penanggung Jawab Fathul Mufid Redaktur Umma Farida Mas’udi Editor/Penyunting Abdul Karim Ahmad Atabik Desain Grafis Nur Sa’id Masdi Sekretariat M. Nuruddin Ma’mun Mu’min Muchlisin Dwi Sulistiono Marhamah Fikrah Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Diterbitkan Oleh: Jurusan Ushuluddin Program Studi Ilmu Aqidah STAIN Kudus Alamat Redaksi Jl. Conge Ngembalrejo PO. Box. 51 Kudus 59322. Telp. (0291) 432677. Fax. 441613. Email: [email protected] Terbit 2 dua kali dalam satu tahun Bulan Januari-Juni dan Juli - Desember DAFTAR ISI • Mewujudkan Tradisi Islam dalam Manifestasi Harmoni Keberagamaan Umat —Mas’udi—................................................................ 1-16 • Kritik Wacana Pluralisme Agama —Andi Hartoyo— ...................................................... 17-38 • Relativitas Ajaran Agama: Menuju Pluralisme Keberagamaan Yang Harmonis —Ahmad Atabik—...................................................... 39-56 • Ambivalensi Kota Demokrasi dalam Filsafat Politik Al-Farabi Studi Kritis Madinah Al Fadhilah Al Farabi — Moh. Yasin —........................................................ 57-85 • Teologi Islam Kontekstual-Transformatif —Nur Said—............................................................... 87-107 • Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi dan Filsafat Islam —Tahir Sapsuha— . ................................................... 109-130 • Dikotomi Agama dan Ilmu dalam Sejarah Umat Islam Serta Kemungkinan Pengintegrasiannya —Syamsul Kurniawan—............................................ 131-151 v • Jihad Melawan Terorisme: Merekonstruksi Pemahaman tentang Makna dan Implementasi Jihad dalam Islam —Abdurrahman Kasdi—............................................ 153-173 • Teologi Anti Korupsidalam Tinjauan Al-Qur’an —Abdul Karim— ....................................................... 175-194 • Ritus dalam Keberagamaan Islam: Relevansi Ritus dalam Kehidupan Masa Kini —Ulya— ..................................................................... 195-206 vi PENGANTAR REDAKSI Bismillahirrahmanirrahim Teriring puji syukur ke hadirat Allah dan shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad saw., penerbitan edisi perdana Jurnal Fikrah Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan ini dapat terlaksana. Hal ini secara niscaya merupakan sebuah kesyukuran tiada tara karena pentingnya kehadiran jurnal ini untuk pemenuhan kebutuhan akademis para ahli di bidang Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Edisi perdana, Vol. I, No. 1, Januari – Juni 2013 ini merupakan bagian integral dari kajian Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Kajian ini dihadirkan berdasar kepada muatan studi tentang dinamika Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat kontemporer. Secara nyata pula beberapa kajian pada edisi ini mengarah kepada studi pemikiran yang berhaluan kepada analisa agama dan dinamika kehidupan keberagamaan di masyarakat. Pada edisi perdana ini, Jurnal Fikrah sebagai representasi dari Kajian Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan menampilkan beberapa kajian tentang Ritus, Polarisasi Keagamaan, Eksistensi Transformasi Islam, Nilai-nilai Integratif antara Studi Keagamaan dan Sains serta Teknologi, dan Perpsektif Teologis Korupsi menurut al-Qur’an. Secara terintegrasi kajian-kajian ini diarahkan vii untuk memberikan mapping pemikiran keaqidahan dan keagamaan kepada segenap pemerhatinya. Walhasil, rumusan pada kajian ini akan memaparkan tentang objektivikasi Kajian Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Sebagai harapan akhir, Fikrah, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan pada edisi ini diorientasikan sepenuhnya untuk memberikan wawasan baru keilmuan tentang Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Dari semua rumusan yang dihadirkan di dalamnya tercurah harapan besar eksistensinya mampu memberikan pencerahan baru bagi pengembangan Studi Ilmu Aqidah dan Keagamaan. Semoga bermanfaat…..!!! Kudus, Juni 2013 Redaksi viii MEWUJUDKAN TRADISI ISLAM DALAM MANIFESTASI HARMONI KEBERAGAMAAN UMAT Mas’udi STAIN KUDUS Email: [email protected] ABSTRAK Islam adalah agama misi yang diwahyukan Allah swt., kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw. Dalam perjalanannya pula, Islam berjalan beriringan dengan dinamika kehidupan umat sehingga menjadikannya kadang dipertentangkan dan di diteladani. Plus minus keberadaan ini tidak menjadikan Islam surut dalam usahanya mengentaskan keberadaban umat manusia. Islam terus menjalankan misi sucinya dengan memberikan uraian keilmiahan hidup sehingga pada akhirnya masyarakat mulai mengerti akan hakikat dari keharmonisan hidup bersama dalam lintasan keyakinan. Tuntutan utama yang diajarkan oleh Islam adalah menyadarkan masyarakat akan arti penting tradisi sebagai perekat utama doktrin keislaman dengan perjuangan Rasulullah saw. Tradisi dalam Islam dengan pengertian akan eksistensi keanekaragaman sosial, budaya, dan bahkan agama itu sendiri menjadikan Islam sebagai jalan tengah bagi masyarakat. Islam memberikan beberapa deskripsi realistis tentang hakikat hidup setiap pribadi yang mustahil dinafikkan kebersandarannya kepada nilai-nilai suci masing-masing agama. Di atas kenyataan Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 1 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) inilah, tuntutan untu menghadirkan harmoni Islam sebagai pemersatu kehidupan umat niscaya dikedepankan. Kata Kunci: Tradisi, Jalan Tengah (middle roader), al-Sunnah, Ritual, Keberagamaan Pendahuluan Ritual merupakan manifestasi utama perjalanan dinamika keberagamaan para pemeluk agama. Di atas kenyataannya, masing-masing pemeluk agama akan menghadirkan kenyataan ini sebagai perwujudan dari keyakinan mereka terhadap agama yang dianut dan dipercaya. Berbagai pola niscaya dikembangkan oleh segenap pemeluk agama guna mengejawantahkan doktrin agama sebagai kesatuan praktek dalam kehidupan beragama. Berbagai ritual dalam Islam sebagai menifestasi dari nilai-nilai dan budaya suatu agama, terdapat beberapa entitas yang bisa diperhatikan eksistensinya; kuatnya akar dari tradisi, budaya keagamaan—ritual—yang terdapat dalam diri masingmasing pemeluknya. Realita ini adalah gambaran yang sangat faktual untuk mengkajinya dengan baik dan sempurna guna menemukan suatu hakekat terbesar dari agama atas perwujudan nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha ESa. Kebesaran suatu agama dengan berbagai bentuk atributnya menjadi semakin debatable atau diperdebatkan dalam masyarakat ketika tradisi ekspresi yang mereka tampilkan sangat berbeda dari aksentuasi orang lain dalam pengimplementasian agamanya. Dalam masyarakat yang sederhana dan yang hampir tidak dapat dibedakan, ada sedikit perbedaan antara kisah-kisah keagamaan dengan kisah-kisah kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, agama tidak sama sekali diidentikan dengan ketertiban sosial. Dalam masyarakat yang lebih maju, kisah-kisah keagamaan muncul sebagai simbol keagamaan dan simbol sosial yang secara jelas dapat dibedakan, yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya pada kutub pengaruh yang saling menguntungkan. Akhirnya, di dalam masyarakat yang komplek dan sangat beragam dewasa ini, kisah keagamaan hanya mempunyai pengaruh yang tidak langsung terhadap kisah kemasyarakatan melalui pengaruhnya dalam membentuk penilaian dan pandangan dunia 2a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) dari individu dan keluarga.1 Sebagai penghujung dari realitas tersebut, aspek kompleksitas dalam tatanan suatu agama semakin mengisolasikan satu pemeluk agama tertentu terhadap pemeluk agama yang lainnya. Pertautan realita sosial dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan pengimplementasian semua aspek-aspek ekspresif mereka dalam beragama—ritual—tidak akan semakin tajam, jika pemetaan nilai-nilai keagamaan dapat disandingkan bersama. Pemetaan nilai-nilai tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua hal; Pertama, Human Contruction—kontruksi manusia—. Budaya sebagai realita sosial dalam masyarakat, mempunyai unsur kebiasaan, kontinuitas dan tidak pernah berhenti. Keberlanjutan ini sebagai manifestasi konstruk budaya pada manusia dan mengendap kuat pada masing-masing mind setting pola pikir mereka dan akhirnya menjadi suatu ideologi tanpa adanya suatu deskripsi yang valid, penyokong terhadap nilai budaya yang ada. Kenyataan ini bisa terjadi karena pemahaman masing-masing masyarakat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuh kehidupannya dengan belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.2 Bagian kedua dari pemetaan tersebut adalah sinkretisme budaya—Cultural Sincreticism—. Ritual dalam suatu agama pada awalnya adalah implementasi dari nilai suci ajaran agama yang ada. Tradisi keagamaan tersebut secara bertahap mengalami proses transformatif seiring dengan sampainya ajaran agama tersebut di luar domain agama itu sendiri diturunkan. Perbedaan lokasi, wilayah, kultur, dan tradisi yang ada ini menjadi paradigma logis dalam diri pemeluk agama. Tranparansi tradisi agama yang ada dengan unsur budaya yang mereka miliki membentuk pola-pola ritual keagamaan baru di masyarakat sehingga terciptalah budaya keagamaan baru dalam kehidupan mereka. Melalui beberapa pola ini pula terjadilah sinkretasi tradisi suatu agama dengan budaya lokal yang ada. Andrew M. Greely, Agama Suatu Teori Sekuler (Jakarta:Erlangga, 1982), hlm. 113. 2 Sujarwa, Manusia dan Fenomena Budaya (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1. 1 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 3 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) Membentuk kemajuan di tengah-tengah kehidupan umat secara niscaya perlu menyadarkan masyarakat itu sendiri akan eksistensi dari pertumbuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebagaimana dicatat oleh Ris’an Rusli bahwa modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pikiran dan aliran ini segera memasuki lapangan agama dan modernisme dalam hidup keagamaan di Barat mempunyai tujuan untuk menyesuaikan jaran-ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafat modern. Aliran ini akhirnya membawa kepada timbulnya sekularisme di Barat.3 Ide-ide sekularisme yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyaraka Barat memberikan kontribusi terhadap tuntutan modernisme bagi kehidupan masyarakat dalam beragama. Hal ini tentunya bukanlah dengan usaha menafikkan hakikat dasar agama dengan mengedapankan nilai-nilai materi semata bagi pemeluknya. Islam secara utuh memberikan perekatan nilainilai sosial dan ketuhanan demi menghadirkan sikap modernisme kehidupan pemeluknya. Hal ini secara niscaya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw., sebagai teladan hakiki kehidupan masyarakat muslim. Fakta ini dicatat oleh Afif Muhammad dengan penjelasannya bahwa tipologi manusia Qur’ani diwujudnyatakan oleh Rasulullah saw., demi menghadirkan kehidupan masyarakat yang sudah mengalami dekadensi. Nabi Muhammad saw., hadir sebagai pengejawantah al-Qur’an dalam bentuk manusia. Jika dia berbicara, maka cara berbicaranya adalah cara berbicara menurut al-Qur’an. Jika dia duduk, maka duduknya adalah duduk model al-Qur’an.4 Terilustrasi dari beberapa argumentasi di atas terdapat dua eksistensi keagamaan yang ingin diwujudnyatakan masyarakat terhadap pola-pola pemahaman keagamaan masing-masing. Secara Ris’an Rusli, Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 176. 4 Afif Muhammad, Islam Mazhab Masa Depan Menuju Islam Nonsektarian (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 89. 3 4a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) komparatif terlihat bahwa fenomena keagamaan masyarakat di Barat menyentuh kepada nilai-nilai sekularitas kehidupan. Untuk meluncur melewati kejumudan dalam keberagamaan masyarakat diajak untuk meninggalkan tradisi dan beralih kepada pemikiran. Hanya dengan fakta ini akan terwujud sepenuhnya pertumbuhan masyarakat yang lebih moderat. Hal ini secara berbeda dengan eksistensi Islam yang bersandar kuat kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., sebagai rasul-Nya. Modernisme Islam ditunjukkan oleh Rasulullah saw., dengan pengejawantahan dirinya sebagai insan Qur’ani. Pada praktek kehidupan beliau semua aktifitas lahir dan batin manusia ditunjukkan. Representasi Ritual Islam bagi Kejahiliyahan Masyarakat Arab Islam terlahir sebagai jawaban atas tradisi Jahiliyyah yang telah mengakar kuat dalam diri masyarakat Arab. Kelaliman yang telah mereka perbuat dari, penganiyayaan, perjudian, perzinaan dan lain sebagainya, telah mengendap kuat dalam diri mereka dan menjadi tipikal utama kehidupan di masa tersebut. Perwujudan keagamaan yang mereka lakukan di masa tersebut merupakan manifestasi utama dari pola kehidupan masyarakat Arab yang lebih menyentuh ke aspek dekaden. Fakta ini secara nyata ditegaskan oleh Afif Muhammad bahwa pada masa awal Islam diwahyuka ke tengah-tengah kehidupan masyarakat diorientasikan seutuhnya untuk mengikis kejahiliyahan mereka.5 Kehadiran Islam dengan keutuhan etimologinya sebagai ajaran berserah diri kepada Allah swt., datang untuk meluruskan hakekat hidup masyarakat Arab yang telah keluar dari sumbu utama kehidupan Rabbani. Kelaliman yang secara implisit mereka kultuskan sebagai esensi dari hidup mereka, berangsur-angsur diarahkan kepada kenyataan hidup di dunia ini. Nabi Muhammad saw., sebagai pioner dari ajaran ini, menerima pesan suci dari Allah swt., untuk memberikan suatu paradigma baru dalam hidup yang lebih imajinatif dan progresif. Rasulullah mendapatkan pesan Penjelasan tentang hal ini dikupas secara deskriptif analitis oleh Afif Muhammad dalam karyanya pada bab pembahasan tentang Manusia Qurani. Lebih lanjut baca; Afif Muhammad, Islam Mazhab Masa Depan Menuju Islam Non-sektarian. Ibid., hlm. hlm. 87. 5 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 5 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) pertama dengan wahyu Allah swt., pada QS. Al-‘Alaq (96:1-5)6 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan; Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan pernatara kalam; Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. Menganalisa secara deskriptif penjelasan ayat al-Qur’an tersebut, masyarakat Arab dengan kehadiran ajaran Islam dan tuntutan perwujudan ritual keagamaannya diperintah untuk memahami hakikat kosmologi sebagai tempat mereka bernaung dan mengemban amanat dalam hidup. Pada bagian selanjutnya fakta kehidupan mereka dituntut untuk menyadari tentang nilainilai antropologis karena kehidupan mereka tercipta dari aneka warna bentuk suku, ras, dan social. Kesadaran berikutnya dari tuntutan Islam dengan ayat tersebut adalah pemahaman akan nilai teologis. Nilai ini seutuhnya mengajak kehadiran akan kesadaran mereka bahwa pengertian akan Pencipta adalah kenisccayaan dalam kehidupan. Pada bagian nilai berikutnya yang dituntut kepada mereka kehadirannya adalah nilai-nilai sosiologis. Kehiduapan masyarakat Arab tercipta dengan aneka bentuk sosial pendukungnya. Untuk itulah, tiada suatu kebenaran yang bisa dipahami bahwa suatu kedudukan sosial tertentu mampu mendominasikan dirinya terhadap nilai sosial yang lain. Pada bagian akhir, masyarakat Arab dituntut kesadaran diri mereka akan nilai-nilai eskatologis kehidupan. Semua kehidupan yang dijalankan oleh setiap pribadi akan berakhir semua pengembaraan tersebut ke hadirat-Nya. Untuk selanjutnya pula, melalui wahyu inilah Rasulullah saw., memulai misi sucinya untuk meluruskan akidah (kepercayaan orang-orang Arab) yang telah hilang jauh dari ajaran suci agama. Islam dalam realitas perjalanannya memberikan kontribusi besar dalam peradaban sosial, budaya, dan kultur dalam masyarakat. Kontribusi peradaban yang dimilikinya tumbuh sempurna. Kebudayaannya menjadi pembimbing bagi kebudayaan-kebudayaan lain, serta akhlak dan adat istiadatnya Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemahnya (Semarang: Al-Wa’ah, 1989), hlm. 1079. 6 6a Al-Qur’an dan Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) lebih tinggi dari pada yang ada sezamannya. Untuk selanjutnya, umat-umat yang lain merasa bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti contoh-contoh umat ini dan menerima ajaranajarannya. Sehingga meskipun dari segi jumlah umat ini kecil saja, namun ia mempunyai ruang gerak yang amat luas, seakanakan umat ini merupakan ruh bagi alam, dan alam merupakan jasad baginya.7 Ketimpangan-ketimpangan serta kebodohan yang menimpa umat manusia pada masa itu, berangsur-angsur hilang dan pergi digantikan dengan tradisi baru, yaitu tradisi Islam dengan semangat suci yang menyertainya “Rahmatan lil ‘Alamin” Islam rahmat bagi segenap umat. Kemegahan peradaban dan ketinggian tradisi yang telah diberikan serta disumbangkan oleh Islam terhadap peradaban umat manusia, bukti monumental yang harus diketahui dan diresapi serta diaktualisasikan realitasnya oleh para generasi muda Islam sebagai sarana penyeimbang—balancing power—bagi mereka dalam melihat, mengasah dan mejalankan realitas global yang semakin bebas. Kemajuan yang tealah diberikan oleh zaman modern ini, tidak dapat dihindarkan bahwasanya kenyataan ini tercipta dari sumbangan Islam pada zaman klasik, pertengahan, dan zaman modern saat ini. Islam sebagai Manifesto Tradisi Kehidupan Umat Bangunan tradisi yang telah ditanamkan dalam Islam adalah manifestasi dari akumulasi peradaban yang tertanam kokoh dalam sanubari kaum muslimin saat ini. Nilai peradaban ini dapat dilihat dari peta geografis dunia saat ini. Masing-masing dapat melihat bahwa dunia muslim berada di antara Cina, Korea, dan Jepang pada sisi timur dan Eropa sisi barat: antara Rusia di bagian utara dan sub sahara Afrika dan Australia di bagian selatan. Maksud dari “Dunia Muslim” dalam perspektif ini adalah bagian bumi yang mayoritas ditempati oleh masyarakat yang memeluk agama Islam, dan terbentang dari Maroko di ujung barat hingga Indonesia di ujung timur, Rusia di bagian utara hingga Comoro di lautan India di bagian selatan. Fakta geografis ini saja, yang kurang lebih tetap demikian adanya di bagian terbesar Nurkhalish Madjid, Khazanah Intelektual Bintang, 1994), hlm. 345. 7 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Islam (Jakarta:Bulan 7 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) sejarah Islam cukup untuk menetapkan “Dunia Muslim” sebagai “Bangsa Tengah” (middle nation). Secara geografis, dunia muslim merupakan jembatan antara timur dan barat, dan antara utara dan selatan”8. Letak geografis inilah Islam memberikan warna yang signifikan bagi sosio-kultur dan budaya masyarakat muslim. Middle Nation “Bangsa Tengah” yang telah dipredikatkan pada wilayah-wilayah yang telah terdoktrinasikan tradisi Islam, secara variatif memunculkan keanekaragaman sosio-kultur dan sosio-budaya pada domain yang mereka diami. Akan tetapi Islam dengan stigma pokoknya sebagai “rahmatan lil “alamin” rahmat untuk sekalian alam telah memberikan kombinasi yang begitu megahnya untuk kehidupan mereka, dari tradisi sosial, seni, politik, pendidikan, arsitektur dan banyak lagi yang lainnya. Satu aspek penting yang telah disumbangkan oleh Islam untuk kemajuan peradaban yaitu dari bidang tradisi pemikiran. Dalam melakukan telaah terhadap pemikiran Islam, pertama-tama harus dilihat kembali masa para sahabat. Dari sana terlihat bahwa sahabat Nabi Muhammad saw., yang paling kreatif dalam berpikir adalah tokoh yang kemudian menjadi khalifah kedua, ‘Umar ibn Khattab (586-644). Kreatifitas pemikiran ‘Umar memberikan kesan kuat bahwa sekalipun beriman teguh, ia tidak bersifat dogmatis. ‘Umar adalah seorang beriman sekaligus intelektual, yang dengan intelektualitasnya itu ia berani mengemukakan ideide dan melaksanakan berbagai perkara inovatif yang sebelumnya tidak dicontohkan oleh Nabi.9 Dari zaman ‘Umar ibn Khattab inilah Islam mulai berkibar di kawasan Eropa, peradaban besar yang dapat dilihat dari kenyataan ini, kemegahan Cordoba dengan masjid agungnya. Islam mengkombinasikan tradisinya dalam daerah kekuasaan Raja Alexander Agung, sehingga makin menjadikan Islam lebih dikenal di antara kawasan dunia. Kemajuan ini telah menjadikan tradisi Islam mewarnai separuh belahan dunia. Kemajuan yang telah dicapai oleh Islam dalam membumikan tradisi dan kebudayaanya tidak dapat dipertahankan Osman Bakar, Islam dan Dialog Peradaban (Yogyakarta:Fajar Pustaka. 2003), hlm. 3. 9 Suadi Putro, Islam dan Modernitas (Jakarta:Paramadina, 1998), hlm. 35. 8 8a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) lagi secara kokoh. Kejumudan mulai menggejala di kalangan umat Muslim pada masa—Renainsance—kebangkitan di Eropa. Eropa sebagai negara terbelakang di saat Islam mencapai kejayaannya, saat itu pula mereka mulai bangkit melakukan ekspansi ke dunia Islam. Nilai tradisi, ilmu pengetahuan, teknologi, arsitektur yang sudah begitu melekat dalam Islam jatuh ke tangan mereka. Unsur fatalistik sebagi mainstream dari perjalanan kehidupan mengakar kuat dalam nilai tradisi umat manusia. Menyikapi kejumudan dan nilai fatalisme dalam Islam harus dimunculkan peranan konstruktif terhadap ajaran-ajaran Islam yang telah mencapai kegemilangannya di masa lampau. Untuk itu, dunia Islam harus kerja keras. Pemikiran tradisional dan sikap fatalislis yang telah ratusan tahun berkembang di kalangan umat perlu dihilangkan untuk diganti dengan pemikiran rasional dan sikap dinamis. Sains dan teknologi modern harus dikuasai, karena sejarah telah membuktikan bahwa ketika dunia Islam mementingkan sains dan teknologi, Islam menghasilkan adikuasaadikuasa. Eksklusifitas umat yang telah menggejala harus diganti dengan nilai-nilai inklusif akan transparansi Islam yang terbuka untuk segala zaman dan keadaan. Tuntutan untuk menghadirkan Islam dalam proporsinya yang terbuka seutuhnya menegeskan akan modernisme tradisi Islam. Hal ini menyandar kepada kenyataan akan kemoderatan Islam yang berciri khas dan mustahil ditemukan pada agama lain. Sebagaimana Muhammad Imarah menjelaskan bahwa kemoderatan Islam (moderatisme Islam) merupakan gabungan antara kerohanian dan jasmani, kombinasi wahyu dan akal, kitab yang tertulis dan kitab yang terhampar di alam semesta.10 Membandingkan tentang proses indoktrinasi ini dikukuhkan oleh Imarah bahwa dalam doktrin Kristen, seseorang diwajibkan untuk beriman sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh agama tersebut. Bahwa keimanan dalam Kristen tidak membutuhkan rasionalitas sementara dalam Islam bahwa Allah dapat diketahui banyak dengan akal. Sebelum beriman seseorang kepada nabi dan rasul, maka tertuntut pada dirinya agar beriman kepada Allah Muhammad Imarah “Islam Moderat sebagai Penyelamat Peradaban Dunia” dalam Hery Sucipto, ed., Islam Madzhab Tengah Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 438. 10 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 9 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) swt., dengan perantara akal. Perintah beriman dalam Islam merupakan piranti atau media utama untuk menjadikan diri setiap muslim mampu bertempat dalam wilayah trnsformatif kehidupan. Dalam Islam dinyatakan bahwa suatu perbuatan baru dikatakan bermakna jika dilandaskan pada keimanan. Tanpa iman, perbuatan apapun akan sia-sia di hadapan Allah swt. Itu sebabnya, Afif Muhammad menjelaskan bahwa kewajiban pertama bagi manusia adalah berimana terlebih dahulu sebelum dia melakukan apapun. Secara niscaya pula, hal ini menjadi petunjuk dasar bagi segenap manusia bahwa kaidah yang ada dalam Islam ini jika dipegang dengan baik, akan menghasilkan makna ganda dalam diri setiap muslim. Pertama; dalam hubungannya dengan Allah yang dengan kenyataannya pekerjaan tersebut mempunyai nilai ibadah yang dijanjikan pahala di akhirat. Kedua; dalam hubungannya dengan sesama manusia yang dengan pekerjaan tersebut mempunyai nilai manfaat duniawi.11 Islam dan Eksistensi Tradisi Tradisi yang dibangun Islam dengan keterbukaan atas realitas zaman yang berkembang harus disadari oleh para pemeluknya. Kejumudan tradisi yang telah lama menggejala dalam masyarakat dengan beraneka ragam ritual yang menemani mereka harus dikaji kembali keabsahannya untuk kemajuan umat Islam itu sendiri. Perlulah masing-masing orang membuka ingatannya— rethinking—bahwasanya kemunduran Islam terdahulu disebabkan oleh jutifikasi umat terhadap hasil pemikiran ulama-ulama tanpa mempertanyakan validitas dari pemikiran mereka. Ibarat ayam bertelur emas, mereka sering bertaklid buta dengan pemikiranpemikiran tersebut. Timbal balik atas pemikiran itu pembenaran buta akan pemikiran yang ada. Sementara itu, realita futuristik umat membuktikan, relevansi kebenaran di zaman ini terhadap zaman mendatang senantiasa debatable kebenarannya. Kajian dalam tradisi ritual dalam Islam harus dimanifestasikan dalam wadah yang continue, tidak statis. Konstruk yang ada dalam Islam masa Afif Muhammad, Islam Mazhab Masa Depan Menuju Islam Nonsektarian....., hlm. 245. 11 10a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) depan adalah perpaduan antara tradisi lokal dengan ajaran-ajaran normatif yang ada dan diajarkan oleh agama. Kejumudan dalam perjalanan tradisi Islam yang beraviliasi dengan ekstremitas tidak akan pernah terjadi, jika pengertian tradisi Islam yang instan, kolaboratif, adoptisiasi terhadap budaya lokal senantiasa diketahui oleh para pemeluknya. Kontruksi tercepat terhadap pemberitahuan akan keadaan tradisi Islam yang instan ini adalah dengan mensosialisasikan sistem terpadu terhadap masyarakat dari elemen-elemen yang paling bawah sampai yang atas. Alternatif ini dapat dijadikan jalan tengah—middle roader— untuk mengantisipasi kesalahpahaman akan hakekat tradisi Islam yang termanifestasikan dari nilai-nilai normativitas agama serta ajaran lokal. Tradisi ritual dalam Islam yang telah mengakar kuat dalam lubuk sanubari para pemeluk agama Islam adalah suatu bukti akan tradisi dalam Islam yang berhaluan kepada hakikat normativitas-historisitas. Normativitas itu dapat dilihat dari asas dasar yang senantiasa mereka nomersatukan dengan tidak mengenyampingkan unsur budaya lokal. Historisitas sebagai komunitas berbagi dalam keseharian mereka, pada akhirnya akan terkuaklah suatu pengertian pasti tradisi Islam adalah tradisi yang senantiasa menyanjung tinggi dengan mengedepankan unsurunsur dasar agama dari pada cabang-cabangnya yang debatable, sehingga terciptalah suatu tradisi dalam Islam yang menjadikannya rahmat bagi alam semesta. Dalam catatannya, Mas’udi merumuskan bahwa manusia perlu melihat kembali identitasnya sebagai manusia yang utuh dan diciptakan oleh Tuhan untuk mengemban amanat terbesar sebagai pelindung dan pelestari bumi. Itulah pesan moral yang senantiasa dipersinggungkan dalam kajian perenial. Sebuah pesan keabadian yang bersandar seutuhnya kepada prinsip-prinsip tradisi dalam kehidupan masyarakat. Konsep “keabadian” yang diperlambangkan dalam kajian perenialisme adalah untuk melihat suatu kesejajaran akan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam agama yang mewadahi aspek kehidupan manusia.12 Untuk inilah Mas’udi, “Perenialisme dalam Islam (Studi atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)”, dalam Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 12 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 11 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) Seyyed Hossein Nasr menekankan bahwa dalam perenialisme pada hakekatnya terdapat kebenaran dalam seluruh agama. Inilah yang disebutnya ”inner metaphysical truth of religion” (kebenaran metafisis batiniah agama)—dalam kamus peristilahan Islam disebut al-din al-hanif—primordial relegion. Kebenaran sejati itu selalu hadir sepanjang sejarah, berlaku abadi. Dengan kata lain, terdapat persatuan prinsip hakikat keilahian sebelum terjadinya keragaman.13 Pembahasan tentang aspek primordial agama yang dijelaskan oleh Seyyed Hossein Nasr dengan pengukuhan tradisi merupakan hakikat yang diajarkan Islam kepada seluruh pemeluknya. Hal ini secara niscaya pula dilakukan oleh seluruh lapisan pemeluk agama dengan harapan besar mereka untuk mengukuhkan doktrin agama yang berlandaskan kepada tradisi keniscayaan yang perlu dipertahankan. Semangat ajaran-ajaran kitab suci itu dipertegas dengan firman Allah, “Dan barang siapa Alloh menghendaki untuk diberikanNya hidayah, maka Dia lapangkan dada orang itu untuk ( atau karena ) Islam; dan barang siapa Alloh menghendakinya sesat, maka Dia jadikan dada orang itu sempit dan sesak, seolah-olah naik ke langit” (QS.al-An’am, 6:125). Membaca ayat al-Qur’an di atas sebuah keniscayaan hadir ke tengah-tengah kehidupan beragama umat bahwa sikap terbuka adalah bagian dari pada iman. Sebagai alasannya, seperti ternyata dari firman di atas berkenaan dengan sikap kaum kafir tersebut, tidak mungkin menerima kebenaran jika dia tidak terbuka. Karena itu difirmankan bahwa sikap tertutup, yang diibaratkan dada yang sempit dan sesak, adalah indikasi kesesatan. Sedangkan sikap terbuka itu sendiri adalah bagian dari sikap”tahu diri”, yaitu tahu bahwa diri sendiri mustahil mampu meliputi seluruh pengetahuan akan kebenaran. Sikap “tahu diri” dalam makna yang seluas-luasnya adalah kualitas pribadi yang amat terpuji, sehingga ada ungkapan bijaksana bahwa ” Barang siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya.” Artinya, kesadaran orang akan keterbatasan dirinya adalah akibat kesadarannya akan 72. 13 12a Ulumul Qur’an, No. 4. Vol. IV, 1993, hlm. 111. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) ketidak terbatasan dan kemutlakan Tuhan. Jadi tahu diri sebagai terbatas adalah isyarat tahu tentang Tuhan sebagai Yang Tak Terbatas, yang bersifat serba Maha. Dalam tingkah laku nyata, “tahu diri” itulah yang membuat orang juga rendah hati (harap jangan dicampuraduk dengan “rendah diri”). Dan sikap rendah hati itu adalah permulaan adanya sikap jiwa yang suka menerima atau receptive terhadap kebenaran. Inilah pangkal iman dan jalan menuju Kebenaran.14 Harapan Ideal Islam Masa Depan Sebagaimana terilustrasi dari beberapa pembahasan terdahulu tampak bahwa Islam secara niscaya hadir di tengahtengah kehidupan umat sebagai pencerah dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan atau bahkan politik seutuhnya. Islam “mengambil istilah Osman Bakar sebagai middle roader” menjadi jalan tengah di antara kompleksitas kebutuhan umat manusia akan hidup dan kemanusiaan itu sendiri. Kenyataan ini secara hakiki diwujudkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehingga mampu menghadirkan Islam sebagai solusi kebutuhan umat manusia. Islam menjadi pintu utama manusia berhutang akan hidupnya kepada Ilahi. Untuk itulah, Mas’udi mencatat bahwa seorang Muslim tidak dapat secara langsung mengerti atas pemenuhan dirinya untuk membayar keberhutangan dirinya kepada Tuhan. Di atas kenyataan inilah dalam tradisinya yang berlanjut Islam melalui pembawa amanatnya Nabi Muhammad saw., menjadikannya patokan dalam kehidupan kaum Muslim. Dalam pandangan Nasr sebagaimana dikutip oleh Mas’udi dijelaskan bahwa upaya untuk meniru Nabi, yang merupakan inti dari spiritualitas dan kesalehan Islam, harus didasarkan atas al-Sunnah, atau tradisitradisi dan perbuatan-perbuatannya. Al-Sunnah memberikan contoh-contoh konkret dan akses pada teladan Muhammad yang telah diperintahkan oleh al-Qur’an agar ditiru oleh orang yang beriman.15 Al-Sunnah adalah ulasan atas al-Qur’an dan tata cara Dianalisa dari “Pintu-Pintu Menuju Tuhan” karya Nurcholish Madjid melalui pengungguhan pada http://paramadina.wordpress.com/category/ pemikiran-cak-nur/ diakses pada tanggal, 7 Agustus 2009. 15 Mas’udi, “Perenialisme dalam Islam...........”, hlm. 78-79. 14 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 13 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) kaum Muslim mengetahui bagaimana kebenaran-kebenaran Teks Suci itu dihidupkan oleh makhluk Tuhan yang paling sempurna dalam kehidupan manusiawi namun benar-benar suci.16 Melalui al-Sunnah, setiap segi kehidupan manusia disakralkan, karena hukum Ilahi (al-Syari’ah) itu sendiri yang menjadi acuan bagi kehidupan Islam, didasarkan bukan hanya pada al-Qur’an melainkan juga pada al-Hadits. Dan dalam pengertian yang lebih umum, al-Sunnah, yang karena mencakup seluruh amalan-amalan dan tradisi-tradisi Nabi, dalam suatu pengertian juga mencakup al-Hadits. Al-Hadits sendiri adalah bagian dari al-Sunnah, karena ia terdiri dari tradisi Nabi yang berbentuk ucapan dan bukan perbuatan. Kata al-hadits itu sendiri berarti “ucapan”, tetapi ia juga diterjemahkan sebagai “tradisi”.17 Kedua panduan hukum dalam Islam tersebut memiliki peranan yang sangat berarti bagi perjalanan kehidupan seorang Muslim. Hanya al-Qur’anlah yang mempunyai nilai lebih tinggi dan otoritas lebih besar. Al-Hadits sesungguhnya, adalah ulasan paling pertama dan paling penting atas al-Qur’an.18 Pada saat yang sama ia melengkapi Teks Suci dan menguatkan serta lebih memperjelas ayat-ayatnya. Al-Hadits merupakan perluasan dalam bahasa manusia, yakni Nabi, dari Firman Ilahi yang berwujud al-Qur’an. Penutup Mengkaji Islam dari sudut pandang eksklusif akan memunculkan ketimpangan dalam pemahaman itu sendiri. Produk aktif yang dapat dikedepankan dalam memahami aspek-aspek tradisi ini adalah suatu bagan pengertian dari hakekat tradisi sebagai konstruksi pemahaman yang tercipta dari kebiasaankebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam kesehariaannya. Kesalahan dalam masyarakat terhadap asas tradisi tidak akan muncul tatkala penetahuannya seputar tradisi; adalah pengetahuan yang diciptakan oleh warisan-warisan nenek moyang mereka masing-masing bersandar kepada nilai dasar beragama dan beradat-istiadat. Ibid. Ibid. 18 Ibid. 16 17 14a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) Menumbuhkan keterbukaan akan komplektisitas hidup yang sarat kehidupan yang bersifat normatif dan historis adalah realitas yang diperjuangkan Islam bagi kehidupan umat. Sejarah adalah bukti dari suatu kenyataan. Akan tetapi bersifat dinamis terhadap kemunculan sejarah itu sendiri akan menyelamatkan setiap orang dalam kebutaan terhadap hal-hal yang harus direalisasikan dalam kemajuan tradisi yang telah ada.*** Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 15 Mewujudkan Tradisi Islam (oleh: Mas’udi) DAFTAR PUSTAKA M. Greely, Andrew. Agama Suatu Teori Sekuler. Jakarta: Erlangga, 1982. Sujarwa, Manusia dan Fenomena Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Afif Muhammad, Islam Mazhab Masa Depan Menuju Islam Nonsektarian. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: Al-Wa’ah, 1989. Nurkhalish Madjid, Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Bakar, Osman, Islam dan Dialog Peradaban. Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2003 Suadi Putro, Islam dan Modernitas. Jakarta: Paramadina, 1998. http://paramadina.wordpress.com/category/pemikiran-cak-nur/ Ulumul Qur’an, No. 4. Vol. IV, 1993 Mas’udi, “Perenialisme dalam Islam (Studi atas Pemikiran Seyyed Hossein Nasr)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. Hery Sucipto, ed., Islam Madzhab Tengah Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher. Jakarta: Grafindo, 2007. Ris’an Rusli, Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013 16a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 KRITIK WACANA PLURALISME AGAMA Andi Hartoyo Sekolah Harapan Utama Batam Email: [email protected] ABSTRAK Kehidupan adalah sebuah proses dialog terus-menerus dan di dalam dialog tersebut seseorang akan memberi dan menerima. Dialog akan terwujud hanya ketika seseorang bisa duduk sejajar dalam dataran kediriannya. Dunia ini milik bersama, hidup ini dijalani bersama dan semua persoalan manusia adalah juga persoalan semua orang, termasuk persoalan keber-Tuhan-an dan masalah agama serta keberagamaan adalah juga persoalan sebagai sesama manusia. Kedirian akan lestari serta akan menimbulkan rasa damai serta kreatif kalau tali pengikatnya adalah ikatan cinta, simpati dan didasari rasa saling menghormati, saling mempercayai serta masing-masing bisa dipercaya. Spiritualitas akan membuat seseorang semakin lembut, semakin peduli terhadap lingkungan dan sesama makhluk hidup. Apabila seseorang menjadi semakin egois, semakin mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok berarti seseorang itu belum spiritual (belum beragama), walaupun seseorang itu mengenakan jubah seorang pendeta atau pastor atau ulama, maka orang itu belum memahami esensi agama. dan jika seseorang sudah memahami esensi agama maka, seseorang itu tidak akan terjebak dengan Fanatisisme, Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 17 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Kelompokisme, Eklusivisme dan Isme-isme yang lain. Kata Kunci: Pluralisme, Menghormati, Peraturan-peraturan, Simpati Masalah Pluralisme Agama Saat ini, manusia hidup dalam dunia yang bergerak begitu cepat kearah pluralisme dengan beragam agama, bahasa dan budaya sebagai akibat dari perkembangan modernisme, liberalisme dan globalisasi.1 Di tengah gemerlap perubahan dahsyat itu, masyarakat agama justru memperlihatkan kultur sebaliknya: kerusuhan, kekerasan dan konflik berkepenjangan. Terutama dalam dekade terakhir ini. Banyak ketegangan muncul yang sebagaian dipicuh oleh minimnya paham keberagamaan, etnik dan budaya yang pluralis.2 Dampak modernisme adalah kecenderungannya untuk massifikasi (penyeragaman manusia dalam kerangka kerja teknis), sistem kerja industri yang menempatkan semua orang sebagai mesin atau sekrup dari sebuah sistem teknis rasional. Maka itu agama yang berposisi menempatkan nilai masing-masing manusia sebagai unik berharkat yang merupakan citra Tuhan. Dan dampak yang kedua adalah sekularisme yang tidak mengakui lagi ruang nafas buat yang Ilahi atau dimensi relegius dalam hidup ini. Sekulerisme adalah wujud ekstrem negatif dari proses skulerisasi karena mau memilah-milah adanya jagat relegius dengan hukum-hukum dan jadag dunia sekular dengan hukum-hukumnya pula. Mampukah krisis sekularisme lewat wajah-wajah ekstrim ateisme ditanggapi oleh religiositas agama secara kritis bisa menegaskanb bahwa rasionalitas atau akal budi memang pemberian Tuhan Tertinggi untuk manusia. Lihat lagi Mudji Sutrisno, Agama, Harkat Manusia dan Modernisme dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, seri DIAN I/th I, (Yogyakarta; Interfield, 1993), hlm. 203 2 Peperangan, kekerasan atau dorongan kearah yang menggunakan label agama, secara implicit atau ekplisit terus merebak dan menguat di sana sini. Ini dapat ditemui pada hampir semua agama. Misalnya pada agama Yahudi Sholomo Goren (1984), mantan pimpinan Rabbi untuk kelompok Yahudi Eropa Barat di Israel yang mengeluarkan fatwa bahwa “melakukan pembunuhan terhadap Yaser Arafat merupakan bagian dari tugas suci keagamaan. Kemudian dalam agama Kristen juga, sejak awal decade 90-an yaitu pengaruh Serbia yang didukung Gereja ortodoks membumi hanguskan Masjid-masjid di Sarajevo menjai lautan darah. Sementara di dalam Islam adanya gerakan terorisme dalam beragam bentuknya seperti Hezbullah yang sering disebut sebagai pelaku pengerahan truk-truk bom maut yang menghancurkan markas besar pasukan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis di Beirut. Itu semua dikatakan secara samar-samar digerakkan oleh semangat keagamaan. Di luar itu banyak kasus lain akan meneguhkan adanya kekerasan yang digerakkan oleh semacam motivasi 1 18a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Karena itu, paham pluralisme agama perlu disegarkan kembali. Konflik berkepanjangan dan kerusuhan yang tak kunjung henti dan maraknya beragam bentuk kekerasan menyadarkan manusia bahwa nilai-nilai kemanusian tampaknya kini mulai memudar paling tidak kurang diperhatikan dari kehidupan umat beragama. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa adanya sebagian umat beragama yang menganggap kekerasan atau pola-pola agresivitas sebagai sesuatu yang biasa atau lumrah, bahkan di antara mereka ada yang menjadikan sikap dan prilaku agresif itu sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Anand Krishna mengungkapkan bahwa agama berpotensi mempersatukan umat manusia dan bukan justru memecah belah. Walaupun pandangan tentang agama setiap umat beragama (manusia) berbeda-beda, itu disebabkan oleh pemahaman masingmasing pemeluk agama juga berbeda. Karena agama merupakan pengalaman individu, maka tujuan utama dari agama adalah memanusiakan manusia. Sebenarnya, akar berbagai kerusuhan yang berbau agama, bermula pada rasa prustasi dan alienasi serta deprivasi ekonomi dan politik. Marginalisasi periferialisasi dan depresi serta politik yang dialami massa menjadi kepahitan dan kemarahan yang siap meledak setiap saat menjadi kekerasan politik. Pada kondisi semacam itu, agama menjadi pemicu paling mudah dan efektif sebagai alat3 pemersatu untuk mengarahkan massa melakukan keagamaan. Lihat Abd ‘A’la, Melampaui Dialog Agama, Qomaruddin SF, ed., (Jakarta: Kompas, 2002), hlm, 16-17 3 Salah satu kemajemukan yang sangat krusial mengundang konflik atau pertentangan adalah diversitas dalam agama, bahkan dalam realitasnya perbedaan dalam aspek-aspek yang lain sering ditarik oleh sebagaian orang atau kelompok karena pemahaman agama mereka yang literalis atau karena kepentingan tertentu kedalam wilayah agama dalam rangka pembenaran (justifikasi). Justifikasi agama dalam suatu konflik, khususnya konflik yang timbul pada antar penganut agama –agama yang berbeda sangat mudah muncul kepermukaan. Dalam kondisi semacam itu agama merupakan bahan empuk sebagai bahan pemersatu massa (kelompok) yang histeris dan anarkis. Demikian pula simbol-simbol agama merupakan teriakan-teriakan pembangkit semangat efektif. Dengan mengatas namakan agama dan mengangkat simbol-simbol sakral, massa atau kelompok menjadi semacam pasukan berani mati yang berupaya melenyapkan kelompok lain. Baca Mudji Sutrisno, Agama, Harkat Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 19 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) kekerasan yang dibungkus dengan label agama. Dalam tataran tersebut agama-agama diharapkan memiliki focus terhadap persoalan hidup manusia. Sejalan dengan itu pula sejumlah tokoh seperti Schuman menunjukkan sikap optimistiknya tentang masa depan kehidupan manusia. Dia menyatakan : Memasuki millenium ketiga umat manusia akan mengalami perubahan kearah signifikan yang lebih baik. Namun untuk pencapaian kearah sana, rekontruksi pemahaman keagamaan umat manusia menjadi niscaya untuk dikembangkan karena manusia agama bersifat eksklusif. Agama-agama hendaknya berperan mengontrol manusia menjadi individu dewasa, merdeka dan bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat dan bangsa di dunia. Tetapi harapan semacam itu, hanya sekedar harapan belaka. Kehidupan sejahtera yang mencerminkan perdamaian secara hakiki belum dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan manusia.4 Memasuki millenium ketiga, kekerasan tetap mewarnai kehidupan manusia sampai derajat tertentu menunjukan tingkat eskalasi yang mengerikan. Dalam skala internasional, terorisme menjadi monster yang mengintai mangsanya setiap saat. Menara kembar World Trade Centre (WTC) dan gedung Pentagon yang menjadi sasaran kaum teroris merupakan bukti paling konkrit tentang jauhnya kehidupan yang damai di atas bumi. Pada tingkat nasional, kerusuhan dan kekerasan dalam bentuk yang beragam terus mewarnai kehidupan bangsa, bahkan para elite bangsa yang seharusnya menjadi teladan masih sering menampakkan sikap mereka yang jauh dari nilai-nilai civility. Secara langsung atau tidak langsung mereka mentolerir atau bahkan mendorong penggunaan kekerasan sekedar untuk mempertahankan kekuasaan. Terlepas dari adanya perbedaan mengenai bentuk-bentuk konkrit dari aplikasi nilai dan ajaran setiap agama, maka semua Manusia...., hlm. 33. Baca juga Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan, (Bandung: PT. Rosda Karya , 1999), hlm. 11 4 Olaf Schuman, Milenium Ketiga dan Tantangan Agama-agama dalam Martin L. Sinaga Edt. Agama-agama Memasuki Milenium Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 5. 20a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) agama berdiri dalam dataran yang sama,5 semuanya bertujuan kebahagian manusia. Untuk itu, tiap-tiap agama meyakini bahwa tujuan substansial itu tidak mungkin terwujud secara utuh tanpa adanya kerukunan dan kerja sama di antara semua umat manusia, terutama antar umat beragama yang berbeda-beda. Kearah sanalah (Tuhan) semua umat akan kembali. Di sini, pola keberagamaan yang berkembang masih menampakkan karakter yang sarat dengan nuansa formalisme yang kering dari nilai-nilai spiritual dan moral. Akibatnya nilainilai substansial agama yang bernuansa inklusif, moderat, toleran dan yang searti dengan nilai-nilai itu tidak pernah ditangkap dan diimplementasikan secarah utuh. Sebaliknya, klaim kebenaran sepihak yang meniadakan kebenaran kelompok lain kian mengental pada sebagian kelompok. Konsekuensinya terjadi penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain. Pada sisi lain dialog yang berkembang masih berjalan pada dataran retorik semata, serta menitikberatkan pada relasi subyek-obyek yang terkesan menindas. Pola ini tentunya semakin memperburuk relasi antara manusia yang sudah tidak kondusif lagi untuk menciptakan kehidupan yang sejuk. Semua agama yang berdiri pada dataran yang sama dari aplikasi nilai dan ajaran. Dalam islam misalnya, kemanusian hakiki adalah kembali kepada fitrah manusia itu sendiri, sebagai manusia yang cenderung kepada nilainilai keagamaan yang subtansial dan nilai-nilai moral spiritual. Oleh karena itu manusia dituntut untuk bercermin pad sifat-sifat Allah dan menyebarkannya dalam kehidupan. Sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sebagainya perlu diupayakan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehingga dunia ini menjadi dunia yang penuh kasih, penuh ketentraman, damai dan sejahtera. Nyaris tidak berbeda dengan Islam, Kristen mengajak manusia untuk untuk melepaskan diri dari beban ketakutan terutama terhadap kematian, beban rasa bersalah dan beban kungkungan egoisme. Dari pembebasan ini manusia diharapkan menuju satu hidup yang sama sekali baru. Dalam agama Kristen, satusatunya kekuatan yang dapat membebaskan manusia dan mampu menimbulkan perubahan kehidupan sebagai mana ang diinginkan oleh cinta. Dengan demikian menyebarkan kasih dan nilai-nilai sejenisnya menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus. Pada prinsipnya hal semacam itu merupakan ajaran hampir semua agama yang hidup dan berkembang di dunia. Konkretnya semua agama mengajarkan tentang kebajukan, keadilan dan pertanggung jawaban semua amal perbuatan manusia dihadapan Sang Pencipta. Abd ‘A’la, Melampaui Dialog., hlm.xi-xii 5 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 21 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Kenyataan itu menuntut manusia untuk merekontruksi dialog antar sesama dalam segala keberagamannya yang telah berjalan selama ini menuju suatu penciptaan dialog antar subyek yang mencerahkan. Pada saat yang sama dialog tersebut hendaknya dikembangkan lebih jauh lagi ke dalam bentuk konkrit yang bersifat praksis. Melalui model ini juga manusia diharapkan bukan sekedar dapat menyadari tentang pluralisme kehidupan sebagai suatu realitas yang konkrit yang tidak mungkin dihindari lagi, tetapi lebih jauh lagi kesadaran itu bisa di bumikan dalam kerja kreatif yang berwajah manusiawi. Perkembangan spiritual dan material Jika spiritualitas mempresentasikan totalitas sumbersumber kearifan, cinta dan perdamaian bersama di antara semua agama, maka bagaimanakah hubungannya dengan realitas tertentu dari tempat tertentu dan waktu tertentu? Bagaimanakah kaitan spiritualitas total dari totalitas warisan keagamaan manusia dengan totalitas sejarah manusia?. Selama berabad-abad, orangorang Hindu, Jaina, Budha, Yahudi, Kristen dan Islam mengklaim memiliki petunjuk unik dan sempurna bagi keselamatan manusia. Akan tetapi, tahap yang dicapai pada titik ini tampaknya bertentangan dengan klaim-klaim tersebut. Karena dimana-mana dijumpai kegelapan, diskriminasi, kebencian, pertumpahan darah dan ancaman total bagi kehidupan dan keberlangsungan hidup seluruh ras manusia. Jika dilihat secara global dimanakah peran spiritualitas sebagai penyembuh. Manusia secara fitrahnya merupakan makhluk spiritual dan makhluk rasional, memerlukan agama sebagai kebutuhan dasar dan di samping itu kebutuhan lain yang bersifat fisikal – kuantitatif dan rasional – saintifik. Untuk itu, agama yang terdiri dari seperangkat ajaran, nilai dan simbol perlu dipahami secara utuh oleh manusia, sehingga kehadirannya benar-benar fungsional bagi penyempurnaan kehidupan dan kehadiran mereka. Akan tetapi dalam perkembangannya, identitas agama pada umumnya ditransformasikan menjadi identitas etnik dalam jangka waktu yang panjang. Suatu agama sering memulainya sebagai suatu credo abstrak dengan tampilan dan ruang lingkup universal. Dalam generasi-generasi berikutnya agama menjadi lebih 22a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) konkrit sebagai seperangkat liturgy dan praktek yang terbatas pada komunitas tertentu dan pada wilayah tertentu. Kemudian agama mengkristalkan menjadi seperangkat ritual dan kebiasaan yang lebih konkrit yang membedakan komunitas tertentu dari komunitas lainya. Komunitas agama menjadi komunitas etnik. Komunitas etnik masih menjadi komunitas agama dalam banyak hal, maka agama sekarang telah sangat berbeda dengan agama generasi terdahulu. Selaras dengan hal itu Anand mengatakan: Pernah saya mendengar seorang tokoh lewat layar tv, kurang lebih ia mengatakan bahwa kita harus “membudayakan agama, jangan mengagamakan budaya”, tokoh ini patut dikasihani – beliau masih tidak dapat melihat esensi agama itu sendiri. Agama berkembang dari budaya, budaya tertentu melahirkan agama-agama besar kita. Budaya itu ibarat akar agama. Agama adalah batang pohon yang berkembang lewat spiritualitas, berbuah lewat kesadaran. Bagaimana anda bisa memisahkan budaya dari agama atau agama dari spiritualitas?. Berhentilah memilah-milah pahami proses ini, jangan mentuhankan budaya dan jangan pula mentuhankan agama. Ketahuilah bahwa semua itu merupakan anak-anak tangga untuk mencapai kesadaran tertinggi, untuk mencapai tujuan utama kita yang satu dan sama – Tuhan, Allah, Widi, Budha dan sebutan apapun yang anda berikan kepada-Nya.6 Keanggotaan etnik berperan sebagai kartu identitas. Kebutuhan identitas diyakini berasal dari masa yang sangat awal, bersamaan dengan munculnya kebudayaan manusia yang hidup dalam komunitas. Kebutuhan ini cenderung dilembagakan dalam jaringan kekeluargaan yang diperluas. Oleh karena itu, suatu kelompok etnik adalah kelompok sodilaritas yang untuk dimana orang terlahir dan terikat secara kultural dan biologis. Dari perspektif ini, keanggotaan dalam komunitas etno-kultural secara psikologis dekat dengan kekuatan yang memaksa individu memilih keanggotaan yang tidak disukai dalam kelas yang secara sosio-ekonomi menentukan dan menyatukan orang-orang yang Anand Krishna, Wedhatama Bagi Orang Modern – Madah Agung Kehidupan – Karya Sri Paduka Mangkunegoro IV, (Jakarta, Gramedia, 1999), hlm. 92-93 6 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 23 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) tersebar luas dan dari berbagai komunitas etnik yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan berbicara dengan bahasa berbeda pula. Dalam setiap komunitas baik komunitas agama atau kultural memiliki hukum (Syir’atan atau Syari’at) dan jalan hidupnya sendiri (Minhaj) serta mengalami perkembangan spiritualnya. Istilah Syir’ah atau Syari’ah secara bahasa berarti ‘jalan mengalirnya air’. Al-Qur’an menggambarkan syari’ah sebagai suatui sistem hukum yang niscaya bagi kesejahteran komunitas sosial dan spiritual. Istilah Minhaj pada sisi lain berarti ‘jalan terbuka’, yaitu jalan hidup.7 Dengan demikian, tampak jelas bahwa para Nabi yang diutus kepada umat-umat yang berbeda memberikan hukum dan jalan hidup kepada masyarakat sesuai tingkat kecerdasan dan hal-hal yang dapat mengantarkan perkembangan spiritual dan material. Anand pun mengatakan “ Tuhan tidak membedakan aapakah seorang itu Islam, atau Hindu, atau Budha yang Tuhan perhatikan adalah amal saleh manusia itu sendiri”.8 Bukanlah hal sulit bagi Allah untuk membuat umat manusia menjadi satu komunitas.9 Tetapi Allah memberi rahmat kepada manusia berupa pluralisme, sehingga menambah kekayaan dan keberagaman hidup. Setiap komunitas memiliki jalan hidup, kebiasaan, tradisi dan hukum sendiri, tetapi semua hukum dan cara hidup itu haruslah dapat menjamin perkembangan dan memperkaya hidup walaupun berbeda satu sama lain. Oleh karena itu kebesaran sebuah agama akan diukur melalui kebesaran tradisi yang ditinggalkannya, sedangkan kuat-lemahnya sebuah tradisi agama akan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pendukungnya. Di samping itu tentu saja oleh muatan ajaran atau doktrinnya, namun sesungguhnya semua doktrin agama selalu berkembang Mun’im A Sirry, Membendung Militansi Agama – Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 171 8 Anand Krishna, Bersama Sufi…. Hlm. 153 9 “… kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali…. QS: 5; 48 7 24a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) dalam perjalanan historisnya. Dalam perjalan sejarahnya agama-agama berperilaku tampaknya ditentukan oleh pandangan dunia yang pada intinya mereka melihat diri mereka sendiri. Dengan kata lain, pandangan dunia tidak dapat dihindarkan terkait dengan identitas10 mereka sebagai pemilik dan yang memproyeksikan klaim kebenaran yang menafikan klaim-klaim kebenaran lainnya. Ada banyak identitas dan masing-masing mengaku memiliki finalitas klaim-klaim kebenaran, maka hal itu cenderung menjadi konflik dan hal itulah yang dapat disaksikan pada dekade ini. Baik pada skala kecil maupun besar dalam sepanjang sejarah manusia. Maka penyamaan antara spiritualitas dan identitas harus dipandang sebagai penyebab utama perselisihan dan perpecahan. Kekuatan penyamaan spiritualitas dan identitas sebegitu besar, sehingga kendatipun terdapat beberapa kesaksian verbal (lisan) pada hampir semua tradisi keagamaan terdapat universalitas Tuhan dan transendensi-Nya, akan tetapi hubungan aktual di antara komunitas-komunitas agama pun tidak berkembang dengan mudah. Dalam penyamaan yang tertutup antara persepsi dan identitas yang dapat dipahami bukanlah pribadi, melainkan jenis dimana pengertian manusia akan identitas diri yang tertutup memproyeksikan pengertian orang lain. Sebagai contoh, jika seseorang memperkenalkan Smith kepada Ahmad, maka karena dikondisikan oleh pemahaman dirinya yang tertutup sebagai Manusia didefinisikan sebagai sekelompok yang terikat memiliki kebutuhan identitas yang hanya dapat dipertemukan secara komperatif, jika tidak bersifat relasi oposisi inklusif /eklusif dengan kelompok lain. Pembentukan dan keberlangsungan identitas sering bersifat relasional, oposisional dan konfliktual. Para anggota etnik dapat menciptakan ikatan-ikatan yang unik dalam bentuk simbol maupun fisik dalam berhubungan dengan kelompok lain. Ini tidak berarti ikatan-ikatan yang dibangun secara sosial yang diwujudkan oleh simbol budaya yang merupakan sistem tertutup. Karena itu tidak mengizinkan pertukaran dan interaksi yang membentuk kembali identitas. Jika identitas sebagai diferensiasi dipandang sebagai dimensi yang mempertahankan hidup, maka ia merupakan bagian yang dibangun dengan menemukan orang lain. Dinamika kami-mereka dalam hal ini terbentuk secara batiniah dalam psikologi manusia. Zakiyuddin Baidhawy, Ambivalensi Agama – Konflik dan Nirkekerasan, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm.112 10 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 25 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) seorang muslim Ahmad akan memandang Smith sebagai seorang Kristen. Inilah yang membentuk semua hal yang oleh Islamnya Ahmad disamakan dengan Kristen. Begitu pula Smith tidak melihat Ahmad sebagai pribadi, tetapi sebagi jenis yang membentuk semua hal yang oleh Kristennya Smith disamakan dengan Islam.11 Pertemuan spiritual adalah pertemuan antara dua pribadi dan bukan antara dua tipe. Pertemuan spiritual bersamaan dengan realitas orang lain bagaimana pun benarnya menurut cirri-ciri tertentu dalam penampilan dan prilaku (baik verbal maupun fisik) orang lain, citra yang diproyeksikan terhadap orang lain (Kristen, Yahudi ataupun Muslim) menjadikan seseorang buta dalam melihatnya sebagai pribadi dengan segala keraguan, kecemasannya yang membaur dalam kedalaman diri dan misteri kebenaran transenden, mengajak orang lain agar berhubungan dengannya, serta mencari titik temu dengan perjalanan spiritual orang lain. Kendatipun mungkin berbeda dan bahkan bertentangan dalam upaya berkomunikasi dan memasukinya. Karena tantangan besar di dalam pencarian spiritualitas yang mengatasi identitas-identitas dan klain-klaim kebenaran yang tertutup adalah mengakui pribadi konkrit dan nyata yang dia jumpai. Dengan kata lain, jika tidak ditemukan realitas orang lain sebagai pribadi, maka semua klaim untuk mengenal dan untuk memiliki spiritualitas akan menjadi abstrak dan kemunafikan yang terburuk. Sayangnya beban sejarah yang dipikul, politik yang mengekploitasi agama dan ketakutan sekular (yang bersifat rasial, nasional dan internasional) yang membangun pertahanan keagamaan tampaknya tidak pernah mengizinkan seseorang untuk melihat orang lain sebagai pribadi, tetapi sebagai kelompok luar yang diciptakan oleh kelompok dalam umat beragama itu sendiri. Dengan demikian langkah yang perlu diperhatikan menghubungkan spiritualitas dengan realitas adalah kesiapan seseorang untuk menerima orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai jenis. Untuk meraih hal ini seseorang harus menyelami bentuk lahiriah dan simbol serta memahami kesatuan internal (batiniah) dari: 1] asal usul manusia dalam Tuhan.12 2] ketidak Hasan Askari, Hasan Askari, Askari Hasan, Lintas Iman – Dialog Spiritual, Terj., Sunarwoto, (Yogyakarta, LKIS, 2003), hlm. 170. 12“ sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami 11 26a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) terbagian (indivisibilitas) manusia sebagai diri tunggal sebagaimana ciptaan.13 3] wujud spiritual itu berdasarkan asal usul dan indivisibilitas Ilahiyahnya.14 Bentuk lahiriah, baik berupa ras, bangsa, bahasa, kultur, keimanan maupun perbuatan manusia adalah bentuk dan tirai yang menutupi kesatuan esensial manusia yang tak terlukiskan. Akan tetapi, ada individu dan spesifitas pribadi dan tradisi. Selama seseorang mampu mengesampingkan kebiasaan orang lain sebagai jenis. Maka ia tidak hanya melihatnya menurut kesatuan, tetapi juga sebagai individu yang unik. Hanya saja jika ia melihat orang lain tidak hanya sebagai orang yang bersamanya dalam wujud lahiriah yang esensial, tetapi juga unik dan tunggal. Maka ia berhadapan langsung dengan realitas orang lain, baik sebagai pribadi yang terbatas maupun sebagai cermin dari yang lainnya yakni yang Esa dan unik, sumber segala wujud. Dalam setiap tradisi agama terdapat jalan esoterik dan gaib yang mengantarkan pada pusat realisasi ini. Tetapi kekuatan lahiriah yang sedemikian rupa sehingga jalan internal yang mengantarkan pada umumnya tertutup oleh beragam bentuk dan simbol, hingga manusia tersesat dalam pintu bentuk dan simbol yang tertutup. Berkumpul bersama berarti mengetuk pintu tersebut dan dengan demikian kebersamaan antar agama merupakan tanda pencarian kesatuan batin tersebut. Tidak tampak sama sekali wujudnya yang terpisah dan eksistensinya yang monologis. Begitu seseorang mengetahui orang lain sebagai pribadi riil, baik secara individual maupun universal maka ia bersama-sama dengannya mewujudkan cinta dan simpati spontan. Oleh karena itu, dalam tiap do’a, dalam tiap mereka menyembah Tuhan, dalam setiap yang benar dan bahkan dalam perbedaan paham umat beragama ada kesatuan dan perdamaian, harapan dan cinta. Agama-agama dalam Perbedaan dan Persamaan Agama dalam segala sesuatu dalam kehidupan, berdiri di kembali” QS: 2; 156 13“ Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu” QS: 4; 1 14 Hasan Askari, Lintas Iman ......., hlm. 173 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 27 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) bawah ambiguitas. Ambiguitas berarti bahwa agama adalah kreatif sekaligus destruktif. Agama memiliki kesuciannya (sakralitas) dan ketidaksuciannya (profanitas), oleh karena itu setiap agama mempunyai perbedaan dan persamaannya. Kesatuan dari berbagai bentuk agama itu dapat digambarkan dengan jelas oleh hubungan timbal balik antara tiga agama besar (Yahudi, Kristen dan Islam) yang disebut sebagai agama monoteisme.15 Karena dari ketiga agama itulah yang sering menampakkan dirinya dalam bentuk eksoterik yang tidak dapat dirukunkan satu sama lainnya. Akan tetapi yang perlu diperjelas perbedaan antara yang dapat disebut dengan kebenaran simbolis dan kebenaran objektif. Monoteisme pada hakikatnya didasarkan pada konsepsi dogmatis tentang kesatuan Ilahi. Konsepsi dogmatis itu bermaksud menunjukan konsepsi yang disertai sikap yang menolak pandangan lain. Tanpa sikap tersebut (yang merupakan pembenaran bagi semua dogma), tidak mungkin adanya penerapan eksoteris. Walaupun pembatasan ini penting demi kelangsungan hidup bentuk-bentuk eksoteris. Pembatasan itu pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan yang ada dalam setiap sudut pandang teologis.16 Paham monoteisme sudah dikenal sejak dahulu sebelum orangorang kemudian beralih menyembah Tuhan-tuhan yang banyak (politeisme). Dengan demikian ajaran monoteisme yang didakwahkan oleh agama semitik sesungguhnya bukanlah hal baru, melainkan mempertegas dan memperjelas kembali paham yang pernah tumbuh, tetapi karena berbagai faktor lalu menjadi samar-samar. Dalam sejarahnya manusia menyebut Tuhan Yang Esa dan Mutlak itu dengan berbagai nama dan istilah, namun secara subtansial, beragam nama itu menunjuk kepada Dzat yang sama. Untuk lebih jelas lagi baca Amstrong Karen, Sejarah Tuhan, Penerjemah Zaimul Am, (Bandung, Mizan, Cet VI, Mei 2003), hlm. 11-37 Baca juga Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyudi Nafis, Agama Masa Depan – Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta, Gramedia, 2003), hlm. 69-73. 16 Sebuah agama tidak dibatasi oleh apa yang dicakup olehnya melainkan oleh apa yang tidak dicakup olehnya. Ketidak pencakupan ini, tidak akan merusak kandungan agama yang terdalam – setiap agama pada hakikatnya merupakan suatu totalitas – tetapi sebagai gantinya akan lebih banyak wilayah perantara yang sering dinamakan “batas manusia” dan yang merupakan arena spekulasi dan kegairahan teologis baik moral maupun mistis. Jelas bukan metafisika murni atau esoterisme yang akan membebani umat dengan kewajiban untuk berpura-pura bahwa suatu pertentangan yang tampak mencolok itu bukan suatu pertentangan. Dengan itu yang perlu dilakukan adalah mengetahui bahwa pertententangan-pertentangan yang tidak hakiki dapat mengesampingkan 15 28a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Dengan kata lain, sudut pandang teologis ditandai oleh ketidak sesuaian dalam bidangnya sendiri antara berbagai konsepsi. Dan dari segi bentuk berbagai konsepsi itu saling bertentangan, namun dari segi ajaran metafisika atau kerohanian murni rumusanrumusan yang kelihatannya saling bertentangan, sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau saling berhubungan satu sama lain.17 Keterbukaan yang makin berkembang terhadap kebaikan dan kebenaran yang terdapat dalam tradisi agama-agama lain memberi harapan bagi terbentuknya era baru pemikiran keagamaan. Meskipun pertentangan antar agama-agama tetap menodai kehidupan bersama. Namun kekacauan sejarah agama dalam semua priode sejak zaman primitif terdahulu sampai perkembanganperkembangan terakhir akan sangat membingungkan, karena kunci yang melahirkan aturan di luar kekacauan itu adalah segala sesuatu dalam realitas, dapat mempengaruhi dirinya sebagai sebuah simbol bagi hubungan khusus pikiran manusia pada dasar dan arti pokoknya. Maka untuk membuka pintu yang tertutup atas kekacauan simbol agama ini, seseorang harus bertanya apa yang menjadi hubungan pokok tersebut yang disimbolisasikan dengan simbol-simbol agama itu?. Oleh karena itu Anand selalu menegaskan tentang manusia yang sadar akan esensi agama dan dapat melampaui kesadaran pikirannya sendiri yang dapat menjaga ketentraman hidup bersama dalam perbedaan agama. Secara simbolis, simbol-simbol agama menunjukan pada simbol yang melebihi mereka sendiri. Akan tetapi mereka sendiri turut serta di dalamnya sebagai simbol-simbol yang mereka tunjukan. Sehingga selalu cenderung (dalam pemikiran manusia) menggantikan hal yang dianggap menunjuk dan menjadi pokok diri mereka, sehingga mereka menjadi patung-patung. Pemberhalaan bukanlah sesuatu yang berbeda dengan absolutasi simbol-simbol Sang suci dan membuat simbol-simbol itu identik dengan Sang kesesuaian atau identitas yang hakiki, yang sama artinya dengan mengatakan bahwa masing-masing yang bertentangan itu mengandung kebenaran, karena adalah salah satu aspek dari seluruh kebenaran serta satu jalan menuju totalitas. Frithof Schuon, Islam dan Filsafat Perennial, penerjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan,1998), Cet IV, hlm. 55 17 Fritchof Schuon, ibid., hlm. 154 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 29 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Suci itu sendiri. Dengan cara ini orang-orang suci bisa menjadi Tuhan. Tindakan-tindakan ritual dapat memberikan validitas mutlak meskipun hanya merupakan ungkapan situasi yang khusus. Disini dapa dilihat dengan apa yang sering disebut sebagai “demonisasi” dalam semua aktivitas sakramental agama dalam semua obyek suci, doktrin-doktrin suci dan upacara-upacara suci. Semuanya menjadi demonik yang terangkat pada karakter pokok dan mutlak dari Sang Suci itu sendiri.18 Dalam semua simbol agama, ada tingkatan-tingkatan simbol yang fundamental yaitu: tingkat transenden dan tingkat imanen. Tingkat transenden adalah tingkat yang mulai di luar realitas empiris yang dihadapi, sedangkan tingkat imanen adalah tingkat yang dijumpai dalam pertemuan dengan realitas.19 Pada tingkat transenden, simbol dasar akan menjadi Tuhan itu sendiri. Tetapi, Tuhan tidak dapat begitu saja dikatakan sebuah simbol karena ada dua hal yang selalu berkembang dengan Tuhan itu sendiri. Pertama adalah bahwa ada elemen non-simbolis berada dalam image Tuhan yaitu Tuhan adalah realitas pokok, makhluk diri, dasar kekuatan makhluk dan makhluk tertinggi dari segala hal-hal yang benar-benar eksis dengan jalan yang paling sempurna. Dengan demikian manusia memiliki image wujud tertinggi dalam benak mereka dan makhluk dengan karakteristik kesempurnaan tertinggi. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki simbol yang merupakan simbolisasi gagasan tentang Tuhan yaitu “makhluk diri”.20 Kedua adalah kualitas-kualitas dan lambang-lambang Tuhan. Apapun yang dikatan umat beragama tentang-Nya ; Dia Maha Pengasih, Maha Pemurah, Ada dimana-mana dan lain sebagainya merupakan lambang-lambang Tuhan yang berasal dari kualitas-kualitas yang telah dialami dalam diri manusia, dan itu tidak dapat diaplikasikan pada Tuhan dengan pemahaman harfiah. Paul Tillich, Teologi Kebudayaan – Tendensi, Aplikasi dan Komparasi, Penerjemah, Mimin Muhaimin, (Yogyakarta: Ircisod, 2002), hlm. 71 19 Ibid 20 Ibid, hlm. 72 18 30a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Jika hal itu terjadi, maka ia mengarah pada absurditas yang tak terbatas jumlahnya. Ini juga menjadi salah satu penyebab destruksi agama akibat interpretasi komunikasi yang keliru tentang-Nya. Sedangkan pada tingkat Imanen yaitu tingkat penampilanpenampilan Tuhan dalam waktu dan ruang. Diantaranya adalah Inkarnasi-inkarnasi Tuhan,21 Makhluk-makhluk berbeda dalam waktu dan ruang. Gagasan inkarnasi ini selalu berhubungan dengan tingkat transenden dan tingkat imanen. Secara historis seseorang dapat mengatakan bahwa perjalanan keduanya merupakan situasi tingkat imanen dan transenden, yang ia tidak membedakannya. Tetapi, inkarnasi-inkarnasi22 karakter sakramental lebih dibutuhkan di Yunani (Dewa-dewa dalam Mitologi), bangsabangsa Semitik dan India karena untuk menghindari keterasingan Tuhan yang berkembang bersama penguatan elemen transenden. Masalah inkarnasi ini pun Anand Krishna menjelaskan: Penciptaan itu terjadi dimana saja, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Apakah seorang bayi lahir secara alami, lewat test-tube Inkarnasi Tuhan dalam hal ini adalah mitos Kristen yaitu Tuhan turun ke dalam pribadi anak-Nya yang dilahirkan di bumi sebagai anak kecil, yang meninggal demi ampunan dosa-dosa manusia dan bangkit kembali untuk melanjutkan kehidupan di bumi dan kemudian naik ke surga, untuk nantinya kembali lagi di hari akhir dengan segala kebesarannya. Dalam kata-kata yang terkenal dari pernyataan iman (yang berasal dari abad keempat),ini adalah kisah Tuhan Yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi dan putera-Nya Yesus penguasa umat, yang eksis sebelum ada waktu dan dilahirkan di bumi dari Roh Kudus dan perawan maria. Dia menderita di bawah Pontius Pilate dan disalib demi ampunan dosa-dosa, bangkit kembali di hari ketiga, naik ke Surga dimana ia duduk di tangan kanan Tuhan Bapa dan kemudian datang lagi untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Lihat John Hick, Dimensi Kelima Menelusuri Makna Kehidupan, Terj., Hermansyah Tantan, (Jakarta, PT.Rosda Grafindo Persada, 2001), hlm.302 22 Penganut Budha biasanya berbicara tentang kelahiran kembali ketimbang inkarnasi, karena tidak ada kontinuitas entitas yang berinkarnasi secara berurutan. Salah satu ajaran Budha adalah tidak ada diri, jiwa, atman, yang abadi. Bahkan diri empiris atau ego bukan entitas yang tahan lama tetapi (seperti yang dikatakan David Hume) merupakan suksesi momen kesadaran yang terkait bersama-sama dengan fakta bahwa momen yang berikutnya dipengaruhi oleh dan memasukan memori momen-momen awal. Di dalam kontunuitas kasual, menurut doktrin karma, semua tindakan manusia (termasuk aksi mental) mempengaruhi masa depan seseorang dan masa depan orang lain. John Hick, ibid., hlm. 316 21 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 31 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) ataupun cloning – kelahirannya tetap membuktikan kehadiran Allah. Jangan takut Tuhan anda akan menganggur. Yang berulang kali mengalami kelahiran dan kematian adalah ego kita yang begitu kompleks. Keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, obsesi-obsesi terpendam semuanya itu yang menyebabkan terjadinya kelahiran kembali. Kelahiran dalam dunia ini ibarat belajar di sekolah. Alam semesta ini ibarat lembaga pendidikan, universitas. Ada fakultas-fakultas lain pila yang terdapat dalam dimensi lain. Masih ada begitu banyak bentuk kehidupan yan lain. Apabila seseorang mati dalam kesadaran ia akan tahu persis mata pelajaran apa yang harus dipelajari. Begitu lahir kau tersenyum. Susah sekali bagi seorang bayi yang baru lahir untuk memberikan senyuman semacam itu. Kau harus menggunakan seluruh energimu untuk memberikan senyuman pertama. Otot-otot yang belum berkembang sempurna harus dipaksa sedikit. Kau tidak akan perduli akan rasa sakit dan memberikan senyuman pertama. Ah, kembali lagi ke dunia. Kau mengenali ayahmu dalam kelahiran ini.23 Oleh karena itu, meskipun setiap agama memiliki klaim kebenaran sendiri, ini tidak berarti persamaan dan perbedaan pada tradisi agama menjadi jurang pemisah antar pemeluk agama. Justru karena adanya klaim-klaim itulah maka dialog menjadi sangat urgen, karena agama pada akhirnya tampil dalam prilaku pemeluknya. Maka setiap umat agama adalah makhluk sosial yang mau tidak mau mesti terlibat dalam situasi konflik dan dialog. Meskipun respon iman pada dasarnya dialamatkan pada Tuhan, tetapi oleh Tuhan komitmen dan respon iman tadi diperintahkan untuk diwujudkan dalam hubungan sosial, sehingga aktualisasi komitmen beragama tidak mungkin terwujud tanpa melibatkan diri dalam usaha-usaha kemanusiaan. Sebagai konsekuensinya iman selalu menuntut terwujudnya hubungan dialogis baik antara seorang hamba dengan Tuhannya maupun antar sesama umat beriman, hanya dengan dialog maka seseorang bisa berbagi pengalaman iman dan berbagi kebenaran. Lebih dari itu hanya melalui dialog maka kualitas kemanusiaan akan tumbuh dan Anand Krishna, Reinkarnasi – Hidup Tak Pernah Berakhir, (Jakarta, Gramedia, 1998), hlm. 29-31. 23 32a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) terbentuk. Tuhan dalam Konsepsi dan Persepsi Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan saat berdiskusi mengenai Tuhan. Pertama : Dia dapat didekati sebagai ‘something to be argued about’, yang dalam hal ini objek formalnya adalah segala hal yang berkaitan dengan theism, atheism, non-atheism, deism, dan agnosticism. Pendekatan kedua: dapat dilakukan dengan memposisikan Tuhan sebagai something to be sacrificed, yang dalam hal ini berkenaan dengan segenap aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat, baik berupa commitment, dedication, maupun involvement. Sejalan dengan itu, ada hal lain yang perlu dimengerti saat seseorang memahami Tuhan, yaitu bahwa manusia harus mengerti dan memahami keterbatasan konsepsinya tentang Tuhan, karena tak ada yang bisa mengenal Tuhan kecuali Dia sendiri. Dari sini seseorang memiliki dua macam pengertian tentang Tuhan, yaitu: Tuhan dalam konsepsi manusia dan Tuhan Yang Hakiki yang berada jauh di luar konsepsi manusia. Tuhan dalam konsepsi manusia adalah Tuhan yang dibicarakan, didiskusikan, diperdebatkan lewat bahasa maupun akal pikiran sedangkan Tuhan Yang Hakiki adalah Tuhan yang tidak bisa dibicarakan baik oleh siapa pun. Dalam tradisi monotheistik diyakini bahwa Tuhan tidak bisa sungguh-sungguh dapat dikenal dan diketahui oleh makhluk, sebab:”Tidak ada yang hakiki selain Dzat Maha Hakiki”. Karena sesungguhnya Tuhan secara mutlak dan tak terhingga sungguhsungguh sebagai Dzat Maha Hakiki, sedangkan realitas alam semesta hanya hakiki secara relatif sehingga realitas-Nya berada jauh di luar pemahaman realitas makhluk. Jelasnya, yang relatif tidak akan pernah sanggup menjangkau Yang Maha Mutlak, Sang Maha Hakiki. Ibarat timbangan emas tidak dapat dipergunakan untuk menimbang gunung. Andai manusia bisa mengetahui sesuatu tentang Tuhan maka pengetahuannya itu bersifat relatif. Makhluk berhubungan dengan Tuhannya melalui sifat-Nya yang menampakkan tanda dan jejak-Nya dalam eksistensi kosmos. Manusia tidak bisa mengetahui Tuhan dalam diri-Nya sendiri tetapi hanya sejauh Tuhan mengungkapkan diri-Nya melalui kosmos. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 33 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Dia adalah ‘Mutiara Terpendam’, lalu Dia ciptakan makhluk yang dengan ciptaan-Nya itu makhluk mengenal dan mengetahui-Nya. Tegasnya, Tuhan menciptakan alam semesta seisinya sehingga Dia dapat diketahui melalui ciptaan-Nya itu. Tuhan bukan mitos, Dia adalah Realitas Ultim, yang eksistensi-Nya akan meyakinkan manusia bahwa dalam rentang sejarah umat manusia yang immorial ini kebaikan dan kebahagiaan bisa berpadu dalam proporsi yang ‘sempurna’. Realitas itu sendirisebagaimana Kierkegaard menyatakan-adalah sebuah sistem bagi Tuhan, meskipun realitas itu sendiri tidak bisa menjadi sistem bagi setiap jiwa yang eksis. Tuhan dalam Konsepsi24 Secara keilmuan, Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin menjadi objek kajian ilmu, karena kajian ilmu selalu parsial, terukur, terbatas dan dapat diuji secara berulang-ulang pada lapangan atau laboratorium percobaan keilmuan. Dengan demikian, kehendak untuk membuka adanya Tuhan melalui pendekatan ilmu, akan mengalami kegagalan karena sudah dari sejak awal tidak benar secara metodelogis.25 Dalam filsafat hakikat Tuhan telah menjadi bahan perenungan yang sangat intens, sejak Yunani Kuno bahkan sampai saat ini. Semula Tuhan dipahami sebagai asal usul kejadian semua yang ada ini, yang ditegaskan dengan prinsip adanya sebab pertama first causa atau prima kausa26 yaitu yang menyebabkan adanya Konsepsi berasal dari bahasa Latin Concipere, artinya memahami, menerima, menangkap. Yang merupakan gabungan dari Con artinya, bersama dan Cappere artinya menangkap atau menjinakkan secara istilah dapat diartikan: 1] kesan mental atau pemikiran, ide, suatu gagasan yang mempunyai derajat ke kongkretan atau abstraksi yang digunakan dalam pemikiran abstrak. 2] apa yang membuat pikiran mampu membedakan satu benda dari yang lainnya. 3] suatu ide yang diberikan dari persepsi (hasil persepsi) atau penginderaan (sensasi). Lihat Lorens Bagus, Kamus Filsafat Barat, (Jakarta, Gramedia, 2002), hlm.481 25 Musa Asy’arie, Filsafat Islam – Sunnah Nabi Dalam Berpikir, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm.151 26 Pada zaman pra-Sokrates yang berpandangan monistik menganggap kosmos itu didasari oleh satu prinsip atau asas; Thales menyatakan bahwa prinsip itu adalah air, menurut Aximenes prinsip itu udara; menurut Anaximandros prinsip itu adalah to apeiron (yang tidak terbatas): dan bagi Heraklitos prinsip 24 34a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) semua ini. Sebab pertama itu juga disebut sebagai penggerak yang tidak bergerak, yang menggerakkan semua yang ada ini dan yang ada ini selalu berada dalam pergerakan atau perubahan.27 Penetapan adanya yang pertama bisa jadi karena kebuntuan berpikir yang memaksanya harus menetapkan adanya prilaku awal, padahal hokum sebab akibat bisa terjadi berulang-ulang.28 Dengan demikian penggerak pertama yang tidak bergerak, bagai mana mungkin terjadi gerakan, jikalau penggerak pertama tidak menggerakkan. Kebuntuhan berpikir pada akhirnya melawan logikanya sendiri denag memotong lingkaran sebab akibat yang terputus.29 Dalam perkembangan selanjutnya, oleh kemampuan manusia mengelolah dan menundukan alam, maka ia dapat membentuk alam seperti yang dikendakinya dan seakan-akan hanya dialah yang menentukan segala-galanya.30 Selanjutnya konsep Tuhan menurun, bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan dibalik makro- cosmos atau salah satu faktor di dalamnya dan juga bukan mikro-cosmos yaitu eksistensi manusia denag kekuatan ide dan kemampuan kecerdasan yang kreatif, tetapi turun pada apa yang dibuat sendiri yaitu simbolisasi benda-benda hasil karya sendiri.31 Tetapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang makin canggih, manusia menciptakan sistem kebudayaan yang berorientasi pada cita-cita social yang makin komplek. Karena berhadapan dengan realitas social dan kehidupan masyarakat itu adalah api. Bertand Rusell, Sejarah Filsafat Barat, Terj., Sigit Jatmiko dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 31-65 27 Musa Asy’arie, Filsafat Islam......, hlm. 152 28 Ibid, hlm. 153 29 Ibid, dan logika tentang pencarian Tuhan dengan menunjuk faktor alam yang dianggap layak menjadi Tuhan. Lihat QS: Al-An’am [6]; 76 - 79 30 Pada dataran ini Tuhan sebagai yang menentukan dalam kehidupan yang disimbolisasikan pada seorang raja sebagai pemegang kuasa, maka dengan itu manuialah yang bertindak sebagai Tuhan. Seperti yang terjadi pada kekuasaan raja Fir’aun yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Seperti digambarkan dalam al-Qur’an QS: Al-Qasas [28];38-39 31 Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an QS: Al-Anbiya’ [21]; 57-59. dan tentang perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan baca lagi Musa Asy’arie, Filsafat Islam......, hlm 157-159. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 35 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) yang bersifat plural dan kompleks. Pada dataran ini manusia membangun basis ideologi yang mengikatnya dalam kesatuan komunitas yang berorientasi pada usaha mewujudkan cita-cita ideologi dalam realitas kehidupan manusia. Pada perkembangan ini manusia menciptakan ideologi bahkan mempertuhankannya, mereka siap membela dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memenangkan ideologinya, suatu perjuangan yang menuntut suatu totalitas. Jika dilihat perkembangan konsep pemikiran tentang Tuhan, sebagai kekuatan yang maha dahsyat yang menetukan kehidupan manusia, ternyata telah mengalami berbagai perkembangan dan pergeseran, akan tetapi tidak saling menafikan dan meniadakan. Semua konsep itu sampai sekarang masih tetap ada dan bertahan, meskipun mengalami banyak modifikasi dan variasi sesuai denagn perubahan zaman. *** DAFTAR PUSTAKA 36a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Abd ‘A’la, Melampaui Dialog Agama, Qomaruddin SF, ed.,. Jakarta: Kompas, 2002. Amstrong Karen, Sejarah Tuhan, Penerjemah Zaimul Am. Bandung, Mizan, Cet VI, Mei 2003. Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan. Bandung: PT. Rosda Karya , 1999. Bagus, Lorens. Kamus Filsafat Barat. Jakarta, Gramedia, 2002. Frithof Schuon, Islam dan Filsafat Perenial, penerjemah Rahmani Astuti. Bandung: Mizan,1998. Hasan Askari, Hasan Askari, Askari Hasan, Lintas Iman – Dialog Spiritual, Terj., Sunarwoto. Yogyakarta, LKIS, 2003. Hick, John. Dimensi Kelima Menelusuri Makna Kehidupan, Terj., Hermansyah Tantan. Jakarta, PT.Rosda Grafindo Persada, 2001. Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyudi Nafis, Agama Masa Depan – Perspektif Filsafat Perennial. Jakarta, Gramedia, 2003. Krishna, Anand. Reinkarnasi – Hidup Tak Pernah Berakhir. Jakarta, Gramedia, 1998. Krishna, Anand. Wedhatama Bagi Orang Modern – Madah Agung Kehidupan – Karya Sri Paduka Mangkunegoro IV. Jakarta, Gramedia, 1999 Mudji Sutrisno, Agama, Harkat Manusia dan Modernisme dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, seri DIAN I/th I. Yogyakarta; Interfield, 1993. Mun’im A Sirry, Membendung Militansi Agama – Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Erlangga, 2003. Musa Asy’arie, Filsafat Islam – Sunnah Nabi Dalam Berpikir. Yogyakarta: LESFI, 2002. Rusell, Bertand. Sejarah Filsafat Barat, Terj., Sigit Jatmiko dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Schuman, Olaf Milenium Ketiga dan Tantangan Agama-agama dalam Martin L. Sinaga Edt. Agama-agama Memasuki Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 37 Kritik Wacana Pluralisme Agama (oleh: Andi Hartoyo) Milenium Ketiga. Jakarta: Gramedia, 2000. Tillich, Paul. Teologi Kebudayaan – Tendensi, Aplikasi dan Komparasi, Penerjemah, Mimin Muhaimin, (Yogyakarta: Ircisod, 2002), hlm. 71 Zakiyuddin Baidhawy, Ambivalensi Agama – Konflik dan Nirkekerasan. Yogyakarta: LESFI, 2002. 38a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) RELATIVITAS AJARAN AGAMA: MENUJU PLURALISME KEBERAGAMAAN YANG HARMONIS Ahmad Atabik STAIN KUDUS Email: [email protected] ABSTRAK Deskripsi fenomena keberagamaan manusia, sebenarnya tidaklah semudah dan sesederhana seperti yang biasa dibayangkan oleh banyak orang. Ada manfaatnya memang untuk sesekali melihat agama dalam bentuknya yang tidak sederhana, lantaran berbagai persoalan pelik yang terkait dengan fenomena itu sendiri. Menunjuk agama dengan sebutan proper noun seperti Islam, Katolik, Proterstan, Hindu, Budha adalah sangat mudah, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar apakah tidak ada bentuk abstrat noun dari segala macam bentuk kepercayaan dan penghayatan agama yang beraneka ragam tersebut? Jika tidak ada bentuk abstract noun sebagai landasan ontologi seuatu kepercayaan, mustahil agaknya manusia dapat menyebut dengan sebutan proper noun terhadap apapun, lantaran abstract noun sebenarnya adalah dasar logika penyebutan proper noun. Menurut M. Amin Abdullah, adanya “truth claim” yang sering kali melekat pada sebutan agamaagama dengan proper noun, sangat boleh jadi lantaran tidak atau kurang dikenalinya wilayah abstract noun yang menjadi Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 39 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) landasan logis-ontologis bagi keberadaan masing-masing proprer noun. Dari sini pula sebenarnya bermula segala macam kesulitan yang mengitari persoalan. Pluratitas agama-agama yang dipeluk oleh berbagai macam gologan, kelompok dan sekte keagamaan pada level historis-empiris. Kata Kunci: Relativitas, agama, pluralisme dan harmonis Pendahuluan Secara empiris keberagamaan yang telah berkembang dalam wacana kontemporer didefinisikan sebagai pencarian akan realitas asali. Dalam rangka pencarian ini, tampaknya agama sering terdorong untuk menegaskan dirinya sebagai unik dan universal. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan terselubung dalam agama-agama tersebut sehingga banyak agama menyebut dan mengklaim bahwa dirinya adalah agama yang paling benar sementara yang lain adalah imitasi atau palsu. Padalah kalau kita mengadakan analisa mengenai kebenaran agama yang bersifat absolut muncul suatu kesan bahwa kebenaran agama hanya sebatas “kulit luar” atau khas simbol-simbol luar yang bersifat rutinitas, elementer, dan fisiologis. Sehingga klaim kebenaran agama akan memunculkan sikap keberagamaan yang angkuh bagi pemeluknya. Kalau analisa kita kembangkan lebih pada pertanyaan; mengapa sampai muncul sikap angkuh dalam agama itu? Maka kita bisa membaca bahwa ternyata dibalik semua itu terdapat suatu kepentingan politik agama untuk memainkan lakon signifikan dalam pembentukan masyarakat melalui aturan normatifnya yang diinterpretasikan menjadi ritual dan legalitas tertentu sebagaimana tertuang dalam teks-teks agama. Untuk menganalisa lebih dalam mengenai fenomena keberagaman manusia, terdapat dua tawaran pendekatan yaitu; Pertama, melalui pendekatan normativitas ajaran wahyu. Pendekatan ini merupakan ciri khas dari semua agama. Kedua, menggunakan pendekatan historitas pemahaman dan interpretasi orang-perorang atau kelompok-kelompok terhadap norma-norma 40a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) ajaran agama yang dipeluknya.1Pemberangkatan pendekatan normatif doktrinal agama-agama itu bermuara pada teks-teks yang tertuangkan dalam kitab suci agama-agama yang bersifat literalis, tektualis dan skriptualis. Menurut M. Amin Abdullah kedua pendekatan ini tidak berjalan secara romantis bahkan keduanya diwarnai dengan tension atau ketegangan baik bersifat kreatif maupun destruktif. Pendekatan dan pemahaman terhadap fenomena keberagaman pendekatan pertama tidak sepenuhnya menyetujui alternasi pemahaman yang dikemukakan oleh pendekatan kedua. pendekatan terhadap fenomena keberagaman yang kedua dituduh oleh yang pertama sebagai pendekatan keagamaan yang besifat “reduksionis”, yakni pendekatan keagamaan yang hanya terbatas pada aspek eksternal-lahriah dari keberagamaan manusia dan kurang begitu memahami, menyelami dan menyentuh aspek batiniah eksoteris serta makna terdalam dan moralitas yang dikandung oleh ajaran agama-agama itu sendiri. Sedang pendektan studi agama yang kedua, yang lebih bersifat histories balik menuduh corak pendekatan yang pertama sebagai jenis pendekatan dan pemahaman keagamaan yang cenderung bersifat “absolutis” lantaran para pendukung pendekatan pertama ini cenderung mengabsolutkan teks yang sudah tertulis, tanpa berusaha memahami terlebih dahulu apa sesungguhnya yang melatarbelakangi berbagai teks keagamaan yang ada. 2 Normativitas Ajaran Agama Pendekatan normatif doktrinal ajaran agama tidak dapat dilepaskan dari teks-teks yang tertulis dalam kitab-kitab suci agama-agama. Namun, teks-teks kitab suci yang disinyalir bersifat absolut banyak disalahguna dan artikan oleh sebagian kalangan yang intens dalam studi mereka tentang teks-teks agama. Oleh karenanya, kemudian muncul pertanyaan dibenak kita, siapakah sesungguhnya subyek yang berbicara dan siapakah obyek yang disapa oleh oleh teks tersebut?. Lihat M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historitas? (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996), hlm.v. 2 M. Amin Abdullah, Studi Agama…, hlm. vi. 1 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 41 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) Untuk menjawab pertanyaan di atas kita dituntut bersifat kreatif dan tidak berkutat pada pandangan terhadap teks-teks itu saja. Bukankan sebuah teks hanyalah sebagian dari pikiran pengarangnya di samping juga sebuah teks tidak selalu akurat dalam menghadirkan sebuah realitas atau menyajikan sebuah konsep?. Menurut Komaruddin Hidayat, di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar kita lebih mendekati kebenaran mengenai gagasan yang hendak disajikan oleh pengarangnya.3 Pensoalan inti yang muncul kemudian adalah mampukah akal dan bahasa manusia menyajikan deskripsi dan atribusi yang tepat mengenai Tuhan? Bukankah sejauh-jauh manusia berfikir dan berimajinasi dan bertata bahasa hanya berkutat pada wilayah pengalaman empiris dan inderawi?4 Jika statemen ini dapat diterima, maka Tuhan Yang Maha Ghaib yang berada diluar jangkauan inderawi, nalar dan bahasa manusia tidak mungkin diungkap dalam bahasa manusia. Pertanyaan lebih jauh adalah bagaimana kita memahami ungkapan bahasa kitab suci, misalkan al-Qur’an, tentang Tuhan? Menurut Komaruddin, sebagian berpendapat bahwa apapun yang yang diungkapkan oleh kitab suci tentang Tuhan hanya mampu dipahami oleh manusia sebagai ungkapan-ungkapan analogis dengan alam pikiran dan dunia empiris manusia. Karena berbagai pernyataan tentang Tuhan tidak bisa diverifikasi atau difalsivikasi secara obyektif dan empiris, maka dalam memahai kitab suci seseorang cenderung menggunakan standar ganda. Yaitu, seorang berpikir dalam kapasitas dan berdasarkan pengalaman manusia namun diarahkan untuk suatu obyek yang diimani yang berada Tanpa memahami motif di balik penulisan sebuah buku, suasana potitis-psikologis dan sasaran pembaca yang dibayangkan oleh pengarangnya sendiri, maka sangat mungkin kita akan salah paham ketika membaca sebuah karya tulis. Lihat Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996), hlm. 2. 4 Limit kemampuan nalar manusia untuk mengetahui metafisik secara sistematis dipaparkanoleh Immanuel Kant (1724-1804) dalam karyanya yang terkenal Critique of Pure Reason dan Religion Within the Limits of Real son Alone. Bagi Kant, argument yang paling tepat untuk memamahi Tuhan adalah argument moral yang menggunakan practical reason bukan pure reason yang bekerja melakukan penalaran kritis dan analitis. Ibid, 6. 3 42a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) di luar jangkauan nalar dan inderanya.5 Olehnya wilayah ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang remang-remang, karena dalam sikap “beriman” terdapat hal-hal yang diyakini kebenarannya namun tidak ketahui dan tidak terjangkau oleh nalar. Wilayah inilah yang kemudian melahirkan Ilmu Kalam. Dalam wilayah Ilmu Kalam ini, Komaruddin Mengatakan bahwa muatan Ilmu Kalam terletak pada penalaran tentang firman Tuhan dalam dalam rangka melayani iman atau beriman pada Tuhan berdasarkan pertimbangan logis. Selanjutnya ia mengatakan; Dalam berteologi, meskipun nalar telah berusaha memahami dan menafsirkan firman Tuhan secara logis, namun pada ujungnya orang yang beragama kan pasrah pada keputusan imannya ketika dihadapkan pada firman Tuhan yang sulit dicerna oleh akal. Orang yang beriman menekankan makna dan pesan perspektif kitab suci ketimbang ungkapan deskriptifnya, meskipun dalam berbagai hal perlu juga dipahami makna deskriptif-literalnya, terutama yang berkenaan dengan hukum.6 Intinya bahwa kandungan pokok kitab suci adalah pesan normatif, mengajarkan seseorang agar berserah diri pada Tuhan, mentaati jaran-ajaran-Nya, demi kebaikan hidup manusia di bawah ridla-Nya. Hal yang senada juga diungkap oleh Harun Nasution,7 bahwa masyarakat beragama, khususnya masyarakat modern percaya pada kemampuan rasio dan pendekatan ilmiah. Dasar agama lebih banyak berkaitan dengan perasaan dan keyakinan daripada rasio. Perasaan dan keyakinan, berlainan dengan dengan rasio yang mempunyai tendensi dogmatis. Ajaran-ajaran agama oleh pemeluknya dirasakan dan diyakini mesti benar, sungguhpun ajaran-ajaran itu terkadan berlawanan dengan rasio. perasan dan Uraian Lebih Jauh tentang hal ini, lihat Ronal E. Santoni (edt.), Religious Language and The Problem of Religious Knowledge (London: Indiana University Press, 1968), sebagaimana dikutip oleh Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama…, hlm. 6. 6 Ibid, 7. 7 Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 88 5 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 43 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) keyakinan juga banyak bersifat subyektif dan kurang bersifat obyektif. Selanjutnya, agama banyak dan erat hubungannya dengan hal-hal yang bersifat imaterial dan yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Sedangkan pembahasan ilmiah pada umumnya dipakai dalam wilayah materi. Menurut M. Amin Abdullah,8 dalam menggambarkan kesulitan mendasar yang dihadapi seseorang ketika hendak memahami fundamental values dari kitab suci agama yang dianutnya, khususnya bagi seorang muslim di dalam memahami al-Qur’an secara utuh dan komprehensif lewat keteladanan Nabinya. Pertama, adalah kesulitan bahasa. sebagimana kita ketahui bahwasanya al-Qur’an dan al-Hadis adalah tertulis dalam bahasa Arab, sehingga diperlukan waktu dan tenaga ekstra keras untuk menguasai dan memahami inti pokok ajarannya, belum lagi, kemudian menginternalisasikan ajaran-ajaran dasarnya dalam satu keutuhan pandangan hidup seseorang. Kedua, adalah terbentuknya lapisan geologi pemikiran keagamaan Islam lantaran pengaruh proses pengendapan sejarah pemikiran yang mengiringi perjalanan peradaban manusia Muslim itu sendiri. salah satu konsekuensi dari adanya kedua kesulitan tersebut di atas, adalah bahwasanya misi kenabian yang dulunya relatif sangat sederhana dan mudah dicerna, seringkali menjadi kian bertambah sulit dan rumit lantaran dalam perjalannya yang panjang, berubah menjadi doktrin-doktrin teologis yang eksklusif, atau aturan-aturan fiqh yang legal formal, atau berubah menjadi ajaran architektonik tarekat dalam tasawuf yang seringkali bersifat eskapistik. Belum lagi, jika partialitas pemahaman subtansi ajaran Islam tersebut ditambah dengan letaknya berbagai kepentingan atau interest kelompok maupun gologan politik yang menyertainya. M. Amin Abdullah menambahkan, adanya pengaruh pemahaman ajaran keagamaan Islam yang parsial, yang kemudian, bentuk pemahaman keagamaan tersebut menggumpal dalam lapisan geologi pemikiran keagamaan, maka moral kenabian Islam yang aturannya bersifat universal, inklusif, hanif, tereduksi sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi semat-mata “eksklusif”, “partikularistik”, “lagalistik-formalistik” dan “ahistoris”, sehingga M. Amin Abdullah, Studi Islam…., hlm. 24. 8 44a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) untuk wilayah dan era tertentu dalam sejarah peradaban Islam terjadi proses distorsi nilai-nilai etika Islam dan menjadikannya begitu sempit menjerat. Bukan lagi proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan yang fundamental yang berjalan secara gradual yang dipentingkan, tetapi yang terjadi adalah proses pemilahan yang bersifat dikotomis-antagonistik. 9 Oleh karenya, semua agama—juga lebih-lebih Islam— yang aturan syari’ahnya begitu menonjol, tidak dapat dibatasi wilayah realitas “normatifitas” nilai-nilai etikanya pada wilayah intelektual-transendental yang steril, kering dan formal, jauh dari realitas kemanusiaan muslim dalam wilayah “das sein” kesejarahan dan kekhalifahannya. Meskipun begitu, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai etika yang fundamental yang dimiliki oleh agama-agama, dapat menjadi benang merah yang dapat menghubungkan pengikut agama yang satu dengan yang lainnya dan sekaligus dapat menjadi modal dasar untuk mencari titik-temu antar pengikut agama yang ada. Dimensi Historitas Keberagamaan Perjalanan epistemologis manusia dalam mencari kepuasan terhadap kebutuhan yang fitri itu sangat tergantung dengan tingkat perkembangan intelektualnya, sehingga bentuk-bentuk agama yang ada (saat itu) demikian sederhananya. Emile Dukheim (1858-1917) salah seorang tokoh sosiologi agama avant garde, mendapatkan bukti sejarah bahwa totem merupakan evolusi paling elementer, sementara ilmuwan lainnya, E.B. Taylor, menjelaskan dalam Primitive Culture, bahwa evolusi agama dimulai dari kepercayaan animisme yang berlanjut pada tahap politeisme dan monoteisme.10 Proses evolusi agama tidak diletakkan dalam alur sejarah yang sama oleh para ahli sosiologi agama. Robert N. Bellah dalam Beyond Belief, membuat diskripsi yang lain bahwa evolusi agama melalui lima tahapan, di mana masing-masing tahapan tersebut mempunyai simbol-simbol dan tindakan sosial yang berbeda. Kelima tahapan tersebut adalah primitive religion, archaic relegion, Ibid, 25. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat dalam Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 18-20. 9 10 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 45 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) historic religion, early modern religion, dan modern religion.11 Dalam bentuk elementernya sekalipun, agama ternyata tidak hanya berfungsi sebagai pijakan keyakinan terhadap realitas yang disebut Rudolf Otto sebagai mysterium tremendum et fascinan.12 Tapi agama juga berperan sebagai sistem pengetahuan rujukan manusia dalam memenuhi kebutuhan kognitifnya, misalnya; problem intelektual yang berhubungan dengan ihwal penciptaan kosmos dengan segala mekanisme sunnatullah; adanya hal-hal yang tidak dapat diterima manusia yang kemudian menimbulkan rasa takut, perasaan frustasi, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Agama yang berada demikian awal dalam sejarah kemanusiaan mengalami proses institusionalisasi sebagai lembaga kepercayaan yang tertua di dunia ini dan menjadi satu-satunya pemberi legitimasi kultural dan struktural masyarakat. Dalam sejarah kekuasaan, agama sering dijadikan legitimasi untuk membangun persepsi politik masyarakat, agar suatu kekeuasan diakui sebagai pengejawantahan dari ilahi, sehingga dianggap tabu melakukan kritik sosial ketika terjadi penyimpangan kekuasaan sekalipun.13 Agama juga menjadi sumber legitimasi sains pada awal sejarah perkembanganya sedian rupa sehingga semua penemuan sains harus mendapatkan pembenaran dari agama. Namun pada perkembangan selanjutnya terjdai konfrontasi antara agama (Nasrani) di satu pihak dengan paradigma sains di pihak lain. Akhirnya agama mengalami degradasi fungsional dalam konteks perkembangan dan revolusi sains. Berawal dari Copernicus memperkenalkan paradigma kosmologi baru sebagai penolakan (dekonstruksi) terhadap paradigma kosmologi Aristoteles (doktrin keagamaan gereja) yang memandang kosmos sebagai statis dan berpusat pada bumi. Penemuan Copernicus mempunyai pandangan sebaliknya, bahwa Ibid. Lihat Joachim Wach, The Comparative Study of Religions, (New York: Columbia University Press, 1958), hlm. 24. 13 C.A. Van Peursen, Pengantar ke Filsafat Ilmu (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 17. 11 12 46a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) alam ini berpusat pada matahari. Ide ini memberi inspirasi bagi ilmuwan berikutnya seperti Tycho, Kepler dan Galileo. Terhadap pandangan ini, gereja terang-terangan menentang dan meminta agar pandangan tersebut dicabut.14 Sketsa historis di atas mencerminkan fluktuasi peran agama dalam rentang waktu sejarah kemanusiaan yang panjang. Berawal dari wibawa agama yang demikian kokoh dalam kehidupan spiritual, mistikal dan kognitif manusia, secara lambat laun namun pasti, agama mulai mengalami reduksionisasi setelah berhadapan dengan dominasi rasionalisme manusia seperti yang ditujukan dengan adanya dominasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia pada zaman modern. Deskripsi fenomena keberagamaan manusia, sebenarnya tidaklah semudah dan sesederhana seperti yang biasa dibayangkan oleh banyak orang. Ada manfaatnya memang untuk sesekali melihat agama dalam bentuknya yang tidak sederhana, lantaran berbagai persoalan pelik yang terkait dengan fenomena itu sendiri. Menunjuk agama dengan sebutan proper noun seperti Islam, Katolik, Proterstan, Hindu, Budha adalah sangat mudah, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar apakah tidak ada bentuk abstrat noun dari segala macam bentuk kepercayaan dan penghayatan agama yang beraneka ragam tersebut? Jika tidak ada bentuk abstract noun sebagai landasan ontologi seuatu kepercayaan, mustahil agaknya manusia dapat menyebut dengan sebutan proper noun terhadap apapun, lantaran abstract noun sebenarnya adalah dasar logika penyebutan proper noun.15 Menurut M. Amin Abdullah, adanya “truth claim” yang sering kali melekat pada sebutan agama-agama dengan proper noun, sangat boleh jadi lantaran tidak atau kurang dikenalinya wilayah abstract noun yang menjadi landasan logis-ontologis bagi keberadaan masing-masing proprer noun. Dari sini pula sebenarnya bermula segala macam kesulitan yang mengitari persoalan. Pluratitas agama-agama yang dipeluk oleh berbagai macam gologan, kelompok dan sekte keagamaan pada level Lihat Syamsul Arifin, et al., Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan. (Yogyakarta; Sipress, 1996). 47. 15 Lihat M. Amin Abdullah, Studi agama…, 24. 14 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 47 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) historis-empiris. Oleh karenanya, jika pendekatan teologi dan normatif dogmatig cenderung untuk menekankan “truth claim” dengam membawa implikasi adanya penyekatan atau pengkotak-kotakan pemahaman teologi pada enclave tertentu, maka pendekatan fenomenologi terbebas dari tuntutan dan implikasi seperti itu. Kaum fenomenolog dapat mengapresiasi dimensi ke dalam pengalaman keberagamaan manusia tanpa perlu terjerat oleh bentuk “formal” kelembagaan agama tertentu seperti yang ditekankan oleh para teolog dan agamawan pada umumnya. Para fenomenolog mencari “essence”, “Form”, “archetype”, dimensi universalitas dari pengalaman keberagamaan manusia.16 Ketika para teolog dengan truth claim yang disandangnya telah kehingan tempat berpijak yang paling kokoh untuk melakukan dialog dengan sesama penganut agama-agama yang lain, metode dan cara bepikir fenomenologis dapat membantu dan memberi sumbangan yang cukup berharga untuk menunjukkan kembali di mana sebenarnya mereka perlu berpijak untuk dapat berjumpa dan bekerja sama dengan penganut agama-agama lainnya. Dengan begitu fenomenologi lebih menekankan segi-segi “persamaan” dan bukannya segi-segi “perbedaan” seperti yang ditekankan oleh para teolog. Berangkat dari pernyataan di atas, Seandainya di terima faham yang menyatakan: kebenaran agama adalah apa yang ditemukan manusia dari pemahaman kitab sucinya sehingga kebenaran agama dapat beragam dan bahwa Tuhan merestui perbedaan cara keberagamaan ummatnya, atau apa yang dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah tanawu’ al-ibadah, niscaya tidak akan timbul kelompok-kelompok yang saling mengklaim bahwa dirinya paling benar.17 Sejarah pada masa silam telah merekam bahwa dua agama besar—Kristen dan Islam—pernah hidup berdampingan dengan serasi dan harmonis, kendatipun terdapat perbedaan anutan antara mereka. Ketika kerajaan Bizantium yang beragama Ibid, 36. Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung; Mizan, 1997), hlm. 217. 16 17 48a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) Kristen kalah dalam peperangan melawan kerajaan Persia yang menyembah api, kaum muslimin bersedih karena kekalahan itu, al-Qur’an turun menggembirakan mereka dengan pernyataan bahwa setelah sembilan tahun, Romawi akan menang dan ketika itu kaum muslimin akan bergembira.18 Walaupun diakui bahwa dalam sejarah agama-agama telah terjadi pertikaian antar pemeluk agama yang sesama atau antar pemeluk berbagai agama, namun pertikaian tersebut lebih banyak disebabkan oleh kepentingan-kepentingan non-agama. Dapatkah ummat masa kini, menemukan pandangan dan jalanyang telah ditetapkan oleh generasi terdahulu yang hidup berdampingan dan harmonis itu? Kalau jalan tersebut tidak dapat ditemukan oleh pemimpin-pemimpin agama sendiri, maka ketika itu, mereka harus membenarkan pandangan yang menyatakan bahwa krisis agama, karena dengan demikian, agama telah menjadi sumber keresahan pemeluknya dan jangan heran, bila agama hanya akan tinggal sebagai kenangan buruk sejarah. Pemikiran Pluralisme Keagamaan dan Teologi Agama-Agama Pluralisme keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadap agama-agama dunia dewasa ini, meskipun dalam arti tertentu pluralisme keagamaan selalu ada bersama kita. Setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhdap pluralisme tersebut. Ketegangan kreatif yang ditimbulkan pluralisme sering menjadi katalisator bagi wawasan baru dan perkembangan agama. Misalkan, wahu Allah melalui Muhammad tampil ditengah-tengah keanekaragaman masyarakat Mekkah yang terdiri dari orang Yahudi, orang Kristen, pengikut Zoroaster dan lain-lain. Di tengah-tengah penyembahan para dewa setempat yang beranekaragam Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan Musa. Tantangan dari Gnostisisme dan filsafat Yunani membantu orang Kriten purba mengenal keterpisahannya dari agama Yahudi.19 Pernyataan ini terbukti kebenarannya pada tahun 625. Catatan histories ini disebut dalam al-Qur’an dalam awal-awal surat ar-Rum. 19 Lihat Harold Coward, Pluralism, Challenge to World Religions. 18 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 49 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) Berteologi dalam konteks agama-agama mempynyai tujuan tuntuk memasuki dialog antaragam, dan dengan demikian mencoba memahami cara baru yang mendalam mengenai agaimana Tuhan mempnyai jalan penyelamat. Pengalaman ini penting untuk memperkaya pengalaman antariman, sebagai pintu masuk ke dalam dialog teologis.20 Dewasa ini, di saat antargama semakin intens dan akrab mengadakan pertemuan-pertemuan agama-agama, justru pada level teologis—yang merupakan dasar agama itu—muncul kebinguan-kebingungan, khususnya menyangkut bagaimana kita harus mendefinisikan diri di tengah-tengah agama lain yang juga eksis, dan punya keabsahan. Dalam persoalan ini didiskusikan apakah ada kebenaran dalam agama lain—implikasinya adalah apakah ada keselamatan dalam agama lain?21 Hugh Goddard, seorang Kritiani, ahli teolog Islam di Nottingham University, Inggris menulis bahwa dalam seluruh sejarah hubungan Kritiani-Islam: apa yang telah membuat hubungan itu berkembang menjadi kesalahpahaman—bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman di antara keduanya—bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman di antara keduanya—adlah suatu kondisi adanya “standar ganda’ (double standards). Maksudnya orang-orang Kristiani maupun Islam selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya, yang biasanya standar yang bersifat ideal dan normatif untuk agama sendiri, sedangkan terhadap agama lain, memakai standar lain, yang lebih bersifat realistis dan historis. Melalui standard ganda inilah, muncul prasangka-prasangka (prejudices) teologis, yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antarumat beragama. Anggapan ada tidaknya keselamatan dalam agama lain sering kali ditentukan oleh pandangan mengenai standar ganda ini.22 (terj.Pluralisme; Tantangan bagi Agama-agama), (Yogya: Kanisius, 1989), hlm. 167-168. 20 Budhy Munawar-Rachman, Islam Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 32. 21 Ibid,33. 22 Lihat uraian lengkapnya dalam karya, Hugh Goddard, Christians & Muslim: From Double Standards to Mutual Understanding, (Nottingham: 50a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) Akan tetapi, justru dalam persoalan teologi standar yang menimbulkan persoalan truth claim adalah standar: bahwa agama kita adalah agama yang paling sejati berasal dari Tuhan, sedangkan agama yang lain adalah konstruksi dari manusia atau mungkin juga berasal dari Tuhan akan tetapi telah dirusak dan dipalsukan oleh ulah manusia. Lewat standar ganda inilah bermunculnya perang klaim-klaim kebenaran dan janji keselamatan yang kadang berlebihan dari satu agama atas agama yang lain. Sebuah buku mengenai “Ahli Kitab” misalnya menggambarkan standar ganda ini, dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur’an. “Dan diantara orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani”, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Maidah; 14)... Ayat di atas bernada sumbang, dan berisi kecaman terhdap orang-orang Nasrani yang melupakan jinji mereka kepda Allah. Al-Qur’an mengecam mereka karena sikap dan perilaku mereka yang mengubah kitab sucinya. (Q.S. Al-Maidah; 13). Bahkan lebih fatal lagi, yaitu aqidah tawhid yang menjadi inti ajaran para nabi dan rasul. Ajaran tawhid tersebut mereka ubah menjadi konsep trinitas, (Q.S. Al-Maidah; 73), dengan mengkultuskan Nabi Isa as dan mengangkatnya menjadi Anak Allah (Q.S. at-Taubah;3). Dalam posisi ini Nabi Isa a.s. kemudian dijadikan sebagai salah satu unsur Tuhan (Q.S. Al-Maidah; 72).”23 Dalam klaim-klaim kebenaran ini, kajian sosiologi agama sering memperlihatkan bahwa religion’s way of knowing ini bisa mengalami pengerasan sedemian rupa, sehingga fenomena yang terjadi adalah: satu agama menjadi ancaman bagai agama lain. Di sini ketika persoalannya bercampur dengan politik, logikanya pun menjadi, “siapa yang kebetulah berkuasa, dialah yang akan mendominasi yang lian.” Dan di sinilah kita bisa melihat, Nottingham University Press). 23 Lihat Muhammad Galib, Ahl al-Kitab, Makna dan Cakupannya (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 59. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 51 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) seringkali rumusan-rumusan teologis terbetuk berdasarkan suatu real politik tertentu.24 Apa yang perlu diambil hikmah dari adanya klaim-klaim kebenaran adalah kebutuhan untuk lebih memperjelas apa yang disebut the meaning and the purpose of life (makna dan tujuan hidup) manusia itu—yang dalam agama terbungkus dalam segisegi spiritualnya—yang ternyata dari sudut pandang perennial philosophy, menjadi alasan mengapa diturunkannya sebuah agama. Setiap agama mempunyai cerita besar dalam menjelaskan nasib keberadaan manusia: terutama mengenai keselamatan, kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia ini, dan setelah di dunia ini. Dan untuk mengerti sumbangan agama-agama kepada masalah manusia modern dewasa ini, penjelasan inklusivisme keagamaan perlu dikembangkan supaya lebih pluralis, dan itu berarti perlunya meletakkan agama-agama lain dalam kedudukan yang sederajat dengan agama sendiri. Inilah usaha-usaha mutakhir yang sedang dijalankan para pendukung dialog agama-agama.25 Dari Kritik Teks Menuju Relativitas Kebenaran Agama Sistem baca yang basah dan kreatif dengan membongkar makna kebenaran yang tidak diungkap dalam teks mengundang pertanyaan tentang makna suatu hakikat atau kebenaran. Karena, kebenaran atau hakikat itu ada dan diserap hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam bentuk teks-teks itu yang ternyata menutupi hakikat atau kebenaran lain yang tidak diungkap dalam teks itu. Dari sinilah kritik kebenaran muncul. Menurut Ali Harb, berangkat dari kritik teks (naqd al-nash) selanjutnya menuju ke arah Kritik kebenaran (naqd al-haqiqah), dan mengarah ke ‘kebenaran agama.’ Kebenaran yang selama ini diakui oleh agama-agama sebagimana diatur dalam teks-teks keagamaannya. Dalam kritik kebenaran agama (naqd al-haqiqah ad-diny), kita harus mengritik agama sendiri sebelum mengritik agama lain.26 Budhy Munawar-Rahman, Islam Pluralis, 36. Ibid, 41. 26 Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat Ali Harb, Naql al-Haqiqah 24 25 52a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) Kebenaran itu tidak tetap tetapi terwujud dalam bentuk kesementaraan, partikular, dan dalam proses yang panjang. Kebenaran akan menjadi kebenaran minimal dari apa yang seharusnya “benar” pada batas, pada waktu, dan wilayah kebenaran yang bersifat universal. Sehingga, pada akhirnya kebenaran ada pada ungkapan; “tidak ada sesuatu pun yang dapat dibenarkan atau dipersalahkan. Kita, misalnya, tidak bisa menilai bahwa Barat itu baik dan benar secara universal, dengan menilai Timur itu salah dan jelek secara universal pula”. Kebenaran sering menjadi suatu bentuk pengklaiman dari berbagai pihak secara subyektif dan menjadi konsep tunggal dan sederhana atau teologis metafisik yang sangat jauh dari wilayah penelitian dan pemikiran. Kebenaran sendiri merupakan wacana irrasional yang “diam”. Menurut Harb, kita selayaknya mengritik konsep kebenaran kita sendiri, karena kebenaran bukan hanya kemenangan kebenaran atas kebatilan, kebenaran atas kesalahan, atau antara petunjuk dengan kesesatan yang dibenturkan pada aspek ilmu pengetahuan,otoritas dan kesenangan. Sejarah kebenaran bukanlah kemenangan rasio atas prasangka. Dan solusi untuk menjembatani adalah diadakannya dialog antara konsep yang bertentangan, antara agama-agama yang saling bertentangan dalam dimensi eksoteriknya (syariah adalah dimensi eksoterik Islam sementara dimensi esoterisnya di isi tasawuf).27 Dalam dialog yang hakiki, terdapat kriteria saling memahami satu sama lain untuk memberi dan menerima. Tidak ada sikap saling memberi dan menerima tanpa sikap saling pengertian atau pengakuan akan hak-hak untuk berbeda. Hal ini dapat membawa kita merubah pemahaman tentang kebenaran dimana kebenaran tidak lagi dipikirkan sebagai esensi yang stasis, kekal, transenden dan mendahului realitas, melainkan sesuatu yang partikular dan bisa ditemukan di mana saja. Artinya, kita akan menangkap dan memahami kebenaran sebagai eksistensi yang berbeda stereotipe dan penampakannya, atau sebagai peristiwa yang bermacam-macam pembacaan dan (Kritik Kebenaran), terj. Sunarwoto Dema, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 45. 27 Bandingkan Ali Harb, Naql an-Nash (Kritik Nalar al-Qur’an), terj. M. Faishal Fatawi, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 24. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 53 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) bentuk-bentuk penangkapannya, atau sebagai teks yang jelas penafsiran, interpretasi dan metode penelitiannya. Maka kebenaran akan sangat mungkin hanya bisa menjadi sistem eksperimen atau proses untuk menjelaskan sesuatu sebagai pedoman prinsip, sistem aksioma, kerangka acuan untuk melihat sesuatu dan atau sebagai dasar pemikiran untuk meneliti. Sehingga apa yang paling bisa dan yang paling mungkin kita lakukan adalah menjadi saksi atas kebenaran itu sendiri.28 Dari sini tampak sekali bahwa dalam membaca kecenderungan klaim kebenaran absolut terhadap agama, dapat dilihat dari teori Psikoanalisa Freud (Id, Ego, Superego) yang memiliki kecocokan dengan konsep jiwa dalam Al-Qur’an (an nafs al amarah, an nafs al muthmainnah, dan an nafs al lawwamah). Id merupakan sumber seluruh instink, keinginan, kesesatan tidak mengakui larangan dan pemikiran. Superego merupakan esensi persoalan moral (kemanusiaan, peradaban, kemasyarakatan, dan otorisasi). Ego membentuk prinsip keharmonisan dan keseimbangan dalam kahidupan seseorang dan penyeimbang antara paham pragmatisme (id) dan paham realisme (superego). Maka tidak ada unsur kerelaan dalam pribadinya bila ia tidak berusaha untuk menyempurnakan dirinya, bagaimana menjadi diri yang baik. Analogi terhadap an-Nafsu al-Amarah dengan id (di antara karakter id adalah perilaku agresif) untuk membaca kecenderungan seseorang membenarkan dirinya sendiri. Artinya jika Id mengalahkan Ego maka akan menimbulkan “brutalisme” atau “terorisme”.29 Fenomena demikian itulah yang seringkali diperlihatkan oleh umat beragama dengan bentuk klaim-klaim kebenaran atas agamanya yang dalam studium lanjut riskan mengarah pada konflik. Ketika sampai pada wilayah ini, maka substansi agama akan hilang. Kebenaran agama-agama itu tidak akan ada gunanya. Mungkin yang agak menarik di sini adalah kesadaran bahwa tidak mungkin berhasil mengadakan dialog agama-agama tanpa terlebih dahulu diadakan dekonstruksi terhadap teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, yang penting bagi kita sekarang adalah melatih 28 29 54a Ibid, 23. Ali Harb, Naqd al-Haqiqah…, hlm. 47. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) dan mengoptimalkan rasio supaya produktif guna menghasilkan ilmu dan pengetahuan, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya realitas dan rekonstruksinya. Pun ada yang berusaha untuk menggali relevansi antara pemikiran dan gagasannya dengan khazanah keilmuan lama disaat keterbukaan terhadap seluruh sumber keilmuan dan hasil budaya, baik yang lama dan kuno maupun yang baru dan modern walaupun bertentangan dan berlawanan. Tradisi dengan teks dan simbolnya telah menciptakan suatu subyektifitas dan bentuk identitas budaya bagi kelompok masyarakat. Wallahu a’lam.*** Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 55 Relativitas Ajaran Agama (oleh: Ahmad Atabik) DAFTAR PUSTAKA M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historitas? (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996). Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996) Ronald E. Santoni (edt.), Religious Language and The Problem of Religious Knowledge (London: Indiana University Press, 1968). Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan, 1995). Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, (New York: Oxford University Press, 1996). Joachim Wach, The Comparative Study of Religions (New York: Columbia University Press, 1958). C.A. Van Peursen, Pengantar ke Filsafat Ilmu (Jakarta: Sinar Harapan, 1987). Syamsul Arifin, et al., Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan. (Yogyakarta; Sipress, 1996). M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung; Mizan, 1997), hlm. 217. Harold Coward, Pluralism, Challenge to World Religions. (terj. Pluralisme; Tantangan bagi Agama-agama), (Yogya: Kanisius, 1989), hlm. 167-168. Budhy Munawar-Rachman, Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum beriman, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001). Hugh Goddard, Christians & Muslim: From Double Standards to Mutual Understanding, (Nottingham: Nottingham University Press). Muhammad Galib, Ahl al-Kitab, Makna dan Cakupannya (Jakarta: Paramadina, 1998). Ali Harb, Naql al-Haqiqah (Kritik Kebenaran), terj. Sunarwoto Dema, (Yogyakarta: LKiS, 2004). -----------, Naql an-Nash (Kritik Nalar al-Qur’an), terj. M. Faishal Fatawi, (Yogyakarta: LKis, 2003). 56a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 AMBIVALENSI KOTA DEMOKRASI DALAM FILSAFAT POLITIK AL FARABI STUDI KRITIS MADINAH AL FADHILAH AL FARABI Mohammad Yasin Mahasiswa Program Islamic Philosophy Pasca Sarjana IC-London in Corporation with Universitas Paramadina Jakarta Email: [email protected] ABSTRACT It is fashionable nowadays to be democratic; prompted by the desire to portray Islam as a modern ideology and a progressive government system, they have interpreted Islamic political and juridical theory in democratic terms. In short, some people assumed that democracy is the only good government system. But, in few centuries ago, al-Faraby criticized democracy as a bad government system. Al Farabi said democracy is a good system between bad systems, he proposed “the prime city (Madinah alFadlilah)” system. The prime city is the post democracy system, giving direction to the people to achieve ‘highest happiness’. But in other hand Al Farabi said that democracy possible to grow up men of excellent, more civilized, more populated, more productive and more perfect. It is also possible to glean from it certain parts of the virtuous city. Thus it may include philosophers, rhetoricians, and poets dealing with all kinds of things. Al Farabi seems to tell us that democracy is the most favourable for the founding of a Virtuous city. Al Farabi never tell us how the virtuous city may arise from the city of pigs; but Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 57 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) he tells us how we may glean the various city from democracy. Al Farabi mentioned that democracy is bad system, but he also said that a virtuous city can rise from democracy city. According to me, Al Farabi inconsistent on his theory of democracy and it open to be criticized. This article will explain the Al Farabi’s theory of democracy deeply and criticize it. Keywords: Democracy, City, State, and Madinah-al-Fadhilah, Pendahuluan Topik tentang demokrasi merupakan tema yang penting didiskusikan, terlebih di semua Negara telah mengklaim bahwa negaranya adalah Negara demokratis. Tidak terkecuali negaranegara berkembang di belahan Asia terutama Negara-Negara Muslim yang gencar menyuarakan bahwa Islam sebagai ideologi modern dan menganut paham progresif lewat para pemikir Muslim yang berlomba menafsirkan kembali teori politik dan paham keagamaan Islam ke dalam istilah-istilah demokrasi. Padahal konsep tentang demokrasi pada beberapa abad silam telah menuai kritik pedas dari seorang Filosof politik Muslim bernama Al Farabi. Al-Farabi mengkritik sistem pemerintahan demokrasi dan meletakkan sistem demokrasi termasuk kategori Negara jahiliyah, demokrasi hanya terbaik diantara sistem-sistem pemerintahan jahiliyah yang ada. Al Farabi kemudian mengusulkan madinah al fadhilah atau kota utama sebagai sistem pemerintahan terbaik. Gagasan Al Farabi ini sebagaimana dtuangkan dalam karya-karya penting filsafat politiknya di antaranya, Al Siyasah Al Madaniyah, dan Mabadi Ara Ahlu Al Madinah Al Fadhilah.1 Penulis sangat tertarik dengan konsep Negara demokrasi Al Farabi dan mencoba melakukan analisis secara kritis terhadap bangunan teori politik Al Farabi terutama yang berkaitan dengan tema demokrasi. Apalagi Al Farabi meletakkan demokrasi sebagai Negara jahiliyah. Sementara faktanya saat ini demokrasi dengan segala perkembangannya telah menyita perhatian dunia dan H zainal Abidin Ahmad, Negara utama; Madinatul Fadhilah (Jakarta: PT. Kinta, 1968), hal. 41-43. 1 58a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) bahkan memungkinkan menjadi sistem Negara yang paling baik. Saat ini Negara-Negara saling klaim bahwa negaranya sebagai Negara demokrasi seperti Negara-Negara di belahan Barat Eropa dan Amerika Utara, Negara-Negara berkambang, dan terbaru adalah Negara-Negara di Timur Tengah. Biografi Singkat Al Farabi Al Farabi tidak menuliskan riwayat hidupnya, dan tidak ada seseorang di antara para pengikutnya yang merekam kehidupannya. Biografi al-Farabi secara lebih panjang dipaparkan oleh biographer Ibn Khallikan dalam karyanya Wafayat al A’yan,.2 Paling tidak kehidupan al Farabi dapat dipaparkan menjadi dua periode, pertama, kehidupannya sejak lahir hingga berusia lima puluh tahun, masa ini adalah masa dimana al Farabi memulai karir intelektualnya. Kedua, masa tua kehidupan al-Farabi yaitu saat al Farabi berumur lima puluh tahun, pada masa ini al Farabi telah mengalami kematangan dan membentuk karakteristik filsafatnya. Al Farabi bernama lengkap Abu Nashr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn al-Uzlagh al Farabi lahir di Wasij di Distrik Farab (yang juga dikenal dengan nama Utrar) di Transoxiana (sekarang Uzbekistan), pada tahun (257 H / 870 M.), dan wafat di Damaskus pada tahun (337 H/950 M.)3 Dalam sumber-sumber Islam dia lebih akrab dikenal dengan Abu Nashr, wakil terkemuka kedua dari madzhab filsafat paripatetik (masy sya’i) muslim setelah al-Kindi (185-260 H. / 801-873 M).4 Sementara dalam teks-teks latin di abad pertengahan, al Farabi dikenal dengan nama al-Pharabius atau Avennasr.5 Sebutan al Farabi sendiri diambil dari kata tempat di mana dia dilahirkan, yaitu Farab.6 Dalam karir intelektualnya al Farabi tidak hanya Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>” dalam M. M. Sharif (ed.), A History of Muslim Philosophy, Vol. I (Delhi: Low Price Publication, 1961), hlm. 450. 3 Yamani, Filsafat Politik Islam; Antara dan Khomeini (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 51. 4 Osman Bakar, Hierarki Ilmu; Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu, terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 26. 5 M. Nastsir Arsyad, Ilmuan Muslim Sepanjang Sejarah (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 98. 6 Farab disebut juga dengan Utrar, dahulu termasuk wilayah Iran, 2 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 59 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) mendapat gelar sebagai komentator Aristoteles, tetapi juga bergelar sebagai mu’alim al-tsa>ni (guru kedua).7 Para biographer seperti Said Ibn Said (w. 1070 M.), Ibn al-Nadim (w. 990) dan Abi Usaibah mengungkapkan bahwa ayah al Farabi adalah penduduk asli Iran yang menikah dengan seorang wanita dari Turkestan, ayahnya adalah seorang perwira di Turkestan.8 Beberapa sumber menyebutkan bahwa ayah al Farabi adalah seorang opsir tentara keturunan Persia, namun keluarganya dianggap sebagai orang Turki.9 Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi militer di kalangan dinas ketentaraan Dinasti Samaniyah yang menguasai sebagian besar wilayah Transoxiana, propinsi yang memperoleh kekuasaan otonom dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah sejak tahun 260 H/ 874-999 M.10 Uraian di atas membuktikan bahwa latar belakang keluarga al Farabi adalah sebagai seorang keturunan bangsawan yang terhormat dan memiliki kekayaan. Maka bisa dipastikan bahwa kehidupan al Farabi memiliki kemudahan fasilitas untuk memenuhi apa yang diinginkan dalam kehidupannya. Masa kecil dan remaja al Farabi dijalani di kota dimana dia dilahirkan yaitu Farab, sebuah kota yang sebagian penduduknya mengikuti madzhab Syafi’i, dari situ al Farabi belajar berbagai ilmu tentang bahasa termasuk juga aritmatika dan ilmu tentang al-Qur’an.11 Selanjutnya al Farabi pindah ke Damaskus dan kemudian pindah ke Baghdad yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan akan tetapi sekarang menjadi bagian dari Republuk Uzbekistan dalam daerah Turkestan Rusia. Lihat Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 81. 7 M. Saeed Sheikh, Studies in Muslim Philosophy (India: Adam Publisher, 1994), hlm. 75. 8 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, hlm. 81. Lihat Juga Majid Fakhry, Al-Fa>ra>bi> Founder of Islamic Neo Platonism: His Life, Work and Influence (Oxford: Oneworld, 2002), hlm. 6. 9 Bukan hanya karena mereka berbicara dalam bahasa Sogdia, sebuah dialek Turki, tetapi karena gaya hidup dan kebiasaan kultural mereka mirip orang Turki. Lihat. Osman Bakar, Hierarki Ilmu: Membangun Kerangka, hlm. 26. 10Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya II (Jakarta: UI-Press, 2002), hlm. 44. Lihat Juga Yamani, Filsafat Politik Islam, hlm. 51. 11 M M. Syarif, Para Filosof Muslim Terj. Tim Penerjemah Mizan (Bandung: Mizan, 1996), hlm 56. 60a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) dan pusat pemerintahan. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Baghdad al Farabi pindah ke Harran salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil, dan tidak lama kemudian dia kembali ke Baghdad dan tinggal di Baghdad selama 30 tahun. Masa tua al Farabi dijalani di Damsyik, setelah puluhan tahun tinggal di kota Baghdad, al Farabi meninggal di Damsyik pada tahun 330 H./ 941 M.12 Latar belakang keluarga al Farabi bahwa dia adalah anak seorang militer sangatlah penting dalam kaitannya mengenai karier intelektual yang dibangunnya. Karena di era al Farabi tentara khalifah terutama terdiri dari pasukan-pasukan Turki, melalui hubungan keluarga militer al Farabi membangun akses hubungan dengan para sekretaris negara dan wazir di Baghdad yang menjadi patron filsafat. Risalah besar al Farabi mengenai musik, misalnya, ditulis atas permintaan wazir Abu Ja’far alKharkhi.13 Ibrahim Madzkour mengungkapkan bahwa basis pendidikan dasar al Farabi adalah di bidang ilmu-ilmu religius dan bahasa. Pada bidang ilmu-ilmu religius dia belajar tentang fiqih, hadis, al-Qur’an dan tafsir, sementara pada wilayah bahasa dia belajar bahasa Arab, Persia dan Turki,14 selain itu dia juga belajar aritmatika dasar.15 Apa yang dipelajarinya dari tingkat dasar, baik di bawah bimbingan guru privat di rumahnya maupun dalam pertemuan-pertemuan formal di masjid tidak jauh berbeda dengan kurikulum tradisional yang diberikan pada anak-anak muslim sebayanya.16 Bahwa basis pendidikan dasarnya adalah keilmuan yang bersifat religius diperkuat oleh pernyataan Ibn Khaldun, berdasarkan kajiannya terhadap berbagai metode pendidikan anak yang digunakan di kota-kota Muslim, menyebutkan, bahwa kurikulum di kawasan Timur Islam bersifat campuran, ilmu-ilmu religius dan bahasa menjadi kurikulum pengajarannya. Sementara Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, hlm. 81. Lihat Juga Majid Fakhry, Al-Fa>ra>bi> Founder of Islamic, hlm. 7. 13 Yamani, Filsafat Politik Islam, hlm. 52. 14 Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 451. 15 Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 28. 16 Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 27-28. 12 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 61 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) bahwa telah banyak belajar tentang kesusastraan dan ilmu bahasa diperkuat oleh para sejarawan, yang memiliki laporan bahwa menjelang akhir hayatnya telah mengenal banyak bahasa seperti Arab, Turki, Persia, Syria, Yunani dan juga menguasai berbagai dialek bahasa Asia Tengah serta bahasa-bahasa lokal.17 Fase kedua pendidikan al Farabi adalah di Bukhara setelah di Farab, di Bukhara al Farabi mengembangkan keilmuannya di berbagai disiplin termasuk di bidang musik.18 Setelah mendapatkan pendidikan awalnya, terutama studi ilmu-ilmu religiusnya, al Farabi kemudian menjadi seorang hakim (qadhi), dan selanjutnya pergi ke Merv / Marw Khurasan (sekarang Iran). Kemudian al farabi ke Baghdad dan bertemu dengan seorang ahli logika terkemuka di masa itu yaitu Yuhanna Ibn Hailan (w. 910 M) dan Abu Bisyr Matta (w. 940 M) seorang penerjemah karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Kepada merekalah dia belajar tentang logika dan sejak itu pula ia meninggalkan pekerjaannya sebagai al-qadhi (hakim) dan mulai sibuk dan tenggelam mempelajari ilmu-ilmu di bidang tersebut.19 bidang logika al Farabi telah mampu menjelaskan sesuatu yang rumit dan mengungkap rahasianya serta memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang telah ditinggalkan oleh al-Kindi lewat metode dan analisisnya.20 Kota Baghdad, saat al Farabi menggali ilmu di sana, menjadi kota yang dianggap sebagai pemilik ahli waris utama tradisi filsafat dan kedokteran Alexandria. Salah satu sumbangan terpenting al Farabi pada dunia intelektual Baghdad adalah ia bersama para guru logikanya membentuk salah satu rantai paling awal antara filsafat Yunani dengan dunia Islam.21 Pada masa kekhalifahan al-Mu’tadid (892902 M.) al Farabi dan Yuhanna Ibn Hailan (gurunya) telah mampu Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 29. Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 29. 19 Minat al-Fa>ra>bi> terhadap filsafat terutama ilmu logika sebenarnya sudah sejak dia tinggal di Bukhara, kalau kemudian dia mengalihkan perhatiannya dari mempelajari bidang filsafat tidak lebih karena masih langkanya pengajar di bidang ini. Lihat Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 30. 20 Majid Fakhry, Al-Fa>ra>bi> Founder of Islamic Neo Platonism, hlm. 6-7. 21 Deborah L. Black, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 221. 17 18 62a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) menyumbangkan dalam penempaan sebuah bahasa filsafat baru dalam bahasa Arab, meskipun dia juga menyadari akan perbedaan antara tata bahasa Yunani dan Arab.22 Minat al Farabi pada logika dan ilmu-ilmu yang bernuansa filosofis, termasuk metafisika muncul sejak pertama kali dia mempelajari dalam disiplin ilmu linguistik dan religius.23 Tepatnya di kota Marv (Marw) di Khurasan tempat pertama kalinya al Farabi berkenalan dengan logika dan ilmu-ilmu filsafat, terutama logika Aristoteles.24 Namun, pengetahuannya mengenai logika Aristotelian baru sebatas unsur-unsur yang diterima atau yang dikritik oleh disiplin kalam. Dari sini, al Farabi mengalami ketidakpuasan, kemudian al Farabi mengembangkannya di Baghdad dengan berguru kepada Yuhanna Ibn Hailan dan Abu Bisyr Matta. Di Baghdad dan Harran dia belajar hanya melanjutkan studinya terdahulu untuk menguasai beberapa penerapan tentang logika, dan di Baghdad dia telah menguasai pemikiran Aristoteles dengan mempelajari karya Analitics Posateriora bersama Ibn Hailan. Pada masa Khalifah al-Muqtadir (908-932 M.) al Farabi pindah dari Baghdad menuju Konstantinopel, besar kemungkinan karena pengaruh pemikiran Ibn Hailan, kepindahannya ke konstantinopel Yunani, dimana Konstantinopel pada masa itu menjadi salah satu madzhab filsafat yang erat kaitannya dengan madzhab Alexandria. Di Universitas Konstantinopel al Farabi mempelajari seluruh silabus filosofis dan ilmu-ilmu lain, selama Yamani, Filsafat Politik Islam, hlm. 55. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Osman Bakar bahwa sebelum masanya kalam maupun Ushul Fiqih telah berkembang hingga pemakaian sistem logika yang menampilkan banyak unsur dan gambaran umum logika Stoik. Dimana logika Yurisprudensial-teologis yang dikenal dengan adab alkalam telah ditunjukkan oleh Makdisi sebagai bagian integral dari kurikulum ilmu-ilmu religius sebelum dan selama masa . Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 30. 24 Jawaban atas pertanyaan di mana pertama kalinya mulai berkenalan dengan studi logika Aristotelian dan filsafat menjadi perdebatan para sarjana modern. Namun Walzer dan Mahdi menyebut kota Marv (Marw) di Khurasan sebagai tempat dimana berkenalan dengan filsafat dan logika Aristotelian, sementara Majid Fakhry, F.E. Peters, De Boer dan F.W. Zimermann bertempat di Baghdad. Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 31. 22 23 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 63 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) delapan tahun.25 Rentang waktu tahun (910-920 M.) al Farabi kembali ke Baghdad mendalami filsafat, sesudah menguasai ilmu logika serta mengajar dan menulis dan mengulas karya-karya filsafat. Pada masa itu tercatat bahwa Matta’ Ibn Yunus, al-Mawarzi dan Quwairi adalah para ahli logika terkemuka, yang begitu berpengaruh terhadap murid-muridnya, al Farabi juga menjadi salah satu muridnya. Pada masa itu kemampuan al Farabi dalam mengungkap bahasa-bahasa yang dianggap sangat rumit dengan istilah-istilah yang mudah dicerna dan dipahami menaikkan reputasinya. Tercatat bahwa sebagai ahli logika di masanya al Farabi telah membaca (juga mengajar) Physic-nya Aristoteles sebanyak empat puluh kali dan Rhetoric-nya Aristoteles dua ratus kali serta telah membaca bukunya De Anima-nya Aristoteles sebanyak seratus kali.26 Pada akhir tahun 942 M karena gejolak politik Baghdad yang semakin memburuk al Farabi pindah ke kota Damaskus, di bawah kekuasaan Dinasti Ikhsyidiyah, Damaskus pada masa itu menjadi kota yang tenang dan damai. Pada masa awal tinggal di Damaskus diterangkan bahwa al Farabi bekerja sebagai penjaga kebun sepanjang siang hari dan mencurahkan waktu untuk menulis dan membaca buku-buku filsafat di siang harinya.27 Menurut Abi Usaibiah di Damaskus al Farabi menyelesaikan karyanya A>ra>>’ Ahl al-Madi>>nah al-Fa>dhilah yang sebelumnya telah mulai ditulis di Baghdad. Karena alasan yang sama, al Farabi pindah ke Mesir setelah dua tahun tinggal di kota Damaskus, yaitu karena terjadinya ketegangan politik antara dinasti Hamdaniyyah dari Mosul dan Ikhsyidiyah dari Siria, sehingga memaksa kota Damaskus pada masa itu diduduki dinasti Hamdaniyyah selama periode 945-946. Di mana mesir pada masa itu dibawah kekuasaan Ikhsidiyyah, dan menurut Ibn Khallikhan di Mesir al Farabi menyelesaikan Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 34. Yamani, Filsafat Politik Islam, hlm. 55. 27 Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 36. Lihat juga Majid Fakhry, AlFa>ra>bi> Founder of Islamic Neo Platonism, hlm. 7. 25 26 64a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) karyanya yang berjudul Siyasah al-Madaniyah yang semula telah mulai ditulis di Baghdad. Pada tahun 949 M al Farabi kembali ke Damaskus, al Farabi kemudian berjumpa dengan putra mahkota dinasti Hamdaniyah Saif al-Daulah sang penyokong besar seni dan kesusastraan di Aleppo. Di sinilah al Farabi bertemu dengan lingkaran orangorang terpelajar yang dikumpulkan oleh Saif al-Daulah seperti al-Mutanabbi, Abu Firas, Abu al-Fajar dan ahli tata bahasa Ibn Khalawaih. Saif al-Daulah sangat menghormati al Farabi karena kecerdasan dan keahliannya menguasai berbagai pengetahuan, juga karena sikap al Farabi yang sangat sederhana baik dalam hal pakaian maupun tingkah lakunya, bahkan dia hanya menerima pensiunan harian sebesar empat dirham meskipun dia menjadi penasehat negara.28 Pada bulan Rajab 339 H/ Desember 950 M, al Farabi meninggal dunia di Damaskus pada usia delapan puluh tahun. Dia dimakamkan di pekuburan yang terletak di luar gerbang kecil kota bagian selatan.29 Dari uraian panjang mengenai latar belakang pendidikan dan kehidupan ilmiahnya, tidak dapat diragukan bahwa al Farabi mempunyai pengetahuan yang luas, bahkan dia hampir dapat menguasai segala macam ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa hidupnya, sehingga tidak ada keraguan sama sekali bagi kita bahwa al Farabi memahami sepenuhnya filsafat Yunani.30 Al Farabi hidup pada periode kedua masa pemerintahan Abbasiyyah: suatu masa di mana dari sisi politik, Khalifahkhalifah yang memerintah di Baghdad tidak lagi kuat seperti sebelumnya, sehingga mereka tidak kuasa melawan kehendak para perwira pengawal keturunan Turki, dan dari sisi intelektual dan ideologi ditandai dengan munculnya kembali pengaruh ajaran Salaf menyusul memudarnya aliran Mu’tazilah. Menurut Khudhari periode kedua Bani Abbas ini merentang dari tahun 874 M, masa ke Khalifahan al-Mutawakkil, sampai tahun 945 M, Majid Fakhry, Al-Fa>ra>bi> Founder of Islamic Neo Platonism, hlm. 7. Lihat juga Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 37. 29 Osman Bakar, Hierarki Ilmu, hlm. 37. 30 Ahmad Fuad al-Ahwani, Filsafat Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 60. 28 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 65 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) masa kekuasaan al-Mustakhfi.31 Periode kedua masa pemerintahan Abbasiyyah biasa juga disebut dengan periode akhir Abbasiyyah, dimana kekuasaan para khalifah mengalami kemunduran, sedangkan yang berkuasa sesungguhnya adalah Dinasti-dinasti baru yang sebagian besar berasal dari Turki dan Persia yang berada di batas luar pemerintahan. Namun, pada puncaknya justru Dinasti-dinasti baru itu yang menguasai Baghdad sementara khalifah hanya menjadi boneka di tangan mereka.32 Al Farabi hidup pada masa terjadinya pergolakan dan pergeseran arus pemikiran di Baghdad, yaitu: pertama, rasionalisme kalam Mu’tazilah yang pada mulanya berpengaruh pada kekuasaan mulai tersingkir digantikan oleh kaum Salaf. Kedua, adanya ketegangan antara ulama’ fikih dengan kaum sufi. Bersamaan dengan itu di Bukhara tempat di mana al Farabi menghabiskan masa mudanya terjadi perkembangan bahasa dan sastra yang sangat pesat, sedangkan di Aleppo (sekarang Siria) dan Damaskus dua tempat dimana al Farabi menekuni karier intelektual dan menghabiskan masa tuanya, berkembang pemikiran filsafat dan logika yang sangat besar. al Farabi sendiri faham dengan trend besar zamannya ini karena dia menyaksikan dan bahkan terlibat langsung dalam gerak intelektual tersebut.33 Karya-Karya al Farabi Menurut Ahmad Daudy ada sekitar tiga puluh karya al Farabi yang dijumpai dalam bentuk Bahasa Arab.34Karya-karya al Farabi paling tidak dapat dikelompokkan dalam beberapa tema di antaranya: logika, fisika, metafisika, politik, astrologi, musik dan beberapa risalah yang berisikan tentang sanggahan atau tanggapan atas pemikiran para filosof tertentu. Di bidang Muhammad al-Khudhari, Muha>darat al Umam al-Isla>miyah (Kairo: Tp, 1921), hlm. 542-543. 32 Yamani, Filsafat Politik, hlm. 52. 33 Yamani, Filsafat Politik Islam; Antara, hlm. 53-54 34 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 27-28. 31 66a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) logika al Farabi menguraikan Organon karya Aristoteles secara tuntas, yang mencakup Hermeneutika, Analitika Prior, Analitika Posterior, Sofistik, puisi atau syair dan retorika, selain itu al Farabi juga menguraikan Isagoge Phorphyry. Al Farabi menulis risalah pendek yang secara khusus membahas aspek-aspek logika di antaranya: Risa>lah Sudi>ra Biha> al-kita>b, Risa>lah fi> Jawa>b alMasa>’il Su’ila ‘nha> dan Risa>lah fi> Qawa>nin Shina’at al-Syi’r. Naskah-naskah yang orisinil tentang logika yang pembahasannya jauh lebih pelik dari pada Categories karya Aristoteles dan Isagog karya Porphyry di antaranya adalah al-Alfaz al-Musta’malah fi> al-Mantiq (istilah-istilah logika), al-Fushu>l alKhamsah (lima pasal logika) dan Risa>lah fi> al-Mantiq (Pengantar Logika) dan semua karya-karya ini masih terdokumentasi dengan baik. Sementara di bidang fisika (fisika dalam pengertian tradisional, khususnya dalam pengertian Paripatetik dan filsafat alam), al Farabi menulis beberapa uraian tentang pemikiran Aristoteles dan filsafat Yunani di antaranya: Syarh Kita>b al-Sama’ al-Thabi’i li Aristhu>thalis dan Syarh Kita>b al-Sama’ Wa al-Alam li Aristhu>thalis serta Syarh Maqa>lat al-Iskandar al-Afrudisi’i fi> alNafs. al Farabi juga menulis mengenai risalah-risalah lepas yang mencakup ilmu Psikologi, zoologi, meteorologi, ruang waktu dan vakum di antaranya: Risa>lah fi> al-Khala’, Kala>m fi> al-A’dha’ alHayawan, Kalim fi> al-Haiz Wa al-Miqdar dan Maqa>lat fi> Ma’a>ni al-Aql. Karya-karya al Farabi yang merupakan sanggahan atas pandangan dan pemikiran para filosof dan teolog mengenai filsafat alam. Di antaranya adalah Kita>b al-Raad Ala> Jalinus fi> Ma> Ta Awwaluhu Min Kala>m Aristhu>, dan Kita>b al-Raad Ala> Ibn al Rawandi fi> al-Adab al-Jadal, dan al-Raad Ala> Yahya al-Nahwi fi> Ma> Raddahu Ala> Aristhu> serta kitab al-Raad Ala> al-Razi fi> al-Ilm al-Ila>hi. Sementara tentang musik al Farabi menulis karya yang berjudul Kita>b al-Musi>qa al-Kabi>r dan al Farabi juga menulis tentang astrologi yudisial yang berjudul fi> Ma> Yashihh Wa Ma> La> Yashihh Min Ahka>>m al-Nuju>m. Pada bidang metafisika al Farabi menulis beberapa uraian, sanggahan dan risalah lepas di antaranya: Maa>lat fi> Aghradh Ma> Ba’d al-Thabi’ah dan Kita>b al-Huru>f dan karya-karyanya yang masih terselamatkan dalam Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 67 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) bidang ini adalah Fushu>s al- H~ikam, Kitab fi> al-Wahi>d Wa alWahdah serta kitab yang ditujukan guna menyelaraskan gagasan Plato dan Aristoteles seperti Falsafat Aristhu>thalis, Kitab Falsafah Afla>thu>n Wa Ajzaha dan Kitab al-Jam‘ bain Ra’yai al- Haki>main: Afla>thu>n Wa Aristhu>. Karya al Farabi mengenai teori pengetahuan dan prinsipprinsip pertama dari ilmu-ilmu khusus di antaranya Kitab Fi Ushu>l Ilm al-Thabi’ah dan Ihsha’ al-Ulu>m, Fushu>s al-Hika>m, Ta’liqat fi> al-H~ikam, Kitab fi> Dzuhu>r al-Falsafah. Karya al Farabi mengenai filsafat politik diantaranya Kitab A>ra>>’ Ahl al-Madi>>nah al-Fa>dhilah, Kitab al-Syiyasah al-Mada>niyah, Kitab al-millat al-Fa>dhilah, Fushu>sh al-Madani> sementara karyanya mengenai konsep kebahagiaan berjudul Tahsil al-Sa’a>dah. Filsafat al Farabi Menurut Massignon, seorang sarjana Prancis, al Farabi adalah filosof Muslim pertama dalam arti sesungguhnya. Sebelum al Farabi memang telah tampil al-Kindi (185-260 H. / 801-873 M) yang membuka pintu filsafat ke dunia Islam. Tetapi, bagi Massignon, al-Kindi tidak memiliki sebuah filsafat yang sistematis. Sebaliknya, al Farabi, dalam pandangan Massignon, telah menciptakan suatu filsafat yang lengkap dan sekaligus menjadi guru dari para filosof Islam yang datang sesudahnya seperti Ibnu Si>na dan Ibn Rusyd.35 Al-Kindi mengalami kebingungan dalam memastikan perbedaan yang mendasar pemikiran Plato, Aristoteles dan Plotinus. Lain halnya dengan al Farabi, dia telah mampu memahami perbedaan mendasar tentang pemikiran para filosof Yunani tersebut. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan karya al Farabi yang berjudul al-Jama’ Baina Ra’y al-Hakimain,36 Posisi unik al Farabi dalam sejarah filsafat Islam tampak Abu Ahmadi, Filsafat Islam (Semarang: Toha Putra, 1982), hlm. 35 102. Ahmad Fuad al-Ahwani, Filsafat Islam, hlm. 76-77. Lihat Juga dalam Muhsin Mahdi, Al-Fa>ra>bi>’s Philosophy of Plato and Aristotle, (New York: The Free Press of Glencoe, 1962), hlm. 3-10. 36 68a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) dari sejumlah risalah “metodologis” nya, seperti Philosophy of Plato and Aristotle dan Reconciliation of Plato and Aristotle, yang kesemuanya itu berupaya melempangkan jalan bagi pengembangan studi filsafat dikemudian hari. Dalam Ihsha’ alUlu>m (Enumerasi Sains), misalnya, al Farabi mengantarkan para pembaca pada kurikulum filsafat Yunani. Dalam kurikulum filsafat Yunani, ilmu pengetahuan terklasifikasi ke dalam ilmu bahasa, alam, filsafat dan seterusnya.37 Filasafat al Farabi mempunyai corak dan tujuan yang berbeda dengan para filosof sebelumnya (baik dari Yunani maupun Islam), dia mengadopsi doktrin-doktrin para filosof terdahulu kemudian membangun kembali dengan disesuaikan lingkup kebudayaannya dan disusun dengan sangat sistematis dan harmonis atau selaras.38 Unsur-unsur penting filsafat al Farabi dapat dilihat dari tiga pokok pemikirannya yaitu logika, kesatuan filsafat (the unity of philosophy) dan teori intelek (akal). Pada masa muda, al Farabi lebih tertarik mempelajari logika, sebagian karyanya pun banyak yang dipusatkan pada studi tentang logika. Menurut al Farabi seni logika umumnya memberikan aturan-aturan yang bila diikuti memberi pemikiran yang besar dan mengarahkan manusia secara langsung kepada kebenaran dan menjauhkan dari kesalahan-kesalahan. Menurut al Farabi logika mempunyai kedudukan yang mudah dimengerti, sebagaimana hubungan antara tata bahasa dengan kata-kata, dan ilmu matra dengan syair. Selain itu logika juga membantu untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah dan menunjukkan bagaimana memperoleh cara yang benar dalam berpikir serta menunjukkan dari mana seharusnya memulai berpikir dan mengarahkannya kepada kesimpulan-kesimpulan akhir.39 Masalah pokok logika menurut al Farabi adalah topik-topiknya yang membahas aturan-aturan pemahaman, dimana topik-topik itu dikelompokkan menjadi delapan yaitu: pengelompokan, penafsiran, pengupasan pertama, pengupasan Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam; Sebuah Peta Kronologis, terj. Zaimul Am. (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 46. 38 Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 454. 39 Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 455. 37 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 69 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) kedua, topik, sofistik, retorik dan puisi yang semua itu merupakan tujuan utama logika. al Farabi meletakkan landasan bagi lima bagian penalaran demonstrative, dialektik, sofistik, retorik, dan puitis.40 al Farabi memberi ketegasan bahwa ada perbedaan mendasar antara logika dengan bahasa, menurutnya tata bahasa hanya berkaitan dengan kata-kata sedangkan logika berkaitan dengan arti dan kata-kata yang merupakan penjelmaan makna, selain tata bahasa selalu berkaitan dengan aturan-aturan bahasa tetapi logika berkaitan dengan pemikiran manusia yang selalu sama dimana dan kapan pun.41 Al Farabi membangun keilmuan logikanya mengikuti logika Aristoteles dengan menambahkan retorika dan puisi, kecerdasan al Farabi dalam menjabarkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Arab dan memaparkan prinsip-prinsip silogisme Aristoteles sekaligus merubah dari contoh-contoh yang dipaparkan oleh Aristoteles (yang begitu sulit dipahami oleh para filosof atau sarjana muslim) dengan contoh-contoh kejadian sehari-hari kehidupan dalam masyarakat Arab dinilai sebagai sumbangan terbesar oleh para filosof Islam setelahnya. Sehingga menjadikan al Farabi dijuluki sebagai “guru kedua” setelah Aristoteles. Setelah logika pikiran pokok dalam filsafat al Farabi adalah kesatuan filsafat (the unity of philosophy). al Farabi berpendapat bahwa pada hakekatnya filsafat merupakan satu kesatuan karena itu satu-satunya tujuan adalah mencari kebenaran, oleh karenanya menurut al Farabi tidak ada aliran filsafat yang ada hanya satu yaitu “aliran kebenaran”, oleh karenanya kebenaran agama dan kebenaran filsafat menurut al Farabi secara nyata adalah satu meskipun secara formal berbeda.42 Ajaran al Farabi ini didasarkan pada dua hal yaitu pertama, al Farabi bermaksud memperbaiki filsafat pengikut Aristoteles dan membungkusnya dalam bentuk Platonis agar lebih sesuai dengan ajaran Islam dan kedua, memberikan penafsiran rasional tentang kebenaran agama. Maka tujuan utama filsafat al Farabi adalah menerangkan filsafat dengan cara agama dan memfilsafatkan agama sehingga mendorong keduanya pada satu arah dan dapat dipahami secara Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 456. Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 455. 42 Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 456-457. 40 41 70a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) selaras.43 Pemikiran al Farabi ini membawa pengaruh pada filosof setelahnya seperti Ibn Rusyd dan Ibnu Si>na yang cenderung memadukan antara filsafat dan agama atau mengharmonisasikan keduanya. Al Farabi mendasarkan penyelarasan antara filsafat dengan agama didasarkan atas revisi filsafat para pengikut Aristoteles yang didasarkan pada dua teori yaitu teori kosmologis dan teori psikologis yaitu teori akal dan intelek sepuluh yang penjelasan rasionalnya bertumpu pada dua teori yaitu melalui penafsiran al-Qur’a>n dan teori kenabian. Oleh karenanya bangunan seluruh filsafat al Farabi dapat dikatakan terangkum dalam emapat teori ini yang saling berkaitan dan semuanya mengarah ke satu tujuan.44 Bagi al Farabi, filsafat mencakup matematika, dan matematika bercabang pada aritmatika, geometri, astronomi, astrologi, musik, mekanika, dan seterusnya. Sementara itu, ilmuilmu alam terbagi menjadi delapan, mengikuti delapan tema fisika Aristoteles, yakni Physics, Heavens, Generation and corruption, Meteorology, Book of Minerals, on Plants, Zoology, dan on the Soul. Semua bagian ilmu ini berlanjut pada “metafisika”. Dalam sumber-sumber Arab, “Metafisika” ini lazim pula disebut “ilmu ketuhanan“. Menurut al Farabi, bagian metafisika ini secara lengkap dipaparkan oleh Aristoteles dalam Metaphysics, yang sering jadi acuan dalam sumber-sumber Arab sebagai Book of Letters.45 M Saeed Shaikh menyimpulkan menjadi lima pokok pembahasan mengenai pandangan atau pemikiran filosofis al Farabi yaitu ontologi, teologi metafisik, kosmologi, psikologi rasional dan filsafat politik. Ontologi mencakup pembahasan tentang “yang ada” kemudian teologi metafisik berbicara tentang bagaimana Tuhan itu berada serta bukti-bukti yang menunjukkan ke-eksistensian-Nya, rasional Psikologi membahas tentang tubuh dan jiwa, dan filsafat politik mengkaji tentang gagasan kota utama, pemimpin yang ideal dan sebagainya.46 Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm.457. Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm.457 45 Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>”, hlm. 457. 46 M. Saeed Sheikh, Studies in Muslim Philosophy, hlm. 77-88. 43 44 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 71 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) Minat dan perhatian al Farabi yang amat besar terhadap ilmu pengetahuan, diikuti oleh kecerdasan dan ketekunannya yang mendalam dan keterbukaannya terhadap segala macam pandangan atau gagasan yang dijumpainya, menyebabkan dia tidak dapat mengelak dari pengaruh tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik, diantaranya Plato, Aristoteles dan Plotinus. Di mana pandangan para filosof Yunani klasik telah merasuki dalam pemikiran al Farabi.47 Plato mempengaruhi al Farabi pada pemikiran tentang etika dan politik, Aristoteles mempengaruhi al Farabi pada bidang ilmu logika, sementara pengaruh Plotinus terhadap al Farabi pada ajaran-ajarannya tentang bagaimana yang banyak ini berasal dari yang Esa yang tunggal yaitu ajaran emanasi. Yang kemudian teori emanasi dikembangkan oleh al Farabi dengan sepuluh akal yang mengalir dari Tuhan, dan pelimpahan itu terjadi dengan sendirinya ibarat mengalirnya cahaya / sinar dari matahari tanpa mengurangi zatnya sedikit pun.48 Filsafat al Farabi merupakan campuran antara filsafat yang bercorak Aristotelean dengan Neo Platonisme dan pemikiran ke-Islaman yang jelas dan corak aliran Syi’ah Imamiah. Dalam masalah logika dan filsafat misalnya dia mengikuti Aristoteles, dalam masalah etika dan politik al Farabi menganut Plato, sementara masalah metafisika dia merujuk pada pemikiran Plotinus.49 Dalam kaitannya dengan dirinya yang dinobatkan sebagai ‘guru kedua’ karena pencapaian keilmuan dalam bidang logika, hal ini berkaitan dengan kemampuan al Farabi dalam menulis banyak komentar dan paraphrase atas kumpulan karya logika Aristoteles yang dikenal dengan Organon, Rethoric dan Poetics yang menjadi bagian Organon dalam tradisi Suryani dan Arab ataupun Isagog karya Porphyry, juga dikomentari oleh al Farabi. Naskah-naskah yang orisinil tentang logika yang pembahasannya jauh lebih pelik dari pada categories karya Aristoteles dan Isagog karya Porphyry di antaranya adalah al-Alfaz al-Musta’malah fi> Syaifuddin, ”Konsep Pemikiran Tentang Kenabian”, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001. hlm. 24-25. 48 Syaifuddin, ”Konsep Pemikiran Tentang Kenabian”, hlm. 29. 49 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, hlm. 83. 47 72a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) al-Mantiq (istilah-istilah logika), al-Fushu>l al-Khamsah (lima pasal logika) dan Risalah fi> al-Mantiq (Pengantar Logika) dan semua karya-karya ini masih terdokumentasi dengan baik.50 Tentang alam al Farabi lebih condong ke pemikiran Plato, dia sependapat dengan Plato bahwa alam ini baru dan terjadi dari yang tidak ada. Sementara mengenai proses terjadinya alam dan bagaimana hubungan Khalik dengan makhluk al Farabi begitu juga al-Kindi menganut ajaran emanasi Neo-Platonisme. Mula pertama al Farabi memahami prinsip Aristoteles bahwa Tuhan adalah akal yang berfikir, al Farabi menyebutnya dengan akal murni. Prinsip Aristoteles itu kemudian diisi oleh al Farabi dengan teori emanasi Neo Platonisme dan Plotinus.51 Sekilas Filsafat Politik al Farabi Perkembangan ilmu politik secara umum dan khususnya persoalan demokrasi saat ini tidak bisa lepas dari Filsafat politik Plato, Plato menjelaskan bahwa manusia secara natural adalah makhluk politik karena fitrahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri kecuali melalui perkumpulan atau kelompok.52 Filosof Muslim, Al Farabi meletakkan dasar filsafat politik Islam melalui karyanya philosophy of Plato dimana Al Farabi menghadirkan Plato sebagai seorang ahli politik yang dalam karya-karya filsafat filosof Muslim sebelumnya yaitu Al Kindi dan al Razi filsafat politik tidak dihadirkan.53 Tidak berbeda dengan filsafat politik Plato, Al Farabi meletakkan dasar filsafat politiknya dengan mengkaji psikologi manusia dan kebahagiaannya. Manusia, menurut Al Farabi termasuk dalam spesiesMajid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam; Sebuah Peta Kronologis, Terj. Zaimul Am (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 45-46. 51 Poerwanto, Seluk Beluk Filsafat Islam (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 135. 52 Fauzi M Najjar, “Democracy In Islamic Political Philosophy” dalam Jurnal Studia Islamica, La Loi du 1957, G.P Maisonneuve et Larose 1980, hal. 108-122 53 Muhsin S Mahdi, Al Farabi and the Foundation of Philosophy, dalam (ed) Parvis Morwedge Islamic Philosophy and Mysticism. (New York: Carvana Book, 1981), hal. 14-16 50 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 73 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) spesies yang tidak dapat menyelesaikan urusan-urusan penting mereka ataupun mencapai keadaan baik mereka kecuali melalui asosiasi (perkeumpulan) banyak kelompok dalam suatu tempat tinggal yang sama.54 Psikologi manusia menurut Al-Farabi mempunyai fitrah sosial, fitrah untuk berhubungan dan hidup bersama orang lain, dari fitrah ini kemudian lahir apa yang disebut masyarakat, kota dan Negara.55 Al Farabi mengibaratkan Kota atau Negara dengan tidak ubahnya susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna dimana masing-masing saling berusaha dan bekerjasama, dalam tubuh manusia ada kepala, hati, jantung, tangan, dan kaki yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Begitu pula dalam Negara, masing-masing rakyat mempunyai tugas dan kadar kecerdasan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan saling kerjasama dimana harus ada kepala Negara, dan yang lain membantu dalam berbagai kedudukan sehingga tercapai kebahagiaan. Gagasan Al Farabi ini sebagaimana diungkapkan dalam karya-karya penting filsafat politiknya di antaranya, Al Siyasah Al Madaniyah, dan Mabadi Ara Ahlu Al Madinah Al Fadhilah.56 Hirarki wuju>d-nya al-Fa>ra>bi dijadikan landasan untuk mengembangkan teori politiknya, terutama tentang konsep pengaturan sebuah kota atau negara. Al Farabi mengajarkan bahwa sebuah kota atau negara harus diatur berdasarkan tingkatan-tingkatan hierarki yang di dalamnya dan yang paling atas mengatur yang di bawahnya secara berturut-turut dan bertahap. Yang paling tinggi adalah pengatur utama dan mutlak, sementara yang paling bawah adalah yang diatur secara mutlak, kemudian yang berada di antaranya mempunyai kedua aspek sekaligus, yaitu mengatur yang di bawahnya dan diatur oleh yang Yamani, Al Farabi Filosof Politik Muslim, (Jakarta: Teraju, 2005), 54 hal. 37. Dikemudian hari, gagasan tentang fitrah sosial ini diulangi oleh Jean-Jacques Rousseau (1712-1778 M) dengan konsep “kembali ke alam” ( retur a la nature ) yang kemudian melahirkan konsep Sosial Contrat (kontrak sosial); kemauan untuk bekerjasama demi tercapainya kebutuhan bersama diantara individu. Lihat Frans Magnis Suseno, Etika Politik , (Jakarta, Gramedia, 1994), 238-239. 56 H. Zainal Abidin Ahmad, Negara utama; Madinatul Fadhilah (Jakarta: PT. Kinta, 1968), hal. 41-43. 55 74a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) di atasnya.57 Sementara mengenai pemimpin utama atau imam dalam pemikiran politik al Farabi, dia mengadopsi dari pemikirannya mengenai struktur akal manusia. Menurut al Farabi adalah mereka yang telah mampu sampai pada akal mustafad yang layak jadi pemimpin, karena orang tersebut telah terhubung dengan akal aktif dan telah tercurahkan oleh akal kesepuluh sehingga teraktualisasikan ilmu pengetahuan dan orang tersebut menjadi tahu tentang hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Menurut al Farabi orang yang telah mencapai tingkat ini sebenarnya kontaknya dengan akal aktif akan berlangsung terus-menerus. Karena ketika akal kenabian bersatu dengan akal aktif, akal kenabian secara terus menerus teraktualisasi dan dia pun menjadi mengetahui tentang segala sesuatu, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Pemimpin yang seperti ini menurut al Farabi terus-menerus berada dalam bimbingan Tuhan, atau dalam istilah teknis filsafat, akal aktif telah menjadi forma atau forma (akal)-nya dan seseorang telah menjadi materi bagi wuju>d komposit yang terdiri dari materi (yang sesungguhnya adalah) forma (akal)-nya dan forma yang sesungguhnya adalah akal aktif itu sendiri.58 Mengenai pemimpin atau imam, al Farabi kemudian memberi rincian karakter yang harus dimiliki, menurut al Farabi ada dua belas karakter bagi seorang imam di antaranya: jujur, cinta keadilan, cerdas, sehat jasmani, lugas, berakhlak mulia, moderat dan pemberani. Teorinya ini mirip dengan konsep Plato tentang raja filosof serta karakter-karakter khalifah menurut para ahli fiqih Islam 59 Hubungan yang akrab antara metafisika dengan filsafat politik dalam pemikiran al Farabi lebih lanjut melukiskan pandangan organik manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta, dan dengan sesama manusia, sebagaimana Yamani, Antara Al-Fa>ra>bi> dan Khomeini, Filsafat Politik Islam, 57 hlm. 154. 58 hlm. 157. Yamani, Antara Al-Fa>ra>bi> dan Khomeini, Filsafat Politik Islam, Abu Nasr al-Fa>ra>bi>, A>ra>>’ Ahl al-Madi>>nah al-Fa>dhilah, hlm. 197199. Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta, hlm. 54. 59 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 75 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) yang diwujudkan dalam sistem kepercayaan Islam. Bagi al Farabi ilmu politik dan etika dipahami sebagai suatu perluasan atau perkembangan metafisika atau sebagai manifestasinya yang tertinggi yaitu teologi, yakni, ilmu tentang Tuhan. Karena itu karya metafisika al Farabi yang agung A>ra>>’ Ahl al-Madi>>nah al-Fa>dhilah tidak dimulai dengan keadilan dan diskusi tentang hubungan manusia dengan negara seperti dalam Republik Plato, tetapi dengan diskusi tentang wuju>d pertama atau yang maha esa menurut Plotinus, sifat-sifat dan caranya mengada di dunia ini. Ciri khas ini benar-benar menunjukkan kemurnian filsafat al Farabi dan model pemikiran al Farabi.60 Oleh karenanya tidak dapat disangkal bahwa al Farabi adalah filosof Muslim pertama yang mampu memberikan teori politik yang didasarkan pada metafisika emanasionis dan kosmologi Plotinus ataupun Proclus. Dan dijalan itulah al Farabi membangun utopia politik yang sejalan dengan kekhalifahan Islam, terutama dalam bentuknya yang diyakini oleh kalangan Syi’ah Ima>mah.61 Pemikiran politik al Farabi ini tidak hanya berpengaruh pada filosof-filosof Islam klasik yang datang setelahnya. Tapi khazanah pemikiran politik al Farabi menjadi sangat penting kaitannya dengan pemikiran politik Islam kontemporer. Pemikiran Ayatullah Khomeini (seorang tokoh revolusi Iran) misalnya, tidak beranjak jauh dari konsep-konsep yang dikembangkan oleh al-Fa>ra>bi. Tidak hanya Khomeini, para pemikir Islam lain seperti Jawad Mughniyyah, Muhammad Baqir Shadr, Kahzhim Hairi juga mengembangkan pemikiran politik al Farabi. Mereka memunculkan konsep pemerintahan yang Islami, dengan dua bentuk spektrum, mulai dari yang paling populist (berorientasi pada rakyat) sampai yang paling statist (berorientasi pada negara). Al Farabi juga membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dengan mensintesakan pemahaman Plato dan hukum Ilahiah Islam. Jika kebahagiaan menurut Plato puncaknya hanya dapat diraih dalam negara (politeia), bagi al Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam, hlm. 177. Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta, hlm. 54. 60 61 76a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) Farabi kesempurnaan dan kebahagiaan puncaknya hanya dapat diperoleh dalam negara ideal yang sempurna pemerintahannya, yang dipimpin oleh raja-filosof yang identik dengan pemberi hukum dan imam. 62 Demokrasi dalam Filsafat Politik al Farabi Sebagaimana dituliskan dalam karya-karyanya, Al Farabi menggunakan kata madinah (Kota) untuk membahas Negara, tujuan akhir dari Kota atau Negara adalah pencapaian kebaikan atau kebahagiaan. Demi mencapai tujuan akhir berupa kebaikan dan kebahagiaan sebuah Kota atau Negara dalam konteks sistem pemerintahan dan kemungkinan pencapaian kebahagiannya AlFarabi membagi Kota atau Negara dalam beberapa kategori diantaranya; negara jahiliyah, negara fasiq, negara mubadilah, dan negara sesat (dlalah). (1) Negara jahiliyah adalah negara yang pemerintahannya tidak tahu dan tidak mampu mengarahkan rakyatnya pada kebahagiaan; (2) Negara fasiq adalah Negara yang pemerintahannya-- sebenarnya-- tahu dan mampu membawa rakyatnya kepada kebahagiaan, tetapi mereka tidak mengakui dan tidak melakukannya melainkan justru mempraktekkan permainanpermainan politik kotor yang akhirnya menjerumuskan mereka pada martabat rendah; (3) Negara mubaddalah adalah Negara yang pemerintahannya--secara zahir--melakukan tindakan dan kebijakan yang membantu rakyat, padahal yang terjadi sesungguhnya justru sangat merugikan rakyat, semua dilakukan semata demi menutupi kecurangan dan kebobrokan aparat; (4) Negara sesat adalah Negara yang pemerintahannya tidak membawa rakyat pada kedamaian melainkan justru membawa mereka pada pertentangan, disintegrasi, konflik dan kehancuran.63 Di dalam karyanya Al Siyasah Al Madaniyah, dan Mabadi Ara Ahlu Al Madinah Al Fadhilah, al-Farabi tidak memberi uraian lebih rinci tentang tiga sistem pemerintahan yang terakhir, tetapi dia banyak memberikan penjelasan tentang sistem pemerintahan Yamani, Antara Al-Fa>ra>bi> dan Khomeini, Filsafat Politik Islam, 62 hlm. 51-91. Al-Farabi, Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadilah dalam Richard Welzer (ed), on The Perfect State, (Oxford, Clarendon Press, 1985), hal 225259. 63 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 77 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) jahiliyah. Menurutnya, pemerintahan jahiliyah setidaknya terbagi atas empat golongan; (1) sistem timokrasi, rezim yang mengutamakan kehormatan atau kewibawaan (karamah), (2) sistem plutokrasi, rezim yang mengutamakan kelompok kecil dimana kekuasaan atau kepemimpinan dipegang orang tertentu dengan cara didasarkan atas perhitungan besar kekayaan, konglomeratisme (baddalah), (3) sistem tirani, rezim yang mengutamakan pemimpin seorang tiran, militerisme (taghallib), (4) sistem demokrasi, rezim yang mengutamakan perwakilan orang-orang banyak (jama`iyah).64 Al Farabi meletakkan Kota demokrasi atau Negara demokrasi termasuk dalam Kota jahiliyah.65 Namun, diantara empat sistem pemerintahan yang tidak baik (jahiliyah) tersebut, sistem demokrasi diakui oleh Al-Farabi sebagai sistem yang paling baik. Menurut Al Farabi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik diantara rezim-rezim yang jelek. Demokrasi merupakan negara yang paling didambakan dan dianggap paling bahagia, setiap orang menyukainya dan ingin tinggal di dalamnya karena tidak ada satu pun keinginan atau potensi--baik maupun jahat-yang tidak tertampung dan tidak terkembangkan di dalamnya. Menurut Al Farabi, kota demokrasi adalah kota yang tujuan penduduknya adalah kebebasan yang setiap penduduknya melakukan yang dikehendakinya tanpa sedikit pun dikekang kehendaknya.66 Penduduknya setara dan samasekali tidak ada orang yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya.67 Ada dua prinsip yang dianut dalam Kota demokrasi; (1). Prinsip kebebasan (liberty), rezim demokratis disebut juga rezim “bebas” atau “kesatuan orang-orang bebas”. Negara demokrasi berjalan dimana setiap individu berhak dan bebas melakukan apa yang dikehendaki dan disukai, dan tidak seorang pun berhak atas otoritas kecuali berbuat untuk memanfaatkan kebebasaanya. Al-Farabi, Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadilah dalam Richard Welzer (ed), on The Perfect State, hal. 225-259. 65 Yamani, Al Farabi Filosof Politik Muslim, hal. 49-54 66 Al-Farabi, Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadilah , dalam Richard Welzer (ed), on The Perfect State, hal. 225-259 67 Al Farabi, al-Siyasah al-Madaniyah, Dar wa Maktabah al-Hilal, hal. 29-32. 64 78a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) (2). Prinsip kesejajaran (equality), setiap orang dalam rezim demokrasi adalah sama dan sejajar dihadapan hukum, tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat jelata, bahkan rakyatlah sumber dan pemegang otoritas kekuasaan yang sebenarnya, sedang pemerintah hanya menjalankan tugasnya sesuai yang dikehendaki rakyat.68 Melalui dua prinsip tersebut, terutama kebebasan, sistem demokrasi tidak hanya mendorong lahirnya ilmu dan peradaban tinggi dalam sebuah kehidupan Kota atau Negara, tetapi bersamaan itu juga membuka peluang bagi berkembangnya kekuatan-kekuatan jahat, minimal yang secara moral bertentangan dan menghambat tercapainya kebahagiaan masyarakat, karena tidak ada otoritas atau rasa tanggungjawab untuk mengendalikan nafsu jahat (amoral) dan harapan-harapan warga negara. Inilah ketidaksempurnaan sistem demokrasi, karena itu, meski demokrasi diakui sebagai negara paling besar, paling berperadaban, paling produktif dan paling sejahtera, ia juga merupakan negara yang paling banyak mengandung kejahatan dan keburukan.69 Kota demokrasi memungkinkan di dalamnya berkembang kebaikan dan kejahatan, tetapi ketika ada pemimpin yang berusaha memebawanya pada kebahagiaan penduduk cenderung menentangnya karena faktor kebebasan yang dianut penduduk lebih menghendaki pemimpin yang memudahkan penduduk pada pencapaian keinginannya dan melestarikan yang diinginkannya.70 Berdasar kenyataan atas ketidaksempurnaan sistem demokratis di atas, Al-Farabi mengajukan gagasannya tentang sistem pemerintahan Negara utama (Madinah al-Fadilah). Negara tidak diperintah oleh perwakilan orang banyak (parlemen) melainkan oleh pemimpin utama yang bertugas untuk mendidik dan mengarahkan rakyat pada pencapaian kebahagiaan tertinggi (aktualisasi potensi-potensi terbaik dari ruhani dan pemikiran). Gagasan ini didasarkan atas kenyataan, (1) bahwa susunan Al-Farabi, Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadilah , dalam Richard Welzer (ed), hal. 257. 69 Al-Farabi, Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadilah , dalam Richard Welzer (ed), hal. 257. lihat juga Fauzi M. Najjar, “Demokrasi dalam Filsafat Politik Muslim”, dalam Jurnal al- Hikmah, (edisi 2, Oktober 1990), 92. 70 Yamani, Al Farabi Filosof Politik Muslim, hal. 76 68 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 79 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) masyarakat atau pemerintahan tidak berbeda dengan badan. Pada badan, semua gerakan yang dilakukan oleh tangan, kaki, kepala dan lainnya, adalah atas perintah hati. Hati bertindak sebagai pemimpin atas tindakan jasad. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat, tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada jasad: ia bertindak sesuai dengan perintah pemimpin atau pemerintah, pemerintah adalah pemimpin masyarakat. (2) Bahwa karena perbedaan-perbedaan alamiah, tidak semua orang mengetahui dan memahami kebahagiaan lewat dirinya sendiri atau sesuatu yang harus diperbuatnya guna mencapai kebahagiaan mereka membutuhkan guru, pendidik dan pembimbing. Disinilah tugas dan fungsi pemimpin utama, yakni dengan kesempurnaan dan kebijaksanannya, menunjukkan pada masyarakat tentang objek utama (primary intellegibles) yang bisa mengarahkan pada kebahagiaan.71 Berdasarkan pemaparan tersebut secara jelas bahwa Al Farabi meletakkan Kota demokrasi atau Negara demokrasi termasuk dalam Kota jahiliyah. Al-Farabi bahkan mengungkapkan kelemahan dan kelebihan Negara demokrasi dan menyatakan bahwa Kota demokrasi hanya terbaik di antara sistem-sistem pemerintahan yang jelek dan kemudian mengajukan Madinah alFadilah (Negara Utama) sebagai sistem pemerintahan terbaik, sistem pemerintahan post-demokrasi. 72 Kritik atas Demokrasi al Farabi Menurut penulis, Kota demokrasi Al Farabi meskipun konsepnya tidak sepenuhnya bisa disebut identik dengan demokrasi modern, namun konsep Kota demokrasi Al Farabi mengandung segala elemen demokrasi modern seperti dasar kebebasan dan kesetaraan di dalamnya. Berdasarkan pemaparan di atas penulis perlu mencermati beberapa poin penting untuk dikritisi dan teliti lebih dalam terkait kota demokrasi Al Farabi. Pertama, Al Farabi cenderung bersifat mendua mengenai kemungkinan Kota utama atau Fauzi M. Najjar, “Demokrasi dalam Filsafat Politik Muslim”, dalam Jurnal al- Hikmah, (edisi 2, Oktober 1990), hal. 92 72 Al-Farabi, Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadilah , dalam Richard Welzer (ed), hal. 257. 71 80a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) madinatul fadhilah bisa muncul dari Kota demokrasi, sementara dalam penjelasan Al Farabi Negara demokrasi sangat kontras dengan Negara utama bahkan Negara demokrasi termasuk Negara jahiliyah. Melalui prinsip kebebsan dan kesetaraannya, Kota demokrasi, menurut Al Farabi, memungkinkan berkembang menjadi negara paling besar, paling berperadaban, paling produktif dan paling sejahtera, di dalamnya memungkinkan lahir seorang fadhil, intelektual, pemikir dan filosof. Namun, karena prinsip kebebasan dan kesetaraannya, Negara demokrasi juga merupakan negara yang paling banyak mengandung kejahatan dan keburukan sehingga memungkinkan penduduknya mengangkat penguasanya yang memudahkan kebebasan dan keinginan penduduk demi kepentingan individu masing-masing, bukan mengangkat pemimpin dari orang bajik yang membawanya pada kebahagiaan sebagai tujuan sebuah negara.73 Kedua, ada pernyataan yang kontradiktif pada pemikiran politik Al Farabi terkait Kota demokrasi. Al Farabi menjelaskan dalam kitab al siayasah ala madaniayah bahwa pembangunan kota-kota utama dan penegakan pemerintahan orang-orang uatama adalah lebih efektif dan jauh lebih mudah diwujudkan dari kota-kota demokratis dibandingkan dengan kota-kota jahiliyah lainnya.74 Namun, di kitab Al Siayasah Al Madaniyah Al Farabi juga menjelaskan bahwa masyarakat kota demokrasi cenderung tidak menghendaki pemimpin dari orang bijak, kalaupun terpilih menjadi pemimpin akan selalu diganggu dan kedudukannya tidak stabil, masyarakat demokrasi cenderung menolak pemerintahan orang bajik dan tidak menyukainya.75 Menurut penulis, pernyataan Al Farabi tersebut tampaknya mengandung kontradiksi satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sangat tidak logis. Ketiga, terkait kritik Aristoteles terhadap pemikiran Plato yang sedikit dibahas Al Farabi, meskipun secara tidak langsung tapi melalui tanggapannya tentang pemikiran Plato. Kemungkinan bentuk pemimpin despotik dalam bentuk-bentuk pemerintahan ideal Plato maupun yang dapat juga terjadi di dalam Fauzi M. Najjar, “Demokrasi dalam Filsafat Politik Muslim”, dalam Jurnal al- Hikmah , (edisi 2, Oktober 1990), hal. 92. 74 Al Farabi, al-Siyasah al-Madaniyah, hal. 29-32. 75 Al Farabi, al-Siyasah al-Madaniyah, hal. 29-32. 73 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 81 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) bentuk kota utama disetujui Al Farabi tapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan dalam konteks tertentu dia setuju dengan penguasa atau pemimpin yang despotik.76 Menurut Al Farabi despotisme hanya tidak benar dan terkutuk bila penguasanya menjadi dispotik lantaran kecenderungan alaminya, bukan karena diperlukan menjadi seperti itu untuk rakyat. Asumsi yang dapat dilihat dari tidak adanya penjelasan Al Farabi yaitu bahwa dia percaya penuh kemungkinan bentuk despotis negatif tidak akan terjadi pada penguasa kota utama seperti dikhawatirkan Aristoteles terhadap bentuk pemerintahan ideal Plato. Despo-tisme pun diperlukan untuk efektifitas sistem daripada demokrasi. Meski demokrasi memiliki kemungkinan baik jika dilakukan akan membutuhkan waktu yang lama mengingat sistemnya tidak memberikan tempat bagi dispotisme.77 Yamani, Antara Al Farabi dan Khomaeni; Filsafat Politik Islam, 76 hal. 77-78 Yamani, Antara Al Farabi dan Khomaeni; Filsafat Politik Islam, 77 hal. 77-78 82a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) DAFTAR PUSTAKA Abu Nasr al-Farabi. Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadhilah. Al Atruk: Al Maktabah Al Azhar, 2002. -------, Al-Farabi’s Philosophy of Plato and Aristotle. Terj. Muhsin Mahdi. New York: The Free Press of Glencoe, 1962 -------, al-Siyasah al-Madaniyah, Dar wa Maktabah al-Hilal Fakhry, Majid Al-Fa>ra>bi> Founder of Islamic Neo Platonism: His Life, Work and Influence Oxford: Oneworld, 2002 --------, Sejarah Filsafat Islam; Sebuah Peta Kronologis, terj. Zaimul Am. Bandung: Mizan, 2001 Bakar, Osman, Hierarki Ilmu; Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu, terj. Purwanto Bandung: Mizan, 1997 Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya II Jakarta: UI-Press, 2002 Arsyad, M. Nastsir, Ilmuan Muslim Sepanjang Sejarah Bandung: Mizan, 1995 Hanafi, Ahmad, Pengantar Filsafat Islam Jakarta: Bulan Bintang, 1996 Sheikh, M. Saeed, Studies in Muslim Philosophy India: Adam Publisher, 1994 Ahmad, zainal Abidin Negara utama; Madinatul Fadhilah Jakarta: PT. Kinta, 1968 Ibrahim Madkour, “Al-Fa>ra>bi>” dalam M. M. Sharif (ed.), A History of Muslim Philosophy, Vol. I Delhi: Low Price Publication, 1961 M M. Syarif, Para Filosof Muslim Terj. Tim Penerjemah Mizan Bandung: Mizan, 1996 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek. Edisi V. Cet. XII. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002 Baker Anton dan Zubair, A. Charis. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisus, 1990 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 83 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) Bakker, Anton. Metode-Metode Filsafat. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986 Copleston, F. A Hsistory of Philosophy I. London: Burns Oates and Washbourne Ltd, 1951 Hadi, Sutrisno. Metode Research. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987 Morwedge, Parvis (ed.). Islamic Philosophical Theology. Albany: State University Of New York Press, 1979 -------, Islamic Philosophy and Mysticism. New York: Carvana Book, 1981 Netton, I.R. Al-Farabi and His School, Arabic Thought and Culture Series. London and New York: Routledge, 1992 Walzer, Richard. Al-Farabi on the Perfect State : Abu Nasr AlFarabi Mabadi’ Ara’ Ahl al-Madinah al-Fa>dhilah. Oxford: Clarendon Press, 1985 Wippel, John F (ed.). Studies in Medieval Philosophy. Washington DC: the Catholic University of America Press, 1987 Yamani. Al-Farabi Filosof Politik Muslim. Jakarta: Teraju, 2005 -------, Antara al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam. Bandung: Mizan, 2002 Fuad al-Ahwani, Ahmad, Filsafat Islam Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995 al-Khudhari, Muhammad, Muha>darat al Umam al-Isla>miyah Kairo: Tp, 1921 Daudy, Ahmad, Kuliah Filsafat Islam Jakarta: Bulan Bintang, 1992 Ahmadi, Abu, Filsafat Islam Semarang: Toha Putra, 1982. Mahdi, Muhsin, Al-Fa>ra>bi>’s Philosophy of Plato and Aristotle, (New York: The Free Press of Glencoe, 1962 Syaifuddin, ”Konsep Pemikiran Tentang Kenabian”, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001. hlm. 24-25. Poerwanto, Seluk Beluk Filsafat Islam Bandung: Rosda Karya, 1994 Najjar, Fauzi M, “Democracy In Islamic Political Philosophy” 84a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) dalam Jurnal Studia Islamica, La Loi du 1957, G.P Maisonneuve et Larose 1980, -------, “Demokrasi dalam Filsafat Politik Muslim”, dalam Jurnal al-Hikmah, edisi 2, Oktober 1990 Mahdi, Muhsin S, Al Farabi and the Foundation of Philosophy, dalam (ed) Parvis Morwedge Islamic Philosophy and Mysticism. New York: Carvana Book, 1981, Suseno, Frans Magnis, Etika Politik , Jakarta, Gramedia, 1994 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 85 Ambivalensi Kota Demokrasi (oleh: Muhamad Yasin) Halaman ini bukan sengaja dikosongkan 86a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) TEOLOGI ISLAM KONTEKSTUALTRANSFORMATIF Nur Said STAIN Kudus Email: [email protected] ABSTRACT A Religion has strong influence on humanity, morality, ethics, and aesthetics in the process of humankind development. This of course, will construct the worldview individually and socially as well. It may be said that nearly all the social life haven’t been ignored the role of religion in the making humanity as an expression of the whole of collective life. Therefore the religious spirit is also in constant change, which formulated in a certain theology in line with the historical progress contextually. In addition, theology is a discourse through which believers develop and express the content of their faith as they have confessed it. The notion of this article tries to elaborate the contextualization of Islamic Theology in Indonesia in respecting to the social phenomena such as colonialism, oppression, human right, and pluralism in Indonesia. It also gives paradigmatic contribution to interpret the Secret text on historical situation in order to determine public morality more than just individual morality. The main points are a searching of meaning between “text” and context in Indonesia society as manifestation of Islamic contextual theology. It means that Islam should be “translated” in particular way in order may “come down to earth” and meet in the contemporary demands. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 87 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) Keywords: Islam, contextual-transformative theology, human right, Indonesia Pendahuluan Agama sebagai suatu sistem keyakinan dan pedoman hidup sangatlah penting dan fundamental bagi umat manusia, lebih-lebih untuk para pemeluknya. Namun dalam kelompok masyarakat yang mengalami derita sosial, multikrisis yang berkepanjangan, selain agama yang sebenarnya memiliki fungsi profetik yang mulia, tidak jarang dalam bias perilaku para pengikutnya mendorong pelarian diri dari kehidupan duniawi seperti hidup zuhud kaum sufi atau sebaliknya memicu radikalisme dan militansi perilaku yang serba mutlak seperti konsep jihad yang serba fisik belaka. Sehingga secara kasat mata seringkali menemukan sekelompok umat beragama dengan berbagai simbol keagamaan yang kental dan atraktif justru menunjukkan perilaku kekerasan fisik, teror, ancaman, hingga ke kesediaan untuk menumpahkan darah sesama. Wajah seperti ini menampakkan Agama justru akan membawa keterbelakangan umat dan belum bisa memberikan peran yang begitu berarti lantaran ketidakmampuan para pemeluknya dalam merumuskan persoalan dengan jelas, terutama bagaimana konteks teologi dibenturkan dengan kenyataan kehidupan yang begitu kompleks dan selalu berubah. Disamping itu, teologi agama-agama yang telah ada kurang memberikan sentuhan yang berarti untuk perkembangan ilmu-ilmu sosial dan historisitas keagamaan yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi keagamaan sejalan dengan locus dan tempus yang menyelimutinya. Akibatnya teologi agama-agama tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap masa depan kemanusiaan di planet ini. Bagaimana Islam sebagai agama besar di dunia ini mampu menjawab berbagai tantangan di tengah tantangan global dan transformasi sosial yang begitu cepat. Tulisan singkat ini akan mencoba menawarkan beberapa pointer menuju terbangunnya teologi kontekstual yang membebaskan, membumi dan menyentuh persoalan riil kemanusiaan dengan meletakkan Islam 88a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) sebagai rohnya. Oleh karena itu yang dikedepankan adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai spirit bagi terciptanya budaya perdamaian dan pembebasan sejalan dengan tuntutan konteksnya. Posisi Agama dalam Struktur Sosial Penting kiranya terlebih dahulu memahami agama dalam ranah sosial, karena paradigma yang ingin dibangun adalah bagamana memahami agama secara sosiologis-kontekstual sebagai kerangka menuju teologi Islam yang kontekstual. Untuk kepentingan ini menuntut adanya analisa kenyataan sosial sebagaimana adanya, tanpa memberikan penilaian etis ataupun politis dan bersamaan itu pula akan kita temukan bahwa dalam realitas sosial mengandung makna dan nilai yang melingkupinya. Hal ini mengandaikan suatu penafsiran dalam pemahaman makna dan pranata sosial berikut hubungan kausalnya. Dalam konteks inilah relevan kiranya mengaktualkan konsep umum yang dibangun oleh Berger dalam menggambarkan fenomena kenyataan sosial ini secara lebih komprehensif dan di mana posisi agama itu terposisikan. Bagi Berger fenomenologi merupakan aspek yang penting bagi pemahaman dunia sehari-hari sebagai obyek penelitian sosiologi. Setidaknya ada 3 (tiga) macam fenomenologi, pertama, fenomenologi transendental yang berusaha mencapai pengetahuan tanpa pengandaian. Kedua, fenomenologi hermenetik, lebih menekankan pada sifat linguistik manusia, sehingga teks menjadi obyek dari analisa fenomenologi. Ketiga, fenomenologi eksistensial, menekankan analisa dunia kehidupan (life-world). Fenomenologi jenis ketiga inilah yang banyak mempengaruhi Berger dalam kajian sosiologisnya. Pengaruh ini dapat dilihat dari pandangannya tentang manusia. Baginya dunia manusia ditandai dengan keterbukaan, sehingga perilaku manusia hanya sedikit saja dipengaruhi oleh naluri. Oleh karenanya manusia harus membentuk sendiri perilakunya melalui pengaturan dan penertiban yang berlangsung Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 89 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) secara terus menerus.1 Ini menandakan bahwa perilaku manusia merupakan manifestasi dari fenomena dialektika antar manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu masyarakat tertentu. Pola kausalitas dalam kenyataan sosial digambarkan Berger dalam uraiannya: Masyarakat adalah suatu gejala dialektik, yaitu suatu hasil manusia dan tak lain adalah hasil manusia, tetapi terus menerus mempengaruhi hasil itu. Masyarakat adalah hasil produk manusia. Ia tak lain adalah aktifitas dan kesadaran manusia. Tidak ada kenyataan sosial lepas dari manusia, tapi dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah hasil dari masyarakat. Biografi setiap individu adalah suatu episode dalam sejarah masyarakat yang mendahului dan melestarikannya. Masyarakat sudah ada sebelum individu dilahirkan dan tetap ada sesuadah individu itu mati.2 Kejelian Berger dalam melihat relasi manusia dengan masyarakat sebagai yang berinteraksi secara dialektis, dengan demikian menyangkal suatu determinisme sepihak yang mengganggap individu dibentuk oleh struktur sosial yang tidak memililiki peran dalam menentukan struktur lainnya. Dengan kata lain Berger ingin menegaskan bahwa manusia dibentuk oleh struktur sosial, bersamaan itu pula manusia juga mempengaruhi untuk mengubah institusi dan struktur sosialnya. Bagi Berger ada tiga momen dialektis yang terjadi dalam masyarakat yaitu eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, manusia mengekpresikan diri membangun dunianya. Expresi ini memanifestasikan suatu relitas obyektif setelah melalui proses obyektifikasi. Demikian pula realitas James Davison Hunter, Stephan C. Ainly, “Introduction” dalam Making Sense of Modern Time, Peter L. Berger and the Vision of Interpretatif Sosiologi, Roudledge & Kegan Paul, (London, 1986) hlm. 1-8. Berger juga melihat kesadaran manusia sebagai kesadaran yang intensional yang selalu terarah kepada obyek. Demikian pula kesadaran juga dipengaruhi oleh obyek di luarnya, Peter L. Berger, The Social Construction of Reality, diterj. Hasan Basari, Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta, LP3ES, 1990) hlm. 30 2 Peter L. Berger, The Sacred Canopy, (Doubleday, Garden City, New York, 1967) hlm. 3 1 90a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) obyektif juga akan berpengaruh kuat bagi pembentukan perilaku manusia, setelah manusia tadi melewati tahap internalisasi.3 Sampai di sini bukan berarti harus berhenti, akan tetapi setiap masyarakat masih mewariskan pranata sosial yang dibangun kepada generasi berikutnya. Di sinilah proses sosialasi di upayakan. Dalam proses sosialisasi ini makna dan nilai dari pranata sosial harus di dijelaskan sedemikian rupa secara legitimatif, sehingga individu dapat menerimanya. Menurut Sastraprateja, fungsi legitimasi adalah kognitif dan sekaligus normatif. Kognitif karena menjelaskan mengenai makna realitas sosial dan normatif dalam arti akan memberi pedoman bagaimana seseorang harus berlaku dalam kehidupan riil. Legitimasi memiliki tujuan mempertahankan realitas. Ada beberapa tingkat legitimasi yang bisa mewujud pada kata-kata mutiara, legenda, perumpamaan, perintah-perintah moral, sistem simbol sampai pada perkembangan yang paling mutakhir dan sistematis yakni teori ilmiah.4 Dan bagi Berger agama merupakan satu satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Karena agama yang paling komprehensif membicarakan tentang realitas seperti tragedi, penderitaan, ketidakadilan dan kematian.5 Penjelasan di atas memberikan suatu kerangka teoritik bahwa agama merupakan suatu penutup atau kanopi sakral (sacred canopy) yang melindungi manusia dari chaos, sesuatu yang tidak menentu tanpa arti. Dengan demikian agama meligitimasi institusi sosial dengan menempatkannya dalam suatu kerangka sakral. Sebegitu kuat posisi agama dalam konstruksi sosial, oleh karena itu agama yang secara operasional menjelma dalam berbagai bentuk teologi agama-agama harus tetap terintegrasi secara positif pada konteks sosial yang mewarnainya. Hal ini tentu dilakukan dengan tidak mengabaikan tahap-tahap dialektika sosial 3 Ibid, hal 2-4 4 M. Sastraprateja, dalam Pengantar, Peter L. Berger, Kabar dari Langit, Makna Teologis Dalam Masyarakat Modern, (Jakarta, LP3ES, 1991) hlm. xvi 5 Peter L. Berger , The Sacred Canopy…hlm. 105-107. Dan ternyata legitimasi kematian merupakan potensi transendensi dari universom simbolis memanifestasikan diri dengan cara yang paling jelas Peter L. Berger, The Social…hlm.145 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 91 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) yang sedang berproses. Pada tahap inilah kontekstualisasi teologi menjadi penting dengan menempatkan iman secara transformatif dan beranjak dari pemahaman agama yang doktriner-normatif menuju menuju historis-empiris. Kontekstualisasi Teologi Agama-agama Dalam dialektikanya, antara iman dan komunitasnya ada interaksi yang begitu kuat dan berkelanjutan secara terus menerus. Macquarrie menegaskan bahwa teologi mensyaratkan adanya partisipasi dan refleksi dalam suatu komunitas iman dan berusaha menyatakan inti iman itu dalam bahasa yang sejelas mungkin.6 Partisipasi-refleksi ini menuntut suatu kelanjutan (continuity), sekaligus keterputusan (discontinuity). Berkelanjutan karena teologi bergumul dalam iman yang sudah ada dan bertitik tolak dari iman itu, sehingga teologi merupakan suatu kegiatan yang terlibat. Teologi juga merupakan suatu keterputusan lantaran melalui teologi iman dirumuskan dalam suatu pandangan (thought), sehingga teologi juga sebagai suatu ekspresi.7 Ini menandakan bahwa teologi secara sosiologis akan selalu bersinggungan dengan konteks sosial dan berhadapan dengan arus perubahan yang sebegitu pesat dalam suatu bingkai kebudayaan tertentu. Sementara Geert menilai, kebudayaan sebagai seperangkat nilai dan makna yang memberi petunjuk untuk hidup dalam institusi sosial yang beragam Baginya agama adalah “sistem budaya” (cultural system).8 Ini menandakan dalam setiap agama manapun akan mengandung sistem sosio-kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Artinya konsepsi manusia tentang realitas itu sendiri tidaklah bersumber dari pengetahuan, akan tetapi dari kepercayaan pada suatu otoritas mutlak yang berbeda menurut John Macquarrie, Principle of Christian Theology, (London, SCM Press, 1966) hlm. 1-3 7 John A. Titaley, Th.D, Menuju Teologi Agama-agama yang Kontektual, Pidato Pengukuhan Jabatan Fungsional Akademik Guru Besar Ilmu Teologi, Universitas Satya Wacana, Salatiga, 29 Nopember 2001, hlm. 4-5 8 Clifford Geertz, The Interpretation of Culture, (New York: Basic Books, 1973) 6 92a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) agama dan keyakinannya. Karena agama juga merupakan realitas sosial, maka akan selalu hidup dan termanifestasikan dalam masyarakat. Dengan demikian konstruksi teologi agama selayaknya mengakar kepada dinamika sosial dengan segala keprihatinan dan keajaibannya. Maka cukup beralasan kalau Bevans secara tegas menilai, suatu teologi bisa disebut teologi apabila dia kontekstual,9 atau –dengan meminjam istilah Azyumardi Azra- perlu adanya akomodasi budaya dalam berteologi10 agar teologi agama-agama yang terbangun tidak berbenturan dengan realitas sosial yang selalu berubah. Apalagi kalau mau berpikir lebih jauh bahwa dalam wacana keagamaan tidak bisa terlepaskan dari persentuhannya dengan konsepsi tentang Yang Transesden atau -menurut bahasa Hick- the Real. Bagi Hick konsepsi manusia tentang the Real11 tak terlepas dari pengalaman keadaan yang historis dan adanya intervensi kebudayaan tertentu yang melingkupinya. Sehingga ketika konteks teologi ini telah menyentuh pada dimensi kebenaran, Hick menegaskan itu terjadi sebagai sesuatu yang budayawi, dalam pengertian bahwa pemahaman itu terjadi dalam Stephan B. Bevans, Model of Contextual Theology, Faith and Cultures Series, (Maryknoll-New York: 1996) hlm. 33. Gagasan kontekstualisasi teologi mulai diprakarsai Theological Education Fund (TEF) dalam upaya mengembangkan suatu teologi yang memadai dan menyentuh kebutuhan manusia, David J. Hasselgrave & Edward Roman, Kontektualisasi: Makna, Metode dan Model, Terj. Stephan Suleeman, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996) hlm. 49-50 10 Azyumardi Azra, MA, Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam, (Bandung, Mizan, 1999) hlm. 11 11 Hick menerapkan konsep distingsi Imanuel Kant dalam memahami perbedaan fenomena keagamaan antara the Real sebagai sesuatu yang eksis dan the Real sebagai hasil pemahaman dari pengalaman individu dalam tradisi tertentu, John Hick, An Interpretation of Religion (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989), hlm. 236. Oleh karena itu akan ada perbedaan persepsi tentang the Real sebagai akibat tidak adanya akses secara langsung kepada the Real sehingga melahirkan konflik konsepsi terhadap the Real (conflicting conception of the Real). Semua persepsi terhadap the Real selalu melalui mediator yaitu tradisi keagmaan yang unik (unique religious tradition), John Hick, Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993), 159. 9 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 93 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) kondisi-kondisi simbol budaya suatu masyarakat tertentu. Dalam masyarakat Israil kebenaran atau disebutnya eternal one, yang kekal hanya dapat dipahamai sebagai Yahweh secara kongrit dalam bentuk Tuhan Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sedangkan dalam masyarakat India yang kekal itu dipahami sebagai Syiwa atau Krishna.12 Kesadaran bahwa kapasitas imaginasi dan pengalaman manusia dalam beragama yang terbatas dan selalu bersentuhan dengan budaya meyakinkan kita bahwa teologi yang kontekstual akan senantiasa dinamis, terbuka dan menyadari bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan yang akan selalu hadir dalam kehidupan. Dengan demikian meletakkan kriteria kemanusiaan (humanum)13 atau lebih rincinya –seperti ditegaskan pula oleh Engineer-14 persaudaraan universal (universal brotherhood), kesetaraan (equality), dan keadilan sosial (social justice) dalam berteologi cukuplah mendesak sebagai tanggung jawab global setiap manusia. Islam dan Konteks Teologi di Indonesia Mencermati perjalanan Islam di Indonesia, maka akan menemukan konteks teologi yang begitu dinamis dan responsible terhadap kondisi sosial yang mengiringinya. Benar bahwa secara historis aliran teologi Islam yang dominan adalah aliran teologi Asy’ariyah yang kemudian menjadi aliran utama (mainstream school of theology) madzhab Ahl Sunnah wa-al-Jama’ah (Sunni) yang diikuti oleh mayoritas kaum Muslim di Indonesia. Teologi Asy’ari muncul sebagai respon atas aliran Mu’tazilah. Dalam masalah kebebasan berkehendak Mu’tazilah memandang Tuhan tidak benar-benar memainkan peran dalam John Hick, God Has Many Names (London: Macmillian, 1980), 12 hlm. 52-54 Hans Kung menggambarkan resiprokal antara agama dan kemanusiaan secara dialektis dalam suatu statemennya, “The Humanity is the presupposition for the true religion…and the true religion is the fullfilment of true humanity…” Hans Kung, Global Responsibility: In Search of a New World Ethic, trans. John Bowden (New York, Crossroad, 1991) hlm. 91-92 14 Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 33 13 94a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) kegiatan manusia dan manusia diposisikan sebagai pusat segalanya.15 Teologi Asy’ariyah sebaliknya berkeyakinan pada posisi ekstremnya dengan menolak ide bahwa manusia bisa bertindak semuanya dan berkehendak bebas. Menurutnya Tuhan menciptakan semua tindakan manusia dan manusia hanya memperolehnya (acquire) bukan melakukan (do). Dapat dilihat di sini teologi Asy’ary cenderung menekankan pada takdir (predestination), kendatipun ia memiliki potensi untuk mewujudkan kenginan dan perbuatannya (kasb) di bawah kekuasaan Tuhan.16 Kecenderungan teologi Asy’ary yang bersifat jabariyah (predestination) seperti itu oleh para pengamat dan peneliti dipandang sebagai yang bertanggung jawab atas kemunduran dan keterbelakangan sosial ekonomi karena akan melemahkan berkembangnya semangat etos kerja. Namun kalau mau meniti lebih jauh bagaimana teologi itu berkembang dan memberikan respon terhadap realitas sosial sepertinya harus berhati-hati karena dalam kenyataannya Islam mampu memberikan spirit bagi perlawanan terhadap kekuatan penjajah dengan adanya perubahan dan pergeseran teologi Islam (Asy’ariyah) dari waktu ke waktu. Kenyataan ini bisa dilacak sejak berkembangnya paham neosufisme yang disebarkan oleh ulama-ulama Indonesia yang baru kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Sufisme yang dikembangkan adalah reform sufism, sufisme yang telah dimurnikan dari praktek-praktek yang antinomian17, sehingga menjadi selaras dengan hukum Islam. Salah satu tema sentral neosufism adalah rekonstruksi sosio-moral masyarakat Muslim melalui aktifitas dan upaya kaum Fazlur Rahman, Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam, penyunting Ebrahim Moosa, (Jakarta, PT RajaGrafindo, Persada) hlm. 78-79 16 Ibid. hal 79. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, Konteks Teologi di Indonesia:Pengalaman Islam, (Jakarta, Paramadina, 1999) hlm. 44-45 17 Antinomianisme merupakan suatu keloyalan terhadap agama tertentu namun kurang respek terhadap hukum-hukum moral yang dianggapnya sebagai sekuler, lihat Jonathan Z. Smith, The Harper Dictionary of Religion, (San Francisco, HarperCollin, 1995) hlm. 54 15 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 95 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) Muslim sendiri, tanpa harus menunggu campur tangan eskatologi.18 Kesadaran ini memungkinkan para Ulama terlibat di berbagai urusan sosial antara lain menjadi mufti yang memberikan saran kepada para penguasa tidak saja pada urusan keagamaan tetapi juga dalam urusan perdagangan, diplomatik dan politik seperti yang terjadi pada Syekh Yusuf ketika bekerja sama dengan Sultan Ageng Tirtayasa dalam perang Banten dengan melawan melawan Belanda19. Bahkan seiring dengan terjadinya konsolidasi kolinialisme Belanda, abad 18, neosufisme mengalami proses politisasi dan radikalisasi yang kemudian munculah “teologi jihad” melawan penjajah Belanda yang jelas-jelas melakukan ekploitasi dan penindasan terhadap bangsa Indonesi. Teologi jihad ini semakin menguat setelah terbitnya sebuah buku khusus yang membicarakan tentang keutamaan jihad dalam Fadha’il alJihad20, yang dimotori oleh Syekh Abd al Shomad al-Palimbani, seorang ulama dan pemikir tasawuf yang beraliran al Ghozaly. Manifestasi teologi jihad di Jawa juga bisa terlihat pada perang Diponegoro melawan Belanda tahun 1825-1830. Demikian juga yang terjadi pada abad 19 di Kalisalak, Pekalongan dengan munculnya Syekh Ahmad Rifa’i. Setelah belajar cukup lama di Mekkah lalu beliau kembali ke desanya dan membentuk kelompok “Santri Tarjamah”. Melalui kelompoknya beliau mengecam penghulu yang diangkat oleh pemerintah Belanda dan berfatwa bahwa pernikahan yang melalui penghulu yang diangkat oleh Belanda dianggapnya sebagai tidak sah.21 Dari beberapa data di atas semakin meyakinkan bahwa teologi Islam telah begitu mengalami pergeseran secara dinamis sejalan dengan tatangan yang dihadapinya. Kemudian kalau melangkah ke era kontemporer pergeseran teologi ini semakin kompleks dan progresif. Hal ini bisa dilihat saat bangsa Indonesia mulai Azyumardi Azra, Konteks Teologi…,hlm. 46-47 Ibid. hlm.47 20 Buku ini membawa pengaruh yang cukup besar bagi kaum Muslim saat itu dan puncaknya adalah meletusnya pemberontakan kuam thariqat Naqsabandiyah dan Qodiriyah di Cilegon, Banten, 1888. Ibid. hal 48 21 Ibid. hlm. 48 18 19 96a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) mempersiapkan kemerdekaannya yang diwarnai adanya suatu “pergulatan” berbagai pandangan dunia (world view) yang diwarnai prinsip teologi tertentu mengenai posisi negara vis-a-vis doktrin agama. Melihat kenyataan bangsa Indonesia yang sangat majmuk dengan beragam suku, ras agama dan kepercayaan, mustahil terbentuk suatu negara kesatuan yang berdaulat tanpa adanya sebuah kesadaran akan pentingnya mengedepankan nilainilai kemanusiaan dan kebangsaan di atas segalanya sehingga muncullah ‘teologi kebangsaan”.22 Kebesaran tokoh-tokoh Islam -yang lebih mengedepankan kepentingan kebangsaan sebagai buah ijtihad politiknya – menjelang kemerdekaan tak heran kalau para pengamat dan peneliti memberikan suatu catatan sejarah yang mengagumkan terhadap fenomena keberagamaan di Indonesia terutama terkait dengan eksistensi minoritas non-Muslim dalam masyarakat Muslim. Hal ini bisa lihat misalnya uraian Smith: “Nowhere in the Moslem world (except perhap in Indonesia?) do Muslims feel that a non-Moslim member of their nation is ‘one of us”. And Nowhere do monorities feel accepted”23 Meskipun penilaian itu sebagai hasil dari suatu interpretasi terhadap fakta-fakta yang dilihatnya sebagai seorang peneliti, setidaknya itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bahwa kesadaran keagamaan para tokoh-tokoh Islam terdepan saat itu begitu humanis an inklusif. Di sinilah nampak teologi Islam telah begitu membumi dan senantiasa bersentuhan dengan konteks sosialnya. Dan nampaknya upaya kontektualisasi teologi dalam Islam itu tak pernah berhenti hingga sekarang dengan agenda persoalan yang lebih serious. Maka tak heran kalau proses kreatif melalui Hal ini menunjukkan terjadinya suatu pergeseran dan meninggakan keharusan adanya suatu negara Islam. Memang pada era ini awalnya terjadi polemik yang sangat keras antara kelompok Nasionalis dan Islam terutama perdebatan seputar dasar Negara yang akhirnya memutuskan Pancasila sebagai Dasar negara setelah terjadi perdebatan sengit seputar Piagam Jakarta, lihat misalnya BJ Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesian, The Hague Martinus Nijhoff, 1971, p. 27-29 23 Wilfred Cantwell Smith, Islam in Mdern History, (Princeton, 1957) hlm.80 atau bisa disimak pada BJ Boland, The Struggle…hlm. 224 22 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 97 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) “ijtihad” secara terus menerus melahirkan beragam formulasi teologi yang berbasis Islam. Dari beragamnya teologi itu misalnya, teologi modernisme yang dipelopori oleh Harun Nasution dan Nurcholish Madjid, teologi transformatif yang dimotori oleh para tokoh LSM semisal Adi Sasono, M. Dawam Raharjo dan Muslim Adurrahman, teologi Inklusifisme dengan Mukti Ali, Abdurrahman Wahid, dan Djohan Effendi sebagai tokohnya, dan teologi Neotradisionalisme yang dikembangkan oleh Sayyed Hussain Nasr dan sangat berpengaruh di Indonesia.24 Semua itu sebagai wujud upaya kontektualisasi teologi Islam dalam menjawab tantangan zaman menuju kehidupan yang berkeadaban dilandasi semangat keislaman dan keilahian. Dan upaya-upaya itu tidak mungkin terwujud tanpa kesadaran pentingnya pemahaman Islam secara kontekstualtransformatif. Pemahaman Islam Kontekstual-Transformatif Jelaslah bahwa teologi yang mampu hidup di tengah manusia adalah setidaknya teologi yang terbangun mampu merespon persoalan riil kehidupan kemanusiaan. Teologi yang tidak hanya berkutat pada persoalan metafisik tetapi yang mampu merubah ritus menjadi aksi sosial. Akan tetapi persoalannya tidak semudah dengan hanya mengedepankan kekuatan apologisme tanpa pemahaman wacana keislaman yang terangkum dalam teks-teks Kitab suci secara progresif-revolusioner. Tak cukup hanya menekankan pada pemahaman tekstual-normatif-skriptualis terhadap Islam seperti yang mengedepan pada kalangan ahli fiqh, akan tetapi perlu secara cerdas menangkap “term-term kunci” dalam doktrin Islam dengan menyerap makna terdalam (deep insight) darinya teksteks itu kepada konteksnya. Celakanya gejala pemahaman ahli fiqh ternyata Azyumardi Azra, Konteks Teologi…,hlm. 50-51 Sebenarnya masih banyak jenis teologi Islam dengan segala keunikannya sebagai respon iman terhadap realitas sosial dengan segala problematikanya, uraian lebih terinci mengenai keragaman pemikiran yang sangat berpengaruh bagi wacana teologi di Indosesia dapat dilihat dalam Dr. H. Abuddin Nata, MA., Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 24 98a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) mengedepan setidaknya sebagimana dirasakan oleh Arkoun dalam suatu keprihatinannya: ”Para ahli fiqh yang sekaligus teolog tidak mengetahui hal itu, mereka mempraktekkan jenis interpretasi terbatas dan membuat metodologi tertentu, yakni fiqh dan perundang-undangan. Dua hal ini mengubah diskursus al-Qur’an yang mempunyai makna mitis majazi, yang terbuka bagi berbagi makna dan pengertian, menjadi diskursus baku dan kaku dan …telah menyebabkan diabaikannya historisitas norma-norma etika keagamaan dan hukum-hukum fiqh. Jadilah norma-norma dan hukum fiqh itu seakan-akan berada diluar sejarah dan diluar kemestian sosial, menjadi suci: tidak boleh disentuh dan didiskusikan...”25 Hal ini membuktikan betapa umat Islam umumnya masih begitu sempit dalam menangkap semangat Islam dan terkesan sudah tercerabut dari realitasnya. Sehingga teologi yang terbangun hanya menyentuh pada wilayah metafisik dan isu-isu transendental saja. Keprihatinan inilah –setidaknyayang mendorong Engineer membangun landasan keislaman bagi teologi pembebasan sebagai jawaban atas persoalan kemanusiaan yang dihadapi saat itu. Menurut Engineer teologi pembebasan ini tidak hanya terbatas pada logika spekulatif metafisik akan tetapi lebih menekankan pada wilayah praksis dengan mengubah iman menjadi spirit bagi kesalehan sosial.26 Penegasan di atas mengukuhkan bahwa antara iman dan praksis dalam teologi pembebasan merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Asumsi dasar dalam teologi pembebasan menegaskan bahwa Islam senantiasa tidak memberikan ruang bagi adanya tindak kedlaliman dan diskriminasi. Kerena sejak awal diturunkan Islam telah mengadung missi pembebasan dan perdamaian. Menurut Mukti Ali, setidaknya ada tiga pesan penting Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, pertama, membawa ajaran tauhid, kedua, perlawanan Nabi SAW tehadap penumpukan harta Muhammad Arkoun, al-Islam: al-Akhlaq wa al-siyasah, (Beirut: Markaz al-Inma’ al_Qauni, 1986) hlm. 172-173 26 Asghar Ali Engineer, “Islam and Liberation”, In Islam and Its Relevan to our Age, (Kuala Lumpur : Iqroq, 1987) hlm.59 25 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 99 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) benda pada sekelompok orang tertentu, karena ini bisa berakibat pada ketdakadilan dan jatuh pda syirk. Ketiga, menghapuskan rasdiskriminasi, yang menganggap hubungan kekerabatan mereka hanya didasarkan pada hubungan darah/suku.27 Dengan kata lain, munculnya Islam sebenarnya tidak bisa terpisahkan dari konteks sosial dan sekaligus sebagai respon teologis atas fenomena ketidakadilan, eksploitasi dan penindasan yang merebak kala itu. Ketidakadilan bukanlah kondisi yang “given” secara metafisik, tetapi lebih merupakan konstruksi manusia melalui pemaksaan yang harus direspon dengan perlawanan. Wujud perlawanan dengan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi juga dilakukan oleh Farid Esack di Afrika Selatan dengan mencoba secara kreatif menemukan makna terdalam teks dalam konteks karena baginya antara wahyu dan konteks ada hubungan yang kuat, …the process of revelation itself was never independent of the community’s context but consisted of a dynamics interaction between the two.28 Nampaknya Esack ingin menegaskan bahwa Islam harus ditransformasikan menjadi spirit untuk menjawab segala tatangan sosial yang empiris dan historis. Di sinilah pentingnya teologi pembebasan itu digagas dan kembangkan secara kontinyu meskipun dengan format dan bentuk yang berbeda. Sejalan dengan Engineer, Esack menilai teologi pembebasan merupakan upaya pembebasan agama dari bentuk ketidakadilan dan eksploitasi termasik di dalamnya adalah ras, gender, kelas dan agama.29 Dan ini semua mensyaratkan adanya suatu dialektika antara teks dengan konteks sehingga “hidup” dan selalu menemukan “kata kunci” dalam Islam yang mampu melahirkan api perubahan dalam perdamaian. Setidaknya ada empat kata kunci yang bisa dijadikan bahan renungan bagi bagi misi pembebasan sebagai respon H.A. Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, (Bandung, Mizan, 1991) hlm. 64-65 28 Farid Esack, Qur’an,Liberation and Pluralition an Islamic Perspectiveof interreligius solidarity again operation, (Oxford: Oneworld, 1997) hlm.16 29 Farid Esack, Qur’an,Liberation … hlm.83 27 100a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) terhadap konteks: Pertama, tauhid, menurut Engineer doktrin ini nerupakan inti ajaran Islam yang memiliki dua dimensi yaitu; pertama dimensi spiritual, menegasikan penyembahan terhadap “berhala” dalam masyarakat Mekkah saat itu. Kedua dimensi sosial politik, berhubungan dengan pertahanan Nabi Muhammad terhadap dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam bidang ekonomi. Dengan demikian Tauhid tidak hanya menunjukkan keesaan Tuhan tetapi kesatuan umat manusia tanpa kelas.30 Sejalan dengan Engineer, Ali Syari’ati memahami Tauhid sebagai kesatuan universal dan eksistensinya antara Tuhan, alam dan manusia.31 Kesadaran ini secara tidak langsung juga memposiskan manusia secara egaliter memupuk semangat humanisme lintas kultur dan iman. Kedua, Adl (keadilan), karena adanya kesatuan kemanusiaan maka keadilan harus ditegakkan secara komprehensif. Islam tidak membolehkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama bahasa dan pertimbangan etnis. Al-Qur’an menggunakan terminologi adl dan Qist untuk menjelaskan persoalan keadilan.32 Dengan tetap mengacu pada semangat tauhid, menjadi jelas bahwa keadilan sebagai suatu sistem nilai yang perlu diperjuangkan harus mampu masuk pada berbagai wilayah yang multireligious dan multikulturalisme. Ketiga, Iman. Al-qur’an selalu menghubungkan “iman” dengan perbuatan-perbuatan yang baik (amal sholeh). Izutzu menjelaskan amal baik dan iman sebagai dua unit yang tidak bisa dipisahkan. Mereka yang merasa beriman idealnya Asghaar Ali Engineer, Islam and Liberation Teologi, hlm. 8 Doktrin tauhid ini Esack mampu mentransformasikannya menjadi konsep “masyarakat tauhidi (tauhidi society) sebagai idiologi yang mampu merangkul semua elemen masyarakat dalam suatu kehidupan yang lebih damai dan membebaskan perpecahan tradisional karena agama dan politik dan sekaligus sebagai konter terhadap idiologi apatheid, Farid Esac, Qur’an,Liberation … hlm. 91. Bandingkan juga dengan Nur Said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hlm. 70 – 75. 31 Ali Syari’ati, On the Sosiologi of Islam, (Barkeley : Mizan Press, 1984) hlm.83 32 QS. 49 ayat 9, lihat juga QS. 59 ayat 7, Qs 51 ayat 19, Qs. 69 ayat 33,34, Qs. 89 ayat 17,18. Uraian lebih terinci bisa juga dilihat pada Farid Esack, Qur’an,Liberation … hlm. 103-106 30 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 101 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) mengaktualisasikan perilaku yang baik termasuk dalam hal penegakan keadilan.33 Sebagai implikasinya orang yang benarbenar beriman akan selalu menempatkan nilai keadilan sebagai hal penting dalam kehidupannya Keempat, jihad. Memahami makna jihad menarik mencermati uraian Esack yang lebih mengandung nuansa pembelaan hak-hak kemanusiaan. Bagi Esack jihad harus diletakkan pada konteks kebangsaan dan kemanusiaan yang selalu bersentuhan pada kehidupan praksis. Karenanya konsep Esack –dengan mengutip Qibla- cenderung mengkontekskan jihad sebagai paradigma Islam bagi perjuangan pembebasan (the islamic paradigm of the liberation struggle…an effort, an exertion to the utmost, a striving for truth and justice)34. Jelas sekali penekanan Esack bahwa menegakkan keadilan merupakan tujuan utama jihad daripada mengedepankan Islam sebagai sistem keagamaan namun bersamaan itu masih berlanjut terus penindasan, ekploitasi maupun diskriminasi. Namun tak jarang oleh sekelompok orang memahami jihad sebagai “perang suci” dan memberangus naluri kemanusiaan yang semestinya harus dikedepankan. Oleh Satha-Anand, pemikir muslim dari Thailand, kelompok ini mendapat kritik tajam. Menurut Satha-Anand; “Istilah jihad yang umumnya diterjemahkan dengan “perang suci’ mengandung arti suatu tindakan putus asa orang-orang irasional dan fanatik yang ingin memaksakan pandangan hidup mereka pada orang lain”35. Satha-Anand cenderung memaknai jihad sebagai perjuangan melawan penindasan, kedzaliman dan ketidakadilan dalam semua bentuknya, dimanapun ditemui dan demi mereka yang tertindas siapapun mereka.36 Model-model pemahaman Thoshihiko Izutsu, Etnicho Religious Concepts in the Qur’an (Montreal; McGill University Press, 1966) hlm. 204 34 Farid Esack, Qur’an,Liberation … hal 106-110 35 Satha-Anand memberikan penjelasan cukup rinci dengan menguraikan beberapa ayat al Qur’an yang menguatkan, lihat, Chaiwat SathaAnand, Agama dan Budaya Perdamaian, pent. Taufik Adnan Amal (Yogyakarta, Forum Kajian Agama dan Budaya, 2002) cet.II. hlm. 6 36 Ibid, hlm.8 bisa dilihat juga dalam Asghaar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, pent. Agung Prihantoro (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 33 102a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) yang yang bernuansa pembebasan seperti di atas setidaknya akan memberikan wawasan yang mencerahkan manakala pada tataran berikutnya diimplementasikan pada kehidupan nyata, dengan menghadirkan Islam secara kontekstual-transformatif. Masih banyak “kata kunci” lainnya dalam tradisi keislaman yang mengharuskan pola-pola penafsiran yang lebih progresiftransformatif dengan penggunaan metode dan pendekatan yang tepat. Untuk kepentingan ini al Jabiri menekankan pentingnya “obyektivisme” dan “rasionalitas” dalam memahami tradisi itu. Dengan obyektivisme (maudluiyyah) akan menjadikan tradisi lebih kontekstual dengan keberadaannya sendiri dan berarti memisahkan dirinya dari kondisi kekinian kita. Sebaliknya rasionalitas (ma’quliyyat) yaitu menjadikan tradisi itu lebih kontekstual dengan kondisi kekinian kita.37 Maka Al Jabiri- juga menegaskan begitu pentingnya “dekonstruksi” yakni merombak sistem relasi yang baku (dan beku) dalam satu struktur tertentu dan menjadikannya sebagai bukan struktur melainkan menjadikannya sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan “cair”38. Hubungan obyektifikasi dan rasionalitas sebagaimana Al Jabiri agaknya sejalan dengan pola penafsiran Fazlur Raham seperti dikedepankan oleh Esack dalam diagram sebagai berikut 39 : 1999) hlm. 33-39 37 Muhammad Abed al-Jabiri, Post Tradisionalime Islam, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LkiS, 2000) hlm.28. 38 ibid hlm. 30 Pola dekonstruksi terhadap wacana keagamaan ini sepertinya merupakan suatu keharusan lantaran bagi Armstrong umat manusia tak akan mampu menahankan kehampaan dan ketandusan, mereka akan selalu mengisi kekosongan itu dengan menciptakan sebuah pusat perhatian baru tentang “makna”. Mereka akan mencari tuhan-tuhan baru jika Tuhan yang diajarkan agama tidak relevan lagi. Dalam kegelisahan inilah Armstrong merasakan pentingnya mempertimbangkan “sejarah Tuhan” sebagai pelajaran dan peringatan sebagai bentuk dekonstruksi yang begitu radikal, lihat Karen Amstrong, Karel Amstrong, A History of God, The 4,000 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, (United States of America, First Ballatin Books Edition, 1994) hal 399 39 Dikutip dari pemaparan Esack tentang suatu “pencarian makna antara teks dan konteks” Farid Esack, Qur’an,Liberation … hlm. 66 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 103 pentingnya “dekonstruksi” yakni merombak sistem relasi yang baku (dan beku) dalam satu struktur tertentu dan menjadikannya sebagai bukan struktur melainkan menjadikannya sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan “cair”38. Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) n rasionalitas sebagaimana Al Jabiri agaknya Historical Situation Qur’anic Response Generalizing Specific Answer Determining Moral-Social Objectives of the Qur’an Qur’anic Values Contemporary Islamic Diagram di atas mengilustrasikan bahwa untuk memahami al Qur’an setidaknya melalui dua langkah; pertama, menganalisa situasi sejarah serta tuntutan moral-etik (ethicomoral requirements) yang dilanjutkan dengan kajian terhadap teks-teks al Qur’an pada situasi tertentu. Selanjutnya, melakukan suatu “generalisasi” jawaban spesifik dari hasil hubungan antara teks dengan konteks menjadi sebuah “hukum moral sosial” (determining Moral-Social Objectives of the Qur’an). Langkah kedua adalah implementasi “hukum moral sosial” dalam konteks sosial yang kongrit saat ini setelah melalui kajian lebih serius tentang realitas sosial itu secara kritis. Pola ini diharapkan mampu mendudukkan semangat teks benar-benar memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Lebih jauh Amin Abdullah menambahkan pentingnya penjelajahan penafsiran dengan pola (abductive)40 yang lebih menekankan the logic of discovery daripada the logic of justification.41 Semangat inilah yang akan meneguhkan pola penalaran kontekstual historis-empiris yang agaknya memang relevan untuk era kontemporer yang sarat dengan problematika dengan mengembalikan kesadaran komunitas keagamaan yang deep insight ‘hati nurani” manusia yang paling dalam. Dengan Pola pikir ini lebih menekankan unsur hipotesis, interpretasi, proses pengujian di lapangan terhadap rumus-rumus, konsep-konsep, dalil-dalil dan gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh kombinasi pola pokir deduktif dan induktif, Amin Adullah, “Agama Masa Depan: Intersubjektif dan Posdogmatik”, dalam BASIS No.05-06, Tahun ke-51, Mei-Juni 2002, hlm. 54 41 Ibid 40 104a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) cara pemahaman seperti inilah agaknya teologi Islam yang kontekstual akan bisa hidup dalam segala zaman (shalihun li kulli zaman wa makan). Penutup Kehadiran Islam di tengah pergumulan manusia ini sejak awal membawa misi kemanusiaan di samping ketuhanan. Ini sekaligus respon atas hegemoni kultur dan idiologi yang tak beradab, menindas dan diskriminatif. Islam akan tetap memenuhi tantangan zaman dengan berbagai persoalan yang dihadapinya manakala umat pemeluknya secara kreatif mengkontekskan dan mentransformasikan ajaran-ajarannya dengan senantiasa berusaha menemukan “makna terdalam” dari semangat teks-teks Kitab Suci. Pada tahap inilah teologi Islam kontekstual-transformatif menjadi penting dan relevan untuk dikembangkan di tengah masyarakat global yang multireligious dan multikultur menuju perdamaian bersama terutama bagi STAIN Kudus yang sedang mengusung Islam trnasformatif sebagai Pola Ilmiah Pokok (PIP) nya.*** Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 105 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Amin, “Agama Masa Depan: Intersubjektif dan Posdogmatik”, dalam BASIS No.05-06, Tahun ke-51, Mei-Juni 2002 Ali, Mukti H.A., Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, (Bandung, Mizan, 1991) Al-Jabiri, Muhammad Abed, Post Tradisionalime Islam, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LkiS, 2000) Amstrong, Karel, A History of God, The 4,000 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, (United States of America, First Ballatin Books Edition, 1994) Anand, Chaiwat Satha-, Agama dan Budaya Perdamaian, pent. Taufik Adnan Amal (Yogyakarta, Forum Kajian Agama dan Budaya, 2002) Arkoun, Muhammad, al-Islam: al-Akhlaq wa al-siyasah, (Beirut: Markaz al-Inma’ al_Qauni, 1986) Azra, Azyumardi, Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam, (Bandung, Mizan, 1999) Bevans, Stephan B., Model of Contextual Theology, Faith and Cultures Series, (Maryknoll-New York: 1996). Boland, BJ, The Struggle of Islam in Modern Indonesian, The Hague Martinus Nijhoff, 1971, Engineer, Asghaar Ali, Islam dan Teologi Pembebasan, pent. Agung Prihantoro (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999) Engineer, Asghar Ali, “Islam and Liberation”, In Islam and Its Relevan to our Age, (Kuala Lumpur : Iqroq, 1987) Esack, Farid, Qur’an,Liberation and Pluralition an Islamic Perspectiveof interreligius solidarity again operation, (Oxford: Oneworld, 1997) Geertz, Clifford, The Interpretation of Culture, (New York: Basic Books, 1973) Hasselgrave, David J. & Edward Roman, Kontektualisasi: Makna, Metode dan Model, Terj. Stephan Suleeman, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996) 106a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) Hick, John, An Interpretation of Religion (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989), Hick, John, Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993), Hick, John, God Has Many Names (London: Macmillian, 1980), Hunter, James Davison, Stephan C. Ainly, “Introduction” dalam Making Sense of Modern Time, Peter L. Berger and the Vision of Interpretatif Sosiologi, Roudledge & Kegan Paul, (London, 1986) Izutsu, Thoshihiko, Etnicho Religious Concepts in the Qur’an (Montreal; McGill University Press, 1966) Kung, Hans, Global Responsibility: In Search of a New World Ethic, trans. John Bowden (New York, Crossroad, 1991) Macquarrie, John, Principle of Christian Theology, (London, SCM Press, 1966) Nata, Abuddin Dr. H., MA., Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Rahman, Fazlur, Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam, penyunting Ebrahim Moosa, (Jakarta, PT RajaGrafindo, Persada) Said, Nur, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005). Sastraprateja, M., dalam Pengantar, Peter L. Berger, Kabar dari Langit, Makna Teologis Dalam Masyarakat Modern, (Jakarta, LP3ES, 1991) Smith, Jonathan Z., The Harper Dictionary of Religion, (San Francisco, HarperCollin, 1995) Smith, Wilfred Cantwell, Islam in Mdern History, (Princeton, 1957) Syari’ati, Ali, On the Sosiologi of Islam, (Bandung: Mizan Press, 1984) Titaley, John A, Menuju Teologi Agama-agama yang Kontektual, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Teologi, Univ. Satya Wacana, Salatiga, 29 Nopember 2001. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 107 Teologi Islam Kontekstual-Transformatif (oleh: Nur Said) 108a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Struktur NALAR DI BALIK POLEMIK TEOLOGI DAN FILSAFAT ISLAM Tahir Sapsuha STAIN Ternate Email: ...................... ABSTRAK Tulisan ini dilatar-belakangi oleh keinginan penulis untuk menghindarkan diri dari keharusan menyuguhkan kenyataan polemik teologi dan filsafat sebagai sejarah yang mewarnai diskursus keilmuan Islam. Lebih dari itu penulis berharap bisa —meminjam istilah agama— memetik hikmah dari polemik berkepanjangan itu, baik yang berlaku di lingkungan disiplin keilmuan, maupun dalam bentuk konflik cara pandang sikap keagamaan. Penulis berupaya meraih hal itu dengan menggunakan kerangka kerja hermeneutika appropriasi yang dikenalkan oleh Paul Ricoeur. Dalam kerangka ini, polemik teologi dan filsafat Islam ditempatkan sebagai teks yang terbaca dan mau ditemukan maknanya. Tiga tahap hermeneutis yang ditawarkan Ricoeur (semantik, reflektif, eksistensial), ditemukan kemungkinan untuk memaknai polemik teologi dan filsafat itu untuk menghasilkan pemahaman-diri-eksistensial, yang tentunya setelah melalui beberapa penelusuran metodologis dan teoritis di tiap-tiap tahap tersebut (appropriasi). Munculnya pemahaman-diri-eksistensial inilah yang dalam tulisan ini penulis sebut sebagai buah dari appropriasi. Kata Kunci: Kerjasama, Nalar Teologi, Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Nalar Filsafat, Polemik, 109 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Pendahuluan Kita tidak harus malu untuk mengakui bahwa dalam Islam dan dalam agama-agama besar lainnya, hubungan antara teologi dan filsafat, baik di wilayah keilmuan-teoritis maupun di wilayah praksis-keberagamaan, jarang sekali atau bahkan tidak pernah akur dan harmonis. Hampir sepanjang masa, dua disiplin dan cara pandang keilmuan ini senantiasa terlibat dalam perseteruan, saling menonjolkan diri, saling sikut, saling hantam, dan saling berebut pengaruh di kalangan para peminat keilmuan dan para penganut agama pada umumnya. Hal ini karena masing-masing disiplin dan cara pandang keilmuan ini memiliki asumsi dasar, kerangka teori, logika, paradigma, dan struktur fundamental keilmuan yang berbeda satu sama lain. Teologi cenderung memapankan dirinya melalui postulatpostulat teoritis-teologis, yang kemudian mendominasi bagian terbesar dari model keberagamaan umat. Sedangkan filsafat terus menggonggong dan menjaga diri agar tidak terjebak dalam wilayah terlarang, yang disinyalir akan bisa menghapus daya kritis yang dimilikinya. Muhammad ‘Ãbid al-Jãbiri1 mengungkapkan bahwa seluruh khazanah intelektual Islam yang dihasilkan oleh mutakallimũn (teolog) muslim selama tahun 150 H hingga 550 H adalah dalam rangka menyerang dan memojokkan filsafat, baik sebagai disiplin keilmuan maupun sebagai metode dan epistemologi. Hingga saat ini, perseteruan serupa masih ditemukan. Singkatnya, hubungan teologi dan filsafat, —baik in the first level of discourse maupun in the second level of discourse— tidak mudah didamaikan, apalagi dikompromikan.2 Para ilmuwan Muslim sejak generasi pertama telah berupaya semampu mereka untuk mengkompromikan dua disiplin dan cara pandang keilmuan ini. Menurut Harun Nasution3 sejak semula, al-Kindi yang dikenal sebagai filosof pertama di kalangan Muhammad ‘Ãbid al-Jãbiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi; Dirãsah Tahlĩliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma‘rifah fĩ ats-Tsaqãfah al-‘Arabiyyah (Beirut: Markaz Dirãsah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990), hlm. 497-498. 2 M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.117. 3 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 43-44. 1 110a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Muslim telah berupaya memadukan antara teologi dan filsafat. Bagi al-Kindi, agama dan filsafat tidak bertentangan. Teologi merupakan cabang termulia dari filsafat, dan keduanya samasama mengarahkan kajiannya pada hakikat pertama (al-haqq alawwal). Pandangan semacam inilah yang kemudian memunculkan teori epistemologi al-Kindi yang dikenal luas hingga saat ini. Demikian pula halnya dengan generasi ilmuwan Muslim mutakhir. Mereka tetap berupaya untuk mengkompromikan teologi dan filsafat, apalagi mengingat kompleksitas fenomena keberagamaan umat yang telah memunculkan berbagai persoalan yang tidak bisa hanya didekati secara teologis saja atau secara filosofis an sich. Jika para ilmuwan dan umat Muslim masih menjebakkan diri pada pola hubungan yang dikotomis ini, maka hal itu sama artinya dengan melakukan bunuh diri intelektual dan keberagamaan. Upaya untuk mengkompromikan teologi dan filsafat tersebut merupakan semangat tulisan ini. Pada prinsipnya, berbagai terobosan baru dari perspektif dan sudut pandang yang beragam harus senantiasa dikembangkan. Upaya ini tidak boleh ditundatunda lagi, karena akibat-akibat yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin menuntut adanya kerjasama dan keharmonisan teologi dan filsafat dalam merumuskan solusi-solusi yang mendesak untuk memecahkan persoalan keagamaan dan sosial-keberagamaan umat yang semakin kompleks. Umat Islam mutlak membutuhkan upayaupaya kreatif guna mengembangkan landasan-landasan teoritis dalam merajut kerjasama dan keharmonisan dua disiplin dan cara pandang keilmuan tersebut. Menurut hemat penulis, agar dapat melihat polemik teologi dan filsafat secara lebih jernih, maka harus ditelusuri hingga struktur nalar yang membentuknya. Hanya hanya di wilayah itulah kerjasama dan keharmonisan yang dimaksud bisa diupayakan. Struktur Nalar: Pembatasan Awal Istilah ‘nalar’ dalam hubungannya dengan kebudayaan, menjadi salah satu kosa-kata penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para peminat Islamic Studies. Nalar menjadi Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 111 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) salah satu alternatif wilayah yang harus direkonstruksi, jika ingin mengakhiri masa kemunduran Islam. Untuk bisa mengupayakan kemajuan, umat Islam dituntut untuk lebih jeli dalam memotret dan menyikapi nalar yang berkembang di balik fenomena keilmuan dan keberagamaan umat. Menurut al-Jãbiri4—tokoh yang mempopuler-kan kajian tentang nalar (‘aql)—, kebangkitan dan kemajuan yang dicita-citakan oleh umat Islam tidak akan pernah bisa diwujudkan tanpa melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap nalar. Kebudayaan yang maju dan berkembang harus didasarkan atas ‘nalar yang bangkit’ (al-‘aql an-nãhidh) dan progresif. Bagi al-Jãbiri, nalar (‘aql) tidak bisa disamakan begitu saja dengan ‘pemikiran’ (al-fikr), meskipun secara kebahasaan dua istilah itu memiliki kesamaan makna denotatifnya. Dalam terminologi kontemporer, ‘pemikiran’ (al-fikr) lebih merujuk pada arti produk pemikiran ketimbang instrumen pemikiran. Arti yang semacam ini tergambar dalam ungkapan “pemikiran filosofis”, “pemikiran Eropa” dan sebagainya. Al-Jãbiri5 memandang bahwa sebagai produk pemikiran, nalar (‘aql) sama arti dan muatannya dengan ideologi, yakni sekumpulan pandangan dan pemikiran yang dihasilkan dan digunakan oleh masyarakat tertentu untuk mengungkapkan norma-norma moral, doktrin-doktrin aliran, serta ambisi sosial-politik mereka. Titik tekan penjelasan al-Jãbiri tentang nalar yang penulis terapkan dalam tulisan ini bukan dalam artinya sebagai ideologi atau produk pemikiran, akan tetapi dalam posisinya sebagai instrumen untuk memproduksi pandangan-pandangan teoritis, yang bisa jadi berupa ideologi-ideologi tertentu itu. Untuk lebih mengkontraskan perbedaan ini, perlu ditegaskan distingsi antara pemikiran sebagai alat dan pemikiran sebagai produk (lihat bagan 1-A).6 Dalam dua bentuk yang berbeda itu, al-Jãbiri menisbatkan nalar (‘aql) pada posisi pemikiran sebagai alat. Ini berarti Muhammad ‘Ãbid Al-Jãbiri. Takwĩn al-‘Aql al-‘Arabi (Berut: Markaz Dirãsãt al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1989), hlm. 5. 5 Ibid., hlm. 11. 6 Perlu digaris-bawahi bahwa pembedaan ini sebenarnya tidak bersifat esensial , akan tetapi lebih pada pertimbangan metodologis semata, demi ketajaman analisis yang diinginkan dalam tulisan ini. 4 112a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) pemikiran dalam posisinya sebagai alat-lah yang menghasilkan produk-produk pemikiran yang bersifat teoritis maupun berupa ideologi-ideologi tertentu. Meskipun bisa dilihat secara terpisah, al-Jãbiri mengakui bahwa pemikiran —baik sebagai alat maupun sebagai produk—, tidak bisa dilepaskan dari pergesekannya dengan lingkungan sosial dan kebudayaan yang melingkupinya. Pemikiran adalah produk sosial, budaya, lingkungan geografis, dan bahkan bahasa.7 Kekhasan dan karakteristik unsur-unsur pembentuk tersebut sangat menentukan kekhasan dan karakteristik pemikiran yang dihasilkannya. Nalar yang khas muncul dari persinggungannya dengan dan dibentuk oleh unsur-unsur pembentuk yang khas pula. Oleh karena itu, menurut al-Jãbiri,8 Nalar Arab (al-‘Aql al‘Arabĩ) merupakan produk dari dan dibentuk oleh budaya Arab itu sendiri.9 Dari batasan al-Jãbiri di atas bisa dipahami bahwa al-‘Aql al-‘Arabĩ dibentuk oleh kebudayaan atau kultur Arab yang khas, dan bukan oleh kebudayaan atau kultur lainnya. Kalau kemudian batasan ini disandingkan dengan penjelasan Martin Heidegger10 tentang “kekhasan”,11 maka budaya dan kultur yang khas yang dimaksudkan oleh al-Jãbiri tersebut dapat dilihat sebagai entitas yang sebangun dengan “dunia” (welt, world) yang dimaksud oleh Heidegger. Dalam pemaknaan semacam ini, kebudayaan Arab merupakan “dunia” yang darinya Nalar Arab terbentuk. Dengan kata lain, dalam “dunia” inilah Nalar Arab mewujudkan dirinya (mengada; menjadi ada). Demikian juga, di dalam dan karena “dunia” itu pula Nalar Arab bereksistensi dan menjadi autentik. Muhammad ‘Ãbid Al-Jãbiri. Takwĩn al-‘Aql, hlm. 12. Ibid, hlm. 13-14. 9 Batasan-batasan yang digariskan al-Jãbiri inilah yang penulis gunakan untuk membatasi apa yang nantinya disebut Nalar Teologi dan Nalar Filsafat. Tentu saja batasan-batasan itu perlu sedikit direnovasi dan disesuaikan dengan pembahasan yang dikembangkan dalam tulisan ini. 10 Martin Heidegger, Being and Time, trans. Joan Stambaugh (New York: State University of New York Press, 1996), hlm. 42. 11 Heidegger berpandangan bahwa “kekhasan” dibutuhkan oleh manusia untuk bisa menjadi Dasein, dalam arti untuk bisa bereksistensi sesuai dengan “kekhasannya” sebagai Mengada yang mampu bertanya tentang Adanya. 7 8 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 113 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) “Dunia” tersebut (yakni kebudayaan Arab) merupakan poros eksistensial dari Nalar Arab, yang menjamin —namun sekaligus mengikat dan membatasi— kebebasannya untuk bereksistensi. Hanya di dalam dunia semacam itulah Nalar Arab dapat mewujudkan autentisitasnya. Lewat pemaknaan kebudayaan sebagai “dunia”, maka kita bisa sampai pada premis bahwa segala bentuk realitas (Mengada) yang kita temukan dalam kehidupan ini memiliki “dunia”-nya yang khas, yang menjadi unsur determinan bagi eksistensi dan keberadaannya. Kalau premis ini dikenakan pada teologi dan filsafat, maka bisa dikatakan bahwa teologi dan filsafat juga merupakan entitas yang memiliki “dunia”-nya sendiri. Hal ini akan ditemukan juga ketika kita mengatakan bahwa politik, sepak bola, catur, artis, dan sebagainya merupakan entitas-entitas yang juga memiliki dan dilingkupi oleh dunianya masing-masing. Oleh karena itu kita menyebut adanya dunia politik, dunia artis, dunia sepak bola, dunia catur, dan seterusnya. Di sini, “dunia” tidak mengacu kepada ruang spesifik yang bersifat fisik, akan tetapi merupakan wahana yang melingkupi dan menentukan karakteristik keberadaan tiap-tiap realitas (Mengada) itu. Terkait dengan teologi dan filsafat, dunia tersebut dapat dilihat dalam dua wilayah yang berbeda. Sekali lagi, meminjam kebiasaan al-Jãbiri, pembagian semacam ini hanya dimaksudkan demi analisis yang berlangsung dalam pembahasan ini, dan tidak bersifat esensial. Di wilayah yang pertama, ‘dunia’ merujuk pada realitas normatif yang mendeter-minasi struktur nalar teologi maupun filsafat. Sedangkan di wilayah kedua, ‘dunia’ berupa realitas historis yang menjadi unsur-unsur penopangnya (lihat bagan 1-B). Namun demikian, pemilahan secara normatif dan historis ini hanya berlaku jika di-lihat sebagai bentuk pure science (keilmuan murni) saja, yakni sebagai kerangka keilmuan dasar yang melandasi keberadaannya. Sedangkan dalam bentuk applied science (keilmuan praktis), realitas normatif dan historis tersebut saling berkait-kelindan dan hampir tidak bisa —untuk tidak mengatakan sama sekali tidak bisa— dipisahkan.12 Istilah dan pembedaan antara yang normatif dan historis 12 114a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Dari titik ini tidak sulit untuk memahami bahwa keterkaitan dan kejumbuhan realitas normatif dan historis yang khas, yang masing-masing melingkupi teologi dan filsafat akan menjadi unsur penopang dan pembentuk bagi munculnya Nalar Teologi dan Filsafat. Pada masing-masingnya, terdapat karakteristik dan kekhasan sendiri-sendiri pula (lihat bagan 1-C). Nalar inilah yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran teologi dan filsafat, baik yang berupa sejarah maupun alat analisis (tool of analysis). Nalar ini pula-lah seharusnya yang “bertanggungjawab” atas munculnya polemik berkepanjangan antara teologi dan filsafat. Secara bersamaan, titik ini pula yang menjadi awal bagi terbukanya kemungkinan untuk mengkompromikan dua disiplin dan cara pandang keilmuan yang berbeda tersebut. 7 BAGAN: STRUKTUR NALAR TEOLOGI DAN BAGAN:ȱSTRUKTURȱNALARȱTEOLOGIȱDANȱ BAGANȱ Al-fikr sebagai alat untuk memproduksi pemikiran Al-fikr sebagai produk pemikiran BAGANȱ BAGANȱ NALARȱTEOLOGIȱ DANȱFILSAFATȱ NALARȱTEOLOGIȱ DANȱFILSAFATȱ YANGȱ“KHAS”ȱ (al-fikr sebagai alat untuk memproduksi pemikiran) Nalar Teologi: Dogmatis-Pre-Reflektif-Bayãnƭ Nalar Teologi: Dogmatis-Pre-Reflektif-Bayãnĩ Bagian akan penulis awali awali dengan mengajukan berikut: Bagian iniini akan penulis dengan pertanyaan mengajukan “Jika nalar teologi“Jika dan filsafat untukfilsafat menghasilkan pemikiranpertanyaan berikut: nalar—sebagai teologialatdan —sebagai pemikiran teologis dan filosofis— dibentuk oleh realitas normatif historis alat untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran teologisdan dan yang khas, maka seperti apakah bentuk masing-masing realitas normatif filosofis— dibentuk oleh realitas normatif dan historis yang khas,dan historis apakah itu, dan bagaimanakah karakter nalar realitas yang dihasilkan oleh dan realitas maka seperti bentuk masing-masing normatif tersebut? Masing-masing realitas normatif dan historis yang melatar-belakangi terbentuknya teologidan danjuga filsafat, karakter masing-masing nalar yang digunakan oleh Fazlurnalar Rahman olehserta Amin Abdullah untuk menengahi dihasilkannya akan penulis telusuri berikut ini. Kita mulai dengan nalar teologi, hubungan yang saling berkait-kelindan antara agama dan kepentingan sosialkemasyarakatan, antara yang sakral dan yang profan. Lebih lanjut baca; dan kemudian disusul dengan penjelasan tentang nalar filsafat. “Rekonstruksi Tidak Metodologi Agama dalam Masyarakat dantiga ada agama yang tidak mempunyai ajaran Multikultural ketuhanan. Dalam Multireligius”, dalam, Abdullah, M. Amin, dkk. Rekonstruksi Metodologi Ilmuagama monoteis (Abrahamic Religion), Tuhan berada pada poros yang menjadi Ilmu Keislaman: Seri Kumpulan Pidato Guru Besar. Yogyakarta: Suka Press, sentral keberadaan (eksistensi) segala yang ada di dunia ini. Tuhan adalah 2003), hlm. 5. pencipta langit dan bumi dan bertahta “di atasnya”, namun bukan bagian darinya. Tuhan menjadi tempat bergantung bagi segala eksistensi.13 Demikian gambaran Fikrah, Vol. I, No.yang I, Januari-Juni 2013 umum diketahui dari ajaran Teologi berbagai agama, termasuk dalam115 teologi Islam. Sebagaimana halnya agama-agama monoteis, teologi Islam mengajarkan Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) historis itu, dan bagaimanakah karakter nalar yang dihasilkan oleh realitas tersebut? Masing-masing realitas normatif dan historis yang melatar-belakangi terbentuknya nalar teologi dan filsafat, serta karakter masing-masing nalar yang dihasilkannya akan penulis telusuri berikut ini. Kita mulai dengan nalar teologi, dan kemudian disusul dengan penjelasan tentang nalar filsafat. Tidak ada agama yang tidak mempunyai ajaran ketuhanan. Dalam tiga agama monoteis (Abrahamic Religion), Tuhan berada pada poros yang menjadi sentral keberadaan (eksistensi) segala yang ada di dunia ini. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan bertahta “di atasnya”, namun bukan bagian darinya. Tuhan menjadi tempat bergantung bagi segala eksistensi.13 Demikian gambaran umum yang diketahui dari ajaran Teologi berbagai agama, termasuk dalam teologi Islam. Sebagaimana halnya agama-agama monoteis, teologi Islam mengajarkan bahwa kebenaran pengetahuan tentang Tuhan dapat dicapai melalui wahyu. Al-Quran sebagai wahyu tidak hanya memuat aturan-aturan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan penjelasan tentang Tuhan dan eksistensi-Nya, meskipun dalam porsi yang lebih sedikit.14 Keberadaan Tuhan dan pengetahuan tentang-Nya yang diperoleh lewat wahyu inilah yang menjadi realitas normatif bagi nalar teologi Islam. Penjelasan-penjelasan wahyu (alQuran) tentang Tuhan menjadi landasan bagi para teolog untuk menempatkan-nya sebagai satu-satunya sumber kebenaran mengenai pengetahuan tentang Tuhan. Para teolog meyakini bahwa Tuhan telah mengintrodusir diri (eksistensi)-Nya kepada manusia melalui kalãm-Nya, yang sepenuhnya termaktub di dalam al-Quran. Sementara yang menjadi realitas historis bagi nalar teologi Islam dapat dirunut dari berbagai peristiwa historis yang melingkupi lahirnya teologi Islam atau yang sering disebut Ilmu Kalãm. Di titik ini harus digaris-bawahi bahwa teologi Islam atau Franz Magnis Suseno, Menalar Tuhan (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 39. 14 Fazlur Rahman, Islam, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 116. 13 116a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Ilmu Kalãm merupakan produk pemikiran umat Islam tentang persoalan-persoalan ketuhanan dalam penggal waktu tertentu. Sama halnya dengan fiqh dan tasawuf, Ilmu Kalãm tidak dikenal pada masa Nabi. Meskipun Nabi Muhammad beserta para nabi dan rasul lainnya membawa ajaran-ajaran teologis, namun mereka tidak pernah disebut sebagai teolog (mutakkallim). Ilmu Kalãm muncul setelah Muhammad wafat. Dari berbagai literatur sejarah Islam diketahui bahwa kelahiran ilmu Kalãm tidak bisa dilepaskan dari pergolakan politik dalam tubuh umat Islam setelah terbunuhnya khalifah ketiga ‘Utsmãn ibn ‘Affãn. Pergolakan politik ini mengkristal pasca terjadinya arbitrase (tahkĩm) antara ‘Ali ibn Abi Thãlib dan Mu‘ãwiyah ibn Abu Sufyãn. Pertikaian politik ini dengan cepat menjelma menjadi persoalan teologis setelah segolongan umat berpendapat bahwa hukum yang sah dan benar hanyalah hukum yang diputuskan Allah dan telah digariskan-Nya di dalam alQur’ãn. Mereka juga berpandangan bahwa hukum yang digunakan dalam arbitrase tersebut adalah hasil keputusan manusia.15 Dalil yang mereka gunakan adalah ayat 44 dari surat al-Mãidah yang berbunyi: “Barangsiapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orangorang yang kafir”. Sejak saat itu, penentuan seseorang apakah akan disebut kafir atau tidak bukan lagi semata-mata menjadi persoalan politik, akan tetapi soal teologi. Demikian juga perumusan konsepsi tentang ĩmãn, nifãq, dosa besar, dan persoalan kebebasan perbuatan manusia di hadapan Allah. Disusul pula dengan munculnya aliran-aliran seperti Syi‘ah, Khawãrij, Murji‘ah, Mu‘tazilah, Asy‘ariyyah dan sekte-sekte lainnya. Latar historis yang demikian itu mengandaikan bahwa produk keilmuan Kalãm sangat kental dengan suasana pertikaian politik saat itu, sehingga tanpa terasa persoalan tauhĩd dan ‘aqĩdah yang digagas oleh para teolog juga sangat terkait dengan kepentingan politik mereka.16 Perkembangan ilmu Kalãm berikutnya jelas tidak immune Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.5-7. 16 Fazlur Rahman, Islam....., hlm. 38 dan 126) 15 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 117 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) dari suasana konflik antar berbagai kelompok yang berkepentingan di atas. Kenyataan inilah yang mengundang banyak kritik dari para pemikir terhadap rancang bangun keilmuan Kalãm klasik. Abu Hãmid al-Ghazãli —yang pada batas-batas tertentu dapat disebut sebagai seorang teolog (mutakallim)—, mengkritik keberadaan ilmu Kalãm yang menurutnya hanya menyesatkan dan mempunyai bahaya yang lebih besar dari manfaat yang dikandungnya. Menurutnya, konsep al-‘aqĩdah al-islãmiyyah (akidah Islam) yang digambarkan dalam ilmu Kalãm tidak akan dapat mengantarkan manusia mendekati Allah dan kepada pengetahuan yang hakiki. Al-Ghazãli menambahkan bahwa hanya model ‘aqĩdah tasawuf-lah yang dapat mengantarkan seseorang kepada tujuan itu.17 Selain al-Ghazãli, al-Jãbiri (1990: 497-498) juga menilai bahwa tujuan terpokok ilmu Kalãm adalah untuk mempertahankan doktrin-doktrin kelompok dari kecaman lawan-lawannya dan sekaligus menolak pandangan kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya. Tujuan ini dilakukan dengan penyingkapan secara terus-menerus segala bentuk ketidakkonsistenan pihak lawan melalui logika dan metode-metode perdebatan yang dikembangkan dalam Ilmu Kalãm. Selain itu, banyak juga kritikan-kritikan lain yang tak kalah pedasnya terhadap rancang bangun keilmuan Kalãm.18 Dari keterkaitan antara dua wilayah berbeda yang melingkupi keberadaan teologi Islam itu dapat dilihat betapa “dunia” teologi telah memunculkan nalar teologi yang bersifat dogmatis-pre-reflektif. Nalar yang dogmatis-pre-reflektif ini selanjutnya melahir-kan paham-paham, ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip teologi yang mendominasi, menuntut loyalitas dan kesetiaan dari para penganutnya, serta dibekukan dalam prinsip-prinsip dan dogma-dogma teologis yang diterima dan dipraktekkan secara turun-temurun. Dalam struktur yang dominan dan baku ini nalar Teologi menjadi instrumen yang memunculkan paham-paham dan aliran-aliran teologi di atas. Merujuk pada alMahmud Hamdi Zaqzuq, Al-Ghazãlĩ; Sang Sufi Sang Filosof, terj. Ahmad Rofi‘ ‘Utsmani (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 2-7 18 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 127-128. 17 118a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Jãbiri,19 struktur Nalar Teologi seperti ini disebut sebagai al-‘Aql al-Mukawwan. Menurutnya, nalar teologi yang dominan ini bisa dianalisis secara obyektif, lantaran ia bisa diamati dalam bentuk konsep, ajaran dan prinsip teologi yang telah baku. Dominasi nalar teologi yang bersifat dogmatis-pre-reflektifbayãni itu menyebab-kan para teolog lebih mengedepankan sikap apologis dan lebih mengutamakan kebenaran doktrin yang terdapat dalam wahyu, serta menyalahkan semua pandangan yang tidak sesuai dengannya. Sikap itu muncul karena mereka menerima mentah-mentah apa yang telah diterima secara dominan, tanpa mempertimbangkan atau merefleksikannya lebih lanjut. Sebenarnya sikap semacam ini adalah sah-sah saja dan bahkan diperlukan. Tanpa adanya justifikasi kebenaran —atau sering disebut sebagai truth claim)—, teologi akan terjebak pada kesiasiaan belaka. Akan tetapi, sikap terlalu memutlakkan kebenaran atau menggantungkan kebenaran mutlak itu kepada transcendent aspect20 sama artinya dengan membunuh keberadaan (eksistensi) manusia. Sikap itu menutup kemungkinan-kemungkinan baginya untuk mengembangkan eksistensinya lebih lanjut. Bukankah hanya melalui adanya kemungkinan-kemungkinan dan pilihanpilihan sesuatu bisa berkembang dan menjadi penuh? Nalar Filsafat: Kritis-Reflektif-Burhãnĩ Jika demikian halnya dengan nalar teologi, maka bagaimanakah yang terjadi dengan nalar filsafat? Berbeda dengan ajaran yang dikembangkan oleh agama yang menempatkan Tuhan di pusat eksistensi, filsafat berangkat dari pertanyaan tentang unsur-unsur apakah yang berada di balik alam semesta ini. Dalam perbendaharaan ontologi dan metafisika, unsur tersebut disebut sebagai Ada (Being). Being tidak bisa disamakan begitu saja dengan Tuhan. Pertanyaan tentang Being ini merupakan kutub pendulum normatif dari dunia yang membentuk nalar filsafat. Manusia adalah makhluk selalu bertanya tentang diri dan keberadaannya. Hal itu dimungkinkan karena manusia adalah Muhammad ‘Ãbid Al-Jãbiri. Takwĩn......, hlm. 15-16. Fazlur Rahman, “Approach to Islam in Religious Studies: Review Essays”, dalam Approaches to Islam in Religious Studies, Martin, Richard C. (ed). (Tuscon: The University of Arizona Press, 1985), hlm. 194. 19 20 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 119 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) satu-satunya “Mengada” yang mampu bertanya tentang “Ada” dan mempertanyakan keberadaannya. Kenyataan normatif pada filsafat yang berupa pertanyaan tentang Being tersebut telah pula menjadi guratan perjalanan filsafat di ranah historis. Manusia telah bertanya tentang Being sejak masa Yunani Kuno dan belum berhenti hingga saat ini. Mengakhiri masa mitologi Yunani Kuno, Heraklitus (540480 SM) menyebutkan bahwa Being itu adalah Akal Universal atau Hukum Universal, yakni sistem yang menguasai alam. Heraklitus menyebut Akal atau Hukum Universal itu sebagai Logos. Menurutnya, manusia akan mampu memahami fenomenafenomena alam ini —termasuk asal-usul kejadiannya— secara benar, jika ia melibatkan diri bersamanya. Baginya, agama yang benar adalah kesesuaian antara akal yang dimiliki oleh masingmasing individu manusia dengan Hukum atau Akal Universal yang berjalan di alam. Berbeda dengan Heraklitus, Anaxagoras (570-526 SM) menyebut Akal Universal itu sebagai Nous. Menurutnya, Nous adalah Akal Universal yang mengatur alam raya, menjadi penyebab bagi segala sesuatu yang ada di alam ini, dan -yang terpenting- terpisah dari alam ini. Menurut al-Jãbiri,21 pemikiran Anaxagoras inilah yang kemudian melatar-belakangi revolusi Socrates, dan berikutnya Plato dan Aristoteles. Sedangkan sebaliknya, Pemikiran Heraklitus tentang logos, lebih banyak diadopsi oleh paham-paham yang mengumandangkan wahdah al-wujũd, yang menganggap adanya kesatuan antara Ada dan realitas, sebagaimana ditemukan dalam filsafat illuminasionis dalam Islam. Sejarah pencarian Being masih dapat diperpanjang lagi hingga zaman ini. Akan tetapi kita tidak akan berlama-lama dalam hal itu, karena yang ingin dibahas adalah nalar filsafat yang muncul dari pergesekan antara realitas normatif dan historis dunia filsafat. Di sini setidaknya bisa dikemukakan beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Pertama, kajian dan analisis yang dilakukan dalam filsafat dimulai dari mempertanyakan realitas yang ditemukan secara langsung dalam kehidupan di Muhammad ‘Ãbid Al-Jãbiri. Takwĩn....., hlm. 18-20. 21 120a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) dunia ini. Realitas-realitas itu, baik yang berupa fenomena alam maupun fenomena sosial, dilihat sebagai realitas otonom yang mengandung keterkaitan langsung dengan akal -baik dalam arti universal maupun individual. Kedua, kajian terhadap realitas itu diarahkan pada perumusan ide-ide abstrak yang bersifat fundamental (fundamental ideas), yang membantu akal manusia untuk memahami kenyataan alam dan sosial yang ditemuinya. Ide-ide itulah yang diterjemahkan dalam bentuk istilah teknis kefilsafatan sebagai al-falsafah al-ũlã, substansi, hakikat dan esensi. Ketiga, penerjemahan yang bersifat abstrak itu didasarkan pada keyakinan bahwa akal mampu mengungkap dan menjelaskan kenyataan alam dan sosial yang bersifat abstrak tersebut. Keempat, dengan demikian, secara tidak langsung dunia filsafat telah melatih para filosof untuk senantiasa bersikap kritis, dan tidak terjebak dalam diminasi nalar tertentu. Kelima, sikap kritis itu dilandasi dengan penelitian filosofis yang berkesinambungan, yang dilakukan melalui refleksi-refleksi keilmuan yang sistematis. Dan keenam, sikap kritis-reflektif inilah yang akan mampu menjamin kebebasan intelektual dan sikap inklusif terhadap kebenaran-kebenaran yang diterima secara dogmatis dan fanatis oleh masyarakat pada umumnya.22 Dengan demikian, Nalar Filsafat yang bersifat kritisreflektif-burhãnĩ ini, menjadi unsur penopang yang paling utama bagi manusia untuk mewujudkan eksistensinya. Bagi al-Jãbiri23 nalar seperti inilah yang sangat dibutuhkan untuk memunculkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah baru. Hal itu karena nalar yang telah mendominasi kehidupan sosial-keberagamaan dalam bentuk institusi-institusi dan kelembagaan agama dan sistem teologi yang sudah mapan (ortodoksi) tidak akan bisa dikembangkan, direvitalisasi dan direkonstruksi tanpa bantuan dari nalar filsafat yang bersifat kritis-reflektif-burhãnĩ. Muhammad ‘Ãbid Al-Jãbiri., Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi; Dirãsah Tahlĩliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma‘rifah fĩ ats-Tsaqãfah al-‘Arabiyyah (Beirut: Markaz Dirãsah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990), hlm. 27. Baca juga, M. Amin Abdullah, “Rekonstruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam, Abdullah, M. Amin, dkk. Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman: Seri Kumpulan Pidato Guru Besar (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 9-10. 23 Muhammad ‘Ãbid Al-Jãbiri. Takwĩn, hlm. 16. 22 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 121 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Polemik Teologi dan Filsafat Polemik yang terjadi antara teologi dan filsafat akan dapat dilihat secara lebih jernih pada level nalar yang melatarbelakanginya. Struktur nalar teologi yang bersifat dogmatisprereflektif-bayãnĩ akan melahirkan ketegangan-ketegangan tertentu jika dihadapkan dengan struktur nalar filsafat yang bersifat kritis-reflektif-burhãnĩ. Ketega- tersebut hanya berlangsung pada wilayah epistemologi, tetapi juga di wilayah ontologi. Sebagai nalar yang mendominasi sistem pengetahuan umat Islam, nalar teologi tidak jarang memaksa nalar filsafat untuk memposisikan dirinya di bawah kebenaran wahyu, yang justru hanya menghilangkan kadar kritis-reflektif yang dimilikinya. Akal dipaksa untuk membuktikan kebenaran wahyu yang telah dianggap mutlak. Dalam teologi agama-agama, hal ini sering disebut sebagai pertanggung-jawaban iman secara rasional. Ada tuntutan untuk “mencari pengertian” tentang iman, yang disebut fides quaerens intellectum.24 Dalam peradaban Islam, perdebatan teologi dan filsafat dapat dilacak sejak dari perdebatan antara Abu Sa‘id asy-Syirãfi (893-979) seorang teolog Mu‘tazilah dengan Abu Bisyr Matta (870-940), guru filsafat al-Fãrãbi yang beraliran Nestorian.25 Perdebatan ini mengental pada masa al-Fãrãbi yang menempatkan Teologi (juga Jurisprudensi) pada rangking bawah setelah ilmuilmu Filsafat dalam hierarki ilmu yang disusunnya.26 Al-Fãrãbi beralasan bahwa secara metodologis, pembagian kesimpulan teologi tidak didasarkan atas prinsip-prinsip logika yang benar dan teruji secara rasional, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Teologi tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang meyakinkan, tapi baru pada tahap mendekati keyakinan.27 Oleh sebab itu, teologi hanya cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat awam (baca: masyarakat non-filosofis) dan bukan untuk Franz Magnis Suseno, Menalar Tuhan.., hlm. 22. Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam, terj. M. Amin Abdullah (Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 12-13. 26 Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu, terj. Purwanto. Bandung: Mizan, 1998), hlm. 145-148. 27 Osman Bakar, Tauhid dan Sains, terj. Yuliani Liputo (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 149. 24 25 122a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) golongan lainnya. Pada kenyata-annya, klasifikasi yang disusun oleh al-Fãrãbi inilah yang banyak dianut oleh pada filosof Islam berikutnya, seperti Ibn Sinã (980-1037), Ibn Thufail (w. 1186), Ibn Rusyd (1126-1198), dan Ibn Khaldun (1332-1406). Kenyataan ini pula yang telah menaikkan pamor Filsafat di atas Teologi dalam Islam. Puncak ketegangan Teologi dan Filsafat terjadi pada masa al-Ghazãli (1058-1111). Sebagai wakil dari teolog (mutakallim), al-Ghazãli menyerang filsafat, khususnya pemikiran filsafat al-Fãrãbi dan Ibn Sinã melalui karyanya Tahãfut al-Falãsifah dan kemudian dipertegas dalam al-Munqidz min adh-Dhalãl.28 Meskipun demikian, hujatan yang dilancarkan oleh al-Ghazãli ini tidak sampai menyentuh wilayah di luar metafisika, karena alGhazãli29 masih mengakui pentingnya logika dalam penjabaran ajaran-ajaran agama. Namun sayangnya, hujatan itu telah terlalu dibesar-besarkan oleh umat Islam, sehingga menimbulkan sikap antipati dan mengenyampingkan filsafat dalam diskursus keilmuan Islam. Jika kemudian al-Ghazãli sering juga dituduh dan dipersalahkan sebagai biang kerok tumpulnya nalar kritis dalam Islam, maka sudah selayaknya kenyataan itu dilihat sebagai suatu keharusan sejarah, demi mengasah ulang dominasi nalar yang melatar-belakangi keagamaan Islam secara umum. Terkait dengan perdebatan yang bersifat ontologismetafisik ini, maka polemik itu bisa dilihat sebagai perdebatan dalam hal bagaimana menempatkan Tuhan, manusia dan alam, sebagai tiga kutub yang ditemui dalam kehidupan ini. Dalam nalar teologi, hubungan timbal balik terjadi antara Tuhan dan manusia, sebagaimana yang dapat pula ditemukan pada model keberagamaan pada umumnya, —terutama pada paham mistik. Kenyataan ini bukan berarti menafikan adanya kutub alam sebagai kutub ketiga, akan tetapi, dalam relasi Tuhan dan manusia ini, alam berada pada posisi justifikatif terhadap kebenaran pengetahuan manusia tentang Tuhan. Dengan kata lain, alam tidak dipahami kecuali dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang Tuhan Abu Hãmid Al-Ghazãli, Tahãfut al-Falãsifah, Sulaimãn Dunyã (ed.). (Mesir: Dãr al-Ma‘ãrif, 1966), hlm. Th. 29 Abu Hãmid Al-Ghazãli, Al-Munqidz min adh-Dhalãl, Musthafã Abu al-’Alã (ed.). Berut: al-Maktabah as-Sab‘iyyah, t.t., hlm. 49. 28 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 123 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) (lihat bagan 2-A). Kenyataan inilah yang -menurut al-Jãbirimelingkupi keberagamaan Islam pada umumnya.30 Sedangkan nalar filsafat yang bersifat kritis itu, tidak memposisikan Tuhan sebagai obyek yang harus diketahui, akan tetapi memposisikannya sebagai alat yang menjustifikasi kebenaran pengetahuan manusia terhadap alam semesta ini (lihat bagan 2-B). Sebagaimana telah disebutkan di atas, nalar inilah yang melatar-belakangi peradaban Yunani Kuno dan Eropa Modern hingga saat ini. Tuhan tidak dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari manusia, atau diposisikan sebagai puncak pengetahuan manusia, akan tetapi difungsikan sebagai “pembenaran” bagi pengetahuannya. Implikasi cara pandang yang demikian itu, akan dapat ditemui langsung dalam kecenderungan filsafat yang empiris, dan kecenderu-ngan teologi yang idealis. 16 Bagan: Perbandingan Proses Pembentukan Nalar Teologi dan Filsafat Bagan 2-a. Nalar Teologi Bagan 2-a. Nalar Filsafat Tuhan Tuhan Fungsi justifikatif manusia alam alam manusia Fungsi justifikatif Teologi dan Filsafat: Polemik, Kerjasama, dan Kemungkinan Apropriasi Dewasa ini, para pakar dan peminat Islamic dan Studies Kemungkinan telah berupaya untuk Teologi dan Filsafat: Polemik, Kerjasama, sebisa mungkin mendamaikan kecenderungan yang berbeda dari dua nalar Apropriasi tersebut. Mereka beranggapan bahwa polemik dan perdebatan yang selama ini Dewasa ini, para pakar dan peminat Islamic Studies telah terjadi, sudah tidak saatnya lagi untuk dibesar-besarkan, apalagi diteruskan. berupaya untuk sebisa mungkin mendamaikan kecenderungan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, berikut dengan akibatyang berbeda dari dua nalar tersebut. Mereka beranggapan akibat positif dan negatif yang muncul darinya, dan ditambah lagi semakin berkembangnya persoalan sosial-keagamaan, mengharuskan adanya kerjasama Muhammad Al-Jãbiri. Takwĩn...., hlm.keberagamaan 29. antara teologi‘Ãbid dan filsafat, dalam menatap persoalan umat Islam di 30 berbagai lini. Belum lagi jika perkembangan itu dikaitkan dengan pluralisme 124a keyakinan dan pandangan hidup, globalisasi budaya, keragaman kepercayaan dan Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 kebenaran yang menghantui kehidupan masyarakat luas. Jika ingin tanggap terhadap persoalan umat, maka kerjasama tersebut harus segera diwujudkan dan Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) bahwa polemik dan perdebatan yang selama ini terjadi, sudah tidak saatnya lagi untuk dibesar-besarkan, apalagi diteruskan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, berikut dengan akibat-akibat positif dan negatif yang muncul darinya, dan ditambah lagi semakin berkembangnya persoalan sosialkeagamaan, mengharuskan adanya kerjasama antara teologi dan filsafat, dalam menatap persoalan keberagamaan umat Islam di berbagai lini. Belum lagi jika perkembangan itu dikaitkan dengan pluralisme keyakinan dan pandangan hidup, globalisasi budaya, keragaman kepercayaan dan kebenaran yang menghantui kehidupan masyarakat luas. Jika ingin tanggap terhadap persoalan umat, maka kerjasama tersebut harus segera diwujudkan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berangkat dari adanya kerjasama yang ingin diwujudkan itu dan dari persoalan ontologis-metafisik yang diperdebatkan oleh teologi dan filsafat, penulis melihat kemungkinan untuk bisa mewujudkan polemik dan kerja-sama itu menjadi sesuatu yang bisa dimiliki melalui pembacaan kembali (re-saying) terhadapnya, guna menga-rahkannya pada cakrawala baru. Cakrawala baru itu adalah makna yang dipetik dari polemik dan kerjasama itu, untuk bisa dimengerti dan dipahami secara eksistensial, yakni sebagai suatu cara alternatif untuk memahaminya. Tentu saja, apa yang penulis maksud dengan appropriasi di sini masih debatable dan harus diperkaya lebih lanjut. Pada kenyataannya, Tuhan yang ingin dipahami dan dijelaskan dalam teologi, maupun Logos, Nous, al-‘Aql al-Kullĩ, al-Qãnũn al-Kullĩ, Being, dan sederet istilah lainnya yang merujuk pada hal yang sama, yang hendak dijelaskan dan dipahami dalam filsafat, benar-benar tidak bisa dibuktikan secara empiris dan objektif oleh rasio, dan juga tidak bisa diyakinkan eksistensi dan keberadaannya oleh wahyu. Oleh sebab itu, Tuhan -jika Nalar Filsafat tidak keberatan dengan sebutan itu- benar-benar merupakan misteri. Tuhan adalah terlalu kaya (baca: tidak bisa dibatasi), sehingga tidak mungkin hanya satu tradisi keagamaan atau tradisi pemikiran-pun yang dapat mengungkap, menjelaskan dan menggambarkan secara menyeluruh “kekayaan”-Nya itu. Hal itu dikarenakan tradisi keagamaan atau keilmuan bersifat terbatas. Sehingga tidak mungkin jika sesuatu yang terbatas mampu Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 125 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) menjelaskan dan memahami sesuatu yang tidak terbatas. Prinsip ini selayaknya melandasi penerimaan atas keragaman pengalaman ketuhanan dan menjauhkan diri dari klaim-klaim kebenaran yang eksklusif. Dari prinsip ini, monopoli kebenaran dipertanyakan, dan kekhasan pemahaman dan pluralisme dikedepankan, guna memurni-kan pandangan kita terhadap polemik yang terjadi itu. Dalam prinsip ini, polemik teologi dan filsafat itu dilihat menyerupai “teks” yang mengandung struktur maknanya sendiri. Makna tersebutlah yang hendak digali dan ditemukan, guna dimiliki dan dikembangkan. Oleh sebab itu, tugas utama yang dijalankan di sini tidak lagi dimengerti sebagai upaya untuk mencari kesamaan dan keselarasan antara pemahaman penafsir (kita sebagai peneliti) dan maksud pengarang (makna yang terkandung dalam polemik itu), karena hal itu hanya akan menjebakkan kita pada kutub subjektif-objektif; menerima atau tidak menerima; dan akhirnya hanya akan memenangkan salah satunya -teologi atau filsafat- saja. Akan tetapi, tugas utama itu mirip-mirip dengan hermeneutika-appropriasi, yang pertama, mencari dan menemukan dinamika yang dituju oleh keberadaan polemik itu dan struktur nalar yang berada di belakangnya; dan kedua, mencari di dalam polemik itu kemampuan masing-masing untuk memproyeksikan diri keluar dari dirinya dan melahirkan suatu “dunia” yang khas miliknya, dan selaras dengan makna yang ditujunya.31 Dua tugas utama itu telah dimulai sejak awal pembahasan ini. Gambaran tentang struktur nalar dan polemik yang terjadi antara teologi dan filsafat, merupakan upaya pada level semantik, guna menelusuri polemik itu secara struktural, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian, upaya pada level refleksi, dila-kukan dengan mengungkapkan kemungkinan adanya kerjasama antara dua disiplin dan cara padang keilmuan itu, yang bisa dimulai dari struktur nalar yang berada di balik polemik tersebut. Selanjutnya, upaya pada level eksis-tensial-lah yang penulis maksudkan dengan kemungkinan appropriasi di atas, agar polemik dan kerjasama itu bisa dilandasi dengan kerangka Untuk Prinsip hermeneutika yang mendasari ini, lihat: E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 107-108. 31 126a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) pandang hermeneutis, guna menghindarkan diri dari dikotomi subjektif-objektif yang seringkali menjebak, dan mengarahkan polemik tersebut kepada pemaham-diri yang mendewasakan. Tahap penting antara penjelasan yang dimunculkan melalui analisis struktural terhadap polemik itu dan perwujudan pemahaman-diri (eksistensial) melalui appropriasi ini, ditenggarai oleh sikap memposisikan polemik itu sebagai teks yang mengandung struktur maknanya sendiri. Apakah makna dari polemik dan kerjasama itu, yang bisa diungkapkan di sini? Yaitu bahwa teologi dan filsafat benar-benar entitas otonom yang memiliki kekhasannya dan karakteristik masing-masing, yang tidak seharusnya direduksi pada salah satunya saja. Makna inilah kemudian yang didialogkan dengan kenyataan pluralisme dan relativitas kebenaran yang kita temui dalam horizon kehidupan keberagamaan dan keilmuan dewasa ini. Dua kutub ini hendaknya dilihat secara dialektis, sebagai dua hal yang saling mengisi, dan menandai pertemuan antara makna yang terkandung di balik polemik dan kerjasama itu dengan dunia konkrit yang kita hadapi dewasa ini. Pembauran ini menjadi niscaya karena kita tidak mungkin mengambil alih polemik itu secara keseluru-han ataupun meninggalkan dunia aktual yang di dalamnya kita hidup saat ini. Dengan kata lain, pembauran itu akan mampu menjaga intensitas ritme dari dua kutub tersebut, tanpa harus menolak atau melibatkan diri dalam polemik itu, ataupun menutup mata dari realitas pluralisme kebenaran yang ada saat ini. Pada tahap inilah dunia kita -sebagai “pembaca” atas polemik dan kerjasama itu- mengalami transformasi, yang terjadi berkat adanya pengaruh yang dibaca dan dihayati dari kenyataan itu, sehingga membantu untuk mencapai pemahaman-diri yang lebih baik (appropriasi). Dan dengan pemahaman-diri eksistensial melalui appropriasi ini, manipulasi-manipulasi kebenaran, baik yang mengatas-namakan teologi maupun filsafat, bisa dibongkar, dan potensi konflik dari polemik itu dapat diminimalisir. Bukankah keberlanjutan polemik teologi dan filsafat itu disebabkan oleh -salah satunya- tiadanya bentuk pemahaman-diri eksistensial yang bisa dimunculkan dari pembacaan terhadapnya? Hal itu disebabkan oleh sikap kita yang benar-benar memposisikan diri sebagai pembaca yang hanya Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 127 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) sekedar ingin mengetahui polemik itu sebagaimana adanya, namun tidak bisa -meminjam bahasa agama- mengambil hikmah darinya demi mewujudkan pemahaman-diri eksistensial tersebut.*** 128a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Daftar pustaka Abdullah, M. Amin. Falsafah Kalam di Era Postmodernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995 _____. Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996 _____. “Rekonstruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam, Abdullah, M. Amin, dkk. Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman: Seri Kumpulan Pidato Guru Besar. Yogyakarta: Suka Press, 2003 Al-Jãbiri, Muhammad ‘Ãbid. Takwĩn al-‘Aql al-‘Arabi. Berut: Markaz Dirãsãt al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1989 _____. Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi; Dirãsah Tahlĩliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma‘rifah fĩ ats-Tsaqãfah al-‘Arabiyyah. Beirut: Markaz Dirãsah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990 Al-Ghazãli, Abu Hãmid. Tahãfut al-Falãsifah, Sulaimãn Dunyã (ed.). Mesir: Dãr al-Ma‘ãrif, 1966 _____. Al-Munqidz min adh-Dhalãl, Musthafã Abu al-’Alã (ed.). Berut: al-Maktabah as-Sab‘iyyah, t.t. Al-Qur’ãn dan Terjemahnya. Madinah: Mujamma‘ al-Malik Fahd li Thibã‘ah al-Mushhaf asy-Syarif, 1422 H Bakar, Osman. Tauhid dan Sains, terj. Yuliani Liputo. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 _____. Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu, terj. Purwanto. Bandung: Mizan, 1998 Heidegger, Martin. Being and Time, trans. Joan Stambaugh. New York: State University of New York Press, 1996 Leaman, Oliver. Pengantar Filsafat Islam, terj. M. Amin Abdullah. Jakarta: Rajawali Press, 1989 Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, 1974 _____. Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan. Jakarta: UI Press, 1986 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 129 Struktur Nalar Di Balik Polemik Teologi (oleh:Tahir Sapsuha) Rahman, Fazlur. Islam, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984 _____. Membuka Pintu Ijtihad, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1984 _____. “Approach to Islam in Religious Studies: Review Essays”, dalam Approaches to Islam in Religious Studies, Martin, Richard C. (ed). Tuscon: The University of Arizona Press, 1985 Sumaryono, E. Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1999 Suseno, Franz Magnis. Menalar Tuhan. Yogyakarta: Kanisius, 2006 Zaqzuq, Mahmud Hamdi. Al-Ghazãlĩ; Sang Sufi Sang Filosof, terj. Ahmad Rofi‘ ‘Utsmani. Bandung: Pustaka, 1987 130a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 DIKOTOMI AGAMA DAN ILMU DALAM SEJARAH UMAT ISLAM SERTA KEMUNGKINAN PENGINTEGRASIANNYA Syamsul Kurniawan IAIN Pontianak Email: [email protected] ABSTRAK Secara historis-filosofis kajian ini mendeskripsikan tentang bagaimana dikotomi agama dan ilmu sedang terjadi dalam perjalanan sejarah umat Islam dan seberapa besar kemungkinan ia dapat kembali diintegrasikan. Kajian ini dilakukan berangkat dari kegelisahan penulis dalam menanggapi pemikiran Islam yang dikotomistik antara agama dan ilmu. Hal ini mengakibatkan umat Islam berada dalam kondisi yang terpuruk yaitu mengalami kemunduran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah usaha integrasi perlu dilakukan umat Islam dengan tidak mendikotomi agama dengan ilmu. Manfaat dari kajian ini secara teoritis adalah adanya tuntunan teoritis bagi umat Islam dalam memandang agama dan ilmu secara integratif, sehingga berikutnya muncul kesadaran untuk melakukan reinterpretasi terhadap ilmu termasuk adanya semangat mengkaji ilmu yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam. Kata Kunci: Dikotomi, Integrasi, Agama, Ilmu. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 131 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) Pendahuluan Pengakuan adanya kebenaran ayat qauliyah (yang tertera di dalam kitab suci) dan ayat kauniyah (ayat yang ada di alam semesta) harusnya dipandang cukup untuk menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu dalam Islam. Karena secara ontologis kedua jenis ayat tersebut berasal dari Yang Satu. Motivasi Islam menempatkan ilmu-ilmuan dalam kedudukan yang tinggi sejajar dengan orang-orang yang beriman,1 sesungguhnya mengisyaratkan perintah bagi setiap muslim untuk selalu berpikir dan mengembangkan ilmu. Turunnya ayat pertama dalam al-Quran juga sejalan dengan maksud ini. Ayat pertama tersebut dimulai dengan ayat yang scientific yaitu iqra’,2 dan sejalan dengan misi Nabi Muhammad Saw untuk memberantas kebodohan (jahiliyah). Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan suatu pencarian religius. Sebagai pedoman umat Islam, al-Quran memang menguatkan hubungan antara agama dan ilmu. Kuntowijoyo berpendapat bahwa al-Quran menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir inilah yang selanjutnya harus menjadi paradigma. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu yang berdasarkan pada paradigma al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Paradigma ini dapat menjadi pendorong munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Jelas bahwa premis-premis normatif al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. Struktur transedental al-Quran menurut Kuntowijoyo adalah sebuah ide normatif dan filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan rasional yang empiris, dalam artian sesuai dengan kebutuhan pragmatis umat manusia sebagai khalifah di bumi. Kuntowijoyo berpendapat bahwa pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan Islam dimaksudkan untuk kemashlahatan umat Islam.3 Namun sayangnya dalam sejarah perkembangan keilmuan, termasuk Islam, keduanya seringkali QS al-Mujadalah (58): 11. QS al-’Alaq (96): 1-5. 3 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 251 2 26. 132a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) mengalami pendikotomian sampai kemudian ada kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan kembali keduanya. Jika dilacak pengertiannya, maka dikotomi menurut bahasa (etimology) berarti pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian.4 Dikotomi juga dapat diartikan sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan.5 Sementara definisi dikotomi menurut istilah (terminology), mengutip Ruhyana, dapat dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik-dikotomik lainnya, seperti dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam dan bahkan dikotomi dalam diri muslim itu sendiri (split personality).6 Sementara Ali Anwar Yusuf menjelaskan dikotomi sebagai pola pikir yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Agama hanya dipandang sebagai salah satu aspek hidup yaitu kebutuhan manusia pada penyembahan pada Yang Maha Kuasa. Adapun pada aspek-aspek kehidupan lainnya agama tidak bisa diperankan. Pemahaman yang parsial ini melahirkan pandangan yang sempit terhadap Islam dan menumbuhkan sekularisasi.7 Saat ini ada kecenderungan pengelompokkan disiplin ilmu menjadi disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum. Hal ini secara implisit menunjukkan adanya dikotomi ilmu. Kondisi seperti ini sesungguhnya bukan barang baru, karena sudah nampak pada saat akhir-akhir abad pertengahan yaitu ketika Islam mulai mengalami kemunduran. Pandangan dikotomis terhadap agama dan ilmu pengetahuan tersebut sesungguhnya tidak didapati dalam permulaan sejarah umat Islam atau periode klasik Islam. Ternyata pandangan dikotomis dalam sejarah umat Islam yang menempatkan agama sebagai suatu disiplin yang John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia Utama. 1992), hlm. 180. 5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), hlm. 205. 6 Ruhyana, “Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia” dalam http://jorjoran.wordpress.com/2011/04/04/dikotomi-dan-dualisme-pendidikandi-indonesia/(akses internet 8 Oktober 2013). 7 Ali Anwar Yusuf, Islam dan Sains Modern (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 49. 4 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 133 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) selama ini terasing dari disiplin ilmu lain telah menyebabkan ketertinggalan para ilmuan Islam baik dalam pengembangan wawasan keilmuan maupun untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan multimensional approach. Oleh karena itulah wajarlah jika dikotomi yang terjadi ini mendapat gugatan dari para ilmuan muslim melalui wacana tentang pentingnya integrasi agama Islam dan ilmu pengetahuan. Bahkan selama beberapa dekade dapat dikatakan bahwa persoalan dikotomi ilmu yang dihadapi dunia Islam tak pernah berhenti dan selalu dihadapkan pada pembedaan antara apa yang disebut ilmu Islam dan non Islam, ilmu barat dan ilmu timur. Bahkan lebih parah ketika dikotomi tersebut menjalar sebagai satu bentuk dikotomi antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya di bidang pendidikan, dikotomi ilmu ini menjalar sebagai satu bentuk pembedaan antara sekolah bercirikhaskan agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan sekolah umum dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekolah bercirikhaskan agama secara khusus diwakili oleh madrasah, sedangkan sekolah bercirikhaskan umum menempati kontradiksinya.8 Kesalahan pertama pelacakan dasar-dasar keilmuan antara agama dengan ilmu adalah tidak dimulai dari sumber, metode, tahapan dan fungsi dari masing-masing objek ilmu. Akibatnya, agama yang secara metodologi cenderung bersumber dari penalaran berpikir bercampur secara acak dengan ilmu pengetahuan yang secara metodologi cenderung bersumber dari daya mengindera manusia tanpa penjelasan yang tepat. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara pengembangan ilmu pengetahuan yang dibangun di atas basis ilmu murni, dengan ilmu agama yang dibangun di atas basis ilmu empiri.9 Ilmu murni melahirkan pandangan ilmu pengetahuan sebagai ilmu, sementara ilmu empiri terarah pada unsur manusia sebagai pembentuk ilmu pengetahuan. Ilmu murni meletakkan manusia Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif. Yogyakarta: Pustaka, 2005), hlm 1-2. 9 Penggunaan istilah klasifikasi ilmu murni dan ilmu empiri baca penjelasan Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 13-23. 8 134a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) di “luar pagar ilmu”, oleh sebab itu ilmu pengetahuan cenderung bersifat objektif. Pada sisi lain, ilmu agama dalam konteks ini bersifat empiris karena manusia mendapatkan peranannya dalam pembentukan ilmu, dalam hal ini ilmu empiri seringkali menjadi bersifat subjektif. Hakikat hubungan konsep keduanya menjadi kurang dapat dijelaskan. Akibatnya gagasan Islamisasi ilmu untuk mengintegrasikan agama dan ilmu sampai sekarang belum dapat dirasakan hasil kongkritnya.10 Demikianlah, sampai sekarang perdebatan seputar dikotomi antara agama dan ilmu masih menjadi isu aktual. Sebagian berpandangan bahwa antara agama dan ilmu merupakan dua kategori yang berbeda, memiliki wilayah kajian yang berbeda dan diorientasikan pada hal-hal yang berbeda pula. Sementara pandangan lain mengatakan sebaliknya, baik agama dan ilmu adalah dua hal yang bersifat integratif, dua aktivitas yang sama dan keduanya tidak boleh dipilah-pilah, karena keduanya dapat saling melengkapi serta dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Kajian ini menggunakan pendekatan historis dan filsafat untuk mendeskripsikan tentang bagaimana dikotomi agama dan ilmu sedang terjadi dalam perjalanan sejarah umat Islam dan seberapa besar kemungkinan ia dapat kembali diintegrasikan. Kajian ini berangkat dari kegelisahan penulis dalam menanggapi pemikiran yang dikotomistik antara agama dan ilmu. Hal ini mengakibatkan umat Islam berada dalam kondisi yang terpuruk yaitu mengalami kemunduran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu usaha integrasi perlu dilakukan umat Islam dengan tidak mendikotomi agama dengan ilmu. Manfaat dari kajian ini secara teoritis adalah adanya tuntunan teoritis bagi umat Islam dalam memandang agama dan ilmu secara integratif, sehingga berikutnya muncul kesadaran untuk melakukan reinterpretasi terhadap ilmu pengetahuan termasuk adanya semangat mengkaji ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, hlm. 2. 10 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 135 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) Dikotomi Agama dan Ilmu dalam Sejarah Umat Islam Ian Barbour memetakan hubungan ilmu dan agama selama ini dalam empat tipologi yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Pertama, konflik. Hubungan ini ditandai dengan adanya dua pandangan yang saling berlawanan antara agama dan ilmu dalam melihat suatu persoalan. Keduanya sama-sama mempunyai argumentasi yang tidak hanya berbeda tapi juga saling bertentangan dan bahkan menafikan satu dengan yang lain. Ian Barbour seorang fisikawan sekaligus teolog mencatat bahwa momentum kuat munculnya konflik antara agama dan ilmu telah terjadi pada abad pertengahan, manakala otoritas gereja menjatuhkan hukuman kepada Galileo Galilei pada tahun 1663, karena mengajukan teori Copernicus bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari (heliosentris) dan menolak teori Ptolomeus yang didukung otoritas ilmiah Aristoteles dan otoritas kitab suci yang meyakini bahwa bumi sebagai pusat alam semesta (geosentris). Seseorang tidak dapat menerima pandangan heliosentris dan geosentris sekaligus atau dengan kata lain harus memilih salah satu apakah akan menerima kebenaran agama atau kebenaran ilmu. Jika menerima kebenaran agama akan berimplikasi pada penolakan objektifitas kebenaran ilmu dan jika menerima kebenaran ilmu akan berimplikasi pada pengingkaran kebenaran agama dan dituduh sebagai kafir. Persoalan lain yang menggambarkan hubungan konflik antara agama dan ilmu adalah masalah teori evolusi Darwin yang muncul pada abad XIX. Sejumlah ilmuan dan agamawan menganggap bahwa teori evolusi Darwin dan kebenaran kitab suci tidak dapat dipertemukan. Kaum literalis Biblikal memahami bahwa alam semesta diciptakan Tuhan secara langsung, sementara kaum evolusionis berpendapat bahwa alam semesta terjadi secara alamiah melalui proses yang sangat panjang atau evolusi. Dengan menunjukkan bukti-bukti empiris kaum evolusionis tidak menisbahkan proses panjang tersebut pada Tuhan namun melalui proses yang alamiah. Makhluk hidup menurut kaum evolusionis dapat berkembang menjadi beraneka ragam melalui mekanisme adaptasi, survival for live, dan seleksi alam. Bagi Darwin dan kaum evolusionis, manusia bukanlah makhluk yang diciptakan khusus dan kemudian ditempatkan di bumi ini sebagaimana pendapat kaum literalis Biblikal. Menurut 136a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) mereka, manusia hanyalah proses evolusi tersebut. Pandangan demikian tentu menggeser pandangan gereja bahwa Tuhanlah yang menciptakan satu persatu makhluk hidup dan secara khusus menciptakan manusia yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari makhluk yang lain. Ada sementara agamawan menyatakan bahwa teori evolusi bertentangan dengan keyakinan agama, sedangkan ilmuan atheis bahkan mengklaim bahwa berbagai bukti ilmiah atas teori evolusi tidak sejalan dengan keimanan. Dua kelompok ini sepakat bahwa tidak mungkin seseorang dapat mempercayai Tuhan dan teori evolusi sekaligus. Jadilah agama dan ilmu berada pada posisi yang bertentangan. Kedua, Independensi. Berbeda dengan yang pertama, pandangan independensi menempatkan agama dan ilmu tidak berada dalam posisi konflik. Kebenaran agama dan ilmu samasama absah selama berada pada batas ruang lingkup penyelidikan masing-masing. Agama dan ilmu tidak perlu saling mencampuri satu dengan yang lain karena memiliki cara pemahaman akan realitas yang benar-benar terlepas satu sama lain, sehingga tidak ada artinya mempertentangkan keduanya. Menurut pandangan ini upaya peleburan merupakan upaya yang tidak memuaskan untuk menghindari konflik. Kalangan Kristen Konservatif berusaha meleburkan agama dan ilmu dengan mengatakan bahwa kitab suci memberikan informasi ilmiah yang paling dapat dipercaya tentang awal mula alam semesta dan kehidupan, yang tidak mungkin mengandung kesalahan. Mereka menolak teori evolusi Darwin dan membangun konsep baru tentang penciptaan yang dinamakan creation science berdasarkan atas penafsiran harfiah terhadap kisah-kisah Biblikal. Karl Bath berpendapat bahwa agama dan ilmu memiliki metode dan pokok persoalan yang berbeda. Ilmu dibangun berdasarkan pengamatan dan penalaran manusia, sedangkan teologi berdasarkan wahyu Tuhan. Oleh karenanya Bath berpendapat bahwa agama dan ilmu mesti berjalan sendiri-sendiri tanpa ada campur tangan satu dengan yang lain. Barbour menambahkan bahwa selain metode dan pokok persoalan, bahasa dan fungsinya juga berbeda. Bahasa ilmiah berfungsi menjawab “bagaimana”, yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan mencari jalan keluar atas fenomena riil kemanusiaan, sedangkan bahasa agama berfungsi untuk Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 137 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) menjawab “mengapa”, yang akan mendorong seseorang untuk mematuhi prinsip-prinsip moral tertentu. Gambaran yang sering digunakan untuk menjelaskan tipologi ini adalah seperti halnya permainan, misal catur dan ular tangga. Peraturan dalam catur tidak dapat diterapkan dalam permainan ular tangga, demikian pula sebaliknya. Demikian pula ilmu dan agama, tidak ada yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lain dan keduanya tidak dapat ditempatkan pada posisi bersaing atau konflik. Pendekatan independensi ini dinilai cukup aman karena dapat menghindari konflik dengan cara memisahkan hubungan di antara keduanya. Pendekatan ini menggambarkan agama dan ilmu sebagai jalur kereta yang berel ganda, masing-masing mempunyai jalan yang independen dan otonom. Ketegangan antara Galileo Galilei dengan gereja semestinya tidak perlu terjadi jika agama dapat masuk ke wilayah privasi ilmu, demikian pula ilmu tidak memaksakan diri dengan rasionalisme-empirisme pada agama. Agama dan ilmu mempunyai bahasa sendiri karena menjalani fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Agama berurusan dengan fakta objektif, agama rentan dengan perubahan karena sifatnya yang deduktif, sedangkan ilmu setiap saat bisa berubah karena sifatnya yang lebih induktif. Menurut pandangan independen, agama dan ilmu adalah dua domain independen yang dapat hidup bersama sepanjang mempertahankan “jarak aman” satu sama lain. Agama dan ilmu berada pada posisi sejajar dan tidak saling mengintervensi satu dengan yang lain. Ketiga, Dialog. Pendekatan independensi meskipun merupakan pilihan yang cukup aman, namun dapat menjadikan realitas kehidupan menjadi terbelah. Penerimaan kebenaran agama dan ilmu menjadi satu pilihan dikotomis yang membingungkan karena tidak dapat mengambil keduanya sekaligus. Adapun bagi seseorang yang berusaha menerima keduanya dapat mengalami split personality, karena menerima dua macam kebenaran yang saling berseberangan. Menurut Barbour, pendekatan ini membantu tetapi membiarkan segala sesuatu berada pada jalan buntu yang bisa membuat seseorang putus asa. Karena itulah pendekatan dialog memandang bahwa agama dan ilmu tidak dapat disekat dengan kotak-kotak yang sama sekali terpisah, meskipun pendekatan ini menyadari bahwa keduanya berbeda secara logis, 138a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) linguistik, maupun normatif. Bagaimanapun juga, di Barat, agama telah memberikan banyak inspirasi bagi perkembangan ilmu, demikian pula penemuan-penemuan ilmiah juga mempengaruhi teologi. Meskipun keduanya berbeda namun tidak mungkin benar-benar dipisahkan. Pendekatan dialog ini dapat membangun hubungan yang mutualis. Dengan belajar dari ilmu, agama dapat membangun kesadaran kritis dan lebih terbuka sehingga tidak terlalu over sensitive terhadap hal-hal yang baru. Sebaliknya, ilmu perlu mempertimbangkan perhatian agama pada masalah harkat kemanusiaan. Dalam dunia manusia, ada realitas batin yang membentuk makna dan nilai. Ilmu bukanlah satu-satunya jalan menuju kebenaran, dan ilmu bukan hanya untuk ilmu tetapi ilmu juga untuk kemanusiaan. Agama dapat membantu memahami batas-batas rasio, yaitu pada wilayah adikodrati atau supranatural ketika ilmu tidak mampu menyentuhnya. Hubungan dialogis berusaha membandingkan metode kedua bidang yang dapat menunjukkan kemiripan dan perbedaan. Dialog dapat terjadi manakala agama dan ilmu menyentuh persoalan di luar wilayahnya sendiri. Keempat, Integrasi. Ada dua makna dalam bentuk ini: (a) bahwa integrasi mengandung makna implisit reintegrasi, yaitu menyatukan kembali agama dan ilmu setelah keduanya terpisah; (b) integrasi mengandung makna unity yaitu bahwa agama dan ilmu merupakan kesatuan primordial. Makna pertama populer di Barat karena kenyataan sejarah menunjukkan keterpisahan itu. Adapun makna kedua lebih banyak berkembang di dunia Islam karena secara ontologis diyakini bahwa kebenaran agama dan ilmu adalah satu. Perbedaannya ada pada ruang lingkup pembahasan, yang satu pengkajiannya dimulai dari pembacaan al-Quran, sementara yang satu lagi dimulai dari pembacaan alam. Kebenaran keduanya saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Secara historis, periode klasik Islam memang mencatat bahwa ilmuan dan cendekiawan muslim ketika itu memandang agama dan ilmu sebagai sesuatu yang integratif. Menurut Endang Saifuddin Anshari, ilmuan dan cendekiawan muslim memandang bahwa ajaran agama Islam memuat semua sistem ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada dikotomi dalam sistem Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 139 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) keilmuan Islam.11 Sebagian ilmuan dan cendekiawan muslim saat itu memang berasumsi bahwa dalam dataran konsep ideal, Islam diyakini sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna.12 Ajaran Islam juga komprehensif dan universal,13 sehingga memungkinkan memuat semua sistem ilmu pengetahuan. Namun, kenyataan yang terjadi sebaliknya, paska abad pertengahan muncullah pemisahan antara kelompok ilmu profan yaitu ilmu-ilmu keduniaan yang melahirkan perkembangan sains dan teknologi, yang selanjutnya dihadapkan pada ilmu-ilmu agama pada sisi lain.14 Amin Abdullah berpendapat bahwa kecelakaan sejarah umat Islam terjadi pada saat bangunan keilmuan natural science menjadi terpisah dan tidak bersentuhan sama sekali dengan ilmu-ilmu agama yang fondasi dasarnya berupa teks atau nash, yaitu al-Quran dan Hadits.15 Meskipun peradaban Islam klasik pernah mencatatkan tinta emas dalam sejarah umat Islam dengan nama-nama ilmuan yang terkenal seperti Ibn Sina sebagai seorang filsuf yang juga menguasai disiplin ilmu kedokteran, Ibn Haitsam seorang fisikawan, Abu Abbas al-Fadhl Hatim an-Nizari seorang ahli astronomi, Umar ibn Ibrahim al-Khayyami (yang lebih dikenal dengan sebutan Umar Khayyam) penulis buku alJabbar, Muhammad al-Syarif al-Idrisi seorang ahli ilmu bumi, dan lain-lain. Namun sayangnya nama-nama ini di kalangan umat Islam pada hari ini kurang dikenal atau mungkin tidak dikenal sama sekali. Pada periode klasik perkembangan Islam yaitu abad VIIXIII mencatatkan umat Islam pernah mengalami era keemasan, yang mana telah terjadi perkembangan pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Setidaknya ada beberapa faktor yang Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya (Jakarta: Rajawali Press,1991), hlm. 120-125. 12 Nasruddin Razak, Dienul Islam (Bandung: Al-Maarif, 1996), hlm. 7. 13 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, hlm. 1. 14 Azyumardi Azra, “Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam”, dalam Abdul Munir Mulkhan, dkk., Religiusitas Iptek. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7883. 15 M. Amin Abdullah, dkk. Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi (Yogyakarta: Suka-Press, 2007), hlm. 27. 11 140a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) mendorong kemajuan pesat ilmu pengetahuan pada periode ini, yaitu: pertama, Agama Islam menjadi motivasi; kedua, Kesatuan bahasa yang memudahkan komunikasi ilmiah (yaitu bahasa Arab); ketiga, Adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan; keempat, Didirikannya akademi, laboratorium, dan perpustakaan sebagai sarana perkembangan ilmu; kelima, Ketekunan ilmuan untuk mengadakan riset dan eksperimen; keenam, Pandangan internasional yang membuka isolasi dengan dunia luar; dan ketujuh, Penguasaan terhadap bekas wilayah pengembangan filsafat klasik Yunani. Pada periode klasik perkembangan Islam ini telah mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, demikian pula ilmu pengetahuan yang bersumber dari alam dan masyarakat, tetapi masih berada dalam “satu atap” yaitu pengetahuan Islam.16 Dalam konteks ini Mulla Shadra seorang pemikir Islam kelahiran Persia menganologikan integrasi agama dan ilmu dengan “sinar yang satu” yang menyinari suatu ruangan yang mempunyai jendela yang beragam warna. Setiap jendela akan memancarkan warna yang bermacam-macam sesuai dengan warna kacanya. Melalui analogi ini Shadra hendak menggambarkan bahwa kebenaran berasal dari Yang Satu, dan akan tampak muncul beragam kebenaran tergantung sejauh mana manusia mampu menangkap kebenaran itu. Dapatlah dimengerti bahwa kebenaran yang ditangkap ilmuan hanyalah sebagian yang mampu ditangkap dari kebenaran Tuhan, demikian pula kebenaran yang ditangkap oleh agamawan. Jadi kebenaran yang ditangkap oleh ilmuan dan agamawan bagi Mulla Shadra bersifat komplementer dan saling melengkapi. Sesudah periode klasik ini yaitu sejak abad XIII, perkembangan ilmu pengetahuan dalam umat Islam menampakkan gejala kemunduran. Sebaliknya di dunia Barat, warisan ilmu pengetahuan yang sebelumnya berkembang pada umat Islam, mereka pelajari dan kembangkan sehingga mampu mengantar mereka ke era renaissance. Mulai saat inilah ada kecenderungan umat Islam memilah-milah mana ilmu yang boleh mereka pelajari Lihat M. Shaleh Putuhena, “Ke Arah Rekonstruksi Sains Islam,” dalam Nurman Said, dkk., Sinergi Agama dan Sains (Makassar: Alauddin Press, 2005), hlm. 107. 16 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 141 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) dan mana yang tidak. Ilmu yang diambil langsung dari al-Quran dan Hadits dapat dipelajari dan dipandang sebagai struktur ilmu Islam, sedangkan ilmu yang bersumber dari alam dan dari masyarakat hendaknya ditepikan dari struktur ilmu pengetahuan dalam Islam. Keadaan inilah yang melatar-belakangi adanya dikotomi antara agama dan ilmu sejarah umat Islam yang berujung pada kemunduran umat Islam hingga sekarang dalam banyak aspek. Kemungkinan Pengintegrasian Kembali Agama dan Ilmu Telah diuraikan bahwa dikotomi antara agama dan ilmu selanjutnya berdampak pada kemunduran umat Islam. Hal ini yang kemudian memotivasi para ilmuan dan cendekiawan muslim untuk mewacanakan kembali tentang pentingnya pengintegrasian kembali agama dengan ilmu. Bagi sebagian ilmuan dan cendekiawan muslim, mustahil mengandaikan kemajuan umat muslim, tanpa memposisikan agama secara mutualis sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan ilmu. Dalam konteks integrasi ini, muncullah istilah-istilah untuk mendukung proyek integrasi agama dan ilmu ini seperti islamisasi ilmu pengetahuan, ilmuisasi Islam, integrasi ilmu, integrasi dan interkoneksi, dan lain-lain. Beberapa tokoh yang dikenal aktif menyuarakan integrasi agama dan ilmu di antaranya: Ismail Raji al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Fazlur Rahman, Ziauddin Sardar, Kuntowijoyo, Azyumardi Azra, Imam Suprayogo dan M. Amin Abdullah. Ismail Raji al-Faruqi seorang ilmuan kelahiran Palestina yang hijrah ke Amerika Serikat berpendapat bahwa agama dan ilmu dapat diintegrasikan, dan dapat dimulai dengan mengembalikan ilmu pada pusatnya yaitu tauhid. Hal ini dimaksudkannya agar ada korelasi atau hubungan antara ilmu pengetahuan dengan iman. Selanjutnya Kuntowijoyo yang mewacanakan pentingnya ilmuisasi Islam. Dalam konteks ini, Kuntowijoyo berpendapat bahwa agama dapat diintegrasikan dengan ilmu manakala ilmuan dan cendekiawan muslim segera melakukan perumusan teori ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada al-Quran dan menjadikan al-Quran sebagai suatu paradigma. Upaya yang dilakukan adalah 142a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) objektifikasi. Agama Islam dijadikan sebagai ilmu yang objektif, sehingga ajaran agama yang terkandung dalam al-Quran dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh alam atau menjadi rahmatan lil ‘alamin, dalam arti tidak hanya untuk umat Islam tapi juga non Islam dapat merasakan manfaat dari objektifikasi ajaran agama Islam. Kuntowijoyo menyatakan bahwa inti dari integrasi adalah upaya menyatukan bukan sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau sebaliknya mengucilkan manusia (other worldly asceticism).17 Jika membandingkan pendapat keduanya, model integrasi agama dan ilmu agaknya Ismail Raji al-Faruqi lebih riil dibandingkan model integrasi agama dan ilmu yang diwacanakan Kuntowijoyo yang hanya bergerak pada tataran teoritis an sich.18 Imam Suprayogo berpendapat bahwa model integrasi agama dan ilmu hendaknya menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai grand theory pengetahuan, sehingga ayat-ayat qauniyah dan qauliyah, kedua-duanya dapat dipakai.19 Sejalan dengan pendapat Imam Suprayogo di atas, Azyumardi Azra mengklaksifikasikan tiga tipologi respons cendekiawan muslim yang berkaitan dengan hubungan antara ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Pertama, Restorasionis yang mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan adalah praktik agama (ibadah). Cendekiawan yang berpendapat seperti ini adalah Ibrahim Musa dari Andalusia. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan dari Nabi saja. Begitu juga Abu al-A’la al-Maududi seorang ulama dari Pakistan mengatakan bahwa ilmu-ilmu dari Barat seperti geografi,fisika, kimia, biologi, zoologi, geologi, dan ilmu ekonomi adalah sumber kesesatan karena tanpa rujukan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw. Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, hlm. 57-58. Eko Juhairi Rismawan, “Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Integrasi Ilmu dan Agama”, dalam http://ekojuhairirismawan.blogspot.com/2011/02/ pemikiran-kunto.html (akses internet tanggal 8 Oktober 2013). 19 Lihat Imam Suprayogo, “Membangun Integrasi Ilmu dan Agama: Pengalaman UIN Malang”, dalam Zainal Abidin Bagir (ed.), Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 49-50. 17 18 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 143 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) Kedua, Rekonstruksionis interpretasi agama untuk memperbaiki hubungan peradaban modern dengan Islam, dengan asumsi bahwa Islam pada masa Nabi Muhammad Saw sangat revolutif, progresif, dan rasionalis. Sayyid Ahmad Khan mengatakan bahwa firman Allah SWT dan kebenaran ilmiah adalah sama-sama benar. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Jamaluddin al-Afghani yang menyatakan bahwa Islam memiliki semangat ilmiah. Ketiga, Reintegrasi dalam arti merekonstruksi ilmu-ilmu yang berasal dari ayat-ayat al-Quran dan ayat-ayat qauniyah sehingga dapat kembali pada kesatuan transedental semua ilmu pengetahuan.20 Integrasi yang dimaksud Azra berkaitan dengan usaha memadukan agama dan ilmu tanpa harus menghilangkan keunikankeunikan dari masing-masing keilmuan tersebut. Hanya saja memang ada sejumlah kritikan yang dilontarkan sejumlah ilmuan atau cendekiawan muslim dalam kaitannya dengan integrasi agama dan ilmu ini, di antaranya datang dari M. Amin Abdullah. M. Amin Abdullah memandang bahwa sejauh ini integrasi agama dan ilmu masih mengalami kesulitan, yaitu memadukan studi Islam dan studi umum yang kadang tidak saling akur karena keduanya ingin saling mengalahkan. Oleh karena itu menurutnya diperlukan usaha menginterkoneksikan studi Islam dan studi umum yang lebih arif dan bijaksana. Dapat dimengerti bahwa interkoneksitas yang diwacanakan oleh M. Amin Abdullah adalah usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, sehingga setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman, tidak dapat berdiri sendiri. M. Amin Abdullah berpendapat, agar agama dan ilmu terintegrasi dan terinterkoneksi maka disiplin keilmuan tersebut perlu bekerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling keterhubungan.21 Azyumardi Azra, “Reintegrasi Ilmu-ilmu dalam Islam” dalam Zainal Abidin Bagir (ed.), Integrasi Ilmu dan ..., hlm. 206-211. 21 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. vii-viii. 20 144a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) Pendekatan integratif-interkonektif yang diwacanakan oleh M. Amin Abdullah merupakan pendekatan yang tidak saling melumatkan dan tidak pula berarti peleburan antara agama dan ilmu. Secara rinci M. Amin Abdullah mengklaksifikasikannya ke dalam tiga pola yaitu, pola pararel, pola linear dan pola sirkular. Pertama, Pola pararel adalah pola yang masing-masing corak keilmuan umum dan agama berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dan persentuhan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, Pola linear adalah pola yang mana salah satu dari keduanya akan menjadi primadona, sehingga akan ada kemungkinan berat sebelah. Ketiga, Pola sirkular, yaitu masing-masing corak keilmuan dapat memahami keterbatasan, kekurangan dan kelemahan pada masing-masing keilmuan, dan sekaligus bersedia mengambil manfaat dari temuan-temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan yang lain serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekurangan yang melekat pada diri sendiri.22 Dapat dipahami bahwa konsep integrasi-interkoneksi yang diwacanakan M. Amin Abdullah merupakan usaha untuk menjadikan sebuah koneksitas atau keterhubungan antara keilmuan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Muara dari konsep integrasi dan interkoneksi ini menjadikan keilmuan mengalami proses objektifikasi di mana keilmuan tersebut dirasakan oleh orang non Islam sebagai suatu yang natural atau sewajarnya, bukan sebagai praktik keagamaan. Sementara itu bagi umat Islam, bisa tetap menganggapnya sebagai bagian dari praktik keagamaan dan dinilai sebagai amal ibadah. Ini memungkinkan ilmu-ilmu dalam agama Islam menjadi rahmat bagi semua orang. Contoh konkrit dari konsep ini adalah perbankan syariah yang praktik atau teori-teorinya dirumuskan dari wahyu Allah SWT. Seperti kita mafhumi bahwa agama Islam melalui alQuran dan As-Sunnah telah menyediakan etika dan perilaku yang semestinya dalam mengurusi perbankan. Di sinilah agama Islam mengalami objektivitas di mana etika agama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh manusia, baik muslim maupun non muslim, bahkan bagi seorang yang atheis dapat memanfaatkan. Kedepan, seperti dijelaskan M. Amin Abdullah, pola kerja 22 Ibid., hlm. 219-223. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 145 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) keilmuan yang integralistik dengan basis moralitas keagamaan yang humanistik dituntut untuk dapat masuk pada wilayahwilayah yang lebih luas seperti psikologi, sosiologi, antropologi, kesehatan, teknologi, ekonomi, politik, hubungan internasional, hukum dan peradilan, dan seterusnya.23 Manfaat dari Integrasi Agama dan Ilmu Pentingnya integrasi agama dan ilmu ini sesungguhnya tidak hanya sebagai respon ketertinggalan umat Islam dalam ilmu, tapi juga merupakan respon mutakhir umat Islam terhadap sains Barat yang sekular. Hal ini dibenarkan oleh Kuntowijoyo, yang mana modernisasi telah memaksakan suatu kondisi terpisahnya antara ilmu dan agama, antara ilmu yang mandiri dan ilmu yang sekular. Maka wajar menurut Kuntowijoyo, jika pada masa ini umat Islam banyak yang menghendaki paradigma baru yang merupakan hasil rujuk kembali antara agama dan ilmu atau antara wahyu dan rasio.24 Integrasi agama dan ilmu tentu merupakan hal yang urgen. Hal ini dikarenakan kadang-kadang kita merasakan bahwa situasi yang penuh problematik di dunia modern justru disebabkan oleh pemikiran manusia sendiri. Di balik kemajuan ilmu atau perkembangan sains dan teknologi pada saat ini, sesungguhnya mempunyai potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Menurut Kuntowijoyo umat manusia memang telah berhasil mengorganisasikan ekonomi, menata struktur politik, serta membangun peradaban yang maju untuk dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa umat manusia telah menjadi tawanan dari hasil-hasil ciptaannya itu. Sejak manusia memasuki zaman modern, yaitu sejak manusia mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya, mereka memang telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran mistis yang irrasional dan belenggu pemikiran hukum alam yang sangat mengikat kebebasan manusia. Tetapi ternyata di dunia modern ini menurut Kuntowijoyo, sebagian manusia tak dapat melepaskan diri dari jenis belenggu lain, yaitu penyembahan kepada dirinya Lihat Ibid., hlm. 105. Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 58-59. 23 24 146a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) sendiri.25 Karena itu, integrasi agama dan ilmu menjadi sesuatu urgen terutama ketika merespons gejala dehumanisasi seperti diuraikan Kuntowijoyo di atas. Mengutip pendapat Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan: Jika bangunan sebuah ilmu merupakan bangunan yang syarat dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebuah bangunan yang syarat dengan kriteria etik, moral, dan berbagai ketentuan yang memancar dari ajaran agama, atau penuh dengan kesadaran ketuhanan, dengan sendirinya tidak akan menghasilkan berbagai produk yang kontraproduktif dengan ajaran agama. Karena itu, kekhawatiran akan terjadinya dehumanisasi atau mengubah hakikat kemanusiaan akibat perkembangan ilmu dan teknologi tidak akan terjadi.26 Dengan adanya integrasi agama dan ilmu ini, agama diharapkan bisa bermakna, demikian pula sebaliknya bagi ilmu supaya tidak kehilangan nilai-nilai ketuhanan, sehingga keduanya dapat menjadi rahmat bagi pemeluknya, bagi umat manusia, atau bahkan keseluruhan alam semesta. Mengutip pendapat Bambang Sugiharto, beberapa manfaat yang dapat dipetik dari integrasi yang terjadi antara agama dan ilmu: Pertama, Kesadaran kritis dan sikap realistis yang dibentuk oleh ilmu pengetahuan sangatlah berguna untuk menguliti sisisisi ilusi dari suatu agama, bukan untuk menghancurkan agama, melainkan untuk menemukan hal-hal yang lebih esensial dari ajaran agama. Dalam praksisnya banyak hal dalam kehidupan beragama yang mungkin saja bersifat ilusi, sehingga membuat sebagian pemeluk agama cenderung oversensitive dan mudah menimbulkan konflik yang pada akhirnya justru menggerogoti martabat agama sendiri tanpa disadari. Kedua, Kemampuan logis dan kehati-hatian mengambil kesimpulan yang dipupuk dalam dunia ilmiah menjadikan kita mampu menilai secara kritis segala bentuk tafsir baru yang kini makin hiruk-pikuk dan Ibid., hlm. 112. Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Filsafat Ilmu (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2012), hlm. 112. 25 26 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 147 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) membingungkan. Ketiga, lewat temuan-temuan barunya, ilmu dapat merangsang agama untuk senantiasa tanggap memikirkan ulang keyakinan-keyakinannya secara baru dan dengan begitu menghindarkan agama itu sendiri dari bahaya stagnasi. Keempat, temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun dapat memberikan peluang-peluang baru bagi agama untuk makin mewujudkan idealisme-idealismenya secara konkret, terutama yang menyangkut kemanusiaan umum.27 Sebaliknya menurut Bambang Sugiharto, agama juga punya kontribusi pada ilmu, yaitu: pertama, menjaga ilmu supaya tetap manusiawi dan selalu menyadari persoalan-persoalan konkrit yang mesti dihadapinya. Agama bisa selalu mengingatkan bahwa ilmu bukanlah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan makna terdalam kehidupan manusia. Dalam dunia manusia ada realitas pengalaman batin yang membentuk makna dan nilai, dan itu adalah wilayah yang tak banyak disentuh oleh ilmu pengetahuan atau sains. Kedua, agama bisa juga selalu mengingatkan ilmu untuk senantiasa membela nilai kehidupan dan kemanusiaan bahkan di atas kemajuan ilmu itu sendiri. Misalnya, jika demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi justru harus mengorbankan manusia, maka seyogyanya yang terjadi adalah sebaliknya. Ketiga, agama dapat membantu ilmu memperdalam penjelajahan di wilayah kemungkinan-kemungkinan adikodrati atau supranatural. Apalagi jika wilayah-wilayah itu memang merupakan ujung tak terelakkan dari aneka pencarian ilmiah yang serius saat ini. Keempat, agama pun dapat selalu menjaga sikap mental manusia agar tidak mudah terjerumus ke dalam mentalitas pragmatis-instrumental, yang menganggap sesuatu dianggap bernilai sejauh jelas manfaatnya dan bisa diperalat sesuai kepentingan.28 PENUTUP Dikotomi antara agama dan ilmu berdampak pada kemunduran umat Islam. Hal ini yang kemudian memotivasi para Bambang Sugiharto, “Ilmu dan Agama dalam Kurikulum Perguruan Tinggi”, dalam Zainal Abidin Bagir, Zainal Abidin Bagir (ed.), Integrasi Ilmu dan ..., hlm. 45. 28 Ibid., hlm. 45-46. 27 148a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) ilmuan dan cendekiawan muslim untuk mewacanakan kembali tentang pentingnya pengintegrasian kembali agama dengan ilmu. Bagi sebagian ilmuan dan cendekiawan muslim, mustahil mengandaikan kemajuan umat muslim, tanpa memposisikan agama secara mutualis sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan ilmu. Selanjutnya muncul istilah-istilah untuk mendukung proyek integrasi agama dan ilmu ini seperti islamisasi ilmu pengetahuan, ilmuisasi Islam, integrasi ilmu, integrasi dan interkoneksi, dan lain-lain. Beberapa tokoh yang dikenal aktif menyuarakan integrasi agama dan ilmu di antaranya: Ismail Raji al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Fazlur Rahman, Ziauddin Sardar, Kuntowijoyo, Azyumardi Azra, Imam Suprayogo dan M. Amin Abdullah. Adanya wacana integrasi agama dan ilmu di kalangan ilmuan dan cendekiawan muslim sesungguhnya tidak hanya sebagai respon ketertinggalan umat Islam dalam ilmu, tapi juga merupakan respon mutakhir umat Islam terhadap sains Barat yang sekular. Dengan adanya integrasi agama dan ilmu, agama diharapkan bisa bermakna, demikian pula sebaliknya bagi ilmu supaya tidak kehilangan nilai-nilai ketuhanan, sehingga keduanya dapat menjadi rahmat bagi pemeluknya, bagi umat manusia, atau bahkan keseluruhan alam semesta.*** Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 149 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) DAFTAR PUSTAKA Abdul Munir Mulkhan, dkk., 1998. Religiusitas Iptek. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar. Ali Anwar Yusuf, 2006. Islam dan Sains Modern. Bandung: Pustaka Setia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Eko Juhairi Rismawan, “Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Integrasi Ilmu dan Agama”, dalam http://ekojuhairirismawan. blogspot.com/2011/02/pemikiran-kunto.html (akses internet tanggal 8 Oktober 2013). Endang Saifuddin Anshari, 1991. Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya. Jakarta: Rajawali Press. Jasa Ungguh Muliawan, 2005. Pendidikan Islam Integratif. Yogyakarta: Pustaka. John M Echols dan Hassan Shadily, 1992. Kamus InggrisIndonesia. Jakarta: Gramedia Utama. Kuntowijoyo, 2005. Islam Sebagai Ilmu. Jakarta: Teraju. Kuntowijoyo, 2006. Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana. M. Amin Abdullah, 2006. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. M. Amin Abdullah, dkk., 2007. Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi. Yogyakarta: Suka-Press. M. Shaleh Putuhena, “Ke Arah Rekonstruksi Sains Islam,” dalam Nurman Said, dkk., 2005. Sinergi Agama dan Sains. Makassar: Alauddin Press. Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, 2012. Filsafat Ilmu. Pontianak: STAIN Pontianak Press. 150a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) Nasruddin Razak, 1996. Dienul Islam. Bandung: Al-Maarif. Ruhyana, “Dikotomi dan Dualisme Pendidikan di Indonesia” dalam http://jorjoran.wordpress.com/2011/04/04/ dikotomi-dan-dualisme-pendidikan-di-indonesia/(akses internet 8 Oktober 2013). Sutari Imam Barnadib, 1993. Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis. Yogyakarta: Andi Offset. Yayasan Penerjemah al-Quran, 1980. Al-Quran dan Terjemahannya. Medinah: Qadim al-Haramain al-Syarifain. Zainal Abidin Bagir (ed.), 2005. Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi. Bandung: Mizan. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 151 Dikotomi Agama dan Ilmu (oleh: Syamsul Kurniawan) 152a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) JIHAD MELAWAN TERORISME: (Merekonstruksi Pemahaman tentang Makna dan Implementasi Jihad dalam Islam) Abdurrohman Kasdi STAIN Kudus Email: [email protected] ABSTRAK Terorisme kembali lagi datang mengancam bangsa Indonesia setelah terjadinya ledakan bom di Hotel JW Marriott, Ritz Carlton dan bom Bali beberapa tahun lalu. Dari peristiwa peledakan ini, dapat dianalisis bahwa serangan sengaja dilakukan di tempat-tempat umum dengan target yang jelas. Inilah sesungguhnya tipikal aksi terorisme yang terjadi di berbagai belahan dunia. Serangan 11 September terhadap WTC dan gedung Pentagon di Amerika Serikat, peledakan bom Bali, ledakan bom JW Marriott 1, peledakan bom di Hotel Marriott 2 dan Ritz Carlton memberikan bukti yang jelas bahwa terorisme membidik sasaran di tempat keramaian. Hal ini menandakan betapa aksi kekerasan yang terjadi sudah mulai mengarah pada aksi yang menimbulkan dampak massif dengan dilakukan oleh para pelaku yang terorganisir. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk membahas teroris, dalam perspektif normatif dan mengkomparasikan dengan konsep jihad. Selama ini para orientalis menganggap bahwa banyaknya terorisme yang terjadi karena seorang Muslim mempunyai konsep jihad. Jihad yang sebenarnya dalam konteks sekarang tidak mesti dilakukan dalam bentuk perang. Islam menolak semua pembenaran untuk Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 153 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) perang duniawi, seperti kolonialisme, rasisme, ketamakan, dan ekspansi ekonomi. Di bawah pemerintahan Islam semua orang akan bekerja bersama-sama sebagai satu keluarga besar, menjadikan semua makhluk sebagai satu kesatuan tanpa tujuantujuan yang saling bertentangan. Kata Kunci: Jihad, Terorisme, Rekonstruksi, Impelementasi Pendahuluan Penangkapan Abu Tholut alias Mustopa alias Pranata alias Imron Baihaki di Kudus pada hari Jumat (10/12), tahun lalu sekitar pukul 8:30 pagi menandakan bahwa ancaman terorisme masih menghantui kita. Menurut United States Code, Section 2656 f (d), istilah “terorisme” berarti aksi kekerasan bermotif politik yang direncanakan sebelumnya dan dilakukan terhadap sasaran nontempur (noncombatant) oleh agen-agen rahasia atau sub nasional, yang biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi kalangan tertentu. Sedangkan E.V. Walter dalam Terror and Resistance: A Study of Political Violence with Case Studies of Some Primitive African Communities, memandang terorisme sebagai proses teror mempunyai tiga unsur: pertama, tindakan atau ancaman kekerasan. Kedua, reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban. Dan ketiga, dampak sosial yang mengikuti ancaman dan rasa ketakutan yang muncul kemudian. Jika dilihat secara seksama, ada perubahan mendasar dari aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Indonesia, yang dikaitkan dengan terorisme. Padahal, aksi teroris bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan nilai-nilai esensial semua agama. Jika dahulu, aksi kekerasan lebih berupa pada persoalan konflik antaragama, gerakan protes, dan aksi sweeping, maka sejak tahun 2005 aksi kekerasan sudah mengarah pada kekerasan sporadis, yang terencana dan terorganisir secara rapi, yang melibatkan korban sipil yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Hal ini dapat kita lihat dari dua peristiwa penting, yakni tragedi bom Bali dan tragedi bom di Hotel Marriot. Kedua peledakan ini seakan-seakan memberikan pesan bahwa eksistensi gerakan 154a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) mereka masih kuat dan mampu melakukan perlawanan meskipun aksi penangkapan terus-menerus dilakukan pemerintah. Definisi Jihad Islam menolak semua pembenaran untuk perang duniawi, seperti kolonialisme, rasisme, ketamakan, dan ekspansi ekonomi. Di bawah pemerintahan Islam semua orang akan bekerja bersama-sama sebagai satu keluarga besar, menjadikan semua makhluk sebagai satu kesatuan tanpa tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Satu-satunya perang yang sah dalam Islam adalah perang yang dilakukan untuk membela kebenaran dan keadilan. Perang yang dimaksud adalah jihad yang berusaha menegakkan sistem dan tatanan Islam, dengan mengukuhkan peradabannya di bumi.1 Secara etimologis, jihad mempunyai makna berjuang untuk mencapai tujuan yang terpuji. Dalam konteks Islam, kata jihad memuat banyak makna. Kata ini bisa berarti perjuangan melawan kecenderungan jahat atau pengerahan daya upaya demi menegakkan Islam dan umat. Misalnya, mencoba mengimankan orang yang ingkar (kafir atau tidak beriman) dan bekerja keras memperbaiki moral masyarakat Islam. Dalam kitab-kitab fiqih Islam, kata jihad berarti perjuangan bersenjata melawan orang kafir. Kadang-kadang jihad dengan pedang disebut ”jihad kecil”, sebagai lawan dari bentuk damainya, yang dinamai ”jihad besar”.2 Menurut Hasan al-Banna, jihad mempunyai beberapa makna, di antaranya: Pertama, adalah amar ma’ruf nahi munkar, memberikan nasehat kepada para pemimpin dan segenap umat Islam menuju jalan Allah SWT., Rasul-Nya dan kitab-Nya. Tidak ada suatu kaum yang meninggalkan aktivitas saling menasehati, kecuali kaum itu akan menjadi hina; tidak ada suatu kaum yang meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar, kecuali kaum itu akan direndahkan. Kedua, menyisihkan sebagian waktu, sebagian harta, dan sebagian kepentingan pribadi untuk kebaikan Islam Sayyid Quthb, As-Salâm al-‘Alami wa al-Islâm, (Dâr asy-Syurûq, Kairo, 1974), hlm. 23-24. 2 John L. Esposito, Dunia Islam Modern, jilid II, (Mizan, Bandung, 2001), hlm. 63. 1 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 155 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) dan putra-putra kaum Muslimin. Jika mempunyai posisi sebagai pemimpin, ia berinfak untuk memenuhi kebutuhan anak buahnya. Ketiga, menjadi pejuang Allah, mempersembahkan jiwa dan kekayaan hanya untuk-Nya hingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Ketika keagungan Islam diganggu, keotentikannya dikoyak, kemuliaannya dinodai, lalu terompet kebangkitan ditiup untuk perjuangan mengembalikan kejayaan Islam, maka ia menjadi orang pertama yang memenuhi panggilan itu dan menjadi orang pertama yang maju membela Islam. Keempat, menentang orang yang mengingkari agamanya, memutus hubungan dengan orang yang memusuhi Allah dan rasul-Nya. Kelima, berjuang mewujudkan neraca keadilan di tengah masyarakat dan memperbaiki urusan mereka, menolong orang yang dizhalimi dan membasmi kezhaliman, siapa pun pelakunya.3 Menurut al-Mawdudi, makna jihad adalah bahwa di dalam diri umat Islam, terdapat semangat (ghirah) terhadap keimanan, cinta kepada agama, dan nasehat yang tulus untuk saudara-saudara Muslim. Jihad fî Sabîlillah dalam pengertiannya yang khusus, yaitu perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di hadapan musuh-musuh Islam. Tidak ada yang memicu perjuangan tersebut, selain mencari keridlaan Tuhan.4 Dengan demikian jihad adalah kelanjutan dari ”politik Tuhan”. Jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk melucuti musuh-musuh Islam, sehingga memungkinkan kaum Muslimin menerapkan ketentuanketentuan syari’at yang selama ini diabaikan. Penegakan hegemoni Islam melalui jihad adalah membebaskan individu-individu dari dominasi politik nonMuslim. Begitu kekuasaan politik berada di tangan elit Muslim dan syariat Islam ditegakkan, maka seluruh warga negara dibebaskan; apakah memeluk Islam atau tetap dalam kepercayaannya yang non-muslim, asalkan mereka berdamai dan tidak menyerang Taufiq Yusuf Al-Wa’iy, 2003, Al-Fikr as-Siyâsi, al-Mu‘âshir ‘Inda Ikhwân al-Muslimîn; Dirâsah Tahlîliyah, Maidaniyah, Muwatsaqah (Pemikiran Politik Kontemporer Ikhwanul Muslimin; Studi Analitis, Observatif, dan Dokumentatif), Era Intermedia, Solo. 24-26. 4 Muhammad Abdullah Al-Khatib dan Muhammad Abdul Halim Hamid, Nadlarât fî Risâlah at-Ta‘lîm, (Konsep pemikiran dan gerakan Ikhwan (terj.) (Bandung: Asy-Syâmil Press, 2001), hlm. 148. 3 156a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) Islam. Berkaitan dengan jihad ini, Abdullah Ibnu al-Mubarak melantunkan syairnya yang indah: Wahai ahli ibadah di Haramain, andai kamu melihat kami Kamu tahu, bahwa kamu bermain-main dengan ibadahmu Bila orang membasahi pipi dengan cucuran air matanya Maka leher-leher kami telah berlumur dengan darah kami Bila kuda-kuda orang lelah dalam (membela) kebatilan Maka kuda kami pun kelelahan dalam peperangan Buat kalian adalah wanginya minyak, tetapi bagi kami Wanginya derap kuda dan debu suci yang beterbangan.5 Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian jihad secara khusus adalah berjuang di jalan Allah Swt., sedangkan pengertiannya secara umum, seluruh kehidupan manusia dari awal sampai akhir merupakan jihad. Jihad yang dilakukan oleh kaum Muslim mempunyai tujuan yang jelas, memotivasi semangat kesalehan dan keagamaan, untuk membuktikan kebenaran dan kejayaan Islam. Di sini jihad secara tegas dimaknai sebagai bellum justum dan sekaligus bellum pium—berjuang untuk keadilan dan kesalehan. Dengan makna ini, menurut teori hukum Islam, dunia dibagi menjadi dua: dâr al-Islâm (wilayah Islam), yang terdiri dari wilayah-wilayah Islam di bawah kedaulatan Islam, dan selebihnya adalah dâr al-harb (wilayah perang). Wilayah pertama mencakup komunitas Muslim dan non-Muslim yang menerima, serta bersekutu dengan kekuasaan Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam syari’ah atau fiqih. Sedangkan wilayah kedua, yang berada di luar wilayah Islam, tidak atau kurang mempunyai kompetisi legal untuk masuk ke dalam hubungan dengan Islam. Sebagian ahli fiqih, terutama dari pengikut madzhab Syafi’i mengatakan bahwa pembagian dunia menjadi dua wilayah Ibid., hlm. 157-158. 5 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 157 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) itu tidak memadai. Mereka menambahkan wilayah ketiga yang disebut dâr al-shulh (wilayah damai). Melalui kategori ketiga ini pengakuan penuh diberikan kepada masyarakat agama dan etnis politik non-Muslim, jika mereka mengadakan perjanjian nonagresi dengan kekuasaan Islam. Namun pengikut madzhab Hanafi tidak mengakui pembagian ketiga ini, dengan alasan bahwa penduduk wilayah non-Muslim yang mengadakan perdamaian dan membayar jizyah kepada kekuasaan Islam menjadi bagian integral dari wilayah Islam dan karena itu berhak mendapat perlindungan, jika tidak demikian mereka masuk dalam kategori dâr al-harb. Secara teoritis, dâr al-Islâm berada dalam keadaan ”pertentangan nilai” secara terus-menerus dengan dâr al-harb. Tetapi perlu ditegaskan, ”pertentangan” dalam kaitan misi universal Islam itu tidak harus selalu melibatkan jihad dalam pengertian perang, sebab menyebarkan Islam dapat pula dicapai dengan cara damai. Bagaimanapun, perang tentu saja tetap potensial dalam dinamika hubungan antara kedua wilayah, terutama jika mempertimbangkan doktrin Islam tentang keutamaan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Untuk menguatkan eksistensi jihad sebagai sarana memperjuangkan syari’at Tuhan, sebagian kalangan memakai beberapa dalil sebagai penopangnya, di antaranya: 1. Al-Qur’an sering menyebut jihad melawan orang kafir, di antaranya firman Allah, ”Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata: ”Tuhan kami adalah Allah.”6 Ayat ini diturunkan tak lama setelah hijrah, yang menurut para mufassir (ahli tafsir) dianggap sebagai ayat pertama tentang melawan orang tak beriman. 2. Al-Qur’an telah menegaskan keutamaan jihad ini, dalam firman Allah Swt., ”Tidaklah sama antara mukmin yang 6( 158a QS. Al-Hajj {22}: 39-40) Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) duduk-duduk (tidak turut berjihad) yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orangorang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orangorang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orangorang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari-Nya, ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”7 3. Allah Swt. berfirman, ”Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berjihad) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasulullah. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shaleh. Sesungguhnya Allah tidak menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shaleh pula). Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”8 Masih banyak ayat lain yang menyuruh seorang Muslim ikut ambil bagian dalam jihad ”dengan harta dan jiwanya (bi amwâlihim wa anfusihim). Ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan masalah praktis, seperti pembebasan dari wajib militer, berjihad pada bulan-bulan suci hukumnya haram dan dalam kawasan suci Mekkah hukumnya juga haram, nasib para tawanan perang, meminta perlindungan, dan gencatan senjata atau perjanjian damai. 7 8( (QS. An-Nisâ {4}: 95-97) QS. At-Taubah {9}: 120-121) Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 159 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) Ada dua hal yang dapat ditangkap dari makna yang terkandung dalam ayat-ayat tentang jihad. Di satu sisi, Al-Qur’an memperbolehkan memerangi orang kafir hanya sebagai usaha mempertahankan dan membela diri terhadap agresi, dan di sisi lain jihad boleh dilakukan dalam segala keadaan. Untuk mendukung pandangan pertama, dapat disitir sejumlah ayat yang secara tegas membenarkan perang karena agresi atau pengkhianatan (melanggar perjanjian damai atau gencatan senjata) di pihak orang kafir, diantaranya: ”Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang melampaui batas.”9 Dan ”Tetapi, jika mereka merusakkan sumpah (janji)-nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, perangilah para pemimpin orang-orang kafir itu.”10 Ayat-ayat ini memerintahkan kepada kaum Muslim untuk memerangi orang kafir tanpa syarat. Pandangan kedua, syarat umum bahwa perang hanya diperkenankan untuk membela diri dapat dipahami dari ayat berikut, ”Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta m,ereka tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya –dan tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang) yang telah diberikan Al-Kitab— hingga membayar jidzah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk.”11 4. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, ”Sesungguhnya, di dalam surga terdapat seratus derajat yang disediakan untuk para mujahidin di jalan Allah; di mana jarak antara derajat satu dengan lainnya itu seperti jarak antara langit dan bumi.”12 5. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Muadz ra. berjalan QS. Al-Baqarah {2}: 190) (QS. Al-Taubah {9}: 12) 11( QS. Al-Taubah {9}: 29) 12 (HR. Al-Bukhari) 9( 10 160a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) bersama Rasulullah Saw., kemudian beliau bersabda kepadanya, ”Wahai Muadz, bila kamu mau, maka kuceritakan kepadamu pokok bagi urusan (agama) ini serta puncaknya; pokok urusan (agama) ini adalah kalimat ”Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah saja; tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya. Tiang penyangga urusan (agama) ini adalah penegakan shalat dan penunaian zakat. Sedangkan puncak dari urusan (agama) ini adalah jihad fî sabîlillah; Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah saja; tiada sekutu bagi-Nya, dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Apabila mereka melakukan semua itu, maka mereka telah berpegang teguh (dengan agama Islam) serta terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan (hisab) mereka diserahkan kepada Allah Swt. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah pucat wajah seseorang dan berdebu kedua kakinya dalam amal untuk mencari derajat (yang tinggi) di surga setelah (melakukan) shalat wajib, seperti jihad fî sabîlillah. Tiada yang memberatkan timbangan (amal kebaikan) seorang hamba, (melebihi) seseorang yang mati di jalan Allah, atau membawa beban (perbekalan) di jalan Allah.”13 Jihad sebagai Doktrin dan Gerakan Doktrin hukum dan konsep tentang jihad merupakan hasil perdebatan dan diskusi panjang yang sudah berlangsung sejak Nabi wafat. Melalui perdebatan dan diskusi inilah doktrin itu dikembangkan. Periode perumusan doktrin jihad secara bertahap ini berlangsung bersamaan dengan periode penaklukan besarbesaran oleh kaum Muslim. Para penakluk Muslim umumnya terbuka terhadap budaya-budaya rakyat yang mereka taklukkan. Doktrin jihad mungkin telah dipengaruhi oleh budaya Kerajaan Bizantium, tempat gagasan tentang perang agama dan gagasangagasan yang terkait dengannya masih banyak yang hidup. 13 (HR. Ahmad) Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 161 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) Meskipun demikian, amatlah sulit mengidentifikasi pengaruh ini. Jika memang ada kemiripan, itu tidak mesti merupakan hasil dari transformasi, tetapi mungkin akibat dari perkembangan yang terjadi secara paralel. Jihad terdiri dari beberapa tahapan dan rangkaian; setiap rangkaian mengantarkan pada rangkaian berikutnya. Tahapan ini dinarasikan oleh para pemikir Muslim dalam tiga strategi: Strategi pertama, orang dipersilahkan masuk Islam, agama terakhir, jalan kebenaran, hukum yang melaksanakan keadilan bagi semua orang. Strategi kedua, jika mereka menolak, mereka diminta membayar jidzah (pajak perlindungan) sebagai tanda dihentikannya permusuhan, dan pengakuan mereka akan kebebasan kaum Muslim untuk menyebarkan keyakinannya. Jika mereka masih menolak, maka strategi ketiga, satu-satunya pilihan terakhir yang ada hanyalah perang, karena musuh-musuh Islam akan melawan kehendak Tuhan dan mencegah umat Islam untuk berdakwah. Jadi perang bukan satu-satunya jalan dalam jihad. Perang melawan orang kafir, tidak boleh dilakukan tanpa sebelumnya menyeru mereka kepada Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadits ketika Nabi mengangkat seorang komandan pasukan atau ekspedisi perang, beliau bersabda, ”… Sekiranya engkau bertemu dengan musuh-musuhmu ajaklah mereka kepada tiga hal. Terimalah apa yang mereka sepakati dan janganlah memerangi mereka. Ajaklah mereka masuk Islam. Apabila mereka setuju, terimalah pengakuan mereka. Dalam hal ini, ajaklah mereka berpindah dari wilayah mereka ke wilayah imigran (madinah). Apabila mereka menolak, biarkan mereka mengetahui bahwa mereka adalah seperti orang badui Muslim yang hanya turut ambil bagian dalam rampasan perang ketika mereka berperang bersama kaum Muslim (lainnya). Apabila mereka menolak untuk memeluk Islam, mintalah mereka membayar jidzah (pajak jiwa). Apabila mereka setuju, terimalah ketundukan mereka. Akan tetapi, apabila mereka menolak, mohonlah pertolongan dari Allah dan perangilah mereka”.14 Hadits ini merangkum dengan baik tujuan memerangi orang kafir: konversi (memeluk Islam) atau tunduk di bawah 14( 162a HR. Muslim) Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) bendera dan undang-undang Islam. Dalam kasus yang terakhir, para musuh berhak bertahan pada agamanya dan mempraktikkan agamanya sebagai imbalan bagi pembayaran pajak jiwa. Dua alternatif pertama merupakan tawaran yang mengarah pada kedamaian (pilihan antara masuk Islam atau membayar jidzah), namun jika dua alternatif ini tidak bisa dikompromikan, maka tidak ada larangan untuk memerangi mereka. Doktrin jihad, seperti yang dijelaskan dalam karya-karya hukum (fiqih) Islam, berasal dan diturunkan dari wacana AlQur’an serta contoh Nabi dan Khulafaurrasyidîn sebagaimana yang termaktub dalam sejarah Islam. Inti doktrin tersebut adalah menciptakan suatu negara Islam tunggal, yang meliputi dan memerintah segenap umat. Umat berkewajiban memperluas wilayah negara itu untuk mengajak sebanyak mungkin manusia berada di bawah kekuasaannya. Tujuan akhirnya adalah membawa seluruh manusia di permukaan bumi ini ke dalam pelukan Islam. Islam sendiri dengan sangat tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama.15 Tetapi, menurut Sayyid Quthb, paksaan biasanya terjadi ”terhadap mereka yang menentang agama dengan kekerasan.”16 Dalam hal ini Islam telah meletakkan tanggung jawab tertentu pada kaum Muslim, meliputi: (1) Kaum Muslim wajib menjaga kepercayaannya, agar mereka tidak menyimpang dari agama, dengan memperkenankan penggunaan kekuatan untuk memukul mundur kekerasan. (2) Islam harus dijamin kebebasannya dalam melakukan dakwah, kalau tidak, maka menjadi kewajiban bagi kaum Muslim untuk melenyapkan kekuasaan penindas mana saja di bumi yang merintangi dakwah Islam. (3) Kaum Muslim harus sanggup mengukuhkan kedaulatan Tuhan di bumi, dan menyingkirkan mereka yang merebut kedaulatan-Nya dengan membuat undang-undang ala manusia. (4) Kaum Muslim harus bebas menegakkan keadilan tertinggi, sehingga semua orang dapat menikmati kebaikannya. Ini berarti kaum Muslim harus melawan penindasan dan ketidakadilan di mana saja berada, baik penindasan individu terhadap diri sendiri, penindasan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, (QS. Al-Baqarah {2}: 256) Sayyid Quthb, As-Salâm al-‘Alami wa al-Islâm, hlm. 22. 15 16 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 163 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) maupun penindasan pemerintah terhadap rakyatnya. Ada beberapa fungsi terpenting dari doktrin jihad, di antaranya: pertama, memobilisasi dan memotifasi kaum Muslim untuk mengambil bagian dalam perang melawan orang kafir, karena hal itu dinilai sebagai kewajiban religius. Motifasi ini di dorong oleh gagasan bahwa mereka yang gugur dalam peperangan (yang disebut syahid) akan langsung masuk surga. Ketika akan berlangsung perang melawan orang kafir, teks-teks religius diedarkan, penuh dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan haditshadits yang memuji keutamaan dan kebaikan berjihad, serta menggambarkan dengan jelas balasan yang menanti di akhirat bagi yang meninggal dalam peperangan sebagai syahid. Kedua, doktrin jihad memberikan sehimpunan ketentuan yang mengatur hubungan kaum Muslim dengan kaum non-Muslim, dan mengatur perilaku selama peperangan berlangsung. Para mufti bisa menetapkan ketentuan-ketentuan ini dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri seorang penguasa sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Islam. Aturan-aturan ini dapat ditetapkan agar sesuai dengan keadaan. Jika perang dilakukan sebagai usaha membela diri dari agresi, perang tersebut mempunyai justifikasi. Gagasan-gagasan tentang kesatriaan dalam perang melarang prajurit membunuh yang bukan prajurit; seperti anak-anak, wanita dan orang tua. Ketiga, doktrin jihad menurut John L.Posito memberikan legitimasi bagi penguasa dalam memerintah wilayah-wilayah dunia Muslim yang berbeda.17 Ketika persatuan dan kesatuan politik umat yang pernah terjalin dalam sistem kekhalifahan lenyap dan tidak pernah dapat dipulihkan kembali, maka penguasa bertanggung jawab untuk merangkul semua eksponen yang ada dalam negaranya. Salah satu cara untuk memperoleh legitimasi yang lebih besar adalah melakukan jihad untuk menyatukan umat. Permasalahannya adalah ketika dua negara Muslim berperang satu sama lainnya—suatu kemungkinan yang bisa terjadi setelah hancurnya sistem kekhalifahan dan persatuan politik Islam— maka harus ada solusinya. Dalam situasi demikian, biasanya para mufti mencari dalih atau sebab untuk menyatakan pihak John L. Esposito, Dunia Islam Modern, hlm. 183. 17 164a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) lawan sebagai pembangkang atau zindik, sehingga memberikan pembenaran untuk memerangi mereka. Slogan jihad tidak hanya digunakan oleh penguasa untuk meredam gejolak para pemberontak, tetapi juga digunakan oleh kelompok-kelompok radikal muslimin untuk melancarkan aksinya. Ketika mereka berjuang melawan penjajah dan dominasi orang asing di Suez, Ismailiah, Kairo dan beberapa tempat lainnya, mereka menerapkan sistem jihad ini. Demikian halnya dalam memperjuangkan pemurnian Islam dan pendirian suatu negara Islam, mereka juga memaklumkan jihad terhadap lawanlawan mereka, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Kelompok ini, menganjurkan penggunaan kekerasan untuk menjatuhkan pemerintahan yang mapan. Namun, mereka dihadapkan pada problem doktrin serius ketika mereka mempropagandakan revolusi bersenjata terhadap para penguasa Muslim, karena hukum Islam hanya membolehkan pemberontakan dalam situasi yang sangat khusus, salah satunya adalah apabila seorang penguasa menanggalkan kepercayaan Islamnya; sebagai seorang yang murtad, penguasa itu layak untuk diperangi. Dengan demikian, eskalasi politik dan pemikiran kontemporer tentang jihad menawarkan spektrum pandangan yang lebih luas. Interpretasi yang radikal dalam memaknai jihad sebagai perang, tidaklah mutlak identik dengan organisasi Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Sebab sebagian mereka tidak memaknai jihad secara taken for granted. Dalam perkembangannya, Ikhwanul Muslimin sendiri terbagi dalam dua orientasi: pertama, kelompok radikal fundamentalistik yang menarik pelajaran berharga dari kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivis Ikhwanul Muslimin era 40-an. Menurut mereka, hanya dengan sikap menentang terhadap pemerintah yang berkuasa, mereka akan berhasil. Mereka inilah yang cenderung memaknai jihad sebagai perang dan penggunaan cara-cara radikal dalam melawan pemerintah. Pandangan kelompok ini terinspirasi oleh ideolog Ikhwan, seperti Sayyid Quthb. Selain pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Sayyid Quthb, pernyataan paling fasih dan canggih dari kelompok ini disampaikan oleh Abd al-Salam Faraj yang dimuat dalam risalahnya berjudul: Al-Farîdah Al-Ghâibah. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 165 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) Penulis buku ini meminjam fatwa yang dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328), ketika dia dimintai pendapat berkenaan dengan legitimasi kekuasaan mongol di Timur Tengah. Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah adalah fakta bahwa para penguasa mongol memberlakukan hukum mereka sebagai kafir, sekalipun mereka mengaku beriman. Menurut Faraj, situasi yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah tadi mirip dengan situasi Mesir, karena hukum Mesir– kecuali hukum keluarga dan hukum waris—didasarkan atas aturan perundangan yang berasal dari gagasan Barat. Kendatipun ada tuntutan dari berbagai kelompok Islam, pemerintah selalu menolak untuk memberlakukan syari’at Islam. Sehingga, Faraj menyimpulkan pemerintah seperti itu tidak bisa dianggap sebagai pemerintah Islam dan harus dilawan. Selain kaum radikal, yang setia pada bentuk penafsiran yang dikemukakan dalam kitab-kitab klasik tentang jihad, terdapat kelompok kedua, kelompok yang berupaya untuk menampilkan wajah yang lebih moderat terhadap kelompok lain dan pemerintah. Yang menjadi simbol tren kelompok ini adalah diangkatnya Hasan al-Hudaiby pada 1951, seorang hakim Mesir yang terkenal sikap moderatnya dalam politik, untuk menggantikan Imam Hasan al-Banna. Kelompok ini terinspirasi oleh sikap moderat yang ditampilkan oleh Muhammad Abduh (1849-1905) dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) yang berpendapat bahwa hidup berdampingan secara damai antara wilayah Islam dan non-Islam merupakan kondisi normal dan bahwa jihad dengan peperangan tidak diperkenankan, kecuali untuk mempertahankan diri. Pembuktian terhadap kebenaran dan eksistensi Islam, bagi kaum moderat Ikhwan tidak mesti dicapai hanya dengan cara-cara militer dan kekerasan, tetapi dapat juga dengan cara-cara damai. Jika merujuk pada kelompok kedua ini, sangat wajar bila beberapa pemikir Ikhwan menolak pemahaman Barat yang telah melebih-lebihkan dan mendistorsi makna jihad. Mereka juga menolak tuduhan Barat yang mengatakan bahwa kata jihad sering diartikan umat Islam dengan kekejaman dan pertumpahan darah. Islam menurut Barat disebarkan dengan pedang, dan syari’at Islam adalah syari’at yang tidak bersahabat. Seorang mujahid, 166a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) bagi Barat digambarkan sebagai gerombolan-gerombolan buas, manusia liar yang selalu menghunus pedangnya, sorot matanya menampakkan kebencian, seluruh pikirannya terfokus pada pembunuhan dan perampasan. Setiap melihat orang kafir langsung ingin menyerangnya dan memegang lehernya, sambil memberikan pilihan: masuk Islam, membayar jidzah, atau diperangi. Padahal, menurut mereka tidak satu pun peristiwa dalam sejarah Islam yang mendukung dan menguatkan pendapat Barat. Sesungguhnya, sejarah sampai hari ini memberikan kesaksian sebaliknya; Barat selama berabad-abad, dari generasi ke generasi, berperang dan menjajah demi memenuhi keinginan mereka, memuaskan ketamakan mereka yang tak terpuaskan. Kaum Muslim di mana pun mereka berada selalu menjadi korban pengkhianatan, penindasan, intimidasi dan penyiksaan. Melawan Dominasi Barat Setelah berakhirnya Perang Dingin, yang dipicu oleh bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, dunia menyaksikan pergeseran struktur politik global. Selama lebih dari 50 tahun, dunia terbelah dalam struktur bipolar dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet berada pada dua kutub yang berbeda secara diametral. Bubarnya Uni Soviet kemudian menyisakan sebuah kutub, yakni Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan. Sejak saat itu, para pemikir Barat, berusaha keras mendefinisikan lingkup global yang baru tersebut dan bagaimana menempatkan Amerika Serikat sebagai sebuah kekuatan yang hegemonik. Samuel P. Huntington mempunyai analisa menarik tentang hal ini. Walaupun tulisan awalnya mengenai the clash of civilization di jurnal Foreign Affair tahun 1993 dihujani kritik tajam, namun Huntington mengelaborasi lebih jauh persoalan dominasi dan hegemoni Amerika Serikat. Huntington memperingatkan Amerika Serikat terhadap munculnya peradaban lain (the others), peradaban Timur dan peradaban lainnya. Dalam tulisannya yang berjudul The Lonely Superpower di Foreign Affairs (1999), ia juga menyatakan bahwa walaupun Amerika Serikat sekarang menjadi satu-satunya negara super power, namun tidak berarti dunia saat ini berstruktur Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 167 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) unipolar, seperti yang dianggap oleh banyak pihak. Para ahli percaya, terorisme merupakan suatu bentuk serangan balik (blowback) atas hegemoni Amerika Serikat. Terorisme, menurut Profesor Johnson, merupakan harga dan konsekwensi yang harus dibayar oleh ”American Empire.” Fakta sejarah membuktikan adanya hubungan yang kuat antara keterlibatan Washington dalam masalah internasional dengan peningkatan serangan teroris terhadap Amerika. Serangan teroris, munculnya negara pembangkang (rogue state) semacam Afghanistan dan Korea Utara atau maraknya perdagangan senjata ilegal, merupakan serangan balik terhadap operasi militer dan kebijakan intervensi Amerika Serikat di negara-negara lain. Embargo Amerika Serikat terhadap Irak, Afghanistan, Libya dan negara-negara lainnya atau dukungan Washington kepada Israel yang berlebihan membuat Amerika Serikat jadi sasaran utama aksi terorisme. Sejak Perang Teluk sampai sekarang, Amerika Serikat mensponsori embargo Irak yang mengakibatkan tewasnya setengah juta lebih penduduk sipil Irak karena ketiadaan obat, makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Sandy Berger, Ketua Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat bahkan mengatakan bahwa blokade ekonomi itu telah menimbulkan kesengsaraan yang terhebat sepanjang sejarah dunia. Penderitaan dan rasa ketidakadilan yang sengaja ditebarkan oleh Amerika Serikat telah membuat orang-orang Irak dan negara lain yang survive membenci Amerika Serikat sampai ke ubunubun. Pada saat yang sama, kebijakan Amerika Serikat di Timur tengah dan pemihakannya terhadap Israel, menyulut kemarahan yang luar biasa terhadap Amerika Serikat. Konsekwensinya, terorisme adalah senjata ampuh dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuatan. Orang bilang ”Terrorism is the power of the powerless.” Namun, pasti ada aksi berantai (action-reaction chains) jika teror dilakukan. Hal ini sudah merupakan hukum besi-teror, tidak ada teror yang dapat berjalan tanpa melahirkan teror balasan. Buktinya, pengeboman Kedubes Amerika Serikat di Nairobi dan Dar Es-Salam pada 7 Agustus 1998, melahirkan serangan balasan Amerika Serikat dengan menembakkan lebih dari 80 rudal ke pabrik obat di Khourtoum, Sudan dan kamp Mujahidin, di Afganistan. Serangan terorisme ala 168a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) kamikaze ke WTC dan Pentagon pada 11 September tahun 2001 lalu, juga melahirkan agresi Amerika Serikat ke Afganistan. Jihad versus Terorisme Terorisme seringkali dialamatkan kepada salah satu pengikut agama. Padahal, aksi terorisme yang dilakukan oleh mereka sebenarnya lebih didorong oleh keyakinan terhadap agamanya yang diekspresikan secara radikal dan fundamental. Kelihatannya, ada hubungan yang paralelism antara aksi terorisme dengan ekspresi beragama yang radikal dan fundamental. Tak heran, jika terorisme yang terjadi di belahan dunia ini lebih banyak dimunculkan oleh kelompok-kelompok agama yang mendasarkan pada doktrin fundamental agama, dan pada gilirannya memiliki watak yang khas, yakni berkeinginan untuk merubah tatanan sosial sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang paling fundamental tersebut. Jika kita analisis, ada perbedaan yang signifikan antara terorisme dengan konsep jihad dalam agama Islam. Terorisme setidaknya mencakup beberapa unsur; Pertama, adanya kelompok atau negara yang ingin mengartikulasikan kepentingannya. Kedua, artikulasi itu diwujudkan lewat aksi kekerasan. Dan, Ketiga, aksi kekerasan itu terkadang ditujukan pada warga sipil atau sasaran tertentu, untuk menimbulkan ketakutan atau memperoleh dampak reaksi yang diinginkan. Sedangkan istilah jihad sendiri tidak memberi konotasi adanya keterkaitan antara agama dan kekerasan. Dalam hal ini, jihad, bukanlah sinonim istilah Islam terhadap istilah ‘Terorisme’. Ibnu khaldun dalam Muqaddimah dan al-Mawardi dalam Ahkam Sulthaniyah menerangkan secara detil tentang hal ini. Menurut mereka, jihad lebih berupa suatu konsep tindakan, yang realisasinya tidak harus berwujud peperangan, tetapi juga mencakup cara-cara damai. Rudoph Peters dalam Jihad in Medieval and Modern Islam menyebutkan, tujuan utama jihad bukanlah untuk memaksa orang kafir memeluk Islam, seperti dikemukakan dalam banyak literatur Barat. Tujuan pokoknya, adalah perluasan dan juga pembelaan kawasan Islam. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Montgomery Watt dalam Islamic Political Thought. Menurutnya, Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 169 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) istilah jihad tidak bisa disamakan dengan “perang suci”. Karena perang suci, umumnya dipahami sebagai perang yang dilakukan semata-mata atas alasan konfrontasi agama. Apapun makna aktual yang kita berikan pada istilah itu, pada kenyataannya telah terjadi simplifikasi makna dengan mereduksi makna jihad, menjadi sekedar “perang suci demi agama”. Bahkan, dalam berbagai wacana pun sering terjadi bias simplifikasi makna ini. Akibatnya, banyak energi yang kita habiskan, bukan untuk merumuskan masalah pokok atau memberikan solusi, namun hanya untuk meluruskan bias-bias tentang makna jihad ini. Apa yang dilakukan oleh para teroris ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Hal ini karena Islam sesungguhnya tidak mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan aksi kekerasan kepada orang-orang yang tidak berdosa demi menegakkan agama. Bukankah ini juga menciptakan citra buruk agama Islam di mata umat agama lain? Padahal wajah agama Islam tidak demikian, ia damai, santun dan elegan. Islam adalah agama perdamaian, sementara terorisme adalah perbuatan biadab yang tidak berperikemanusiaan. Yang jelas, terorisme adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Islam misalnya, selalu mengajarkan kedamaian dan kelembutan. Kata “Islam” sendiri memiliki arti pasrah, menyerah diri, dan damai. Karena itulah, dalam al-Qur’an disebutkan, “Allah menyeru kepada dar al-salam, negeri yang damai, bukan negeri yang penuh dengan gejolak, ketakutan, kekhawatiran, dan perang. Bahkan, ajaran perang di dalam Islam tidak diperbolehkan membunuh kepada musuh-musuh yang tidak sedang dalam keadaan menyerang, para wanita dan anak-anak. Ideologi jihad dalam Islam tidak dilakukan untuk menghancurkan orang-orang yang tidak berdosa, melainkan untuk mempertahankan diri. Karena itulah, perang melawan terorisme mesti kita serukan dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang lebih damai dan tidak dihantui rasa takut dan kekhawatiran karena teror para terorisme. Dengan demikian, kekerasan atas nama agama tidak pernah mendapatkan pembenaran. Justru agamalah yang memberikan konsep kepada kita untuk menghormati jiwa, 170a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) akal, harta benda, dan kehormatan, sehingga agama tidak bisa dilabelkan pada aksi kekerasan yang dilakukan penganutnya. Di sinilah kita semua mesti memberikan penyadaran kepada semua umat beragama untuk bersatu melawan terorisme dan melindungi diri dengan paham-paham keagamaan yang toleran demi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Penutup Ketika mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush menggalang sebuah koalisi internasional dalam semangat ”Wanted: Dead or Alive”, kita pun tercengang dan berfikir, telah terjadi kemunduran yang sangat jauh dan akut dalam dunia diplomasi. Agresi Amerika Serikat ke Irak dan Afganistan dengan menggunakan kekerasan, nyatanya bukanlah senjata ampuh dalam membasmi terorisme. Mobilisasi dan eskalasi kekuatan militer di kawasan Timur Tengah pun tidak membuahkan hasil yang signifikan, selain kerusakan bangunan dan ekonomi setempat. Kita pun bertanya, perlawanan terhadap terorisme seperti inikah yang ingin dibangun dan dibentuk oleh negara-negara yang mengatasnamakan perdamaian dan keadilan? Media yang menguasai pasar Amerika Serikat tidak banyak menyebarkan pesan pemikir, seperti Edward W. Said dan Noam Chomsky yang mengingatkan bahwa serangan militer tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali penderitaan, dendam panjang dan lingkaran kekerasan yang sukar diputuskan. Peringatan ini seperti menegaskan apa yang dikatakan oleh tokoh anti kekerasan, Mahatma Gandhi, ”An eye for an eye makes the whole world blind.” Memang sudah waktunya dunia mulai memberikan perhatian dan jawaban terhadap masalah-masalah internasional. Pengaturan dan penataan ulang berbagai permasalahan internasional, mulai dari persenjataan pemusnah massal sampai terorisme, bisa diselesaikan secara beradab melalui mekanisme peradilan multilateral daripada di medan pertempuran atau melalui berbagai sanksi ekonomi. Peradilan internasional yang menangani hak asasi manusia, genocide, penyiksaan, kejahatan perang dan sejenisnya perlu penanganan dengan damai dan diplomasi. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 171 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) Agresi Amerika Serikat terhadap negara-negara yang dianggap terlibat bahkan mendalangi terorisme harus disertai bukti-bukti keterlibatan secara langsung dalam penyerangan WTC dan Pentagon. Karena, seperti yang disampaikan oleh mantan menlu Amerika Serikat, Henry A. Kissinger dalam tulisannya, ”The Pitfall of Universal Jurisdiction” dalam jurnal Foreign Affairs (Agustus 2001), jangan sampai mekanisme yang sekarang sedang berlangsung dalam tatanan peradilan universal sekarang ini didorong terlalu jauh ke sebuah titik ekstrem yang bisa melahirkan bahaya apa yang disebutnya sebagai pengganti ”tirany of judges” dari pemerintahan yang berkepentingan. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Irak pun harus melihat perspektif ini, sehingga tidak lagi muncul ketimpangan dan terorisme balasan yang semakin dahsyat.*** 172a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) DAFTAR PUSTAKA Quthb, Sayyid. As-Salâm al-‘Alami wa al-Islâm. Kairo: Dâr asySyurûq, 1974. Esposito, John L. Dunia Islam Modern, jilid II. Mizan, Bandung, 2001. Al-Wa’iy, Taufiq Yusuf. Al-Fikr as-Siyâsi, al-Mu‘âshir ‘Inda Ikhwân al-Muslimîn; Dirâsah Tahlîliyah, Maidaniyah, Muwatsaqah (Pemikiran Politik Kontemporer Ikhwanul Muslimin; Studi Analitis, Observatif, dan Dokumentatif), Era Intermedia, Solo, 2003. Al-Khatib, Muhammad Abdullah dan Muhammad Abdul Halim Hamid, Nadlarât fî Risâlah at-Ta‘lîm, (Konsep pemikiran dan gerakan Ikhwan (terj.) Bandung: AsySyâmil Press, 2001. Al-Qur’an al-Karim Hadits Shahih Bukhari Hadits Shahih Muslim Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 173 Jihad Melawan Terorisme (oleh:Abdurrohman Kasdi) 174a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) TEOLOGI ANTI KORUPSI DALAM TINJAUAN AL-QUR’AN Abdul Karim STAIN Kudus Email: [email protected] ABSTRAK Masalah korupsi sebenarnya merupakan wacana klasik yang terus bergulir dan terus mengalami dinamika perkembangan zaman. Menjadi sebuah isu yang sangat krusial untuk dipecahkan dan masih membelit bangsa Indonesia khususnya sampai saat ini. Tindak pidana korupsi disinyalir telah menjalar di semua bidang dan sektor pembangunan dan sulit untuk diatasi. Hal ini pun kemudian menjadi menarik untuk diperbincangkan dalam konteks teologi anti korupsi, mengingat bahwa praktek korupsi seakan menjadi suatu aliran tersendiri dalam kehidupan sosial keagamaan. Kita harus menghadirkan sebuah formula yang mampu menjelaskan atas pembacaan korupsi yang lebih komperhensif, khususnya dari sudut pandang al-Qur’an. AlQur’an memang tidak secara lugas menyebutkan term korupsi sebagai kesatuan hukum yang eksplisit, melainkan term-term tertentu seperti ghulu>l, al-suht, al-dawl, hira>bah yang mengarah pada subtansi korupsi tersebut. Berangkat dari term-term tersebut pula, sebuah kerangka rumusan anti korupsi mulai diperbincangkan dalam berbagai ragamnya sebagai bentuk epistemologi pencegahan dan juga pemberantasannya. Keywords: Teologi Anti Korupsi, Al-Qur’an, Pencegahan. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 175 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) Pendahuluan Masih tingginya indeks persepsi korupsi (IPK) atau angka tindak pidana korupsi sesungguhnya dapat kita lihat dari derasnya informasi di berbagai media yang memberitakan tentang tindak korupsi, hampir setiap hari dapat kita baca dari berbagai media yang terbit, artikel yang menyorot perilaku pejabat pusat sampai pejabat daerah yang menyalahgunakan wewenangnya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Ditinjau dari sudut Etimologis, kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio (penyuapan) dan corruptus (merusak). Kata ini lalu disalin ke dalam kosa kata bahasa Inggris yang disebut corruption atau corrupt. Selain itu dalam bahasa Perancis juga dikenal dengan kata corruption, sementara dalam kaidah bahasa Belanda dikenal dengan sebutan corruptie (korruptie). Menurut Andi Hamzah sebagaimana yang ditulis oleh M. Nurul Irfan dalam bukunya Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, bahwa kata korupsi yang sampai dan sering dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan plagiasi dari kata korruptie dalam bahasa Belanda.1 Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976), secara harfiah kata korupsi dapat diartikan “perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Hal senada juga disampaikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibio (Kamus Hukum: 1996), kata corruptio adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Sementara dalam khazanah Islam kata korupsi diistilahkan dengan kata risywah.2 Secara terminologi risywah sesuatu yang M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 33, lihat juga Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 4. Secara terminologis banyak ahli memiliki definisi masingmasing. Robert Klitgaard misalnya mendefinisikan “corruption is the abuse of public power for private benefit”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Lihat: Robert Klitgaard dkk., Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 3. 2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, 1 176a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.3 Sementara kata ghulul bermakna berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta yang lain, hal ini dapat diperhatikan dalam al-Qur’an surah Ali ‘Imran (3) ayat 161. Terlepas dari itu semua, pada intinya menurut penulis adalah bahwa setiap perbuatan yang berkaitan dengan merampas, mencuri, dan mengambil harta orang lain dengan cara zhalim, termasuk di dalamnya suapmenyuap merupakan bentuk dari korupsi. Selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana wawasan dan penjelasan al-Qur’an mengenai kejahatan dan bahaya korupsi. Sekilas Catatan Sejarah Korupsi Sebenarnya korupsi bukanlah merupakan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena korupsi ini telah dikenal dan menjadi bahan diskusi, bahkan sejak 2000 tahun yang lalu ketika seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya menulis buku berjudul ”Arthasastra”. Begitu juga Ungkapan “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” menjadi sangat terkenal pada tahun 1887-an, ungkapan sejarawan Inggris Lord Acton ini, menegaskan bahwa korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi. Tindak korupsi tidak hanya menjadi wabah di negara Indonesia saja, akan tetapi telah menyebar ke seluruh negara di Asia, bahkan negara-negara di dunia sehingga muncul berbagai ragam istilah yang mendefinisikan korupsi. Di China, Hong Kong dan Taiwan, misalnya, korupsi dikenal dengan nama yum cha, atau di India terkenal dengan istilah baksheesh, atau di Filipina dengan nama lagay dan di Indonesia atau Malaysia memiliki padanan kata yaitu suap.4 Akan tetapi tidak semua istilah ini (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 499, 1015. Dalam Kamus Bahasa Arab Modern (Al-Azhar: 2009), risywah tidak saja diartikan penyuapan, tapi juga diartikan dengan ketidakjujuran dan korupsi. 3 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, hlm. 89 4 Lihat: W.J.S. Poerwadarminta, kamus umum Bahasa Indonesia, 1976, hlm. 56, dan Lihat juga Kamus Dewan, edisi 3, 1994 dan juga Andi Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 177 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) secara spesifik mendefinisikan pengertian dari praktek korupsi. Istilah lokal yang dianggap paling mendekati adalah istilah yang berlaku di Thailand, yaitu istilah gin muong, yang secara literal berarti nation eating (memakan keuangan negara dengan cara ilegal). Sejarah mengenai korupsi sendiri memang cukup panjang. Menurut petunjuk Hans G. Guterbock, catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuapan terhadap hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah. Dalam sejarah Islam sendiri, pada era kekuasaan Khulafâ al-Râsyidîn tepatnya pada masa Umar bin al-Khattab juga telah ditemui upaya praktek korupsi. Hal ini dikuatkan dengan usaha Umar memerintah seorang sahabat yang bernama Maslamah untuk mengawasi harta kekayaan para pejabat pemerintah.5 Sejarah korupsi di Indonesia bukanlah wacana yang baru. Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa perilaku korup di negeri ini sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara. Pada waktu itu, perilaku korupsi diimplementasikan dalam bentuk upeti yang diberikan kepada pejabat atau pamong daerah setempat. Sehingga tidak heran hasil survei yang dilakukan oleh Transparancy Internasional (TI), di mana menurut TI fakta perkembangan korupsi di Indonesia per 2010 dapat dilihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2010 yang tetap pada angka 2,8 atau di peringkat 110 dari 178 negara yang disurvei. Posisi IPK sama dengan 2009. Maka dengan ini, bisa dikatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa progres.6 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mencatat, selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak kurang dari Rp. 103 Triliun dana pembangunan dirampok. Karena data itu merupakan hasil audit, jumlah itu baru sampling. Oleh karenanya, Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), cet. I, hlm. 339 5 Muhammad Husain Haikal, Sayyidina Umar bin khattab, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 665. 6 Bambang Soesatyo, Perang-perangan Melawan Korupsi, (Jakarta: Ufuk Press, 2011), hlm. xiii. 178a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) jumlah itu masih terus bisa bertambah.7 Selain BPK, statistik lain yang dirilis oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menyatakan, pada 2010 Indonesia adalah Negara paling korup di Asia Pasifik. Hasil survei PERC menyatakan, skor Indonesia adalah 9,27 (dari skala0-10) Semakin besar skornya, semakin koruplah sebuah negara. Dengan demikian, korupsi Indonesia bahkan lebih buruk dibanding beberapa negara di Asia Tenggara semisal Kamboja (9,10), Filipina (9,0), dan Thailand (8.0).8 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang semakin meningkat dan kemudian cenderung stagnan dalam pemberantasannya diasumsikan karena supremasi hukum yang tumpul terhadap penguasa. Boleh jadi hukum memiliki taring akan tetapi korupsi terus mengalami perkembangan dan lebih dilakukan secara sistematis. Oleh karenanya wacana pemberantasan korupsi harus terus diperbincangkan secara intensif, dalam hal ini, salah satu tawarannya apa yang akan segera penulis kemukakan. Dengan melihat beberapa fakta sejarah tersebut, maka sebetulnya pada masa Arab Era Islampun sesungguhnya kasus korupsi sudah ditemukan. Namun, seperti penulis tuturkan di muka, Al-Qur’an tidak mengemukakan ayat korupsi secara eksplisit. Bahkan secara tegas Ahmad Baidlawi menyebut bahwa dalam Islam, dalam konteks ini Al-Quran, kasus korupsi tidak diuraikan secara tekstual dengan jelas.9 Namun demikian, Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam, sumber inspirasi ilmu pengetahuan, pedoman dan sumber hukum dalam agama menyinggung tentang tindak pidana korupsi secara umum yang intinya adalah suatu praktek penyimpangan terhadap penyalahgunaan wewenang, dalam al-Qur’an korupsi atau riswah dianalogikan dengan istilah ghulu>l yaitu praktik Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melansir bahwa semenjak 2004 hingga 2008 tercatat ada lebih dari 31 laporan tindak pidana korupsi yang masuk selama 2008 saja, tercatat dalam satu hari ada 37 laporan yang masuk, dengan kerugian negara sekitar 1 miliar untuk setiap laporan. Jika dikalikan, maka dalam sehari 37 miliar uang negara melayang. 8 Bambang Soesatyo, Perang-perangan Melawan Korupsi, (Jakarta: Ufuk Press, 2011), hlm. xiii-xiv. 9 Ahmad Baidlawi, “Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam”, dalam Jurnal Esensia, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009, hlm. 8 7 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 179 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) suap menyuap (Q.S Ali Imran:161). Menurut Ibnu Katsir, seorang pakar tafsir ternama, menegaskan bahwa ghulul berarti menyalahgunakan kewenangan untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya dan berakibat merugikan pihak lain. Definisi Ibnu Katsir tersebut disepakati oleh para Ulama Indonesia (MUI: 1999) dalam fatwanya menetapkan bahwa algulul identik dengan korupsi, dan dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan haram. Sedangkan di lain ayat, al-qur’an mengistilahkan korupsi dengan al-batil (al-Baqarah:188) yaitu memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Imam al-Qurthubi menambahkan dalam Al-Ja>mi’ Li Ahka>mi al-Qur’a>n bahwa al-ba>t}il adalah perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak di benarkan syariat. Al-qur’an juga mengistilahkan korupsi dalam surat Al-a’ra>f: 56 dengan alfasa>d.10 Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Sayyid Husain al-Alatas menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khususnya, yaitu: (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, (g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, (i) menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.11 Sebagai sang pembawa risalah Nabi muhammad juga tidak ketinggalan dalam menyinggung hal ini, dalam hadistnya Rasulullah saw. bersabda: لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الرايش واملرتيش Al-Qurthuby (w. 681H). Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H), Cetakan ketiga, Juz 2, hlm. 711 11 S.H. Al-Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, terj. Nirwono, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 2. 10 180a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” [HR. Abu Daud no. hadits 3580] Kesemua istilah memiliki pengertian yang variatif, namun pada ujungnya merupakan kegiatan ilegal yang berlaku di luar sistem formal. Pengertian dari beberapa istilah tersebut menunjukkan adanya kerusakan yang luar biasa besar terhadap kehidupan suatu bangsa akibat dari adanya perilaku praktek korupsi. Jadi, dari berbagai definisi yang telah disebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu: 1. Korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 2. Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang di percayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Merujuk kepada beberapa definisi yang telah disebut, maka Al-Qur’an sebagai Kitab Suci Umat Islam sejatinya sangat menentang, mengutuk bahkan mengharamkan tindak korupsi, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan dalam bentuk pengkhianatan, penmyelewengan, mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Tindak korupsi, suap menyuap dan perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan munkar yang harus dicegah dan diberantas. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya penulis akan mencoba menguraikan interpretasi ayat-ayat yang mengandung term korupsi dengan memandang korupsi secara definitif pada konteks kekinian. Ayat-Ayat Tentang Korupsi Pada dasarnya, terminologi korupsi dalam Al-Qur’an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 181 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, misalnya, term perampokan (al-harb), pencurian (alsarq), term penghianatan (al-ghulu>l), dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin beragam, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. Al-Qur’an menjelaskan term-term tersebut sebagai berikut: 1. Ghulu>l (Penghianatan) Qs. Ali Imran : 161 ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ Ayat 161 dari surat Ali Imran ini, menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa kata ghulu>l dalam ayat itu bermakna ‘al-akhdz al-khafiyyah’, yaitu mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, semisal mencuri sesuatu. Kemudian makna ini sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum didistribusikan.12 Rasulullah sendiri memperluas makna ghulu>l menjadi dua bentuk: (a) Komisi, yaitu tindakan mengambil sesuatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan. Tentang hal ini Nabi menyatakan “Siapa saja yang aku angkat dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulu>l ).” HR. Abu Daud. (b) Hadiah, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda “Hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulu>l)”. HR. Ahmad.13 2. Al-Sa>riqah (Pencurian) Qs. Al-Maidah: 38 ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Bairut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2006), hlm. 98. 13 Ahmad Baidlawi, “Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam”, dalam Jurnal Esensia, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009, hlm. 4 12 182a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) ﭫ ﭬﭭ Kaitannya dengan ayat ini, Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri, maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata pada Nabi saw. “Wahai Nabi, wanita ini telah mencuri perhiasan kami”. Maka wanita itu berkata “Kami akan menebus curiannya.” Nabi bersabda, “Potonglah tangannya!” Kaumnya berkata, “Kami akan menebusnya dengan lima ratus dinar.” Maka Nabi Saw. pun bersabda, “Potonglah tangannya!” Maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya. “Ya Rasul, apakah ada jalan untuk aku bertobat?” Jawab Nabi saw,, “Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu”. Kemudian turunlah QS. Al-Maidah: 38 tersebut.14 Kata saraqa sendiri secara etimologi bermakan “akhdzu ma li al-ghairi khufyatan”(mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi).15 Sedangkan secara terminologis kata ‘mencuri’ (al-sarq) terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian besar dan kecil. Pencurian besar merupakan arti lain dari term hirabah sebagaimana penulis jelaskan pada term sebelumnya. Sedangkan definisi tentang pencurian kecil, beberapa ulama memiliki makna yang bervariasi, yaitu (a) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, (b) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan jalan menganiaya, (c) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang bukan diamanatkan padanya.16 Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-sarq adalah mengambil harta orang lain yang bukan miliknya dengan jalan sembunyi-sembunyi tanpa kerelaan pemiliknya. Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur’an al-Karim, hlm. 94. Ahmad Warson al-Munawwir, Al-Munawwir, hlm. 628 16 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 375 14 15 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 183 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) 3. Al-Hira>bah (Perampokan) Qs. Al-Maidah: 33 ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ Istilah berikutnya yang terindikasi sebagai term korupsi dalam Al-Qur’an adalah hira>bah. Hakim Muda Harahap menguraikan bahwa arti lain dari kata yuha>ribu>na apabila dirunut ke asal bentukan awalnya dari tsula>tsi mujarrad maka ia bermakna seseorang yang merampas harta dan meninggalkannya tanpa bekal apa pun.17 Hal yang sama juga datang dari pandangan sebagian ahli fikih mengenai kata hira>bah. Menurut mereka orang yang melakukan tindakan hirabah sebagai qa>thi’u al-thari>q atau penyamun dan al-sa>riq al-kubra> atau pencurian besar. Dengan kata lain, makna hira>bah di sini adalah seseorang yang merampok harta orang lain. Pengertian seperti inilah yang kemudian sering digunakan oleh ulama untuk memaknai kata yuha>ribu>na dalam QS. Al-Maidah: 33 tersebut.18 4. Al-Suh}t (Penyuapan) Qs. Al-Maidah: 42 ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ Kata al-suht dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari sah}ata yang memiliki makna memperoleh harta yang Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hlm. 80-82 18 Lihat: Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 384. 17 184a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) haram.19 Hal senada juga dijelaskan oleh Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan al-suh}t adalah harta haram.20 Ibn Khuzaimah, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan al-suh}t adalah bila seseorang makan karena kekuasaanya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (risywah) yang dapat diambilnya. Jika kembali dicermati, ayat tersebut menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian. Di mana praktek suap menyuap orang yang memiliki kekuasaan merupakan bagian dari bentuk praktek korupsi yang telah menjamur di masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa suap (al-suh}t), baik yang menerima maupun yang memberi, termasuk dalam tindakan korupsi. 5. Ad-Dalwu (Pengaruh Korupsi) Qs. Al-Baqarah: 188 ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ Ayat tersebut, jika dibaca dalam konteks korupsi, mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (alba>thil). Makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menyuap hakim, kadi, dan lain sebagainya yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan sang penyuap dari tuntutan sesuatu.21 Asba>b al-nuzu>l ayat tersebut dijelaskan Ibn Katsir dalam tafsirnya melalui khabar dari jalur Ibn Abbas, dia berkata: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang menanggung hutang, sedangkan orang yang memberi hutang tidak mempunyai bukti yang kuat (ketika ingin menagih hutang tersebut). Maka laki-laki yang mempunyai hutang tersebut mengingkari hutangnya dan Ahmad Warson al-Munawwir, Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 614. 20 Al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasyaf, Juz III, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, 1968), hlm. 57 21 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, hlm. 255 19 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 185 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) mengadukan perkaranya pada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada dalam pihak yang salah.” Setting historis inilah yang kemudian direspons oleh Al-Qur’an dengan turunnya ayat tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dan memperjuangkan sesuatu yang batil.22 Karena itu, Islam melarang keras membawa urusan harta benda kepada hakim bila hal yang melatarbelakangi adalah kebatilan. Al-Qur’an dan Ideologi Anti Korupsi Kita mengetahui bahwa secara atropologis al-Qur’an memiliki kekuatan yang dapat membentuk budaya masyarakat. Bahkan lebih jauh Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa peradaban Arab-Islam dan Islam secara umum, adalah merupakan “peradaban teks”. Artinya, bahwa dasar-dasar ilmu dan budaya Arab-Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas landasan dimana teks sebagai pusatnya tidak dapat diabaikan. Hal ini membuktikan bahwa dalam peradaban Islam pada umumnya, al-Qur’an memiliki peran budaya yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk wajah peradaban dan dalam menentukan sifat dan watak keilmuan yang berkembang di dalamnya.23 Bangsa Indonesia sesungguhnya mayoritasnya adalah kaum pinggiran yang meletakkan agama sebagai kekuatan spiritual belaka. Namun pada prinsipnya bahwa al-Qur’an memiliki kekuatan emosional yang dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Akan tetapi patut disayangkan sesungguhnya bahwa doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Qur’an itu, bagi kebanyakan umatnya tidak memiliki dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi. Sungguh asumsi seperti ini perlu direkonstruksi, sebab Islam bukanlah teologi eskapistik yang mengamini umatnya untuk larut dalam buaian spiritual belaka, sehingga lupa akan tanggung jawab sosialnya. Bagi penulis jika ditelaah lebih mendalam, al-Qur’an Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur`ān al-Azhīm, (Kairo: AlMatba’ah Al-Fanniyah, t. th.), Jilid II, hlm. 226. 23 Nasr Haid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qur’an: Kritik Terhadap Ulumul Qur’an, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LkiS, 2003, hlm. 17 22 186a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) mempunyai rentetan perangkat teoritis yang bisa digunakan untuk membendung beragam bentuk dari manifestasi ketidakadilan sosial termasuk korupsi. Berbicara tentang korupsi, al-Qur’an sangat tegas memberikan argumen normatif bahwa dalam setiap harta yang dimiliki manusia, senantiasa ada hak orang lain, dan hak itu jelas bukan miliknya (Q.S. al-Ma’arij, 70: 24-25). Dengan ungkapan yang berbeda Allah ingin memberi ketegasan bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkahkan harta yang dikuasai kepada jalan yang diridhai Allah. Seperti yang digambarkan dalam surah al-Hadid (57): 7 “berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. Jika korupsi terus dilakukan, bukankah itu merupakan pengingkaran atas amanah kebendaan yang telah dititipkan Allah kepada manusia. Namun peringatan Tuhan melalui al-Qur’an ini sepertinya hanya menjadi kesadaran kultural, tidak memiliki daya paksa struktural, sehingga sang koruptor menjadi tak bergeming. Tindak korupsi yang dipahami sebagai bentuk dari penyimpangan normatif (menyangkut harta) juga merupakan bagian yang integral dari kejahatan sosial, sebab korupsi adalah mengambil harta orang lain baik perorangan maupun kelompok dengan cara yang zhalim termasuklah dalam kasus suap-menyuap. Korupsi merupakan dosa besar yang paling berbahaya yang dapat menimbulkan kehancuran ekonomi, politik, dan sosial masyarakat.24 Secara garis besar Islam dibangun atas tiga unsur utama, yaitu akidah, syari’at, dan akhlak (akidah, syari’at, dan akhlak merupakan istilah lain dari iman, Islam, dan ihsan.25 Akidah merupakan pondasi bangunan keyakinan umat Islam secara vertikal, syari’at berisi tentang aturan-aturan dalam membimbing Husain Husain Syahatah, Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah, terj. Kamran As’ad Irsyady, Jakarta: Amzah, 2005, hlm. xi 25 Muslim, Imam, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar as-Salam, 1998), cet. 1, hlm. 79 24 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 187 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) kehidupan manusia disamping juga berisi sangsi-sangsi terhadap yang melanggar aturan tersebut, sementara akhlak berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan baik kepada Allah (hablum minallah) maupaun terhadap sesama manusia (hablum minannas). Ketiga unsur utama ajaran Islam ini pada intinya untuk mencapai tujuan teologis yakni sebagai rahmat bagi sekalian alam (QS. AlAnbiya’: 107) Konsep maqasid al-Syari’ah sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima halyaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari lima aspek ini, aspek terakhir yang menjadi perhatian Syari’at Islam adalah masalah harta. Harta harus dijaga dengan baik, tidak boleh saling mencurangi dan menuasai dengan cara yang batil dalam bermuamalah, tidak boleh menzalimi hakhak anak yatim, mengkorupsi, melakukan penyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu, memberikan hadiah dengan tujuan dan maksud khusus kepada seorang pejabat, mencuri atau merampok.26 Pada sisi yang berbeda, disamping sebagai rahmat, secara spesifik dalam setiap aturan hukum terdapat konsep maqasid al-Syari’ah yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara’ berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.27 Menurut Syahatah jika diklasifikasikan secara sistematis bahwa diantara justifikasi syara’ (al-Qur’an) terhadap bahaya dan keharaman korupsi adalah: Pertama, korupsi termasuk salah satu bentuk perampasan harta orang lain dengan cara yang kotor, batil, dan semena-mena. Deskripsi ini dalam al-Qur’an digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan korupsi (suap), seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah:188. Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut secara tersirat terkait dengan pelarangan perbuatan menyogok dan disogok. Menurutnya dalam ayat ini perbuatan itu diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 2-4 27 Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 4, hlm. 1108 26 188a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) air. Timba yang turun tidak terlihat oleh yang lain, khususnya yang berada jauh dari sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara tersembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah, lalu dengan tegas ayat ini mengutuk perbuatan itu.28 Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi adalah termasuk pembuat kerusakan di muka bumi yang wajib ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sebab perilaku orangorang ini akan dapat menimbulkan kekacauan dalam interaksi dan relasi sosial serta mengancam stabilitas masyarakat, mereka yang melakukan semua ini patut divonis sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah (5): 33. Ketiga, jika yang melakukan korupsi (suap) berposisi sebagai hakim (qadhi), maka konpensasi dari penerimaan suap itu adalah memutuskan perkara sesuai dengan pesanan dari siapa yang menyuap, hal ini secara nyata adalah merupakan penyimpangan dari prinsip keadilan yang lebih ironis adalah bahwa keputusan yang diambil sudah pasti tidak berdasar pada apa yang telah diturunkan Allah pada sisi inilah al-Qur’an mengklaimnya sebagai orang yang kafir, zalim, dan fasik (QS. Al-Maidah: 44, 45, 47). Keempat, penyebaran wabah korupsi (suap dan penggelapan) berdampak jelas pada ketimpangan sosial. Korupsi adalah mengambil hak rakyat yang dianggap kalangan atas sebagai masyarakat bodoh dan dungu, karena tidak bisa mengambil haknya secara adil dan tegas. Korupsi juga mencuri uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu korupsi yang dilakukan penguasa adalah dosa yang sangat besar karena mereka menurut al-Qur’an mengemban tanggung jawab untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi demi kesejahteraan rakyat (QS An-Nisa’ 4:58), namun kenyataannya justru menyengsarakan rakyat. Kelima, pada zaman Rasul perilaku seseorang berbuat curang dan menyimpang (korupsi) terhadap harta rampasan perang (ghanimah) diabadikan Allah dalam al-Qur’an sebagai orang yang berkhianat dan akan dan mereka akan dibalas setimpal M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 2002, Vol I., hlm. 387 28 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 189 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) dengan yang mereka lakukan (QS. Ali Imran: 3; 161). Keenam, dalam sebuah riwayat hadis di jelaskan bahwa suatu saat Rasul saw. memerintahkan para sahabat untuk menyalati seorang jenazah, namun beliau sendiri tidak berkenan melaksanakannya. Para sahabat bertanya-tanya, tidak basanya Rasul berbuat demikian, ternyata keengganan beliau menyalati jenazah tersebut disebabkan karena jenazah tersebut semasa hidupnya sempat mengorupsi perhisan semacam intan atau manic-manikyang nilainya tidak mencapai batas minimal pencurian, yaitu dua dirham. Atas dasar ini Imam al-Nawawi menganjurkan agar para ulama dan orang-orang shaleh untuk tidak ikut menyalatkan jenazah orang yang berlaku fasik (koruptor) sebagai sebuah pelajaran dan mencegah bagi yang lain agar tidak mengikuti perbuatan fasik tersebut.29 Sedangkan menurut Munir Mulkan secara ekstrim tindak korupsi dapat dikatakan sebuah kekafiran yang nyata, sebab kekafiran bukan semata-mata karena sesorang tidak bersedia menyatakan diri beriman kepada Tuhan secara formal (verbal/ lisan), tetapi lebih empiris dalam praktek korupsi, politik uang, dan politik preman (dengan kekerasan). Penyelewangan jabatan, penggunaan berbagai ancaman kekerasan dalam praktek politik, manipulasi hukum dan perundangan yang berlaku merupakan bentuk pemalsuan logika rakyat dan sekaligus pemalsuan kesalehan yang secara sistematis bisa menghancurkan sisitem demokrasi dan kesalehan keagamaan.30 Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, yang dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan dosa besar. Penutup Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, hlm. 137 Abdul Munir Mulkan, Manusia Al-Qur’an: Jalan Ketiga Religiositas di Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 224 29 30 190a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) dari tugas-tugas resmi yang secara sengaja dilakukan sendiri atau bersama-sama untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Untuk konteks Indonesia, ketika sistem hukum dan sistim sosial tidak mendukung, maka keteladanan tokoh masyarakat akan berperan sangat penting dalam memberantas korupsi. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Untuk pola hubungan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi community leader (pemimpin kelompok) faktor keteladanan memang harus lebih ditonjolkan. Sayangnya, sentimen sosial kaum muslim terhadap isu-isu seperti korupsi, dan problem-problem sosial lainnya yang bersinggungan langsung dengan kita, nampaknya kurang bersemangat untuk mendapatkan perhatian dibandingkan dengan sentimen persaudaraan sesama muslim seperti dengan Palestina ataupun Irak yang sangat luar biasa. Semua energi bisa dilibatkan dan sedia dikerahkan. Padahal menurut sejarah, perhatian pertama Nabi Muhammad dalam dakwahnya terletak pada usaha perbaikan sistem sosial. Banyak ayat dalam al-Qur’an yang memberikan argumen yang sangat tegas bahwa dalam setiap harta yang dimiliki manusia, senantiasa ada hak yang tersurat. Dan hak itu, jelas bukan miliknya (Qs. Al-Maarij: 24-25). Dengan ungkapan yang berbeda, Allah ingin memberi ketegasan, bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkahkan atas harta yang dikuasai (Qs. Al-Hadid: 7). Lalu, jika korupsi dilakukan, bukankah itu merupakan pengingkaran besar atas amanah kebendaan yang dititipkan pada manusia. Hanya saja, ini sekadar menjadi kesadaran kultural, tidak punya daya paksa struktural, sehingga sang koruptor menjadi tak bergeming. Sesungguhnya memang sudah saatnya al-Qur’an tidak lagi diletakkan sebagai kesadaran normatif yang hanya bergerak pada wilayah kultural. Ia juga harus mampu menyelinap dalam perbaikan pada ruang-ruang struktural. Dan itu artinya, alQur’an juga sesungguhnya bisa menjadi landasan teoritik yang bisa dipakai untuk melakukan pembebasan kemanusiaan, bahkan untuk masalah seperti korupsi. Al-Qur’an mempunyai kekuatan untuk membentuk Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 191 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) budaya masyarakat. Al-Qur’an memiliki impetus emosional yang dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Hanya saja, yang patut disayangkan, doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Qur’an itu, bagi kebanyakan umatnya tidak mempunyai dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi.*** 192a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006. Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh, I, Surabaya: Kalista, 2006. Abdul Munir Mulkan, Manusia Al-Qur’an: Jalan Ketiga Religiositas di Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 2007 Ahmad Baidlawi, “Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam”, dalam Jurnal Esensia, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: ArabIndonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Bairut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2006. Al-Syatibi, Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari’ah, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004. Al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasyaf, Juz III, Bairut: Dar alIlmiyyah, 1968. Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986 Anwar Harjono,. Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1968. Bambang Soesatyo, Perang-perangan Melawan Korupsi, Jakarta: Ufuk Press, 2011 Duski Ibrahim, “Perumusan Fikih Anti Korupsi” dalam Suyatno,ed, Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama, Yogyakarta: Gama Media, 2006. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 193 Teologi Anti Korupsi (oleh:Abdul Karim) Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi, Yogyakarta: Gama Media, 2009. Husain Husain Syahatah, Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah, terj. Kamran As’ad Irsyady, Jakarta: Amzah, 2005. Jonathan Crowther (ed), Oxford: Advanced Learners Dictionary, 1995. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2011. M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan,Tangerang: Lentera Hati, 2011. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2000. Mahfudz Masduki, “Beberapa Prinsip dan Metode Penafsiran alQur’an” dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis, Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga, 2000. Muhammad Husain Haikal, Sayyidina Umar bin khattab, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003. Nasr Haid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qur’an: Kritik Terhadap Ulumul Qur’an, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LkiS, 2003. Robert Klitgaard dkk., Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002. 194a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) RITUS DALAM KEBERAGAMAAN ISLAM: RELEVANSI RITUS DALAM KEHIDUPAN MASA KINI Ulya STAIN Kudus Email: [email protected] ABSTRAK Sebagai pegangan hidup segenap kaum muslim, Islam memberikan petunjuk umum yang bisa mengarahkan kehidupan mereka ke arah yang benar menurut doktrin agama. Dalam hal ini, Islam menjelaskan tentang ritus-ritus keagamaan yang bisa mengantarkan para pelakunya ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup mereka. Tidak dapat dipungkiri kenyataannya, berbagai ritus dalam doktrin ajaran Islam akan membawa pelakunya mengerti hakikat sakral dan profan dalam kehidupan.Artikel ini menyajikan beberapa pola utama aspekaspek ritual Islam. Dari pembahasan pada kajian ini pula masing-masing pribadi muslim diarahkan kepada pengetahuan mereka akan nilai-nilai luhur akidah Islamiyah yang mewujud dari ritus-ritus keagamaan yang diwujudkan. Eksistensi ritus keislaman yang akan diuraikan pada artikel ini sepenuhnya diarahkan kepada pola perkembangan ritus, dasar perwujudan ritus, dan implikasi logis ritus keislaman bagi pelakunya. Kata Kunci: Ritus, Sakral dan Profan, Keislaman, Hidup Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 195 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) Pendahuluan Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur seluruh kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang utuh. Fi addunya hasanah wa fi al-akhirah hasanah. Islam juga tidak hanya berisi proposisi-proposisi teologis belaka tetapi ia juga memuat aspek-aspek perilaku. Demikian relevan dengan pernyataan Mahmud Syaltut bahwa Islam itu aqidah wa syari’ah.1 Akidah adalah dimensi internal keberagamaan yang terkait dengan materi-materi kepercayaan manusia (the human belief), sedangkan syari’ah adalah dimensi eksternalnya yang memiliki representasi berupa perilaku keberagamaan (the religious behaviour), yakni berupa ajaran-ajaran praktis agama yang terelaborasi dalam tata hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Dalam bahasa agama, kedua wilayah ini tersimpulkan dalam arkan al-iman dan arkan al-Islam. Praktik-praktik syar’i merupakan implementasi dan aktualisasi dari akidah,2 yang dalam realisasinya terdiri dari 2 (dua) kategori fundamental, yakni ajaran yang universal, yang tidak meruang-waktu dengan model-model perilaku yang partikular dan meruang waktu. Jika yang pertama disebut doktrin maka yang kedua disebut dengan ritus atau ritual. Keduanya menjadi satu kesatuan sisten yang tak bisa dipisahkan dalam proses pengamalan agama. Ritus – dalam perkembangan selanjutnya – bertolak dari pemahaman tentang Islam sebagai rahmah li al-`alamin yang membuka peluang masalah-masalah untuk diinterpretasikan kembali sesuai situasi dan kondisi sosiologis, menurut konteks ruang dan waktu, dan sebagainya, maka ritus juga dimungkinkan akan mengalami pergeseran opini. Ritus-ritus Islam muncul dan berkembang bersamaan dengan turunnya risalah Islam pada masa Nabi Muhammad, apabila diimplementasikan pada kehidupan Mahmud Syaltut, Islam Akidah wa Syari’ah, (T.tp : Dar al-Qalam, 1966), hlm. 32 2 Bandingkan dengan konsep iman menurut Imam al-Asy’ari bahwa al- iman huwa tasdiq bi al-qalbi, qaul bi al-lisan, wa amal bi al-jawarih fa furu’uh . Lihat dalam as-Syihrastani, al-Milal wa an-Nihal , (Beirut Dar al-Fikr, t.th), hlm. 101 1 196a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) sekarang, apakah masih bermakna dan relevan? Persoalan tersebut akan dijawab dengan tulsan singkat ini, dengan pembahasan secara berurutan : pengertian ritus dan ritus Islam, elemen-elemen ritus Islam, ruang lingkup ritus Islam, makna ritus dan kaitannya dengan konteks kekinian, dan ditutup dengan relevansi ritus Islam. Pengertian Ritus dan Ritus Islam Term ritus dalam bahasa Inggris, yaitu rite (tunggal) dan rites (jamak), yang mempunyai arti secara leksikal, yaitu perilaku atau upacara-upacara (act and ceremonies) yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan.3 Sedangkan secara definitif, ritus berarti aturan-aturan pelaksanaan (the rules of conduct), yang melukiskan bagaimana seseorang seharusnya bertingkah laku dalam kehadirannya di depan obyek – obyek yang sakral atau disucikan.4 Dalam konteks yang lebih spesifik, bahwa ritus dalam Islam dideskripsikan sebagai perwujudan dari doktrin-doktrin Islam (expression of Islamic doctrine). 5 Dari batasan di atas maka ritus dalam Islam pada dasarnya adalah semua bentuk praktik keberagamaan, baik berupa perilaku atau upacara-upacara keagamaan yang pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa, sebagai bentuk penyembahan (worship), pengabdian atau pelayanan (service), ketundukan (submission), dan ekspresi rasa syukur (gratitude), yang lahir dari seorang hamba kepada Tuhannya dalam rangka merealisasikan ajaranajaranya dan menjalankan hidup secara religius menuju klaim saleh dan takwa. Elemen-Elemen Ritus Islam Setiap bentuk praktik keberagamaan, baik berupa perilaku atau upacara-upacara keagamaan yang pelaksanaannya AS. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (New York : Oxford University Press, 1987), hlm.734 4 Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religious Life, (London : George Allen and Unwin, 1982), hlm. 41 5 Frederick M. Denny, “Islamic Ritual (Perspective and Theory)”, dalam Richard C Martin, Approaches to Islam in Religious Studies, (USA : Arizona State University, 1985), hlm. 64 3 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 197 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) telah diatur oleh ajaran agama, sebagai bentuk penyembahan, pengabdian atau pelayanan, ketundukan , dan ekspresi rasa syukur, yang dilaksanakan oleh seorang hamba karena Tuhannya dalam rangka merealisasikan ajaran-ajarannya dan menjalankan hidup secara religius, memiliki elemen-elemen sebagai berikut : 1. Adanya sistem perilaku yang pelaksanaanya diulang-ulang terus-menerus, dan reguler. Dalam ritus harus mengandung perilaku yang diperlihatkan dalam praktik sebab ritus adalah model dari tindakan atau perilaku. 2. Dalam ritus mengandung unsur penyembahan atau pengabdian atau ketundukan atau pemujaan atau ungkapan perasaan bersyukur, dari yang lebih inferior, yakni hamba sebagai makhluk yang diciptakan, kepada yang paling superior yakni Allah, Tuhan yang menciptakan. 3. Allah sebagai tujuan akhir (the final purpose of Islamic rites) sehingga apabila sikap atau perilaku yang di dalamnya telah memuat unsur penyembahan, pengabdian, pemujaan, dan lainlain, tetapi tidak ditujukan pada Allah maka perilaku tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi ritus Islam. 4. Adanya sistem pemisahan (system of separation) antara yang suci dan yang tida suci, yakni ritus dilaksanakan pada tempat atau waktu tertentu yang disucikan atau dilarang karena tidak disucikan. Dalam perspektif ini Annimarie Schimmel menyatakan bahwa di dunia ini terdapat beberapa aspek yag suci dan yang disucikan. Kesucian sesuatu itu disebabkan 3 (tiga) hal, yaitu : a. Karena watak atau karakternya (sacred aspect of nature), seperti: air zam-zam, babi haram karena tidak suci atau bangkai binatang laut halal karena suci adalah berdasarkan wataknya. b. Karena tempat dan waktu (sacred space and time), seperti: malam lailah al-Qadar, bulan Raadhan, Bait al-Haram, Ka’bah, dan lain-lain c. Karena perbuatannya sendiri (sacred actions), seperti: salat, haji , berkurban, wudhu, dan seterusnya. 6 Baca penjelasan selengkapnya dalam Annimarie Schimmel, Deciphering The Sign of God (A Phenomenological Approach to Islam), (New York : State University of New York, 1994), hlm.1-89. 6 198a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) 5. Konsekwensi adanya pembedaan antara yang suci dan yang tak suci (sacred and profane) maka perilaku-perilaku ritual atau ritus selalu terkait dengan hukum Islam yang oleh ulama fuqaha’ dikategorisasikan menjadi 5 (lima), yaitu wajib, sunnah, hram, makruh, dan mubah. Atau dengan pemisahan yang lebih clear and distinc, meminjam term Rene Desacartes, adalah antara halal dan haram, dianjurkan dan dilarang (permitted and forbidden). Sebagai contoh bahwa pelaksanaan berkorban pada hari raya ‘id al- adha adalah dianjurkan, sedangkan menyembah selain Allah adalah dosa dan dilarang. Ruang Lingkup Ritus Islam Ritus atau ritual keagamaan secara umum, termasuk ritus dalam Islam, di dalamnya pasti melibatkan perilaku (action) dan atau upacara-upacara keagamaan (ceremonies) dalam rangka berdoa, memuji, mengabdi kepada Tuhan, Dzat yang suci dan disucikan. Pelaksanaannya kadang-kadang secara berkelompok, tetapi sering juga dilaksanakan secara individual, pada waktuwaktu yang telah ditentukan (bisa harian – mingguan – bulanan – tahunan), pada tempat-tempat tertentu (walaupun yang ini tidak mutlak), selalu diuulang-ulang secara terus-menerus. Ritus atau ritual hampir berada dan melekat pada seluruh perilaku keberagamaan yang merupakan aktualisasi konkret dari kepercayaan atau keimanan seseorang pada Tuhan, secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) ruang lingkup, yaitu : Yang pertama, praktik ritual yang masuk dan terelaborasikan dalam arkan al-islam, yang terdiri dari salat, puasa, zakat, dan haji. Masing-masing perilaku tersebut termasuk dalam sacred actions, dilaksanakan pada momen-momen tertentu dan diulang-ulang (salat wajib dilaksanakan lima waktu yang disucikan dalam seharinya , puasa ramadhan wajib dilaksanakan ddengan kesucian blan Ramadhan, zakat terkait dengan periode tahunan atau waktu pencapaian satu nishab atau standar pencapaian tertentu, begitu pula haji erat hubungannya dengan kesucian bulan Dzu al-Hijjah) ; merujuk pada temat tertentu (salat menuju atau menghadap tempat suci, Ka’bah, haji merupakan perjalanan suci menuju bait al-haram yakni Makkah dan Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 199 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) Madinah) ; kesemuanya diorientasikan hanya untuk dan sebagai bukti pengabdian, ketundukan, pemujaan, juga mengekspresikan rasa syukur kepada Allah sebagai tujuan utamanya. Yang kedua, yaitu praktik-praktik ritual yang berada di luar wilayah arkan al-Islam, seperti: wudhu diwajibkan setiap sebelum salat, membaca al-Qur’an atau tawaf , menyembelih hewan untuk berkurban dilaksanakan setiap bulan dzu al-hijjah, akikah dianjurkan untuk dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi, upacara-upacara kelahiran yang lain, pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam, dan sebagainya, yang semuanya itu tidak semata-mata hanya mengandung unsur rutinitas, melainkan mengandung unsur simbolik yang memiliki makna di balik perilaku itu sendiri. Makna Ritus, Kaitannya dengan Konteks kekinian Allah telah memerintahkan, menganjurkan atau melarang hambanya untuk berbuat sesuatu tidak tanpa maksud. Hal yang demikian karena tidak selaras dengan tradisi Allah yang selalu berbuat, menciptakan sesuatu pasti menuju tujuan dan arah yang teah ditetapkan. Firman Allah : “ Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya tanpa guna”7 Demikian itu pula ketika Allah mewajibkan salat, puasa , menganjurkan berkorban, melarang makan babi, dan lain-lain. Pastinya di balik semua itu terdapat rahasia atau makna yang seharusnya diungkap oleh semua umat silam, tetapi mungkin akan timbul pertanyaan : “Adakah sebuah keniscayaan bahwa perintah atau larangan Allah yang turun bersamaan dengan diwahyukannya al-Qur’an pada masa Nabi Muhammad pada masa berabad-abad yang lalu masih mempunyai keterkaitan makna sesuai dengan rentang waktu sekarang yang semuanya telah berubah ?”. Dalam hal ini harus diingat bahwa dengan selesainya risalah Nabi berarti telah sempurna pula ajaran-Nya. Allah berfirman bahwa : “ Pada hari ini telah Aku sempurnakanuntukmu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu”. 8Sempurna di sini bukan berarti selesai, Lihat al-Qur’an, Qs. Shad : 27 Lihat al-Qur’an , Qs. al-Maidah : 3 7 8 200a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) menjadi usang, dan ketinggalan zaman, dan tidak ada kaitannya dengan masa sekarang, tetapi sempurna karena universalitasnya dan relevansinya sepanjang masa. Salih li kulli zama wa makan. Selanjutnya, berikut ini aan disajikan beberapa contoh ritus keberagamaan dalam Islam, makna hubungannya dengan konteks kekinian: Yang pertama, adalah salat. Salat adalah ritual dalam Islam yang paling utama. Seperti yang telah diketahui bahwa salat adalah ibadah yang dimulai dengan niat dan takbirah alihram dan diakhiri dengan gerakan salam, namun tidak sekedah formalisme-legalisme. Dengan menghayati makna bacaan dan gerakan dalam salat maka kita bisa mengembangnkan darinya ahlak-khlak yang terpuji, seperti : sikap rendah diri, mencegah keangkuhan dan ketakabburan sebab setelah kita bersujud kepadaNya dengan penuh kesadaran, kita akan merasa kecil dihadapanNya.9 Atau dengan salat yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah maka akan mendidik pelakunya untuk bersikap egaliter, memunculkan rasa sosial.10 Sebelum salat diwajibkan mengambil air wudhu yang mencerminkan vbahwa Islam menganjurkan kebersihan. Tidak hanya kebersihan ragawi, tetapi juga kesucian rohani. Yang kedua, puasa. Puasa dalam arti yang umum adalah tidak makan dan tidak minum yang diakukan di abad ini dengan berbagai motif. Biasanya untuk menjaga kesehatan, dalam rangka berdiet, merupakan ungkapan solidaritas atau sebagai protes sosial, yang semuanya memiliki eseni yang sama, yaitu untuk mengendalikan diri (self control). Begitupun puasa sebagai ritual dalam Islam, yang setelah kita melakukan dan menghayatinya maka akan menimbulkan sikap kontrol diri terutama berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan faali dan berkembangnya potensi diri agar mampu membentuk diri sesuai dengan citra Allah, takhallaqu bi akhlaq Allah, 11 tentunya dengan menyontoh Secara normatif telah disebutkan dalam firman-Nya bahwa “ Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar”. Lihat dalam al-Qur’an Qs. .... 10 Hasbi ash-Shiddieqy, Kuliah Ibadah, (jakarta : Bulan Bintang, 1954), hlm.230 11 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Jakarta : Mizan, 9 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 201 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) perilaku Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah.12 Selain itu bisa menumbuhkan rasa solidaritas sosial, menumbuhkan perasaan simpati, bahkan empati terhadap kaum yang tidak beruntung secara material. Kemudian ritual zakat. Zakat berarti menyucikan harta yang dimiliki dari hak-hak orang lain dengan memberikan sebagian kekayaannya kepaa mereka yang berhak di jalan Allah. Secara nyata, dengan berzakat akan memacu dan memicu kesejahteraan sosial (social welfire) di kalangan umat, juga mengembangkan kepribadian, kedermawanan, mengikis sikap kikir bagi pemberi dan mengikis sikap iri dan dengki bagi si penerima,13 juga sebagai sarana untuk memusnahkan penyakit riba,14 juga menghalangi timbulnya kelas-kelas sosial, kapitalisme, dan mengentaskan kemiskinan. Dan seperti zakat pula, ritual korban, akikah sebagai pengorbanan (sacrifices) versi Islam , terutama bertujuan sebagaimana di atas di samping sebagai ekpresi ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang teah diberikan. Selanjutnya haji. Banyak makna yang ada di balik ritual haji sesuai dengan konteks kekinian, di antaranya : ihram mempunyai makna kesederhanaan, tawaf yakni berkunjug ke Ka’bah yang di situ terdapat Hijr Ismai yang mengandung sejarah bahwa Nabi Ismail pernah berada di pangkuan ibunya yang bernama Siti Hajar, seorang bekas budak berkulit hitam dan miskin, yang dimakamkn di sana menandakan bahwa Islam mengembangkan prinsip persamaan (equality) yang tidak melihat manusai atas dasar perbedaan ras, suku, golongan, status sosial. Lalu peristiwa Arafah atau wuquf di arafah akan mengingatkan kita pada perjlanan akhir dunia yakni nanti kita akan dikumpulkan Allah di padang maskhsyar,15 dan seterusnya. Demikian beberapa contoh yang telah disebutkan di atas mennjukkan bahwa ritus atau ritua dalam Islam mempunyai makna yang mendalam, selalu menampakkan keterkaitannya di sepanjang masa sehingga tetap relevan untuk ditumbuhkan 1997), hlm.308 12 Lihat al-Qur’an , Qs. .... 13 Ibid., hlm.325 14 Lihat al-Qur’an , Qs. al-Baqarah :276 15 M. Quraish Shihab, Membumikan, hlm.335-337 202a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) dan dikembangkan pada masa sekarang dan masa-masa yag aka datang. Relevansi Ritus Islam Berdasarkan uraian di atas maka secara tak langsung bisa dinyatakan bahwa antara ibadah dan pelaksanaan ritus atau ritual berdiri dalam satu entitas yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainya. Ritus selalu menyertai pelaksanaan ibadah, ibadah merupakan perilaku keagamaan yang harus dilakuka oleh setiap musim kapanpun dan dimanapun mereka besada. Ibadah adalah sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan seperti pusa, mengukutu perintah Allah dan Rasu-Nya. 16 Dengan demikian maka apabila ibadah harus dilaksanakan sapai kapanpun maka pelaksanaan ritus yng direfleksikan dengan simbol-simbol perbuatan atau upacara yang ada di dalamnya tak dapat ditinggalkan dan pula akan tetap sesuai untuk dilaksanakan. Pelaksanaan ritus cenderung tetap sebagaimana pendapat Catherine Bell, bahwa : “Aktivitas ritual pada umumnya cenderung untuk menolak perubahan dan lebih serig dilakukan dari pada bentuk-bentuk lain dari pada kebiasaan-kebiasaan lainnya (social customs).” 17 Pada sisi yang lain, bahwa ritus dalam Islam adalah sesuatu yang signifikan, yang tak hanya memiliki nilai fisik tetapi juga menjelaskan aspek-aspek spiritual tertentu,18 sikap-sikap tertentu yang membuat kehidupan ini lebih bermakna setelah kita memahami dan menghayati semangat yang terkndung di dalamnya. Ritus sebagai sebuah system of symbol and actions ternyata juga emainkan peranan yang penting dalam menegaskan kepada dunia akan kekayaan pemikiran dan kultur Islam sehingga Islam sepanjang masa memberikan kontrbusi tentag pemikiran, budaya, dan literatur-literatur yang berkonsentrasi pada persoalan ini. 19 Lihat al-Qur’an , Qs. al-Baqarah :2, juga dalam Qs. al-Ahzab : 36 Catherine Bell, Ritual : Perspective and Dimensions, (New York : Oxford University Press, 1997), hlm.241 18 Annimarie Schimmel, Deciphering, hlm.xiii 19 John L. Esposto, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Wordl, Vol.III, (New York : Oxford niversity Press, 1995), hlm.442 16 17 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 203 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) Akhirnya penulis mengakhiri dengan mengutip pendapat ali Syariati, seorag pemikir besar Modern dari Iran, terkait dengan pembahasan relevansi dan peranan ritus masa kini. Dia menyatakan bahwa :” Keselamatan seseorang berada pada keberhasilannya dala mengatasi tantangan antara komponen spiritual dan material yang membuat kepribadian manusia (human personality) tercermin dalam ketundukan dan ungkapan rasa syukur pada Tuhan yang diekspresika secra simbolik (melalui ritus –pen).”20 Penutup Dari keseluruhan pembahasan di atas artikel dengan tema “Ritus dalam Keberagamaan Islam : Relevansi Ritus dalam Kehidupan Masa Kini ” maka bisa dicatat sebuah kesimpulan bahwa ritus dalam keberagamaan Islam adalah bagian yng tak terpisahkan dari ibadah. Dan Ibadah adalah unsrur penting dalam syari’ah. Dia sebagai sebuah sistem simbol yang mengandung nilai-nilai spriritual dan makna terdalam, yang realisasinya berupa perilaku dan upacara-upacatra keagamaan. Nilai- nilai spriritual dan makna terdalam di balik simbol ritus itulah yang seharusnya dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan konkret, setelah kita melakukan perilaku ritual dan menghayati semangatnya, sehingga di sinilah maka ritus dalam keberagamaan Islam akan tetap relevan, bermakna, dan penting di setiap perjalanan rentang sejarah manusia. Pada bagian yang lain tetap perlu diwaspadai bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang selalu berinteraksi dengan lingkungan, kultur, tradisi serta pemeluk agama atau kepercayaan lain sehingga tidak berlebihan jika muncul harapan agar kita tetap bersama-sama menjaga ritus dalam keberagamaan Islam tetap pada kesuciannya, tidak sengaja atau sengaja dilakukan sinkritisme dengan kultur atau tradisi lain yang tidak islami yang menyebabkan ritus Islam tidak terjamin kemurniannya lagi. Meskipun yang demikian itu kita seharusnya tetap berada dalam kesadaran bahwa manusia itu bagai astronot, yang keberadaannya tergantung dan dipengaruhi oleh hal-hal 20 204a Ibid. Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) lain yang ada di sekitarnya. Kata al-Jabiri bahwa : “Manusia dianalogikan dengan astronot. Sebagai astronot maka manusia sebagai penafsir akan selalu bergerak, diserap, dan ditarik ke dalam arus gerak rotasi iklim intelektual, sosial, maupun politis yang dikondisikan oleh sejarah, yang disebutnya sebagai al-itar al-marji’i (bingkai rujukan)”.21 Ketika seorang astronot terbang dengan pesawat ruang angkasanya maka pesawatnya itu baginya bisa disebut sebagai bingkai rujukan dimana melalui dan dengan kerangka itulah dia memandang sesuatu. Bintang, tata surya, dan pesawat ruang angkasa lainnya, bisa terlihat dekat atau jauh, di atas atau di bawah, cepat atau lambat, bila dilihat dari posisi dan kecepatan pesawatnya. Dengan ungkapan yang lebih umum, pandangan astronot terhadap segala sesuatu yang ada di alam dibatasi oleh ikatan imajinatif yang terentang sampai ke dinding yang merupakan panjang ruangan, dinding yang merupakan lebar ruangan, dan atap yang memisahkan antara lampu dengan lantai ruangan. Sesungguhnya seluruh manusia bagaikan astronot tersebut. Masing-masing memiliki bingkai rujukan yang membatasi hubungannya dengan alam. Kita tidak mengetahui atau mengetahui sesuatu kecuali melalui hal yang menghubungkan sesuatu itu dengan bingkai rujukannya. Muḥammad Abid al-Jabiri, Takwin alAql al-Arabi (Beirut : al-Markaz as-Saqafi al-Arabi, 1991), hlm.61. 21 Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 205 Ritus Dalam Keberagamaan Islam (oleh: Ulya) DAFTAR PUSTAKA Annimarie Schimmel, Deciphering The Sign of God (A Phenomenological Approach to Islam), (New York : State University of New York, 1994) AS. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (New York : Oxford University Press, 1987) as-Syihrastani, al-Milal wa an-Nihal , (Beirut Dar al-Fikr, t.th) Catherine Bell, Ritual : Perspective and Dimensions, (New York : Oxford University Press, 1997) Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religious Life, (London : George Allen and Unwin, 1982) Frederick M. Denny, “Islamic Ritual (Perspective and Theory)”, dalam Richard C Martin, Approaches to Islam in Religious Studies, (USA : Arizona State University, 1985) Hasbi ash-Shiddieqy, Kuliah Ibadah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1954) John L. Esposto, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Wordl, Vol.III, (New York : Oxford niversity Press, 1995) M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Jakarta : Mizan, 1997) Mahmud Syaltut, Islam Akidah wa Syari’ah, (T.tp : Dar al-Qalam, 1966) Muhammad Abid al-Jabiri, Takwin al-Aql al-Arabi (Beirut : alMarkaz as-Saqafi al-Arabi, 1991) 206a Fikrah, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 fikrah Vol. 1 N0. 1. Januari - Juni 2013 ISSN : 2354-6174 Page: 1-206 Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan fikrah Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol. 1 N0.1. Januari- Juni 2013 MEWUJUDKAN TRADISI ISLAM DALAM MANIFESTASI HARMONI KEBERAGAMAAN UMAT Mas'udi KRITIK WACANA PLURALISME AGAMA Andi Hartoyo RELATIVITAS AJARAN AGAMA: MENUJU PLURALISME KEBERAGAMAAN YANG HARMONIS Ahmad Atabik ISSN :2354-6174 AMBIVALENSI KOTA DEMOKRASI DALAM FILSAFAT POLITIK AL‐FARABI STUDI KRITIS MADINAH AL FADHILAH AL FARABI Moh. Yasin TEOLOGI ISLAM KONTEKSTUAL‐TRANSFORMATIF Nur Said STRUKTUR NALAR DI BALIK POLEMIK TEOLOGI DAN FILSAFAT ISLAM Tahir Sapsuha Diterbitkan oleh: Jurusan Ushuluddin Program Studi Ilmu Aqidah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Telp. (0291) 432677 fax. (441613) Kudus 59322 Jurusan Ushuluddin Program Studi Ilmu Aqidah SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS JAWA TENGAH ‐ INDONESIA




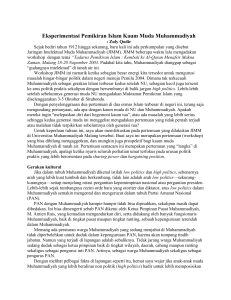
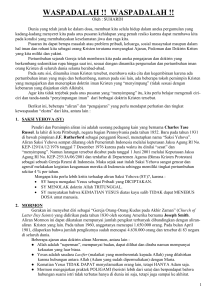

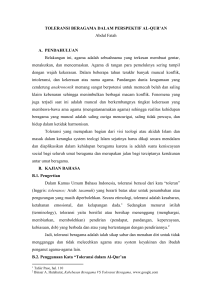
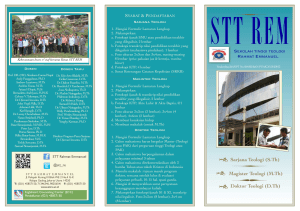
![Modul Filsafat Ilmu Dan Logika [TM5]](http://s1.studylibid.com/store/data/000081376_1-c4b3e4f727fdbd3f265cd0e936095e07-300x300.png)