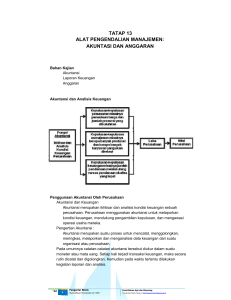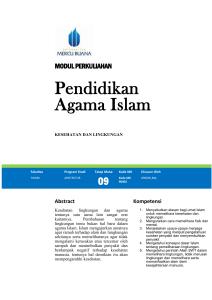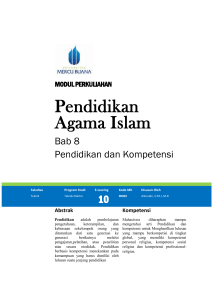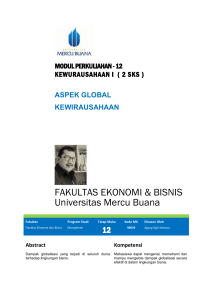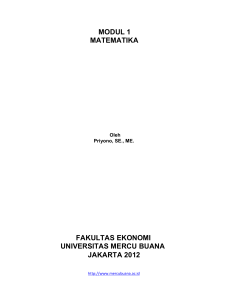Konflik Antar Kelompok - Universitas Mercu Buana
advertisement

MODUL PERKULIAHAN Kognisi Sosial Konflik Antar Kelompok Fakultas Program Studi Psikologi Psikologi Tatap Muka 10 Kode MK Disusun Oleh 61017 Filino Firmansyah, M.Psi Abstract Kompetensi Materi tentang konflik antar kelompok Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai konflik antar kelompok Konflik Antar Kelompok Pada modul ini akan dibahas beberapa teori Konflik antar Kelompok. Materi diambil dari Buku Psikologi Sosial karangan Sarlito WIrawan Sarwono dan Eko Meinanrno (2009). Bentrokan Antarkelompok Terjadi di Cakung (02 Juli 2002) Eduardus Karel Dewanto-Tempo News Room Bentrokan antarkelompok “Pak Ogah” terjadi di Jalan Cakung-Cilincing, Jakarta Timur persis di depan Dapyek ABRI, selasa (2/7). Petugas Polsek Metro Ckaung, Brigadir Dua Polisi Sukirno kepada Temp News Room, mengatakan bahwa bentrokan terjadi karena perebutan lahan menarik uang dari pengguna jalan di putaran jalan tersebut. “Petugas sekarang sudah ada disana semua untuk mengamankan lokasi,” ujarnya dengan nada tergesa-tegas. Menurut Sukirno, peristiwa berawal sekitar pukul 11.00 WIB. Petugas menduga kedua kelompok yang berbeda etnis itu telah bermusuhan sejak lama itu. Mencium gelagat bakal meluasnya bentrokan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Cakung segera meluncur ke lokasi kejadian. Bentrokan pun berhasil direda. Namun, hingga pukul 16.30 WIB, kedua kelompok masih bersitegang dan aparat masih berjaga di tempat tersebut. Sumber : www.tempo.co.id/hg/jakarta/2002/07/brk,20020702-14,id,html BATASAN, DEFINISI, DAN RUANG LINGKUP PERILAKU ANTARKELOMPOK Manusia merupakan makhluk yang selalu berada dalam kelompoknya. Sejak bayi sampai wafat, manusia menghabiskan kegiatannya, berinteraksi, dan melakukan berbagai hal dengan kelompok di sekitarnya. Perilaku antarkelompok berkaitan dengan bagaimana anggota kelompok memersepsikan, memikirkan, menghayati, dan bertingkah laku terhadap seseorang dari kelompok lain. Kelompok yang dibahas dapat berupa kelompok kecil (keluarga), kelompok yang tidak terlalu besar (perusahaan, organisasi), serta kelompok yang jauh lebih besar dan kompleks (suku, agama, bangsa). Perilaku antarkelompok dapat dilihat dan ditemui di sekitar kita secara langsung maupun tidak langsung (melalui berbagai media cetak, audio visual, dan sebagainya). Beberapa contoh yang kita temui, diantaranya tawuran SMA dengan STM, perkelahian antardesa di Ambon, protes pemilih terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), konflik antaretnis di Kalimantan, kecurigaan penduduk daerah tertentu bahwa terjadi manipulasi hasil pemilihan oleh KPUD, perang antara Amerika dengan Afghanistan, negosiasi antara penduduk korban Lumpur Lapindo dengan wakil dari Lapindo Brantas, protes buruh kepada atasannya, dan kekerasan antara Fron Pembela Islam (FPI) terhadap pengunjuk rasa pluralisme di Monas. ‘13 2 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id Sebaliknya, kerja sama antarbangsa, tolong-menolong, dukungan langsung maupun tidak langsung untuk korban bencana di Situgintung juga merupakan tingkah laku antarkelompok. Konflik, perang, perkelahian, kecurigaan, negosiasi, ataupun kerja sama merupakan perilaku antarkelompok karena melibatkan sejumlah orang yang berasal dari kelompok yang berbeda dan karena mereka menghayati dirinya sebagai bagian dari kelompok yang berbeda. Bahkan, pada situasi di mana, misalnya, Nana mengatakan pada pacarnya, Andi: “Selama kita pacaran satu tahun ini, selalu saja saya yang harus mengeluarkan uang bila kita makan siang bersama. Sebagai pria, kamu (Andi) seharusnya yang membayar makan siang jika kita makan bersama”, sehingga pertengkaran mereka yang tadinya merupakan pertengkaran antarpribadi/individu kemudian berubah dan bergeser menjadi pertengkaran/konflik antarkelompok. Pergeseran ini terjadi karena pada saat ia berbicara, Nana menghayati dirinya sebagai bagian dari ‘kelompok wanita’ sehingga pada saat yang sama is menganggap Andi bukanlah sebagai pacarnya semata, melainkan sebagai bagian dari kelompok pria. Contoh perilaku Nana menunjukkan bahwa penghayatan dan pemikiran bahwa seseorang merupakan bagian dari kelompok tertentu dapat membuat interaksi yang terjadi antara dua orang berubah menjadi interaksi antarkelompok. Ada berbagai definisi tentang perilaku antarkelompok; definisi berikut sangat menekankan adanya interaksi yang saling bertatap muka (face to face) antara kelompok yang berinteraksi. “Intergroup behavior is any behavior that involves interaction between one or more representative of two or more separate groups” (Vaughan dan Hogg, 2005). Batasan tersebut menunjukkan dengan sangat jelas ciri yang selalu akan ditemukan dalam hubungan antarkelompok, yaitu adanya interaksi antara dua kelompok atau lebih dan interaksi kelompok tersebut dilakukan secara tatap muka. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak sekali interaksi yang dilakukan dengan cara yang berbeda dan tidak selalu bertatap muka. Apabila jumlah anggota kelompok cukup besar (misalnya partai, warga desa, kelompok mahasiswa, dan lain-lain), interaksi yang terjadi biasanya harus melalui juru bicara atau sejumlah wakil dari kelompok tersebut sehingga interaksi yang tatap muka hampir tidak mungkin dilakukan. Kini, dengan adanya sarana teknologi bahkan memungkinkan untuk dilakukannya perundingan secara ‘remote’ antarkelompok yang berbeda pendapat. Vaughan dan Hogg kemudian mengemukakan definisi perilaku antarkelompok yang lebih luas dari yang pertama dan menekankan hal yang agak berbeda. “Intergroup behavior is any perception, cognition or behavior that is influenced by people's recognition that they and others are members of distinct socialgroups”(Vaughan dan Hogg, 2005). Definisi ini menekankan adanya persepsi dan penghayatan anggota kelompok bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok sosial yang sangat berbeda satu sama lainnya. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa tingkah laku anggota kelompok kemudian akan dipengaruhi oleh persepsi dan penghayatan tersebut. Seseorang tetap dapat menampilkan tingkah laku antarkelompok meskipun ia berada jauh dari kelompok ‘aslinya’ dan interaksi yang terjadi dengan kelompok lain juga tidak selalu dilakukan secara tatap muka. Hal yang penting adalah perilaku itu ia tampilkan karena merasa bahwa ia dan kelompok lainnya berasal dari kelompok yang sangat berbeda. Sebagai contoh, bila seseorang merasa dirinya adalah fans fanatik dari Persija, maka ia akan merasa sangat berlawanan dengan fans Persib yang merupakan musuh bebuyutan Persija. la akan menunjukkan fanatisme kelompoknya dengan memakai warna dan atribut Persija, memasang foto Persija di kamarnya, mengumpulkan cerita tentang Persija, serta ‘13 3 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id mendukung Persija saat menonton bola. Selain itu, apabila ia bertemu dengan fans dari Persib yang merupakan musuh bebuyutan Persija, ia akan menyatakan bahwa Persib adalah ‘lawannya’ secara eksplisit dengan berbagai cara. Berbagai tingkah laku antarkelompok di atas hanya mungkin terjadi dalam situasi di mana terdapat sejumlah kelompok yang saling berhubungan dan berinteraksi. Interaksinya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang penting adalah anggota kelompok tersebut merasa bahwa mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Hal ini sesuai dengan batasan yang dikemukakan oleh Sherif (1962) mengenai hubungan antarkelompok, yaitu “relations between two or more groups and their respective members. Whenever individuals belong to one group interact, collectively or individually, with another groups or its members in terms of their group identifications we have an instance of intergroup behavior” : Hubungan antarkelompok terjadi apabila anggota dua kelompok atau lebih saling berinteraksi dan terjadi berdasarkan penghayatan anggota kelompok tersebut pada kelompoknya atau berdasarkan seberapa kuat ia mengidentifikasikan diri pada kelompoknya. Seseorang yang mengidentifikasikan diri dengan kuat pada kelompok tertentu akan sangat merasa sebagai bagian dari kelompok tersebut, merasa bangga, dan sama seperti anggota kelompok lainnya. Apabila ketua FPI, Habib Riziq misalnya, menyatakan: “Sebagai ketua FPI, saya menuntut petugas keamanan atas perlakuan buruk terhadap anggota saya.” Pernyataan tersebut berarti ia memosisikan diri dalam hubungan antarkelompok atau institusi dan bukan mengenai hubungan antara dirinya pribadi dengan seorang aparat. Tingkah laku yang mungkin terjadi pada hubungan antarkelompok ini bisa jadi berbeda dengan hubungan antarpribadi. Berbagai perilaku kelompok seperti prasangka, diskriminasi, kerja sama, konflik, dan kompetisi menjadi mungkin terjadi apabila individu menempatkan serta menghayati dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu pada saat ia berinteraksi. Namun, perilaku kelompok yang positif juga banyak dilakukan, misalnya kerja sama, kompetisi, tolong-menolong antarkelompok, saling mendukung antarbangsa, dan lainlain. Berikut akan dibahas beberapa teori mengenai perilaku antarkelompok, khususnya perilaku yang sering menimbulkan masalah seperti konflik, prasangka, diskriminasi, dan lainlain. Dalam psikologi, teori merupakan upaya untuk menjelaskan mengapa perilaku tersebut terjadi; selain itu juga memungkinkan kita mengantisipasi kemungkinan munculnya suatu kejadian atau perilaku. Teori yang baik akan memenuhi tiga ciri tertentu, yaitu (1) proposisinya (hukum, konsep, ‘dalil’) harus logis dan konsisten satu sama lainnya; (2) teori tersebut harus sesuai dengan fakta dan observasi; (3) harus dapat diuji kebenarannya untuk menentukan kegunaannya (Shaw dan Constanzo, 1982). Pada bab ini akan dibahas beberapa teori mengenai perilaku antarkelompok, yaitu etnosentrisme, realistic conflict theory, teori deprivasi relatif, teori frustrasi agresi, dan teori identitas sosial. ETNOSENTRISME-CIRI KEPRIBADIAN OTORITARIAN Psikologi sejak lama berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana seseorang dapat berkembang menjadi penuh dengan prasangka, sedangkan ada orang lain yang tidak demikian. Adorno et al. (1950 dalam Vaughan dan Hogg, 2005) menjelaskan hal ini dengan ‘13 4 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id apa yang disebutnya kepribadian otoritarian. Adorno yakin bahwa prasangka merupakan konsekuensi dari struktur kepribadian tertentu, yaitu kepribadian otoritarian. Pada zaman itu, Eropa baru bebas dari Nazi, di mana Holocaust dan pembunuhan kepada jutaan orang yang dilakukan Hitler sangat mengguncang banyak orang. Hampir tidak bisa dipercaya bahwa manusia bisa menyiksa dan membunuh sekelompok orang dengan kejam semata-mata karena mereka berasal dari ras yang berbeda (Yahudi). Adorno menjelaskan perilaku di atas dengan mengadopsi pandangan Freud bahwa prasangka merupakan gejala dari keadaan fungsi psikologis yang tidak normal, yang diinternalisasi seorang anak melalui pola asuh orang tuanya. Anak yang dibesarkan dengan cara yang ‘keras’ dan sangat menekankan aturan, kewajiban, otoritas, serta kepatuhan pada orang tuanya, akan tumbuh menjadi anak yang sangat patuh dan takut. Akan tetapi, pada saat yang sama, anak tersebut juga menyimpan dendam dan membenci orang tuanya. Orang tua oleh anak selalu dikagumi, namun sebenarnya anak menekan kebencian pada orang tua mereka dalam-dalam. Identifikasi pada orang tua digeneralisasi pada kelompok otoritas lainnya, sedangkan kritisisme terhadap orang tua maupun figur otoritas lain cenderung ditekan, bahkan dialihkan dan diproyeksikan pada kelompok lain yang lebih lemah. Ciri apakah seseorang memiliki kepribadian otoritarian adalah mereka menghormati dan menghindari figur otoritas, terobsesi dengan ranking dan status, memiliki toleransi rendah terhadap ketidakpastian dan ambiguitas, membutuhkan lingkungan yang strukturnya jelas, serta mengekspresikan kebencian dan diskriminasi terhadap orang lain yang lebih lemah dari dirinya. Adorno mengembangkan teorinya setelah melakukan penelitian pada dua ribu orang kulit putih mengenai sikap terhadap Yahudi, sikap terhadap ‘anti-Negro’; Political dan Economic Conservatism, serta Etnosentrisme. Adorno menemukan bahwa setiap orang memiliki kebencian yang berbeda terhadap berbagai kelompok etnis. Dalam hubungan antarkelompok, anggota kelompok biasanya menjadikan kelompoknya sendiri sebagai acuan utama untuk menilai kelompok lain. Fenomena ini dikenal dengan istilah etnosentrisme dan dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam penyebab konflik. Etnosentrisme adalah cara seseorang memandang lingkungan sekitarnya di mana ia menjadikan kelompoknya sebagai pusat dari segala hal, sehingga berbagai hal lain diukur dengan mengacu pada kelompoknya sendiri. Konsep ini dikemukakan oleh seorang sosiolog bernama William Sumner pada tahun 1906 dan Adorno mengadopsi konsep ini dalam teorinya. Pada orang yang etnosentris (menurut Sumner) atau memiliki authoritarian personality (menurut Adorno), outgroup dipersepsi sebagai kelompok yang mencari kekuasaan dan mengancam serta survival dari ingroup bergantung pada penghancuran semua outgroup. TEORI KONFLIK REALISM Salah satu teori yang paling berpengaruh dan memberi penjelasan mengapa kelompok saling membandingkan diri atau berkompetisi satu sama lain adalah teori konflik realistik (theory conflict realistic-TCR). Berbeda dengan penjelasan otoritarianisme atau etnosentrisme yang menerangkan penyebab perilaku antarkelompok sebagai proses yang bersifat individual atau interpersonal, teori konflik realistik menjelaskan perilaku antarkelompok sebagai fenomena yang hanya dapat dijelaskan pada level kelompok. ‘13 5 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id Teori ini dikemukakan oleh Sherif (1966), di mana ia menekankan pentingnya peran hubungan fungsional antara dua kelompok atau lebih dalam hubungan antarkelompok. Ia juga menyatakan bias, prasangka, ataupun konflik antarkelompok terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ini dapat berupa benda, peluang, wilayah, orang, informasi, atau apa pun juga. Tiga asumsi dasar teori ini adalah (1) manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya; (2) konflik merupakan hasil dari adanya ‘kepentingan’ yang tidak sesuai satu sama lain (incompatibel); dan (3) bahwa aspek psikologi sosial dari hubungan antarkelompok ditentukan oleh kecocokan atau kesamaan minat kelompok. Sheriff, dkk. mengembangkan teori konflik realistik berdasarkan tiga rangkaian studinya (1949, 1953, dan 1954) pada sekelompok remaja kulit putih kelas menengah berusia sekitar 11-12 tahun. Studi ini dilakukan dalam seting alamiah, dalam sebuah ‘summer camp’. Hipotesis dasarnya, apabila sebuah kelompok ‘memisahkan’ diri dari kelompok lain, maka kelompok tersebut akan terbentuk suatu norma, yang kemudian akan menjadi dasar untuk menetapkan reward ataupun sanksi tertentu. Kemudian, kelompok akan menetapkan stereotip terhadap outgroup yang biasanya merupakan sesuatu yang merendahkan dan bersifat negatif. Pada eksperimen lapangan yang berlangsung beberapa minggu ini, para remaja menyangka mereka benar-benar beraktivitas dalam suatu kemping untuk anak-anak muda. Sherif, dkk. meneliti berbagai proses yang terjadi, dari pembentukan kelompok sampai terbentuknya konflik, kerja sama, dan solusi konflik. Terdapat empat tahap eksperimen, yaitu (1) tahap perkenalan secara spontan; (2) pembentukan kelompok; (3) konflik antarkelompok; (4) kerja sama antarkelompok atau menurunnya konflik antarkelompok. Pada tahap pertama eksperimen ini, sejumlah remaja yang belum saling mengenal diberi kesempatan untuk berkenalan dan melakukan aktivitas bersama. Mereka bebas memilih teman, kemah, dan aktivitas yang mereka sukai, sehingga mereka menjadi cukup akrab. Pada tahap kedua, peserta yang sudah akrab tadi dibagi menjadi dua kelompok baru, sehingga kini mereka terpisah dari teman akrabnya dan menjadi sekelompok dengan orang lain. Menurut Sherif, dalam kelompok baru ini, pola individu dalam memilih teman ternyata menjadi berubah, dari rasa tertarik/cocok pada teman menjadi berdasarkan memilih teman karena dia ada dalam kelompoknya (ingroup exclusiveness). Dalam tahap kedua ini, anggota kelompok harus berinteraksi dan melakukan beberapa tugas kompetitif bersama teman sekelompoknya, seperti memasak, kemah bersama, naik kano, dan lain-lain. Mereka kemudian membuat nama kelompok (The Eagles dan The Rattlers), yel, jargon, serta membuat sejumlah norma dan aturan untuk dipatuhi anggotanya. Tahap ketiga dirancang untuk melihat apa yang akan terjadi apabila kedua kelompok terlibat dalam kompetisi yang memberikan hadiah, misalnya bertanding bola basket, mencari jejak, dan lain-lain. Ternyata, dalam proses kompetisi ini mereka kemudian menjadi saling mengejek, meledek, bahkan di akhir kompetisi mereka menjadi sangat bermusuhan dan tidak mau saling bicara. Dalam studi Sherif yang dikenal dengan “Robber's Cave study” (1954), kedua kelompok dikumpulkan dan berkompetisi untuk mengumpulkan sejumlah ‘biji’ sebanyak mungkin dalam waktu tertentu. Ternyata mereka memperkirakan jumlah ‘biji’ yang dikumpulkan kelompoknya sendiri jauh lebih tinggi daripada yang dikumpulkan kelompok lain. Oleh karena kompetisi yang ada membuat anggota kelompok tampaknya semakin menjadi kasar dan membenci satu sama lain, Sheriff kemudian memutuskan untuk ‘13 6 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id menghentikan studi ketiganya karena ia sangat khawatir apabila perkembangan yang terjadi mengarah pada kebencian antarkelompok. Ia kemudian merancang untuk memperbaiki hubungan antarkelompok dan menurunkan konflik yang ada (tahap keempat). Hal ini ia upayakan dengan berbagai cara, antara lain memberi kuliah mengenai cinta dan pemberian maaf-yang ternyata tidak membantu. Ia kemudian memperkenalkan apa yang dikenal dengan musuh bersama (‘common enemy’), yang meskipun cukup berhasil memperbaiki hubungan antarkelompok, tetapi dikhawatirkan justru akan memperbesar skala konflik. Pada Robber's cave study ia memunculkan superordinate goal, suatu tujuan bersama yang penting bagi kedua kelompok, tetapi tidak mungkin dicapai hanya oleh salah satu kelompok saja; kedua kelompok harus bekerja sama untuk mencapai dan mewujudkannya. Sherif memunculkan superordinate goal dengan membuat situasi ‘krisis’ di mana tangki untuk suplai air mereka bocor dan kedua kelompok harus bekerja sama untuk mengatasi situasi tersebut. Superordinate goal berikutnya adalah membuat situasi di mana pengurus camp tidak bisa membayar film yang ingin ditonton oleh anak-anak dan bila ingin menonton film tersebut, mereka semua harus ikut patungan. Superordinate goal ketiga terjadi pada saat truk makanan mereka mogok waktu mereka akan jalan-jalan ke danau. Truk tersebut baru bisa berjalan apabila mereka semua menariknya dengan tali agar bisa dihidupkan. Penelitian Sherif merupakan tonggak penting bagi psikologi sosial karena menunjukkan adanya diskontinuitas antara proses individual dengan proses kelompok serta membuktikan bahwa proses kelompok merupakan proses yang terpisah dan berbeda dengan proses individual. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkah laku agresif antarkelompok ternyata bukan merupakan proses yang bersifat individual ataupun hubungan antarpribadi. TEORI IDENTITAS SOSIAL Teori ini dikembangkan oleh Tajfel dan Turner (Turner dkk., 1987). Menurut teori identitas sosial, perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses penting, yaitu proses kognitif dan proses motivasional. Proses kognitif membuat individu melakukan kategorisasi pada berbagai stimulus yang ia hadapi, termasuk juga pada kelompok yang ia temui, sehingga individu cenderung untuk memandang orang lain sebagai anggota ingroup atau anggota outgroup (Hogg dan Abrams, 1990). Sementara itu, sebagai proses motivasional, perilaku yang ditampilkan anggota suatu kelompok merupakan usaha individu agar memperoleh harga diri dan identitas sosial yang positif. Setiap individu memiliki motivasi untuk memiliki harga diri yang positif dan untuk ‘memelihara’ harga dirinya. Ia mengidentifikasikan diri pada kelompok tertentu terutama yang memiliki berbagai kualitas positif. Menurut teori ini, perilaku kelompok menekankan adanya tiga struktur dasar. Struktur pertama adalah kategorisasi, yaitu proses di mana individu memersepsi dirinya sama atau identik dengan anggota lain dalam kelompok yang sama. Di samping individu memersepsi dirinya memiliki identitas sosial yang sama dengan anggota tersebut, individu juga akan bertingkah laku sesuai dengan kategori di mana ia termasuk di dalamnya. Kategorisasi ini akan mendorong individu untuk menekankan kesamaan dengan sesama anggota yang berada dalam kelompok yang sama, tetapi akan menekankan perbedaan dengan anggota dari kelompok yang lain. Struktur kedua adalah identitas, yang dapat didefinisikan sebagai ‘13 7 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id citra diri, konsep diri, atau pemaknaan seseorang terhadap diri sendiri (Augoustinos dan Walker, 1995; Hogg dan Abrams, 1990). Identitas merupakan hal yang penting karena setiap individu memiliki dorongan kuat untuk menganggap bahwa dirinya baik dan memiliki identitas serta harga diri yang positif. Menurut teori ini, individu juga dapat memperoleh identitas sosial melalui keanggotaannya pada kelompok tersebut (Hogg dan Abrams, 2000). Menurut Turner (1999), untuk mencapai dan mempertahankan identitas sosial yang positif, individu cenderung mengutamakan kelompok sendiri (ingroup) dibandingkan kelompok lain (outgroup). Hal ini dapat menimbulkan intergroup bias di mana individu memberi penilaian yang tidak objektif untuk kelompoknya, cenderung untuk lebih mengutamakan kelompok sendiri dan tidak mengutamakan kelompok lain (Augoustinos dan Walker, 1995; Myers, 1996). Struktur ketiga dari proses kelompok adalah perbandingan sosial. Penilaian seseorang tentang diri sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perbandingan dengan orang lain. Individu memaknai dan menilai dirinya berdasarkan kelompok di mana ia berada serta individu biasanya menggunakan kelompoknya sendiri sebagai acuan utama. Individu yang memiliki harga diri positif merupakan individu yang menilai dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Individu juga memperoleh identitas sosial melalui keanggotaannya pada kelompok tersebut (Hogg dan Abrams, 2000). Teori ini dikembangkan berdasarkan studi Tajfel dan Turner yang dikenal dengan istilah minimal group paradigm. Pada studi ini, sejumlah anak sekolah dibagi ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan preferensi mereka terhadap lukisan yang lebih mereka senangi (lukisan Klee atau Kadinsky). Mereka kemudian diminta membagi sejumlah uang untuk anggota kelompok mereka sendiri atau anggota kelompok lain, tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Hasil studi Tajfel membuktikan bahwa anak-anak ternyata memberi lebih banyak uang untuk anggota kelompoknya sendiri dan bukan untuk anggota kelompok lain. Temuan studi ini membuktikan bahwa meskipun dalam kondisi minimal, individu tetap membentuk kelompok, terlihat dari kecenderungan mereka untuk memberi jumlah yang lebih banyak pada kelompoknya sendiri. Maksud dari ‘minimal’ di sini, meskipun individu tidak mengetahui identitas kelompok sendiri maupun kelompok lain, tidak ada self-interest sama sekali atau kelompok tersebut tidak mempunyai latar belakang sejarah sama sekali, seseorang akan tetap membagi diri dan kelompok lain ke dalam dua kelompok yang berbeda. Individu tetap mengategorikan dirinya dan orang lain ke dalam kelompok yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengategorisasikan diri dalam kelompok tertentu. Berbagai studi replikasi kemudian dilakukan untuk menguji kecenderungan ini dengan menggunakan partisipan dari berbagai kelompok. Tajfel dan Billig (1973) membagi kelompok ke dalam kategori X dan Y untuk membuat kelompok yang terbentuk semakin ‘minimal’ karena tidak didasarkan pada kesamaan minat atau pelukis. Alokasi sumber dayanya dapat berupa uang, poin, ataupun pengukuran aspek sikap, afek, dan konatif dari etnosentrisme. Temuan berbagai studi replikasi terhadap minimal group paradigm ini menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu penggolongan individu ke dalam kategori tertentu dapat menimbulkan etnosentrisme dan tingkah laku kompetitif kelompok (Bourhis, Sachdev, dan Gagnon, 1994). Menurut teori identitas sosial, intergroup bias terjadi karena adanya kebutuhan anggota kelompok untuk menilai kelompok sendiri-dan berarti dirinya sendiri-secara positif. Bias ini dapat berupa (1) menampilkan perilaku diskriminatif dalam upayanya untuk ‘13 8 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id meningkatkan harga dirinya atau (2) individu yang tadinya memiliki harga diri yang rendah (misalnya status rendah dan kelompok marginal) berusaha meningkatkan harga dirinya agar mencapai tingkat ‘normal’. Bukti tentang adanya intergroup bias terlihat pada studi yang dilakukan Taylor dan Jaggi (1974). Mereka meneliti mengenai intergroup attribution bias pada dua kelompok di India bagian selatan yang memiliki latar belakang konflik antara kelompok Islam dan Hindu. Partisipan Hindu diminta untuk membayangkan seorang Hindu (ingroup) atau Muslim (outgroup) melakukan tindakan yang secara sosial dapat diterima dan yang secara sosial tidak dapat diterima. Kemudian, mereka diminta menilai sejauh mana tingkah laku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal/situasional. Ternyata, konsisten dengan intergroup attribution bias, partisipan Hindu lebih memberikan atribusi internal pada tingkah laku positif yang dilakukan orang Hindu daripada Muslim. Sebaliknya, mereka lebih memberikan atribusi eksternal terhadap tingkah laku negatif yang dilakukan orang Hindu dibandingkan tingkah laku positif yang dilakukan orang Muslim. Intergroup bias dapat terlihat dalam berbagai macam bentuk. Salah satu bentuknya adalah fenomena ultimate attribution error/attribution bias (kecenderungan untuk memberi penjelasan secara bias), di mana individu cenderung memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap anggota kelompoknya dibandingkan kepada anggota kelompok lain (Baron dan Byrne, 2002). Intergroup bias juga dapat timbul dalam bentuk outgroup homogeneity effect yang merupakan kecenderungan kelompok untuk melihat anggota kelompok lain lebih homogen dibandingkan dengan anggota kelompok mereka sendiri (Jones, Wood, dan Quattrone, 1981; Linville dan Jones, 1980). Bentuk intergroup bias lainnya adalah black sheep effect, yaitu suatu keadaan bila anggota kelompok melakukan tingkah laku yang buruk dan dianggap menyimpang dari kelompoknya akan mendapat penilaian lebih buruk dibandingkan hal yang sama yang dilakukan oleh anggota dari kelompok lain (Marque dkk., 1988). Suatu bentuk intergoup bias yang agak khusus dan terkait dengan kritisisme antarkelompok adalah intergroup sensitivity effect atau kecenderungan anggota kelompok untuk lebih mau menerima kritik dari sesama kelompok sendiri dibandingkan dari anggota kelompok lain. Sebuah studi mengenai kesediaan menerima kritik (intergroup sensitivity effect) pada atasan-bawahan (Melissa A, 2006) menemukan bahwa reaksi atasan ketika menerima kritik ternyata berbeda pada saat ia menerima kritik dari sesama atasan (ingroup) atau dari bawahannya (outgroup). Studi ini membuktikan adanya pengaruh dari keanggotaan sumber kritik terhadap kesediaan menerima kritik. Kritik dari sesama atasan dianggap memang ditujukan untuk kebaikan atasan sehingga cenderung disetujui. Mereka juga lebih mau berubah berdasarkan kritik dari sesama rekan atasan tersebut dibandingkan ketika kritik yang sama disampaikan oleh bawahannya. Namun, kritik dari sesama atasan dianggap lebih menyinggung perasaan dibandingkan apabila berasal dari bawahan. Di Indonesia, sebuah studi tentang intergroup bias pada pengguna jalan di Jakarta (draft RUUI 08/09) menemukan adanya bias persepsi yang timbal balik antara pengemudi kendaraan umum terhadap pengemudi mobil pribadi dan antara pengemudi kendaraan umum terhadap pengendara motor. Pengendara motor dan mobil pribadi menganggap pengemudi kendaraan umum mengakibatkan kemacetan jalan dengan berhenti ‘13 9 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id sembarangan mengambil penumpang dengan tidak memperhatikan keadaan, sebaliknya pengemudi kendaraan umum merasa tidak dimengerti bahwa mereka butuh mencari sewa dari penumpang. Pengemudi kendaraan umum justru menganggap pengendara motor yang membahayakan penumpang mereka dan pengemudi mobil pribadi dianggap tidak peduli/egois. Studi ini dilakukan terhadap sekitar 50 pengemudi kendaraan umum di Jakarta. Hal yang menarik, dalam hal bias atribusi terhadap perilaku positif kelompok pengguna jalan yang lain, pengemudi kendaraan umum tidak menunjukkan adanya penilaian yang bias. Perilaku positif semua pengguna jalan (pengemudi mobil pribadi, motor, pejalan kaki, polantas, dan pedagang kaki lima) diatribusikan kepada faktor internal. Namun, terhadap perilaku positif kelompoknya sendiri, mereka juga mengatribusikannya pada faktor internal, yang merupakan indikasi adanya bias atribusi. Terhadap perilaku negatif ingroup ataupun outgroup, studi ini tidak menemukan indikasi adanya bias atribusi. Partisipan mengatribusikan perilaku negatif ingroup maupun outgroup-nya pada faktor eksternal, perilaku negatif yang ada dianggap disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada di luar diri pengguna jalan (aturan yang tidak jelas, macet, jalan buruk, hujan, dan lain-lain). TEORI DEPRIVASI RELATIF Apabila teori identitas sosial menekankan pentingnya peran motivasional individu dalam perilaku kelompok yang ia tampilkan. Teori deprivasi relatif menekankan pada pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi ‘kekurangan’ (deprivasi) dan ‘kurang beruntung’ (disadvantage). Konsep ini dikemukakan oleh Stouffler dkk. (1949) dalam studi mengenai tentara Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa dalam kelompok air force di mana banyak tentara yang mendapat promosi, justru lebih banyak tentara yang mengajukan komplain dibandingkan dalam kelompok polisi, yang umumnya jarang memperoleh promosi. Oleh karena di antara polisi tidak banyak yang memperoleh kenaikan pangkat, mereka tidak merasa kekurangan (deprive) dan tidak merasa perlu mengajukan komplain pada atasannya. Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi lebih formal oleh Davis (1959) dan didefinisikan sebagai persepsi terhadap adanya perbedaan (discrepancy) antara kenyataan (what is) dengan harapan atau keinginan (what ought to be). Menurut Gurr (1970), keadaan deprivasi relatif ini bersumber dari pembandingan antara pengalaman dengan harapan yang dimiliki seseorang dan merupakan kondisi yang bersifat relatif. Kondisi deprivasi relatif merupakan prakondisi yang sangat menentukan bagi terjadinya agresi antarkelompok, seperti perilaku agresi kolektif atau riot. Aplikasi yang terkenal dari teori ini adalah dalam menjelaskan Watt's riot, suatu kerusuhan yang terjadi di Los Angeles pada tahun 1967. Pada saat itu, sedang musim panas dan kondisi ini memfasilitasi terjadinya kekerasan kolektif. Menurut Berkowitz, dalam kondisi di mana orang merasa bahwa kenyataan yang dihadapi berbeda dengan yang ia harapkan (terdapat deprivasi relatif) banyak orang yang merasa frustrasi. Temperatur yang tinggi pada musim panas (summer) memperkuat frustrasi yang dirasakan individu, terutama pada daerah ‘slum’ di mana mereka tidak memiliki AC atau kipas angin. Agresivitas individu menjadi meningkat, menyebar, dan melalui proses fasilitasi sosial dapat mengalami transformasi menjadi kekerasan kolektif. Penjelasan deprivasi relatif juga dapat diterapkan misalnya untuk kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, di mana pada saat itu masyarakat sangat frustrasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. ‘13 10 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id “Hostile media bias” dalam kaitan dengan pemberitaan konflik yang tinggi Penelitian ini mengkaji tentang fenomena `hostile media bias" atau tentang sejauh mana pemberitaan media dipersepsi sebagai bias, tidak objektif, dan berpihak. Meskipun seseorang membaca, mendengar, atau melihat informasi yang sama, informasi tersebut dipersepsi sebagai bias, berpihak pada ‘outgroup’, dan dianggap dapat memengaruhi seseorang yang tadinya netral menjadi berpihak pada outgroup. Fakta bahwa berita yang sama dinilai secara berbeda menunjukkan bahwa bias yang terjadi adalah bias persepsi. Gunther (1992) menemukan bahwa keanggotaan pada kelompok merupakan prediktor terbesar bagi apakah media akan dipersepsi secara bias. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2000-2004, saat konflik Ambon sedang pada puncaknya. Konflik ini sering diberitakan dalam media sebagai konflik antara kelompok Islam dan Kristen. Partisipan penelitian adalah 215 mahasiswa beragama Islam dan Kristen dari 3 universitas di Jakarta. Partisipan diminta membaca sebuah artikel mengenai konflik ‘antar agama’. Artikel ini diambil dari sebuah koran, tetapi dimodifikasi dalam hal waktu, tempat, dan pelakunya. Tiga kelompok mahasiswa membaca artikel tersebut dalam 3 kondisi, yaitu dalam koran ‘Islam’, koran ‘Kristen’, dan koran yang tidak berorientasi pada kelompok agama tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan ‘hostile media bias’, tetapi hanya pada responden yang memiliki identifikasi tinggi pada agamanya. Selain itu, ditemukan pula peran latar belakang media dalam memengaruhi bias persepsi yang terjadi: artikel di persepsi sebagai memihak pada kelompok muslim apabila ditulis dalam koran “Islam”, berpihak pada kelompok Kristen apabila ditulis dalam koran “Kristen”, dianggap tidak jelas berpihak apabila ditulis dalam koran yang tidak terkait dengan agama tertentu. Efek dari latar belakang ‘agama’ koran dimediasi oleh adanya ‘prior belief’ tentang adanya bias. Sumber: Disertasi oleh Ariyanto AA, School of Psychology, University of Queensland, Brisbane tahun 2005 Runciman (1966 dalam Hogg, 1988) mengemukakan adanya dua macam deprivasi relatif. Pertama adalah deprivasi relatif egoistik, yaitu perasaan deprivasi yang dialami individu dalam hubungan dengan individu lain yang berasal dari kelompok yang sama dengan dirinya. Misalnya, seorang guru yang membandingkan diri dengan guru lain yang menurutnya lebih berhasil dan memperoleh banyak penghasilan dibandingkan dirinya. Bentuk lainnya adalah deprivasi relatif fraternal, yaitu deprivasi relatif yang dirasakan saat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang berbeda, yang berasal dari kelompok lain. Misalnya, seorang guru, yang membandingkan diri dengan seorang pengusaha. Guru tersebut merasa kekurangan karena si pengusaha memperoleh lebih banyak penghasilan, status, maupun kekuatan yang dianggapnya jauh lebih banyak dibandingkan dirinya. Strategi meningkatkan hubungan antarkelompok. Kelompok yang berkonflik dapat berusaha memperbaiki hubungan dengan yang lain, dengan membina komunikasi secara langsung antara mereka. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi (bargaining), mediasi (menggunakan perantara), atau arbitrase. Ketiga cara ini melibatkan prosedur yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai upaya untuk mengurangi ‘13 11 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id hambatan psikologis yang telah terbentuk agar dapat mencapai sebuah resolusi antara kedua kelompok. Berbagai hambatan psikologis yang telah terbentuk antarkelompok selama kelompok tersebut berinteraksi (misalnya harga diri, emosi, bias atribusi, ‘luka emosi’, ingkar janji, dan lain-lain) mempersulit terbentuknya komunikasi yang baik dan efektif antara kelompok yang berkonflik. Negosiasi (Bargaining). Negosiasi antarkelompok biasanya dilakukan antara pihak yang terlibat langsung dalam konflik yang terjadi. Misalnya, antara kelompok buruh dengan pimpinan perusahaan, antara korban Lapindo dengan pihak Lapindo Brantas, dan lain-lain. Negosiasi (bargaining) adalah proses resolusi konflik di mana perwakilan antara kedua kelompok berusaha mencapai kesepakatan melalui negosiasi langsung. Pengalaman mengenai negosiasi menunjukkan bahwa apabila kedua kelompok bernegosiasi langsung atas nama kelompoknya, proses yang terjadi bisa cukup ‘keras’ dan sulit tercapai kompromi daripada apabila mereka bernegosiasi semata-mata untuk dirinya sendiri. Suatu studi menemukan bahwa proses negosiasi dapat menjadi lebih sulit apabila negosiator yang terlibat menyadari bahwa mereka diawasi oleh anggota kelompoknya, baik secara langsung ataupun melalui media. Negosiasi secara langsung antara perwakilan kelompok yang bertikai juga menjadi cukup sulit dan kedua kelompok dapat menganggap bahwa mereka sukar untuk bisa mencapai kompromi tanpa merasa kehilangan ‘muka’. Mediasi. Untuk mengatasi ‘deadlock’, biasanya diminta bantuan orang atau pihak ketiga untuk menjadi mediator antara kelompok yang bertikai. Agar efektif, mediator seharusnya merupakan pihak yang memiliki ‘power’, dianggap tidak berpihak, dan kelompok yang berkonflik sudah berada pada tahap yang ‘agak dekat’ satu sama lain. Apabila mediator dinilai sebagai tidak objektif, berpihak, dan ‘lemah’, biasanya ia akan merupakan negosiator yang tidak efektif. Namun, meskipun dianggap lemah, adanya mediator tersebut tetap dapat menumbuhkan beberapa efek positif seperti: - mengurangi tekanan emosi bahwa perundingan yang dilakukan mengalami deadlock’; - dapat mengurangi kesalahan persepsi, menambah saling pengertian antarkelompok, dan menumbuhkan ‘trust’; - membantu kedua kelompok untuk mengalah tanpa kehilangan muka; - mengurangi konflik intrakelompok dan membantu kelompok menemukan posisi mereka dalam konflik yang terjadi. Arbitrase. Arbitrase merupakan proses untuk mengatasi konflik dimana sebuah kelompok yang dianggap netral diminta untuk menengahi dan mengembangkan ikatan antara kelompok yang bertikai. Cara ini dianggap merupakan ‘upaya terakhir’ yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik antarkelompok, setelah negosiasi dan mediasi tidak berhasil mencapai resolusi konflik. Namun, kadangkala prospek dari sebuah arbitrase justru dapat menjadi ‘melemahkan’ upaya yang telah dicapai karena pihak yang berpihak menjadi terlalu berharap akan dicapai suatu kompromi yang baik. Oleh karena itu, kadang dilakukan ‘final-offer arbitrase’, di mana pihak ketiga kemudian memilih satu ‘upaya final yang ditawarkan’ dalam upaya mendorong dicapainya posisi final yang lebih dapat diterima kedua belah pihak. ‘13 12 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id KESIMPULAN Hubungan antarkelompok terjadi apabila anggota dua kelompok atau lebih saling berinteraksi, dan interaksi tersebut terjadi berdasarkan penghayatan anggota kelompok tersebut pada kelompoknya atau seberapa kuat ia mengidentifikasikan diri pada kelompoknya. Perilaku antarkelompok dapat melibatkan pertemuan yang tatap muka maupun tidak, melibatkan interaksi, dan individu yang terlibat merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang terpisah dari kelompok lainnya. Beberapa teori yang dapat menjelaskan perilaku antarkelompok ini adalah teori konflik realistik, teori identitas sosial, teori authoritarian personality, dan teori deprivasi relatif. Beberapa upaya meningatkan hubungan antara kelompok adalah melakukan negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Daftar Pustaka Sarwono, S.W., & Meinarno, E.A. (2009). Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika ‘13 13 Psikologi Sosial 2 Filino Firmansyah, M.Psi Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

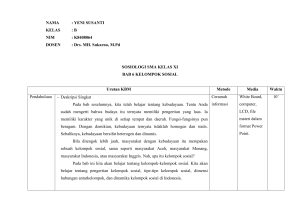


![Modul Pendidikan Agama Islam [TM14]](http://s1.studylibid.com/store/data/000037080_1-41e1da2303d0f0482fc45d50091bab4e-300x300.png)