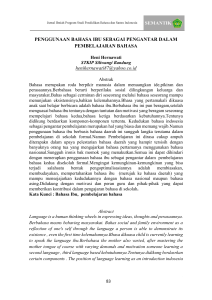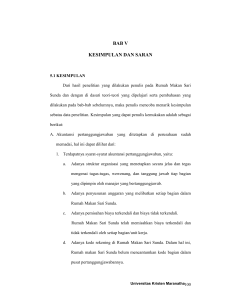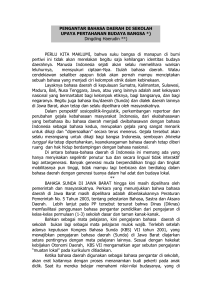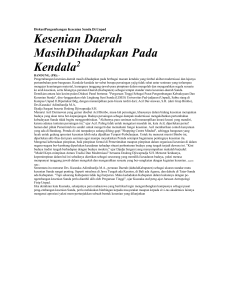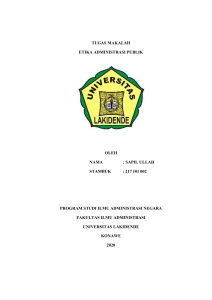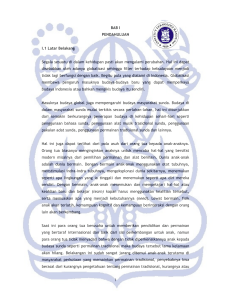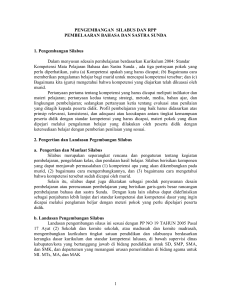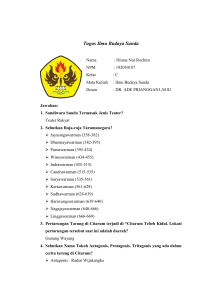Interupsi Nopember 2005
advertisement
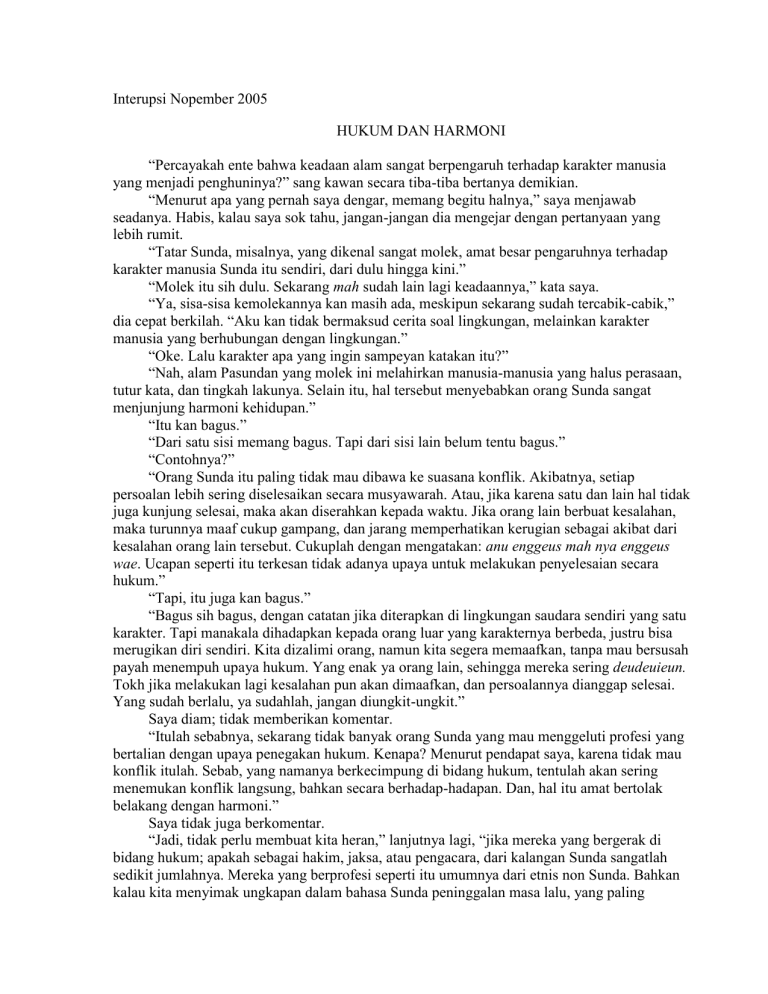
Interupsi Nopember 2005 HUKUM DAN HARMONI “Percayakah ente bahwa keadaan alam sangat berpengaruh terhadap karakter manusia yang menjadi penghuninya?” sang kawan secara tiba-tiba bertanya demikian. “Menurut apa yang pernah saya dengar, memang begitu halnya,” saya menjawab seadanya. Habis, kalau saya sok tahu, jangan-jangan dia mengejar dengan pertanyaan yang lebih rumit. “Tatar Sunda, misalnya, yang dikenal sangat molek, amat besar pengaruhnya terhadap karakter manusia Sunda itu sendiri, dari dulu hingga kini.” “Molek itu sih dulu. Sekarang mah sudah lain lagi keadaannya,” kata saya. “Ya, sisa-sisa kemolekannya kan masih ada, meskipun sekarang sudah tercabik-cabik,” dia cepat berkilah. “Aku kan tidak bermaksud cerita soal lingkungan, melainkan karakter manusia yang berhubungan dengan lingkungan.” “Oke. Lalu karakter apa yang ingin sampeyan katakan itu?” “Nah, alam Pasundan yang molek ini melahirkan manusia-manusia yang halus perasaan, tutur kata, dan tingkah lakunya. Selain itu, hal tersebut menyebabkan orang Sunda sangat menjunjung harmoni kehidupan.” “Itu kan bagus.” “Dari satu sisi memang bagus. Tapi dari sisi lain belum tentu bagus.” “Contohnya?” “Orang Sunda itu paling tidak mau dibawa ke suasana konflik. Akibatnya, setiap persoalan lebih sering diselesaikan secara musyawarah. Atau, jika karena satu dan lain hal tidak juga kunjung selesai, maka akan diserahkan kepada waktu. Jika orang lain berbuat kesalahan, maka turunnya maaf cukup gampang, dan jarang memperhatikan kerugian sebagai akibat dari kesalahan orang lain tersebut. Cukuplah dengan mengatakan: anu enggeus mah nya enggeus wae. Ucapan seperti itu terkesan tidak adanya upaya untuk melakukan penyelesaian secara hukum.” “Tapi, itu juga kan bagus.” “Bagus sih bagus, dengan catatan jika diterapkan di lingkungan saudara sendiri yang satu karakter. Tapi manakala dihadapkan kepada orang luar yang karakternya berbeda, justru bisa merugikan diri sendiri. Kita dizalimi orang, namun kita segera memaafkan, tanpa mau bersusah payah menempuh upaya hukum. Yang enak ya orang lain, sehingga mereka sering deudeuieun. Tokh jika melakukan lagi kesalahan pun akan dimaafkan, dan persoalannya dianggap selesai. Yang sudah berlalu, ya sudahlah, jangan diungkit-ungkit.” Saya diam; tidak memberikan komentar. “Itulah sebabnya, sekarang tidak banyak orang Sunda yang mau menggeluti profesi yang bertalian dengan upaya penegakan hukum. Kenapa? Menurut pendapat saya, karena tidak mau konflik itulah. Sebab, yang namanya berkecimpung di bidang hukum, tentulah akan sering menemukan konflik langsung, bahkan secara berhadap-hadapan. Dan, hal itu amat bertolak belakang dengan harmoni.” Saya tidak juga berkomentar. “Jadi, tidak perlu membuat kita heran,” lanjutnya lagi, “jika mereka yang bergerak di bidang hukum; apakah sebagai hakim, jaksa, atau pengacara, dari kalangan Sunda sangatlah sedikit jumlahnya. Mereka yang berprofesi seperti itu umumnya dari etnis non Sunda. Bahkan kalau kita menyimak ungkapan dalam bahasa Sunda peninggalan masa lalu, yang paling ditakuti –dalam tanda kutip– oleh balarea dulu adalah jaksa, sehingga ada ungkapan khusus tentang hal itu. Kata kakek saya dulu, kalau pohon buah-buahan, khususnya petai, tidak mau berbuah, maka akan dikata-katai semacam ancaman: pek siah, hayang dijieun padung jaksa? Maksudnya, pohon tersebut diancam akan ditebang, lalu kayunya akan dijadikan penutup lubang lahat jaksa. Konon katanya pohon tersebut akan segera berbuah, saking takutnya dijadikan padung. Jadi, jangankan orang, pohon petai pun amat takut terhadap jaksa mah. Padahal, jaksa yang berada di lubang lahat pastilah yang sudah tidak lagi bernyawa—apalagi oleh jaksa yang masih hidup.” Menarik juga cerita si kawan ini. “Ada juga ungkapan lain yang mengandung makna bahwa kita pantang berurusan di meja hijau, yaitu: ulah hayang unggah bale watangan. Yang dimaksud bale watangan adalah pengadilan pada masa lalu. Sampai-sampai jika sekadar bermimpi pun, orang tua kita mengatakan: ngimpi ge diangir mandi. Maksudnya, jika suatu saat kita bermimpi mengalami berurusan dengan pengadilan, maka harus segera mandi untuk membersihkan diri. Karena itulah, saking pantangnya berurusan dengan pengadilan, banyak persoalan yang akhirnya diselesaikan di luar hukum, yang baik puas maupun tidak puas maka harus dianggap selesai. Jika kondisi seperti itu masih diterapkan pada kehidupan masa kini, saya kira akan banyak merugikan kita sendiri. Tokh dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita banyak bersinggungan dengan etnis lain, yang tentu saja karakternya berbeda dengan kita.” “Tapi, saya kira ada juga orang Sunda yang berprestasi di bidang penegakan hukum. Sebut saja Benyamin Mangkudilaga, Apong Herlina, atau Absar Kartabrata. Selain itu, ada juga nama Teten Masduki atau Erry Riyana Hardjapamekas,” sanggah saya. “Iya, tapi jumlahnya amatlah sedikit. Lagi pula, mereka itu bukan jaksa,” ia segera menimpali.*** (Tatang Sumarsono)