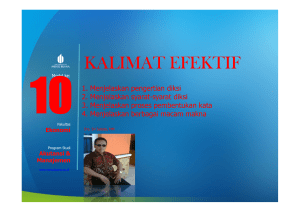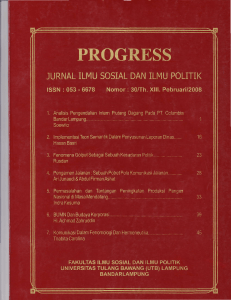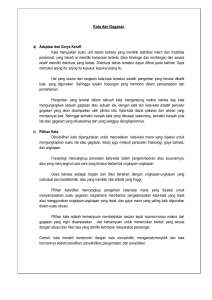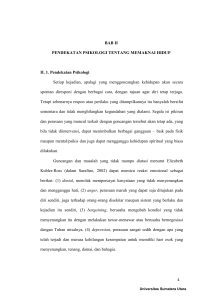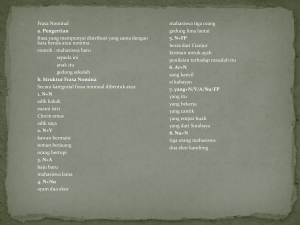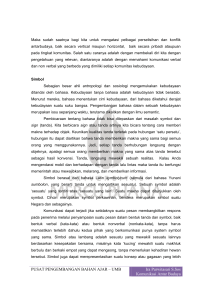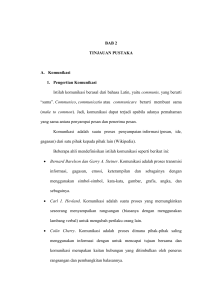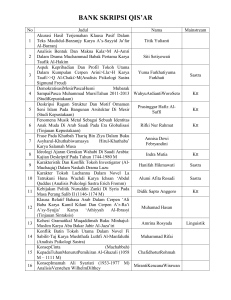8 Bab 2 Landasan Teori 2.1 Teori Sastra Menurut Rene Wellek dan
advertisement

Bab 2 Landasan Teori 2.1 Teori Sastra Menurut Rene Wellek dan Austin Warren Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Setiap karya sastra pada dasarnya bersifat umum dan sekaligus bersifat khusus, atau lebih tepatnya lagi individual dan umum sekaligus. Setiap karya sastra mempunyai sifat-sifat yang sama dengan karya seni lainnya (Wellek dan Warren, 1989: 9). Salah satu batasan sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Greenlaw (teoritikus sastra Inggris) dalam Wellek dan Warren (1989: 11), mendukung gagasan ini: “Segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan termasuk dalam wilayah kita” (“Nothing related to the history of civilization is beyond our province”). Ilmuwan sastra “tidak terbatas pada belles letters atau manuskrip cetakan atau tulisan dalam mempelajari sebuah periode atau kebudayaan” (“Not limited to belles letters or even to printed or manuscript record in our effort to understand a period or civilization”), dan ilmuwan sastra harus dilihat dari “sumbangan pada sejarah kebudayaan” (“in the light of its possible contribution to the history of culture”). Istilah “sastra” paling tepat diterapkan pada seni sastra, yaitu sastra sebagai karya imajinatif. Sastra tidak hanya mengkontraskan “pikiran” dan “emosi” atau “perasaan”, sastra juga mengandung pikiran, sedangkan bahasa emosional tidak selalu dimiliki oleh sastra. Bahasa sastra penuh ambiguitas dan homonim (kata-kata yang sama bunyinya tetapi berbeda artinya), serta memiliki kategori-kategori yang tak beraturan dan tak rasional seperti gender (jenis kata yang mengacu pada ungkapan atau karya yang diciptakan sebelumnya). Dengan kata lain, bahasa sastra sangat “konotatif” sifatnya. 8 Bahasa sastra bukan sekedar bahasa referensial, yang hanya mengacu pada satu hal tertentu. Bahasa sastra mempunyai sifat ekspresif, menunjukkan nada (tone) dan sikap pembicara atau penulisnya. Bahasa sastra berusaha membujuk, mempengaruhi dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca (Wellek dan Warren, 1989: 14-15). Istilah sastra sebagai karya imajinatif disini tidak berarti bahwa setiap karya sastra harus memakai imaji (citra). Di bawah pengaruh Hegel, mereka memberi batasan bahwa semua karya seni adalah the sensuous shining forth of the idea “bersinarnya ide secara indrawi.” Aliran lain seperti Riehl Hildebrandt Fidle menganggap bahwa semua karya seni adalah karya yang sepenuhnya nampak (pure visibility), tetapi banyak karya sastra tidak membangkitkan imaji indrawi. Kalaupun ada, imaji itu muncul secara kebetulan dan kadang-kadang, bahkan dalam menampilkan tokoh, seorang pengarang tidak selalu perlu memakai citra klasik (Wellek dan Warren, 1989: 21). 2.2 Teori Intertekstual Secara luas interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Selain itu, teks itu sendiri secara etimologis (textus, bahasa Latin) berarti tenunan, anyaman, penggabungan, sususan, dan jalinan. Kristeva dalam Culler (1975: 139), menyatakan bahwa setiap teks adalah mozaik kutipan-kutipan, penyerapan dan transformasi dari teks lain, termasuk di dalamnya adalah teks karya sastra. Menurut Kristeva dalam Teeuw (1984: 145-146), setiap teks sastra harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lain; tidak ada satu teks pun yang benar-benar mandiri, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan, kerangka; tidak dalam arti bahwa teks baru hanya meneladani teks lain atau mematuhi kerangka-kerangka yang telah diberikan lebih dahulu, tetapi 9 dalam arti bahwa dalam penyimpangan dan transformasi pun model teks yang sudah ada memainkan peranan yang penting: pemberontakan atau penyimpangan menyatakan adanya sesuatu yang memungkinkan untuk terjadinya pemberontakan atau penyimpangan. Produksi makna terjadi dalam interteks, yaitu melalui proses oposisi, permutasi, dan transformasi. Penelitian dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan bermakna di antara dua teks atau lebih. Teks-teks yang dikerangkakan sebagai interteks tidak terbatas sebagai persamaan genre, interteks memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk menemukan hipogram, karena konsep penting dalam teori interteks adalah hipogram, dikemukakan oleh Riffaterre (1978: 11-13), yang sesungguhnya sudah digunakan dalam tradisi Saussurean. Menurut Riffaterre, hipogram adalah struktur pra teks, yang dianggap sebagai energi puitika teks. Interteks dapat dilakukan antara novel dengan novel, novel dengan puisi, novel dengan mitos. Hubungan yang dimaksudkan tidak semata-mata sebagai persamaan, melainkan juga sebaliknya sebagai pertentangan, baik sebagai parodi maupun negasi. Menurut Barthes (1977: 159), pluralisme makna dalam interteks bukan merupakan akibat ambiguitas, melainkan sebagai hakikat tenunannya. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada teks tanpa interteks (Hutcheon, 1992: vii). Jadi, usaha untuk mencari asal usul teks merupakan kegagalan, sebab dalam interteks tidak ada sumber dan pengaruh. Interteks memungkinkan terjadinya teks plural dan dengan demikian merupakan indikator utama pluralisme budaya. Menurut teori interteks, pembacaan yang berhasil justru apabila didasarkan atas pemahaman-pemahaman terhadap karya-karya terdahulu. Oleh karena itu, secara praktis aktivitas interteks terjadi melalui dua cara, yaitu: a) membaca dua teks atau lebih secara berdampingan pada saat yang sama, b) 10 hanya membaca sebuah teks tetapi dilatarbelakangi oleh teks-teks lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya. Intertekstulitas yang sesungguhnya adalah yang kedua sebab aktivitas inilah yang memungkinkan terjadinya teks jamak, teks tanpa batas. Menurut Riffaterre dalam Ratna (2006: 175), karya sastra yang secara metodologis dibayangkan sebagai sumber interteks disebut hypogram. Dalam suatu aktivitas pembacaan dengan demikian akan terdapat banyak hypogram yang berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas aktivitas pembacaan terdahulu. Hypogram juga merupakan landasan untuk menciptakan karya-karya yang baru, baik dengan cara menerima maupun menolaknya. Melalui antar hubungan tersebutlah teks saling menetralisasikan satu dengan yang lain sehingga masing-masing menampilkan makna yang sesungguhnya. Dengan pandangan yang seperti itu, makna karya sastra selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga ditentukan oleh hubungannya dengan karya-karya yang lain (Ratna, 2006: 174). 2.3 Semantik Semantik ( 意 味 論 ’imiron’) merupakan salah satu cabang Linguistik ( 言 語 学’gengogaku’) yang mengkaji tentang makna. Objek kajian semantik antara lain makna kata (語の意味’go no imi’), relasi makna (語の意味関係’go no imi kankei’) antar satu kata dengan kata yang lainnya, makna frase dalam suatu idiom (句の意味’ku no imi’), dan makna kalimat (文の意味’bun no imi’) (Sutedi, 2003: 103). 1. Makna kata satu persatu (語の個々の意味’go no koko no imi’) Makna setiap kata merupakan salah satu objek kajian semantik, karena komunikasi dengan menggunakan suatu bahasa yang sama seperti bahasa Jepang, baru akan berjalan lancar jika setiap kata yang digunakan oleh pembicara dalam 11 komunikasi tersebut makna atau maksudnya sama dengan yang digunakan oleh lawan bicaranya. 2. Hubungan antar makna kata dengan kata yang lainnya (relasi makna) Hasil relasi makna dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata (語 彙’goi’) berdasarkan kategori tertentu. Misalnya pada verba 「話す’hanasu’ 」 <berbicara>, 「言う’iu’」 <berkata>, 「しゃべる’shaberu’」 <bicara>, dan 「食 べる’taberu’」 <makan>, dapat dikelompokkan ke dalam 「言葉を発する’kotoba wo hassuru’ 」 <bertutur> untuk tiga verba pertama, sedangkan taberu tidak termasuk ke dalamnya. Contoh lainnya, misalnya hubungan makna antara kata 「話 す’hanasu’」 dan 「言う’iu’」, 「高い’takai’」 <tinggi> dan 「低い’hikui’」 <rendah>, 「 動 物 ’doubutsu’ 」 <binatang> dan 「 犬 ’inu’ 」 <anjing> akan berlainan dan perlu diperjelas. Pasangan pertama merupakan sinonim, dan pasangan kedua merupakan antonim, sedangkan pasangan terakhir merupakan hubungan superordinat. 3. Makna frase Dalam bahasa Jepang, ungkapan 「本を読む’hon wo yomu’」 <membaca buku>, 「靴を買う’kutsu wo kau’」 <membeli sepatu>, dan 「腹が立つ’hara ga tatsu’」 <*perut berdiri (=marah)> merupakan suatu frase. Frase “hon wo yomu” dan “kutsu wo kau” dapat dipahami cukup dengan mengetahui makna kata hon, kutsu, kau, dan wo; ditambah dengan pemahaman tentang struktur kalimat bahwa “nomina + wo + verba.” Jadi, frase tersebut dapat dipahami secara leksikalnya (文 12 字通りの意味’mojidoori no imi’). Tetapi, untuk frase “hara ga tatsu,” meskipun seseorang mengetahui makna setiap kata dan strukturnya, belum tentu dapat memahami makna frase tersebut jika tidak mengetahui makna frase secara idiomatikalnya (慣用句的の意味’kanyoukuteki no imi’). Berbeda dengan frase 「足 の洗う’ashi no arau’」yang memiliki dua makna, yaitu secara leksikal (文字通り の意味) adalah <mencuci kaki>, dan juga secara idiomatikal (慣用句的の意味) yakni <berhenti berbuat jahat>. 4. Makna Kalimat Suatu kalimat ditentukan oleh makna setiap kata dan strukturnya. Makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimat tersebut. Suatu kalimat dapat menimbulkan makna ganda yang berbeda. Dengan demikian, selain adanya berbagai macam relasi makna antara suatu kata dengan kata lainnya, dalam kalimat pun terdapat berbagai jenis hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek kajian semantik adalah berupa makna suatu kata dan frase; relasi makna antara beberapa kata; dan makna suatu kalimat (Sutedi, 2003: 103-106). Dalam semantik, terdapat jenis dan perubahan bahasa yang antara lain adalah makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konoatif, dan makna dasar dan makna perluasan. 1. Makna Leksikal dan Makna Gramatikal Makna leksikal dalam bahasa Jepang disebut dengan 「辞書的意味’jishotekiimi’ 」 「 語 彙 的 意 味 ’goiteki-imi’ 」 . Makna leksikal adalah makna kata yang 13 sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indra dan terlepas dari unsur gramatikalnya, atau dapat juga dikatakan sebagai makna asli suatu kata. Misalnya, kata 「猫’neko’」 dan kata 「学校’gakkou’」 memiliki makna leksikal: <kucing> dan <sekolah>. Makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut 「文法的意味 ’bunpoutekiimi’ 」 yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Contohnya partikel 「に’ni’」 secara leksikal tidak jelas maknanya, tetapi akan jelas jika digunakan dalam kalimat 「バンドンに住んでいる’Bandon ni sunde iru’」 <tinggal di Bandung>. 2. Makna Denotatif dan Makna Konotatif Makna denotatif dalam bahasa Jepang disebut 「明示的意味’meijiteki-imi’」 atau 「外延’gaien’」. Makna denotatif adalah makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan dapat dijelaskan dengan analisis komponen makna. Makna konotatif disebut 「暗示的意味’anjiteki-imi’」 atau 「内 包’naihou’」 yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Misalnya, pada kata 「父 ’chichi’」 dan 「親父 ’oyaji’」. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu <ayah>. Makna denotatif dari kedua kata tersebut sama, karena merujuk pada referent yang sama, tetapi nilai rasa berbeda. Kata ‘chichi’ digunakan lebih formal dan lebih halus, sedangkan kata ‘oyaji’ terkesan lebih dekat dan lebih akrab. Makna denotatif 「子供’kodomo’」 adalah <anak>, melahirkan makna konotatif <tidak mau diatur> atau <kurang dipertimbangkan>. 14 3. Makna Dasar dan Makna Perluasan Makna dasar disebut dengan 「基本儀’kihon-gi’」 merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata. Sedangkan makna perluasan 「 転 義 ’ten-gi’ 」 merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar, di antaranya akibat penggunaan secara kiasan (majas/比喩’hiyu’) (Sutedi, 2003: 106108). 2.3.1 Kumo no Ito Secara etimologis, Kumo (蜘蛛) berarti laba-laba, Ito (糸) berarti benang: senar, dawai, tali (Nelson, 2002: 695, 797). Sedangkan no (の) adalah partikel yang berarti punya; milik (Matsuura, 1994: 728). Sehingga Kumo no Ito dapat diartikan sebagai Benang (milik) Laba-Laba atau Benang Laba-Laba. Dalam cerpen karya Akutagawa Ryūnosuke, Kumo no Ito adalah alat yang digunakan oleh Kandata untuk keluar dari neraka (Kelly, 1999). Kumo no Ito diberikan oleh Sang Buddha sebagai imbalan atas perbuatan baik yang pernah dilakukannya, yaitu tidak membunuh laba-laba (Akutagawa, 1918). Sedangkan dalam lirik lagu yang ditulisnya, Mika Nakashima menyatakan bahwa Kumo no Ito mewakili sifat tenggang rasa yang ada pada manusia (Ohno, 2005: 173). 15