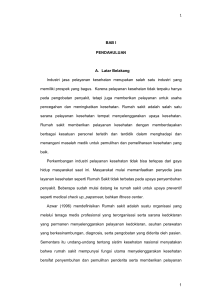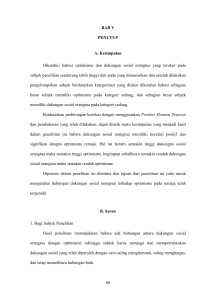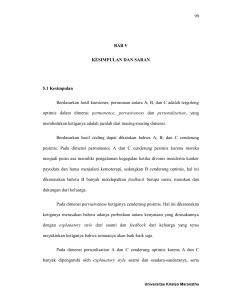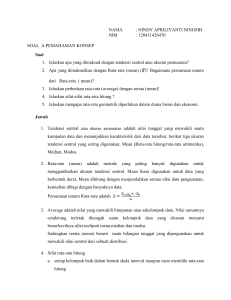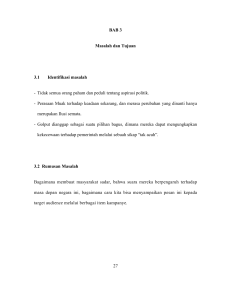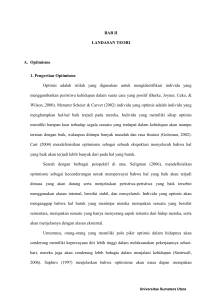BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Bias Optimisme Bias optimisme
advertisement
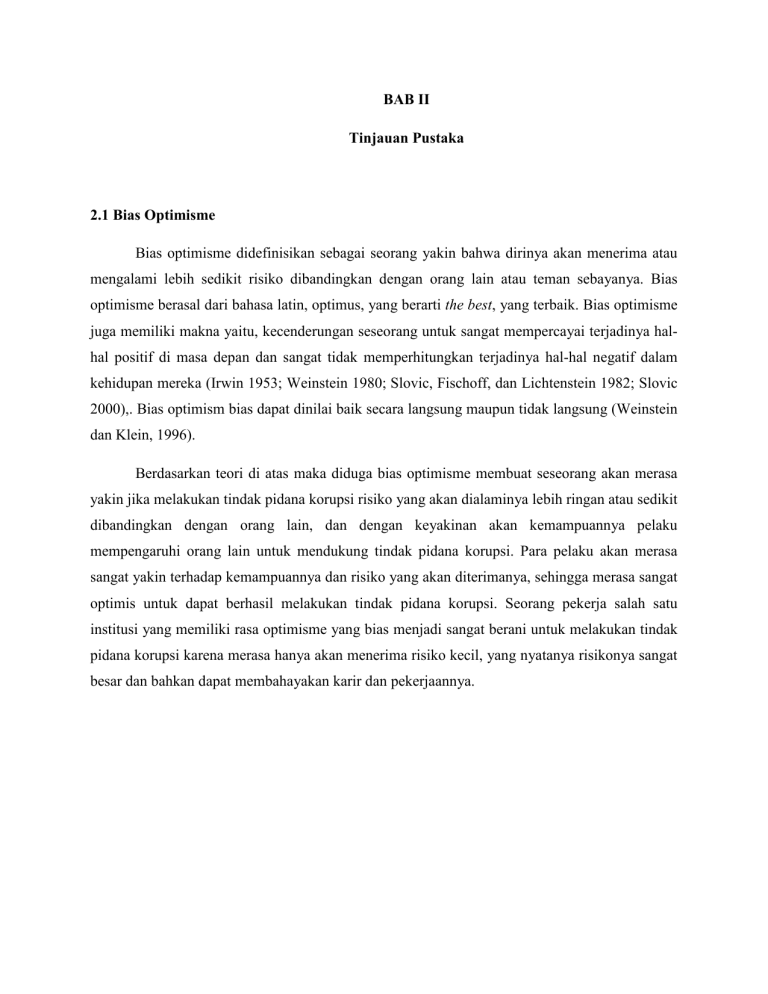
BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Bias Optimisme Bias optimisme didefinisikan sebagai seorang yakin bahwa dirinya akan menerima atau mengalami lebih sedikit risiko dibandingkan dengan orang lain atau teman sebayanya. Bias optimisme berasal dari bahasa latin, optimus, yang berarti the best, yang terbaik. Bias optimisme juga memiliki makna yaitu, kecenderungan seseorang untuk sangat mempercayai terjadinya halhal positif di masa depan dan sangat tidak memperhitungkan terjadinya hal-hal negatif dalam kehidupan mereka (Irwin 1953; Weinstein 1980; Slovic, Fischoff, dan Lichtenstein 1982; Slovic 2000),. Bias optimism bias dapat dinilai baik secara langsung maupun tidak langsung (Weinstein dan Klein, 1996). Berdasarkan teori di atas maka diduga bias optimisme membuat seseorang akan merasa yakin jika melakukan tindak pidana korupsi risiko yang akan dialaminya lebih ringan atau sedikit dibandingkan dengan orang lain, dan dengan keyakinan akan kemampuannya pelaku mempengaruhi orang lain untuk mendukung tindak pidana korupsi. Para pelaku akan merasa sangat yakin terhadap kemampuannya dan risiko yang akan diterimanya, sehingga merasa sangat optimis untuk dapat berhasil melakukan tindak pidana korupsi. Seorang pekerja salah satu institusi yang memiliki rasa optimisme yang bias menjadi sangat berani untuk melakukan tindak pidana korupsi karena merasa hanya akan menerima risiko kecil, yang nyatanya risikonya sangat besar dan bahkan dapat membahayakan karir dan pekerjaannya. 2.1.1 Karakteristik Bias Optimisme Bias optimisme (terlalu optimis) memiliki makna kecenderungan seseorang yang selalu mempercayai hal-hal positif akan terjadi di masa depan tanpa memperhitungkan hal-hal negatif dikehidupannya. Dengan begitu, Bias optimisme memiliki karakteristik sebagai berikut yaitu salah satunya adalah meremehkan, dan meminimalisasi risiko yang mungkin akan muncul (Larsen & Buss, 2005) memiliki sikap dan pemikiran yang meremahkan suatu risiko yang ada terhadap sesuatu hal atau melebih-lebihkan hal-hal tertentu. 2.1.2 Faktor-Faktor Bias Optimisme Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Bias optimisme (terlalu optimis) adalah tingkat optimistis yang berlebihan, pengalaman dan penguasaan diri akan suatu hal, yang mana membuat individu tersebut menjadi Bias optimisme (terlalu optimis). Meremehkan orang lain atau suatu hal dan selalu menganggap akan menerima risiko yang lebih kecil dibanding dengan orang lain atau teman sebayanya, serta selalu menganggap hal-hal positif akan terjadi di masa depan tanpa memperhatikan hal-hal negatif yang ada atau yang akan terjadi (Weinstein, 1996). 2.2 Ilusi Kendali Ilusi Kendali adalah suatu fenomena dimana seorang merasa yakin mampu mengendalikan atau mempengaruhi hasil dari suatu keputusan, padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Menurut (Taylor & Brown, 1998) mengungkapkan bahwa ilusi kendali merupakan persepsi yang tidak realistis atas suatu peristiwa atau suatu hal yang terjadi dimana ketika kita akan melakukan atau sedang melakukan kegiatan sering kali mengembangkan ilusi seolah-olah bisa mengendalikan semua hasil atau mengendalikan orang dan lingkungan yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya disebabkan oleh kesempatan. Dimana ketika seseorang individu merasa seakan-akan ia dapat mengendalikan orang-orang disekitar atau lingkungannya padahal sebenarnya tidak (Langer, 1975). 2.2.1 Karakteristik Ilusi Kendali Karakteristik dari ilusi kendali adalah merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis hal dan akan menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam hal-hal tertentu adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan/keberhasilan (illusion of control). Contoh, penjudi merasa terampil akan satu atau beberapa jenis permainan dan cenderung akan menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangannya karena keahlian yang dimilikinya. Sering kali para penjudi ini tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keahliannya dan mana yang hanya kebetulan semata. 2.2.2 Faktor-Faktor Ilusi Kendali Faktor yang menyebabkan seseorang memiliki sifat ilusi kendali adalah keahlian, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh individu tentang satu atau beberapa jenis hal sehingga individu tersebut dapat mempengaruhi orang lain atau dapat mengendalikan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut adalah di bawah keterampilan dasar dari situasi, seperti pilihan, stimulus atau respon kedekatan, persaingan, dan keterlibatan pasif atau aktif (Langer , 1975). 2.3 Korupsi Korupsi menurut Black’s Law Dictionary (1968) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Korupsi juga didefinisikan dengan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi. Dalam penelitian ini tendensi korupsi didefinisikan secara operasional sebagai rasa malu dan rasa bersalah yang rendah. Pengertian Definisi Korupsi menurut Alatas (1975, hal 13-15) menyebutkan benang merah yang menghubungkan aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Kartini Kartono, (2005) mengatakan bahwa, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi terjadi kerena penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan tugas dan administrasi. 2.3.1 Tendensi Korupsi Tangney (2003) dalam Cohen (et al. 2011) memaparkan bahwa emosi moral memberikan dorongan dan motivasi pada individu untuk melakukan hal yang baik seta menghindari perilaku yang buruk Kaligis (2006), menyatakan korupsi berasal dari bahasa latin yaitu n Corruptio atau Corruptus. Artinya, korupsi adalah suatu perbuatan yang dipolitisir menjadi suatu kejahatan terhadap negara dan masyarakat dalam pengertian seluas-luasnya. Menurut Quah (2003), korupsi adalah perilaku menyimpang dari aturan yang ada karena uang atau keuntungan tertentu. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu korupsi besar, kecil, dan politik (Transparency International). • Korupsi besar merupakan tindakan yang dilakukan pada tingkat tinggi atau pemerintah atau fungsi sentral negara yang memungkinkan pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik. • Korupsi kecil yaitu mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan sehari-hari dipercayakan oleh pejabat publik rendah dan menengah dalam interaksi mereka dengan masyarakat atau publik, yang sering mencoba untuk mengakses barang atau jasa di tempat-tempat seperti rumah sakit, sekolah, departemen kepolisian, dan instansi-instansi lainnya. • Korupsi politik yaitu memanipulasi kebijakan, lembaga, dan aturan prosedur dalam alokasi sumber daya dan pembiayaan oleh para pembuat keputusan politik, yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka, status dari kekayaan. Kaligis (2008), bagi perkara tindak pidana korupsi, selain menggunakan KUHAP, digunakan juga ketentuan-letentuan mengenai hukum acara yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001, menjelaskan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang berisi ancaman mengenai pidana mati bagi pelaku korupsi. Perhatian internasional terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan, penanganan korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa saja. (Ordinary Measure) yaitu oleh aparat hukum dengan senjata undang-undang anti korupsi saja (UU No. 31 Tahun1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Berdasarkan beberapa teori tersebut disimpulkan bahwa tendensi korupsi adalah rendahnya rasa malu dan rasa bersalah dengan melakukan perilaku yang cenderung tidak etis yang berhubungan dengan emosi-moral demi mendapatkan keuntungan tertentu. 2.3.2 Definisi Rasa Malu Dan Rasa Bersalah Perasaan malu dan bersalah terjadi apabila terdapat stress yang muncul sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukan Cohen et al. (2011). Tangney (2003) dalam Cohen et al. (2011) memaparkan bahwa rasa malu dan bersalah merupakan emosi yang terjadi dari kesadaran diri sebagai hasil dari refleksi dan evaluasi diri. Kedua emosi ini juga merupakan pendorong munculnya regulasi diri. Akan tetapi, walau terlihat serupa, perlu diingat bahwa kedua hal ini adalah variabel yang berbeda. Berdasarkan pandangan perilaku diri (self-self) yang dikemukakan oleh Tracy dan Robins (2004) dalam Cohen et al. (2011), perasaan bersalah terjadi ketika seseorang membuat atribusi internal mengenai perilaku spesifik yang tidak sesuai dengan perilakunya sehingga merujuk pada munculnya perasaan negatif mengenai perilaku yang dilakukan. Di sisi lain, rasa malu muncul ketika seseorang membuat atribusi internal yang bersifat stabil dan global mengenai dirinya sehingga merujuk pada perasaan negatif mengenai diri secara global (Cohen et al. 2011). Pandangan lainnya yang turut mengulas perbedaan mengenai rasa malu dan bersalah adalah pandangan umum-pribadi (publicprivate) yang dikemukakan oleh Combs, Campbell, Jackson, dan Smith (2010) dalam Cohen et al. (2011). Pandangan ini melandaskan pandangan antropologi dalam pembahasannya. Menurut pandangan ini, perasaan bersalah diasosiasikan dengan perasaan pribadi bahwa telah melakukan hal yang salah dan bertentangan dengan hati nuraninya. Sebaliknya, perasaan malu merupakan perasaan negatif yang muncul ketika seseorang melakukan kesalahan dan kesalahannya dikemukakan di muka umum (Cohen et al. 2011). 2.3.3 Dimensi Tendensi Korupsi Cohen et al. (2011) menyatakan terdapat beberapa dimensi tendensi korupsi, yaitu: variabel kecenderungan perasaan malu dan bersalah disusun oleh dua dimensi utama, yaitu dimensi kecenderungan rasa malu dan dimensi kecenderungan rasa bersalah Cohen et al. (2011). Setiap dimensi ini memiliki masing-masing 2 indikator. Dimensi kecenderungan perasaan bersalah dapat diindikasikan dengan adanya evaluasi perilaku negatif dan perbaikan diri berkorelasi dapat dijelaksan bahwa individu yang memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku yang negatif akan memiliki kecenderungan untuk melakukan perbaikan diri. Dimensi rasa malu memiliki dua indikator, yaitu menarik diri (withdrawal) dan mengevaluasi diri dari hal negatif (Negative Self Evaluation) berkorelasi secara negatif dengan kedua indikator perasaan bersalah, yakni indikator perbaikan diri (Repair) dan evaluasi perilaku negatif (Negative Self Evaluation). Sebaliknya, indikator menarik diri ditemukan berkorelasi dengan meyerang lawan dan pelanggaran janji serta berkorelasi positif dengan kesalahpahaman. 2.3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Tendensi Korupsi Tangney dan Dearing (2002) dalam Cohen et al. (2011), memaparkan bahwa kepribadian merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kecenderungan munculnya rasa malu dan rasa bersalah. Sebagai contoh, rendahnya kepercayaan diri lebih merujuk pada kecenderungan akan perasaan malu dibandingkan bersalah. Sebalikanya, perasaan empati lebih merujuk pada kecenderungan akan perasaan bersalah dibandingkan malu. (Cohen et al. 2011) 2.3.5 Dampak Dari Tendensi Korupsi Schmader dan Lickel (2006) dalam Cohen et al. (2011) membuktikan bahwa sama seperti rasa bersalah, perasaan malu juga dapat menimbulkan perbaikan perilaku, namun dapat juga menyebabkan seseorang menjadi menarik diri. Selain itu juga terjadi ketidakadilan pada masyarakat, antara individu yang memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi dan dapat menikmati hasil korupsi tersebut dengan individu yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi dan menikmati hasil korupsi. 2.3.6 Karakteristik Korupsi Korupsi di manapun dan kapanpun selalu memiliki karakteristik (ciri khas). Berikut ini adalah beberapa karakteristik Korupsi dari beberapa sumber; Alatas (1999), Kaligis (2008), antara lain: 1. Melibatkan lebih dari satu orang, 2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta, 3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita, 4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya, 5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang, 6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum, 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat, 8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan. 9. suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, 10. penipuan terhadap badan pemerintah, 11. dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, 12. dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, 13. melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, 14. adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, 15. terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, 16. adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan 17. menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. 2.3.7 Faktor-Faktor Korupsi Berikut ini adalah faktor-faktor sosial dan psikologis penyebab terjadinya korupsi dari beberapa sumber menurut Abraham & Pane (2014), Alatas (1999) : 1. Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan huku hanya sebagai make-up politik, bersifat sementara dan sellalu berubah tiap pergantian pemerintahan. 2. Rasa iri dan cemburu, berkaitan dengan kekuatan dan otoritas, mekanisme pertahanan-diri. 3. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan. 4. Dimensi budaya dari ketidakpastian dalam penghindaran moderat (memperkuat) hubungan antara kesulitan ekonomi suatu bangsa dan korupsi, sedangkan power distance dan ketidakpastian penghindaran berhubugan positif dengan korupsi. 5. Langkanya lingkungan yang antikorup : sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. 6. Pemegang kekuasaan pada umumnya mengontrol sumber daya yang diinginkan. Mereka cenderung berpikir dan menemukan bahwa ide-ide mereka dan pandangannya segera disepakati oleh bawahan mereka. 7. Rendahnya pndapatan penyelenggaraan negara. Pedapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 8. Tingkat penyalahgunaan kekuasaan sebagai fungsi dari beberapa konsekuensi aversive dan reinforcing, dimensi konsekuensi (besarnya konsekuensi, kedekatan, keterlambatan dari konsekuensi, frekuensi konsekuensi dan jadwal konsekuensi), serta jumlah individu dalam mengendalikan konsekuensi dapat diterapkan. 9. Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. 10. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah. 11. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap. 12. Budaya permisif/serba membolehkan; tidakmau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak perduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. 13. Gagalnya pendidikan agama dan etika : ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan insttusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain. 2.4 Kerangka Berpikir Tendensi Korupsi Rasa Malu Evaluasi diri negatif Bias Optimisme Menarik diri Rasa Bersalah Evaluasi perilaku negatif Perbaikan diri Ilusi Kendali Dalam penelitian ini penulis akan menceritakan hal-hal yang menyangkut dalam penelitian ini seperti bias optimisme, ilusi kendali, korupsi, rasa bersalah (guilt) dan rasa malu (shame). Kerangka berpikir ini dirumuskan sebagai paradigma peran bias optimisme dan ilusi kendali dalam memprediksi kecenderungan korupsi pada aparatur negara di Jakarta. Korupsi didefinisikan dengan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, yang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai rasa malu dan rasa bersalah yang rendah. Korupsi adalah hal yang sering dikaitkan dengan kekuasan, jabatan, pangkat, dan wewenang namun tidak semua pelaku korupsi adalah orang yang berpangkat tinggi atau memiliki jabatan tinggi. Seperti yang belum lama terjadi di Indonesia, negara kita dihebohkan oleh seorang pegawai ditjen pajak yang bukanlah orang nomor satu dalam institusinya melainkan hanya pegawai biasa, namun dia memiliki wewenang untuk dapat bisa menggelapkan uang atau korupsi. Seorang pegawai biasa seperti Gayus Tambunan diduga merasa sangat yakin jika risiko yang akan dihadapinya sangat kecil dengan tindakan yang dilakukannya (bias optimisme), dan keahliannya memanipulasi data dalam bidang keuangan dan perpajakan membuat dia melakukan tindak pidana korupsi, dan dia juga merasa dapat mengendalikan orang-orang atau lingkungan yang ada disekitarnya padahal kenyataannya boleh jadi demikian (ilusi kendali), serta faktor lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah tingkat rasa bersalah yang rendah (guilt) yang membuat dia merasa seperti tidak melakukan kesalahan apapun. Seseorang yang merasa sangat yakin akan suatu hal tanpa memikirkan dan menganggap remeh risiko yang ada (bias optimisme), kemudian diiringi dengan tingkat rasa bersalah (guilt) yang rendah diduga dapat memprediksi kecenderungan korupsi seseorang. Rasa malu (shame) termasuk ke dalam salah satu faktor yang memprediksi untuk membuat seseorang berkecenderungan melakukan tindak pidana korupsi, dengan segala kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, serta merasa dapat mengendalikan situasi sekelilingnya, dia merasa dapat melakukan korupsi dengan leluasa. Rasa optimis yang sangat tinggi (bias optimisme) dan kemampuan yang mumpuni serta diiringi dengan rendahnya tingkat rasa malu (shame) dapat diduga memprediksi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketika seseorang merasa dirinya akan dapat mengendalikan situasi atau mempengaruhi orang lain, padahal nyatanya tidak demikian (ilusi kendali), kemudian juga diiringi dengan rasa malu (shame) yang rendah diduga dapat membuat orang tersebut berkecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi.