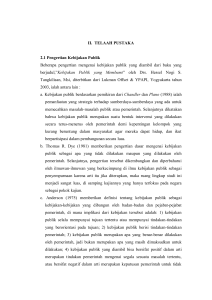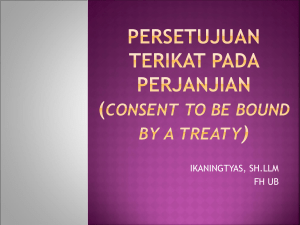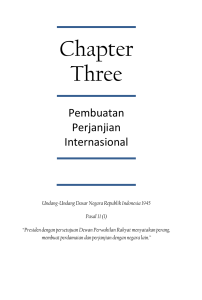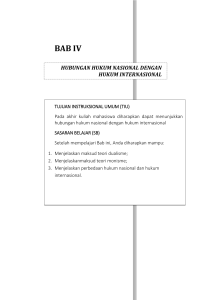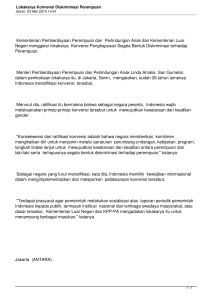52 BAB III PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN
advertisement

BAB III PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Bab ini menjelaskan tentang definisi perjanjian internasional (PI), fungsi dan jenisjenis perjanjian internasional. Dalam bagian pertama dijelaskan mempunyai Konvensi Wina tahun 1969, dengan muatan materi dasar dari perjanjian internasional. Selain itu, dijelaskan tentang ratifikasi internasional dan keterlibatan negara-negara dalam pembentukan perjanjian internasional. Terakhir, bagaimana perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Adapun bab ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami secara komprehensif tentang prinsip-prinsip, teori-teori, dan norma-norma hukum perjanjian internasional, baik dalam cakupan internasional maupun perjanjian internasional dalam konteks tingkat nasional di Indonesia. 1. Istilah Perjanjian Internasional dalam Konvensi Wina 1969 Hubungan internasional yang diperankan negara-negara dan organisasi internasional, tidak akan tercipta secara harmonis jika tidak didukung perjanjian internasional. Suatu instrumen hukum internasional, digunakan sebagai peraturan, pedoman utama dan kaidah normatif bagi pihak-pihak dalam menjalankan hubungan internasional secara baik dan damai. Sebagai sumber hukum utama, Pasal 38 ICJ (International Court of Justice) menegaskan adanya Perjanjian Internasional memberikan kepastian hukum yang saling mengikat bagi para pihak dalam melangsungkan praktek hubungan antara satu atau lebih negara dalam berbagai kepentingan. Baik perjanjian internasional bersifat antara kedua negara (bilateral treaties), oleh tiga negara (trilateral treaties), dan juga perjanjian diselenggarakan oleh banyak negara (multilateral) sama-sama memberi daya ikat karena menimbulkan hak dan kewajiban. 52 Bilateral Treaties, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan secara resmi ataupun tidak resmi dan menyangkut bidang/sektor tertentu yang disepakati bersama diantara dua negara yang melakukan perjanjian. Selain itu, terdapat pula model perjanjian yang melibatkan 3 (tiga) negara peserta dengan disebut Trilateral Treaties. Dalam skala jumlah peserta perjanjian yang lebih banyak dikenal istilah Multilateral Treaties, yaitu suatu perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari 2 (dua) atau 3 (tiga) negara peserta. Umumnya, perjanjian multilateral berisi kesepakatan bersama bersifat regional ataupun atas dasar kepentingan yang sama antar negara-negara. Sumber HI lainnya adalah kebiasaan internasional (international costumary rules), keputusan pengadilan (court decission), prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui negara-negara beradab (general principle of law recognized by civilized countries), dan karya-karya ahli hukum internasional yang memiliki kemasyhuran secara internasional (justice world). Keempat sumber hukum tersebut dapat dijadikan sumber hukum internasional, ketika sumber hukum satu sama lain saling melengkapi. Ketika PI tidak memuat ketentuan hukum tertentu, maka kebiasaan hukum internasional dijadikan sumber berikutnya. Sesungguhnya PI tidak terbatas pada ketiga jenis tersebut di atas, lebih penting dari itu bagaimana suatu PI memiliki kekuatan mengikat yang secara langsung (self-executing) atau tidak langsung (non self-executing) terhadap negara-negara dengan tuntutan prosedur ratifikasi. Self executing treaties adalah suatu perjanjian internasional yang secara langsung dapat mengikat dan diberlakukan dalam suatu negara tanpa memerlukan persetujuan dari parlemen, dengan aklamasi Presiden sudah cukup diberlakukan. Sehingga ratifikasi oleh Parlemen atau Konggres hanya terjadi jika terdapat kasus atau persoalan yang sangat berat. Kondisi seperti ini terjadi di Amerika Serikat, Jerman, dan juga Perancis. Sedangkan non-self executing treaties adalah perjanjian-perjanjian yang hanya akan mengikat jika kesepakatan internasional tersebut telah diratifikasi oleh atau harus mendapatkan persetujuan DPR atau 53 Parlemen. Sifat dari non-self executing treaties dalam pemberlakuan di suatu negara sangat berat. Di satu pihak, setiap negara mewajibkan kesepakatan internasional di ratifikasi melalui persetujuan DPR atau Parlemen. Dan di pihak lain, pengadilan-pengadilan nasional tidak akan menggunakannya sebagai sumber hukum jika tidak/belum diratifikasi menjadi bagian hukum nasional.1 Penerapan PI dalam suatu negara tergantung pada teori-teori penerapan PI yang digunakan negara-negara. Adakalanya negara tersebut menggunakan teori monisme (monism theory) dan juga ada beberapa kelompok negara menggunakan teori dualisme (dualism theory). Namun demikian, penggunaan teori-teori tersebut di atas tidak selalu menjamin suatu negara dapat menerapkan secara seragam. Keabsahan suatu PI memang sangat tergantung selain kepada terpenuhi atau tidak suatu persyaratan menurut ketentuan Komisi Hukum Internasional (International Law Commission), juga penting menjadi pertimbangan bagaimana suatu kesepakatan disetujui oleh banyak pihak. Konsekuensinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiabn secara internasional dapat timbul dan mengikat negara-negara secara berangsung-angsur. Negara-negara sebagai peserta dalam suatu PI umumnya memiliki kesamaan status hukum (equality) sebagai negara-negara berdaulat. Status kesamaan hukum (equality before the law) mutlak dalam PI, sebab hanya Negara-negara berdaulat penuhlah yang memiliki hak bicara dan hak suara. Namun, tidaklah mengherankan jika terdapat perbedaan kemampuan atau kapasitas dalam menjalankan berbagai kewajiban internasional. Untuk itu, dalam kondisi-kondisi tertentu suatu negara dapat menanggalkan sebagian ketentuan hukum yang terdapat dalam PI. Suatu pengecualian yang diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional mengingat kemampuan negara berbeda-beda. Reservasi adalah metode yang paling sering digunakan negara-negara ketika ketentuan PI tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum nasional, 1 Wisnu Aryo Dewanto, Perjanjian Internasional Self-Executing Dan Non-Self-Executing Di Pengadilan Nasional, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011, Hlm: 49. 54 khususnya ketentuan hukum pidana, hukum tata negara, dan juga hukum hak asasi manusia suatu negara. Dalam bagian tulisan ini, perlu dikemukakan tentang bagaimana keberadaan sumber hukum Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaty, 1969) yang digunakan dalam hubungan internasional antara negara-negara? Kedua, apakah fungsi dan kegunaan PI dalam hukum hubungan internasional? Ketiga, bagaimana daya ikat perjanjian internasional terhadap negara-negara baik karena putusan yang mengikat secara terbatas (closed agreement) atau daya ikat terhadap negara secara lebih terbuka dan meluas (open agreement)? Keempat, bagaimana kontribusi negara-negara dalam proses pembuatan hukum perjanjian internasional? Kelima, bagaimana praktek dan metode negara-negara dalam memberlakukan hukum perjanjian internasional dalam sisten hukum nasional masing, termasuk dalam praktek di Indonesia? Definisi Perjanjian Internasional dan Fungsinya Definisi perjanjian internasional di kalangan publik, khususnya di Indonesia sangat bervariasi. Secara populer, perjanjian internasional memiliki arti semua bentuk perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional. Di kalangan publik, tidak dibedakan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional, karena keduanya dipahami sebagai perjanjian internasional tanpa melihat subjek, karakter hubungan hukum, serta rezim hukum yang menguasainya.2 Menurut Pasal 2 ayat (1) butir (a) Konvensi Wina 1969, definisi PI adalah: “An International Agreement concluded between States (and International Organizations) in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”. Artinya, “suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis 2 Domus Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 19. 55 dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya”. Suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: (i) antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya”. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, definisi PI adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.3 Berdasarkan beberapa definisi PI di atas, maka suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai PI apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: 1. Perjanjian harus memiliki karakter internasional, baik secara formal (pembentukannya) maupun materiil (substansinya). 2. Perjanjian harus dibuat oleh para pihak yang merupakan subjek hukum internasional, yakni negara dan/atau organisasi internasional, sehingga tidak dibenarkan jika perjanjian dibuat oleh pihak yang bukan merupakan subjek hukum internasional. 3. Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan memiliki daya ikat yang kuat bagi seluruh pihak yang andil dalam perjanjian. 3 Pasal 1 poin (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 56 Dengan demikian, perjanjian internasional yaitu suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, negara-negara sebagai subyek hukum internasional atau obyek yang jelas, dibuat secara tertulis dan mengikat secara sebagian besar negara-negara. Adapun fungsi PI dalam hubungan internasional, sebagai berikut: Pertama, PI merupakan suatu tanda bagi suatu negara yang telah menempatkan dirinya sebagai negara moderen yang beradab. Menggunakan perundingan dan perjanjian, negara-negara akan berusaha untuk menahan diri dari tindakan penggunaan kekeran di dalam penyelesaian sengketa. Sebab, dalam merumuskan perjanjian internasional, pihak-pihak yang mewakili negara hendaknya menggunakan mekanisme lobi, negosiasi, dan pertimbangan untung dan rugi bagi kepentingan nasional (national interest). Kedua, sebagai pedoman tertulis yang mengandung kepastian hukum bagi kedua negara atau lebih untuk dijadikan rujukan dalam melakukan hubungan internasional dan juga sebagai arah dari pembangunan nasional negara masing-masing. Misalnya, berdirinya badan PBB terkait dengan bantuan program pembangunan (United Nations for Development Program - UNDP), bagi negara-negara yang sedang membangun dan mengembangkan demokrasi. Ketiga, sebagai sertifikat atau bukti bahwa negara-negara tersebut terikat berbagai kesepakatan internasional, sehingga jika dikemudian hari terdapat sengketa maka model penyelesaian sudah jelas ada rujukannya di luar atau di dalam pengadilan.4 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional Sebagai suatu instrumen hukum hubungan internasional, perjanjian internasional tidak sedikit istilah yang digunakan untuk memperlihatkan adanya transaksi atau perikatan dalam tatanan internasional. Istilah tersebut antara lain, perjanjian atau perundingan (Treaty), kesepakatan (agreement), perjanjian (Tractaat), piagam (Charter), Deklarasi 4 Dicari dalam J. O’Brien dan Malcolm Shaw, International Law, dalam Malcolm D. Evans. 57 (Declaration), Anggaran Dasar (Statuta), Kesepakatan (Covenant), Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Protokol Tambahan (Protocol), dan lain-lainya.5 Dasar yang harus diyakinkan kebenarannya adalah bahwa suatu PI menurut Konvensi Wina, harus memiliki lima unsur utama: (1) Adanya pihak-pihak negara-negara sebagai subyek hukum (states as international legal subject), (2) Menyetujui suatu kesepakatan atau obyek tertentu; (3) Diatur oleh hukum internasional didasarkan Komisi Hukum Internasiomal, (governed by International Law Commission); (4) didasarkan pada perjanjian secara tertulis (made in written form); dan (5) memiliki daya ikat yang kuat (enter into binding force). Dengan kata lain, syarat sahnya perjanjian internasional memiliki daya ikat yang efektif, jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan kata lain, bahwa Konvensi Wina 1969 hanya mengatur berbagai perjanjian internasional yang diikuti hanya oleh negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Suatu negara yang memiliki kedaulatan penuh (full state sovereignity), adalah negara-negara yang memiliki kewenangan penuh, baik untuk urusan dalam negeri (domestic affairs), maupun untuk urusan luar negeri (foreign affairs) tanpa ada campur tangan dari kekuatan negara luar. Sedangkan pengaturan PI yang diterapkan oleh subyek hukum non-negara, dapat disandarkan kepada hukum kebiasaan internaasional, dimana organisasi internasional dan lainnya diakui memiliki status yang sederjat seperti kedudukan negara. Selain terdapat perjanjian yang diikuti oleh subyek hukum negara, organisasi internasional, baik berbentuk organisasi antara negara (inter-governmental organization) atau organisasi swadaya masyarakat (non-governmental organization). Vatikan atau Tahta Suci di Vatikan Roma, Organisasi Gerakan Pembebasan (Liberation Movement Organization), dan juga organisasiComment [AVK1]: - #tolong di cek, bagaimana organisasi-organisasi noninternasional harus mengikuti prosedur dan mekanisme pembuatan perjanjian internasional. organisasi profesi setingkat dunia lainnya.6 Dalam Protokol Tambahan 5 6 Lihat dalam Pasal berapa istilah-istilah tersebut diatur oleh Konvensi Wina 1969. Lihat subyek hukum internasional dalam J. G. Starke, An Introduction To International Law, Sidney: Butterworth, 1988. 58 Berlaku dan Mengikatnya Perjanjian Internasional Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 (1) Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian internasional mulai dapat diberlakukan bergantung pada dua hal, yaitu: Ketentuan perjanjian internasional itu sendiri; atau, apa yang telah disetujui oleh negara peserta. Pada umumnya, pemberlakuan suatu perjanjian dapat dilihat pada bagian klausula formal (klausula final) yang biasanya terletak dalam pasal-pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial (dispositive provision) perjanjian internasional tersebut. Misalnya ketentuan yang menjelaskan pada salah satu pasalnya bahwa perjanjian ini berlaku segera setelah penandatanganan. Sehingga sejak penandatanganan dilakukan oleh negara peserta, maka perjanjian yang ditandatangani secara otomatis berlaku bagi negara yang bersangkutan. Dari praktek-praktek penerapan PI, daya ikatnya tergantung selain pada jumlah negara-negara yang menyetujui dan meratifikasi. Misalnya, Statuta Roma yang disetujui di San Remo tahun 1998, baru kemudian dapat diimplementasikan sejak setelah Comment [AVK2]: #cek kepastiannya pemberlakuan Statuta Roma tahun 2004 atau 2005? enam puluh negara meratifikasinya dalam sistem hukum nasionalnya. Adapun mengenai mengikatnya perjanjian, suatu perjanjian internasional baru mulai dapat mengikat bagi negara peserta perjanjian tersebut bergantung pula pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu sendiri. Jika perjanjian tersebut tidak mensyaratkan adanya ratifikasi, maka negara peserta akan terikat secara hukum sejak penandatanganan perjanjian itu. Jika perjanjian tersebut mensyaratkan ratifikasi, maka negara peserta baru akan terikat secara hukum sejak diratifikasinya perjanjian itu. Sebaliknya, masih saja dilematis pemberlakuan PI, seperti Statuta Roma. Sebab, selain negara-negara ada yang dapat menolak pemberlakuannya, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Juga Israel dan termasuk Indonesia. Di pihak negara-negara yang menolak umumnya, selain dapat berdampak pada sistem hukum pidana nasionalnya. Juga negara-negara penolak umumnya tidak menghendaki pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu dipersoalkan oleh Komisi HAM Internasional dan juga tentunya Dewan Keamanan PBB. 59 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu PI dapat berakibat timbulnya hukum lain, atau dapat menuntut suatu negara atas pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu bahwa perjanjian yang dilanggar adalah sah telah berlaku dan perjanjian itu pula telah mengikat secara hukum bagi negara yang melanggar perjanjian tersebut.7 Kesamaan status negara-negara, sebagai negara pihak atau negara yang sama-sama meratifikasi statuta Konvensi menjadi dasar mutlak kebolehan kedua negara melakukan klaim dan pertanggungjawaban hukum. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional Setidaknya ada tiga jenis PI yang selama ini dijadikan pegangan dalam mempelajari kerjasama internasional. Pertama, PI dilakukan oleh dua negara (Bilateral Treaties) untuk mengikatkan diri ke dalam suatu obyek perjanjian bersifat publik (ketertiban, perdamaian, kepentingan politik, militer, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang kebudayaan lainnya), atau juga obyeknya keperdataan, bersifat mengikat tetapi terbatas hanya kepada dua pihak saya (closed agreement). Di satu pihak, negara yang menyelenggarakan PI secara bilateral wajib mematuhi dan menghormatinya (Pacta Sunt Servanda). Karena itu, pihak-pihak yang berada di luar kesepakatan tersebut tidak merasa ada kewajiban untuk mematuhinya. Sebab, praktek perjanjian hanya memihak terbatas pada negara-negara yang menyepakati saja. Namun, tidak berarti negara-negara lain dapat mencampurinya. Kewajiban untuk menghormati dan untuk tidak ikut intervensi, menjadi batasan moralitas/kode etik internasional. Dalam suatu hubungan antara kedua negara, Bilateral treaties tidak mudah dilakukan mengingat kedua sistem hukum mereka berbeda-beda. Di satu pihak, terdapat negaranegara menganut sistem common law, di mana negara-negara terikat dengan sistem hukumnya, dan kebiasaan hukum, putusan-putusan hakim dijadikan dasar dalam 7 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, April 2010, hlm. 32-34. 60 menentukan sikap dan penerima terhadap PI ke dalam hukum nasional. Doktrin Precedent, atau putusan-putusan hakim nasional dan internasional merupakan rujukan utama bagi hakim-hakim di pengadilan. Misalnya, Inggris, dan Amerika Serikat tergolong negara-negara penganut sistem common law yang lebih mengutamakan hukum kebiasaan internasional. Namun, tidak berarti negara-negara tersebut tidak memiliki sumber hukum tertulis, termasuk dalam hal ini Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Amerika sebagai negara yang menempatkan PI sebagai sumber hukum nasional yang statusnya sejajar dengan konstitusi Pasal 6 UUD AS; The international treaties shall be supreme law of the land. Di pihak lain, negara-negara penganut sistem Kontinental adalah negara-negara yang lebih mengutamakan sumber hukum tertulis, atau perundang-undangan (legisme). Hampir kebanyakan negara-negara model kedua ini menempatkan hukum tertulis lebih utama dijadikan sumber hukum oleh para penegak hukumnya. Karena itu, PI dapat digunakan sebagai sumber hukum nasional, bilamana pemerintah negara tersebut telah meratifikasinya ke dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum negara-negara kontinental atau civil law, seperti Belanda dan negara-negara sejenisnya seperti Indonesia, umumnya pemberlakuan PI lebih sulit dan bahkan sangat birokratis. Pertama, setiap PI wajib di ratifikasi oleh lembaga Parlemen, Konggres, Senat atau DPR. Kedua, pengadilan-pengadilan tidak akan menempatkan PI sebagai sumber hukum nasional jika PI belum diratifikasi sebagai bagian dari hukum nasional yang berbentuk Undang-Undang. Trilateral Treaties, yaitu ketiga negara meningkatkan diri untuk menyepakati pada suatu obyek tertentu untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, timbul hak dan kewajiban yang mengikat negara-negara. Misalnya perjanjian ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dengan Singapura terhadap keberadaan Selat Malaka sebagai suatu wilayah perairan yang bersentuhan ketiga negara tersebut. Dalam kenyataan Selat Malaka sebagai suatu selat perairan yang sangat sibuk dengan lalu lintas kapal pengangkut barangbarang berbagai negara. 61 Tidak mengherankan jika pelanggaran dan kejahatan lintas negara (Transnational Organized Crimes), seperti pembajakan, penyelundupan, transaksi senjata gelap dan perdagangan manusia acapkali dilakukan di Selat Malaka tersebut. Untuk mencegah dan menindak pelaku pelanggaran dan kejahatan tersebut, ketiga negara merasa terpanggil untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi pengguna Selat tersebut. Ketiga negara memiliki jurisdiksi masing-masing untuk melakukan tindakan kedaulatan terhadap pelaku kejahatan yang terjadi di selat Malaka, sehingga mereka dapat meminta pertanggung jawaban hukum kepada pelaku kejahatan tersebut yang terjadi di wilayah Selat Malaka, sebagai tempat kejadian (locus delicti). Namun demikian, kedua model PI tersebut di atas, mengisyarakatkan adanya sifat Treaty of Contract. Perjanjian ini tidak secara langsung sebagai sumber hukum internasional. PI dapat digunakan sebagai sumber hukum yang mengikat hanya kepada pihak-pihak yang menandatangani dan juga terbatas hanya pada hukum yang khusus. Karena itu, Treaty of Contract dapat saja menjadi sumber hukum internasional sepanjang mendasarkan pada proses perubahan dari kebiasaan internasional. Sekalipun peristiwa dari perjanjian yang memiliki daya ikat yang sama sebagai akibat dari hukum kebiasaan internasional. Misalnya, setiap perjanjian internasional bersifat bilateral dalam hal tindakan diplomasi negara, hukumhukum negara, putusan-putusan pengadilan dan praktek organisasi internasional hanya akan mengikat lebih luas jika telah mengalami proses yang saling diakui. Di satu pihak, negara-negara yang terlibat dalam suatu perjanjian bilateral maupun trilateral treaties terikat untuk menghormati dan mematuhi asas hukum perjanjian. Misalnya, asas contractual international transaction consensus. Sebaliknya, negara-negara di luar pihak juga wajib menghormatinya sepanjang negara-negara tersebut terlibat dalam pengambilan manfaat dari obyek perjanjian tersebut. Misalnya, perjanjian bilateral antara Inggris dan Amerika Serikat. Negara-negara yang lewat selat tersebut wajib tunduk pada peraturanperaturan perairan yang disepakati oleh kedua negara. 62 Ketiga, Multilateral Treaties yaitu suatu perjanjian atau perundingan yang diikuti banyak negara untuk membuat kesepakatan terhadap obyek tertentu, dengan prosesdur dan mekanisme menurut ketentuan Komisi Hukum Internasional, dilakukan secara tertulis dimana setiap utusan negara-negara memiliki hak lobi, negosiasi (berunding) untuk dan atas kepentingan memperjuangkan kepentingan negara-negara di tingkat internasonal. Setiap delegasi negara memiliki hak untuk memohon penjelasan klarifikasi (clarification), dan menentukan tentang kepastian dan keakuratan kata dan kalimat (authenticity), untuk menyetujui (approve), menerima (accept) dan menandatangani (signature) perjanjian tersebut. PI bersifat multilateral dapat mengikat negara-negara sepanjang negara-negara tersebut selain turut menyetujui perundingan, juga memiliki i’tikad baik (good faith) untuk menerima dan menjadikan PI tersebut bagian dari hukum nasionalnya masing-masing.8 Misalnya, pada tahun 1998 negara-negara dan segenap organisasi internasional, bertemu di San Remo, Italia untuk menyetujui lahirnya perjanjian Statuta Roma 1998, tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional bersifat permanen. Selama ini, dari tahun 1946 telah ada peradilan pidana, namun peradilan tersebut sifatnya sementara atau ad-hoc. Sebagaimana telah digelar dalam Kasus Nuremberg Genocide Convention 1946 terhadap penjahat genosida NAZI di Jerman, yang juga diikuti oleh Konvensi Tokyo 1948 atas kejahatan perang yang dilakukan tentara Jepang. Perbedaan yang mendasar antara Bilateral dan Trilateral Treaties dengan Multilateral adalah bukan sekedar jumlah subyek hukumnya negara-negara yang ikut begitu banyak. Namun, karena multilateral treaties memiliki sifat hukum law making treaties (perjanjian membuat hukum). Suatu perjanjian internasional yang membuat hukum, dimaknai sebagai suatu kesepakatan yang memiliki daya ikat hukum yang terbuka dan luas, dapat dipaksakan baik kepada negara-negara yang ikut menandatangani (third parties) atau sebagai negara pihak, atau negara-negara yang tidak hadir karena memang negara tersebut belum berdiri 8 Diambil dari Starke – Eddy Pratomo 63 atau belum memiliki kedaulatan penuh atau negara-negara tersebut tidak mau menyetujui. Tetapi bagi negara-negara yang tidak memiliki kedaulatan penuh maka negara-negara tersebut dapat menundukan diri untuk mematuhi perjanjian tersebut (adhesion). Misalnya, Piagam Pendirian PBB di San-Fransisco, 1945 telah mengikat semua negara, sebagai anggota sah dan wajib mematuhi maksud dan tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara yang tidak ikut PI, selain ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia (world peace), ketertiban dunia (world order), juga wajib berupaya mencegah atau mengendalikan diri untuk tidak menggunakan kekerasan militer dalam suatu penyelesaian persengketaan.9 Adanya metode negara-negara yang tidak turut penyelesaian sengketa internasional, selain menggunakan model diplomasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan pencarian fakta, juga cara-cara damai dapat dilakukan melalui peradilan internasional dan arbitrase internasional. Comment [AVK3]: tolong ditambahkan materi batalnya, berakhirnya PI. Kebolehan negara mengundurkan diri dan juga penafsiran dalam amandemen PI (dilihat Pasalnya). # 3.2. Keterlibatan Negara-negara dalam Pembuatan Perjanjian Internasional Hakikat PI dalam konteks perkembangan hukum internasional kontemporer menunjukan perkembangan luar biasa. Bukan sekedar jumlahnya PI hampir puluhan ribu, melainkan juga telah bersinggungan dengan semakin toleransinya negara-negara dalam mengakomodir hukum-hukum kebiasaan internasional untuk disejajarkan dengan status PI. Karena itu, seberapa jauh negara-negara terlibat dalam suatu pembentukan PI tergantung kepada kemampuan negara-negara tersebut dalam mengelola dan merawat hubungan internasional, baik antara sesama negara maupun antara negara sebagai anggota dari Comment [AVK4]: #cek tulisan Theodore Coulombis organisasi internasional. 9 Pasal 3 ayat (2) Piagam PBB. 64 Dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969, suatu negara yang akan menghadiri pembuatan PI harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, bahwa wakil suatu negara memiliki surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negaranya, Presiden atau Perdana Menteri, dengan surat kepercayaan (Letter of Credential), yang memberikan kewenangan penuh kepada delegasi suatu negara (Full Powers). Sebagaimana ditegaskan oleh Konvensi Wina. Di Amerika Serikat, Sekretaris Negara bersama Kementerian Luar Negeri memiliki kewenangan untuk menentukan serta menerbitkan Surat Kepercayaan tersebut. Kedua, yang dapat mewakili negara ke dalam pembuatan PI, antara lain Kepalakepala negara (Heads of State), Kepala pemerintahan (Heads of Government), Menteri Luar Negeri (Minister for Foreign Affairs), Kepala-kepala negara, Menteri suatu negara tidak memerlukan surat kepercayaan (letter of credence). Dengan demikian, letter of credence diwajibkan bagi utusan diplomasi. Kepala perwakilan diplomatik (Heads of diplomatic missions), dan perwakilan-perwakilan yang disahkan pejabat berwenang untuk menjadi delegasi dalam PI, baik yang diselenggarakan negara-negara, maupun organisasi internasional. Ketiga, adalah delegasi melakukan pendaftaran (registration) dan menyerahkan surat kepercayaan tersebut, sebagai peserta dalam PI, dengan kewenangan untuk melakukan perundingan atau adu tawar (negotiation), penjelasan (clarification), kepastian dan kesaksian (authencity), persetujuan (approval), dan penandatanganan (signature). Semestinya, utusanutusan negara-negara menjadi terikat (enter to be bound) sejak penandatanganan. Namun, ternyata daya ikat perjanjian internasional memerlukan persyaratan atau tahapan pemberlakuan melalui ratifikasi. 3.3. Praktek Ratifikasi di Berbagai Negara Ratifikasi merupakan suatu prosedur dan mekanisme hukum terkait dengan pemberlakukan PI ke dalam hukum nasional, sehingga dapat menjadi sumber hukum untuk dipergunakan oleh hakim-hakim suatu pengadilan negaranya masing-masing. Dalam 65 Comment [AVK5]: #jelaskan menggunakan footnote istilah dalam lighter kuning tersebut prakteknya, ratifikasi dibedakan ke dalam beberapa tahapan, berdasarkan kepada landasan teoritis dan filosofis suatu negara. Monisme dan dualisme merupakan dua teori yang paling masyhur digunakan untuk melihat seberapa jauh negara-negara berdaulat dapat mematahkan perjanjian internasional, dan diimplementasikan dalam kasus-kasus yang dihadapinya, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Penting untuk dicatat, bahwa perbedaan isu hukum, antara hukum publik dengan hukum ekonomi merupakan dua ranah hukum berdimensi internasional. Dalam konteks hukum ekonomi internasional, negara-negara adidaya dengan mudah menyetujui berbagai transaksi atau perjanjian internasional. Bahkan lebih dari itu, negaranegara adidaya dapat memaksa negara sekutunya untuk menyetujui perjanjian-perjanjian multilateral. Misalnya, berbagai perjanjian multilateral, termasuk APEC, perdagangan bebas dan WTO, tergolong PI multilateral yang mudah disepakati dan diimplementasikan secara global. Sebab kepentingan ekonomi nasional negara-negara peserta tidak luput dari perdagangan internasional, termasuk praktek impor dan ekspor barang, jasa dan teknologi informatika lainnya. Di pihak lain, isu-isu hukum publik, keamanan dan pertahanan, kejahatan internasional, dan juga pelanggaran HAM berat acapkali menjadi persoalan yang sangat sulit mendapatkan dukungan dari negara-negara adikuasa. Kelima negara anggota tetap DK PBB seringkali menjadi contoh paradoks atau tidak konsisten dalam mengimplementasikan perjanjian internasional. Konvensi internasional tentang Terorisme tahun 2003, termasuk PI yang secara kebijakan tergolong sangat cepat didukung untuk diimplementasikan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara Barat lainnya, merasa terancam oleh gerakan teroris dari negara-negara ketiga, khususnya negara-negara Muslim. Namun, berbeda halnya dengan PI seperti Statuta Roma 1998, negara-negara besar tidak peduli mengingat ancaman besar terhadap kedaulatan negaranya tidak dapat dihindarkan. Kasus Pemerintah Amerika Serikat terhadap Suku Indian, kasus Pemerintah Inggris di Australia terhadap Suku Aborigin, juga China terhadap bangsa Tibet. 66 Ratifikasi PI di Negara Penganut Monisme Negara-negara penganut teori monisme tampak jauh lebih sederhana dalam melakukan ratifikasi, sehingga sekali suatu negara telah menyepakati PI, suatu negara dapat memberlakukannya di tingkat nasional. Hal ini terjadi karena negara-negara penganut paham monisme, menempatkan hukum internasional, atau PI dan hukum nasional merupakan kedua sistem hukum yang satu sama lain tidak terpisahkan (inseparable part of law) satu sama lain. Ada tiga alasan mengapa negara-negara penganut monisme lebih sederhana dalam melakukan ratifikasi. Pertama, konstitusi atau hukum dasar negara-negara tersebut menempatkan PI sebagai sumber hukum yang sejajar dengan konstitusinya. Di Amerika Serikat, dengan jelas diatur dalam Pasal 6, bahwa PI menjadi sumber hukum yang tinggi di negerinya, International Treaty... shall be the supreme law of the land. Meskipun Jerman tidak menggunakan sistem Pemerintahan Presidensil, dalam konteks pemberlakuan PI hampir sama dengan AS, yaitu menempatkan PI sebagai sumber hukum nasionalnya yang setara dengan konstitusi. Alasan kedua, negara-negara penganut monisme menempatkan PI dan urusan hubungan luar negeri, sebagai urusan kekuasaan eksekutif (executive affairs). Dalam pembelakuannya PI cukup dengan suatu keputusan Presiden (President Decree) atau Perdana Menteri. Self executing treaties, suatu perjanjian internasional yang dengan sendirinya dapat diberlakukan dengan penguatan atau pengesahan dari Kepala Pemerintahan atau Presiden. Akibatnya, daya ikat PI di tingkat hukum nasional lebih cepat oleh karena model ratifikasi tidak membutuhkan persetujuan dari parlemen (parliament endorcement). Namun, dalam kondisi tertentu, seperti di AS, ada juga suatu PI yang memerlukan suatu persetujuan dari Kongres, apabila berkaitan dengan hal-hal yang penting dan dalam penerapannya akan berdampak pada situasi nasional. Tentu saja, persoalan 67 pertahanan dan keamanan (security and defence) dipandang sebagai persoalan sensitif baik ke dalam negaranya maupun dampak keluar negeri.10 Alasan ketiga, hakim-hakim di negara-negara penganut teori monisme secara teknis dapat dengan mudah menjadikan PI sebagai sumber hukum dalam putusannya, mengingat sejak ratifikasi hanya memerlukan pengesahan dari Presiden. Penganut teori monisme, pemerintah suatu negara sangat jelas menempatkan urusan luar negeri (foreign affairs) sebagai urusan eksekutif, sehingga hampir sebagian besar kebijakan luar negeri dibuat oleh Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Dalam hal suatu PI tersebut kontradiksi dengan kebiasaan internasional, maka hakimhakim dengan sendirinya akan mengutamakan hukum kebiasaan internasional, sebagai pelaksanaan dari asas Jus Cogen. Karena itu, ketika terdapat PI yang bertentangan dengan Jus Cogen, maka dengan sendirinya hakim-hakim dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung akan membatalkan peraturan hukum bersumber PI tersebut. Sebab, Jus Cogen tergolong sumber hukum kebiasaan internasional yang memiliki derajat tertinggi yang tidak dapat dikalahkan oleh hasil kesepakatan PI, termasuk yang bersifat multilateral.11 Ratifikasi PI di Negara Penganut Teori Dualisme Kondisi ratifikasi di negara-negara penganut teori dualisme memang berbeda mengingat prosedur dan mekanisme agak berbelit-belit. Hakim-hakim di negara-negara tersebut hampir cenderung untuk mengutamakan sumber hukum nasionalnya. Mengapa di negara-negara penganut teori dualisme praktek ratifikasi tidak semudah praktek di negaranegara penganut monisme. Pertama, negara-negara penganut teori dualisme, beranggapan bahwa perjanjian internasional (PI) dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum terpisah. Ajaran kedaulatan hukum negara secara nasional lebih diutamakan untuk dijadikan sumber hukum 10 11 Op.Cit, Wisnu Aryo Dewantoro. Yudha Bakti, Disertasi 68 utama (prima facie). Mereka memandang bahwa PI hanya dapat dijadikan bagian dari sistem hukum nasional manakala telah dilakukan suatu proses ratifikasi yang prosedural oleh parlemen atau hakim-hakim di pengadilan. Dengan kata lain, kompleksitas implementasi PI di dalam negara penganut teori dualisme menunjukan urusan luar negeri tidak sekedar ikhwal kewenangan eksekutif, melainkan juga kewenangan parlemen atau DPR. Sebagai salah satu contoh di negara federal di Australia, ratifikasi PI memerlukan persetujuan dari Parlemen, karena urusan luar negeri termasuk kewenangan pengawasan parlemen. seberapa jauh urusan luar negeri membuktikan kepentingan rakyat sangat tergantung pada wakil-wakil rakyat di Parlemen. Sifat dan daya ikat PI dalam negara-negara penganut dualisme adalah non-self executing treaties, yaitu PI tidak dengan sendirinya dapat diimplementasikan mengingat memerlukan adanya persetujuan dari Parlemen atau DPR. Untuk mengimplementasikan PI di negara-negara tersebut memang agak sulit.12 Kedua, persoalan PI bukan sekedar urusan Presiden, atau Perdana Menteri melainkan juga urusan dari wakil-wakil rakyat. Setiap upaya untuk memberlakukan PI menuntut adanya suatu pengesahan dari anggota parlemen DPR. Model ratifikasi demikian ini, tentu tidak saja terbatas pada PI bersifat Multilateral saja, akan tetapi berlaku pada PI bersifat bilateral dan Trilateral. Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura menyepakati perjanjian ekstradisi, yaitu saling tukar-menukar penjahat dari kedua negara. Syarat utamanya adalah pelanggaran atau kejahatan tersebut harus sama tergolong kejahatan yang juga dilarang oleh kedua negara (double criminality). Meskipun demikian, perjanjian ekstradisi batal ditindak lanjuti oleh karena beberapa alasan, salah satunya, perjanjian ekstradisi yang telah disepakati memerlukan pengakuan dari hakim-hakim. 13 Konsekuensi dari PI bukan sekedar eksekutif menuntut adanya suatu dukungan dan pengesahan dari parlemen. Prosedur ratifikasi menjadi birokratif mengingat mekanisme 12 13 Wisnu, Eddy, atau Maurize Jawahir Thontowi, Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY, Yogyakarta: Leutika, 2009, Hlm: 225. 69 terkadang tidak mudah ditempuh. Hal ini mengingat prosedur dan mekanisme ratifikasi pertama perlu diajukan oleh beberapa kementerian yang terkait. Misalnya, Menteri Luar Negeri (Minister of Foreign Affairs) dan Menteri Kehakiman (Minister of Justice) mempersiapkan untuk mengusut tersebut negara. Meskipun dalam ratifikasi tidak perlu adanya pengesahan setiap pasal-pasal, karena setelah diterjemahkan ke dalam bahasa nasional masing-masing, anggota-anggota DPR hanya menyetujui pemberlakuan PI tersebut secara keseluruhan. Terkecuali, terdapat adanya persyaratan (reservasi), maka beberapa pasal dapat dianulir. Misalnya, ketika Pemerintahan Indonesia melakukan ratifikasi terhadap HAM, maka konsep kejahatan perang (war of crimes), kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), dan tindakan agresi (the act of aggression) tidak diberlakukan di Indonesia. Ketiga, dalam praktek ratifikasi PI ke dalam hukum nasional di negara-negara penganut teori dualisme memang tidak mudah. Selain hakim-hakim dalam hal menemukan hukum baru ketika dalam hukum nasional tidak diaturnya, maka hakim sangat tergatung kepada pengesahan dari anggota parlemen. Hal ini juga menjadi lebih rigid ketika hakimhakim di negara-negara sistem kontinental tidak memberlakukan doktrin precedent. Meski putusan-putusan hakim di masa lalu, yang mengandung kebenaran dan keadilan sekalipun, tetap saja hakim tidak mudah untuk menjadi putusan-putusan tersebut sebagai sumber hukum yang patut dipertimbangkan. Karena itu, dalam hal ada tidaknya pertentangan antara PI dengan hukum kebiasaan internasional, maka hakim-hakim di negara-negara tersebut umumnya merujuk pada hukum nasional, dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang bertahap, yakni penafsiran kebahasaan (linguistic interpretation), penafsiran sejarah (historical interpretation), penafsiran sosiologis dan antropologis (sociologist and anthropologist interpretation). Perjanjian Internasional di Indonesia Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. 70 Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional. Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subyek hukum internasional lain. Dasar hukum pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sejatinya undang-undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam praktiknya di Indonesia, bentuk pengesahan suatu Perjanjian Internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu: 1. Ratifikasi (ratification) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian; 2. Aksesi (accesion) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian; 3. Penerimaan (acceptance); dan 4. Penyetujuan (approval) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia sebelum disahkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijabarkan dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturnya. 71 Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia dapat dilakukan dengan undangundang atau Keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang- undang, apabila berkenaan dengan:14 1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 3. kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5. pembentukan kaidah hukum baru; dan 6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Adapun pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan Keputusan Presiden. Dalam hal pengesahan perjanjian internasional melalui Keputusan Presiden, maka Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.15 A. Istilah-istilah dalam Perjanjian Internasional 1. Agreed minutes, yaitu risalah yang disepakati. 2. Agreement (persetujuan), yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. 3. Charter yaitu istilah yang dapat dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif Misal Atlantic Charter. 4. Convention (konvensi), yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). 5. Covenant yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa Bangsa) 6. Declaration (Deklarasi), yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dan batang tubuh ketentuan traktat dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan 14 15 Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 72 lampiran pada traktat atau konvensi. Deklarasi sebagai persetujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting. 7. Exchange notes (Pertukaran nota), yaitu metode yang tidak resmi tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka. 8. Final act (Ketentuan penutup), yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang serta Inasalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 9. General act (Ketentuan Umum), yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Misalnya, LBB (Liga Bangsa Bangsa) menggunakan ketentuan umum mengenai arbritasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928. 10. Letter of intens yaitu nota kesepakatan. 11. Modus vivendi, yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanent, terinci dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi. 12. Negotiation (perundingan), merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu. Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full powers). 13. Proses verbal, yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulankesimpulan konferensi diplomatic atau catatan-catatan suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi. 14. Protocol (protokol), yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara, mengatur masalah-masalah tambahan seperti ketentuan tambahan sebuah perjanjian. 15. Ratification (ratifikasi), yaitu persetujuan terhadap rencana perjanjian internasional agar menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara peserta perjanjian. 16. Signature (penandatanaganan), yaitu penandatanganan hasil perundingan yang dituangkan dalam naskah perundingan yang dilakukan wakil-wakil negara peserta yang 73 hadir. Dalam perjanjian bilateral, penandatanganan dilakukan oleh kedua wakil negara yang telah melakukan perundingan sehingga penerimaan hasil perundingan secara bulat dan penuh, mutlak sangat diperlukan oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, dalam perjanjian multilateral penandatanganan naskah hasil perundingan dapat dilakukan jika disetujui 2/3 dan semua peserta yang hadir dalam perundingan, kecuali jika ditentukan lain. Namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya. 17. Statute (piagam); yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Piagam itu dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi seperti piagam kebebasan transit. 18. Summary record, yaitu catatan singkat, ikhtisar. 19. Treaty (traktat), yaitu perjanjian formal yang merupakan persetujuan dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. B. Pejabat Berwenang dalam Perjanjian Internasional Sebuah perjanjian internasional tidak dapat membebankan sebuah kewajiban atau memberikan hak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak tersebut. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional penegrtian pernyataan tersebut terangkum dalam sebuah prinsip pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Prinsip tersebut tercantum dalam VCLT 1969 Pasal 34 , “A treaty does not create either obligations or rights for a third state without its consent”. Dalam praktek pernyataan persetujuan keterikatan terhadap aturan sebuah perjanjian internasional tersebut tidak bisa dilakukan secara begitu saja oleh sebuah negara. Untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian internasional sebuah negara akan mengirimkan representasinya yang memiliki wewenang untuk bernegosiasi, bernegosiasi dan melakukan ratifikasi. Pada setiap negara,pihak yang berwenang membuat perjanjian internasional ditentukan oleh konstitusi masing-masing. Dilihat dari pembagian wewenang melalui 74 amanah konstitusi maka pejabat yang berwenang mewakili negara dalam pembuatan perjanjian internasional dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu: Kewenangan mutlak eksekutif : perjanjian internasional terpusat pada kepala negara. Kewenangan mutlak legislative : kewenangan pembuat perjanjian internasional pada lembaga legislative. Pasal 7 VCLT menyatakan representatif negara dalam perundingan perjanjian internasional dapat dikategorikan: Kepala Negara, Kepala Pemrintahan dan Menteri Luar Negeri dengan kewenangan mewakili negara dan mengkatkan diri terhadap perjanjian internasional. Kepala Misi Dimplomatik, untuk tujuan mengadopsi teks perjanjian antara negara yang mengakui dan negara yang diakui. Perwakilan negara yang diakreditasi untuk konferensi internasional atau organisasi internasional (atau salah satu instansinya) dengan tujuan untuk mengadopsi teks perjanjian dalam pertemuan tersebut. Di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk membuat perjanjianinternasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat. C. Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Inggris dan Amerika Serikat Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa siapa yang memiliki wewenang untuk mewakili negara dalam negosiasi pembentukan perjanjian internasional tergantung dalam perangkat pengaturan konstitusi di masing-masing negara. Di Inggris, hal yang berkaitanm dengan proses negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi perjanjian internasional menjadi hak prerogative menteri luar negeri. Sedangkan mengenai siapa yang berhak mewakili negar adalam permbuatan perjanjian internasional di Amerika Serikat, tercantum dalam dalam Pasal II, Ayat 2 konstitusi negara menyatakan bahwa Presiden 75 memili kuasa wewenang oleh dan dengan nasehat dan persetujuan dari senat untuk membuat perjanjian internasional, dengan dukungan persetujuan minimal dua pertiga dari jumlah Senator. D. Tahapan Pemberlakuan Perjanjian Internasional Setelah melalui tahapan proses ratifikasi, maka tahapan selanjutnya dalam memberlakukan perjanjian internasional menjadi berbeda-beda di setiap negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh teori berlakunya hukum internasional yang di anut oleh negara. Terdapat dua aliran mengenai hukum internasional yang berkembang dan umum dipraktekan negara-negara berdaulat, aliran tersebut adalah mereka yang memberdakan hukum nasional dengan hukum internasional dan mereka yang menganggap hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu keasatuan hukum. Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini: 1. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional; 2. Subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukum internasional adalah negara; 3. Struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional. 4. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional. 76 Maka sebagai akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena dua perangkat hukum ini tidak saja berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain tetapi juga terlepas antara satu dengan yang lainnya. Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah renvoi. Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis. Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional. Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional. Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain beranggapan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini disebut dengan paham monisme dengan primat hukum internasional. Hal ini dimungkinkan dalam teori monisme. Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri. Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut: 1. tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negaranegara; 77 2. dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Pada kenyataannya kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara. Indonesia sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2000, proses pengesahan perjanjian internasional diatur pada BAB III (Pasal 9 – 14) tentang Pengesahan Perjanjian Internasional. Menurut ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2000, semua pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah RI juga dapat membuat perjanjian internasional melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Materi perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, c. kedaulatan atau hak berdaulat negara, d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup, e. pembentukan kaidah hukum baru, f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. E. Tugas Delegasi Negara Tugas dan fungsi dari seorang perwakilan/delegasi negara dalam proses perumusan perjanjian internasional terkandung dalan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 yaitu: 78 a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional. c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Perwakilan diplomatik memiliki fungsi Negosiasi mendiskusikan dan mendialogkan (negotiation), Representasi memerankan sebagai pimpinan negara (representation), Perlindungan berkewajiban untuk melindungi (protection), Pelaporan sebagai kewenangan membuat (report function), dan Hubungan persahabatan (friendly relations) F. Reservasi dan Alasanya Perumusan Reservasi (pasal 19 Konvensi wina) Suatu Negara pada waktu melakukan penandatangan, ratifikasi, menerima, mengesahkan atau aksesi terhadap suatu perjanjian boleh mengajukan reservasi kecuali jika : a. Reservasi itu dilarang oleh perjanjian b. Perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa hanya reservasi-reservasi tertentu yang tidak termasuk reservasi yang dipersoalkan, boleh diajukan Dalam hal tidak termasuk di dalam sub paragraph (a) dan (b), maka reservasi itu bertentangan dengan tujuan dan maksud perjanjian. Pasal 20 Konvensi Wina 1969 mengatur reservasi yg diizinkan oleh perjanjian tidak memerlukan penerimaan oleh negara peserta lainnya. Jika penerapan perjanjian secara keseluruhan sebagai syarat utama untuk terikat oleh perjanjian maka reservasi memerlukan penerimaan seluruh peserta perjanjian. Jika perjanjian merupakan instrumen konstitusi organisasi internasional maka reservasi memerlukan penerimaan dari organ kompeten organisasi tersebut. 79 Reservasi dapat dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu dengan tidak memerlukan persetujuan negara peserta lainnya dan melalui persetujuan dari :Semua negara peserta,Organ yang kompeten dari organisasi internasional yang bersangkutan. Akibat hukum Pensyaratan / reservasi adalah : merubah ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian, memodifikasi akibat hukum ketentuan tertentu dalam hal pelaksanaannya oleh negara yang melakukan ratifikasi. Prosedur reservasi Reservasi, pernyataan menerima reservasi, menolak reservasi harus diformulasikan dalam dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada negara peserta lain dan negara yang berhak menjadi peserta Jika reservasi diformulasikan pada saat penandatangan maka harus diformalkan pd saat meratifikasi atau mengikutsertai perjanjian. Pembatalan reservasi, dan penolakan reservasi dapat setiap saat dilakukan dan tidak memerlukan penerimaan dari negara anggota atau organisasi anggota. Pembatalan penolakan reservasi dapat dilakukan setiap saat dan berlaku efektif setelah pemberitahuan tertulis di terima oleh peserta perjanjian lainnya. Sedangkan pembatalan penolakan reservasi dapat efektif setelah pemebritahuan tertulis diterima oleh negara pengaju reservasi G. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Internasional Untuk mencegah negara mengelak dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dalam sebuah perjanjian internasional, Pasal 42(1) VCLT menyatakan bahwa ,” sahnya sebuah perjanjian atau persetujuan sebuah negara untuk tunduk pada aturan dalam sebuah perjanjian internasional hanya dapat diberhentikan melalui aturan yang tertuang dalam konvensi ini”. Tujuan pembuatan pasal tersebut adalah untuk mencegah adanya tindakan meremehkan integritas perjanjian internasional dengan alasan yang tidak masuk akal. Dalam peraturan lebih lanjut Pasal 44(1) VCLT secara tegas menyatakan bahwa negara hanya diperbolehkan untuk menangguhkan atau menarik pemberlakuan perjanjian internasional secara keseluruhan dan bukan pada bagian tertentu saja terkecuali apabila terdapat peraturan dalam perjanjian tersebut yang mengatur sebaliknya. Demikian pula dalam Pasal 80 44(3) VCLT yang hanya memperbolehkan penangguhan atau menarik pemberlakuan sebuah perjanjian pada bagian/aturan tertentu apabila berkenaan dengan : (a) Pasal yang dimaksud merupakan pasal tunggal yang tidak berkaitan dengan pasalpasal yang lain dalam perjanjian tersebut dalam penerapanya. (b) Telah diatur dalam perjanjian tersebut bahwa pengakuan terhadap pasal yang dimaksud bukanlah hal yang perlu dilakukan/wajib sehingga tidak membutuhkan keterikatan kepada seluruh peserta perjanjian. (c) Keberlangsungan penerapan sisa pasal-pasal dalam perjanjian itidak akan diragukan/terpengaruh. Dalam konsep pembatalan sebuah perjanjian internasional acapkali yang menjadi kendala adalah keabsahan sebuah perjanjian internasional ditinjau dari segi konstitusi sebuah negara peserta perjanjian. Di beberapa kasus terdapat negara yang dalam konstitusinya menjelaskan bahwa pelaksana eksekutif sebuah negara tidak dapat melakukan kewajiban tertentu yang dibebankan sebuah perjanjian internasional tanpa seijin parlemen atau penguasa legislatif. Hal tersebut menyebabkan negara melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional yang dibebankan oleh konstitusinya. Berbagai macam pendapat ahli berkembang menanggapi isu tersebut , namun terdapat sebuah pendapat yang menyatakan bahwa sebuah perjanjina internasional akan secara otomatis batal demi hukum apabila dalam aturan konstitusi negara peserta perjanjian internasional tersebut melarang pemberlakuanya. Alasan dasar pendapat tersebut adalah ketika perwakilan negara (penguasa Eksekutif) bertindak dalam ranah wewenang yang diberikan oleh konstitusi,yang mana koridor kebebasan bertindak dibatasi oleh aturanaturan yang tercantum dalam konstitusi. Pendapat ahli yang lainya menyebutkan bahwa perjanjian internasional masih dapat berlaku, namun keabsahanya tidak lagi terjaga apabila rekanan negara peserta perjanjian internasional tersebut mengetahui bahwa negara tersebut telah melanggar peraturan konstitusinya dengan tunduk pada perjanjian internasional yang dipermasalahkan. Pendekatan yang kedua dapat dilihat dalam Pasal 46 VCLT yang menyatakan bahwa: 81 1. Negara tidak dapat menarik kembali fakta ketika negara tersebut telah mengekspresikan keinginanya untuk tunduk terhdap sebuah perjanjian internasional telah melanggar aturan hukum di dalam negerinya terkait kompetensi untuk mengikatkan diri terhdap sebuah perjanjian dan akan berakibat batalnya pernyataan untuk mengikatkan diri tersebut, kecuali pelangaran tersebut merupakan perwujudan dan dianggap terkait dengan hukum nasional yang sifatnya fundamentalis. 2. Sebuah pelanggaran akan menjadi nyata apabila pelanggaran tersebut akan menjadi bukti obyektif bagi setiap negara yang melakukan hal serupa apabila dibandingkan dengan praktek pada umunya dan prinsip iktikad baik. Sedangkan dalam berakhirnya perjanjian internasional terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan, yang paling umum adalah berakhirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian terlebih dahulu. Pada umumnya dalam penyusunan sebuah perjanjian internasional akan mencantumkan kapan mulai berlakunya perjanjian dan pilihan apakah perjanjina akan berakhir atau dapat diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 54(1)(b) VCLT mengakui adanya praktek pengakhiran perjanjian internasional dengan kesepakatan para pihak dengan adanya musyawarah/konsultasi terlebih dahulu. Apabila didalam sebuah perjanjian tidak terdapat pasal yang menjelaskan mengenai masa berakhirnya perjanjian maka negara peserta perjanjian dapat merujuk pada aturan Pasal 56 VCLT yang memberikan hak kepada negara peserta perjanjian internasional untuk menarik atau mengakhiri keikutsertaanya dalam perjanjian yang dapat dilakukan engan memberikan sebuah pemberitahuan tidak kurang dari 12 bulan dari keinginan untuk menarik diri atau mengakhiri perjanjian. Aturan serupa juga dapat dijumpai pada Pasal 58 VCLT yang memperbolehkan dua atu lebih negara peserta dapat menunda pemberlakuan perjanjian selama penangguhan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hak ,kewajiban dan tidak melanggar atau bertentangan dengan isi dari ketentuan dalam perjanjian. Pelanggaran isi perjanjian dapat pula menyebabkan negara mengajukan berakhirnya perjanjian atau pemberian ganti rugi. Dalam beberapa perdebatan banyak dibahas mengenai kategori pelanggaran berat dan pelanggaran ringan terhadap perjanjian dimana pelanggaran 82 berat dapat menjadi alasan pengajuan berakhirnya perjanjian. Pasal 60(1) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap materi/isi pokok perjanjian oleh salah satu pihak perjanjian bilateral dapat membuat pihak yang lain mengajukan pembatalan atau penangguhan pelaksanaan perjanjian baik sebagian maupun secara keseluruhan. Berbeda dengan perjanjian bilateral, dalam perjanjian multilateral proses pengajuan pengakhiran perjanjian jauh lebih rumit karena melibatkan banyak pihak. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian multilateral melakukan pelanggaran maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalah atau pemutusan perjanjian karena pelanggaran yang dilakukan akan memberikan ketidakadilan bagi pihak yang lain. Pasal 60(2) VCLT mengatur 3 hal yang dapat dilakukan dalam pembatalan/pengakhiran perjanjian multilateral, yang pertama adalah bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap materi/isi pokok dalam sebuah perjanjian multilateral, maka peserta perjanjian yang lain dengan suara bulat boleh mengajukan penangguhan atau penghentian sebagian/keseluruhan perjanjian tersebut,baik terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ataupun terhadap semua pihak peserta perjanjian secara keseluruhan. Selain itu pihak yang menderita kerugian secara langsung dapat mengajukan penangguhan/mengakhiri perjanjian multilateral antara negara tersebut dengan negara yang melakukan pelanggaran saja, dan yang terkahir pihak yang tidak secara langsung dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan salah satu peserta perjanjian dapat mengajukan penangguhan/mengakhiri keikutsertaan dalam perjanjian apabila pelanggaran tersebut telah mempengaruhi proses berjalanya hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Berakhirnya perjanjian internasional juga dapat dilakukan ketika kewajiban yang dibebankan oleh perjanjian tidak mungkin untuk dilakukan karena obyek yang bersangkutan hilang/rusak secara permanen (Pasal 61 VCLT). Perjanjian internasional juga dapat berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang terjadi sejak pembentukan perjanjian, sehingga objek yang ingin dicapai oleh perjanjian menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Pasal 62 VCLT membolehkan pembatalan perjanjian yang diakibatkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelelah perjanjian dibuat dan diterapkan. 83 H. Penafsiran, Amandemen, dan Modifikasi Perjanjian Internasional Konvensi Wina 1969 mengenai interpretasi perjanjian internasional diatur dalam tiga pasal saja, yaitu pasal 31, 32 dan 34, tetapi meliputi masalah yang sangat luas sekali, oleh karena itu memerlukan pembahasan tersendiri. Dalam bagian ini hanya membahas yang pokok-pokok saja sekedar mengetahui isi ketentuan Konvensi Wina 1969. naskah suatu perjanjian dapat diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih sesuai atau sejalandengan kehendak semula daripada pembuat perjanjian. Pasal 31 Konvensi Wina menetapkan ketentuan umum tentang penafsiran yang terdiri dari empat ayat, yaitu : 1. Suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan iktikad baik menurut arti kata-katanya yang biasa dalam rangka obyek dan maksudnya. 2. Kerangka maksud penafsiran harus mencakup sebagai tambahan atau teks, kecuali naskah mukadimah dan lampiran yang mencakup setiap persetujuan dan naskah yang ada hubungannya dengan penetapan perjanjian tersebut. 3. Harus juga diperhatikan setiap persetujuan dan praktek penerapan yangmenyusul pembentukan perjanjian, serta setiap aturan hukum internasional yang relevan. 4. Arti yang khusus dapat ditetapkan bagi suatu hal bila dikehendaki demikian. Pasal 31 ini memiliki dasarnya pada ayat yang pertama, yaitu pada Iktikad baik (good faith) dan arti yang biasa dari kata-kata (ordinary meaning of term). Dalam Hukum Internasional dikenal tiga school of thoughts” aliran/approach mengenai interpretasi, yang pertama adalah Aliran yang berpegang pada kehendak para pembuat perjanjian itu. Aliran ini menggunakan secara luas “preparatory work/travaux preparatories” pekerjaan pendahuluan dan bukti-bukti yang menggambarkan kehendak para pihak. Aliran Textual school, yang menghendaki bahwa kepada naskah perjanjian hendaknya diberikan arti yang lazim dan terbaca dari kata-kata itu (ordinary and apparent meaning of the words). Jadi unsur pentingnya adalah naskah perjanjian itu dan kemudian kehendak para pihak pembuat perjanjian serta obyek dan tujuan dari perjanjian itu. Aliaran Teleogical thought, cara penafsiran ini menitik beratkan pada interpretasi dengan melihat obyek dan tujuan umum dari perjanjian itu yang berdiri sendiri terlepas dari kehendak semula pembuat perjanjian itu. Dengan demikian naskah suatu perjanjian dapat 84 diartikan secara luas dan ditambah pengertiannya selama masih sesuai atau sejalan dengan kehendak semula daripada pembuat perjanjian. International law comission (ILC) yang menyusun rancangan Wina 1969, memberikan pengertian Amademen sebagai perubahan terbatas maupun perubahan umum dari suatu perjanjian yang dalam hal ini berlaku untuk semua peserta. Amademen sebagai mana dimaksud dalam uraian tersebut, hanyalah satu dari beberapa bentukperubahan perjanjian yangdikenal dalam hukum Internasional. Perubhanperjanjian itu sendiri terjadi bilamana diadakan penambahan ketentuan-ketentuan asli, sementara perjanjian itu sendiri tetap berlaku. Karena amandemen merupakan suatu bentuk perubahan dari suatu perjanjian, maka bentuk-bentuk lainya adalah modifikasi. Konvensi wina 1969 membedakan secara tegas antara amademen dan modifikasi serta mengaturnya dalam ketentuan yang berbeda. Modifikasi adalah perubahan perjanjian yang diadakan oleh dua atau lebih peserta akan tetapi tidak semua pserta dari suatu perjanjian multilateral. Perubahan atau pembuatan amandemen terhadap perjanjian itu tergantung dari kesepakatan para pihak. Mengenai perubahan atau amandemen terhadap perjanjian multilateral ini tidak mengharuskan adanya prakarsa dari semua Negara pihak dari perjanjian tersebut. Namun setiap usul perubahan baik di dalam bentuk amandemen atau revisi haruslah diberitahukan kepada semua Negara pihak dan semuanya berhak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan tentang kelanjutan usul perubahan tersebut. Setiap Negara akan mempunyai hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang yang akan diambil mengenai usul tersebut dan berpartisipasi dalam perundingan dan persetujuan mengenai perubahan perjanjian tersebut. 85