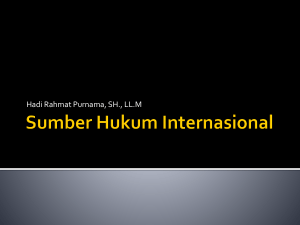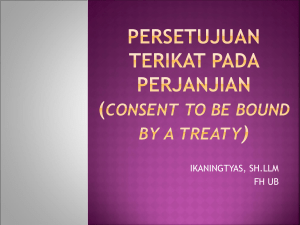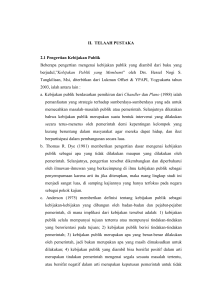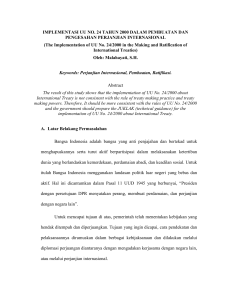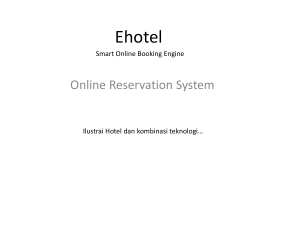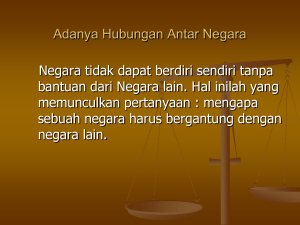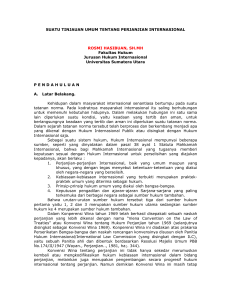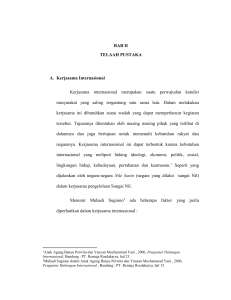Chapter Three - Repository UNIMAL
advertisement

Chapter Three Pembuatan Perjanjian Internasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 11 (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.” Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 29 A. Kewenangan Membuat Perjanjian Internasional dan Surat Kuasa (Full Powers) Konstitusi masing-masing negara umumnya mengatur dengan jelas badan yang berwenang untuk melakukan pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal ini, dikenal ada tiga bentuk kewenangan dalam membuat perjanjian internasional, yaitu : (a) Kewenangan Mutlak Eksklusif; yaitu kewenangan yang biasanya terdapat pada system monokrasi dengan kekuasaan terfokus kepada kepala negara sebaga kepala eksekutif. Sistem ini dipakai pada sistem monarki absolut namun sudah sangat jarang terjadi; (b) Kewenangan Mutlak Legislatif; yaitu kewenangan yang biasanya berkembang pada saat lembaga legislative suatu negara memegang seluruh kekuasaan termasuk kekuasaan pembuatan perjanjian. (c) Pembagian Kewenangan antara Eksekutif dengan Legislatif; yaitu sistem yang dianut oleh banyak negara di dunia, dimana kewenangan untuk membuat perjanjian berada di tangan lembaga eksekutif, namun untuk melaksanakannya lembaga eksekutif harus meminta persetujuan dari pihak legislative. Ini merupakan pembagian kerjasama antara rejim presidential dengan rejim parlementer. Pada umumnya, negara bagian dari suatu negara federal tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional. Namun, terkadang ada juga yang diberikan wewenang oleh konstitusi federal negara yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian internasional. Artinya, wewenang umum untuk mengadakan perjanjian internasional (treaty making power) dalam suatu negara federal lazimnya berada pada pemerintah federal. 30 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional UUDNRI 1945 Pasal 11 telah menetapkan bahwa yang menjadi pemegang kekuasaan membuat perjanjian internasional adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Kemudian dalam peraturan operasional untuk melaksanakan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomorr. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jelas bahwa dalam konteks pembuatan perjanjian internasional pemegang treaty making power di Indonesia adalah Presiden yang dapat memberikan wewenangnya kepada Menteri Luar Negeri. Atas dasar KEPPRES No. 102/2001, ditentukan bahwa Departemen Luar Negeri merupakan bagian dari pemerintah negara dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok DEPLU adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan di luar negeri. Dalam melakukan hubungan luar negeri, Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian yang telah menjadi hukum positif internasional dan dasar hukum pembuatan perjanjian internasional. Konvensi ini menentukan bahwa yang dapat mewakili negara dalam pembuatan perjanjian adalah: a. Kepala Negara (Presiden) atau Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri); b. Menteri Luar Negeri; c. Kepala Perwakilan atau Misi Diplomatik; d. Pejabat Pemerintah yang diberi kuasa (full power) oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri. Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 31 Selanjutnya dalam pelaksanaan treaty making power, Presiden dibantu oleh Menteri Luar Negeri, yang selanjutnya Deplu c.q. Dit. Perjanjian Polkamwil dan Dit. Perjanjian Ekososbud tidak saja bertugas menyiapkan naskah perjanjian, tetapi juga merundingkan dengan pihak-pihak lainnya dalam perjanjian. Dalam Konvensi Wina disebutkan bahwa surat kuasa adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam berunding, menerima, atau membuktikan keaslian naskah suatu perjanjian, menyatkaan persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian atua melaksanakan perbuatan lainnya sehubungan dengan suatu perjanjian. Dalam praktik internasional, utusan-utusan suatu negara ke suatu konferensi internasional biasanya dilengkapi dengan surat kuasa, walaupun tidak mutlak diperlukan. Pasal 7 (1) (b) Konvensi Wina menyatakan bahwa wakil dari suatu negara dalam suatu perundingan dapat dibebaskan dari surat kuasa kalau memang demikian praktik dari negara yang bersangkutan. Bahkan utusan yang tidak mempunyai surat kuasa juga dapat mengikuti suatu perjanjian asal saja dikonfirmasikan kemudian oleh pemerintahnya. Surat kuasa bukanlah satu-satunya dokumen yang diperlukan oleh suatu utusan untuk mewakili negaranya dalam sebuah konferensi bilateral maupun multilateral. Surat kepercayaan (credential) adalah surat yang wajib diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Badan-Badan Subsider lainnya seminggu sebelum sidang dimulai.21 PBB akan dapat menentukan delegasi mana yang benar-benar mewakili suatu negara, terutama bila negara tersebut memiliki pemerintahan tandingan. Walaupun demikian, Mochtar Kusumaatmadja memiliki pendapat bahwa apabila seseorang yang dikirim menghadiri konferensi 21 Lihat Pasal 27 Rules of Procedure of the General Assembly. 32 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional tidak membawa surat kuasa penuh, dan hanya disampaikan melalui email ataupun telephone saja kepada ketua atau sekretaris konferensi, secara hukum tindakan tersebut dibenarkan asalkan kemudian disahkan atau dikirimkan surat kuasa penuh oleh negara yang bersangkutan. Tanpa pengesahan tersebut, maka semua tindakan yang dilakukan oleh perwakilan tersebut tidak memiliki kekuatan yang sah (batal demi hukum).22 B. Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional a. Tahap Penjajakan Pada tahap ini para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi atau lembaga pemerintahan (negara) di Indonesia ataupun inisiatif dari calon mitra. Penjajakan bertujuan untuk bertukar pikiran tentang berbagai masalah yang akan dituangkan dalam perjanjian dimaksud. b. Tahap Perundingan Kebutuhan suatu negara untuk berhubungan dengan negaranegara lain untuk membicarakan dan memecahkan berbagai persoalan yang timbul diantara mereka menimbulkan kehendak negara-negara tersebut untuk mengadakan perundingan. Tahap perundingan merupakan suatu upaya yang ditempuh oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui dalam tahap penjajakan. Tahap ini juga berfungsi sebagai wahana memperjelas pemahaman setiap pihak tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional. Setelah para pihak mendapatkan persetujuan untuk mengadakan perundingan, maka masing-masing pihak akan 22 Mochtar Kusumaatmadja, Ibid. Hlm. 43-44. Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 33 menunjuk organ-organ yang berwenang untuk menghadiri perundingan tersebut. Jika Kepala Negara tidak dapat menghadiri perundingan, maka akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri, atau wakil diplomatiknya, dan apabila tidak maka akan ditunjuk wakil-wakil berkuasa penuh yang mendapat surat kuasa untuk mengadakan perundingan menandatangani atau menyetujui teks perjanjian dalam konferensi tersebut.23 Pada tahap perundingan ini, beberapa draft atau rancangan perjanjian ditawarkan dan dibahas, sehingga muncul usul, amandemen, pro maupun kontra. c. Tahap Perumusan Naskah Rumusan naskah adalah hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi perjanjian internasional. Pada tahap ini diberikan tanda paraf terhadap materi yang telah disetujui, dan dihasilkan juga Agreed Minutes, atau Minutes of Meeting, atau Records of Discussion atau Summary Records yang berisi hal-hal yang sudah disepakati, belum disepakati, serta agenda perundingan berikutnya. Apabila suatu perjanjian merupakan perjanjian bilateral dari dua negara yang mempunyai bahasa yang sama, hal ini tidak akan menimbulkan kesulitan. Masing-masing pihak pada perjanjian tersebut membuat naskah atas kertasnya sendiri dengan mendahulukan nama negaranya setiap nama negara para pihak muncul. Begitu juga dengan letak tanda tangan, di sebelah kiri ataupun di bagian atas secara berurutan. Sedangkan bila perjanjian tersebut dibuat oleh lebih dari dua negara atau perjanjian multilateral dapat dibuat dengan memilih salah satu bahasa yang disetujui oleh semua para pihak dalam perjanjian. Sebuah naskah perjanjian juga biasanya terdiri dari unsur-unsur formil, yaitu mukaddimah, batang tubuh, klausula penutup, dan annex. Dalam mukaddimah terkandung unsur-unsur filosofis, 23 Lihat Pasal 7 (1) dan (2) Konvensi Wina 1969. 34 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional politis dan sosiologis sebagai dasar dibentuknya perjanjian tersebut. Khusus bagi negara-negara Islam, mukaddimah biasanya dimulai dengan puji-pujian kepada Tuhan. d. Tahap Penerimaan Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut sebagai penerimaan yang ditandai dengan pemberian tanda paraf pada naskah perjanjian oleh masing-masing ketua delegasi. Terhadap perjanjian multilateral, proses penerimaan biasanya merupakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. Penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text) dalam suatu perjanjian bilateral ataupun multilateral dengan anggota yang masih terbatas, akan lebih mudah dilakukan dengan suara bulat. Namun untuk perjanjian yang diikuti oleh banyak negara seperti PBB, pengambilan keputusan dengan suara bulat sangat sulit dilakukan, sehingga para pihak menentukan sendiri proses penentuan keputusan mereka. Konvensi Wina menentukan bahwa penerimaan dapat dilakukan dengan suara bulat ataupun dengan dua pertiga dari peserta yang hadir dan memberikan suara.24 Kesaksian naskah perjanjian (authentication of the text) adalah suatu perbuatan dalam proses pembuatan perjanjian yang mengakhiri secara pasti naskah yang telah dibuat. Bila suatu naskah sudah disahkan, maka naskah ini tidak boleh diubah lagi. Menurut Pasal 10 Konvensi Wina, pengesahan naskah suatu perjanjian dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam naskah itu sendiri, atau sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak. Dapa juga dilakukan dengan membubuhi tanda tangan atau 24 Lihat Pasal 9 Konvensi Wina 1969. Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 35 paraf di bawah naskah perjanjian atau tanda tangan dalam suatu final act. Penerimaan naskah berbeda dengan kesaksian naskah. e. Tahap Penandatanganan Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah perundingan untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian internasional. Namun penandatanganan tidak selalu berarti pemberlakuan perjanjian internasional. Pemberlakuan tergantung dari klausula pemberlakuan yang telah disepakati dalam perjanjian internasional. Akibat dari penandatanganan suatu perjanjian tergantung dari ada atau tidaknya persyaratan ratifikasi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian harus diratifikasi, maka penandatanganan hanya berarti utusan-utusan telah menyetujui teks perjanjian dan bersedia menerimanya serta akan meneruskan kepada pemerintah yang berhak untuk menerimnya atau bahkan menolak perjanjian tersebut.25 Secara yuridis, apabila suatu negara yang telah menandatangani perjanjian tapi belum meratifikasinya, maka negara tersebut belum merupakan peserta dalam perjanjian. Dalam hal ini negara tersebut berkewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan obyek dan tujuan perjanjian selama negara tersebut belum meratifikasinya.26 Penandatanganan disini hanya dapat dilakukan oleh utusanutusan yang memiliki surat kuasa penuh. Penandatangan ini bukan berarti otentifikasi naskah, melainkan persetujuan negara untuk diikat secara hukum. Menurut Pasal 7 (2) Konvensi Wina, hanya kepala negara, kepala pemerintah, dan Menteri Luar Negeri yang dapat menandatangani tanpa memerlukan surat kuasa 25 26 Starke, An Introduction to International Law, 9th edition, Butterworths, London, 1987. Hlm. 429. Lihat Pasal 18 Konvensi Wina 1969. 36 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional penuh, sedangkan perwakilan lain wajib memiliki surat kuasa penuh.27 C. Ketentuan Khusus Dalam Proses Mengikat Diri (Consent to be Bound) Ada beberapa cara yang dapat dilakukan negara dalam memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian internasional, dan ini tergantung pada kesepakatan para pihak saat membuat perjanjian. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negaranegara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. Pasal 11 Konvensi Wina menyatakan: “the consent of the State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instrumen constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.” Dengan banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam mengikatkan diri pada sebuah perjanjian internasional, sayangnya telah memunculkan banyak kebingungan dalam pelaksanaannya. Cara yang paling banyak dilakukan adalah penandatanganan dan ratifikasi. Lebih lanjut Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa: The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when: (a) The treaty provides that signature shall have that effect; (b) It is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that effect; or 27 Lihat Pasal 7 (2) Konvensi Wina 1969. Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 37 (c) The intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiations. Ssedangkan Pasal 14 (1) menyatakan bahwa: The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when: (a) The treaty provides for such consent to be expressed by ratification; (b) It is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required; (c) The representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or (d) The intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiations. Sebelum adanya Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 UUD 1945 ini memerlukan suatu penjabaran lebih lanjut bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan menjadi hukum di Indonesia. Untuk itu melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 mencoba menjabarkan lebih lanjut Pasal 11 UUD 1945 tersebut. Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini yang dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam 38 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional perjanjian internasional. Tetapi dalam prateknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional. Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000. Dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu: 1. Ratifikasi (ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional; 2. Aksesi (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian; 3. Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut; 4. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing(langsung berlaku pada saat penandatanganan). D. Ratifikasi Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional, penandatanganan suatu perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 39 Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden. Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan DPR. Pengesahan dengan keputusan Presiden hanya perlu pemberitahuan ke DPR. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk diikat suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi bila: a. Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi; b. Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi; c. Bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat utnuk meratifikasinya kemudian, atau; d. Penerima Kuasa delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian. Adapun kewenangan dan proses ratifikasi suatu perjanjian di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 9, 10 dan 11 ayat (1) Undangundang No. 24 Tahun 2000. Pasal 9 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang disyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, dan dilaksanakan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang (Pasal 10), apabila berhubungan dengan: 40 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. Pembentukan kaidah hukum baru; f. Pinjaman atau hibah luar negeri. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk ratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan melalui keputusan presiden, apabila materi perjanjian tersebut tidak termasuk seperti yang dicantumkan dalam Pasal 10. Materi perjanjian ini bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam jangka waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian ini diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan penanaman modal serta perjanjian yang bersifat teknis. Proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia baik bilateral maupun multilateral melalui Keppres ataupun undangundang, oleh lembaga pemrakarsa atau instansi terkait dalam perjanjian tersebut mengadakan rapat interdepartemen dengan tujuan: a. Menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumendokumen yang dibutuhkan lainnya. b. Mengkoordinasikan pembahasan rancangan atau materi permasalahan dimaksud bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya. c. Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden. Di dalam mekanisme fungsi dan wewenang, DPR dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan dari pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 41 merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang No. 24 tahun 2000.Indonesia sebagai negara yang menganut paham gabungan antara monisme dan dualisme, walaupun masih belum konsisten, hal ini terlihat dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa: ”Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undangundang atau keputusan presiden.” Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional indonesia tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia mulai memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undangundang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjanjian internasional yang diratifikasi, contoh Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut dalam undang-undang yang lebih spesifik. E. Reservasi Sebuah negara dapat memilih untuk menerima semua ketentuan dalam perjanjian atau hanya sebagian ketentuan perjanjian saja. Dalam kasus seperti ini, negara dapat membuat sebuah reservasi sebagai bentuk persetujuan atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 2 (1) (d) Konvensi Wina, reservation 42 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving, or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effects of certain provisions of the treaty in their application to that State. Jadi reservasi adalah suatu pernyataan resmi negara yang diberikan sewaktu menandatangani, meratifikasi atau menyatakan ikut serta dalam suatu persetujuan yang menentukan halhal tertentu sebagai syarat kesediaannya menjadi pihak dalam perjanjian. Reservasi dapat berbentuk suatu pernyataan yang dilampirkan pada naskah perjanjian itu sendiri, biasanya di atasnya, di sebelah bawah atau di bawahnya tanda tangan wakil atau wakil-wakil negara yang mengadakan reservasi tersebut. Reservasi juga dapat dilampirkan pada naskah ratifikasi ataupun pernyataan ikur serta (aksesi) dari suatu negara. Selain itu, reservasi juga dapat tertera dalam suatu instrumen resmi tersendiri yang merupakan bagian dari perjanjian, seperti protokol atau proses verbal dari tanda tangan, suatu proses verbal pertukaran atau deposit naskah ratifikasi, atau bentuk lainnya yang disetujui.28 Dampak dari reservasi sangat tergantung dari diterima atau tidaknya reservasi tersebut oleh negara para pihak lainnya. Reservasi untuk perjanjian bilateral sepertinya tidak akan menimbulkan masalah, karena sebagai gantinya akan dengans endirinya dinegosiasikan kembali ruang lingkup yang diatur sebagai hasil negosiasi tersebut. Sebaliknya dalam perjanjian multilateral, permasalahan akan semakin rumit karena reservasi mungkin saja diterima oleh sebagian negara anggota, dan ditolak oleh negara anggota lainnya. Menurut ketentuan hukum tradisional, sebuah negara tidak bisa melakukan reservasi apabila tidak diterima oleh seluruh negara anggota yang sudah menandatangani perjanjian tersebut, walaupun belum 28 Schwarzenberger, Ibid. Hlm. 126. Lihat Chairul Anwar, Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989. Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional 43 diratifikasi. Tetapi aturan ini kemudian dikesampingkan oleh pendapat Hakim Mahkamah Internasional dalam kasus genosida.29 Pengadilan memutuskan bahwa teori tradisional tentang reservasi telah difahami dengan baik, namun ada beberapa kasus yang tidak bisa diterapkan teori ini. Khususnya tidak dapat diterapkan terhadap Konvensi Genosida, yang bertujuan untuk melindungi individu, dan menyebabkan harus diberlakukannya hak resiprokal terhadap negara anggota.30 Mahkamah Internasional mengakui praktik reservasi dengan memberikan pembatasan rangkap, yaitu: a. Reservasi tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian internasional; b. Negara yang menyatakan keberatannya terhadap reservasi yang diajukan oleh negara lain, dapat menganggap dirinya tidak terikat dalam perjanjian dengan negara tersebut. Konvensi Wina sendiri menyatakan bahwa sebuah negara dapat mengajukan ratifikasi, kecuali terhadap perjanjian yang memang sudah dilarang untuk melakukan reservasi dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian. Di samping itu, Konvensi juga menyebutkan bahwa bila negara keberatan terhadap sebuah reservasi yang diajukan oleh negara lain, karena reservasi tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian, maka yang tidak berlaku hanyalah yang direservasi saja. Dalam praktiknya, reservasi yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam perjanjian multilateral umumnya terkait dengan masalah penyelesaian sengketa. Misalnya reservasi terhadap Pasal 12 ayat 1 pada Convention for Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft atau Pasal 14 ayat 1 pada Convention for the Suppression on Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, dimana dinyatakan bahwa penyelesaian 29 30 Lihat E. Klein, Genocide Convention (Advisory Opinion), EPIL II, 1995, Hlm. 544-546. Akehurst, Michael, A Modern Introduction to International Law, 7th edition, Peter Malnczuk, Routledge, New York, 1997 44 Chapter Three – Pembuatan Perjanjian Internasional sengketa ke Mahkamah Internasional harus mendapatkan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya.