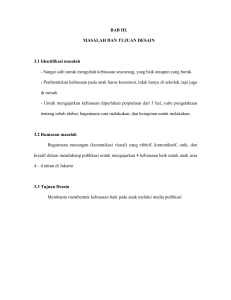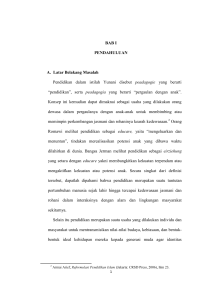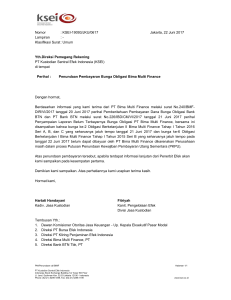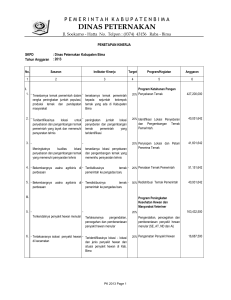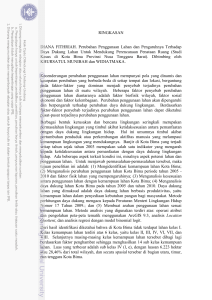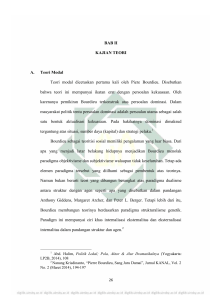21 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN
advertisement

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN Bagian ini memaparkan kajian pustaka, penjabaran konsep, teori, dan model penelitian. Dalam kajian pustaka dikemukakan beberapa karya terdahulu yang relevan, baik substansi maupun perspektif, sehingga dapat menentukan posisi disertasi ini dan memberi basis argumen. Pemaparan konsep adalah memberi batasan dan pengertian dari kata kunci atau frasa yang tertera dalam judul disertasi untuk dioperasionalisasi dalam kajian selanjutnya. Sementara itu, dalam kajian teori didiskusikan tiga teori utama untuk menjawab masalah penelitian, yaitu teori praktik dari Pierre Bourdieu, teori hegemoni dari Antonio Gramsci, dan teori tindakan komunikatif dari Juergen Habermas. Bagian terakhir adalah model penelitian berupa gambaran konstruksi penelitian yang berfungsi sebagai anatomi dalam menjelajahi alur berpikir dalam penelitian. 2.1 Kajian Pustaka Karya-karya akademik dalam subjek sosial, politik, budaya, dan agama berupa laporan penelitian, buku, monografi, dan tulisan-tulisan yang membentuk kepustakaan mengenai masyarakat Bima di Nusa Tenggara Barat tidak susah ditemukan. Sementara itu, penelitian lebih spesifik tentang Dou Mbawa di Bima masih jarang dilakukan, kecuali oleh Peter Just (2001). Etnolog Amerika ini melakukan studi di Mbawa pada 1981, hasilnya diterbitkan dalam buku berjudul Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society. Karya ini 21 22 dapat disebut perintis yang pernah dilakukan mengenai Mbawa – yang ia sebut sebagai Doro Ntika (gunung cantik). Just mengidentifikasi beberapa aspek moralitas yang hidup dalam Dou Mbawa sebagai basis harmoni sosial. Ia mengemukakan argumentasi bahwa basis moralitas yang bersumber dan terpatri di dalam kepercayaan akan nenek moyang dan roh-roh, bekerja sebagai jalan penyelesaian konflik dan pemecahan persoalan yang muncul di masyarakat. Just menyimpulkan bahwa berlangsungnya sistem hukum di Mbawa hanya bisa dipahami dalam konteks moralitas, yaitu pandanganpandangan dasar mengenai asal-usul alam, makhluk yang menempatinya, dan hubungan antarsesama mereka. Just menempatkan kepercayaan Dou Donggo terhadap roh jahat dan dewa-dewa, konsepsi dan persepsi diri, dan kekuatan magic yang dimiliki para otoritas adat sebagai titik tolak dari sistem hukum konsensus yang dianut oleh masyarakat. Studi ini juga membahas tentang formulasi moralitas dan kesepakatan-kesepakatan komunitas yang mendasari kehidupan sehari-hari mereka. Konstruksi moralitas komunal itulah yang dapat menjadi modal sosial bagi mereka dalam meretas kehidupan yang langgeng, termasuk menjadi mekanisme penyelesaian konflik dan ketegangan di antara mereka. Penelitian disertasi ini, harus diakui, untuk sebagian mengambil inspirasi dari karya Just di atas. Hanya saja, Just memberi porsi terbatas bagi ekspresi ritual, sedangkan penelitian disertasi ini menelusuri lebih jauh lagi dan merangkai lebih detail tentang ekspresi ritual tersebut sebagai wadah bagi manifestasi sistem kepercayaan sebagaimana disinggung Just. Perbedaan berikutnya, penelitian 23 disertasi ini lebih lanjut menelusuri aspek-aspek ritual yang merefleksikan adanya transformasi gagasan mengenai hidup bersama dan berhadapan dengan orang lain atau orang luar. Jika Just berhenti dan berkutat pada identifikasi sistem kepercayaan, maka disertasi ini fokus pada praktik budaya Raju yang bukan saja sebagai representasi sistem kepercayaan itu, tetapi juga sebagai ideologi yang bekerja dalam ranah sosial-budaya di Mbawa. Selain karya Peter Just, studi lain di Mbawa yang relevan dan dapat memberi gambaran terhadap kemajemukan Dou Mbawa dilakukan oleh Kadri dkk (2009, tidak dipublikasikan), Satu Leluhur Dua Agama: Dinamika Komunikasi Komunitas Islam dan Kristen di Mbawa-Donggo. Penelitian ini mengenai hubungan sosial antara penganut kepercayaan berbeda, khususnya bagaimana dua entitas budaya (Islam dan Kristen) yang dianut oleh masyarakat seleluhur bertautan dalam ranah publik dan melahirkan corak hubungan yang khas, yaitu harmoni sekaligus riak-riak. Dalam kajian ini, Dou Mbawa memiliki kearifan dalam menyikapi perbedaan sekaligus kesamaan yang mereka miliki. Selain pola hidup komunal yang mengandalkan gotong-royong, Dou Mbawa cenderung meletakkan identitas keagamaan di ruang privat, sementara identitas kultural yang menggambarkan kesamaan di antara mereka ditampilkan di ruang publik. Kajian di atas, di mana peneliti terlibat di dalamnya, adalah pengamatan awal dan sekilas untuk melihat kembali situasi keragaman di Mbawa setelah sekian lama kosong dari pengamatan akademik setelah Just. Kajiannya bersifat umum, bukan merupakan studi kasus pada praktik-praktik spesifik yang menjadi pranata kultural masyarakat Mbawa, sebagaimana dilakukan oleh kajian disertasi 24 ini. Namun demikian, kajian tersebut, selain kajian Just, memberi petunjuk mengenai adanya perangkat kultural yang spesifik yang dapat dipandang sebagai inti dan identitas kebudayaan Dou Mbawa. Celah itulah yang hendak diisi oleh kajian disertasi ini. Mengkaji Mbawa (sebagai subkultur) tidak memadai tanpa mengaitkan dengan kajian tentang Bima (sebagai kultur dominan), karena kedua entitas budaya itu memiliki jalinan yang intens baik konvergensi maupun divergensinya. Dengan demikian, perlu dikemukakan beberapa kajian yang berkaitan dengan masyarakat Bima secara lebih luas dengan tema yang lebih spesifik mengenai praktik keagamaan dan proses pembentukan identitas keagamaan. Karya-karya itu dapat disebutkan sebagai berikut: Abdul Wahid dkk (2001) berupa laporan penelitian dengan judul Tata Nilai dan Kehidupan Islami: Hubungan antara Pemahaman dan Pengamalan Agama Masyarakat di Kabupaten Bima. Kajian ini adalah survey yang memberi pemahaman awal mengenai pola Islamisasi dalam masyarakat Bima secara umum dengan membandingkan antara daerah perkotaan dan daerah pedalaman. Dalam studi ini terungkap bahwa corak dan praktik keagamaan masyarakat di Bima sangat ditentukan oleh cara dan sumber mereka memperoleh pemahaman dan pengajaran agama. Tentu saja ada perbedaan akses kepada sumber pengetahuan keagamaan antara kota dan pedalaman, maka ada pula perbedaan dalam cara mereka memahami dan mempraktikkan agama. Pemahaman agama masyarakat di perkotaan secara umum dikategorikan memadai karena besarnya akses terhadap sumber ajaran agama, sementara pedesaan miskin dengan sumber pengetahuan 25 keagamaan. Corak keagamaan mainstream di kota cenderung bersifat ritualformalistik, sementara di wilayah pedesaan agama cenderung mengambil bentuk mistis dengan perpaduannya yang intens dengan budaya-tradisi lokal. Fachrir Rachman (2009) menulis buku Islam di Bima, Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan. Karya ini adalah kajian historis tentang Islamisasi di Bima, yaitu proses transformasi kehidupan keagamaan masyarakat Bima, termasuk di MbawaDonggo. Dalam studi ini terungkap bahwa pengakaran Islam dalam masyarakat Bima telah berlangsung sejak era kesultanan abad ke-16 melalui pola top down dari sultan ke rakyat secara massif. Dalam buku ini terungkap pula bahwa Islamisasi di Mbawa terjadi pada masa-masa akhir kesultanan Bima. Dengan demikian, muncul anggapan bahwa Islamisasi di Mbawa atau Donggo pada umumnya baru dimulai dan menjadi prioritas pada era-era selanjutnya. Michael Prager (2010) menulis “Abandonning the ‘Garden of Magic’: Islamic Modernism and Contested Spirit Assertion in Bima,” dalam jurnal Indonesia and the Malay World Vol. 33 No. 110 Maret 2010. Kajian tentang situasi keagamaan masyarakat pedalaman Bima. Menurutnya, agama di Bima sampai abad ke-20 adalah perpaduan kepercayaan Islam dan pra-Islam yang sering disebut sebagai sinkretisme. Sejak era 1960-an kepercayaan dan praktik keagamaan sinkretik itu menjadi sosok antagonis di hadapan protagonis Muslim reformis, terutama dari kalangan organisasi Muhammadiyah. Mereka yang disebut terakhir ini berupaya membasmi segala bentuk kepercayaan lokal dan ritual keagamaan mereka. Kajian Prager ini membentangkan benang merah sejarah 26 Islamisasi di Bima sembari mengidentifikasi faktor-faktor pendukungnya, yaitu munculnya kaum reformis lokal dari hasil pergi haji ke Mekah dan berkembangnya doktrin keagamaan yang dibawa oleh Muhammadiyah. Syarifuddin Jurdi (2011) menulis buku Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima. Karya ini menggambarkan proses Islamisasi di Bima yang berlangsung dengan kekuatan politik dan payung kekuasaan telah membentuk identitas keislaman yang kuat bagi masyarakt Bima. Islamisasi itu berlangsung tiga abad sejak masa Sultan Abdul Kahir (1640) sampai sultan terakhir Sultan Salahuddin (1955). Transformasi kesultanan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menandai pudarnya identitas Islam politik di Bima. Puncaknya berlangsung pada Orde Baru yang dianggap tidak ramah dengan Islam politik. Semangat Islamisasi kembali mencuat dengan munculnya era reformasi yang menemukan momentumnya ketika Zainul Arifin menjadi bupati Bima periode 2000-2005 dengan program ‘Jum’at Khusyu’ dan motto ‘Bima Ikhlas’. Walaupun pemerintah menunjukkan kemauan politik yang baik dan didukung oleh gerakan sosial dan kultural, program-program ini tidak berhasil. Jurdi melihat kegagalan itu terutama disebabkan ketidakkonsistenan pemerintah sendiri dalam menjalankan program, dengan tiadanya perangkat regulasi yang bisa menopang pelaksanaan ide-ide Islamisasi. Proyek setengah hati ini juga menggiring opini akan eksklusivisme umat Islam dalam pergaulan sosialkeagamaan dengan adanya tindakan penafikan kelompok-kelompok kecil. Hal terakhir ini punya preseden pada masa kesultanan di mana kelompok masyarakat di Donggo, yang telah memiliki kepercayaan lokal dan agama selain Islam, 27 merasakan bahwa proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan mengeksklusi mereka. Muhammad Adlin Sila (2014) melakukan penelitian disertasi dengan judul “Being Muslim in Bima of Sumbawa, Indonesia: Practice, Politics and Cultural Diversity” (Jurusan Antropologi Australian National University, Canberra). Kajian ini adalah sebuah narasi mengenai keragaman budaya, politik, dan praktik, dan cara masyarakat Muslim Bima menegakkan identitas Islam. Membidik makna budaya, simbol dan sistem keagamaan yang terpancar melalui proses praktik dan wacananya dalam ritual dan festival, karya ini melihat ritual dan festival Islam sebagai representasi keragaman ekspresi Islam dalam mana Muslim mengkoseptualisasikan religiusitasnya. Temuannya, makna-makna keislaman menyebar di komunitas Muslim di Bima, baik di kalangan elite agama atau ulama maupun di tataran umat atau awam. Tidak ada gambaran mengenai Islam yang tunggal di saat setiap Muslim memiliki cara sendiri menafsirkan agama sesuai respons mereka terhadap kondisi sekeliling. Ini berarti menjadi Muslim di Bima adalah soal negosiasi di mana mereka menganggap praktik sehari-hari sebagai Islam. Kajian ini, dipandu oleh argumentasi historisitas Islam dan konsep Islam lokal, melihat pentingnya konteks sosial sebagai faktor pembentuk citra Muslim sebagai aktor sosial. Sekalipun praktik-praktik Islam pada dasarnya satu dan seragam, tetap saja ekspresi lahiriahnya berbeda-beda karena perbedaan khazanah sejarah dan budaya serta konteks sosial-politik. Kajian-kajian di atas menggambarkan proses Islamisasi di Bima dalam setiap periode sejarah selalu melibatkan infrastruktur politik. Melalui 28 insfrastruktur politik ini, agama tersebar dengan topangan otoritas yang kuat, baik ideologi maupun agennya. Dalam proses itu terdapat juga simbiosa mutualistik antara agama dan negara. Bila pada awal lahirnya Islam dipayungi oleh negara, pada masa kontemporer berlangsung politisasi agama, di mana pemerintah menggunakan perangkat dan bahasa agama sebagai wahana menggalang opini/persetujuan dan keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan. Relevansi karya-karya di atas dengan penelitian disertasi ini terletak pada dimensi hegemoni dan permainan ideologi yang menjadi isu sentral. Jika kajian terdahulu menyangkut upaya pemerintah melakukan hegemoni di segala sisi kehidupan dengan Islamisasi, maka kajian disertasi ini melihat hegemoni melalui Islamisasi itu berlangsung dan ditanggapi oleh Dou Mbawa – sebuah masyarakat kecil yang masuk dalam jangkauan kekuasaan pemerintah Bima – dengan cara mereka sendiri yang tidak sama dengan masyarakat Bima yang lain. Selain kajian-kajian mengenai masyarakat Bima dan Mbawa di atas, sebagai bahan perbandingan dikemukakan beberapa karya yang mengkaji praktik dan corak keagamaan di beberapa masyarakat Indonesia lainnya. Hal ini untuk memberi pemahaman bandingan mengenai perubahan tradisi keagamaan dan kontestasi budaya sebagaimana yang terjadi di Mbawa. Beberapa penelitian itu sebagai berikut: AG. Muhaimin (2006) menulis buku The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat among Javanese Muslims terbitan The Australian National University E-Press. Buku ini menampilkan corak dan tradisi sosial-keagamaan kalangan Muslim di Cirebon, Jawa Barat yang merupakan manifestasi dari sistem 29 kepercayaan, pandangan dunia mitologi dan kosmologi. Perpaduan antara tradisi Islam universal dengan tradisi lokal melahirkan citra Islam yang khas, yakni Islam yang berkarakter sufistik. Skeptis terhadap trikotomi ‘priyayi-santri-abangan’ yang dibuat oleh Cliffort Geertz dalam memahami dinamika sosio-kultural Jawa, penulis mengajukan perspektif perennialisme dari Syed Hussein Nasr dalam melihat tradisi Islam dan memahami praktik keberagamaan Muslim di Cirebon. Dalam perspektif Nasr, antara yang sakral dan yang profan dari agama tidaklah mudah dipilah karena keduanya telah berjalin sedemikian rupa dan membentuk entitas keagamaan yang utuh. Dengan demikian, praktik dan tradisi keagamaan tidak serta merta bisa diberi justifikasi, kecuali setelah dilakukan penelusuran secara mendalam terutama terhadap klaim penganut tradisi akan akar praktik tradisi tersebut. Posisi teks dan bahasa agama sebagai sumber otoritas keagamaan menjadi sangat penting, hal yang justru diabaikan oleh Geertz. Secara metodologis, pandangan ini mengarahkan pada berlakunya analisis hermeneutika dan fenomenologi dalam membaca sistem tanda-simbolis dan memahami motifmotif di balik praktik keagamaan. Posisi penulis sebagai ‘insider’ amat sesuai dan mendukung penggunaan cara kerja hermeneutis-fenomenologis ini. Karya ini juga melihat peranan sumber otoritas keagamaan, yakni Pesantren Buntet, dalam memainkan agensi bagi pembentukan dan pemertahanan identitas dan corak keagamaan. Sebagai institusi, pesantren Buntet adalah ranah bagi elite agama dalam menentukan dan melegitimasi praktik keagamaan masyarakat. Jelas terdapat pertarungan dalam proses itu, dan seperti biasanya pertarungan, baik berakibat menang-kalah maupun dominasi, selalu menyediakan ruang bagi 30 hidupnya identitas. Karya Muhaimin relevan bagi kajian disertasi ini sebagai bahan analisis perbandingan. Karakteristik masyarakat Muslim Cirebon mirip masyarakat Muslim Bima, di mana praktik tradisi Islam juga hidup dan menjadi identitas. Jika di Cirebon terdapat banyak situs Islam, maka di Bima juga banyak ditemukan artefak atau budaya fisik yang menandai kehadiran Islamisasi, bahkan di Bima masih berdiri kokoh legacy kesultanan Islam yang diperlihatkan secara fisik maupun sebagai realitas sosio-kultural. Praktik keagamaan di kedua daerah ini juga menunjukkan kecenderungan akulturasi atas persinggungannya dengan budaya lain. Nuansa adat yang kental bersinggungan dengan norma syari’at juga mengalami internalisasi sedemikian rupa sehingga membentuk kesatuan yang utuh antara keduanya. Integrasi dua entitas itu di Bima bahkan terlembagakan dalam struktur otoritas yang merupakan dwitunggal pilar kekuasaan kesultanan, yaitu Majlis Sara (syari’ah/agama) dan Majlis Hadat (adat). Penguatan aspek mistisisme juga terjadi antara lain dengan berkembangnya ngaji fi tua (tasawuf falsafi) di kalangan masyarakat (Sila, 2014), yang dalam tataran tertentu mengalami mistifikasi. Pertemuan dengan khazanah lama yang masih diwariskan melahirkan kecenderungan mistis dan magis yang mengitari kehidupan masyarakat Islam sampai sekarang. Namun, di Bima struktur agensi kelembagaan yang mengusung pengembangan sufisme berbentuk tarekat tidak sekuat di Cirebon, maka kekuatan reformis-puritan, seperti Muhammadiyah, berhasil memenangkan pertarungan sehingga massifikasi praktik tradisional Islam dapat dilokalisir ke masyarakat-masyarakat pedalaman yang tak terjangkau 31 (Prager, 2010). Mbawa di daerah pegunungan Donggo, tempat penelitian disertasi ini, adalah salah satu tempat ‘pelarian dan persembunyian yang aman’ bagi praktik keagamaan tradisional tersebut. Buku lain ditulis oleh Hyung-Jun Kim (2007) berjudul Reformist Muslims in a Yogyakarta Village: The Islamic Transformation of Contemporary SocioReligious Life juga terbitan The Australian National University E-Press. Karya ini merupakan narasi historis-analitik mengenai pembentukan kultur, identitas, ideologi, praktik, dan pandangan sosia-keagamaan dari masyarakat heterogen di Jawa. Yogyakarta, tempat studi ini dilangsungkan, adalah kota dengan citra multikulturalisme yang sangat kental. Beragam budaya berinteraksi dan meninggalkan jejak-jejak kultural, termasuk tradisi-tradisi keagamaan hadir dan berkembang, menyumbang keragaman alam pikiran masyarakat. Tradisi intelektual Muslim dan Kristen bertautan melalui intensitas praksis sosial kalangan cerdik pandai, ulama-kiyai dan romo serta kaum intelektual berideologi. Karakteristik Yogyakarta sebagai kota multikultural sekaligus sebagai pusat budaya Jawa menjadi tantangan bagi kekuatan-kekuatan keagamaan “missionaris” untuk melakukan inkorporasi ideologi dan budaya. Hal ini menambah lagi khazanah muatan kultural Yogyakarta dan menjadikannya sebagai medan ‘adu kekuatan’ bagi kaum reformis dari kalangan Islam dan Kristen. Kristenisasi dan Islamisasi kerap saling berpacu memperebutkan ruang dalam mengisi nalar, jiwa, dan keberagamaan masyarakat. Dalam atmosfir seperti itu, tidak gampang menjadi beragama di kota itu. Terombang-ambing dalam sikap keberagamaan menjadikan orang cenderung 32 memiliki identitas keagamaan yang kabur atau multi-identitas yang mewujud dalam berbagai paham-praktik inkulturatif, moderatif, pluralis, dan inklusif. Ini tentu saja menjadi lahan dakwah yang menantang bagi kaum reformis keagamaan, seperti Muhammadiyah di kalangan Islam. Karya Kim (2007) merekonstruksi upaya para reformis yang dipengaruhi alam pikiran Muhammadiyah dalam membentuk corak ideologi dan praktik keagamaan di kampung Kolojonggo (nama samaran) wilayah Yogyakarta. Upaya transformasi sosial ini bergerak dalam kerangka pikir reformis yang puritanistis, ialah gagasan pemurnian praktik keagamaan agar tidak bercampur dengan unsur syirik, bid’ah, dan khurafat. Dalam upaya ini, mereka dihadapkan pada dua kelompok keagamaan sekaligus: pertama dari kalangan internal Islam, yaitu mereka yang dianggap bukan penganut Islam yang taat; kedua dari penduduk beragama Kristen. Dakwah internal dan eksternal ini tentu saja menghadirkan suatu dinamika sosial di kampung Kolojonggo yang berpengaruh pada sikap keberagamaan ketiga komponen baik dari kalangan reformis itu sendiri, kalangan ‘abangan’ yang sinkretis, dan kalangan Kristen. Terjadi pertarungan segitiga atau perselingkuhan di antara kelompok tersebut. Terutama di kalangan Muslim yang mayoritas, terjadi transformasi dalam hal cara pandang internal terhadap diri mereka sendiri, agama mereka, dan eksternal lingkungan di sekitar dan penganut agama lain. Meskipun tidak terlalu memadai dalam menggambarkan proses dan akhir dari kontestasi ideologi-praksis dua kekuatan besar eksternal yang melanda masyarakat tradisional ini, Kim berhasil menggambarkan proses pembentukan varian dari gerakan pembaharuan sosial keagamaan dari kalangan reformis, dan 33 menunjukkan supremasi Islam dari kalangan reformis terhadap tradisionalisme kultural sekaligus terhadap ke-Kristenan. Relevansi kajian di atas dengan tesis disertasi ini terlihat dalam aspek masyarakat Kolojonggo yang pluralistik mirip dengan masyarakat Mbawa dengan segmentasi Islam, Kristen, dan penganut tradisi. Praktik keagamaan masyarakat menunjukkan gejala inkulturasi dan sinkretisme seperti yang berlangsung di Jawa (Kolojonggo). Mbawa juga adalah daerah sasaran dakwah dari dua agama besar itu sehingga menjadi locus Islamisasi dan Kristenisasi di era kini. Proses transformasi budaya, identitas, dan religiusitas di Mbawa adalah isu penting dalam diskursus kajian saya, di samping topik mengenai aktor, aparatus, dan ruang publik. Berporos pada isu konflik, kajian peneliti adalah menganatomi silang sengkarut sengketa perebutan dominasi antarkelompok, dalam berbagai bentuknya, dan melihat gejala dan kemungkinan adanya potensi yang bisa menjadi wahana bagi masyarakat setempat untuk menyelamatkan komunalitas yang mereka sendiri bangun, definisikan, impikan, dan perjuangkan. Bekerja di bawah payung cultural studies, antropologi, atau kajian ilmu politik memiliki tantangan sendiri-sendiri, dan bisa me(re/ng)konstruksi realitas yang berbeda di atas gejala yang sama. Nanti akan segera terlihat, apakah nalar dan postur masyarakat Kolojonggo akan termanifestasikan juga di Mbawa, atau ada narasi lain yang berkarakter Austronesian. Juga, pasti akan ada proyeksi ‘teoretis-politis’ yang tercetus dari pilihan cara kerja Kajian Budaya yang penulis lakukan, yang mungkin berbeda dari Kim atau Muhaimin. 34 Karya lain yang tidak kurang relevan adalah buku berjudul Longing for the House of God, Dwelling in the House of the Ancestors: Local Belief, Christianity, and Islam among the Keo of Central Flores ditulis Philipus Tule (2004) terbitan Academic Press, Fribourg Switzerland. Buku ini menampilkan gambaran suatu konstruksi bangunan dan hubungan sosial dari masyarakat plural Keo Flores bagian tengah dan bagaimana mereka menegosiasikan perbedaan dan identitas. Buku ini adalah kajian antropologi agama mengenai isu-isu penting agama, budaya, identitas, dan ideologi lokal yang tercakup dalam ritual, organisasi sosial, dan ikatan perkawinan. Kebanyakan orang Keo beragama Islam dan Katolik, namun tetap menganut kepercayaan dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas mereka. Islam dan Kristen, bagi mereka, bukan sekedar praktik agama yang diinspirasi dari kitab-kitab suci, tetapi menjadi basis bagi pandangan hidup dan hidup sehari-hari. Terjadi pertautan di mana ajaran-ajaran monoteistik mengambil elemen-elemen tertentu dari budaya Keo dan sebaliknya budaya Keo mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen ajaran monoteistik. Inilah yang menandai masyarakat Keo berkarakter inkulturatif yang bisa dilihat sebagai akar yang kuat harmoni dan toleransi di antara penduduk dalam hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dan masalah rumah, pemukiman, dan lahan. Bekerja dengan semangat antropologi struktural, terutama dari Levi Strauss, karya ini mengeksplorasi konsep ruang dalam hubungan sosial masyarakat Keo. Tanah dan penguasaannya adalah simpul dari harmoni dan konflik di dalam masyarakat heterogen Keo. 35 Dalam aspek hubungan antaragama, buku karya Suprapto (2013) berjudul Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim relevan sebagai bahan bandingan. Karya ini memberi gambaran konflik dan integrasi dalam relasi sosial antara komunitas berbeda etnis dan agama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kajian ini menyangkal tesis bahwa konflik komunal terjadi karena perbedaan identitas primordial, nilai-nilai dasar teologis, dan fragmentasi sosial. Menurutnya, konflik dapat terjadi karena kurangnya ruang publik, seperti taman kota, sarana olah raga dan kesenian yang membuat komunikasi dan ikatan antarwarga lemah. Berkurangnya ikatan antarwarga ditambah faktor lain seperti sejarah, politik, ekonomi, dan budaya, menyebabkan berbagai pertentangan antarwarga gampang bergeser dari ketegangan personal menjadi konflik komunal. Integrasi dan harmoni sosial antarumat beragama yang tercipta melalui ketersediaan ruang publik akan terawat dengan baik oleh adanya pemahaman keagamaan inklusif yang memproduksi teologi kerukunan. Bersama faktor lain seperti ikatan perkawinan dan koalisi politis lintas etnis, dan nilai-nilai luhur adat, teologi kerukunan yang ada pada Islam dan Hindu merupakan modal sosial terpenting dalam merawat harmoni sosial sekaligus unsur potensial bagi upaya peace building (bina damai). Beberapa kepustakaan di atas telah membuka wawasan baru bagi peneliti tentang praktik dan tradisi keagamaan, khususnya di Bima, dan lebih spesifik lagi di Mbawa. Kajian-kajian yang telah disebutkan bermanfaat bagi rekonstruksi pemahaman yang lebih baik terhadap praktik keagamaan beserta semua nuansa 36 yang mengitarinya. Untuk kajian yang penulis sedang lakukan mengenai praktik budaya ritual di Mbawa, bacaan-bacaan ini bisa menjadi titik berangkat berikutnya, signifikan bagi pengkayaan perspektif dan orientasi teoretik, serta menjadi basis bagi konstruksi argumen bagi penelitian disertasi ini. Selain sebagai bahan analisis perbandingan, juga dapat menjadi penuntun dalam merumuskan atau menata kembali struktur kajian sebagai suatu karya bernilai disiplin tinggi. Berdasarkan penelusuran kepustakaan di atas, studi yang dilakukan Peter Just dapat dikatakan sangat mendalam mengenai moralitas dan karakter Dou Mbawa. Sebagai sebuah studi antropologi yang bersifat naturalistik studi Just mampu menggambarkan sisi-sisi esoteris Dou Mbawa. Meskipun tidak fokus pada masalah praktik budaya atau relasi kuasa antara berbagai elemen masyarakat, studi Just mengungkap dimensi konflik dalam masyarakat dan cara khas penyelesaiannya. Studi Just memberi benang merah bagi penelitian lebih lanjut dengan tema yang lebih spesifik lagi, antara lain mengenai praktik budaya. Dengan demikian, penelitian mengenai praktik budaya dengan perspektif cultural studies yang dilakukan melalui disertasi ini dapat dikatakan sebagai studi inisiasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika Just membidik moralitas konflik antaranggota komunitas, maka penelitian ini membidik konflik antara komunitas dengan pihak-pihak luar yang dianggap mendominasi kehidupan komunitas Mbawa. Adapun argumen yang bisa dibangun berdasarkan pemahaman dan refleksi kajian pustaka di atas adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan identitas keagamaan dan lokal bersumber dari pandangan budaya/kosmologi dan faktor 37 sosial-politik-ekonomi yang melingkupinya. Kedua, praktik budaya adalah akumulasi pengetahuan dan representasi struktur dan relasi sosial, karenanya mengandung dimensi kultural berupa visi sosial dan kepentingan serta mengatur relasi. Ketiga, budaya Raju yang dipraktikkan orang Mbawa adalah strategi komunikasi, manajemen konflik, cara mengatasi hegemoni, dan jalan mengembalikan atau memproyeksikan harmoni di masa depan. 2.2 Konsep Dalam penelitian ini tertera konsep mengenai praktik budaya Raju, masyarakat pluralistik, dan konsep Dou Mbawa. Uraian konsep ini membantu peneliti dalam memahami gejala-gejala kultural yang memiliki struktur, kategori, dan berbagai sistem norma yang berbeda (Ratna, 2010: 110), sebagaimana halnya praktik budaya Raju yang diteliti. 2.2.1 Praktik Budaya Raju Praktik adalah cara melakukan sesuatu, sebuah tindakan atau perilaku yang dilaksanakan sebagai refleksi dari niat, kebiasaan dan rutinitas (Barker 2004: 163). Menurut Barker, istilah praktik dalam cultural studies diderivasi dari konsep-konsep mengenai bahasa, teks, dan diskursus. Habermas menggunakan istilah “praksis” yang merujuk kepada suatu proses pencerahan rasio yang berujung pada pemihakan emansipatoris (Hardiman, 2009b: 61). Dengan kata lain, praktik adalah kesinambungan dari gagasan, teori, dan wacana. Praktik adalah representasi makna yang sengaja dirancang untuk mewadahi keterbatasan bahasa, sehingga secara semiotik, praktik adalah tanda, teks, atau bahasa itu 38 sendiri. Sementara budaya adalah konsep paling kompleks dan rumit dalam ilmuilmu sosial humaniora. Kata “budaya” memiliki makna konotatif yang banyak, dan mempunyai kesenjangan pengertian antara penggunaan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, mendefinisikan budaya tidak lain dari upaya memahami situasi dan lingkungan pembentuknya. Teori-teori kebudayaan, mulai dari cultural evolusionism sampai teori-teori progresif dari tradisi kritis dan poststrukturalisme, telah banyak membahas mengenai kebudayaan dan aspek yang melingkupinya. Selain dari definisi yang beragam dan luas mengenai budaya dari tradisi sosiologi, antropologi, dan sastra, cultural studies memiliki coraknya sendiri dalam memahami budaya (Barker 2009: 37). Raymond William, salah seorang perintis dalam tradisi cultural studies, misalnya, memahami budaya sebagai masalah keseharian hidup yang luas sampai hal remeh temeh (Barker 2009: 39). Dalam pengertian Barker, ritual dan hal-hal yang menyertainya termasuk bagian dari budaya. Sementara Hartley (2010: 29) mendefinisikan budaya sebagai produksi dan sirkulasi dari rasa, makna, dan kesadaran, pada saat bersamaan budaya adalah ranah reproduksi bukan atas benda-benda material, tetapi atas hidup. Dengan demikian, praktik budaya adalah sesuatu yang kompleks. Dalam cultural studies, praktik dipandang sebagai representasi wacana, teks atau bahasa. Praktik adalah budaya itu sendiri, dan sebaliknya, yang bekerja seperti bahasa sebagai representasi sesuatu yang sedang bekerja menghasilkan makna. Artinya, 39 pembentukan representasi makna melibatkan seleksi dan organisasi tanda ke dalam teks yang terbentuk melalui suatu bentuk tata bahasa. Bahasa mewadahi objek material dan praktik sosial dengan makna-makna yang terusung sehingga bisa dipahami. Praktik budaya ibarat bahasa yang memuat berbagai makna dan wacana, tidak netral, dan sarat muatan kepentingan. Praktik budaya menjadi arena pertarungan kepentingan dan ranah bagi relasi kuasa yang bergerak dinamis dalam masyarakat. Praktik budaya Raju adalah ritual adat yang dilaksanakan oleh Dou Mbawa secara rutin dalam rangka menyongsong musim tanam. Lama waktu rangkaian ritual dalam praktik budaya Raju tidak sama setiap tahun, berlangsung dalam jumlah hari ganjil, 3, 5, 7, atau 9 hari tergantung dari perhitungan bulan yang diputuskan oleh para tetua adat. Puncak dari rangkaian itu ditandai dengan berkumpulnya para pendukung praktik budaya Raju di Uma Ncuhi, sebuah rumah warisan leluhur yang terletak di sebuah bukit kecil di tengah kampung. Uma Ncuhi adalah bangunan berupa gubuk tradisional ala Donggo yang berdiri di lokasi gundukan bukit kecil di bawah sebuah pohon besar dan bongkahan batu. Mereka percaya di situs itulah leluhur mereka bersemayam. Mereka mengadakan upacara dan persembahan sesajen di situ dengan pembacaan mantra dan doa. Tiga hari sebelum acara sesajen dan berdoa dilangsungkan, para lelaki pergi berburu ke hutan di sekitar kampung, sebagian untuk bekal perayaan itu, sebagian lagi sebagai penanda baik buruknya hasil tanaman mereka di musim yang akan tiba. Jika hewan tangkapan mereka lebih banyak betina, pertanda hasil panen mereka nanti akan berlimpah, dan 40 sebaliknya. Praktik budaya Raju dilaksanakan oleh Dou Mbawa secara lintas agama. Pendukungnya dari agama Kristen (Katolik dan Protestan) dan Islam, terutama mereka yang masih berpegang kuat pada kepercayaan Parafu. Doa yang digunakan adalah campuran antara lafal-lafal doa Islam dan Kristiani serta mantra-mantra lama yang bersumber dari tradisi. Bahasa doa yang digunakan adalah perpaduan antara bahasa Bima dialek setempat dengan selipan ungkapanungkapan doa dalam bahasa Arab. Berdasarkan pengertian yang terpisah di atas, frase praktik budaya Raju dalam penelitian ini merujuk kepada praktik budaya Raju dan seluruh rangkaian ritual, pertunjukan, dan perangkat-perangkatnya. Praktik budaya Raju itu telah menjadi fenomena budaya yang dilingkupi berbagai simbolisasi kultural yang mengandung makna, kontestasi, kepentingan, dan relasi-relasi di dalamnya. 2.2.2 Pluralitas Pluralitas secara bahasa berasal dari kata plural, sesuatu atau bentuk yang merujuk kepada lebih dari satu. Secara sosiologis, istilah pluralitas merujuk kepada realitas kemajemukan dalam masyarakat dibangun dari komposisi ragam suku, ras, agama, dan budaya. Sebagai cara pandang, istilah pluralitas membentuk suatu konsep mengenai pluralisme yang memiliki pengertian: (a) “Existence in one society of a number of groups that belong to different races or have different political or religious beliefs” (Keberadaan dalam satu masyarakat sejumlah kelompok yang memiliki ras, anutan politik, dan kepercayaan agama yang berbeda); (b) “Principle that these different groups can live together peacefully in 41 one society” (Prinsip bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa hidup bersama secara damai dalam satu masyarakat) (Hornby, 1989: 889). Pengertian pluralisme mengacu kepada realitas keragaman. Selain mengacu kepada kenyataan keragaman, pluralisme sekaligus sebagai prinsip atau sikap terhadap keragaman itu. Min (1997: 592) membedakan dua istilah tersebut, di mana pluralitas adalah suatu realitas nyata, sedangkan pluralisme adalah bentuk kesadaran atas realitas tersebut. Sebagai realitas sosial, pluralitas adalah kenyataan lama, sedangkan pluralisme adalah fenomena baru. Sementara Panikkar (1994: 33) menempatkan pluralisme sebagai bentuk pemahaman moderat yang bertujuan menciptakan komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal balik antara budaya yang berbeda-beda serta membiarkan mereka bicara dan mengungkapkan pandangan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Pluralitas, bagi Panikkar, berbeda dengan pluralisme. Pluralitas adalah keberagaman yang tidak saling menyapa dan berhubungan yang merupakan lawan dari kesatuan monolitik. Pluralisme berdiri antara pluralitas dan kesatuan monolitik tersebut. Wacana posmodernisme yang gencar mengedepankan pluralisme sebagai isu penting masyarakat kontemporer. Posmodernisme menolak ide dasar filsafat modern yang melegitimasi kesatuan ontologis. Menurut Jean Francois Lyotard, kampiun gerakan posmodernisme, dalam kehidupan kontemporer yang teknologik ini, ide kesatuan ontologis tidak lagi relevan dan harus disubstitusi oleh paralogi atau ide pluralitas. Lyotard menolak klaim modernitas yang memutlakkan kebenaran tunggal yang universal dan terpusat. Baginya, kebenaran itu majemuk dan lokal (Fauzi, 1994: 34). Kebenaran bukanlah realitas tunggal, tetapi 42 multivarian dan karenanya memungkinkan adanya dialog. Dengan asumsi ini, bangunan pemikiran modernisme yang telah menjebak manusia ke dalam absolutisme dan totalitarianisme yang represif, dihancurkan. Idiom-idiom pluralisme, relativisme, fragmentasi, heterogenitas, dan dekonstruksi, karenanya, menjadi bagian penting dari kesadaran intelektual dewasa ini. Secara sederhana, pluralisme adalah kesadaran akan adanya beragam kebenaran, aneka corak keyakinan dan anutan budaya. Dari kesadaran ini tumbuh sikap saling memahami, menghargai dengan cara membiarkan perbedaan, membiarkan setiap individu pihak lain eksis dengan keunikannya sendiri, atau berusaha menemukan kesamaan-kesamaan yang dimiliki masing-masing anutan untuk ditransformasikan bagi kebaikan hidup bersama. 2.2.3 Dou Mbawa Dou Mbawa merujuk kepada sekumpulan orang atau masyarakat yang hidup di Kampung Mbawa, di Bima Nusa Tenggara Barat. Dou adalah kata dalam bahasa Bima yang berarti people (orang). Kata Dou membentuk konsep peoplehood (keorangan) yang menjadi bagian dari identitas. Masyarakat Bima menyebut “Dou” (orang) sebagai identifikasi diri dan identitas kolektif. Ketika menjawab pertanyaan siapa atau dari mana mereka, jawabannya mengacu kepada sebuah kesatuan etnis atau kampung tempat mereka tinggal, seperti “nami Dou Mbojo” (kami orang Bima), “nami Dou Mbawa” (kami orang Mbawa). Identifikasi diri ini mengandung arti bahwa mereka menempatkan diri dalam suatu unit sosial-politik dan keseragaman budaya dalam sebuah wilayah geografi yang bernama Dana (tanah). Gordon (1964: 24) menyebut fenomena ini 43 sebagai sense of peoplehood (rasa keorangan), dan inilah yang dinamakan etnisitas (dari bahasa Yunani ‘ethnos’ yang berarti ‘orang’ atau ‘bangsa’), yaitu sekelompok orang yang membagi rasa keberorangan dalam sebuah kelompok etnis (Francis, 1947: 393-400). Identifikasi diri dalam Dou berlangsung juga pada unit sosial lain seperti masyarakat Donggo dengan penyebutan Dou Donggo, demikian juga pada masyarakat Mbawa dengan Dou Mbawa. Hal ini menunjukkan bahwa di Bima terdapat unit-unit sosial yang membentuk kelompok etnis, sub-etnis, dan sub-sub-etnis. Dengan demikian, Dou Mbawa dalam penelitian ini merujuk kepada masyarakat yang mendiami wilayah Desa Mbawa (sering disebut Mbawa Ese) atau penduduk sekitarnya yang memiliki kesamaan budaya, tradisi, dan asal usul. Masyarakat yang mendiami Dusun Tolonggeru (sering disebut Mbawa Awa) juga termasuk dalam konsep Dou Mbawa meskipun saat ini dusun itu terpisah dari Desa Mbawa dan menjadi bagian Desa Monggo Kecamatan Madapangga. Hal ini karena Dusun Tolonggeru memiliki sejarah asal-usul dan tradisi yang tidak bisa dipisahkan dengan kerabat mereka dari Mbawa Ese, kecuali dipisahkan secara geografis oleh sebuah lembah dan bukit dari sanak famili mereka di Mbawa Ese. 2.3 Landasan Teori Praktik budaya dalam penelitian ini adalah tentang ritual Raju. Ritual, dalam sosiologi, dipandang sebagai fakta sosial, sementara dalam antropologi dilihat sebagai bentuk dasar dari sistem kebudayaan. Adapun teori-teori kritis menganggap ritual sebagai tindakan politik yang mencerminkan gagasan 44 mengenai visi sosial dan ideologi dari pendukung dan aktornya (Bennet dalam Tester, 2009). Berangkat dari argumen Bennet, maka relevan jika penelitian ini menggunakan perspektif dari teori praktik Bourdieu, teori hegemoni Gramsci, dan teori tindakan komunikatif dan ruang publik Habermas untuk mengurai faktorfaktor yang melatar belakangi praktik budaya Raju dan menyingkap selubung ideologi dari relasi hegemonik serta memahaminya sebagai praktik komunikasi di ruang publik. Tiga teori ini digunakan secara eklektik sebagaimana karakteristik kajian budaya dan mengingat satu sama lain saling menunjang. Dalam penerapannya, teori praktik membantu untuk mengurai pertanyaan penelitian pertama, teori hegemoni untuk pertanyaan kedua, dan teori tindakan komunikasi untuk pertanyaan ketiga. 2.3.1 Teori Praktik Bourdieu Teori Praktik dikumandangkan oleh Pierre-Felix Bourdieu (1930-2002), salah seorang pemikir Prancis terkemuka di penghujung abad ke-20. Karya Bourdieu sendiri mencakup bidang yang sangat luas, dari etnografi hingga seni, sastra, pendidikan, bahasa, gaya hidup, dan media. Ulasan-ulasan atas karya karyanya itu telah memberi inspirasi bagi penjelajahan cultural studies di berbagai belahan dunia. Bourdieu adalah seorang teoretikus yang banyak dibahas dalam memahami budaya, terutama menyangkut geneologi suatu praktik budaya dalam masyarakat. Dari sekian banyak yang dikemukakan Bourdieu, teorinya mengenai PraktikHabitus dan Modal banyak dibicarakan dan kiranya sangat relevan diterapkan 45 dalam memahami hubungan-hubungan antarsubjek dalam suatu lingkup budaya tertentu yang kompleks. Dengan teori itu, budaya dipahami secara utuh, sebagai sesuatu yang given (diwarisi) sekaligus constructed (direkayasa), subjektif sekaligus objektif, tubuh sekaligus ide, manifest sekaligus laten. Bourdieu berusaha memecahkan kepelikan struktur dan agensi dalam apa yang disebut strukturalisme generik. Ia berpendapat bahwa praktik meniscayakan adanya agen atau aktor, tetapi perlu dipahami dalam konteks struktur objektif dari suatu budaya dan masyarakat. Secara khusus, Bourdieu prihatin dengan kekuatan kelas penentu sebagai kendala struktural. Bourdieu terkenal dengan argumennya bahwa selera budaya adalah konstruksi sosial yang terletak dalam konteks habitus kelas sosial tertentu (Barker, 2004). (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Fokus perhatian Bourdieu dalam lapangan budaya adalah praktik. Baginya, ada tiga aspek utama yang menjadi inti atau titik tolak lahirnya praktik budaya, yaitu habitus, modal, dan ranah. Habitus adalah sekian produk perilaku yang muncul dari berbagai pengalaman hidup manusia. Habitus akumulasi dari hasil kebiasaan dan adaptasi manusia, yang berakar kuat menjadi suatu karakter, pada gilirannya membentuk suatu struktur yang mendasari praktik dan representasi (Bourdieu, 1990: 53). Habitus mendasari ranah yang merupakan jaringan relasi antarposisi-posisi objektif dalam tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual. Ranah mengisi ruang sosial, yang mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Sementara itu, praktik adalah produk dari relasi antara habitus dengan ranah, yang keduanya merupakan produk sejarah. Dalam ranah inilah ada pertaruhan kekuatan antarorang yang memiliki modal. Konsep modal dari 46 Bourdieu lebih luas daripada sekadar modal material, yakni bisa juga berupa modal ekonomi, modal intelektual maupun modal kultural. Komposisi praktik sosial dari Bourdieu dapat dinyatakan dengan persamaan: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik (Harker, dkk, 2010). Rumus generatif ini menggantikan setiap relasi sederhana antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan ranah yang melibatkan modal. Dengan konsep habitus ini, Bourdieu berupaya menjembatani subjektivisme dan objektivisme, dengan melihat hubungan dialektika antara keduanya. Habitus memproduksi praktik individual dan kolektif (Bourdieu, 1990: 54). Sementara habitus ada di dalam pikiran aktor, lingkungan ada di luar pikiran mereka. Habitus adalah “struktur mental atau kognitif” yang digunakan aktor/subjek untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan untuk digunakan dalam merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan dan memnebri pembenaran. Secara dialektis, habitus adalah “produk internalisasi struktur” dunia sosial. Habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari intensitas posisi dalam struktur dan relasi sosial. Habitus akan berbeda-beda tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Tidak setiap orang sama kebiasaannya: orang yang menduduki posisi yang sama dalam kehidupan sosial cenderung memiliki kebiasaan yang sama. Habitus, karenanya, dapat pula menjadi fenomena kolektif, tetapi dengan adanya banyak habitus 47 berarti kehidupan sosial dan strukturnya tidak dapat dipaksakan seragam kepada seluruh orang. Teori ini juga menekankan determinasi waktu. Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode sejarah yang relatif panjang. Habitus adalah produk sejarah (Bourdieu, 1990: 54). Kebiasaan individu atau masyarakat tertentu diperoleh melalui pengalaman hidupnya dan mempunyai fungsi tertentu dalam sejarah dunia sosial di mana kebiasaan itu terjadi. Habitus dapat bertahan lama dan dapat pula berubah atau dialihkan dari satu bidang ke bidang lain. Pada tataran ini dimungkinkan terjadi transformasi dalam praktik sosial-budaya tergantung kepada kebutuhan dan tantangan sejarah. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Satu sisi, habitus adalah structuring structures (struktur yang membentuk), artinya sebuah kesadaran yang membentuk kehidupan sosial. Sisi lain, habitus adalah structured structures (struktur yang dibentuk), yakni kesadaran yang dikondisikan oleh dunia sosial. Dengan kata lain, habitus adalah dialektika internalisasi dari eksternalitas dan eksternalisasi dari internalitas. Tindakanlah yang mengantarai habitus dan kehidupan sosial. Dengan demikina, habitus diciptakan melalui praktik (tindakan); sekaligus menciptakan tindakan tertentu dalam kehidupan sosial. Bourdieu mengungkapkan fungsi perantara tindakan ketika ia mendefinisikan habitus sebagai “struktur kognisi dan pemberi motivasi” (Bourdieu, 1995: 78). Walau habitus sebuah struktur yang diinternalisasikan, yang mengendalikan pikiran dan pilihan tindakan, namun habitus tidak menentukan pikiran dan tindakan. Habitus semata-mata “mengusulkan” apa yang sebaiknya 48 dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk dilakukan. Dalam menentukan pilihan, aktor menggunakan pertimbangan mendalam berdasarkan kesadaran, meski proses pembuatan keputusan ini mencerminkan berperannya habitus. Habitus menyediakan prinsip-prinsip dengan mana aktor membuat pilihan strategi yang akan digunakan dalam kehidupan sosial. Jadi, habitus bekerja di bawah tingkat kesadaran dan bahasa, di luar jangkauan kemampuan pengamatan dan pengendalian. Adanya habitus dan cara kerjanya tidak disadari, namun berwujud dalam aktivitas manusia yang sangat praktis seperti cara makan, berjalan, berbicara dan bahkan dalam cara bersendawa. Kebiasaan atau habitus ini berperan sebagai struktur, tetapi orang abai terhadapnya atau terhadap struktur eksternal yang mempengaruhi secara mekanis. Dialektika antara habitus dan lingkungan adalah penting karena saling menentukan. Habitus hanya terbentuk dan berfungsi dalam sebuah lingkungan, karena habitus itu sendiri tidak lain dari “lingkungan dari kekuatan yang ada,” sebuah situasi dinamis di mana kekuatan hanya terjelma dalam hubungan dengan suasana tertentu di sekitarnya. Dalam pengertian lain, habitus adalah “sense of one’s place,”, yaitu persepsi seseorang tentang tempat atau posisinya di hadapan orang lain dalam struktur sosial di mana dia hidup, dan persepsi itu mempengaruhi tindakan dan interaksinya (Hillier & Rooksby, 2005). Berdasarkan pengertian habitus dan ranah serta mekanisme kerjanya dalam diri manusia dan struktur, Bourdieu memberi tekanan bahwa salah satu efek mendasar dari konfigurasi ini adalah produksi commonsense world (semesta kesadaran bersama) yang dinilai sebagai sebuah objektivitas yang dilindungi oleh 49 konsensus akan makna dari sebuah praktik dan dunia objektif (Bourdieu, 1995: 80). Itulah mengapa habitus memiliki keterkaitan dengan konsep doxa sebagai padanan dari ideologi. Doxa dapat diartikan sebagai tatanan sosial yang melingkupi individu yang terikat pada tradisi yang memiliki kekuasaan yang tampak natural. Dalam praktiknya, doxa tampil lewat pengetahuan-pengetahuan yang given dalam masyarakat (Takwin, 2009: 115). Gagasan Bourdieu boleh dikatakan membuka tradisi baru dalam wacana sosiologi. Pendekatan sosiologi sebelumnya tidak jauh berbeda dengan pendekatan ekonomi klasik yang melihat fenomena sosial sebagai produk-produk tindakan individual. Pada Bourdieu, terdapat upaya penyatuan kedua unsur ini, yakni antara agen dengan struktur, antara objektivisme Marxian dengan subjektivisme dari fenomenologi, antara kebebasan individu ala Sartre dan determinisme struktur ala Levi Strauss. Teori yang dikemukakan oleh Bourdieu ini bisa menjadi acuan praktis dalam melihat realitas sosial-budaya. Fenomena sosial-budaya yang tampak kompleks jika diteropong menggunakan formulasi Bourdieu ini akan jelas memiliki unsur geneologi yang terikat dengan lingkungan pendukungnya, subjek/aktor dan relasi-relasi antarsubjek dan lingkungannya. Praktik sosial budaya, karenanya, tidak ada yang lahir dalam ruang “hampa”, tanpa konteks dan semangat zamannya. Praktik-praktik tradisi, misalnya, bisa lahir karena proses pewarisan secara turun temurun sehingga menjadi given dalam masyarakat tertentu. Meskipun pewarisan itu melibatkan kesadaran kognitif yang tampak tidak disadari, tetapi dipicu oleh adanya kebutuhan sosial serta dukungan nilai-nilai dalam masyarakat. 50 Antara yang given dan konstruksi sosial dari pembentukan suatu budaya, karenanya, tidak bisa diklaim sebagai paling penting. Menjadi jelas, bahwa praktik sosial-budaya adalah representasi suatu ide dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu struktur masyarakat. Perspektif teoretik Bourdieu tampaknya sengaja diposisikan sebagai perangkat untuk membongkar struktur-struktur tidak adil dalam masyarakat. pembongkaran dilakukan dengan cara mencari hubungan yang tidak terlihat di belakang agen/subjek sekaligus menyelidiki persepsi-persepsi kognitif yang dimilikinya (Mutahir, 2011: 55-56). Karya-karya Bourdieu dan ulasannya sudah mulai diminati di kalangan intelektual Indonesia, terutama dalam lapangan sosiologi budaya. Model pendekatannya atas fenomena kebudayaan bahkan ditengarai sebagai yang terbaik dalam penelitian ilmu sosial (Herwanto, 2005: 184). Konsep-konsepnya digunakan dalam cultural studies untuk melihat hubungan praktik budaya dengan struktur-struktur subjektif dan objektif yang melingkupi dan menghasilkannya. Konsep-konsepnya sekaligus merupakan kritik ideologi yang bisa membongkar selubung-selubung yang mengungkung subjek dalam ketertindasan sosial budaya. Konsepnya dapat dikatakan sebagai cara keluar dari lingkaran setan dan menjadi strategi praktis melakukan objektivasi terhadap subjek. Cara ini membongkar kategori-kategori yang berasal dari ketidaksadaran manusia (Haryatmoko, 2010: 14). Dengan demikian, konsep ini melahirkan kesadaran struktural, dan mengilhami posisi khas dari aktor terhadap proses budaya, mulai dari praksis 51 perlawanan, pembelaan, dan emansipatoris. Teori Praktik dari Bourdieu di atas dapat memberi tuntunan kepada peneliti untuk melihat suatu budaya sebagai suatu praktik yang terstruktur, sehingga dengan itu praktik budaya Raju dapat ditempatkan sebagai suatu teks yang bisa dibaca secara sistematis. Dengan teori ini praktik budaya Raju bisa diuraikan aspek-aspek yang meliputinya sehingga bisa dilihat bahwa budaya ini diproduksi melalui habitus yang didukung oleh modal dan berlangsung dalam ranah tertentu. Selanjutnya dengan memahami jalinan praktik tersebut dengan aktor-aktor yang terlibat, selubung-selubung kepentingan di dalamnya dapat dibongkar. Selubung kepentingan itu sendiri bisa dilihat operasinya dalam lingkup masyarakat yang terlibat dalam relasi dengan dunia luar, berupa hegemoni kelompok dominan yang memandang Dou Mbawa sebagai ‘the other’. Oleh karena itu, penting juga penelitian ini menggunakan Teori Hegemoni untuk melihat sisi politis dari praktik budaya Raju sebagai wacana perlawanan dan resistensi masyarakat pendukungnya terhadap dominasi dari luar. Dengan demikian, dua teori ini ibarat “dua ujung tombak” yang akan membongkar dimensi-dimensi struktur ide, kepentingan, dan relasi dari praktik budaya Raju. 2.3.2 Teori Hegemoni Gramsci Hegemoni merujuk kepada fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa di sini memiliki arti luas, tidak terbatas pada penguasa negara atau pemerintah. Hegemoni bisa 52 didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa kekerasan melainkan melalui wacana-wacana yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi sehingga diterima sebagai common sense, sesuatu yang wajar. Antonio Gramsci, teoretikus dan politikus kiri yang sangat berpengaruh pada penerapan analisis Marxis pada masyarakat modern di Eropa, adalah orang yang memperkenalkan teori tentang hegemoni. Pada era 1970-an ia mengembangkan konsep ideologi dan hegemoni yang sangat penting artinya bagi cultural studies dalam melihat fenomena kebudayaan. Dengan konsep hegemoni Gramsci telah memberi perspektif bagi eksplorai makna dan gagasan sebagai faktor pembangun suatu struktur ekonomi. Gagasannya sangat mempengaruhi kaum Marxsis Barat seperti Stuart Hall yang kemudian menerapkan kembali konsep hegemoni pada lapangan budaya. Dalam pandangan Gramscian, praktik budaya, khususnya budaya populer (budaya kerakyatan) adalah situs perjuangan ideologi. Konsekuensinya, perjuangan dan konflik ideologi di dalam masyarakat menjadi arena utama politik kebudayaan. Konsekuensi metodologisnya, menerapkan analisis hegemoni dalam arena budaya adalah cara menyeimbangkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Konsep hegemoni memainkan peranan signifikan dalam pengembangan cultural studies dan menjadi konsep penting selama 1970-an dan 1980-an, karena analisis Gramsci melampaui variabel-variabel politik sebagaimana dimaknai ilmu politik konvensional. Analisisnya mencakup juga proses sosial peristiwa dan budaya sehari-hari, karena kondisi-kondisi sosial dan budaya sehari-hari memiliki 53 nilai politis dan strategis yang memungkinkan terjadinya peristiwa politik (Imam, 2010: 175). Dengan demikian, terdapat suatu makna dalam suatu praktik budaya yang ditengarai sebagai pengaturan dan prakondisi bagi kekuasaan. Proses menciptakan, merawat, dan mereproduksi seperangkat makna, ideologi, dan praktik yang otoritatif inilah yang disebut hegemoni. Bagi Gramsci, hegemoni menyiratkan suatu situasi di mana suatu ‘historical bloc’, yaitu kelompok yang menguasai jalannya sejarah, yaitu kelas penguasa menerapkan otoritas dan kepemimpinan sosial kepada kelas subordinasi melalui perpaduan antara pemaksaan dan terutama persetujuan. Dengan mengandalkan pengaruh moral dan intelektual kelompok hegemonis membangkitkan dan meraup dukungan dan persetujuan dari kelompok lain dalam struktur dan relasi kekuasaan. Dalam analisis Gramscian, blok hegemoni tidak monolitik, melainkan saling berhubungan dalam suatu formasi sosial yang membentuk landasan bagi konseptualisasi hegemoni. Ada tiga konsep utama pembentuk formasi itu, yaitu perekonomian, masyarakat politik (negara), dan masyarakat sipil. “Perekonominan” diartikan sebagai bentuk dominasi produksi dalam suatu wilayah pada suatu waktu. Perekonomian ini terdiri dari sarana teknis produksi dan hubungan-hubungan sosial produksi yang dibangun berdasarkan suatu pembedaan yang di dalamnya kelas-kelas dikaitkan dengan kepemilikan sarana produksi. “Negara” terdiri atas sarana kekerasan, seperti polisi atau militer, dalam suatu wilayah tertentu, bersama dengan pelbagai birokrasi yang didanai dan ditopang oleh negara, seperti pamong praja, lembaga pemerintah, lembaga hukum, 54 lembaga sosial dan pendidikan. Istilah “masyarakat sipil” merujuk kepada organisasi-organisasi lain dalam suatu formasi sosial yang bukan merupakan bagian dari proses produksi material dalam perekonomian serta bukan merupakan organisasi yang didanai oleh negara, tetapi merupakan lembaga-lembaga yang relatif berumur panjang yang didukung dan dijalankan oleh orang-orang di luar bidang perekonomian dan negara. Komponen masyarakat sipil yang termasuk dalam kategori ini adalah lembaga dan organisasi religius yang tidak didanai dan dikontrol oleh negara, sarana komunikasi yang tidak beredar dalam topangan dan sensor negara (Bocock, 2011: 34). Dalam jejaring struktur dan formasi sosial ini, ideologi berperan sangat penting membiarkan dan melanggengkan kelas penguasa, dalam hal ini negara dan pemilik sarana produksi, mengatasi kelas subordinat. Dengan demikian, keutuhan sosial-budaya, atau konsensus, dicapai melalui kehendak dan tujuan yang berbeda dan beragam dan diracik dalam bentuk konsepsi bersama tentang dunia. Membangun dan merawat konsepsi bersama tentang dunia itulah salah satu aspek perjuangan ideologi yang melibatkan transformasi pemahaman melalui kritisisime terhadap ideologi-ideologi populer yang ada. Hegemoni dapat dipahami sebagai strategi pemertahanan pandangan dunia dan kekuasaan kelompok sosial dominan. Namun, relasi bersifat rentan, karena persekutuan hegemoni pada dasarnya sementara, dan memungkinkan terjadi penjungkir-balikan keadaan. Hegemoni bukanlah entitas yang baku, melainkan rangkaian diskursus dan praktik yang selalu berubah menurut dinamika sosial. Hegemoni selalu berproses dalam pergulatan jungkir balik, maka terbuka kemungkinan dilakukan penantangan berupa kontra-hegemoni dari kelompok 55 subordianat. Suatu budaya yang diciptakan dan dipelihara oleh suatu kelompok dapat dipahami sebagai suatu ‘teks’ yang menghasilkan makna berbeda sebagai pengganti makna lain yang dominan. Maka dari itu, budaya adalah medan konflik, perebutan, dan perjuangan atas makna. Dalam merevisi konsep hegemoni, Laclau dan Mouffe dari post-Marxian, mengenyampingkan tujuan akhir dari hubungan-hubungan kelas sosial budaya. Bagi mereka, hubungan kelas itu tidak menentukan makna, dalam pengertian ideologi tidak memiliki ‘class belonging’ tertentu. Mereka menekankan bahwa sejarah tidak memiliki agen utama bagi perubahan sosial, dan sebuah formasi sosial tidak memiliki faktor antagonisme (Barker, 2004: 85). Pandangan ini berakar dari tesis Althusser bahwa ideologi merepresentasikan hubungan imaginer dari individu-individu pada kondisi eksistensinya yang nyata, ideologi lebih merupakan partisipasi segenap kelas sosial, bukan sekedar seperangkat ide yang dipaksakan oleh suatu kelas terhadap kelas lainnya (Althusser, 2010: 39). Dengan kata lain, perubahan formasi sosial terjadi karena hubungan yang kompleks dari berbagai faktor dalam masyarakat. Sebaliknya, blok hegemonik dan kontra-hegemonik terbentuk melalui aliansi strategis yang bersifat sementara berdasarkan kepentingan. ‘Masyarakat’ di sini tidak dipahami sebagai objek melainkan sebuah lapangan kontestasi di mana berbagai deskripsi dan makna dari berbagai subjek bersaing untuk memperoleh kekuasaan. Dalam konteks inilah peranan praktik hegemonik untuk memperbaiki perbedaan dan merekatkan makna-makna yang retak dalam diskursus kebudayaan (Barker, 2004: 85). Dalam penjelasannya mengenai hegemoni, Strinati (2009: 254) melihat 56 hegemoni sebagai sarana kultural maupun ideologis di mana kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat melestarikan dominasinya dengan mempertahankan “persetujuan spontan” kelompok-kelompok subordinat melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan maupun yang didominasi. Dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan, the ruling party (kelompok yang berkuasa). Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar dan dipraktikkan. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian rupa sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa. Dengan demikian, hegemoni bisa dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan, atau dalam bahasa Simon (1999: 23) sebagai praktik-praktik kelas kapitalis atau representasinya untuk meraih kekuasaan negara dan kemudian mempertahankannya. Jika dilihat sebagai strategi, maka konsep hegemoni bukanlah strategi eksklusif milik penguasa saja. Maksudnya, kelompok manapun bisa menerapkan konsep hegemoni dan menjadi penguasa. Dalam konteks itulah suatu praktik budaya diciptakan atau dijaga kelestariannya dan diwariskan secara turun-temurun. Berbagai studi kebudayaan memperlihatkan bahwa pada masyarakat-masyarakat tradisional, praktik budaya seperti ritual terutama diarahkan untuk menangkal atau mendekatkan kekuatan 57 gaib yang dianggap bisa membahayakan atau membantu kehidupan mereka sebagai individu atau komunitas. Kekuatan ghaib memiliki dua wajah sekaligus, wajah yang menakutkan dan wajah yang bersahabat, maka praktik budaya pun dibentuk sedemikian rupa dinamisnya sehingga bisa difungsikan sebagai tameng penangkal dan magnit penarik. Sebuah praktik budaya menjadi sedemikian kompleks. Sementara itu, pada masyarakat modern, ketika cara pandang terhadap dunia makrokosmos dan mikrokosmos berubah, di mana kekuatan-kekuatan ghaib tidak lagi punya tempat karena dianggap sebagai mitos omong kosong, praktik-praktik budaya atau ritual tidak lagi bersifat magis, tetapi juga politis. Musuh atau pahlawan manusia modern bukan lagi kekuatan adikodrati, melainkan suatu jejaring invisible thing (yang tak kasat mata), menyelubungi manusia saat ini dan di sini, bukan di luar sana dan di hari kemudian. Manusia hidup dalam suatu era post-realitas (Piliang, 2010) atau dalam kebudayaan yang super kompleks, hiper-realitas/hipersemiotika (Piliang, 2009), dan “dunia yang dilipat” yang melampaui batas-batas kebudayaan itu sendiri (Piliang, 2011). Praktik-praktik budaya diwariskan, dipertahankan, dimodifikasi, atau diciptakan baru sama sekali tidak sekedar bersifat sakral (ketuhanan), tetapi sangat profan (manusiawi), sebagai perangkat untuk mewadahi kepentingan atau menyiasati hidup. Jika masih ada unsur sakralnya, itu untuk memberi bobot mistifikasi seiring dengan masih adanya unsur sakralitas itu dalam diri manusia modern. Praktik budaya mengalami transformasi bentuk, fungsi, dan maknanya. Praktik budaya menjadi medan pertarungan. Jika pada masyarakat tradisional, pertarungan dalam medan budaya itu berlangsung untuk menghadapi atau menyerap kekuatan lain yang dianggap sakral, maka di dunia hiper-realitas 58 ini, pertarungan itu terjadi antarsesama yang hidup dalam struktur dunia yang satu namun berbeda-beda dalam aspirasi, identitas, ras, etnisitas, gender, kelas, dan agama. Budaya tidak lagi sesuatu yang dilihat bentuknya sebagaimana ia diwariskan bulat-bulat, tetapi sebagai praktik signifikasi (Barker, 2009: 9) yang menyatakan atau menjadi media ungkap bagi makna dan pengetahuan sang pencipta dan penganutnya. Praktik budaya sebenarnya adalah medan pertarungan memperebutkan makna dan kuasa pengetahuan di antara berbagai subjek berkepentingan atas hasrat-hasrat tertentu. Semua subjek itu memasuki medan budaya dengan menawarkan nilai dan makna, menukarkan, menegaskan, dan sebagainya. Praktik budaya menjadi penuh dengan makna, jalinan relasi, subjek, aktor, agen, motif, kepentingan, dan karenanya sangat ideologis. Bagi kelompok dominan yang menguasai struktur masyarakat, budaya direkayasa untuk tujuan pengukuhan dan pelanggengan kekuasaan dan dominasi, budaya menjadi alat legitimasi hegemoni. Sementara itu, kelompok-kelompok subordinasi membangun atau mewarisi suatu praktik budaya dengan modifikasi tertentu dalam rangka membungkus “perlawanan damai” atau menyuarakan “kesadaran palsu” yang mereka terima. Watak praktik budaya seperti ini terutama tampak dalam praktik keseharian, dalam budaya populer (kerakyatan), budaya massa, gaya hidup, perhelatan rakyat, budaya underground (bawah tanah), serta praktik-praktik dari kaum subaltern dan pinggiran dari kelas tertindas. Signifikansi praktik budaya sebagaimana dipaparkan di atas terlihat kental dalam masyarakat multiagama. Masyarakat berkarakter multiagama sangat intens 59 dan rentan dengan hubungan-hubungan yang pelik, yang bernaunsa konflik dan penuh ketegangan, baik bersifat laten maupun manifes. Akhir dari hubungan itu bisa berbentuk penguasaan (tirani) atau kompromi (harmoni), tetapi ada juga kategori sikap lain, yaitu pseudo-harmoni, di mana suatu kelompok menerima keadaan terpaksa dan mereka meretas suatu hidden transcripts (perlawanan diamdiam). Perlawanan diam-diam itulah mereka wadahi dalam praktik budaya. Berdasarkan uraian mengenai hegemoni dan teori praktik terdahulu, dapat dijelaskan bahwa proses hegemoni dan kontranya serta tindakan dalam ranah sosial melibatkan praktik komunikasi dengan segala perangkat dan variannya. Untuk mempertegas hal ini, maka Teori Tindakan Komunikatif dari Habermas juga penting ditilik dan diuraikan sebagai perspektif dalam penelitian ini. 2.3.3 Teori Tindakan Komunikatif Habermas Jurgen Habermas adalah salah satu punggawa Mazhab Frankfurt generasi kedua setelah trio Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Dalam upayanya mengubah wajah dunia melalui proyek ilmu sosial kritis, Habermas mengembangkan teori tentang tindakan komunikatif dan konsep mengenai ruang publik, dalam pengandaiannya mengenai situasi masyarakat yang bebas dominasi. Masyarakat bebas dominasi adalah suatu konsensus yang dicapai melalui otonomi dan kedewasaan kolektif, itulah masyarakat cerdas yang berhasil membentang komunikasi di mana satu sama lain saling memahami atas klaimklaim (Hardiman, 2009a: 18). Teori Tindakan Komunikatif berangkat dari asumsi dasar dan keyakinan Habermas pada rasionalitas pencerahan, bahwa rasio 60 manusia memiliki kekuatan pendorong untuk manusia mengetahui berbagai hal dengan pasti. Dengan kemampuan berbicara satu sama lain, manusia memiliki instrumen untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang ditemukan ketika berkomunikasi. Manusia tidak dihambat oleh kebudayaan, tak soal betapa beragam kebudayaan dan pengalaman hidup, manusia selalu mempunyai satu hal yang sama, yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi (Jones, 2010: 233). Bagi Habermas, jembatan moral antarkebudayaan harus diretas melalui sarana komunikasi, karena komunikasi adalah hal yang bisa dilakukan sepanjang waktu dan dalam kesempatan sosial mana pun. Hanya saja, dalam berkomunikasi itu harus dilandasi asumsi bahwa kesepakatan biasa dicapai tentang makna (Jones, 2010: 238). Komunikasi adalah tindakan yang rasional dari manusia yang berakal sehat dan hasilnya pun adalah makna yang juga rasional. Selanjutnya, bagi Habermas, komunikasi adalah hubungan yang simetri atau timbal balik manusia terhadap manusia lain. Komunikasi selalu terjadi di antara pihak yang sama kedudukannya. Komunikasi bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan hanya dapat terjadi jika kedua pihak saling mengakui kebebasan dan saling percaya (Suseno, 1992: 187). Habermas menyamakan komunikasi sebagai interaksi, dan itulah yang disebutnya sebagai tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif adalah interaksi simbolis yang ditentukan oleh norma-norma konsensual yang mengikat, yang menentukan harapan-harapan timbal-balik mengenai tingkah laku dan yang harus dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang bertindak. 61 Jika terdapat pelanggaran atas norma-norma yang disepakati, maka berakibat pada munculnya sanksi-sanksi dan berlakunya hukuman. Pelaku tindakan komunikatif memiliki orientasi pada pencapaian pemahaman. Dalam hal ini, kesuksesan tidak diukur dari tindakannya, melainkan dari tercapainya saling pemahaman (Hardiman, 2009b: 96). Dalam The Theory of Communicative Action, Habermas (2007a) mengemukakan, bahwa seseorang berhubungan dengan dunia kehidupan, maka dia mengalami salah satu dari tiga relasi pragmatis. Pertama, berhubungan dengan sesuatu di dunia objektif (sebagai totalitas entitas yang memungkinkan adanya pernyataan yang benar. Kedua, berhubungan dengan sesuatu di dunia sosial (sebagai totalitas hubungan antarpribadi yang diatur secara legitim/sah). Ketiga, berhubungan dengan sesuatu di dunia subjektif (sebagai totalitas pengalaman yang akses ke dalamnya hanya dimiliki si pembicara dan yang dapat dia ungkapkan di hadapan orang banyak). Ucapan komunikatif selalu melekat pada berbagai hubungan dengan dunia. Tindakan komunikatif bersandar pada proses kooperatif interpretasi tempat partisipan berhubungan bersamaan dengan sesuatu di dunia objektif, sosial, dan subjektif. Pembicara dan pendengar menggunakan sistem acuan ketiga dunia tersebut sebagai kerangka kerja interpretatif tempat mereka memahami definisi situasi bersama. Mereka tidak secara langsung mengaitkan diri dengan sesuatu di dunia namun merelatifkan ucapan mereka berdasarkan kesempatan aktor lain untuk menguji validitas ucapan tersebut. Kesepahaman terjadi ketika ada pengakuan intersubjektif atas klaim validitas yang dikemukakan pembicara. Konsensus tidak akan tercipta manakala pendengar menerima kebenaran 62 pernyataan namun pada saat yang sama juga meragukan kejujuran pembicara atau kesesuaian ucapannya dengan norma. Proses yang terjadi dalam ucapan komunikasi adalah konfirmasi (pembuktian), pengubahan, penundaan sebagian, atau dipertanyakan secara keseluruhan. Proses defenisi dan redefinisi yang terus berlangsung ini meliputi korelasi isi dengan dunia (ditafsirkan secara konsensual dari dunia objektif), sebagai elemen privat dunia subjektif yang hanya bisa diakses oleh orang yang bersangkutan. Jadi komunikasi terbentuk dalam situasi intersubjektif, di mana “situasi” tidak didefinisikan secara kaku, tapi diselami konteks-konteks relevansinya, Tindakan komunikatif memiliki dua aspek, aspek teleologis yang terdapat pada perealisasian tujuan seseorang (atau dalam proses penerapan rencana tindakannya) dan aspek komunikatif yang terdapat dalam interpretasi atas situasidan tercapainya kesepakatan. Dalam tindakan komunikatif, partisipan menjalankan rencananya secara kooperatif berdasarkan definisi situasi bersama. Jika definisi situasi bersama tersebut harus dinegosiasikan terlebih dahulu atau jika upaya untuk sampai pada kesepakatan dalam kerangka kerja definisi situasi bersama gagal, maka pencapaian konsensus dapat menjadi tujuan tersendiri, karena konsensus adalah syarat bagi tercapainya tujuan. Namun, keberhasilan yang dicapai oleh tindakan teleologis dan konsensus yang lahir dari tercapainya pemahaman merupakan kriteria bagi apakah situasi tersebut telah dijalani dan ditanggulangi dengan baik atau belum. Oleh karen itu, syarat utama agar tindakan komunikatif bisa terbentuk adalah partisipan menjalankan rencana mereka secara kooperatif dalam situasi tindakan yang didefiniskan bersama. Sehingga mereka 63 bisa menghindarkan diri dari dua resiko, resiko tidak tercapainya pemahaman (ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan) dan resiko pelaksanaan rencana tindakan secara salah (risiko kegagalan). Pandangan baru ini hendak menjelaskan makna reproduksi simbolis duniakehidupan ketika tindakan komunikatif digantikan oleh interaksi yang dikendalikan media, ketika bahasa (dalam fungsi koordinasinya) digantikan oleh media-media sepertia uang dan kekuasaan. Konversi ini menimbulkan proses deformasi infrastruktur komunikatif dunia-kehidupan yang mengakibatkan patologis dalam masyarakat. Salah satunya adalah dominasi para kapitalis. Agar tidak terjadi pengambilalihan tindakan komunikatif yang sehat akibat berkuasanya kelompok-kelompok tertentu, Teori tindakan komunikatif dari Habermas, membawa angin segar perubahan. Dunia-kehidupan bisa berjalan harmoni, ketika tidak ada pemaksaan sesuka hati dari beberapa atau kelompok orang. Pemahaman awal pengetahuan manusia mula-mula memang diterima sebagai dunianya sendiri. Tapi ketika kita berhadapan dengan dunia sosial, di mana manusia hidup, bertindak, dan berbicara satu sama lain serta berhadapan satu dengan yang lawan dengan pengetahuan eksplisit sesuatu membawanya praktik komunikatif. Sering kali hanya sebagian kecil dari pengetahuan valid. Ketika memasuki ruang sosial makan timbul persoalan-persoalan. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi intersubjektif yang membawa setiap orang menjadi otonom dengan ikatan fungsional kebaikan bersama. Atas dasar paradigma ini, Habermas ingin mempertahankan isi normatif yang terdapat dalam modernitas dan pencerahan kultural. Isi normatif modernitas adalah apa yang disebutnya rasionalisasi dunia-kehidupan dengan dasar rasio 64 komunikatif. Dunia kehidupan terdiri dari kebudayaan, masyarakat dan kepribadian. Rasionalisasi dunia-kehidupan ini dimungkinkan lewat tindakan komunikatif. Rasionalisasi akan menghasilkan tiga segi. Pertama, reproduksi kultural yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru yang muncul, tetap ada kelangsungan tradisi dan kohenrensi pengetahuan yang memadai untuk kebutuhan konsensus dalam praktik sehari-hari. Kedua, integrasi sosial yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi yang baru, koordinasi tindakan tetap terpelihara dengan sarana hubungan antarpribadi yang diatur secara legitim dan kekonstanan identitas-identitas kelompok tetap ada. Ketiga, sosialisasi yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru, perolehan kemampuan umum untuk bertindak bagi generasi mendatang tetap terjamin dan penyelarasan sejarah hidup individu dan bentuk kehidupan kolektif tetap terpelihara. Ketiga segi ini memastikan bahwa situasi-situasi baru dapat dihubungkan dengan apa yang ada di dunia ini melalui tindakan komunikatif. Dalam komunikasi itu, para partisan melakukan komunikasi yang memuaskan. Para partisan ingin membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang disebutnya “klaim-klaim kesahihan”. Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai “hasil konsensus”. Habermas menyebut empat macam klaim. Pertama, jika ada kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, berarti mencapai klaim kebenaran. Kedua, jika ada kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, berarti mencapai klaim ketepatan. Ketiga, jika ada kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, berarti mencapai klaim autentisitas atau 65 kejujuran. Keempat, jika mencapai kesepakatan atas klaim-klaim di atas secara keseluruhan, berarti mencapai klaim komprehensibilitas. Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai klaim keempat ini, dan mereka yang mampu melakukannya disebut memiliki “kompetensi komunikatif” (Hardiman, 2009a: 18). Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, akan tetapi dengan memberikan argumentasi. Habermas membedakan dua macam argumentasi, yaitu diskursus dan kritik. Diskursus dilakukan dengan mengandaikan kemungkinan untuk mencapai konsensus. Namun demikian, meskipun dimaksudkan untuk konsensus, komunikasi atau diskursus juga bisa terganggu, sehingga tidak semua berakhir pada konsensus. Habermas kemudian menyodorkan kritik sebagai cara lain membangun argumentasi. Bentuk kritik itu dibaginya menjadi dua: kritik estetis dan kritik terapeutis. Kritik estetis kalau yang dipersoalkan adalah norma-norma sosial yang dianggap objektif. Kalau diskursus praktis berkutat pada objektivitas normanorma, kritik dalam arti ini mempersoalkan dimensi penghayatan dunia batiniah. Sementara itu, kritik terapeutis adalah jika hal itu dimaksudkan untuk menyingkap selubung muslihat masing-masing pihak yang berkomunikasi. Dalam komunikasi itu yang paling penting dan menentukan adalah kontak antarindividu dan antarmasyarakat yang dijembatani oleh lambang, isyarat, dan bahasa (Kusumohamidjojo, 2009: 111). Konflik dan ketegangan akibat adanya distorsi dan keterbatasan instrumen komunikasi dan kepentingan tertentu yang menyertai pihak berkomunikasi, 66 Habermas memandang penting untuk terus-menerus memproduksi bahasa dan makna yang relevan bagi kepentingan pencapaian konsensus, agar manusia dan masyarakat tidak terperangkap dalam kebudayaan beku yang diciptakannya sendiri. Peranan ruang publik menjadi penting dalam masyarakat komunikatif, sebagai tempat pertemuan antarsubjek dan gagasan yang memungkinkan klaim komprehensibilitas dicapai. Itulah mengapa teori tindakan komunikatif harus bergandengan dengan konsep mengenai ruang publik yang dipikirkan oleh Habermas. Pengertian tentang “ruang publik” dalam pemikiran Habermas mengacu kepada kajiannya mengenai kemunculan, transformasi dan dan keterkotakan (kategori) ruang publik dalam masyarakat borjuis (modern). Dalam konteks ini, ruang publik lahir dari kondisi historis masyarakat pasar dengan ketegangan-ketegangan yang menyertainya, baik ketegangan internal di kalangan subjek borjuis maupun ketegangan antara negara dan masyarakat sipil. Ketika tampil sebagai jembatan komunikasi, ruang publik menampilkan dirinya dalam suatu metamorfosa yang sesuai jamannya, maka fungsi ruang publik dapat ditemukan dalam komunitas baca, cafe-kedai, praktik jurnalisme, sastra, dan diskusi kritis antarwarga. Dalam konteks masyarakat tradisional, perwujudan ruang publik sebagai tempat menemukan konsensus dan klaim bersama bisa ditemukan dalam ritual atau berbagai praktik budaya. Pada tataran inilah pemikiran Habermas mengenai ruang publik menjadi penting bagi penelitian ini. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan gagasan. Sebagaimana tergambar dalam kultur Barat, misalnya di Inggris dan Prancis, orang-orang dan komunitas bertemu, 67 ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan, di kedai atau galeri seni. Menurut Habermas, perubahan sosial dapat dan sering terjadi dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis. Hal itu dimungkinkan karena di ruang publik itu masyarakat sipil berbagi minat, tujuan, dan nilai,yang memicu terbentuknya visi sosial secara cair tanpa paksaan – yang dipertentangkan dengan konsep dan cara negara yang bersifat memaksa. Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung-warung kopi dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung. Misal dari ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah media massa. Pelaksanaan ruang publik merupakan tanda telah terbentuknya masyarakat madani, di mana setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk biacara, mengemukakan pendapat, serta menolak dominasi. Habermas membuat sketsa sebuah model yang disebutnya “ranah publik borjuis” yang berfungsi memperantarai keprihatinan privat individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga, yang dihadapkan dengan tuntutantuntutan dan keprihatinan dari kehidupan sosial dan publik. Ini mencakup fungsi menengahi kontradiksi antara kaum borjuis dan citoyen (kalau boleh menggunakan istilah yang dikembangkan oleh Hegel dan Marx awal), mengatasi kepentingan-kepentingan dan opini privat, guna menemukan kepentingankepentingan bersama, dan untuk mencapai konsensus yang bersifat sosial (Habermas, 2007). 68 Ranah publik di sini terdiri dari organ-organ informasi dan perdebatan politik, seperti surat kabar dan jurnal, serta institusi diskusi politik, seperti parlemen, klub politik, salon-salon sastra, majelis publik, tempat minum dan kedai kopi, balai pertemuan, dan ruang-ruang publik lain, di mana diskusi sosio-politik berlangsung. Ranah publik yang diamaksud Habermas adalah ruang diskusi kritis, terbuka bagi semua orang. Pada ranah publik ini, warga privat berkumpul untuk membentuk sebuah publik, di mana “nalar publik” tersebut akan bekerja sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara (Hardiman, 2009b: 87). Dalam konsep Habermas, media dan ranah publik berfungsi di luar sistem politis-kelembagaan yang aktual. Fungsi media dan ranah publik ini sebagai tempat diskusi, dan bukan sebagai lokasi bagi organisasi, perjuangan, dan transformasi politik. Mencermati paparan teoretik di atas dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga teori sehingga dapat digunakan secara eklektik dalam pembahasan dan analisis data penelitian. Benang merah itu adalah keterlibatan ideologi, aktor atau agen, dan sumber-sumber otoritas dalam praktik, hegemoni, dan tindakan komunikasi-ruang publik. Dengan menguraikan ketiga teori tersebut kiranya dapat dipahami bahwa praktik budaya Raju adalah sebuah tindakan sosial dalam konteks hegemoni kekuatan pemeluk agama atau budaya mainstream. Praktik budaya ini bisa dikatakan bukan saja tindakan resistensi yang sekedar bertahan, tetapi juga tindakan komunikatif yang menciptakan sebuah alternatif hubungan dalam masyarakat pluralistik untuk menciptakan harmonisasi kehidupan internal. Lebih dari itu, praktik budaya sekaligus tindakan meretas dan 69 melawan dominasi dari pihak luar. Dalam penerapannya, teori praktik digunakan untuk mengurai aspek-aspek yang mendasari produksi praktik budaya Raju, teori hegemoni dipakai sebagai sebuah lensa untuk meneropong dan mengurai operasi relasi kuasa yang tertangkap dari praktik budaya Raju, sementara teori tindakan komunikatif dan ruang publik menjelaskan fungsi dan makna budaya Raju itu melalui apa Dou Mbawa mengeksperesikan diri dan cara mereka menghadapi dominasi pihak luar. Dari sini dikonstruksi terbentuknya ruang bersama untuk mendialogkan perbedaan dan menegosiasikan identitas yang berbeda menjadi gagasan mengenai harmoni dan toleransi dalam atmosfir pluralitas. 2.4 Model Penelitian Penelitian ini menempatkan praktik budaya Raju yang dilakukan oleh Dou Mbawa di Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai fokus kajian. Dalam kaitan ini, praktik budaya Raju dikitari oleh ideologi, otoritas, dan agen dari tiga kelompok utama dalam masyarakat, yaitu Islam, Kristen, dan Parafu. Ketiga kekuatan ini bertarung untuk memperebutkan dominasi atas masyarakat, yang kemudian direspons secara kreatif oleh Dou Mbawa antara lain dengan praktik budaya Raju. Pertarungan juga terjadi secara internal dan eksternal sekaligus. Secara internal berlangsung hubungan kuasa antara komunitas adat atau agama dengan elitenya, diwakili oleh Ncuhi dan otoritas adat lainnya dengan pendukung adat, antara penganut agama Kristen dengan (pastur/pendeta), antara penganut agama Islam dengan ulama. Secara eksternal berlangsung relasi hegemonik antara pendukung praktik budaya Raju dari ketiga kelompok keagamaan di Mbawa yang 70 ‘bersatu’ dalam ‘identitas sinkretik’ berhadapan dengan kaum puritan dari agamaagama besar. Jika digambarkan, maka model penelitian seperti berikut: Gambar 2.1: Model penelitian Bagan di atas memberi gambaran bahwa penelitian ini berkenaan dengan konfigurasi Dou Mbawa yang terpetakan ke dalam tiga kelompok utama sosiokultur-religius. Dalam konfigurasi itu, penelitian ini mengambil fokus pada praktik budaya Raju sebagai “teks” dan representasi dari struktur sosial dan 71 dinamika kehidupan Dou Mbawa. Posisi praktik budaya Raju dianggap sentral karena lahir dari inti kehidupan, yaitu pandangan dunia kosmologi, dan dipraktikkan oleh ketiga kelompok keagamaan. Pada gilirannya praktik budaya Raju menjadi pusat perdebatan (kontestasi) dari kekuatan-kekuatan sosial yang berkepentingan. Islam, Kristen, dan Parafu menjadi faktor yang membentuk religiusitas dan visi sosial-politik Dou Mbawa, termasuk mempengaruhi produksi budaya. Sebaliknya, kekayaan budaya yang diwariskan kepada Dou Mbawa memberi arti bagi keislaman dan kekristenan sebagai agama yang masuk ke ranah Dou Mbawa. Jalinan terjadi sedemikian rupa di seputar kehidupan Dou Mbawa yang melibatkan ideologi, otoritas, dan agen atau aktor (elite agama), menghasilkan ketegangan dan pertarungan – internal dan eksternal – yang bermuara pada kreasi budaya dan transformasinya. Dalam situasi ini praktik budaya Raju diwarisi dan bertahan sebagai praktik komunal. Akhirnya praktik Budaya Raju menjadi tumpuan bagi Dou Mbawa untuk memproduksi nilai-nilai sosial yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan bersama dalam situasi pluralistik. Berdasarkan telaah pustaka dan mempertimbangkan urgensi masalah, penelitian ini tidak mengkaji semua aspek dalam praktik budaya Raju. Tiga hal yang diturunkan sebagai aspek kajian dalam praktik budaya Raju, yaitu basis sosial dan modal, respons hegemoni, dan makna tindakan komunikatif. Ketiga hal itu adalah ranah relasi kuasa yang memungkinkan praktik budaya Raju eksis dan dimaknai dalam konteks kehidupan komunal Dou Mbawa. Untuk menyingkap konstruksi kesadaran berpraktik, membongkar hegemoni 72 dan responsnya, dan membingkai makna komunikasi dalam praktik budaya Raju, penelitian ini menggunakan teori-teori kritis yang diramu dari teori praktik Bourdieu, teori hegemoni Gramsci, dan teori tindakan komunikatif Habermas. Ketiga teori ini digunakan secara eklektik karena memang mempunyai benang merah yang menghubungkan satu sama lain, yaitu sama-sama menyinggung peran ideologi, atoritas, dan agen dalam relasi kuasa. Dalam praktiknya, ketiga teori ini memiliki tekanan masing-masing terhadap tiga aspek penelitian, tetapi juga dalam aspek-aspek tertentu saling memperkuat.