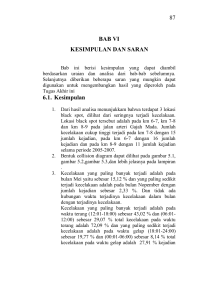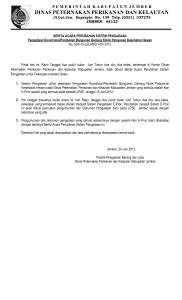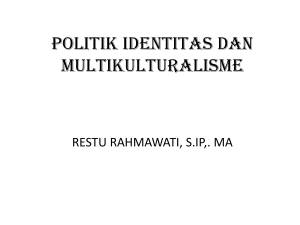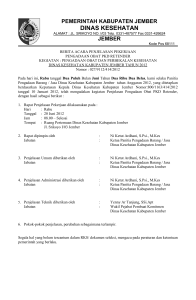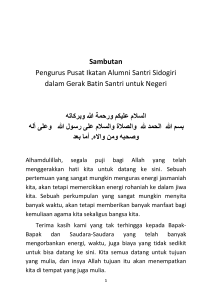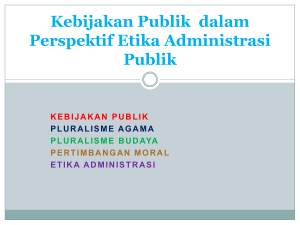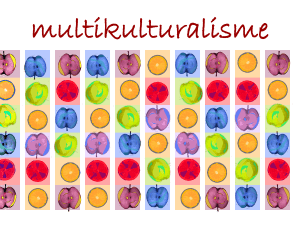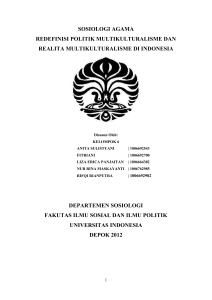pengembangan model inquiry di dalam pendidikan ilmu
advertisement

Multikulturalisme Masyarakat Kota Jember, Tinjauan Kritis Dari Perspektif Sejarah Perkotaan Rudolf Chrysoekamro IKIP Jember Abstrak Sejarah perkotaan Jember mencatat bahwa istilah ‘Pendhalungan’ sebagai wahana asimilatif dan akulturatif sangat mencitrakan kota Jember yang multikulturalis. Multikulturalisme itu seakan tak bisa membendung dinamika sejarah yang melingkupi kota Jember hingga mewujudkan citra Jember seperti apa yang dilihat kini. Kata Kunci : Multikulturalisme, Sejarah Perkotaan PENDAHULUAN Sejarah perkotaan di Indonesia sudah mulai banyak dikupas, secara ilmiah salah satunya dipelopori oleh Werthem dengan bukunya yang terkenal ‘The Indonesia Town, Study Urban Sociology’. Dalam karyanya ini ia menganalisis berbagai macam persoalan perkotaan yang sudah semakin melebar, dari yang bersifat sejarah hingga administrasi kota. Di Indonesia suatu lokasi dapat dikategorikan sebagai sebuah kota secara empiris telah melalui perjalanan sejarah tersendiri. Apabila ditilik berdasarkan periodisasi kebudayaan, maka istilah kota dapat ditemui dari jaman prasejarah, kerajaan tradisional jaman Hindu/Budha, kerajaan Islam, jaman moder dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Dari periodekeperiode kota mengalami tranformasi, baik ditinjau secara fungsionalnya, struktur hingga perubahan fisiknya. Tidak salah apabila kajian masalah perkotaan di Indonesia menjadi menarik untuk selalu dikaji, sebab masalah perkotaan akan selalu dinamis (Heddy S A P, Humaniora). Tidak terkecuali bila mengkaji tentang kota Jember, maka yang langsung dapat kita bayangkan salah satunya adalah perkebunan tembakaunya. Bila bertolak dari sini maka dapat dirunut tentang keadaan geografisnya, tenaga kerjanya, perekonomiannya dan bahkan tentang budaya yang berkembang pada masyarakat yang bermata pencaharian seperti itu yang didasarkan atas ketersediaan sumber alamnya atau ekologinya. Keberadaan Jember sebagai kota, lahirnya tepat pada jaman kolonial, tepatnya dengan dibukanya perkebunan-perkebunan oleh pihak swasta. Dikarena pada saat itu penduduknya sangat sedikit maka kebutuhan tenaga kerja diupayakan didatangkan baik dari Jawa maupun Madura. Untuk itulah dengan segala sepak terjangnya dalam upaya mendatangkan penduduk yang digunakan sebagai tenaga kerja akhirnya Jember dijadikan sebagai daerah tujuan migran pada masa itu. Seiring dengan perkembangan Jember sebagai 178 Rudolf Chrysoekamro sebuah kota maka masyarakat yang menghuni juga bertambah beragam, seperti: Osing, Arab, Cina dan tentu saja masyarakat komunitas kolonial. Keunikan Jember juga dapat ditelusuri dari pemetaan kebudayaankebudayaan dominan yang ada di Jawa Timur. Ayu Sutarto (2002), memetakan 7 kebudayaan dominan di Jawa Timur, yaitu, Jawa, Madura, Tengger, Osing, Pendhalungan, Arek, Ponorogoan. Kabupaten Jember termasuk dalam kebudayaan Pendhalungan. Disebut dan dikategorikan sebagai kebudayaan Pendhalungan adalah didasarkan atas tinjauan historis yang merupakan kebudayaan perpaduan antara budaya Jawa dan Madura. Hal ini juga didukung oleh pendapat Hatley (1984), yang membedakan apa yang disebut dengan budaya Madura di kepulauan Madura yang berbeda nantinya dengan budaya Madura di tempat barunya. Perpaduan dari bermacam-macam budaya di tempat yang sama-sama baru karena sama-sama sebagai migran inilah yang menarik untuk dikaji. Berdasar keberagaman yang dimiliki masyarakat Jember tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan. Mulai dari persoalan pemukiman, ekonomi, sosial dan tentu saja budaya. Namun demikian dikatakan oleh Evers (1982), bahwa sejarah perkembangan kota sejak hilangnya dominasi kolonial sampai dewasa ini pasti sudah ada kesadaran tentang masalahmasalah bersama, yaitu rasa ‘perkotaan’. Realitas di atas jelas menunjukkan adanya multikulturalisme. Multikulturalisme memang lazim terjadi di perkotaan. Bila itu terjadi, maka fenomena lanjutan yang bisa ditangkap adalah mengemukanya realitas masyarakat sipil. Masyarakat sipil akan muncul dengan indikator adanya situasi spesifik di mana masyarakat yang terbangun merupakan formulasi sebagai reduksi dari masyarakat barat yang menggambarkan keadaan transisi dari masyarakat alamiah (natural society) menuju masyarakat politik (political society). Masyarakat alamiah adalah masyarakat yang belum mengenal hukum, norma, dan tatanan kehidupan bersama yang tidak jarang melahirkan anarkisme dan kesewenang-wenangan. Masyarakat politik adalah arena di mana aktor politik dan lembaganya bersaing untuk menjadi pemimpin. Sedang civil society adalah masyarakat yang telah mengenal, menghormati, dan melindungi hak-hak politik masyarakat maupun hak azasi yang melekat pada setiap anggota masyarakat, yaitu masyarakat yang demokratis. Itulah sebabnya, masyarakat beradab merupakan arti lain dari civil society. Interseksi antara realitas masyarakat sipil dalam wadah multikulturalisme di kota Jember cukupmenarik untuk dikaji lebih dalam. Untuk itulah, penelitian ini akan memusatkan kajian pada ‘Fenomena Masyarakat Sipil dalam Bingkai Multikulturalisme, Studi masyarakat Kota Jember dari Sudut Pandang Interaksionisme Simbolik’. Bertolak dari penjelasan di atas penggunaan kata kebudayaan ‘dominan’ adalah merupakan identitas dari suatu kelompok masyarakat yang didasarkan atas dasar etnisitas. Identitas yang dimiliki oleh masing-masing Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 Multikulturalisme Masyarakat 179 elemen masyarakat yang berada dalam satu komunitas baru dalam berinteraksinya pasti mengalami pasang-surut. Dalam pasang-surutnya itu apakah mampu membentuk budaya baru yang disebut dengan budaya pendhalungan, ataukah hanya salah satu budaya yang menonjol, artinya ada yang tergeser. Kalau ada yang tergeser maka bagian mana saja dari unsurunsur budaya yang mengalami pergeseran. Berdasar asumsi ini maka permasalahan yang muncul adalah sejauh mana konsep masyarakat sipil dan konsep multikulturalisme dapat menjelaskan perjalanan masyarakat Jember dalam dimensi sejarah perkotaan. KAJIAN TEORI Multikulturalisme Tema tentang Multikulturalisme, menariknya tema ini disebabkan oleh berbagai alasan berikut ini. Pertama, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan multidimensional yang sangat krusial dan berimbas pada situasi krisis. Kekerasan kemudian menjadi realitas sehari-hari, baik kekerasan struktural, kekerasan fungsional, maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah benar kekerasan tersebut datang sebagai akibat dari kesalahan sistem pendidikan nasional di negara ini. Kedua, momentum penting di tahun 1998 secara ideal hendak merubah seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Reformasi merupakan kata kunci tematis dan membutuhkan kerangka implementatif yang harus ditindaklanjuti, tidak terkecuali dari kaca mata pembangunan karakter bangsa Indonesia. Pembangunan karakter bangsa Indonesia harus ditempatkan kembali sebagai basis kekuatan kultural (cultural force). Sehingga, reformasi harus ditempatkan secara proporsional dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia ini. Ketiga, pembangunan nasional (national building) linier dengan momentum reformasi memerlukan revisinya untuk menjawab tantangan bangsa ke depan. Situasi kacau dan tidak menentu itu harus dicari penyebabnya dan sedapat mungkin ditemukan penanganan solutif yang efektif. Oleh karenanya, perlu ditelusuri pendekatan apa yang sarat dengan solusi alternatif terhadap permasalahan tersebut. Keempat, masyarakat madani merupakan realitas yang menjadi harapan bersama. Hiper-realitas ini memerlukan banyak prasyarat, di antaranya kesiapan dunia pendidikan untuk memproses pendidikan kewargaan (civic education) menuju tercapainya budaya kewargaan (civic culture) dengan harapan terbangunnya masyarakat madani (civil society). Oleh karenanya, pembangunan karakter bangsa Indonesia dalam struktur dan fungsinya sangat penting dan merupakan agenda mendesak yang harus segera diselenggarakan, dan salah satu solusinya adalah mengedepankan konsep penumbuhan kesadaran hidup bersama di atas perbedaan. Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 180 Rudolf Chrysoekamro Sebagai sebuah ide, Multikulturalisme baru dibahas dan diwacanakan untuk pertama kalinya di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada Tahun 1960 oleh sebuah gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas baik itu di tempat-tempat publik, di rumah, dan di tempat-tempat kerja, maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Selama itu, di Amerika dan di negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yakni kebudayaan kulit putih yang kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan terhadap hak-hak mereka (Suparlan, 2002:2-3). Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James A. Bank (1989:4-5) berimplikasi pada dunia pendidikan dengan munculnya sejumlah tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah beberapa kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (cultural diversity). Perubahan Identitas Proses urbanisasi (pengkotaan) di negara berkembang telah terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Dijelaskan oleh Evers (1982) bahwa kotakota di Asia Tenggara pada masa kolonial ditata berdasar sistem pemisahan etnik, yang sekarang ini berkembang didasarkan atas kelas sosial. Akibatnya kelompok-kelompok etnik di kota mengalami perubahan identitas yang batas-batas etniknya semakin kabur. Diterangkan oleh Parsudi Suparlan (1989), bahwa identitas etnik adalah sebuah nilai kemasyarakatan yang dipaksakan begitu saja untuk diterimakan kepada para pendukung kebudayaan pada masa-masa formatif dari usia mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh F Barth (1969: 13), yang menyatakan bahwa identitas etnik itu bersifat askriptif, sebab dengan identitas etnik maka seseorang diklasifikasikan atas identitasnya-yang paling umum dan mendasar- yaitu berdasar atas tempat atau asalnya. Ditunjukkan oleh Barth bahwa batas-batas etnik itu tetap ada walaupun terjadi proses saling penetrasi kebudayaan diantara kelompok etnik yang berbeda. Ditambahkan oleh Lehman (1967: 106), tentang pentingnya masalah peranan yang dimainkan oleh pelaku dalam hubungan antar etnik. Bahwa dalam interaksi antar etnik sebenarnya pada pelaku itu “mengambil posisi-posisi dalam sistem-sistem yang secara kebudayaan telah didefinisikan yang mengatur hubungan-hubungan antar kelompok yang bersangkutan”. Berdasarkan hal ini, interaksi sosial dapat dilihat sebagai interaksi diantara identitas-identitas sosial yang berbeda serta perwujudannya sesuai dengan kondisi dimana interaksi sosial itu terwujud. Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 Multikulturalisme Masyarakat 181 E.M Bruner yang mencetuskan relasi antara kebudayaan dominan dengan perwujudan etnisitas dikota menyatakan bahwa kondisi yang dimaksudkan adalah mengacu pada sebuah hipotesis dominan, yang bunyinya kondisi setempat yang terwujud sebagai kekuatan sosial, yaitu apakah ada kekuatan dominan atau tidak, mempengaruhi wujud dari corak hubungan diantara suku-suku bangsa yang berbeda yang tinggal ditempat tersebut. Perubahan identitas di daerah sebagai kelompok minoritas suku bangsa yang ada di kota harus berinterksi kedalam suasana kebersamaan. Mereka memilih satu identifikasi etnik yang utama (dominan) dan mengakui yang lainnya. Fenomena ini (perubahan identitas) dapat terjadi melalui perkawinan antar suku (amalgamasi). Setiap kelompok, bagaimanapun juga menunjukkan kulturnya. Dalam penelitian Bruner diketahui bahwa adanya kebudayaan dominan pada suatu kota, perubahan identitas dari anggota kelompok mayoritas ke identitas sosial kelompok minoritas bisa saja terjadi. Aplikasi konsep kebudayaan dominan untuk melacak minoritas bisa saja terjadi. Aplikasi konsep kebudayaan dominan untuk melacak proses perubahan identitas etnik di kota adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari studi sejarah masyarakat kota. Bersamaan dengan proses percampuran etnik ada kecenderungan bahwa masing-masing etnik berusaha menjaga identitas etniknya untuk kepentingan-kepentingan kompetisi dengan etnik lain (Daldjuni, 1982: 46) karena kota adalah sebagai “melting pot”. Hal ini dapat dimaklumi sebab semakin besar jumlah kelompok-kelompok etnik di perkotaan, maka semakin besar pula heterogenitas masyarakatnya. Oleh sebab itu studi sejarah masyarakat kota dengan mengaitkan pada konteks proses urbanisasi akan lebih bernuansa. Sebagaimana yang disebut dengan kota adalah akan ditandai oleh deferensiasi vertikal (jarak sosial kelas atas dengan kelas bawah), adalah juga ditandai oleh deferensiasi horizontal (perbedaan antar kelompok etnik). Pada heterogenitas yang ditandai oleh deferensiasi horizontal, konsep kebudayaan dominan dari Edward M. Bruner relevan untuk dijadikan model penelitian dalam perspektif historis. Hipotesisnya meliputi tiga variabel, yaitu mayoritas penduduk, kekuatan budaya lokal, kekuatan politik. Kajian sejarah masyarakat kota tidak saja hanya dilihat dari aspek kependudukannya saja, melainkan dapat dilihat dari dinamika integrasinya. Sebab masyarakat kota adalah masyarakat yang dinamis untuk itu deferensiasi adalah merupakan faktor penunjang dari proses perubahan sosial. Sebab dengan deferensiasi inilah akan muncul proses integrasi pada tingkat kehidupan sosial yang lebih maju. Berdasarkan hal ini maka konsep kebudayaan Bruner dapat dipakai sebagai pisau analisis yang tajam untuk mengupas persoalan sosial kota sebagao suatu sistem. Apabila digunakan pada masa kolonial dimana sistem pemisahan etnik menjadi acuan penataan kota, dan pada masa sesudah kemerdekaan yang ditandai oleh kepentingan untuk melakukan integrasi secara mendesak. Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 182 Rudolf Chrysoekamro METODE PENELITIAN Kajian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian yang dikembangkan diupayakan demi mendapatkan detail informasi terkait multikulturalisme masyarakat Jember. Setiap detail informasi yang digali selanjutnya dikumpulkan secara cermat dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi (content analysis) merupakan teknik analisis yang memadukan dua pendekatan kualitatif sekaligus dengan pendekatan kuantitatif, di mana teknik ini merujuk pada ketepatan maknawi atas pernyataan, isi pidato, ungkapan masyarakat local, serta semua proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Analisis isi (content analysis) sebenarnya menjawab pertanyaan ‘siapa mengatakan apa, kepada siapa, mengapa, bagaimana dan dengan efek apa? Oleh karenanya analisis isi (content analysis) berupaya menemukan unit-unit hermeneutical melalui kata-kata atau pernyataan atau ungkapan yang dimaknakan. Seberapa seringkah ungkapan itu dikemukakan dan di mana saja ungkapan itu dikemukakan. Analisis isi (content analysis) mencoba mencari jejak sebuah pernyataan, ungkapan, serta percakapan dari sudut leksikal (kata apa yang sering digunakan), sudut sintaksis (bagaimana ungkapan, pernyataan itu diformulasikan), serta sudut semantic (apa yang dimaksudkan). Dalam analisis isi (content analysis) ada istilah KWIK (Key Word In Context), yakni menelusuri ungkapan atau istilah pada konteks semantic asli/original. Analisis isi (content analysis) sesungguhnya muncul sebagai alternative sebagai variasi aplikasi riset pada lingkup kajian komunikasi dan informasi serta kepustakaan (Allen & Resser, 1990). Meski awalnya muncul pada jenis penelitian kuantitatif, namun demi menutup kelemahan tradisi kuantitatif, maka penelitian kualitatif berupaya meminjam dan melengkapinya sebagai teknik analisis yang akurat khususnya pada dunia ilmu sosial, yakni sebagai sebuah metode riset untuk intepretasi subjektif atas isi teks dan pernyataan serta ungkapan melalui proses klasifikasi semantic dan identifikasi tema atau pola (Hsieh & Shanon, 2005). Analisis isi (content analysis) juga menjadi sebuah pendekatan empiris dan analisis terkontrol secara metodologis atas teks/pernyataan dalam sebuah komunikasi dengan mengikuti aturan analisis isi yang mendalam (Marying, 2000). Analisis isi (content analysis) pun merupakan reduksi data dan informasi kualitatif serta sebagai upaya pembuatan ‘rasa’ guna mendapat isi material kualitatif serta demi identifikasi keajegan fokus dan makna (Patton, 2002). Oleh karenanya, analisis isi (content analysis) kemudian banyak dikembangkan pada kajian anthropologi, sosiologi kualitatif serta psikologi dalam rangka menggali makna dari sebuah teks/ungkapan/istilah/percakapan. Analisis isi (content analysis) dalam kaitan ini, memungkinkan untuk perolehan deskripsi atas tipologi melalui Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 Multikulturalisme Masyarakat 183 ekspresi dari subjek/informan yang mencerminkan bagaimana dunia sosial memandang. Ini mengingatkan kita bagaimana konstruksi sosial dipandang oleh individu dan sekelompok individu. Analisis isi (content analysis) berupaya keras menggali makna di balik perilaku dan pikiran seseorang (Schilling, 2006). PEMBAHASAN Secara geografis, sejarah perkotaan Jember memang khas dan berbeda dengan wilayah lain. Kekhasan ini nampak pada spesialisasi daerah ini yang beriklim unik. Wilayah kota ini secara merata akan mengalami dua musim sepanjang tahun, artinya hujan masih akan turun meski di musim kemarau sekalipun, dan sebaliknya panas akan acap datang walau di musim penghujan. Model iklim seperti inilah yang secara geografis menjadikan kota Jember layak mendapat julukan daerah ‘perpaduan musim’. Daerah perpaduan ini barangkali yang menjadikan tumbuh suburnya tanaman tembakau, dengan citra dan cita rasanya khas ‘Jember’ hingga mampu menembus pasaran Eropa sejak dulu kalanya. Sementara itu, aspek demografis kota ini pun tak jauh dari kekahasan berupa dominasi pekerja buruh di masa lalu, dan makin bervariasinya struktur kependudukannya sejalan makin marak dan berkembangnya struktur dan kultur kota dewasa ini. Perkembangan aspek demografi kota ini selanjutnya menjadikan citra kota ini khas sebagai arena bagi banyak pendatang untuk mengadu dan memperbaiki nasib hidup mereka. Maka, dalam konteks demografi, kota Jember juga layak dicitrakan sebagai arena bertemu dan berkumpulnya banyak pencari kerja di masa lalu, walau sesungguhnya kota ini tidak sepenuhnya menjanjikan di masa kini. Oleh karenanya, citra yang nampak pada aspek demografi sesungguhnya lebih dekat pada tema integratif, yakni sebagai arena bagi bertemunya para pencari kerja. Secara social budaya, kota Jember sangat berbeda dengan kebanyakan kondisi social budaya kota lain. Meski agak serupa dengan beberapa kota di area tapal kuda seperti Bondowoso, Situbondo dan Probolinggo, yang membedakan kota Jember dengan kota lain di area tapal kuda adalah kompleksitas warganya baik secara sosial ataupun budaya. Memang benar apa yang pernah disebutkan oleh beberapa budayawan setempat yang menengarai kota ini sebagai pusat berinteraksinya dua budaya besar yakni Jawa dan Madura. Kekhasannya selanjutnya mewujud dalam istilah ’pendhalungan’, yang kurang lebih sarat dengan nuansa makna perpaduan yang integratif meski budaya Jawa terkesan dominan di daerah pusat kota. Namun oleh karena pertumbuhan budaya ’pendhalungan yang ’integralis’ marak hanya di pusat kota atau pada orang-orang yang bangga dengan Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 184 Rudolf Chrysoekamro status ’kota’, maka ’pendhalungan’ memang layak disandang masyarakat sosial budaya di area perkotaan Jember. Meminjam definisi budaya Julian Hoxley, dimensi mental dan pemahaman budaya Madura pada aspek seni bela diri dan tarian Islami lebih dominan di pusat perkotaan, sementara itu di daerah pinggiran ada beberapa bbudaya tarian dan seni gamelan Jawa sedikit mendominasi khususnya hanya di daerah pemukiman Jawa. Seni bela diri pencak silat serta tarian javen dan musikalitas gambus atau sejenisnya yang menyeruak dari pemukiman pesantren lebih mencolok di pusat perkotaan dan beberapa di daerah konsentrasi warga Madura. Namun kekhasannya boleh jadi mencitrakan kota Jember sebagai representasi budaya Islami atau dalam beberapa hal dicitrakan sebagai kota ’santri’, termasuk di dalamnya bagaimana budaya santri ini berhasil mengikis atau minimal mengimbangi perilaku buruk kalangan penjahat khususnya dari wilayah budaya Madura daerah pinggiran yang berdekatan areal hutan. Budaya santri ini pada perjalanannya mampu menjadi katalisator penyadaran kalangan penjahat, bahkan ada tradisi bahwa ’penjahat takut kepada santri atau kyai’. Citra sosial budaya yang mengemuka dari warga budaya Jawa di pemukimannya mewujud pada ritual ruwatan. Citra ini sebenarnya nyaris sama dengan tradisi Jawa di daerah lain. Oleh karenanya, ’ruwatan’ adalah pemahaman bawah sadar budaya Jawa sebagai sesuatu yang lazim dan wajib bagi warga Jawa. Di perkotaan, kini citra ini kian merosot sejalan dengan pemahaman religius yang kian mantap khususnya di kalangan umat Islam baik dari ormas Nu ataupun Muhammadiyah. Alhasil, citra budaya kota Jember mungkin lebih dekat pada sebutan ’kota santri’. Citra sosial budaya yang menyeruak selanjutnya adalah munculnya realitas daerah perkebunan yang memberikan konsekuensi perlunya hiburan bagi pekerja dan pegawai yang ingin melemaskan kepenatan. Pencarian hiburan menjadi keniscayaan. Bentuk dan model hiburan makin mendapatkan tempatnya, mulai dari pusat pertemuan dansa dansi di canteen, tempat pemandian, atau bahkan penginapan yang menyediakan wanita hiburan. Inilah yang menjadi paradoks bagi pencitraan kota santri. Dimensi sosial ekonomi kota Jember tempo dulu sangat mencitrakan betapa tembakau adalah penghasil utama dan berhasil mengdongkrak popularitas di mata bangsa-bangsa di Eropa. Untuk konteks ini, Jember layak disebut sebagai ‘kota tembakau’. Dimensi keagamaan menjadi faktor determinan warga kota ini, karena Islam berkembang sangat sporadis dan bahkan berakhir secara simultan seiring kedatangan warga Madura khususnya yang datang dari Pamekasan dan Sumenep yang di dalamnya menyertakan kelompok keluarga kyai Abdul hamid bin Itsbat Banyuanyar dan keluarga kyai Ibrahim Batuampar, serta yang datang dari komunitas Jawa dari Kediri semisal keluarga kyai Shidiq atau kyai Faruq. Kedatangan elemen Islam ini mempengaruhi pencitraan kota santri. Citra kota santri diperkuat oleh keberadaan pesantren yang kian banyak, berkembangnya Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 Multikulturalisme Masyarakat 185 tradisi Islam secara simultan, serta permasalahan yang melanda jamaah hajji di seluruh koloni Hindia Belanda termasuk di Jember. Masuknya pengaruh agama Kristen dan Katholik dan beberapa aliran keprcayaan dari orang-orang Jawa memang tidak boleh dikesampingkan. Namun oleh karena dominasi agama Islam terlalu kuat di kota ini, maka pencitraan kota santri layak disematkan di pundak kota ini. Pencitraan kota santri sedikit banyak turut mempengaruhi aspek politis kota ini. Di awal tahun 1900-an, seiring dengan masuknya keluarga kyai yang berpartisipasi dalam membangun dimensi kemasyarakatan kota Jember, pesantren menjadi salah satu pendobrak gerakan kemerdekaan. Layak bagi pesantren kemudian untuk disandingkan sebagai agen munculnya pahlawan kota Jember. Di awal kedatangan Jepang, pesantren di Jember menjadi kompetitor kekerasan dan disiplin yang disosialisasikan oleh penjajah Jepang. Penyebaran tradisi ilmu kanuragan oleh pesantren menjadi penyeimbang kekerasan Jepang. Citra kota santri menjadi sangat berguna di masa penjajahan Jepang. Di awal kemerdekaan, secara politis di Jember berkembang aspirasi apolitis. Tepatnya setelah Kyai Baqir bin Abdul hamid mendapatkan petunjuk atas istikharohnya terkait keberadan empat partai besar PNI, NU, Masyumi dan PKI. Keempatnya dihukumi harom. Realitas ini memberikan keteguhan sikap kebanyakan kalangan pesantren di Jember untuk menjauhi dimensi politik. Realitas berkata lain setelah masuknya zaman orde baru, di mana pemerintahan Soeharto dipandang sebagai diktator dan wajib ditandingi melalui keikutsertaan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Namun beberapa penerus tradisi apolitik masih ada yang bertahan untuk tidak terpengaruh melibatkan diri ke dalam dunia politik. Beberapa pesantren di bawah keluarga kyai Baqir bin Abdul Hamid menjadi basis sikap apolitik ini. Hingga zaman reformasipun, sikap apolitik ini masih dipertahankan beberapanya oleh sekelompok keluarga kyai pencetus apolitik, termasuk santri pengikut setia mereka. Bertolak dari realitas perkembangan pendidikan di kota ini, tidak banyak prestasi pendidikan yang cukup membanggakan warga kota. Kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan bahkan kondisi relijius masyarakat kota ini cukup menjadikan Jember kurang memiliki pencitraan positif dari sisi pendidikan. Warga masyarakat Jember tempo dulu yang sebagian besar terpola sebagai pekerja perkebunan seolah-olah mengabaikan aspek pendidikan. Kalaupun kemudian belakangan muncul geliat yang cukup signifikan, itu belum mampu menerobos dominasi kota besar lainnya dalam sektor pendidikan. Bila kualitas perguruan tinggi dipakai sebagai acuan, maka Univeritas Jember dalam perkembangannya masih berada di bawah bayang-bayang Universitas besar seperti UGM, Unair, Unbra, UI, Unpad serta beberapa perguruan tinggi besar lainnya. Kalaupun sekedar untuk disejajarkan, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto atau perguruan tinggi selain tersebut di atas barangkali berada satu level dengan Universitas Jember. Letak di pinggiran dan mengesankan Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 186 Rudolf Chrysoekamro jauh dari akses informasi bukanlah alasan mengapa pendidikan tinggi di Jember kurang berkembang. Salah satu alasan kuat barangkali adalah lemahnya jaringan alumni yang di perguruan tinggi besar menjadi salah satu faktor determinan pertumbuhan almamater. Oleh karena kondisi ini, dengan latar belakang historis Jember sebagai daerah perkebunan yang pertumbuhannya lebih dekat pada pemberdayaan sektor sosial ekonomi, sosial budaya termasuk di dalamnya memendam potensi pariwisata, maka perkembangan sektor pendidikan tidak mendapatkan prioritas pertumbuhan yang menentukan. Sehingga, dengan demikian kota pelajar belum layak disandang oleh kota Jember Dan bila harus dipaksakan, kota santri justru lebih relevan. Bukankah santri adalah juga pelajar yang banyak menghabiskan waktu belajarnya di pesantren. KESIMPULAN Dari sekian penjelasan pencitraan atas kota Jember dari berbagai aspek, muncul satu benang merah ihwal bagaimana identitas dan pencitraannya. Citra integratif sebagai kumpulan dan perpaduan elemen budaya yang akulturatif dala sebuah wadah ’dhalung’, elemen demografis yang memusat pada ethos kerja di sektor perkebunan, elemen iklim geografis yang khas dan unik, elemen aspirasi politis dengan fenomena apolitisnya, elemen agama dan kepercayaan yang sarat nilai toleransi, serta elemen sosial ekonomi yang mengemukakan julukan kota emas hijau, maka pada akhirnya tawaran untuk memberikan identitas kota ini sebagai ’kota santri’ mungkin tidak terlalu berlebihan. Sebab, hampir seluruh sendi kehidupan yang terpecah pada beberapa aspek, titik temunya tertuju pada kata ’santri’. DAFTAR PUSTAKA Allen, B., & Reser, D. (1990). Content analysis in library and information science research. Library & Information Science Research, 12(3), 251-260. Bonie Setiawan, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat Sipil, dalam Prisma No.7, 1996. Budi Winarno, Peran Elite Desa dalam Pembangunan, Suara Merdeka, 31 Juli 1990. C Wright Mills, The Power Elites, New York: Oxford University Press, 1956. De Wever, B., Schellens, T., Valcke, M., & Van Keer, H. (2006). Content analysis schemes to analyze transcripts of online asynchronous discussion groups: A review. Computer & Education, 46, 6-28. Dwaine Marvick, Elites, University of California, dalam Ensiklopedia IlmuIlmu Sosial. Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187 Multikulturalisme Masyarakat 187 Bonie Setiawan, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat Sipil, dalam Prisma No.7 1996, Larry Diamond ,”Rethinking Civil Society: Toward Democratic Concolidation”’ dalam Journal of Demacracy, Vol V.No.3, Juli 1994 Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat menuju kebebasan, Bandung, Mizan, 1994 Jeff Haynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, 2000 Ron Hatley, Mapping Cultural Regions of Java, Monash University, 1984 I Made Sujana, Negari Tawon Madu, Denpasar, Larasan Sejarah, 2001 Robert H Bates, Agrariaan Politics, Little Brown and Company, 1987 James c Scott, Moral Ekonomi Petani, LP3ES, 1981 Samuel L Popkin, The Rational Peasants: Political Economy of Rural Society in Vietnam, Berkeley, University of California Press, 1979 Olle Tornquist, Notes on the Rural Change in Java and India, in Arief Budiman, State and Civil Society in Indonesia, Clayton, Australia: Monash Papers on Southeast Asia, No. 22 Cliffort Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta, Pustaka Jaya, 1989 Kusnadi, Masyarakat Tapal Kuda, Konstruksi Kebudayaan & Kekerasan Politik, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora Vol. II No. 2.Juli 2001 Klaus Krippendorff, Content Analysis: Pengantar Teori dan Metodologi, terjemahan Farid Wajdi, Jakarta, Rajawali Press, 1991. Klaus Krippendorff, Content Analysis An Introduction to Its Methodology, London, Sage Publication Inc Hsieh, H.-F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Retrieved July 28, 2008, from http://217.160.35.246/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.pdf. Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage. Schilling, J. (2006). On the pragmatics of qualitative assessment: Designing the process for content analysis. European Journal of Psychological Assessment, 22(1), 28-37. Jurnal Progress Vol. 1 No. 2, 2012:177-187