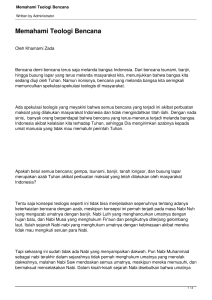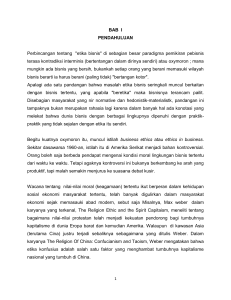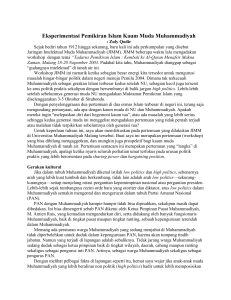pengantar - Studia Philosophica et Theologica
advertisement

PENGANTAR Studia Philosophica et Theologica. Demikian nama jurnal ilmiah terpadu disiplin filsafat dan teologi ini. Terminologi studia mengatakan kedalaman refleksi dan elaborasi. Menyeruak. Menggugah. Mencerap. Mencermati. Meneliti. Menggagas. Studia philosophica diupayakan agar disiplin filsafat makin kokoh menyumbang gagasan konstruktif kritis kepada masyarakat. Filsafat itu menyimak. Menganalisis. Mengkritik. Mengusik. Mencerahkan. Memanusiawikan. Mengajukan telaah-telaah rasional, kultural, kontekstual. Dengan studia philosophica, diharapkan nilai-nilai kemanusiaan universal makin menjadi pilihan utama peziarahan kita menuju peradaban yang lebih manusiawi. Studia theologica dijalankan agar refleksi atas iman kepada Tuhan menyumbang sinar cahaya penghayatan yang otentik, mengakar, kontekstual, dialogal. Karl Rahner SJ menulis frase menyentuh: The very concept of theology is in itself difficult and obscure ... (Karl Rahner SJ, “The Current Relationship between Theology and Philosophy,” dalam Theological Investigation XIII, 61). Benar. Teologi itu tidak dari sendirinya jelas. Maka, diperlukan studia theologica yang menyentuh realitas kontekstual dan kultural peradaban manusia-manusia di dunia, Asia, dan Indonesia khususnya. Studia terpadu disiplin filsafat dan teologi dimungkinkan, karena philosophy is the partner of theology (Karl Rahner). Refleksi mendalam tentang partnership antara filsafat dan teologi memutukan kehidupan iman, memurnikan penghayatannya dan menumbuhkan kebersamaan dalam membangun Kerajaan Allah di dunia ini. Jurnal ilmiah Studia Philosophica et Theologica ini diterbitkan secara regular untuk mendulang khasanah kekayaan berbagai disiplin filsafat dan teologi yang digumuli secara khusus dalam perguruan tinggi ini, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang. Semoga jurnal ilmiah ini menandai, mematri, mengembangkan, melestarikan tradisi intelektual yang menjadi ciri khas kokoh STFT Widya Sasana ini. Penanggung Jawab i Studia Philosophica et Theologica ISSN 1412-0674 Vol. 1 No. 1 Maret 2001 Hal. 1 - 67 DAFTAR ISI Pengantar ................................................................................................................... i Fides et Ratio: Menggagas Pertautan Filsafat dan Teologi plus Implikasinya dalam terang Ensiklik Fides et Ratio Armada Riyanto............................................................................................. 1 - 28 Rekan-Anggota dan Rekan-Pembangunan Kerajaan Allah: Pendasaran Teologis untuk Penghayatan Iman yang Merangkul P.M. Handoko ................................................................................................ 29 - 37 Allah, Universalitas, dan Pluralitas Achmad Jainuri ............................................................................................. 38 - 43 Social Construction Of Balinese World And Christianity Ray Sudhiarsa ................................................................................................ 44 - 54 On Humanism: Exploring the Concept of Humanism in Indonesia Robert Wijanarko .......................................................................................... 55 - 61 TELAAH BUKU Fifty Key Contemporary Thinkers (50 Filsuf Kontemporer) Paulus Dwintarto .......................................................................................... 62 - 63 GLOBAL/LOKAL Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia Th. X - 2000 A. Abimantrono, Lic. Th ................................................................................ 64 - 66 Biodata Kontributor .................................................................................................... ii 67 FIDES ET RATIO Menggagas Pertautan Teologi dan Filsafat plus Implikasinya dalam terang Ensiklik Fides et Ratio Dr. Armada Riyanto CM STFT Widya Sasana, Malang Abstraksi Fides et Ratio (iman dan akal budi) bagaikan dua sayap manusia untuk terbang membubung tinggi pada kontemplasi tentang kebenaran. Apa yang disebut fides adalah segala apa yang ditekuni oleh refleksi teologis. Dan ratio menjadi lapangan luas disiplin filsafat. Tulisan ini mencoba menguak pertautan keduanya, teologi dan filsafat, secara luas sekaligus menyebut aneka implikasi yang akhirnya harus bermuara pada perubahan dan pembaharuan hidup konkret komunitas manusia-manusia yang beriman. Tulisan menyuguhkan tracing history of Christian philosophy dan rincian implikasi luas relasi teologi filsafat dalam terang Ensiklik Paus Yohanes Paulus II tahun 1998, yang menegaskan peringatan 20 tahun pontifikalnya. Tulisan ini mengalirkan jalan pikirannya dalam tiga bagian: (1) pengantar tentang “ratio” dan “fides”; (2) menggagas pertautan filsafat dan teologi secara historis dalam rincian sejarah pertemuan iman dan filsafat; (3) implikasi luas dari pertautan filsafat teologi. 1. PENGANTAR TENTANG “RATIO” Manusia adalah makhluk rasional. Felix, qui semper vitae bene computat usum. Berbahagialah orang yang senantiasa menggagas pelaksanaan hidupnya dengan baik. Demikian kata seorang penyair Croatia, M. Marulic dalam Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in Cruce, v. 77. Dengan menggagas dimaksudkan memeriksa, memikirkan, memperhitungkan, merencanakan, mencermati, meneliti, setiap kali menyimak ulang. Aktivitas menggagas merupakan aktivitas rasio atau akal budi manusia. Every man has by nature desire to know. Setiap manusia dari kodratnya ingin tahu. Demikian kalimat pembuka buku monumental dari Aristoteles, Metaphysics (980a25). Manusia dari kodratnya merupakan makhluk berpikir, ingin mengenal, menggagas, merefleksikan. Tentang apa? Tentang dirinya, sesamanya, Tuhannya, hidup kesehariannya, lingkungan dunia kehadirannya, asal dan tujuan keberadaannya, dan segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya. Keinginan rasional (rational desire) ini merupakan bagian kodrati Esse manusia (keberadaan, kehadiran manusia). Karakter rasional kehadiran manusia merupakan suatu kewajaran, kenormalan, kenaturalan. Selain makhluk berpikir, manusia juga bukan makhluk pembual. Artinya, manusia bukan makhluk yang berkata-kata secara ngawur, sembarangan atau sekenanya. Manusia dari kodratnya adalah makhluk yang berpikir (atau ingin berpikir) Armada Riyanto, Fides et Ratio 1 secara benar. Recta ratio (“right reason”) adalah bagian kodrat manusia karena dia tidak pernah lega dengan sekedar “bualan” atau omong kosong. Berpikir secara benar artinya berpikir secara rasional. Aktivitas “membual” merupakan aktivitas tidak manusiawi, karena menendang prinsip-prinsip rasional yang menjadi karakter kehadirannya sebagai manusia. Pembualan merupakan diskrepansi dengan rasionalitas manusia. Rasionalitas manusia merupakan cetusan karakter tanggung jawab. Bertanggung jawab selalu berkaitan dengan soal benar tidaknya apa yang dipikirkan, diputuskan, dihidupi dalam konteks kehadirannya sebagai manusia. Karena rasionalitasnya, setiap manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap manusia dari kodratnya (harus) berpikir secara benar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya.1 Term “harus” ditambahkan dalam parentesi untuk menegaskan tuntutan karakter natural-nya. Makna “harus” merupakan konsekuensi etis sekaligus logis dari karakter tanggung jawab kehadirannya sebagai manusia. Kata “harus” dituliskan, karena berpikir secara benar bukanlah kecenderungan yang ada dari sendirinya, melainkan harus dikejar, diraih, diusahakan, dilatihkan. Karakter rasional kehadiran manusia korespondensi dengan karakter realitas. Realitas – menurut Aristoteles – bersifat intelligibilis, maksudnya realitas senantiasa dapat dimengerti atau sekurang-kurangnya pasti mengundang kita untuk dapat mengertinya. Dan, manusia mampu mengerti karena rasionya. Ilmu pengetahuan dapat dipahami (paling sedikit dalam arti Aristotelian) sebagai relasi antara manusia sebagai subyek rasional (subyek yang mengerti) dan realitas sebagai obyek intelligibilis (obyek yang dapat dimengerti). TENTANG “FIDES” FIDES dan AGAMA. Fides berarti iman, tetapi dapat pula menunjuk kepada realitas ketaatan hidup beragama. Maksudnya, di sini, iman dan agama tidak dibedakan secara real. Iman sering dihubungkan dengan ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Bagaimana persisnya ketaatan itu diwujudkan? Dalam ketaatan kepada agama. Tanpa terbelit pada diskusi epistemologis soal terminologi iman dan agama, beriman 1 Dari frase, setiap manusia dari kodratnya harus berpikir secara benar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya, dapat ditarik sekaligus skema jalinan hubungan aneka bidang atau disiplin filsafat yang lain. Misalnya, segala apa yang ada adalah lapangan penjelajahan metafisika. Berpikir secara benar merupakan tugas logika untuk melatihkannya. Apa itu berpikir menjadi pertanyaan pertama disiplin epistemologi. Makna harus berpikir (termasuk di dalamnya harus bertindak, memutuskan, mengambil penilaian) masuk dalam lapangan penelitian etika/moral, filsafat politik, moral dan yang semacamnya. Sementara tema manusia dari kodratnya merupakan tema luas bagi penyelidikan antropologi, psikologi, dan ilmu-ilmu humanities lainnya. 2 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 terealisasikan dalam hidup beragama. Berikut ini rincian pengertia tentang agama yang dapat didistingsi dalam dua kolom pengertian esensial dan eksistensial: ESENSI AGAMA EKSISTENSI AGAMA OBYEKTIF: agama sebagai realitas obyektif; konstatasi kebenaran dogmanya tak bisa diperdebatkan/ditawar SUBYEKTIF: agama sebagai suatu realitas subyektif, langsung berkaitan dengan manusia sebagai subyek beragama DOKTRINAL: agama adalah suatu “ajaran” WAHYU: agama sebagai berasal dari realitas “Atas,” diturunkan oleh Tuhan TRANSENDENTAL: agama menawarkan prinsipprinsip kebenaran yang mengatasi akal budi dan konteks hidup sehari-hari ONTOLOGIS: kebenaran yang ditawarkan absolut, mutlak, universal EKSISTENSIAL: agama sebagai kesaksian PENGALAMAN: agama adalah sebuah pengalaman relasional manusia dengan Tuhan IMANENSIAL: agama menghadirkan kebenaran yang menyentuh dan berurusan dengan konteks hidup manusia ANTROPOLOGIS: kebenaran ilahi dihadirkan dalam cara-cara manusiawi, insani, kontekstual Memahami Makna Agama. Bila berbicara tentang agama, esensi atau eksistensinya yang perlu diartikulasi? Dalam metafisika (Aristotelian dan skolastik), kita menikmati distingsi gamblang terminologi esensi dan eksistensi. Esensi merupakan hakikat, sementara eksistensi menjadi semacam “roh” yang menghidupkan. Esensi agama adalah prinsip-prinsip hakiki dari agama. Eksistensinya adalah realitas cetusan konkret hidup beragama dari manusia-manusianya. Yang pertama berkaitan dengan prinsip-prinsip doktrinal, dogmatis, normatif. Yang kedua menunjuk pada kenyataan bentuk-bentuk penghayatan eksistensial, personal, subyektif (berkaitan langsung dengan subyeknya yang beragama). Barangkali akan lebih mudah memahami makna agama dalam contoh konkret dari Injil Lukas berikut ini: Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapanNya. Lalu Yesus berkata kepada ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kataNya: “Diperboleh- Armada Riyanto, Fides et Ratio 3 kankah menyembuhkan orang pada hari Sabat2 atau tidak?” Mereka itu diam semuanya. Lalu Ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian Ia berkata kepada mereka: “Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik ke luar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?” Mereka tidak sanggup membantahnya. (Lukas 14: 1-6). ... Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. (Matius 12: 1-6). Dari kutipan contoh kisah di atas, kita bisa menarik beberapa elemen pengertian agama secara lebih kurang demikian: 1- Agama sebagai “hukum” dan konfliknya dengan realitas hidup konkret. Dalam kisah ringkas Injil Lukas di atas, terdapat dua kubu pandangan tentang esensi agama. Di sini, dengan agama dimaksudkan dalam arti luas sebagai suatu bentuk ketaatan/ketakwaan/bakti/sembah-sujud/berserah diri kepada Allah. Kubu pertama adalah kubu orang-orang Farisi (pemerhati peraturan Allah) dan ahliahli Taurat (pakar Kitab Suci). Kubu kedua adalah kehadiran Yesus. Kubu pertama jelas langsung menggagas agama sebagai suatu ketaatan terhadap hukum Tuhan, bahwa pada hari Sabat orang sama sekali tidak boleh bekerja. Yesus merevolusi cara beragama semacam ini. Yaitu, yang dikehendaki Allah ialah belas kasih. Rigoritas bakti kepada Allah hanya akan menemukan kesempurnaannya pada belas kasih, bukan persembahan. Jika kita kesampingkan kemunafikan kaum Farisi – harus kita andaikan – dari sendirinya mereka menampilkan ketaatan hukum-hukum Allah dengan motivasi untuk Allah. Yesus sementara itu langsung menegaskan bahwa suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk Allah harus langsung menampilkan kasih kepada manusia. Yang pertama mengira bahwa kebenaran transendental suatu hukum Allah meniadakan pertimbangan manusiawi. Bagi yang kedua, Yesus, yang imanensial justru meneguhkan yang transendental. Suatu kebaikan mengenai soal-soal kemanusiaan justru langsung menunjukkan penghormatan terhadap keilahian. Jika orang Farisi menampilkan cara hidup beragama dari sudut pandang legalistis, normatif, obyektif, tekstual; Yesus sebaliknya menghadirkan suatu sikap bakti kepada Allah yang eksistensial, supradoktrinal, subyektif, berpangkal pada pengalaman kehidupan konkret, kontekstual. 2- Agama pertama-tama adalah realitas subyektif, bukan obyektif. Sebenarnya agama mencakup keduanya, realitas subyektif dan obyektif. Tetapi, artikulasi utama harus diletakkan pada realitas subyektif. Mengapa? Dengan realitas subyektif, dimaksudkan realitas yang terdiri dari subyek-subyek. Agama itu pertama- 2 Inilah firman yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni sabat, hari perhentian penuh bagi TUHAN; setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api di manapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat (Keluaran 31:12-17; 35:1-3. 4 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 tama bukanlah serangkaian prinsip-prinsip suci sebagaimana ditulis di dalam Kitab Suci. Bukan tampilnya rumah-rumah ibadat yang megah yang merupakan simbolsimbol belaka. Bukan pula, bahkan, aneka rincian liturgis, ritus, persembahan, yang menyibukkan. Agama bukanlah pertama-tama realitas yang terdiri dari obyek-obyek. Agama adalah realitas dari manusia-manusia sebagai subyek-subyek beragama. Artinya, esensi agama adalah eksistensinya. Keluhuran prinsip-prinsip ajaran Kitab Suci menjadi mungkin apabila ditampilkan dalam keluhuran perilaku manusia-manusia sebagai subyek-subyek yang menghidupinya. Jika tidak, prinsip-prinsip itu tidak berbicara apa-apa. Masjid, gereja, surau, kapel, vihara, pura, sinagoga, dan seterusnya hanyalah simbol-simbol yang pada gilirannya sangat tergantung pada manusia-manusia yang datang kepadanya untuk berdoa. 3- Dari realitas subyektif, dimungkinkan relasi antarmanusia sebagai umat beragama karena nilai-nilai universal. Artinya, hidup bersama sebagai umat beragama tali temali dengan berbagai prinsip yang mengedepankan kemanusiaan. Etika ketetanggaan yang menjadi ciri khas keseharian kita bukan hanya penting, melainkan juga selaras dengan ketaatan kepada Tuhan. Etika ketetanggaan adalah etika yang mengedepankan persahabatan antartetatangga. Dalam persahabatan itu bukan hanya konflik dicegah, melainkan juga kebaikan bersama diupayakan. Etika ketetanggaan mengejar kerukunan, kerjasama, kedamaian. Etika ketetanggaan memperlakukan sesamanya bukan sebagai tamu asing yang tidak dikenal dan merepotkan, melainkan memandang sesamanya sebagai bagian dari kesibukan kesehariaan. Tetangga saya adalah dia yang menyapa dan saya sapa. Di lain pihak, saya juga sangat menghargai aneka kesibukannya sebagai yang berbeda dari saya. Kehadirannya menyapa tetapi juga memiliki otonomi sendiri yang harus saya hargai. Etika ketetanggaan bukanlah aturan, tetapi mengajukan nilai-nilai kemanusiaan. Aristoteles menggagas manusia sebagai makhluk sosial. Aristoteles hendak mengemukakan apa yang menjadi kesempurnaan kodrati manusia, yaitu kesempurnaan itu hanya mungkin dalam hidup sebagai socius (teman, sahabat, tetangga) yang darinya ditarik terminologi social, society. Etika ketetanggaan dengan demikian merupakan cetusan langsung dari kecerdasan rasional manusia dalam menggarap kesempurnaan hidupnya dan hidup bersamanya dengan yang lain. Dalam etika ketetanggaan dimungkinkan suatu cetusan makna agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Kesimpulan dari satu dua telaah di atas ialah bahwa makna fides mencakup keduanya, dimensi esensialnya dan dimensi eksistensialnya. Iman adalah kepercayaan akan kebenaran sekaligus kesaksian hidup yang benar. Iman adalah rahmat yang dianugerahkan Tuhan sekaligus pengalaman relasional manusia dengan Tuhan. Iman adalah penyerahan diri kepada yang absolut sekaligus ditampilkan dalam cara-cara hidup yang manusiawi kontekstual. Wahyu, sejauh ditujukan kepada manusia, jelas memiliki konteks. Relasi wahyu dan pengalaman konkret hidup manusia menjadi rincian pengertian iman yang hendak kita bahas dalam diskusi pertautan filsafat dan teologi. Armada Riyanto, Fides et Ratio 5 II MENGGAGAS RELASI FILSAFAT DAN TEOLOGI Mengenai tema relasi teologi dan filsafat, saya mencoba mengelaborasi empat diskursus: (1) elaborasi skema Yerusalem-Atena, (2) diskursus tradisional atau klasik bahwa filsafat adalah ancilla theologiae dan praeambulum fidei (dengan tokoh utama para filosof klasik, seperti Dionisius dari Areopagus, Agustinus, Boezius, Scotus Eriugena, Anselmus, Bonaventura dan terutama sang Doktor Angelicus, Thomas Aquinas); (3) diskursus filsafat modern (dengan perintisnya Descartes, lalu berlanjut ke para filosof rasionalis, kaum Kanan Hegelian, para eksistensialis, dan seterusnya); dan (4) diskursus filsafat postmodern (dengan tokoh Derrida, Lyotard, Vattimo Gianni, Foucault, dan seterusnya). Dalam peradaban kristiani (saya kira juga dalam agamaagama lain), agama langsung berkaitan dengan pergumulan refleksi iman kepada Allah dalam tataran konteks filsafat (yang didalamnya termasuk kultur dan aneka infrastruktur kehidupan manusia pada umumnya). Relasi Teologi dan Filsafat: Skema Yerusalem – Atena Relasi mengandaikan perjumpaan, pertemuan. Relasi teologi dan filsafat memiliki rincian sejarah konkret perjumpaan iman dan filsafat. Perjumpaan pertama iman dan filsafat – dalam sejarah iman Kristiani – direpresentasi oleh figur Paulus. Sebenarnya wahyu itu sudah dari sendirinya memiliki locus kontekstual hidup manusia dengan segala kekayaan filosofis kulturalnya. Demikian wahyu iman Kristiani. Tetapi, representasi pertemuan iman dan filsafat menemukan rincian pergumulan paling jelas pada pengalaman apostolis Paulus. Dalam buku Kisah Para Rasul, Paulus tampil sebagai sosok pewarta iman Kristiani yang memiliki otentisitas ajaran paling berwibawa dalam Gereja Awali. Dari Yerusalem dia melakukan perjalanan misioner ke berbagai wilayah. Sampailah juga di Atena. Yerusalem merupakan kota, dari mana iman Kristiani mengalir. Mengapa? Karena Kristus menderita, mati dan bangkit di sana, yang menjadi inti sari credo iman Kristiani. Yerusalem juga menjadi pusat pertemuan umat beriman. Yerusalem adalah kota di mana wahyu Kristiani menemukan locus kontekstualnya. “Kamu akan menjadi saksi-saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi!” (Kis. 1:8). Dengan kata lain, Yerusalem adalah kota iman. Sementara itu, Atena adalah kota filsafat. Atena dengan tradisi filosofisnya mendominasi peradaban kebudayaan pada waktu itu. Kisah tentang Paulus di Atena direkam singkat tetapi mengena. Dikisahkan Paulus bertemu dengan para ahli pikir (jelas maksudnya adalah para filosof) dari kalangan Epikurian dan Stoa. Mereka terlibat dalam percakapan yang intens. Beberapa filosof tertarik untuk mendengarkan ajaran “baru” Paulus. “Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini?” Dia lantas dipersilakan untuk memberikan kuliah perdananya di sidang Areopagus di hadapan para filosof. Dari sendirinya Paulus tidak akan memberikan kuliah filsafat, melainkan menjelaskan iman Kristiani. Membayangkan Paulus harus menjelaskan rincian elemen-elemen iman Kristiani di hadapan para filosof sangat menarik. Paulus mulai dengan konteks (sebuah 6 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 pendekatan kontekstual): “... aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa ... Aku menjumpai sebuah mezbah [di tengah kota] dengan tulisan: Kepada Allah yang tidak dikenal” (Kis 17:23). Penyebutan bahwa para pendengar merupakan orang-orang yang sangat beribadah, jelas manampilkan apresiasi kontekstual pewartaan. Pewartaan itu berangkat dari nilai-nilai kultural/ kontekstual setempat. Kemudian sampailah Paulus pada inti sari kuliahnya, yaitu Yesus Kristus. Siapa Kristus? Dengan keyakinan yang mantap Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah “Nama” dari pribadi Allah yang mereka sembah, yang creator, inkarnatoris, menderita, wafat, dan bangkit dari antara orang mati. “Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu,” tegas Paulus (Kis 17: 23). Sampai pada poin “kuliah” tentang kebangkitan orang mati, Paulus mengalami kesulitan. “Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata: ‘Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu.’ Lalu Paulus pergi ...” (Kis 17:32-33). Inilah kegagalan dramatis dari katekese Paulus. Pewartaannya yang dia impor dari Yerusalem mengalami kebuntuan di Atena. Teologi Yerusalem belum kompatibel dengan locus kontekstual Atena. Teologi perlu mengkontekstualisasi diri. Mengapa Atena mengejek teologi Yerusalem? “Mengejek” merupakan terminologi dari Kisah Para Rasul sendiri. Persoalannya jelas. Atena memiliki frame rasionalitas, religiusitas, dan kulturalitas tersendiri. Jika diringkas perbedaan keduanya dapat diskemakan demikian: YERUSALEM : ATENA : 1- Teologi/Iman 2- pengetahuan yang mengatasi rasional 3- berasal dari Allah 4- yang dicurahkan/dianugerahkan Allah 5- tentang kebenaran-kebenaran Allah (ditampilkan dalam rincian credo) 6- dimensi transendental 7- otoritas yang memastikan kebenaran itu 8- penyataan Allah yang relasional, personal, menyejarah dalam hidup manusia 9- PRIBADI (sang Pencipta yang mencipta dari ketiadaan) 1- Filsafat/Rasio 2- pengetahuan rasional 10- Allah yang punya nama Armada Riyanto, Fides et Ratio 3- berasal dari Natura (kodrat) 4- yang dikejar/diusahakan/dilatihkan 5- tentang segala apa yang ada, yang berhubungan dengan hidup manusia 6- dimensi imanensial, kontekstual 7- pencarian rasional manusia 8- sampai pada penemuan realitas absolut (Idea Prinsip dari segala yang ada) 9- substansi (tidak mencipta; segala yang ada mengalir dari prinsip/ Arché) 10- tanpa nama 7 Ketika masih berada di Yerusalem, iman (maksudnya fides quae atau kebenaran yang direvelasikan) demikian gamblang dan tanpa persoalan. Iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terasa tanpa persoalan, karena diwahyukan oleh Allah. Allah adalah otoritas penjamin kebenaran itu sendiri. Tetapi, ketika sampai di Athena (maksudnya iman bergumul dalam ruang lingkup, konteks, bingkai peradaban akal budi/filsafat), apa yang semula gamblang menjadi tidak serentak tanpa persoalan. Allah, sang Pencipta, yang menciptakan segala apa yang ada dari ketiadaan (creatio ex nihilo) menjadi pewartaan yang mustahil dalam alam filsafat Yunani yang sudah terbiasa dengan frase kebenaran univokal Parmenedian bahwa “segala apa yang ada, ada; dan yang tidak ada, tidak ada.” Aristoteles pun, kendati telah menggagas prinsip actus dan potentia dari ada (dan dengan demikian menghantam univositas cara pandang Parmenedian mengenai segala apa yang ada) toh tidak mampu menjelaskan dari mana dunia dengan segala isinya ini berasal. Berbeda sedikit dengan Plato, Aristoteles hanya bisa berkata bahwa dunia dengan segala isinya ini abadi (artinya telah senantiasa ada dan akan senantiasa demikian). Allah sang Pencipta dalam skema Athena korespondensi dengan sang motor immobilis (sang Penggerak yang tak digerakkan oleh yang lain) atau sang causa prima non causata (sang Penyebab yang tak disebabkan oleh apa pun) atau sang actus purus (sang Prinsip Kesempurnaan itu sendiri). Sang Sabda (Verbum) yang dariNya segala apa yang ada tercipta (Yerusalem) menjadi Logos yang darinya segala apa yang ada mengalir (Athena). Ini sumbangan filsafat Stoa. Aliran filsafat Stoa-lah yang menggagas bahwa logos adalah realitas awal/asal/cikal-bakal dari segala apa yang ada. Allah yang adalah Pribadi yang menyejarah dan terlibat dalam pejiarahan kehidupan manusia (dalam skema Yerusalem, misalnya, Allah malahan dilukiskan ikut berperang melawan bangsa Mesir, suku Amalek, bangsa Filestin, dan seterusnya), dalam skema Atena menjadi Substansi (yang jelas bukan hanya tidak terlibat dalam hidup manusia melainkan juga sukar dimengerti). Misteri Allah Tritunggal lantas mendapat perumusan rumit, satu kodrat ke-Allah-an tiga substansi (perumusan dogma iman Tritunggal dalam Gereja Katolik Timur). Pandangan lain, seperti digagas oleh Plato, ialah bahwa Allah adalah realitas tertinggi yang darinya segala apa yang ada berasal dan mengalir. Di mana kesulitan Atena menerima kuliah tentang kebangkitan orang mati, yang mengakibatkan kebuntuan pewartaan Paulus? Agak sulit dilacak. Tetapi, dari filsafat Epikuros dan Stoa satu dua alasan dapat disebutkan di sini. Bagi Epikurian, segala yang ada dapat dijelaskan dari apa yang disebut sebagai Prinsip atau Kausa intellegibilis. Artinya, realitas apa saja dapat dipahami dalam prinsip intellegibilis (prinsip yang masuk dalam lapangan kapasitas intelektual manusia). Akhir kehidupan, misalnya, dipahami oleh akal budi sebagai akhir dari penderitaan atau kesenangan yang dapat dirasakan oleh badan. Realitas badani, dengan demikian, tidak menemukan arti kepentingannya sesudah kematian. Demikian juga Stoa, aliran filsafat yang didirikan oleh Zenone ini, tidak mengajukan rincian pandangan pada pemuliaan badan sebagai badan. Stoa amat dipengaruhi oleh Plato, yang memiliki pandangan dualistis tentang manusia. Manusia adalah jiwanya. Bukan badannya. Tema Paulus yang mengajukan “hal baru” berkaitan dengan pemuliaan badan (dalam kebangkitan orang mati yang menjadi mungkin karena kebangkitan Kristus) jelas macet, buntu, 8 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 aneh. Kebangkitan badan bagi orang Yunani adalah kenaifan. Sementara bagi Paulus, kebangkitan badan adalah kemuliaan. Bahkan inti sari iman Kristiani. “Sia-sialah iman kita, jika Kristus tidak bangkit!” (Simak Kor 15 seluruhnya). Dari pengalaman Paulus ini, ada sesuatu yang baru. Yaitu bahwa mewartakan iman bukanlah sekedar berkata-kata tentang isi kebenaran iman. Pewartaan bukanlah pemberitahuan tanpa perduli konteks siapa pendengarnya. Pewartaan iman tidak bisa hanya doktrinal, melainkan inkultural. Tidak hanya memberikan informasi, melainkan menawarkan transformasi. Teologi tidak hanya berbicara tentang Allah, melainkan tentang Allah dalam konteks lapangan kehidupan manusia. Dari pengalaman ini, seakan-akan tampil suatu model teologi baru, yaitu teologi antropologis. Maksudnya, teologi tidak bertolak dari ajaran tentang Allah, melainkan berangkat dari realitas alam pikir dan mentalitas manusianya yang menerima ajaran tentang Allah tersebut. Maksudnya bukan untuk merelativir kebenaran ajarannya, melainkan justru untuk memfasilitasi pendengar untuk menyambut kebenaran iman dan mengakarkan penghayatannya dalam hidup. Tetapi, dari pengalaman Paulus, muncul pula reaksi penyangkalan terhadap filsafat. Tertullianus, salah satu Bapa Gereja apologetis, berpendapat bahwa kebijaksanaan filosofis hanyalah kesia-siaan belaka. Tidak ada keserupaan antara filosof Yunani dan seorang yang beriman Kristiani.3 Iman mengatasi rasio manusia. Ungkapan yang amat terkenal dari dia ialah credo quia absurdum (saya percaya karena absurd). Bagi Tertullianus, untuk sampai kepada Tuhan cukup sekedar jiwa berserah diri. Kultur filosofis tidak ada gunanya. Namun demikian Ambrosius, Agustinus, Origenes dan para Bapa Gereja yang lain tidak sejalan dengan Tertullianus. Mereka memandang bahwa filsafat sangat berperan dalam refleksi iman Kristiani. Dan, sebaliknya. Iman Kristiani mempengaruhi diskursus filsafat, mentransformasikannya dan membabtisnya. Pada periode BapaBapa Gereja memang terjadi apa yang lebih tepat disebut sebagai “kristianisasi” filsafat Yunani. Filsafat Yunani mulai menyibukan diri dalam urusan iman Kristiani. Apa pengaruh iman Kristiani terhadap filsafat Yunani? Pertama, konsep monoteisme Kristiani menggeser politeisme Yunani. Berikutnya, prinsip penciptaan dari ketiadaan (creatio ex nihilo) mendominasi tema-tema refleksi antara realitas konkret dan realitas absolut. Panteisme tidak lagi dominan. Konsep Allah sebagai pribadi yang inkarnatoris memungkinkan pemahaman dunia yang antroposentris jelas menggantikan tema-tema diskusi kosmologis mengenai dunia hidup manusia. Pengertian hukum kodrat dalam filsafat Yunani yang amat rasional “dibaptis” menjadi pengertian yang lebih teologal, yaitu hukum itu berasal dari Allah. Ketidaktaatan terhadap hukum Allah adalah dosa dan mengakibatkan keterpisahan manusia dari Allah. Tema tentang “cinta” Kristiani yang berasal dari Allah menggantikan diskusi filosofis cinta yang bertumpu hanya dari pengalaman manusiawi (yang dalam filsafat Yunani sangat terbatas rincian pengertiannya). Dengan demikian juga aneka keutamaan lain yang mengalir dari cinta menikmati pembahasan filosofis yang mendalam pada periode ini. Persoalan 3 Tertullianus, Apologetico, XLVII (terj. E. Buonaiuti, Laterza). Armada Riyanto, Fides et Ratio 9 keabadian jiwa manusia sebagaimana sangat diminati oleh filsafat Yunani, pada periode Patristik, menemukan pemaknaan teologis. Jiwa manusia menyatu dengan Sang Pencipta. Tema yang menyeruak hebat, tentu saja, juga soal kebangkitan badan. Filsafat Yunani tidak memiliki minat terhadap soal ini. Tetapi, filsafat patristik mempromosikannya dalam cara yang amat mengesankan. Pendek kata, filsafat pada periode Bapa-Bapa Gereja telah menampilkan transformasi pilihan refleksi yang luas dan mendalam tentang iman Kristiani.4 Pseudo-Dionisius dari Areopagus (penulis memakai nama “Dionisius dari Areopagus” karena mengidentikan dirinya sebagai salah satu filosof yang ikut hadir dalam kuliah Paulus di Atena di hadapan sidang Areopagus) merupakan salah satu filosof Kristiani awali yang mengeksplorasi filsafat Plato untuk menjelaskan iman Kristiani. Dari Dionisius Areopagus ini, filsafat Platonian mengalir ke Agustinus, Thomas Aquinas dan kebanyakan filosof Mediovale. Diskursus tradisional: ancilla theologiae & praeambulum fidei. Pengalaman Paulus mengenai kebuntuan pewartaan dan ketidakmampuan Atena menyambut iman Kristiani inilah antara lain yang menjadi awal rincian episode elaborasi filsafat sebagai ancilla theologiae dan praeambulum fidei. Ancilla theologiae (pembantu wanita teologi) merupakan terminologi yang dikatakan oleh para Bapa Gereja, dan menjadi terkenal dalam filsafat Thomas Aquinas. Praeambulum fidei artinya bahwa filsafat merupakan pendahuluan, pembuka, pengantar iman. Memang, kalau orang belajar prinsip kausalitas Aristotelian, misalnya, penelusuran “sebab-sebab” secara rasional akan sampai pada sang Sebab Pertama yang harus diakui oleh budi manusia. Sama halnya dengan prinsip Leibnizian, prinsip “cukup-alasan” (sufficient reason), yang dipakai sebagai pembuka bahan perdebatan mengenai pembuktian eksistensi Allah oleh Romo Frederick Copleston SJ dengan Bertrand Russell. Dalam prinsip cukup-alasan, jika disimak secara mendalam alasan masuk akal dari segala apa yang ada – yang harus diakui benar oleh rasio manusia – ialah realitas ilahi, Allah sendiri. Sebagai ancilla theologiae, filsafat bak pembantu wanita yang setia bertugas memudahkan manusia memahami secara rasional aneka misteri iman yang diwahyukan Allah. Wahyu sering kali tidak masuk akal. Filsafat membantu sedemikian rupa bahwa misteri iman yang tidak bisa dipahami oleh budi manusia sepenuhnya itu tidak berarti irrasional. Contoh paling konkret ialah mengerti secara rasional misteri Allah Tritunggal. Dalam membantu mengerti misteri Tritunggal Mahakudus, filsafat mengajak kita menyadari bahwa bahasa manusia itu terbatas. Memahami realitas pun orang tidak boleh gegabah. Diperlukan kesadaran rasional mengenai pemaknaan bahasa yang digunakan. Dalam kaitannya dengan memahami misteri Allah, bahasa manusia sangat bersifat analogal. Artinya, sebagian sama sebagian berbeda. Maksudnya, kata “satu”, “tunggal”, “tiga” dalam Tritunggal Mahakudus tidak memaksudkan bilangan (seakan- 4 10 Cf. Giovanni Reale – Dario Antiseri, Storia della Filosofia: Dall’Antichita’ al Medioevo, Editrice La Scuola, Brescia 1993, 394. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 akan Allah bisa dihitung; atau seakan-akan Allah bisa dimasukkan dalam kategori kuantitas). Makna “satu” memaksudkan keutuhan, kesempurnaan (Allah adalah Dia itu sendiri), sedangkan makna “tiga” yang menunjuk kepada realitas “pribadi yang distingtif” memaksudkan relasi atau kodrat relasionalnya. Jadi, Allah Tritunggal adalah Allah yang sempurna dan relasional dalam kodrat ke-Allah-annya yang sempurna. Relasi macam apa? Kesempurnaan semacam itu hanya bisa dijelaskan dalam relasi kasih.5 Dengan demikian, revelasi Allah adalah komunikasi diriNya, komunikasi kasih. Mengenai diskursus ancilla theologia dan praeambulum fidei, Thomas Aquinas, Agustinus, Dionisius dari Areopagus, Anselmus, Bonaventura (yang menulis Itinerarium Mentis in Deum atau Pejiarahan Budi menuju ke Allah yang secara tegas menjelaskan bahwa pengembaraan budi manusia akan sampai kepada Allah!), Scotus Eriugena adalah tokoh-tokoh terdepan yang tidak boleh dilupakan oleh para filosof dan mahasiswa filsafat penyoal eksistensi Allah. Bagi Agustinus, sebagaimana juga para filosof Mediovale yang lain, iman mencari pengertian. Fides quaerens intellectum. Artinya, iman tidak ngawur. Tidak membabi buta. Iman mencari dan berkelana mengejar pengertian yang benar. Beriman kepada Tuhan berarti terus mencari pengertian tentang Tuhannya. Di lain pihak, menurut Agustinus, jika tidak beriman tak mungkin mengerti Tuhan. Maksudnya, pengetahuan akan misteri Tuhan sangat meminta syarat beriman, berserah diri sekaligus mencari tiada henti. Inquietum est cor meum donec requiescat in te (gelisah hatiku sampai beristirahat di dalam Engkau) melukiskan pergumulan Agustinus yang beriman sekaligus terus gelisah untuk mencari pengertian tentang imannya. Thomas Aquinas yang menjadi representasi filsafat mediovale merupakan figur yang menggabungkan keduanya, teologi dan filsafat. Dialah yang mengawinkan antara filsafat dan teologi dalam suatu cara yang amat sistematis. Thomas Aquinas – seperti para filosof pendahulunya – mengelaborasi pengertian-pengertian misteri Ekaristi, perubahan dari roti menjadi tubuh Kristus dan dari anggur menjadi darah Kristus. Transubstantiatio merupakan terminologi filosofis yang diadopsi untuk menjelaskan misteri Ekaristi. Teologi Thomas memiliki karakter filosofis. Dan filsafatnya memiliki rincian pembahasan tema-tema teologis. Diskursus modern: rasionalisme dan sistematisasi iman. Sesudah Doktor Angelicum, Thomas Aquinas, gaya berfilsafat yang memesrakan hubungan antara iman dan filsafat mengendor. Berbarengan dengan itu, muncul jaman baru yang lebih mengedepankan nilai-nilai kodrati manusiawi. Abad ini disebut Abad Renaisan. Renaisan berarti “lahir kembali.” Artinya, manusia mulai memiliki kesadaran-kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Manusia seperti mengalami kelahiran kembali dalam menggarap kehidupannya. Jika dalam Abad pertengahan, nilai-nilai manusia direlatifkan pada nilai-nilai keilahian 5 Cf. Armada Riyanto, “Allah Tritunggal,” dalam Agama Anti-Kekerasan, Malang 2000. Armada Riyanto, Fides et Ratio 11 karena iman, jaman Renaisan memegang teguh kodrat manusia yang luhur dalam dirinya sendiri. Jaman Renaisan disebut jaman “kelahiran kembali,” karena suasana gaya dan budaya berpikirnya memang melukiskan “kembali kepada semangat awali,” yaitu semangat jaman filsafat Yunani kuno yang mengedepankan penghargaan kodrat manusia sendiri, tidak dalam hubungannya dengan agama. Jadi, jaman Renaisan adalah jaman pendobrakan manusia untuk setia dan konstan dengan jati dirinya. Jaman ini sekaligus menggulirkan alur semangat baru yang menghebohkan terutama dalam hubungannya dengan karya seni, ilmu pengetahuan, sastra dan aneka kreativitas manusia yang lain. Galileo Galilei adalah contoh filosof dan ilmuwan sekaligus yang revolusioner produk dari abad Renaisan. Ia mengembangkan keilmiahan budaya berpikir. Demikian pula Thomas Hobbes, salah satu perintis filsafat politik modern yang menjadi cikal bakal teori-teori individualisme – liberalisme – kapitalisme berada pada suasana jaman ini. Newton, salah satu pendekar ilmu fisika dan pencetus teori gravitasi, juga hadir pada zaman ini. Lantas, Bacon dengan jargon kritisnya bahwa science is power mendobrak kebekuan cara berpikir tradisional (abad pertengahan). Bila Abad pertengahan memegang teguh konsep ilmu pengetahuan sebagai rangkaian argumentasi, jaman Renaisan merombaknya dengan paham baru bahwa ilmu pengetahuan itu soal eksperimentasi. Pembuktian kebenaran bukan lagi pembuktian argumentatif dan spekulatif, melainkan eksperimental, matematis, kalkulatif. Metode semacam ini menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan alam modern. Sebuah pendekatan yang meminta verifikasi eksperimental dan bukan argumentasi spekulatif. Sesudah Renaisan, muncul gelombang cara berpikir baru yang disebut dengan “jaman modern”. Rene Descartes adalah perintisnya. Dengan Descartes, filsafat tidak lagi bertolak dari esse (ada), melainkan conscientia (kesadaran). Dengan kata lain, berfilsafat tidak lagi berangkat dari obyek yang dipikirkan, melainkan dari subyek yang memikirkan. Pengetahuan budi manusia tidak lagi merupakan pengetahuan obyektif, melainkan pengetahuan intuitif atau subyektif. Artinya, jika dalam Aristoteles pengetahuan budi manusia pertama-tama adalah soal korespondensi dengan realitas obyektif, dalam Descartes pengetahuan manusia berangkat dari kesadaran sendiri mengenai ada kita (bukan pertama-tama berkaitan dengan realitas obyektif). Cogito ergo sum. Saya (subyek) berpikir atau menyadari, maka saya ada. Pandangan ini memiliki konsekuensi revolusioner. Penegasan cogito ergo sum dapat dikatakan membalik gaya berpikir Aristotelian. Dengan Descartes, pengembaraan budi manusia tidak lagi berurusan dengan realitas obyektifnya, melainkan menemukan pusatnya pada rasionalitas manusia. Filsafat mengalami revolusi metodologis (beranjak dari subyek, bukan dari obyeknya) sekaligus perubahan obyek materialnya (bukan lagi mempersoalkan korespondensi atau diskrepansi budi manusia dengan realitas, melainkan menguji rasionalitas manusia). Mulai dari jaman inilah rasionalisme mulai menguasai pengembaraan budi manusia. Manusia secara tegas dimengerti sebagai res cogitans, entitas yang berpikir, yang rasional. Rasionalisme mengalami puncaknya pada Immanuel Kant yang memproklamasikan bahwa kebenaran sejati pengetahuan manusia ialah pengetahuan a priori, pengetahuan yang diproduksi oleh struktur akal budi manusia sebelum (atau tidak berdasarkan) pengalaman dengan sistem aneka kategori imperatif yang 12 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 sudah terpatri dalam budi manusia. Kant bukan saja menegaskan bahwa kesadaran kita tertutup sama sekali dari res in se (realitas obyektif di dalam dirinya sendiri), melainkan juga menggariskan sistem pengetahuan dalam rasio murni manusia. Jika dalam Aristoteles kategori-kategori adalah leges entis (aneka tata realitas segala apa yang ada), dalam Kant kategori-kategori menjadi leges mentis (aneka tata pengetahuan transendental dalam akal budi manusia). Rasionalisme bukan cuma pengedepanan akal budi dan pembelakangan segala sesuatu yang tidak berpartisipasi di dalamnya. Peradaban rasionalisme secara ekstrim dan menyolok identik dengan pembangunan atau konstruksi sistem-sistem di segala bidang kehidupan manusia. Apa maksudnya konstruksi sistem di segala bidang kehidupan? Maksudnya konstruksi itu merambah pada sistem hubungan antara subyek dengan obyek (dalam taraf epistemologis); pada sistem hubungan antara subyek dengan tingkah lakunya sendiri (dalam taraf etis/moral/eksistensialis/psikologis/ psikodinamis); pada sistem hubungan antara subyek dengan dunianya (dalam taraf kosmologis/fenomenologis), dengan sesamanya atau lingkungan masyarakatnya (dalam taraf sosiologis), dengan dunia materi-ekonomisnya (dalam taraf ekonomis/politis yang mencetuskan aneka sistem ideologi kapitalisme, sosialisme, Marxisme, dan seterusnya); pada sistem hubungan antara subyek dengan Tuhannya (dalam taraf teologis/doktrinal agama atau segala sesuatu yang secara organisasional dan spiritual menunjuk kepada agama). Konstruksi rasionalis sistem kehidupan mencapai puncaknya pada Abad Pencerahan dan idealisme Hegel. Filsafat hegelian – konon – merupakan sistem filsafat itu sendiri. Idealisme Hegelian dengan sistem “Dialektika Roh,” menurut Habermas, secara meyakinkan menjadi representasi absolut konstruksi sistem filsafat rasionalisme Abad Pencerahan. Nanti Marx membumikan sistem dialektika hegelian pada taraf materialis ekonomis. Konstruksi sistem tetap dibela (tesis-antitesis-sintesis), tetapi relevansinya menyentuh realitas hidup konkret. Pada taraf historis, sistem ini mengejawentah dan terealisasikan dalam pertentangan antara kelas borjuis/pemilik modal dengan kelas proletariat/buruh yang akan mensintesis menjadi masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis. Dalam peradaban modern yang “homogen” oleh ambisi para filosof rasionalis konstruktor sistem realitas, bagaimanakah teologi? Para teolog mendadak harus bekerja keras untuk menjawabi tantangan peradaban. Kaum Kanan Hegelian mencoba mengawinkan sistem canggih yang pernah digagas oleh manusia Hegel dengan refleksi iman. Iman pun disistematisasikan sedemikian rupa. Bulan madu filsafat dan teologi dalam skema ancilla theologiae dan praeambulum fidei yang menjadi tidak mungkin karena pudarnya pamor filsafat Aristotelian dan Platonian, oleh para teolog dicoba dibangkitkan lagi dengan dialektika Hegelian. Yaitu, dialektika sebagai metode yang memungkinkan pencapaian pengetahuan akan yang absolut dalam arti Hegelian diambil untuk pencapaian pengetahuan akan Tuhan dalam iman. Dalam filsafat eksistensial Kierkegaard nantinya, upaya untuk menteologikan konstruksi sistem Hegelian menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Refleksi tentang Tuhan hanya menjadi mungkin oleh pengalaman pergumulan hidup manusia sebagai single (eksistensi unik) dalam penderitaan, kecemasan, ketakutan, harapannya. Kaum Armada Riyanto, Fides et Ratio 13 Kanan Hegelian hanyalah salah satu kelompok para pemikir Kristiani yang gerakannya masih diliputi nostalgia mentalitas manusia Abad Pertengahan. Mereka mengira dengan “mengemas” teologi dalam skema konstruksi filsafat Hegel mampu menjawabi tantangan peradaban rasionalis. Kierkegaard, sebaliknya, meyakini bahwa sudah tidak diperlukan lagi sistem-sistem canggih yang hanya berada dalam level rasional untuk mengefektifkan pengalaman akan Tuhan. Tetapi pengedepanan eksistensi manusia oleh Kierkegaard – yang lantas berlanjut pada penyembahan altar the self – juga tidak meyakinkan. Pemusatan pergumulan pengalaman dengan self-center justru menggiring peradaban kepada subyektivisme yang menghantam aneka kebenaran iman yang secara obyektif benar, kekal, abadi, menyelamatkan. Mentalitas self-center dewasa ini menjadi tantangan tidak kurang runyamnya bagi aktualitas dan relevansi iman. Diskursus postmodern: pemberontakan atas sistem-sistem Apakah Postmodernisme? Postmodern adalah gelombang cara berpikir, yang secara sepintas dapat disebut, “sesudah” filsafat modern. Postmodern memandang sistem-sistem, prinsip-prinsip, metode-metode, ide-ide yang pasti, sahih dan rasional yang menjadi ciri khas filsafat modern telah rontok dan ketinggalan jaman. Ketinggalan jaman artinya kehilangan legitimasinya, kehilangan aktulitas dan relevansinya. Seperti sering dikatakan, filsafat modern adalah cetusan kebudayaan rasionalisme Barat. Postmodern memproklamasikan bahwa peradaban rasionalisme Barat telah rontok seiring dengan berkembangnya peradaban baru yang mendobrak bentuk-bentuk kemapanan di segala bidang kehidupan manusia. Sistem ideologi telah mati. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah terbukti malah tidak makin memanusiawi. Aneka macam sistem pemerintahan demokrasi dan yang lain hanyalah legitimasi bentuk-bentuk korupsi (tengok tidak perlu jauh-jauh, pengalaman Indonesia!). Agama dan segala macam bentuk refleksi mengenai Allah atau siapa saja yang diallahkan hanyalah pemecah belah kesatuan dan pendera kehidupan manusia yang damai. Postmodern adalah gelombang filsafat kritis, atau lebih tepat, filsafat “tidak”. Maksudnya postmodern memproklamasikan tidak-sistem, tidak-konstruksi budaya, tidak-keseragaman, tidak-aneka paket-paket atau pola-pola mati mengenai bidangbidang kehidupan kehidupan. Dalam artian ini postmodern adalah gelombang filsafat yang secara dahsyat menggoyang Enlightenment (Abad Pencerahan) yang menjadi kebanggaan sekaligus legitimasi setiap konsep kemajuan pembangunan, teknologi, ideologi, ilmu pengetahuan. Karakteristik abad Pencerahan yang berupa: (1) faith in the European Reason and human Rationality to reject the tradition and the pre-established institutions and thoughts, dan (2) search for the practical, useful knowledge as the power to control nature,6 telah ketinggalan kereta peradaban 6 14 Jadi ada dua karakteristik: pengedepanan rasionalitas manusia di satu pihak (dan ini memiliki konsekuensi penolakan atas tradisi yang sudah ada, atau berarti tradisi agama – Kant membahasakannya sebagai saat Vol. 1 No. 1, Maret 2001 manusia yang telah sampai pada titik kekompleksannya. Menuturkan kegagalan mentalitas kemodernan, Postmodern menunjuk pada aneka macam penindasan dengan segala dalih yang justru bertentangan dengan akal budi manusia itu sendiri, seperti holocaust yang mengerikan untuk pengunggulan ras Aria (Jerman), aneka pembunuhan dan intimidasi yang brutal dalam revolusi masyarakat komunis di Rusia dan di berbagai tempat di dunia, revolusi kaum Islam Shiah di Iran, pemberontakan masyarakat demokratis di Revolusi Perancis, juga aneka tindakan pembabatan komunis dengan segala kaumnya oleh para penegak Orde Baru di Indonesia – yang kebrutalannya hampir semua direlatifkan pada alasan-alasan ideologi, agama, dan aneka paham represif yang lain. Atau perpecahan dan pertikaian sangat mengerikan yang terjadi di eks-Yugoslavia atas nama keadilan ras/agama/suku/demokrasi dan tetek bengek yang lain. Jürgen Habermas manyadari semua kegagalan kemodernan itu. Tetapi dia tetap setia hendak melanjutkan program modernisme dengan mengajukan sistem teori emansipatoris dan pencerahan baru, yaitu masyarakat komunikatif, masyarakat yang mengajukan pola-pola hubungan komunikatif, emansipatoris, kritis bukan dengan jalan kekerasan melainkan dengan diskursus argumentatif. Menurut Habermas, masyarakat yang demikian itu mengandaikan konsensus untuk menciptakan komunikasi yang menyatukan. Caranya? Komunikasi itu harus mencapai klaim-klaim validitas kesepakatan: tentang dunia obyektif, kita harus mencapai klaim kebenaran (truth); tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia moral dan sosial, kita harus mencapai klaim ketepatan (rightness); tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, kita mesti mencapai klaim otentisitas (sincerety); dan tentang penjelasan atas macam-macam klaim di atas, kita harus mencapai klaim komprehensibilitas (comprehensibility). Tetapi, cita-cita Habermas dipandang utopis oleh para Postmodernis, misalnya oleh Lyotard. Lyotard justru membalik utopia Habermas ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Seluruh usaha untuk meraih klaim-klaim kesepakatan seperti itu justru memperkosa kodrat heterogenitas ilmu pengetahuan dan kemajuan pluralitas peradaban manusia. Sistem Habermasian yang demikian tentu saja sangat ambisius. Habermas mempolakan kehidupan pada level frame-frame yang indah dan mempesona, tetapi sejarah mencatat strategi semacam itu tidak lebih dari mendulang manusia bangkit melawan inferioritasnya dari kungkungan hegemoni tradisi agamis, dan dengan demikian saat manusia berdiri di kaki sendiri) dan pencarian cara-cara baru untuk mengontrol alam demi menggapai kemajuan di lain pihak (secara konkret mulai dalam ilmu-ilmu pengetahuan empiris, eksperimental untuk mencari jalan bagaimana mengembangkan kehidupan manusia – dalam lapangan epistemologis / ilmu pengetahuan John Locke termasuk menjadi pionir untuk urusan ini karena ia mengajukan tesis bahwa pengetahuan manusia itu diasalkan dari pengalaman). Dua karakteristik ini memadu sedemikian rupa dalam kehidupan manusia sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa abad Enlightenment adalah abad rasionalitas manusia. Sistem sebagai demikian diakarkan pada mentalitas gelombang filsafat yang demikian. Di Perancis, pada abad ini produk monumentalnya direalisir dalam pembuatan ensiklopedia untuk pertama kalinya pada tahun 1770: tentang ilmu pengetahuan, seni, dan profesi. Ensiklopedia ini muncul sebagai suatu sistem baru dalam memberdayakan rasio manusia untuk menggariskan sistem kehidupan secara keseluruhan pada taraf kognitif. Armada Riyanto, Fides et Ratio 15 kegagalan yang telah berulang-ulang terjadi. Demi aneka klaim-klaim kebenaran semacam itu, berapa ratus juta manusia telah dikorbankan! Demikian antara lain komentar sinis para postmodernis. Kaum postmodern tidak percaya akan emansipasi dan pencerahan yang dijanjikan oleh Habermas. Postmodernisme pertama-tama diinspirasikan oleh Nietzsche yang kritis terhadap rasionalitas modern dan memandang bahwa rasio – yang telah menjadi dewa Abad Pencerahan – hanyalah bersifat komplementer belaka. Maka, rasio tidak mungkin menjadi segala-galanya bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, juga segala sistem yang diproduksi oleh rasio secanggih apa pun (misalnya secanggih seperti yang digagas oleh Hegel) tidak valid sedemikian rupa. Terminologi “postmodernism” menunjuk pada “post-strukturalism” (1960an) di Perancis: gerakan ini menolak kemungkinan pengetahuan obyektif tentang dunia nyata, “univocal” meaning words and texts, the unity of the human self, the cogency of the distinctions between rational inquiry and political action, literal and metaphorical meaning, science and art, and even the possibility of truth itself. Filsafat postmodern adalah filsafat tidak. Tidak kepada apa? Postmodern berkata tidak kepada pengetahuan immediately presented; kepada origin; kepada unity; kepada transendence; kepada book. Postmodern mengajukan apa yang disebut sebagai the idea of constitutive otherness. Rincian ide-ide yang disangkal ini mendominasi diskusi filsafat postmodern. Postmodern menolak paham-paham pengetahuan yang berkarakter immediately presented atau pengetahuan kesekaligusan/keserentakan/kesekarangan mengenai realitas; dan mengajukan kesadaran bahwa realitas itu hanyalah represented atau realitas adalah sistem simbol-simbol yang mewakili realitas sebenarnya. Di sini postmodern berhadapan dengan fenomenologi. Adalah Edmund Husserl yang membuka tabir ketertutupan kesadaran manusia akan realitas (Kant misalnya berkata bahwa kita tidak bisa mengetahui realitas itu sendiri; yang bisa kita ketahui hanyalah penampakan-penampakannya!). Fenomenologi mencermati fenomen sebagai pengetahuan itu sendiri. Apa yang sesungguhnya disebut pengetahuan adalah apa yang diketahui, dikenali, dicermati pada waktu itu. Ada semacam karakter kesekaligusan dalam rangka kita mau menggapai pengetahuan realitas. Postmodernisme menggasak fenomenologi dengan mengklaim bahwa realitas di hadapan kita hanyalah simbol-simbol yang merepresentasi realitas sebenarnya. Realitas sebenarnya tidak bisa sekaligus kita tangkap. Realitas yang demikian itu masih harus dicari, ditemukan. Postmodern juga menyangkal origin. Artinya, bagi postmodern tidak ada pendasaran asal-usul suatu pengetahuan. Bagi para filosof self-centering (misalnya, existensialisme, psikoanalisis, phenomenologi, juga marxisme), menemukan origin of the self berarti menemukan otentisitas! Postmodern menyangkal kemungkinan semacam ini. Postmo menolak kembali kepada origin sebagai suatu realitas di balik phenomena, realitas sumber, realitas terakhir. Dalam aktivitas kuliah untuk memahami suatu teks tulisan Aristoteles, misalnya, menurut Nietzsche, provokator postmodernisme – tidak diperlukan lagi maksud original-nya. Mengapa? Karena 16 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 Aristoteles sudah tidak hidup lagi, dan teksnya sudah bukan untuk pembaca pada jamannya, melainkan untuk kita sekarang ini. Dari sebab itu pemahaman teks Aristoteles tidak perlu mesti mengenal privilese pemaknaan asali-nya. Upaya penemuan arti asali teks itu terlalu bersifat authoritarian, seakan-akan setelah ditemukan semuanya selesai, tuntas. Bagi Nietzsche, every author is a dead author. Dalam skema pemahaman ini, Derida menulis mengenai the end of book and the beginning of writing. Artinya, book sebagai kristalisasi dari maksud origin dari penulisnya sudah tidak berlaku lagi (setiap pengarang adalah pengarang yang mati!). Tetapi mulai suatu penulisan, artinya mulai suatu pemahaman-pemahaman kontekstual yang tidak lagi dibuntu oleh maksud orisinalnya. Dan pada saat yang sama pembacaan baru mengenai suatu tulisan, mulai! Postmodern juga menolak paham unity. Bagi postmodern apa yang kita lihat, pandang, mengerti, pikirkan tak pernah merupakan suatu eksistensi singular, integral, uniter. Misalnya, dalam memahami sosok Gus Dur, orang harus menyimak bahwa kehadirannya tidak tunggal; kehadiran Gus Dur (pembicaraannya, opininya, tindakannya, guyonan-nya, dan seterusnya) jelas tidak tunggal, melainkan plural, kompleks, belum selesai. The human self is not a simple unity, tegas para postmodernis, karena manusia itu eksistensi kompositoris, tersusun atas banyak elemen. Dari sebab itu, menurut postmodern, manusia itu lebih tepat memiliki selves daripada a self. Realitas lebih pas untuk diapresiasi karena kekayaan keragamannya, daripada direduksi dalam keseragaman, ketunggalan. Postmodern menolak transendensi norma-norma. Menolak transendensi itu menolak apa? Menolak norma-norma sebagai truth, goodness, beauty, oneness, rationality sebagai semacam pondasi terakhir. Maksudnya, bagi postmodern, normanorma sebagai truth dan seterusnya itu selalu merupakan produk dari proses dan selalu merupakan imanensi. Bukan sebagai itu yang mengatasi segala-galanya, melainkan sebagai itu yang diproduksi oleh proses – yang berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Ini tentu saja mengkomplikasi setiap klaim mengenai keadilan dan aneka kebenaran mengenai relasi-relasi sosial yang ada. Penolakan transendensi di satu pihak, dan penegasan proses imanensi di lain pihak memberi ruang kepada manusia untuk mengedepankan proses belajar, writing, negosiasi, dan realitas-realitas sosial yang memproduksi apa-apa yang menyapa. Di samping itu, postmodern mengajukan strategi memahami realitas dengan penelaahan lewat The idea of constitutive otherness. Realitas bagi postmodern itu bagaikan sebuah teks. Realitas masyarakat kita adalah society yang dibangun dalam atau dengan mengekslusifkan yang lain. Misalnya, era reformasi dipahami dengan mengeksklusifkan era Order Baru; sama persis ketika era Orde Baru muncul, yang diekslusikan adalah Orde Lama. Strategi constitutive otherness artinya “ke-lainan” (segala sesuatu yang mengitari atau mengelilingi atau yang dieksklusifkan) justru bersifat konstitutif. Gagasan ini secara kurang lebih tepat hendak mengatakan bahwa setiap formatio atau pendidikan haruslah bersifat well-rounded. Setiap pendidikan tidak boleh sekedar melatihkan segala sesuatu agar memproduksi peserta didik “siap pakai.” Melainkan pendidikan itu mesti membawa peserta didik kepada kesiapsiagaan untuk menghadapi fenomen tantangan apa saja yang ada di sekeliling ruang lingkup hidupnya. Armada Riyanto, Fides et Ratio 17 3. IMPLIKASI LUAS REFLEKSI PERTAUTAN FILSAFAT DAN TEOLOGI - Artikulasi dimensi KEKINIAN / KESEKARANGAN (aktualkontekstual) dalam studi filsafat dan teologi. Kuliah teologi sebagai suatu penjelajahan reflektif, meditatif, integratif dari iman kepada Tuhan terasa sudah harus mengatasi sistem paket jadi yang diulang-ulang pada setiap semester. Sekurangkurangnya kalau ingin agar refleksi iman atas wahyu Allah yang demikian komunikatif mampu menjawabi tantangan dan kebutuhan jaman sekarang hic et nunc (di sini saat ini) dengan segala peradabannya. Diperlukan sekarang pembaharuanpembaharuan yang dinamis, yang tidak memandang sepele aneka penemuan dan kreativitas yang menyapa masyarakat. Teologi kontekstual, teologi dialog, teologi bumi, teologi proyek, teologi inkulturatif, teologi entah apa lagi namanya merupakan tantangan-tantangan baru yang meminta keseriusan. Memperkokoh disiplin filsafat dengan pendalaman dimensi kekinian penjelajahannya dan perkuliahannya; dan tak terperangkap pada pendewaan kebenaran empirikal/praktis, melainkan bertekun untuk menjadi kritis. Para mahasiswa filsafat (juga dosen) sering jatuh dalam sistem mentalitas binary opposition. Maksudnya, mentalitas kita terlalu kerap direduksi pada pasangan-pasangan pertentangan, seperti abstrak-konkret, teori-praktek, teoritis-praktis, subyekobyek, lampau-sekarang, rohani-jasmani, bumi-angkasa, salah-benar, suci-dosa, dan seterusnya. Kita terlalu membelah-belah kehidupan dalam pola-pola pertentangan sedemikian rupa sehingga cara pandang tidak sampai menjangkau keseluruhan. Contoh: metafisika kerap dipahami langsung sebagai urusan di dunia abstrak, sementara psikologi / liturgi perkawinan langsung berkaitan dengan dunia konkret manusia. Percakapan mengenai gagasan persahabatan menurut Aristoteles langsung dipahami sebagai ide-ide masa lampau, sementara bila bicara mengenai masalah narkoba yang sempat dikaitkan dengan artis-artis ibu kota adalah masalah hangat saat ini. Orang seakan-akan terlalu dikurung dalam sekat-sekat masa lampau, masa sekarang yang lantas malah menggiringnya pada ketidakmampuan untuk memiliki orientasi pemikiran dalam keseluruhan. Jika mahasiswa diajak untuk berspekulasi tentang prinsip Cukup-alasan (sufficient reason) milik Leibniz atau prinsip Nonkontradiksi atau prinsip Identitas atau prinsip Kausalitas, sering dikatakan terlalu spekulatif. Beberapa persoalan yang dijumpai dalam hidup sekarang memang harus segera ditanggapi. Tetapi, tanggapan tak perlu harus menyempitkan cara pandang keseluruhan yang luas dan mendalam. - Penjabaran relasi antara filsafat dan teologi, jangan sampai reduktif, sempit, sepihak. Hubungan filsafat dan teologi sudah bukan jamannya lagi dipahami dalam nostalgia mentalitas Abad Pertengahan (ancilla theologiae dan praeambulum fidei) sejauh bertolak melulu dari filsafat Aristotelian-Thomistik, yang meskipun menurut saya tetap memikat untuk didalami. Kaitan filsafat dan teologi dewasa ini hampir tak terumuskan, tak tersistematisasikan, tak terkonstruksikan. Dari sendirinya juga lantas tak mungkin direduksi, disempitkan sepihak. Misalnya, belajar filsafat 18 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 cuma berarti sejauh mendukung fasilitasi pemahaman apa yang diberikan dalam kuliah teologi dogmatik. Cara pandang semacam ini reduktif sepihak. Seakan-akan filsafat selesai setelah mahasiswa mengerti secara lebih masuk akal mengenai misteri-misteri iman yang digumuli dalam teologi. Justru diperlukan kreativitas dan tekad-tekad pencarian untuk menggagas relevansi dan aktualitas pertautannya di jaman yang meminta pertanggungjawaban iman secara lebih radikal ini. Harus dipandang wajar aneka kreativitas kelompok studi, memutukan majalah ilmiah filsafat teologi kita dan aneka aktivitas seminar rutin atau diskusi-diskusi panel yang lain. Filsafat harus makin membuka mata kita akan suatu dunia yang makin berubah dan meminta pembaharuan relevansi iman terus-menerus. Bahkan, program pengajaran pada level teologi murni pun tak mungkin melepaskan diri dari relevansi filsafat, apabila ingin agar refleksi imannya aktual, kontekstual, kultural. Perlu dipikirkan semacam teologi antropologis, misalnya, dalam suatu mata kuliah yang bersifat semi seminar. Atau, teologi dialog, teologi persahabatan, teologi pertemuan agama-agama, dan seterusnya, yang semuanya memungkinkan kontak dengan realitas kekayaan kultural filosofis kontekstual hidup manusia. - Studi filsafat dan teologi menawarkan transformasi keterbukaan kepada dunia dan budaya luas. Ensiklik Fides et Ratio (1998) menegaskan bahwa filsafat adalah lapangan yang sangat kaya dan luas. Filsafat adalah medan dialog manusia tanpa batas dengan dirinya, sesamanya, dunia, dan alam kehidupannya. Jika ensiklik sebelumnya, Veritatis Splendor (Cemerlangnya Kebenaran), membela dasar-dasar obyektif prinsip-prinsip moral, Fides et Ratio membela dasar-dasar obyektif pengetahuan akal budi manusia. Dengan iman dan budi, manusia sanggup menggapai kebenaran sejati yang senantiasa menjadi kerinduan dan kedahagaannya. Kebenaran sejati tidak pernah atau tidak akan pernah mengantar manusia kepada sikap-sikap anti-toleransi. Sebaliknya, kebenaran itu menjadi dasar kokoh bagi kemungkinan terbukanya pencarian dialog dalam keanekaragaman apa saja meliputi budaya, ekonomi, ras, agama, politik dan yang lainnya. Seorang pencinta kebenaran tidak menyisihkan siapa pun, dan tidak mengisolasikan dirinya dari kehadiran siapa pun. Dalam kunjungan Yohanes Paulus II di Maroko tahun 1985, untuk pertama kalinya seorang Paus berpidato di hadapan sekitar sembilan puluh ribu pemudapemudi Muslim. Sebuah peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Peristiwa itu menandai dua hal sekaligus: pertama, secara konkret pribadi Yohanes Paulus II telah menyentuh banyak hati dari siapa pun; kedua, peristiwa itu juga sekaligus mengungkapkan kedahagaan yang mendalam di hati banyak umat Muslim di dunia akan suatu dialog yang berpangkal pada kebenaran yang tidak mengecualikan siapa pun. Suatu kebenaran sejati itu tidak memecah belah. Ia menyatukan, menawarkan rekonsiliasi, dan mengantar siapa pun kepada kerjasama yang tulus. Ensiklik Fides et Ratio menyangkal setiap pandangan yang mengatakan bahwa iman mengalienasi manusia dari kehidupannya yang nyata. Dalam semangat ini pula, saya kira sudah saatnya, perguruan tinggi filsafat teologi membuka pintu terhadap kelompok umat atau siapa pun yang berminat belajar filsafat dan teologi; dan tidak mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat/dunia. Sudah tidak mungkin lagi, sebuah perguruan tinggi filsafat teologi, memagari diri dengan tembok-tembok tinggi, kokoh. Karena dunia Armada Riyanto, Fides et Ratio 19 luar pun sedang menunggu kita, meminati apa yang sedang kita tekuni, dan menawarkan rincian kerjasama yang perlu ditindak-lanjuti. Filsafat itu membela nilai-nilai manusiawi, mengajukan cara-cara berpikir rasional dan mendalam, serta mengedepankan kemandirian dan tanggung jawab. Ia tidak tunduk pada kebenaran-kebenaran umum – yang lebih sering merupakan kompromi-kompromi sepihak. Analisis yang ditawarkannya menukik menembus batas-batas normatif yang ditabukan. Bukan untuk menentang sistem normatif, melainkan justru untuk memanusiawikan doktrin-doktrin yang diilahikan agar menyentuh kehidupan konkret manusia sekalian mendobrak kemandegan dan secara kritis membongkar kesempitan mentalitas dan cara berpikir. Dengan kata lain, filsafat “mencerahkan” budi manusia, melawan setiap bentuk ketidak-manusiawian, sekaligus berusaha cerdik memaknai setiap pengalaman seraya menaruh hormat pada kekompleksan, kerumitan, keanekaragaman dan pluralitas kehidupan bersama. Felix, qui semper vitae bene computat usum. - Iman dan filsafat bagaikan dua sayap manusia untuk terbang membubung tinggi menuju kontemplasi kebenaran. Fides et Ratio, judul ensiklik yang diterbitkan pas peringatan ke-20 tahun pontificat Yohanes Paulus II, dibuka dengan pernyataan yang secara tegas mengatakan tesis utamanya: “Iman dan budi adalah bagaikan dua sayap dengan mana roh manusia terangkat menuju kontemplasi kebenaran.” Yang dimaksud “kebenaran” di sini ialah apa yang secara mendalam menyentuh pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan hidup manusia. Menurut Sri Paus, iman tidak bertentangan dengan akal budi. Juga, budi tidak mendangkalkan misteri iman. Keduanya budi dan iman bersama-sama mengantar manusia kepada sang kebenaran sejati, yang memberikan kepenuhan kepada tujuan hidup manusia. Ensiklik filsafat yang terbilang panjang dan sulit itu dialamatkan kepada para uskup seluruh dunia. Karena keterlibatan filsafat dalam kehidupan manusia sangat konkret dan luas, seruan-seruan ensiklik ini ditujukan pula kepada para dosen dan mahasiswa filsafat, kaum intelektual, para teolog serta semua orang yang dahaga akan kebenaran. Filsafat adalah lapangan yang secara luas memberikan ruang bagi pengembaraan budi manusia dalam pergulatannya mencari kebenaran. Menurut Sri Paus, setiap manusia pada dasarnya adalah seorang filosof. Artinya, seorang manusia adalah pencari, penggapai, pencinta, perindu kebenaran sejati. - Studi filsafat teologi mesti memungkinkan orang untuk peka dan responsif terhadap aneka gelombang mentalitas jaman yang berubah dan berkembang. Ensiklik Fides et Ratio memberikan penegasan-penegasan yang menjadi seruan keprihatinan. Berkaitan dengan filsafat, ensiklik ini mengajukan aneka gelombang pemikiran yang perlu mendapat tanggapan serius.7 Ensiklik menyebut antara lain, Eklektisme, suatu gaya berpikir yang menggabung-nggabungkan argumentasi filosofis/teologis tanpa perduli kepada konteks historisnya sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang baru sama sekali yang kerap menyangkal kebenaran humanis universal. Satu dua argumentasi dari kaum 7 20 Yohanes Paulus II, Encyclic Fides et Ratio, Vatican, 1998, Chapter VII. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 postmodernis yang – antara lain – mengajukan jargon pemikiran/nalar lemah manusia (dikatakan misalnya oleh filosof Vattimo Gianni, salah satu filosof postmodernis terdepan di Italia) juga disangkal oleh ensiklik ini. Aliran ini mengidealkan paham lemahnya akal budi manusia sedemikian rupa sampai harus diakui bahwa budi manusia tidak mampu meraih kebenaran mutlak. Menurut aliran ini, setiap kepastian merupakan kenaifan. Bukan soal kepastian mengenai suatu pernyataan proposisi, melainkan terutama soal sistem tata kehidupan. Termasuk di dalamnya sistem moral, kebenaran misteri iman, budaya, dan seterusnya. Semuanya tidak ada yang pasti. Aliran-aliran lain yang menjadi keprihatinan ialah scientisme dan historisme. Selain itu, pragmatisme, menurut ensiklik ini, juga tidak kurang bahayanya. Aliranaliran yang jelas diandaikan disanggah ialah nihilisme, fideisme, dan marxisme. Mereka semua ini tidak hanya menyempitkan kapasitas kemungkinan budi manusia untuk meraih kebenaran, melainkan juga memandekkannya pada suatu level ketidakpastian dan ketidaktentuan. Nihilisme merupakan akar baru dari cara berpikir manusia yang menolak identitas sendiri. Fideisme menyisihkan pengetahuan rasional mengenai iman akan Allah. Sementara tuduhan bahwa agama hanya menimbulkan suatu sistem totaliter bagi manusia disembulkan oleh Marxisme. Paham terakhir ini merupakan humanisme ateis yang tentu saja menghantam setiap bentuk kepercayaan adikodrati. Scientisme adalah aliran baru dalam filsafat yang hanya mengakui kebenaran sejauh merupakan pengetahuan positif. Sejauh positif artinya sejauh dapat dibuktikan secara ilmiah, dapat dikalkulasi dalam statistik, dapat diverifikasi secara matematis. Tentu saja pendekatan pencarian kebenaran semacam ini tidak seluruhnya keliru. Tetapi, karena pendekatan ini diterapkan dalam banyak bidang kehidupan, termasuk di dalamnya moral, teologi, estetika, dan bidang-bidang yang semacamnya, konsekuensi kebenaran yang dihasilkannya hampir selalu merupakan penendangan prinsip-prinsip metafisis. Jika prinsip-prinsip metafisis dipandang tak punya makna, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai iman dan kemanusiaan menjadi sangat mendangkal. Prinsip seks di luar nikah misalnya, menurut jalan pikiran aliran ini, tidak perlu lagi dipandang tabu atau melawan tata kehidupan karena banyak orang jaman sekarang telah melakukannya. Tidak perlu dipandang tabu, karena sudah menjadi suatu kewajaran baru. Sri Paus tentu saja memprihatini kecenderungan mentalitas semacam ini, karena yang dipertaruhkan bukan hanya in se nilai tindakan seks-nya, melainkan nilai kesetiaan keluarga, dan akhirnya nilai-nilai kehidupan masyarakat itu sendiri. Lebih jauh, scientisme memisahkan secara tegas apa yang ilmiah dan apa yang moral. Apa yang scientific, dalam jargon aliran ini, bebas dari kungkungan penilaian moral. Atas nama sejarah yang terus mengalir, historisme memiliki pandangan yang hampir seragam dengan eklektisme, yaitu menolak kebenaran mutlak. Historisme merupakan paham filosofis yang ditarik dari pemikiran filosof Hegel. Aliran ini mengajarkan bahwa sejarah memiliki kriteria-kriteria kebenarannya sendiri. Tidak ada kebenaran kekal. Dalam beberapa segi, pendekatan historisme ini tidak bisa begitu saja dipandang sempit. Misalnya, pusat tata kehidupan semesta yang semula dianggap bumi ternyata yang benar matahari. Atau, bahkan sekarang malah apa Armada Riyanto, Fides et Ratio 21 yang disebut dengan pusat tata semesta itu tidak ada, sebab ternyata ditemukan ada banyak bintang seperti matahari. Tetapi, apabila pendekatan semacam itu dikenakan pula pada soal-soal yang menyangkut kebenaran iman atau prinsip-prinsip moral kehidupan, soalnya menjadi lain sama sekali. Historisme dengan mudah dapat membawa kepada krisis-krisis baru berupa aneka penyangkalan terhadap kebenarankebenaran yang secara prinsipial kekal. Studi filsafat dan teologi, pendek kata, mesti memungkinkan orang mampu membaca merebaknya pemikiran-pemikiran baru dengan segala macam persoalan yang ditimbulkan. Aneka kekerasan dan krisis nilai kehidupan yang terjadi pada banyak kalangan masyarakat dunia memiliki akar-akar paham filosofis teologis yang dewasa ini sangat menggejala. Filsafat teologi adalah medan dialog manusia tanpa batas dengan dirinya, sesamanya, dunia, dan alam kehidupannya. - Refleksi pertautan filsafat teologi mesti berani berdialog dengan tantangan Nietzschean dan Marxis yang menyoal secara radikal kepentingan hidup beriman. Persoalan hidup beriman barangkali bisa diringkas dalam jargon radikal “Tuhan sudah mati” (Nietzsche) dan “agama hanyalah candu masyarakat” (Marx). Dewasa ini terasa, dalam berbagai bentuk, kita sedang berhadapan dengan aneka gelombang pemikiran yang menggoyang iman. Bukan hanya validitas kebenaran misteri iman yang diragukan, melainkan juga aktualitas kepentingannya bagi kehidupan manusia yang disangsikan. Allah telah dibunuh Nietzsche pada akhir peradaban filsafat kemodernan. Eksistensi Allah yang dibela mati-matian oleh pemazmur (misalnya seorang pemazmur menyebut “bodoh”/”dungu” dia yang berkata bahwa Allah tidak ada”), Filone, Dionisius dari Areopagus, Agustinus, Yohanes Scotus Eriugena, Anselmus d’Aosta, para filosof Islam Abad Pertengahan, Thomas Aquinas, Kant (sekurang-kurangnya ia pernah berkata bahwa akal budi kita tanpa syarat apa pun sudah harus yakin bahwa ada realitas absolut dan paling tinggi yang namanya Allah), telah “dihabisi” oleh Nietzsche dengan mitos Dionysus yang sekaligus telah membunuh dewa rasionalisme filsafat kemodernan. Saat ini persoalannya menjadi lebih runyam lagi, karena bukan eksistensi Allah yang dipersoalkan melainkan kepentingan aktivitas beriman kepada realitas yang mengatasi kehidupan manusia yang disangkal. Apakah iman? Untuk apa beriman? Marx, sementara itu, malahan mensinyalir bahwa beriman mengalienasi manusia sedemikian rupa sehingga dia terhempas kepada ketidak-realistisan. Iman justru telah mengasingkan manusia dari kehidupannya yang nyata, kaya, mempesona. Kesimpulan ini mengalami kristalisasi perumusan ideologisnya dalam Marx. Karena agama dipahami sebagai “aktivitas beriman kepada Tuhan,” dalam Marx tidak ada ruang bagi agama. Mengapa? Marx setuju dengan Feuerbach: bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusia yang telah menciptakan “Tuhan.” Maksudnya, manusialah yang membuat aneka konsep mengenai iman kepada Tuhan. Bagi Marx, tidak ada Tuhan, yang ada adalah aneka konsep/ide/ajaran/dogma atau apalah namanya tentang Tuhan. Feuerbach berhenti pada tesis bahwa manusialah yang menciptakan Tuhan, sedangkan Marx melanjutkan soalnya: Mengapa manusia menciptakan Tuhan? Marx menjawab bukan dengan membunuh Tuhan, bukan dengan menyoal eksistensi Tuhan, melainkan dengan menyadari realitas kehidupan 22 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 konkret masyarakat yang tidak adil. Marx mengambil sikap kritis bahwa manusia menciptakan aneka konsep suci tentang Tuhan, karena ingin meneguhkan ketidakadilan, karena ingin menggariskan rupa-rupa peraturan moral suci (supaya dengan demikian tidak dimungkinkan perubahan!), karena berlari kepada Tuhan itu menciptakan rasa aman (sementara manusia tetap teralienasi di tanah sendiri dalam kehidupan sehari-harinya). Dengan kata lain, bagi Marx agama itu opium, maksudnya membius manusia untuk tidak melek dengan ketidakadilan, untuk tidak sadar akan apa yang sedang terjadi (para buruh semakin payah bekerja, semakin pendek usia mereka, semakin miskin karena gaji pas-pasan, semakin senang memproduksi banyak anak karena kalau malam tidak ada hiburan lain kecuali bermain-main dengan isteri sendiri dan isteri orang lain), dan seterusnya. Agama itu opium, karena manusia dibuat teler, terlelap, ekstase keenakan (sekaligus kecanduan) dalam status quo ketidakadilan yang merajalela. Jadi, apakah yang dikritik oleh Marx mengenai agama? Bukan soal Tuhannya, atau soal dewanya, melainkan soal realitas imaginer yang mempesona yang ditawarkan oleh setiap agama – yang pada kenyataannya tidak mengubah kehidupan tidak adil dan semrawut, melainkan justru malah meneguhkannya. Kritik Marx terhadap agama, sesungguhnya bukan kritik atas realitas ilahi, melainkan kritik atas realitas kehidupan manusiawi. Kritik Marx atas surga/langit sesungguhnya memaksudkan kritik atas bumi/hidup konkret. Dialektika “roh” dalam Hegel menjadi dialektika “daging” dalam Marx. Marx lantas mematerialkan dialektika kehidupan. Kritik Marx atas teologi lantas memaksudkan kritik atas politik (sistem/tata hidup bersama) yang dipandang sepele oleh para teolog, agamawan, kaum beriman. Marx bukan protes atas agama sebagai agama, melainkan protes atas agama sebagai realitas “atas”/“surga”/“di sana”/“nanti” yang meninabobokkan manusia yang seharusnya sadar akan realitas hidupnya “di bumi”/“di tanah sendiri”/“di sini”/“saat ini!” Marx tidak protes kepada Tuhan, melainkan protes kepada manusia yang mengalienasikan diri atau yang melarikan diri dari kenyataan hidup sesungguhnya dengan melakukan aktivitas beriman. - Refleksi mendalam tentang pertautan filsafat teologi secara kokoh mencegah kerancuan penghayatan agama yang campur baur dengan tindakan kekerasan dan fanatisme sempit. Dewasa ini aktivitas konkret beriman telah gandeng dan rentan soal-soal kemanusiaan dengan intensitas yang sangat serius: kekerasan. Kekerasan terjadi di mana-mana dengan label agama. Aktivitas beriman terasa tidak menambah kedamaian, malah menghantam kemanusiaan dalam taraf sangat memalukan. Tidak hanya telah terjadi jauh di sana, di daerah Balkan atau di Afganistan atau di Sudan, atau di Belfast Irlandia Utara melainkan di sekitar kita, di sini, saat ini. Saya menyebut “memalukan,” karena aktivitas beriman semakin terasa identik dengan menyimpan bom (dalam artian sungguh konkret, bukan dalam artian analogal!), identik dengan memanggul senjata/senapan/pedang/clurit/tombak, identik dengan mengusir orang dari rumah dan tempat tinggalnya, identik dengan aktivitas sweeping, dan yang sejenisnya. Dengan menyebut nama Allah atau Tuhan atau Realitas ilahi atau siapa lagi yang di-Tuhan-kan, orang menyembelih sesamanya, membakar perkampungannya, memusnahkan tempat tinggal dan panenannya, membabat habis anak-anak (yang tidak termasuk dalam agamanya), mengusir sesamanya, dan Armada Riyanto, Fides et Ratio 23 segudang model-model kekerasan lain yang tak terbayangkan kekejiannya. Bermunculan aneka “laskar” atau “komando” yang siap mati (mereka menyebut mati sahid, berjihat, atau yang semacamnya). “Siap mati” artinya dengan demikian juga siap membunuh sesamanya dengan segala cara entah dengan permainan ninja sampai kepada pengiriman bom-bom. Ironis. Atau, dalam terminologi saya, memalukan! Menyimak itu semua, terasa nyaman justru kalau tidak beriman. Nyaman, karena manusia disatukan oleh persaudaraan kemanusiaannya, bukan dipecahbelah oleh aneka kecemburuan/benci/dengki karena macam-macam agama/iman dengan segala aktivitas yang membeda-bedakannya.8 8 24 Konflik agama (atau lebih tepat, konflik antarmanusia yang beragama) dalam negara kita gandeng dengan aneka interpretasi terminologi “jihat.” Dalam khasanah kearifan hidup beragama, makna jihat menyentuh realitas semua agama, meskipun paling umum terminologi itu kerap disebut dalam agama Islam. Kata jihat sudah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua 1994) menyebut beberapa arti: (1) usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan, (2) usaha sungguhsungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga, (3) perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Dalam istilah jihat akbar, dimaksudkan perang besar melawan hawa nafsu (yang jahat); dalam istilah jihat fisabilillah, ditampilkan makna jihat pada jalan Allah (untuk kamajuan agama Islam atau untuk mempertahankan kebenaran). Dalam doktrin kearifan ajaran suci agama Islam, terminologi jihat pastilah merangkum kekayaan arti yang lebih mendalam dari yang disebut ini. Dalam ajaran tradisi Kristen, terminologi jihat kurang lebih menemukan padanan maknanya dalam kata martir. Dalam ajaran kearifan agama Kristen, mahkota kemartiran konon merupakan puncak upaya memberikan kesaksian tentang imannya. Dalam tradisi Yudaisme, tidak ada terminologi khusus untuk menyebut kemartiran. Namun demikian, orang-orang Yahudi mengenal apa yang disebut dengan profesi iman akan Allah yang esa, yaitu kesetiaan tanpa batas kepada Allah dalam kesaksian hidup sehari-hari yang membuat mereka lebih suka mati dalam cara apa pun daripada menyangkal hukum Allah (term “Märtyrtum” dalam Lexikon Religiöser Grundbegriffe, Judentum – Christentum – Islam, Graz-Wien-Köln 1987). Tanpa menyebut arti khusus lain, pastilah dijumpai aneka ajaran kearifan yang serupa dalam agama-agama Hindu, Budha, atau tradisi-tradisi religius yang lain. Pendek kata, jihat atau aneka terminologi padanannya merupakan ekspresi terdalam dari manusia yang ingin menampilkan konsep-konsep heroik kesetiaan kepada Allah yang diimaninya. Terminologi ke-jihat-an dan ke-martir-an menemukan realitas paling konkret dalam simbol peradaban baru, peradaban kota Ambon di negeri kita. Di Ambon dan sekitarnya, hadir kelompok, laskar, pasukan yang langsung berhubungan dengan konkretisasi terminologi tersebut. Ambon secara nyata telah berubah menjadi lapangan kemartiran dan jihat yang manisbikan kemanusiaan. Menyimak apa yang terjadi di Ambon, Wakil Presiden Megawati memberikan komentar singkat, “bangsa ini telah kehilangan jati diri (kemanusiaannya).” Siap mati berarti siap “terbunuh/dibunuh” oleh lawan. Dalam realitas siap terbunuh juga memaksudkan pada saat yang sama siap “membunuh” lawan atau siapa saja yang dipandang sebagai lawan. Jika “jihat” atau “martir” digagas dan dihayati dalam konteks aktivitas bunuh-membunuh, dari sendirinya jihat/martir sebagai ungkapan bakti kepada Tuhan sama sekali tidak pas untuk suatu tata hidup bersama, untuk societas yang mengedepankan penghargaan kepada kehidupan Pendek kata, segala aktivitas agamis yang mengeksplorasi teror, ketakutan, ketidak-nyamanan mesti ditolak dalam societas yang merujuk kepada civil society. Jihat atau martir kerap diungkapkan sebagai kesetiaan tanpa batas kepada Allah. Kesetiaan yang memberikan harta melimpah terakhir, yaitu nyawa kita sendiri. Suatu kesetiaan – dari sendirinya – didasarkan pada cinta kasih kepada Allah, bukan kebencian kepada sesama (apalagi dengan maksud membalas dendam atau dengan alasan-alasan sloganistis suci yang dibuat-buat). Cinta kasih kepada Allah harus disertai dengan cinta kasih kepada sesama. Maka, aktivitas jihat atau ingin menjadi martir sebagai bukti kesetiaan kepada Allah dengan didasarkan kebencian kepada sesama, tidak bisa diterima oleh nurani manusia. Aktivitas kesetiaan kepada Allah justru harus langsung tercetus pada aneka tindakan cinta kasih kepada sesama, ciptaan Allah – yang diciptakan segambar denganNya. Jihat atau menjadi martir sebagai suatu cara heroik dalam mengabdi kepada Allah meminta syarat-syarat moral dan etis manusiawi. Jika tidak, malah akan langsung menampilkan suatu bentuk terorisme baru dengan aneka alasan suci sebagai baju. Tidak dari sendirinya memperlakukan orang lain sebagai musuh Allah dan menghabisinya merupakan tindakan heroik. Sering kali justru kebalikannya. Tindakan itu malah mencetuskan terorisme dan kebodohannya. Dalam suatu civil society, “musuh” bersama adalah ketidakadilan, korupsi, dan yang semacamnya. Agama menemukan fungsi kesempurnaannya jika mengeksplorasi kekuatan moral melawan segala macam bentuk ketidakadilan dan korupsi. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 Bertolak dari keprihatinan mengenai realitas hidup beriman semacam ini, hadir bersliweran di dalam benak kita aneka pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Bukankah agama tidak mempromosikan kekerasan? Atau, bukankah manusia yang beriman adalah dia yang memuja perdamaian? Atau lagi, tidakkah iman atau agama mengedepankan paham-paham pemuliaan keluhuran martabat kemanusiaan? Untuk apa hidup beriman, jika yang menaati ajaran agama hidupnya “berlumuran” dengan kekerasan? Soal pertautan agama dan kekerasan pada intinya adalah pertanyaan yang menggugat agama dan kepentingan iman dalam hidup kemanusiaan kita. Bukan menggugat eksistensi Tuhan. Soal-soal inilah yang membedakan gelombang mentalitas manusia beriman dewasa ini dan abad pertengahan (yang suka bergumul dengan argumentasi metafisis untuk membuktikan eksistensi Tuhan). Dari sebab itu, juga pengertian relasi filsafat teologi tidak boleh sekedar direduksi pada konstatasi bahwa filsafat mendukung teologi dan teologi didukung filsafat! Filsafat menggugat kenaifan dalam beragama/beriman.9 Dan refleksi teologis mesti korespondensi dengan aktualitas tantangan jaman. - Hubungan filsafat teologi akhirnya mesti bermuara pada pembangunan Kerajaan Allah dan cara baru dalam beriman/beragama. Hidup beriman dalam societas – dari sendirinya – tidak boleh dipikirkan melulu sekedar dalam kaitannya dengan maksud mengejar kebahagiaan jiwa melainkan juga merangkul penghargaan terhadap realitas manusia.10 Dialog menempati kepentingan yang sangat menyolok. Mengapa dialog? Dewasa ini makin disadari realitas kekayaan kehidupan bersama. Realitas kebenaran yang saya pegang, saya hayati, saya hidupi belumlah selesai. Dialog lahir justru dari kesadaran bahwa ternyata kehidupan bersama kita ini sangat kaya dan mempesona. Kontemplasi Allah: dari transendensi (Allah jauh memerintah) kepada imanensi (Allah dekat hidup bersama kita). Dewasa ini, makin disadari bahwa kita memiliki kesibukan keseharian yang menantang. Keseharian hidup kita menjadi lahan refleksi kita yang baru akan Allah kita. Dari kesadaran ini bangkit usaha-usaha untuk membangun sekaligus menghayati cara-cara baru dalam berelasi dengan Allah. Allah itu kita jumpai dalam orang-orang yang kita temui dalam keseharian hidup kita. Allah itu kita rasakan kehadirannya dalam saat-saat tidak istimewa. Tetapi, kehadirannya menyentuh. Kebenaran: dari kebenaran dogmatis kepada kebenaran dialogal. Kepenuhan kebenaran tidak diletakkan kepada ajaran yang sudah tidak bisa diapaapakan, melainkan kepada apa yang dialogal, merangkul, menyentuh hati manusia siapa saja. Kebenaran sebagai suatu kebenaran hampir tidak ada gunanya. Kebenaran yang mengubah/mentransformasi ialah kebenaran yang menyentuh hidup. 9 10 Cf. Armada Riyanto, Agama-Kekerasan: Membongkar Eksklusivisme, Malang 2000 Simak Vincent Holzer CM, Le Dieu Trinité dans l’histoire, Paris 1995: khusus bab I tentang Esquisse du Rapport Philosophie-Théologie sous l’Horizon Théologique d’une Ouverture Kénotique de-à l’Absolu (Hans Urs von Balthasar); juga bab II tentang Le Rapport Philosophie-Théologie sous l’Horizon Théologique de la Selbstmitteilung Gottes: Dieu comme Donateur, Don et Fondement de l’Acceptation du Don (Karl Rahner). Armada Riyanto, Fides et Ratio 25 Berikutnya, relasi antarmanusia: dari keseragaman kepada keanekaragaman. Mentalitas upaya-upaya penyeragaman jelas sempit. Contoh konkret ialah kenyataan berikut ini. Sepanjang pemerintahan Orde Baru, kita simak bagaimana pemerintah meminta agar di setiap atap rumah ditulis PKK. Inilah bukti kesempitan cara berpikir apabila kehidupan yang begini kaya dengan segala dinamisitasnya diseragamkan. Keteraturan memang perlu diupayakan, tetapi keseragaman tidak diperlukan. Kreativitas yang perlu ditumbuhkan. Kesadaran manusia: dari berpusat pada “diri” (human-self) kepada pengedepanan konteks hidup manusia (human-culture). Dewasa ini makin hebat gelombang cara berpikir yang tidak meletakkan pusat kesadaran manusia pada self (diri sendiri), melainkan pada konteks kehidupannya secara luas. Dengan demikian horison ruang lingkup hidupnya makin luas dan lebar. Cetusan kearifan hidup beragama dalam aktivitas cinta kasih merambah pula batas-batas perbedaan iman. Maka, mengenai kerasulan terjadi pergeseran dari kerasulan sendiri kepada kerasulan dialogal. Alam berpikir postmodern, misalnya, mengikis orientasi self (diri sendiri). Dewasa ini sudah terasa bukan jamannya untuk menggagas keaktifan sendiri dan lantas mengklaim ini atau itu karyaku. Dalam banyak hal justru makin dirasakan perlunya aktivitas kerasulan bersama, dialogal lintas agama/lintas iman. Dari kerasulan eksklusif kepada kerasulan inklusif partisipatif: Kerasulan eksklusif artinya karya kerasulan yang mengedepankan keaktifan sendiri dan menyisihkan keikutsertaan pihak lain. Hidup bersama itu kaya dan mempesona, maka umat/masyarakat pantas diberi kemungkinan partisipasi yang lebih besar. Umat basis – yang saat ini menjadi tema sentral pembangunan Gereja Indonesia – mengandaikan kerasulan partisipatif dan merangkul semua pihak. Dari kerasulan iman kepada kerasulan kehidupan: Apakah yang kita khususkan dalam kerasulan? Alam postmodernisme meminta kita untuk memiliki orientasi luas dan lebar dalam menegaskan kerasulan. Kerasulan tidak hanya dalam hubungannya dengan hal-hal yang rohani, melainkan dalam hubungannya dengan kehidupan itu sendiri (menjangkau pula aneka aktivitas yang tampaknya tidak langsung berkaitan dengan rohani). Dari kerasulan personal kepada kerasulan komuniter (persaudaraan sejati): Kerasulan komuniter merupakan tuntutan. Kerasulan pribadi pasti menemukan kesulitan. Salah satu indikasi tuntutan karakteristik komuniter ialah merebaknya peran komputer. Dimungkinkan kemudahan luar biasa dalam menjalin komunikasi, dari sebab itu tindakan mengisolasikan diri dalam karya kerasulan hampir tidak mungkin. Hidup komunitas (hidup bertetangga): dari menjaga peraturan agamis eksklusif kepada kesadaran tentang relasi persahabatan personal. Peraturan adalah ketentuan yang membimbing, tetapi bukan yang memaku. Hidup komunitas itu kaya. Sedemikian kayanya sehingga jalinan hubungan antarpribadi anggotaanggotanya tidak mungkin dipaku dalam peraturan ketat sedemikian rupa. Justru saat ini diperlukan kesadaran baru: memaknai ketaatan peraturan komunitas dengan suatu relasi persahabatan. Apakah persahabatan? Dalam persahabatan, hubungan “aku – engkau” menemukan kepenuhan penjabaran konkretnya. Dalam hubungan semacam ini tidak ada lagi “ia” atau “mereka”. Dengan kata lain, tidak ada lagi orang 26 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 ketiga, orang lain, atau orang yang dipandang sebagai di luar lingkungan “kita”. Dalam persahabatan “engkau” tidak lagi sebagai pribadi “lain” yang berbeda dari aku, melainkan menjadi “aku yang lain” yang berbicara kepadaku. Kesadaran mengenai alteritas aku ini (atau pribadi lain sebagai “aku yang lain”) diperlukan justru agar aku semakin menjadi aku sejati. Karena orang lain adalah “aku yang lain”, aneka pengalaman kegembiraan, harapan, dan kecemasannya adalah kegembiraan, harapan, dan kecemasanku sendiri. Segala macam bentuk perlakuan kepadanya identik dengan segala macam bentuk perlakuan terhadapku. Persahabatan meminta kesadarankesadaran baru semacam ini, yaitu kesadaran yang mengedepankan sikap-sikap identifikasi diri dengan orang lain. Sikap solider merupakan pilihan utamanya. Pembangunan Kerajaan Allah meminta rincian konkret – paling sedikit dalam konteks kultur hic et nunc – beberapa perubahan mentalitas seperti di atas. Pertautan fides et ratio dengan demikian memiliki kedalaman dan keluasan implikasi penelaahan yang akhirnya harus sampai pada perubahan dan pembaharuan hidup konkret manusia beriman secara menyeluruh dan dalam cara sejauh mungkin sepenuhnya. BIBLIOGRAFI (Sumber Bacaan) ARISTOTLE, Metaphysics (dari The Complete works of Aristotle, edited by Jonathan Barnes, New Jersey 1984). CAHOONE, L., ED., From Modernism to Postmodernism. An Anthology, Oxford 1997. CHARLES E. SCOTT, “The Sense of Transcendence and the Question of Ethics,” dalam The Ethics of Postmodernity, edited by Gary B. Madison and Marty Fairbairn, Illinois 1999. DULLES, AVERY SJ., “Reason, Philosophy, and the Grounding of Faith: Reflection on Fides et Ratio,” in International Philosophical Quarterly, Vol. XL, No. 4, Issue No. 160, December 2000, 479-490. GILSON, É., L’Esprit de la Philosophie Médiévale, Paris 1932. HOLZER, VINCENT CM, Le Dieu Trinité dans l’histoire, Paris 1995. JOHN PAUL II, Fides et Ratio, Vatican 1998. JULIAN WOLFREYS ED., The Derrida Reader. Writing Performances, Edinburgh 1998. MANINTIM, MARCELO C.M., The Concept of Lifeworld in Jürgen Habermas, Rome 1993 PADEN, WILLIAM E., “World,” in Willi Braun-Russell T. McCutcheon ed., Guide to the Study of Religion, London 2000 PLATO, Apology (dari Plato. The Collected Dialogues, edited by Edith Hamilton and Huntington Cairns, Princeton 1989). Armada Riyanto, Fides et Ratio 27 RAHNER, KARL, “On the Importance of the Non-Christian Religions for Salvation,” in Theological Investigation XVIII, New York 1983, 294+ —————, “The Current Relationship between Philosophy and Theology,” in Theological Investigation XIII, New York 1983, 61-79. —————, “On the Relationship between Theology and the Contemporary Sciences,” in Ibid., 94-104. RIYANTO, ARMADA, “Membongkar Eksklusivisme Hidup Beragama,” dalam Armada Riyanto ed., Agama-Kekerasan. Membongkar Eksklusivisme, Malang 2000. ROBERT C. SALAZAR, “The fundamentalist Evangelical Movement in the Philippines: An Overview,” dalam Rethinking New Religious Movements, ed. By Michael A Fuss, Rome 1998. SHAMIR, KHALIL S., “Monotheism and Trinity. The Problem of God and Man and its Implications for Life in our Society”, in Vincentiana, July-October 1999, 291-300 THONNARD, F.J., Précis d’Histoire de la Philosophie, Paris 1963. TILLIETTE, XAVIER, “Du Dieu théiste à la Trinité spéculative” (dari Allah yang teistis kepada Trinitas spekulatif), in Communio, No XXIV 5-6 (Sept-Dec 1999), 197-206. ————, Filosofi Davanti a Cristo, Brescia 1991. 28 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 REKAN-ANGGOTA DAN REKAN-PEMBANGUN KERAJAAN ALLAH: Pendasaran Teologis untuk Penghayatan Iman yang Merangkul Dr. P.M. Handoko, CM STFT Widya Sasana, Malang Abstraksi Mengenai penghayatan iman yang merangkul, dapat diberikan dua macam pendekatan: praksis dan doktrinal. Artikel ini bermaksud mengajukan pendekatan yang kedua. Tema dibahas berdasarkan dokumen-dokumen Konsili dan ajaran Bapa Suci juga dokumen FABC (Konferensi Uskup-Uskup Asia). Tulisan akan mengalir dalam jalan pikiran pertama-tama menggali monoteisme Abraham sebagai dasar universal agama-agama monoteis. Berikutnya menyimak konsep regnosentris (seputar tema Kerajaan Allah) tentang agama-agama lain. Dan akhirnya, pembahasan sampai kepada rincian tema “rekan-anggota dan rekan-pembangun Kerajaan Allah,” yang menjadi cetusan konkret penghayatan iman yang merangkul. 1. Pengantar Tema ini bisa didekati dengan dua pendekatan, yaitu pada tingkat ajaran (doktrinal) dan tingkat praktis (praksis). Makalah ini akan mendalami permasalahan pada tingkat ajaran (doktrinal) dan akan saya konsentrasikan khususnya tentang ajaran Gereja Katolik, yaitu pada sifat inklusivisme dari ajaran-ajaran Gereja Katolik berkaitan dengan ajaran dan pengikut agama lain. Ajaran-ajaran itu saya ambil dari dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik, khususnya dokumen Konsili Vatikan II dan ensiklik atau Himbauan dari Bapa Suci. Kiranya dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan ensiklik Bapa Suci bisa dipandang mempunyai otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci (semacam departemen). Karena itu, saya tidak akan membahas secara khusus dokumen-dokumen resmi dari berbagai Kongregasi Suci di Vatikan, termasuk Dominus Iesus yang diterbitkan tgl. 5 September 2000 oleh Kardinal Ratzinger, Perfek dari Kongregasi Suci untuk ajaran iman. Secara khusus, perhatian juga akan diberikan kepada dokumen-dokumen resmi dari Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) sebagai Magisterium Lokal yang nampaknya lebih relevan untuk tema kita kali ini. P.M. Handoko CM, Rekan-Anggota & Rekan-Pembangunan 29 2. Allah Abraham sebagai Asal-usul dan Tujuan Manusia Paham monoteis berarti pengakuan bahwa Allah itu esa, bahwa hanya ada satu Allah, dan tidak ada allah-allah lain. Allah ini adalah Sang Pencipta alam semesta dan Allah ini juga adalah tujuan semua orang. Maka, Allah itu adalah Tuhan (dalam arti “Ketuhanan yang Mahaesa”dalam Pancasila). Pengakuan ini tidak asing juga bagi umat Islam, sebab dalam ajaran Islam juga diakui bahwa Allah dari orang Kristiani ini adalah sama dengan Allah yang mereka sembah. Paham monoteis Gereja Katolik ini bersumber pada Allah yang diimani oleh Abraham dan tercermin dalam skema Israel: “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!” (Ul 6:4). Keesaan Allah ini kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Deutero-Yesaya: “Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak ada Allah.” (Yes 45:5); “Aku, Akulah TUHAN, dan tidak ada juruselamat selain dari padaKu” (Yes 43:11; lihat juga 43:8-13; 44:6-8. 24-28; 45:20-25, dll.). Pesan yang sama diulangi dalam Perjanjian Baru: “Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah:’Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.” (Mk 12:29-30; lih. Mt 22:37-38). Monoteisme Kristiani ini merupakan kelanjutan dari monoteisme Israel. Menganut paham monoteisme ini tidak langsung berarti bahwa Gereja langsung mengakui bahwa Allah yang disembah oleh agama-agama lain adalah Allah yang sama. Dalam teologi tentang agama-agama, tidak banyak yang bisa ditulis tentang pergulatan pandangan Gereja tentang agama-agama lain, khususnya tentang agama Islam. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa sampai dengan Konsili Vatikan II, Gereja memandang agama-agama lain sebagai “lawan”.1 Pandangan ini baru berubah dengan dan dalam Konsili Vatikan II seperti tercermin dalam berbagai dokumennya, khususnya dalam Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-agama Bukan Kristen Nostra Aetate (dikeluarkan 28 Oktober 1965).2 Konsili Vatikan II mengakui bahwa seluruh umat manusia mempunyai satu titik-temu dalam Allah, yaitu sebagai asal-usul bersama dan tujuan akhir bersama (NA 1). Kesatuan dalam Allah ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Hal ini kemudian diuraikan lebih rinci berkaitan dengan Budha dan Hindu, terlebih Yahudi dan Islam. Karena itulah maka seluruh umat manusia membentuk “satu masyarakat.” Konsili mengakui bahwa “penyelenggaraan Ilahi, bukti-bukti kebaikan-Nya dan rencana penyelamatan-Nya meliputi semua orang” (NA 1). Dalam agama-agama itu 1 2 30 Uraian lebih lengkap tentang berbagai pandangan tentang Islam dalam Gereja dan perkembangan pandanganpandangan itu bisa dilihat pada R. Casper, “Le Concile et l’Islam,” Etudes, 324 (1966), 114-126; A. Roest Crollius, “Vaticano II e le religioni non cristiane,” RassTeol, 8 (1967), 65-74; N. Daniel, Islam and the West, The Making of an Image (1960), dan P. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (1962). Untuk semua rujukan ke dokumen Konsili Vatikan II, digunakan: Dokumen Konsili Vatikan II, (Terj.: R. Hardawiryana, S.J.), Dokumentasi dan Penerangan KWI, Obor 1993. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 manusia mencari jawaban atas pertanyaan eksistensiil tentang dirinya, dan karena itu agama-agama itu menyadarkan mereka akan pengakuan adanya Allah yang tersembunyi dan menumbuhkan “semangat religius yang mendalam.” Gereja katolik “tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci” (NA 2). Ada hubungan khusus karena “warisan rohani yang sama” antara agama Kristiani dan agama Yahudi, yaitu dalam Perjanjian Lama. Makalah ini tidak akan membahas lebih lanjut hubungan dengan agama Yahudi ini. Tentang hubungan dengan agama Islam, Gereja Katolik menyatakan bahwa umat Islam menyembah Allah yang “satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belaskasihan dan mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia.” (NA 3) Allah itu tidak lain adalah Allah yang sama yang disembah dalam agama Kristiani, yaitu Allah Abraham. Konsili Vatikan II juga mengakui peran penting yang dimiliki oleh penganut agama lain dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah, khususnya kaum muslimin. Konsili berkata: “Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka, yang mengakui Sang Pencipta; di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin, yang menyatakan, bahwa mereka berpegang pada iman Abraham, dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maharahim, yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Pun dari umat lain, yang mencari Allah yang tak mereka kenal dalam bayangan dan gambaran, tidak jauhlah Allah, karena Ia memberi semua kehidupan dan nafas dan segalanya (lih. Kis 17:25-28), dan sebagai Penyelamat menghendaki keselamatan semua orang (lih. 1 Tim 2:4)” (LG 16). Dalam ajaran Al Quran bisa diketemukan ajaran yang searah dengan ajaran Konsili tentang universalitas Allah. Ketika berbicara tentang “umat dari Kitab”, dikatakan: “Kita percaya pada apa yang telah diwahyukan kepada kami dan kepada kalian; Allah kami dan Allah kalian, adalah Satu, dan kita taat (muslimum) kepadaNya” (Surah 29:46). Demikian juga dikatakan dalam Al Quran: “Tidak ada Allah lain selain Aku (illa ana)” (Surah 16:2; 21:14).3 Persamaan ini tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan mendasar antara ajaran Islam dan Katolik tentang Allah yang Esa itu. Dalam studinya yang mendalam tentang ketiga agama monoteis, Arnaldez menyimpulkan bahwa perbedaanperbedaan itu terjadi pada tataran ajaran, namun demikian semua itu benar-benar bisa diharmoniskan pada tataran penghayatan iman oleh para mistikus dari masingmasing agama. Para mistikus baik dari Islam maupun dari Katolik (juga Yahudi) merindukan satu Allah yang sama, yang transenden dan imanen. Dialah Pencipta kehidupan yang melimpahkan rahmatNya kepada para ciptaan yang tak berarti itu. Para mistikus itu memberikan kesaksian tentang nilai-nilai yang sama tentang 3 Jacques Dupuis, Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, New York: Orbis Books, 1997, hlm. 260. P.M. Handoko CM, Rekan-Anggota & Rekan-Pembangunan 31 persekutuan dan kehausan insani untuk bersatu dengan Allah. Pada tataran penghayatan itu, para mistikus dari ketiga agama itu memberikan kesaksian tentang pesan yang satu dan sama, dan memanggil umat manusia untuk mencari dan menemukan Satu Allah yang berada dalam relung hati mereka.4 Jika demikian, kerusuhan dan pertikaian antar agama harus ditelusuri bukan dengan mempersoalkan perbedaan-perbedaan pada tataran ajaran agama masing-masing, tetapi pada tataran penghayatan iman masing-masing. Dengan demikian, kesatuan yang merangkul bisa dicapai bukan dengan mendiskusikan ajaran agama-agama itu pada tataran ajaran, tetapi menyatukannya dalam penghayatan iman masing-masing. Dengan semangat ini, kita bisa mengerti ajakan Gereja katolik untuk melupakan pertikaian dan permusuhan di masa lalu, dan mendorong semua orang “supaya dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan.” (NA 3). 3. Visi Regnosentris tentang Agama-agama Lain Ajaran monoteis belumlah merupakan landasan yang kuat untuk menghayati iman yang merangkul. Kesadaran akan kesamaan asal-usul dan tujuan akhir kiranya tidak begitu saja memuluskan semua kerja sama dalam praksis iman. Kita tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap adanya perbedaan-perbedaan yang sangat potensial untuk mempersulit relasi antar penganut agama. Lagipula, para penganut agama-agama itu bukanlah para mistikus, tetapi “orang-orang biasa” yang menghayati iman mereka dalam hidup sehari-hari. Maka muncullah pertanyaan, apa yang bisa dijadikan dasar untuk kerjasama itu? Ajaran mana yang mendorong para pengikut agama-agama itu untuk memandang penganut agama lain secara positif tanpa kecurigaan sehingga dimungkinkan kerjasama yang tulus dan efektif untuk kebaikan bersama? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh masing-masing panganut agama. Dalam makalah ini, saya akan menyoroti pandangan Gereja katolik tentang siapakah penganut agama lain itu dan apa nilai agama-agama lain itu dalam keseluruhan rencana Allah. Umat katolik sendiri mungkin bertanya-tanya, kalau memang menyembah Allah yang satu dan sama, apakah tujuan keberadaan Gereja? Bagaimana misi Gereja harus dimengerti dalam konteks penghayatan iman yang merangkul ini? Apakah iman yang merangkul ini hanya strategi Gereja katolik Indonesia sebagai minoritas agar diterima dan tidak dimusuhi ataukah ini memang ajaran Gereja Universal yang mengalir dari keyakinan imannya? Kejelasan tentang hal ini sangat 4 32 Arnaldez, R. Trois messagers pour un seul Dieu, Paris: Albin Michel, hlm. 69 seperti dikutip oleh Jacques Dupuis, Ibid., hlm. 262. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 menentukan mungkin atau tidaknya suatu penghayatan iman yang merangkul, sebab penjelasan tentang hal ini akan memperjelas jati diri dan tugas perutusan umat katolik. Sangat penting diperhatikan bahwa kesamaan pandangan monoteis berarti bahwa semua agama itu akan berakhir pada satu muara, yaitu Allah sendiri. Titik Omega ini dalam Gereja katolik juga dikenal sebagai Kerajaan Allah. Pandangan teologis katolik tentang agama-agama lain dan peran mereka bisa dijelaskan dalam teologi tentang Kerajaan Allah ini. Harus diakui adanya berbagai pandangan teologis tentang Kerajaan Allah. Bahkan dokumen-dokumen Konsili Vatikan II sendiri bisa ditafsirkan secara berbeda untuk mendukung masing-masing pandangan teologis itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa cita-cita untuk memiliki penghayatan iman yang merangkul masih harus melalui perjalanan yang panjang. Tidak semuanya sudah jelas dan siap dijalani secara mulus. Banyak hal masih perlu diperjelas melalui praksis dan renungan lebih lanjut. Tetapi hidup ini harus terus bergulir tanpa harus menunggu konsep-konsep, sebab konseptualisasi akan baru datang kemudian. Benih-benih pengertian yang inklusif itu sudah bisa ditemukan dalam Konsili Vatikan II. Tulisan ini tidak bermaksud mengupas secara panjang-lebar proses pergulatan Gereja katolik, sebelum, pada saat dan masa setelah Konsili Vatikan II, untuk sampai pada penghayatan iman yang merangkul tersebut, karena analisa seperti itu akan membutuhkan makalah yang sangat panjang. Banyak buku yang sudah ditulis tentang hal ini.5 Pertama-tama harus dikatakan bahwa sangat penting membedakan antara Kerajaan Allah dalam kepenuhan eskatologisnya dan Kerajaan Allah sebagai realitas historis kita pada saat ini, artinya membedakan antara Kerajaan Allah yang “sudah datang” (bdk. Mrk 1:15; Luk 11:20; Mat 12:28) dan yang “belum penuh.” Allah telah memulai KerajaanNya di dunia ini dan dalam sejarah melalui dan dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam pewartaan dan tindakan Yesus, khususnya dalam wafat dan kebangkitanNya, Kerajaan Allah itu “sudah datang” dan terus berkembang menuju kepenuhan eskatologisnya pada akhir jaman (bdk. LG 5).6 Bagaimana hubungan antara Gereja dengan Kerajaan Allah itu? Harus diakui bahwa Lumen Gentium masih mengidentifikasikan Kerajaan Allah yang “sudah datang” itu dengan Gereja yang hadir dalam sejarah ini. Perbandingan antara LG 5 dan LG 9 cukup mewakili untuk menunjukkan kesimpulan ini. Lumen Gentium menegaskan bahwa Gereja adalah “benih dan awal dari Kerajaan” (LG 5: huiusque Regni in terris germen et initium constituit).7 Kemudian nomor yang sama melanjutkan: “Sementara itu Gereja lambat-laun berkembang, mendambakan Kerajaan yang sempurna, dan dengan sekuat tenaga berharap dan menginginkan, agar kelak dipersatukan dengan Rajanya dalam kemuliaan.” Berbicara tentang tujuan Gereja, Konstitusi dogmatis tentang Gereja itu berkata: 5 6 7 Analisa tentang pergulatan Gereja bisa diikuti dalam Jacques Dupuis, Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, New York: Orbis Books, 1997. Lihat Oscar Cullman, Christ and Time: The Christian Conception of Time and History, London: SCM Press, 1952. Bdk. Jacques Dupuis, Ibid., hlm. 334-336. P.M. Handoko CM, Rekan-Anggota & Rekan-Pembangunan 33 Tujuannya Kerajaan Allah, yang oleh Allah sendiri telah dimulai di dunia, untuk selanjutnya disebarluaskan, hingga pada akhir zaman diselesaikan olehNya juga, bila Kristus, menampakkan diri (lih. Kol 3:4), dan bila “makhluk sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan memasuki kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah” (Rom 8:21). (LG 9). “Penyelesaian” Kerajaan Allah (LG 9) nampaknya disejajarkan dengan Gereja yang berkembang menuju “Kerajaan yang sempurna” (LG 5). Kepenuhan yang satu disamakan dengan kepenuhan yang lain. Gereja disamakan dengan Kerajaan Kristus yang sudah hadir di dunia ini, meskipun masih dalam misteri (bdk. LG 3). Dupuis dalam studinya yang ekstensif atas teks-teks Konsili menyimpulkan: “For the moment it would seem right to conclude that in Lumen Gentium the Church and the Reign of God are still identified, both in their historical realization and in their eschatological fulfillment.”8 Pertumbuhan Gereja dipandang sebagai pertumbuhan Kerajaan itu sendiri. Namun demikian perlu dicatat bahwa Lumen Gentium tidak secara khusus memikirkan perbedaan antara Kerajaan yang “sudah datang” dan kerajaan yang “belum penuh.” Pandangan Lumen Gentium (diterbitkan 21 November 1964) ini nampaknya berbeda dengan pandangan dokumen Konsili Vatikan II yang terakhir, yaitu Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern Gaudium et Spes (diterbitkan 7 Desember 1965). GS 39 berbicara tentang pertumbuhan Kerajaan Kristus dan Kerajaan Allah dalam sejarah dan pemenuhan eskatologisnya. Tidak ada rujukan khusus kepada Gereja, tetapi nomor tersebut merujuk kepada seluruh umat manusia. Nomor itu diakhiri dengan mengatakan: “Di dunia ini Kerajaan itu sudah hadir dalam misteri; tetapi akan mencapai kepenuhannya bila Tuhan datang.” Para Bapa Konsili mempertegas tujuan Gereja: “Sementara Gereja membantu dunia dan menerima banyak dari dunia, yang dimaksudkannya hanyalah: supaya datanglah Kerajaan Allah dan terwujudlah keselamatan segenap umat manusia.” (GS 45). Maka bisa dikatakan bahwa Konsili Vatikan II berakhir dengan sikap yang sangat terbuka terhadap dunia pada umumnya. Kita bisa mengandaikan bahwa “dalam dunia” itu mencakup juga dan terutama, agama-agama. Gereja hanyalah “membantu dunia” dan tujuan Gereja bukanlah dirinya sendiri, tetapi Kerajaan Allah dan keselamatan segenap umat manusia. Posisi teologis GS melampaui apa yang digariskan oleh LG. Kemajuan lebih lanjut dalam pengertian relasi antara “dua” kerajaan di atas muncul dalam ensiklik Yohanes Paulus II Redemptoris Missio,9 yaitu pada bab kedua yang berjudul “Kerajaan Allah.” Ensiklik ini dengan jelas membedakan antara Kerajaan Allah sebagai “realitas eskatologis” dan realitas “yang sudah dekat dan sedang terjadi” (RM 13). Di antara dokumen-dokumen Gereja, RM adalah dokumen 8 9 34 Jacques Dupuis, Ibid., hlm. 336. Redemptoris Missio (Tugas Perutusan Sang Penebus), Ensiklik Bapa Suci Yohanes Paulus II tentang Amanat Misioner Gereja, 7 Desember 1990, Seri Dokumen Gerejani no. 14, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1991. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 pertama yang membedakan secara jelas keduanya, tetapi tidak memisahkan keduanya. Kerajaan Allah diperuntukkan bagi semua orang, dan semua orang dipanggil untuk menjadi anggota Kerajaan itu” (RM 14). Perwujudan Kerajaan itu di dunia ini tidak langsung dikaitkan dengan Gereja, melainkan dalam pembebasan dan keselamatan untuk “pribadi manusia baik dalam dimensi-dimensi jasmaniahnya maupun dimensi-dimensi rohaniahnya.” Dua sifat utama Kerajaan yaitu “menyembuhkan dan mengampuni,” (RM 14) juga tidak langsung dikaitkan dengan Gereja. Selanjutnya RM merumuskan kehadiran dan pertumbuhan Kerajaan dalam tataran nilai-nilai: Kerajaan itu dimaksudkan untuk mengubah hubungan-hubungan antar manusia; Kerajaan itu secara perlahan-lahan bertumbuh begitu orang secara lambat-laun belajar mencintai, mengampuni dan melayani satu sama lain. .....Kerajaan itu merupakan urusan setiap orang: pribadi-pribadi, masyarakat, dan dunia. Bekerja bagi Kerajaan berarti mengakui dan memajukan kegiatan Allah, yang hadir dalam sejarah manusia serta mengubah sejarah itu. Membangun Kerajaan berarti bekerja demi pembebasan dari kejahatan dalam segala bentuknya. Singkatnya, Kerajaan Allah itu merupakan pengejawantahan dan perwujudan-nyata dari rencana Allah dalam segala kepenuhannya. (RM 15). RM juga menegaskan dengan keras sekali bahwa Kerajaan itu sudah terwujud dalam Yesus dan diidentifikasikan dengan Yesus. Karena itu Kerajaan ini tidak bisa dipisahkan dari Yesus dan Gereja (RM18). Tugas Gereja ialah “melayani Kerajaan.” (RM 20). Gagasan yang sama tentang Kerajaan telah diungkapkan oleh Uskup-uskup Asia dalam Pernyataan Akhir Sidang Lokakarya Uskup-uskup ke II untuk hal-ikhwal antar Agama tentang Teologi Dialog di Pattaya, Thailand, 1985: Kerajaan Allah sendirilah dasarnya, mengapa ada Gereja. Gereja berada dalam dan demi Kerajaan Allah. Kerajaan yang dianugerahkan dan diprakarsai oleh Allah itu, sudah mulai dan terus-menerus diwujudkan serta dihadirkan melalui Roh Kudus. Dimanapun Allah diterima, bila nilai-nilai Injil dihayati, dimanapun manusia dihormati, di situ hadirlah Kerajaan Allah. Kerajaan itu jauh lebih luas dari lingkup Gereja. Kenyataan yang sudah hadir itu ditujukan ke arah penampilan mutakhir dan pemekaran paripurna Kerajaan Allah.10 10 “Pernyataan Akhir Sidang Lokakarya Uskup-uskup ke II untuk hal-ikhwal antar Agama tentang Teologi Dialog di Pattaya, Thailand, 1985,” no. 8.1., dalam Dokumen Sidang-sidang Federasi Konferensi-konferensi Para Uskup Asia 1970-1991, alih bahasa: R. Hardawiryono, SJ., Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1995, hlm. 423. Teks ini bisa dibandingkan juga dengan “Tesistesis tentang Dialog antar Umat Beragama” no. 6.3., dalam Dokumen Sidang-sidang Federasi Konferensikonferensi Para Uskup se-Asia 1995-1998 (volume I), alih bahasa: R. Hardawiryono, SJ, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1998, hlm. 143: “Fokus misi Gereja mewartakan Injil ialah membangun Kerajaan Allah, dan membangun Gereja untuk melayani Kerajaan itu. Oleh karena itu Kerajaan Allah lebih luas dari Gereja. Gereja ialah Sakramen Kerajaan yang menampilkannya, terarah kepadanya, memajukannya, tetapi tidak menyamakan diri dengannya.” P.M. Handoko CM, Rekan-Anggota & Rekan-Pembangunan 35 Konsultasi teologis yang diorganisir oleh Biro FABC untuk Evangelisasi yang diadakan di Hua Hin (Thailand) pada November 1991 tentang “Evangelisasi di Asia” menegaskan dengan lebih terurai: Oleh karena itu Kerajaan Allah hadir dan berkarya dimana-mana. Dimana pun manusia membuka diri bagi Misteri Ilahi yang adisemesta, yang mendorongnya untuk meninggalkan dirinya dalam kasih dan pelayanan kepada sesama manusia, di situlah berkarya Kerajaan Allah. . . . Dalam segala situasi itu manusia menanggapi tawaran rahmat Allah melalui Kristus dalam Roh dan memasuki Kerajaan Allah dengan menyatakan imannya. . . . Ini menunjukkan, bahwa Kerajaan Allah merupakan kenyataan universal, yang lingkupnya jauh melampaui batas-batas Gereja. Itulah kenyataan keselamatan dalam Yesus Kristus; di situlah umat Kristiani dan umat lainnya saling berbagi. Itulah “misteri kesatuan” yang fundamental dan menyatukan kita secara lebih mendalam daripada perbedaan-perbedaan keanggotaan kegamaan dapat memisah-misahkan kita. Ditinjau begitu, pendekatan “regnosentris” (berpusatkan Kerajaan Allah) terhadap teologi tentang misi sama sekali bukan ancaman terhadap perspektif Kristosentris iman kita. Sebaliknya “Regnosentrisme” memerlukan “Kristosentrisme”, dan sebaliknya. Sebab dalam Yesus Kristus dan melalui peristiwa Kristuslah bahwa Allah mendirikan Kerajaan-Nya di dunia dan dalam sejarah manusia.11 Berbagai pernyataan para Uskup Asia ini menunjukkan perkembangan pandangan tentang realitas Kerajaan Allah. Universalitas Kerajaan Allah berarti bahwa orang-orang Kristiani dan para penganut agama lain mengambil bagian dalam misteri Kerajaan Allah yang sama meskipun Kerajaan itu dicapai melalui jalan-jalan yang berbeda. Itulah misteri keselamatan Yesus Kristus. Oscar Cullman menyatakan bahwa Gereja dan dunia tidak boleh dibayangkan sebagai dua lingkaran yang berdampingan, yang bahkan tidak bersentuhan. Lebih tepat jika Gereja dan dunia dibayangkan sebagai dua lingkaran yang berpusat sama (ko-sentris) dalam Kristus.12 4. Rekan-Anggota dan Rekan-Pembangun Kerajaan Allah Telah dijelaskan bahwa para penganut agama lain menjadi anggota Kerajaan Allah melalui ketaatan dalam iman dan pertobatan kepada Allah. Demikian juga telah diungkapkan bahwa Kerajaan itu hadir di dunia dimana saja “nilai-nilai Kerajaan” dihayati dan dikembangkan. Redemptoris Missio menyatakan bahwa “realitas pada tahap awal dari Kerajaan” hadir dalam umat manusia “sejauh bahwa mereka 11 12 36 Biro FABC untuk Evangelisasi, Hua Hin, Thailand, tanggal 10 November 1991, “Kesimpulan-kesimpulan Konsultasi Teologis,” no. 29-30 dalam Dokumen Sidang-sidang Federasi Konferensi-konferensi Para Uskup Asia 1970-1991, alih bahasa: R. Hardawiryono, SJ., Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1995, hlm. 562-563. Oscar Cullman, Ibid., hlm. 187. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 menghayati nilai-nilai Injil” dan terbuka terhadap karya Roh yang berhembus kapan dan kemana saja Dia kehendaki” (RM 20). Maka kita bisa mengatakan bahwa para penganut agama lain sebenar-benarnya telah menjadi anggota aktif Kerajaan Allah itu melalui tanggapan iman kepada Allah yang mereka lakukan dalam tradisi keagamaan mereka. Melalui tradisi religius itulah mereka mengungkapkan iman mereka. Jika dipandang demikian, para penganut agama lain itu adalah rekan-anggota Kerajaan yang sudah hadir dan berkembang di dunia ini. Kenyataan ini harus mendorong “sesama-anggota” untuk meningkatkan persekutuan yang sifatnya lebih fundamental, daripada perbedaan-perbedaan lahiriah. Persekutuan yang mendalam dalam Roh mungkin dilakukan antara orang-orang Kristiani dengan para penganut agama lain. Dalam persekutuan itulah mungkin dilakukan dialog antar-agama sebagai bentuk “sharing,” baik untuk menerima maupun memberi. Sangat mungkin terjadi “saling-membagikan” (mutual-exchange). Kerjasama dan persekutuan membuat eksplisit persekutuan yang telah ada pada tingkat “keanggotaan” Kerajaan. Karena itu, membangun Kerajaan adalah tugas bersama. Membangun Kerajaan mencakup berbagai dimensi, baik horizontal maupun vertikal. Orang-orang Kristiani dan para penganut agama lain bersama-sama membangun Kerajaan setiap kali mereka mengusahakan pembebasan integral dari setiap pribadi, khususnya mereka yang miskin dan tertindas. Mereka juga mengembangkan Kerajaan ketika mereka menggalakkan nilai-nilai religius dan rohani. Kedua dimensi Kerajaan, insani dan religius, tidak bisa dipisahkan. Apa yang insani mengungkapkan apa yang religius. Visi regnosentris memberikan dasar teologis dan motivasi untuk penghayatan iman yang merangkul, meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam tata-cara maupun ungkapan iman. Para anggota tradisi religius lain adalah rekan-anggota Kerajaan dalam sejarah. Bersama-sama kita berziarah menuju kepenuhan Kerajaan, menuju umat manusia yang baru yang diinginkan oleh Allah pada akhir jaman. Bersamasama kita adalah rekan-pembangun Kerajaan bersama Allah. Dalam konteks inilah kita bisa berdoa bersama memohon agar masyarakat kita diperbaharui melalui penghayatan iman mereka secara sungguh. Dalam konteks inilah kita bisa bekerjasama dalam mewujudkan iman itu dalam praksis kemanusiaan, agar akhirnya datanglah umat manusia baru itu. Marilah membangun bersama-sama Indonesia menuju Indonesia Baru! P.M. Handoko CM, Rekan-Anggota & Rekan-Pembangunan 37 ALLAH, UNIVERSALITAS, DAN PLURALITAS Achmad Jainuri, PhD IAIN Sunan Ampel, Surabaya Abstraksi Harold Coward menulis sebuah buku menarik, Pluralism Challenge to World Religions. Gagasan pluralisme dewasa ini mendominasi dunia agama-agama. Coward bahkan menarik sebuah kesimpulan bahwa tingkat spiritualitas seorang agamawan ditentukan oleh bagaimana dia bersikap terhadap agama-agama lain. Tulisan ini menjabarkan tiga tesis menarik Coward seputar pluralisme: realitas transenden tampil dalam fenomena agama-agama (satu), ada pengakuan umum seputar pengalaman keagamaan tertentu (dua), identifikasi spiritualitas sendiri yang sering kali dipandang lebih tinggi dari agama orang lain (tiga). Rincian ide dari Coward ini dijabarkan untuk suatu pembahasan tentang dialog antarumat beragama. Sebuah pembahasan yang memiliki kepentingan perenial di Indonesia dan di dunia saat ini. Ada tesis menarik yang disampaikan oleh Harold Coward dalam membicarakan universalitas Tuhan dalam kaitannya dengan pluralitas agama. Ia mengatakan bahwa dalam menjawab tantangan pluralisme keagamaan masing-masing umat beragama harus memahami tiga prinsip dasar: (1) bahwa pluralisme keagamaan bisa dipahami secara baik melalui sebuah logika bahwa realitas transenden (Tuhan) muncul dalam fenomena agama yang beragam; (2) bahwa ada pengakuan yang umum di kalangan umat beragama tentang kualitas instrumental dari pengalaman keagamaan tertentu; dan (3) bahwa spiritualitas biasanya diidentikkan dengan ketinggian kriteria diri sendiri atas agama orang lain.1 Prinsip pertama dan kedua merupakan elemen penting yang perlu ditanamkan dalam menumbuhkan kesadaran beragama. Sedang prinsip ketiga merupakan fenomena yang masih kuat melekat di sebagian besar pemeluk agama, dan karenanya harus bisa dipecahkan. Tuhan dan Pluralitas Agama Prinsip pertama, seperti yang disebutkan di atas, bisa ditemukan dalam pandangan Weda tentang Yang satu yang memiliki banyak nama. Seorang Budha yakin bahwa hukum sebab akibat dari Karma adalah realitas tunggal yang menjadi 1 38 Harold Coward, Pluralism Challenge to World Religions (Maryknoll. NY: Orbis Books, 1985), hal.95. Vol. 1 No. 1, Maret 2001 rujukan bagi semua agama. Sumber Kitab Suci Yahudi dan Kristen menyebutkan bahwa semua manusia dan bangsa berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu: mereka juga mengakui pandangan filsafat Yunani tentang Logos. Dalam Islam ditemukan istilah umm al-kitab yang menjadi kumpulan dari semua kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi logika Yang Satu yang menjelma menjadi yang banyak merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih tetap menarik untuk membicarakannya dalam kaitannya dengan pluralisme agama.2 Oleh karena ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana posisi Yang Satu ini di antara yang banyak; bagaimana hubungan antara keduanya; apa implikasi hubungan ini bagi doktrin suatu agama tentang agama lain? Berkaitan dengan hubungan internal antara Yang Satu dengan yang banyak, semua agama nampaknya sepakat untuk menempatkan Yang Satu sebagai sumber spiritual. Menyamakan sumber spiritual dengan Yang Satu memungkinkan yang banyak berubah tanpa merusak Yang Satu. Konsep ini menunjukkan bahwa Yang Satu adalah Yang Mutlak dan yang banyak adalah relatif karena perubahan yang dialaminya. Oleh karena itu kekayaan pluralitas memberikan dinamika kepada banyak agama untuk kembali kepada sumber spiritualnya. Di sini pusat gravitasi tetap pada Yang Satu tanpa menghilangkan yang banyak. Jika yang banyak itu diartikan sama dengan agama yang beraneka ragam maka agama hendaknya dipandang sebagai jalan untuk mengetahui sumber spiritual semua agama secara mendalam. Dalam membicarakan Yang Satu sebagai sumber segala-galanya, seorang sufi sekaligus filosof Muslim abad ke-12 dan 13, Ibn Arabi menjelaskannya dalam konsep wahdat al-wujud (monisme). Ia dipandang sebagai seorang pemikir Muslim yang memberikan interpretasi filosofis yang memecahkan berbagai persoalan dualisme. Ia disebut sebagai seorang minist karena pemikirannya dalam membuktikan non-dualitas dari segala sesuatu menyangkut hubungan antara Tuhan dan alam, persoalan antara Tuhan yang sempurna dan alam yang tidak sempurna, baik dan buruk, kekuasaan Tuhan dan kehendak manusia. Berkaitan dengan hubungan antara Tuhan dengan alam, Ibn Arabi menyatakan bahwa “tidak ada sesuatupun di alam ini kecuali Tuhan”. Ia menolak konsep Tuhan sebagai pencipta dan penyebab terjadinya alam ini, dan mengatakan bahwa Tuhan adalah “everything”sebuah unifikasi yang mutlak. Bagi Ibn Arabi Tuhan bukanlah sosok yang menciptakan tetapi Ia yang menjelmakan diriNya sendiri ke dalam yang tidak terbatas. Karena Tuhan merupakan esensi dari semua wujud, maka manusia membutuhkanNya agar supaya ia bisa hidup. Sebaliknya Tuhan membutuhkan manusia agar Ia bisa menjelmakan diri ke dalam diriNya sendiri. Ibn Arabi menegaskan bahwa esensi ketuhanan itu adalah murni tanpa atribut dan sifat. Tuhan memiliki sifat ketika Ia menjelmakan diri apakah di alam raya atau dalam manusia, karena semua wujud yang ada merupakan atributNya. Karena alam seisinya ini adalah manifestasi sifat Tuhan maka keberadaanNya adalah relatif hanya eksistensi Tuhan saja yang absolut. Berkaitan dengan persoalan keesaan Tuhan dan berlipat gandanya wujud yang ada di alam ini, Ibn Arabi menyatakan bahwa hanya ada satu Realitas yang di 2 Ibid. Achmad Jainuri, Allah, Universalitas dan Pluralitas 39 sebut al-haqq. Realitas tunggal ini hanya bisa dianggap banyak apabila dilihat semata sebagai manifestasi dari esensi Tuhan. Bagi Ibn Arabi wujud yang berlipat ganda tidak memiliki realitas spiritual karena wujud ini bukanlah bagian dari Yang Satu. Hanya pandangan manusia sendirilah yang mengatakan seolah-olah semua wujud di alam ini memiliki realitas spiritual. Manusia hanya bisa melihat bagian terkecil dari keseluruhan. Mereka ini tidak mampu menembus sesuatu di luar permukaannya sendiri. Menurut Ibn Arabi hubungan antara Tuhan dan wujud di alam semesta ini laksana sebuah benda yang memantul ke dalam bayangan yang tidak terhingga jumlahnya. Semua bayangan ini jelas tidak akan pernah bisa tampak tanpa Dia. Dengan kata lain semua ini bukanlah Dia. Mereka bisa menjadi Dia apabila mereka sadar bahwa bayangan yang memantul itu semata adalah refleksi, dan mereka tidak bisa menjadi Dia ketika melupakan obyek yang memantulkan diri mereka dan menerimanya sebagai realitas sesungguhnya. Pengalaman Keagamaan dan Pluralitas Berbicara tentang agama sebenarnya menyangkut banyak segi, baik yang berkaitan dengan ajaran agama itu sendiri maupun yang berhubungan dengan pemeluk agama yang bersangkutan. Agama bersumber dari wahyu Tuhan dan menjadi bentuknya yang terakhir melaui proses pengalaman sejarah kehidupan manusia yang cukup panjang. Oleh karena itu agama bukan hanya menekankan segi eskatologis tetapi juga secara fenomenologis muncul dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan umat pemeluk agama. Selain nilai ajaran agama itu sendiri, maka latar belakang pribadi masing-masing pemeluk agama turut pula membentuk pengalaman keagamaan yang bersangkutan. Faktor ini kemudian menumbuhkan keberagaman pada diri para pemeluk agama baik di tingkat rasionalitas pemahaman ajaran maupun pada ikatan emosional keagamaannya. Karena itu jika seseorang berbicara tentang agama, maka di situ terdapat persamaan dan perbedaan muatan karakter yang terkandung dalam ajaran setiap agama. Pada akhirnya persamaan dan perbedaan tersebut membentuk pula garis sejajar pada jajaran pemeluk agama yang diformalkan menjadi sebutan: umat Hindu, Budha, Yahudi, Nasrani, Islam, bahkan kemudian terpecah lagi menjadi paham aliran besar seperti: Hindu-Bali, Hinayana, Mahayana, Hasyidiyah, Katolik, Protestan, Sunni, Syiah, dan sebagainya. Persamaan serta perbedaan ini juga tergambarkan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Karena itu yang penting adalah bagaimana umat yang beragama itu hidup bersama dan berhubungan satu sama lainnya tanpa hambatan psikologis karena berbeda paham keagamaan. Pada titik ini ada sebagian orang yang mencoba mengangkat kembali persoalan pemahaman keagamaan untuk menentukan persamaan ajaran yang terdapat dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dengan dasar ini mereka berharap bisa membantu mewujudkan kehidupan yang saling menghargai di tengah-tengah pluralitas keagamaan di Indonesia. 40 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 Tetapi karena perhatian hanya diarahkan pada unsur persamaannya saja, hal ini dikhawatirkan akan mengesampingkan makna dari label atau “nama” yang terdapat pada masing-masing agama. Di sinilah persoalannya orang akan terjebak pada permainan label atas dasar adanya kesamaan ajaran di antara agama-agama tersebut, tetapi mereka lupa tidak merinci lebih detail unsur persamaan yang ada pada agamaagama yang disamakan sehingga terkesan abstrak. Perincian ini penting karena, pertama, dalam nama itu tidak hanya memuat persamaan tetapi juga perbedaan. Kedua, bahwa dalam perbedaan itu memuat juga aspek ajaran yang sangat fundamental bagi masing-masing agama. Atas dasar perbedaan yang ada maka Kristen itu bukan Islam, dan demikian juga sebaliknya Islam itu bukan Kristen. Memang pada akhirnya dalam persoalan ini “nama” menjadi sangat penting. Karena di samping ia memiliki nilai sejarah dan karakteristik ajaran tertentu ia mampu menumbuhkan ikatan emosional bagi penyandang “nama” tersebut. Memang di kalangan para ahli ilmu agama ditemukan sesuatu ide bahwa secara ideal agama itu berasal dari sumber yang sama, yakni Zat Yang Maha Tinggi, yang diturunkan kepada umat manusia. Karena itu secara esensial agama yang ideal ini memiliki ajaran yang sama, meski dalam aspek ajaran yang lain berbeda. Dalam teori kenabian disebutkan bahwa persamaan ini meliputi prinsip ajaran tentang keEsa-an Tuhan sedang perbedaannya menyangkut hukum yang mengatur tentang kehidupan sosial kemasyarakatan serta masalah kemanusiaan lainnya. Yang terakhir ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa agama-agama yang diturunkan itu berkaitan erat dengan kondisi kehidupan manusia yang beragam. Prinsip ini yang menurut Islam diajarkan oleh para nabi sejak zamannya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Namun dalam perjalanan sejarah, dari prinsip ajaran yang sama (keEsaan Tuhan) ini muncul rumusan yang tidak sama. Perbedaan ini terlihat manakala Islam dan Kristen sekarang ini berbicara tentang konsep keEsaan Tuhan tersebut. Dalam agama Kristen misalnya rumusan yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses perjalanan sejarah yang amat panjang. Meskipun diyakini bahwa proses serupa masih terus berjalan. Selain Kitab Perjanjian Baru, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Gereja yang menjadi dasar rumusan teologis sekarang ini barangkali keputusan yang dihasilkan oleh Konsili Nicea tahun 325. Kekuatan keputusan yang dihasilkan menjadi landasan resmi ajaran Gereja tentang rumusan ketuhanan. Perbedaan-perbedaan tentang dasar ajaran Kristen ini ternyata terus berlangsung dan menghasilkan perbedaan yang cukup fundamental di kalangan Kristen. Di antara hasil perbedaan tersebut pada abad pertengahan muncul Kristen Protestan yang dalam banyak hal berbeda secara prinsip dengan Katolik. Karena perbedaan ini Protestan dan Katolik mewakili mainstream tradisi ajaran yang disejajarkan bobotnya secara kategoris dengan Hindu, Budha dan Islam. Pengakuan ini setidak-tidaknya yang menjadi landasan pemerintah Indonesia untuk mencantumkan lima nama agama: Budha, Hindu, Islam, Katolik, dan Protestan yang dianggap mewakili masyarakat beragama di Indonesia. Demikian di kalangan masyarakat Muslim pemahaman tentang Tuhan Yang Esa telah memunculkan berbagai ragam pendapat dikaitkan dengan zat, sifat dan fungsi yang terkait denganNya. Berkaitan dengan sifat Tuhan, selain pandangan Ibn Achmad Jainuri, Allah, Universalitas dan Pluralitas 41 Arabi yang telah disebutkan di atas, terdapat dua aliran teologis besar yang berbeda pendapat. Asy’ariah misalnya berpandangan bahwa Tuhan memiliki semua sifat seperti yang disebutkan dalam al-Quran dan bahwa semua sifat seperti Tuhan memiliki kaki, tangan, telinga, mata dan duduk di atas singgasana hendaknya diartikan secara literer. Pandangan tentang sifat Tuhan seperti itu merupakan pandangan anthropomorphism yang melihat eksistensi Tuhan secara fisik. Pemahaman mengenai Tuhan seperti ini oleh sebagian kalangan disamakan dengan pemahaman mengenai Tuhan melalui konsep Trinitas dalam agama Kristen. Pandangan Asy’ariah seperti di atas ditolak oleh Mutazillah yang menolak sifat Tuhan berada di luar esensiNya. Perdebatan tentang semuanya telah melahirkan aliran teologi yang beraneka ragam jumlahnya dengan label yang berbeda. Perbedaan-perbedaan dalam memahami agama pada akhirnya memunculkan nama besar dalam komunitas Islam seperti Sunni dan Syi’i. Dari sini menunjukkan bahwa “nama” atau label sesungguhnya memuat dimensi perbedaan ajaran seperti yang diuraikan di atas. “Nama” di sini bukan sekedar nama, bukan pula “apalah arti sebuah nama” sebagaimana Shakespeare menanyakannya, tetapi nama yang mempunyai nilai historis serta karakter ajaran yang istimewa bagi masing-masing penyandang “nama” tersebut. Ungkapan seperti “Kristen bukan Islam” atau “Islam bukan Kristen” hendaknya dipahami dalam batas yang wajar atas dasar ciri ajaran yang ada pada masing-masing agama tersebut: bukan merupakan ungkapan yang dipahami untuk menghilangkan satu sama lainnya. “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” yang disebutkan dalam Quran jelas memberikan landasan perintah larangan untuk “saling menghilangkan”, meskipun mungkin ada yang memahaminya sebagai peng-kotak-an umat beragama. Catatan Penutup: Membangun Dialog Ada satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam membangun wawasan keagamaan yang merangkul, yaitu menekankan pada pendekatan dialogis. Dialog itu sendiri sebenarnya berpijak pada satu asumsi bahwa tiap-tiap agama memiliki klaim keabsolutan atas keyakinannya sendiri yang tidak bisa direlatifkan. Oleh karena itu persyaratan dialog sesungguhnya bukan menyamakan semua keyakinan tetapi pengakuan bahwa masing-masing orang beragama memiliki komitmen akan keyakinannya sendiri, dan keyakinan yang dimiliki oleh semua umat beragama itu berbeda. Umat Kristiani meyakini Tuhan melalui Yesus Kristus, umat Muslim meyakini al-Quran sebagai kalam Tuhan terakhir, umat Hindu percaya akan adanya banyak jalan menuju Satu Brahmana (absolutisasi sebuah relativisme) dan seterusnya. Dalam pendekatan dialog ini masing-masing agama dipandang memiliki sebuah kemutlakan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dialog semacam ini memerlukan kedewasaan ego yang cukup tinggi “untuk membiarkan orang lain yang berbeda itu hidup bersama-sama tanpa memandang bahwa mereka itu bisa disamakan”. Jika semua keyakinan seperti ini dipahami oleh semua pemeluk agama, maka dialog akan 42 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 bisa berjalan lancar. Suasana ketentraman hidup beragama itu bisa dicapai melalui dialog dan tanpa harus menghilangkan identitas serta ciri yang ada pada perbedaan agama masing-masing. Kita harus yakin bahwa dengan memberikan kebebasan tumbuhnya perbedaan ciri masing-masing agama kepada pemeluk suatu agama secara psikologis akan menciptakan ketenangan kepada pemeluk agama yang bersangkutan, dan demikian juga sebaliknya mereka akan bersikap yang sama terhadap pemeluk agama lain. Achmad Jainuri, Allah, Universalitas dan Pluralitas 43 SOCIAL CONSTRUCTION OF BALINESE WORLD AND CHRISTIANITY Dr. Ray Sudhiarsa, SVD STFT Widya Sasana, Malang Abstract: Artikel ini merupakan pengolahan ulang bagian kedua dari paper yang pernah dibawakan sebagai ‘kuliah perdana’ pada pembukaan tahun akademis 2001-2002 STFT Widya Sasana Malang, 10 September 2001. Di sini penulis menganalisis kondisi historis, sosial, politis, dan kultural masyarakat Bali dalam hubungannya dengan kehadiran Gereja-gereja di sana. Gereja selalu berusaha menjadi bagian integral dari masyarakat dan kebudayaan Bali, namun setiap kali dia masuk, setiap kali pula dia terlempar ke luar. Analisis historis kultural ini menunjukkan bahwa memang pada dasarnya masyarakat tradisional Bali adalah komunitas-komunitas tertutup yang ‘lengkap’. Kenyataan ini diperteguh oleh kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang menduduki pulau Bali (18821950), khususnya politik isolasi dan Balinisasi yang diterapkannya pada pertengahan pertama abad ke-20. Pada bagian akhir, penulis tidak memberikan kesimpulan, melainkan menawarkan pekerjaan rumah, yakni poin-poin yang harus dipertimbangkan oleh Gereja dalam mengaktualkan kehadiran dan misinya di dalam masyarakat setempat. INTRODUCTION The goal of this article is to examine the Balinese world, in which Christianity1 has been struggling to be its integral part. The issue is that every time Christianity tries to enter, every time it is denied to get access. It is more impossible to redefine and reconstruct Balinese community based on a multicultural society. Already in 1924 Soekawati,2 a member of the Volksraad in Batavia (now, Jakarta) and the head of the district of Ubud, Bali, strongly opposed the present of Christianity on the island, saying: “Westersche invloeden, welke ook, zijn welkom, alleen de 1 2 44 According to the official statistics (1995), in Bali live 2.631.210 Hindus, 158.564 Muslims, 16.037 Buddhists, 11.957 Catholics and 10.258 Protestants (BPS Kantor Statistik Propinsi Bali, Bali Dalam Angka 1995, Denpasar: BPS, 1996, p. 133). Cokorda Gde Raka Soekawati later on became the President of the State of East Indonesia (NIT, Negara Indonesia Timur), established under Dutch auspices in December 1946, with Anak Agung Gde Agung as Prime Minister and minister of the interior. NIT collapsed in 1949-1950 with the downfall of Dutch power in Indonesia, and Bali eventually joined the Republic of Indonesia. “Educated in the Netherlands, married to a French woman, and having lived much of his adult life outside of Bali, he was regarded by many people at home as arrogant and excessively westernized (kebarat-baratan)” (Robinson, 1995:171). Vol. 1 No. 1, Maret 2001 christelijke godsdienst niet” (all Western influences whatsoever are welcome, but never Christianity). In the first few months of the year 20003 emerged another wave of opposition against Christian presence, which might echo the long lasting resistance against Christianity on the island. Few decades ago a Balinese leading person was cited of expressing his bitterness towards Christian missions. On the eve of the opening of the Catholic mission station, the ruler of Karangasem asked that the missie should not be allowed to open either a school or a hospital, because he felt that those attending either place of western influence would inevitably fall under the spell of Christianity, children and sick people being easy prey for Christian propagandists (Webb, 1986:33). What does this all mean for the churches (Catholics as well as Protestants)? In my opinion, we can start our investigation by citing the statement highlighted by the late Anak Agung Gede Agung in an interview conducted by the research team of the CRI Alocita, Yogyakarta.4 He insisted that in Bali adat, agama, dan budaya (tradition, religion, and culture) have to be accepted as a unity, an integrated one.On the other hand, the role of the Dutch colonialism in the first half of the twentieth century was very influencial in reconstruting the Balinese society. It could not be ignored. BALINESE COMMUNITY There are three important aspects in the traditional community which make Bali a closed community, namely community of ancestry, caste system, and customary village. Descent group: community of ancestral group The traditional Balinese community is basically an association of blood relation, which refers to the common ancestors (tunggal kawitan) that bind the members in their exclusive patrilineal ancestry. Within this closed community, the people worship their common deified ancestors (pitara, common origin)5 – real or fictional 3 4 5 E.g. Putu Setia, “Om Swastyastu,” http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2000/3/4/bd4.htm; Putu Setia, “Adat,” http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2000/3/18/bd3.htm; Bali Aga, “Dinilai Rancukan Ajaran Hindu: PHDI Kecewa Sendratari Natal di TVRI,” Bali Aga, Denpasar (29 December 1999); Bali Aga, “Kepala Siaran TVRI Denpasar Mengaku Kecolongan,” Bali Aga, Denpasar (29 December 1999); Bali Post (sut), “Tantangan PHDI, Inventarisasi Simbol Hindu, Bali Post, Denpasar (23 January 2000); Bali Post (sut), “Mengantisipasi Penetrasi Simbol Hindu,” Bali Post, Denpasar (23 January 2000). Interview with the late Anak Agung Gde Agung, a leading figure in Bali’s history. He insisted that adat, agama, dan budaya (tradition, Bali-Hinduism, and culture) blended in a way that have composed the one whole Bali’s identity (CRI Alocita, Yogyakarta, October 1996). Spirits of the dead are commonly distinguished in three groups, namely pirata, pitara, and dewa hyang. The piratas are the spirits of the dead and are considered unclean and dangerous. The pitaras are those who Ray Sudhiarsa SVD, Social Construction of Balinese World and Christianity 45 – who are believed to have been merged in the deity (dewata). Every female incorporates herself into her husband’s ancestral origin (kawitan), performing rituals in his ‘genealogical temple of origin’ (pura kawitan, pura dadia, pura panti, pura pamaksan), in the household shrine (sanggah, mrajan) or in the bigger temple of her father-in-law (sanggah gede). Balinese community is a social and spiritual bond of the living and the dead, sekala (the visible world) and the niskala (the invisible, the dead, the gods and spirits). On every temple anniversary the deified ancestors and the gods are invited to come down from their heavenly abode to inhabit the temple, to join the festivals, and to receive offerings and worships from their family (descendants). The gods are thanked for the prosperity of the earth and offered the ‘first-fruits’ of the harvest. Through the medium, they are also expected to convey some advice and/or request to their descendants, particularly if there is a sick person in the family. Eiseman (1995:61) remarks: Under normal circumstances the ordinary small canang will do as offerings. But is (sic) is not unusual for a family to promise to prepare a larger offering if the god of a particular temple will grant a special wish. This wish more often than not is a request that a sick person regain (sic) his health. If the wish is granted, the wife has to prepare a high offering and carry it to the temple as a masaudan, the fulfillment of the promise. And the lay priest, the pemangku, performs a special little ceremony in which this offering is made to the gods in question. Frankly speaking, religious life is primary to Balinese identity. Religious aspects dominate the private as well communal life, except with regard to the content of the doctrine. It is said that nobody would take doctrine seriously, or more precisely, in most cases, the Balinese do not know or do not want to know the nature of niskala (divine, sacred, invisible world, gods, spirits, and supernatural realm). On this ground, Geertz (1973:177) argues: You can believe virtually anything you want to actually, including that the whole thing is rather a bore, and even say so. But if you do not perform the ritual duties for which you are responsible you will be ostracized, not just from the temple congregation, but from the community as a whole.6 As a matter of fact, the Balinese kin-groups (dadia, wangsa, batur) frequently overlaps caste divisions. 6 46 have been purified through a series of rituals. The dewa hyangs are those who have been merged into the deity and have no more individuality. Many ordinary people, however, do not distinguish the pitara from the dewa hyang. So they call the two groups as ‘Batara Hyang’, ‘Dewa Hyang’, and ‘Pitara Hyang’ interchangeably. Scures (1994:57-8) writes: “[...] changing faith (through marriage or conversion) means that a Balinese person is no longer Balinese. What remains important among the Balinese is attention to ritual duty.” Vol. 1 No. 1, Maret 2001 Cast system: insiders and outsiders Balinese society has been for centuries divided into two groups of the minority ‘upper’ triwangsa and the majority ‘lower’ jaba class. The first group consists of three castes, namely brâhmana, ksatrya (satria, satriya) and vaiœya (wesya, waisya), and the second are the commoners, the ‘outsiders’ or the úûdra. “This, of course, is more than a little ironic,” Eiseman (1996:34) argues, “because the triwangsa, and the rest of Hinduism, came to the original inhabitants of Bali by way of the Javanese.” This caste system has been imposed on the Balinese social conscience for the benefit of the ‘upper’ three castes, especially for the superiority of the Pedanda (brâhmana priests) who regard themselves as the embodiment of the gods on earth. The brâhmana priests, who claimed to be the direct descendants of the sixteenth century Shaivite Hindu priest Dang Hyang Nirartha,7 a Javanese, have preserved for themselves all the knowledge of the sacred manuscripts and anything to do with the gods. Dang Hyang Nirartha came to Bali sometime before 1537 following the fall of the Hindu Majapahit Empire of Java in 1515 and joined the mass Javanese refugees to escape their Muslim conquerors. This division does not merely mean a social separation between the two exclusive groups (insiders-outsiders), but also a support to feudalism (upper-lower class). This ‘triwangsa-jaba’ construction is considered as the ideal way to describe the Balinese social order from the sixteenth century to the present day. The Dutch colonialism regarded the triwangsa the main vehicle of Hinduisation of the island, the pillar of the traditional order, the fundament of Balinese culture and society, and the barrier against Islam and the spirit of nationalism. This system was institutionalised particularly during the period of the Dutch colonial occupation (we will discuss later). In order to make simpler the colonial administration, the Dutch authorities chose Ida Wayan Pidada, the brâhmana priest of Gria (priestly house) Pidada, Klungkung (Vickers, 1996:147; Schulte Nordholt, 1996:240) to be their adviser. A consultation organised by three priests of the north Bali and three others of Gianyar conducted by Ida Wayan Pidada of Klungkung was held and it was decided who belonged to whom and what rights and duties each caste had. Vickers (1996:147-8) mentions: All the Dutch authorities, even later researchers such as Korn, depended on him and his priestly brethren to give the most expert advice, ignoring others 7 Nirartha was regarded as the author of several ‘kakawin’ (epic court literature) including the Usana Bali (composed between 1550-1560) and known in various names such as Dang Hyang Nirartha, Pedanda Sakti Wawu Rawuh, and Dang Hyang Dwijendra. He came to Bali, arrived at Purancak, on his long journey from Majapahit headquarters to Daha, to Pasuruan and then to Blambangan. The Brâhmanas of Nirartha’s descendants are now known as ‘Catur Brâhmana’ (the four groups of Brâhmana), namely Brâhmana Mas, Brâhmana Keniten, Brâhmana Manuaba and Brâhmana Kemenuh. They are different from the other ‘Panca Brâhmana’ (the five Brâhmana), namely Mpu Semeru, Mpu Gana, Mpu Kuturan, Mpu Beradah and Mpu Genijaya who lived prior to them and had similar responsibility as a priest. See M.J. Wiener, 1995: 123-4; N. Djoni Gingsir, 1996:117-20, 259-62. Ray Sudhiarsa SVD, Social Construction of Balinese World and Christianity 47 with some claim to expertise, such as the various types of commoner priests, and even the female priests from the brahmana caste. Customary community: desa/banjar adat8 Each desa (village) community is a corporate unit, which shares a collective descent from the desa founders, namely the deified ancestors or ‘common origin’ of the whole desa. It means that one who comes from outside and lives in the desa can never be a full member (pengarep) of the desa. He or she can at best be a pengempian who generally pays half-contributions for the temple ceremonies and other levies. He or she is treated as just a guest or tenant without any obligation to participate in the adat affairs,9 and, therefore, has no right to use the desa’s property as well. In the last few decades, this corporate desa community has been defined as desa adat (customary village, corporate law village community) which strictly means a ‘Bali-Hindu community’.10 Its unity is characterised by three elements, namely territory, members, and temples (palemahan, pawongan, parhyangan), which make Bali a ‘steady and harmonious world’ (gumi enteg). There are three main temples called Kahyangan Tiga for each desa adat.11 Also introduced was a concept of an island-wide temple, even a ‘worldwide’ temple, pura jagatnatha (1962) for the worship of Jagannath, Lord of the World (Hooykaas, 1973:3), which has been built in the centre of Denpasar, the capital city of Bali. In this ‘modern’ temple, people can theoretically worship their deified forefathers in unity with the gods and deities in the One Divinity, Sang Hyang Widhi, which emphasises that the whole Bali is sacred for the people. To some extent, Bali as a whole is also regarded as a large community, i.e., a home. Not surprisingly, if two Balinese are abroad, they address each other: “Ten 8 9 10 11 48 The word ‘desa’ is usually translated as ‘village’, while ‘banjar’ is ‘ward’ or ‘hamlet’. Therefore, ‘desa adat’ should be ‘customary village’ and ‘banjar adat’ should be ‘customary ward.’ But, according to the surveys so far available from the Law Faculty of Udayana University (Denpasar), nearly half the desa adat of the district of Badung, Klungkung and Karangasem were comprised of single banjar (Warren, 1991: 213ff). Picard translates ‘adat’ as “custom; local customary law, institutions, and ritual,” while Vickers puts it as “tradition or customary regulations.” (Picard, 1996: 203; Vickers, 1996:223). Goris (1960:293) writes: “The relation between adat law and Hindu canon law in early Java and present-day Bali might well be compared to that between early Germanic law and Christian canon law in medieval Europe.” Desa adat might not neatly fit the actual village structure in most of Bali, but no doubt this common perception gives great social and political advantages to Bali-Hindus against the non-Bali-Hindus. It significantly supports their concept that desa adat is a ‘closed and steady community’ tied by the classic three village temples as mentioned above. Furthermore, many Bali-Hindu intellectuals of today ardently promote the idea of desa adat as a conceptual and ideal Hindu village community. Ketut Wiana, for example, mentions that desa adat consists of three different spaces called tri-mandala, namely utama mandala (temples), madya mandala (space where human beings live), and nista mandala (graveyard) (Wiana, 1995:44). Each Balinese adat village has three public pura, known as kahyangan tiga, which may be visited by members of all strata and castes: the uranian temple of creation or origin (pura puseh), located mountainward, in the purest part of the village; the village temple (pura desa), with its large assembly hall for the traditional village council (bale agung); and the chthonian temple of death (pura dalem), which is attached to the cemetery and is located seaward, low and hence in the most impure area of the village (Hobart et.al., 1996:127). Vol. 1 No. 1, Maret 2001 mantuk ka Bali?” (Don’t you go back home to Bali?). They seem to have a close relationship to each other on the ground of the same land, the earth. What lies behind this idea is nothing more than that the land is the inheritance of the gods, their forefathers. Therefore, the Balinese social life is overwhelmed with religious elements in connection with their ancestors, which create and perpetuate the relation among the individuals. ROLE OF THE DUTCH COLONIALISM After the Dutch Colonial Authorities could establish their power over the most part of Indonesia, they also managed to establish their economic and political control over Bali. They sent several expeditions against Buleleng (North Bali) and Karangasem (East Bali) in 1846-1849 to ‘teach the Balinese a lesson’, because the Balinese refused to be their subjects. The Balinese responded in the words best expressed by the chief minister of Buleleng: “Let the keris [wavy-bladed dagger] decide” (Vickers, 1995:30). In 1858 the Dutch sent the fourth military expedition to make Buleleng subservient. In fact, only after the fifth military aggression (1882), North Bali was completely under the Dutch East Indies control. At the turn of the twentieth century, the Dutch colonial authorities were struggling to control the whole island. They forced the Kingdom of Gianyar to accept the status of Regency under Dutch sovereignty in 1900. Six years later the Dutch troops landed at Sanur coast on their way westward to attack south Bali, followed by puputan (ending)12 of the princely families of Badung and Tabanan. The puputan was described as nothing but a mass-suicide, where everybody was entirely dressed in white to face the Dutch troops, who were apparently superior in everything. Armed with only lances and keris, the Balinese refused to surrender. They stepped forward to face their death before their conquerors. Two years later (1908) the kingdoms of Mengwi and Bangli were subjected to Dutch rule, following the puputan of the most prestigious royal family of the Gelgel dynasty of Klungkung. It was the end of the lineal descendants of Majapahit, the kingdom of the Dewa Agung. An era in Balinese history was ended and the new one started. Vickers (1996:133) puts it as follows: Those few members of the royal families of Badung and Klungkung who survived the slaughters of 1906-1908 were sent into exile, to join members of other important Balinese families who were not willing to accept Dutch authority. The royal families who remained lost much of their power and 12 The Balinese ‘puputan’ is translated and interpreted in various ways such as ending, fight to the death cum self-sacrifice, a kind of ‘holy war,’ massacre and suicide. In a word of a Balinese king: “It is better that we die with the earth as our pillow than to live like a corpse in shame and disgrace” (Vickers, 1995: 32). Ray Sudhiarsa SVD, Social Construction of Balinese World and Christianity 49 authority. In all their actions they were closely watched by Dutch officials, whom the Balinese rajas were forced to think of as their ‘older brothers’, making it clear for all to see that the Dutch were at the top of Balinese society. The politics of ‘Baliseering’ The horrible series of puputan of the early 20th century shocked Europeans. Agitation provoked in Holland and foreign diplomatic circles made the colonial Dutch embarrassed. It was said that they could not easily cover up or obliterate the memory of their brutal acts towards the indigenous in those serial military interventions. Therefore, some new policy had to be taken to create a new image of the Dutch East Indies for the international public. The Dutch colonial government then introduced a new strategy called ‘ethical policy’.13 Suffice it to say that by this policy, the Netherlands government acknowledged its ‘moral obligation’ toward the welfare of its subjects, the inlanders (natives). However, as many scholars argue, with this new approach the Dutch could more deeply consolidate its colonial grip on the local societies and expand its boundaries. In the name of accelerating reformation of the indigenous with the ideal of ‘peace, order and welfare’, the colonial administration felt both obliged as well as justified in their action (Picard, 1996: 20). The Dutch were struggling to develop a worthier self-image in Bali, based on this policy of preserving the Balinese culture. They claimed that their role now was one of trusteeship to keep Bali the paradise it is today (McKenzie, 1988:11) – protecting and preserving Bali from outside harmful influence and exploitation. The policy was known as Baliseering, Balinization of Bali, to protect and preserve Bali from outside influence and exploitation. In 1924 G.P. Rouffaer, a former director of the Bali Instituut, which was part of the Koloniaal Instituut (1915), provided the classic statement of the preservationist position: Let the Balinese live their own beautiful native life as undisturbed as possible! Their agriculture, their village life, their own forms of worship, their religious art, their own literature -all bear witness to an autonomous native civilization of rare versatility and richness. No railroads on Bali; no Western coffee plantations; and especially no sugar factories! But also no proselytizing, neither Mohammedan (by zealous natives from other parts of the Indies) nor Protestant nor Roman Catholic. Let the colonial administration, with the strong backing of the Netherlands government, treat the island of Bali as a rare jewel that we must protect and whose virginity must remain intact (Robinson, 1995:41). 13 50 The Dutch ‘ethische politiek’, as it was called in the Netherlands Indies, was fully exposed when Queen Wilhelmina gave her annual speech to the Netherlands Parliament in September 1901. Reflecting on the Christian spirit and after 300 years of the Dutch occupation on Java and their exploitation of the archipelago, the Queen spoke of an ‘ethical obligation and moral responsibility to the peoples of the East Indies’. “Als Christelijke mogendheid is Nederland verplicht, geheel het regeringsbeleid te doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking dier gewesten ene zedelijke roeping heeft te vervullen ...” [As a Christian power the Netherlands is compulsory to imbue the whole conduct of government with the consciousness that the Netherlands has a moral duty to fulfill towards the people in the regions ...”] (Mommersteeg, 1947:6). Vol. 1 No. 1, Maret 2001 As a matter of fact, Bali was struggling to change from within under the guidance and protection of this Western rule. The colonial period did leave a great deal of ‘scratches in the rocks’ and ‘a new hierarchical order was emerging, intimately intertwined with the colonial regime’ (Schulte Nordholt, 1996:191). Ironically, in keeping Bali isolated from the outside world and foreign impact, various visitors (scholars, artists, tourists, etc.) flooded Bali, the newly created ‘living museum’, ‘the last paradise on earth’, ‘a dancing and singing people’, and a ‘happy and peaceful Bali’ (Covarrubias, 1986:405; Schulte Nordholt, 1996:192). The foundation of the Bali Hotel in Denpasar (1928), the first major hotel in Bali by Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM) had helped to facilitate the tourist industry and the touristification of the island.14 ‘Politiek isolatie’ This new policy of cultural conservation was not so simple as it seemed. The Dutch colonials had also to confront the increasing nationalist sentiment and nationalist movements in Indonesia with the spread of Islamic radicalism which forced the Dutch to isolate Bali – politiek isolatie. With great help from orientalists, the Dutch conservation policy was directed to secure the position of Balinese nobility. The triwangsa were regarded as the main vehicle of Hinduization of the island as well as the pillar of its traditional order. They were also regarded as the best barriers, at least in Bali, against the threat of Islam in the country and the rise of nationalism. The Dutch colonial authorities seemed to sort out how to carry out their policy by ensuring the triwangsa’s loyalty. The caste system was codified as ‘the principal foundation of Balinese society’ (1910)15 and the royal houses were restored to their previous position and became ‘important administrators and large landowners’ (1929) under the Dutch ‘older brothers’ (Vickers, 1996:133), while the commoners were really ‘outsiders’ (jaba). What the Dutch colonials did in Bali was a typical colonial conservatism and faith in the idea of ‘traditions’, where the authority of aristocracy was expected to guarantee the continuity of the colonial system. By emphasising this entire cultural heritage and religious tradition as adat, the link between the native rulers and the colonial state became stronger and hence the ‘harmony’ between the centres (palace, ruling class) and the villages (periphery, jaba) was guaranteed as well. Therefore, by employing their scholars, who were supposed to support the main policy of the Dutch colonial power, at least three main goals could be achieved. Adrian Vickers (1995:32) puts it this way: [...] creating a colonial society which included a select group of the aristocracy, labelling and categorizing every aspect of Balinese culture with a view 14 15 KPM was the Royal Packet Navigation Company that in 1924 established a weekly steamship service that connected Bali through its northern port of Buleleng with Makassar, Surabaya and Batavia (Kersten, 1940: 179). See the minutes of an administrative conference, 15-17 September 1910, Collectie Korn, no. 166, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV) (Robinson, 1995:32-3). Ray Sudhiarsa SVD, Social Construction of Balinese World and Christianity 51 to keeping it pure, and idealizing this culture so as to market it for the purposes of tourism. All this gives way to the Balinese to regain their ‘rasa bangga dan harga diri,’ an ethnic pride and self-esteem, characterised by a strong religious sentiment – their identity. It also aggrandise the so-called ‘island mentality’ with its exclusive ‘insidersoutsiders’ way of thinking, an ‘Us-Them’ dichotomy which affects the attitudes of most Bali-Hindus (insiders, hosts) towards the non-Bali-Hindus (outsiders, guests) – in our case, the Christians. AGENDA FOR THE CHURCHES Despite all the achievement and contribution of Christian missions on the island (education centres, healt cares, social economic enterprises, inculturation) and the new formulation of their ministry as ‘vocation to serve’, their image as a religion of the fanatics cannot be easily erased. Although there is gradually a great shift in mission approach from evangelical way in the early 1930s to cultural adaptation and then contextualization (evangelising culture), Christian churches are always mistrusted. On the other hand, the history of opposition against Christianity was (and is) intertwined with the social and political interests of the government (the Dutch Colonial Authorities, the traditional ruling class or triwangsa) and the ‘host’ majority BaliHindu community of today. On their eyes, there are very likely at least three important points the churches have to take into consideration. Firstly, due to the truth claim of their faith the Christians build their own communities of believers, therefore, they are potential to loosen and even split up the integration of the territorial and ancestral communities – desa adat dan tunggal kawitan. Christianity cannot in agreement with the traditional way of life that is founded on ancestor worship, the various rituals and festivals for Bali’s ‘founding fathers’. Strictly speaking, Christianity has no sense of gratitude to the ancestors and the gods who own the island. Secondly, the Christian churches as the new comers (guests, outsiders) have tried some cultural adaptation, therefore, they are capable to loosen and spoil the unity of Balinese adat, agama, dan budaya (tradition, religion, and culture). In so doing, they have committed a pelecehan agama (‘religious harassment’). They have polluted Bali with their ‘Christian-ness’ for using the Balinese religious symbols and cultural heritage for the sake of non-Bali-Hinduism. In other words, their missions are harmful for Bali at its heart. Thirdly, although there has never been any explicit statement regarding the Balinese type of caste system, the Christian churches are not in favour towards this ‘sacred’ social division that for a long time has distinguished people into two major groups, the exalted triwangsa and the lower jaba. In this ‘steady and harmonious 52 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 world’ the triwangsa were (and are) regarded as the main vehicle of Hinduization of the island and the pillar of the traditional order. Christianity on the contrary teaches just the opposite that everybody is equal in God’s eyes and is created in God’s image (Genesis 1:26), so, everybody should have the same opportunity in the society and share the same ideals as brother and/or sister. In other words, these are the three ‘cardinal sins’ Christianity has committed in Bali on the eyes of the Bali-Hindus. The Christian deconstruction and redefinition of the Balinese society cannot be tolerated. Then, what is the response of the churches? How can they defend themselves and justify their works? How can their explanation be acceptable, namely what they have been doing is, e.g. to carry out faithfully the sacred mission of ‘redemption’ and ‘salvation’? SELECTED BIBLIOGRAPHY BPS Kantor Statistik Propinsi Bali, Bali Dalam Angka 1995, Denpasar: BPS, 1996. COVARRUBIAS, Miguel, The Island of Bali, London: KPI Ltd., (1937) 1986. DJONI GINGSIR, N., Babad Bali Agung. Seri K.G.P. Bendesa Manik Mas, Jakarta: Yayasan Diah Tantri, 1996. EISEMAN, F.B., Jr., Bali: Sekala and Niskala. Vol. 1: Essays on Religion, Ritual, and Art, Singapore: Puriplus Editions, 1996. —————, Bali: Sekala and Niskala. Vol. II: Essay on Society, Tradition, and Craft, Singapore: Puriplus Editions, 1995. GEERTZ, C., Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1973. GORIS, Roelof, “The Position of the Blacksmith,” in Dutch Scholars, eds., Bali. Studies in Life, Thought, and Ritual, The Hague, Bandung: van Hoeve, 1960, pp. 289-99. HOBART, Angela, Urs RAMSEYER and Albert LEEMANN, The Peoples of Bali, Cambridge: Blackwell, 1996. HOOYKAAS, C., Religion in Bali, Leiden: E.J. Brill, 1973. KERSTEN, Jan, Bali. Hoe een Missionaris het Ziet, Eindhoven: De Pelgrim, 1940. MOMMERSTEEG, J.A., Indonesië: Chronologisch Documentair Overzicht, Amsterdam: Uitgave van Systemen Keesing, 1947. PICARD, Michel, Bali. Cultural Tourism and Touristic Culture, Singapore: Archipelago Press, 1996. ROBINSON, Geoffrey, The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, Ithaca: Cornell University Press, 1995. SCHULTE NORDHOLT, H., The Spell of Power. A History of Balinese Politics, 1650-1940, Leiden: KITLV Press, 1996. Ray Sudhiarsa SVD, Social Construction of Balinese World and Christianity 53 SCURES, J.S., Culture Contact and Social Change Through Tourism: Crossroads of An International Village on Bali, Ph.D. dissertation, San Diego: University of California, 1994. VICKERS, Adrian, “Colonial era. Conquests and Dutch colonial rule,” in Eric Oey, ed., Bali, Singapore: Periplus Editions, 1995, pp. 30-3. —————, Bali: A Paradise Created, Singapore: Periplus Editions, 1996. WARREN, Carol, “Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali,” in H. Geertz, ed., State and Society in Bali, Leiden: KITLV Press, 1991, pp. 213-44. WEBB, Paul R.A.F., Palms and the Cross. Socio-economic Development in Nusatenggara 1930-1975, James Cook University of North Queensland Townsville, 1986. WIANA, Ketut, “Penataan dan Pelembagaan Agama Hindu di Bali,” in U. Wiryatnaya and J. Couteau, eds., Bali di Persimpangan Jalan, vol. I, Denpasar: Nusa Data Indo Budaya, 1995, pp. 28-55. WIENER, Margaret J., Visible and Invisible Realms: Power, Magic, and Colonial Conquest in Bali, Chicago: University of Chicago Press, 1995. 54 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 ON HUMANISM Exploring the Concept of Humanism in Indonesia Robert Wijanarka, CM De Paul University, Chicago (USA) Abstraksi Konflik yang menghiasi peradaban bangsa Indonesia terasa demikian mengoyak humanisme. “Kemanusiaan yang beradab” terasa asing di negara kita. Keberadaban di banyak tempat telah mendadak lenyap. Yang ada malahan kebalikannya, kebiadaban. Tulisan ini mencoba menguak kembali ide- ide yang pernah dimiliki oleh para pendiri negara ini khususnya dalam mendulang konsep tentang humanisme. Kita diingatkan kembali. Ditegur malahan, untuk mengupayakan peradaban kemanusiaan baru di negeri tercinta ini. Segala upaya politis untuk meredam konflik dan kekerasan tidak boleh menyisihkan prinsip-prinsip humanis. A series of profound and enriching discourses on humanism, which is many times have mirrored the influence of the modern concept of humanism to our intellectuals or thinkers, in the various newspapers have raised some questions in my mind. What is the contribution and relevance of this discussion to our country that is raising discourses and actions on human promotion? Can we track the echo of the concept of such a modern concept of humanism to the half-naked inhabitants of the jungle in our isolated areas, such as the people in Sumatra, Kalimantan, and Irian Jaya? Can we identify the concept of such a modern humanism in the different faces and expressions in our country, Indonesia? Or, by being involved in the discussion, do our scholars and intellectuals start to build their status as a new bourgeois who is only expert in the room of discussion but immune from the concrete and dark-unending struggle of the people in our country in increasing our quality of life? In its turn, somehow, such questions intrigue me to explore the concept on humanism in our country. I do realize since in the beginning that exploring such a huge concept is really a big project. The next questions that came up in my mind were how do I start? How do I inventory the resources that can be accessed and should be taken into account? What kind of approach or method I can use? Won’t I find the classical difficulty that is the epistemological question? Instead of just being captured by those difficulties, somehow, I should start, just by using some resources I can access, even if it is only a small step on the long journey. Otherwise, I will not start and will do nothing. It seems to me that investigation of the discussion among the Indonesian founding fathers, concerning the formation of the state and nation, can be a fruitful initial step in exploring Indonesian concept on humanism. This study, then, is intended to track concept of humanism in Indonesia by examining the discussions and negotiations that were conducted in 1945 and thereafter in Indonesia, concerning Robert Wijanarka CM, On Humanism 55 the formation of the sate and nation. Investigating the main themes of the founding father’s discussions in that time apparently will help us to identify how Indonesians have pictured and reflected themselves either as a nation or as human beings. And since in that period the themes of the European ideological discourses were also focused on humanism, it is not impossible that the concepts of humanism of our founding fathers, to a certain measure, were also influenced by the certain western schools, such as existentialism and Marxism. Another aim of this study, then, is to identify the influences of Western concept of humanism on the Indonesian’s. To pursue this project I will first present the discussion of the founding fathers about the state and nation in 1945 and after, and then reflect on its implications on the concept of humanism. In this step I will also identify the influences of western concept of humanism, especially Marxism, on the Indonesian’s. Second, I will investigate the implications of this concept on some political policies in Indonesia today. An Exploration of A new State and Nation Instead of giving a chronological story of what was happening in the period, in which our leaders had striven to find a suitable format for the new state and nation after the long and tiring war of 1945 and after, I would rather giving some notable information and present the dominant issues in relation to the idea of a new nation and state. At first, while challenged to find the form of a new nation and state, our leaders should formulate the objectives, nature, and sources, of the Indonesian State and nation. Our leaders, during this time, were also facing some crucial issues. In this period people were still in the strong trauma of imperialism and colonialism of the Western world. In such an atmosphere the leaders had to find a sort of elan vital that could energize and motivate people to build a new nation. The other fact should be faced is that awareness that Indonesia contains so many different ethnic groups, languages, economical resources, religions, and even various local histories as a background. Moreover, geographically some inhabitants were so scattered and isolated in the different islands so that people were out of touch. The second, there were four outstanding founding fathers that were involved as the key persons in the process of preparations. They are: Sukarno, the intellectual, politician, and later, President; Muhammad Yamin, the historian and lawyer; Soepomo, professor in adat (traditional) law at the former college in Batavia, and Mohammad Hatta, the economist graduated from Roterrdam, Netherlands (Holtzappel, Nationalism 68). Actually there were some other figures, in the stage of post-war Indonesian, that had been involved in the discussions, especially the members of PPKI and BPKI 1 , which had had an European education. But it is 1 56 BPKI was the committee for Examination of Independence or Badan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia. It was formed with the permission of the Japanese occupational administration. This committee completed Vol. 1 No. 1, Maret 2001 obvious that the ideas of the key founding fathers colored and dominated strongly the discussions, either in the formal meetings or in the informal discussions (Holtzappel, Nationalism 70-71). The third, there were three main tendencies of alliances that should be taken into account during that period, namely: 1) the progressive nationalism of Sukarno, Which based itself on the co-operation between Marxists; 2) the conservative one, which based itself on co-operation between government bureaucracy, the new middle class, and the army; 3) and The Islamic nationalism, which see Islam as an instrument of Indonesian nationalism. 2 Let me start mapping out the main raising ideas that came up during that time. First of all, it is obvious that the founding fathers and most post-war Indonesian Intellectuals believed that in the face of traumatic experiences, the fact of plurality, and the challenge to move forward as a new nation, nationalism is an effective and valuable instrument of national development (Holtzappel, Nationalism, 70). This conviction is in tune with European concept from the eighteenth century Enlightenment that “society can be made/constructed”. The element that in the first place brings the various currents and “school” of thought together, is the idea that nationalism is not just any ideology. Nationalism, to all post-war leaders of Indonesia, is a strategy of central interest to country. On the one hand, it concerns the struggle for political and economical independence, on the other, the struggle for internal development. The critical and authentic question concerning the idea of nationalism in Indonesia, then, is what is the source of unity that should be accommodated to build nationalism? Is it language, history, territory, tradition, or race? In the absence of a homogenous and uniform cultural heritage that could serve as the source of the new state and nation, it was important to find out the source, that is common objectives and values, that can be accommodated as the basis of nationalism. This basis of nationalism should be able to unite the heart and mind of the Indonesians in striving for independence and development. In this struggle all would go through the mill and learn to shape themselves on the basis of national objectives and values. Thus, one was to be able to loosen one’s ties with local roots, and class or town background. Only on that basis of such common objectives and values that independence can be achieved and independent national development be successful. Such a nationalism, which is shaped by common objectives and values, was ready for battle and primarily oriented to the future. It did not tie itself to what Indonesia was or is, but rather strive for a new Indonesia. Only that Indonesia could be the real Indonesia. It is obvious that it should be invented the common objectives and values that could unite and guide the minds of the Indonesians and substitute for the loss of local 2 its task in July 1945. While PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) was the Committee for the Preparation of Independence of Indonesia that laid down the definitive text on 18 August 1945. These two committees had several meeting in preparing the concept of nation and state. Among others alliances Coen Holtzappel mentioned these tree strong alliances. Robert Wijanarka CM, On Humanism 57 culture, religion, and local history as sources of Indonesian nationalism. In emphasizing the need of a new state and nation that is tied by nationalism on the certain occasion Sukarno said:3 “We see in this world that there are many nations which are free, and that many of those free nations exist on the basis of a Weltanschauung, i.e. the Marxist Historical-Materialistic Weltanscauung. Nippon established the nation Dai Nippon on the basis of Tenno Koodoo Seishin,…Saudi Arabia, Ibn Saud established the state of Arabia on a Weltanscahuung, even on a religious basis, i.e. Islam. Idealists in the entire world worked to the utmost in the creation of various types of Weltanschauung…(as quoted, Holtsappel, Nationalism, 73) Obviously, Sukarno viewed Weltanschauung as a deliberately constructed product of political idealists who provide the country with a new spiritual or moral foundation. In this way, finally man become master of his own history and his own legal rules and morals. Regarding the principle of the common objectives and values of the nationalism Sukarno cited the ideas of Ernest Renan:4 “Nationalism! To be nation! It was no later than the year 1882 that Ernest Renan published his idea of concept of “nationhood”. “Nationhood”, according to this author is a spirit of life, an intellectual principle arising from two things: firstly, the people in former times had to be together to face what came, secondly, the people now must have the will, the wish to live and be one. Not race, nor language, nor religion, not similarity of needs, nor the borders of the land make that nation…(as quoted, Holtsappel, Nationalism, 74). Being weaned by the tradition and culture, the Indonesians as human beings are placed in their free stand. They aren’t burdened by a certain moral conception or standard of human beings. They are distanced from a certain conception of human beings that might be inherited from the traditional perspectives. Human beings in such a new perspective are the concrete and free beings. Moreover, by his idea of new nationalism Sukarno, influenced by Marxism5 , erased the social stratification that had been living in the several feudalistic communities of the society in our country. 3 4 5 58 As quoted by Coen Holtzappel from “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945” (edited by Mohhamad Yamin) this statement was made by Radjiman as requested by Sukarno. This statement, then, delivered by Sukarno in a meeting and then colored the spirit of BPKI and PPKI meeting. As quoted by Coen Holtzappel Sukarno’s article, that was published in Soeloeh in 1926, became the spirit of the BPKI and PPKI meetings. It is obvious also that in the course of time Sukarno was influenced strongly by Marxism. And his concern to the real people indicates that he knew that Marxism should be close to the real-concrete people (Marxistexistentialist), that is the poor. That is why during his time he was expected as “the just king” that would save the people from the poverty. The Film” The Year of Living Dangerously” demonstated that finally Sukarno was intrigued by the promises of Capitalism, represented by USA power (See Sartre, Search For A Method 17-21, 31). Vol. 1 No. 1, Maret 2001 It is obvious that the idea of nationalism as thought by Sukarno dominated and colored strongly the discussions in this period, and it seems that most leaders agreed to this conception. The problem followed, then, was in correlation to the system of state. In this case there were two strong different opinions. The first was Sukarno and his alliance’s opinion that the form of state is a sort of unitary state, in which the individual freedom and right should be subjected to the goal of the unitary state. Also the presidential system, in this case Sukarno adopted the American System as a model of new democratic country, is believed as a suitable system for Indonesia. Practically this option gives concentration of executive power in the hands of the President (Holtsappel, Nationalism 76-77). Furthermore, in the face of heterogeneous peoples the conflict or different opinion should be solved by “azas kekeluargaan” (family loyalty) principle. In such a perspective the individual freedom and interests should be subjected to the ideal of the unitary state. Supomo affirmed the idea of Sukarno by stating that “nothing was allowed to divide state and nation, not even procedure of Constitutional law.” (Holtsappel, Nationalism 76) It means that right for freedom of the people and even procedure of Constitutional law should be subjected to the ideal of the unitary state. As a well western-educated figure Hatta disagreed to ideas of presidential system and “azas kekeluargaan” principle by showing the danger of political abuse of power. He mentioned the risk that a President, as the highest law-making power in the country, would manipulate Parliament in order to disable the controlling power of the institution. Hatta also disagreed to the “azas kekeluargaan” principle by demonstrating the risk of abuse of right and freedom of the individual. Unfortunately in the atmosphere of the trauma of imperialism and colonialism, the critical need of the unitary state, and the absence of a homogenous and uniform of cultural heritage, Sukarno’s and Supomo’s ideas got more support from the majority (Holtsappel, Nationalism 76-77). Exploring the concept on Humanism By weaning people from their habitat, which are their ethnic background, traditional value system, culture, language, tradition, geographical territory, the founding fathers wanted to set people free from the bondage of the past and put them in the same stand before the law and constitution. Instead of being used as only a living vehicle to perpetuating tradition or system of values and beliefs, people are freed and invited to live and foresee their future according to the common objective and values, which were formulated in the concept of the nationalism and the unitary state. Again, instead of being used as a living vehicle to perpetuate the inherited history, the new Indonesian is invited to create his/her own histories. Who the Indonesians, hence, are not determined by their history in the past rather determined by the way they concretize or express themselves in the process of constructing a new nation and state. Robert Wijanarka CM, On Humanism 59 As a strategy, the concept of nationalism and the unitary state was understood as the mean to eliminate the potency of conflict, as a consequence of the fact of plurality, and intended also to destroy a sort of systematical and continuos colonization in the form of the social stratification, as an inheritance of feudalistic society, that calculated and divided people based on the certain social status. In short, in such a way actually Sukarno and the other founding fathers wanted to make the Indonesians as the concrete beings that are free from any determinations and not subjected to the traditional conceptions and moral standards. And such a perspective, it seems to me, is in tune with the concept of the existential humanism and indeed not impossible influenced by the existential humanism, as proposed by Sartre6 or Heidegger. This influence was made possible by the fact that Sukarno’s circle in Netherlands had a regular contact with Hatta’ circle in France. This new intellectual generation was well educated in European schools. Realizing the need of elan vital that can energize and unite the hearts and minds of the people, the founding fathers promoted the spirit of nationalism and the unitary state. This strategy can also avoid the risk of the individualistic concept of human beings, since although human beings were weaned from their historical background, they are united by the spirit of nationalism and the unitary state in pursuing the ideals of a independent and developed country. Moreover, the decision to adopt “azas kekeluargaan” (family loyalty) as a moral code underlines the communal dimension of human beings. Accordingly, even though peoples are uprooted from their cultural background so that they become the independent persons, they are still tied by the same spirits that unite them as a one nation and member of the same state. Investigating Some Political Policies Creating a new society is never a simple project. The decision to uproot peoples from their culture and to create a new nation and state is really a long process, because culture, historical inheritances, and any other elements as a background of human beings are integrated in the real persons. The system of values and system of beliefs as a form of culture usually are integrated in such a way that shape the horizon of the peoples in interpreting or comprehending their experiences, even in understanding their self-identity. Furthermore, social structure and stratification is not only an external-objective fact but it really is incorporated in the mentality and frame of mind of the concrete persons. Such a phenomenon is a sort of critic for the existential humanism, in the sense that human beings are not the closed entities that can be isolated from their culture or context, regarding the fact that their culture and 6 60 In his exposition “existentialism is a Humanism” Sartre believes that existence comes before essence. Thus, there is no human nature. Man is nothing else but that which he makes of himself, he will no be anything until later, and then he will be what he makes of himself. (In Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism, 1946) Vol. 1 No. 1, Maret 2001 historical background, such as system of values and beliefs and social stratification, are integrated or united in the real persons. Realizing this phenomenon, as far as I am concerned, the Indonesia government has used the field of education as the main mean for the process of interiorization of the concept of nationalism and the unitary state. Consequently, the educational institutions and resources have been mobilized to support the process of socialization of the concept of nationalism and the unitary state until this time. But in the course of time, after the founding fathers generation, many Indonesian leaders do not have the same vision in relation to such a strategy. That is why the process of socialization of concept of nationalism and the unitary state, is actually not succeeding. The raising separation movements that happen along the Indonesian history, it seems to me, can be explained by this context (East Timor, Aceh, Maluku, Irian Jaya). The other phenomenon that has intrigued me is the product of law. It is obvious that the Indonesian product of law is constructed by accommodating the some traditional values. And unfortunately these values are mainly adopted from the Javanese culture as the culture of majority. This decision shows the ambiguity of the Indonesian leaders, since in the one hand they tried to wean people from their cultural, geographical, and historical background, in the other hand they used the traditional values to construct the product of law that rules the peoples. This phenomenon, to a certain degree, can explain the source of ethnical conflicts in Indonesia today. Robert Wijanarka CM, On Humanism 61 Telaah Buku Judul Buku Penulis Penerjemah Penerbit Tebal : : : : : Fifty Key Contemporary Thinkers (50 Filsuf Kontemporer) John Lechte A. Gunawan Admiranto Kanisius, Yogyakarta 2001 380 halaman Ketika gedung World Trade Center di New York dihancurleburkan oleh sekelompok teroris, semua orang terhenyak dan dihadapkan pada pertanyaanpertanyaan filosofis tentang terorisme. Bagaimana filsafat menjawabi atau menjelaskan persoalan ini? Dalam kacamata Jean Baudrillard, peristiwa terorisme di atas merupakan sebuah simulasi atas realitas terdalam yang hendak diungkapkan, artinya peristiwa tragedi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk representasi dan reproduksi realitas yang tersimpan dalam masyarakat dunia. Realitas kekecewaan atas ketidakadilan oleh Amerika yang sering bersikap ganda memunculkan peristiwa hiperrealitas. Sementara dari semiotika Roland Barthes fenomen terorisme adalah sebuah mitos. Mitos adalah sebuah pesan yang tersembunyi, tidak jelas, absurd. Mitos adalah sebuah cara menyampaikan pesan. Kekuatan mitos ada pada dampak yang ditimbulkan. Distorsi yang kuat dan menghebat adalah ukuran kesuksesan sebuah mitos yang disampaikan secara alami. Teroris adalah sebuah mitos justru karena tidak pernah jelas siapa orang-orangnya, tidak menampakkan jati dirinya, anonim, namun mampu bertindak hebat dan mengguncangkan dunia kehidupan. Peristiwa kekacauan global yang diakibatkan oleh serangan terorisme memiliki dampak-dampak lokal. Yang paling dirugikan dengan peristiwa ini adalah perempuan, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan kebutuhan rumah tangga keluarga. Sebab serangan itu menimbulkan resesi global, akibatnya barang-barang kebutuhan naik, mahal dan tak terkendali. Kaum bapak umumnya dipandang tidak berhadapan dan pusing dengan soal-soal ini. Inilah bentuk penjajahan patriarkal menurut para feminis. Konstruksi sosial yang sudah distigmakan pada perempuan adalah bias gender. Bias gender itu ternyata bermuara pada ideologiideologi yang umumnya diciptakan oleh kaum pria sehingga filsafat, hukum, budayapun berbau “kepriaan.” Mereka justru menuntut dimensi feminin dari produk-produk kehidupan. Kaum feminis tidak ingin menjadi seperti pria tetapi ingin sentuhan kaum perempuan mendapatkan tempat dalam konstruksi sosial. Melihat analisa filosofis di atas betapa filsafat memang diperlukan untuk melihat kenyataan secara kritis, kreatif. Dalam filsafat kenyataan bisa dilihat, dianalisa, diteropong dalam banyak segi. Contoh di atas hanya merupakan kajian semiotik dan feminis atas realita. Tetapi kenyataan terorisme bisa dilihat juga dari berbagai pandangan filosofis yang lain. Maka penting bagi kita untuk mengenal berbagai pikiran para filsuf dari berbagai aliran. Dengan demikian analisa kita terhadap suatu kenyataan menjadi semakin tajam. 62 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 Dalam buku ini, John Lechte menawarkan kepada kita buah pikiran 50 filsuf kontemporer. Tetapi penulis tidak menyajikan begitu saja buah pikiran 50 filsuf tersebut melainkan juga mengkaji dan memahaminya. Dengan kata lain penulis sudah menginterpretasi pemikiran ke-50 filsuf ini. Karena tidak mungkin merangkum pemikiran 50 filsuf dalam buku setebal 380 halaman ini penulis hanya menampilkan pemikiran inovatif yang khas dari masing-masing filsuf. Dengan kata kontemporer dimaksudkan orientasi pemikiran strukturalis pasca-Perang Dunia II. Tetapi kriteria ini tidaklah ketat karena penulis juga menampilkan beberapa filsuf yang secara kronologis tidak termasuk dalam kelompok ini. Pertimbangannya adalah bahwa beberapa filsuf tersebut (Saussure, Freud, Nietzche) menyemaikan wawasan baru serta secara intelektual cukup kontemporer. Dalam penyajiannya penulis mengelompokkan ke-50 filsuf tersebut dalam 9 kategori: strukturalisme awal, strukturalisme, sejarah struktural, pemikiran poststrukturalis, semiotika, feminisme generasi kedua, post-Marxisme, modernitas, dan akhirnya postmodernitas. Seorang filsuf dimasukkan dalam salah satu kategori bila ada pemikirannya yang sesuai dengan kategori tersebut; tidak harus berdasarkan keseluruhan pandangannya. Pada bagian awal dari setiap kelompok filsuf diberikan pendahuluan singkat untuk memberikan garis besar tentang arah yang diambil para filsuf tersebut. Dalam pembahasan setiap filsuf, penulis mengawalinya dengan menyajikan biografi singkat, dilanjutkan dengan butir pemikiran inovatif yang khas, dan ditutup dengan daftar kepustakaan yang harus dibaca bila ingin lebih mendalami filsuf yang bersangkutan. Ada beberapa kelebihan buku ini. Pertama, keuntungan praktis. Pembaca, yang memiliki latar belakang filsafat, bisa mengetahui butir pemikiran inovatif dari 50 filsuf kontemporer dalam satu buku. Kedua, penulis membantu kita dalam proses pengkategorian itu sendiri; bagaimana dia menganalisa pemikiran seorang filsuf dan memasukkan dalam salah satu kategori. Kelemahan buku ini: pertama, tidak bisa dibaca dan dimengerti oleh orang yang tidak memiliki latar belakang filsafat dan sejarah pemikiran masing-masing filsuf yang ditampilkan. Misalnya, banyaknya istilah teknis yang digunakan tanpa ada keterangan seperti semiotika, stukturalisme, positivisme, realisme, fenomenologis, diferensial, dan lain-lain. Kedua, pembaca bisa terjebak pada pemahaman bahwa gagasan yang disajikan dalam buku ini adalah gagasan orisinal filsuf yang bersangkutan padahal ulasan di sini sudah tercampur dengan pemahaman John Lechte tentang filsuf tersebut. Perlu disadari bahwa untuk memahami pemikiran seorang filsuf paling tepat adalah dengan membaca karya aslinya; bukan dengan membaca ulasan tentang pemikirannya. Paulus Dwintarta, CM Didik P., CM Telaah Buku 63 Telaah Buku Judul Penerbit Tebal : GLOBAL/LOKAL Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia Th.X – 2000 : Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, Bandung : IX + 136 halaman “Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia” ini diterbitkan oleh Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI) di Bandung mulai tahun 1990. Pada terbitannya yang ke X (tahun 2000), Jurnal ini mendokumentasikan makalah-makalah yang disampaikan dalam “Temu Ilmiah MSPI” Tirtagangga, Karangasem, Bali pada tanggal 10 – 13 September 1999. Tema waktu itu “Seni Petunjukan Global, Globalisasi Seni Pertunjukan” diringkas sebagai judul jurnal terbitan ini: “GLOBAL/LOKAL”. Ada 12 penyumbang tulisan: seorang dari bidang Sastra, 5 orang dari Seni Pertunjukan, 4 orang dari bidang Etnomusik, seorang sosiolog, dan seorang lagi dari bidang Tari. Kebanyakan dari mereka adalah dosen universitas. Sebagai dokumen, jurnal ini memperkenalkan kepada “outsider kultural” (Endo Suanda) gambaran dan sikap dunia seniman terhadap fenomena baru: globalisasi, yang menuntut penyesuaian diri (penyusunan identitas baru) lewat cara mewawas secara baru dan strategi-strategi yang baru. Situasi “identitas yang membingungkan” ini diungkapkan oleh R. Anderson Sutton (Michigan) dengan meneliti lagu-lagu pop dari MTV (lebih-lebih MTV Asia- Indonesia) yang mottonya jelas global, “Satu Dunia, Satu Citra, Satu Gelombang”, lagu-lagu Dangdut di Indonesia dan akhirnya sebuah jenis musik yang dinamakan “Dua-Warna” , yang mengambil instrumen-instrumennya dari Barat maupun Timur. Meskipun sebagai contoh, grup pimpinan Djaduk Ferianto ini mengambil nama “Kua Etnika”. Sutton melihat bahwa ke “dua-warna” itu tidak seimbang: warna pop jauh lebih dominan daripada warna etnik. Alat-alat bertangga-nada Jawa-Bali dirubah larasnya supaya sama dengan tangga-nada diatonis. Konfrontasi dan ketegangan dalam mempertahankan “identitas lokal” ini disharing oleh hampir semua penulis jurnal. Soalnya menjadi soal kalah dan menang secara kultural, meskipun dalam era global itu, orang justru mendapat kesempatan dan peluang-peluang baru dalam menyatakan ekspresi dirinya. (Piliang, 111; Rahayu, 83; Zulkifli, 59). Tetapi di sini juga nampak pemahaman tentang apa yang disebut “global” itu sendiri diterima secara berlain-lainan. Mohamed Anis (Malaysia) melihat penyebaran instrumen dan cara memainkan Kulintang “ di dunia Malayo-Polynesia” yang mengalami “transformasi dari sistem lokal otonom ke himpunan heterogen berbagai sistem lokal” pun disebut globalisasi. Menarik bahwa dalam pendekatan budaya ini muncul persepsi yang lebih dalam tentang “ruang”. Orang mulai menggunakannya dalam arti yang baru: ada “ruang identitas” (Jazuli dari Universitas Diponegoro), penataan “ruang budaya” baru. 64 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 Zulkifli (dari Universitas Serawak) memeriksa bagaimana perkembangan teater di Thailand dari waktu ke waktu menempuh ruang yang sama. Tetapi di ruang yang sama yang dipahami secara fisik itu ia melihat pergulatan memperebutkan ruang, antara teater tradisional dan teater kontemporer. “Kita telah terperangkap dengan ide untuk memiliki sebuah ruang teater murni, sebuah pemandangan yang diformulasikan dan dikontrol. Tanpa menyadarinya, kita sebenarnya telah membatasi ruang-ruang pertunjukan... Kita seharusnya tidak mengeluh tentang tidak mendapat ruang... tetapi dengan menembus batasan-batasan (dan meraih komunitas), kita secara konstan membangun ruang-ruang budaya baru”. (51-62). Pengalaman yang sama kita lihat peristiwa “Srimulat” yang ruangnya digeser oleh Plaza Modern, tetapi “Srimulat” tetap berusaha mencari ruangnya sendiri dan tidak pernah kehilangan komunitas pemirsa. Dengan judul artikel “Melacak Identitas di tengah Budaya Global” I Made Bandem menguraikan bagaimana para seniman kreatif melihat kekuatan lokal sangat efektif untuk memasuki global culture. Dramatari Gambuh dengan ekspresi seni paling lokal dapat tampil di era global ini karena memiliki unsur “total theatre”. Karya yang sarat dimuati dengan spirit lokal, nilai-nilai lokal tampil dalam kemasan “baru” (32). Berbagai eksperimen dalam masa trasisi budaya seperti ini menghasilkan budaya “baru” yang mengundang pro dan kontra. Di sini muncul istilah “hibridisasi budaya” yang tidak masuk baik dalam kategori lokal maupun global. Dua budaya yang berlainan bertemu karena persepsi dan penggarapannya dilakukan oleh seniman yang tidak termasuk dalam budaya lokal yang digarapnya. Rahayu Supanggah yang menulis artikel “Kolaborasi Seni” mengetengahkan contoh Peter Brook dari Inggris yang menggarap “Mahabarata”, sedangkan Ong Keng Sen dari Singapura menggarap (King) Lear karya Shakespeare. Dalam bentuk hibrid, Rahayu melihat bahwa karyakarya itu masih berada pada level material, struktural dan vokabuler, belum sampai pada tataran makna atau jiwa. Tetapi justru kultur hibrid itulah yang oleh Jazuli dianggap mengikuti konteks globalisasi, yaitu bahwa orang menghasilkan jenis baru dari hasil saling silang. Struktur hibridisasi ditandai oleh lintas batas, transisi dari berbagai sumber budaya, pengemasan baru dari budaya lama. (“Seni Pertunjukan Global,” artikelnya dalam hal. 93). Kasus lintas batas itu sebenarnya sesuatu yang wajar bila kita mengamati penduduk yang hidup di perbatasan budaya, antara tanah Sunda dan Jawa Tengah. Dalam hal ini Endo Suanda melihat bahwa peta geokultural tidak memiliki garis batas yang tegas. Ada sifat kelenturan dari geokultural itu. Kalau ditanya, penduduk di perbatasan itu bingung. Ada yang menjawab “ya Sunda ya Jawa”, dan ada yang menjawab: “bukan Sunda bukan Jawa” (Tulisannya “Waktu dan Identitas: masalah pemetaan budaya”; 63-70). Menghadapi situasi transisi penuh paradoks dan jurang ketidakselarasan dari era globalisasi, Y. Amir Piliang (ITB) mengajak para seniman untuk lebih merencanakan masa depan. Artikelnya: “Global/Lokal:mempertimbangkan masa depan” (111-123), menguraikan berbagai wacana perubahan dalam skala global. Salah satunya adalah perubahan dalam wacana estetika, perubahan dari modernisme Telaah Buku 65 ke postmodernisme. Secara garis besar disebutkan ciri sikap baru itu: penghargaan atas nilai-nilai heterogenitas, fragmentasi dan perbedaan; pembauran antara “seni tinggi” dengan “seni rendah”; gerakan kembali ke masa lalu dengan menghargai kembali idiom atau bahasa-bahasa estetik masa lalu; ekklektisisme radikal berupa pencampuran berbagai gaya dalam ungkapan seni; pencairan hubungan ‘pusat’ ‘pinggiran’. (Sitatnya dari Pauline Marie Rosenau, “Postmodernism and the social sciences”, Princeton Univ. Press, 1992) Menghadapi tantangan demikian masa depan, kebudayaan dan kesenian Indonesia ditentukan oleh kemampuan menyaring berbagai prinsip dan pengaruh yang muncul dari pergaulan budaya global itu. Diperlukan sikap kehati-hatian (122). A. Abimantrono CM, Lic. Th. 66 Vol. 1 No. 1, Maret 2001 BIODATA KONTRIBUTOR A. Abimantrono, CM, LicTh: Licensiatus teologi dari Universitas Trier, Jerman; dosen beberapa bidang teologi dogmatik dan menaruh perhatian pada kontekstualisasi teologi di STFT Widya Sasana Malang. Achmad Jainuri, PhD: Program studi S3 ditempuhnya di McGill University, Canada untuk bidang yang berkaitan dengan Islam; wakil rektor Universitas Muhammadiyah di Sidoardjo, dosen pasca-sarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dr. Armada Riyanto, CM: Doktor filsafat dari Universitas Gregoriana, Roma; dosen pengantar filsafat, metafisika, filsafat etika, filsafat politik di STFT Widya Sasana Malang. Dr. P.M. Handoko, CM: Doktor teologi dogmatik dari Universitas Gregoriana, Roma; dosen berbagai mata kuliah teologi dogmatik dan membidangi pula kontekstualisasi teologi di STFT Widya Sasana Malang. Dr. Ray Sudhiarsa, SVD: Doktor misiologi dari Universitas Birmingham, Inggris; dosen misiologi di STFT Widya Sasana Malang. Paulus Dwintarta, CM & Didik P., CM: Mahasiswa-mahasiswa program pasca-sarjana (lokal) di STFT Widya Sasana Malang. Robert Wijanarka, CM: Alumnus STFT Widya Sasana Malang, kandidat doktor filsafat di DePaul University Chicago, USA. Biodata Kontributor 67