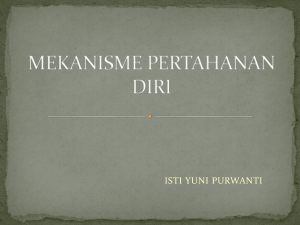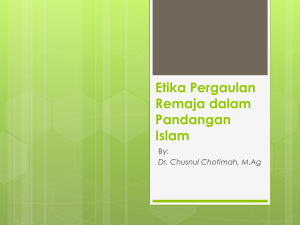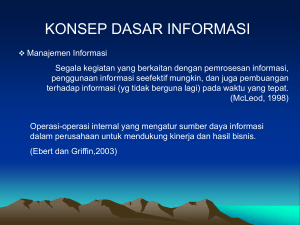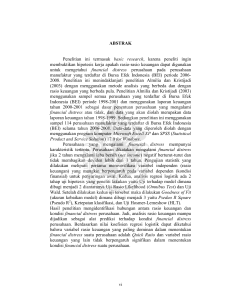1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Konsep empati
advertisement
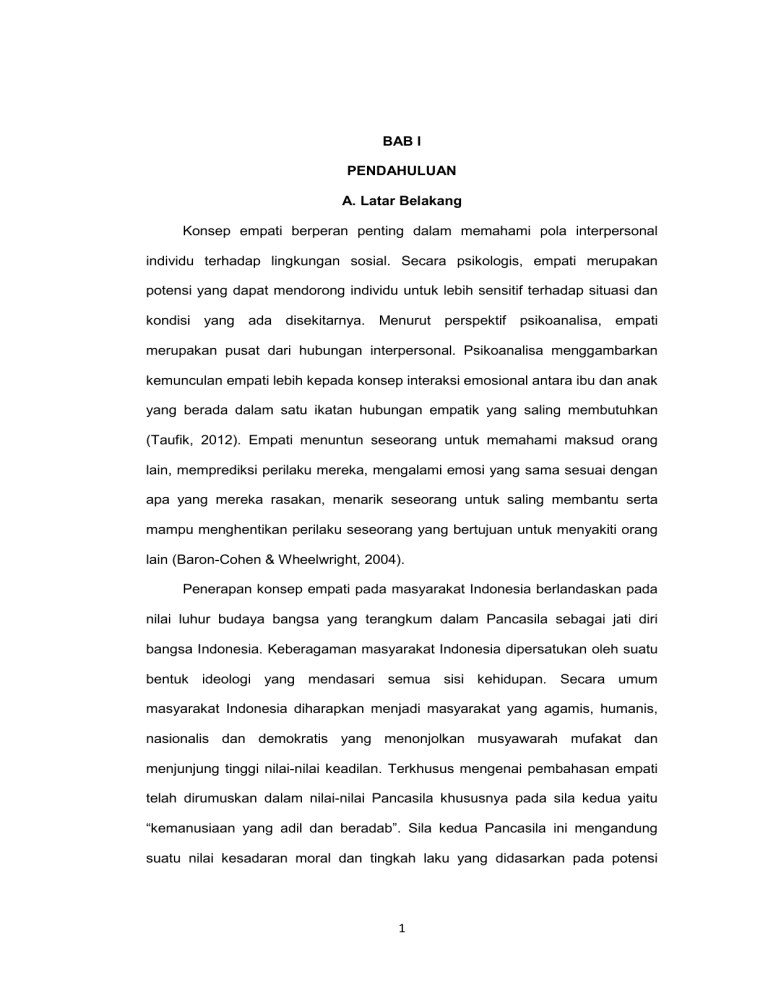
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Konsep empati berperan penting dalam memahami pola interpersonal individu terhadap lingkungan sosial. Secara psikologis, empati merupakan potensi yang dapat mendorong individu untuk lebih sensitif terhadap situasi dan kondisi yang ada disekitarnya. Menurut perspektif psikoanalisa, empati merupakan pusat dari hubungan interpersonal. Psikoanalisa menggambarkan kemunculan empati lebih kepada konsep interaksi emosional antara ibu dan anak yang berada dalam satu ikatan hubungan empatik yang saling membutuhkan (Taufik, 2012). Empati menuntun seseorang untuk memahami maksud orang lain, memprediksi perilaku mereka, mengalami emosi yang sama sesuai dengan apa yang mereka rasakan, menarik seseorang untuk saling membantu serta mampu menghentikan perilaku seseorang yang bertujuan untuk menyakiti orang lain (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Penerapan konsep empati pada masyarakat Indonesia berlandaskan pada nilai luhur budaya bangsa yang terangkum dalam Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipersatukan oleh suatu bentuk ideologi yang mendasari semua sisi kehidupan. Secara umum masyarakat Indonesia diharapkan menjadi masyarakat yang agamis, humanis, nasionalis dan demokratis yang menonjolkan musyawarah mufakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Terkhusus mengenai pembahasan empati telah dirumuskan dalam nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua Pancasila ini mengandung suatu nilai kesadaran moral dan tingkah laku yang didasarkan pada potensi 1 2 nurani individu dalam konteks hubungan terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan sesuai dengan norma dan kebudayaan pada umumnya. Nilai-nilai pada sila kedua berisi tentang sifat-sifat yang mengharapkan individu dan masyarakat untuk menjunjung tinggi hak azazi manusia, tenggang rasa, empati, kasih sayang dan keadilan. Maka dari itu, potensi yang bersifat kultural menjadi cerminan semua bangsa dalam menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Pada kenyaataannya saat ini, berbagai isu mengenai kemerosotan moral akibat menurunnya empati remaja terhadap orang lain, mengakibatkan terbentuknya suatu kondisi yang tidak terkontrol dalam kehidupan sosial remaja. Kasus yang terjadi pada tahun 2014 merupakan salah satu contoh dari remaja yang telah hilang rasa empatinya. Dikutip dari artikel surat kabar bahwa terdapat seorang remaja putri yang mencaci maki seorang ibu yang sedang hamil ketika meminta tempat duduk remaja tersebut. Melalui akun jejaring sosial Path, remaja putri tersebut mengungkapkan rasa kekesalannya atas kejadian yang dialaminya (Hilangnya rasa empati dari kaum muda, 2014). Akibat perbuatannya, remaja putri yang berinisial “D” tersebut mendapat kecaman dan kemarahan dari semua kalangan. “D” dianggap sebagai gadis remaja yang apatis, cuek dan tidak memiliki rasa empati sama sekali. Ironisnya, tindakannya tersebut mendapat dukungan dari beberapa teman Pathnya sendiri. “D” akhirnya meminta maaf kepada publik atas perbuatannya melalui akun jejaring sosial yang sama. Kasus ini menjadi sebuah pelajaran bahwa remaja yang berubah menjadi egois dan hanya mementingkan diri sendiri dari pada rasa sosialnya di masyarakat, akan menghancurkan sisi kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku ini bertentangan dengan pendidikan Pancasila yang disebut Pedoman Penghayatan 3 dan Pengamalan Pancasila (P4). Pancasila mengajarkan untuk menjadi manusia yang menghormati, tenggang rasa, toleransi dan menghargai kepada setiap orang, terlebih kepada orang tua. Selain itu banyak hal yang diajarkan seperti dalam etika pergaulan, adat dan budaya timur yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ditinjau dari psikologi perkembangan, tahapan usia remaja berada pada kondisi pergantian moralitas dari konsep-konsep moral khusus ke konsep moral individual (Hartati, Nihayah, Shaleh, & Mujib, 2005). Selama berada dalam keadaan tersebut, remaja mengalami ambiguitas dalam pola berpikir kognitif dan respon afektif sebagai pengarah kepada perilaku yang akan ditampilkan. Salah satu contoh ambiguitas yang dialami remaja adalah mencari identitas diri. Menurut teori Psikososial Erikson, remaja berada di tahap 5 yaitu identity vs identify confusion (identitas vs kebingungan identitas), menurut Erikson jika remaja menerima dukungan sosial yang memadai, maka akan muncul eksplorasi personal, kepekaan diri, perasaan mandiri, dan kontrol diri. Begitu juga sebaliknya, remaja yang tidak yakin terhadap kepercayaan diri dan sering kali mendapatkan penolakan dari orang tua, maka dapat dipastikan remaja akan terus mengalami kebingungan (Santrock 1995). Kebingungan-kebingungan inilah yang berdampak pada ketidakstabilan emosi yang akan menimbulkan konflik. Konflik internal antara remaja dan orang tua mempengaruhi perkembangan empatinya. Dengan kata lain, semakin banyak konflik yang muncul akan membuat empati semakin rendah (Van Lissa dkk, 2014). Menurut Carr emosi itu timbul jika individu dihadapkan pada rintangan yang menghambat kebebasannya untuk bergerak, sehingga semua tenaga dan upaya dikerahkan untuk mengatasi 4 rintangan tersebut dan merangsang individu tersebut untuk merugikan lawannya tanpa pertimbangan terlebih dahulu (Hartati dkk, 2005). Empati yang ditampilkan merujuk kepada kesadaran individu untuk dapat berpikir, merasakan, dan mengerti keadaan orang lain dilihat dari perspektif orang tersebut. Sebuah artikel yang ditulis oleh McDonald & Messinger (2014) mendefinisikan empati sebagai kemampuan untuk merasakan atau membayangkan pengalaman emosi orang lain. Menurut Cotton empati tidak hanya sekedar kemampuan afektif untuk berbagi perasaan (sharing feeling) dan kemampuan kognitif untuk memahami kondisi orang lain, akan tetapi individu memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dalam mengungkapkan empati tersebut (Garton & Gringart, 2005). Kemampuan dalam berkomunikasi terus berkembang seiring bertambahnya usia dan kematangan fisik individu. Kemampuan komunikasi harus terjalin dengan baik antara orang tua dan anak, salah satunya dengan menghindari konflik dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi dan dukungan keluarga berpengaruh positif terhadap aspek kognitif empati yang berkaitan dengan persepsi remaja terhadap orang lain (Henry, Sager, & Plunkett, 1996). Terkait dengan kemampuan empati seseorang yang dapat membangun hubungan sosial yang baik, maka konsep empati dapat menjelaskan berbagai macam perilaku sosial yang terjadi di masyarakat, contohnya perilaku agresif. Penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif dan afektif empati berhubungan negatif terhadap perilaku agresif langsung maupun tidak langsung terutama pada perspective taking seseorang (Heerebeek, 2010), berhubungan dengan altruisme pada anak (Eisenberg & Lennon, 1980) serta pentingnya empati terhadap perilaku antisosial (Schaffer, Clark, & Jeglic, 2009). Empati terlihat berbeda dari 5 masing-masing jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perempuan menunjukkan skor empati yang lebih tinggi dari pada laki-laki (Davis, 1980; Bryant, 1982; Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Schieman & Van Gundy, 2000; Barr & Higgins-D’alessandro, 2007). Pentingnya empati tidak hanya terbatas pada kondisi normal seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan fungsi autis yang tinggi mampu merespon empatik perasaan dan emosi orang lain, mengambil peran dan pengalaman orang lain (Yirmiya, Sigman, Kasari, & Mundy, 1992). Baron-Cohen & Wheelwright (2004) merancang skala baru empati untuk melihat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dengan sindrom asperger. Empati terlihat rendah pada anak-anak dengan masalah perilaku, lebih sedikit berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta memiliki kualitas hubungan pertemanan yang rendah (Schonert-Reichl, 1993). Penelitian lain menunjukkan usia berhubungan positif dengan peningkatan empati. Kapasitas untuk mengambil peran (role taking) berkembang setiap tahapan usia di masa kanak-kanak terutama pada usia 2-3 dan 5 tahun. Empati meningkat cepat pada tahapan anak-anak akhir dan remaja awal (Gurucharri & Selman, 1982). Perubahan yang signifikan menghubungkan usia dengan perubahan role taking terkait dengan ekspresi emosi (Robert & Strayer, 1996) serta respon empatik berhubungan dengan penalaran moral yang mengalami peningkatan pada usia 15 tahun. Pengambilan peran dan perasaan simpati berkembang dari tahapan usia remaja yang ditandai dengan kematangan cara berpikir (Eisenberg, Carlo, Murphy, & Van Court, 1995; Lovell, 1999). Terkait dengan penelitian mengenai empati, terdapat beberapa peneliti empati kontemporer seperti Hoffman, Eisenberg, Batson, dan Davis yang sangat 6 produktif melakukan berbagai penelitian. Mereka semua setidaknya sampai batas tertentu berfokus secara eksplisit bagaimana empati berkaitan dengan altruisme dan perilaku prososial. Hoffman, dan Eisenberg telah mempelajari empati terutama dalam kaitannya dengan perilaku prososial pada masa perkembangan anak-anak, sementara Batson meneliti empati terkait dengan altruisme dan motivasi prososial terhadap orang-orang pada umumnya. Dari ketiga peneliti di atas, konsep yang ditampilkan oleh Davis mengambil pendekatan yang lebih luas dan memandang empati secara eksplisit sebagai fenomena multidimensi dan mengusulkan model konstruksi empati (Håkansson, 2003). Davis berjuang dengan kebingungan terhadap persoalan-persoalan tentang empati. Davis mencoba untuk memahami dan mengintegrasikan pandangan-pandangan dari konsep empati yang telah ada sebelumnya, dan kemudian mencoba untuk mengkonstruksikan kembali agar dapat memiliki makna yang lebih tepat (Taufik, 2012). Konsep pengukuran empati dari Mark H. Davis (1980-1983) melihat empati melalui dua aspek yaitu kognitif dan afektif (emosional). Dalam jurnalnya “A Multidimentional Approach to Individual Differences in Empathy” Davis (1980), menemukan bahwa ada empat subskala yang mampu mengukur empati seseorang, antara lain yaitu perspective taking, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. Fantasy, yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah diri mereka secara imajinatif dalam mengalami perasaan dan tindakan dari karakter khayal dalam buku, film, sandiwara yang dibaca atau yang ditontonnya. Empathic concern, yaitu perasaan simpati yang berorientasi kepada orang lain dan perhatian terhadap kemalangan 7 yang dialami orang lain. Personal distress, yaitu kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri sendiri serta kegelisahan dalam menghadapi setting interpersonal yang tidak menyenangkan. Personal distress bisa disebut sebagai empati negatif. Dari keempat subskala inilah Davis (1980) menyebutnya sebagai “Interpersonal Reactivity Index” (IRI). Selama 35 tahun terakhir, beberapa peneliti memberikan kritik terhadap alat ukur Interpersonal Reactivity Index (IRI). Baron-Cohen & Wheelwright (2004) menyatakan bahwa IRI merupakan pengukuran empati yang terbaik untuk saat ini, karena tiga dari empat faktor secara langsung relevan mengukur empati, namun beberapa item pada setiap faktor tidak mengungkap apa yang menjadi tujuan penelitian, contohnya item pada subskala fantasy yang berisi “Saya berhayal dan membayangkan berulang-ulang tentang suatu hal yang akan terjadi pada diri saya”, dan item pada subskala personal distress yang berisi “Dalam situasi darurat, saya merasa gelisah dan mudah sakit”. Item ini terlihat mengukur kemampuan berimajinasi atau mengontrol emosi. Hal ini terlihat jelas bahwa item tersebut bukan hanya mengukur empati saja. Peneliti lain mengritik bahwa IRI tidak dapat digunakan pada bidang neuroscience, karena IRI tidak mengungkap adanya self-other awareness pada setiap subskala (Lietz dkk, 2011). Pengukuran empati menggunakan IRI menghasilkan nilai psikometri yang baik pada sampel orang dewasa dan tidak bisa diterapkan kepada anak-anak dan remaja (Garton & Gringart, 2005; Hawk dkk, 2013). Meskipun demikian, banyak kalangan yang tetap menggunakan skala IRI untuk mengukur empati. Alasannya adalah (a) IRI merupakan satu-satunya skala yang didasarkan pada konsep multidimensional, adapun beberapa penelitian lain yang multidimensi (Garton & Gringart, 2005), the empathy assassment index 8 (Lietz dkk, 2011) hanyalah pengembangan dari konsep multidimensional Interpersonal Reactivity Index (IRI) dengan mengambil beberapa aspek empati yang mewakili dari kedua dimensi kognitif dan afektif. (b) IRI dianggap sebagai alat ukur yang paling komprehensif dalam mengungkap empati seseorang serta pengadministrasian IRI relatif singkat dan sederhana. (c) empat aspek IRI merupakan konsep multidimensi yang unik, karena masing-masing aspek terpisah satu sama lain, akan tetapi tetap mengukur satu atribut yang dinamakan “empati”. Pengembangan alat ukur ini terbukti dari beberapa peneliti yang telah melakukan berbagai macam adaptasi versi beberapa negara seperti Belanda, Prancis, Chili, China dan Spanyol (Decorte dkk, 2007; Gilet, Mella, Studer, Gruhn, & Labouvie-Vief, 2013; Fernández, Dufey, & Kramp, 2011; Siu & Shek, 2005; Tello, Egido, Ortiz, & Gandara, 2013). Akan tetapi, beberapa upaya pengembangan alat ukur dengan proses pengadaptasian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil pengujian kesesuaian model tidak fit berdasarkan kriteria goodness of fit. Artinya, keempat aspek empati (perspective taking, fantasy, empathic concern dan personal distress) terbukti tidak sesuai dengan data penelitian. Uji kesesuaian model yang dilakukan oleh Siu & Shek (2005) menunjukkan bahwa konstruk empati yang sesuai dengan sampel orang-orang Cina menghasilkan tiga faktor. Pengembangan alat ukur yang sama juga dilakukan oleh Cliffordson yang menguji kesesuaian model terhadap sampel orang-orang Swedia. Hasil menunjukkan bahwa tiga aspek mengukur empati, kecuali personal distress (Fernández, Dufey, & Kramp, 2011). Meskipun IRI telah diadaptasi ke dalam beberapa bahasa, namun belum ditemukan pengembangan skala empati versi Indonesia yang memiliki reliabilitas 9 dan validitas yang baik berdasarkan properti psikometri. Setelah menganalisis semua item dalam skala IRI, peneliti memutuskan untuk melakukan pengembangan alat ukur dengan proses modifikasi. Proses modifikasi alat ukur empati IRI dilakukan dengan menambah jumlah item pada masing-masing aspek berdasarkan hasil observasi yang akan dilakukan kepada sejumlah sampel. Proses perubahan secara tata bahasa sangat penting untuk dilakukan, karena pada dasarnya skala IRI dibuat untuk usia dewasa. Target penelitian ini ialah sampel remaja, oleh karena itu harus dilakukan kesetaraan pemahaman agar penelitian ini menghasilkan alat ukur yang sesuai dengan pemahaman remaja di Indonesia. Pengembangan alat ukur menurut Paterson dapat dilakukan dengan memperbaiki, mengadaptasi, atau memperbaharui dan mengadaptasi. Istilah adaptasi alat ukur perlu dilakukan ketika alat ukur psikologis tersebut akan digunakan di negara lain yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan negara dimana alat ukur tersebut diciptakan. Oleh karena itu, harus dilakukan standarisasi kembali untuk memastikan alat ukur psikologis tersebut berkualitas, seperti mengevaluasi validitas, reliabilitas, dan norma sehingga setelah proses yang dilakukan atas alat ukur tersebut, diharapkan dapat bebas dari bias budaya yang dapat mengotori data yang diperoleh (Milanzahri, 2013). Menurut Suyasa (2011) terdapat beberapa hal yang mendasari perlunya suatu alat ukur dimodifikasi, antara lain sebagai berikut: (a) ketidaksesuaian model/teori serta norma yang ada untuk diterapkan pada suatu budaya. (b) keterbatasan alternatif alat ukur itu sendiri. Strong juga mengungkapkan bahwa terdapat kriteria dalam memodifikasi butir/item agar menjadi item yang baik, diantaranya: (a) familiarity, artinya objek yang dinyatakan dikenal oleh partisipan 10 sesuai dengan kondisi saat ini; (b) no-ambiguity, artinya interpretasi item hanya mengarah pada aspek yang akan diukur; (c) daya beda item, artinya pilihan respons dari suatu item alat ukur akan sesuai dengan pilihan dari kelompok yang menjadi acuan (Suyasa, 2011). Proses modifikasi akan diuji dengan analisis faktor konfirmatori (CFA). Pada umumnya sebelum melakukan analisis model struktural, peneliti terlebih dahulu harus melakukan pengukuran model untuk menguji validitas dan reliabilitas dari indikator pembentuk konstruk laten. Konstruk dapat dibentuk secara unidimensional dan multidimensional. Dalam pengujian proses modifikasi akan dilakukan kedua-duanya, baik secara unidimensional maupun ini mampu multidimensional (Latan, 2013). Proses pengembangan alat ukur empati diharapkan memberikan kontribusi yang lebih mendalam. Alat ukur empati dianggap sangat berguna dalam mengukur kemampuan individu untuk memahami kondisi dan perasaan orang lain. Alat ukur empati yang telah dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia dapat digunakan pada bidang pendidikan, contohnya sebagai landasan guru bimbingan konseling untuk membuat pelatihan-pelatihan terkait peningkatan empati siswa. Salah satu contoh pelatihan terkait empati adalah PEACE (Parent Empowerment, Empathy Training, Anger Management, Character Education, Essential Social Skills) curriculum (Salmon, 2003) sebuah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan empati dan mencegah perilaku agresif. Melalui pengukuran empati, pihak sekolah mampu membuat kebijakan lainnya seperti membentuk ekstrakurikuler yang berbasis peningkatan empati siswa, salah satunya ialah kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) dan Pusat Informasi Konselor-Remaja (PIK-R). Kegiatan tersebut mampu 11 mendidik siswa untuk membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dengan bertindak sebagai konselor teman sebaya. Usaha ini harus ditanamkan sedini mungkin supaya terbentuk hubungan interpersonal yang baik dan berkualitas khususnya di kalangan remaja Indonesia saat ini. Alat ukur empati yang telah dimodifikasi secara bahasa akan memberikan kontribusi yang besar pula pada bidang psikologi perkembangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa empati sebagai landasan perkembangan kualitas sosial dan emosi seseorang. Empati yang dijelaskan berdasarkan konsep multidimensi terkait antara aspek kognitif dan afektif akan berhubungan dengan fungsi dan proses perkembangannya. Ketika terjadi hambatan pada fungsi dan proses perkembangan dari kedua aspek tersebut, akan mempengaruhi pula proses untuk berempati. Anak dengan hambatan kognitif akan berdampak pada kualitas pemahaman dan bahasa. Mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami maksud yang dikatakan oleh orang lain. Hal serupa juga dikatakan Titchener bahwa empati membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi orang lain (Taufik, 2012). Dampak serupa yang akan terjadi ketika aspek afektif mengalami hambatan. Konsep empati terkait aspek afektif menjelaskan bahwa empati merupakan bentuk reaksi emosi terhadap kondisi orang lain. Pada perkembangannya, fungsi afektif tidak terlepas dari peran orang tua terutama ibu dalam mengelola emosi anak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana skala empati IRI dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi remaja di Indonesia. Kelayakan alat ukur juga akan dilihat apakah memenuhi persyaratan secara 12 psikometris, sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul berdasarkan konstruk “Pengembangan Skala Empati Remaja”. B. Rumusan Permasalahan Apakah skala multidimensional empati Davis yang sesuai dan dikembangkan dapat digunakan untuk mengukur kecenderungan empati remaja di Indonesia? C. Pertanyaan dalam Penelitian 1. Apakah skala empati yang telah dimodifikasi secara bahasa dan budaya Indonesia memiliki reliabilitas yang baik? 2. Bagaimana model struktur faktor skala empati yang telah modifikasi? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah skala empati yang telah dimodifikasi sesuai dengan pemahaman secara bahasa dan budaya Indonesia serta dapat digunakan khususnya pada remaja di Indonesia. 2. Manfaat a. Secara praktis Melalui penelitian ini diharapkan mampu menyediakan skala pengukuran empati yang baik secara karakteristik psikometri yang dapat digunakan khususnya di bidang perkembangan sosial emosi. Selain itu, melalui penelitian ini yaitu pengembangan skala empati berdasarkan konstruk 13 multidimesional dapat digunakan dengan mudah oleh kalangan non psikolog sehingga dapat memudahkan pihak sekolah dalam membuat kurikulum sekolah dan ekstrakurikuler yang berbasis pengembangan empati guru dan peserta didik b. Secara teoritis Manfaat dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasiinformasi terkait dengan kesesuaian konstruk dari keempat aspek empati (perspective taking, fantasy, empathic concern, dan personal distress) terhadap kondisi remaja. E. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian telah mencoba untuk membuat alat ukur empati yang dilihat dari sisi Personality, Social Self-Confidence, Even Temperedness, Sensitivity, dan Nonconformity (Johnson, Cheek, & Smither, 1983). Terdapat pula penelitian dari Zoll (in Press) yang menggabungkan beberapa skala pengukuran empati dari Bryant’s Index of Empathy Measurement, Leibetseder’s E-Skala, Garton & Gringart’s IRI version, dan Eisenberg’s Child-Report Sympathy Scale, sehingga terbentuk skala pengukuran empati baru untuk anak dan remaja. Penelitian kali ini akan mencoba menggunakan skala pengukuran Interpersonal Reactivity Index” (IRI) dari Davis (1980) dengan subskala perspective taking, fantasy, empathic concern, dan personal distress. Perbedaan dalam penelitian ini ialah peneliti mencoba melakukan perakitan item dengan melakukan penulisan item serta modifikasi terhadap beberapa item dari IRI yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi remaja di Indonesia saat ini. Proses modifikasi dilakukan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap menterjemahkan ke dalam bahasa 14 Indonesia melalui para ahli, keterbacaan/pra uji coba subjek, expert judgement, setelah itu dilakukan uji coba dan dianalisis menggunakan penghitungan psikometri untuk melihat model fit, validitas dan reliabilitas alat ukur.