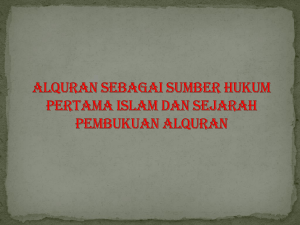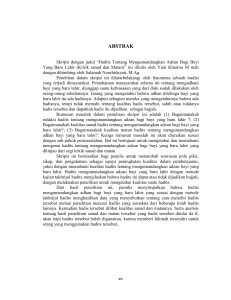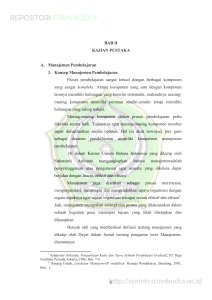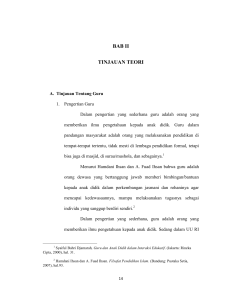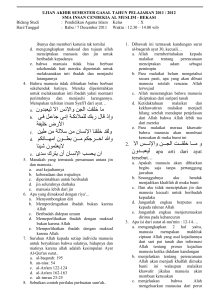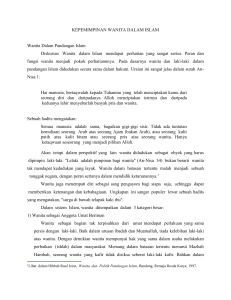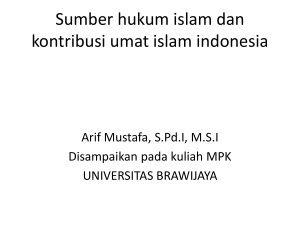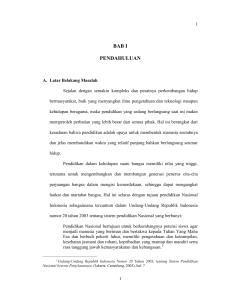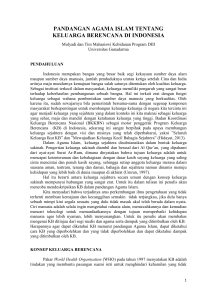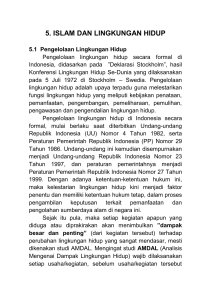Document
advertisement
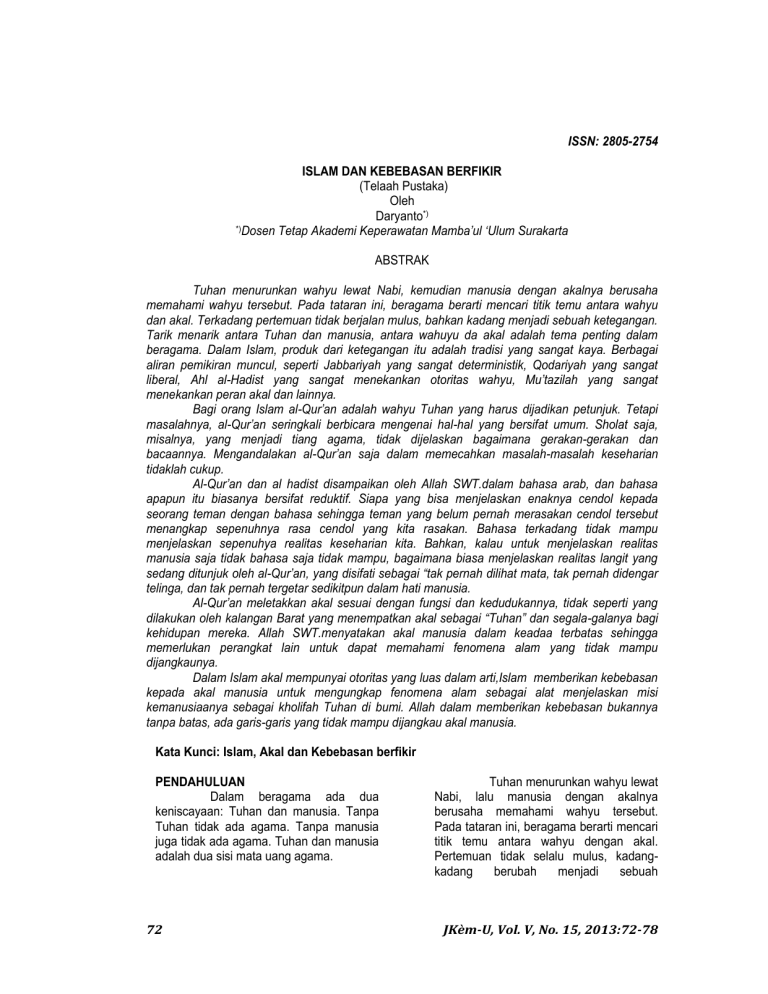
ISSN: 2805-2754 ISLAM DAN KEBEBASAN BERFIKIR (Telaah Pustaka) Oleh Daryanto*) *)Dosen Tetap Akademi Keperawatan Mamba’ul ‘Ulum Surakarta ABSTRAK Tuhan menurunkan wahyu lewat Nabi, kemudian manusia dengan akalnya berusaha memahami wahyu tersebut. Pada tataran ini, beragama berarti mencari titik temu antara wahyu dan akal. Terkadang pertemuan tidak berjalan mulus, bahkan kadang menjadi sebuah ketegangan. Tarik menarik antara Tuhan dan manusia, antara wahuyu da akal adalah tema penting dalam beragama. Dalam Islam, produk dari ketegangan itu adalah tradisi yang sangat kaya. Berbagai aliran pemikiran muncul, seperti Jabbariyah yang sangat deterministik, Qodariyah yang sangat liberal, Ahl al-Hadist yang sangat menekankan otoritas wahyu, Mu’tazilah yang sangat menekankan peran akal dan lainnya. Bagi orang Islam al-Qur’an adalah wahyu Tuhan yang harus dijadikan petunjuk. Tetapi masalahnya, al-Qur’an seringkali berbicara mengenai hal-hal yang bersifat umum. Sholat saja, misalnya, yang menjadi tiang agama, tidak dijelaskan bagaimana gerakan-gerakan dan bacaannya. Mengandalakan al-Qur’an saja dalam memecahkan masalah-masalah keseharian tidaklah cukup. Al-Qur’an dan al hadist disampaikan oleh Allah SWT.dalam bahasa arab, dan bahasa apapun itu biasanya bersifat reduktif. Siapa yang bisa menjelaskan enaknya cendol kepada seorang teman dengan bahasa sehingga teman yang belum pernah merasakan cendol tersebut menangkap sepenuhnya rasa cendol yang kita rasakan. Bahasa terkadang tidak mampu menjelaskan sepenuhya realitas keseharian kita. Bahkan, kalau untuk menjelaskan realitas manusia saja tidak bahasa saja tidak mampu, bagaimana biasa menjelaskan realitas langit yang sedang ditunjuk oleh al-Qur’an, yang disifati sebagai “tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah tergetar sedikitpun dalam hati manusia. Al-Qur’an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan Barat yang menempatkan akal sebagai “Tuhan” dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah SWT.menyatakan akal manusia dalam keadaa terbatas sehingga memerlukan perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Dalam Islam akal mempunyai otoritas yang luas dalam arti,Islam memberikan kebebasan kepada akal manusia untuk mengungkap fenomena alam sebagai alat menjelaskan misi kemanusiaanya sebagai kholifah Tuhan di bumi. Allah dalam memberikan kebebasan bukannya tanpa batas, ada garis-garis yang tidak mampu dijangkau akal manusia. Kata Kunci: Islam, Akal dan Kebebasan berfikir PENDAHULUAN Dalam beragama ada dua keniscayaan: Tuhan dan manusia. Tanpa Tuhan tidak ada agama. Tanpa manusia juga tidak ada agama. Tuhan dan manusia adalah dua sisi mata uang agama. 72 Tuhan menurunkan wahyu lewat Nabi, lalu manusia dengan akalnya berusaha memahami wahyu tersebut. Pada tataran ini, beragama berarti mencari titik temu antara wahyu dengan akal. Pertemuan tidak selalu mulus, kadangkadang berubah menjadi sebuah JKèm-U, Vol. V, No. 15, 2013:72-78 ketegangan. Tarik menarik antara Tuhan dan manusia, antara wahyu dan akal adalah tema penting dalam beragama. Dalam Islam, produk dari ketegangan itu adalah tradisi yang sangat kaya. Berbagai aliran pemikiran muncul: Jabbariyah yang sangat deterministic, Qadariyah yang sangat liberal, Ahl al-Hadits yang sangat menekankan otoritas wahyu, Mu’tazilah yang sangat menekankan peran akal, dan lain-lain. Wahyu adalah sumber kebenaran. Demikian juga akal. Wahyu menyatakan bahwa membunuh dan berdusta itu buruk. Tetapi tanpa wahyu, terutama menurut pandangan Mu’tazilah, akalpun bisa menyatakan hal yang sama. Berasal dari Tuhan, kebenaran wahyu bersifat mutlak dan abadi. Berasal dari manusia, kebenaran akal relative dan kontekstual. Karena posisinya yang demikian, kebenaran wahyu lebih unggul dari kebenaran akal. Akal harus tunduk pada wahyu. Tapi masalahnya, siapa selain Tuhan yang bisa mengetahui kebenaran wahyu yang mutlak tersebut? Manusia dengan akalnya. Manusia yang paling memahami wahyu adalah Nabi. Dialah manusia sempurna yang dekat dengan Tuhan. Kata-kata dan perbuatan Nabi, yang kemudian disebut hadits atau sunnah, menjadi alat penting dalam menjelaskan wahyu. Sumber untuk mengetahui kebenaran Tuhanpun menjadi dua: AlQur’an dan Hadits Nabi. Berbicara tentang kebebasan berfikir dalam Islam sesungguhnya adalah diskusi tentang hubungan, atau ketegangan, antara Al-Qur’an, hadits dan akal manusia. Reflkeksi dan Analisis A. Hubungan al-Qur’an dan Hadits Bagi orang Islam al-Qur’an adalah wahyu Tuhan yang harus dijadikan petunjuk. Tapi masalahnya, al-Qur’an seringkali berbicara mengenai hal-hal yang bersifat umum. Shalat saja, misalnya, yang menjadi tiang agama, tidak dijelaskan Islam dan Kebebasab berfikir bagaimana gerakan-gerakan dan bacaannya. Mengandalkan al-Qur’an dalam memecahkan masalah-masalah keseharian tidaklah cukup. Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H / 65661 M) sekelompok muslim yang dikenal sebagai khawarij, menolak kebijakan Ali untuk bertahkim ( menyelesaikan peperangan lewat arbitasi) dengan Muawiyah. ‘Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan mereka dengan harapan kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah serta mengakui kekhalifahan ‘Ali. Sebelum berangkat Ali menasehati Ibnu Abbas untuk tidak menggunakan al-Qur’an sebagai dasar berargumen, karena alQur’an itu multi-interpretasi (dhu’ wujuh). Apa yang Ibnu Abbas katakan dari alQur’an akan selalu dijawab khawarij yang juga diambil dari al-Qur’an. “berargumenlah dengan sunnah,” tegas Ali. Ali melihat bahwa menggunakan alQur’an tanpa rujukan lain tidak akan memberikan jalan keluar. Walaupun alQur’an adalah sumber Islam yang pertama, tetapi dalam prakteknya sumber rujukan yang paling produktif ada diluar alQur’an dan sunnah. Nabi sendiri menyebut al-Qur’an sebagai “tali yang membentang dari langit ke bumi (habl mamdud min al-sama’ ila alard).” Sebagai tali penghubung, al-Qur’an sangatlah penting. Tanpa al-Qur’an kita tidak bisa berhubungan dengan dunia langit. Tapi yang lebih penting lagi adalah realitas yang ada di ujung tali itu. Dalam ilmu kajian (teologi), terutama diantara pengikut Abu Hasan al-Anshari (w.324 H/ 935-6 M), tokoh penting dibalik munculnya madzhab Ahlussunnah wal Jama’ah, realitas diujung tali itu disebut dengan Madlul (signified), yang ditunjuk), yaitu alkalam al-haqiqi (kalam Tuhan yang sebenarnya). Sementara al-Qur’annya sendiri disebut dal (signifier, yang menunjuk). Berada dalam diri Tuhan, realitas ini sangat luas dan abadi. Para mufassir menyadari hal ini. Mereka mengenal tafsir dan ta’wil. Sementara tafsir lebih menitikberatkan pada makna zahir 73 (permukaan), sementara ta’wil pada makna batin. Juga ada makna qarib (dekat) dan makna ba’id (jauh). Kalau al-Qur’an oleh Nabi disebut tali penghubung antara langit dan bumi, maka hadits bisa disebut sebagai tali penghubung antara Nabi dan masyarakat Muslim. Berbeda dengan al-Qur’an, realitas yang ditunjuk oleh hadts adalah realitas manusia. Dibanding realitas Tuhan, realitas manusia lebih bisa dijangkau dan dimengerti karena manusia manapun pada dasarnya memiliki karakter dan kebutuhan yang sama. Tetapi masalah lain muncul. Karena berasal dari manusia, nilai kebenaran yang dikandung hadits berada dibawah objektifitas al-Qur’an. Padahal memilih objektifitas dari timbunan subjektifitas sangatlah sulit. Tidak mengherankan kalau para ulama mempertanyakan kebenaran, atau shahih tidaknya, suatu hadits. Bukhari (w.256 H/ 870 M) dan Muslim (d.261/875) banyak menghabiskan waktu, tenaga dan fikiran untuk memisah-misah mana haditshadits yang benar dan yang tidak. Hasilnya? Selama 16 tahun bukhari berhasil mengumpulkan 600.000 hadist dan hanya 7397 (atau 2762 tanpa pengulangan) yang dinilai shahih. Sementara Muslim berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 dan hanya 4.000 (atau 3.000 tanpa pengulangan) saja yang dipilih. Jumlah ini terlalu terbatas untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat Muslim yang demikian kompleks. Belum lagi masalah dekontekstualisasi Hadits. Saya berfikir Nabi sering berbicara panjang lebar, tetapi jarang sekali ada hadist panjang. Nampaknya pembicaraan Nabi yang panjang itu dipotong-potong menjadi kalimat-kalimat pendek sehingga konteks kalimatnya hilang. Hadits cenderung diperlakukan sebagai suatu pernyataan yang autonomus dan self sulfficient. Faktor bahasa juga penting untuk diperhatikan. al-Qur’an dan hadits disampaikan dalam bahasa Arab dan 74 bahasa, bahasa apapun itu, sangatlah reduktif. Siapa yang bisa menjelaskan enaknya cendol kepada seorang teman dengan bahasa sehingga teman yang belum pernah merasakan cendol tersebut mengkap sepenuhnya rasa cendol yang kita rasakan.? Bahasa tidak mampu menjelaskan sepenuhnya realitas keseharian kita. Akan lebih sulit lagi menjelaskan realitas yang jauh dari ruang dan waktu kita. Bahkan, kalau untuk menjelaskan realitas manusia saja bahasa sudah tidak mampu, bagaimana bisa menjelaskan realitas langit yang sedang ditunjuk oleh al-Qur’an, yang disifati sebagai “ tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah tergetar sedikitpun dalam hati manusia.” Pada sisi lain, dengan latar belakang masyarakat Nabi abad ke-7, alQur’an dan hadits mengandung kata-kata dan benda-benda yang khas. Perlu usaha untuk menegaskan bahwa makna katakata itu atau benda-benda itu melampaui batas ruang dan waktu sehingga, walaupun secara fisik pada abad ke-7, mereka jga milik kita; bahwa kata-kata dan benda-benda itu yang kita miliki sehingga nilainya bisa di transfer. Memedakan antara makna dan kata, dan memperluas makna dan kata, nampaknya menjadi tema besar yang harus difikirkan oleh masyarakat muslim. B. Hukum ketika tidak ada dalam alQur’an dan Hadits Sifat al-Qur’an yang demikian umum dan jumlah hadits yang terbatas mengharuskan kita untuk mencari sumber lain diluar keduanya. Ibnu ‘Abbas, kalau ditanya tentang suatu masalah, pertamatama ia akan melihatnya didalam alQur’an. Jika tidak ditemukan, dia akan merujuk ke hadits. Jika juga tidak ditemukan, dia akan merujuk ke hadist. Jika juga tidak ditemukan. “aku akan menggunakan fikiranku sendiri (ajtahid ra’yi).” Kata-kata “aku akan menggunakan fikiranku sendiri” memiliki makan sosiokultural yang sangat kompleks. Ibnu JKèm-U, Vol. V, No. 15, 2013:72-78 ‘Abbas adalah produk masyarakat dan zamannya. Ketika berfikir, pada hakikatnya dia sedang membuka dirinya pada realitas social budaya yang ada di sekitarnya. Maka untuk memahami alqur’an, dia menguasai syair Arab, geneologi, maghazi (cerita peperangan yang diikuti oleh Nabi), dan ayyam al-arab (kisah-kisah yang berisi peperangan dan peristiwa-peristiwa penting lainnya, tokoh-tokoh terkenal, dan adat kebiasaan Arab sebelum islam yang transmisikan secara lisan dalam bentuk syair), empat kebudayaan yang sangat penting bagi masyarakat Arab waktu itu. Semangat Ibnu ‘Abbas adalah semangat untuk membuka keluasan fikiran dan memperkaya penafsiran agama dengan kekayaan tradisi dan budaya local. Sikap terbuka terhadap tradisi local, bahkan tradisi diluar Arab sekalipun, sesungguhnya sudah digariskan oleh islam. Beberapa contoh sudah bisa disebutkan disini. Pertama, sunat (khitan). Sebelum islam sunat (khitan) sudah menjadi tradisi Arab yang demikian kuat sehingga jika ada orang yang tidak melakukannya dia akan malu besar. Dalam sebuah peperangan antara pasukan Nabi melawan suku Thaqif,’ seorang Anshar menemukan bahwa satu dari pasukan Thaqif yang terbunuh tidak disunat. Dia pun berteriak sekuat tenaga, “tuhan tau orang-orang thaqif tidak disunat.” AlMughirah Ib.Shu’bah segera menahan orang-orang Anshar tersebut, takut kalaukalau berita itu akan menyebar ke semua penduduk arab. Dengan bersumpah, dia memohon supaya orang Anshar tadi tidak lagi mengatakan hal itu. Menurutnya, orang yang tidak disunat itu hanyalah seorang budak suku Thaqif yang beragama Kristen. Dia lalu membuka celana orang-orang Thaqif yang terbunuh untuk menunjukkan bahwa mereka semuanya disunat. Kedua, khumus, yaitu menyisihkan 1/5 dari rampasan perang untuk Nabi, seperti disebutkan dalam alQur’an S.8:41. Sebelum Islam orang-orang Arab terbiasa menyisihkan ¼ harta dari Islam dan Kebebasab berfikir rampasan yang didapat dan diberikan kepada kepala sukunya, untuk meng-cover biaya-biaya keperluan bersama. Nabi, sebelum al-Qur’an 8:41 diturunkan, atau sebelum khumus diwajibkan, sudah mengambil 1/5 harta rampasan yang didapat dari sahabat-sahabatnya. Ketiga, potong tangan. Pada usia 35 tahun, atau 5 tahun sebelum jadi Nabi, Nabi beserta orang-orang Quraisy lainnya membangun kembali Ka’bah. Dindingnya diperkuat, ditinggikan dan diberi atap. Salah satu alasannya adalah karena benda-benda berharga yang disimpan didalamnya sering dicuri orang. Duwayk, si pencuri, akhirnya tertangkap dan orang-orang Quraisy memotong tanggannya. Sunat, khumus, dan potong tangan adalah tradisi local Arab yang kemudian diadopsi Islam. Peran Nabi dalam hal ini sangatlah penting. Nabi, sebelum diangkat jadi Nabi sekalipun, adalah seorang yang terbuka dan cerdas, bisa berfikir melampaui batas-batas pemikiran yang selama ini digariskan oleh masyarakatnya. Atas dasar renungannya, misalnya, dia menolak praktek penyembahan berhala. Karena sikap terbukannya juga, peran kenabian bisa diemban dengan baik. Kalau tidak, nilainilai Islam yang sering kontradiktif dengan nilai-nilai masyarakatnya, yang hadir dalam dirinya lewat wahyu, juga akan ditolaknya. Bukankah dia tidak mau menerima fikirafikiran atau nilai-nilai baru ? memang tidak mudah untuk membedakan mana peran Nabi sebagai nabi, atau nabi sebagai instrument Tuhan, dengan nabi sebagai manusia biasa. Apakah Nabi mengakomodasi tradisi itu atas dasar insiatifnya atau atas dasar perintah Tuhan ? informasi yang disampaikan al-Tabari, bahwa Nabi mengambil khumus sebelum wahyu tentang khumus diturunkan, mungkin bisa dijadikan indikasi bahwa inisiatif datangnya dari Nabi, lalu Alqur’an menguatkannya. Terlepas dari persoalan apakah Nabi memutuskan dahulu lalu Al-Qur’an 75 memperkuatnya atau sebaliknya, sebagai seorang individu ketika wahyu tidak mengkonfirmasipun, Nabi memang seorang yang berfikir terbuka. Nabi sendiri menyatakan bahwa dirinya pernah berfikir untuk melarang umatnya ‘menyentuh’ istriistri mereka pada masa menyusui anak. Tetapi setelah mengetahui bahwa orangorang Romawi dan Persia tetap menyentuh istri mereka dan tidak berakibat negative pada anak-anak mereka. Nabi tidak jadi mengeluarkan larangan tersebut. Kalau saja Nabi tidak mengetahui bahwa orang-orang Romawi dan Persia melakukannya, Nabi akan melarangnya dan akan menjadi putusan agama atas dasar hadits Nabi ; menyentuh istri pada saat penyusuan. Dengan kata lain, tradisi romawi dan Persia dijadikan acuan pembatalan rumusan hukuman oleh Nabi. Ada baiknya, ketika membaca haditshadits Nabi, untuk diingat (1) kemungkinan kurangnya informasi yang dimiliki Nabi ketika mengatakan atau melakukan sesuatu, (2) informasi yang dimiliki masyarakat muslim sekarang jauh lebih banyak dari yang dimiliki generasi Nabi. C. Batasan kebebasan berfikir Ibnu ‘Abbas, menurut sebuah riwayat, pernah berbagi nasehat seperti yang disampaikan Nabi kepadanya. Nabi memintanya untuk tidak berbicara kecuali jika diminta dan untuk tidak tetap berbicara jika yang memintanya adalah orang-orang yang fikirannya sangat terbatas. Dalam hal terakhir ini, jika pun Ibnu ‘Abbas tetap berbicara, yang akan muncul adalah fitnah. Karena nasehat Nabi tersebut Ibnu ‘Abbas menyembunyikan banyak hal dan hanya disampaikan kepada orang-orang yang berilmu. Batas-batas fikiran, karena itu, sangat personal dan sosiologis. Batas fikiran dari satu orang keorang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain, berbeda-beda. Seringkali batas seseorang, atau suatu kelompok masyarakat, dalam suatu waktu disuatu tempat tidak bisa dipakai untuk membatasi orang atau kelompok lain. Batas orang Syi’ah dan orang Sunni berbeda-beda. Demikian juga 76 antara Mu’tazilah dengan ahl al-Hadits. Mencari batas dalam al-Qur’an dan hadits juga terkadang tidak menyelesaikan masalah sebab keduanya tidak bisa berbicara sendiri, tetapi melalui orang-orag Islam, para musafir, fuqaha, teolog, dan lain-lain, yang manusia dengan segala keterbatasannya. Pada prakteknya, bisa jadi batas yang sesungguhnya bukan ada dalam ajaran islam itu sendiri tapi ada di kalangan pemeluknya. Memang hanya Tuhan yang memiliki sifat tak terbatas. “ Sesungguhnya Allah itu Maha Tak Terbatas dan Maha Mengetahui (innallah wast’ alim).” Sebagai sesuatu yang terbatas, manusia tidak mungkin mampu menangkap dzat yang tak terbatas. Islam, sebagai system nilai yang terhubungkan dengan Allah, juga memiliki keluasan makna yang tak terbatas. Menarik untuk dilihat bahwa akar kata’islam’ adalah ‘aslama’, bukan salima. Sementara salima berarti selamat, aslama berarti sedang berusaha untuk selamat, atau seseorang yang berusaha untuk menangkap nilai-nilai luhur yang ada di wilayah Tuhan yang tak terbatas itu. Dan pada hakikatnya manusia tidak akan bisa menangkapnya. Dia akan meninggal dalam usaha itu. Kebiasaan para ulama, baik dahulu maupun sekarang, untuk menggunakan kata-kata “wallahu a’lam (Allah Maha Tahu)” sebagai penutup dari semua penjelasan adalah bentuk pengakuan yang sangat jujur tentang keterbatasan mereka. Ajaran untuk taqarrub, ilallah, berusaha dekat dengan Allah, mengingatkan hal yang sama. Dalam taqarrub ada pengakuan jarak abadi antara seorang Muslim dengan Tuhannya. Tidak ada penyatuan, yang ada hanya pendekatan pada Tuhan. Kalau Tuhan adalah sumber kebenaran mutlak, maka yang akan dicapai manusia secara maksimal hanyalah mendekati kebenaran tersebut. Karena setiap pandangan seorang Muslim tentang Islam selalu relative (zann). Biasanya, dalam konteks ini, orang membedakan antara fiqih JKèm-U, Vol. V, No. 15, 2013:72-78 dengan syariah. Sementara syariah adalah nilai-nilai abadi yang ada di wilayah Tuhan, fiqih adalah pemahaman manusia tentang syariah. Sementara syariah bersifat mutlak, fiqih relative. Sementara syariah tidak kontekstual, fiqih kontekstual, tergantung pada ruang dan waktu tertentu. Karena itu walau kita mengenal banyak madzhab fiqh (ada Syafi’i, Maliki, Hanafi, Hambali dan lain-lain.) Syariat Islam tetap satu. Penerapan syariat Islam di Indonesia, seperti yang ramai dikemukakan akhirakhir ini, sebenarnya adalah penerapan fiqih. Menyamakan fiqih dengan syariah sam dengan menyamakan produk manusia dengan produk Tuhan, atau, bahkan, menyamakan manusia dengan Tuhan karena sama-sama mampu memproduksi suatu yang tidak terbatas, abadi dan tidak kontekstual. Kemampuan manusia untuk bertaqarrub kepada Tuhan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Ada orang yang jauh dengan Tuhan, ada yang dekat, tergantung usaha, ilmu, kemampuan, lingkungan, ibadah dan seterusnya. Dalam konteks kebebasan berfikir itu berarti kemampuan manusia untuk berfikir menangkap kebenaran nilai-nilai Tuhan berbeda-beda satu sama lain. Batas-batas kebebasan sangat dinamis. Menyamakan batas kebebasan bagi semua orang sama saja dengan menyamakan jarak antara Tuhan dengan semua orang : menyamakan seorang koruptor dengan seorang ulama Shaleh. Apa yang dinasihatkan Nabi kepada Ibnu ‘Abbas sengatlah bijak. Nabi tidak melarang Ibnu ‘Abbas untuk berfikir sedalam-dalamnya sebatas kemampuan dirinya. Yang dia larang adalah menyampaikan hasil fikirannya kepada orang-orang yang batas fikirannya sangat dekat. Laranngan sangat kontekstual, tidak inheren dalam proses berfikir. Kebebasan berfikir adalah satu hal, menyampaikan hasil fikirannya adalah hal lain. Ibnu alRumi yang berkunjung kerumah Umm alTalq, seorang sahabat perempuan, mendapatkan langit-langit rumahnya Islam dan Kebebasab berfikir sangat pendek. Waktu ditanya kenapa, Umm al-Talq, menjelaskan bahwa Umar pernah menulis surat kepada orang-orang yang bekerja untuknya supaya tidak berlomba-lomba meninggikkan bangunannya karena, menurut Umar, masa terburuk adalah masa dimana orangorang sudah berlomba-lomba mempertinggi bangunannya. Kesimpulan Al-Qur’an meletakkan akal sesuai dengan fungsinya dan kedudukannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan Barat yang menempatkan akal sebagai ‘Tuhan’ dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menyatakan akal dalam keadaan terbatas sehingga ia memerlukan perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Dalam Islam akal mempunyai otoritas yang luas dalam arti Islam, memberikan kebebasan kepeda akal manusia untuk mengungkap fenomena alam alat untuk menjalankan misi kemanusiaannya sebagai kholifah (wakil) Tuhan dibumi. Allah dalam memberikan kebebasan bukannya tanpa batas, ada garis-garis yang tidak mampu dijangkau akal manusia sebagai mana firman Allah. Allahu ‘A’lamu Bisshowaf. DAFTAR PUSTAKA Profetika, Jurnal Studi Islam diterbitkan oleh Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume.5.2 Juli 2003 Putro Suadi, Mohammed Arkoun tentang, Islam dan Modernitas, Penerbit Paramida Jakarta,1998 Rahmad Jalaludin, Islam alternative, Pengantar : Muhammad Imaduddin Abdurrakhim, Penerbit Mizan Bandung, 1998 77 Nasution Harun, Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran, Penerbit Mizan Bandung, 1989 Ruslinasrun, Konsep Ijtihar Al-Syaukani, Relevansi Bagi pembaharuan Hokum Islam di Indonesia, Penerbit Logos Bandung, 1999 78 Maarif Syafi’I Ahmad, Membumikan Islam, Penerbit Pustaka, 1995 Pelajar Yogyakarta, 1995 Shimogaki Kasuo, Kiri Islam, Antara Modernisme dan Postmodernisme, telaah kritis Pemikiran Hasan Hanafi, Pengantar Abdurrahman Wakhid, diterbitkan, Lkis Yogyakarta, 2000. JKèm-U, Vol. V, No. 15, 2013:72-78