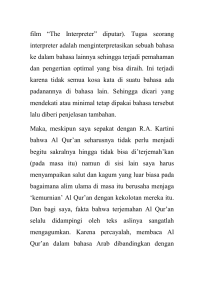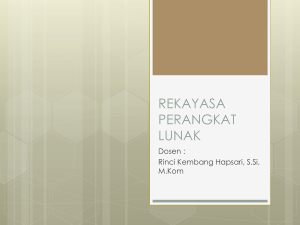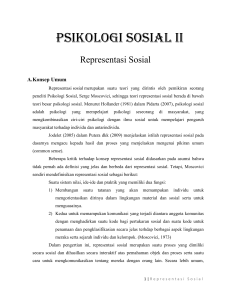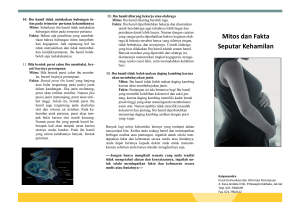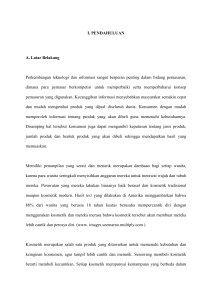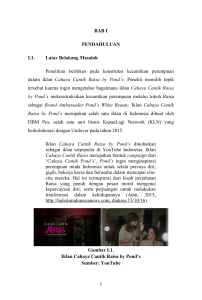CULTURAL STUDIES:
advertisement

IDENTITAS KELAS DAN MITOS KECANTIKAN KULIT PUTIH Gindho Rizano Universitas Andalas Padang ABSTRACT This article takes Indonesia’s modern myth of whiteness as the criteria of women’s beauty as the object of analysis. It focuses on how media, especially through advertisement, spread the class-biased and racially-biased myth. By using generally Barthesian, Foucauldian and Marxist cultural theory as the theoritical positions, it argues that the myth is the product of the ideology of classicism and class identity. This paper seeks to dysmantle the myth by showing its relation to its social origins and power structure. It also seeks to repudiate the previous and well-known claim that the myth is (solely) the product of colonialism and its ideologies. Key words: mitos, putih, identitas, kelas, kelasisme, ras, ideologi, wacana, habitus, semiotik 1. Pendahuluan Sistem ekonomi berbasis pasar bebas Indonesia pasca-reformasi memberi jalan pada media, terutama lewat iklan, untuk menyebar mitos modern dan mengonstruksi identitas yang sesuai dengan interest pasar. Salah satu mitos modern yang dominan dalam masyarakat kita adalah kulit putih sebagai kriteria kecantikan wanita—sebuah mitos yang membuat ungkapan ‘hitam manis’ atau ‘sawo matang’ yang populer pada dekade 80-an menjadi istilah yang arkaik. Mitos ini tidak banyak memberikan pilihan bagi perempuan. Dalam sistem ekonomi yang tidak menganggap perempuan sebagai tenaga kerja yang seberharga pria, banyak perempuan hanya mempunyai pilihan menjadi konsumen pasif dan menjadikan kecantikan sebagai komoditas untuk mobilitas kelas sosial. Pilihan lainnya adalah untuk bekerja secara temporer pada perusahaan swasta yang menjadikan kriteria ‘menarik’ sebagai sarat; dan untuk menjadi menarik atau cantik, adalah terutama sekali menjadi putih—setidaknya begitu mitos yang disebar media lewat iklan-iklan produk pemutih dengan jenis produk yang beragam dan frekuensi iklan yang tidak wajar. Telah banyak usaha untuk menjelaskan penyebab kenapa ‘putih’ yang menjadi kriteria utama kecantikan. Salah satu penjelasan yang paling berterima sebelumnya adalah apa yang Aquarini Prabasmoro sebut sebagai “obsesi [kolonial] lama bahwa kulit putih adalah kulit ideal” (2003:26). Dari sudut pandang ini, perempuan ingin kelihatan putih karena kulit yang demikian berasosiasi dengan ras yang dianggap, atau lebih tepatnya, di-konstruksi sebagai ras ‘superior’. Ini merujuk pada ras kaukasia yang menghabiskan waktu berabad-abad mengekplorasi, meng-kolonialisasi hampir seluruh pelosok dunia dan seiring itu, menciptakan wacana-wacana barat-sentris yang melegitimasi kolonialisasi. Wacana tersebut secara kolektif dirujuk Edward Said sebagai Gindho Rizano ‘orientalisme’ yang mengandaikan inferioritas kelompok terjajah dan superioritas kelompok penjajah. Wacana ini kemudian diinternalisasi oleh kelompok terjajah, memberikan ilusi bahwa kulit ‘berwarna’ mereka adalah penanda inferioritas dan bahwa superioritas hanya bisa didapat dengan menjadi ‘putih’ layaknya kelompok penjajah. Namun demikian, pada konteks Indonesia kontemporer, ada masalah yang serius dengan anggapan bahwa kekaguman terhadap barat memberi jalan pada mitos kecantikan kulit putih. Pertama, apa yang dianggap ‘putih’ dalam kesadaran masyarakat kita bukanlah ‘putih’ ras kulit putih. Survey informal yang penulis lakukan terhadap tujuh koresponden 1 menunjukkan kecenderungan bahwa ras yang dianggap putih menarik adalah ras (mongoloid) Cina. Kedua, kulit kaukasia cenderung dikonotasikan dengan freckles atau bercak-bercak, sesuatu yang berlawanan dengan kulit putih yang berasosiasi dengan kebersihan. Ini terbukti dengan fakta bahwa iklan-iklan produk pemutih yang beredar di Indonesia tidak memakai perempuan kaukasia sebagai modelnya. Namun demikian, benar adanya sebagian model iklan pemutih adalah indo. Saya setuju dengan Aquarini yang mengatakan bahwa hal ini adalah strategi ‘glokalisasi’ kapitalisme barat. Tetapi ini hanya sebatas asosiasi produk dengan ‘kebaratan’ yang pada intinya berasosiasi dengan kemapanan dan nilai-nilai kosmopolitan yang selama ini dipropagandakan oleh globalisme; bukan dengan kulit ras kaukasia secara spesifik. Saya berargumen bahwa pemilihan indo untuk beberapa iklan pemutih, selain karena asosiasi kosmopolitannya, adalah karena individu-individu indo adalah individu-individu yang relatif ‘tidak kelihatan’ dalam kehidupan sehari-hari kaum kelas menengah kebawah sehingga mudah dijadikan objek imajinasi; suatu ‘simulakra’ yang tak perlu ada secara nyata namun hanya berada dalam tataran ideal untuk terus menurus digapai. Pemilihan indo sebagai model secara implisit juga menunjukkan bahwa ras kaukasia tidak dianggap sebagai ras yang mewakili kulit yang ‘paling menarik’. Jika putih yang didambakan perempuan-perempuan yang di-interpelasi oleh media bukanlah masalah ingin berasosiasi dengan ras kaukasia, mungkin hal ini dapat dijelaskan dengan hal yang sepenuhnya berbeda. Saya merujuk pada kategori umum yang membagi manusia menjadi kelompok besar menurut fungsinya dalam moda produksi, yaitu kelas. 2. Politik Identitas: Kelasisme Kelas harus dipahami bukan hanya sebagai fakta sosial, namun juga sebagai identitas: Identitas yang perlu dikonstruksi terus-menerus, diasosiasikan dengan berbagai hal sebagai petanda bahwa subjeknya adalah bagian dari kelas tersebut. Ini berarti identitas kelas adalah sesuatu yang tidak mempunyai esensi karena ia merupakan konstruksi, seperti layaknya gender dan ras. Individu dari kelas manapun dapat mengadopsi identitas kelas atas—setidaknya secara psikologis—dengan memakai produk-produk yang berasosiasi dengan kelas atas. Inilah yang menjadi strategi banyak produk-produk kecantikan seperti Lux. Selain bahwa ia merupakan sebuah konstruksi, sebuah identitas, layaknya sebuah tanda dalam teori strukturalis-linguistik, terbentuk lewat azas perbedaan (differential), seperti yang dikemukakan strukturalis kondang Jonathan Culler: 220 Linguistika Kultura, Vol.02, No.03/Maret/2009 The process of identity-formation not only foregrounds some differences and neglects others; it takes an internal difference or division and projects it as a difference between individuals or groups. (2000:117) Dengan begitu, identitas kelas atas hanya bisa dibentuk dengan menegasi kelas lainnya. Prinsip perbedaan inilah yang mendasari pembentukan identitas barat dan timur seperti yang dikemukakan Edward Said. Barat mendefinisikan dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dari timur; dan pada saat yang sama barat melakukan konstruksi identitas demi melanggengkan oposisi imajiner tersebut; timur dibentuk sebagai yang ‘eksotis’, ‘feminim’, ‘irasional’, ‘keterbelakang’, berbeda dengan barat yang memahami dirinya sebagai ‘maju’, ‘beradab’ , dan ‘rasional’. Saya berargumen bahwa prinsip yang serupa juga terjadi dalam identitas kelas; dan hal ini akan menjelaskan mengapa ‘putih’ menjadi kategori utama dalam kecantikan. Untuk hal ini, yang perlu diketahui adalah bagaimana kelas bawah dimaknai dan bagaimana kelas atas memaknai dirinya sendiri. (Saya memilih morfem aktif ‘me-‘ untuk kelas atas dikarenakan karena media adalah milik kelas sosial tersebut). Pendek kata, kita perlu mengetahui bagaimana keduanya—identitas kelas atas dan kelas bahwah—dicoba dikontraskan. Juga penting diketahui adalah konteks spesifik wilayah perkotaan Indonesia: tempat dimana iklan-iklan dengan mitos kulit putihnya diciptakan lalu kemudian disebarkan keseluruh Indonesia lewat berbagai media. Salah satu fitur yang membedakan individu dari kelompok ekonomi kelas bawah dengan individu dari kelompok ekonomi kelas atas urban Indonesia adalah kulitnya yang terbakar matahari. Pada konteks perkotaan, pekerjaan kelas menengah kebawah adalah jenis pekerjaan yang selalu ter-ekspos oleh matahari. Ambil buruh, pedagang kaki lima, sopir angkutan, salesman sebagai contoh. Berkulit lebih gelap adalah konsekuensi wajar dari pekerjaan jenis ini. Kulit gelap pun serta merta menjadi (dijadikan) penanda akan status sosial seseorang, seperti halnya mata sipit menjadi penanda suatu ras tertentu atau langkah yang gemulai menjadi penanda feminimitas. Masyarakat kelas atas, jika ingin dikatakan mempunyai identitas kelas atas, tentunya harus mengikuti prinsip dikotomi sederhana dengan menjadi apa yang bukan kelas bawah. Disinilah kulit putih, meminjam istilah Roman Jakobson, di-foreground merelegasi warna yang lebih gelap ke background. Kulit yang jarang terkena sinar matahari yang membakar kelompok menengah kebawah kemudian menjadi penanda akan identitas kelas atas dan kemudian mendapat makna yang positif karena dalam sistem ekonomi kompetitif kelas atas adalah kelas yang ideal: kelas yang individu-individu di dalamnya di-wacanakan sebagai pemenang dalam kompetisi tersebut. Identitas kelas yang dikonstruksi secara relasional dan dengan azas differential juga dibahas oleh sosiolog ternama Pierre Bourdieu: Social subjects, classified by their classifications, distinguish themselves by the distinctions they make, between the beautiful and the ugly, the distinguished and the vulgar, in which their position in the objective classification is expressed or betrayed. (Dalam Hitchcock, 2008:94) 221 Gindho Rizano Lebih lanjut, Bourdieu berpendapat bahwa individu dari kelas tertentu mempunyai habitus, atau “satu set kecenderungan atau prinsip-prinsip pengatur yang menentukan struktur aksi dan sifat manusia. (2008:90). Habitus yang dimiliki masing-masing kelas hanya bisa dimengerti dengan mengontraskan dua kelas tersebut. Hitchcock dalam pembahasannya tentang habitus memberikan contoh dengan mengontraskan dua tipe individu dari dua kelas: … a corporate executive with an advanced college degree, disposable income, season tickets to the opera, and a taste for fine wine, contrasts with the dispositions (habitus) of a “blue collar” worker with a high school diploma, significant debt, who watches sports on television, and prefers Budweiser to Bordeaux. (2008:90-91). Tidak sukar untuk melihat kontras tersebut pada konteks Indonesia kontemporer. Seorang individu kelas atas akan mempunyai kecenderungan, kebiasaan dan selera yang kontras dengan individu kelas bawah. Jika individu kelas bawah memilih olahraga sepakbola, individu kelas atas harus memilih olahraga yang berbeda seperti golf atau tenis. Ini juga berlaku pada konteks kulit. Jika berkulit gelap adalah properti dari kaum kelas bawah, kulit yang terang secara relasional dan kontras menjadi milik kelas atas. Dengan kata lain, mempunyai kulit yang lebih putih menjadi habitus bagi kelas atas; menjadi semacam penanda sosial (social marker) akan identitas kelas tersebut 2 . Kulit putih sebagai habitus kelompok kelas atas semakin mendapat makna karena ia mempunyai serentetan konotasi: bahwa individu yang mempunyainya mampu secara ekonomi untuk ‘merawat’ tubuhnya dengan jasa dan produk yang ditawarkan pasar, dan bahwa individu tersebut mempunyai pekerjaan kantoran yang bonafid sehingga terlindung dari matahari. Perlu penulis tekankan bahwa pemaknaan kulit putih sebagai kulit yang menarik adalah sesuatu yang sepenuhnya arbiter (berdasarkan konvensi belaka). Ia hanya bermakna positif karena perbedaannya dengan kulit gelap yang berasosiasi dengan kelas menengah kebawah dan pekerjaannya. Kearbiter-an ini bisa dibuktikan dengan melihat konteks barat. Bagi masyarakat urban Amerika Serikat, kulit yang terbakar matahari dianggap lebih menarik daripada kulit yang pucat—suatu hal yang dibuktikan dengan pemilihan model dengan kulit kecoklatan akibat sinar matahari pada sampul depan majalahmajalah seperti Cosmopolitan. Ini disebabkan karena kulit kecoklatan akibat matahari menandakan kemampuan ekonomi individu untuk berlibur di pantai atau daerah tropis; berbeda dengan kelas pekerja yang tak mempunyai dana yang cukup untuk berlibur. Hal lain yang menjadi fitur pembeda antara dua kelas tersebut adalah terawat atau tidak terawatnya kulit oleh jasa dan produk-produk yang ditawarkan pasar. Dalam kapitalisme pasca industri, wibawa sosial terletak pada kemampuan ekonomi individu untuk mendapatkan jasa; kemampuan individu melakukan intervensi pada tubuhnya yang alami dengan produk-produk atau jasa yang ditawarkan pasar. Ini berarti, sebagai contoh, rambut yang menarik adalah rambut yang diluruskan atau dikeritingkan oleh jasa salon atau dengan bantuan produk tertentu. Tidak ada tempat untuk lurus atau keriting alami. Hal yang sama juga bisa dilihat pada kasus kulit. Kulit yang menarik adalah kulit yang telah diintervensi oleh perawatan atau produk yang ditawarkan pasar. 222 Linguistika Kultura, Vol.02, No.03/Maret/2009 Ukuran wibawa sosial pun bersifat arbiter. Ia berbeda tiap zaman karena ia bergantung pada apa yang disebut oleh Ernest Mendel sebagai ‘produk surplus sosial’ (2006:10) suatu kelompok masyarakat. Jika produk surplus sosial masyarakat pasca industri berupa uang, wibawanya akan tergantung pada bagaimana uang itu dihabiskan untuk pendekorasian diri dengan produk dan jasa. Berbeda dengan masyarakat pascaindustri, masyarakat feodal Hawaii, sebagai contoh, mempunyai produk surplus berupa makanan sehingga wibawa sosialnya tergantung pada berat badan individu (2006:10). Dibalik dari dikotomi yang menentukan identitas ini adalah ideologi kelasisme. Kelasisme menurut Lois Tyson dalam Critical Theory Today adalah sebuah ideologi yang menyamakan nilai seseorang sebagai manusia dengan posisi kelasnya: semakin tinggi kelas sosial seseorang semakin tinggi tinggi pula nilainya sebagai manusia (2006:59). Ideologi yang muncul dari struktur masyarakat kapitalis ini menjelaskan mengapa segala hal yang berhubungan dan kelas atas bermakna positif: sepatu dimaknai lebih positif dari sendal, kompetisi lebih diutamakan dari kerjasama, individualisme diletakkan di atas kebersamaan, hal yang berbau urban lebih dianggap bagus dari hal yang berhubungan dengan kehidupan rural, baju jas seberapa pun tidak cocoknya dengan iklim tropis kita lebih dihargai dari sekedar baju kemeja, kerja kantoran lebih mempunyai prestise dari kerja yang mengandalkan otot, dan tentunya, kulit putih lebih diidealkan dari kulit gelap. Ideologi ini juga yang membuat mitos-mitos yang ditawarkan pasar lewat media dapat diterima dan dianggap taken-for-granted. ‘Naturalisasi’ mitos ini ke dalam kesadaran masyarakat tersebut dibuat mudah dengan minimnya wacana atau ideologi alternatif dalam media yang dimonopoli oleh kelompok sosial tunggal. Kita akan melihat bagaimana ideologi kelasisme yang memberi previlise pada identitas kelas atas menjadi basis bagi mitos kulit putih pada iklan produk pemutih Pond’s, yang saya anggap sebagai produk yang mewakili produk lain atas beberapa pertimbangan: a) Pond’s merupakan produk internasional yang diterima dengan baik oleh konsumer nasional, dan b) frekuensi dan popularitas iklan yang cukup tinggi. 3. Kulit Putih sebagai Identitas Kelas Atas dalam Iklan Pond’s Untuk melihat bagaimana superioritas kelas atas dikonstruksi dan juga bagaimana kulit putih menjadi penanda akan identitas kelas atas, saya akan menganalisis sebuah iklan produk-produk Pond’s versi Pond’s 10 Most Beautiful Women yang saya ambil dari Kompas Minggu tanggal 25 Mei 2008, hlm 8-9. Iklan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama [Gambar 1 dalam lampiran] mengambil setengah halaman koran. Bagian pertama ini melihatkan sepuluh wanita, kesemuanya adalah selebriti ternama Indonesia dalam pakaian gaun malam berwarna krem dengan latar taburan bias cahaya gemerlap. Pada bagian atas terdapat judul yang berbunyi “Pond’s mempersembahkan 10 Pond’s Beautiful Women” dan kemudian diikuti oleh caption berbunyi “Karena POND’s percaya semua wanita itu cantik dan cantik tak mengenal batas usia”. Iklan bagian kedua [Gambar 2 dalam lampiran] mengambil satu halaman penuh koran dan meilhatkan sembilan macam produk Pond’s yang empat diantaranya adalah produk pemutih. Latarnya serupa dengan bagian pertama. Analisis ini akan fokus pada bagian pertama yang mempunyai lebih banyak pesan-pasan kultural dan ideologis. 223 Gindho Rizano Nilai ideologis iklan pertama sekali dapat dilihat dari caption iklan yang berbunyi “Karena Pond’s percaya semua wanita itu cantik dan cantik tak mengenal batas usia”. Proyek ideologis caption tersebut adalah meyakinkan pembaca bahwa semua wanita itu cantik jika mau merawat kulitnya dengan produk Pond’s. Namun, pembacaan kritis dapat melihat bahwa kata ‘semua’ pada konteks keseluruhan iklan adalah sesuatu yang kontradiktif. Kata tersebut meng-ekspos apa yang disebut Pierre Macherrey sebagai gap atau kontradiksi dalam ideologi karena jelas hanya satu kelompok sosial yang dihadirkan dalam iklan ini—hal yang mematahkan (mendekonstruksi) klaim bahwa ‘semua’ wanita cantik. Memang benar kesepuluh model dalam iklan tersebut bukan dari kisaran umur yang sama; mereka pun bukan dari ras tunggal (Kebanyakan adalah Melayu, dan beberapa seperti Sandra Dewi adalah keturunan Tionghoa). Namun, semua wanita lewat berbagai penanda dalam iklan ini, berbagi identitas yang sama: kelompok sosial kelas atas. Kelompok kelas bawah, seperti banyak iklan lainnya, menjadi sesuatu yang absen dan otomatis menjadi yang liyan (the other). Secara relasional hal ini menjadikan kelompok kelas atas sebagai ‘center’, atau ‘the self’. Penanda-penanda visual dalam iklan ini adalah penanda-penanda yang berasosiasi dengan nilai-nilai kelas atas. Ini dapat dilihat dari penanda perhiasan, pakaian gaun malam, dan pose elegan setiap model. Hal-hal tersebut berasosiasi dengan ‘keglamoran’, ’kegemerlapan’, ‘kekayaan’ dan ‘kemapanan’ yang selalu dilihat sebagai properti kelas atas. Latar pun memberikan aksen pada keglamoran dengan imaji gemerlap cahaya yang bisa saja merepresentasikan gemerlap perhiasan atau gemerlap kehidupan bintang dan masyarakat kelas atas. Namun, yang paling menarik dari semua penanda dalam iklan ini adalah bagaimana kulit para model ini dihadirkan. Seperti gaun malam, ia pun menjadi penanda akan identitas kelas atas. Namun, hal ini diraih dengan mengasosiasikan kulit tesebut dengan gemerlap cahaya. Sangat menarik bahwa ke-putih-an kulit yang dihadirkan dalam iklan ini adalah sesuatu yang beraksen; penggunaan cahaya dalam iklan ini membuat hanya bagian-bagian tertentu yang kelihatan putih bercahaya. Hal ini mengasosiasikan putihnya seseorang dengan gemerlap perhiasan atau gemerlap kehidupan bintang yang dikonotasikan oleh latar dan perhiasan. Asosiasi ini penting karena ia menyampaikan dua pesan implisit: (1) layaknya gemerlap kehidupan kelas atas atau perhiasan, kulit putih adalah sesuatu yang didapat (budaya), bukan dari-sananya (alami). Untuk menjadi putih mengharuskan konsumen membeli produk, karena putih yang diinginkan adalah putih hasil intervensi produk yang ditawarkan; (2) Layaknya kehidupan gemerlap dan perhiasan, fitur kulit putih hanya dimiliki oleh kelas atas, bukan oleh kelas lainnya. Juga menarik bahwa Iklan ini, seperti banyak iklan produk kecantikan dan pemutih lainnya, tidak menjadikan ras tertentu sebagai sesuatu yang mendefinisikan kulit putih. Iklan Pond’s di televisi (ditayangkan circa awal 2008) versi gabungan tiga iklan Pond’s sebelumnya juga menunjukkan kecenderungan 3 yang serupa. Model-model iklan tersebut adalah tiga wanita dengan fitur ras yang berbeda 4 . Namun, ketiganya dihadirkan sebagai wanita urban kelas menengah keatas sehingga mengasosiasikan kulit putih dengan kelas tertentu, dan bukan dengan ras tertentu. Dengan ini, kita sekarang dapat melihat hubungan yang kuat dan hampir tak terpatahkan antara mitos kulit terang dengan kelompok sosial kelas menengah ke atas. 224 Linguistika Kultura, Vol.02, No.03/Maret/2009 4. Kesimpulan Kita telah melihat bahwa identitas kelompok ekonomi kelas atas terbentuk dalam hubungan relasional dengan identitas kelompok ekonomi kelas bawah. Dalam konteks ini, mempunyai kulit yang putih merupakan ciri penanda kelas atas karena kulit yang gelap dimaknai sebagai properti kelas bawah. Kita juga telah melihat bahwa lewat media, kelas atas dikonstruksi menjadi ‘the self’ dan meletakkan kelompok kelas bawah menjadi ‘the other’—sebuah struktur biner yang juga tampak pada kategori-kategori lain seperti gender (dengan perempuan sebagai ‘the other’) dan etnisitas (dengan ras-ras kulit ‘berwarna’ sebagai ‘the other’). Pandangan kelasis ini kemudian membuat mitos kulit putih—suatu hal yang dimaknai sebagai fitur kelompok kelas atas—mendapatkan kepopuleran yang luar biasa. Ideologi kelasis dan mitos kulit putih yang mengandaikan superioritas kelompok kelas atas dengan nilai-nilainya tentunya mempunyai sisi negatif. Pandangan tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak (i.e. produsen dan kelompok kelas atas) dan sangat merugikan bagi pihak mayoritas yang dibuat merasa inferior dan pada saat yang sama harus membayar untuk tampil ‘berkelas’. Untuk itu, yang diperlukan adalah pemaknaan aktif atau alternatif pembaca terhadap penanda-penanda yang di-kodekan oleh media. Dengan kata lain, pembaca/penonton perlu membaca media atau teks budaya lainnya, meminjam istilah Stuart Hall, secara oppositional dengan menolak dan tidak selalu menerima semua pemahaman dunia yang tidak sesuai dengan kelompok sosialnya. Ini dinilai penting karena penolakan terhadap mitos berarti pembebasan pikiran dari ideologi. Perlu ditambahkan bahwa Ideologi kelasis yang terejawantahkan pada mitos superioritas kulit putih juga berimbas pada hal yang lain, yaitu rasisme. Dengan pemahaman bahwa hanya individu yang berkulit terang adalah individu yang menarik (dan secara implisit, superior) iklan dan media secara tak langsung menyampaikan bahwa kebanyakan saudara-saudara kita di bagian Indonesia timur adalah makhluk yang tidak menarik dan inferior. ‘Kekejian’ dan rasisme media Indonesia pascaindustri ini tidak jauh beda dengan sikap rasisme negaranegara imperialis tempo dulu pada manusia-manusia di negara jajahannya yang berkulit gelap. Perbedaannya adalah bahwa rasisme dulu terjadi dalam lingkup kolonialisme sedangkan rasisme sekarang dalam lingkup pasar bebas. Kelasisme dan mitos kulit putih juga berpengaruh pada relasi gender. Menarik bahwa kelompok sosial yang menjadi target pasar produk pemutih adalah perempuan. Hal ini terkait erat dengan posisi perempuan dalam sistem kapitalisme. Kulit putih, yang telah dimaknai sebagai properti atau satu habitus kelas atas, adalah semacam ‘capital’ untuk keberlangsungan hidup perempuan dalam kapitalisme. Seperti yang penulis sentuh pada bagian pendahuluan, mempunyai kulit putih dapat berarti mobilitas sosial yang lebih mudah dan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan dalam kapitalisme pascaindustri yang meng-kapitalisasi kecantikan perempuan. Hal ini kontras dengan peran laki-laki yang dalam sistem ini lebih dituntut sebagai pencari nafkah utama. Akhir kata, penulis ingin menekankan bahwa faktor basis ekonomi dan kelas merupakan faktor penentu sebuah fenomena sosial. Namun, faktor-faktor lainnya pun harus diakui juga mempengaruhi sebuah fenomena sosial. Pandangan yang mengatakan bahwa previlise kulit putih adalah akibat ideologi etnosentris barat dan rasisme tidak bisa sepenuhnya ditolak. Ideologi ini memang pernah menjadi faktor penentu utama tumbuhnya mitos kecantikan kulit putih di 225 Gindho Rizano berbagai tempat pada beberapa waktu; dan mungkin saja ideologi ini masih punya andil dalam mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia tentang daya tarik warna kulit tertentu. Inilah yang disebut dengan konsep ‘overdetermination’ oleh Louis Althusser: bahwa suatu fenomena sosial atau produk budaya tertentu tidak hanya dideterminasi oleh satu hal (ekonomi). Namun demikian, filsuf yang sama juga menegaskan bahwa pada akhirnya adalah faktor sistem ekonomi beserta struktur kekeuasaannya yang menjadi penentu. Wacana etnosentris dan rasisme pun pada awalnya muncul karena faktor ekonomi. Ann Louise Keating, misalnya, berpendapat bahwa pembedaan antara kulit hitam dan kulit putih hanya muncul seiiring dengan praktek perbudakan yang dilakukan oleh imperialis Eropa terhadap orang-orang Afrika 5 . Hal ini dilakukan untuk melegitimasi perbudakan: para imperialis memberi label dirinya ‘putih’ dan mengasosiasikan ‘putih’ dengan hal-hal yang positif seperti ‘kebenaran’, ‘cahaya’, kemurnian’ sementara orang-orang Afrika (yang terdiri dari berbagai ras) diberi label hitam dan diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif. Dengan kata lain, wacana rasisme dan pandangan bahwa ras eropa yang ‘putih’ adalah superior dibanding ras lain yang ‘berwarna’, pada awalnya hanyalah sebuah konstruksi yang digunakan untuk melegitimasi sistem perbudakan dan imperialisme. Kembali pada konteks Indonesia, adalah sesuatu yang anakronistis untuk mengatakan bahwa mitos kecantikan kulit putih adalah terutama sekali disebabkan oleh ‘obsesi kolonial’ yang mengidealkan kulit penjajah Eropa (Walau sangat mungkin hal ini pernah menjadi faktor dominan sebelumnya). Kolonialisme datang dan pergi. Seiiring dengan lenyapnya kolonialisme dikotomi penjajah dan terjajah pun dirasa kurang relevan; dan digantikan oleh dikotomi kelas atas dan kelas bawah yang masih menjadi faktor penentu kehidupan sosial di berbagai tempat di dunia. DAFTAR PUSTAKA Culler, Jonathan. (2000). Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Keating, AnnLouise. (1995). “Whiteness,” (De)Constructing “Race”. College English Vol 57, No. 8. http://jstor.org/stable/378620 (27 Februari 2008). Hitchcock, Louise A. (2008). Theory for Classics: A Student’s Guide. New York: Routledge. Mandel, Ernest. (2006). Tesis-Tesis Pokok Marxisme. (Terj). Yogyakarta: Resist Book. Prabasmoro, Aquarini Priyatna. (2003). Becoming White: Representasi Ras, Kelas, Femininitas, dan Globalitas dalam Iklan Sabun. Yogyakarta: Jalasutra. Tyson, Louis. (2006). Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. (2nd Edition). New York: Routledge. 226 Linguistika Kultura, Vol.02, No.03/Maret/2009 Lampiran Gambar 1. 10 Pond’s Beautiful Women. Sumber: Kompas Minggu 25 Mei 2008. Gambar 2. Produk-produk Pond’s. Sumber: Kompas Minggu 25 Mei 2008. 227 Gindho Rizano 1 Koresponden terdiri atas tiga pria dan empat wanita. Ketika ditanya ras mana yang wanitanya mempunyai kulit putih yang menarik, empat koresponden menjawab Cina, tiga koresponden lainnya masing-masing menjawab Melayu, Indo, dan Arab. 2 Perbedaan habitus tidak hanya berujung pada perbedaan identitas kelas. Menurut Bourdieu, habitus dan identitas yang berbeda berguna sebagai kekuatan simbolis untuk melegitimasi ketidakadilan sosial. Lihat Hitchcock. Hal. 89-96. 3 Kecenderungan untuk tidak mengasosiasikan kulit putih dengan ras tertentu ini memerlukan penelitian kualitatif dan kuantitatif lebih lanjut. 4 Melayu, campuran, dan Tiong Hoa. Namun perlu dicatat kedua iklan Pond’s yang disebutkan di artikel ini tidak memakai model dengan ras yang berfitur kulit gelap. Ini akan disentuh pada bagian kesimpulan. 5 Lihat AnnLouise Keating . “Whiteness,” (De)Constructing “Race”. College English Vol.57, No.8. (2008), 911—912. 228