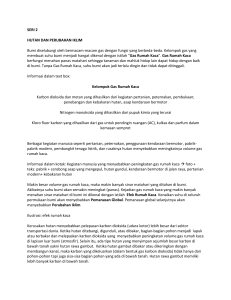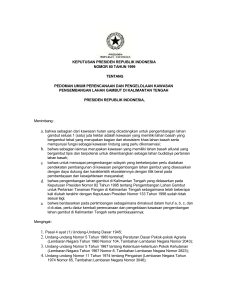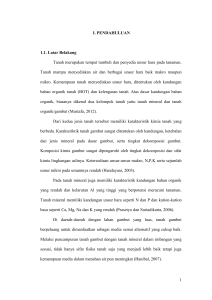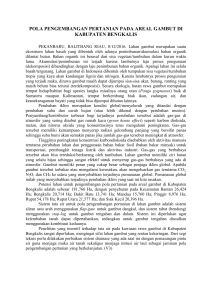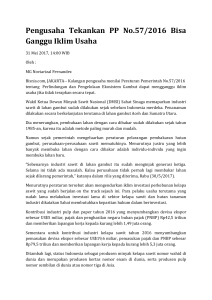“Community Development” di Wilayah Lahan
advertisement
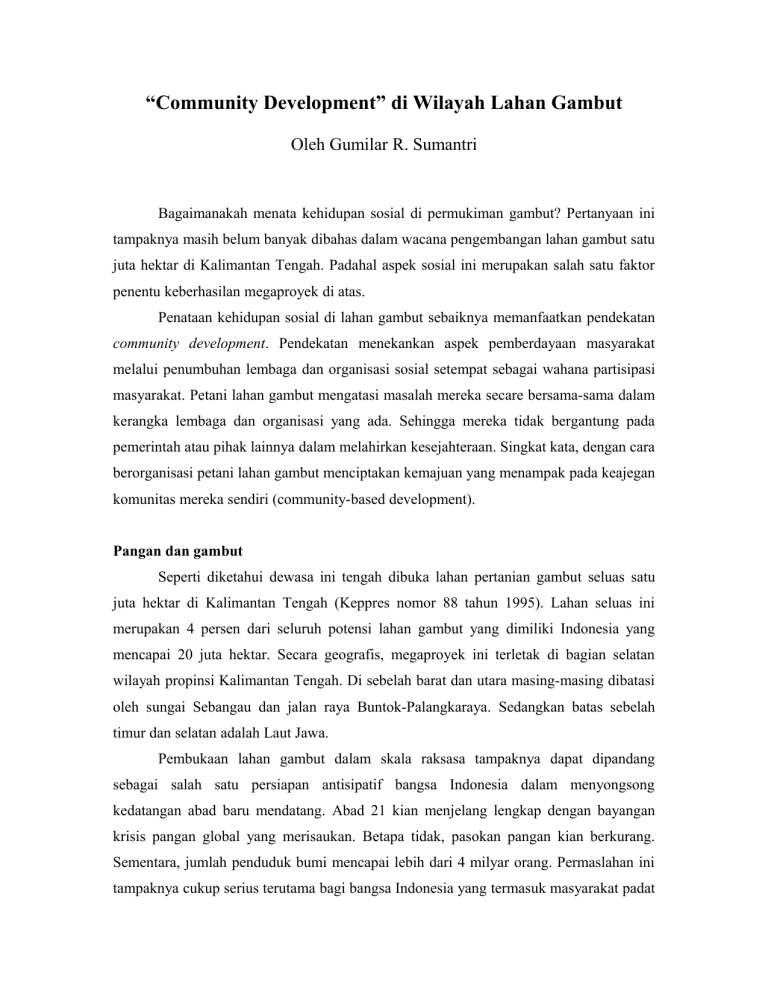
“Community Development” di Wilayah Lahan Gambut Oleh Gumilar R. Sumantri Bagaimanakah menata kehidupan sosial di permukiman gambut? Pertanyaan ini tampaknya masih belum banyak dibahas dalam wacana pengembangan lahan gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah. Padahal aspek sosial ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan megaproyek di atas. Penataan kehidupan sosial di lahan gambut sebaiknya memanfaatkan pendekatan community development. Pendekatan menekankan aspek pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhan lembaga dan organisasi sosial setempat sebagai wahana partisipasi masyarakat. Petani lahan gambut mengatasi masalah mereka secare bersama-sama dalam kerangka lembaga dan organisasi yang ada. Sehingga mereka tidak bergantung pada pemerintah atau pihak lainnya dalam melahirkan kesejahteraan. Singkat kata, dengan cara berorganisasi petani lahan gambut menciptakan kemajuan yang menampak pada keajegan komunitas mereka sendiri (community-based development). Pangan dan gambut Seperti diketahui dewasa ini tengah dibuka lahan pertanian gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah (Keppres nomor 88 tahun 1995). Lahan seluas ini merupakan 4 persen dari seluruh potensi lahan gambut yang dimiliki Indonesia yang mencapai 20 juta hektar. Secara geografis, megaproyek ini terletak di bagian selatan wilayah propinsi Kalimantan Tengah. Di sebelah barat dan utara masing-masing dibatasi oleh sungai Sebangau dan jalan raya Buntok-Palangkaraya. Sedangkan batas sebelah timur dan selatan adalah Laut Jawa. Pembukaan lahan gambut dalam skala raksasa tampaknya dapat dipandang sebagai salah satu persiapan antisipatif bangsa Indonesia dalam menyongsong kedatangan abad baru mendatang. Abad 21 kian menjelang lengkap dengan bayangan krisis pangan global yang merisaukan. Betapa tidak, pasokan pangan kian berkurang. Sementara, jumlah penduduk bumi mencapai lebih dari 4 milyar orang. Permaslahan ini tampaknya cukup serius terutama bagi bangsa Indonesia yang termasuk masyarakat padat penduduknya. Dan pangan bukanlah masalah yang sederhana bagi negeri 200 juta penduduk ini. Hal di atas menarik jika dikaitkan dengan pernyataan salah satu badan PBB, FAO (Food and Agriculture Organization), pada hari pangan tahun 1995. Badan internasional ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Pasifik yang termasuk kategori LIFC (Low Income Food Countries) atau negara berpendapatan rendah kurang pangan. Pernyataan ini jelas bukanlah hal yang harus dicari apologinya. Ini adalah hal serius yang jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan membawa bangsa pada kesengsaraan kekurangan pangan yang menakutkan. Tentu saja pernyataan FAO mengejutkan kita semua. Mengingat bangsa ini pernah meraih prestasi besar di bidang pengadaan pangan, yaitu pada tahun 1984 Indonesia meraih swasembada pangan. Artinya, Indonesia tidak lagi tergantung pada impor di dalam pengadaan bahan makanan pokok, khususnya beras. Prestasi ini membanggakan. Betapa tidak, pada tahun 1969, Indonesia merupakan pengimpor beras ketiga terbesar di dunia, setelah kurang lebih dua dekade bekerja keras membangun, predikat buruk itu berganti dengan pujian dari masyarakat internasional. Swasembada pangan, khususnya beras, bila mengacu pada pernyataan FAO diatas kini tidak ada lagi. Pertanyaan kita adalah, mengapa produksi pangan khususnya beras mengalami penurunan? Menurunnya produksi beras Indonesia dijelaskan dengan menengok dua faktor berikut. Pertama, adalah perubahan tata guna lahan (Land use). Sebagaimana diketahui, lumbung padi dan pangan nasional yang utama dewasa ini adalah pulau Jawa, Bali dan Lombok. Dinamika pembangunan yang luar biasa pesat di pulau berpenduduk terpadat asia tenggara ini, tampaknya berdampak pada penyusutan lahan pertanian. Data statistik membuktikan, setiap tahun pulau Jawa kehilangan kurang lebih seratus ribu hektar lahan sawah. Kawasan pertanian ini berganti fungsi menjadi permukiman baru (real-estate), komplek industri, jalan raya, perkantoran dan sebagainya. Sedangkan alasan kedua, dari menurunnya produksi beras bertalian dengan keengganan petani di beberapa kawasan Indonesia untuk menanam padi. Harga gabah yang relatif rendah dan kurang stabil mendorong petani untuk mengalihfungsikan penggunaan lahan sawah pada perkebunan kelapa dan sayuran. Berkebun kelapa tidak memerlukan pupuk khusus dan perawatan yang rumit. Akan tetapi petani dapat panen setiap bulan. Harga kelapa bahan kopra pun cenderung naik dari waktu ke waktu. Demikian pula dalam memproduksi sayuran, petani relatif dapat memetik keuntungan lebih dibanding bertanam padi. Sampai titik ini, jelaslah pembukaan lahan gambut satu hektar diharapkan dapat menjadi alternatif pengadaan pangan khususnya beras di masa datang. Oleh karena itu, kita seyogyanya cermat dan komprehensif dalam rencana dan realisasi megaproyek ini. Salah satunya adalah aspek sumber daya manusia dan kehidupan sosialnya. Jika aspek sosial seperti pengembangan masyarakat tidak diperhatikan secara serius (sentral), bukan mustahil proyek ini gagal total. Secara umum pengamat melihat beberapa titik lemah dari megaproyek ini. Pertama proyek tidak produktif karena alasan ekologis. Misalnya gagalnya panen akibat hama. Kedua, panen mengalami penurunan terus menerus karena faktor kesuburan tanah berkurang. Ketiga, petani memilih untuk berimigrasi ke kota. Konsentrasi penduduk kirakira satu juta orang mendukung untuk munculnya suatu kota baru dengan struktur okupasi dan kesempatan ekonomi lebih menarik bagi petani. Keempat, produksi panan terganggu akibat hubungan antar kelompok etnik kurang baik. Dan sebagainya. Kendala-kendala di atas penyelesaiannya bersifat sosial. Bertani adalah salah satu bentuk tindakan sosial. Dan ia dikonstruksi secara sosial. Mereka melakukan aktifitas tani tidak secara soliter, akan tetapi tergantung pada keberadaan jaringan sosial, organisasi sosial dan lembaga-lembaga sosial setempat. Dengan demikian, mengatasi keberlangsungan megaproyek di atas harus mulai dari penataan aspek kehidupan sosialnya. ”Community development” Pertanian di lahan gambut merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Pertanian lahan gambut dilakukan transmigran di Sumatera, penduduk setempat di Kalimantan Barat dan Tengah dan sebagainya. Menurut sementara orang, secar sosial budaya, sistem produksi pangan di atas tanah bergambut ini ”tidak ada masalah”. Pemikiran semacam ini tidak tepat dan menyesatkan. Saat ini skala proyek pengembangan lahan gambut sudah relatif besar (satu juta hektar). Namun, pengalaman pemerintah maupun masyarakat mengenai hal ini masih terbatas pada lahan gambut yang relatif skalanya kecil. Kompleksitas megaproyek satu juta hektar lahan gambut ini begitu tinggi dan belum pernah dihadapi sebelumnya oleh masyarakat kita. Sementara itu, meskipun dinyatakan lebih dari 50 persen calon petani adalah perambah hutan dan penduduk di Kalimantan Tengah. Namun diduga jumlah transmigran asal pulau padaat penduduk seperti Jawa, Bali dan Lombok akan menjadi dominan. Hal ini bertalian dengan upaya pemerataan penduduk melalui transmigrasi yang menjadi salah satu perhatian pokok dari pembangunan nasional. Alasan lain adalah karakteristik lahan gambut bervariasi. Sehingga produktifitas ekonomi tampaknya harus ditunjang oleh keberadaan sistem dan kelembagaan sosial komunitas tani yang kontekstual untuk masing-masing karakteristik di atas. Terdapat lahan gambut yang subur, akan tetapi terdapat pula yang sebaliknya. Menghadapi situasi seperti ini, petani tidak mungkin bertahan dan sukses tanpa kerjasama dengan yang lain dalam kerangka organisasi sosial setempat yang mengakar kontekstual. Terakhir, jumlah petani yang akan dilibatkan relatif besar yaitu 300 ribu keluarga. Secara teoritis, megaproyek ini akan menciptakan aglomerasi penduduk sebanyak satu juta jiwa. Sebagai akibatnya, tidak dapat dihindari akan lahir pusat-pusat pertumbuhan yang akan berkembang menjadi kota. Kota ”gambut” ini harus mulai diantisipasi agar menjadi titik pusat yang secara sosiologis menunjang pengembangan pertanian gambut berkelanjutan. Keberadaan kota yang tidak terkendali dalam beberapa tinngkatan dapat menggagalkan megaproyek yang dimaksudkan sebagai lumbung padi dan pangan. Migrasi petani dan pergeseran struktur okupasi dapat turut mengalihkan proyek pada arah yang tidak dikehendaki. Paparan di atas menunjukan tingginya proses kompleksitas permasalahan sosial pengembangan lahan gambut satu juta hektar. Tampaknya, salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menata kehidupan sosial lahan gambut adalah penerapan pendekatan community development. Pendekatan ini menitikberatkan pembangunan pada aspek partisipasi masyarakat (citizen participation). Dipahami kini, pembangunan merupakan urusan bersama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tampaknya sektor masyarakat relatif belum berkiprah sejauh kedua sektor lainnya. Masyarakat mempunyai potensi untuk membangun lingkungan mereka sehingga dapat mengatasi masalah mereka tanpa tergantung pada pemerintahan. Pemberdayaan semacam ini dapat dilakukan dengan perorganisasian masyarakat. Penataan kehidupan sosial di lahan gambut satu juta hektar dilakukan pertamatama dengan mempersiapkan calon petani dan petani dalam wawasan, ketrampilan sosial, bahkan sistem nilainya. Mereka perlu mengikuti program pendidikan dan latihan masyarakat. Pada program ini diajarkan mengenai masalah pangan dan lahan gambut, prinsip dasar dan manfaat pengembangan komunitas, aspek-aspek teknis yang bertalian denga lahan ini, dan sebagainya. Setelah mereka bermukim di lokasi, perlu diturunkan para penggerak masyarakat terlatih sebagai fasilitator. Penggerak masyarakat merangsang petani gambut berorganisasi. Misalnya dalam suatu sistem organisasi dan kelembagaan sosial tertentu mereka melakukan pemupukan lahan, pengaturan air, mengatasi hama, pemanenan hasil tanaman, serta penanganan tanah pasca panen. Pembekalan ketrampilan sosial lain juga penting. Misalnya teknik pengelolaan konflik, menggalang dana setempat, berkoperasi, melakukan usaha bersama dan sebagainya. Warga masyarakat yang mampu mengatasi masalah dengan cara di atas, pada dasarnya mempunyai landasan komunitas yang kukuh. Mereka diharapkan menjadi warga komunitas yang secara internalized menganut nilai dan perilaku rukun, peduli, mandiri dan maju / sejahtera. Semoga. * Gumilar R Sumantri, doktor sosiologi Universitas Bilefeld, Jerman (1995), dosen FISIP Universitas Indonesia; tinggal di Bogor, Jawa Barat.