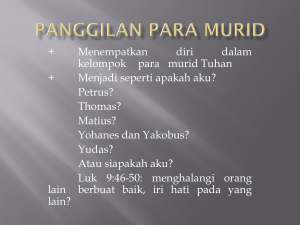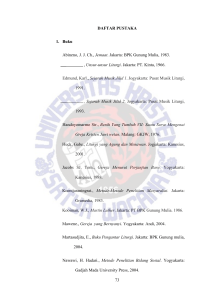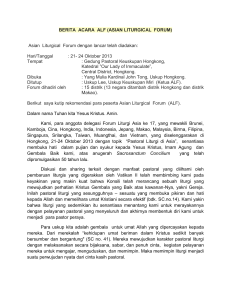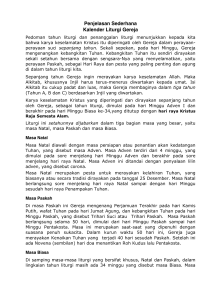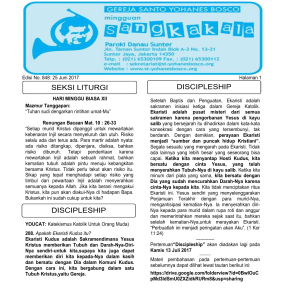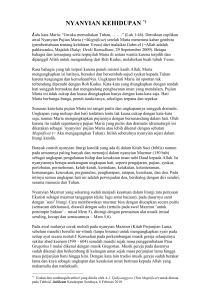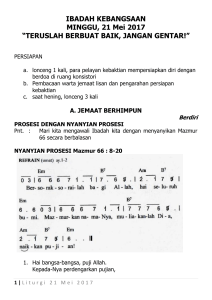Judul Buku : Catholicism at the Crossroads. How
advertisement

RESENSI BUKU Judul Buku Pengarang Penerbit Halaman : : : : Catholicism at the Crossroads. How the Laity can save the Church Paul Lakeland Continuum, London-New York, 2007 164 hlm. Pada tahun 1950an Yves Congar menerbitkan buku besar yang boleh disebut “teologi awam” pertama dengan judul Lay People in the Church atau “Kaum Awam Dalam Gereja”. Pemikiran Congar dalam buku ini sangat membantu refleksi para bapa Konsili Vatikan II untuk menemukan kembali identitas Gereja sebagai komunitas Injili. Gereja bukanlah semata-mata sebuah organisasi hirarkis-piramidal, dibebani oleh klerikalisme yang gaungnya tetap ada misalnya dalam pastorsentrisme. Gereja adalah umat Allah yang disatukan secara mendasar dalam sakramen pembaptisan dalam Kristus, Sang Pewarta kabar Gembira dari Allah. Dalam arus usaha “kembali kepada Injil” yang kentara sekali dalam Gereja Vatikan II inilah, Paul Lakeland menuliskan gagas an-gagasannya tentang “teologi awam”. Perbedaannya terletak pada titik berangkatnya. Sementara Congar mengkritisi ekklesiologi pra-Vatikan II, Lakeland berangkat dari pengamatan dan telaah terhadap Gereja pascaVatikan II yang dipandangnya condong meragukan Insight konsili Vatikan II. Ditambah lagi peristiwa gerejani akhir-akhir ini, seperti pencabutan ekskomunikasi 4 uskup yang ditahbiskan oleh uskup agung Levebvre tahun 1988,mengindikasikan semakin kembalinya praktek-praktek dan cara pikir praVatikan II dan soal “pembatasan legal/teologis” peranan kaum awam dalam hidup dan perutusan Gereja di tengah dunia. Lakeland menerbitkan Catholicism at the Crossroads dengan maksud utama menyapa pembaca lebih luas yang belum banyak mendapatkan training dalam bidang teologi. Buku kecil ini tidak dapat dipisahkan dari bukunya yang lebih besar tentang teologi awam, yaitu yang berjudul The Liberation of the Laity (2003). Sebagai catatan buku dari tahun 2003 inilah yang membuat Lakeland dikenal sebagai pencetus terpenting tentang teologi awam sesudah Yves Congar tersebut atau John Henry Newman. Buku ini kemudian mendapatkan penghargaan dari Catholic Press Association’s 2005 Award sebagai pemenang pertama. Buku-buku Lakeland ini memuat usulan konstruktif tentang sebuah ekklesiologi yang lebih serius berdialog dengan sekularitas yang menjadi konteks hidup nyata kaum awam katolik dan perjuangannya mengemban misi Gereja berhadapan dengan kapitalisme global. Jelas baginya bahwa dalam konteks yang tidak bisa ditarik kembali inilah, kaum awam termasuk kaum perempuan dan keluarga-keluarga akan menjadi ujung tombak bagi misi Gereja. Yang dikritiknya adalah model Resensi Buku — 97 “karier-karier” dalam Gereja sebagaimana dalam klerikalisme yang beruratberakat dalam Gereja Katolik. Lakeland ingin menggerakkan orang-orang Katolik dewasa demi terbangunnya Gereja yang dewasa. Komunitas Yesus (Gereja) bukan sekedar soal keanggotaan, melainkan cara berelasi dan cara bertindak orang kristiani yang semakin didasarkan pada Injil. Akuntabilitasnya perlu juga diuji dengan prinsip organisasi kemasyarakatan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya semacam “demokrasi” yang dialami umat kristiani di Amerika Serikat, negara asal pengarang. Pengandaiannya bahwa tradisi bukanlah “harga mati”, melainkan senantiasa perlu diterangi dan ditransformasikan oleh Injil. Lembaga gerejani perlu senantiasa diuji baik berkaitan dengan dasar teologisnya dan berkaitan dengan mekanisme kelembagaannya misalnya dengan fungsi kelembagaan “sekular” sejauh didasarkan pertanggungjawaban rasional dan Injili; bahwa struktur kepemimpinan gerejani yang biasanya dilegitimasikan secara teologis perlu terbuka pada perkembangan teologi dan kesadaran manusia yang terbuka pada wahyu Allah di setiap zaman; bahwa semangat pembaruan konsili Vatikan II perlu diperjuangkan terus menerus dalam terang pergulatan jemaat perdana untuk setia pada visi (komunitas) Yesus berhadapan dengan aneka kemapanan tradisional seperti Yudaisme ketat, ritualisme atau logika keagamaan yang menindas dari zaman ke zaman; bahwa dalam Gereja katolik, gereja sebagai umat Allah perlu lebih diwujudnyatakan khususnya oleh kaum awam yang mayoritas hidup dalam suasana Gereja yang tetap klerikal, pastorsentris dan condong bias secara teologis. Maka Lakeland mulai dengan bab tentang doa, pertimbangan rohani secara dewasa (discernment) dan hal-hal yang berseberangan. Bab 1 ini diawali dengan penjelasan situasi, orientasi teologis dan tujuan penulisan buku kecil ini. Adakah perbedaan antara cara pandang seorang katolik dewasa terhadap tanggungjawab sekularnya dengan tanggungjawabnya dalam hidup menggereja? Bagaimana mengupayakan agar semua orang katolik, yang konservatif dan yang liberal, bergandeng tangan dalam pembangunan Gereja yang lebih baik dan lebih dewasa? Manakah peran penting forum menguji pandangan dan pendapat serta forum doa tulus demi persatuan Gereja? Bab 2 menjelaskan tentang peran kaum awam: siapakah dan dimanakah mereka, peran dan pergulatannya? Bagaimana kita kembali kepada Gereja atas dasar pembaptisan (bukan tahbisan) dan bersama berbagi tanggungjawab mengemban misi gereja yang bersifat imami? Mungkinkah kita mengatasi istilah “imam”atau “awam” dan mulai saja bicara soal aneka pelayanan yang berbeda dan berpikir dalam kesatuan bahwa komunitas mengemban misi Yesus atau pelayanan Injili? Bab 3 dan bab 4 membicarakan soal pentingnya pertanggungjawaban yang transparan (akuntabilitas) sebagai pengandaian dasar setiap kelompok, organisasi atau lembaga di zaman ini. Adakah dinamika dalam Gereja yang melemahkan 98 — ORIENTASI BARU, VOL. 18, NO. 1, APRIL 2009 atau menghalangi pertanggungjawaban transparan dan dewasa? Apakah dinamika paroki atau keuskupan hanya terus mengikuti metafora “orangtuaanak”? Apakah para klerus memahami tugasnya sebagai tanggungjawab orangtua terhadap anak-anaknya, yaitu umat? Sebaliknya apakah maum awan memang lebih senang diperlakukan sebagai anak-anak? Dalam hal ini, teologi Allah Tritunggal mengajarkan apa? Struktur Gereja macam apakah yang akan memungkinkan kaum awam berpartisipasi berdasarkan “prinsip konsensus” sebagaimana dijelaskan Yves Congar? Bab 5 mendiskusikan kasus-kasus yang memukul Gereja saat ini, khususnya soal pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam Gereja katolik. Pemahaman masalah pelecehan seksual dan tali temalinya, penanganan dan antisipasinya menunjukkan adanya sesuatu yang “tidak jalan” dengan Gereja (klerikal) seperti sekarang ini. Bagaimana kita memahami hubungan Yesus dan Gereja? Apakah kita sungguh belajar dari sejarah dan teologi secara serius? Gereja terkenal sebagai pembela kebebasan manusia; tetapi bagaimana tempat kebebasan sendiri dalam Gereja? Bab 6 dan bab 7 merupakan upaya menggagas lebih jauh tentang Gereja yang lebih dewasa dan terbuka, dilengkapi dengan penjelasan 10 langkah untuk merealisasikannya. Ciri-ciri Gereja-umat Allah yang dewasa adalah berpengetahuan (tidak masa bodoh), inklusif dan melihat ke depan, berorientasi pada pelayanan (bukan karier). Oleh karena itu pula penting mengenal realitas dunia saat ini sampai kepada wajah kemiskinan yang semakin buruk, sikap dewasa dari semua pihak dan mengaktifkan peran deliberatif-konsultatif kaum awam dalam hidup gereja, perlunya belajar sejarah tradisi katolik dengan serius, memahami sakramen baptis sebagai dasar semua pelayanan gerejani, menseriusi implikasi perayaan ekaristi dalam hidup dan struktur Gereja, menyadari sumber pengetahuan dan pembaruan yang ada di dunia perguruan tinggi dan kolese katolik lain yang membantu gereja untuk berpikir, serta pentingnya peran dan sumbangan kaum perempuan bagi pembangunan dunia yang bermasa depan. Maka bab 8 mengkhususkan pembahasan tentang kaum awam, kepemimpinan keuskupan dan perutusan Gereja di dunia masa kini. Buku ini ditutup dengan sharing pengalaman dan pencerahan menjadi orang katolik di Amerika Serikat dengan identitas dan dinamika negaranya yang khas di dunia sekarang, termasuk sikap dan pertimbangan orang katolik di tengah kebudayaan Amerika Serikat yang dominan serta menimbulkan aneka reaksi dan perasaan dari yang pro sampai yang kontra. Lakeland menyatakan bahwa: “Para ahli tentang Gereja pada umumnya setuju bahwa 500 tahun pertama dalam sejarahnya, Gereja lebih terbuka terhadap aneka macam partisipasi. Sebagian besar atau bisa dikatakan semua dari mereka setuju bahwa ketika gereja semakin memisahkan awam dari klerus, Gereja kehilangan lebih banyak daripada memperoleh sesuatu darinya. Kesepahaman para ahli demikian ini semakin jelas menunjukkan pentingnya reformasi Gereja…” (hlm. 10). (Hartono Budi) Resensi Buku — 99 Judul Buku Pengarang Penerbit Halaman : : : : The Oxford History of Christian Worship G. Wainwright dan K.B.W. Tucker (editor) Oxford University Press, New York, 2006 xx + 916 Kita mengenal banyak buku mengenai sejarah liturgi dan ibadat Gereja. Tetapi kiranya tidak terlalu banyak literatur yang tersedia, yang memuat sejarah liturgi dan ibadat Gereja dalam satu “compendium” yang berisi tulisan tentang sejarah liturgi dari berbagai komunitas Gereja sekaligus. Dari yang tidak banyak itu, terbit buku The Oxford History of Christian Worship yang sungguh memberikan sumbangan yang tinggi terhadap informasi mengenai sejarah peribadatan Gereja lintas waktu, lintas tempat dan lintas kepercayaan. Buku setebal 916 halaman ini diedit oleh ahli teologi dan liturgi yang tersohor, yakni Geoffrey Wainwright, seorang teolog liturgis dari Gereja Metodis di Inggris, dan Karen BN. Westerfield Tucker, seorang Profesor Ibadat di Universitas Boston dan ketua Dewan Redaksi jurnal ilmiah Studia Liturgica. Buku ini berupa bunga rampai tulisan begitu banyak ahli teologi dan liturgi di seluruh dunia. Ada hampir 36 ahli selain kedua editor di atas yang menyumbangkan tulisannya di seputar sejarah liturgi dan ibadat Gereja. Yang sangat menarik ialah para kontributor karangan dalam buku ini mencakup para ahli dari berbagai komunitas Gereja, seperti Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks, Gereja Lutheran, Gereja Baptis, Gereja Menonit, Gereja Metodis, Gereja Presbyteran, Gereja Pentakosta dan denominasi lainnya. Para pengarang juga berasal dari berbagai tempat yang bahkan mencakup ke lima benua sekaligus dan dari berbagai bahasa (seperti Perancis, Jerman, Portugis, Belandan, Swedia dan Korea) yang dalam buku sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Pantaslah kalau kita menyebut buku The Oxford History of Christian Worship ini sebagai sumbangan yang sangat berharga bagi studi sejarah liturgi dan peribadatan pada awal abad ke-21 ini, terutama karena pendekatannya yang lintas batas tempat, waktu, budaya, bahasa dan komunitas Gereja. Buku The Oxford History of Christian Worship terutama mengupas tematema liturgi dan ibadat Gereja sebagaimana dirayakan oleh umat di gereja Katedral atau paroki, termasuk juga di komunitas-komunitas biara. Tema-tema liturgi yang dikupas terutama berhubungan dengan perayaan liturgi atau ibadat pada hari Minggu, pesta atau peringatan tertentu, upacara inisiasi, ritus sakramental, upacara perkawinan dan pemakaman, atau doa-doa yangb sudah menjadi tradisi dalam Gereja-Gereja. Menilik karangan-karangan dalam buku ini, tampak bahwa buku ini menggunakan alur gagasan kronologis meskipun perkembangan alurnya tidak selalu lancar menurut urutan kronologis mengingat tema kupasannya mencakup berbagai kelompok Gereja dan daerah. Dengan membaca buku ini kita memang akan memperoleh sebuah panorama 100 — ORIENTASI BARU, VOL. 18, NO. 1, APRIL 2009 cakupan tema sejarah liturgi dan ibadat yang luas, bahkan luas sekali, sekaligus bahasan tema-tema liturgis yang sangat bervariasi. Hal yang pantas dipuji adalah usaha editor untuk memberi kerangka pada seluruh karangan yang aslinya tersebar-sebar dan tidak langsung berhubungan satu sama lain itu. G. Wainwright memberikan landasan awal yang kuat dan mempersatukan: yakni kupasan dasar biblis Ibadat Kristen dan kerangka teologis seluruh ibadat Kristen (hlm. 1-31). Pada akhir atau epilog buku ini (hlm. 858-865), kedua editor yakni G. Wainwrigrht dan Karen B. Westerfield Tucker menyampaikan Retrospect dan Prospect atau tinjauan kembali dan harapan, yang intinya mau memberi sentuhan terakhir sebagai semacam rangkuman umum dan harapan akan perjalanan liturgi dan ibadat di masa depan. Liturgi dan ibadat Kristen berpangkal tolak dari satu iman yang sama yakni kepada Tuhan Yesus Kristus. Perayaan iman pada Kristus yang satu dan sama ini ternyata dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan cara, tradisi dan budaya sepanjang sejarah. Sudah sejak zaman abad-abad pertama kekristenan, muncul berbagai bentuk dan gaya perayaan liturgi dan ibadat di jemaat-jemaat Kristen. Praktek ibadat orang-orang Kristen ternyata tidak seragam, tidak sama saja, melainkan berbeda-beda dengan variasi yang sangat besar antar jemaat yang satu dan jemaat lainnya. Tulisan Hyppolytus (+ th 215) yang berjudul The Apostolic Tradition (Latin: Traditio Apostolica), yang juga dijadikan sebagai judul karangan nomer dua dari buku The Oxford History of Christian Worship ini (hlm.32), aslinya juga sebuah tulisan yang ingin menyampaikan tata liturgi Gereja yang dipandang resmi dan asli berasal dari para Rasul, berhubung adanya kebingungan umat terhadap praktek liturgi dan ibadat yang begitu bervariasi antara tempat satu dan tempat lainnya. Nyatanya, sejarah Gereja terus bergulir dan sejarah juga mencatat bahwa Gereja Kristus terbagi-bagi menjadi begitu banyak Gereja dengan sejarah munculnya yang masing-masing dan tentu juga tata ibadatnya yang masing-masing pula. Ada banyak faktor mengapa Gereja terbagi-bagi begini. Namun tentusaja orientasi buku ini tidak mau mengupas faktor-faktor historis – teologis munculnya Gereja-Gereja ini. Buku ini mau menyajikan sejarah ibadat Gereja-Gereja Kristus yang macammacam itu. Tampak sekali bahwa setiap liturgi atau ibadat Gereja memiliki kekayaan tradisinya masing-masing. Kekayaan liturgi atau ibadat Gereja Katolik Roma, Ortodoks dan Gereja-Gereja Timur lainnya, Gereja-Gereja Protestan dan Reformasi dapat dibaca melalui panorama yang disajikan oleh buku The Oxford History of Christian Worship ini. Salah satu hal yang menarik ialah kupasan usaha inkulturasi yang dilaksanakan di Asia dan Afrika (hlm. 661-677 dan 678-695). Anscar J. Chupungco, seorang ahli liturgi dan inkulturasi dari Filipina, menyampaikan gagasan prinsip-prinsip inkulturasi liturgi dan contoh-contoh usaha inkulturasi di India, Cina dan Filipina. Begitu pula, inkulturasi di Afrika juga merupakan usaha Resensi Buku — 101 yang sangat digiatkan. Nwaka Christ Egbulem menyampaikan tantangantantangan inkulturasi liturgi di Afrika dan memberikan contoh Tata Perayaan Ekaristi Ritus Congo (dahulu: Zaire). Meskipun sebagian besar karangan buku ini berisi deskripsi tata peribadatan macam-macam denominasi Gereja dengan latar belakang historisnya, buku The Oxford History of Christian Worship ini juga menyampaikan tulisan yang sifatnya umum dan terfokus pada topik-topik liturgi seperti perempuan dalam liturgi (hlm. 755-768), musik liturgi (hlm. 769-792), tata ruang (hlm. 793-816), seni dalam liturgi (hl,.817-840), busana dan perlengkapan ibadat (hlm. 841-857). Buku The Oxford History of Christian Worship ini merupakan sebuah buku studi liturgi dan sejarah liturgi yang sangat kaya dan baik. Nyatanya, para ahli meyakini bahwa studi terhadap sejarah liturgi dan peribadatan Gereja praktis sama saja merupakan studi atas sejarah kekristenan itu sendiri. Bagaimanapun juga apa yang diimani tampak dan terungkap dalam apa yang didoakan, lex orandi lex credendi. Buku ini cukup mudah dibaca dan dipelajari, apalagi buku ini dilengkapi oleh banyak gambar dan lukisan, serta bagan/skema peribadatan, sehingga para pembaca akan sangat terbantu memahami topik yang sedang dibaca. Namun harus diakui, sebagai sebuah bunga rampai, buku ini memiliki kelemahan pada kesatuan alur atau plot-nya. Banyaknya pengarang pada buku ini tentu membuat ide gagasan keseluruhan sebagai satu kesatuan dari buku ini tidak sungguh jelas dan tidak padu. Setiap pengarang tentu memiliki cara pandang dan gaya bahasa yang berbeda, sehingga sulit ditemukan satu alur yang terjaga dari awal hingga akhir. Meskipun begitu, buku ini sangat layak untuk dibaca dan dipelajari, khususnya oleh para pemimpin jemaat dan peminat liturgi yang ingin memperdalam ilmu dan wawasannya. (E. Martasudjita). Judul Buku Pengarang Penerbit Tahun Halaman : : : : The Risk of Discipleship, Imamat Bukan Sekadar Selibat Roderick Strange Kanisius 2007 376 Status imamat tidak jarang menimbulkan kebingungan dalam berelasi, baik bagi imamnya sendiri maupun bagi umat khususnya bagi yang perempuan. Mengapa? Jawabannya: karena imam hidup selibat. Hidup tidak menikah – meski bukan inti paling penting – adalah perkara yang menjadi tantangan terberat dalam hidup imamat. Itulah situasinya, setidaknya, menurut penulis buku terjemahan yang aslinya berjudul The Risk of Discipleship: The Catholic Priest Today ini. 102 — ORIENTASI BARU, VOL. 18, NO. 1, APRIL 2009 Zaman sekarang ”selibat memang tidak menjadi semakin mudah, bahkan semakin sulit, tetapi saya semakin memahami makna selibat dengan baik dan semakin dapat menghargainya. Bagi saya, kita perlu meletakkan persoalan selibat pada sudut pandang yang tepat” (hlm. 163). Selibat adalah komitmen, pilihan bebas sekaligus risiko kemuridan. Risiko kemuridan dalam mengikuti Kristus itulah yang menjadi tema utama buku ini. Roderick Strange, sang penulis, adalah seorang imam Keuskupan Shrewbury Inggris yang berpengalaman bertahun-tahun sebagai rektor seminari. Meskipun penulisnya berlatar belakang Eropa (Inggris), buku ini bagus untuk dibaca dalam konteks Indonesia. Buku ini tidak memusatkan perhatian pada masalah-masalah kontraversial seperti skandal seksual imam, perlakuan yang tepat pada para imam yang kedapatan memiliki kecenderungan homoseksual ataupun pro-kontra tahbisan imam perempuan. Berdasar pengalaman pribadi, penulis pertama-tama dan terutama ingin merefleksikan imamat dalam Gereja Katolik terutama aspek teologi dan spiritualitasnya. Bicara tentang imam zaman ini, penulis mengajak pembaca – entah pemuda yang sedang mempertimbangkan panggilan hidupnya, entah kaum awam yang ingin lebih memahami panggilan imamat, ataupun kaum tertahbis yang ingin menegaskan kembali komitmen imamatnya – untuk kembali ke jalan yang benar. Berdasar pengalaman panggilan para murid pertama (Mrk 1:16-20; Yoh 1:37-51), tahbisan mesti dipahami sebagai sebuah jawaban atas panggilan Yesus, Sang Guru. Tahbisan bukanlah inisiatif pribadi melainkan inisiatif Tuhan. ”Bukan kamu yang memilih Aku, melainkan Akulah yang telah memilihmu” (Yoh 15:16). Seorang imam telah dipanggil dan ia telah menjawab panggilan itu. Di saat itulah, di sini dan kini, ia mesti menjalani risiko atas jawaban itu sekaligus membangun komitmen untuk tetap menerima apa pun yang diminta darinya. Hidup imamat, idealnya, ibarat arus di dasar samudera yang semakin dalam ketika ombak di permukaan terpecah menghantam pantai, adalah hidup yang kian mendalam meski dalam ketidakpastian. Bagaimana itu mungkin? Di sinilah penulis, sebelum panjang lebar mengulas sejumlah aspek mendasar hidup imamat, lebih dahulu menampilkan pribadi Yesus dari Nazareth sebagai model hidup imamat. Ia adalah guru, sahabat dan saudara kita yang telah membuka risiko kemuridan dengan menerima wafat di salib karena taat kepada kehendak Allah, Bapa-Nya. Dengan mengenal kembali panggilan dalam terang siapa dan apa yang telah dilakukan Yesus, kita senyatanya semakin terbantu untuk merefleksikan lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan menjadi imam. Sama seperti setiap orang kristiani, oleh rahmat baptisan, seorang imam dipanggil untuk mengikuti Kristus. Namun oleh rahmat tahbisan, secara istimewa, seorang imam dipanggil untuk menyerupai pribadi Yesus. Konkretnya, yakni dengan meneladan sikap Resensi Buku — 103 penerimaan-Nya terhadap orang-orang, cara-Nya menggunakan situasi sebagai kesempatan, kesediaan-Nya menolong orang untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, dan cara-Nya mendorong orang untuk berani bertanggung jawab. Lebih dari itu, sebagaimana Yesus memanggul salib sebagai tanda cinta yang tidak terbatas, demikian jugalah para imam dipanggil untuk ”memilih” memanggul salib. ”Salah satu keutamaan hidup imam adalah sikap tidak mudah mengasihi diri sendiri” (hlm. 361). Dalam rangka menjawab kebingungan relasional berkaitan status imamat, buku ini pertama-tama berusaha menjernihkan perbedaan antara imamat umum yang diterima setiap orang beriman dan imamat jabatan yang diterima kaum tertahbis. Dari situlah, kemudian, buku ini mencoba menampilkan identitas kaum tertahbis dalam komunitas dimana mereka hidup tanpa bermaksud memisahkan mereka dari komunitas. Kaum imam berbeda dari kaum awam, namun kaum imam tidak terpisah dari kaum awam. Mengutip kata-kata Paus Yohanes Paulus II dalam Pastores Dabo Vobis: ”Para imam tidak melayani diri mereka sendiri, tetapi Umat Allah” (PDV 78). Demi pelayanan untuk Umat Allah itulah, dalam bagian-bagian selanjutnya, penulis membahas aspek-aspek pokok dalam hidup imamat, seperti: hidup dalam doa; hasrat untuk terus belajar demi mempertanggungjawabkan harapan yang ada; totalitas dalam pelayanan sabda, merayakan misteri dan memimpin jemaat. Menarik bahwa masing-masing aspek hidup imamat didalami oleh penulis secara serius berdasar Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium sekaligus secara baru, bertolak dari pengalaman 30 tahun lebih sebagai imam. Yang membuat buku ini layak untuk dibaca bahkan pantas menjadi buku wajib di seminari-seminari adalah usulan-usulan konkretnya. Dalam mewartakan Injil Allah sebagai tugas pertama kaum tertahbis, misalnya, penulis membagikan resepnya bagaimana berkotbah dengan baik. Pertama, cobalah berusaha membuat agar kotbah yang disampaikan menarik. Sebagai alat bantunya, cobalah bertanya, ”Apakah saya akan tertarik jika saya menyampaikan kotbah dengan cara demikian?” Kedua, berusahalah untuk berhati-hati dalam menggunakan pilihan-pilihan kata. Konkretnya, jangan mencoba mengatakan segala macam hal pada kesempatan itu juga. Ketiga, aturlah waktu bicara. Sering kali terjadi, kotbah yang baik menjadi kacau ketika pengkotbah berbicara terlalu lama. Keempat, kaitkanlah kotbah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, termasuk kejadian-kejadian sederhana dan tidak terduga yang terjadi saat misa (hlm. 272-279). Jelas, kotbah yang baik adalah kotbah yang sungguh dipersiapkan. Untuk itulah diperlukan pengurbanan. Meski hidup imamat bukan sekadar selibat, bagaimanapun, diakui bahwa salah satu bentuk pengurbanan terbesar seorang imam adalah hidup tidak menikah. Imam juga manusia. Imam juga bisa jatuh cinta. ”Mencintai dengan 104 — ORIENTASI BARU, VOL. 18, NO. 1, APRIL 2009 perasaan mendalam, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perasaan cinta itu, terlebih lagi harus berada dalam jarak yang cukup dengan orang yang Anda cintai merupakan hal yang sangat berat” (hlm. 195). Satu hal lagi yang membuat buku ini berharga adalah spiritualitas imamatnya yang manusiawi, yang bertolak pada pandangan yang sehat tentang seksualitas. Cinta tidak berlawanan dengan selibat. Seperti Yesus yang datang bukan untuk mati tetapi untuk mencinta, kaum tertahbis pun dipanggil untuk mencinta. Berbeda dengan perasaan cinta secara emosional, “cinta membutuhkan sebuah keputusan. Kita mencintai karena kita memutuskan untuk mencintai. ... Cinta yang sejati memperoleh dasarnya pada komitmen seseorang” (hlm. 184). Sambil terus berproses dalam kedewasaan afektif, para imam menemukan dasar yang kuat hidup selibat mereka dalam komitmen yang terus bertahan pada cinta akan Kristus. (Y.B. Prasetyantha) Resensi Buku — 105