- RP2U Unsyiah - Universitas Syiah Kuala
advertisement

PROCEEDING THE 7th ACEH INTERNAL MEDICINE SYMPOSIA (AIMS) Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Indonesia Thursday-Saturday On, July, 29-31 2016 Tema: “The Challenge of The Globalisation Era : How To Prepare Yourself For A Comprehensive Patient Management ” Editor : Abdullah Azzaki Abubakar Masra Lena Siregar Vera Abdullah Desi Salwani Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2016 KATA PENGANTAR KETUA PANITIA ACEH INTERNAL MEDICINE SYMPOSIA (AIMS) Assalamulaikum Wr. Wb dan Salam Sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Panitia Pelaksana mengucapkan selamat datang di Banda Aceh kepada semua Pembicara, Moderator dan Peserta baik Simposium maupun Workshop ACLS-BLS pada acara Aceh Internal Medicine Symposia (AIMS) ke-7 yang merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh kalangan klinisi. Acara ini tentunya menghadirkan pendekatan yang komprehensif dalam manajemen penyakit. Kualitas standar dalam manajemen sebaiknya ditingkatkan sejalan dengan berkembangnya ilmu kedokteran. Menyikapi kondisi ini, kami berupaya menjembatani klinisi untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen pasien. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada : Rektor Universitas Syiah Kuala, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, Kepala Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala atas dukungan yang diberikan, kepada para pembicara dan moderator baik dalam daerah maupun dari luar daerah, para peserta simposium dan workshop serta rekan-rekan farmasi, atas segala partisipasinya sehingga pertemuan ini dapat terselenggara dengan baik. Kepada seluruh panitia, saya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jerih payah yang telah dicurahkan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Harapan kami, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi para klinisi. Ketua Panitia Pelaksana The 7th Aceh Internal Medicine Symposia (AIMS) dr. Abdullah, SpPD-KGH, FINASIM KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Assalamu‘alaikum Wr Wb Puji sukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW Kami ucapkan selamat datang peserta Aceh Internal Medicine Symposia (AIMS) ke-7 tahun 2016, kami bersyukur acara ini dapat berlangsung dan telah menjadi salah satu acara ilmiah tetap di Banda Aceh. Sebagai implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi adalah suatu keniscayaan untuk tetap terus mengikuti dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang ilmu kedokteran. Dalam tiga hari ini peserta akan mengikuti acara AIMS dengan tema “The Challenge of The Globalisation Era : How to Prepare Yourself for a Comprehensive Patient Management”. Semoga acara ini memberi kontribusi bagi peningkatan kompetensi dalam bidang akademik maupun profesi dalam mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Terimakasih dan penghargaan kami kepada Panitia, serta semua pihak yang ikut terlibat dan mengupayakan acara ini dapat terlaksana. Wassalamu‘alaikum Wr Wb Banda Aceh, Juli 2016 Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH, FINASIM KATA PENGANTAR DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL BIDIN BANDA ACEH Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD dr. Zainoel Abidin, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Ketua Panitia serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan acara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh Internal Medicine Symposia (AIMS) ke-7 tahun 2016 merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/ RSUD dr. Zainoel Abidin, yang banyak memberikan manfaat dalam aplikasi ilmu terkini terutama kepada dokter dan paramedis khususnya yang mengabdi di seluruh Provinsi Aceh. Kami menyambut baik acara simposium dan workshop ini, sesuai dengan misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai rumah sakit pendidikan, yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, keperawatan dan ilmu kesehatan lainnya serta pengembangan sistem dan prosedur pelayanan kesehatan yang bertaraf Internasional. Akhirnya terlepas dari segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mengharapkan bahwa AIMS ke-7 ini dapat memberikan manfaat dan aplikasi terkini ilmu pengetahuan dokter serta paramedis di Provinsi Aceh yang berjalan secara terintegratif dan berkesinambungan. Banda Aceh, Juli 2016 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin dr. Fahrul Jamal, SpAn, KIC KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA Assalamu‘alaikum Wr Wb Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tuntutan di seluruh dunia dalam kancah persaingan global. Ilmu kedokteran menjadi tonggak terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Informasi dan aplikasi ilmu terbaru sangat diharapkan bagi semua pihak yang berkecimpung di bidang kesehatan. Semua ini sesuai dengan harapan Tri Darma Perguruan Tinggi. Program-program teraplikatif terus kami dukung dan upayakan untuk mengembangkan pusat pendidikan spesifikasi yang berguna dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Diantaranya berupa program pendidikan bagi konsultan (Sp-2) maupun doktoral (S3) tentunya akan banyak menciptakan penelitian yang berguna bagi dunia kedokteran dan kesehatan. Dengan demikian kami akan mempersiapkan rumah sakit pendidikan yang representatif dan penelitian yang terintergrasi di lingkup Universitas Syiah Kuala yang dapat merekrut dan menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Pada kesempatan ini, saya menyambut baik dan selamat kepada panitia Aceh Internal Medicine Symposium (AIMS) ke-7 yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga menjadi kegiatan yang konsumptif bagi praktisi kesehatan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Selamat dan semoga sukses. Wassalamu‘alaikum Wr Wb Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng SUSUNAN PANITIA THE 7th ACEH INTERNAL MEDICINE SYMPOSIA (AIMS) Penasehat : Rektor Universitas Syiah Kuala Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin Ketua PAPDI Provinsi Aceh Ketua IDI Wilayah Provinsi Aceh Penanggung Jawab : Kepala Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD dr. Zainoel Abidin Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Seksi Ilmiah Koordinator Anggota : dr. Abdullah, SpPD-KGH, FINASIM : dr. Azzaki Abubakar, SpPD-KGEH : dr. Masra Lena Siregar, SpPD : dr. Vera Abdullah, SpPD : dr. Eva Musdalita, SpPD : dr. Kurnia Fitri Jamil, MKes,SpPD – KPTI, FINASIM : dr. Desi Salwani, SpPD dr. Siti Adewiah dr. Febri Andini dr. Ricky Virnardo dr. Radit Nauval dr. Munawar Anwar Fuadi Seksi Dana dan Stand Pameran Koordinator : dr. Krishna W Sucipto,SpPD –KEMD, FINASIM Anggota : dr. Fauzi Yusuf, SpPD – KGEH, FINASIM Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD – KGH, FINASIM dr. Syamsu Umar, SpPD, FINASIM dr. Chacha Marissa Isfandiari, SpPD dr. Nazaruddin dr. Derina Dewi Seksi Akomodasi dan Transportasi/ Wisata Koordinator : dr. Hendra Zufry, SpPD-KEMD, FINASIM Anggota : dr. Muhammad Riswan, SpPD-KHOM, FINASIM dr. Hendra Wahyudi dr. Teuku Muhammad Reza Tandi dr. Fardiansyah dr. Muhammad Reza Haris Seksi Tempat dan perlengkapan Koordinator : dr. Ivan Ramayana, M. Ked (PD), SpPD Anggota : dr. Tambunta Tarigan dr. Ridhalul Ikhsan dr. Teuku Emier Bravo dr. Afrizal Seksi Publikasi dan Dokumentasi Koordinator : dr. M. Darma Muda Setia, SpPD Anggota : dr. Islamuddin, SpPD dr. Sylva Nazli dr. Muhammad Indra dr. Ade Baswin Seksi Acara Koordinator Anggota : dr. Azhari Gani, SpPD-KKV, FCIC, FINASIM : dr. Muhammad Diah, SpPD – KKV, FINASIM dr. Agustia Sukri Ekadamayanti, SpPD dr. Imelda dr. Muhammhad Irfan dr. Suheir Muzakkir dr. Intan Juwita Seksi Keamanan Koordinator : dr. M. Fuad, SpPD Anggota : dr. Teuku Mamfaluti, MKes, SpPD dr. Abdul Aziz Mubarak dr. Arie Setyawan Seksi Konsumsi Koordinator : dr. Mahriani Sylvawani, SpPD Anggota : dr. Meta Maulinda dr. Indah Fajarini dr. Cut Herlinda TA dr. Zurriaty Savitri Sekretariat Koordinator Anggota : dr. Price Maya, SpPD : dr. Andrie Gunawan dr. Nasriah dr. Cut Henna Hikmah Saputra Hasdiana Safrida Muzakkir Rita Maulina Mursalina Hendra Marlinta Ferdian Fuad Bakhruddin Ummi Nadrah DAFTAR KONTRIBUTOR Abdullah Divisi Ginjal dan Hipertensi, Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Asrul Harsal Divisi Hematologi-Onkologi Medik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia / RS Kanker Dharmais Jakarta Azhari Gani Divisi Kardiologi, Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Azzaki Abubakar Divisi Gastroentero dan Hepatologi, Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Desi Salwani Divisi Ginjal dan Hipertensi, Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Fauzi Yusuf Divisi Gastroentero dan Hepatologi, Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Hendra Zufry Divisi Endokrinologi, Metabolik dan Diabetes - Pusat Pelayanan Tiroid Terpadu Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Islamuddin Divisi Pulmonologi dan Penyakit Kritis Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Krishna W. Sucipto Divisi Endokrinologi, Metabolik dan Diabetes- Pusat Pelayanan Tiroid Terpadu Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Mahriani Sylvawani Divisi Rheumatologi Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Masra Lena Siregar Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Maimun Syukri Divisi Ginjal dan Hipertensi Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. M. Darma Muda Setia Divisi Geriatri Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. M. Diah Divisi Kardiologi, Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Vera Abdullah Divisi Psikosomatis Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh T. Mamfaluti Divisi Alergi-Imunologi Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Yensuari Bagian Penyakit Dalam BLUD RSUD dr. Yuliddin Away Tapaktuan Aceh Selatan. DAFTAR ISI Sambutan Ketua Panitia Pelaksana Aceh Internal Medicine Symposia (AIMS) ke-7 .......................................................................................... iii Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ........... iv Sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh ............................................................................................... v Sambutan Rektor Universitas Syiah Kuala .............................................. vi Susunan Panitia Aceh Internal Medicine Symposia (AIMS) ke-7 .......... vii Daftar Kontributor ....................................................................................... Daftar Isi ...................................................................................................... SIMPOSIUM PENDEKATAN DIAGNOSIS SINDROMA KORONER AKUT Azhari Gani ............................................................................................... ROLE OF ANTICOAGULANT IN ACUTE CORONARY SYNDROME M Diah ....................................................................................................... STEROID : USE AND ABUSE Hendra Zufry ............................................................................................... APPLICATIONS OF STEROID IN INTERNAL MEDICINE CASES Krishna W Sucipto ...................................................................................... MANAGEMENT NUTRITION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE Maimun Syukri ............................................................................................ KETO ACID IN CHRONIC KIDNEY DISEASE Abdullah ...................................................................................................... TATALAKSANA SEPSIS PADA USIA LANJUT Masra Lena Siregar...................................................................................... ULKUS DEKUBITUS PADA USIA LANJUT FOKUS PADA PENCEGAHAN DAN TATALAKSANA M.Darma Muda Setia .................................................................................. DIAGNOSIS DAN PENANGANAN YANG CEPAT LUPUS ERYTEMATOSUS SISTEMIK Mahriani Sylvawani .................................................................................... DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF HYPERSENSITIVITY REACTION T. Mamfaluti................................................................................................ RESUSITASI CAIRAN PADA WANITA HAMIL Masra Lena Siregar ..................................................................................... HEPATITIS B PADA KEHAMILAN Azzaki Abubakar ......................................................................................... DEPRESSION IN PREGNANCY Vera Abdullah ............................................................................................. INISIASI INSULIN PADA PASIEN DM TIPE 2 Hendra Zufry ............................................................................................... WHY, WHEN AND HOW TO ADD PRANDIAL INSULIN AFTER BASAL OPTIMIZATION (FOCUS ON BASAL PLUS) Krishna W Sucipto ...................................................................................... TEHNIK INJEKSI INSULIN Yensuari ...................................................................................................... PPOK: DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA Islamuddin ................................................................................................... GANGGUAN KESEIMBANGAN ELEKTROLIT Desi Salwani ............................................................................................... DIAGNOSIS DAN PENATALAKSANAAN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE Azzaki Abubakar ......................................................................................... DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING Fauzi Yusuf ................................................................................................. APPROPRIATE PAIN MANAGEMENT Asrul Harsal................................................................................................. UPDATE MANAGEMENT OF CANCER PAIN Asrul Harsal ................................................................................................. WORKSHOP DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA TERKINI NODUL TIROID Hendra Zufry ............................................................................................... PENDEKATAN DIAGNOSIT KRISIS HIPERTENSI Abdullah ...................................................................................................... MAKALAH BEBAS PROBLEM DIAGNOSTIK ASITES PADA CA COLON Arie Setyawan, Azzaki Abubakar, Fauzi yusuf ........................................... KISTA DUKTUS KOLEDOKUS PADA DEWASA MUDA Chairunnisa, M. Fuad .................................................................................. FIBROSARKOMA GINJAL PADA WANITA DEWASA Cut Henna Mariza, M.Fuad, M. Riswan...................................................... PLEBOTOMI SEBAGAI TERAPI PILIHAN PADA POLISITEMIA VERA Cut Herlinda TA, M.Fuad, M.Riswan ......................................................... A CASE OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN PREGNANT WOMAN 34 WEEKS GESTATIONAL AGE Imam Zahari, Cut Meurah Yeni .................................................................. PERIKARDIOSINTESIS PADA EFUSI PERIKARDIUM MASIF Indah Fajarini, Azhari Gani, M.Diah ........................................................... CEREBRAL SALT WASTING SYNDROME PADA PASIEN TUMOR CEREBELLUM DEXTRA Munawar Anwar Fuadi, Muhammad Fuad, Desi Salwani, Abdullah, Maimun Syukri ............................................................................................ KEHAMILAN DAN LUARAN PASIEN EKLAMSIA GRAVIDARUM DAN DEMAM BERDARAH DENGUE DENGAN MANIFESTASI GANGGUAN JANTUNG Rizka Aditya, Cut Meurah Yeni, Yuyun Lisnawati .................................... HUBUNGAN GAMBARAN ELEKTROKARDIOGRAM DENGAN DERAJAT KEPARAHAN PENDERITA PENYAKT JANTUNG KORONER DI RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH Ruziqni Arihanim P, Muhammad Ridwan, Ratna Idayati, Muhammad Diah Yusuf, Taufik Suryadi .................................................... HUBUNGAN FUNGSI SISTOLIK VENTRIKEL KIRI DENGAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN GAGAL JANTUNG DI RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH 2015 Sarah Fadillah, Muhammad Ridwan, Bakhtiar , Teuku Mamfaluti, Subhan Rio Pamungkas ............................................................................... CARDIOVASCULAR DISEASE IN PREGNANCY: A CASE REPORT Teuku Yudhi Iqbal, Mohd. Andalas ............................................................ Simposium PENDEKATAN DIAGNOSIS SINDROMA KORONER AKUT Azhari Gani Divisi Kardiologi Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Universitas Syiah Kuala, RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Abstrak Sindroma Koroner Akut (SKA) merupakan kejadian iskemik atau infark pada miokard yang biasanya diakibatkan berkurangnya aliran darah di arteri koroner. SKA terbagi menjadi infark miokard akut dengan elevasi segmen ST (ST elevation myocardial infarction / STEMI), infark miokard akut tanpa elevasi segmen ST (non ST elevation myocardial infarction / NSTEMI), dan Angina Pektoris Tidak Stabil (APTS) / Unstable Angina Pectoris (UAP). Kriteria diagnosis yang dipakai dari adanya gejala klinis nyeri dada khas kardiak, adanya perubahan bentuk EKG, perubahan pada biomarker jantung. Keluhan klasik dengan nyeri dada tipikal ditandai dengan perasaan tertekan pada retrosternal dan nafas yang terasa berat yang menjalar ke lengan kiri (jarang pada kedua lengan atau ke lengan kanan), leher dan rahang, dapat bersifat intermiten atau presisten. Berubahnya nilai troponin pada beberapa jam pertama memberikan pengaruh penting dalam diagnosis, dimana nilai prediksi negatif dari troponin mencapai >99%. Diagnosis yang akurat menentukan prognosis yang penting pada kelangsungan hidup pasien. Diagnosa banding baik kardiak maupun nonkardiak harus dipertimbangkan dari awal. Beberapa diagnosa banding juga bersifat gawat darurat. Kata Kunci : Sindrom Koroner Akut, STEMI, NSTEMI, UAP PENDEKATAN DIAGNOSIS SINDROMA KORONER AKUT Azhari Gani Divisi Kardiologi Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Universitas Syiah Kuala, RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh I. Pendahuluan Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan salah satu manifestasi klinis Penyakit Jantung Koroner (PJK) yang utama dan menyebabkan angka perawatan rumah sakit yang sangat besar serta paling sering mengakibatkan kematian. (Amsterdam EA, dkk 2014) Diperkirakan 17,5 juta orang meninggal disebabkan Cardiovascular diseases (CVD) di tahun 2012, yaitu 31% dari semua kematian global. Kematian ini, sekitar 7,4 juta karena penyakit jantung koroner dan 6,7 juta karena stroke. Lebih dari tiga perempat kematian CVD berlangsung di negara berkembang. Dari 16 juta kematian di bawah usia 70 karena penyakit tidak menular, 82% di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dan 37% disebabkan oleh CVD (WHO 2014). Di Indonesia, menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan PJK menempati peringkat ke-3 penyebab kematian setelah stroke dan hipertensi (Riskesdas 2008), bahkan PJK pada orang dewasa masih termasuk dalam 10 besar penyakit tidak menular paling banyak di Indonesia (Riskesdas 2013). SKA adalah suatu istilah atau terminologi yang digunakan untuk menggambarkan spektrum keadaan atau kumpulan proses penyakit yang meliputi angina pektoris tidak stabil/APTS (unstable angina/UA), infark miokard gelombang non-Q atau infark miokard tanpa elevasi segmen ST (Non-ST elevation myocardial infarction/ NSTEMI), dan infark miokard gelombang Q atau infark miokard dengan elevasi segmen ST (ST elevation myocardial infarction/STEMI) (Gambar 1) (Amsterdam EA 2014). APTS dan NSTEMI mempunyai patogenesis dan presentasi klinik yang sama, hanya berbeda dalam derajatnya. Bila ditemui petanda biokimia nekrosis miokard (peningkatan troponin I, troponin T, atau CKMB) maka diagnosis adalah NSTEMI, sedangkan bila petanda biokimia ini tidak meninggi, maka diagnosis adalah APTS. (Amsterdam EA 2014) II. Patogenesis SKA SKA disebabkan oleh obstruksi dan oklusi trombotik pembuluh darah koroner, yang disebabkan oleh plak aterosklerosis yang vulnerable mengalami erosi, fisur, atau ruptur. Penyebab utama SKA yang dipicu oleh erosi, fisur, atau rupturnya plak aterosklerotik adalah karena terdapatnya kondisi plak aterosklerotik yang tidak stabil (vulnerable atherosclerotic plaques) dengan karakteristik; lipid core besar, fibrous cups tipis, dan bahu plak (shoulder region of the plague) penuh dengan aktivitas sel-sel inflamasi seperti sel limfosit T dan sitokin. Tebalnya plak yang dapat dilihat dengan persentase penyempitan pembuluh koroner pada pemeriksaan angiografi koroner tidak berarti apa-apa selama plak tersebut dalam keadaan stabil. Dengan kata lain, risiko terjadinya ruptur pada plak aterosklerosis bukan ditentukan oleh besarnya plak (derajat penyempitan) tetapi oleh kerentanan (vulnerability) plak. Perkembangan terkini menjelaskan dan menetapkan bahwa proses inflamasi memegang peran yang sangat menentukan dalam proses patobiologis SKA, dimana vulnerabilitas plak sangat ditentukan oleh proses inflamasi. Inflamasi dapat bersifat lokal (pada plak itu sendiri) dan dapat bersifat sistemik. Inflamasi juga dapat mengganggu keseimbangan homeostatik. Pada keadaan inflamasi terdapat peninggian konsentrasi fibrinogen dan inhibitor aktivator plasminogen di dalam sirkulasi. Inflamasi juga dapat menyebabkan vasospasme pada pembuluh darah karena tergganggunya aliran darah. Vasokonstriksi pembuluh darah koroner juga ikut berperan pada patogenesis SKA. Vasokonstriksi terjadi sebagai respon terhadap disfungsi endotel ringan dekat lesi atau sebagai respon terhadap disrupsi plak dari lesi itu sendiri. Endotel berfungsi mengatur tonus vaskular dengan mengeluarkan faktor relaksasi yaitu nitrit oksida (NO) yang dikenal sebagai Endothelium Derived Relaxing Factor (EDRF), prostasiklin, dan faktor kontraksi seperti endotelin-1, tromboksan A2, prostaglandin H2. Pada disfungsi endotel, faktor kontraksi lebih dominan dari pada faktor relaksasi. Pada plak yang mengalami disrupsi terjadi platelet dependent vasocontriction yang diperantarai oleh serotonin dan tromboksan A2, dan thrombin dependent vasoconstriction diduga akibat interaksi langsung antara zat tersebut dengan sel otot polos pembuluh darah. Gambar 1. Ilustrasi progresifitas pembentukan plak dan onset NSTEMI, 1) arteri normal, 2) lipid ekstra selular masuk ke subintima, 3) fibrofatty stage, 4) ekspresi prokoagulan dan terbentuknya fribrosis, 5) terlepasnya jaringan fibrosis yang merangsang terbentungya trombogensis sehingga mengkibatkan sindoroma koroner akut, 6) resorpsi trombus diikuti akumulasi kolagen dan pertumbuhan otot polos (dikutip dari Amsterdam EA, dkk. 2014) III. Diagnosis Diagnosa adanya suatu SKA harus ditegakkan secara cepat dan tepat dan didasarkan pada tiga kriteria, yaitu; gejala klinis nyeri dada spesifik, gambaran EKG (elektrokardiogram) dan evaluasi biokimia dari enzim jantung (Roffi 2015) Kriteria European Society of Cardiology (ESC 2015) untuk nyeri angina untuk SKA memiliki kriteria berikut: 1. Nyeri berlangsung > 20 menit, nyeri pada saat istirahat 2. Onset baru (de novo) angina derajat II atau III Canadian Cardivascular Society (CCS) classification 3. Nyeri baru yang lebih berat dari nyeri sebelumnya dan setidaknya CCS derajat III (cresendo angina) 4. Post miokard infark Tabel 1. Kriteria angina pectoris Canadian Cardiovascular Society (Lucien 1976) Derajat Deskripsi Derajat Aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan angina, seperti berjalan, I menaiki tangga. Angina pada aktivitas yang berat, cepat atau berkepanjangan. Derajat Keterbatasan ringan pada aktivitas biasa, berjalan atau menaiki II tangga dengan cepat, mendaki jalan menanjak, berjalan atau menaiki tangga setelah makan, atau dalam cuaca dingin, atau dalam kondisi stres, atau selama beberapa jam setelah bangun. Berjalan lebih dari 2 blok pada jalanan datar. Derajat Keterbatasan aktivitas fisik nyata. Berjalan satu atau dua blok pada III permukaan rata atau menaiki tangga pada keadaan dan kecepatan normal Derajat Ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas fisik secara nyaman, IV sindroma angina muncul pada istirahat 1. Riwayat / Anamnesis Gejala utama yang menandakan suatu SKA adalah nyeri dada tipikal (angina). Sifat nyeri dada yang spesifik angina sebagai berikut (Muller 2014) : - Pasien dengan nyeri dada akut (>20 menit), dapat bersifat intermiten atau presisten. - Lokasi : substermal, retrostermal, dan prekordial - Sifat nyeri : rasa sakit, seperti ditekan, rasa terbakar, ditindih benda berat, seperti ditusuk, rasa diperas, dan dipelintir. - Penjalaran ke : leher, lengan kiri, mandibula, gigi, punggung/interskapula, dan dapat juga ke lengan kanan. - Nyeri membaik atau hilang dengan istirahat atau obat nitrat - Faktor pencetus : latihan fisik, stress emosi, udara dingin, dan sesudah makan - Gejala yang menyertai : mual, muntah, nyeri perut, sulit bernafas, keringat dingin, lemas, dan sinkop. 2. Pemeriksaan Fisik Tujuan dari pemeriksaan fisik adalah untuk mengidentifikasi faktor pencetus dan kondisi lain sebagai konsekuensi dari APTS/NSTEMI. Hipertensi tak terkontrol, anemia, tirotoksikosis, stenosis aorta berat, kardiomiopati hipertropik dan kondisi lain, seperti penyakit paru. Keadaan disfungsi ventrikel kiri (hipotensi, ronki dan gallop S3) menunjukkan prognosis yang buruk (Haff 2012). 3. Elektrokardiografi EKG memberi bantuan untuk diagnosis dan prognosis. Rekaman yang dilakukan saat sedang nyeri dada sangat bermanfaat. Gambaran diagnosis dari EKG adalah : 3.1. Gambaran EKG pada STEMI Gambaran yang khas adalah elevasi segmen ST dari J point setidaknya pada 2 sadapan sebesar 2 mm (0,2 mV) pada lakilaki atau 1,5mm (1,5 mV) pada wanita pada sadapan V2-V3 dan/atau lebih dari 1mm (0,1 mv) pada sadapan dada lain atau pada sadapan ekstremitas. Kebanyakan pasien akan mengalami evolusi EKG menjadi gelombang Q (Gambar 2). Blok cabang kiri baru dapat dipertimbangkan sebagai STEMI (O‘Gara 2013). Selama terjadi STEMI, dapat diamati karakteristik perubahan morfologi EKG yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu, di antaranya adalah: a. Gelombang T hiperakut Pada periode awal terjadinya STEMI, bisa didapatkan adanya gelombang T prominen. Gelombang T prominen itu disebut gelombang T hiperakut, yaitu gelombang T yang tingginya lebih dari 6 mm pada sadapan ekstremitas dan lebih dari 10 mm pada sadapan prekordial. Gelombang T hiperakut ini merupakan tanda sugestif untuk STEMI dan terjadi dalam 30 menit setelah onset gejala. Namun, gelombang T prominen ini tidak selalu spesifik untuk iskemia (O‘Gara 2013). b. Gambaran awal elevasi segmen ST Jika oklusi terjadi dalam waktu lama dan derajatnya signifikan (menyumbat 90% lumen arteri koroner), gelombang T prominen akan diikuti dengan deviasi segmen ST. Elevasi segmen ST menggambarkan adanya daerah miokardium yang berisiko mengalami kerusakan ireversibel menuju kematian sel (dapat diukur berdasarkan peningkatan kadar troponin) dan lokasinya melibatkan lapisan epikardial. Diagnosis STEMI ditegakkan jika didapatkan elevasi segmen ST minimal 0,1 mV (1 mm) pada sadapan ekstremitas dan lebih dari 0,2 mV (2 mm) pada sadapan prekordial di dua atau lebih sadapan yang bersesuaian. Elevasi segmen ST merupakan gambaran khas infark miokardium akut transmural, tetapi bisa ditemukan pula pada kelainan lain. Pada kebanyakan kasus, untuk membedakan STEMI dari kelainan lain biasanya tidak sulit, cukup dengan memperhatikan gambaran klinisnya (O‘Gara 2013). Gambar 2. Perubahan morfologi segmen ST dan gelombang T pada SKA (O‘Gara 2013) c. Elevasi segmen ST yang khas (berbentuk konveks) Gelombang R mulai menghilang. Pada saat bersamaan, mulai terbentuk gelombang Q patologis. Gelombang Q patologis berhubungan dengan infark transmural yang disertai dengan adanya fibrosis pada seluruh dinding. Pada 75% pasien, elevasi segmen ST yang khas ini terbentuk dalam beberapa jam sampai beberapa hari (O‘Gara 2013). d. Inversi gelombang T Bila berlangsung lama dan tidak dilakukan reperfusi arteri koroner, elevasi segmen ST mulai menghilang kembali ke garis isoelektrik. Bersamaan dengan itu, mulai timbul gambaran inversi gelombang T. Gelombang T dapat kembali normal dalam beberapa hari, minggu, atau bulan (O‘Gara 2013). e. Morfologi segmen ST kembali normal Segmen ST biasanya stabil dalam 12 jam, kemudian mengalami resolusi sempurna setelah 72 jam. Elevasi segmen ST biasanya menghilang sempurna dalam 2 minggu pada 95% kasus infark miokardium inferior dan 40% kasus infark miokardium anterior. Elevasi segmen ST yang menetap setelah 2 minggu berhubungan dengan morbiditas yang lebih tinggi. Jika elevasi segmen ST menetap selama beberapa bulan, perlu dipikirkan kemungkinan adanya aneurisma ventrikel (O‘Gara 2013). 3.2. Gambaran EKG pada angina tidak stabil dan NSTEMI Depresi segmen ST > 0,05 mV dan inversi gelombang T > 0,2 mV yang simetris di sandapan prekordial (Gambar 3). Pada gambaran EKG normal, gelombang T biasanya positif pada sadapan (lead) I, II, dan V3 sampai dengan V6; terbalik pada sadapan aVR; bervariasi pada sadapan III, aVF, aVL, dan V1; jarang didapatkan terbalik pada V2. Perubahan EKG lainnya termasuk bundle branch block (BBB) dan aritmia jantung, terutama Sustained VT. Serial EKG harus dibuat jika ditemukan adanya perubahan segmen ST. Namun EKG yang normal pun tidak menyingkirkan diagnosis APTS/NSTEMI (Roff 2015). Gambar 3. Gelombang T terbalik (inversi) dan Depresi segmen ST (Roffi 2015) 4. Petanda Biokimia Jantung Biomarker dapat dipakai sebagai pelengkap diagnosis selain EKG 12 sadapan, dimana troponin lebih dipilih dalam melakukan diagnosis. High sensitive troponin lebih dipilih, dan disarankan pada semua pasien yang curigai sebagai NSTEMI. Dimana suatu negative troponin memiliki nilai >95% nilai prediksi negatif untuk suatu infark, sedangkan high sensitif troponin memiliki nilai negatif >99%. Petanda biokimia seperti troponin I (TnI) dan troponin T (TnT) mempunyai nilai prognostik yang lebih baik dari pada CKMB. Troponin C, TnI dan TnT berkaitan dengan konstraksi dari sel miokrad. Susunan asam amino dari Troponin C sama dengan sel otot jantung dan rangka, sedangkan pada TnI dan TnT berbeda (Tabel 2). Nilai prognostik dari TnI atau TnT untuk memprediksi risiko kematian, infark miokard dan kebutuhan revaskularisasi dalam 30 hari, adalah sama (Keller 2011) Kadar serum creatinine kinase (CK) dan fraksi MB merupakan indikator penting dari nekrosis miokard. Keterbatasan utama dari kedua petanda tersebut adalah relative rendahnya spesifikasi dan sensitivitas saat awal (<6 jam) setelah onset serangan. Risiko yang lebih buruk pada pasien tanpa elevasi segmen ST lebih besar pada pasien dengan peningkatan nilai CKMB (Bhardwaj 2011). Tabel 2. Rekomendasi AHA dalam mendiagnosis sindroma koroner akut (Amsterdam 2014) Kerena tingginya nilai sensitivitas dan akurasi diagnosis untuk mendeteksi suatu akut koroner, waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi troponin kedua dapat dipersingkat dengan pemakaian high sensitive troponin assay (Gambar 4). ESC merekomendasikan pemakaian algoritme 0h/3h Role Out algoritm (Roffi 21014). Gambar 4. 0h/3h Role Iut algoritm pada pasien NSTEMI menggunakan high sensitive troponin (Roffi 2014) Gambar 5. 0 h/1 h rule-in and rule-out algorithms menggunakan high sensitivity cardiac troponins (hs-cTn) assays pada pasien yang dicurigai (NSTEMI) 0 h and 1 h merujuk pada waktu dilakukan pemerikssan darah. NSTEMI dapat di Role Out jika konsentrasi hs-cTn sangat rendah. Pasien sangat mungkin mengalami NSTEMI jika konsentrasi hs-cTn meningkat sedikit atau konsentasi hs-cTn meningkat dari jam pertama (Roffi 2015) Sebagai alternatif dapat digunakan 0h/1h Role In jika high sensitive toponin assay tersedia (Gambar 5). Algoritme Role In ini memiliki 2 konsep, pertama kemungkinan suatu infark miokard jika diikuti dengan peningkatan nilai high sensitif kardiak troponin. Kedua, hampir dapat dipastikan jika terjadi peningkatan pada satu jam pertama, maka juga akan terjadi peningkatan nilai pada jam ke 3 dan 6 (Roffi 2015). Algoritme Role Out memiliki nilai prediksi negatif sebesar 98% pada beberapa kohort dengan populasi yang cukup besar. Sedangkan algoritme Role In memiliki nilai prediksi positif 75%-80% (Roffi 2015). Pemakaian biomarker jantung sebagai alat diagnosis juga direkomendasikan AHA, dimana pemakaian troponin harus diukur pada jam ke-3 dan jam ke-6 setelah serangan untuk menidentifikasi adanya pola peningkatan atau penurunan. Dimana adanya peningkatan kadar troponin dan perubahan EKG akan dianggap sebagai suatu sindroma koroner akut (Amsterdam 2014). Evaluasi nilai troponin dalam 3 hingga 4 hari dapat digunakan untuk sebagai evaluasi ukuran infark dan nekrosis (Reichlin 2013). 5. Pencitraan Pencitraan dengan X-ray torak diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis nyeri dada yang bersumber dari paru. Adanya pelebaran mediastinum dapat mengidentifikasi adanya diseksi aorta (Steg 2012). Computed tomography scanning dengan kontras intravena dapat membantu menyingkirkan kemungkinan adanya emboli paru (Mockel M 2015). Ekokardiografi transesofageal dapat mengidentifikasi adanya efusi pleura, tanda tamponade, dan dapat mendeteksi adanya abnormalitas pergerakan dinding jantung (Eggers 2012). Cardiac magnetic resonance (CMR) dapat digunakan untuk mendeteksi perfusi danabnormalitas pergerakan dinding jantung. CMR juga dapat mendeteksi adanya jaringan parut (dengan menggunakan kontras gadolinium) dan dapat membedakan dengan infak baru (menggunakan T-2 untuk mendeteksi edema miokard), lebih jauh, CMR dapat digunakan untuk membedakan infark dan miokarditis (Roffi 2015) Pencitraan dengan radionuklir dapat digunakan untuk mendeteksi adanya sindroma koroner akut. Deteksi terhadap adanya defek perfusi pada miokard yang nekrosis dapat membantu diagnosis pada pasien pasien dengan nyeri dada tanpa adanya perubahan EKG atau peningkatan kardiak troponin (Roffi 2015). Gambar 6. Algoritme diganosis sindroma koroner akut bedasarkan American Heart Association (AHA) 2015. IV. Diagnosis Banding Diantara pasien yang masuk unit gawat darurat dengan keluhan nyeri dada, 5-10% adalah STEMI, 15-20% adalah NSTEMI, 10% unstable angina, 15% keadaan jantung yang lain, dan 50% adalah penyakit non-kardiak. Beberapa kondisi kardiak dan non-kardiak dapat menyerupai NSTEMI, kondisi ini harus dianggap sebagai suatu NSTEMI karena dapat bersifat mengancam nyawa termasuk diseksi aorta, emboli pulmonal dan tension pneumothorak. Ekhokardiografi direkomendasikan pada semua pasien dengan hemodinamik tidak stabil yang dicurigai akibat gangguan kardiovaskular (Zahlev 2015). Tabel 3. Diagnosa banding sindroma koroner akut V. Kesimpulan Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan salah satu manifestasi klinis Penyakit Jantung Koroner (PJK) yang utama dan menyebabkan angka perawatan rumah sakit yang sangat besar serta paling sering mengakibatkan kematian. Diagnosa adanya suatu SKA harus ditegakkan secara cepat dan tepat dan didasarkan pada tiga kriteria, yaitu; gejala klinis nyeri dada spesifik, gambaran EKG (elektrokardiogram) dan evaluasi biokimia dari enzim jantung. Suatu negative troponin memiliki nilai >95% nilai prediksi negatif untuk suatu infark, sedangkan high sensitif troponin memiliki nilai negatif >99%. Petanda biokimia seperti troponin I (TnI) dan troponin T (TnT) mempunyai nilai prognostik yang lebih baik dari pada CKMB. Selama STEMI, dapat diamati karakteristik perubahan morfologi EKG yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu. Terdiri dari gelombang hiperakut T, gambaran awal elevasi segmen ST, Elevasi segmen ST yang khas (berbentuk konveks), inversi gelombang T, dan morfologi segmen ST kembali normal. Gambaran EKG pada angina tidak stabil dan NSTEMI didapatkan depresi segmen ST > 0,05 mV dan inversi gelombang T > 0,2 mV yang simetris di sandapan prekordial. Diagnosa banding pasien yang masuk unit gawat darurat dengan keluhan nyeri dada, 5-10% adalah STEMI, 15-20% adalah NSTEMI, 10% unstable angina, 15% keadaan jantung yang lain, dan 50% adalah penyakit non-kardiak. DAFTAR PUSTAKA Amsterdam EA, dkk. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;130:e344-e426. Eggers K, Venge P, Lindahl B. High-sensitive cardiac troponin T outperforms novel diagnostic biomarkers in patients with acute chest pain. Clin Chim Acta. 2012;413:1135-40. Bhardwaj A, dkk. A multicenter comparison of established and emerging cardiac biomarkers for the diagnostic evaluation of chest pain in the emergency department. Am Heart J. 2011;162:276-82. Haff P. Highsensitivity cardiac troponin in the distinction of acute myocardial infarction from acute cardiac noncoronary artery disease. Circulation 2012;126:31–40. Keller T. Serial changes in highly sensitive troponin I assay and early diagnosis of myocardial infarction. JAMA 2011;306:2684–2693. Lucien C. Grading of angina pectoris. Circulation 1976;54:5223. Mockel M. Early discharge using single cardiac troponin and copeptin testing in patients with suspected acute coronary syndrome (ACS): a randomized,controlled clinical process study. Eur Heart J 2015;36:369–376. Muller C. Biomarkers and acute coronary syndromes: an update. Eur Heart J 2014;35:552–556. O'Gara, dkk. 2013 ACCF/AHA STEMI Guideline: Full Text. JACC Vol. 61, No. 4, 2013. O'Gara, dkk. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of STelevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;127. Reichlin T, dkk. Risk stratification in patients with unstable angina using absolute serial changes of 3 high-sensitive troponin assay. Am Heart J 2013;165:371–378, e373. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Des 2008. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Steg, dkk. ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J 2012;33:2569–2619. Roffi M, dkk. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal. August 2015:1-59. WHO. Global status report on noncommunicable diseases 2014. Switzerland: WHO; 2014. Zehlev Z, dkk. Diagnostic accuracy of single baseline measurementof Elecsys troponin T high-sensitive assay for diagnosis of acute myocardial infarction in emergency department: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015;350:h15. ROLE OF ANTICOAGULANT IN ACUTE CORONARY SYNDROME Muhammad Diah Divisi Kardiologi, Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unsyiah/RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh Pendahuluan Acute Coronary Syndrome (ACS) atau sindrom koroner akut disebabkan oleh ketidak stabilan koroner berupa pecahnya plak yang menyebabkan aktivasi platelet, berhentinya aliran darah miokard, dan iskemia koroner, yang mana akan berpotensi menghasilkan nekrosis miokard. ACS terdiri atas unstable angina (tidak ada peningkatan biomarker jantung), Non-ST-Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI), dan ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI). ACS menyebabkan lebih dari 1,4 juta angka rawatan di rumah sakit di Amerika Serikat. Di Indonesia ACS masih dianggap sebagai penyumbang angka kematian tertinggi dengan angka prevalensi 7,2% pada tahun 2007. Survei yang dilakukan Departemen Kesehatan RI menyatakan prevalensi SKA di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Trombosis platelet terkait fibrin pada arteri koroner adalah dasar patologi dari infark miokard, dimana antiplatelet dan antikoagulan merupakan landasan penatalaksanaan ACS, yang dapat mengurangi baik tingkat morbiditas maupun kematian akibat ACS. Terapi medis rutin yang diberikan selama ini adalah obat antiplatelet yang dikombinasikan dengan antikoagulan parenteral seperti heparin atau low molecular weight heparin. Kadang-kadang, pasien dianggap memerlukan terapi tiga antikoagulan yaitu dengan aspirin, clopidogrel, dan warfarin setelah ACS, oleh karena karena kondisi seperti atrial fibrillation (AF), trombosis vena dalam, katup jantung prostetik, atau riwayat emboli paru. Pada gambar 1 dan 2 seperti yang terlihat pada lampiran adalah pedoman dari American College of Cardiology Fondation dan American Heart Association mengenai peranan berbagai macam antikoagulan dalam penanganan ACS. Gambar 1. Algoritma Terapi Antiplatelet dan Antikoagulan dalam Penanganan NSTEMI. Gambar 2. Algoritma Terapi Antiplatelet dan Antikoagulan dalam Penanganan STEMI Antiplatelet Aspirin Aspirin, suatu asetilat enzim cyclooxygenase-1 ireversibel, bekerja dengan menghalangi pembentukan intraplatelet tromboksan A2 (Gambar 3), aggregator platelet yang ampuh dan vasokonstriktor endotel. Uji klinis besar telah menegaskan bahwa aspirin dapat mengurangi nilai morbiditas dan mortalitas sebanyak 50% pada pasien ACS. Selama periode ACS, pasien harus menerima satu dosis aspirin 325 mg (dosis standar di Amerika Serikat). Aspirin harus dikunyah, oleh karena penyerapan bukal menghasilkan efek sistemik yang lebih cepat efek sistemik. Setelah itu, pasien harus menerima aspirin 81 mg per hari, terus dilanjutkan tanpa batasan waktu. Dosis 81mg juga berlaku untuk pasien yang menjalani Percutaneous Coronary Intervention (PCI) dimana berhubungan dengan adanya stent. Rekomendasi sebelumnya merekomendasikan dosis yang lebih tinggi, namun studi terbaru menunjukkan bahwa dosis tinggi menimbulkan resiko perdarahan yang lebih tinggi dari tanpa adanya manfaat klinis tambahan. Penggunaan aspirin berlapis enterik tidak mengurangi resiko ini. Penggunaan bersamaan dengan Non Steroid Antiinflammatory Drug (NSAID) harus dihindari, karena NSAID mengikat trombosit secara reversibel, alih-alih mencegah aspirin untuk berikatan. Saat aspirin keluar dari tubuh, NSAID akan berikatan dengan trombosit, dan trombosit akan kembali aktif. Gambar 3. Aktivasi Platelet dan Lokasi Kerja Antiplatelet P2Y12 Receptor Inhibitors Obat ini mengikat reseptor P2Y12 di trombosit untuk menghambat adenosine diphosphate terkait aktivasi platelet (Gambar 3). Clopidogrel dan prasugrel adalah prodrug yang ireversibel, sedangkan ticagrelor bersifat reversibel. Clopidogrel Clopidogrel memiliki waktu paruh 8 jam dan waktu puncak konsentrasi selama 4 jam. Sebanyak 85% dosis diinaktifkan oleh esterase usus. Sisanya dimetabolisme terutama oleh sistem enzim sitokrom P4502C19 ke bentuk metabolit aktif. Dosis yang dianjurkan adalah bolus 600 mg pada awal perjalanan ACS. Hal ini berkaitkan dengan tingkat kejadian kardiovaskular yang lebih rendah dibandingkan dengan dosis 300 mg. Pada pasien ACS yang tidak dapat menerima aspirin karena hipersensitivitas ataupun kontraindikasi gastrointestinal, clopidogrel dapat menjadi terapi alternatif. Namun, pada pasien yang menjalani tindakan Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) beresiko perdarahan sebanyak 53% (resiko absolut 3,3%) jika mendapat clopidogrel dalam waktu 5 hari tindakan. Hal ini telah menyebabkan praktisi klinis menunda memberikan clopidogrel sampai setelah anatomi koroner telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan pasien tidak mendapat manfaat antiiskemia dengan memberikan clopidogrel sejak awal dan tetap menjadi isu perdebatan, dengan kecenderungan untuk tetap memberikan clopidogrel sejak awal, sebelum angiografi, berdasarkan risk-benefit ratio, kecuali ada kemungkinan besar bahwa tindakan akhirnya akan diperlukan. Pilihan lainnya adalah mempertimbangkan menggunakan short acting glikoprotein IIb/ IIIa inhibitor intravena seperti Eptifibatide sebagai "bridging therapy" sampai strategi reperfusi yang definitif ditentukan. Prasugrel Prasugrel adalah P2Y12 antagonis reseptor ireversibel (Gambar 3) yang dimetabolisme menjadi metabolit aktif lebih cepat dan lebih dapat diprediksi dari clopidogrel. Waktu paruh prasugrel adalah 7 jam dan puncak efek antiplatelet adalah dalam waktu 30 menit setelah dosis oral, dibandingkan clopidogrel dalam waktu 4 jam. Oleh karena itu, jika pasien NSTEMI akan menjalani ke kateterisasi segera, tidak boleh menerima prasugrel terlebih dahulu, dan harus menerima setelahnya jika hasil angiografi menunjukkan bahwa CABG tidak akan diperlukan segera. Hal Ini merupakan pertimbangan penting bila menggunakan prasugrel, oleh karena tingkat perdarahan akibat tindakan adalah empat kali lebih tinggi pada prasugel dibanding dengan clopidogrel. Jika memungkinkan, obat ini harus ditunda untuk setidaknya 7 hari sebelum CABG. Ticagrelor Ticagrelor adalah inhibitor langsung reversibel dari reseptor P2Y12, yang bekerja menghambat adenosine diphosphate terkait aktivasi dan agregasi (Gambar 3). Memiliki waktu median puncak konsentrasi 1,3 sampai 2 jam dan waktu paruh dari 9 jam. Ticagrelor berhubungan dengan insiden perdarahan 19% lebih tinggi pada tindakan non CABG atau tindakan dengan pendarahan besar, perdarahan intrakranial fatal, insiden dispnea yang lebih tinggi dan blok ventrikel secara signifikan. Ticagrelor sebaiknya dihentikan 5 hari sebelum CABG. Glycoprotein IIb/IIIa Inhibitors Eptifibatide, Tiroban, Abciximab Glikoprotein IIb/IIIa inhibitor adalah obat intravena yang bekerja dengan menghambat fibrinogen dan faktor Von Willebrand, jalur final agregasi platelet (Gambar 3). Penggunaan obat ini untuk penatalaksanaan ACS telah menurun, sebagian besar digunakan sebelum era terapi dual antiplatelet. Antikoagulan parenteral Unfractioned Heparin Heparin mengikat antitrombin yang berinteraksi dengan antitrombin III dan menginduksi perubahan konformasi, menyebabkan penghambatan cepat faktor IIa (trombin), faktor IXa, dan Faktor Xa sehingga mencegah propagasi trombus lebih lanjut (Gambar 4). Bolus heparin 60 unit/kg intravena menghasilkan waktu puncak 5 sampai 10 menit dan waktu paruh 30 sampai 60 menit. Efek heparin dapat dibalik dengan memberikan protamine sulfat (1 mg per 100 unit heparin). Untuk penatalaksanaan ACS, heparin diberikan berupa bolus 60 unit/kg, tidak melebihi 4.000 unit, diikuti oleh infus drip 12 unit/kg /jam, dengan pemantauan waktu tromboplastin parsial teraktivasi setiap 6 jam dengan nilai tujuan 50 sampai 70 detik atau 1,5 sampai 2,5 kali kontrol. Efek samping heparin termasuk trombositopenia, (kondisi yang berbeda), dan perdarahan. Kelebihan dari unfractioned heparin adalah murah, dan efeknya dapat dengan cepat dibalik. Kelemahannya adalah efek samping yang serius, termasuk heparin induced trombositopenia dan lebih mungkin menyebabkan perdarahan dari pada antikoagulan intravena yang lebih baru. Bivalirudin Bivalirudin adalah inhibitor trombin langsung sintetis terhadap fase cairan dan ikatan gumpalan trombin (Gambar 4). Bivalirudin juga menghambat trombosit secara langsung. Enoxaparin Enoxaparin adalah low molecular weight heparin yang menghambat faktor Iia dan faktor Xa melalui antitrombin, kira-kira dalam rasio 1: 3 (Gambar 4). Enoxaparin memiliki waktu puncak dari 10 menit ketika diberikan secara intravena, dan 3 sampai 5 jam ketika diberi subkutan. Waktu paruh enoxaparin adalah 4,5 jam, namun akan lebih panjang pada pasien dengan disfungsi ginjal, sehingga membutuhkan penyesuaian dosis. Efek antikoagulan enoxaparin sebagian reversibel. Jika itu harus dibalik antara 0 dan 8 jam setelah pemberian dosis, pembalikan direkomendasikan menggunakan rejimen 1 mg protamine sulfat untuk setiap 1 mg enoxaparin yang digunakan. Setelah 8 sampai 12 jam, digunakan 0,5 mg protamine untuk setiap 1 mg enoxaparin. Setelah 12 jam, protamine tidak diperlukan. Dibandingkan dengan unfractioned heparin, enoxaparin kurang berikatan plasma protein dan efek antikoagulan lebih konsisten. Bioavailabilitas yang tinggi juga memungkinkan untuk pemberian dosis subkutan. Aktivitas antiXa yang lebih besar sehingga menghambat pembentukan trombin baru yang lebih efektif, dan resiko dari trombositopenia dan heparin induced trombositopenia yang lebih rendah. Fondaparinux Fondaparinux adalah sintetis pentasakarida yang secara tidak langsung menghambat faktor Xa melalui aksi antitrombin (Gambar 4). Setelah pemberian dosis 2.5 mg subkutan, konsentrasi waktu puncak 2 jam dan waktu paruh terjadi dalam 17-21 jam. Meskipun penggunaan tambahan unfractioned heparin tampaknya mengurangi resiko perdarahan, fondaparinux tetap merupakan pilihan yang kurang ideal untuk tindakan PCI primer akibat STEMI. Antikoagulan oral Warfarin Warfarin, suatu vitamin K antagonis oral, telah digunakan selama beberapa dekade sebagai antikoagulan untuk pengobatan AF, katup jantung buatan, trombosis vena dalam, emboli paru, dan berbagai gangguan pembekuan. Penelitian sebelumnya mengevaluasi peran warfarin dalam kombinasi dengan aspirin untuk pengobatan ACS. Apixaban Apixaban adalah faktor Xa inhibitor oral langsung dengan penyerapan cepat, waktu paruh 12 jam, dan ekskresi ginjal 25%. Studi APPRAISE yang membandingkan apixaban 5 mg dua kali sehari vs plasebo untuk penanganan ACS, menemukan tidak ada perbedaan dalam tingkat kematian kardiovaskular, infark miokard, dan stroke. Gambar 4. Kaskade Koagulasi dan Lokasi Kerja Antikoagulan Dabigatran Dabigatran adalah inhibitor trombin langsung oral. Studi REDEEM mebandingkan empat dosis dabigatran (50, 75, 110, dan 150 mg dua kali sehari) dan plasebo pada pasien ACS. Kelompok dabigatran memiliki lebih beresiko terjadi pendarahan mayor dan minor, dan semakin tinggi dosis maka akan lebih tinggi kejadian perdarahan. Kesimpulan Dalam pengobatan ACS, keuntungan memperbaiki perfusi dengan mencegah propagasi trombus lebih lanjut dan agregasi platelet , sejalan dengan resiko perdarahan yang lebih tinggi secara signifikan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan resiko kematian melalui berbagai mekanisme, termasuk shock, memburuknya iskemia, penghentian antiplatelet dan terapi antikoagulasi menyebabkan stent thrombosis, dan anemia menyebabkan transfusi, yang merambat yang mendasari terjadinya proses inflamasi. REFERENSI 1. Kar S dan Bhatt DL. Anticoagulants for the Treatment of Acute Coronary Syndrome in the Era of New Oral Agents. Coronary Artery Disease 2012, 23:380-90 2. Singh D, Gupta K, dan Vacek JL. Anticoagulant and Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndromes. Cleveland Clinic of Journal of Medicine, Volume 81, Number 2, 2014:103-14 3. Pollack CV. Anticoagulation in Acute Coronary Syndrome and Beyond. University of Pennsylvania Health System: 1-6 4. Wright RS, Anderson JL, Adams CD, et al; American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2011 ACCF/AHA focused update incorporated into the ACC/ AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients with Unstable Angina/Non-STElevation Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2011; 57:e215–e367. 5. Jneid H, Anderson JL, Wright RS, et al. 2012 ACCF/AHA focused update of the guideline for the management of patients with unstable angina/ non-ST-elevation myocardial infarction (updating the 2007 guideline and replacing the 2011 focused update): a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2012; 60:645–681. 6. Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association Task Force on Practice Guidelines; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. J Am Coll Cardiol 2011; 58:e44–e122. 7. Steg PG, Huber K, Andreotti F, et al. Bleeding in acute coronary syndromes and percutaneous coronary interventions: position paper by the Working Group on Thrombosis of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2011; 32:1854–1864. 8. Giugliano RP, Braunwald E. The year in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. J Am Coll Cardiol 2012; 60:2127-2039. 9. Braunwald E. Unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185:924–932. 10. Pedoman Tata Laksana Sindrom Akut. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Edisi Tiga, 2015. STEROID : USE AND ABUSE Hendra Zufry Divisi Endokrinologi, Metabolik & Diabetes- Pusat Pelayanan Tiroid Terpadu. Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/RSUD.Dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. Pendahuluan Testosteron adalah hormon dasar pada manusia yang menghasilkan karakteristik seks sekunder laki-laki (androgenik) merupakan hormon penting menjaga keseimbangan nitrogen yang adekuat, sehingga membantu penyembuhan jaringan dan pemeliharaan massa otot (anabolik). Testosteron memiliki aksi ganda digambarkan dalam kapasitas androgenik dan anaboliknya. SAA adalah obat yang berasal dari modifikasi molekul testosteron untuk meningkatkan atau membatasi karakteristik tertentu dari testosteron. Secara umum, testosteron telah diubah untuk memproduksi obat yang lebih kurang sebagai anabolik atau androgenik, yang memiliki perbedaan afinitas untuk reseptor testosteron, memiliki jalur breakdown metabolisme yang berbeda, atau yang berkhasiat untuk penggunaan oral; atau dapat juga dikombinasikan dari perubahan ini. Lebih dari seribu senyawa yang berbeda telah disintesis dan dipelajari sejak tahun 1950 dengan harapan menghasilkan senyawa yang memiliki sifat anabolik atau androgenic yang mempunyai efek lebih tinggi dari testosteron. Secara umum, tujuan mengubah suatu SAA ini adalah untuk meningkatkan karakteristik anabolik dan untuk mengurangi fitur androgenik, sehingga dapat digandakan senyawa yang diinginkan, yaitu karakter sifat anaboliknya, efek nitrogen-sparing senyawa dan meminimalkan yang tidak diinginkan secara umum seperti sifat androgenik, dan efek virilisasi. Secara klinis, SAA telah digunakan untuk treatment sejumlah kondisi, yaitu: Anemia Luka akut dan kronis Malnutrisi Kalori-Protein dengan penurunan berat badan luka bakar yang parah Perawakan pendek Osteoporosis Hipogonadisme Primer dan Skunder Katabolik skunder berkepanjangan untuk penggunaan jangka panjang kortikosteroid Human immunodeficiency virus (HIV) sindrom wasting Hampir sejak awal, testosteron dan analog anabolik-androgenik telah digunakan dan disalahgunakan oleh individu yang ingin meningkatkan efek anabolik dan potensi androgenik. Dengan demikian, orang-orang ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fisik mereka dalam pemugaran dan peningkatan fisik. Atlet angkat besi dan atlet trek blok timur mengatur tahapan latihan atletik selama beberapa dekade dengan menggunakan senyawa tersebut. Penggunaan SAA telah menjadi fenomena di seluruh dunia, perlahan-lahan merambat ke perguruan tinggi, SMA, dan bahkan tingkat SMP.1 Penegasan awal dari komunitas medis bahwa "Steroid anabolik belum dapat meningkatkan kemampuan atletik" di Physicians Desk Reference 2002, berkontribusi untuk fenomena ini. Orang-orang yang menyalahgunakan obat ini dengan cepat menyadari bahwa efek peningkatan kinerja itu nyata dan kemudian tanpa memperhatikan kontraindikasi, dosis rekomendasi, dan peringatan dari Praktisi Kesehatan.2,3 Biopharmacology Testosteron Testosteron, merupakan hormon seks pria yang utama, diproduksi di testis dipengaruhi hormon luteinizing (LH) dalam jumlah 2,5-11 mg/d.4 Aktivitas testosteron dimediasi melalui reseptor androgen yang hadir dalam berbagai jaringan di seluruh tubuh manusia. Testosteron mengikat reseptor intraseluler dalam sitosol sel, membentuk kompleks reseptor yang bermigrasi ke dalam nukleus, yang mengikat asam deoksiribonukleat (DNA) segmen tertentu. Selanjutnya mengaktifkan asam ribonukleat (mRNA) untuk meningkatkan transkripsi, yang mengarah ke peningkatan laju sintesis protein; dalam kasus sel-sel otot, ini berarti peningkatan produksi dari protein aktin dan myosin. Setelah proses ini selesai, reseptor berdisosiasi kompleks dan didaur ulang bersama dengan hormon, untuk mengulangi proses ini beberapa kali sebelum metabolisme. Aksi kerja anabolik testosteron terutama disebabkan testosteron bertindak pada reseptor androgen pada jaringan anabolik-responsif. Efek androgenik yang mungkin dimediasi melalui reseptor androgen yang sama pada jaringan androgen-responsif di bawah pengaruh dihidrotestosteron (DHT), yang diproduksi oleh interaksi dari 5-alpha reductase (5AR) dengan testosteron dan pengurangan berikutnya dari C45 ganda obligasi. Selain itu, DHT tidak dapat menjalani pengurangan lebih lanjut, juga bukan substrat untuk aromatase; dengan demikian, tidak dikonversi ke metabolit estrogenik. DHT telah ditunjukkan untuk mengikat ke reseptor dalam jaringan, seperti kulit, kulit kepala, dan prostat, dan untuk mengerahkan 3-4 kali efek androgenik testosteron. Dengan demikian, hormon utama yang memediasi efek androgenik testosteron sebenarnya adalah 5-alpha berkurang DHT. Mekanisme lain dari efek anabolik langsung dan tidak langsung termasuk aktivitas anti-glukokortikoid yang dimediasi oleh perpindahan dari glukokortikoid dari reseptor,5 meningkat pada aktivitas creatine phosphokinase di otot rangka,6 dan peningkatan di sirkulasi faktor pertumbuhan insulin (IGF)-1,7 serta up-regulasi reseptor IGF-1.8 Oleh karena itu, dosis supraphysiologic testosteron atau AAS tidak berpengaruh terhadap meningkatnya efek anabolik pada atlet yang sehat. Biokimia dan Farmakologi Kebanyakan AAS berasal dari 3 senyawa: testosteron, dihidrotestosteron, dan 19-nortestosteron. Senyawa ketiga secara struktural identik dengan testosteron kecuali untuk penghapusan karbon19. Senyawa induk ini menawarkan sifat yang berbeda yang berkaitan dengan tindakan dan metabolisme yang umumnya konstan di seluruh kelompok senyawa tersebut. Ester Testosteron dan Turunannya Ester testosteron semakin digunakan dalam terapi pengganti, namun penyalahgunaan senyawa ini juga meningkat. Ester ini berbeda dalam bentuk struktural dan ukuran berfungsi untuk menentukan tingkat di mana testosteron dilepaskan dari jaringan. Preparat testosteron umumnya adalah: Testosteron propionate, Testosteron cypionate, Testosteron enanthate dan derivat testosterone (Metiltestosteron) Metiltestosteron adalah bentuk paling dasar dari anabolicandrogenic steroid (AAS). Eliminasi degradasi pertama terjadi di hepar, sebisa mungkin dapat diberikan dosis minimal secara oral. Karena dapat menyebabkan hepatotoksisitas terkait dosis. Efek samping androgenik dan estrogenik sangat kuat dan merupakan pilihan yang buruk. Methandrostenolone dapat mengurangi estrogenik dan sifat androgenik.10 Steroid ini pertama kali diproduksi secara komersial pada tahun 1960 oleh Ciba dengan nama merek "Dianabol" yang dengan cepat menjadi steroid yang paling banyak digunakan dan disalahgunakan di seluruh dunia, bahkan juga sampai saat ini. Agen ini sangat berefek anabolik, dengan waktu paruh sekitar 4 jam. Gugus metil pada C-17 membuat AAS pada preparat oral dapat berpotensi sebagai hepatotoksik. Fluoxymesterone adalah androgen ampuh yang diproduksi di bawah nama merek "Halotestin". Dapat diberikan secara oral, namun dapat menimbulkan keprihatinan terhadap kondisi hepatiknya. AAS ini tidak disukai dalam praktek klinis karena efek anaboliknya yang minim, namun atlet menyalahgunakannya untuk adrogenic. Derivat Nandrolone11 Nandrolone dekanoat adalah anabolik kuat dengan profil keamanan yang relatif menguntungkan.12 Nandrolone adalah obat yang relatif aman dengan efek androgenik minimal dan tindakan anabolik cukup pada dosis terapi. Nandrolone dekanoat adalah preparat intramuskular (IM) dan tidak memiliki sifat hepatotoksik. Namun, agen ini adalah salah satu AAS paling banyak disalahgunakan, karena kemanjurannya.13 Ethylestrenol adalah derivat oral 19-nortestosteron dan dipasarkan di Amerika Serikat dengan nama merek Maxibolin, tetapi saat ini telah dihentikan. Trenbolone merupakan obat androgenik dan anabolik yang ampuh memliki efek androgenik yang lebih dibandingkan nandrolone. Trenbolone adalah obat Eropa dengan rekor penyalahgunaan sangat tinggi. Di USA, digunakan dalam preparate dokter hewan sebagai trenbolone asetat. Derivat DHT Oxandrolone AAS sangat anabolik, dengan efek androgenik kecil pada dosis terapi. Pertama kali dipasarkan oleh Searle, DHT dihentikan pada pertengahan 1990-an. BTG mematenkan kembali AAS sebagai Oxandrin, sebagian besar untuk penggunaan obat pada penyakit terkait HIV. Karena sifat androgeniknya ringan, oxandrolone adalah salah satu dari beberapa agen disalahgunakan secara rutin oleh atlet wanita. Atlet angkat besi, petinju, berusaha untuk meningkatkan kekuatan tanpa mengalami penambahan berat badan. Stanozolol adalah AAS sangat aktif dalam jaringan androgen dan anabolik-sensitif. Ini adalah androgen lemah dari DHT dan memberikan efek relatif kurang androgenik. AAS ini dipasarkan di USA dan luar negeri sebagai Winstrol, dalam bentuk oral dan Injeksi. Atlet, baik itu yang di trek dan lapangan, telah menyalahgunakannya. Pada tahun 1988, sprinter Kanada Ben Johnson dicabut medali emas Olimpiade setelah positif stanozolol. Oxymetholone merupakan agen AAS yang cukup ampuh dan unik. Aksi agen ini pada jaringan androgen sensitif dan cukup androgenik. Oxymetholone adalah satu-satunya AAS yang untuk saat ini dipertimbangkan menjadi sebagai suatu zat karsinogen.14. Oxymetholone dipasarkan di USA sebagai Anadrol-50 dan disalahgunakan di seluruh dunia oleh atlet angkat besi dan atlet kekuatan untuk efek anabolik dan efek androgenik yang kuat. Dampak buruk Sebagian besar efek samping dari penggunaan anabolikandrogenik steroid (AAS) tergantung dari dosis dan reversibel dengan penghentian agen penyebab atau agen. Ikhtisar mengenai efek samping dan interaksi ini hanya mengenai gambarannya saja, dan tidak dimaksudkan untuk mewakili spektrum penuh potensi efek samping. Efek Kardiovaskular Efek buruk yang paling umum dari penggunaan AAS pada sistem kardiovaskular meliputi peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, dan perubahan metabolisme lipid, termasuk menurunkan highdensity lipoprotein (HDL) dan peningkatan lipoprotein densitas rendah (LDL). Efek ini, bila dikombinasikan dengan pemulihan ginjal meningkat ion, seperti natrium, menyebabkan retensi cairan dan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pengguna steroid anabolik dapat memiliki penurunan ejeksi fraksi ventrikel kiri. Penyalahgunaan steroid Ananbolic juga telah dikaitkan dengan aritmia ventrikel.11,15,16,17,18 Efek hepatik Perubahan yang dibuat untuk C-17 untuk menghambat degradasi hati membuat hampir semua sediaan oral hepatotoksik. ALT/ AST cenderung naik 2-3 kali dari nilai normal. Rasio risiko dan manfaat masih terus dievaluasi. Tumor hati primer telah dilaporkan, yang sebagian besar adalah jinak. Beberapa laporan kasus ada anak muda, atlet sehat yang telah meninggal karena karsinoma hati primer, dengan satu-satunya faktor risiko diidentifikasi penggunaan AAS oral.19 Efek endokrin Sistem endokrin memiliki array yang luar biasa dari checks and balances yang memastikan tubuh manusia adalah pada atau dekat homeostasis pada setiap titik waktu. Gangguan satu sistem umpan balik telah terbukti menghasilkan perubahan dalam sistem umpan balik hormon lain melalui perubahan reseptor langsung, serta melalui kompetisi untuk enzim umum dan jalur metabolisme. Penelitian telah menunjukkan bahwa AAS mengikat glukokortikoid, progesteron, dan reseptor estrogen dan mengerahkan beberapa efek. AAS mempengaruhi KGDP dan mengurangi toleransi glukosa, mungkin karena efek hati atau perubahan reseptor insulin. Tiroksin-binding globulin (TBG) juga dapat diturunkan dengan AAS dan mengakibatkan kadar total T4 menurun, dengan tingkat T4 bebas yang tersisa normal. Up-regulasi hormon seks globulin mengikat, dengan penurunan bersamaan di TBG, diduga menyebabkan perubahan total tingkat T4. Efek samping yang paling jelas dan umum adalah pertumbuhan tender, jaringan estrogen-sensitif di bawah puting laki-laki. Pertumbuhan ini disebut ginekomastia dan dapat diobati secara medis atau pembedahan.20 Efek urologi Prostat laki-laki sangat sensitif terhadap androgen, terutama mereka yang berkurang pada jaringan prostat menjadi dihidrotestosteron (DHT) atau analog DHT. Menanggapi rangsangan ini, prostat tumbuh dalam ukuran, berpotensi menyebabkan atau memperburuk benign prostatic hyperplasia (BPH). Selain itu, penggunaan AAS pada pasien dengan karsinoma yang mendasari prostat adalah benar-benar kontraindikasi karena potensi pertumbuhan tumor hormon-sensitif. Namun, sebuah studi 3 tahun hipogonadisme orang di terapi penggantian testosteron gagal menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok dan kontrol dalam gejala kencing, laju aliran urin, atau sisa urine postvoid.21 Efek hematologi Faktor pembekuan langsung dapat dikurangi dengan peningkatan waktu protrombin. Pada pasien dengan terapi antikoagulan bersamaan, peningkatan ini bisa menyebabkan pendarahan. AASs penyebab peningkatan hemoglobin dan hematokrit dan digunakan dalam banyak kasus anemia, meskipun dokter harus menyadari potensi polisitemia. Efek dermatologi Kulit, terutama wajah dan kulit kepala, memiliki derajat yang tinggi dari reseptor androgen dan 5AR. DHT diketahui menyebabkan peningkatan produksi sebum, yang menyebabkan jerawat klinis. Juga, pola kebotakan laki-laki berhubungan dengan produksi kulit kepala DHT dan mengikat, bersama dengan faktor genetik yang mempengaruhi pertumbuhan rambut. Pola kebotakan laki-laki sangat diperburuk oleh sebagian AAS pada individu yang rentan. Penggunaan klinis Jelas, terapi penggantian hormon adalah penggunaan paling umum dari testosteron. AAS memiliki banyak kegunaan klinis potensial lainnya.22 Sebagian besar pusat ini pada sifat anabolik obat ini dan penggunaannya pada orang dengan cachexia, penderita HIV, hati dan gagal ginjal, PPOK, beberapa jenis kanker, dan luka bakar, serta selama pemulihan pasca operasi. Dalam semua kasus klinis, dengan pengecualian kanker, AAS telah menunjukkan keberhasilan dalam kenaikan berat badan. Pada infeksi HIV, penggantian testosteron dan penggunaan AAS umumnya dianggap. AAS umum digunakan termasuk oxandrolone, nandrolone, dan Oxymetholone. Semua 3 agen telah dipelajari untuk meningkatkan LBM dan berat badan.23-26 AAS telah dipelajari dalam cachexia PPOK terkait. Stanozolol (12 mg/ d), setelah 250 mg IM testosteron injeksi awal, telah terbukti menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam berat badan, indeks massa tubuh pasien (BMI), dan kekuatan dibandingkan dengan kontrol pada 26 minggu.27,28,29 Gagal hati juga terkait dengan malnutrisi protein kalori dan wasting. Dalam sebuah studi dari 273 pasien dengan penurunan berat badan moderat karena hepatitis alkoholik, oxandrolone (80 mg/ d) meningkatkan fungsi dan gizi parameter hati dan meningkatkan kelangsungan hidup 6 bulan bila dibandingkan dengan kontrol.30 AAS pada penyembuhan luka bakar, termasuk ester testosteron, stanozolol, oxandrolone, dan nandrolone. Agen ini meningkatkan sintesis kolagen dan aktivitas fibroblas dermal31 dan memiliki efek positif pada penyembuhan tarif di sebelumnya nonhealing luka.32 Cachexia terkait kanker dan anemia yang sangat umum. AAS juga telah digunakan untuk efek erythropoietik, biasanya dalam pengobatan leukemia. AAS digunakan pada gagal ginjal, terutama pada pasien hemodialisis, telah diteliti. Sebuah studi terkontrol plasebo double-blind dari 29 pasien dialisis menerima baik nandrolone (100 mg/ minggu) atau plasebo selama 6 bulan menunjukkan hasil yang signifikan dalam LBM dan parameter fungsional.33 Studi juga menunjukkan bahwa efek erythropoietic dari AAS (nandrolone dekanoat) berguna dalam penyakit ginjal kronis dan pemakaian secara kombinasi lebih bermanfaat.34 Penyalahgunaan Anabolik-androgenik steroid Sejumlah efek kompleks neurologis dari AAS masih dipelajari. Berkaitan biopharmacology ini untuk individu menyalahgunakan AAS adalah tugas yang sangat sulit karena beberapa faktor. Untuk satu, banyak orang menyalahgunakan AAS melakukannya di relatif kerahasiaan, dan banyak yang enggan untuk terlibat dalam penelitian medis yang valid. Kurangnya standar saat melakukan penelitian-karena sejumlah besar agen yang dijual di seluruh dunia di pasar gelap dan potensi relatif mereka, atau kurang lengkap daripadanya-masalah lain. Banyak produk palsu yang dijual dan digunakan, yang mempersulit studi penyalahgunaan. Dalam lebih dari beberapa kasus, data yang kontradiktif ada, terutama mengenai efek psikologis. Satu harus ingat bahwa interaksi kekuatan, yang akhirnya mempengaruhi pelaku, luas dan multidimensi, web kompleks gain diduga dan reward yang ada karena kondisi dan masalah psikososial terkait. Penggunaan zat meningkatkan kinerja bukan ide yang baru dan dapat tanggal kembali ke Yunani. Penggunaan AAS untuk peningkatan kinerja dimulai pada tahun 1950 dengan atlet elit, dan penggunaan yang telah perlahan-lahan menetes ke termasuk sekolah tinggi dan tingkat SMP. AAS telah ditunjukkan untuk mengubah suasana hati oleh sejumlah mekanisme.35, 36, 37 Studi menunjukkan bahwa testosteron dan AAS dapat bertindak sebagai pusat inhibitor MAO. Vogel dkk membandingkan efek antidepresan dari amitriptyline (75 mg/d maks 300 mg/d) dengan orang-orang dari Mesterolone (100 mg/d, maks 550 mg/d) dalam double-blind desain dengan 34 pasien rawat jalan laki-laki depresi.38 Para peneliti menemukan bahwa 2 obat sama-sama efektif dalam mengurangi gejala depresi dan Mesterolone diproduksi efek samping lebih sedikit daripada amitriptyline. Studi lain gabungan metiltestosteron (15 mg/d) dengan imipramine (25-50 mg/d) menemukan respon paranoid cepat dalam 4 dari 5 orang dirawat.39 Hal ini kemungkinan besar disebabkan inhibisi MAO pusat dengan metiltestosteron, dikombinasikan dengan efek diketahui imipramine. Respon cepat mereda ketika metiltestosteron dihentikan. Penelitian lain menunjukkan testosteron, terutama pada periode prenatal tetapi juga selama masa pubertas dan dewasa, adalah penting dalam membangun kesiapan biologis untuk perilaku agresif normal dan dalam memfasilitasi ekspresi agresi dalam pengaturan sosial yang sesuai. Laporan juga menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan belajar secara signifikan mempengaruhi ekspresi yang sebenarnya.40 Tahun 1983 studi dari 32 lifter menggunakan AAS, 56% melaporkan peningkatan sementara iritabilitas diri didefinisikan dan perilaku agresif. Ketika efek psikoaktif menggabungkan dengan penguatan positif yang kuat dari berat badan dan kekuatan keuntungan, serta dari peningkatan citra diri, AAS dibuktikan dapat bersifat adiktif.1, 13 Sebuah studi retrospektif dirilis di British Journal of Sports Medicine tahun 2013, mempelajari kekuatan atlet Swedia (angkat besi, pelempar, pegulat) yang berlaga di tingkat elit antara tahun 1960 dan 1979. Dari 700 atlet yang disertakan, 20% mengaku menggunakan AAS selama karir atletik mereka. Para pengguna AAS lebih mungkin telah dirawat karena depresi, masalah konsentrasi, dan perilaku agresif.41 Kecanduan AAS umumnya diartikan sebagai kecanduan psikis, tetapi efek penarikan yang terjadi ketika menggunakan AAS berhenti secara jelas menunjukkan unsur kecanduan fisik juga. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa gejala penarikan termasuk depresi, kelelahan, paranoia, dan pikiran dan perasaan bunuh diri.35 Sebuah ulasan di 1989 menyarankan bahwa efek psikoaktif, gejala penarikan, dan mekanisme biologis yang mendasari AAS tampak mirip dengan mekanisme dan komplikasi yang menyertai kokain, alkohol, atau penyalahgunaan opioid. Beberapa pasien mungkin memerlukan pengobatan untuk mengembalikan regulasi hormonal fisiologis setelah penyalahgunaan AAS, sedangkan mendukung konseling dan antidepresan obat dapat membantu dengan aspek psikologis. Penyalahgunaan AAS juga meningkat pada atlet perempuan dari semua tingkatan. kekhawatiran tambahan khusus untuk pelaku perempuan termasuk pertumbuhan rambut wajah, kebotakan pola lakilaki atau regresi garis rambut frontal, atrofi payudara, pengkasaran kulit, perubahan siklus menstruasi atau amenore, pembesaran klitoris, dan memperdalam suara. The perubahan terhadap sistem reproduksi wanita disebabkan oleh peningkatan buatan kadar testosteron, yang biasanya hadir pada wanita dalam jumlah kecil. Karena sistem umpan balik negatif, pelepasan LH dan FSH menurun, mengarah ke penurunan estrogen dan progesteron. AAS digunakan oleh wanita hamil dapat menyebabkan pseudohermafroditisme atau virilisasi pada janin perempuan atau bahkan kematian janin. Pada ulasan yang dirilis oleh American College of Obstetricians dan Gynecologists tahun 2011, profesional kesehatan didorong untuk mengatasi penggunaan dan konsekuensi dari zat, mendorong penghentian, dan merujuk pasien ke pusat-pusat pengobatan penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan AAS, terutama sejak abad ke-20, telah memiliki efek merugikan pada penggunaan klinis dari senyawa ini. Obat ini sekarang dianggap zat yang dikendalikan di Amerika Serikat (jadwal 2 dan 3), dan ini, bersama dengan perhatian media yang negatif yang berlebihan, telah mengakibatkan penurunan tajam kesesuaian dalam penggunaan klinis. Memang, banyak AAS telah ditarik dari pasar AS; namun, minat klinis di efek menguntungkan dari obat ini sekali lagi telah datang ke permukaan. Dengan kenaikan baru-baru ini digunakan (diperkirakan 400%), AAS sekali lagi diresepkan untuk aplikasi yang diketahui, dan penelitian yang sedang berlangsung akan terus mengungkap novel menggunakan untuk agen ini dan selanjutnya akan menentukan mekanisme aksi mereka. Dengan demikian, dokter harus membantu untuk memastikan bahwa AAS digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Daftar Kepustakaan 1. Kokkevi A, Fotiou A, Chileva A, et al. Daily exercise and anabolic steroids use in adolescents: a cross-national European study. Subst Use Misuse. 2008 Aug 27. 1. [Medline]. 2. Di Paolo M, Agozzino M, Toni C, et al. Sudden anabolic steroid abuse-related death in athletes. Int J Cardiol. 2007 Jan 2. 114(1):1147. Epub 2005 Dec 20. [Medline]. 3. Di Pasquale MG. Drug Use and Detection in Amateur Sports. Warkworth, Ontario, Canada: MGD Press; 1984. 4. Rosenfeld RL. Role of androgens in growth and development of the fetus, child, and adolescent. Adv Pediatr. 1972. 19. 5. Danhaive PA, Rousseau GG. Binding of glucocorticoid antagonists to androgen and glucocorticoid hormone receptors in rat skeletal muscle. J Steroid Biochem. 1986 Feb. 24(2):481-7. [Medline]. 6. Samuels, Sellers, McCaulay. The source of excess creatine following methyl testosterone. J Clin Endocrinol Metab. 1946. 7. Arnold AM, Peralta JM, Thonney ML. Ontogeny of growth hormone, insulin-like growth factor-I, estradiol and cortisol in the growing lamb: effect of testosterone. J Endocrinol. 1996 Sep. 150(3):391-9. [Medline]. 8. Urban RJ, Bodenburg YH, Gilkison C, et al. Testosterone administration to elderly men increases skeletal muscle strength and protein synthesis. Am J Physiol. 1995 Nov. 269(5 Pt 1):E820-6. [Medline]. 9. Dimick DF, Heron M, Baulieu EE, et al. A comparative study of the metabolic fate of testosterone, 17 alpha-methyl-testosterone. 19-nortestosterone. 17 alpha-methyl-19-nor-testosterone and 17 alphamethylestr-5(10)-ene-17 beta-ol-3-one in normal males. Clin Chim Acta. 1961 Jan. 6:63-71. [Medline]. 10. Steele RE, Didato F, Steinetz BG. Relative importance of 5alpha reduction for the androgenic and LH-inhibiting activities of delta-4-3ketosteroids. Steroids. 1977 Mar. 29(3):331-48. [Medline]. 11. Phillis BD, Abeywardena MY, Adams MJ, et al. Nandrolone potentiates arrhythmogenic effects of cardiac ischemia in the rat. Toxicol Sci. 2007 Oct. 99(2):605-11. Epub 2007 Jul 25. [Medline]. [Full Text]. 12. Gaul, Morato, Hayano, et al. Biosynthesis of estrogens. Endocrinol. 1962. 71: 13. Birgner C, Kindlundh-Högberg AM, Alsiö J, et al. The anabolic androgenic steroid nandrolone decanoate affects mRNA expression of dopaminergic but not serotonergic receptors. Brain Res. 2008 Sep 13. [Medline]. 14. Berkow R, ed. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. 15th ed. Rahway, NJ: Merck Sharp and Dohme Research Laboratories; 1987. 1208. 15. Fineschi V, Riezzo I, Centini F, et al. Sudden cardiac death during anabolic steroid abuse: morphologic and toxicologic findings in two fatal cases of bodybuilders. Int J Legal Med. 2007 Jan. 121(1):48-53. Epub 2005 Nov 15. [Medline]. 16. Lau DH, Stiles MK, John B, et al. Atrial fibrillation and anabolic steroid abuse. Int J Cardiol. 2007 Apr 25. 117(2):e86-7. [Medline]. 17. Achar S, Rostamian A, Narayan SM. Cardiac and metabolic effects of anabolic-androgenic steroid abuse on lipids, blood pressure, left ventricular dimensions, and rhythm. Am J Cardiol. 2010 Sep 15. 106(6):893-901. [Medline]. 18. Baggish AL, Weiner RB, Kanayama G, Hudson JI, Picard MH, Hutter AM Jr, et al. Long-term anabolic-androgenic steroid use is associated with left ventricular dysfunction. Circ Heart Fail. 2010 Jul 1. 3(4):472-6. [Medline]. [Full Text]. 19. Schwingel PA, Cotrim HP, Salles BR, Almeida CE, dos Santos CR Jr, Nachef B, et al. Anabolic-androgenic steroids: a possible new risk factor of toxicant-associated fatty liver disease. Liver Int. 2011 Mar. 31(3):348-53. [Medline]. 20. Basaria S. Androgen abuse in athletes: detection and consequences. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Apr. 95(4):1533-43. [Medline]. 21. Snyder PJ, Peachey H, Hannoush P, et al. Effect of testosterone treatment on bone mineral density in men over 65 years of age. J Clin Endocrinol Metab. 1999 Jun. 84(6):1966-72. [Medline]. [Full Text]. 22. Basaria S, Wahlstrom JT, Dobs AS. Clinical review 138: anabolicandrogenic steroid therapy in the treatment of chronic diseases. J Clin Endocrinol Metab. 2001 Nov. 86(11):5108-17. [Medline]. [Full Text]. 23. Berger JR, Pall L, Hall CD, et al. Oxandrolone in AIDS-wasting myopathy. AIDS. 1996 Dec. 10(14):1657-62. [Medline]. 24. Strawford A, Barbieri T, Van Loan M, et al. Resistance exercise and supraphysiologic androgen therapy in eugonadal men with HIVrelated weight loss: a randomized controlled trial. JAMA. 1999 Apr 14. 281(14):1282-90. [Medline]. [Full Text]. 25. Bucher, Berger, Fields-Gardner, et al. A prospective study on the safely and effect of nandrolone decanoate in HIV positive patients. Abstract of the 11th Conf. on AIDS. 1996. 26. Gold J, High HA, Li Y, et al. Safety and efficacy of nandrolone decanoate for treatment of wasting in patients with HIV infection. AIDS. 1996 Jun. 10(7):745-52. [Medline]. 27. Ferreira IM, Verreschi IT, Nery LE, et al. The influence of 6 months of oral anabolic steroids on body mass and respiratory muscles in undernourished COPD patients. Chest. 1998 Jul. 114(1):19-28. [Medline]. 28. Schols AM, Soeters PB, Mostert R, et al. Physiologic effects of nutritional support and anabolic steroids in patients with chronic obstructive pulmonary disease. A placebo-controlled randomized trial. Am J Respir Crit Care Med. 1995 Oct. 152(4 Pt 1):1268-74. [Medline]. 29. Spungen AM, Grimm DR, Strakhan M, et al. Treatment with an anabolic agent is associated with improvement in respiratory function in persons with tetraplegia: a pilot study. Mt Sinai J Med. 1999 May. 66(3):201-5. [Medline]. 30. Mendenhall CL, Moritz TE, Roselle GA, et al. A study of oral nutritional support with oxandrolone in malnourished patients with alcoholic hepatitis: results of a Department of Veterans Affairs cooperative study. Hepatology. 1993 Apr. 17(4):564-76. [Medline]. 31. Falanga V, Greenberg AS, Zhou L, et al. Stimulation of collagen synthesis by the anabolic steroid stanozolol. J Invest Dermatol. 1998 Dec. 111(6):1193-7. [Medline]. 32. Demling R, De Santi L. Closure of the "non-healing wound" corresponds with correction of weight loss using the anabolic agent oxandrolone. Ostomy Wound Manage. 1998 Oct. 44(10):58-62, 64, 66 passim. [Medline]. 33. Johansen KL, Mulligan K, Schambelan M. Anabolic effects of nandrolone decanoate in patients receiving dialysis: a randomized controlled trial. JAMA. 1999 Apr 14. 281(14):1275-81. [Medline]. [Full Text]. 34. Gaughan WJ, Liss KA, Dunn SR, et al. A 6-month study of low-dose recombinant human erythropoietin alone and in combination with androgens for the treatment of anemia in chronic hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 1997 Oct. 30(4):495-500. [Medline]. 35. Talih F, Fattal O, Malone D Jr. Anabolic steroid abuse: psychiatric and physical costs. Cleve Clin J Med. 2007 May. 74(5):341-4, 346, 349-52. [Medline]. 36. Bahrke MS, Yesalis CE 3rd, Wright JE. Psychological and behavioural effects of endogenous testosterone levels and anabolicandrogenic steroids among males. A review. Sports Med. 1990 Nov. 10(5):303-37. [Medline]. 37. Graham MR, Evans P, Davies B, Baker JS. AAS, growth hormone, and insulin abuse: psychological and neuroendocrine effects. Ther Clin Risk Manag. 2008 Jun. 4(3):587-97. [Medline]. [Full Text]. 38. Vogel W, Klaiber EL, Broverman DM. A comparison of the antidepressant effects of a synthetic androgen (mesterolone) and amitriptyline in depressed men. J Clin Psychiatry. 1985 Jan. 46(1):68. [Medline]. 39. Wilson IC, Prange AJ Jr, Lara PP. Methyltestosterone with imipramine in men: conversion of depression to paranoid reaction. Am J Psychiatry. 1974 Jan. 131(1):21-4. [Medline]. 40. Rada RT, Kellner R, Winslow WW. Plasma testosterone and aggressive behavior. Psychosomatics. 1976 Jul-Sep. 17(3):138-42. [Medline]. 41. Lindqvist AS, Moberg T, Eriksson BO, Ehrnborg C, Rosén T, Fahlke C. A retrospective 30-year follow-up study of former Swedish-elite male athletes in power sports with a past anabolic androgenic steroids use: a focus on mental health. Br J Sports Med. 2013 Oct. 47(15):9659. [Medline]. 42. Berning JM, Adams KJ, Stamford BA. Anabolic steroid usage in athletics: facts, fiction, and public relations. J Strength Conditioning Res. 2004. 18(4):908–917. 43. Gruber AJ, Pope HG Jr. Psychiatric and medical effects of anabolicandrogenic steroid use in women. Psychother Psychosom. 2000. 69(1):19-26. [Medline]. 44. Hartgens F, Kuipers H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Med. 2004. 34(8):513-54. [Medline]. APPLICATIONS OF STEROID IN INTERNAL MEDICINE CASES Krishna W. Sucipto Division of Endocrinology, Metabolism & Diabetes- Thyroid Center Department of Internal Medicine, School of Medicine University of Syiah Kuala/ Dr. Zainoel Abidin General Teaching Hospital, Banda Aceh- Indonesia Introduction Steroids are perhaps one of the most widely used group of drugs in present day practice, sometimes with indication and sometimes without indications. Corticosteroids and their biologically active synthetic derivatives differ in their metabolic (glucocorticoid) and electrolyteregulating (mineralocorticoid) activities. Glucocorticoid (GC) hormones are secreted by the cortex of the adrenal gland, under control of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. GCs are stress hormones that facilitate a flight or fight reaction by providing substrate for oxidative metabolism by increasing hepatic glucose production, adipose tissue lipolysis and proteolysis, and by maintaining adequate blood pressure.1,2 In the clinic, synthetic GCs are extensively used in the treatment of numerous disease entities due to their potent anti-inflammatory and immunosuppressive actions when administered at pharmacological dosages. GCs affect both the innate and the acquired immune system. As such, GCs impair the ability of leukocytes to exit the bloodstream and enter sites of infection and tissue injury, resulting in suppression of the inflammatory response. In addition, GCs impair the phagocytic function of macrophages and reduce the production of inflammatory cytokines required for inflammatory responses. Moreover, GCs reduce the activity of the acquired immune system by inducing T-cell depletion, while B-cell function is mostly minimally altered by GC treatment.3 This paper focuses on highlights the recent trends, relevance, and consensus issues on the use of steroids as adjunct pharmacological agents in relation to internal medicine practice along with emphasis on important clinical aspects of usefulness. Corticosteroids: A Brief History In 1908, it was first established that ‗substances‘ secreted by the adrenal gland were involved in glucose metabolism following studies in adrenalectomised dogs that developed hypoglycaemia. In the following decades, the critical role of the adrenal cortex in intermediary metabolism and energy homeostasis was further characterised. A major advance was made in 1936 with the simultaneous isolation of the inactive form of the adrenal hormone cortisol, known as cortisone, by the Polish-born, Swiss chemist Tadeusz Reichstein and the American chemist Edward Calvin Kendall. This breakthrough enabled further experiments into the various physiological roles of adrenal cortex hormones. The amount of cortisone that could be isolated from bovine adrenal glands, however, was small and the need to produce adrenocorticosteroids through synthetic methods soon became apparent. This process was fuelled by the US entry into the Second World War, when rumours circulated that Luftwaffe pilots were taking adrenal extracts to increase their resistance to oxygen deprivation at high altitudes. Although this rumour was never confirmed, it induced an all-out quest for large-scale synthesis of active adrenal hormone. In 1946, Lewis Hastings Sarett of Merck Research Laboratories succeeded in synthetically producing cortisone from desoxycholic acid.4,5 By the summer of 1948, sufficient material was produced to initiate the first studies in humans. The newly produced cortisone indeed improved the symptoms of Addison‘s disease. In addition, rheumatologist Philip Showalter Hench, a friend and collaborator of Kendall, tested cortisone in patients with rheumatoid arthritis. This was driven by observations that joint complaints were reduced by jaundice and that the newly discovered steroid cortisone seemed structurally related to bile acids. Indeed, cortisone treatment induced a spectacular reduction in joint tenderness and swelling in chronic rheumatoid arthritis patients. In the following year, the use of cortisone was successfully introduced in the treatment of other autoimmune diseases. In 1950, the ‗wonder drug‘ cortisone was officially launched as a pharmacological agent. In the same year Tadeusz Reichstein, Philip Showalter Hench and Edward Calvin Kendall shared the Nobel Prize for Physiology or Medicine ‗for research on the structure and biological effects of adrenal cortex hormones‘. Currently, over six decades later, GCs remain the cornerstone in the treatment of numerous diseases that cover the entire spectrum of internal medicine (table 1).4 Table 1. Common indications for systemic glucocorticoid therapy within the field of internal medicine. Subspeciality Indication Rheumatology RA, SLE, GCA, PMR, Sarcoidosis Nephrology Vasculitis/glomerulonephritis Gastroenterology IBD, autoimmune hepatitis Haemato-oncology Lymphoma, multiple myeloma Infectious diseases Meningitis Pulmonology COPD Emergency medicine Anaphylactic/allergic reactions COPD = chronic obstructive pulmonary disease; GCA = giant cell arteritis; IBD = inflammatory bowel disease; PMR = polymyalgia rheumatica; RA = rheumatoid arthritis; SLE = systemic lupus erythematosus Mechanisms of Action Corticosteroids Glucocorticoids increase or decrease transcription of many genes to alter the synthesis of proteins that regulate their many physiologic effects (eg, enzymes, transport proteins, structural proteins). Metabolic effects do not occur for at least 45 to 60 minutes because of the time required for protein synthesis. Several hours or days may be needed for full production of proteins. Because the genes vary in different types of body cells, glucocorticoid effects also vary, depending on the specific cells being targeted. For example, supraphysiologic concentrations of glucocorticoids induce the synthesis of lipolytic and proteolytic enzymes and other specific proteins in various tissues. Overall, corticosteroids have multiple mechanisms of action and effects (Fig. 1), including the following:6,7 Inhibiting arachidonic acid metabolism. Normally, when a body cell is injured or activated by various stimuli, the enzyme phospholipase A2 causes the phospholipids in cell membranes to release arachidonic acid. Free arachidonic acid is then metabolized to produce proinflammatory prostaglandins and leukotrienes. At sites of tissue injury or inflammation, corticosteroids induce the synthesis of proteins that suppress the activation of phospholipase A2. This action, in turn, decreases the release of arachidonic acid and the formation of prostaglandins and leukotrienes. Strengthening or stabilizing biologic membranes. Two biologic membranes are especially important in inflammatory processes. Stabilization of cell membranes inhibits the release of arachidonic acid and production of prostaglandins and leukotrienes, as described above. Stabilization of lysosomal membranes inhibits release of bradykinin, histamine, enzymes, and perhaps other substances from lysosomes. (Lysosomes are intracellular structures that contain inflammatory chemical mediators and enzymes that destroy cellular debris and phagocytized pathogens.) This reduces capillary permeability and thus prevents leakage of fluid into the injured area and development of edema. It also reduces the chemicals that normally cause vasodilation and tissue irritation. Inhibiting the production of interleukin-1, tumor necrosis factor, and other cytokines. This action also contributes to the antiinflammatory and immunosuppressant effects of glucocorticoids. Impairing phagocytosis. The drugs inhibit the ability of phagocytic cells to leave the bloodstream and move into the injured or inflamed tissue. Impairing lymphocytes. The drugs inhibit the ability of these immune cells to increase in number and perform their functions. Inhibiting tissue repair. The drugs inhibit the growth of new capillaries, fibroblasts, and collagen needed for tissue repair. Fig.1 Inflammatory processes and anti-inflammatory actions of corticosteroids. Cellular responses to injury include the following: Phospholipid in the cell membrane is acted on by phospholipase to release arachidonic acid. Metabolism of arachidonic acid produces the inflammatory mediators prostaglandins and leukotrienes; Lysosomal membrane breaks down and releases inflammatory chemicals (eg, histamine, bradykinin, intracellular digestive enzymes). White blood cells (WBCs) are drawn to the area and release inflammatory cytokines (eg, interleukin-1 [IL-1], tumor necrosis factor [TNF] alpha). Overall, corticosteroid drugs act to inhibit the release, formation, or activation of various inflammatory mediators.7 Corticosteroids are extensively used to treat many different disorders. Except for replacement therapy in deficiency states, the use of corticosteroids is largely empiric. Because the drugs affect virtually every aspect of inflammatory and immune responses, they are used in the treatment of a broad spectrum of diseases with an inflammatory or immunologic component.1,3 Corticosteroid Therapy in Clinical Practice Corticosteroids and gastrointestinal conditions Corticosteroids are useful in very few specific gastrointestinal and hepatic conditions. These include inflammatory bowel diseases (ulcerative colitis, Crohn‘s disease), autoimmune hepatitis, severe alcoholic hepatitis, and certain other rare conditions like collagenous sprue/eosinophlic gastroenteritis. Corticosteroids are ―double-edged swords‖ and while useful, have potential dangers especially with prolonged use. Other than the well known systemic side effects of corticosteroids, specific effects in the gastrointestinal tract include an increased incidence of complications of peptic ulcer disease and reactivation of hepatitis B.3 Corticosteroids in rheumatological conditions In patients with acute gout affecting one or two joints, intraarticular injection of a long-acting corticosteroid preparation, such as methylprednisolone, triamcinolone acetonide or triamcinolone hexatonide, will control symptoms within 1 to 2 days. It should be given only when the diagnosis is confirmed and infection has been excluded. Patients with polyarticular gout who have a suboptimal or delayed response to oral non-steroidal anti-inflammatory drugs often benefit from adjunctive corticosteroid injections into those joints with persistent synovitis.1,7 Corticosteroid therapy is widely used in the management of connective tissue diseases such as systemic lupus erythematosus, polymyositis/dermatomyositis and systemic vasculitis. Corticosteroids can been used as intravenous pulses to obtain rapid control of disease activity in ill patients. More often varying dosages of oral prednisolone are used depending on the disease condition, its manifestations and disease activity. Based on pathophysiologic and pharmacokinetic data, standardization of the terms such as "low" or "high" dose has been recently proposed to minimize problems in interpretation of these generally used terms. As there are specific indications for corticosteroids in these multi-systemic disorders, they are best managed in, or comanaged with, a specialist practice.3 Corticosteroid in Respiratory diseases Corticosteroids are commonly used in the treatment of asthma because of their anti-inflammatory effects. In addition, corticosteroids increase the effects of adrenergic bronchodilators to prevent or treat bronchoconstriction and bronchospasm. Other condition use steroid in respiratory disorders such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and inflammatory disorders of nasal mucosa (rhinitis). In severe asthma there is airway obstruction and airway inflammation. In order to reduce the inflammation systemic corticosteroids must be included as part of the regimen in all patients with acute severe asthma. Receptor-binding affinities of lung corticosteroid receptors are reduced in the face of airway inflammation, that‘s why multiple daily dosing of systemic corticosteroids for the initial therapy of acute asthma exacerbations appears necessary. As in severe COPD exacerbations, the optimal dose and duration of steroids in severe asthma exacerbations are unknown. The oral and IV routes are equally effective, so that the oral route may be used if patients can swallow. Regarding the duration a 7 day-day course in adults has been found to be as effective as 14-day course.8 Corticosteroids in Hemato-oncology Corticosteroids are commonly used in the treatment of lymphomas, lymphocytic leukemias, and multiple myeloma. In these disorders, corticosteroids inhibit cell reproduction and are cytotoxic to lymphocytes. In addition to their anticancer effects in hematologic malignancies, corticosteroids are beneficial in treatment of several signs and symptoms that often accompany cancer, although the mechanisms of action are unknown and drug/dosage regimens vary widely. Corticosteroids are used to treat anorexia; nausea and vomiting; cerebral edema and inflammation associated with brain metastases or radiation of the head; spinal cord compression; pain and edema related to pressure on nerves or bone metastases; graft-versus-host disease after bone marrow transplantation; and other disorders that occur in clients with cancer. Clients tend to feel better when taking corticosteroids, although the basic disease process may be unchanged.1,3 Corticosteroids in other conditions There are many theoretical benefits of using steroids in patients with anaphylaxis. However, there are no placebo-controlled trials to confirm these assumed benefits of steroids in anaphylaxis. The use of prednisone 1 mg/kg up to 50 mg orally or hydrocortisone 1.5-3 mg/kg IV is suggested.3,4 Suppression of the HPA axis may occur with corticosteroid therapy and may lead to life-threatening inability to increase cortisol secretion when needed to cope with stress. It is most likely to occur with abrupt withdrawal of systemic corticosteroid drugs. The risk of HPA suppression is high with systemic drugs given for more than a few days, although clients vary in degree and duration of suppression with comparable doses, and the minimum dose and duration of therapy that cause suppression are unknown. When corticosteroids are given for replacement therapy, adrenal insufficiency is lifelong, and drug administration must be continued. When the drugs are given for purposes other than replacement and then discontinued, the HPA axis usually recovers within several weeks to months, but recovery may take a year. Several strategies have been developed to minimize HPA suppression and risks of acute adrenal insufficiency, including:9 Administering a systemic corticosteroid during highstress situations (eg, moderate or severe illness, trauma, surgery) to clients who have received pharmacologic doses for 2 weeks within the previous year or who receive long-term systemic therapy (ie, are steroid dependent) Giving short courses of systemic therapy for acute disorders, such as asthma attacks, then decreasing the dose or stopping the drug within a few days Gradually tapering the dose of any systemic corticosteroid. Although specific guidelines for tapering dosage have not been developed, higher doses and longer durations of administration in general require slower tapering, possibly over several weeks. The goal of tapering may be to stop the drug or to decrease the dosage to the lowest effective amount. Using local rather than systemic therapy when possible, alone or in combination with low doses of systemic drugs. Numerous preparations are available fo local application, including aerosols for oral or nasal inhalation; formulations for topical application to the skin, eyes, and ears; and drugs for intra-articular injections. Using Alternate-day therapy (ADT), which involves titrating the daily dose to the lowest effective maintenance level, then giving a double dose every other day. Conclusions The use of corticosteroids started some 50 years ago. These drugs were widely used but sometimes without strong indications. Most of the uses of corticosteroids have been in the fields of rheumatology, orthopaedics dermatology, oncology, respiratory medicine, otorhinolaryngology (ENT) and ophthalmology. The latest development towards greater safety of corticosteroids usage with preservation of full efficacy is channeled at the glucocorticoid receptor so that reduced potency in side effects is possible. These new insights may pave the way for novel, safer therapies that retain the efficacy of currently prescribed steroids. Until then we will have to prescribe sensibly and rationalize the indications, dose, duration and preparation of the right steroid to the right purpose. References 1. Shaikh S, Verma H, Yadav N, Jauhari M, and Bullangowda J. Applications of Steroid in Clinical Practice:A Review. 2012;(p) 1-11. 2. L. L. Bruton, J. S. Lazo, and K. L. Parker, Goodman & Gilman’S the Pharmacological Basis of Therapeutics, 11th edition, 2006. 3. V. K. Grover, R. Babu, and S. P. S. Bedi, ―Steroid therapy current indications in practice,‖ International Jugglers’ Association, 2007; 51(5); 389–339. 4. Raalte D.H and Diamant M. Steroid diabetes: from mechanism to treatment?. 2014 ;72(2); 62-72. 5. Tole JW, Lieberman P. Biphasic anaphylaxis: review of incidence, clinical predictors, and observation recommendations. Immunol Allergy Clin North Am. 2007;27:309-26. 6. Gupta P and Bhatia V. Corticosteroid Physiology and Principles of Therapy. Indian J Pediatr 2008; 75 (10) : 1039-1044. 7. Rhen T and Cidlowski J.A. Antiinflammatory Action of Glucocorticoids — New Mechanisms for Old Drugs. N Engl J Med 2005;353:1711-23. 8. Sin, D. D., Man, J., Sharpe, H., Gan, W. Q. and Paul Man, S. F.Pharmacological management to reduce exacerbations in adults with asthma: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Medical Association. 2004; 292(3), 367–376. 9. Hoffmeister, A. M. dan Tietze, K. J. Adrenocortical dysfunction and clinical use of steroids. In E. T. Herfindal & D. R. Gourley (Eds.), Textbook of therapeutics: Drug and disease management (7th ed., pp. 305–324). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2000. MANAGEMENT NUTRITION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE Suheir Muzakkir, Maimun Syukri Divisi Ginjal dan Hipertensi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD. dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Abstrak Setiap individu baik dalam keadaan sehat ataupun sakit memerlukan nutrisi untuk mempertahankan homeostasis metabolisme tubuhnya. Pada keadaan sehat maka kebutuhan nutrisi akan seimbang dengan asupannya dari luar. Meningkatnya kebutuhan nutrient akibat sesuatu sebab, tanpa diikuti oleh asupan yang cukup akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam metabolisme tubuh, dimana katabolisme akan lebih besar dari anabolisme dan akan menyebabkan keadaan malnutrisi. Malnutrisi sering terjadi pada pasien-pasien yang dirawat di Bagian Penyakit Dalam, baik yang menderita penyakit kronis ataupun terjadi pada pasien yang mengalami penyakit akut. Pada kegagalan fungsi ginjal yang telah berlangsung lama pada penderita dengan gagal ginjal kronik, diet disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjaga kecukupan asupan makanan dan nutrisi seimbang tanpa mengganggu fungsi ginjal, dan meminimalkan kerusakan ginjal. Kata Kunci: Anemia, Gagal Ginjal Kronik, Nutrisi Abstract Each individual well in a healthy condition or illness requires nutrients to maintain her metabolism homeostasis. In a healthy state the nutritional needs will be balanced with the intake from the outside. The increased nutrient requirements due to any reason, without being followed by a sufficient intake will cause an imbalance in the body's metabolism, which will be larger than the catabolism and anabolism will lead to malnutrition. Malnutrition is common in patients who were treated at the Department of Internal Medicine, both suffering from chronic diseases or in patients who experience an acute illness. On the failure of kidney function that has lasted a long time in patients with chronic renal failure, a diet tailored to the need to maintain adequate food intake and nutrition balance Keywords: Anemia, Cronic Kidney Disease, Nutrition Pendahuluan Terapi nutrisi adalah asupan nutrient yang dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan dari seseorang yang tidak normal (atau sakit) dalam upaya mencapai target tertentu (mencegah malnutrisi, mengurangi overweight, dll). Pada keadaan gagal ginjal, ginjal tidak dapat secara memadai mengeluarkan nitrogen dan sisa metabolisme, baik akut, atau kronis fungsi ginjal menurun. Spektrum gejala dan keluhan dari ginjal akut sangat bervariasi mulai dari anuria sampai dengan urin output yang memadai, dan dari periode singkat menurunnya filtrasi glomerulus sampai dengankebutuhan terhadap terapi pengganti ginjal yang berkepanjangan. Untuk mencerminkan keragaman ini, the Acute Dialysis Quality Initiative Group merekomendasikan perubahan dalam terminologi dari gagal ginjal akut (acute kidney injury=AKI) Penyebab utama AKI termasuk sepsis, trauma, hipotensi, pemakaian kontras intravena, obat-obatan, dan sudah ada penyakit ginjal kronis (CKD). Meskipun perbaikan dalam terapi dialisis dan pemberian dukungan nutrisi, mortalitas AKI terus di kisaran 50% -60%. Banyak pedoman yang dipakai untuk mengevaluasi bukti yang mendasari pemberian dukungan nutrisi untuk pasien dengan AKI dan pada pasien penyakit ginjal kronik (PGK). Anemia Yang Disebabkan Oleh Sayuran Pada Penderita CKD Pada pasien atau orang yang didiagnosis dengan PGK, penting bagi mereka untuk memikirkan jenis diet yang cocok dan sesuai dengan keadaan ginjalnya, namun tetap dibutuhkan oleh tubuh. Ada beberapa jenis diet dan metode yang direkomendasikan untuk pasien dengan PGK untuk menunjang kesehatan dan kondisi dari proses pemulihan. Salah satu pilihan metode diet adalah menjadi seorang vegetarian. Hal ini disebabkan bahwa salah satu program dari diet ginjal adalah untuk mengontrol atau membatasi masukan protein. Bagaimanapun, tubuh tetap memiliki kebutuhan untuk protein dalam jumlah yang cukup, terutama bagi pasien PGK yang rutin menjalani hemodialisis. Namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi vegetarian atau orang yang ingin menjadi vegetarian selama proses penyembuhan. Dengan konsultasi bersama konsultan diet, mereka dapat mengkombinasikan jenis makanan dan merencanakan menu yang sesuai dengan kebutuhan ginjalnyaa. Keuntungan dari diet vegetarian pada panderita PGK , sebagai sumber protein nabati adalah : - Protenuria yang rendah Rendahnya hambatan untuk laju filtrasi glumerolus (LGF) dan aliran darah ginjal Kerusakan jaringan ginjal lebih rendah dibandingkan dengan protein hewani Kecenderungan untuk terbentuk kista ginjal lebih rendah Meningkatkan lemak dalam darah Sumber protein yang berasal dari daging, ikan dan hewan lainnya dapat digantikan dari sumber tumbuhan yang memiliki protein yang sama seperti kedelai, tahu, kacang – kacangan , gandum , dan lainlainnya. Memodifikasi sumber protein lebih efektif dibandingkan mengurangi asupan protein tubuh, terutama pada pasien PGK dengan kegagalan ginjal yang progresif Akan tetapi, diluar dari konteks kebutuhan nutrisi dan protein tubuh kita, ginjal juga dapat mengalami masalah dari akibat diet, misalnya terjadinya anemia. Hal ini disebabkan karena vegetarian tidak mendapatkan asupan vitamin B 12 dalam diet vegetariannya, dimana B 12 didapatkan dari sumber hewani seperti daging, ikan, telur dan susu. Defisiensi Vitamin B12 dapat menyebabkan gangguan sumsum tulang dari saraf spinal untuk memproduksi sel darah merah ,dimana selama sel darah merah ada, zat besi , vitamin B 12 dan asam folat tetap ada. Apabila terjadi kekurangan salah satu dari produk ini, maka produksi sel darh merah akan terganggu dan anemia akan terjadi. Anemia yang terjadi akibat kekurangan vitamin B12 disebut anemia pernisiosa. Dalam hal ini, pasien dengan gangguan ginjal yang mengalami anemia akibat gangguan sekresi hormon eritropoetin dari ginjal, apabila menjalani diet vegetarian, akan memiliki resiko besar mengalami anemia berat. Pasien yang menjalani diet vegetarian yang tidak mengkonsumsi makanan dari sumber hewani dapat menambahkan supplement vitamin B 12 dalam program dietnya untuk menjaga agar kebutuhan vitamin B12 nya tercukupi. Makanan Yang Sebaiknya Dihindari Untuk Menjaga Kesehatan Ginjal Makanan yang berbahaya bagi ginjal sering dikonsumsi dan mudah ditemukan. Banyak yang tidak menyadarinya sampai mereka mengalami gangguan ginjal. Dengan mengetahui lebih banyak makanan yang berbahaya bagi ginjal, masyarakat seharusnya lebih bisa menghindari makanan yang memiliki dampak buruk bagi ginjal. Makanan tidak hanya memberikan manfaat sebagai sumber nutrisi dan memiliki fungsi yang baik bagi kesehatan, tetapi juga memiliki dampak terhadap kesehatan ginjal kita. Makanan yang berbahaya bagi ginjal umumnya berasal dari sumber hewani. Pada dasarnya, protein sangat berguna untuk mempertahankan kesehatan tubuh, Akan tetapi, konsumsi yang berlebihan dapat membahayakan ginjal kita. Sumber protein yang berasal dari hewan seperti daging dan ikan mengandung pospor dan dan purine. Kelebihan dari dua zat tersebut akan membahayakan ginjal. Purin dapat dapat meningkatkan keasaman darah dan nyeri di sendi dan akhirnya akan mengakibatkan efek di ginjal. Natrium yang terlalu tinggi juga akan memberikan efek yang tidak baik buat ginjal karena dapat meningkatkan tekanan darah sehingga akan merusak ginjal. Jumlah natrium yang tinggi ditemukan dalam garam, oleh karena itu kandungan garam harus dibatasi. Hindari makanan yang terlalu asin. Makanan dan minuman dalam kemasan biasanya memiliki kandungan natrium yang tinggi di setiap kemasannya. Oleh karena itu, makanan dan minuman kemasan memiliki konsentrasi natrium yang tinggi. Disamping makanan, ada juga minuman seperti teh, kopi , wine dan alkohol. Jenis minuman ini dapat menyebabkan penimbunan batu di ginjal. Makanan yang berbahaya lainnya juga didapatkan pada makanan dengan kadar kalium yang tinggi. Terlalu banyak kalium akan meningkatkan kadar cairan di tubuh dan akhirnya menghancurkan sistem kerja ginjal. Makanan yang mengandung phospor tinggi juga merupakan salah satu jenis makanan yang membahayakan ginjal. Makanan tinggi phospor biasanya ditemukan pada makanan dengan kandungan coklat, susu, kacang, dan bermacam – macam buahan. Kelebihan jumlah fosfor dalam tubuh dapat menghambat penyerapan kalsium yang dapat mempengaruhi ginjal. Untuk membantu kerja ginjal yang optimal, anda harus menjalani hidup sehat dengan mengkonsumsi banyak air putih, dan harus memperhatikan makanan yang berbahaya bagi ginjal Diet Pada Penderita Hipertensi, Hiperkolesterolemia dan Hiperurisemia Resep sederhana untuk meningkatkan kondisi tubuh adalah dengan makan dan olahraga yang tidak berlebihan. Akan tetapi, apa yang terjadi adalah salah satu nya tidak melengkapi yang lain. Selain itu banyaknya penyakit degenaratif membuat keadaan sulit untuk diobati. Adanya keanekaragaman metabolisme manusia menyebabkan meningkatnya resiko penyakit. Banyak orang menderita darah tinggi, sementara yang lainnya mengalami peningkatan kolesterol dalam darah yang akan menyebabkan penyakit jantung koroner Diet Rendah Garam Untuk pasien dengan hipertensi (peningkatan tekanan darah), atau penyakit ginjal, hanya sedikit masukan garam yang dibutuhkan. Pengurangan jumlah garam tidak diterapkan pada seluruh jenis garam, namun pengurangan itu maksudnya adalah mengurangi jumlah dari garam atau natrium klorida sebagai tambahan dalam makanan terutama makanan yang mengandung MSG dan sodium karbonat Direkomendasikan pada pasien untuk mengkonsumsi garam ( garam iodium) tidak lebih dari 6 gram per hari, setara dengan 1 sendok teh. Diet diatur untuk membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi dan mengurangi penumpukan dari garam atau air di jaringan tubuh. Lebih mudah untuk menjalani diet ini, karena hanya mengubah diet sesuai penyakit, mengurangi kalori, konsumsi protein dan mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh. Untuk memudahkan diet, cobalah untuk : - Jangan meletakkan garam di meja makan - Memilih sayuran segar. Makanan kalengan mengandung banyak garam. Jika ingin mengkonsumsi sayuran kalengan, sebaiknya dicuci dahulu dengan air sebelum dimakan untuk mengurangi garam yang terkandung dalam makanan tersebut - Memilih buah segar, karena buah segar umumnya memiliki kandungan natrium yang rendah, namun tinggi akan kalium - Menggunakan penyedap alami pada makanan seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, garam, gula atau cuka - Memilih makanan ringan sejenis kacang , biskuit atau makanan ringan lain yang tidak mengandung banyak garam - Hindari kecap, MSG, touco dalam makanan yang anda konsumsi - Diet rendah kolesterol Diet rendah kolesterol biasanya dijalani pada pasien yang tinggi kolesterol dan pasien dengan gangguan jantung. Sesuai dengan mekanismenya, kolesterol yang tinggi akan memicu penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan resiko untuk serangan jantung. Pada dasarnya, tubuh manusia membutuhkan kolesterol sebagai bagian untuk pertahanan sel seperti vitamin D, hormon anabolik, dan empedu. Kegunaan diet ini adalah untuk menjaga kecukupan jumlah kolesterol di dalam darah , yang secara tidak langsung bersamaan dengan proses penurunan berat badan. Dalam diet, disarankan makan dalam jumlah sedikit tapi sering. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh, yang umumnya ditemukan dalam daging sapi, daging domba, daging babi, susu, cream , mentega, kuning telur, dan keju. Disamping dari bahaya lemah jenuh, terdapat ancaman bahaya lemak yang bisa didapatkan dari sayuran, seperti minyak kacang dan dan minyak kelapa. Minyak ini sering dimanfaatkan dan disalahpersepsikan oleh para pedagang dalam penjualan minyak goreng. Masyarakat dikenalkan minyak goreng yang terbuat dari nabati seperti minyak kacang, minyak biji kapas, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak biji matahari. Memang benar bahwa minyak nabati yang berasal dari tumbuhan mengandung lemak tidak jenuh dalam kandungannya. Akan tetapi sedikit yang mengetahui bahwa lemak jenuh tetap akan ada saat minyak tersebut masuk dalam proses pencernaan. Bagaimanapun meyakinkannya minyak goreng nabati karena mengandung lemak tidak jenuh, namun saat ia masuk kedalam tubuh manusia, akibat reaksi alami proses pencernaan , pada akhirnya lemak tak jenuh tersebut akan berubah menjadi asam lemak jenuh. Fokusnya adalah mengurangi makanan berminyak. Apabila hal itu telah terjadi, segera imbangi dengan olahraga, sehingga lemak jenuh akan dibakar menjadi energi. Mulailah untuk memilih makanan dengan tinggi karbohidrat atau serat seperti roti, nasi, gandum. Ayam dapat dikonsumsi tanpa kulit. Untuk tambahan dapat ditambah dengan putih telur. Jangan lupa mengurangi makanan yang kaya akan gula seperti es krim, coklat, minuman ringan dan lainnya. Diet Purin Mengurangi konsumsi purin diperlukan pada pasien dengan gangguan asam urat, dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan diet. Diet rendah purin bertujuan untuk mengurangi makanan kaya akan purin seperti sarden, kale, jeroan,bayam. Jika normal kebutuhan purin berkisar antara 600 – 1000 mg, pada program diet purin dikurangi sekitar 120 – 150 mg. Dengan diet purin, kandungan purin bisa berkurang di dalam darah dan meningkatkan pengeluaran asam urat. Diet purin dapat dilakukan dengan tips berikut : - Mengonsumsi kalori, protein, mineral, dan vitamin sesuai dengan kebutuhan tubuh - Dengan menggunakan makanan tinggi karbohidrat, dapat mengurangi asam urat dari urin. Karbohidrat kompleks yang dibutuhkan lebih dari 100 g/ hari. karbohidrat kompleks terdapat pada ubi, roti, dan kentang. - Diet rendah lemak juga dibutuhkan karena lemak memiliki kecenderungan untuk menghambat pengeluaran asam urat - Disamping diet rendah lemak, diet rendah protein juga dibutuhkan, karena protein bisa meningkatkan level asam urat dalam darah. Jumlah protein yang direkomendasikan untuk pasien maksimal berkisar 50 – 70 g/hari - Untuk mengurangi kelebihan asam urat dan mencegah penumpukan asam urat di ginjal, cobalah untuk minum 2 – 3liter/ hari - Jauhi alkohol, karena alkohol dapat mencegah pelepasan asam urat dalam tubuh Buah dan Pasien Dengan Penyakit Ginjal Berdasarkan paradigma yang menunjukkan bahwa buah-buahan mampu menyediakan nutrisi terbaik untuk tubuh, masyarakat sering percaya bahwa seseorang yang sedang sakit membutuhkan tambahan buah semasa dalam tahap penyembuhan. Tapi sayangnya tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan buah-buahan . Beberapa penyakit malah bisa bertambah buruk akibat buah- buahan, salah satunya adalah penyakit ginjal. Bertambahnya asam akan mengganggu sistem kerja ginjal, terutama ginjal yang telah mengalami perburukan dibandingkan ginjal pada orang yang sehat. Jika kita mengkonsumsi buah yang mengandung banyak zat asam, ada kemungkinan ginjal akan mengalami inflamasi, infeksi atau bahkan akan mencetuskan terjadinya batu ginjal. Melihat hal ini, kita harus melakukan konsultasi kesehatan dengan para ahli secara rutin pada pasien dengan penyakit ginjal. Hal ini dimaksudkan kita harus meningkatkan kondisi ginjal dibandingkan mengabaikannya akibat kerja yang berlebihan akibat asupan buah – buahan. Bagaimana Seharusnya Makan Penderita Gagal Ginjal Kronik? Ada kegagalan fungsi ginjal yang telah berlangsung lama pada penderita dengan gagal ginjal kronik. Diet disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjaga kecukupan asupan makanan dan nutrisi seimbang tanpa mengganggu fungsi ginjal, dan meminimalkan kerusakan ginjal. Diet pada pasien dengan gagal ginjal kronik pada dasarnya memperlambat penurunan fungsi ginjal dengan cara mengurangi kerja nefron dan mengurangi kadar urea darah. Diet Yang Dibutuhkan Bagi Penderita PGK Normalnya pasien dengan PGK memerlukan 35 kkal/kgBB. Pada pasien geriatri ( lebih dari 60 tahun), kalori yang dibutuhkan adalah 30 kkal/kgBB , sesuai dengan komposisi berikut : - Karbohidrat sebagai sumber energi sebanyak 50 – 60 % dari total kalori - Protein untuk mempertahankan jaringan tubuh dan mengganti kerusakan sel sekitar 0,6 g/KgBB. Jika masukan energi tidak cukup, proteinbisa diberikan sampai 0,75g/Kg. Protein yang diberikan kurang dari normal, oleh karena itu disebut diet rendah protein. Disarankan 50% protein yang dikonsumsi adalah protein hewani . Anda dapat menggantinya dengan protein nabati yan berasal dari kedelai segai variasi menu. - Lemak dibutuhkan untuk energi sebesar 30 %, lebih disarankan lemak tak jenuh. - Kebutuhan cairan disesuaikan dengan jumlah urin output dalam 24 jam ditambah IWL Garam disesuaikan dengan ada tidaknya hipertensi. Sebagaimana proses keseimbangan cairan tubuh . restriksi garam berkisar antara 2,5 – 7,6 g/ hari sampai 1000 – 3000 mg natrium / hari Kalium disesuaikan dengan ada tidaknya hiperkalemia , 40 – 70 meq/ hari Jumlah fosfor yang disarankan ≤ 10 mg/ kg/ hari Kalsium 1400 – 1600 mg/ hari DAFTAR PUSTAKA Cano NJM, Aparico M, Brandori G, Carero JJ, Cianciaruso B, Fiaccadusi E et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition : Adult Renal Failure. Clinical Nutrition 28 (2009) 401–414. Brown RO, Charlene Compher, and the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.P.E.N. Clinical Guidelines: Nutrition Support in Adult Acute and Chronic Renal Failure JPEN J Parenter Enteral Nut 2010 34: 366. Kondrup J, Allison S.P, Elia M, Vella B and Plauth M. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clinical Nutrition (2003) 22(4): 415–421 Locatelli F, Fouque D, Heimburger O, Drueke T.B, Cannata J.B, Horl W.H, et al. Nutritional status in dialysis patients : a European consensus. Nephrol Dial Transplant (2002) 17:563-572. Lochsa H, Allisonb S.P, Meierc R, Pirlicha M, Kondrupd J, Schneidere St, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, Definitions and General Topics. Clinical Nutrition (2006) 25, 180–186. Singer P, Berger M.M, Berghe G.V, Biolo G, Calder P, Forbes A, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care. Clinical Nutrition 28 (2009) 387–400 KETO ACID IN CHRONIC KIDNEY DISEASE Abdullah Divisi Ginjal dan Hipertensi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD. dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Pendahuluan Penyakit ginjal kronis (PGK) adalah suatu sindroma klinis dikarenakan penurunan fungsi ginjal yang menetap akibat kerusakan nefron. Proses penurunan ini berjalan secara kronis dan progresif sehingga pada akhirnya akan terjadi penyakit ginjal terminal (PGT), dan pada saat ini diperlukan pengobatan pengganti ginjal. Residual Renal Function (RRF) penting pada pasien penyakit ginjal kronik (PGK). Temuan yang baru menunjukkan bahwa RRF (dibandingkan RRF plus dialisis) merupakan prediktor yang esensial mengenai kelangsungan hidup pasien dialisis. Pada pasien dialisis, selain kecukupan dialisis, RRF berperan dalam menghambat inflamasi, mempertahankan status nutrisi, mencegah hipertrofi ventrikel kiri, menjaga keseimbangan antara kalsium dan fosfat serum, dan menurunkan angka peritonitis. Pemahaman bahwa dialisis tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi ginjal menggarisbawahi pentingnya melindungi RRF pada pasien PGK, bahkan setelah dialisis. Asupan Rendah Protein dan Progresifitas Kemunduran Fungsi Ginjal Pada Penderita PGK Ada berbagai macam laporan penelitian tentang pengaruh pembatasan protein pada diet dengan progresifitas PGK. Hampir semua penelitian pada DM tipe1 menunjukkan adanya perbaikan dalam pemeliharaan ginjal dengan diet rendah protein. Fouque dan Pedrini dkk dalam penelitian meta analisisnya menunjukkan bahwa diet dengan rendah protein dapat menahan progresifitas PGK secara bermakna pada penderita DM. Maschio dkk (1982) merupakan salah satu peneliti awal yang menunjukkan manfaat pembatasan protein (0.6gram/kgBB/hari) terhadap penurunan progresivitas faal ginjal pada penderita dengan kreatinin serum1.5- 5.4mg/Dl .Rosman(1984) pada pengamatan selama 4 tahun mendapatkan pula manfaat dari diet rendah protein terhadap penurunan fungsi ginjal. Ihle dkk (1989) pada penelitiannya terhadap 64 penderita dengan kreatinin serum 4.0 - 11.0 mg/dl selama 18 bulan mendapatkan hanya 6% penderita dengan diet protein 0.4gram/kgBB/hari jatuh dalam PGT dibanding 27% penderita dengan diet bebas protein. Juga didapatkan perbedaan bermakna dalam penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG). Penelitian The Modification of Die in Renal Disease Study (MDRD Trial) merupakan penelitian multicenter besar yang menilai manfaat penatalaksanaan diet rendah protein terhadap hambatan laju progresifitas kemunduran fungsi ginjal pada penderita PGK non DM. Dibandingkan antara kelompok dengan diet protein 0.58 gram/kgBB/hari terhadap kelompok dengan diet normal protein 1,3gram/kgBB/hari pada penderita dengan laju filtrasi glomerulus 25-55ml/menit/1,73m2 pada kelompok A.Sedang pada kelompok B dibandingkan antara diet protein 0,58 gram/kgBB/hari dengan diet 0,28 gram/kgBB/hari ditambah dengan 2 ketoanalog pada penderita dengan LFG 13-24 ml/menit/1,73m . Dalam observasi selama 2,2 tahun dengan pemeriksaan pembersihan kreatinin setiap 4 bulan terdapat beberapa kontroversi mengenai pengaruh diet rendah protein terhadap laju progresifitas penurunan fungsi ginjal, tergantung saat dilakukan observasi. Tetapi dari laporan MDRD Trial serta meta-analisis dan analisis sekundernya disimpulkan adanya korelasi yang kuat antara asupan protein dan kemampuan untuk memperlambat penurunan fungsi ginjal penderita PGK utamanya dengan LFG < 25ml/menit/1,73m2 dan cukup aman terhadap parameter nutrisi. Keto Acid dan Manfaatnya pada Penderita PGK Tujuan penatalaksanaan nutrisi penderita PGK adalah mencegah penumpukan nitrogen hasil metabolisme tubuh : 1. Mempertahankan status gizi yang optimal agar tidak terjadi malnutrisi dan agar kualitas hidup penderita sebaik mungkin 2. Mempertahankan atau menghambat progresifitas kemunduran faal ginjal 3. Mengurangi atau mencegah gejala uremi dan gangguan metabolisme pada PGK Keto acid sering ditambahkan pada diet rendah protein pada pasien PGK predialisis, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tetapi juga karena pengaruh independen terhadap pemeliharaan RRF. Sebelumnya, belum terdapat studi acak dan prospektif yang mengevaluasi pengaruh diet rendah protein dengan atau tanpa keto acid terhadap status nutrisi dan RRF pada pasien dengan dialisis peritoneal. Studi secara acak dilakukan untuk mengetahui apakah diet rendah protein dengan atau tanpa keto acid aman dan dengan dipertahankannya RRF selama dialisis peritoneal. Pertama-tama dilakukan studi keseimbangan nitrogen untuk menilai keamanan diet rendah protein pada pasien (n= 34) dengan dialisis peritoneal. Pasien secara acak mendapat diet 1,2 g, 0,9 g, atau 0,6 g protein/kgBB ideal/hari selama 10 hari. Kemudian 60 pasien dengan dialisis peritoneal stabil secara acak mendapat diet rendah protein (LP: 0,6-0,8 g/kgBB ideal/hari), diet rendah protein yang ditambah suplementasi keto acid (sLP: 0,6-0,8 g/kgBB ideal/hari ditambah 0,12 g/kgBB ideal keto acid), diet tinggi protein (HP: 1-1,2 g/kgBB ideal/hari). Berdasarkan studi tersebut, beberapa hal yang merupakan hasil studi diantaranya adalah: Keseimbangan nitrogen positif atau netral dicapai pada 3 kelompok (pada studi keseimbangan nitrogen). RRF stabil pada pasien kelompok sLP (3,84 ± 2,17 menjadi 3,39 ± 3,23 mL/menit/1,73 m2, p= tidak bermakna) sementara RRF menurun pada kelompok LP (4,02 ± 2,49 menjadi 2,29 ± 1,72 mL/menit/1,73 m2, p<0,05) dan HP (4,25 ± 2,34 menjadi 2,55 ± 2,29 mL/menit/1,73 m2, p<0,05). Tidak terdapat perubahan terhadap status nutrisi pada ketiga kelompok selama follow up. Dari studi ini disimpulkan bahwa diet yang mengandung protein 0,6-0,8 g/kgBB ideal/hari aman, dan bila dikombinasikan dengan keto acid, berkaitan dengan perbaikan dalam dipertahankannya RRF pada pasien dialisis peritoneal yang relatif baru tanpa malnutrisi atau inflamasi yang bermakna. Suplemen Keto analogue/ Keto acid Menghambat Progresivitas Penyakit Ginjal Kronik Sebuah penelitian terbaru berikut ini menunjukkan bahwa diet sangat rendah protein dengan suplementasi ketoanaloque/ketoacid selain aman ternyata dapat menghambat progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Penelitian yang dilakukan di University of Medicine and Pharmacy in Bucharest, Romania, ini merupakan penelitian prospektif dengan desain acak dengan pembanding, yang bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan efikasi dari suplemen ketoanaloque versus diet rendah protein konvensional. Subjek adalah pasien ginjal kronik tanpa diabetes dengan estimasi nilai laju filtrasi glomerulus (LFG) kurang dari 30 mL/menit/1,73 m2, proteinuria <1g/g kreatinin urin, status nutrisi dan kepatuhan diet yang baik untuk menjalani fase diet rendah protein. Pada bulan ke-3 dilakukan pemisahan pada pasien secara acak, di mana dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan suplemen ketoanaloque (1 kapsul/5 kgBB dan diet protein nabati 0,3 g/kgBB/hari) atau kelompok yang terus menjalani diet rendah protein konvensional (0,6 gram protein/kgBB/hari) hingga bulan ke-15.Sejumlah 207 pasien memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya dilakukan evaluasi waktu dimulainya terapi pengganti ginjal (TPG), yaitu dialisis atau transplantasi, atau terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) >50%. Hasil evaluasi setelah bulan ke-15 adalah jumlah pasien yang mulai menjalani TPG atau mengalami penurunan nilai LFG>50% pada kelompok suplemen ketoanaloque secarasignifikan lebih rendah (13% vs 42%) jika dibandingkan kelompok kontrol (p<0,001). Perbedaan antara dua kelompok adalah 10%. Dari analisis Kaplan-Meier, probabilitas kumulatif untuk terjadinya TPG atau turunnya nilai LFG>50% pada tahun pertama juga lebih rendah pada kelompok suplemen ketoanaloque (12% vs 39%). Probabilitas untuk terjadinya TPG atau penurunan LFG>50% bahkan juga lebih rendah setelah dilakukan penyesuaian berbagai faktor yang dapat mempengaruhi (estimasi LFG, indeks massa tubuh, C-reactive protein(CRP), dan terapi angiotensin–converting enzyme inhibitor [ACEI]/angiotensin receptor blocker [ARB]). adjusted hazard ratio, 0,10; 95% CI 0,05 s/d 0,20. Efikasi dari suplemen ketoanaloque paling tinggi pada pasien yang memiliki nilai LFG < 20 mL/menit. Pada kelompok suplemen ketoanaloque terjadi perbaikan kondisi metabolik yang abnormal (metabolisme kalsium-fosfat, bikarbonat). Suplementasi ketoanaloque ditoleransi dengan baik oleh pasien, tidak dilaporkan efek samping bermakna atau kejadian fatal akibat suplemen ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa suplementasi ketoanaloque dapat diberikan secara aman dan bermanfaat dalam memperlambat progresivitas kerusakan ginjal. Hasil penelitian ini dipublikasikan secara online dalam Journal of the American Society of Nephrology pada bulan Januari 2016. Daftar Pustaka : 1. Jiang N, Qian J, Sun W, Lin A, Cao L, Wang Q, et al. Better preservation of residual renal function in peritoneal dialysis patients treated with a low-protein diet supplemented with keto acids: A prospective, randomized trial. Nephrol Dial Transplant. 2009; 24:2551-8. 2. Teplan V. Supplements of keto acids in patients with chronic renal failure. Nefroloji Dergisi 2004;13(1):3-7. 3. Garneata L and Mircescu G. Effect of low-protein diet supplemented with keto acids on progression of chronic kidney disease. J Ren Nutr. 2013 May;23(3):210-3. doi: 10.1053/j.jrn.2013.01.030. 4. Shah AP, Zadeh K, and Kopple JD. Is there a role for ketoacid supplements in the management of CKD? Am J Kidney Dis. 2015 May;65(5):659-73. doi: 10.1053/j.ajkd.2014.09.029. TATALAKSANA SEPSIS PADA USIA LANJUT Masra Lena Siregar Divisi Penyakit Tropik Infeksi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala – RSUD Dr. Zainoel Abidin Pendahuluan Pertambahan usia pada populasi dunia merupakan pola demografi yang sangat menarik, penting dan terus berlanjut karena berhubungan dengan semua sisi kehidupan sosial, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Sepsis merupakan keadaan yang mengancam jiwa dan berkaitan dengan respon imun terhadap proses infeksi dengan persentase sekitar 20% mengakibatkan kematian di rumah sakit. Insidensi sepsis berat akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan usia dengan rerata usia yang menderita adalah 65 tahun. Penurunan fungsi sistem imun yang diikuti dengan semakin bertambahnya usia merupakan faktor yang meningkatkan terjadinya sepsis pada usia tua (≥ 65 tahun). Pembagian usia tua terdiri dari young elderly dengan kisaran 65-85 tahun dan old elderly (≥ 85 tahun).1 Pasien yang menderita sepsis berkisar 750.000 orang di Amerika Serikat dan sekitar 60% adalah usia ≥ 60 tahun dan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan pertambahan usia dengan insidensi dua kali lipat pada tahun 2030. Insiden sepsis pada semua umur berkisar 3 kasus per 1000 populasi dan akan terus meningkat pada usia >85 tahun sebesar 26,2 kasus per 1000 populasi.2 Bakteremia merupakan penyebab terbanyak infeksi pada usia tua dengan kisaran 40-50% dengan tingkat mortalitas sekitar 40-60% dan akan terus meningkat dengan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif.3 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk melihat perbedaan penting dalam penanganan sepsis pada usia lanjut yang berbeda dengan usia muda. Definisi Sepsis adalah infeksi yang terjadi bersamaan dengan munculnya manifestasi sitemik, sedangkan evere sepsis adalah sepsis yang disertai dengan disfungsi organ atau hipoperfusi organ. Sepsis induced hypotension merupakan penurunan tekanan darah sistolik (TDS) <90 mmHG atau mean arterial pressure (MAP) <70 mmHg atau penurunan TDS >40 mmHg atau kurang dari nilai normal tanpa ada penyebab hipotensi lainnya, sedangkan syok sepsis adalah sepsis induced hypotension yang tidak teratasi dengan resusitasi yang adekuat dan sepsis induced tissue hypoperfusion adalah infeksi yang merangsang terjadinya hipotensi, peningkatan laktat atau oliguria.4 Patofisiologi Perubahan sistem imun tubuh yang dipengaruhi usia dinamakan immunosenesence adalah proses kerusakan respon innate immunity yang meliputi makrofag, netrofil, natural killer (NK) dan sel dendritik sehingga terjadi proses inflamasi yang mengakibatkan sepsis melalui pengkodean yang dilakukan oleh reseptor bakteri untuk mengenali struktur patologi semua mikroorganisme seperti lipopolisakarida (LPS), peptidoglikan, asam lipoethicoic, DNA (deoksiribonucleat acid) bakteri, RNA (ribonucleat acid) bakteri dan glukan. Reseptor yang bersifat soluble seperti mannan akan berikatan dengan lektin dan merangsang terjadinya kaskade komplemen.2 Makrofag dan sel dendrit dikenal sebagai reseptor endotik dan penanda yang berfungsi sebagai fagositosis terhadap mikroorganisme, kemudian disalurkan ke lisosom yang dikenal sebagai major compatibility complex (MHC II) yang terdapat pada permukaan antigen-presenting cells (APC). Reseptor penanda seperti the toll like receptors (TLR) akan meningkatkan jalur tranduksi melalui mitogen-activated protein kinases dan mengaktivasi kerja nuclear factor NF-kB serta menerjemahkan semua kode gen untuk sitokin sehingga akan memicu pelepasan semua mediator proinflamasi termasuk asam arakhidonat (prostglandin) dan sitokin. TNF-alpha merupakan mediator utama yang berespon terhadap bakteri gram negatif yang bekerja secara lokal pada jumlah yang sedikit terutama pada sel endotel dan leukosit, meningkatkan kemampuan untuk membunuh bakteri, meningkatkan permeabilitas, pelepasan interleukin (IL)-1 dan IL-6 dan aktivasi jalur koagulasi melalui peningktan produksi faktor VII juga dilakukan oleh TNF-alpha. Sel hipotalamus akan bekerja melalui perangsangan yang dilakukan oleh reseptor tersebut dalam dosis tinggi sehingga akan menimbulkan demam pada hepatosit dan pelepasam serum protein pada fase akut, selanjutnya akan terjadi depresi miokard, vasodilatasi, efek metabolik seperti hambatan lipase lipoprotein dan peningkatan glukoneogenesis. Pelepasan IL-1, IL-6 yang merangsang pelepasan limfosit T dan Limfosit B, IL-12 yang mempercepat munculnya sel natural killer (NK) dan stimulasi CD8+ lymphocytes juga terjadi pada tahap ini, seperti terlihat pada gambar 1.2,5 Sepsis berhubungan dengan stimulasi sistem imun yang berlangsung terus menerus dan dicetuskan oleh TNF, IL-1 dan IL-12 sehingga menimbulkan systemic inflammatory response syndrome (SIRS) dan menghambat kerja sistem imun yang diaktivasi oleh IL-10 yang dikenal dengan compensative antinflammatory response syndrome (CARS). Infeksi sistemik yang terjadi akan meningkatkan aktivasi netrofil sehingga menyebabkan disfungsi dan kerusakan endotel , pembentukan fibrin, peningkatan permeabilitas, edema interstitial dan penurunan difusi oksigen ke jaringan, kegagalan sumber energi selular dan mengakibatkan kegagalan multi organ yang meliputi gastrointestinal, ginjal, kardiovaskular, sistem saraf pusat, sistem hematopoitik dan hati dan meningkatkan angka mortalitas.6 Gambar 1. Usia dan Patofisiologi Sepsis 2 Sistem imun pada geriatri berbeda dengan dewasa muda. Innate immunity pada usia tua akan menimbulkan atrofi timus, perubahan dari naïve sel T menjadi sel T memori yang berhubungan dengan perubahan sitokin dan peningkatan sel T helper (Th)-2, penurunan fungsi makrofag melalui penurunan sel proinflamasi, peningkatan sel inflamasi dan penurunan aktifitas bakterisidal. Apoptosis yang merupakan proses kematian sel yang dicetuskan melalui perangsangan ekstraseluler dan intraselular yang ditandai dengan perubahan morfologi sel seperti pengecilan sitoplsma, pengrusakan membran, pemadatan kromatin nuklear, fragmentasi kromosom DNA dan pembentukan vesikel-vesikel yang selanjutnya mengalami fagositosis oleh makrofag.7 Proses ini akan meningkat sejalan dengan pertambahan usia dan mengakibatkan gangguan fungsi mitokondria melalui peningkatan sintesa nitrit okside (NO) dan radikal bebas, seperti telihat pada tabel 1.2 Faktor Resiko Faktor resiko terjadinya sepsis pada usia lanjut sangat dipengaruhi oleh penyakit komorbid, paparan instrumen atau prosedur, malnutrisi dan status performance. Status performance meliputi atropi otot, sarkopenia, perubahan respon hormon tropik seperto hormon pertumbuhan, estrogen dan androgen, gangguan neurologi, gangguan regulasi sitokin, perubahan metabolisme protein dan perubahan pola diet. Status imun juga mengalami gangguan yang ditandai dengan mudahnya terserang infeksi dan komplikasi pada penggunaan alat invasif atau penyakit komorbid, sedangkan malnutrisi terjadi karena adanya gangguan penciuman.3 Tabel 1. Perubahan Sistem Imun Pada Geriatri 2 Innate immunity Penurunan fungsi makrofag Penurunan fungsi TLR Penurunan mitogen activated protein kinase Penurunan TNF-α dan IL-6 Peningkatan IL-10 Penurunan aktivitas bakterisidal Sel limfosit T Penurunan sel naïve Penurunan fungsi mitogen-activated protein kinases Penurunan respon sitokin tipe 1 (IL-2, TNF-alpha) Peningkatan respon sitokin tipe 2 (IL-4, IL-10) Sel Limfosit B Penurunan jumlah sel B dan sel plasma Peningkatan imunoglobin polispesifik dengan penurunan produksi sel B 1 Penurunan respon neoantigen Gambaran klinis Gambaran klinis pada usia lanjut berbeda dengan dewasa muda yang ditandai dengan gejala atau tanda SIRS yang minimal, tidak spesifik atau tidak ada seperti cepat lelah, malaise, delirium, confusion dan penurunan nafsu makan atau inkontinensia urin, tidak adanya demam dan sering disertai dengan hipotermia (penurunan suhu tubuh). Sumber infeksi yang terjadi sama seperti usia lainnya mencakup sistem pernapasan, sistem urinarius, gastrointestinal, kulit dan jaringan lunak dengan organisme yang sering ditemukan adalah bakteri gram negatif.3,8 Diagnosa Sepsis ditegakkan sesuai dengan kriteria The surviving sepsis campaign guideline 2012 yang tercantum dalam tabel 2.4 Tabel 2. Diagnosa Sepsis dan Severe Sepsis 4 Sepsis yaitu adanya infeksi atau diduga suatu infeksi diikuti dengan : Variabel Demam (suhu >38,3ºC) atau hipotermia ( suhu < 36ºC) umum Nadi >90 x/menit atau lebih dari 2x batas nilai atas (SIRS) Takipnue Gangguan kesadaran Edema atau balance cairan positif ( >20 ml/kgBB dalam 24 jam) Hiperglikemia ( KGDS > 140 mg/dl atau 7,7 mmol/L) tanpa riwayat Diabetes Mellitus Variabel Leukositosis (leukosit >12.000/uL) atau leukopenia ( leukosit < inflamasi 4000/uL) Leukosit dalam batas normal dengan peningkatan sel batang >10% Peningkatan C reactive protein (CRP) lebih dari 2x batas nilai atas Peningkatan procalcitonin lebih dari 2x batas nilai atas Variabel Hipotensi ( Tekanan darah sistolik/TDS <90 mmHg, MAP <70 hemodinamik mmHg, atau penurunan TDS >40 mmHg pada dewasa atau kurang dari 2x batas nilai bawah) Variabel Hipoksemia (PaO2/ FiO2 <300) disfungsi Oliguria akut ( urine output <0,5 mL/KgBB/jam setelah 2 jam organ mendapatkan resusitasi cairan yang adekuat) Peningkatan serum kreatinin >0,5 mg/dl Gangguan koagulasi ( INR >1,5 atau aPTT >60 detik) Ileus Trombositopenia ( trombosit <100.000/uL) Hiperbilirubinemia ( bilirubin total >4 mg/dl) Variabel Hiperlaktanemia (> 1 mmol/L) perfusi Penurunan pengisian kapiler jaringan Severe sepsis yaitu sepsis yang menyebabkan gangguan hipoperfusi atau disfungsi organ: Hipotensi akibat sepsis Peningkatan laktat lebih dari nilai batas atas normal Urine output <0,5 ml/kgBB/jam lebih dari 2 jam dengan resusitasi yang adekuat Acute Lung Injury dengan PaO2/ FiO2 <250 tanpa pneumonia Acute Lung Injury dengan PaO2/ FiO2 <200 dengan pneumonia Kreatinin serum >2 mg/dl Bilirubin serum >2 mg/dl Trombosit <100.000/uL Koagulopati (INR >1,5) Pembagian klasifikasi berdasarkan grading PIRO( Predisposition, Insult or Infection, Response and Organ Dysfunction) juga menajdi landasan untuk penengakan diagnosa sepsis, seperti terlihat pada tabel 3.9 Tabel 3. Grading PIRO Variabel Gejala klinik Predisposing Usia, jenis kelamin, factor penyakit komorbid, penggunaan steroid atau terapi imunosupresi Infection Lokasi infeksi, tipe infeksi Response Suhu, denyut tekanan darah Organ dysfunction Tekanan darah, output, Glasgow scale (GCS) jantung, urine coma Laboratorium Genetic polymorphism Virulensi, organisme yang resisten Hitung jenis sel leukosit, prothrombin time (PT), Augmented partial thromboplastin time (aPTT), kadar serum laktat , marker sepsis PaO2 /FIO2 , serum kreatinin, serum bilirubin, Jumlah trombosit Penatalaksanaan Penatalaksanaan sepsis pada pasien tua dilakukan berdasarkan guideline yang didasarkan atas patofisiologi penyakitnya meliputi farmakologi, kontrol terhadap sumber penyakit dan terapi suportif seperti pemberian cairan, ventilasi mekanik dan nutrisi. Kontrol terhadap sumber infeksi meliputi drainase abses, membebaskan sumber infeksi tubuh dari kontaminasi mikroba seperti penggunaan kateter. Ventilasi mekanik diindikasikan pada gagal napas berat berdasarkan volume tidal (6 ml/kgBB) sehingga dapat menurunkan mortalitas, durasi penggunaan ventilasi dan IL-6 pada pasien dengan ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).7 Goal Directed Therapy yang telah dibuktikan dari beberapa penelitian membuktikan adanya penurunan mortalitas jika resusitasi dilakukan secepatnya dengan target central venous pressure (CVP) 8-12 mmHg, mean arterial pressure (MAP) >65mmHg, urine output >0.5mL/kg/h dan central venous oxygen saturation >70% yang didapatkan melalui pemberian terapi cairan secara agresif, pemberian dobutamin dan transfusi darah.10 Peningkatan cardiac output (CO) sangat diperlukan pada usia lanjut dengan mempertahankan peningkatan tekanan sistolik karena terjadinya peningkatan denyut jantung yang berhubungan dengan disfungsi diastolik, usia tua dan peningkatan volume preload ventrikel kiri, tetapi harus dilakukan monitoring dengan CVP untuk mempertahankan perfusi jaringan karena usia lanjut sangat rentan untuk terjadinya dehidrasi, seperti telihat pada gambar 2.9 Pemeriksaan kultur harus dilakukan sesegera mungkin sejak terdiagnosa sepsis dan sebelum pemberian antibiotik. Terapi empiris antibiotik broadspectrum menjadi suatu pertimbangan dalam satu jam pertama penanganan sepsis setelah pengambilan sampel kultur berdasarkan penyakit komorbid, immunocompromised, home care, rawat inap berulang dan penggunaan alat invasif. Peningkatan insidensi sepsis berhubungan dengan resistensi mikroorganisme dan deescalation dipertimbangkan jika hasil penyebab infeksi sudah terdeteksi. Konsentrasi antibiotik dalam darah harus dievaluasi ketika akan melakukan titrasi dosis sesuai dengan perubahan metabolik tubuh. Konsentrasi antibiotik dipertahankan sekitar 2-5 kali diatas minimal inhibitor concentration (MIC) untuk patogen spesifik pada jenis timedependent antibiotic seperti golongan beta laktam, glikopeptida dan linezolid atau sekitar 40-100% diantara dua interval pemberian intravena, sedangkan konsentrasi pada dependent antibiotics (metronidazol, kuinolon, aminoglikoside) disarankan konsentrasi maksimum plasma (Cmax) sedkitnya 10 kali dari nilai MIC.8 Farmakokinetik dan farmakodinamik antibitoik yang digunakan untuk mengatasi gangguan ini akan mengalami ketidakseimbangan pada usia lanjut karena penurunan fungsi ginjal, penurunan lean mass tubuh dan penurunan aliran darah hepar yang mempercepat timbulnya syok sehingga diperlukan evaluasi untuk menilai efek samping dan perubahan metabolik serta hemodinamik.2,11 Guideline internasional merekomendasikan pengobatan pada penderita sepsis yang beresiko tinggi mengakibatkan kematian (APACHE score >25), syok sepsis, sedikitnya terdapat 2 disfungsi organ dan sepsisinduced ARDS melalui peningkatan aktivitas protein C yang ditandai dengan profibrinolitik, peningkatan anti koagulan, anti inflamasi dan efek anti apoptosis. Protein C tidak boleh diberikan pada perdarahan aktif, penggunaan anti koagulan, trombosit <30.000/uL, dan pasien yang beresiko mengalami perdarahan yang tidak terkontrol. 2,12 Steroid diindikasikan pada keadaan syok refrakter dengan dosis hidrokortison 50 mg yang diberikan secara IV setiap 6 jam selama 7 hari, namun perubahan imunologis yang terjadi pada usia lanjut menjadi suatu pertimbangan terhadap pemakaian steroid karena penggunaan dosis tinggi menyebabkan imunodepresi, kontrol gula darah yang buruk, penyembuhan luka yang lama dan mioneuropati. Kondisi insufisiensi adrenal akan menunjukkan perbaikan yang lebih nyata dengan penggunaan steroid ini.2,12 Diagnosa syok septik Resusitasi awal Terapi cairan dan vasopresor yang optimal Pemberian antibiotik yang adekuat dan broadspesctrum Target CVP 8-12 mmHg MAP ≥ 65 mmHg Urine output ≥ 0,5 ml/kgBB/jam Tekanan vena sentral atau mixed venous oxygen saturation ≥70% atau ≥65% Akses intravena (IV) Monitoring indeks stroke dan tekanan arteri Hipotensi persisten, Disfungsi organ, Tanda-tanda hipoperfusi jaringan Pertimbangan hidrokortison 50 mg/kgBB/ 6 jam atau 10 mg/kgBB/hari Echocardiografi untuk menentukan fungsi ventrikel kiri (Left ventricel/LV) Evaluasi tekanan arteri untuk menilai respon cairan Fungsi LV depresi- normal Dobutamin 2,5 ug/kgBB/menit Syok persisten LV hiperkinetik Pertimbangan IV activated protein C 24 ug/kgBB/hari selama 9 jam Respon cairan : pertimbangan RL 500 cc atau albumin 5% Monitoring : PaO2/FiO2, saturasi O2, udema paru Vasopressin 0,3 ug/kgBB/menit dilanjutkan dengan titrasi norepinefrin Perbaikan Syok Monitoring : MAP, kadar laktat, urine output Gambar 2. Algoritma manajemen syok sepsis dan sepsis pada usia lanjut 9 Sepsis yang terjadi pada usia tua mempunyai resiko tinggi untuk menderita ansietas, nyeri dan delirium. Penggunaan sedasi atau sedatif melalui pemberian IV secara intermiten dapat menurunkan resiko penggunaan ventilator mekanik dibandingkan dengan pemberian secara kontinous.2 Penanganan lainnya yang menjadi perhatian pada usia lanjut adalah profilaksis yang diberikan terhadap deep vein thrombosis dengan penggunaan obat dosis kecil unfractioned heparin, low molecular weight heparin (LMWH) atau penggunaan alat mekanik, proton pump inhibitor (PPI) untuk mencegah stress ulcer dan kontrol gula darah. Hiperglikemia sering terjadi pada sepsis berat dan menyebabkan kerusakan mekanisme pertahanan antimikroba dan mencetuskan terjadinya koagulopati, sehingga target gula darah yang dipertahankan adalah berkisar 150-180 mg/dl untuk mencegah kerusakan imunologis dan meningkatkan resiko koagulopati.11,12 Monitoring Evaluasi yang dilakukan terhadap penatalaksanaan sepsis pada penderita usia lanjut meliputi gejala klinik, pemeriksaan laju endap darah (LED), darah rutin dan marker sepsis seperti CRP dan procalcitonin. 4,13,14 Lokasi infeksi menentukan keberhasilan terapi dan morbiditas pada kasus sepsis pada lansia.15,16 Prognosa Usia sangat mempengaruhi derajat keparahan sepsis, survival rate dan tingkat mortalitas serta merupakan prediktor prognosa pada penderita sepsis. Prognosa buruk terjadi pada pasien dengan infeksi polimikroba dengan episode rekuren akibat bakteremia sekitar 9% dengan resiko mortalitas dalam 1 tahun sebesar 3,6% dan juga dipengaruhi oleh usia dan sumber infeksi ekstraintestinal.17,18 Prognosa sangat bergantung pada imunitas tubuh, infeksi nosokomial, penyakit komorbid, derajat keparahan penyakit usia ≥75 tahun dan gangguan kesadaran.8 Mortality in emergency department sepsis (MEDS) score dan procalcitonin yang meningkat merupakan faktor prognostik yang dinilai pada usia lanjut dengan sepsis. MEDS merupakan penilaian yang berdasarkan kardorespirasi, neurologi dan hematologi. 16,19 Kesimpulan Usia lanjut merupakan salah satu faktor predisposis untuk terjadinya infeksi yang lebih berat dibandingkan dengan usia muda. Perubahan sistem imun, nutrisi, gangguan mental dan penyakit komorbid merupakan faktor pencetus yang dapat memperberat infeksi dan mengakibatkan prognosa yang buruk pada penderita sehingga penanganan yang cepat dan tepat harus dilakukan melalui evaluasi yang ketat dan asupan nutrisi yang cukup. Daftar pustaka 1. De Gaudio AR, Rinaldi S, Chelazzi C, Borracci T. Pathophysiology Of Sepsis In The Elderly: Clinical Impact And Therapeutic Considerations. Current Drug Targets. 2010;10:60-70 2. Girard TD, Opal SM, Ely EW. Severe Sepsis In The Elderly. Clin. Infect Dis. 2010; 40:719-27 3. Destarac LA, Ely WE. Sepsis in Older Patients: An Emerging Concern in Critical Care. Advances In Sepsis. 2011; 2(1):15-23 4. Dellinger PR, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign : International Guidelines For 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Management Of Severe Sepsis And Septic Shock : 2012. CCJM. 2013;41(2):580-630 Kumar AT, Punith K, Sudhir U, Kumar R, Kumar NV, Rao MY. Cytokine profile in elderly patients with sepsis. Indian J Crit Care Med. 2011;13( 2):74-80 Gentile LF, Nacionales DC, Lopez MC, Szpila BE, Larson S, Shawn, et al. Protective Immunity and Defects in the Neonatal and Elderly Immune Response to Sepsis. The Journal of Immunology. 2014:1-11 Englert NC, Ross C.The Older Adult Experiencing Sepsis. Crit Care. 2015;38(2):175–81 Nasa P, Juneja D, Singh O. Severe Sepsis And Septic Shock In The Elderly: An Overview. World J Crit Care Med. 2012;1(1): 23-30 Raju Y. Treatment Of Sepsis And Delated Syndromes In The Elderly: Indian Scenario. Geriatrics. 2010;26(176):763-7 Heppner HJ, Singler K, Kwetkat A, Popp S, Esslinger AS, Bahrmann P, et al. Do Clinical Guidelines Improve Management Of Sepsis In Critically Ill Elderly Patients? A Before-And-After Study Of The Implementation Of A Sepsis Protocol. The Central European Journal of Medicine. 2012:1-9 Yang Y , Yang KS, Hsann YM, Lim V, Ong BC. The Effect Of Comorbidity And Age On Hospital Mortality And Length Of Stay In Patients With Sepsis. J Crit Care. 2010;25:398-405 Martin GS , Mannino DM, Moss M. The Effect Of Age On The Development And Outcome Of Adult Sepsis. Crit Care Med. 2010.;34: 15-21 Aminzadeh Z, Parsa E Relationship Between Age And Peripheral White Blood Cell Count In Patients With Sepsis. Int J Prev Med.2011;2(4): 238-42 Lee AJ, Kim SG. Mean Cell Volumes of Neutrophils and Monocytes Are Promising Markers Of Sepsis In Elderly Patients. Blood Res. 2013;48:193-7 Anevlavis S, Kaltsas K, Bouros D. Procalcitonin As A Marker Of Bacterial Infection In Elderly Patients. Pneumon. 2014;1(27):13-7 Sehgal V, Bajwa SJS, Consalvo JA, Bajaj A. Clinical Conundrums In Management Of Sepsis In The Elderly. Journal Of Translational Internal Medicine. 2015;3(3):108-26 Besch CL, Sanders CV. Managing Sepsis—A Common Cause Of Geriatric Death. Geriatrics. 1986;41(4):55-67 Leibovici L. Long-Term Consequences Of Severe Infections. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2013;19:510–2 Palomba H, Corrêa TD, Silva E, Pardini A, Assuncao MS. Comparative Analysis Of Survival Between Elderly And NonElderly Severe Sepsis And Septic Shock Resuscitated Patients. Einstein. 2015;13(3):357-63 ULKUS DEKUBITUS PADA USIA LANJUT FOKUS PADA PENCEGAHAN DAN TATALAKSANA M. Darma Muda Setia Divisi Geriatri Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/ RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Pendahuluan Ulkus dekubitus merupakan suatu hal yang serius dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada usia lanjut serta akan menjadi beban keluarga dengan biaya perawatan tinggi. Di Negara-negara maju, prevalensi ulkus dekubitus mencapai 11% yang terjadi dalam dua minggu pertama perawatan. Ulkus dekubitus dapat dapat terjadi pada setiap tahapan usia, pada usia lanjut merupakan masalah khusus akibat imobilisasi yang merupakan masalah besar pada pasien geriatri. Masalah ulkus dekubitus berhubungan dengan pengaduan malpraktek medis di Amerika Serikat. Tindakan Prevensi ulkus dekubitus lebih penting dilakukan pada pasien yang beresiko terjadi ulkus decubitus. Definisi Ulkus dekubitus adalah kerusakan jaringan setempat pada kulit dan/atau jaringan dibawahnya akibat tekanan, atau kombinasi antara tekanan dengan pergeseran (Shear), pada bagian tubuh (Tulang) yang menonjol. Ulkus dekubitus menandakan telah terjadi nekrosis jaringan lokal, sering terjadi pada bagian tubuh yang menonjol, misalnya sakrum, tuberositas iskialgia, trokanter, tumit. Ulkus dekubitus sering disebut sebagai ischemic ulcer, Pressure Ulcer, Pressure sore, bed sore, decubital ulcer. Epidemiologi Sebanyak ± 70% ulkus dekubitus terjadi pada pasien geriatri.Prevalensi meningkat dengan bertambahnya umur, terutama umur 70-80 tahun. Secara umum insiden ulkus dekubitus di rumah sakit berkisar 1,2%-3% dan dapat meningkat sampai 50% pada ruang rawat akut yang berhubungan dengan mortalitas tinggi. Kejadian ulkus dekubitus meningkat sesuai dengan dengan lama perawatan, hospitalisasi meningkat 5 kali lipat bila pasien mengalami ulkus dekubitus. Predileksi Sebanyak 95 % ulkus dekubitus terjadi pada bagian belakang tubuh.Daerah predileksi yang sering terjadi ulkus dekubitus adalah sakrum, koksigeal, tuberositas ischialgia dan trokanter mayor. Sakrum merupakan daerah tersering terjadi ulkus dekubitus (36%), tumit (30%), daerah lain masing-masing 6%. Daerah predileksi ulkus dekubitus: Posisi dorsal: os. Sakrum, koksigeus, tendon achiles, os oksipital Posisi abdominal: os frontal, arkus kostarum , krista illiaka, genue Posisi Lateral: trokanter mayor, os zigomatikum, kostae lateral dan maleolus lateralis Posisi duduk: tuberositas iskialgia, os oksipital, tumit. Patogenesis Ulkus dekubitus terjadi karena tekanan dari luar yang menimbulkan iskemia setempat. Dalam keadaan normal, tekanan intrakapiler arterial adalah ± 32 mmHg., tekanan ini dapat meningkat mencapai maksimal 60 mmHg pada keadaan hiperemia. Tekanan midkapiler adalah ± 20 mmHg, sedangkan tekanan pada daerah vena adalah 13-15 mmHg.Efek destruksi jaringan yang berkaitan dengan keadaan iskemia dapat terjadi dengan tekanan kapiler antara 32-60 mmHg yang disebut tekanan suprakapiler. Bila keadaan suprakapiler ini tercapai, akan terjadi Penurunan darah kapiler yang disusul iskemia setempat. Bila seseorang mengalami iskemia imobilisasi pada tempat tidur secara pasif, maka tekanan pada daerah sakrum akan mencapai 60-70 mmHg dan daerah tumit 30-45 mmHg. Tekanan akan menimbulkan daerah iskemik dan bila berlanjut terjadi nekrosis jaringan kulit. Substansia H yang mirip histamin dilepaskan oleh sel-sel iskemik, terjadi akumulasi metabolik seperti kalium, adenosine dipospat (ADP), hydrogen dan asam laktat, yang diduga sebagai faktor penyebab dilatasi pembuluh darah. Reaksi kompensasi sirkulasi akan tampak hiperemis, reaksi tersebut masih efektif bila tekanan dihilangkan sebelum terjadi periode krisis 1-2 jam. Selain faktor tekanan, ada beberapa faktor lain yang dapat memudahkan terjadi ulkus dekubitus, yaitu: Faktor teregangnya kulit akibat daya luncur antara tubuh dengan alas tempat berbaring, terjadi pada penderita dengan posisi setengah berbaring. Faktor terlipatnya kulit akibat gesekan badan yang kurus dengan alas tempat tidur, sehingga seakan-akan kulit ― tertinggal‖ dari daerah tubuh lainnya. Kondisi microclimate. Kondisi suhu dan kelembaban permukaan kulit atau jaringan. Pada pasien imobilisasi dengan posisi setengah duduk dan kecendrungan tubuh meluncur ke bawah, apalagi keadaan tubuh basah.Sering kali hal ini dicegah dengan memberikan penghalang, misalnya bantal kecil/ balok kayu pada kedua telapak kaki. Upaya ini hanya akan mencegah pergerakan kulit yang terfiksasi dari alas, tetapi rangka tulang akan cenderung maju kedepan. Akibatnya terjadi garisgaris penekanan/peregangan pada jaringan subkutan yang seakan-akan tergunting pada tempat-tempat tertentu, dan akan terjadi penutupan arteriol akibat terlalu teregang bahkan sampai robek. Tenaga menggunting ini disebut shering force. Pada shering force terjadi fiksasi kulit pada permukaan alas tempat tidur akan menyebabkan terjadi lipatanlipatan kulit, terutama terjadi pada penderita kurus dengan kulit kendur, lipatan kulit menyebabkan distorsi dan menutup pembuluh darah. Faktor Resiko Faktor Resiko Primer Faktor resiko primer merupakan faktor resiko yang menyebabkan menurunnya pergerakan (morbiditas) sehingga terjadi imobilisasi relative/total yaitu: Gangguan neurologis dengan paralisis: stroke, hemiplegia, hemiparesis, paraplegia, tetraplegia. Gangguan fungsi kognitif dan Penurunan kesadaran. Intervensi bedah: anestesi (premedikasi, anestesi, fase pemulihan) untuk jangka waktu yang lama. Gangguan psikiatrik dan obat psikotropik: psikosis akut misalnya katatonia dan depresi akut, obat sedasi misalnya neuroleptic, benzodiazepine Nyeri hebat Faktor Resiko Sekunder Faktor resiko sekunder adalah faktor-faktor yang dapat menurunkan toleransi jaringan. Faktor yang menurunkan tekanan intravaskuler: Hipotensi arterial: syok ( hipovolemik, septik, kardiogenik), overdosis obat antihipertensi Dehidrasi: pemakaian diuretic,diare, sengatan matahari. Faktor yang menurunkan transport oksigen ke sel: Anemia: hemoglobin < 9 g% Penyakit oklusi arteri perifer Mikroangiopati diabetic Hipotensi, Bradikardi Syok hipovolemik Faktor yang meningkatkan konsumsi oksigen di sel: Demam 38oC Hipermetabolisme Infeksi, sitokemia Faktor yang menyebabkan defisiensi nutrient dalam sel: Malnutisi: defisiensi protein, vitamin, mineral, trace elements Kakeksia: imobilitas karena katabolisme dan kelemahan otot Limfopenia yang berhubungan dengan malnutrisi: defisiensi imun, gangguan penyembuhan luka. Faktor yang melemahkan pertahanan kulit: Proses menua pada kulit: tipis, atrofi, dengan sedikit sel-sel imun Higiene kulit buruk Penyakit kulit: eksema, kandidiasis Kandungan air pada kulit berkurang, daya regang menurun integritas antara dermis dan epidermis menurun. Kulit kering karena atrofi glandula sebaseus dan apokrin. Kulit menjadi halus mudah maserasi pada inkontinensia urin dan alvi karena sering terpapar urin dan feses. Pemakaian obat steroid yang menyebabkan kulit atrofi, tipis, mudah luka. Faktor resiko ulkus decubitus dapat pula dibagi menjadi faktor intrinsic dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah semua faktor yang yang berasal dari kelainan pada pasien itu sendiri ( faktor resiko primer dan sekunder). Faktor ekstrinsik, meliputi: Kebersihan tempat tidur Peralatan medis (infus, central venous pressure/CPV, ventilator) yang menyebabkan penderita terinfeksi pada sikap tertentu Posisi duduk salah Perubahan posisi kurang. Diagnosis Anamnesis geriatri lengkap dilakukan baik autoanamnesis atau aloanamnesis, terutama sehubungan untuk mencari faktor faktor resiko (primer dan skunder ) misalnya lama terjadi imobilisasi, komorbid penyakit (DM, stroke , penyakit pembuluh darah perifer , penurunan fungsi perifer , penurunan fungsi kognitif ) dan riwayat ulkus decubitus sebelumnya. Pemeriksaan fisik pada kulit dilakukan dengan teliti, terutama pada daerah predileksi (bagian yang menonjol) terjadi decubitus (sacrum, tumit, belikat, siku).Inspeksi pada kulit melihat adanya daerah yang eritem/lesi, luka lecet, luka dalam. Pengkajian paripurn pada pasien geritari (P3G)/Comprehensive geriatric assessment) sangat diperlukan dalam mengidentifikasi pasien yang beresiko ulkus decubitus.Komprehensif dalam menetukan masalah kesehatan (Biopsikososio kultural). Serta mengetahui cadangan fisiologi yang masih ada pada pasien usia lanjut dengan multi morbiditas. Pengkajian paripurn pada pasien geritari mencakup pengkajian tingkat mobilitas ( memeriksaActivity of Daily Living/ ADL Barthel), status kognitif (Mini Mental State Examination/MMSE), status psikis (Geriatric Depression Scale/GDS). Pemeriksaan status fungsional sebelum sakit, saat sakit, selama perawatan dilakukan untuk evaluasi mencapai target keberhasilan mobilisasi jangka pendek, menegah dan panjang. Setelah dilakukan pengkajian paripurna, ditentukan langkah langkah koordinasi tatalaksana dan rencana asuhan keperawatan melalui tim terpadu geriatri. Pemeriksaan untuk menilai terjadinya resiko ulkus decubitus dengan menggunakan skala Norton yang sudah berkembang sejak tahun 1961.Nilai semakin rendah pada skala Norton berarti resiko ulkus decubitus semakin tinggi. Skala lain untuk meniulai resiko ulkus decubitus adalah skala Braden, skala waterlow. Skala Braden terdiri dari 6 sub skala yaitu persepsi sensori, klembaban, aktivitas, mobilitas, nutrisi dan friction dan shear. Diagnosis Banding Eritem non-palpable, yang ―memucat‖ (blanch) pada penekanan Lika kronik tipe yang lain (ulkus diabetes, ulkus venous) Ulkus decubitus atipikal Ulkus decubitus yang terjadi bukan pada tempat predileksi, misalnya permukaan ekstensor lengan/ tungkai, dorsum kaki, ujung jari Tabel 1. Skala Norton ntuk Menilai Risiko Ulkus Dekubitus Kondisi Pasien Keterangan Skor Kondisi fisik umum Baik 4 Cukup/lumayan 3 Buruk 2 Sangat Buruk 1 Kesadaran Kompos Mentis 4 Apatis 3 Konfusio/spoor 2 Stupor/koma 1 Tingkat aktivitas Ambulatori 4 Berjalan dengan bantuan 3 Hanya bisa duduk 2 Hanya bisa tiduran 1 Mobilitas Bergerak bebas 4 Sedikit terbatas 3 Sangat terbatas 2 Tak bisa bergerak 1 Inkontinensia Tidak ada 4 Kadang-kadang 3 Sering inkontinensia urin 2 Sering inkontinensia urin dan alvi 1 Skor < 26 = risiko tinggi skor > 26 = risiko rendah Klasifikasi Klasifikasi ulkus decubitus berdasarkan dalamnya jaringan yang mengalami kerusakan.The National Pressure UlcerAdvisory panel(NPUAP) pada tahun 2007 memperbaharui klasifikasi ulkus decubitus yang pertama kali di buat oleh shea.Klasifikasi baru tersebut menambahkan dua stadium lagi yaitu ulkus decubitus yang tak dapat diklasifikasikan (unstageable/unclassified) dan kerusakan jaringan dalam (deep tissue injury). Tabel 2. Klasifikasi Ulkus Dekubitus Tipe Ulkus Dekubitus Berdasarkan waktu yang diperlukan untuk penyembuhan dan perbedaan temperatur ulkus dekubitus dengan kulit sekitarnya, ulkus decubitus dibagi menjadi 3 bagian: Tipe normal Beda temperatur ± 2,5 ˚C antara dareah ulkus dengan kulit sekitar akan sembuh sekitar 6 minggu selama perawatan. Ulkus ini terjadi karena iskemia jaringan setempat akibat tekanan namun pembuluh dan aliran darah masih baik. Tipe arteriosklerotik Beda temperatur < 1 ˚C antara daerah ulkus dengan kulit sekitar.Ulkus decubitus terjadi karena tekanan dan arteriosklerotik pada pembuluh darah, penyembuhan terjadi dalam 16 minggu. Tipe terminal Terjadi pada penderita yang akan meninggal dan tidak akan sembuh. Penatalaksanaan Penatalaksanaan ulkus decubitus cukup sulit dan butuh waktu lamaSehingga pencegahan sangat penting dilakukan.Pada tatalaksana ulkus dekubitus diperlukan tim terpadu yang bekerja secara interdisiplin, meliputi dokter, konsultan terkait, perawat, ahli gizi, bagian rehabilitasi medic, ahli farmasi klinik. Pasien dan keluarga/ pramurawat harus diedukasi mengenai risiko timbul ulkus decubitus dan perburukan yang akan terjadi serta mengetahui tentang strategi pencegahan dan penatalaksanaannya. Tatalaksana dapat berhasil bila disertai peran serta keluarga terutama pramurawat (care giver). Pencegahan Pencegahan ulkus decubitus adalah hal yang utama karena pengobatan ulkus decubitus membutuhkan waktu dan biaya yang besar.Pencegahan dudah dimulai saat pertama kali kontak dengan pasien. Tindakan pencegahan dibagi atas: a. Perawatan kulit Bersikan kulit dengan air hangat (jangan panas) Oleskan lotion agar kulit tetap lembab Jaga pakaian dan sprei tetap kering. Hindari kulit dari keringan dan urin. Periksa kulit tiap hari, terutama kulit pada bagian yang menonjol, perhatikan adanya perubahan warna kemerahan atau perubahan temperature Pijat kulit yang masih intake untuk membantu sirkulasi dan kenyamanan. Hindari pijat pada bagian yang menonjol. b. Perubahan posisi tubuh Usahakan pasien secara rutin dapat pindah dari tempat tidur ke kursi, berdiri dan berjalan. Bila pasien tidak dapat bangun dari tempat tidur atau hanya bisa duduk di kursi roda, pasien di bantu melakukan latihan linggup gerak sendi (range of motion exercises) Miring ke kanan, ke kiri dan terlentang minimal setiap 2 jam. Gunakan bantal di bawah kaki untuk menjaga agar tumit tidak besentuhan langsung dengan kasur/matras Pada pasien yang duduk dikursi roda, lakukan pergeseran dari tumpuan berat tubuh setiap 15 menit Jangan mengangkat kepala terlalu tinggi dari tempat tidur, karena badan akan meluncur ke bawah sehingga kulit pada punggung dan bokong akan lecet. Gunakan bantal lunak untuk mengurangi tekanan pada daerah yang menonjol, jangan menggunakan bantal donat Jangan memindahkan pasien dengan cara menarik dari tempat tidur c. Alas tempat tidur Sprei, selimut dalam keadaan kering dengan permukaan rata/ halus Gunakan kasur antidekubitus d. Nutrisi dan hidrasi Asupan makanan dan cairan cukup, termasuk vitamin dan mineral. Bila sudah terjadi ulkus decubitus, tentukan stadium dan perencanaan tindakan : Stadium 1 Terjadi reaksi peradangan terbatas pada epidermis, kulit kemerahan dibersihkan hati-hati dengan air hangat dan sabun, diberi lotion, kemudian di pijat 2-3 kali/hari. Stadium 2 Perawatan luka memperhatikan syarat-syarat aseptik dan antiseptik.Daerah ulkus digesek dengan es dan dihembus dengan udara hangat bergantian untuk merangsang sirkulasi.Dapat diberikan salep topikal untuk merangsang timbulnya jaringan muda/ granulasi.Penggantian balut dan pemberian salep jangan terlalu sering karena dapat merusak pertumbuhan jaringan. Stadium 3 Luka kotor dan bernanah dibersihkan dengan larutan NaCL fisiologis.Usahakan luka selalu bersih dan eksudat dapat mengalir keluar.Balut jangan terlalu tebal agar oksigenasi dan penguapan baik.Kelembaban luka dijaga tetap basah, untuk mempermudah regenerasi sel-sel kulit.Perlu pemberian antibiotika sistemik. Stadium 4 Perluasan ulkus sampai ke dasar tulang, sering disertai jaringa nekrotik. Semua langkah diatas tetap dikerjakan, jaringan nekrotik yang akan menghalangi pertumbuhan jaringan/epitelisasi dibersihkan. Rawat bersama dengan bagian bedah jika diperlukan tindakan operatif untuk membersihkan luka dan menutup jaringan. Komplikasi Komplikasi sering terjadi pada stadium 3 dan 4, walaupun dapat juga terjadi pada ulkus superfisial. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain : 1. Infeksi, sering bersifat multibakterial baik yang aerobic ataupun aneorobik 2. Keterlibatan jaringan tulang dan sendi seperti periostitis, osteitis, osteomielitis (38%), artritis septik 3. Septicemia 4. Anemia 5. Hipoalbuminemia 6. Kematian dengan angka mortalitas mencapai 48% Referensi 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory panel. Prevention and treatment of pressure ulcers. Clinical practice guidelines. Washingtong DC: National pressure Ulcer advisory Panel, 2009. 2. Bennet RG. Pressure Ulcers, O‘Sulivan J, DeVito EM, Remsburg R, The increasing medical malpractice risk related to pressure ulcers in the United States. J Am Geriatric Soc 2000, 48:73-81. 3. Orsted HL, Ohura T, Harding K. International review. Pressure ulcer prevention: pressure, shear, friction and microclimate in contex: A consensus document. London; Wound international, 2009; 703-715 4. Bates-Jensen BM. Pressure Ulcers. In : Hazzard‘s Geriatric Medicine and Gerontology. Halter JB, Ouslander JG, Tinetti ME, et al. 6th edition. 2009; 703-715 5. Thomas DR. Issues and Dilimmas in prevention and Treatmen of pressure ulcers: a review : J Gerontol. 2001; 56 A: M328-M340. 6. Dharmarajan TS. Ugalino JT. Pressure Ulcers: Clinical feature and management. Hospital Physician 2002: 64-71 7. Gender AC. Pressure ulcers prevention and management. Gerontology update. ARN Network.2008: 8-9. 8. Chacon JMF, Blanes L, Hochman B, Feirrera LM. Prevalence pressure ulcers among the elderly. Living and long stay institution in sao paolo. Sao paolo Med J. 2009; 127(4): 211-5 9. Leffman C, Andreas J, Heinemann A, Leutenegger, Profener F (* hrg.vom Robert Koch institute 2002): Decubitus, Gesundheitsberichterstatung des bundes, Heft 12,2002. 10. Heinemann A, Lockeman U, Matschke J, Tsokos M, Puschel k. Decubitus in Umfeld der Sterbhephase: Epidemiologische, medizinrechtliche und etische aspekte. DMW 2000: 125: 45-51 11. Meehan M . National pressure ulcer prevalence survey. Adv Wound Care. 1994;(5) : 27-37 12. Hartmann P. In : Phase specific wound management of decubital ulcer. 2 nd edition. 2008: 14-15 13. Anders J, Heinemann A, Lefmann C et al. Decubitus ulcers: Pathophysiolgy and primary prevention. Continuing medical education. Dtsch Artebl int. Humberg 2010: 107(21) 371-82. 14. Pranarka K. Dekubitus. Dalam : Buku Ajar Geriatri ( Ilmu Kesehatan Usia Lanjut). Editor: R. Boedi-Darmojo,H. Hadi Martono. Edisi ke-3. 2006: 234-45. 15. Langemo DK, Brown G. skin fails too: acute, crhonic, and end stage skin failure. Adv skin wound care. 2006; 19:206-211 DIAGNOSIS DAN PENANGANAN YANG CEPAT LUPUS ERYTEMATOSUS SISTEMIK Mahriani Sylvawani Divisi Reumatologi, Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, RSUD dr. Zainoel Abidin PENDAHULUAN Lupus eritematosus sistemik (LES) merupakan penyakit autoimun kronis yang belum diketahui penyebab pastinya. Namun diduga bahwa faktor genetik, hormonal serta lingkungan berperan dalam patofisiologi penyakit ini. Penyakit ini menyebabkan inflamasi dengan beragam manifestasi klinis, patofisiologi dan prognosis.1,2 LES menjadi penyakit reumatik utama di dunia selama 30 tahun terahir dengan prevalensi yang bervariasi pada berbagai populasi, antara 2,9/100.000-400/100.000. Data di Amerika Serikat menyebutkan bahwa terdapat rata-rata lima kasus LES per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Laporan dari National Arthritis Data Working Group tahun 2008 juga menyebutkan bahwa kira-kira 250.000 penduduk Amerika adalah penderita LES.1,2 Belum terdapat data epidemiologi LES yang mencakup semua wilayah Indonesia. Data tahun 2002 di RSUP Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, didapatkan 1,4% kasus LES dari total kunjungan pasien di poliklinik Reumatologi Penyakit Dalam, sementara di RS Hasan Sadikin Bandung terdapat 291 Pasien LES atau 10,5% dari total pasien yang berobat ke poliklinik reumatologi selama tahun 2010.2 Penelitian Amelia PA, data tahun 2013 (periode januari-desember) pada RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, didapatkan pasien LES yang berobat ke poliklinik dan ruangan penyakit dalam sebanyak 30 orang.3 Harapan hidup pasien LES meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Persentase pasien yang bertahan hidup sampai 5 tahun kini mencapai 90% yang sebelumnya hanya 50%. Namun, kematian karena perjalanan penyakit ataupun terapi masih sangat tinggi, yaitu 4,6 kali lebih tinggi dibandingkan kontrol sehat.4 Perkembangan terapi dan skrining telah menyebabkan peningkatan angka prevalensi dan penurunan angka mortalitas. Namun demikian, peningkatan harapan hidup ini menyebabkan sequel dan disability karena perjalanan penyakit ataupun terapi.5 Penyakit LES ditandai dengan eksaserbasi dan remisi, memerlukan pemantauan yang ketat akan aktivitas penyakitnya. Evaluasi aktivitas penyakit ini berguna sebagai panduan dalam pemberian terapi. Indeks untuk menilai aktivitas penyakit seperti SLEDAI, MEX-SLEDAI, SLAM, BILAG Score, dsb. Dianjurkan untuk menggunakan MEX-SLEDAI karena MEX-SLEDAI lebih mudah diterapkan pada pusat kesehatan primer yang jauh dari tersedianya fasilitas laboratorium yang canggih.1,8 Berdasarkan berat-ringannya gejala yang muncul, LES dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu ringan, sedang, dan berat. Menurut kriteria MEX-SLEDAI ,pasien yang memiliki skor < 2 tidak memiliki aktivitas penyakit LES secara aktif (ringan), pasien yang memiliki skor 2-5 memiliki aktivitas penyakit LES secara aktif (sedang), dan pasien yang memiliki skor > 5 memiliki aktivitas penyakit LES secara aktif (berat).8 Epidemiologi dan patofisiologi LES Lupus Eritematosus Sistemik (LES) adalah penyakit autoimun yang menyerang jaringan ataupun organ dengan beragam manifestasi klinis, yang tidak diketahui penyebabnya.1,13 Prevalensi LES di Amerika Serikat diperkirakan sebesar 51 per 100.000 penduduk dengan resiko pada perempuan sembilan kali lebih besar dari laki-laki. Di Indonesia belum terdapat data epidemiologi LES yang mencakup seluruh Indonesia. Laporan tahun 2002 di RSUP Cipto mangunkusumo didapatkan 1,4% kasus dari total kunjungan pasien di poliklinik penyakit dalam divisi Reumatologi. Angka kematian pasien LES hampir 5 kali lebih tinggi dari populasi umum.1,2,14 Penyebab pasti LES ini belum diketahui secara pasti, namun diduga penyebabnya multifaktorial yang terdiri dari faktor genetik, lingkungan dan hormonal.14 Resiko meningkat hingga 30 kali lipat pada orang dengan riwayat LES pada salah satu anggota keluarganya, seperti meningkatnya resiko pada saudara kandung dan kembar monozigot sebanyak 70%. Penelitian mutakhir, seperti yang dilakukan oleh Genome-wide Association Studies (GWAS) menunjukkan gen yang terlibat adalah gen yang mengkode respon imun dan inflamasi (HLA-DR, PTPN 22, STAT4, IRF5, BLK, OX40L, FCGR2A, BANK1, SPP1, IRAK1, TNFAIP3, C2, C4, CIq, PXK), perbaikan DNA (TREX 1), aktivator inflamasi sel ke endhotelium (ITGAM) dan respon jaringan terhadap luka (KLK 1, KLK 3).15 Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya LES pada seseorang adalah faktor lingkungan seperti radiasi ultra violet, tembakau, obatobatan dan infeksi virus. Radiasi sinar UV mengakibatkan apoptosis keratosit, juga ditemukan bukti bahwa sinar UV dapat mengubah DNA sehingga menyebabkan terbentuknya autoantibodi, sedangkan tembakau terkait dengan zat yang terkandung di dalamnya, amino lipogenik aromatik. Pengaruh obat-obatan memberikan variasi dari perjalanan klinik LES, namun infeksi virus seperti rubela dan sitomegalovirus menyebabkan perubahan ekspresi sel permukaan dan apoptosis.14,15 Faktor selanjutnya yaitu faktor hormonal. Hormon yang erat kaitannya dengan patogenesis lupus adalah estrogen atau prolaktin. Diduga bahwa pada pasien SLE terjadi peningkatan estrogen dengan aktivitas androgen yang tidak adekuat sehingga terjadinya disregulasi sistem imun. Estrogen mengaktivasi sel B poliklonal sehingga mengakibatkan produksi auto antibodi yang berlebihan. Penelitian yang dilakukan oleh Garcia-Gonzales dkk mendapatkan kadar leptin yang lebih tinggi pada pasien LES perempuan dibandingkan kontrol sehat. Sehingga Leptin yang merupakan hormon dari sel lemak diduga berperan pada patogenesis LES.15,16 Meningkatnya apoptosis pada LES menyebabkan meningkatnya kebocoran antigen intraseluler yang dapat merangsang respon autoimun dan berpartisipasi dalam pembentukan kompleks imun. Peningkatan apoptosis ini merangsang pembentukan IFNα dan pembentukan autoimun dengan merusak sistem toleransi imun melalui aktivasi antigen presenting-cell (APC), sehingga terbentuk komplek imun dan respon inflamasi secara terus menerus.16 Gambar 1. Proses Pembentukan Endogen dari Interferon-α (IFNα)16 Pembersihan (clearance) dari kompleks imun oleh sistem fagositmakrofag mengalami gangguan pada LES sehingga akan menghambat eliminasi kompleks imun dari sirkulasi dan jaringan. Hal ini diduga akibat dari penurunan jumlah CR1 yang merupakan reseptor untuk komplemen dan terjadi gangguan fungsi dari reseptor pada permukaan sel. Gangguan clearance ini juga diduga akibat dari ketidak adekuatan fagositosis IgG2 dan IgG1.17,18 Dalam keadaan normal, sel-sel yang mengalami apoptosis akan dimakan oleh makrofag pada fase awal dari apoptosis tanpa merangsang terjadinya inflamasi dan respon imun. Terjadinya defek pada clearance dari sel-sel apoptosis diduga akibat dari defek dalam jumlah dan kualitas dari protein komplemen seperti C2, C4 atau C1q.18 LES juga ditandai oleh terjadinya penyimpangan sistem imun yang melibatkan sel T, sel B dan sel-sel monosit. Akibatnya terjadi aktivasi sel B poliklonal, meningkatnya jumlah sel yang menghasilkan antibodi, hypergammaglobulinemia, produksi autoantibodi dan terbentuknya kompleks imun. Aktivasi sel B poliklonal tersebut akan membentuk antibodi yang tidak spesifik yang dapat bereaksi terhadap berbagai jenis antigen termasuk antigen tubuh sendiri. Terdapat bukti bahwa sel B pasien SLE lebih sensitif terhadap stimulasi sitokin seperti IL-6. Jumlah sel B didapatkan meningkat di darah tepi pada setiap tahapan aktivasinya.18,19 Sintesis dan sekresi autoantibodi pada pasienSLE diperantarai oleh interaksi antara CD4+ dan CD8+ sel T helper, dan duoble negative T cells (CD4- CD8-) dengan sel B. Terjadi kegagalan fungsi dari aktivitas supresi CD8+ sel T suppressordan sel NK terhadap aktivitas sel B. CD8+ sel T dan sel NK pada pasien LES tidak mampu mengatur sintesis dari imunoglobulin poliklonal dan produksi autoantibodi. Gagalnya supresi terhadap sel B mungkin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyakit berlangsung terus menerus.20 Manifestasi Klinis LES 1. Gejala konstitusional Kelelahan merupakan keluhan yang umum dijumpai pada penderita LES dan biasanya mendahului berbagai manifestasi klinis lainnya. Namun, diperlukan pemeriksaan kadar C3 serum, mengingat banyaknya kondisi lain yang juga menyebabkan kelelahan seperti anemia, meningkatnya beban kerja, konflik kejiwaan serta pemakaian obat seperti prednison. Kelelahan pada LES akan menunjukkan kadar C3 serum yang rendah dan memberikan respons terhadap pemberian steroid atau latihan.21,22 Penurunan berat badan dijumpai pada sebagian penderita LES. Penurunan berat badan ini dapat disebabkan oleh menurunnya nafsu makan atau gejala gastrointestinal dan terjadi dalam beberapa bulan sebelum diagnosis ditegakkan. Gejala konstitusional lainnya adalah demam. Demam akibat LES biasanya tidak disertai menggigil dan sulit dibedakan dari sebab lainnya.22 Gambar 2. Patogenesis LES18 2. Manifestasi muskuloskeletal Manifestasi muskuloskeletal terjadi pada 53-95% pasien LES. Miositis yang melibatkan otot-otot proksimal tubuh telah dilaporkan sebanyak 5-11% kasus. Sedangkan Avascular Necrosis (AVN) pada tulang terjadi pada 5-12% kasus. Sekitar 70% pasien menderita atralgia atau artritis yang ditandai dengan pembengkakan, kemerahan yang terkadang disertai efusi sering pada sendi jari tangan, pergelangan tangan, siku, bahu dan lutut. Artritis pada LES ini bersifat non erosif.22 3. Manifestasi kulit Manifestasi kulit pada penyakit LES dapat berupa kutaneus lupus akut yang ditandai dengan malar rash (Butterfly Rash), yaitu bentukan ruam pada kedua pipi yang tidak melebihi lipatan nasolabial dan ditandai dengan adanya ruam pada hidung yang menyambung dengan ruam yang ada di pipi. Sedangkan simetrikal eritema sentrifugum, anular eritema, psoriati LE, pitiariasis dan makulo papulo fotosensitif dapat dijumpai pada kutaneus lupus sub akut. Selain itu, lupus diskoid yang berupa bercak kemerahan dengan karatotik pada permukaanya merupakan bentuk kutaneus lupus kronik yang ditandai dengan parut dan atropi pada daerah sentral dan hiperpigmentasi pada tepinya.23 Vaskulitis kutaneus ditemukan pada hampir 70% pasien dengan non spesifik kutaneus lupus. Gejala lainnya dapat berupa Raynaud’s Phenomenon, alopesia, sklerodaktili, nodul reumatoid, perubahan pigmentasi dan oral ulcer.23 4. Manifestasi paru Dapat dijumpai nyeri dada atau efusi pleura jernih dengan peningkatan kadar protein dan leukosit atau friction rub yang merupakan tanda pleuritis. Selain itu dapat juga dijumpai pneumonitis, pulmonary haemorrhage, emboli paru atau hipertensi pulmonal. Alveolar Haemorrhage biasanya terjadi pada pasien dengan titer anti ds-DNAyang tinggi dan dengan penyakit paru aktif. Sedangkan Shrinking Lung Syndrom ditandai dengan dispneu yang progressif dan gambaran paruparu yang kecil pada pemeriksaan radiografi.23 5. Manifestasi kardiologis Manifestasi kelainan jantung terbanyak adalah perikarditis dan efusi perikardium yaitu sebanyak 66%, menyusul kelainan berupa miokarditis dan endokarditis dengan kelainan katup yang paling sering adalah katup mitral dan aorta. Selain itu, juga bisa didapatkan penyakit koroner, hipertensi, gagal jantung dan kelainan konduksi.24 6. Manifestasi renal Hampir 50% pasien LES mengalami lupus nefritis dan sebanyak 0,5% akan berkembang menjadi gagal ginjal kronik. Pembentukan atau deposisi komplek imun pada ginjal menyebabkan intra-glomerular inflamasi dengan aktivasi leukosit dan proliferasi sel renal.24 7. Manifestasi gastrointestinal Manifestasi gastrointestinal dapat berupa hepatosplenomegali nonspesifik, hepatitis lupois, lupus gut atau kolitis. Pankreatitis merupakan kasus yang jarang, hanya sekitar 0,2-8,2 % kasus, namun sudah didapatkan 10 kasus pankreatitis akut sebagai manifestasi awal dari LES dan merupakan pertanda prognosis buruk. Selain itu juga bisa didapatkan Lupus Mesenteric Vaskulitis (LMV) yang juga sering disebut mesenteric arteritis, lupus enteritis, lupus vaskulitis, gastrointestinal vaskulitis, intra abdominal vaskulitis, atau sindrom gastrointestinal akut. Ju et al dan Tian et al. melaporkan prevalensi global pada seluruh pasien LES adalah 0,2-9,7% dan terjadi pada 29% sampai 65% pada pasien dengan nyeri abdomen akut.24,25 Protein-Losing Gastroenteropathy (PLGE) merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan edema dan hipoalbuminemia berat karena hilangnya protein serum dari saluran pencernaan, keadaan ini mirip dengan keadaan sindrom nefrotik. Sampai saat ini, dari berbagai data literatur didapatkan 60 pasien LES dengan PLGE dan dominannya adalah bangsa Asia. Penelitian Tian dkk pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 53,3% pasien LES menunjukkan PLGE sebagai manifestasi awal. Gornisiewicz et al.dan Tian et al, juga menyimpulkan PLGE sering terjadi pada pasien LES berat dengan keterlibatan banyak sistem organ. Intestinal Psudo-Obstruction (IPO) merupakan kasus yang jarang, namun telah diketahui bahwa disfungsi otot polos viscera serta nervus enterikus dan atau saraf otonom viscera merupakan penyebab terjadinya IPO, dan baru ditemukan 28 kasus berdasarkan laporan dari literatur di Inggris.25 Banyak manifestasi klinis lainnya yang juga didapatkan pada psien LES seperti Ulcerativ Colitis (UC) dan telah dilaporkan 27 kasus sampai saat ini dan hanya 3 kasus untuk eosinofilik enteritis pada pasien LES.25 8. Manifestasi neuropsikiatrik Manifestasi neuropsikiatrik pasien LES dapat berupa manifestasi yang sering terjadi (>5%) yaitu Cerebrovascular Disease (CVD) dan kejang, relatif jarang (1-5%) seperti disfungsi kognitif berat, depresi berat, Acute Confusional State (ACS), gangguan saraf perifer dan psikosis.25,26 Perjalanan penyakit LES dapat menyebabkan gangguan baik pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Kejang dilaporkan terjadi pada 7-10% kasus, sedangkan neuropati perifer hanya terjadi pada 1% kasus. Demielinasi, transverse myelopathy dan chorea hanya pada kurang dari 1% kasus. Disfungsi kognitif telah dilaporkan 20-30% dari pasien LES dan psikosis hanya 3,5% yang ditandai dengan delusi atau halusinasi.27,28 Sejumlah penelitian telah menyebutkan bahwa tingginya angka kejadian gangguan psikiatrik pada pasien LES, terutama depresi atau distress. Prevalensi depresi pada pasien LES berkisar antara 17-71% pada berbagai penelitian yang telah dilakukan. Segui et al. dan Bachen et al. melaporkan bahwa dari 20 pasien LES perempuan, 40% mengalami gangguan psikiatrik, terutama Generalized Anxiety Disorder (GAD) dan Panic Disorder. Tingginya angka kejadian Social Introversion dan Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) juga didapatkan pada pasien LES dibandingkan dengan kontrol ataupun populasi sehat. Penelitian Bachen et al, melaporkan 65% dari 326 sampel mengalami salah satu gangguan berikut : MDD (47%), specific phobia (24%), social phobia (16%), OCD (9%), panic disorder (8%), bipolar I disorder (formerly manic-depressive disorder; 6%), GAD (4%), dysthymic disorder (3%), dan agoraphobia tanpapanic disorder (1%).27 9. Manifestasi hemik limfatik Manifestasi kelainan hematologi dapat berupa anemia, leukopenia, limphopenia, nitropenia ataupun trombopenia. Bentuk terbanyak yang didapatkan adalah anemia karena penyakit kronis, anemia hemolitik autoimunhanya didapatkan pada 10% kasus. Limfadenopati terjadi pada sekitar 40% dari pasien.27,28 Pemeriksaan Laboratorium a. Pemeriksaan darah lengkap untuk melihat hemoglobin, jumlah leukosit, trombosit, limfosit dan LED, peningkatan LED menunjukkan aktifnya penyakit. b. Urin lengkap untuk melihat protein urin dan faal ginjal yang merujuk adanya kelainan ginjal. c. Pemeriksaan faal hati untuk melihat adanya autoimun hepatitis, hemolitik anemia serta kadar albumin yang rendah. d. Kadar CRP. Pada lupus yang aktif kadar CRP cenderung normal atau dengan peningkatan yang tidak bermakna, sedangkan pada infeksi terjadi peningkatan kadar CRP. e. Pemeriksaan komplemen C3 dan C4, dimana didapatkan kedua komplemen ini dengan kadar yang rendah pada lupus yang aktif. f. Tes serologi.28 Anti-dsDNA merupakan tes spesifik untuk SLE, jarang didapatkan pada penyakit lain dan spesifitasnya hampir 100%. Dengan demikian, anti ds-DNA berkontribusi besar dalam upaya diagnostik dan merupakan salah satu kriteria klasifikasi LES.28,29 Diagnosis LES Diagnosis LES dapat ditegakkan jika memenuhi minimal 4 dari 11 kriteria ACR untuk LES. Bila hanya terdapat 3 kriteria dan salah satunya adalah ANA positif, maka sangat mungkin LES dan diagnosis ditegakkan bergantung pada pengamatan klinis.1,31 Tabel 1. Kriteria Diagnosis Lupus Eritematosus Sistemik (ACR 1997)1,31 Kriteria Batasan Ruam malar Eritema yang menetap, rata atau menonjol, pada daerah malar dan cenderung tidak melibatkan lipat nasolabial. Ruam diskoid Plak eritema menonjol dengan keratotik dan sumbatan folikular. Pada SLE lanjut dapat ditemukan parut atrofik. Fotosensitivitas Ruam kulit yang diakibatkan reaksi abnormal terhadap sinar matahari, baik dari anamnesis pasien atau yang dilihat oleh dokter pemeriksa. Ulkus mulut Ulkus mulut atau orofaring, umumnya tidak nyeri dan dilihat oleh dokter pemeriksa. Arthritis Artritis non erosif yang melibatkan dua atau lebih sendi perifer, ditandai oleh nyeri tekan, bengkak atau efusia. Serositis : Pleuritis Perikarditis Gangguan renal Gangguan neurologi Gangguan hematologi Gangguan imunologi Antibodi antinuklear positif (ANA) Riwayat nyeri pleuritik atau pleuritc friction rub yang didengar oleh dokter pemeriksa atau terdapat bukti efusi pleura Atau Terbukti dengan rekaman EKG atau pericardial friction rub atau terdapat bukti efusi perikardium. Proteinuria menetap >0.5 gram per hari atau >3+ bila tidak dilakukan pemeriksaan kuantitatif Atau Silinder seluler : dapat berupa silinder eritrosit, hemoglobin, granular, tubular atau campuran. Kejang yang bukan disebabkan oleh obat-obatan atau gangguan metabolik (misalnya uremia, ketoasidosis, atau ketidak-seimbangan elektrolit). Atau Psikosis yang bukan disebabkan oleh obat-obatan atau gangguan metabolik (misalnya uremia, ketoasidosis, atau ketidak-seimbangan elektrolit). Anemia hemolitik dengan retikulosis Atau Lekopenia <4.000/mm3 pada dua kali pemeriksaan atau lebih Atau Limfopenia <1.500/mm3 pada dua kali pemeriksaan atau lebih Atau Trombositopenia <100.000/mm3 tanpa disebabkan oleh obat-obatan. Anti-DNA: antibodi terhadap native DNA dengan diter yang abnormal Atau Anti-Sm: terdapatnya antibodi terhadap antigen nuklear Sm Atau Temuan positif terhadap antibodi anti fosfolipid yang didasarkan atas: 1) kadar serum antibodi antikardiolipin abnormal baik IgG atau IgM, 2) Tes lupus antikoagulan positif menggunakan metoda standard, atau 3) hasil tes serologi positif palsu terhadap siflis sekurangkurangnya selama 6 bulandan dikonfirmasi dengan test imobilisasi Treponemapallidum atau tesfluoresensi absorpsi antibodi treponema. Titer abnormal dari antibodi anti-nuklear berdasarkan pemeriksaan imunofluoresensi atau pemeriksaan setingkat pada setiap kurun waktu perjalan penyakit tanpa keterlibatan obat yang diketahui berhubungan dengan sindroma lupus yang diinduksi obat. Penilaian Aktivitas Penyakit LES Penyakit LES yang ditandai dengan eksaserbasi dan remisi, memerlukan pemantauan yang ketat akan aktivitas penyakitnya. Evaluasi aktivitas penyakit ini berguna sebagai panduan dalam pemberian terapi. Indeks untuk menilai aktivitas penyakit seperti SLEDAI, MEX-SLEDAI, SLAM, BILAG Score, dsb. Dianjurkan untuk menggunakan MEXSLEDAI karena MEX-SLEDAI lebih mudah diterapkan pada pusat kesehatan primer yang jauh dari tersedianya fasilitas laboratorium yang canggih.32,33 Tabel 2. Penilaian derajat keparahan LES (MEX-SLEDAI skor)1,32 Tanda chek ( ) Bobot 8 Deskripsi Gangguan Neurologis Definisi Psikosa. Gangguan kemampuan melaksanakan aktivitas fungsi normal dikarenakan gangguan persepsi realitas. (Halusinasi, kehilangan berasosiasi, isi pikiran yang dangkal, berfikir yang tidak logis). CVA (Cerebrovascular accident) : Sindrom baru. Eksklusi arteriosklerosis. Kejang: Onset baru, eksklusi metabolik, infeksi, atau pemakaian obat. Sindrom otak organik : Sepeti : a) kesadaran yang berkabut dengan berkurangnya kapasitas untuk memusatkan pikiran dan ketidakmampuan memberikan perhatian terhadap lingkungan. b) gangguan persepsi; berbicara melantur; insomnia atau perasaan mengantuk sepanjang hari; meningkat atau menurunnya aktivitas psikomotor. Eksklusi penyebab metabolik, infeksi atau penggunaan obat. Mononeurtis: Defisit sensorik atau motorik yang baru disatu atau lebih saraf kranial atau perifer. Myelitis: Paraplegia dan/atau gangguan mengontrol BAK/BAB dengan onset yang baru. Eksklusi penyebab lainnya 6 Gangguan ginjal 4 Vaskulitis (pada kulit) 3 3 Hemolisis Trombositope nia Artritis 2 2 Gangguan mukokutaneus Castc, Heme granular atau sel darah merah. Haematuria. >5 /lpb. Eksklusi penyebab lainnya (batu/infeksi) Proteinuria. Onset baru, >0.5g/l pada random spesimen. Peningkatan kreatinine (> 5 mg/dl) Nodul pada jari yang lunak, infark periungual, splinter haemorrhages. Data biopsi atau angiogram dari vaskulitis. Hb <12.0 g/dl. Trombositopeni : < 100.000. Bukan disebabkan oleh obat Pembengkakan sendi atau efusi lebih dari 2 sendi. Ruam malar. Onset baru atau malar erithema yang menonjol. Mucous ulcers. Oral atau nasopharyngeal ulserasi dengan onset baru atau berulang. 2 Serositis Abnormal Alopenia. Kehilangan sebagaian atau seluruh rambut atau mudahnya rambut rontok Pleuritis. Terdapatnya nyeri pleura atau pleural rub atau efusi pleura pada pemeriksaan fisik. Pericarditis. Terdapatnya nyeri pericardial atau terdengarnya rub. 1 1 1 Demam Kelelahan Leukopeni 1 Limfopenia Total skor MEX-SLEDAI Peritonitis. Terdapatnya nyeri abdominal difus dengan rebound tenderness (Eksklusi penyakit intra-abdominal). Demam > 38˚ C sesudah eksklusi infeksi Kelelahan yang tidak dapat dijelaskan Sel darah putih < 4000/mm3, bukan akibat obat Limfosit < 1200.mm3, bukan akibat obat. Derajat Berat Ringannya Penyakit LES1, 34,35 1. Kriteria untuk dikatakan LES ringan (Skor < 2) adalah: a. Secara klinis tenang b. Tidak terdapat tanda atau gejala yang mengancam nyawa c. Fungsi organ normal atau stabil, yaitu: ginjal, paru, jantung, gastrointestinal, susunan saraf pusat, sendi, hematologi dan kulit. Contoh, LES dengan manifestasi arthritis dan kulit. 2. Penyakit LES dengan tingkat keparahan sedang (skor 2-5) jika ditemukan: a. Nefritis ringan sampai sedang ( Lupus nefritis kelas I dan II) b. Trombositopenia (trombosit 20-50x103/mm3) c. Serositis mayor 3. Penyakit LES berat (skor > 5) atau mengancam nyawa apabila ditemukan keadaan sebagaimana tercantum di bawah ini, yaitu: a. Jantung: endokarditis Libman-Sacks, vaskulitis arteri koronaria, miokarditis, tamponade jantung, hipertensi maligna. b. Paru-paru: hipertensi pulmonal, perdarahan paru, pneumonitis, emboli paru,infark paru, fibrosis interstisial, shrinking lung. c. Gastrointestinal: pankreatitis, vaskulitis mesenterika. d. Ginjal: nefritis proliferatif dan atau membranous. e. Kulit: vaskulitis berat, ruam difus disertai ulkus atau melepuh (blister). f. Neurologi: kejang, acute confusional state, koma, stroke, mielopati transversa, mononeuritis, polineuritis, neuritis optik, psikosis, sindroma demielinasi. g. Hematologi: anemia hemolitik, neutropenia (leukosit <1.000/mm3), trombositopenia < 20.000/mm3, purpura trombotik trombositopenia, thrombosis vena atau arteri. Pilar Pengobatan Baik untuk SLE ringan atau sedang dan berat, diperlukan gabungan strategi pengobatan disebut pilar pengobatan. Pilar pengobatan SLE ini seyogyanya dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan agar tujuan pengobatan tercapai. Perlu dilakukan upaya pemantauan penyakit mulai dari dokter umum di perifer sampai dokter konsultan, terutama ahli reumatologi. A. Pilar Pengobatan Lupus Eritematosus Sistemik I. Edukasi dan konseling II. Program rehabilitasi III. Pengobatan medikamentosa a. OAINS b. Anti malaria c. Steroid d. Imunosupresan / Sitotoksik I. Butir-butir edukasi terhadap pasien SLE 1. Penjelasan tentang apa itu lupus dan penyebabnya. 2. Tipe dari penyakit SLE dan perangai dari masing-masing tipe tersebut. 3. Masalah yang terkait dengan fisik: kegunaan latihan terutama yang terkait dengan pemakaian steroid seperti osteoporosis, istirahat, pemakaian alat bantu maupun diet, mengatasi infeksi secepatnya maupun pemakaian kontrasepsi. 4. Pengenalan masalah aspek psikologis: bagaimana pemahaman diri pasien SLE, mengatasi rasa lelah, stres emosional, trauma psikis, masalah terkait dengan keluarga atau tempat kerja dan pekerjaan itu sendiri, mengatasi rasa nyeri. 5. Pemakaian obat mencakup jenis, dosis, lama pemberian dan sebagainya. Perlu tidaknya suplementasi mineral dan vitamin. Obatobatan yang dipakai jangka panjang contohnya obat anti tuberkulosis dan beberapa jenis lainnya termasuk antibiotikum. 6. Dimana pasien dapat memperoleh informasi tentang SLE, adakah kelompok pendukung, yayasan yang bergerak dalam pemasyarakatan SLE dan sebagainya. II. Program Rehabilitasi Terdapat berbagai modalitas yang dapat diberikan pada pasien dengan SLE tergantung maksud dan tujuan dari program ini. Salah satu hal penting adalah pemahaman akan turunnya masa otot hingga 30% apabila pasien dengan LES dibiarkan dalam kondisi immobilitas selama lebih dari 2 minggu. Disamping itu penurunan kekuatan otot akan terjadi sekitar 1-5% per hari dalam kondisi imobilitas. Berbagai latihan diperlukan untuk mempertahankan kestabilan sendi. Modalitas •fisik seperti pemberian panas atau dingin diperlukan untuk mengurangi rasa nyeri, menghilangkan kekakuan atau spasme otot. Demikian pula modalitas lainnya seperti transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) memberikan manfaat yang cukup besar pada pasien dengan nyeri atau kekakuan otot.Secara garis besar, maka tujuan, indikasi dan tekhnis pelaksanaan program rehabilitasi yang melibatkan beberapa maksud di bawah ini, yaitu: a. Istirahat b. Terapi fisik c. Terapi dengan modalitas d. Ortotik e. Lain-lain. III. Terapi Medikamentosa Berikut ini adalah jenis, dosis obat yang dipakai pada LES serta pemantauannya : Jenis Ob Dosis Klorokuin 250 mg/hr (3,5-4 mg/ kgBB/hr) Hidroksiklorokuin* 200-400 mg/hr Azatioprin Jenis Toksisitas Pemantauan Evaluasi Awal Klinis Funduskopi dan lapangan pandang mata setiap 3 – 6 bulan. Laboratorik Retinopati, keluhan GIT, rash, mialgia, sakit kepala, anemia hemolitik pada pasien dengan defisiensi G6PD. Evaluasi mata, G6PD pada pasien beresiko. 50-150 mg per hari, dosis terbagi 1-3, tergantung BB. Mielosupresif, hepatotoksik, gangguan limfoproliferatif. Darah tepi lengkap, kreatinin, AST/ ALT. Siklofosfamid Po: 50-150 mg/ hr. Iv: 500-750 mg/m2 dalam dextrose 250 ml, infuse selama 1 jam. Mielosupresif, gangguan limfoproliferatif, keganasan, imunosupresi, sistitis hemoragik, infertilitas. Darah tepi lengkap, hitung jenis leukosit, urin lengkap. Metotreksat 7.5-20 mg/ minggu, dosis tunggal atau terbagi 3. Mielosupresif, fibrosis hepatic, sirosis, infiltrate pulmonal dan fibrosis. Darah tepi lengkap, foto thoraks, serologi hepatitis B dan C pada pasien risiko tinggi, AST, fungsi hati, kreatinin. Gejala mielosupresif, sesak nafas, mual muntah, ulkus mulut. Darah tepi lengkap terutama hitung trombosit tiap 4-8 minggu, AST/ALT dan albumi tiap 4-8minggu, urin lengkap dan kreatinin. Siklosporin A 2,5-5 mg/ kgBB atau sekitar 100- 400 mg/hr dalam 2 dosis, tergantung berat badan. Pembengkakan nyeri gusi, peningkatan tekanan darah, peningkatan pertumbuhan rambut, gangguan fungsi ginjal, nafsu makan menurun, tremor. Darah tepi lengkap, kreatinin, urin lengkap, LFT. Gejala hipersensitifitas terhadap castor oil (bila obat diberikan injeksi), tekanan darah, fungsi hati dan ginjal. Kreatinin, darah tepi lengkap, LFT. 1000-2000 mg dalam 2 dosis. Mual, diare, leucopenia. Gejala gastrointestinal. Darah tepi lengkap terutama leukosit dan hitung jenis. Mikofenolat Mofetil Gejala mielosupresif. Darah tepi lengkap tiap 1- 2 minggu dan selanjutnya 1-3 bulan interval. AST tiap tahun dan papsmear secara teratur. Darah tepi lengkap tiap bulan, sitologi urin dan papsmear tiap tahun seumur hidup. Kesimpulan Lupus eritematosus sistemik merupakan penyakit autoimun kronis yang belum diketahui penyebab pastinya. Faktor genetik, hormonal serta lingkungan berperan dalam patofisiologi penyakit ini. Lupus eritematosus sistemik menyebabkan inflamasi dengan beragam manifestasi klinis, patofisiologi dan prognosis. Penegakan diagnosis lebih dini dan penangan yang cepat dan tepat dapat mencegah perburukan dan kerusakan organ lebih awal. Edukasi yang baik, rehabilitasi dan medikamentosa obat sangat dibutuhkan dalam penanganan LES. Daftar Pustaka 1. Sudoyo WA. Rekomendasi Perhimpunan Reumatologi Indonesia Untuk Diagnosis dan Pengelolaan Lupus Eritematosus. 2011; 154. 2. Biscile S,Chewolkar C. Lupus flare : How to diagnose and treat?. Medicine up date. 2012; 281-7. 3. Amalia PA. Hubungan kadar anti-dsDNA dengan manifestasi klinis penyakit lupus eritematosus sistemik di rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Skripsi Unsyiah. Fakultas Kedokteran. 2014;1-63. 4. Petri M. Measuring disease activity and severity in clinical trials and the clinic: same or different?. the Annual Congress of the American College of Rheumatology.2012; 1-7. 5. Anyanwu C, Langenhan J, Werth P. Measurement of disease severity in cutaneous autoimmune diseases. F1000 Prime Reports. 2013; 5:1-6. 6. Kumar A. Indian Guidelines on the Managemet of SLE. J Indian Rheumatol Assoc. 2002; 10 : 80 – 96. 7. Arbuckle M, James J, Kohlhase K, Rubertone M, Dennis G, Harley J. Development of anti-dsDNA autoantibodies prior to clinical diagnosis of systemic lupus erythematosus. Scandinavian journal of immunology. 2011;54:211-9. 8. Liu C, Manzi S. Biomaekers for systemic lupus erythematosus: a review and perspective. current opinion in rheumatology. 2005; 17: 543-9. 9. Alba P, Bento L, Cuadrado M, Karim Y, Tungekar M, Abbs I, et al. Anti-dsDNA, Anti-SM antibodies, and The lupus anticoagulant; significant factors associated with lupus nephritis. Ann Rheum Dis. 2003;62: 556-60 10. Villalta D, Bizzaro N, Bassi N, Zen M, Gatto M. Anti-dsDNA antobody isotype in Systemic lupus erytematosus; IgA in 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. addition to IgG anti-dsDNA help to identify glomerulonephritis and active disease. Plos ONE. 2013; 8. Sandhu G, Bansal A, Ranade A, Aggarwal R, Narayanswami G,. Negative double stranded DNA and anti-smith antibodies in lupus nephritis. Nephrology reviews. 2012;4:55-7. Susanti H, Salman Y, Gunawan A, Handono K. Kadar antibodi anti-dsDNA dan urine monocyte chemoattractant protein-1 pada nefritis lupus. Jurnal kedokteran Brawijaya. 2012;27: 96-101. Chaichian Y, Tammy O. Targeted therapies in systemic lupus erythematosus : A state of the art review. J Clin Cell Immunol. 2013; 1-8. Narayanan K, Marwaha V, Shankar S. Correlation betwen systemic lupus erythematosus disease activity index, C3, C4, and anti-dsDNA antibodies. MJAFI. 2010; 66 : 102-7. Mosca M, Irastorza R, Khamashta M. Treatment of systemic lupus erytematosus. Elsevier science inter immunopharmacology. 2010; 1065-75. Bertsias G, Cervera R, Boumpas D. Systemic lupus erythematosus: pathogenesis and clinical features. EULAR Textbook on Rheumatic Disease. 2012; 7: 37-54. Handono K, Gunawan A, Rosandi R; Kadar autoantibodi dan manifestasi klinis pada pasien nefritis lupus silent dan nefritis lupus overt. M Med Indonesia.2012; 46: 157-62. Moura G, Lima I, Barbosa L. Athanaziao D, Reis E, Reis M, et al. Anti-C1q antibodies: Association with nephritis and disease activity in systemic lupus erythematosus. J. Clin. Lab.Anal.2009;23:19-23. Monova D, Monovov S, Rosenova K, Argirova T. Autoantibodies against C1q: view on association between systemic lupus erythematosus disease manifestation and Ciq autoantibodies. Ann Rheum Dis. 2012;61: 563-4. Turner E, Dishi V, Chung P, Harris P, Pierce R, Asayuma y. Endothelial function in systemic lupus erythematosus: relationship to disease activity. Vascular Health and Risk Management. 2005;1(4): 357– 60. Stipinska B, Goricka P. Cytokines and MicroRNAs as Candidate Biomarkers for Systemic Lupus Erythematosus. Int. J. Mol. Sci. 2015; 16: 24194-218. Thai HS, Mak A. Anti-NR2A/B Antibodies and Other Major Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Cognitive Dysfunction in Systemic Lupus Erythematosus. Int. J. Mol. Sci. 2015;16: 282-92. 23. Kuhn A, Bonsmann G, Joachim H, Herzer P. The Diagnosis and Treatment of Systemic Lupus Erythematosus. Dtsch Arztebl Int. 2015;112: 423–32. 24. Mikdashi1 J, Tenbrock O. Measuring disease activity in adults with systemic lupus erythematosus: the challenges of administrative burden and responsiveness to patient concerns in clinical research,.Mikdashi and Nived Arthritis Research & Therapy. 2015;17:183-93. 25. Ighe A, Dahlström O, SkogT, Sjowall C. Application of the 2012 Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria to patients in a regional Swedish systemic lupus erythematosus register. Arthritis Research & Therapy. 2015;17:118. 26. Croca S, Bassett P, Chambers S, Davari M, Fouad F, Leach O, et al. IgG anti-apolipoprotein A-1 antibodies in patients with systemic lupus erythematosus are associated with disease activity and corticosteroid therapy: an observational study. Arthritis Research & Therapy. 2015;17:1-10. 27. Freir EA, Souto LM, Ciconelli RM. Assessment measures in systemic lupus erythematosus. Rev Bras Reumatol. 2011;51:7080. 28. Chambers SA, Allen E, Rahman A, Isenberg D. Damage and mortality in a group of british patient with systemic lupus erytematosus followed up forover 10 years. concise report,.London. 2009;673-5. 29. Utomo WN. Hubungan antar aktivitas penyakit dengan status kesehatan pada pasien LES (lupus eritematosus sistemik) di RSUP dr. Kariadi, Semarang. Skripsi Universitas diponogoro. Fakultas Kedokteran. 2012;1- 63. 30. Hoffman I, Peene I, Meheus i, huizinga T, Cebecauer L, Isemberg D, et al. Specific antinuclear Antibodies are associated with clinical features in systemic Lupus Erythematosus. Ann Rheum Dis. 2004;63:1155-8. 31. Yung S, Cheung KF, Zhang Q, Chan TM. Anti-dsDNA antibodies bind to mesangial annexin II in lupus nephritis. J Am Soc Nephrol. 2010; 21:1912-27. 32. Chiewthanakul P, Sawanyawisuth K, Foocharon C, Tiamkao S. Clinical feature and predictive factors in Neuro-Psychiatric Lupus. Asian Pac J Allergy Immunol. 2012; 30:552-60. DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF HYPERSENSITIVITY REACTION T. Mamfaluti Divisi Alergi-Imunologi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD. dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Pendahuluan Reaksi hipersensitivitas yang didasari mekanisme imunologis berlebihan terhadap bahan atau zat yang tidak berbahaya dikenal sebagai reaksi alergi. Istilah alergi diperkenalkan pertama kali oleh dokter ahli anak bernama Clemens von Pirquet (1906) yang diartikan sebagai reaksi pejamu yang berubah. Pada saat ini alergi diartikan sebagai reaksi seseorang yang menyimpang terhadap kontak atau pajanan zat asing (alergen), dengan akibat timbulnya gejala-gejala klinis dimana pajanan zat asing (alergen) tersebut tidak menimbulkan gejala bagi kebanyakan orang. (Hollander, 20013; Kay, 2001; Baratawidjaja, 2009). Insidensi penyakit alergi pada dua dekade terakhir mengalami peningkatan dimana peningkatan insidensi terutama dialami oleh negaranegara maju dan daerah industri serta terjadi terutama di kalangan menengah ke atas dengan tingkat pendidikan dan sosioekonomi tinggi. Alergi juga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan keadaan sosioekonomi penderita. Prevalensi alergi yang meningkat di duga berhubungann dengan pola hidup negara maju, terutama dalam menurunnya penyakit infeksi, berkurangnya pajanan dengan berbagai mikroorganisme (Baratawidjaja, 2009) Istilah Yang Berkaitan dengan Reaksi Hipersensitivitas A. Atopi Atopi adalah kecenderungan genetik dalam keluarga untuk terjadinya hipersensivitas kulit dan membran mukosa terhadap bahan dalam lingkungan yang disertai dengan peningkatan produksi IgE dan atau perubahan reaktivitas nonspesifik, yang menimbulkan penyakit alergi seperti rinokonjungtivitas, asma bronkiale dan dermatitis atopik. B. Alergen Alergen adalah bahan yang dapat menginduksi respon antibodi IgE. C. Alergi Alergi adalah reakasi hipersensitivitas yang didasari mekanisme imunologis baik antibodi maupun cell mediated. Manifestasi klinis berupa asma, rhinokonjungtivitis atau eksema ( Peebles, 2012). Mekanisme Reaksi hipersensitivitas Reaksi hipersensitivitas terdiri dari berbagai kelainan yang heterogen yang dapat dibagi menurut berbagai cara: Menurut waktu timbulnya reaksi: A. Fase Dini Respons alergi terjadi dalam beberapa tahap yang diawali dengan sensitasi (pajanan dengan yang memacu produksi IgE spesifik), reaksi fase dini yang terjadi dalam beberapa menit setelah pajanan dan reaksi fase lambat yang terjadi kemudian. Pada reaksi dini, sel mast melepaskan berbagai mediator yang menimbulkan rekasi di berbagai organ sasaran seperti kulit, hidung, mata, otot polos bronkus, saluran cena dan vaskular. B. Fase Lambat Fase lambat terjadi dalam beberapa jam dan menggambarkan influks mediator . dalam fase lambat terjadi reaksi influks eosinofil yang memproduksi mediator seperti MBP, ECP dan LT yang dapat merusak jaringan dan berhubungan dengan reaksi alergi kronis. Sel Th2 yang diaktifkan dalam fase lambat memproduksi sitokin yang berperan dalam produksi IgE, kemotraksi eosinofil dan peningkatan jumlah sel mast mukosa ( Baratawidjaja, 2012). Menurut Gell dan Coombs Reaksi hipersensivitas oleh Robert Coombs dan Phlip HH Gell (1963) di bagi dalam 4 tipe reaksi. Pembaguan Gell dan Coombs dibuat sebelum analisis yang mendetail mengenai subset dan fungsi sel T diketahui. Berdasarkan penemuan-penemuan dalam penelitian imunologi telah dikembangkkan beberapa modifikasi klasifikasi Gell dan Coombs yang membagi lagi Tipe IV dalam beberapa subtipe reaksi. Meskipun reaksi Tipe I, II dan III dianggap sebagai reaksi humoral, sebetulnya reaks-reaksi tersebut masih memerlukan bantuan sel T atau peran selular. Oleh karena itu pembagian Gell dan Coombs telah dimodifikasi lebih lanjut. Reaksi tipe I ( IgE mediated hypersensitivity) Reaksi tipe I disebut juga reaksi tipe segera atau reaksi atopi dan timbul segera sesudah tubuh terpajan dengan alergen. Alergen yang masuk ke dalam tubuh menimbulkan respon imun berupa produksi IgE yang kemudian akan berikatan dengan suatu reseptor spesifik yang disebut Fcε-R yang terdapat pada dinding sel mast dan basofil. Ig E yang terikat akan menetap selama beberapa minggu. Pajanan ulang dengan alergen yang sama akan menyebabkan degranulasi sel mast atau basofil dan mengakibatkan pelepasan histamine dan mediator lain termasuk leukotrien, prostaglandin, sitokin, SRS-A (slow reacting substance-A), faktor kemotaksis, dan lain-lain. Mediator-mediator tersebut akan menimbulkan perubahan pada jaringan, yaitu: vasodilatasi, kontraksi otot polos, eksudasi cairan, edema, hipersekresi kelenjar dan akumulasi sel-sel radang, terutama eosinofil dan limfosit. Keadaan ini menimbulkan gejala klinis seperti urtikaria, dermatitis atopik pada kulit, bronkospasme pada asma bronkiale, rinitis alergika dengan gejala rinore dan obstruksi cavum nasi. Bila terjadi pada sistim peredaran darah umum maka akan mengakibatkan syok anafilaksis. (Welch JM, 2013, Mohanty, 2014, ). Manifestasi klinis reaksi Tipe I dapat bervariasi dari lokal, ringan sampai berat dan keadaan yang mengancam nyawa seperti anafilaksis dan asma berat. a. Reaksi lokal. Reaksi hipersensivitas Tipe I lokal terbatas pada jaringan atau organ spesifik yang biasanya melibatkan permukaan epitel tempat alergen masuk. Kecenderungan untuk menunjukkan reaksi Tipe I adalah diturunkan dan disebut atopi. b. Reaksi sistemik-anafilaksis Anafilaksis adalah reaksi Tipe I yang dapat fatal dan terjadi dalam beberapa menit. Anafilaksis adalah reaksi hipersensitivitas Gell dan Coombs Tipe I atau reaksi alergi yang cepat, ditimbulkan IgE yang dapat mengancam nyawa. Sel Mast dan basofil merupakan sel efektor yang melepaskan berbagai mediator.Pada 2/3 pasien dengan anafilaksis, pemicu spesisfiknya tidak dapat diidentifikasi. c. Reaksi pseudoalergi atau anafilaktoid Reaksi pseudoalergi atau anafilatoid adalah reaksi sistemik umum yang melibatkan pelepasan mediator oeh sel mast yang terjadi tidak melalui IgE. Secara klinis reaksi ini menyerupai reaksi Tipe I seperti syok, urtikaria, broonkospasme, anafilaksis, pruritus tetapi tidak berdasarkan atas reaksi imun. Reaksi ini tidak memerlukan pajanan terdahulu untuk menimbulkan sensitasi. Reaksi anafilaksis dapat ditimbulkan oleh antimikroba, protein, kontras dengan yodium, AINS dan pelemasan otot (Baratawidjaja, 2012). Reaksi tipe II ( reaksi sitotoksik ) Reaksi hipersensivitas Tipe II disebut juga reaksi sitotoksik atau sitolitik, terjadi karena dibentuk antibodi jenis IgG atau IgM terhadap antigen yang merupakan bagian sel pejamu.Reaksi diawali oleh reaksi antara antibodi dan determinan antigen yang merupakan bagian dari membran sel. Antibodi dapat menimbulkan lisis sel yang diperantarai komplemen atau melibatkan sel makrofag dan polymorphonuklear yang mempunyai Fc dan reseptor komplemen. Reaksi Tipe II dapat menunjukkan berbagai manifestasi klinik berupa reaksi transfusi, penyakit hemilitik bayi baru lahir, anemia hemolitik(Thomas WR, 2001). Reaksi tipe III atau kompleks imun Normal komplek imun dala sirkulasi diikat dan diangkut ke hati, limpa dan selanjutnya dimusnahkan oleh sel fagosit mononuklear tampa bantuan komplemen. Pada umumnya komplek imun yang besar dapat dimusnahkan denga mudah oleh makrofag dalam hati. Komplek imun kecil dan larut sulit dimusnahkan dan akan timbul masalah bila komplek imun tersebut mengendap di jaringan. Reaksi Tipe III mempunyai dua bentuk reaksi, lokal atau fenomen Erthus dan reaksi sistemik-serum sickness. Manifestasi klinik adalah reaksi arthus dengan gejala setempat: eritema, edema, serta serum sickness yang menimbulkan reaksi inflamasi sistemik seperti glomerulonefritis, atau rematoid artritis. Reaksi Herxheimer adalah serum sickness yg terjadi sesudah pemberian obat untuk penyakit infeksi kronis( sufilis, tripanosomiasis dan bruselosis)( Baratawidjaja, 20012) Reaksi tipe IV (Lymphocyte mediated delayed hipersensitivity) Baik CD4+ maupun Cd8+ berperan dalam rekasi Tipe IV. Sel T melepas sitokin, bersama dengan produksi mediator sitotoksik lainnya menimbulkan respon inflamasi seperti pada penyakit kulit hipersensitivitas tipe lambat.. Klinis berupa dermatitis kontak, timbul setelah 24-72 jam kontak dengan antigen obat, biasanya dalam bentuk topikal. Antigen penyebab antara lain anestesi lokal, topical aminoglycosida, paraben, Preservative ethylene diamine. Gejala lain yang sering timbul: erupsi kulit, febris, ‖mucocutaneous steven johnson syndrome”. Dewasa ini Reaksi hipersensivitas Tipe IV telah dibagi dalam DTH yang terjadi melalui sel CD4+ dan T Cell Mediated Cytosis yang terjadi melalui sel CD8+. Manifestasi klinis reaksi Tipe IV: a. Dermatis Kontak Dermatis kontak adalah peyakit CD4+ ang dapat terjadi akibat kontak dengan bahan tidak berbahaya. Kontak dengan bahan seperti formaldehid, nikel dan berbagai bahan aktif dalam cat rambut dapa menimbulkan dermatitis kontak terjadi melalui sel Th1 b. Hipersensivitas tuberkulin Hipersensiitas tuberkulin adalah bentuk alergi bakterial spesifik terhadap produk filtrat biakan M. tuberkulosis yang bila disuntikkan ke kulit akan menimbulkan reaksi hipersensitivitas lambat tipe IV. Yang berperan pada reaksi ini adalah sel limfosit CD4+. Pada individu yang pernah kontak dengan M. tuberkulosis, kulit bengkak terjadi pada hari ke 7-10 pasca induksi. c. T Cell Mediated Cytolysis ( Penyakit CD8+) Dalam T Cell Mediated Cytolysis, kerusakan terjadi melalui sel CD8+/CTL/Tc yang langsung membunuh sel sasaran. Penyakit yang ditimbulkan hipersensivitas selular cenderung terbatas pada beberapa organ saja dan biasanya tidak sistemik. Pada penyakit virus hepatitis, virus sendiri tidak sitopatik, tetapi kerusakan ditimbulkan oleh respon CTL terhadap hepatosisyang terinfeksi ( Baratawidjaja, 2012, Thomas, 2001). Diagnosis reaksi hipersensitivitas(alergi) A. Pemeriksaan Klinis Menegakkan diagnosis penyakit alergi diawali dengan anamnesis yang cermat. Parameter riwayat alergi dan nonalergi perlu diperhatikan. B. Tes Diagnostik Tes diperlukan untuk memastikan dianosis alergi, diagnosis banding dari penyakit lainnya, menemukan alergen yang sebelumnya tidak diduga dan pedoman pengobatan. Menghindari alergen spesifik dan pengobatan hendaknya berdasarkan atas riwayat dan tes diagnosis yang positif. 1. Tes in vivo Berbagai jenis tes alergi seperti tes kulit (gosok, gores, tusuk, intrakutan). a. Tes Tusuk Prinsip umum tes diagnosis adalah Tes Tusuk(TT) atau Skin Prick Test (SPT). Uji kulit hipersensivitas cepat digunakan secara luas untuk menemukan reakasi alergi yang diperantai IgE. Pemeriksaan ini merupakan sarana diagnostik utama di bidang alergi. Tes kulit diindikasikan untuk diagnostik reaksi IgE alergen spesifik. Jika dilakukan dengan baik, SPT memberikan bukti yang baik untuk menujukkan adanya alergi spesifik. Hasilnya harus dihubungkan dengan riwayat klinis penderita. Besar reaksi SPT tidak selalu berhubungan dengan gejala klinis. b. c. d. e. f. g. Tes intradermal Tes gores Tes tempel Tes tuberkulin Dermatografisme dan uji tekanan Tes panas dan dingin 2. Tes in vitro a. Pengukuran kadar IgE alergen spesifik dalam serum. IgE spesifik dapat ditemukan dalam serum. Nilai total IgE serum dan jumlah eosinofil dalam diagnosis rinitis adalah kurang sensitif dan spesifik. IgE total dapat meningkat pada beberapa sindrom nonatopik seperti defisiensi imun tertentu termasuk HIV, mieloma IgE, nefritis insterstisial karena obat, penyakit parasit dan penyakit kulit disamping ekzema dan sindrom hiper-IgE (dermatis dan infeksi piogenik rekuren). b. Petanda alergen dan inflamasi. Tes invitro juga dilakukan untuk menemukan berbagai pertanda alergi dan inflamasi . c. Pemeriksaan Histamin. Mediator alergi yang relevan seperti histamin dan triptase yang dilepaskan sel mast dan basofil, triptase oleh sel mast, ECP oleh eosinofil, merupakan pertanda intensitas rekasi alergi. d. Tes Provokasi Dilakukan dengan memajankan organ yang terliat alergen. Tes provokasi terpenting dalam praktek adalah, tes konjungtival, nasal, bronkial, oral, dan pernteral (misalnya subkutan untuk anatesi lokal). Sistem skoring digunakan sebagai indikasi tes provokasi adalah bila jumlah skor >5. Penanganan Konsep umum penaganan penyakit alergi dan titik-titik intervensinya seperti mencegah alergen, produksi antibodi dan pelepasan mediator. Pada umumnya ada 4 prinsi utama dalam penanganan penyakit alergi. A. Mengontrol lingkungan Yaitu menghindari faktor yang menimbulkan gejala. B. Pengobatan Secara farmakologi menggunakan obat seperti antihistamain, stabilisasi sel mas, modifier Leukotrien , epinefrin, Kortikosteroid, teofilin, dekongestan, β-adrenergik agonis. Secara nonfarmakologik menggunakan pengobatan fisis, konsultasi psikosomatik. C. Imunoterapi Efekif pada penderita yang benar denan RA, AB dan sengatan serangga. Diberikan dengan pengawasan dan pengarahan ahli alergi /imunologi serta petugas kesehatan yang terlatih untuk menangani anafilaktik. D. Penyuluhan Penderita belajar tentang pemicu gejala alergi, mengetahui caracara menangani penyakit dan mampu memberitahukan kepada yang lain mengenai apa yang harus dilakukan pada keadaan darurat. Pencegahan Penyakit Alergi Ada tiga stategi pencegahan yang merupakan kunci untuk meminimalkan respon alergi yaitu : - Primer : fokus terhadap pencegahan sensitasi dan perkembangan respon IgE, - Sekunder : usaha untuk mencegah ekspresi penyakit meskipun sensitasi terjadi. - Tersier : sasaran untuk mengontrol faktor yang menimbulkan gejala. Daftar Pustaka 1. Baratawidjaja KG, Rengganis I. Alergi Dasar. Interna Publising Pusat Penerbit Ilmu Penyakit Dalam, edisi 1; 7-37. 2. Peebles RS, Church MK and Durham SR. Prinsiples of Allergy diagnosis in : Holgate ST, Chruch MK, Broide DH, and Martinez FD,eds. Allergy: 4th ed. Elsevier . 2012. 137-142. 3. Hollander SM. Approach to the Allergic Patient in : Joo S, Kau AL,eds. Allergy, Asthma, and Immunology Subspecialty Consult: 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2013 ; 1-3. 4. Welch JM, Kau AL. Basic Immunology Underlying Allergic Reaction and Inflammation in : Joo S, Kau AL,eds. Allergy, Asthma, and Immunology Subspecialty Consult: 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2013 ; 4-7. 5. Baratawidjaja KG, Rengganis I. Imunologi Dasar. Badan Penerbit FKUI, edisi 10; 2012; 369-75. 6. Mohanty SK, Leela KS. Textbook of Immunology, 2nd Eds . Jaypee Brothers Publisher (Ltd). 20114; 143-144. 7. Thomas WR. Hypersensitivity: Immunological. Encyclopedia of Life Science. 2001; 1-3 RESUSITASI CAIRAN PADA WANITA HAMIL Masra Lena Siregar Divisi Penyakit Tropik Infeksi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala – RSUD Dr. Zainoel Abidin Pendahuluan Kehamilan merupakan suatu proses yang sangat rentan terhadap infeksi dan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi seperti sepsis sebagai penyebab paling sering terjadinya morbiditas dan mortalitas maternal yang berat. 1 Beberapa data penelitian menyebutkan bahwa morbiditas maternal akut yang terjadi akibat sepsis memiliki insiden yang bervariasi dengan kisaran 0,1-0,6 per 1000 kelahiran dengan tingkat mortalitas dan morbiditas selama masa kehamilan berkisar 7,6%. Predileksi terbanyak infeksi pada kehamilan terjadi pada area pelvis sehingga diperlukan penggunaan antibiotik yang bersifat broadspektrum dan tidak bersifat teratogenik.1,2 Definisi Infeksi adalah respon inflamasi sebagai penanda adanya mikroorganisme dalam jaringan sehat, sedangkan sepsis merupakan infeksi yang terjadi bersamaan dengan munculnya manifestasi sitemik atau Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) yang ditandai dengan terdapatnya dua atau lebih variabel berikut ini, yaitu: demam atau hipotermia (suhu >38ºC atau <36 ºC), takikardi (nadi >90x/menit), takipneu (frekuensi napas >20 x/menit), leukosit >12.000/mm3 atau <4.000/mm3, tetapi leukosit pada kehamilan berkisar 5,1-12.200/mm3, trisemester (TM) III berkisar 8.500/mm3, dan post partus berkisar 20-30.000/mm.3,4 Severe sepsis adalah sepsis yang disertai dengan disfungsi organ atau hipoperfusi organ. Sepsis induced hypotension merupakan penurunan tekanan darah sistolik (TDS) <90 mmHG atau mean arterial pressure (MAP) <70 mmHg atau penurunan TDS >40 mmHg atau kurang dari nilai normal tanpa ada penyebab hipotensi lainnya, sedangkan syok sepsis adalah sepsis induced hypotension yang tidak teratasi dengan resusitasi yang adekuat dan sepsisinduced tissue hypoperfusion adalah infeksi yang merangsang terjadinya hipotensi, peningkatan laktat atau oliguria.3 Etiologi Sepsis pada kehamilan merupakan hasil invasi bakteri ke dalam cavum uteri dan paling sering melalui infeksi ascending dari vagina atau cervix dan infeksi pada pelvis yang bersumber dari mikroflora endogen vagina, mikroflora intestinal dan transmisi secara seksual, seperti terlihat pada tabel 1.5,6 Tabel 1. Kuman Penyebab Syok Sepsis Pada Wanita Hamil. 6 Gram-negatif Gram-positif Anaerobic Fungi - Escherichia coli - Haemophilus influenzae Klebsiella species - Proteus species Pseudomonas species - Serratia species Pneumococcus Streptococcus, groups A, B dan C Enterococcus Staphilococcus aureus Listeria monocytogenes Bacteroides species Clostridium perfringens Fusobacterium species Peptococcus Peptostreptococcus - Penyebab sepsis pada kehamilan dibedakan atas infeksi yang berhubungan dengan obstetri dan non obstetri yang berkaitan dengan prosedur operasi seperti aborsi septik dan korioamniositis, infeksi yang tidak berhubungan dengan kehamilan tetapi terjadi pada populasi obstetri seperti pielonefritis dan infeksi saluran kencing bagian bawah, infeksi yang bersifat insidental selama kehamilan seperti pneumonia, HIV dan infeksi yang terjadi di rumah sakit seperti hospital acqiured pneumonia (HAP), seperti terlihat pada tabel 2.5,6 Perubahan Fisiologis pada Kehamilan yang berhubungan dengan Sepsis dan Syok Sepsis Beberapa perubahan fisiologi sistem tubuh pada kehamilan akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi, seperti dijelaskan berikut ini.5,6,7 A. Sistem kardiovaskular. Sistem sirkulasi menjadi hiperdinamik melalui penurunan resistensi vaskular sistemik pada awal kehamilan. Peningkatan cardiac output maternal tercermin pada peningkatan denyut jantung dan stroke volume dengan puncaknya berkisar 30-50% diatas nilai normal pada kehamilan minggu ke-30 dan maksimum pada minggu ke-32 dan disertai peningkatan stres jantung dengan manifestasi berupa penurunan resistensi vaskular sistemik, vasodilatasi dan depresi miokard sehingga menyebabkan kegagagalan hemodinamik yang cepat. Kehamilan normal juga mengakibatkan penurunan serum albumin yang mempengaruhi tekanan osmotik dan mengakibatkan kerentanan yang tinggi terhadap resiko edema paru saat kegagalan jantung terjadi. Tabel 2. Diagnosis yang berhubungan dengan sepsis pada obstetric.6 Infections associated with Chorioamnionitis pregnancy and/or pregnancyPostpartum endometritis related surgical procedures Septic abortion Septic thrombophlebitis Puerpural sepsis Infection of cesarean section wound Episiotomy infection Necrotizing fasciitis Pelvic abscess Infected cerciage Amniocentesis – septic abortion Umbilical cord biopsy Infections unrelated to pregnancy but occuring more often in the obstetric population Lower urinary tract infection Pyelonephritis Malaria Listeriosis Viral hepatitis (E) Varicella pneumonia Coccidioidomycosis Aspiration pneumonia Incidental infections during pregnancy Community-acquired pneumonia HIV-related infections Toxoplasmosis Cytomegalovirus Gastrointestinal infections Disseminated herpes Hospital-acquired infections at any hospital site including the ICU Pneumonia nosocomial Ventilator-associated pneumonia Catheter-related urinary tract infection Central line associated infection Skin and soft tissue infection related to peripheral intravenous catheters, infected surgical wound B. Sistem respirasi. Proses kehamilan dapat meningkatkan terjadinya ventilasi permenit dan menyebabkan alkalosis respiratorik ringan, penurunan volume tidal paru serta kompensasi oleh asidosis metabolik ringan. Faktor ini akan menurunkan kemampuan wanita untuk mengkompensasi untuk setiap asidosis yang merupakan bagian sepsis dan syok sepsis terutama jika terjadi kegagalan respirasi. C. Sistem renal. Dilatasi ureter yang disebabkan oleh relaksasi otot polos dan kompresi ureter oleh kehamilan akan mengakibatkan peningkatan resiko piuria dan pielonefritis, peningkatan tekanan intravesika dan refluks vesikoureter, peningkatan aliran darah renal, penurunan laju filtrasi glomerulus, peningkatan resiko bakteriuria asimptomatik dan penurunan kadar ureum dan kreatinin yang terjadi pada sistem renal. D. Sistem hematologi. Perubahan pada hematologi meliputi peningkatan volume eritrosit, anemia dan peningkatan volume plasma sehingga mencetuskan timbulnya penurunan suplai oksigen ke jaringan. E. Sistem gastrointestinal. Perubahan pada sistem gastrointestinal meliputi penurunan tonus otot saluran cerna, pengosongan lambung yang lama, peningkatan diafragma akibat kehamilan, peningkatan sel proinflamasi dan perubahan komposisi empedu sehingga menyebabkan peningkatan resiko aspirasi, kolestasis, hiperbilirubinemia, ikterus dan perpindahan bakteri. F. Sistem koagulasi. Peningkatan faktor VII, VIII, IX, X, XII, Von willebrand, fibrinogen, penurunan aktifitas fibrinolitik dan protein C merupakan perubahan yang mempengaruhi sistem pembekuan darah sehingga meningkatkan resiko tromboemboli dan disseminated intravascular coagulation (DIC).8 G. Sistem genitalia Perubahan fisiologis traktus genitalia bawah mencakup penurunan pH dan peningkatan glikogen epitel vagina akan menyebabkan timbulnya resiko infeksi intraamniotik dan resiko menderita pielonefritis.5 Penanganan Wanita hamil dengan sepsis dapat mengalami kematian yang cepat setelah onset terjadi. Pengenalan yang cepat, stabilisasi dan penanganan terhadap penyebab dasar dapat mencegah proses kematian sel dan pasien. Pengenalan tanda-tanda syok melalui hipoksia jaringan dan disfungsi organ merupakan kunci utama terhadap penanganan sepsis yang diawali dengan tanda-tanda SIRS. Monitoring yang tepat terhadap fungsi mental, denyut nadi, tekanan darah, frekuensi pernapasan dan suhu direkomenasikan sebagai langkah awal untuk mendeteksi gangguan ini, hal ini terlihat pada gambar 1 di bawah ini.5,9 Penatalaksanaan ditujukan untuk menstabilkan pasien sejalan dengan diagnosa dan terapi resusitasi serta eliminasi sumber infeksi baik dengan tindakan operasi maupun dengan penggunaan antibiotik yang tepat bahkan tindakan operasi berdasarkan The Surviving Sepsis Campaign (SSC) dalam 6 jam pertama dengan target resusitasi adalah central venous pressure (CVP) 8-12 mmHg, mean arterial pressure (MAP) 65 mmHg, produksi urin berkisar 0,5 cc/kgbb/jam dan central venous (superior vena cava) atau mixed venous oxygen saturation 70% atau 65%.9 Penanganan hemodinamik pada sepsis sangat berhubungan dengan hipotensi, resusitasi cairan yang diawali dengan cairan hangat sebanyak 500 ml setiap 15 menit dengan target cairan adalah 20 ml/kgBB selama 1 jam pertama terapi mengoptimalisasikan preload, afterload dan kontraktilitas jantung. Evaluasi meliputi tanda vital, pulse oxymetry, pemakaian CVC dan urin output untuk menghindari edema pulmonal, menjaga cairan yang cukup dan mencegah overload dengan peningkatan tekanan jantung tanpa perubahan hemodinamik. Pemberian bukanlah suatu superior dibandingkan kristaloid tetapi penggunaan cairan ini digunakan untuk mencegah kelebihan air akibat penggunaan kristaloid. Penggunaan CVC dan central venous oxygen saturation bertujuan untuk memastikan saturasi oksigen yang kembali ke jantung, mencerminkan keseimbangan pengiriman oksigen ke sistemik dan pemakaian oksigen di jaringan. Penurunan saturasi oksigen dapat terjadi pada peningkatan konsumsi oksigen (hipertermia, stres) atau penurunan oksigen (hipoksia, penurunan cardiac output, anemia).4 Gambar 1. Diagram Early Goal Directed Treatment Sepsis pada Kehamilan.5 Penggunaan vasopresor dipertimbangkan jika resusitasi cairan mengalami kegagalan dengan MAP <50 mmHg. Tujuan pemberian vasopresor ini adalah untuk mengembalikan perfusi jaringan yang efektif dan menormalkan kembali metabolisme selular. Norepinefrin digunakan sebagai lini pertama pemberian vasoaktif pada syok septik, meskipun mempunyai resiko terjadinya penurunan aliran darah ke uterus, namun dapat memberikan banyak keuntungan yaitu dengan memperbaiki hemodinamik dan saturasi oksigen sebesar 93% dibandingkan pemberian dopamin sebesar 31%, selain itu penggunaan dopamin dapat mengakibatkan aritmia, namun dosis rendah dapat memperbaiki sirkulasi renal. Pemberian vasopresin dilakukan pada hipotensi refrakter setelah resusitasi cairan dan pemberian norepinefrin tidak dapat memperbaiki MAP dan fungsi renal.5,6 Infeksi pada kehamilan disebabkan oleh polimikroba dengan kuman terbanyak disebabkan kuman penyebab infeksi terbanyak pada kehamilan adalah streptococcus beta hemolitikus, Escherichia coli, Clostridium, Staphylococcus aureus, Coliforms, Streptococcus species, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes dan Klebsiella, sedangkan sumber infeksi yang sering terjadi meliputi pyelonephritis, chorioamnionitis, endometritis, septic abortion, necrotizing fasciitis dan infeksi kulit. Antibiotik intravena diberikan sesegera mungkin dalam 1 jam sejak terdiagnosa dengan sepsis berat dan direkomendasikan pemberian broadspectrum yang dapat mengeliminasi gram positif, gram negatif dan bakteri anaerob dan diajurkan penggunaan kombinasi seperti penisilin, aminoglikosida, vancomisin, clindamisin atau piperacilin- tazobactam. Farmakologi antibiotik juga menjadi suatu pertimbangan khusus pada kehamilan karena adanya beberapa perubahan seperti volume distribusi yang lebih besar dan berhubungan dengan absorbi, eksresi dan mengakibatkan penurunan kadar obat dalam serum terutama untuk antibiotik yang dieksresikan melalui urin dan keamanan antibiotik terhadap janin.5,7,10 Pemberian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi dan evaluasi ilakukan untuk melihat efikasi, mencegah resistensi dan toksisitas. Pemeriksaan kultur dianjurkan untuk melihat kuman dan sensitivitas antibiotik. Pemberian kortikosteroid direkomendasikan pada penggunaan vasopresor dan resusitasi cairan yang adekuat namun tidak mencapai target dalam penanganan sepsis. Pemberian hidrokortison dosis rendah 200-300 mg per hari selama 7 hari yang terbagi dalam 3-4 dosis dapat menurunkan angka mortalitas dan meningkatkan survival rate pada penderita vasopressor-dependent septic shock.7 Kontrol gula darah dilakukan dengan pemberian secara intravena pada pasien sepsis berat dengan target <180 mg/dl setiap 1-2 jam dan evaluasi setiap 4 jam dilakukan jika penderita sudah stabil. Penanganan lainnya meliputi profilaksis terhadap stress ulcer dan deep vein thrombosis. Pemberian komponen darah baik trombosit maupun PRC (packed red cell) dilakukan sesuai dengan perdarahan yang terjadi dengan target trombosit >50.000/mm3, sedangkan PRC diberikan jika Hb <7 g/dl dengan target Hb 7-9 g/dl.1,3 Pemantauan terhadap janin ditujukan untuk mencegah gawat janin meliputi monitoring dengan cardiotocography, pertimbangan untuk segera dilahirkan dan pemakaian anestesi.8Mekanisme keseluruhan dapat dilihat pada gambar 2.3 Kesimpulan Penanganan yang cepat dan tepat terhadap sepsis pada kehamilan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Tercapainya target penanganan dalam 6 jam pertama memberikan prognosis yang lebih baik dengan pemakaian antibiotik broadspectrum serta mempertimbangkan efek teratogenik yang terjadi pada janin. Daftar pustaka 1. Cormack C. Diagnosis And Management Of Maternal Sepsis And Septic Shock . BJOG. 2011;118 (1):1–203 2. Fernandez R. Severe Sepsis And Septic Shock - Understanding a Serious Killer. Intechopen. 2012:1-25 3. Barton and Shibai. Severe Sepsis And Septic Shock In Pregnancy. Obstet Gynecol. 2012;120:689–706 4. Dellinger PR, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, et al. Surviving Sepsis Campaign : International Guidelines For Management Of Severe Sepsis And Septic Shock. CCJM. 2013;41(2):580-630 5. SA Maternal & Neonatal Clinical Network. Clinical Practice Guideline On Sepsis In Pregnancy. Government of South Australia. 2015:1-15 6. Ricardo Luiz Cordioli, Eduardo Cordioli, Romulo Negrini, Eliezer Silva. Sepsis And Pregnancy: Do We Know How To Treat This Situation?. Rev Bras Ter Intensiva. 2013;25(4):334-44 7. NHS. Obstetrics Empirical Antimicrobial Guidelines. NHS. 2015:1-5 8. Madiah A, Khan F. A Review Of Critical Care Management Of Maternal Sepsis. Anaesth, Pain & Intensive Care. 2014;18(4):1-23 9. Mathai M, Sanghvi H, Guidotti RJ. Managing Complications In Pregnancy And Childbirth. WHO.2000:1-390 10. Royal Hospital For Women. Sepsis In Pregnancy And Postpartum. Maternity Services LOPs Group.2013:1-6. HEPATITIS B PADA KEHAMILAN Wira idiawati, Azzaki Abubakar Divisi Gastroentero Hepatologi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh I. Pendahuluan Hepatitis B merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV) yang memiliki DNA (deoksiribonucleat acid) berkapsul dan menginfeksi hati serta menimbulkan nekrosis dan inflamasi hepatoselular. Infeksi HBV terbagi atas akut dan kronik dengan derajat keparahan penyakit yang bervariasi yaitu diawali dengan gejala asimptomatik, simptomatik dan progresif.1,2 Hepatitis B akut biasanya sembuh sendiri yang ditandai dengan inflamasi akut dan nekrosis hepatoselular dengan angka kejadian fatal 0,5-1%. Chronic Hepatitis B (CHB) adalah hepatitis B surface antigen (HbsAg) persisten atau menetap selama 6 bulan atau lebih dengan atau disertai replikasi viaral aktif atau kejadian HCC dan inflamasi hati.1 Kronisitas hati sangat dipengaruhi oleh faktor usia dan sering mengikuti proses infeksi akut pada neonatus yaitu sekitar 90% lahir dari ibu dengan hepatitis B e antigen (HbeAg) positif, balita sekitar 20-60% dan jarang terjadi (<5%) pada dewasa. Mayoritas penderita CHB terinfeksi saat lahir atau pada masa balita. Hepatitis B merupakan masalah utama kesehatan dengan estimasi 240 juta orang terinfeksi virus ini terutama pada negara berkembang dan miskin. Komplikasi utama CHB adalah sirosis dan hepatocellular carcinoma (HCC) yang mengenai sekitar 20-30% penderita, sedangkan kematian terjadi pada 650.000 penderita.1,2 Pemberian obat antiviral dengan tujuan menekan replikasi HBV dapat mencegah progresifitas penyakit menjadi sirosis, menurunkan resiko HCC dan kematian, namun obat tersebut tidak tersedia secara meluas atau digunakan di negara ekonomi rendah dan berkembang sehingga pencegahan komplikasi tidak berjalan sempurna.1 Transmisi HBV dicegah mulai dari infeksi perinatal dan balita melalui vaksinasi hepatitis B, vaksinasi ulangan dan strategi pencegahan yang meliputi populasi seperti penggunaan obat suntik, hubungan sesama jenis, pekerja seks komersial dan pencegaha transmisi penyakit ini pada petugas kesehatan.3 II. Etiologi HBV merupakan virus yang sangat kecil, berasal dari Hepadnavirus family, bersifat hepatotropic dan menginfeksi manusia dengan inflamasi hati yang terjadi melalui proses immune mediated. HBV juga dikenal dengan virus onkogenik yang beresiko terjadinya HCC. Genome encodes HbsAg, HBc Ag, polimerase virak dan protein HBx. Virus ini mempunyai komponen luar yang dinamakan HbsAg dan komponen dalam nukleosida yaitu hepatitis B core antigen ( HbcAg). HBV DNA terdeteksi dalam serum dan digunakan untuk menilai replikasi virus. 1 III. Transmisi Penularan HBV terjadi melalui paparan percutaneus atau mukosa dan cairan tubuh termasuk saliva, menstruasi, vagina dan cairan sperma. Transmisi secara seksual terjadi pada penderita l yang tidak mendapatkan vaksinasi, homoseksual, heteroseksual dan kontak dengan pekerja seks komersial. Infeksi yang terjadi pada dewasa mengakibatkan hepatitis kronis pada 5% kasus. Penularan dapat terjadi secara insidental seperti penggunaan alat medis, prosedur dental, sterilisasi alat medis yang tidak adekuat, penyalahgunaan obat suntik, tatto dan akupuntur.1,4 Penularan perinatal merupakan rute utama infeksi HBV diseluruh dunia terutama di Cina dan Asia Tenggara. Profilaksis yang tidak dilakukan terutama pada ibu yang terinfeksi dengan HbeAg seropositif akan menularkan ke bayi segera setelah lahir. Resiko penularan menjadi lebih tinggi jika ibu menderita hepatitis B akut pada trisemester II atau III kehamilan atau dalam 2 bulan setelah melahirkan. Infeksi pada fetus terjadi melalui perdarahan antepartum dan plasenta. Resiko terjadinya infeksi kroni meningkat pada usia 6 bulan sekitar 90% namun menurun 20-60% pada usia antara 6 bulan sampai 5 tahun. Transmisi horizontal terjadi pada keluarga terutama antar anak-anak yaitu sekitar 50%.1,3,5 IV. Patogenesis Fase inkubasi terjadi tanpa adanya respon host terhadap replikasi virus karena HBV tidak merangsang sistem imun innate untuk mengenali kuman patogen, sedangkan pada fase infeksi terjadi respon imun selular termasuk antibodi HBV. Eliminasi HBV dimulai beberapa minggu sebelum onset penyakit melalui mekanisme sel T dependen non sitolitik tetapi kemudian respon imun sitolitik menimbulkan gejala hepatitis akut dan mengakibatkan resolusi serologi klinis. Sel T akan menekan replikasi virus ke kadar terendah dengan timbulnya Anti-HBc pada onset penyakit dan merupakan antibodi HBV pertama, kemudian anti-HBe, anti-pre-S dan anti-SHB yang bertujuan untuk mengeliminasi virus hepatitis pada hati. anti-HBs terbentuk selama fase konvalens, meningkatkan opsonisasi HbsAg dan infeksi hepatosit dengan melaepaskan HBV. Perbaikan serologi ditandai dengan hilangnya HbsAG selama beberap bulan setelah onset penyakit. Vaksinasi mengakibatkan peningaktan imunitas innate dan adaptif, mengakibatkan penurunan viral load dan hilangnya virus dan mencegah infeksi HBV akut dan kronik.5,6 V. Gambaran klinis Acute phase of hepatitis B (AVH-B) mempunyai manifestasi klinis yang bervariasi mulai subklinis atau hepatitis nonikterik, hepatitis ikterik dan hepatitis fulminan. Perjalanan penyakitnya dimulai dari periode inkubasi, preikterik, ikterik dan fase konvalesen. Fase inkubasi merupakan onset timbulnya gejala atau jaundice sekitar 75 hari ( kisaran 40-140 hari). Onset HBV tidak menunjukkan gejala spesifik seperti malaise, penuruna nafsu makan, nausea dan nyeri di regio perut kanan atas. Fase ikterik ditandai dengan perburukan gejala seperi fatique dan anoreksia, jaundice yang timbul beberapa hari sampai beberapa bulan sekitar 2-3 minggu, gatal dan BAB pucat, sedangkan fase konvalesens dimulai dengan perbaikan jaundice. Pemeriksaan fisik pada infeksi ini adalah ditemukan hepatomegali ringan dan nyeri tekan ringan.6 CHB bersifat dinamik dan komplek dan progresifitas melalui beberapa fase yaitu immune toleran, immune active, immune control dan immune escape seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini.7,8 Gambar 1. Fase infeksi dan marker pada hepatitis B VI. Skrining Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi atau skrining awal penderita hepatitis dapat dilakukan dengan menggunakan marker HbsAg pada semua populasi yang beresiko menderita hepatitis Diagnosa HBV melalui pemeriksaan HbsAg menurut Europe guideline terlihat pada gambar 2 di bawah ini.9 Gambar 2. Skrining Hepatitis B dengan menggunakan serum HbsAg9 VII. Diagnosa Diagnosa hepatitis B ditegakkan melalui beberapa pemeriksaan non invasif seperti APRI (Aspartate Aminotrasnferase/ AST to platelet ratio index) yang direkomendasikan oleh WHO untuk melihat adanya sirosis ( skor APRI > 2 pada dewasa) pada daerah dengan sumber daya yang terbatas, selain itu juga dapat digunakan i (FibroScan) atau FibroTest pada daerah maju. Pemeriksaaan APRI dapat digunakan untuk menilai stadium penyakit hati pada tahap awal dan selama dilakukan evaluasi. Algoritma diagnosis menurut WHO ini terlihat pada gambar 3 di bawah ini.1 VIII. Penatalaksanaan Tujuan utama pemberian terapi pada infeksi HBV adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dan bertahan hidup melalui pencegahan progresifitas dan komplikai penyakit seperti sirosis, penyakit hati stadium akhir, HCC dan kematians erta pencegahan transmisi HBV kepada orang lain yang dilakukan melalui vaksinasi, pemberian terapi dan pencegahan transmisi. CHB tidak bisa dieradikasi secara sempurna karena adanya covalently closed circular DNA (cccDNA) pada nukleus sel hepatosit yang terinfeksi dan genome HBV dapat berintegrasi dengan genome host serta mencetuskan onkogenesis menjadi HCC.6 Gambar 3. Algoritma Diagnosis Dan Penatalaksanaan Hepatitis B Kronik 1 Prioritas pengobatan ditujukan pada semua usia dewasa, remaja dan anak-anak yang menderita CHB dan memunyai gejala klinis sirosis hepatis dekompensata atau kompensata berdasarkan skor APRI ( sirosis jika skor > 2 pada dewasa) dan berdasarkan kadar SGPT, status HbeAg atau kadar HBV DNA. Terapi juga direkomendasikan pada dewasa dengan CHB yang tidak mempunyai gejala klinik sirosis berdasarkan skor APRI tetapi berusia lebih dari 30 tahun, kadar SGPT yang persisten abnormal dan tingginya replikasi HBV ( HBV DNA >20.000 IU/ml) tanpa memperhatikan status HbeAg.1,3 Kehamilan sebagai salah satu populasi khusus membutuhkan manajemen khusus dalam penanganan HBV karena berhubungan dengan usia kehamilan dan janin. Manajemen HBV pada kehamilan juga dijelaskan dalam gambar 4 berikut ini.8CHAPTER 5: WHO TO TREAT AND Gambar 4. Manajemen Hepatitis B Kronik Pada Kehamilan Antiviral lini pertama yang direkomendasikan adalah golongan nucleos(t)ide analogues (NAs) atau Peg-IFN. Perbandingan kedua terapi tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.9 Tabel 1. Perbandingan terapi pada infeksi CHB Wanita hamil yang menderita HBV juga diberikan terapi seperti pada dewasa lainnya dan dianjurkan pemberian tenofovir, namun tidak direkomendasikan penggunaan antiviral secara rutin dalam mencegah transmisi HBV secara vertikal dari ibu ke anak. Pencegahan hepatitis B pada infant dan neonatal diberikan dalam 24 jam setelah lahir melalui vaksinasi hepatitis B yang dibagi atas 2 atau 3 dosis.2 ,10Alur skrining, diagnosa dan penatalaksanaan pada wanita hamil terlihat pada gambar 6 di bawah ini.10 Terapi interferon hanya diberikan pada wanita yang merencanakan kehamilan bukan pada wanita hamil karena obat ini memiliki efek anti proliferatif, sehingga dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi pada wanita selama penggunaan interferon. Wanita hamil dengan HBV yng membutuhkan terapi antiviral atau yang merencanakan kehamilan selama menjalani terapi harus mempertimbangkan resiko dan keuntungan bagi ibu dan janin seperti progresifitas penyakit, SGPT yang meningkat pada kehamilan, gangguan pertumbuhan janin, penularan secara vertikal, terapi dalam jangka waktu lama dan kehamilan berikutnya. Tenofovir merupakan pilihan utama pada kehamilan dan diberikan mulai dari semester I sampai semester III. Resiko terjadinya transmisi secara vertikal selama periode perinatal dapat dicegah dengan penggunaan NAs jangka pendek mulai usia kehamilan 28-32 minggu seperti tenofovir atau telbuvidine pada ibu dengan HBV DNA diatas 6–7 log IU/ml dan dihentikan setelah melahirkan dan menyusui jika tidak ada kontraindikasi untuk menghentikan terapi ini. Menyusui tidak dianjurkan saat menjalani pengobatan NAs dan tetap dilanjutkan meskipun ditemukan peningkatan SGPT selama periode pengobatan. 6,9,11 Terapi antiviral yang digunakan dalam kehamilan tercantum dalam tabel 2 berikut ini10.12 Vaksinasi yang dilakukan untuk mencegah HBV meliputi vaksinasi aktif dengan menggunakan antigen HBsAg yang digunakan secara tunggal atau kombinasi dengan vaksinasi lainnya. Vaksinasi pasif diberikan dengan menggunakan Hepatitis B immunoglobulin (HBIg) dengan dosis 0.06 mL/kgBB pada dewasa atau 200 IU pada infant secara intramuskular (IM) dan bertahan selama 3-6 bulan.4,12,13 Indikasi profilaksis sebelum paparan antara lain : semua bayi baru lahir, anak dengan status HbsAg ibu yang tidak diketahui, anak-anak dan remaja yang belum mendapatkan vaksinasi, dewasa yang memiliki faktor resiko infeksi HBV dan pasien dengan penyakit infeksi berat. Vaksinasi diberikan pada bulan 0, 1, dan 6, sedangkan pada bayi baru lahir diberikan dalam 12 jam pertama. Respon vaksin akan menurun pada perokok, obesitas, faktor genetik, imunosuppresi, gagal ginjal dan lainnya. Jika tidak ada respon anti HBs, maka vaksinas diulang kembali pada bulan ke-0, 1 dan 2.13,14,15 Profilaksis setelah paparan diberikan melalui penentuan status HbsAg dan anti-HBs, negara endemis HBV, belum pernah mendapatkan vaksinasi HBV sebelumnya sehingga harus diberikan HBIg dan vaksin hepatitis B 24 jam setelah 24 jam paparan.2,7 Dosis booster tidak diberikan secara rutin kecuali pada individu dengan resiko tinggi dan diberikan jika kadar anti-HBs <10 mIU/ml. vaksinasi yang diberikan pada wanita hamil tidak memiliki efek teratogenik atau faktor resiko lainnya terhadap janin baik vaksinasis aktif atau pasif.14 Tabel 2. Terapi Antiviral Pada HBV dengan kehamilan dan efek samping . Prognosa Kehamilan yang disertai dengan HBV mengakibatkan peningkatan transmisi secara vertikal dari ibu ke bayi. Resiko terjangkitnya infeksi ini dapat dikurangi melalui proses vaksinasi yang diberikan secepat mungkin dan dilakukanvaksinasi booster untuk mencegah komplikasi lanjut dari hepatitis B. IX. X. Kesimpulan Infeksi HBV pada kehamilan merupakan transmisi yang terjadi secara vertikal. Diagnosa yang tepat dan penanganan yang cepat dapat mencegah timbulnya komplikasi HBV baik terhadap ibu maupun janin. XI. 1. 2. 3. 4. Daftar Pustaka Lesi O, McMahon B, Siegfried N, Abraham P, Aghokeng A, et al. Guidelines For The Prevention, Care And Treatment Of Persons With Chronic Hepatitis B Infection. WHO. 2015:1-166 Terrault NA , Bzowej NH, Chang KM, Hwang JP, Jonas MM, et al. AASLD guidelines for treatment of chronic hepatitis B. Hepatology. 2016; 16(1): 261-83 Vu Lam Ng, Gotsch Pb, Langan Rc. Caring for Pregnant Women and Newborns with Hepatitis B or C. Am Fam Physician. 2010;82(10):1225-9 Buggs AM, Dronen SC. Viral Hepatitis. Emedicine.2015:1-21 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Yapali S, Talaat N, Anna S. Management Of Hepatitis B: Our Practice And How It Relates To The Guidelines. Clinical Gastroenterology And Hepatology 2014;12:16–2 Sarin, Kumar, Lau, Abbas, Chan, et al. Asian-Pacific Clinical Practice Guidelines On The Management Of Hepatitis B: A 2015 Update. Hepatol Int. 2016;10:1–98 Feld J, Janssen, Abbas Z, Elewaut A, Ferenci P, Isakov V. Hepatitis B. WGO Global Guideline. 2015: 1-35 Han GR, Xu CL, Zhao W, Yang YF. Management of chronic hepatitis B in pregnancy. World J Gastroentero. 2012;18(33):4517-21 Brook G, Soriano V, Bergin C European Guideline For The Management Of Hepatitis B And C Virus Infections. International Journal of STD & AIDS. 2010; 21:669–78 Apuzzio J, Block JM, Cullison S, Cohen C,Leong SL, Et Al. Chronic Hepatitis B In Pregnancy A Workshop Consensus Statement On Screening, Evaluation, And Management, Part 1-2. The Female Patient. 2012;37:1-9 Curran M. Hepatitis B Virus (HBV) in Pregnancy. Perinatology. 2015:1-6 Borgia G, Carleo MA, Gaeta GB, Gentile I. Hepatitis B In Pregnancy. World J Gastroenterol. 2012; 18(34): 4677-83 Ho V, Ho W Hepatitis B In Pregnancy: Specific Issues And Considerations. J Antivir Antiretrovir. 2012;4(3)): 51-9 Stamatopoulos C, Louise B, Godfrey A, Haworth E, Ryder S, Shing S. Guideline For Identifying And Testing Hepatitis B Positive Pregnant Women And Neonates. NHS. 2014: 1-14 EMA, CHMP. Guideline On The Clinical Investigation Of Hepatitis B Immunoglobulins. European Medicines Agency. 2015:1-11 DEPRESI PADA KEHAMILAN Vera Abdullah Divisi Psikosomatik Bagian / SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Pendahuluan Depresi pada kehamilan dan dua belas bulan pertama setelah melahirkan diperkirakan terjadi sekitar 7-13 % pada wanita.1,2,3 Data menunjukkan juga bahwa tingkatan depresi pada kehamilan lebih sering terjadi dibandingkan setelah melahirkan. Pada depresi setelah melahirkan terkait efek yang tidak diharapkan pada perkembangan dan berikut perilaku anak masih belum diketahui. Dalam hal depresi pada kehamilan ini bisa menjadi suatu kendala terhadap hubungan perkawinan dan mempunyai dampak yang tidak diharapkan pada kehamilannya terkait apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Gejala depresif pada kehamilan trimester akhir terkait dengan tingginya risiko depresi setelah melahirkan, begitu juga dengan risiko persalinan seksio sesaria dan terjadinya perawatan anak nantinya pada unit khusus. Pencegahan gejala depresi demikian menjadi suatu hal yang menguntungkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya.2 Definisi Depresi Depresi pada kehamilan (depresi perinatal) merupakan suatu episode gangguan depresi mayor (Mayor depression disorder) yang terjadi selama kehamilan atau dalam 6 bulan pertama setelah melahirkan, dan merupakan satu satu dari komplikasi yang tersering baik dari periode prenatal dan postpartum dengan prevalensi 10-15% pada wanita usia produktif.4 Faktor Risiko Beberapa penelitian menilai faktor risiko depresi pada kehamilan diantaranya termasuk adanya pengaruh sosiodemografi seperti kurangnya mengecap pendidikan, rendahnya status sosioekonomi, dan kurangnya dukungan pasangan, selanjutnya variabel obstetriknya seperti riwayat kehamilan sebelumnya, kehamilan yang tidak disengaja, adanya komplikasi selama kehamilan, dan kondisi psikososial seperti episode depresif sebelumnya, kehidupan yang penuh dengan stress, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya dukungan sosial.5 Patogenesis Patogenesis depresi pada kehamilan sampai saat ini belum diketahui dan masih terus diteliti. Diduga adanya disregulasi hormonal, abnormalitas pada aktivitas aksis hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA axis) dan kontribusi genetik dan epigenetik yang berperan pada perkembangan gangguan mood reproduksi selama kehamilan.4 Hormon steroid reproduktif wanita, estrogen dan progesteron berasal dari prekursor umumnya yaitu kolesterol. Hormon ini selanjutnya berfungsi untuk reproduksi yang menunjukkan efek neuroregulasi potensial pada perilaku yang nonreproduktif termasuk mood dan kognitif. Estrogen dan progesterone memiliki interaksi kuat dengan HPA axis dan dapat mencetuskan abnormalitas HPA axis pada wanita yang rentan. Menariknya, perubahan hormonal menempati transisi dari periode kehamilan hingga setelah melahirkan. Kehamilan trimester ketiga dikenal dengan tingginya kadar estrogen dan progesterone dan hiperaktif HPA axis (normal pada kehamilan) dengan tingginya kadar kortisol plasma yang dirangsang dengan adanya kadar estrogen dan progesterone yang meningkat. Pada saat mau melahirkan dan selama transisi hingga periode setelah melahirkan, terjadi penurunan cepat kadar estrogen dan progesterone, saat ini aktivitas HPA axis tumpul karena tertekan oleh sekresi hipotalamus kortikotropin releasing hormone (CRH). Penekanan bisa disebabkan oleh lamanya waktu untuk mencapai hipertropis korteks adrenal (karena keadaan hiperstimulus selama kehamilan) menuju pada pengecilan ukurannya yang progresif dan secara bertahap mencapai ukuran normal.4 Gambaran Klinis Gejala depresi pada kehamilan sulit dibedakan dengan gejala yang kebanyakan normal muncul selama kehamilan sehingga menyebabkan salah persepsi sebagai gejala depresif yang akhirnya mempengaruhi dalam diagnosisnya. Gejala depresif terkadang salah diinterpresikan terkait dengan kehamilan. Sebagai contoh perubahan dalam nafsu makan, tidur, hasrat dan kurangnya energi. Depresi pada kehamilan tidak berbeda dengan depresi dalam periode lainnya dari kehidupan.6 Gejala depresi mayor berdasarkan DSM-IV TR sebagai berikut :7 Dijumpai lima atau lebih gejala di bawah ini : selama periode dua minggu menunjukkan perubahan dari fungsi sebelumya; minimal satu gejala berikut : 1. Mood depresif, 2. Kehilangan minat; Tidak termasuk gejala yang jelas terkait kondisi medis umum atau mood inkoheren delusi atau halusinasi mood depresif hampir sepanjang hari, bisa setiap hari dengan gejala subjektif (rasa sedih atau hampa) atau teramati oleh orang lain (berurai air mata) penurunan minat hamper sepanjang hari, bisa setiap hari yang dirasakan atau teramati oleh orang lain kehilangan berat badan yang nyata tanpa diet atau peningkatan berat badan (perubahan lebih dari 5% berat badan dalam sebulan) atau penurunan atau peningkatan dalam nafsu makan hampir setiap hari insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari psikomotor agitasi atau retardasi hampir setiap hari (teramati oleh orang lain, bukan hanya rasa gelisah atau gerakan yang cenderung lambat keletihan atau kehilangan energy hampir setiap hari rasa tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan (bisa berupa delusi) hampir setiap hari berkurangnya kemampuan untuk berfikir atau konsentrasi atau adanya kebimbangan hampir setiap hari (baik dirasakan atau teramati) pemikiran berulang terhadap kematian (bukan hanya takut mati), ide berulang untuk suicide tanpa rencana khusus, atau usuha suicide atau rencana khusus untuk melakukan suicide Diagnosis Skrining terhadap depresi pada kehamilan yaitu :6 1. Prekonsepsi : sebaiknya ditanyakan riwayat gangguan mental dan pengobatan pribadi dan keluarga 2. Kehamilan : selama kunjungan antenatal rutin yang pertama 3. Postpartum : selama kunjungan postnatal minggu 4, 6 dan postpartum bulan 3, 4 Modalitas skiring depresi yang dapat digunakan pada kehamilan dan setelah melahirkan yaitu :6 1. Edinburgh postnatal depression scale yang tervalidasi 2. Patient Health Questionnaire-9 (nilai ≥ 10 menunjukkan gejala depresi yang bermakna klinis) 3. National Institute for Health and Clinical Excellence : skrining untuk depresi pada kehamilan Tatalaksana Pada saat seorang wanita hamil didiagnosis depresi maka individu tersebut harus mendapatkan pengobatan.7 Tujuan pengobatan terapeutik pada depresi pada kehamilan yaitu untuk mencapai kestabilan mental si ibu, tanpa menyebabkan cedera terhadap janinnya. Jadi perlu menilai untung ruginya baik bagi ibu maupun janinnya terhadap risiko penting pengobatan. Pilihan pengobatan untuk depresi pada kehamilan termasuk farmakologi dan psikoterapi. Pada tingkatan depresi ringan hingga sedang, psikoterapi direkomendasikan sebagai pilihan pertama. Meskipun terdapat sedikit penelitian yang memfokuskan pada efikasi psikoterapi terhadap depresi pada kehamilan, Tatalaksana sebaiknya berdasarkan keputusan klinis dokter, kenyamanan pasien dan ketersediaan fasilitas profesional dan dukungan terhadap individu.6 Data menunjukkan keterkaitan antara penggunaan selektif serotonin reuptake inhibitor dengan kecilnya ukuran bayi selama dalam masa kehamilan. Antidepresan dikatakan tidak terkait dengan malformasi kongenital mayor, meskipun paroxetin telah dilabel oleh the US Food and Drug Administration sebagai penyebab defek jantung septum pada janin yang terpapar. Terdapat dua penelitian terkait pemakaian SSRI yang didapatkan < 1% risiko absolut hipertensi pulmoner persisten pada bayi, yang merupakan abnormalitas fungsional sangat fatal.8 Rekomendasi Perhimpunan Psikiatri Amerika dan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Amerika merekomendasikan sebagai berikut :6 1. Wanita yang rencana memulai suatu perkawinan dan mengalami gejala depresi ringan selama 6 bulan atau lebih lama bisa melakukan penurunan dosis obatnya. Hal ini tidak tepat untuk wanita dengan riwayat ansietas dan depresi berat, atau yang memiliki gangguan bipolar atu riwayat tentamen suicide. 2. Wanita hamil yang mengalami kondisi psikiatris stabil dan cenderung melanjutkan pengobatan dapat melanjutkannya setelah berkonsultasi dengan psikiater dan dokter obsginnya. 3. Wanita yang hamil dan mengalami depresi atau ansietas berat sebaiknya tetap meneruskan pengobatan sebagaimana mereka berisiko tinggi untuk kambuh. Komplikasi Kondisi depresi pada kehamilan bila tidak ditatalaksana dengan baik akan berdampak terjadinya hal-hal sebagai berikut berupa depresi di masa mendatang dalam perkiraan periode 5 tahunan, kelahiran bayi yang tidak baik seperti rendahnya berat badan lahir, meningkatnya risiko persalinan premature, dan preeklamsi pada ibu, begitu juga gangguan fungsi kesehatan ibu. Kondisi tersebut juga mempengaruhi mood ibu setelah melahirkan dan kaitannya dengan perasaan ibu terhadap bayinya. Dampak lain berupa afek responsif terhadap bayi, masalah perilaku dan perlambatan kognitif dan perkembangan bahasa untuk bayinya.9 Kesimpulan Depresi pada kehamilan merupakan masalah yang serius perlu perhatian kita untuk mengenal, mendiagnosis dan menatalaksananya dengan baik, dengan harapan nantinya akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang prima dan kesehatan ibu dan anak dapat meningkat. Daftar Pustaka 1. Bos SC et al., Is positive affect in pregnancy protective of postpartum depression?, Rev Bras Psiquiatr. 2013;35:005-012. 2. Golding J, Steer C, Emmett P, Davis JM, Hibbeln JR, High levels of Depressive Symptoms in Pregnancy With Low Omega-3 Fatty Acid Intake From Fish, Epidemiology (Cambridge, Mass.) ·July 2009, 1-7. 3. Yonkers KA et al., The management of depression during pregnancy: a report from the American Psychiatric Association and the American College of Obstetricians and Gynecologists, General Hospital Psychiatry 31 (2009) 403–413. 4. Brody SM, New insights into perinatal depression: pathogenesis and treatment during pregnancy and postpartum, Dialogues Clin Neurosci. 2011;13:89-100. 5. Coelho FMdC et al., Major depressive disorder during teenage pregnancy: socio -demographic, obstetric and psychosocial correlates, Rev Bras Psiquiatr. 2013;35:51–56. 6. Kim DR, O‘Reardon JP, Epperson CN, Guidelines for the Management of Depression During Pregnancy, Curr Psychiatry Rep. 2010 August ; 12(4): 279–281. doi:10.1007/s11920-0100114-x. 7. Mohapatra S, Yaduvanshi R, Agrawal A, Gupta B, Treatment of Depression during Pregnancy, Delhi Psychiatry Journal, Vol. 16 No. 2, 1-6. 8. Clark R et al., Diagnosing and Treating Depression – Adult – Primary Care Clinical Practice Guideline (CPG), Physician plus Meriter, September 2013, 1-38. 9. Marcus SM, Flynn HA, Blow FC, Barry KL, Depressive Symptoms among Pregnant Women Screened in Obstetrics Settings, Journal Of Women‘s Health, Volume 12, Number 4, 2003, 1-10. INISIASI INSULIN PADA PASIEN DM TIPE 2 Hendra Zufry Divisi Endokrinologi, Metabolik & Diabetes- Pusat Pelayanan Tiroid Terpadu. Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/ RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pendahuluan Peningkatan kontrol glikemik telah terbukti dapat mengurangi baik mikrovaskular dan komplikasi makrovaskular pada penderita DM Tipe 2, Negara maju seperti Amerika Serikat dilaporkan 43% dari penderita gagal mencapai kontrol glikemik yang baik, meskipun telah ada beberapa kelompok obat anti-diabetes dapat mencapai target.1 Inisiasi insulin adalah suatu bentuk keputusan dan persetujuan untuk menggunakan insulin antara healthcare provider (HCP) dan pasien dimana proses pengambilan keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural dan sistem pelayanan kesehatan. Masalah terbesar dalam inisiasi insulin adalah penolakan terhadap insulin walaupun sudah disarankan untuk menggunakan insulin. Penelitian lain di Netherland juga menunjukkan angka hamper sama yaiotu jumlah pasien DM yang menolak insulin sebesar 39%, hasil penelitian yang dilakukan di Pakistan menunjukkan 210 dari 307 pasien DM menolak insulin. Di Indonesia tidak ditemukan secara pasti jumlah pasien DM yang menolak untuk menggunakan insulin. Hanya saja seperlima hingga sepertiga pasien menolak pemberian insulin dengan alasan takut. American Diabetes Association (ADA)/EASD dalam konsensus merekomendasikan penggunaan insulin basal/analog insulin sebagai start up insulin sementara dalam inisiasi insulin pada penderita diabetes. Kemampuan insulin basal untuk meningkatkan langkah-langkah kontrol glikemik telah terbukti dalam berbagai penelitian. Meskipun insulin basal secara efektif mengontrol glukosa plasma puasa akibatnya pada kontrol glukosa postprandial tidak adekuat.1 Menurut Perkeni 2011 insulin diperlukan dalam keadaan penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemia berat yang disertai ketosis, hiperosmolar non ketotik, hiperglikemia dengan asidosis laktat, gagal dengan kombinasi OHO dasar optimal stress berar, kehamilan dengan DM, ganguan fungsi ginjal, kontraindikasi dan atau alergi OHO Penelitian terbaru menunjukkan bahwa memulai insulin dengan analog premixed adalah cara efektif untuk meningkatkan kontrol glikemik dengan resiko minimal hipoglikemia. Namun cara yang paling efektif untuk memulai insulin basal dibandingkan dengan premixed masih belum jelas. 1 DM Tipe 2 (DMT2) dikatagorikan dalam DM yang tidak tergantung dengan insulin, namun dalam penelitian yang dilakukan novonordisk di 10 puskesmas wilayah Surabaya ditemukan 99 pasien yang memakai OHO selama 6 tahun tetap tidak bisa mengendalikan kadar glukosa darah ditandai dengan HbA1C mencapai 11%. Hal ini terjadi karena sel beta pancreas sudah mengalami kerusakan pada saat didiagnosis sehingga insulin perlu diberikan secara dini. Prevalensi diabetes di Taiwan meningkat 1,2 kali terutama pada orang tua, tingkat prevalensi adalah 20% dari populasi berusia 65 tahun yang merupakan masalah bagi individu, masyarakat dan pelayanan kesehatan. Pengelolaan pasien DMT2 pada usia lanjut menjadi sulit karena terkait usia perubahan fisiologis dan penyakit komorbid, komplikasi dan hypoglikemia. Insulin glargine telah terbukti dengan baik dalam mengontrol glukosa darah puasa dengan resiko rendah hipoglikemia. Insulin basal adalah pilihan umum untuk inisiasi insulin pada penderita DM Tipe 2 yang tidak terkontrol dengan obat antidiabetes oral (OAD). Penelitian di Taiwan memulai terapi insulin basal dengan insulin glargine pada pasien usia lanjut dengan OAD dapat memberikan kontrol glikemik yang efektif pada HbA1C dan fasting prandial glukosa (FPG) sama dengan kelompok usia muda.2 Berbagai terapi farmakologi telah dikembangkan untuk diabetes, terapi biasanya dimulai dengan obat hipoglikemia oral, seperti metformin, sulfonylurea atau inkretins sangat efektif dalam mencapai kontrol glikemik, selain dapat mengurangi mikro dan komplikasi makrovaskular dan mengurangi mortalitas. Ketika terapi oral tidak mencapai target, berbagai faktor, sejumlah pasien yang ragu-ragu untuk memulai terapi insulin karena sakit ditempat suntikan seperti resiko efek samping, berat badan dan kompleksitas terapi.3 Continuous subkutaneous insulin infusion (CSII) sebagai terapi alternative yang digunakan multiple daily injection (MDI) untuk pengobatan DM Tipe 1.4 Wanita dengan DM tipe 1 memberi hasil yang baik dengan terapi CSII, mungkin berhubungan dengan keberadaan subset dari individu dengan kontrol glukosa lebih baik .4 Penelitian Database retrospektif yang dilakukan di German, terdapat peningkatan awal kontrol glikemik (HbA1C) setelah dimulainya terapi insulin pada penderita DM Tipe 2 dalam perawatan primer yang dipertahankan selama periode 3 tahun, namun tidak ada perbaikan tambahan nilai HbA1C yang dicapai. Penelitian lain dalam perawatan kesehatan primer di Firlandia selatan-barat (1991-1997), terapi inisiasi insulin pada 883 pasien DMT2, rata-rata HbA1C menurun 10% menjadi 8% pada 12 bulan, tetapi peningkatan ini pada dasarnya tidak berubah setelah 4 tahun, hal ini karena perubahan dosis insulin setiap hari pada pasien ini meningkat tajam selama 4 tahun untuk mempertahakan kontrol glikemik.5 American Diabetes Association (ADA), International Diabetes Federation (IDF) merekomendasikan baik insulin premixed dan insulin basal sebagai pilihan terapi yang lebih disukai untuk inisiasi insulin.6 Hambatan dalam inisiasi insulin Inisiasi insulin dipengaruhi oleh adanya hambatan yang dirasakan oleh pasien DM yang mengakibatkan pasien cenderung menolak insulin. Penolakan terhadap insulin mengakibatkan tidak efektifitasnnya terapi yang diberikan sehingga terdapat beberapa hambatan antara lain: - Hipoglikemia Ketakutan terjadi hipoglikemia setelah pemberian insulin merupakan alasan terbesar yang dikemukakan pasien yang menolak insulin. Kejadian hipoglikemia dengan insulin bervariasi antara 6% sampai 64%. - Penambahan berat badan Penambahan berat badan sering terjadi pada pasien setelah pemberian insulin. Peningkatan berat badan bisa mencapai 0,36,4 kg yang terjadi mulai minggu pertama sampai beberapa bulan setelah menggunakan insulin dan setelah satu tahun peningkatan berat badan menjadi semakin rendah. Peningkatan berat badan terjadi karena glukosuria tidak terjadi sehingga sumber kalori tidak terbuang serta efek lainnya yang disebabkan terkendalinya glukosa darah. - Efektifitas penggunaan terapi Pemberian terapi insulin dirasa menyulitkan bagi pasien karena adanya rasa tidak percaya diri untuk memberikan insulin secara mandiri. Hal ini muncul karena informasi dan ketidaktahuan pasien sehingga menjadi hambatan dalam penggunaan insulin. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang penolakan insulin pada pasien DMT2 dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain : - usia - jenis kelamin -Tingkat pendidikan -lama mengalami DM - pendapatan -pengetahuan -sikap -kepercayaan terhadap insulin -efikasi diri -interaksi dengan petugas kesehatan Daftar Pustaka 1. M.John, Kalra s, Unnikrishnan AG,et al, Recommendation for insulin initiation based on ethnicity, medic hipothesis, 2011; 460461 2. Ming-Nan Chien, Lee C, Liu S ,et al, Basal insulin initiation in Elderly Patients with Type 2 Diabetes in Taiwan:A Comparison with Younger Patiens,Intr J of gerontology, 2015; 142-145 3. Alba M, Duque M, Gutierez P, Time to and factors associated with insulin initiation in patients with type 2 diabetes mellitus, diabetes research and clinical practice 107,2015; 332-337 4. Esteves C, Belo S, Neves MC et al, Glycemic Control and Weight Outcome After Initiation of Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Therapy,endocrinol diabetes metab, 2015;10 (2):128-132 5. Rathmann W,Strassburger K, Tamayo T, et al, Longitudinal change in HbA1c after insulin initiation in primary care patients with type 2 diabetes: A database analysis in UK and Germany, Primer care Diabetes,2012; 47-52 6. Kalra S, Gupta Y, Insulin Initiation: Bringing Objectivity to Choice, J of Diabetes & metabolic Disoeder, 2015;14:17 7. Initiation of Biphasic Insulin Aspart 30/70 in Subjects with Type 2 Diabetes mellitus in a Largely Primary Care-based Setting In Sweden, WHY, WHEN AND HOW TO ADD PRANDIAL INSULIN AFTER BASAL OPTIMIZATION (FOCUS ON BASAL PLUS) Krishna W. Sucipto Division of Endocrinology, Metabolism & Diabetes-Thyroid Center Department of Internal Medicine, School of Medicine University of Syiah Kuala/ Dr. Zainoel Abidin General Teaching Hospital, Banda Aceh- Indonesia Introduction Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a progressive disease characterized by co-existing insulin deficiency and insulin resistance. The resulting hyperglycaemia is commonly associated with both micro- and macro-vascular complications and intervention to improve glycaemic control has been shown to limit such complications. Therefore, appropriate and timely intervention strategies are essential. As b-cell function declines, most patients with type 2 diabetes treated with oral agents, in monotherapy or combination, will require insulin therapy. Addition of basal insulin (glargine, detemir, or NPH/neutral protamine lispro insulin) to previous treatment is accepted as the simplest way to start insulin therapy in those patients. But even when basal insulin is adequately titrated, some patients will also need prandial insulin to achieve or maintain individual glycemic targets over time. Starting with premixed insulin is an effective option, but it is frequently associated with increased hypoglycemia risk, fixed meal schedules, and weight gain. As an alternative, a novel approached known as ‗‗basal plus strategy‘‘ has been developed. This approach considers the addition of increasing injections of prandial insulin, beginning with the meal that has the major impact on postprandial glucose values.1,2 To address this issue, a panel of clinical experts convened to develop practical recommendations on how to initiate basal prandial therapy in patients with type 2 diabetes, focusing on patient selection, simple dosing and titration, and monitoring. Importance of prandial insulin Insulin reduces blood glucose principally by inhibiting hepatic glucose production and increasing peripheral uptake of glucose. Prandial insulin secretion is impaired in people with diabetes, resulting in failure to suppress endogenous glucose production, a higher and more prolonged postprandial hyperglycaemia and increased fasting plasma glucose (FPG) (Figure 1).3 Spikes in postprandial glucose levels have adverse metabolic and cardiovascular consequences, including endothelial dysfunction, activation of the polyol pathway, increased levels of markers of chronic systemic inflammation, promotion of coagulation and cell adhesion and increased production of free fatty acids. Observational studies have consistently identified an association between postprandial hyperglycaemia and an increased risk of coronary heart disease or cardiovascular mortality.4 Fig.1 Physiological effects of abnormal insulin secretion in type 2 diabetes. 4 Poor glycaemic control (HbA1C > 8.5%) is associated with high FPG. As treatment brings HbA1C closer to target, postprandial hyperglycaemia accounts for a greater proportion of HbA1C than FPG. Treatment aimed at reducing postprandial glucose will therefore be more effective at improving glycaemic control further. Within the range 7.3– 8.4%, postprandial hyperglycaemia accounts for half of the total HbA1C (Figure 2). Moreover, doses of basal insulin > 0.5 U⁄ kg cause additional weight gain or increase the risk of hypoglycaemia. When optimal basal therapy fails to maintain glycaemic targets, the preferred approach to intensification is therefore not to increase the basal dose further but to add a rapid-acting analogue at mealtimes.5,6 Rationale for Basal-Prandial Insulin Therapy Both basal and postprandial glucose (PPG) excursions contribute to hyperglycemia in type 2 diabetes, and treatment strategies that address both components may enhance attainment of glycemic goals. The ADA guidelines call for a fasting plasma glucose (FPG) target of 90– 130 mg/dL and a 2-hour PPG target of < 180 mg/dL. Failure to achieve glycemic control can lead to the development of serious diabetes-related complications.1,5 There is also a growing body of evidence indicating that postprandial hyperglycemia independently contributes to an increased risk for macrovascular complications. In fact, a meta-analysis of the data has indicated that isolated postprandial hyperglycemia (2- hour PPG >140 mg/dL) in the presence of normal FPG (< 110 mg/dL) and normal A1C (< 6.1%) is associated with a 2-fold increase in the risk of death from cardiovascular disease.5,6,7 Fig.2 Contribution of postprandial hyperglycaemia to overall glycaemic control at different values of HbA1C.6 A stepwise approach to basal-prandial insulin therapy in patients with type 2 diabetes allows treatment to be advanced as the disease progresses to minimize the risk of complications. Initially, elevated baseline FPG levels lead to a higher overall plasma glucose profile and consequently higher PPG excursions. Also, the relative contribution of FPG to A1C progressively increases as glycemic control worsens. The first goal of a physiologic insulin therapy regimen, therefore, is to lower the overall glycemic profile with basal insulin and normalize, or nearly normalize, the FPG level. Conceptually, "fix the fasting first" is the initial agenda. This is accomplished most efficiently by the addition of basal insulin. Decreases in PPG excursions may also be achieved by lowering the overall glycemic profile with basal insulin (Figure 3). However, as the disease progresses, the capacity of patients with type 2 diabetes to respond to PPG excursions becomes progressively impaired due to reduced endogenous insulin secretion resulting from loss of β-cell function. In many patients, basal insulin alone, when added to OADs, is sufficient to attain glucose goals. Due to the natural history of type 2 diabetes, many patients eventually progress to a level of insulin deficiency that requires initiation of prandial insulin (or pharmacotherapy targeted to prandial insulin control) in addition to basal insulin. Prandial insulin can be added with the appropriate meal or meals to control PPG excursions.5,8 Fig.3 24-hour glucose profiles for representative patients at different levels of glycemic control. Increasing A1C values reflect an elevated fasting or preprandial (basal) blood glucose level and elevated PPG excursions. At levels shown as "uncontrolled" A1C (9.0%), the culprit is predominantly loss of control of the FPG, whereas the difference between an A1C of upper normal (6.0%) vs "controlled" A1C (7.0%) predominantly reflects increased PPG. PG = plasma glucose8 Stepwise addition of prandial insulin to basal insulin Clinicians can prepare patients for basal-prandial insulin therapy by facilitating discussions about insulin and educating patients on aspects of diabetes self-management, including the importance of diet and exercise, injection techniques, carbohydrate counting, home glucose monitoring, and hypoglycemia awareness. Clinicians should avoid using insulin as a means for threatening or blaming patients for previous treatment failure, but rather explain that insulin therapy is often a natural consequence due to the progressive nature of the disease: nearly one third of patients with type 2 diabetes are likely to require insulin at some point. It is also important that clinicians discuss and come to an agreement with patients on specific treatment goals for basal-prandial insulin therapy . If oral antidiabetic drugs (OADs) have failed due to gross dietary noncompliance, addition of insulin therapy is unlikely to achieve glycemic goals without adequate diabetes education. Explaining the significance of A1C measurements, discussing A1C goals, and sharing results is an important motivational tool for patients on insulin therapy.8 If A1C goals are not achieved after a period of 3–6 months of treatment with basal insulin plus OADs, patients should be instructed to monitor glucose preprandially and/or 1–2 hours after each meal on a rotating basis to identify the main meal that is contributing to hyperglycemia (ie, high blood glucose levels at breakfast, lunch, dinner, or bedtime). Once identified, 5–10 U of rapid-acting insulin should be administered before this meal. If A1C goals are still not reached after 3–6 months of therapy with OADs and basal insulin plus 1 prandial insulin dose at the main meal, prandial insulin can be added to other meals based on home glucose monitoring. For example, if blood glucose levels are high before lunch, add 5–10 U of rapid-acting insulin at breakfast, with continued titration according to the schedule shown in Table 1.6,8,9 Tabel 1 : Titration Schedule for Basal and Prandial Insulin.8 Blood Glucose Adjust Basal Insulin Adjust Rapid-Acting Insulin Levels for 3 Dose (U) Dose (U per Injection) Consecutive Days (Fasting, Preprandial, or Bedtime) ≥ 180 mg/dl +8 +3 160-180 mg/dl +6 +2 140-160 mg/dl +4 +2 120-140 mg/dl +2 +1 100-120 mg/dl +1 Maintain dose 80-100 mg/dl Maintain dose -1 60-80 mg/dl -2 -2 <60 mg/dl -4 -4 Comments : For elevated fasting blood glucose levels, adjust only the basal insulin dose. For elevated preprandial blood glucose at lunchtime, adjust breakfast rapid-acting insulin dose For elevated preprandial blood glucose at dinnertime, adjust lunchtime rapid-acting insulin dose For elevated bedtime blood glucose, adjust dinner time rapid-acting insulin dose A regimen comprising a single injection of basal insulin plus three (or more) prandial insulin injections daily seems to be complex and, therefore, patients need to be both well educated regarding diabetes and highly motivated to maintain compliance with therapy and glucose monitoring. Patients with type 2 diabetes who are appropriate candidates for basalprandial insulin therapy include those who: 1) are unable to achieve glycemic control on oral antidiabetic drugs, 2) are unable to achieve glycemic control on split-mixed/premixed insulin regimens, 3) are newly diagnosed but unlikely to respond to oral antidiabetic drugs alone (ie, the patient has severe hyperglycemia or a markedly elevated glycosylated hemoglobin A1C level for which oral antidiabetic drug therapy alone is unlikely to achieve goals), and 4) prefer this therapy due to socioeconomic or other individual considerations. Basal-prandial insulin can be initiated in a simple stepwise manner, starting first with the addition of basal insulin to the existing oral antidiabetic drug regimen, followed by the introduction of 1 prandial insulin injection to the basal insulin plus oral antidiabetic drug regimen (after basal insulin has been optimized).8,9 Conclusions Treatment aimed at reducing postprandial glucose is more effective in improving glycaemic control near target levels. Rapid-acting insulins provide the most physiological form of postprandial insulin supplementation, and when added to basal insulin in patients with type 2 diabetes, can bring even relatively well controlled patients much closer to target. Hence, additional therapy for post-prandial hyperglycaemia may be needed to achieve an overall glycaemic control represented by HbA1c<7%. Although new therapies are under development, prandial insulin administration remains the standard approach to this clinical problem. References 1. Gururaj S, Crasto W, Jarvis J, Khunti K, and Davies M.J. New insulins and newer insulin regimens: a review of their role in improving glycaemic control in patients with diabetes. Postgrad Med J. 2016;92:152–164. 2. Ampudia J.F, Rossetti P, and Axcaso J.F. Basal Plus Basal–Bolus Approach in Type 2 Diabetes. 2011;13(1);S-75-S-83. 3. Satish K. Garg , Emily G. Moser . 2011. How Basal Insulin Analogs Have Changed Diabetes CareHow Basal Insulin Analogs Have Changed Diabetes Care. Diabetes Technology Therapeutics 13:S1, S-1-S-4. 4. Raccah D, Bretzel R.G, Owens D, and Riddle M. When basal insulin therapy in type 2 diabetes mellitus is not enough – what next?. Diabetes Metab Res Rev 2007; 23: 257–264. 5. Buse JB, Bergenstal RM, Glass LC, Heilmann CR, Lewis MS, Kwan AYM, Hoogwerf BJ, Rosenstock J: Use of twice-daily exenatide in basal insulin–treated patients with type 2 diabetes. Ann Intern Med 2011;154:103–112. 6. Pfutzner A and Forst T. Intensification with prandial insulin. Int J Clin Pract, October 2009, 63 (Suppl. 164), 11–14. 7. Raccah D. Options for the intensification of insulin therapy when basal insulin is not enough in type 2 diabetes mellitus. Diabetes, Obesity and Metabolism, 10 (Suppl. 2), 2008, 76–82. 8. Edelman S, Dailey G, Floods T, Kuritzky L, and Renda S. A practical approach for implementation of a basal-prandial insulin therapy regimen in patients with type 2 diabetes. Osteopathic Medicine and Primary Care 2007, 1:9 9. Monnier L, Colette C. Addition of rapid-acting insulin to basal insulin therapy in type 2 diabetes: indications and modalities. Diabetes Metab 2006; 32: 7–13. TEHNIK INJEKSI INSULIN Yensuari Bagian Penyakit Dalam BLUD RSUD dr. Yuliddin Away Tapaktuan Aceh Selatan 1. Pendahuluan Jumlah global penderita diabetes saat ini diperkirakan mencapai 415 juta (satu dari sebelas dewasa) dan diperkirakan pada tahun 2040 akan meningkat menjadi 642 juta (satu dari sepuluh dewasa),1. peningkatan tersebut terutama terjadi di negara berkembang sepeti Indonesia. Lebih 25 % penderita diabetes menggunakan insulin untuk mencapai kendali gula darah.2. Insulin diperlukan pada DM tipe 1, DM tipe 2 dengan keadaan tertentu seperti penurunan berat badan yang cepat, hipergliklemia berat yang disertai ketosis, ketoasidosis diabetik, status hiperglikemia hyperosmolar (HHS), hiperglikemia dengan asidosis laktat, gagal dengan kombinasi OHO (obat hiperglikemia oral) dosis hampir maksimal, stress berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokardial akut, stroke), kehamilan dengan diabetes atau diabetes gestasional yang tidak terkendali dengan perencanaan makan, gagal fungsi ginjal atau hati berat dan kontra indikasi atau alergi terhadap OHO.3,4,5. Pada umumnya insulin diberikan dengan injeksi subcutan atau intravena pada keadaan tertentu seperti diabetes dengan komplikasi akut hiperglikemia, stress berat dan pada penderita yang tidak bisa makan dan minum tanpa muntah.6 Selain insulin yang diberikan secara injeksi subcutan untuk terapi diabetes, ada juga bahan (agent) lain seperti GLP-1 (glucagon like peptide 1) receptor agonist atau amylin agonist.7. Teknik injeksi yang tepat merupakan salah satu faktor terpenting dalam managemen diabetes untuk tercapainya kendali gula darah yang baik, sama pentingnya dengan memilih jenis dan dosis bahan (agent) yang akan diinjeksikan.8 Untuk mengoptimalkan teknik injeksi yang tepat sangat diperlukan peranan tenaga kesehatan profesional untuk mengajarkan (edukasi) penderita atau tenaga kesehatan lain bagaimana injeksi yang benar dan mengatasi dampak psikologi yang dihadapi. Tenaga kesehatan profesional harus memahami anatomi tempat yang akan diinjeksi untuk menghindari injeksi intramuskular dan memastikan bahwa injeksi yang dilakukan pada jaringan subcutan tanpa merembes keluar dan komplikasi lain.9. Tenaga kesehatan profesional yang mempunyai latar belakang pendidikan formal sebagai edukator terbukti adanya penurunan HbA1C (hemoglobin A1C) pada kelompok yang diberikan edukasi.10 Penurunan HbA1C tersebut tentunya akibat terapi injeksi insulinnya yang diinjeksikan dengan teknik yang tepat. Penurunan HbA1C akan mengurangi resiko komplikasi makrovaskuler dan mikrovarkuler pada penderita DM tipe 2. Dengan kata lain komplikasi tersebut sangat berhubungan dengan keadaan hiperglikemia sebelumnya, dan penurunan HbA1C sebagai gambaran kendali gula darah.11. Dalam tulisan ini akan dibahas hanya terbatas injeksi insulin subcutan dengan menggunakan pen needle seperti yang digunakan pada insulin short-acting (human insulin), analog rapid-acting (lispro, glulisine, dan aspart insulin) dan insulin analog campuran (premixed). 2. Anatomi Jaringan Subcutan Kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis dan subcutan. Epidermis merupakan lapisan terluar yang merupakan lapisan keratosit mengandung melanosit. Dibawah epidermis terdapat base membrane yang merupakan bentuk berbagai lapisan (multilayered) sebagai penyambung epidermis dan dermis, sedangkan lapisa dermis merupakan penghubung epidermis dengan lapisan dibawahnya yang mengandung kelenjar rambut, kuku, sebacea, keringat, serabut sel saraf dan pembuluh darah serta pembulu lymph. Kemudian lapisan subcutis yang merupakan lapisan jaringan longgar yang mengandung sel-sel lemak dan menjadi sasaran tempat insulin diinjeksikan karena terdapat aliran darah lambat dan sangat stabil yang akan mempengaruhi absorpsi insulin dibanding lapisan dermis dan otot. 12. Ketebalan lapisan epidermis dan dermis berkisar 1.2-3.0 mm pada semua lokasi penyuntikan,13. maka untuk menghindari injeksi intradermal panjang needle harus melebihi 3 mm. 3. Perawatan Sebelum Injeksi 3.1 Mengatasi dampak psikologi penderia. Penderita diabetes dewasa kebanyakan tidak takut (phobia) dengan jarum suntik, namun banyak yang khawatir dan merasa tidak biasa saat melalukan injeksi terutama pada awal terapi. Peranan kita sebagai tenaga kesehatan profesional atau tenaga kesehatan lain sangat diperlukan untuk mengatasi dampak psikolgi yang dihadapi penderita diabetes. Untuk menenangkan ketakutan dan kekhawatiran penderia dapat diatasi dengan memberi contoh proses injeksi dengan memggunakan cairan saline terhadap diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan profesional atau memberi contoh proses injeksi yang diinjeksikan ke penderita dengan injeksi cairan saline atau satu unit insulin.14. Jika penggunaan insulin yang menjadi sumber kekhawatiran, sebaiknya saat pertama kali penderita didiagnosa diabetes diberikan pengertian mengenangi sifat alami perjalanan penyakinya dan kemungkinan akan mendapat terapi insulin kedepannya serta menjelaskan bahwa terapi insulin bukan merupakan akibat kegagalan terapi sebelumnya atau terapi terakhir. Manfaat jangka pendek dan jangka panjang terhadap kendali gula darah yang baik harus juga ditekankan pada penderita. Menemukan kombinasi terapi yang tepat lebih awal untuk kendali gula darah harus menjadi tujuan dari pada meminimalisir jumlah kombinasi terapi yang digunakan. Sebaiknya penderita diberikan penjelasan manfaat terapi insulin dan menghindari pengertian yang secara tidak langsung menyatakan bahwa terapi insulin sebagai hukuman atau ancaman akibat kegagalan terapi.15. Memberikan pengertian dan penjelasan diatas sebaiknya dengan menggunakan kiasan, gambar dan cerita yang sesuai serta memberikan gambaran bahwa terapi injeksi insulin akan meningkatkan kualitas hidup dan usia harapan hidup.16. 3.2 Terapi edukasi penderita. Terapi edukasi yang dapat dilakukan seperti : - Memberikan saran dan pengalaman serta mendiskusikan keputusan untuk menerima atau tidak terapi injeksi insulin.17. - Memberikan pengertian dan berdiskusi dengan penderita pada awal terapi injeksi atau sedikitnya setiap tahun tentang topik : regimen atau bahan yang diinjeksikan seperti jenis dan dosis insulin, memilih dan menggunakan alat injeksi, memilih dan merawat serta memeriksa sendiri lokasi atau tempat diinjeksi, teknik injeksi yang tepat termasuk rotasi lokasi atau tempat diinjeksi, sudut injeksi, dan lipatan kulit, panjang jarum (needle) yang sesuai dan pembuangan limbah alat yang sudah digunakan. Mengevaluasi tehnik injeksi yang selama ini dilakukan apakah sudat tepat dan menganjurkan memeriksa secara mandiri dengan meraba lokasi atau tempat injeksi yang dilakukan untuk mendeteksi adanya lipohipertropi sejak dini.17,18,19,20. - Memastikan apakah semua informasi yang diberikan sudah sepenunya dipahami. 3.3 Menentukan lokasi atau tempat injeksi. Lokasi atau tempat injeksi yang direkomendasikan adalah dinding andomen, paha, bokong dan lengan. (gambar 1) Gambar 1. Lokasi atau tempat injeksi insulin Memeriksa secara mandiri dengan melihat dan meraba (palpasi) dan merubah lokasi atau tempa injeksi jika dijumpai lipohipertropi, peradangan dan infeksi. Lokasi atau tempat injeksi harus bersih dan dilakukan dengan tangan yang bersih. Desinfektan pada lokasi atau tempat injeksi seperti alkohol tidak harus diberikan kecuali pada penderita yang dirawat di rumah sakit. Hindari injeksi pada lengan, paha atau panggul jika penderita akan melakukan latihan fisik, karena insulin akan di absorpsi cepat dan terjadi hipoglikemia.22. 3.4 Penyimpanan insulin pen. Insulin pen yang sedang digunakan disimpan pada suhu ruangan maksimal satu bulan setelah digunakan dan sebelum tanggal kadaluarsa. Sedangkan pen yang belum digunakan disimpan dilemari pendingin di refrigator (bukan pembeku).23. 3.5 Memilih panjang dan diameter jarum suntik (needle). Needle diperlukan untuk mengalirkan insulin ke jaringan subcutan, panjang needle yang direkomendasikan adalah 4, 5 atau 6 mm dan tergantung IMT (indeks massa tubuh) dengan diameter terkecil. Melipat kulit saat injeksi tidak diperlukan pada penderita kurus yang menggunakan needle 4 mm dan penderita gemuk (obese) yang menggunakan needle 5 atau 6 mm dan pen tegak lurus 90 o dengan permukaan kulit. Sedangkan penderita kurus yang menggunakan needle 5 tau 6 mm melipat kulit harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan injeksi intramuskular.24,25. Panjang needle > 8 mm tidak direkomendasikan pada injeksi insulin menggunakan pen. Needle di rekomendasikan hanya di pakai satu kali untuk menghindari rasa nyeri, terlepasnya mirro-pragmen dari needle dan trtinggal di jaringan subcutan dan robekan yang lebih luas akibat needle yang sudah tumpul.22,26. 4. Proses Saat Injeksi Pasangkan needle ke pen dengan membuka kertas segel jarum, dan pasangkan dengan memutar sekaligus menekan jarum. Pen dengan insulin premixed harus diputar dan dibolak balikkan sebanyak 10 kali agar insulin tercampur dengan sempurna.27. Cabut dan buang tutup luar jarum, putar dosis 2 unit pada pangkal pengatur ukuran yang akan disuntikan, buka tutup dalam jarum dan arahkan pen ke atas dan ketuk tabung pen yang berisi insulin untuk mengumpulkan gelembung udara. Tekan knob dose ke atas hingga terlihat aliran insulin yang lancar hingga keluar tetesan insulin.28. Setelah panjang needle ditentukan dengan melihat needle yang dimiliki atau yang tersedia (di pasarkan) di sekitar tempat tinggal penderita, melipat kulit dilakukan sesuai dengan panjang needle yang digunakan dan kurus atau gemuk penderita.29,30. (gambar 2). Gambar 2. Melipat kulit (skin folds), gambar kanan cara yang benar dan kiri yang salah. Pegang dengan posisi ibu jari pada tombol tekan dan injeksikan perlahan dengan arah tegak lurus terhadap permukaan kulit dan pastikan tombol ibu jari pada pen ditekan sepenuhnya. Tunggu 10 detik (hitungan) setelah dosis insulin seluruhnya diinjeksikan, sebelum mencabut pen untuk menghindari perembesan atau aliran balik keluar melalui lubang bekas injeksi. Pemijatan lokasi atau tempat injeksi sebelum atau sesudah injeksi untuk mempercepat absorpsi tidak perlu dilakukan. Untuk mengurangi rasa sakit saat injeksi gunakan jarum suntik (needle) baru dan sekali pakai, jika menggunakan alkohol oleskan pada tempat injeksi sampai mengering kemudian dilakukan injeksi, dan injeksi tidak mengenai akar rambut. Setelah pen dicabut dari lokasi atau tempat injeksi lepaskan needle dari pen untuk menghindari masuknya udara atau kontaminasi lain serta mecegah kebocoran insulin. Pen digunakan untuk satu orang dan tidak digunakan orang lain untuk menghindari penularan penyakit tertentu. 22,27,28. Untuk menjaga jaringan subcutan tetap normal harus merotasi lokasi atau tempat injeksi secara tepat dan berkesinambungan. Penderita harus di edukasi tentang manfaat dan melakukan rotasi lokasi atau tempat injeksi sejak awal terapi injeksi insulin. Untuk mempermudah rotasi dapat diikuti skema yang menggambarkan satu kuadran pada dinding abdomen dan setengah kuadran pada salah satu sisi paha atau pangguldan rotasi dapat dilakukan dengan menggunakan satu kuadran setiap minggunya dan berputar searah jarum jam seperti pada gambar 3 dan 4. Lokasi atau tempat injeksi sebaiknya dilakukan sedikit pada jarak 1 cm dari injeksi sebelumnya untuk menghindari trauma jaringan berulang.22,30. Gambar 3. Pola satu kuadran pada dinding abdomen. Gambar 4. Pola separuh kuadran paha dan panggul. 5. Perawatan Setelah Injeksi. 5.1 Mencegah dan merawat komplikasi pada lokasi atau tempat injeksi. Pemeriksaan dengan melihat dan meraba (palpasi) lokasi atau tempat injeksi harus dilakukan sedikitnya setahun sekali untuk mendiagnosa lebih dini adanya lipohipertropi, dan jika lipohipertropi sudah terjadi maka pemeriksaan tersebut dilakukan pada setiap kali kunjungan. Penderta harus di edukasi agar dapat memeriksa secara mandiri untuk mendiagnosa lipohipertropi atau komlikasi lain seperti akibat reaksi alergi, infeksi atau peradangan. Lipohipertropi merupakan penebalan kenyal (rubbery) pada jaringan subcutan didaerah bekas injeksi, yang dapat terlihat dan lebih mudah dengan cara meraba (palpasi). Lipohipertropi dialami lebih 50 % penderita dengan terapi injeksi insulin, dan keadaan ini sangat penting untuk diperhatikan karena adanya lipohipertropi absorpsi insulin menjadi lambat dan tidak menentu. Injeksi insulin di sekitar jaringan subcutan yang sudah mengalami lipohipertropi juga harus dihindari karena akan memperburuk lipohipertropi dan kendali gula darah tidak tercapai dengan merubah lokasi atau tempat injeksi ke tempat lain.22,30,32. Pada saat injeksi terkadang needle mengenai pembuluh darah yang akan menyebabkan perdarahan dan memar pada kulit dan subcutan. Mengubah panjang dan diameter needle tidak terbukti secara signifikan mengurangi kejadian tersebut. Perdarahan dan memar tersebut tidak akan mempengaruhi absorpsi insulin dan kendali gula darah, walaupun demikian rotasi lokasi atau tempat injeksi sangat dianjurkan.33,34. 5.2 Pembungan limbah needle. Pembuangan limbah biologi terkontaminasi harus menjadi perhatian kita sebagai tenaga kesehatan dan penderita sendiri. Pembungan limbah tidak boleh dilakukan pada tempat pembuangan limbah umum karena akan menciderai pasien sendiri, keluarga dan penyedia layanan pengutip atau pembungan sampah. Edukasi pembungan limbah harus diberikan sejak awal terapi dengan membuang needle yang sudah terpakai di tempat atau wadah pembungan sampah khusus untuk needle, atau wadah lain seperti botol plastik tertutup dan tidak bocor. Sebagai tempat pembungan akhir penderita harus difasilitasi untuk membuang limbah di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.30 6. Kesimpulan Peningkatan jumlah penderita diabetes tipe 2 yang terus bertambah juga akan meningkatan penggunaan injeksi insulin. Edukasi teknik injeksi insulin yang tepat harus diberikan kepada tenaga kesehatan lain dan keluarga serta penderita diabetes agar kendali gula yang baik dapat tercapai. Edukasi meliputi penyimpanan pen insulin, memilih dan merotasi lokasi atau tempat injeksi, memilih penjang dan diameter needle yang sesuai, proses injeksi yang tepat serta mendiagnosa secara mandiri komplikasi pada lokasi atau tempat injeksi dan pembuangan limbah biologi terkontaminasi. Secara keseluruhan urutan proses saat injeksi yang benar adalah membuat atau tidak lipatan pada kulit, suntikan insulin perlahan, biarkan jarum di kulit selama 10 detik (saat menyuntik dengan pen ), tarik jarum dari kulit, lepaskan lipatan kulit, buang jarum suntik dengan aman. Keaadan tersebut harus benar benar diperhatiakn dan dilakukan karena teknik injeksi insulin yang tepat sama pentingnya dengan memilih jenis dan dosis insulin yang akan diberikan kepada penderita diabetes. DAFTAR PUSTAKA 1. Website of the International Diabetes Federation: IDF Diabetes Atlas Update. 2012. [http://www.idf.org/diabetesatlas/ previouseditions], Accessed 28.11.2012. 2. Centers for Disease Control and Preven- tion (CDC) National Center for Health Statistics, Division of Health Interview Statistics, data from the National Health Interview Survey. Age-Adjusted Percentage of Adults with Diabetes using Diabetes Medication by Type of Medication, United States, 1997–2003. Data computed by the personnel of the Division of Diabetes Translation, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, CDC. Available online at http://www.cdc.gov/diabetes/ statistics /medusa /fig2.htm. 2008. 3. Perkumpulan Endokrinologi Indonesis. Konsensus Pengendalian dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia. 2011. 4. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diad Care 2015;38 (suppl,1). 5. Cheng AYY, Zinman B. Principles of insulin Therapy. In : Kahn CR, Weir GC, King GL, Jacobson AM, Moses AC, Smith RJ, editors. Joslin‘s Diabetes mellitus, 14 nd ed. New York : Lippincott Williams & Wilkins; 2005.p. 659-70. 6. Jenkins D, Rogers S. Guideline for the use of continuous variable rate intravenous insulin infusion (CVRII). Woecestershire NHS,2015;WHAT-END-011:1-15. 7. Baron AD, Kim D, Weyer C. Novel peptides under development for the treatment of type 1 and type 2 diabetes mellitus. Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol Disord. 2002; 2:63-82. 8. De Meijer PHEM, Lutterman JA, van Lier HJJ, Van t Laar A. The variability of the absorption of subcutaneously injected insulin; effect of injection technique and relation with brittleness. Diabet Med 1990;7:499-505. 9. Vaag A, Damgaard Pedersen K, Lauritzen M, Hildebrandt P, BeckNielsen H. Intramuscular versus subcutaneous injection of unmodified insulin; consequences for blood glukose control in patients with type 1 diabetes mellitus. Diabetic Medicine 1990a; 7: 335-42. 10. Loveman E, Frampton G, Clegg A. The clinical effectiveness of diabetes education models for type 2 diabetes. Health Technology Assessment 2008 ;12 :1- 36 11. Stratton IM, Adler AI, Neil HAW, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR. On behalf of the UK Prospective Diabetes Study Group Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. diabetes (UKPDS 35): prospective observational study BMJ.2000; Vol 321. Kanitakis, J. Anatomy, histology and immunohistochemistry of normal human skin. European Journal of Dermatology, 2002; 12: 390–401. Laurent A, Mistretta F, Bottigioli D, Dahel K, Goujon C, Nicolas JF, Hennino A, Laurent PE. Echographic measurement of skin thickness in adults by high frequency ultrasound to assess the appropriate microneedle length for intradermal delivery of vaccines. Vaccine. 2007;25:6423-30. Polonsky W, Jackson R. What‘s so tough about taking insulin? Addressing the problem of psychological insulin resistance in type 2 diabetes. Clinical Diabetes 2004;22:147-50. Meece J. Dispelling myths and removing barriers about insulin in type 2 diabetes. The Diabetes Educator 2006; 32:9S-18S. Davis SN, Renda SM. Psychological insulin resistance: overcoming barriers to starting insulin therapy. Diabetes Educ. 2006; 4:146S-52S. Joy SV. Clinical pearls and strategies to optimize patient outcomes. Diabetes Educ. 2008;3:54S-9S. Genev NM, Flack JR, Hoskins PL, et al. Diabetes education; whose priorities are met? Diabetic Medicine 1992; 9: 475-9. Klonoff DC. The pen is mightier than the needle (and syringe). Diabetes Technol Ther. 2001;3:631-3. Heinemann L, Hompesch M, Kapitza C, Harvey NG, Ginsberg BH, Pettis RJ. Intra-dermal insulin lispro application with a new microneedle delivery system led to a substantially more rapid insulin absorption than subcutaneous injection. Diabetologia. 2006;49: abstract. Pledger J, Hicks D, Kirkland F, Down S. Importance of injection technique in diabetes Journal of Diabetes Nursing.2012;16:160-5. Diabetes care in the UK. The first UK injection technique recommendations 2nd edition. 2011 Perriello G, Torlone E, Di Santo S, Fanelli C, De Feo P, Santusanio F, Brunetti P. Effect of storage temperature on pharmacokinetics and pharmadynamics of insulinmixtures injected subcutaneously in subjects with type 1 (insulindependent) diabetes mellitus. Diabetologia. 1988; 31:811-5. Birkebaek NH, Solvig J, Hansen B, Jorgensen C, Smedegaard J, Christiansen JS. (observations) A 4-mm needle reduces the risk of intramuscular injection without increasing backflow to skin suface in lean diabetic children and adult. Diabetes Care 2008;31:e65. 25. Kreugel G, Keers JC, Kerstes MN, Wolffenbuttel BHR. Randomized trial on the influence of the length of two insulin pen needle on glycemic control and patient preference in obese patients with diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics.2011;13:737-41. 26. Torrance T. Effecct of insulin needle reuse, size and site of injection on the risk of bending and breaking. Journal of Diabetes Nursing.2008;12:29-33. 27. NovoMix 30 FlexPen, 30 % soluble insulin aspart (rys) and 70 % insulin aspart (rys) crystallised with protamine. Consumer Medicine Information. 2014:1-12. 28. Lantus, Insulin Glargin (rDNA origin). Product Monograph. 2015;13:1-58. 29. Strauss K. Insulin injection techniques. Practical Diabetes International 1998;15:181-4. 30. A. Frid, L. Hirsch, R. Gaspar, D. Hicks, G. Kreugel, J. Liersch, C. Letondeur, J.P. Sauvanet, N. Tubiana-Rufi, K. Strauss. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes & Metabolism. 2010; 36: S3-S18. 31. Strauss K. Insulin injection techniques. Practical Diabetes International 1998;15: 181-4. 32. Richardson T, D Kerr. Skin-related complications of insulin therapy: epidemiology and emerging management strategies. American J Clinical Dermatol.2003;4:661-7. 33. Kahara T Kawara S. Shimizu A, Hisada A, Noto Y & H Kida (2004) Subcutaneous hematoma due to frequent insulin injections in a single site. Intern Med.2004; 43:148-9. 34. Kreugel G, Beter HJM, Kerstens MN, Maatenter JC, Sluiter WJ, Influence of needle size on metabolic control and patient acceptance. European Diabetes Nursing.2007;4:51-5. PPOK: DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA Islamuddin Divisi Pulmonologi dan Penyakit Kritis Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/ RS dr.Zainoel Abidin Banda Aceh Pendahuluan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyebab utama insiden morbiditas dan mortalitas diseluruh dunia. Sebagian besar penderita meninggal akibat PPOK atau disebabkan oleh komplikasi yang ditimbulkannya. PPOK penyebab kematian nomor empat didunia yang prevalensi dan mortalitas semakin meningkat dalam dekade saat ini. Tembakau merupakan penyebab utama PPOK dan juga beberapa penyakit lainnya. Saat ini anjuran berhenti merokok tembakau telah meningkatkan kualitas kesehatan dan menurunkan prevalensi terjadinya PPOK dan penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Namun demikian rokok tembakau bukan satu satunya faktor penyebab PPOK yang mungkin pada belahan dunia lain bukan merupakan penyebab utama PPOK. Tidak semua perokok akan menderita PPOK, hal ini semua tergantung kepada faktor individu yang ada. Difinisi, faktor risiko dan Patologi PPOK merupakan penyakit akibat keterbatasan aliran udara yang progresif yang disebabkan oleh respon inflamasi kronis pada jalan napas serta paru oleh Karena partikel atau gas yang berbahaya. Insiden eksaserbasi dan adanya penyakit penyerta berperan terhadap beratnya penyakit. Keterbatasan aliran udara yang kronis pada penyakit PPOK disebabkan oleh gabungan penyakit jalan napas kecil (bronkiolitis obstruktif) dan desturksi parenkim (emfisema). Inflamasi kronis menimbulkan perubahan structural dan penyempitan saluran napas kecil. Destruksi dari parenkim paru yang juga disebabkan oleh proses inflamasi menyebabkan hilangnya perlekatan alveolus terhadap jalan napas kecil dan menurunkan elastisitas paru, sehingga perubahan tersebut mengurangi kemampuan jalan napas untuk tetap terbuka pada saat. Keterbatasan jalan napas dapat diukur dengan spirometri. Faktor risiko PPOK meliputi faktor eksogen seperti rokok dan polusi udara ataupun factor endogen yang terdapat dari pasien sendiri. Faktor yang paling sering menyebabkan PPOK adalah rokok ,selain itu paparan debu, bahan kimia, perokok pasif dan penyakit infeksi saluran napas juga berperan. Genetik merupakan factor endogen yang paling pasti penyebab PPOK, defisiensi α-antitrypsin yang menjadi penyebab dasar penyakit ini, namun ini sangat jarang terjadi di jepang. Gambar.1. Diagram phenotype PPOK Table.1.Faktor Risiko PPOK Hipotesis yang menjelaskan patologi PPOK adalah terjadi akibat ketidakseimbangan protease/antiprotease dan ketidakseimbangan oksidan/antioksidan dan juga disertai adanya apoptosis sel paru itu sendiri. Kriteria Diagnosis Gejala Klinis yang didapat seperti batuk dengan sputum, sesak pada saat aktifitas serta usia pertengahan atau usia tua yang mempunayai factor risiko seperti perokok harus diduga kearah PPOK. Spirometri merupakan pemerikasaan baku emas dalam mendiagnosis PPOK. Adanya hambatan aliran udara pada gambaran FEV1 (forced expiratory volume in one second)/FVC 9Force Vital Capacity) kurang dari 70% setelah pemberian bronkodilator sebagai diagnosis pasti PPOK. Gambar 2. Patologi PPOK Derajat PPOK terbagi atas derajat 0 : Kelompok dengan Risiko., derajat I :PPOK mild(FEV1 ≥ 80% nilai prediksi.derajat II: moderate (50% ≤ FEV1 ≤80%prediksi). Derajat III : severe (FEV1≤ 50% prediksi).derajat IV: Very severe FEV1≤ 30% prediksi atau FEV1≤ 50% prediksi dengan gagal napas atau gagal jantung kanan. Gambaran Klinis Keluhan utama yang paling sering dialami penderita PPOK ialah sesak napas pada saat aktivitas, batuk kronik dengan produksi sputum yang banyak. Pemeriksaan fisik umumnya akan tidak dijumpai kecuali penyakitnya telah memberat. Inspeksi tampak bentuk dada barrel chest dan hoover sign.perkusi dada didapatkan suara yang timpani disertai dengan hiperinflasi paru.palpasi akan terlihat penurunan gerakan paru saat bernapas. Ekspirasi akan memanjang disertai suara respirasi yang melemah akan kita dapatkan saat auskultasi,bahkan terkadang diserta dengan wheezing. Berat badan yang menurun disertai dengan anorexia akan didapati seiring dengan progresifitas penyakit, ini akan mengakibatkan prognosis yang buruk. Pemeriksaan Penunjang Sulit untuk mendeteksi adanya PPOK yang ringan dengan thorak foto. CT Scan thorak lebih efektif untuk mendeteksi PPOK. Spirometri merupakan pemeriksaan yang utama untuk mendiagnosis PPOK, nilai FEV1/FVC ≤ 70% menunjukkan adanya keterbatasan aliran udara. Gambar 3. Spirometri pada individu normal dan PPOK. Gambar 4 Kurva Volume inspirasi normal (A). dan PPOK (B) Tatalaksana PPOK stabil Derajat I (mild) PPOK diberikan short acting bronchodilator (SABA) untuk meringakan gejala. Berhenti merokok sangat dianjurkan pada penderita perokok. Derajat II (moderate) PPOK, long acting bronchodilator (LABA) diberikan secara regular, chest Fisioterapi dapat dianjurkan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kemampuan aktivitas. Derajat II-IV (moderate to very severe) PPOK, long acting bronchodilator regular serta mukolitik dapat diberikan atau menggunakan dua bronkodilator dapat diberikan. Derajat III-IV (severe to very severe), penggunaan glukokortikosteroid inhalasi digunakan disamping bronkodilator. Mencegah eksaserbasi dan memperbaiki kualitas hidup harus menjadi tujuan utama terapi. Table.2. Bronkodilator dan glukocortikosteroid yang digunakan pada PPOK Tatalaksana nonfarmakologi meliputi ; Rehabilitasi pulmonary komprehensif. Terapi nutrisi Edukasi Terapi oksigen Ventilator support Pembedahan Tranplantasi paru Tatalaksana PPOK eksaserbasi Penyebab paling umum eksaserbasi pada PPOK ialah karena infeksi saluran napas dan polusi udara. Sampai saat ini belum ada klasifikasi yang tepat untuk merumuskan eksaserbasi pada PPOK termasuk juga klasifikasi pada GOLD standar. Eksaserbasi meningkatkan frekuensi rawatan dirumah sakit. Bronkodilator short acting digunakan untuk mengontrol eksaserbasi, pemberian glukokortikosteroid dapat diberikan dan antibiotik golongan quinolone,B-laktam/b-laktam inhibitor dan sepalosporin generasi III dan IV harus diberikan. Kesimpulan 1. PPOK derajat III dan IV tidak hanya menurunkan kualitas hidup dan mengurangi kemampuan aktifitas tetapi juga prognosis yang buruk. 2. Terapi oksigen jangka panjang memperbaiki outcome namun tidak mempengaruhi terhadap kadar karbon dioksida darah. Daftar Pustaka 1. Fukuchi Y, Nishimura M, Ichinose M, et al : Prebalence of chronic obstructive pulmonary disease in Japan: results from the Nippon COPD epidemiology (NICE) study. Eur Respir J 2001; 18 (suppl 33): 275s. 2. Global Initiative for chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease : National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health. April 2001; Publication Number 2701. 3. Jines PW : Measurement of breathlessness, Lung function tests, physiological principles and clinical applications (eds by Hughes JMB, Pride NB), pp121-131, WB Saunders, London, 1999. 4. Goddard PR, Nicholson EM, Lasco G, et al : Computed tomography in pulmonary emphysema. Clin Radiol 1992 ; 33: 379-387 5. Gibson GJ : Lung volumes and elasticity, Lung function tests, physiological principles and clinical applications (eds by Hughes JMB, Pride NB), pp45-56, WB Saunders, London, 1999. 6. The Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline Panel, Staff, and Consortium Representatives : A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence, JAMA 2000 ; 283 : 3244-3254 7. Kidak K : Comprehensive pulmonary rehabilitation – A manual for team management-( In Japanese), Medical Review, Tokyo, 1998. 8. Manual of pulmonary rehabilitation-exercise training-(In Japanese). Japan Society for Respiratory Care/ Japanese Respiratory Society/ Japanese Physical Therapy Association 2003. 9. Pulmonary rehabilitation guideline committee of the Japan Society for Respiratory Care/ Guideline implementation and management committee of Japanese Respiratory Society : Statement on the pulmonary rehabilitation (In Japanese). Journal of Japan Society for Respiratory Care 2001; 11; 321-330. GANGGUAN KESEIMBANGAN ELEKTROLIT Desi Salwani Divisi Ginjal dan Hipertensi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Hiponatremia Hiponatremia adalah kadar kalium kurang dari 135 mEq/L (normal 135-145 mEq/L). Kadar natrium dan osmolaritas dalam batas normal akan mempertahankan mekanisme homeostatik yang mempengaruhi rangsangan rasa haus, sekresi ADH (antidiuretik hormon) dan proses filtrasi natrium dalam ginjal. Secara klinis keadaan hiponatremia tidak khas dan tidak spesifik meskipun tenaga medis sudah mencurigai kuat ditemukan gejala disertai dengan penurunan kesadaran. Umumnya tampak sebagai gambaran retensi air akibat ketidak seimbangan dalam keseimbangan pengeluaran dan pemasukan air. Terdapat 3 mekanisme yaitu hiponatremia yang terjadi akibat faktor faktor intrarenal seperti turunnya GFR (glomerular filtration rate) dan meningkatnya reabsorbsi natrium dan air di tubulus proksimal yang diikiuti penurunan reabsorbsi di tubulus distal yang menyebabkan pengenceran di segmen segmen nefron. Kedua adalah hasil dari adanya efek transportasi natrium klorida keluar pada segmen nefron pada TALH, ketiga yang paling sering terjadi karena rangsangan sekresi vasopresin oleh mekanisme non osmotik meskipun terdapat keadaan hipoosmolaritas. Sebab SIADH Malignant disease (Bronchogenic carcinoma), Pulmonary disorders (Viral and bacterial pneumonias,Tuberculosis) Neurologic disorders ( Encephalitis, Meningitis, Trauma, Stroke, Alcohol withdrawaL), lain lain (HIV/AIDS, Acute psychosis, Acute intermittent porphyria, Idiopathic) Pendekatan diagnosis Hiponatremia adalah kelebihan cairan relatif yang terjadi bila jumlah asupan cairan melebihi kemampuan kesresi dan ketidak mampuan menekan sekresi adh misalnya pada kehilangan cairan melalui saluran cerna atau gagal jantung atau sirosis hati atau siadh (Sindrome Of Inapropiate Adh Secretion), pendekatan diagnosis terkait dengan klasifikasi hiponatremia 1. Hipovolemik hiponatremia Pada kondisi ini terdapat penurunan kadar total natrium dalam tubuh dan kadar air yang juga menurun. hal ini terjadi karena kehilangan air dan solut yang tinggi dari pencernaan dan ginjal. 2. Hipervolemik hiponatremia Kadar total natrium meningkat lebih dari kadar air dalam tubuh seperti pada penyakit gagal jantung, sindroma nefrotik dan sirosis hati yang berkaitan erat dengan sekresi air 3. Euvolemik hiponatremia Pada pasien rawatan namun tanpa keluhan. Pemeriksaan yang umumnya dilakukan adalah 1. Osmolaritas urin Pemeriksaan osmolaritas urin untuk membedakan impaired freewater excretion dan polydipsia primer. osmolaritas urin >100 mOsm/kg merupakan pertanda bahwa ginjal tidak mampu mengencerkan urin. 2. Osmolaritas serum Untuk membedakan hyponatremia dan pseudohyponatremia. 3. Konsentrasi natrium urin Untuk membedakan hyponatremia sekunder akibat hypovolemia dan syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH). Pada SIADH konsentrasi natrium urin 20-40 mEq/L. Pada hypovolemia < 25 mEq/L Tatalaksana Prinsip penatalaksanan hiponatremia adalah dengan mengatasi penyakit dasar dan menghentikan setiap obat yang ikut menyebabkan hiponatremia. Sebelum memberikan terapi sebaiknya ditentukan apakah hiponatremia merupakan hiponatremia hipoosmolalitas. Untuk hiponatremia hiperosmolalitas, koreksi yang diberikan hanya berupa air saja. Larutan pengganti yang diberikan adalah natrium hipertonik, bisa berupa NaCl 3% atau 5% NaCl. Pada sediaan NaCl 3% yang biasa dipakai, terdapat 513 mmol dalam 1 liter larutan. Koreksi pada hiponatremia kronik yang tanpa gejala, dapat diberikan sediaan oral, yaitu berupa tablet garam. Koreksi natrium secara intravena harus diberikan secara lambat, untuk mencegah central pontin myelinolysis (CPM). Kadar Na plasma tidak boleh dinaikkan lebih dari 10-12 mmol/L dalam 24 jam pertama. Terapi inisial diberikan untuk mencegah udem serebri. Untuk hiponatremia akut dengan gejala serius, koreksi dilakukan agak cepat. Kadar natrium plasma harus dinaikkan sebanyak 1,5-2 mmol/L dalam waktu 3-4 jam pertama, sampai gejala menghilang. Kecepatan cairan infus diberikan 2-3 ml/kg/jam, setelah itu dilanjutkan dengan 1 ml/kg/jam, sampai kadar Na 130 mmol/L. Untuk koreksi hiponatremia kronik, diberikan dengan target kenaikan sebesar 0,5 mmol/L setiap 1 jam, maksimal 10 mmol/L dalam 24 jam. Kecepatan infus dapat diberikan 0,5 – 1 ml/kg/jam. Pemantauan kadar Na serum harus dilakukan setiap 2-4 jam. Untuk menetukan estimasi efek pemberian cairan infus dalam menaikkan kadar natrium plasma, digunakan rumus: Perubahan Na serum= (Na dalam cairan infus-Na serum)/(TBW+1) Saat ini sedang mulai dipakai sediaan vasopressin receptor antagonis untuk meningkatkan kadar natrium. Sediaan ini akan menghambat reseptor V2 di tubulus yang akan meningkatkan ekskresi air, kemudian akan memperbaiki keadaan hiponatremia. Demeclocycline dan litium juga dapat dipakai dimana sedian ini akan mengahambat respon ginjal terhadap vasopressin. Selain itu, sediaan ini dapat juga diberikan sebagai pencegahan overkoreksi. Dosis democlocycline dapat diberikan 300-600 mg perhari. Hipokalemia Hipokalemia didefinisikan sebagai kalium plasma kurang dari 3,5 mEq/L. Hipokalemia dapat terjadi akibat asupan yang kurang, perpindahan ke dalam sel atau kehilangan kalium renal maupun non renal. Regulasi Keseimbangan Kalium Total cadangan kalium tubuh dan distribusi kalium dalam tubuh diatur oleh hormon tertentu. Distribusi kalium transellular diatur oleh minimal 2 sinyal hormonal yang memacu masuknya kation ke dalam sel. Insulin dan katekolamin adrenergik akan meningkatkan ambilan kalium ke dalam sel melalui stimulasi Na+/K+-ATP ase yang terdapat pada membran sel. Insulin menyebabkan umpan balik, hiperkalemia akan menstimulasi sekresi insulin dan hipokalemia akan menghambat sekresi kalium. Hal ini tidak terjadi pada stimulasi adrenergik, namun blokade adrenergik akan meningkatkan kalium serum dan agonis adrenergik akan menurunkan kalium serum. Sintesis N+/K+ ATP ase juga distimulasi oleh hormon tiroid yang berperan pada kejadian hipokalemia pada kondisi Hipertiroidisme. Pemberian alkali menyebabkan kalium masuk ke dalam sel. Pada gagal ginjal kronik, pemberian bikarbonat hanya sedikit mempengaruhi distribusi kalium transsellular. Peran aldosteron dalam distribusi kalium transselular masih belum jelas, namun hormon ini merupakan regulator mayor cadangan kalium tubuh melalui eksresi kalium di ginjal. Deplesi kalium atau hipokalemia juga dapat terjadi karena asupan makanan yang mengandung kalium yang rendah. Tabel 1. Jenis Obat obatan yang menyebabkan Hipokalemia Perpindahan Kalium Transelular Adrenergic agonists Epinephrine Decongestants Pseudoephedrine Phenylpropanolamine Bronchodilators Albuterol Terbutaline Pirbuterol Isoetharine Kehilangan Melalui Ginjal Diuretics Acetazolamide Thiazides Chlorthalidone Indapamide Metolazone Quinethazone Bumetanide Ethacrynic acid Furosemide Kehilangan kalium melalui feses Phenolphthalein Sodium polystyrene sulfonate Fenoterol Ephedrine Isoproterenol Metaproterenol Tocolytic agents Ritodrine Nylidrin Theophylline Caffeine Verapamil intoxication Chloroquine intoxication Insulin overdose Torsemide Mineralocorticoids Fludrocortisone Substances with mineralocorticoid effects Licorice Carbenoxolone Gossypol High-dose glucocorticoids High-dose antibiotics Penicillin Nafcillin Ampicillin Carbenicillin Drugs associated with depletion Aminoglycosides Cisplatin Foscarnet Amphotericin B Obat obat Yang menginduksi perpindahan kalium Obat obat simpatomimetik Obat-obat yang memiliki aktifitas simpatomimetik adalah decongestan, bronkhodilator dan penghambat kontraksi rahim. Albuterol inhalasi dengan dosis standar mampu menurunkan kalium serum 0,2-0,4 mmol per liter dan albuterol dosis selanjutnya setelah satu jam akan menurunkan kalium serum 1 mmol/L. Pseudoefedrin akan menyebabkan hipokalemia berat. Ritodrin, terbutalin dan penghambat kontraksi uterus akan meurunkan kalium serum 2,5 mmol/L setelah 4-6 jam pemberian obat tersebut secara intravena. Meskipun Calcium channel bloker mampu meningkatkan ambilan kalium ke dalam sel, namun obat ini tidak mempengaruhi kadar kalium serum. Pemberian verapamil dosis tinggi akan mmenyebabkan hipokalemia berat. Chlorokuin dosis tinggi mampu menurunkan kalium . Insulin mampu memindahkan kalium ke dalam sel, sehingga pemberian insulin mampu menurunkan konsentrasi kalium serum, namun tidak terlalu bermakna secara klinis kecuali pemberian insulin dosis tinggi pada Ketoasidosis Diabetikum Obat yang menginduksi kehilangan kalium secara abnormal Diuretik Tiazid dan loop diuretik akan memblock chlorida yang terkait dengan reabsorbsi (menghambat different membrane-transport protein) akibatnya hantaran natrium ke collecting tubulus terganggu, reabsorbsi natrium akan menyebabkan perubahana gradien elektrokimia pada sekresi kalium. Kombinasi furosemid atau bumetanid dengan metolazon menyebabkan hipokalemia sedang atau berat. Obat obatan dengan Mineralkortikoid atau glukokortikoid Fludrocortison merupakan mineral kortikoid yang digunakan secara oral, mampu memcetuskan ekskresi kalium melalui ginjal. Obat obat lain Penicillin dan derivat sintetis yang diberikan secara intravena dengan dosis besar akan meningkatkan ekskresi kalium ginjal melallui peningkatan hantaran natrium di distal nefron. Aminoglycoside, cisplatin, dan foscarnet menyebabkan kehilangan kalium melalui ginjal dengan menginduksi deplesi magnesium. Amfoterisin B menyebabkan kehilangan kalium ginjal melalui hambatan sekresi ion hidrogen pada sel ductus collecting juga bersamaan dengan kejadian deplesi magnesium. Laksansia dan enema Laksansia dosis besar menyebabkan kehilangan kalium melalui feses dan juga mampu menyebabkan hipokalemia. Nondrug Causes Due To Transcellular Shifts Hipokalemia berat dapat terjadi pada hipertiroidisme yang ditandai dengan kelemahan otot yang berat. Gejala dan tanda hiperthiroidisme umunya terkait dengan episode akut, kelemahan dan paralisis otot, namun terkadang terjadi kesalahn diagnosis dengan familial periodic paralisis. Kondisi ini sangat respon dengan pemberian kalium. Familial hipokalemi periodik paralisis merupakan kelainan genetika outosom dominan, berkaitan dengan mutasi gen encoding reseptor dehidroperidin, voltagegated calcium channel. Penyakit ini ditandai dengan serangan kelemahan otot yang timbul mendadak terjadi akibat perurunan kalium serum mendadak < 2,5 mmol/L, yang dapat dicetuskan oleh asupan makanan kaya akan karbohidrat atau natrium, latihan berlebihan dan umunya timbul spontan dalam waktu 24 jam. Meskipun hipokalemia yang terjadi akibat perpindahan kalium ke dalam sel. namun pemberian kalium sangat bermanfaat. Pencegahan yang dapat dilakukan dapat berupa pemberian spironolakton, triamteren dan acetazolamid. Senyawa barium yang terhirup juga dapat meyebabkan hipokalemia melalui hambatan pengeluaran kalium dari sel dan pada kondisi berat dapat menyebabkan kelemahan otot, paralisis dan rhabdomiolisis. Barium juga menyebabkan muntah dan diare, hal ini juga menyebabkan perburukan hipokalemia. Pengobatan anemia pernisiosa berat dengan vitamin B dapat pula menyebabkan penurunan kalium serum secara cepat akibat ambilan kalium secara cepat oelh sel yang baru terbentuk. Hipokalemia juga terjadi setelah transfusi washed red cell beku akibat ambilan kalium oleh sel. Nondrug Causes Due To Inadequate Dietary Intake Asupan kalium yang kurang dari 1 gram per hari (25 mmol per hari), deplesi kalium dan hipokalemia akibat ekskresi kalium ginjal. Nondrug Causes Due To Abnormal Losses Of Potassium Kehilangan melalui feses Konsentrasi kalium dalam feses berkisar 80-90 mmol per liter, namun karena kadar air dalam feses yang sangat rendah sehingga kehilangan kalium dalam feses hanya 10 mmol per hari. Pada kondisi diare, kadar kalium dalam feses akan menurun, namun jumlah feses yang yang banyak akan menyebabkan hipokalemia. Volume feses akan meningkat akibat diare dengan infeksi, kemoterapi pada kanker. Kehilangan kalium melalui ginjal Kehilangan kalium melalui ginjal dapat terjadi oleh berbagai sebab, yang diklasifikasikan berdasarkan status keseimbangan asam basa. CAUSES OF POTASSIUM LOSS IN URINE DUE TO MINERALOCORTICOID EXCESS OR RENAL TRANSPORT ABNORMALITIES. Mineralocorticoid excess Primary hyperaldosteronism Adrenal adenoma Adrenal carcinoma Bilateral adrenal hyperplasia Congenital adrenal hyperplasia* 11b-hydroxylase deficiency 17a-hydroxylase deficiency Renin-secreting tumors Ectopic corticotropin syndrome Cushing‘s syndrome Pituitary Adrenal Glucocorticoid-responsive aldosteronism* Renovascular hypertension Malignant hypertension Vasculitis Apparent mineralocorticoid excess Liddle‘s syndrome* 11b-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency* Impaired chloride-associated sodium transport Bartter‘s syndrome* Gitelman‘s syndrome* Metabolic Alkalosis Kondisi alkalosis metabolik akan menginduksi deplesi khlorida akibat muntah atau drainase gaster. Hipokalemia berlangsung selama induksi alkalosis sebagai akibat kehilangan kalium melalui ginjal. Pada kondisi chloride-sensitive form of metabolic alkalosis, pemberian chlorida akan memperbaiki alkalosis dan memberi kesempatan replesi cadangan kalium tubuh juka asupan kalium cukup. alkalosis metbolik dengan hanya deplesi chlorida jarang terjadi. Penyebab paling sering pada kondisi ini adalah primary hyperaldosteronisme, Hipokalemia juga dapat terjadi pada Cushing’s syndrome, namun hipokalemia yang terjadi lebih ringan dibandingkan pada hyperaldosteronisme. Abnormalitas genetik akan mempengaruhi aktivitas transporter ion pada ginjal, namun merupakan penyebab alkalosis metabolik yang jarang dan jarang menyebabkan hipokalemia. Liddle’s syndrome dan 11 43-46 hydroxysteroid dehydrogenase deficiency akan menstimulasi reabsorbsi natrium melalui duktus colecting dan menyebabkan syndrome mineralocorticoid excess. Abnormalitas ini menyebabkan hipertensi dan hipokalemia namun aldosteron serum lebih rendah. Pada Barter Syndrome ( menyebabkan inaktif transpoter natrium chlorida di loop henle) dan Gitelman sindrome ( kelainan pada tubulus distal) akan menyebakna alkalosis metabolik dan hipokalemia namun tanpa menyebabkan hipertensi. Pendekatan Diagnosis Gambaran klinis deplesi kalium sangat bervariasi, dan berat ringannya tergantung derajat hipokalemia. Gejala jarang terjadi kecuali kalium kurang dari 3 mEq/L.Mialgia, kelemahan otot atau cramp otot ektremitas bawah merupakan keluhan yang sering. Hipokalemia yang lebih berat dapat menyebabkan kelemahan progresif, hipoventilasi dan paralisis komplit. Deplesi kalium yang berat dapat meningkatkan resiko aritmia dan rabdomiolisis. Fungsi otot polos juga dapat terganggu dengan gambaran klinis ilues paralitik. Pada hipokalemia berat terdapat keluhan lemas dan konstipasi. Pada kondisi kalium < 2,5 mmol/L, akan terjadi nekrosis otot dan pada kondisi kalium < 2 mmol/L akan terjadi ascending paralise, bahkan mempengaruhi otot pernafasan. Keluhan yang terjadinya sejalan dengan kecepatan penurunan kadar kalium serum. Pada pasien tanpa penyakit jantung, dapat terjadi abnormalitas konduksi otot jantung yang tidak lazim walaupun denngan kadar kalium kurang 3 mmol/L. Pada pasien dengan iskemia, gagal jantung atau hipertropi ventrikel kiri, hipokalemia ringan atau sedang mampu mencetuskan aritmia. Kondisi hipokalemia akan memicu efek aritmogenik pada digoxin. Deplesi kalium dan hipokalemia mampu meningkatkan tekanan darah sistolik dan diastolik walaupun pada kondisi tanpa restriksi garam, kondisi ini mampu mencetuskan retensi garam oleh ginjal. Gejala neuro-muskular dan kardiak yang disebabkan hipokalemia berhubungan dengan terjadinya gangguan potensial aksi. Berdasarkaan persamaan Nerst, potensial membran istirahat behubungan dengan rasio konsentrasi kalium intraseluler-ekstraseluler. Penurunan konsentrasi kalium serum (ekstraselular) akan meningkatkan rasio sehingga menyebabkan hiperpolarisasi membran sel. membuat potensial membran istirahat lebih elektronegatif. Hal ini meningkatkan permeabilitas natrium yang akan meningkatkan eksitabilitas membran. Hipokalemia juga memperlambat repolarisasi ventrikel. Hal ini memperpanjang durasi periode refrakter relatif dan memudahkan terjadinya reentrant. Perubahan EKG akibat hipokalemia tidak sesuai dengan konsentrasi kalium plasma. Perubahan awal berupa mendatarnya atau inversi gelombang T, gelombang U prominen, depresi segmen Stdan pemenjangan interval QT. Deplesi kalium berat dapat menyebabkan pemanjangan interval PR, lowvoltage, dan pelebaran QRS dan meningkatkan risioko aritmia ventrikel. Hipokalemia dapat meningkatkan toksisitas digitalis. Gambar.1 Gambaran Perubahan EKG pada Hipokalemia Deplesi kalium meningkatkankan reabsorbsi HCO3 di tubulus proksimal, meningkatkan ammoniagenesia renal dan emnngkatkan sekresi H+ di tubulus distal. Hal ini menyebabkan alkalosis metabolik yang sering terjadi pada pasien hipokalemia. Diabetes insipidus nefrogenik dapat terjadi pada hipokalemia dan bermanifestasi sebagai polidipsi dan poliuri. Diagnosis penyebab dicari denga anamnesis, pemeriksaan fisik yang baik dan pemeriksaan penunjang. Penatalaksanaan Indikasi koreksi kalium dibagi dalam : - Indikasi mutlak : pemberian kalium mutlak segera diberikan yaitu pada keadaan pasien sedang dalam pengobatan digitalis, pasien dengan ketosidosis diabetik, pasien dengan kelemahan otot pernafasan dan pasien dengan hipokalemia berat (<2 mEq/L) - Indikasi kuat : kalium harus diberikan dalam waktu tidak terlalu lama yaitu pada keadaan insufisensi coroner/ iskemia otot jantung, ensefalopati hepatik dan pasien menggunakan obat yang dapat menyebabkan perpindahan kalium dari ekstra ke intrasel. - Indikasi sedang : pemberian kalium tidak perlu segera, seperti pada hipokalemia ringan ( K 3-3,5 mEq/L). Pemerian kalium oral : - Pemberian Kalium 40-60 mEq dapat meningkatkan kadar kalium 1-1,5 mEq/L dan pemberian 135-60 mEq dapat meningkakan kadar kalium 2,5-3,5 mEq/L Pemberian kalium intravena : - Keceptan pemberian KCL melalui vena perifer 10 mEq per jam, atau melalui vena sentral 20 mEq per jam atau lebih pada keadaan tertentu - Konsentrasi cairan infus KCL bila melalui vena perifer, KCL maksimal 60 mEq dilarutkan dalam NaCl isotonis 1000 ml karena bila melebihi dapat menimbulkan rasa nyeri dan menyebabkan sclerosis vena. - Konsentrasi cairan infus kalium bila melalui vena central, KCL maksimal 40 mEq dilarukan dalam NaCl isotonis 100 ml. - Pada keadaan arimia yang berbahaya atau adanya kelumpuhan otot pernafasan, KCL dapat diberikan dengan kecepatan 40-100 meq/jam. KCL sebanyak 20 meq dilarutkan dalam 100 ml NaCl isotonik. Koreksi penyebab dari hipokalemia merupakan bagian dari terapi hipokalemia. 1. Highest content (>1000 mg [25 mmol]/100 Dried figs, Molasses, Seaweed 2. Very high content (>500 mg [12.5 mmol]/1Dried fruits (dates, prunes) adalah Kacang-kacangan, Alpukat, Bran cereals, Gandum, Lima beans 3. High content (>250 mg [6.2 mmol]/100 g) adalah sayur-sayuran, spinach, tomat, brokoli, winter squash, beets, wortel, kembang kol, kentang, buah-buahan,pisang, cantaloupe, kiwi, jeruk, mangga, daging, ground beef, steak, babi, veal, kambing Daftar Pustaka 1. Elhassan EA., Schrier RW. Disorders of extracellular volume. In: Floege J, Johnson RJ, Feehally J, eds. Comprehensive clinical nephrology. 4th ed. St. Louis: Elsevier Saunders; 2010. p. 85–99. 2. Hoorn EJ, Lindemans J, Zietse R. Development of severe hyponatraemia in hospitalized patients: treatment-related risk factors and inadequate management. Nephrol Dial Transplant. 2006;21(1):70-6. 3. Goh KP. Management of hyponatremia. Am Fam Physician. 2004;69(10):2387-94Schulman M, Narins RG. Hypokalemia and cardiovascular disease. Am J Cardiol 1990;65:4E-9E. 4. Gennari FJ. Disorders of potassium metabolism. In: Suki WN, Massry SG, eds. Therapy of renal diseases and related disorders. 3rd ed. Boston: Kluwer Academic, 1997:53-84. 5. Clausen T, Everts ME. Regulation of the Na,K-pump in skeletal muscle. Kidney Int 1989;35:1-13. 6. Martinez R, Rietberg B, Skyler J, Oster JR, Perez GO. Effect of hyperkalemia on insulin secretion. Experientia1991;47:270-2. 7. Rowe JW, Tobin JD, Rosa RM, Andres R. Effect of experimental potassium deficiency on glucose and insulin metabolism. Metabolism. 1980;29:498-502. 8. AdroguéHJ, Madias NE. Changes in plasma potassium concentration during acute acid-base disturbances. Am J Med 1981;71:456-67. 9. Blumberg A, Wiedmann P, Ferrari P. Effect of prolonged bicarbonate administration on plasma potassium in terminal renal failure. Kidney Int. 1992;41:369-74. 10. Field MJ, Giebisch GJ. Hormonal control of renal potassium excretion. Kidney Int 1985;27:379-87. 11. McKenna TJ, Island DP, Nicholson WE, Liddle GW. The effects of potassium on early and late steps in aldosterone biosynthesis in cells of the zona glomerulosa. Endocrinology 1978;103:14116. 12. Chiou C-Y, Kifor I, Moore TJ, Williams GH. The effect of losartan on potassium-stimulated aldosterone secretion in vitro. Endocrinology 1994;134:2371-5. 13. Tannen RL. Potassium disorders. In: Kokko JP, Tannen RL, eds. Fluids and electrolytes. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1996:111-99. 14. Hernandez RE, Schambelan M, Cogan MG, Colman J, Morris RC Jr, Sebastian A. Dietary NaCl determines the severity of potassium depletioninduced metabolic alkalosis. Kidney Int. 1987;31:1356-67. 15. Squires RD, Huth EJ. Experimental potassium depletion in normal human subjects. I. Relation of ionic intakes to the renal conservation of potassium. J Clin Invest 1959;38:1134-48 Algoritma DIAGNOSIS DAN PENATALAKSANAAN GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE Muhammadji Ramazoni, Azzaki Abubakar Divisi Gastroentero Hepatologi/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh I. Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian para ahli terhadap penyakit refluks gastroesofageal atau gastroesophageal reflux disease(GERD) semakin meningkat, baik dari segi upaya untuk menelaah patogenesis, menegakkan diagnosis, maupun dalam hal penatalaksanaan. Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya perbedaan secara regional dari segi prevalensi dan manifestasi klinik. Selain itu, data regional juga menunjukkan adanya peningkatan angka kejadian komplikasi seperti Barret‘s Esophagus dan adenokarsinoma. GERD merupakan salah satu masalah pencernaan yang paling umum di seluruh dunia. Hampir 1 dari 5 orang akan memiliki gejala setiap kali dalam setahun dan 1 dari 10 akan menderita gejala secara teratur atau setiap hari, hal ini telah menjadi perhatian para ahli GERD di Asia Pasifik termasuk Indonesia yang merupakan Negara dengan problem gangguan saluran cerna terbanyak di wilayah Asia Tenggara. Kemajuan di bidang teknologi kedokteran, khususnya teknik endoskopi gastrointestinal dan perangkat diagnostik lainnya seperti pHmetri 24 jam dan manometri, telah meningkatkan kemampuan penatalaksanaan GERD. Di sisi lain, pengetahuan dan kemampuan para dokter, baik dokter umum maupun spesialis penyakit dalam di negara kita dalam penatalaksanaan GERD yang adekuat, dirasakan belum merata. Begitu pula penyediaan sarana penunjang diagnostik dan terapeutik yang tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya. II. Definisi Konsensus Asia Pasifik mengenai GERD tahun 2008, GERD didefinisikan sebagai suatu gangguan di mana isi lambung mengalami refluks secara berulang ke dalam esofagus, yang menyebabkan terjadinya gejala dan/atau komplikasi. Gejala GERD dapat mengalami tumpang tindih dengan sindroma dispepsia, sehingga pembedaannya harus dilakukan dengan cermat. Heartburn tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, sehingga anamnesis perlu dilakukan dengan cermat. Masyarakat Asia nampaknya lebih mudah memahami regurgitasi asam, yang diartikan sebagai perasaan adanya cairan asam di dalam mulut.1 GERD juga dapat dipandang sebagai suatu kelainan yang menyebabkan cairan lambung dengan berbagai kandungannya mengalami refluks ke dalam esofagus, dan menimbulkan gejala khas seperti heartburn (rasa terbakar di dada yang kadang disertai rasa nyeri dan pedih) serta gejala-gejala lain seperti regurgitasi (rasa asam dan pahit di lidah), nyeri epigastrium, disfagia, dan odinofagia.2 Pasien dapat mengalami gejala-gejala lain seperti nyeri dada non kardiak, kembung, mual, nyeri menelan, mudah kenyang dan nyeri ulu hati, dengan atau tanpa gejala refluks yang tipikal. Pada beberapa kasus dapat pula datang dengan gejala tidak tipikal yang tidak berasal dari saluran cerna, seperti laringitis kronik, bronkitis, dan juga asma bronkial. Penampilan yang tidak tipikal ini diakui merupakan salah satu ciri dari pasien GERD Asia, di mana keluhan nyeri dada non kardiak merupakan manifestasi umum.1 Terdapat dua kelompok pasien GERD, yaitu pasien dengan esofagitis erosif yang ditandai dengan adanya kerusakan mukosa esofagus pada pemeriksaan endoskopi (Erosive Esophagitis/ERD) dan kelompok lain adalah pasien dengan gejala refluks yang mengganggu tanpa adanya kerusakan mukosa esofagus pada pemeriksaan endoskopi (Non-Erosive Reflux Disease/NERD). Data yang ada menunjukkan bahwa gejala-gejala yang dialami oleh pasien NERD juga disebabkan oleh asam, berdasarkan pemantauan pH, respons terhadap penekanan asam dan tes Bernstein yang positif.1 GERD refrakter adalah pasien yang tidak berespons terhadap terapi dengan penghambat pompa proton (Proton Pump Inhibitor/PPI) dua kali sehari selama 4-8 minggu. Pembedaan ini penting oleh karena individu dengan GERD refrakter ini harus menjalani endoskopi saluran cerna bagian atas (SCBA) untuk mengeksklusi diagnosis penyakit ulkus peptik atau kanker dan mengidentifikasi adanya esofagitis.3 Refluks non-asam (Non Acid Reflux/NAR) adalah suatu kondisi di mana refluksat dapat berupa cairan empedu, cairan asam lemah atau alkali, dan/atau gas.4 NAR dapat merujuk kepada: a. Episode refluks yang terdiagnosis dengan manometri atau skintigrafi tanpa adanya penurunan pH di bawah 4. b. Kejadian GERD yang terdiagnosis dengan pemantauan metode spektrofotometri (Bilitec). c. Kejadian refluks yang terdiagnosis dengan pemantauan impedansi tanpa adanya penurunan pH atau penurunan pH yang tidak mencapai angka 4. d. kejadian refluks yang terdiagnosis dengan pemantauan impedansi tanpa adanya perubahan pH atau penurunan pH kurang dari 1. Komplikasi GERD yakni Barrett‘s Esophagus didefinisikan sebagai adanya epitel kolumnar yang dicurigai pada pemeriksaan endoskopi dan terbukti dengan histologi yang membutuhkan adanya metaplasia intestinal. Konsensus Asia Pasifik untuk GERD menekankan pentingnya konfirmasi histologis yang menunjukkan epitel kolumnar dengan metaplasia intestinal dan tidak hanya berdasarkan diagnosis endoskopi, juga digarisbawahi bahwa biopsi yang secara akurat merefleksikan perubahan Barrett harus dilakukan setelah GERD diterapi secara adekuat. Untuk kondisi-kondisi di mana ada kecurigaan metaplasia esofagus dari pemeriksaan endoskopi, namun masih menungggu konfirmasi histopatologi, maka dapat digunakan istilah kecurigaan endoskopi ada perubahan epitel toraks.1 III. Epidemiologi Prevalensi GERD dan komplikasinya di Asia, termasuk Indonesia, secara umum lebih rendah dibandingkan dengan negara barat, namun demikian data terakhir menunjukkan bahwa prevalensinya semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan gaya hidup yang meningkatkan seseorang terkena GERD, seperti merokok dan juga obesitas.1 Data epidemiologi dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa satu dari lima orang dewasa mengalami gejala refluks esofageal (heartburn) dan atau regurgitasi asam sekali dalam seminggu, serta lebih dari 40% mengalami gejala tersebut sekurangnya sekali dalam sebulan.5 Prevalensi esofagitis di negara-negara barat menunjukkan rerata berkisar antara 10-20%, sedangkan di Asia prevalensinya berkisar antara 3-5% dengan pengecualian di Jepang dan Taiwan yang berkisar antara 13-15% dan 15%. Suatu studi prevalensi terbaru di Jepang menunjukkan rerata prevalensi sebesar 11,5% dengan GERD didefinisikan sebagai perasaan dada terbakar paling tidak dua kali dalam seminggu.6,7 Indonesia sampai saat ini belum mempunyai data epidemiologi yang lengkap mengenai kondisi ini. Laporan yang ada dari penelitian Lelosutan SAR dkk di FKUI/RSCM-Jakarta menunjukkan bahwa dari 127 subyek penelitian yang menjalani endoskopi SCBA, 22,8% (30%) subyek di antaranya menderita esofagitis.8 Penelitian lain, dari Syam AF dkk, juga dari RSCM/FKUI-Jakarta, menunjukkan bahwa dari 1718 pasien yang menjalani pemeriksaan endoskopi SCBA atas indikasi dispepsia selama 5 tahun menunjukkan adanya peningkatan prevalensi esofagitis, dari 5,7% pada tahun awal penelitian sampai di tahun kelima menjadi 25,18% dengan rata-rata persentase 13,13% per tahun.9 IV. Patofisiologi dan patogenesis GERD merupakan penyakit multifaktorial (Gambar 1), di mana esofagitis dapat terjadi sebagai akibat dari refluks kandungan lambung ke dalam esofagus apabila:11,12 a. Terjadi kontak dalam waktu yang cukup lama antara bahan refluksat dengan mukosa esofagus. b. Terjadi penurunan resistensi jaringan mukosa esofagus, walaupun waktu kontak antara bahan refluksat dengan esofagus tidak cukup lama. c. Terjadi gangguan sensitivitas terhadap rangsangan isi lambung, yang disebabkan oleh adanya modulasi persepsi neural esofageal baik sentral maupun perifer. Gambar 1. Etiopatogenesis terjadinya GERD.11,12 Kandungan isi lambung yang menambah potensi daya rusak bahan refluksat di antaranya adalah: asam lambung, pepsin, garam empedu dan enzim pankreas. Dari semua itu yang memiliki potensi daya rusak paling tinggi adalah asam lambung. Beberapa hal yang berperandalam patogenesis GERD, di antaranya adalah: peranan infeksi Helicobacter pylori(H. pylori), peranan kebiasaan/gaya hidup, peranan motilitas, dan hipersensitivitas viseral. 11,12 Peranan infeksi H. pylori dalam patogenesis GERD relatif kecil dan kurang didukung oleh data yang ada. Namun demikian, ada hubungan terbalik antara infeksi H. pylori dengan strain virulen (Cag A positif ) dengan kejadian esofagitis, esofagus Barrett dan adenokarsinoma esofagus.13 H. pylori tidak menyebabkan atau mencegah penyakit refluks dan eradikasi dari H. pylori tidak meningkatkan risiko terjadinya GERD.1 Peranan Kebiasaan/Gaya Hidup kosumsi alkohol, diet serta faktor psikis tidak bermakna dalam patogenesis GERD, namun demikian khusus untuk populasi Asia-Pasifik ada kemungkinan alkohol mempunyai peranan lebih penting sebagaimana ditunjukkan dalam studi epidemiologi terkini dari Jepang.14,15 Beberapa studi observasional telah menunjukkan bahwa pengaruh rokok dan berat badan berlebih sebagai faktor risiko terjadinya GERD. Beberapa obat-obatan seperti bronkodilator juga dapat mempengaruhi GERD. 7,15,16 Pada pasien GERD, mekanisme predominan adalah transient lower esophageal spinchter relaxation (TLESR). Beberapa mekanisme lain yang berperan dalam patogenesis GERD antara lain menurunnya bersihan esofagus, disfungsi sfingter esofagus, dan pengosongan lambung yang lambat.11,12 Akhir-akhir ini diketahui peranan refluks non-asam/gas dalam patogenesis GERD yang didasarkan atas hipersensitivitas viseral. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hipersensitivitas viseral memodulasi persepsi neural sentral dan perifer terhadap rangsangan regangan maupun zat non-asam dari lambung.11,12 V. Diagnosis Anamnesis yang cermat merupakan cara utama untuk menegakkan diagnosis GERD. Gejala spesifik untuk GERD adalah heartburn dan / atau regurgitasi yang timbul setelah makan. Di Asia keluhan heartburn dan regurgitasi bukan merupakan penanda pasti untuk GERD. Namun, terdapat kesepakatan dari para ahli bahwa kedua keluhan tersebut merupakan karakteristik untuk GERD.1 Pada RS rujukan, sebelum dilakukan pemeriksaan endoskopi untuk menegakkan diagnosis GERD, sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang lain untuk menyingkirkan penyakit dengan gejala yang menyerupai GERD (laboratorium, EKG, USG, foto thoraks, dan lainnya sesuai indikasi). Para ahli Asia-Pasifik secara aklamasi menyatakan bahwa strategi diagnostik GERD regional, harus mempertimbangkan adanya kemungkinan timbulnya GERD bersamaan dengan kondisi lainnya seperti kanker lambung dan ulkus peptikum. Terkait pemeriksaan H. pylori untuk menyingkirkan infeksi pada pasien dengan gejala GERD di daerah dengan prevalensi tinggi untuk kanker lambung dan ulkus peptikum, para ahli masih bertentangan pendapat. Namun demikian, pemeriksaan tetap direkomendasikan dengan mempertimbangkan faktorfaktor risiko termasuk komorbid, usia, histologi lambung, riwayat keluarga, dan pilihan pasien.1 1. GERD-Q Kuesioner GERD (GERD-Q) (Tabel 1) merupakan suatu perangkat kuesioner yang dikembangkan untuk membantu diagnosis GERD dan mengukur respons terhadap terapi. Kuesioner ini dikembangkan berdasarkan data-data klinis dan informasi yang diperoleh dari studi-studi klinis berkualitas dan juga dari wawancara kualitatif terhadap pasien untuk mengevaluasi kemudahan pengisian kuesioner. Kuesioner GERD merupakan kombinasi kuesioner tervalidasi yang digunakan pada penelitian DIAMOND. Tingkat akurasi diagnosis dengan mengkombinasi beberapa kuesioner tervalidasi akan meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas diagnosis.17,18 Analisis terhadap lebih dari 300 pasien di pelayanan primer menunjukkan bahwa GERD-Q mampu memberikan sensitivitas dan spesifisitas sebesar 65% dan 71%, serupa dengan hasil yang diperoleh oleh gastroenterologis. Selain itu, GERD-Q juga menunjukkan kemampuan untuk menilai dampak relatif GERD terhadap kehidupan pasien dan membantu dalam memilih terapi.17 Di bawah ini adalah GERD-Q yang dapat diisi oleh pasien sendiri. Untuk setiap pertanyaan, responden mengisi sesuai dengan frekuensi gejala yang dirasakan dalam seminggu. Skor 8 ke atas merupakan nilai potong yang dianjurkan untuk mendeteksi individuindividu dengan kecenderungan tinggi menderita GERD.17 2. Endoskopi saluran cerna bagian atas (SCBA) Standar baku untuk diagnosis GERD dengan esofagitis erosif adalah dengan menggunakan endoskopi SCBA dan ditemukan adanya mucosal break pada esofagus. 1,19,20 Peran endoskopi SCBA dalam penegakan diagnosis GERD adalah: • Memastikan ada tidaknya kerusakan di esofagus berupa erosi, ulserasi, striktur, esofagus Barrett atau keganasan, di samping untuk menyingkirkan kelainan SCBA lainnya. • Menilai berat ringannya mucosal break dengan menggunakan klasifikasi Los Angeles modifikasi atau Savarry-Miller. • Pengambilan sampel biopsi dilakukan jika dicurigai adanya esophagus Barrett atau keganasan. 3. Pemeriksaan Histopatologi Pemeriksaan histopatologi dalam diagnosis GERD adalah untuk menentukan adanya metaplasia, displasia, atau keganasan. 4. Pemeriksaan pH-metri 24 jam Pemeriksaan pH-metri konvensional 24 jam atau kapsul 48 jam (jika tersedia) dalam diagnosis NERD adalah:4,21 Mengevaluasi pasien-pasien GERD yang tidak berespons dengan terapi PPI. Mengevaluasi apakah pasien-pasien dengan gejala ekstra esofageal sebelum terapi PPI atau setelah dinyatakan gagal dengan terapi PPI. Memastikan diagnosis GERD sebelum operasi anti-refluks atau untuk evaluasi gejala NERD berulang setelah operasi antirefluks. 5. PPI test PPI test dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada pasien dengan gejala tipikal dan tanpa adanya tanda bahaya atau risiko esofagus Barrett. Tes ini dilakukan dengan memberikan PPI dosis ganda selama 1-2 minggu tanpa didahului dengan pemeriksaan endoskopi. Jika gejala menghilang dengan pemberian PPI dan muncul kembali jika terapi PPI dihentikan, maka diagnosis GERD dapat ditegakkan. Tes dikatakan positif, apabila terjadi perbaikan klinis dalam 1 minggu sebanyak lebih dari 50%.1,19,21 Dalam sebuah studi metaanalisis, PPI test dinyatakan memiliki sensitivitas sebesar 80% dan pesifitas sebesar 74% untuk penegakan diagnosis pada pasien GERD dengan nyeri dada non kardiak. Hal ini Menggambarkan PPI test dapat dipertimbangkan sebagai strategi yang berguna dan memiliki kemungkinan nilai ekonomis dalam manajemen pasien nyeri dada non kardiak tanpa tanda bahaya yang dicurigai memiliki kelainan esofagus.12,18 6. Penunjang diagnosis lain Pilihan pemeriksaan lain yang dapat dilakukan selain pemeriksaan endoskopi dan pH metri yaitu: esofagografi barium, manometri esophagus, tes impedans, tes Bilitec, tes bernstein Tes ini untuk mengukur sensitivitas mukosa esofagus dengan memasang selang trans-nasal dan melakukan perfusi bagian distal esofagus dengan HCl 0,1 N dalam waktu kurang dari 1 jam. Tes ini bersifat pelengkap terhadap pemantauan pH esofagus 24 jam pada pasien dengan gejala tidak khas dan untuk keperluan penelitian. 2,7,21 7. Surveilans Barett’s esophagus Saat ini pemeriksaan penyaring untuk esofagus Barrett masih kontroversial, oleh karena kurangnya dampak pemeriksaan penyaring terhadap mortalitas adenokarsinoma esofageal. Endoskopi surveilans untuk individu dengan risiko tinggi disarankan untuk dilakukan sesuai dengan tingkatan displasia yang ditemukan. Untuk pembahasan lebih lanjut, harap melihat literatur terkait.2,15,18 VI. Penatalaksanaan Pada dasarnya terdapat 5 target yang ingin dicapai dan harus selalu menjadi perhatian saat merencanakan, merubah, serta menghentikan terapi pada pasien GERD. Target tersebut adalah menghilangkan gejala/keluhan, menyembuhkan lesi esofagus, mencegah kekambuhan, memperbaiki kualitas hidup, dan mencegah timbulnya komplikasi. 10,17 Gambar 2. Alur Pengobatan Berdasarkan Proses Diagnostik Pada Pelayanan Primer. 1. Penatalaksanaan non-farmakologik Perhatian utama ditujukan kepada memodifikasi berat badan berlebih dan meninggikan kepala lebih kurang 15-20 cm pada saat tidur, serta faktor-faktor tambahan lain seperti menghentikan merokok, minum alkohol, mengurangi makanan dan obat-obatan yang merangsang asam lambung dan menyebabkan refluks, makan tidak boleh terlalu kenyang dan makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur.28 2. Penatalaksanaan farmakologik Obat-obatan yang telah diketahui dapat mengatasi gejala GERD meliputi antasida, prokinetik, antagonis reseptor H2, Proton Pump Inhibitor (PPI)dan Baclofen.5,9,17 Dari semua obat-obatan PPIpaling efektif dalam menghilangkan gejala serta menyembuhkan lesi esofagitis pada GERD. PPI terbukti lebih cepat menyembuhkan lesi esofagitis serta menghilangkan gejala GERD dibanding golongan antagonis reseptor H2 dan prokinetik. Apabila PPI tidak tersedia, dapat diberikan H2RA.14, 17 Pada individu-individu dengan gejala dada terbakar atau regurgitasi episodik, penggunaan H2RA (H2-Receptor Antagonist) dan/atau antasida dapat berguna untuk memberikan peredaan gejala yang cepat. Selain itu, di Asia penggunaan prokinetik (antagonis dopamin dan antagonis reseptor serotonin) dapat berguna sebagai terapi tambahan.1 Gambar 3. Alur Pengobatan Berdasarkan Proses Diagnostik Pada Pelayanan Sekunder dan tersier.1 Pengobatan GERD dapat dimulai dengan PPI setelah diagnosis GERD ditegakkan (lihat bab diagnosis). Dosis inisial PPI adalah dosis tunggal per pagi hari sebelum makan selama 2 sampai 4 minggu. Apabila masih ditemukan gejala sesuai GERD (PPI failure), sebaiknya PPI diberikan secara berkelanjutan dengan dosis ganda sampai gejala menghilang. Umumnya terapi dosis ganda dapat diberikan sampai 4-8 minggu.1,19,21 Apabila kondisi klinis masih belum menunjukkan perbaikan harus dilakukan pemeriksaan endoskopi untuk mendapatkan kepastian adanya kelainan pada mukosa saluran cerna atas. Untuk esofagitis ringan dapat dilanjutkan dengan terapi on demand. Sedangkan untuk esofagitis berat dilanjutkan dengan terapi pemeliharaan kontinu, yang dapat diberikan sampai 6 bulan.1,19,20 Klasifikasi GERD berdasarkan hasil pemeriksaan endoskopi, grade A dan B termasuk kategori klinis esofagitis ringan sedangkan grade C dan D termasuk kategori klinis esofagitis berat. 1,19 Saat ini terapi untuk refluks non-asam (NAR) masih berkembang. Studi dengan Baclofen (sebuah agonis GABA-B) memberikan hasil yang menjanjikan, namun masih memerlukan data lebih lanjut untuk dapat direkomendasikan rutin. Terapi yang disarankan termasuk menghindari makan besar dan terlalu malam, mempertahankan posisi tegak sampai 3 jam setelah makan, penurunan berat badan dan tidur dengan kepala ditinggikan. Namun demikian masih belum ada yang memastikan bahwa tindakan-tindakan ini bermakna secara klinis. 18,10 Intervensi gaya hidup lainnya seperti menghentikan merokok dan alkohol serta merubah pola diet mampu mengurangi gejala GERD secara bermakna. Modifikasi gaya hidup digunakan sebagai terapi lini pertama seperti penurunan berat badan, mengurangi merokok, pengosongan lambung lebih dari 3 jam sebelum tidur malam. Sebuah studi sistematik yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan bahwa dari semua intervensi gaya hidup yang dilakukan, hanya penurunan berat badan dan meninggikan kepala saat tidur yang mempengaruhi gejala GERD secara bermakna. 1, 20 3. Penatalaksanaan Endoskopik Komplikasi GERD seperti Barret’s esophagus, striktur, stenosis ataupun perdarahan, dapat dilakukan terapi endoskopik berupa Argon plasma coagulation, ligasi, Endoscopic Mucosal Resection, bouginasi, hemostasis atau dilatasi. Terapi endoscopi untuk GERD masih terus berkembang dan sampai sejauh ini asih dalam konteks penelitian. Terapi endoskopi yang telah dikembangkan adalah: Radiofrequency Energy Dilivery Endoscopicsuturing 4. Penatalaksanaan Bedah Penatalaksanaan bedah mencakup tindakan pembedahan antirefluks (fundoplikasi Nissen, perbaikan hiatus hernia, dll) dan pembedahan untuk mengatasi komplikasi. Pembedahan antirefluks (fundoplikasi Nissen) dapat disarankan untuk pasien-pasien yang intoleran terhadap terapi pemeliharaan, atau dengan gejala mengganggu yang menetap (GERD refrakter). Studi-studi yang ada menunjukkan bahwa, apabila dilakukan dengan baik, efektivitas pembedahan antirefluks ini setara dengan terapi medikamentosa, namun memiliki efek samping disfagia, kembung, kesulitan bersendawa dan gangguan usus pascapembedahan.1,20 DAFTAR PUSTAKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Fock KM, Talley NJ, Fass R, et al. Asia-Pacific consensus on the management of gastroesophageal reflux disease: update. J Gastroenterol Hepatol 2012;23:8-22. Martinez-Serna T, Tercero F, Jr., Filipi CJ, et al. Symptom priority ranking in the care of gastroesophageal reflux: a review of 1,850 cases. Dig Dis 1999;17:219-24. Richter JE. How to manage refractory GERD. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2010;4:658-64. Sifrim D, Castell D, Dent J, Kahrilas PJ. Gastro-oesophageal reflux monitoring: review and consensus report on detection and definitions of acid, non-acid, and gas reflux. Gut 2009;53:1024-31. Sontag SJ. The medical management of reflux esophagitis. Role of antacids and acid inhibition. Gastroenterol Clin North Am 1990;19:683-712. Fock KM, Talley N, Hunt R, et al. Report of the Asia-Pacific consensus on the management of gastroesophageal reflux disease. J Gastroenterol Hepatol 2004;19:357-67. Fujiwara Y, Arakawa T. Epidemiology and clinical characteristics of GERD in the Japanese population. J Gastroenterol 2009;44:518-34. Lelosutan SA, Manan C, MS BMN. The Role of Gastric Acidity and Lower Esophageal Sphincter Tone on Esophagitis among Dyspeptic Patients. The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy 2010;2:6-11. Syam AF, Abdullah M, Rani AA. Prevalence of reflux esophagitis, Barret‘s esophagus and esophageal cancer in Indonesian people evaluation by endoscopy. Canc Res Treat 2010;5:83. Rosaida MS, Goh KL. Gastro-oesophageal reflux disease, reflux oesophagitis and non-erosive reflux disease in a multiracial Asian population: a prospective, endoscopy based study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16:495-501. Dickman R, Fass R. The Pathophysiology of GERD. In. Wien ; New York: Springer; 2011:13-22. Quigley EM. New developments in the pathophysiology of gastrooesophageal reflux disease (GERD): implications for patient management. Aliment Pharmacol Ther 2003;17 Suppl 2:43-51. Wu JC, Sung JJ, Chan FK, et al. Helicobacter pylori infection is associated with milder gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2009;14:427-32. Pandolfino JE, Kahrilas PJ. Smoking and gastro-oesophageal reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 2006;12:837-42. 15. Watanabe Y, Fujiwara Y, Shiba M, et al. Cigarette smoking and alcohol consumption associated with gastro-oesophageal reflux disease in Japanese men. Scand J Gastroenterol 2003;38:807-11. 16. Pandeya N, Webb PM, Sadeghi S, Green AC, Whiteman DC. Gastro-oesophageal reflux symptoms and the risks of oesophageal cancer: are the effects modified by smoking, NSAIDs or acid suppressants? Gut 2010;59:31-8. 17 .Jones R, Junghard O, Dent J, et al. Development of the GerdQ, a tool for the diagnosis and management of gastro-oesophageal reflux disease in primary care. Aliment Pharmacol Ther 2009;30:1030-8. 18. Halling K, et al. Gut 2007; 56 (Suppl III) A209: Abstract: TUE-G88. 19. DeVault KR, Castell DO. Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005;100:190-200. 20. Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF, et al. American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2008;135:1383-91, 91 e1-5. 21. Lichtenstein, David, et al. Role of Endoscopy in The Management of GERD. American Society fo Gastrointestinal Endoscopy. 2007. DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING Hendra Wahyudi, Fauzi Yusuf Divisi Gastroentero Hepatologi /SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Abstract A rapid assessment and resuscitation should take precedence over diagnostic evaluation in unstable patients with severe bleeding. Patients with active bleeding cause hemodynamic instability should be treated in intensive care unit (ICU) for resuscitation and observation, and should consider to transfer patients with upper gastrointestinal bleeding significantly to a tertiary medical center. Endoscopic findings, such as the cause of the bleeding and the new bleeding stigmata, can be combined with clinical factors to predict the risk of death and recurrent bleeding using the Rockall Risk Scoring System. Management of acute upper gastrointestinal bleeding consist of triage, general support, resuscitation fluids, blood transfusions, administration of proton pump inhibitor (PPI) and endoscopy. Epidemiologi Insidensi perdarahan saluran cerna bagian atas (PSCBA) setiap tahun di rumah sakit diperkirakan sebesar 100 per 100.000 individu dan lebih sering terjadi dibandingkan perdarahan saluran cerna bagian bawah (PSCBB). Tingkat rawatan inap PSCBA diperkirakan enam kali lipat lebih tinggi daripada PSCBB.1,2 Insiden PSCBA lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita (128 berbanding 65 per 100.000 dalam sebuah studi) dan meningkat terhadap usia. frekuensi yang dilaporkan penyebab spesifik dari UGIB bervariasi dan telah berubah dari waktu ke waktu.3–5 Patofisiologi Ulkus peptikum merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dengan system pertahanan mukosa. Beberapa mekanisme protektif dapat mencegah kejadian ulkus peptikum pada keadaan sehat (Gambar 2).6,7 Pada saat mekanisme-mekanisme ini terganggu atau tidak berfungsi, maka mukosa menjadi rentan terhadap pelbagai serangan. Hal ini sering ditemukan pada berbagai keadaan penyakit, diantaranya syok, penyakit kardiovaskular, hati atau gagal ginjal, yang merupakan kondisi predisposisi terjadinya penyakit ulkus peptikum.8 Gambar 2. Sistem pertahanan mukosa saluran cerna atas.6 Diagnosis Pasien dengan perdarahan gastrointestinal (GI) atas akut umumnya datang dengan keluhan hematemesis (muntah darah atau seperti kopi) dan/ atau melena (feses hitam). Evaluasi awal pasien dengan perdarahan GI atas akut melibatkan penilaian terhadap stabilitas hemodinamik dan resusitasi jika diperlukan.6,9 Penilaian cepat dan resusitasi harus didahulukan dari pada evaluasi diagnostik pada pasien yang tidak stabil dengan pendarahan hebat. Beberapa pasien mungkin memerlukan intubasi untuk mengurangi resiko aspirasi. Pasien dengan perdarahan aktif mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik harus dirawat di unit perawatan intensif untuk resusitasi dan observasi, serta harus mempertimbangkan mentransfer pasien dengan perdarahan saluran cerna atas yang signifikan ke pusat medis tersier.7,9 Anamnesis dan Pemeriksan Fisik Tanda dan gejala tersering dari perdarahan saluran cerna bagian atas adalah hematemesis (muntah darah), muntah berwarna coffee ground dan melena (tinja seperti aspal/tar). Sekitar 30% pasien dengan perdarahan ulkus datang dengan hematemesis, 20% dengan melena dan 50% dengan keduanya. Hematoskezia (darah segar di tinja) biasanya menunjukkan sumber perdarahan saluran cerna bawah, oleh karena darah dari saluran cerna atas berubah hitam dan serupa aspal pada saat melewati saluran cerna, sehingga menghasilkan melena.6,7 Anamnesis yang penting meliputi adanya nyeri perut; muntah seperti kopi; disfagia; feses berwarna hitam; hematemesis; dan nyeri dada. Penggunaan obat sebelumnya harus ditanyakan, terutama penggunaan clopidogrel (Plavix), warfarin (Coumadin), NSAID, aspirin, selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), dan kortikosteroid karena obat-obat ini meningkatkan risiko perdarahan PSCBA.9 Meskipun demikian, 5% pasien dengan perdarahan ulkus datang dengan hematoskezia, yang menandakan perdarahan berat, biasa lebih dari 1.000 mL. Pasien yang datang dengan hematoskezia dan disertai dengan tanda-tanda gangguan hemodinamik, seperti sinkop, hipotensi postural, takikardia dan syok harus dicurigai menderita perdarahan saluran cerna bagian atas.6 Tanda dan gejala nonspesifik termasuk nausea, vomitus, nyeri epigastrik, fenomena vasovagal dan sinkop, serta adanya penyakit komorbid tersering (misalnya diabetes melitus, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit ginjal kronik dan penyakit arthritis) dan riwayat penggunaan obat-obatan harus diketahui.6 Penilaian hemodinamik (denyut nadi, tekanan darah), laju pernafasan, status kesadaran, konjungtiva yang pucat, capillary refill yang melambat, serta tidak ditemukannya stigmata sirosis hati kronik merupakan tanda-tanda awal yang harus segera diidentifikasi. Takikardia pada saat istirahat dan hipotensi ortostatik menunjukkan adanya kehilangan darah yang cukup banyak. Luaran urin rendah, bibir kering dan vena leher kolaps juga merupakan tanda yang cukup berguna. Sebagai catatan, takikardia dapat tidak timbul apabila pasien mendapatkan terapi dengan penyekat beta, sering digunakan pada pasien gagal jantung dan sirosis hati.6 Tes laboratorium awal meliputi pengukuran hemoglobin, hematokrit, nitrogen urea darah, dan kreatinin; trombosit; protrombin dan partial tromboplastin time; rasio normalisasi internasional; tes fungsi hati; dan golongan darah. Pasien dengan perdarahan aktif dan koagulopati harus dipertimbangkan untuk transfusi dengan fresh frozen plasma, dan pasien dengan perdarahan aktif dan trombositopenia harus dipertimbangkan untuk dilakukan transfusi dengan platelets.10 Darah umumnya harus diberikan pada pasien dengan tingkat hemoglobin 7 g per dL ( 70 g per L) atau kurang; Tingkat hemoglobin harus dipertahankan pada 9 g per dL (90 g per L).9 Pemeriksaan Penunjuang Nasogastrik Tube Lavage Apakah semua pasien dengan kecurigaan PSCBA dianjurkan dipasang nasogastric lavage tube masih merupakan kontroversi. Nasogastrik tube lavage memiliki sensitivitas rendah dan kemungkinan hasil negatif yang lemah sangat tinggi terutama pada perdarahan saluran cerna atas dengan gejala klinis melena atau hematochezia.11,12 Namun, hasil yang positif pada nasogastric lavage tube menunjukkan bahwa perdarahan saluran cerna atas jauh lebih mungkin, dan memprediksi bahwa pendarahan tersebut disebabkan oleh lesi yang berisiko tinggi.11,12 Nasogastric lavage tube dibutuhkan untuk menghilangkan darah segar atau bekuan darah dari gaster sebelum dilakukan endoskopi.13 Stratifikasi Risiko Stratifikasi risiko berdasarkan penilaian klinis dan temuan endoskopi. Penilaian klinis meliputi usia, adanya shock, tekanan darah sistolik, denyut jantung, dan kondisi komorbiditas. Mortalitas meningkat dengan usia yang lebih tua dan dengan meningkatnya jumlah temuan kondisi komorbid.14 Temuan endoskopi, seperti penyebab perdarahan dan stigmata perdarahan baru, dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor klinis untuk memprediksi kematian dan risiko perdarahan berulang dengan menggunakan Rockall Risk Scoring System ( Tabel 1). Tabel 1. Rockall Risk Scoring System.6 Variabel Usia Syok Score 0 <60 Tidak ada Score 1 60-79 Nadi>100 kali/menit, TD normal Komorbiditas Tidak ada - Diagnosis endoskopik Robekan MalloryWeiss, tidak ada lesi, tidak ada stigmata perdarahan baru Ulkus dasar bersih, pigmentasi rata Ulkus peptic, esophagitis, atau penyakit erosive Stigmata endoskopik atau perdarahan baru - Score 2 >80 Nadi>100 kali/menit, TD sistolik <100 mmHg Penyakit jantung iskemik, gagal jantung kongestif, komorbid mayor lainnya Keganasan saluran cerna bagian atas (SCBA) Darah dalam SCBA, perdarahan aktif visible tanpa perdarahan atau bekuan yang menempel Score 3 - Gagal ginjal, gagal hati atau penyakit metastatic - - Pemeriksaan endoskopi, tidak hanya mendeteksi ulkus peptikum, namun juga dapat digunakan untuk mengevaluasi stigmata yang dikaitkan dengan peningkatan risiko perdarahan ulang (Gambar 1).6 Gambar 1. Stigmata endoskopik perdarahan ulkus peptikum baru. A, perdarahan aktif menyemprot. B, perdarahan merembes. C, pembuluh darah visible dengan bekuan sekeliling. D, bekuan aheren. E, bintik pigmentasi dasar. F, ulkus berdasar bersih. 6 Diferensial Diagnosis Perdarahan saluran cerna bagian atas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan faktor anatomi dan faktor patofisiologi. Dari perspektif patofisiologi, lesi ulseratif dan erosif (lambung atau duodenum ulkus, esofagitis, dan gastritis) jauh lebih umum daripada lesi vaskular (varises, angiodisplasia), lesi massa (adenocarcinoma, polip), atau lesitraumatik (Mallory-Weiss tears) (Tabel 2).15 Penyebab tersering PSCBA bila diurutkan yaitu:9,15 1. Ulcus gaster atau duodenal 2. Varises esophagus 3. Esofagits erosive atau berat 4. Gastritis/duodenitis erosive atau berat 5. Gastropati hipertensi portal 6. Angiodisplasia 7. Lesi massa (polips atau kanker) 8. Mallory-Weiss syndrome 9. Lesi yang tidak diidentifikasi (10-15%) Penyebab lain yang jarang menyebabkan PSCBA: 9,15 1. Dieulafoy's lesion 2. Gastric antral vascular ectasia 3. Hemobilia 4. Hemosuccus pancreaticus 5. Aortoenteric fistula 6. Cameron lesions 7. Ectopic varices 8. Iatrogenic bleeding setelah intervensi endoskopik Tabel 2. Penyebab perdarahan saluran cerna bagian atas (PSCBA).9 Diagnosis Cara membedakan Frekuensi (%) Pedarahan ulkus Riwayat penggunaan 62 peptikum obat-obat aspirin16 atau NSAID yang berhubungan dengan nyeri perut, nyeri yang berkurang setelah konsumsi makanan, riwayat perdarahan ulkus peptikum, infeksi helicobacter pylori Gastritis dan duodenitis Sama dengan 8 perdarahan ulkus peptikum Varises esophagus Riwayat sirosis dan 6 hipertensi portal Mallory-Weiss tear Riwayat muntah4 muntah berulang Malignansi Riwayat penurunan 2 Gastrointestinal berat badan, merokok, konsumsi alcohol Malformasi Perdarahan tanpa nyeri 10 arteriovenous pada usia >70 tahun, riwayat anemia defisiensi besi Esophagitis atau ulkus Heartburn, esophagus indigestion, atau disfagia Sumber tidak 8 teridentifikasi Penatalaksanaan Triase Semua pasien dengan instabilitas hemodinamik (shock, hipotensi ortostatik) atau perdarahan aktif harus dirawat di unit perawatan intensif untuk resusitasi dan observasi dengan monitoring tekanan darah, monitoring elektrokardiogram, dan pulse oximetry.11 General support Pasien harus menerima oksigen tambahan dengan kanula nasal dan mendapat asupan makanan melalui mulut. Kateter intravena perifer ukuran 16 atau kateter vena sentral harus dimasukkan dan penempatan kateter arteri paru-paru harus dipertimbangkan pada pasien dengan instabilitas hemodinamik atau yang membutuhkan pemantauan ketat selama resusitasi.6,11 Resusitasi cairan Resusitasi yang adekuat dan stabilisasi sangat penting sebelum endoskopi untuk meminimalkan komplikasi yang terkait pengobatan.17 Pasien dengan perdarahan aktif harus menerima cairan infus (misalnya, 500 mL normal saline atau larutan Ringer laktat lebih dari 30 menit) dan dilakukan pemeriksaan golongan darah untuk transfusi. Pasien berisiko kelebihan cairan membutuhkan pemantauan intensif. Bila tekanan darah gagal merespon upaya resusitasi awal, maka pemberian cairan harus ditingkatkan.11 Transfusi darah Keputusan untuk memulai transfusi darah bersifat individual. Pendekatan untuk memulai transfusi darah jika hemoglobin adalah <7 g / dL (70 g / L) untuk sebagian besar pasien (termasuk mereka dengan penyakit arteri koroner stabil) bertujuan menjaga hemoglobin pada tingkat ≥7 g / dL (70 g / L).13 Namun, pasien dengan perdarahan aktif dan hipovolemia mungkin memerlukan transfusi darah meskipun hemoglobin tampaknya normal.6 Hal lain yang sangat penting adalah untuk menghindari overtransfusion pada pasien yang dicurigai perdarahan varises, karena dapat memicu memburuknya perdarahan. Transfusi pasien dengan dugaan perdarahan varises dengan hemoglobin> 10 g / dL (100 g / L) harus dihindari.11 Pengobatan Acid suppression - Pasien dirawat di rumah sakit dengan perdarahan GI atas akut biasanya diobati dengan inhibitor pompa proton (PPI). Pasien dengan perdarahan GI atas akut dimulai secara empiris pada intravena (IV) PPI (misalnya, omeprazole 40 mg IV dua kali sehari).11,13 Pemberian PPI sebelum endoskopi dapat digunakan (Rekomendasi 1B) untuk pasien dengan perdarahan ulkus peptikum (PUP). Suasana lingkungan asam menyebabkan penghambatan agregasi trombosit dan koagulasi plasma, juga menyebabkan terjadinya lisis pada bekuan yang telah terbentuk. Pemberian PPI dapat secara cepat menetralisasi asam lambung intraluminal, yang menghasilkan stabilisasi bekuan darah. Pada jangka panjang, terapi antisekretorik juga mendukung penyembuhan mukosa.6 Waktu endoskopi Endoskopi telah menjadi alat untuk diagnosis dan tatalaksana PSCBA yang utama. Tindakan ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi sumber pendarahan dan terapi pada saat yang sama. Waktu optimal endoskopi masih dalam perdebatan. Endoskopi darurat memungkinkan untuk dilakukan hemostasis dini, namun dapat menyebabkan terjadinya aspirasi darah dan desaturasi oksigen pada pasien yang belum stabil. Sebagai tambahan, jumlah darah dan bekuan yang banyak dapat mengganggu terapi target untuk focus pendarahan, yang dapat menyebabkan dibutuhkannya prosedur endoskopik ulangan.6 Konsensus internasional dan Asia-Pasifik menganjurkan endoskopi dini dalam waktu 24 jam setelah pasien dirawat, oleh karena tindakan ini secara signifikan menurunkan lama rawat inap dan memperbaiki luaran klinis. Endoskopi sangat dini (<12 jam) sampai saat ini belum menunjukkan keuntungan tambahan dalam hal menurunkan risiko pendarahan ulangan, pembedahan dan mortalitas bila dibandingkan dengan waktu 24 jam. Namun demikian, endoskopi darurat harus dipertimbangkan pada pasien dengan pendarahan berat. Pada pasien dengan gambaran klinis risiko lebih tinggi (misalnya: takikardi, hipotensi, muntah darah, atau darah segar pada NGT ) endoskopi dalam 12 jam kemungkinan dapat meningkatkan luaran klinis.6 DAFTAR PUSTAKA 1. Longstreth G. Epidemiology of hospitalization for acute upper gastrointestinal hemorrhage: a population-based study. Am J Gastroenterol. 1995;90:206. 2. Lanas A, Perez-Aisa M, Feu F. A nationwide study of mortality associated with hospital admission due to severe gastrointestinal events and those associated with nonsteroidal antiinflammatory drug use. Am J Gastroenterol2. 2005;100:1685. 3. Boonpongmanee S, Fleischer D, Pezzullo J. The frequency of peptic ulcer as a cause of upper-GI bleeding is exaggerated. Gastrointest 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Endosc. 2004;59:788. Balderas V, Bhore R, Lara L. The hematocrit level in upper gastrointestinal hemorrhage: safety of endoscopy and outcomes. Am J Med. 2011;124:970. Wollenman C, Chason R, Reisch J, Rockey D. Impact of ethnicity in upper gastrointestinal hemorrhage. J Clin Gastroenterol. 2014;48:343. Marcellus S, Syam A, Abdullah M, Fauzi A, Renaldi K. Konsensus Nasional Penatalaksanaan Perdarahan Saluran Cerna Atas Non Varises di Indonesia. In Jakarta: Perkumpulan Gastroenterology Indonesia; 2012. p. 11–2. Adi P. Pengelolaan Perdarahan Saluran Cerna Bagian Atas. In: Ilmu Penyakit Dalam. 6th ed. Jakarta: PAPDI; 2014. p. 1873–80. Hauser S, Pardi D, Poterucha J, Mayo Clinic. Mayo Clinic gastroenterology and hepatology board review. In Mayo Clinic Scientific Press; 2004. Wilkins, Thad., Khan, Naiman., Nabh, Akash. RRS. Diagnosis and management of upper gastrointestinal bleeding. 2011;33:1–26. Barkun A, Bardou M, Kuipers E. International Consensus Upper Gastrointestinal Bleeding Conference Group. International consensus recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med. 2010;152(2):101–13. Saltzman J, Feldman M, Travis A. Approach to acute upper gastrointestinal bleeding in adults. UpToDate Wolters Kluwer. 2016. p. 1. Aljebreen A, Fallone C, Barkun A. Nasogastric aspirate predicts high-risk endoscopic lesions in patients with acute upper-GI bleeding. Gastrointest Endosc. 2004;59:172. Gralnek IM, Dumonceau J-M, Kuipers EJ, Lanas A, Sanders DS, Kurien M, et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2015;47:1–46. Duggan J. Gastrointestinal hemorrhage: should we transfuse less? Dig Dis Sci. 2009;54:1662. Rockey C, Feldman M, Traveis A. Causes of upper gastrointestinal bleeding in adults. UpToDate Wolters Kluwer. 2016. p. 1. Laine L. Upper Gastrointestinal Bleeding Due to a Peptic Ulcer. N Engl J Med. 2016;374:23. Baradarian R, Ramdhaney S, Chapalamadugu R. Early intensive resuscitation of patients with upper gastrointestinal bleeding decreases mortality. Am J Gastroenterol. 2004;99:169. APPROPIATE PAIN MANAGEMENT Asrul Harsal Divisi Hematologi Onkologi Medik Departemen Ilmu Peny Dalam , Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta. Abstrak Pengobatan Nyeri kanker masih dibawah standar , baik di negara maju maupun di Indonesia. Penduduk Indonesia yang sangat banyak pemakaian opioid pertahun hampir sama dengan pemakaian negara Singapura per tahun, dan ini memberi kesan bahwa pasien nyeri kanker di Indonesia tidak mendapatkan pengobatan nyeri yang baik. Banyak hambatan dalam pemakaian opioid antara lain ; dari pasien/keluarga, petugas kesehatan, pengatur kebijakan termasuk pemerintah , semua ini berpengaruh terhadap penatalaksanaan nyeri berat di Indonesia. Hambatan ini harus diatasi secara bersama sama agar pasien nyeri kanker mendapatkan pengobatan yang optimal. Kesadaran akan masalah nyeri sudah mulai ada yang terlihat dalam lembaran status pasien rawat inap, nyeri termasuk 5 pemeriksaan dasar yaitu, tekanan darah , nadi , suhu, nafas dan nyeri (biasanya memakai skala VAS ( Visual analog Scale 1 – 10 )). Penatalaksanaan nyeri kanker harus multidisiplin yang melibatkan banyak keahlian sesuai dengan masalah saat itu. Penatalaksanaan nyeri kanker terdiri dari 2 bagian : Medikamentosa dan non medikamentosa. Hampir 90 % nyeri kanker dapat diatasi dengan cara medikamentosa ( obat - obatan ) . Penatalaksanaan nyeri kanker membutuhkan waktu yang cukup untuk mengenal nyeri itu sendiri dengan asesmen yang baik . anamnesis yang detil akan bisa mendeskripsi nyeri didukung oleh data imaging ,sehingga nyeri akan dikenal dan akan mendapat obat yang tepat dari awal. Penatalaksanaan nyeri ringan mungkin tidak ada masalah , untuk nyeri sedang dan berat pemakaian opioid kuat sudah harus digunakan , karena ketidak tahuan , sehingga ketakutan akan opioid menjadikan obat ini jarang dipergunakan atau hanya dosis kecil saja pada hal pada pasien kanker stadium lanjut kebutuhan opioid bisa sangat besar. Obat obat anti nyeri yang tersedia saat ini terbagi kepada 3 golongan , obat untuk nyeri ringan adalah parasetamol, asam mefenamat dan anti steroid anti inflamasi. Untuk nyeri sedang obat yang dianjurkan adalah codein atau tramadol dan ada yang sudah memulai dengan opioid kuat seperti morfin yang dimulai dengan dosis rendah , untuk nyeri berat dimulai dengan morfin drip dan pasien sebaiknya dirawat di rumah sakit Pemakaian opioid kuat sebaiknya dengan titrasi agar toleransinya baik sehingga pasien bisa mendapatkan dosis tinggi tanpa efek samping . Dosis awal titrasi sangat bervariasi dan biasanya dimulai dengan dosis rendah dan dinaikkan segera secara bertahap sampai nyeri hilang. Obat opioid kuat yang tersedia di Indonesia antara lain : Morfin injeksi. Morfin oral Immediate tablet , morfin tablet lepas lambat 12 jam. Hidromorphone tablet lepas lambat 24 jam dan fentanyl patch / tempel kulit selama 72 jam. Pemakaian opioid harus terus menerus tidak boleh kalau perlu dan jika tidak nyeri lagi maka penurunan dosis secara bertahap tidak boleh tiba tiba. Efek samping yang perlu diperhatikan adalah , obstipasi, mual , mengantuk, bradipneu. Diperlukan pencegahan obsstipasi dengan memberikan laksansia pada saat awal pemberian opioid . Anti dotum Naloxone harus tersedia pada tempat pelayanan yang memberikan opioid. Kesimpulan Penatalaksanaan nyeri kanker yang baik adalah berdasarkan tingkatan dan jenis nyeri, pemakaian opioid yang tepat dengan efek samping yang bisa dicegah, pemberian oioid terus menerus dan pasien kanker bebas nyeri sehingga kualitas hidup pasien menjadi lebih baik UPDATE MANAGEMENT OF CANCER PAIN Asrul Harsal Divisi Hematologi Onkologi Medik Departemen Ilmu Peny Dalam , Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta. Abstrak Nyeri Kanker merupakan keluhan yang tidak jarang ditemukan pada pasien kanker , keluhan ini bisa didapat pada stadium awal dari seorang penderita kanker dan lebih sering ditemukan pada penderita kanker stadium lanjut. Pada perawatan paliatif pasien kanker, ditemukan sekitar 70 % pasien kelompok ini mengeluh nyeri . Penatalaksanaan nyeri kanker secara umum , berdasarkan kepada step Ladder WHO yang sudah dipakai sejak 1986 dan sampai saat ini masih dipakai dan bermanfaat untuk pasien nyeri kanker. Menurut step Ladder WHO, nyeri kanker dibagi atas 3 kelompok, yaitu Nyeri ringan , nyeri sedang dan nyeri berat. Pembagian ini menjadi penting sekali karena merupakan pedoman untuk menentukan tingkatan nyeri dan sekaligus untuk menentukan pemakaian obat yang diberikan Nyeri adalah sesuatu yang sangat subjektif , sehingga diperlukan suatu alat bantu untuk mrnyamakan persepsi . Ada banyak cara yang bisa dipakai, antara lain : Visual Analog Scale ( VAS ), Numeric Rating Scale (NRS ) , Brief Inventory Report ( BIP ) dan lainnya. Semua sistem ini bisa dipakai, akan tetapi yang sering digunakan adalah VAS. Penatalaksanaan nyeri kanker memerlukan beberapa tahap yang saling terkait dan erat sekali hubungannya, yaitu : 1. Asesment / Penilaian. Asesmen ini merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan nyeri kanker.Asesmen meliputi anamnesis yang jelas dan detil, pemeriksaan fisik, pemeriksaan imajing yang menunjang diagnosis kanker . Hasilnya adalah tingkatan nyeri. Selain tingkatan nyeri juga diperlukan jenis nyeri , yang meliputi, nyeri visceral, somatik, neuropatik dan nyeri psikogenik . Dan biasanya nyeri kanker adalah gabungan dari beberapa jenis tersebut. Sehingga akan dapat diberikan obat nyeri yang sesuai. 2. Pengobatan. Nyeri ringan dengan nilai VAS 1 – 4 , obat yang dianjurkan adalah , Parasetamol, asam mefenamat,atau NSAID. Nyeri sedang : Nyeri sedang adalah nyeri dengan nilai VAS 4 – 6. Pengobatan yang diberikan ada 2 pendapat . Pertama . Opioid Ringan seperti Codein atau Tramadol .Kedua,Opioid kuat , Morfin drip atau oral . Nyeri Berat : Opioid kuat , dimulai dengan Morfin drip , dititrasi dengan ketat sampai tercapai dosis yang sesuai , dengan melakukan asesmen secara berkala. Selain opioid perlu diperhatikan juga obat ajuvan yang akan membantu manfaat obat nyeri yang dipakai antara lain ,kortikosteroid, Gabapentin/ pregabalin, amitriptiline dan bisfosfonat yang bermanfaat pada nyeri tulang. 3. Reasesmen dan evaluasi. Penilaian kembali dilakukan secara ketat pada nyeri berat,antara 15 menit sampai 60 menit sampai nyeri hilang . Evaluasi dilakukan setelah nyeri terkontrol dengan baik, apakah dosis morfin masih perlu diteruskan atau bisa diturunkan , adakalanya dosis perlu dinaikkan , tergantung kondisi pasien saat itu. Kesimpulan. Nyeri kanker merupakan masalah besar pada pasien kanker stadium lanjut, nyeri kanker bisa diatasi dengan baik dengan target bebas nyeri, Obat opioid merupakan anti nyeri kanker yang harus digunakan pada nyeri berat agar pasien bebas nyeri. Obat ajuvan diperlukan untuk mendukung obat anti nyeri . Workshop DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA TERKINI NODUL TIROID Hendra Zufry Divisi Endokrinologi, Metabolik & Diabetes- Pusat Pelayanan Tiroid Terpadu Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/RSUD.Dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. I. Pendahuluan Menurut American Thyroid Association, nodul tiroid mengacu pada semua pertumbuhan abnormal pada sel-sel tiroid menjadi kumpulan massa (benjolan) di dalam kelenjar tiroid. Walaupun sebagian besar nodul tiroid bersifat jinak (nonkanker), namun terdapat kemungkinan sebagian nodul tiroid merupakan keganasan pada tiroid. Oleh karena itu, evaluasi nodul tiroid dilakukan untuk menemukan kasus keganasan pada tiroid. 1 Penyakit nodul tiroid umum ditemukan di masyarakat. Risiko untuk mengalami nodul tiroid diperkirakan sebesar 5-50% bergantung pada sensitivitas metode yang digunakan dan populasi yang diteliti. Nodul tiroid lebih sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria. Walaupun secara umum sering ditemukan, namun keganasan kelenjar tiroid hanya sebesar 0.004% dari populasi setiap tahun atau sebanyak 12.000 kasus baru pertahun. Prevalensi nodul tiroid meningkat secara linier dengan penambahan usia, pajanan sinar radiasi pengion, dan defisiensi iodium. Prevalensi ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, riwayat radiasi sinar pengion yang pernah diterima pasien, serta riwayat keganasan tiroid pada keluarga. Anak-anak di bawah usia 20 tahun dengan nodul tiroid dingin mempunyai risiko keganasan dua kali lipat dibandingkan usia dewasa. Kelompok usia di atas 60 tahun selain memiliki prevalensi keganasan lebih tinggi, juga mempunyai tingkat agresivitas penyakit yang lebih berat. 2 Etiologi dan Patofisiologi1,2 Nodul tiroid sebagian besar disebabkan oleh neoplasma jinak (non-kanker), selain itu 1% nodul tiroid disebabkan kanker tiroid. Jenis tersering dari nodul tiroid non-kanker adalah nodul koloid dan neoplasma follikuler. Nodul yang memproduksi hormon tiroid melebihi kebutuhan tubuh disebut autonomous nodule, hal ini akan bermanifestasi menjadi keadaan hipertiroidisme. Sedangkan jika nodul terisi cairan atau darah disebut sebagai kista tiroid. Gangguan pada jalur TRH-TSH hormon tiroid ini menyebabkan perubahan dalam struktur dan fungsi kelenjar tiroid gondok. Jika suatu kelompok kecil sel tiroid, sel inflamasi, atau sel maligna metastase ke II. kelenjar tiroid, akan menyebabkan nodul tiroid (Mulinda, 2005) Defisiensi dalam sintesis atau uptake hormon tiroid akan menyebabkan peningkatan produksi TSH. Peningkatan TSH menyebabkan peningkatan jumlah dan hiperplasi sel kelenjar tyroid untuk menormalisir level hormon tiroid. Jika proses ini terus menerus, akan terbentuk hipertrofi kelenjar tiroid (struma). Penyebab defisiensi hormon tiroid termasuk inborn error sintesis hormon tiroid, defisiensi iodida dan goitrogen . III. Diagnosis Nodul tiroid Diagnosis klinis nodul tiroid ditentukan dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bertujuan untuk memberi keterangan tambahan atau menentukan tindakan definitif. Pemeriksaan penunjang untuk nodul tiroid diantaranya dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG, pemeriksaan scanning tiroid /sidik tiroid. Pemeriksaan FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy), dan pemeriksaan histopatologi dengan parafin coupe atau potong beku . 2. Anamnesa dan pemeriksaan Fisik Anamnesis sangatlah pentinglah untuk mengetahui patogenesis atau macam kelainan dari nodul tiroid. Perlu ditanyakan apakah penderita dari daerah endemis dan banyak tetangga yang sakit seperti penderita. Apakah sebelumnya penderita pernah mengalami sakit leher bagian depan bawah disertai peningkatan suhu tubuh (tiroiditis kronis). Apakah ada yang meninggal akibat penyakit yang sama dengan penderita (karsinoma tiroid tipe meduler) . Pada status lokalis pemeriksaan fisik perlu dinilai :2 1. jumlah nodul, diffusa atau terlokalisasi 2. Permukaan nodul rata atau noduler 3. konsistensi lunak atau padat 4. Mobilisasi, dapat digerakkan atau terfiksasi 5. nyeri pada penekanan : ada atau tidak 6. pembesaran gelenjar getah bening 2. Pemeriksaan Penunjang 2.1. Evaluasi Laboratorium Pemeriksaan TSH sebaiknya dilakukan pada pasien dengan gejala hipotiroidisme atau tirotoksikosis (gambar 4). Jika kadar TSH dalam batas normal, maka aspirasi nodul dapat dipertimbangkan. Jika level TSH rendah, maka diagnosis mengarah ke hipertiroidisme. Sedangkan jika level TSH meningkat, maka dapat ditegakkan suatu diagnosis hipotiroidisme. Kadar kalsitonin diperiksa pada pasien dengan riwayat karsinoma tiroid dalam keluarga. Tes fungsi tiroid sebaiknya tidak digunakan untuk membedakan nodul tiroid jinak dan ganas. T4, antibodi antitiroid peroksidase dan pemeriksaan tiroglobulin kurang bermakna dalam menentukan apakah nodul tiroid bersifat jinak atau ganas, tetapi pemeriksaan ini dapat membantu diagnosis penyakit Graves atau tiroiditis Hashimoto. 2.2. Pemeriksaan Sidik Tiroid.3 Hasil pemeriksaan dengan radioisotop adalah teraan ukuran, bentuk lokasi, dan yang utama ialah fungsi bagian-bagian tiroid. Pada pemeriksaan ini pasien diberi Nal peroral dan setelah 24 jam secara fotografik ditentukan konsentrasi yodium radioaktif yang ditangkap oleh tiroid. Dari hasil sidik tiroid dibedakan 3 bentuk : ·Nodul dingin bila penangkapan yodium nihil atau kurang dibandingkan sekitarnya. · Nodul panas bila penangkapan yodium lebih banyak dari pada sekitarnya. Keadaan ini memperlihatkan aktivitas yang berlebih. ·Nodul hangat bila penangkapan yodium sama dengan sekitarnya. Ini berarti fungsi nodul sama dengan bagian tiroid yang lain. 2.3. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG).3 Pemeriksaan ini dapat membedakan antara padat, cair, dan beberapa bentuk kelainan, tetapi belum dapat membedakan dengan pasti ganas atau jinak. Kelainan kelainan yang dapat didiagnosis dengan USG : ·Kista ·Adenoma ·Kemungkinan karsinoma ·Tiroiditis 2.4. Biopsi Aspirasi Jarum Halus (Fine Needle Aspiration/FNA)4 Mempergunakan jarum suntik no. 22-27. Pada kista dapat juga dihisap cairan secukupnya, sehingga dapat mengecilkan nodul . Dilakukan khusus pada keadaan yang mencurigakan suatu keganasan. Biopsi aspirasi jarum halus tidak nyeri, hampir tidak menyababkan bahaya penyebaran selsel ganas. Kerugian pemeriksaan ini dapat memberika hasil negatif palsu karena lokasi biopsi kurang tepat, teknik biopsi kurang benar, pembuatan preparat yang kurang baik atau positif palsu karena salah interpretasi oleh ahli sitologi. 2.5. Termografi Metode pemeriksaan berdasarkan pengukuran suhu kulit pada suatu tempat dengan memakai Dynamic Telethermography. Pemeriksaan ini dilakukan khusus pada keadaan yang mencurigakan suatu keganasan. Hasilnya disebut panas apabila perbedaan panas dengan sekitarnya > 0,9o C dan dingin apabila <>o C. Pada penelitian Alves didapatkan bahwa pada yang ganas semua hasilnya panas. Pemeriksaan ini paling sensitif dan spesifik bila dibanding dengan pemeriksaan lain. 2.6. Petanda Tumor Pada pemeriksaan ini yang diukur adalah peninggian tiroglobulin (Tg) serum. Kadar Tg serum normal antara 1,5-3,0 ng/ml, pada kelainan jinak rataa-rata 323 ng/ml, dan pada keganasan rata-rata 424 ng/ml. 2.7. Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI)5 RFI memiliki sensitivitas tinggi dan spesifisitas untuk identifikasi tiroid. Teknik ini mungkin berguna untuk memilih pasien dengan nodul tiroid untuk operasi. 2.8. Qualitative Elastography6 Elastography memiliki spesifisitas dan sensitivitas untuk akurasi diagnostik. Kekuatan utamanya dapat mendeteksi benignity, terutama pada soft nodul jinak. sehingga hal ini dapat mencegah prosedur diagnostik invasif yang tidak diperlukan pasien. 2.9. Shear Wave Elastography (SWE)7 parameter kuantitatif SWE adalah prediktor independen darievaluasi keganasan tiroid untuk memprediksi keganasan tiroid. 2.10. Combination of FNA and Core Biopsy (CFNACB)8 Pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang tidak terdiagnosa dengan fine needle aspirasi . CFNACB lebih superior dibandingkan dengan CB atau FNA saja. CFNACB dapat menjadi acuan yang kuat sebagai alternatif untuk melakukan tindakan bedah yang tidak bisa di diagnosa melalui FNAs. IV. Tatalaksana Nodul Tiroid 1,9 4.1. Terapi Medikamentosa dan Bedah pada Pasien Nodul Tiroid Jinak Rekomendasi terapi rutin supresi TSH untuk nodul tiroid jinak pada populasi yang cukup yodium tidak dianjurkan. Rekomendasi pasien individu dengan nodul jinak, padat, atau nodul sebagian besar padat nodul harus mengkonsumsi asupan yodium yang adekuat. Jika tidak adekuat asupan yodiumnya maka dianjurkan pemberian suplemen harian 150 lg iodine.(Strong recommendation, Moderate-quality evidence). Rekomendasi tindakan bedah dipertimbangkan pada nodul yang jinak setelah FNA berulang dengan ukuran> 4 cm, menyebabkan gejala penekanan pada struktural simptomp, atau berdasarkan pada kondisis klinis. (Weak recommendation, Low-quality evidence). Pasien dengan nodul yang jinak setelah FNA harus secara teratur dipantau. kebanyakan asimtomatik nodul menunjukkan pertumbuhan moderat harus diikuti tanpa intervensi. (Strong recommendation, Low-quality evidence). Rekuren nodul tiroid kistik dengan sitologi jinak harus dipertimbangkan untuk operasi pengangkatan atau percutaneous ethanol injection (PEI) berdasarkan gejala tekan dan kepentingan kosmetik. nodul kistik asimtomatik mungkin diikuti konservatif. (Weak recommendation, Low-quality evidence). Tidak ada data yang merekomendasikan pada penggunaan terapi hormon tiroid pada pasien dengan nodul yang jinak berdasarkan hasil sitologi sitologi. (No recommendation, Insufficient evidence) 4.2. Tindakan Ablasi pada Nodul Tiroid. Rekomendasi US-Guided mengenai tindakan ablasi nodul tiroid adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengurangi volume nodul tiroid jinak, chemical (etanol) atau termal (laser dan frekuensi radio) ablasi merupakan modalitas yang dapat dipertimbangkan, 2. Recurrent nodul tiroid cystic setelah aspirasi sederhana dapat diobati dengan ablasi etanol, tergantung pada compresiv simptom dan kepentingan kosmetik, 3. Ablasi termal (frekuensi radio atau laser) menunjukkan efikasi dan keamanan yang tinggi dalam pengobatan nodul tiroid padat yang jinak, dan mungkin dianggap sebagai alternatif yang valid untuk operasi. 4.3. Inisial Managemen Guidline : DIFFERENTIATED THYROID CANCER Tujuan dasar dari terapi awal pasien dengan DTC adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup secara keseluruhan dan penyakit-spesifik, mengurangi risiko persisten / penyakit berulang dan morbiditas terkait, stratifikasi risiko, meminimalkan morbiditas terkait pengobatan dan tidak perlu terapi. Tujuan spesifik dari terapi awal adalah: 1. Mengangkat tumor primer 2. Minimalkan risiko kekambuhan penyakit dan metastasis. Operasi yang memadai adalah pengobatan yang paling penting variabel yang mempengaruhi prognosis, sedangkan pengobatan RAI, penekanan TSH, dan perawatan lainnya masing-masing bermain peran tambahan pada setidaknya beberapa pasien . 3. Memfasilitasi perawatan pasca operasi dengan RAI yang sesuai. 4. Penetapan staging yang akurat dan stratifikasi risiko penyakit. 5. Pengawasan jangka panjang untuk kekambuhan penyakit. 6. Minimalkan morbiditas terkait pengobatan. Luasnya operasi dan pengalaman dokter bedah kedua bermain peran penting dalam menentukan risiko komplikasi bedah. DAFTAR PUSTAKA 1. American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer 2015 Volume 26, Number 1, 2016. 2. Ashor R. Shaha,MD. Diagnosis and work-up of thyroid nodules. 2003. 3. Jung Hee Shin, MD1, Jung Hwan Baek, MD2, Jin Chung. Ultrasonography Diagnosis and Imaging-Based Management of Thyroid Nodules: Revised Korean Society of Thyroid Radiology Consensus Statement and Recommendations Korean J Radiol 2016;17(3):370-395. 4. Young Hen Lee, MD1, Jung Hwan Baek, MD2, So Lyung Jung, MD3, Jin Young Kwak, MD4, Ji-hoon Kim, MD5, Jung Hee Shin, MD6. Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration of Thyroid Nodules: A Consensus Statement by the Korean Society of Thyroid Radiology, Korean J Radiol 2015;16(2):391-401. 5. Jia Zhan, Jia-Mei Jin, Xue-Hong Diao, Yue Chen, Acoustic radiation force impulse imaging (ARFI) for differentiation ofbenign and malignant thyroid nodules—A meta-analysis,2015. 6. Sjoerd Nell, Jakob W. Kist , Thomas P.A. Debray, Bart de Keizer, Timotheus J. van Oostenbruggea, Inne H.M. Borel Rinkesa, Gerlof D. Valkd, Menno R. Vriens, Qualitative elastography can replace thyroid nodule fine-needle aspiration in patients with soft thyroid nodules. A systematic review and metaanalysis, 2015. 7. Ah Young Parka, Eun Ju Sona, Kyunghwa Hanb, Ji Hyun Youka,Jeong-Ah Kima, Cheong Soo Park, Shear wave elastography of thyroid nodules for the prediction ofmalignancy in a large scale study, 2014. 8. Anthony E. Samir,Abhinav Vij, Melanie K. Seale, Gaurav Desai, Elkan Halpern, William C. Faquin, Sareh Parangi, Peter F. Hahn, and Gilbert H. Daniels,Ultrasound-Guided Percutaneous Thyroid Nodule Core Biopsy: Clinical Utility in Patients with Prior Nondiagnostic Fine-Needle Aspirate, Volume 22, Number 5, 2012. 9. Jung Hee Shin, MD1, Jung Hwan Baek, MD2, Jin Chung, MD3, Eun Ju Ha, MD4, Ji-hoon Kim, MD5, Young Hen Lee,et al , Ultrasonography Diagnosis and Imaging-Based Management of Thyroid Nodules: Revised Korean Society of Thyroid Radiology Consensus Statement and Recommendations, Korean J Radiol 2016;17(3):370-395. PENDEKATAN DIAGNOSIT KRISIS HIPERTENSI Abdullah Divisi Ginjal dan Hipertensi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD. dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Pendahuluan Hipertensi krisis merupakan salah satu kegawatan dibidang neurovaskular yang sering dijumpai di instalasi gawat darurat. Hipertensi krisis ditandai dengan peningkatan tekanan darah akut dan sering berhubungan dengan gejala sistemik yang merupakan konsekuensi dari peningkatan darah tersebut. Ini merupakan komplikasi yang sering dari penderita dengan hipertensi dan membutuhkan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa. Duapuluh persen pasien hipertensi yang datang ke UGD adalah pasien hipertensi krisis. Data di Amerika Serikat menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi dari 6,7% pada penduduk berusia 20-39 tahun, menjadi 65% pada penduduk berusia diatas 60 tahun. Data ini dari total penduduk 30% diantaranya menderita hipertensi dan hampir 1%-2% akan berlanjut menjadi hipertensi krisis disertai kerusakan organ target. Sebagian besar pasien dengan stroke perdarahan mengalami hipertensi krisis. Pada JNC 7 tidak menyertakan hipertensi krisis ke dalam tiga stadium klasifikasi hipertensi, namun hipertensi krisis dikategorikan dalam pembahasan hipertensi sebagai keadaan khusus yang memerlukan tatalaksana yang lebih agresif. Tabel 1. Klasifikasi tekanan darah menurut JNC-7 Klasifikasi Tekanan Darah Normal Prehipertensi Hipertensi stadium 1 Hipertensi stadium 2 Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) < 120 120-139 140-159 ≥ 160 dan < 80 atau 80-89 atau 90-99 atau ≥ 100 Definisi Terdapat perbedaan dari beberapa sumber mengenai definisi peningkatan darah akut. Definisi yang paing sering dipakai adalah: 1. Hipertensi emergensi (darurat) Peningkatan tekanan darah sistolik >180 mmHg atau diastolik > 120 mmHg secara mendadak disertai kerusakan organ target. Hipertensi emergensi harus ditanggulangi sesegera mungkin dalam satu jam dengan memberikan obat-obatan anti hipertensi intravena. 2. Hipertensi urgensi (mendesak) Peningkatan tekanan darah seperti pada hipertensi emergensi namun tanpa disertai kerusakan organ target. Pada keadaan ini tekanan darah harus segera diturunkan dalam 24 jam dengan memberikan obat-obatan anti hipertensi oral. Dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan hipertensi krisis antara lain: 1. Hipertensi refrakter Respon pengobatan yang tidak memuaskan dan tekanan darah > 200/110 mmHg, walaupun telah diberikan pengobatan yang efektif (triple drug) pada penderita dan kepatuhan pasien. 2. Hipertensi akselerasi Peningkatan tekanan darah diastolik > 120 mmHg disertai dengan kelainan funduskopi. Bila tidak diobati dapat berlanjut ke fase maligna. 3. Hipertensi maligna Penderita hipertensi akselerasi dengan tekanan darah diastolik > 120-130 mmHg dan kelainan funduskopi disertai papil edema, peninggian tekanan intrakranial, kerusakan yang cepat dari vaskular, gagal ginjal akut, ataupun kematian bila penderita tidak mendapatkan pengobatan. Hipertensi maligna biasanya pada penderita dengan riwayat hipertensi esensial ataupun sekunder dan jarang pada penderita yang sebelumnya mempunyai tekanan darah normal. 4. Hipertensi ensefalopati Kenaikan tekanan darah dengan tiba-tiba disertai dengan keluhan sakit kepala yang hebat, penurunan kesadaran dan keadaan ini dapat menjadi reversibel bila tekanan darah tersebut diturunkan. Etiologi dan Patofisiologi Faktor penyebab hipertensi intinya terdapat perubahan vascular, berupa disfungsi endotel, remodeling, dan arterial striffness. Namun faktor penyebab hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi masih belum dipahami. Diduga karena terjadinya peningkatan tekanan darah secara cepat disertai peningkatan resistensi vaskular. Peningkatan tekanan darah yang mendadak ini akan menyebabkan jejas endotel dan nekrosis fibrinoid arteriol sehingga membuat kerusakan vaskular, deposisi platelet, fibrin dan kerusakan fungsi autoregulasi. Tabel 2.Penyebab hipertensi emergensi Essential Hypertension Penyakit Ginjal Penyakit parenkim Ginjal Pielonefritis kronik Glomerulonefritis Vaskular/kelainan pada glomerulus Sistemeik lupus eritematosus Sistemik sclerosis Vaskulitis ginjal (makroskopik poliarteritis nodusa, Wegener‘s granulomatosis) Nefritis tubulointersisial Penyakit vascular pada ginja; Stenosis arteri ginjal Fibromuskular displasis Penyakit Arteriosklerosis renovaskular Makroskopik poliarteritis nodusa Obat-obatan Abrupt withdrawal of a centrally acting α2-adrenergic agonist (clonidine methyldopa) Phencyclidine, cocacine or other sympathomimetic drug intoxication Interaction with monoamine oxidase inhibitors Kehamilan Eklamsi/pre-eklamsi berat Endokrin Pheochromocytoma Primary aldosteronisme Glucocorticoid excess Renin-secreting tumors Kelainan Sistem Syaraf Pusat CVA infarction/haemorrhage Cedera kepala Gambar 1. Patofisiologi hipertensi emergensi. Mekanisme Autoregulasi Autoregulasi merupakan penyesuaian fisiologis organ tubuh terhadap kebutuhan dan pasokan darah dengan mengadakan perubahan pada resistensi terhadap aliran darah dengan berbagai tingkatan perubahan kontraksi/dilatasi pembuluh darah. Bila tekanan darah turun maka akan terjadi vasodilatasi dan jika tekanan darah naik akan terjadi vasokonstriksi. Pada individu normotensi, aliran darah otak masih tetap pada fluktuasi Mean Atrial Pressure (MAP) 60-70 mmHg. Bila MAP turun di bawah batas autoregulasi, maka otak akan mengeluarkan oksigen lebih banyak dari darah untuk kompensasi dari aliran darah yang menurun. Bila mekanisme ini gagal, maka akan terjadi iskemia otak dengan manifestasi klinik seperti mual, menguap, pingsan dan sinkop. Pada penderita hipertensi kronis, penyakit serebrovaskuar dan usia tua, batas ambang autoregulasi ini akan berubah dan bergeser ke kanan pada kurva,sehingga pengurangan aliran darah dapat terjadi pada tekanan darah yang lebih tinggi (lihat gambar 2). Gambar 2. Kurva autoregulasi tekanan darah. Pada penelitian Stragard, dilakukan pemgukuran MAP pada penderita hipertensi dengan yang nor- motensi. Didapatkan penderita hipertensi dengan pengobatan mempunyai nilai diantara grup normotensi dan hipertensi tanpa pengobatan. Orang dengan hipertensi terkontrol cenderung meng- geser autoregulasi ke arah normal. Dari penelitian didapatkan bahwa baik orang yang normotensi maupun hipertensi, diperkirakan bahwa batas terendah dari autoregulasi otak adalah kira-kira 25% di bawah resting MAP. Oleh karena itu dalam pengobatan hipertensi krisis, penurunan MAP sebanyak 20%-25% dalam beberapa menit atau jam,tergantung dari apakah emergensi atau urgensi. Penurunan tekanan darah pada penderita diseksi aorta akut ataupun edema paru akibat payah jantung kiri dilakukan dalam tempo 15-30 menit dan bisa lebih cepat lagi dibandingkan hipertensi emergensi lainya. Penderita hipertensi ensefalopati, penurunan tekanan darah 25% dalam 2-3 jam. Untuk pasien dengan infark serebri akut atau- pun perdarahan intrakranial, penurunan tekanan darah dilakukan lebih lambat (6-12 jam) dan harus dijaga agar tekanan darah tidak lebih rendah dari 170-180/100 mmHg. Manifestasi Klinis Manifestasi klinis hipertensi krisis berhubungan dengan kerusakan organ target yang ada. Tanda dan gejala hipertensi krisis berbeda-beda setiap pasien. Pada pasien dengan hipertensi krisis de- ngan perdarahan intrakranial akan dijumpai keluhan sakit kepala, penurunan tingkat kesadaran dan tanda neurologi fokal berupa hemiparesis atau paresis nervus cranialis. Pada hipertensi ensefalopati didapatkan penurunan kesadaran dan atau defisit neurologi fokal. Pada pemeriksaan fisik pasien bisa saja ditemukan retinopati dengan perubahan arteriola, perdara- han dan eksudasi maupun papiledema. Pada sebagian pasien yang lain manifestasi kardiovaskular bisa saja muncul lebih dominan seperti; angina, akut miokardial infark atau gagal jantung kiri akut. Dan beberapa pasien yang lain gagal ginjal akut dengan oligouria dan atau hematuria bisa saja terjadi. Gambar 3. Papiledema. Perhatikan adanya pembengkakan dari optik disc dengan margin kabur. Tabel 3. Hipertensi emergensi (darurat) Hipertensi berat dengan tekanan darah > 180/120 mmHg disertai dengan satu atau lebih kondisi akut berikut : 1. Perdarahan intra kranial atau perdarahan subarakhnoid 2. Hipertensi ensefalopati 3. Diseksi aorta akut 4. Edema paru akut 5. Eklampsia 6. Feokromositoma 7. Funduskopi KW III atau IV 8. Insuffisiensi ginjal akut 9. Infark miokard akut 10. Sindrom kelebihan katekolamin yang lain : sindrom withdrawal atau obat ant ihipertensi Hipertensi Urgensi (mendesak). Hipertensi berat dengan tekanan darah > 180/120 mmHg, tetapi dengan minimal atau tanpa kerusakan organ sasaran dan tidak dijumpai keadaan pada tabel 3. : 1. Funduskopi KW 1 atau KW 2 2. Hipertensi post operasi 3. Hipertensi tak terkontrol/tanpa diobati pada perioperatif Pendekatan Diagnosis Kemampuan dalam mendiagnosis hipertensi emergensi dan urgensi harus dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pasien. Anamnesis tentang riwayat penyakit hipertensinya, obat-obatan anti hipertensi yang rutin diminum, kepatuhan minum obat, riwayat konsumsi kokain, amphetamine dan phencyclidine. Riwayat penyakit yang menyertai dan penyakit kardiovaskular atau ginjal penting dievaluasi. Tanda-tanda defisit neurologik harus diperiksa seperti sakit kepala,penurunan kesadaran, hemiparesis dan kejang. Gambar 4. Alur Pendekatan Diagnosis pada Pasien Hipertensi. Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan seperti hitung jenis, elektrolit, kreatinin dan urinalisa. Foto thorax, E K G d a n C T s c a n kepala sangat penting diperiksa untuk pasien-pasien dengan sesak nafas, nyeri dada atau perubahan status neurologis. Pada keadaan gagal jantung kiri dan hipertrofi ventrikel kiri pemeriksaan ekokardiografi perlu dilakukan. Berikut adalah bagan alur pendekatan diagnostik pada pasien hipertensi: Kesimpulan Hipertensi krisis merupakan salah satu kegawatan di bidang neuro-cardiovaskular yang sering dijumpai di instalasi gawat darurat. Hipertensi krisis terdiri dari hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Keduanya harus ditangani dengan tepat dan segera sehingga prognosisnya terhadap organ target (otak, ginjal dan jantung) dan sistemik dapat ditanggulangi. Daftar Pustaka 1. Rampengan SH. Krisis Hipertensi. Hipertensi Emergensi dan Hipertensi- Urgensi. BIKBiomed. 2007. Vol.3, No.4 :163-8. 2. Saguner AM, Dur S, Perrig M, Schiemann U, Stuck AE, et al. Risk Factors Promoting Hypertensive Crises: Evidence From a LongitudinalStudy. Am J Hypertensi. 2010. 23:775-780. 3. Kaplan NM. Primary hypertension. In: Clinical Hypertension. 9 ed. Lippincott Williams &Wilkins; 2006: 50-104. 4. Varon J, Marik PE. Clinical Review: The Management of Hypertensive crises. Critical CareJournals. 2003. 5. Immink RV, Born BH, Montfrans GA, Koopmans RP, Karemaker JM, et al. ImpairedCerebral Autoregulation in Pasient with Malignant Hypertension. Journal of the AmericanHeart Association. 2004. 110:2241-2245. 6. Thomas L. Managing Hypertensive Emergency in the ED. Can FamPhysician. 2011.57:1137-41. 7. Manning L, Robinson T.G, and Anderson C.S. Control of Blood Pressure in Hypertensive Neurological Emergencies.Curr Hypertens Rep .2014. 16:436. 8. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA; 2003;289: 2560–72. Makalah Bebas PROBLEM DIAGNOSTIK ASITES PADA CA COLON Arie Setyawan*, Azzaki Abubakar**, Fauzi Yusuf** *PPDS Ilmu Penyakit Dalam **Divisi Gastro Entero Hepatologi Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Abstrak Pendahuluan Asites merupakan akumulasi patologis dari cairan dalam cavum peritoneal dan tanda suatu prognosis yang kurang baik pada beberapa penyakit. Asites juga menyebabkan pengelolaan penyakit dasarnya menjadi semakin kompleks. Infeksi pada cairan asites akan lebih memperberat perjalanan penyakit dasarnya. Asites dapat disebabkan oleh beberapa kejadian diantaranya malignansi, penyakit hati kronis dengan hipertensi portal, gagal ginjal kongestif dan tuberkulosis. Salah satu penyebab asites tersering non sirotik dapat disebabkan oleh karsinoma. Kasus Seorang perempuan 69 tahun dengan problem diagnostik awal asites. Pasien datang dengan keluhan perut membesar sejak 1 bulan terakhir. Pemeriksaan USG didapatkan Asites non sirotik, dari hasil kolonoskopi tampak massa di caecum curiga carsinoma caecum dan polip caecum. Hasil CT-Scan Abdomen tampak Asites dengan multiple lesi hypodens dilobus kanan hepar dan efusi pleura bilateral. Hasil patologi anatomi post laparotomi eksplorasi adalah mucoid adenocarcinoma colon dengan metastase ovarium. Diskusi Asites merupakan akumulasi patologis dari cairan dalam cavum peritoneal. Asites dapat disebabkan oleh beberapa kejadian diantaranya malignansi, salah satu penyebab asites tersering non cirotik dapat disebabkan oleh karsinoma. Pemeriksaan USG didapatkan Asites non sirotik, dari hasil kolonoskopi tampak massa di caecum curiga carsinoma caecum dan polip caecum. Hasil CT-Scan Abdomen tampak Asites dengan multiple lesi hypodens dilobus kanan hepar dan efusi pleura bilateral. Pasien dilakukan tindakan operasi laparotomi eksplorasi dengan diagnosa atas indikasi Tumor caecum et hemorrhoid externa. Hasil biopsi patologi anatomi adalah mucoid adenocarcinoma colon dengan metastase ovarium. Kesimpulan Kasus ini dibawakan karena keberhasilan diagnostik dalam menegakkan diagnosa pasti terhadap pasien, sebelum pasien meninggal dengan permasalahan ketidaksesuaian klinis dengan hasil pemeriksaan penunjang, serta menentukan tindak lanjut penatalaksanaan dan pilihan regimen kemoterapi terhadap pasien. Keywords : Asites, Adenocarcinoma Colon, Kemoterapi KISTA DUKTUS KOLEDOKUS PADA DEWASA MUDA Chairunnisa*, M.Fuad** *PPDS Ilmu Penyakit Dalam * Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala / RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh Abstrak Pendahuluan Kista duktus koledokus adalah dilatasi kistik dari saluran empedu baik intrahepatik maupun ekstrahepatik. Adanya dilatasi yang mengganggu aliran empedu ekstrahepatik, aliran empedu intrahepatik, maupun keduanya nantinya akan menyebabkan obstruksi saluran empedu dan bahkan duodenum. Dilatasi paling sering terjadi pada duktus koledokus (common bile duct), tapi dilatasi saluran empedu intra hepatik saja atau berkombinasi dengan abnormalitas saluran ekstrahepatik juga mulai banyak ditemukan. Kasus Pasien seorang wanita umur 24 tahun datang dengan keluhan kuning seluruh badan yang dialami sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Kuning kedua mata dan kemudian seluruh tubuh. Pada pemeriksaan fisik didapati conjungtiva palpebra inferior pucat, sklera ikterik, massa di epigastrium, konsistensi keras, permukaan rata dan tepi tumpul, lien tidak teraba. Terapi drainase kista duktus koledokus. Diskusi Kista duktus koledokus adalah dilatasi kistik dari saluran empedu baik intrahepatik maupun ekstra hepatik. Kista koledokus dijumpai nyeri pada regio hipokondrium kanan atas. Komplikasi kolelitiasis, hipertensi portal dan biliary ascites. Prognosis setelah eksisi kista adalah baik. Kesimpulan Telah dilaporkan seorang wanita muda usia 24 tahun, dengan keluhan utama nyeri perut bagian atas kanan sejak 2 bulan SMRS dan didiagnosa menderita kista duktus koledokus. Pada pemeriksaan fisik didapati conjungtiva anemis, ikterik, abdomen dilakukan pemeriksaan hepar dan lien tidak teraba, penderita di rawat di bagian Penyakit Dalam rawat bersama dengan divisi gastroenterologi. Hasil CT-Scan adalah suspect kista di ductus koledokus dan intrahepatik dengan disertai obstruktif system bilier intrahepatik. Hasil Ultrasonografi dijumpai kista duktus koledokus intrahepatik dengan obstruksi sistem bilier intrahepatik, dilakukan tindakan exisi kista. Kasus ini dimajukan karena merupakan suatu kasus yang jarang dijumpai pada dewasa muda . Keyword : Kista duktus koledokus, duktus intrahepatik, duktus ekstrahepatik FIBROSARKOMA GINJAL PADA WANITA DEWASA Cut Henna Mariza*, M.Fuad**, M.Riswan** *PPDS Ilmu Penyakit Dalam **Divisi Hematologi dan Onkologi Medik, Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Rumah sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh Abstrak Pendahuluan Fibrosarcoma infantile dikenal sebagai Mesoblastic nefroma (MN) juga dikenal sebagai fetal mesenchymal hamartoma atau leiomyomatous hamartoma, biasanya dijumpai bayi. Fibrosarcoma (MN). Pada dewasa, tumor ini sangat jarang terjadi. Berdasarkan literatur, hanya 23 kasus fibrosarkoma pada dewasa yang dilaporkan sampai tahun 1999 dan 38 kasus yang telah dilaporkan sampai tahun 2007. Kasus Dilaporkan wanita 39 tahun, dengan benjolan diperut kanan sejak 1 bulan disertai mual, muntah, perut terasa kembung serta nyeri tulang belakang. Penurunan berat badan > 4 Kg selama 4 bulan, Telah menjalani operasi pengangkatan ginjal kanan, dengan hasil suatu mesoblastic nephroma (infantile fibrosarcoma). CT-Scan abdomen dijumpai proses metastase hepar, paru, mediastinum, tulang dan mioma uteri, setelah dilakukan kemoterapi siklus kedua, pasien mengalami Gagal Ginjal Kronik dan dilakukan hemodialisa. Diskusi Fibrosarkoma dapat terjadi akibat pengaruh paparan radiasi dari lingkungan yang mengakibatkan terjadinya translokasi kromosom pada sekitar 90% kasus. x-radiation dan gamma radiation paling berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Ionisasi radiasi menyebabkan terjadinya perubahan genetik yang meliputi mutasi gen, mutasi mini-satellit, formasi mikronukleus, aberasi kromosomal, perubahan ploidi, DNA stand breaks dan instabilitas kromosom. Ionisasi radiasi mempengaruhi semua fase dalam siklus sel, namun fase G 2 merupakan yang paling sensitif. Kesimpulan Prognosis suatu kasus fibrosarcoma ginjal pada dewasa adalah baik, setelah dilakukan operasi pengangkatan seluruh tumor, namun kekambuhan lokal dapat terjadi yang disebabkan oleh operasi pengangkatan tumor yang inkomplit. Kekambuhan lokal dengan metastase ke hati telah dilaporkan 21 tahun setelah operasi pengangkatan ginjal dan juga kekambuhan tumor diketahui 2 tahun setelah reseksi tumor. Kata kunci : Fibrosarkoma, Gagal Ginjal Kronik, Hemodialisa. PLEBOTOMI SEBAGAI TERAPI PILIHAN PADA POLISITEMIA VERA Cut Herlinda TA*, M. Fuad**, M. Riswan** *PPDS Ilmu Penyakit Dalam **Divisi Hematologi dan Onkologi Medik Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/ Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh Abstrak Pendahuluan Polisitemia vera adalah suatu keganasan derajat rendah sel-sel induk hematopoitik dengan karakteristik peningkatan jumlah eritrosit absolut dan volume darah total, biasanya disertai dengan lekositosis, trombositosis dan splenomegali. Polisitemia vera dapat mengenai semua umur, sering pada pasien berumur 40-60 tahun, dengan perbandingan antara pria dan wanita 2:1, di Amerika Serikat angka kejadiannya ialah 2,3 per 100.000 penduduk dalam setahun. Plebotomi merupakan pengobatan yang adekuat bagi pasien polisitemia selama bertahun-tahun dan merupakan pengobatan yang dianjurkan. Kasus Dilaporkan kasus seorang wanita 58 tahun dengan perdarahan melalui hidung atau mimisan 2-3 kali perhari, berlangsung selama sekitar 3 menit setiap mimisan dengan jumlah 10-15 cc, disertai nyeri kepala, mata memerah dan pandangan kabur, mudah lelah dan kedua kaki terasa panas. Laboratorium ditemukan trombositosis, leukositosis, peningkatan hemoglobin dan hematokrit. Diskusi Suatu penelitian sitogenetika menunjukkan adanya kariotipe abnormal di sel induk hemopoisis pada pasien dengan polisitemia vera. Klasifikasi eritrositosis tergantung dengan volume sel darah merah dalam menegakkan diagnosis, karena gambaran klinis yang hampir sama. International Polycythemia Vera Study Group ke 2 dan menurut kriteria WHO. Pada Polisitemia Vera tujuan plebotomi adalah mempertahankan hematokrit ≤ 45%, untuk mencegah timbulnya hiperviskositas dan penurunan shear rate. Manfaat plebotomi disamping menurunkan sel darah merah juga menurunkan viskositas darah kembali normal sehingga resiko timbulnya trombosis berkurang Kesimpulan Diagnosis ditegakkan oleh 2 kriteria mayor , 1 kriteria minor. Setelah di lakukan tindakan plebotomi 2 ( dua ) kali sebanyak 600cc , pasien mengalami perbaikan gejala klinis dan pasien diperbolehkan pulang berobat jalan . Key word : Polisemia Vera, Plebotomi, Hemoglobin A CASE OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN PREGNANT WOMAN 34 WEEKS GESTATIONAL AGE *Imam Zahari, **Cut Meurah Yeni * Fetomaternal division Syiah Kuala Hospital, Banda aceh - Indonesia ** Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine University of Syiah Kuala Abstract Dengue hemorrhagic fever is a global problem of tropical disease, especially in Indonesia. In recent times, the incidence has been increasing among adults and more cases of dengue fever and dengue hemorrhagic fever in pregnancy are being reported. We managed one case of dengue hemorrhagic fever during pregnancy which developed during antepartum periods. Patient complained contraction and bloodslym since 8 hours before admission without waterbroke, patient went to midwife, and then referred to RSCM, due to no facilities (no NICU). No history of cavities. Patient had history of preterm labor in previous pregnancy. This case was treated conservatively. Two days after lung maturation in the ward patient complained fever. We diagnosed dengue hemorrhagic fever during pregnancy with clinical pictures of fever, hemoconcentration and thrombocytopenia with serological proof, and positive in rumple leed test result. We decided to perform emergency C Section 5 days after admission. Patient and the baby were in good condition before discharged. A sound knowledge of its diagnosis and management plays a vital role for an obstetrician, particularly regarding the mode of delivery. Supportive care with analgesics, bed rest, adequate fluid replacement and maintenance of electrolyte balance forms the main stay of treatment. Discussion We have presented cases of Dengue hemorrhagic fever seen during the antepartum periods. The clinical picture is as same as for non pregnant patients. Antepartum management should be conservative. To our knowledge, there is no report that the Dengue virus can cause congenital anomalies, spontaneous abortion, premature labour or fetal death. The patients should be admitted to a hospital for close observation. Intravenous fluid replacement should be given if indicated. In this case, the patient was referred to RSCM for preparation of NICU for preterm birth. It is uncertain whether the Dengue Virus can cause thrombocytopenia in neonate as seen in idiophatic thrombocytopenic purpura. Therefore, the treatments should be conservative, symptomatic and carried on through stage of shock. The critical periode (stage of shock) usually passed within 24 to 48 hours. If delivery is inevitable, the vaginal route is preferable to the abdominal route. Uterine contractions after delivery will strangulate the blood vessels that were torn during parturition and cause hemostasis even though coagulation defects are still ongoing. However, when cesarean section is unavoidable, platelet concentrates should be given intraoperatively or post operatively as necessary. The route of delivery should be given intraoperatively or post operatively as necessary. The route of delivery should be considered under obstetric indication. Tocolytic drugs may be considered until the patient recovers from the stage of shock and the platelet count returns to a normal level. Nevertheles, most of tocolysis can cause tachycardia whic may obscure the patient status. Magnesium sulfate might be a drug of choice in this situation because of it doesnt cause tachycardia. In this case, the platelet count was reduced from 222,000 to 120,000 from the admission to the sixth day. So, we decided to terminate the pregnancy by C section. The average incubation period of dengue fever is estimated to be about 7 days. Dengue infection in the neonate has been reported in many studies. All babies were asymptomatic at birth except one who had fever and was found to be dengue negative. Dengue serology was not performed on normal babies and hence no comment could be made on vertical transmission. However, studies conducted in India, Thailand and Colombia failed to find evidence of vertical transmission among their study subjects. Keywords: Dengue hemorrhagic fever, pregnancy Reference 1. Narayana Swamy M1, Pooja Patil, T Sruthi IOSR Journal of Dental and Medical Sciences IOSR-JDMS e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861. Volume 13, Issue 2 Ver. I. Feb. 2014, PP 71-73 2. Pouliot SH, Xiong X, Harville E, Paz-Soldan V, Tomashek KM. Maternal dengue and pregnancy outcomes: a systematicreview. ObstetGynecolSurv 2010;65: 107–118. 3. Adam I, Jumaa AM, Elbashir HM, Karsany MS. Maternal and perinatal outcomes of dengue in PortSudan, Eastern Sudan. Virol J 2010;7: 153. 4. Deen JL, Harris E, Wills B, Balmaseda A, Hammond SN, Rocha C et al. The WHO dengue classification and case definitions: time for a reassessment. Lancet 2011;368: a. 170-3. 5. Suvit B, Somchai T, NimitT. Dengue Hemorragic fever during pregnancy: antepartum, intrapartum and postpartum management j.Obstet. Gynacol. Res. Vol. 23, No.5:445-448 2012 6. Dengue fever. Yellow book traveller‘s Health. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; c2008. 7. Chye JK, Lim CT, Ng KB, Lim JM, George R, Lam SK. Vertical transmission of dengue. Clin Infect Dis 2007; 25: P. 1374–7. PERIKARDIOSINTESIS PADA EFUSI PERIKARDIUM MASIF Indah Fajarini*, Azhari Gani**, M. Diah** *PPDS Ilmu Penyakit Dalam **Divisi Kardiologi Bagian/ SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala RSUD dr. Zainoel Abidin Banda aceh Abstrak Pendahuluan Perikardium terdiri dari perikardium viseralis yang melekat ke miokardium dan perikardium parietalis yang terdiri dari jaringan elastis dan kolagen serta vili-vili penghasil cairan perkardium dan membungkus perikardium. Efusi perikardium merupakan hasil perjalanan klinis dari suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi, keganasan maupun trauma. Cairan tersebut dapat berupa transudat, eksudat, pioperikardium, atau hemoperikardium. Efusi perikardium bisa akut atau kronis, dan lamanya perkembangan memiliki pengaruh besar terhadap gejala-gejala pasien.Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, laboratorium, EKG, radiologi, dan ekokardiografi . Pengobatan disesuaikan dengan etiologi, dengan mengatasi penyakit dasarnya (misalnya pemberian antibiotik, steroid). Jika terjadi tamponade, diperlukan drainase segera (perikardiosentesis). Kasus Pria, usia 20 tahun datang dengan keluhan sesak nafas sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Dari hasil anamnese, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya pasien didiagnosa dengan : Efusi perikardium masif dengan tanda-tanda tamponade. Berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, EKG, dan ekokardiografi dilakukan tindakan perikardiosentesis. Diskusi Efusi perikardium adalah penumpukan cairan abnormal dalam ruang perikardium. Cairan dapat berupa eksudat, pioperikardium, atau hemoperikardium. Efusi perikardium merupakan hasil perjalanan klinis dari suatu penyakit. Gejala efusi perikardial meliputi antara lain : nyeri dada, jantung berdebar-debar, batuk, sesak nafas, suara serak, kecemasan dan kebingungan. Kesimpulan Dengan diagnosa tepat dan penanganan yang cepat terhadap kasus ini dapat menolong hidup pasien. Keyword : Efusi Pericardium, Tamponade jantung, Perikardiosintesis Cerebral Salt Wasting Syndrome Pada Pasien Tumor Cerebellum Dextra Munawar Anwar Fuadi,* Muhammad Fuad,** Desi Salwani,*** Abdullah***,Maimun Syukri*** *Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam **DPJP Ruang PenyakitDalam Pria ***Divisi Ginjal Hipertensi Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam Universitas Syiah Kuala / RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Pendahuluan Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) adalah penyakit yang ditandai dengan poliuria, natriuresis, hipovolemia, hiponatremia dimana kondisi tersebut merupakan sekunder dari lesi patologis di otak baik berupa trauma,malignansi, maupun infeksi. Kasus Pasien laki-laki 58 tahun, dengan keluhan penurunan kesadaran. Kecurigaan awal hiponatremia pada Syndrome Iapropiate Anti Diuretic Hormone (SIADH). Dalam perjalanan klinis pasien di dapatkan gejala poliuria dan tumor di otak. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan ditemukan tumor Cerebellum Dextra, diagnosa berubah menjadi CSWS. Pasien dilakukan penatalaksanaan secara konservatif dengan terapi rehidrasi cairan dan mengalami perbaikan dalam hal kesadaran dan poliuria. Diskusi Kriteria untuk diagnosis CSWS adalah natrium serum normal atau rendah, osmolalitas serum normal atau rendah, osmolalitas urin normal atau rendah, peningkatan hematokrit,urea, Hipourisemia dan peningkatan natrium urin. Rehidrasi merupakan pengobatan utama pada CSWS. Kesimpulan Dilaporkan satu kasus seorang laki-laki 58 tahun dengan CSWS. Diagnosa pasien berdasarkan klinis, laboratorium dan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan. Kata kunci: Cerebral salt wasting syndrome, tumor Cerebellum, Hiponatremia KEHAMILAN DAN LUARAN PASIEN EKLAMSIA GRAVIDARUM DAN DEMAM BERDARAH DENGUE DENGAN MANIFESTASI GANGGUAN JANTUNG *Rizka Aditya, **Cut Meurah Yeni, ***Yuyun Lisnawati * Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ** Departemen Obstetri dan Ginekologi, Divisi Fetomaternal RSU dr.Zainoel Abidin *** Departemen Obstetri dan Ginekologi, Divisi Fetomaternal RSUP Persahabatan Pendahuluan Kumpulan secara klinis dan laboratorium pada preeklamsi dan demam berdarah dengue banyak kesamaan namun pada tatalaksana keduanya berbeda. 2, 6 Laporan Kasus Ny.25 tahun, gravida 1, rujukan dari RSUD tipe B dengan HELLP syndrome. Demam sejak 5 hari, naik turun, hanya minum obat penurun panas. Pemeriksaan fisik TD 170/100mmHg, bradikardi 42 x/menit, suhu 36.8°C, USG biometri sesuai kehamilan 33 minggu dengan taksiran berat janin 2000g, indeks cairan amnion 1cm, dan SDAU 2.52. CTG kategori III. Laboratorium Hb 15.4 g/dL, Ht 44%, trombositopenia 11.000/uL, PT dan aPTT menunjukkan no coagulation, D-dimer 6.507mg/dL, SGOT 1098 U/L dan SGPT 324 U/L, LDH 1652 U/L, asam urat 9.2mg/dL, serum Mg 10.37 mg/dL, kalsium 8.7 mg/dL, protein urin +2, Ig M dan Ig G anti-dengue positif. Pasien bradikardi simptomatik diterapi dengan sulfas atropine, transfusi trombosit konsentrat 10 unit. Dalam perawatan mengalami kejang tonik klonik selama 2 menit dan penurunan kesadaran (GCS E3M4V2), TD 150/100 mmHg, nadi 113x/menit serta mengalami hematemesis. Terminasi kehamilan perabdominal saat trombosit 24.000/uL, PT 0.9x, dan aPTT 0.9x dan dilakukan B-lynch. Pasca seksio sesaria perawatan di ICU, dengan ventilator selama 2 hari, kondisi perbaikan. Pasien mengalami bradikari kembali, EKG menggambarkan sinus bradikadi, foto thorax gambaran pneumoni tanpa kardiomegali. Echocardiografi normal. CT-scan kepala tanpa kontras tidak terdapat lesi patologis intrakranial. Pembahasan Infeksi virus dengue pada jantung dapat mengakibatkan abnormalitas sistem konduksi jantung yang bervariasi gangguan konduksi atrioventricular, supraventricular aritmia, dan miokarditis, perikarditis. Berbagai laporan kasus mengenai kondisi gangguan jantung pada infeksi dengue diantaranya oleh Wali yang melaporkan 70% dari 17 pasien dengan demam berdarah dengue/dengue syok sindrom berhasil melewati kondisi dimana terjadi vetrikular hipokinetik (EF 40%), Kabra terdapat 16.7% dari 54 anak-anak yang menderita demam berdarah dengue didapatkan penurunan penurunan fraksi ejeksi ventrikel kiri hingga <50%, dari Srilangka juga dilaporkan terdapat abnormalitas EKG pada 62.5% dari 120 penderita demam berdarah dengue. Laporan-laporan tersebut menggambarkan tidak sedikit terjadi komplikasi jantung pada penderita infeksi dengue. Termasuk bradikardi pada penderita demam berdarah dengue (Lateef 2007, Kularatne 2007, Phompran 2004)10. Bradikardi, takikardi, efusi pericardial, disfungsi diastolic adalah gejala yang paling umum terjadi. Pada pasien dengan gangguan jantung tersebut sering dapat ditemukan peningkatan CPK-MB yang diduga berasal dari destruksi sel miokardial oleh virus dngue (DENV). Infeksi DENV menyebabkan gangguan Ca2+ peningkatan kadar calcium dalam sitoplasma yang menjadi penyebab gangguan irama jantung serta berpengaruh pada fungsi kontraktilitas jantung.11,12 Perubahan kardiovaskular pada preeklamsi menyebabkan penurunan cardiac output sebagai akibat peningkatan risistensi perifer, sehingga pada echocardiografi sebaiknya diukur fungsi miokardial dan fungsi ejeksi vetrikel kiri. Kerusakan endotel dapat menyebabkan pula fokal nekrosis dan perdarahan miokardium yang dapat pula menggangu konduksi jantung. 5 Kesimpulan Manifestasi klinis akibat kerusakan endotel pada preeklamsi dan demam berdarah dengue pada kehamilan dapat mengenai seluruh tubuh, manifestasi kardiovaskular sering diabaikan, seperti gangguan konduksi hingga miokarditis. Pengaruh keduanya terhadap kehamilan mimiliki prognosis yang buruk dan merupakan penyebab salah kematian pada ibu hamil. Kata kunci : preeklamsi, eklamsi, HELLP sindrom, demam berdarah dengue Daftar Pustaka 1. Pooja C, Amrita Y, Viney C. Clinical implications and treatment of dengue. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2014:169-78. 2. Khamim K, Khamim B, Pengsaa K. Dengue Infection In Pregnancy. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015;46:153-60. 3. Robert JM, Bernstein IM, Druzin M, Gaiser RR, Granger JP, Jeyabalan A, et al. Hypertension in Pregnancy. The American Collage of Obstetricians and Gynecologists. 2013. 4. Magee LA, Pels A, Helewa M, Rey E, Dadelszen Pv. Diagnosis, Evaluation, and Management of the Hypertensive Disorders of Pregnancy: Executive Summary. SOGC. 2014;36(5):416-38. 5. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, al e. Williams Obstetrics. 24 ed. New York: Mc Graw Hill Education; 2014. 23-2900 p. 6. Pallavi, Sur K. Dengue: Management Guidelines. Journal of the Vivekananda Institute of Medical Sciences. 2012:37-43. 7. Prasittisuk C, Kalra NL, Dash AP. Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever. World Health Organization. 2011:1-195. 8. Paixão ES, Teixeira MG, Costa MdCN, Rodrigues LC. Dengue during pregnancy and adverse fetal outcomes: a systematic review and metaanalysis. Lancet Infect Dis. 2016;16:1-9. 9. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, Landon MB, Galan HL, Jauniaux ERM. Obstetrics: Normal And Problem Pregnancies, Sixth Edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2012. 10. Lee I-K, Lee W-H, Liu J-W, Yang KD. Acute myocarditis in dengue hemorrhagic fever: a case report and review of cardiac complications in dengue-affected patients. International Journal of Infectious Diseases. 2010;14:e919-22. 11. Salgado DM, Eltit JM, Mansfield K, Panqueba C, Castro D, Vega MR, et al. Heart and Skeletal Muscle Are Targets of Dengue Virus Infection. Pediatr Infect Dis J. 2010;29(3):238-4 12. Aneja VK, Kochar G, Bisht N. Unusual Manifestations Of Dengue Fever. Apollo Medicine.2010;7:69-76 HUBUNGAN GAMBARAN ELEKTROKARDIOGRAM DENGAN DERAJAT KEPARAHAN PENDERITA PENYAKT JANTUNG KORONER DI RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH Ruziqni Arihanim P1, Muhammad Ridwan2, Ratna Idayati3, Muhammad Diah Yusuf4, Taufik Suryadi5 1) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala; 2) Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/SMF Jantung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh; 3) Staf Pengajar Bagian Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala; 4) Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/SMF Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh; 5) Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/SMF Ilmu Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh ABSTRAK Penyakit Jantung Koroner merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang tetap berada pada urutan pertama sebagai penyebab kematian terbanyak pada penderitanya. Di RSUDZA Banda Aceh dari tahun 2012 hingga 2014, jumlah pasien PJK mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Penyakit ini dapat diperiksa dengan EKG dan kateter jantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gambaran EKG dengan derajat keparahan penderita PJK serta untuk mendapatkan pola gambaran EKG pada penderita PJK. Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan retrospektif. Penelitian dilakukan di ruangan rekam medik Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dari bulan Febuari 2015 hingga Januari 2016. Pengumpulan data rekam medik diambil dari 80 sampel yang menderita PJK dan memenuhi kriteria inklusi yang terdiri dari 65 laki-laki dan 15 perempuan. Pada penelitian ini diperoleh pola gambaran EKG yang paling banyak ditemukan adalah infark miokard lama sebanyak 37 orang (46,3%) dan hasil pemeriksaan kateter jantung menunjukan dominasi PJK derajat severe stenosis sebanyak 57 orang (71,3%). Analisis data menggunakan Uji Korelasi Spearman (p<0,05) terhadap gambaran EKG dan derajat keparahan PJK memperoleh nilai p 0,000 dimana nilai p lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara gambaran EKG dengan derajat keparahan PJK. Kata kunci : derajat PJK, EKG, infark miokard lama, kateter jantung, PJK HUBUNGAN FUNGSI SISTOLIK VENTRIKEL KIRI DENGAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN GAGAL JANTUNG DI RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH 2015 Sarah Fadillah1, Muhammad Ridwan2, Bakhtiar 3, Teuku Mamfaluti 4, Subhan Rio Pamungkas 5 1) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala; 2) Staf Pengajar Jantung Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh; 3) Staf Pengajar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh; 4) Staf Pengajar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh; 5) Staf Pengajar Ilmu Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh ABSTRAK Fungsi pemompaan jantung yang buruk pada keadaan gagal jantung mengakibatkan penurunan perfusi darah ke otak sehingga terjadi perubahan aliran darah serta kerusakan struktur otak. Perubahan tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi pada berbagai lobus otak, salah satunya ialah gangguan fungsi kognitif. Fungsi kognitif memiliki peran penting terhadap kualitas hidup, morbiditas dan mortalitas pasien gagal jantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fungsi sistolik ventrikel kiri dengan fungsi kognitif pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional menggunakan rancangan cross sectional. Sampel dipilih secara non-probability sampling terhadap pasien gagal jantung dewasa yang melakukan pemeriksaan ekokardiografi di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh mulai Desember 2015 sampai Januari 2016. Data yang dikumpulkan berupa nilai Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri (FEVK) dari hasil pemeriksaan Transthoracic Echocardiography (TTE) dan fungsi kognitif pasien dengan kuesioner Mini Mental State Examination (MMSE). Selama penelitian berlangsung, didapatkan sampel sebanyak 100 pasien yang terdiri dari 67 orang laki-laki dan 33 orang perempuan dengan rerata nilai FEVK ialah 58,82 dan rerata skor MMSE 24,48. Analisis data menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi bermakna antara fungsi sistolik ventrikel kiri dengan fungsi kognitif pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (p = 0,689) dengan kekuatan korelasi sangat lemah (r = 0,041). Kesimpulan penelitian adalah fungsi sistolik ventrikel kiri tidak mempengaruhi fungsi kognitif pada pasien gagal jantung. Kata Kunci: fungsi sistolik ventrikel kiri, fungsi kognitif, gagal jantung, fraksi ejeksi, Mini Mental State Examination. CARDIOVASCULAR DISEASE IN PREGNANCY: A CASE REPORT Teuku Yudhi Iqbal, Mohd. Andalas Department of Obstetric and Gynecology, University of Syiah Kuala, Zainoel Abidin Hospital ABSTRACT Cardiovascular diseases arise during 0,2% to 4% of all pregnancies, with Congenital Heart Disease (CHD) being the most common preexisting condition and hypertension the most common acquired condition. The presence of CVD in pregnant women posing a difficult clinical scenario in which the responsibility of the treating physician extends to the unborn fetus. The complexity of management these patients requires a multidisciplinary approach with the involvement of obstetricians, cardiologists, anesthesiologists and internist who are experienced in caring for these patients. We reported a 21 years old woman at term gestational age, referred to our hospital due to Cardiovascular disease suspected Eisenmenger‘s syndrome. Supportive care and expeditious delivery are essential to optimal maternal-fetal outcomes and remain as the mainstay treatment for CHD. Keyword: Cardiovascular disease, Cardiovascular disease in pregnancy, Congenital Heart Disease, Eisenmenger‘s Syndrom

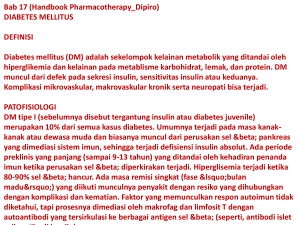
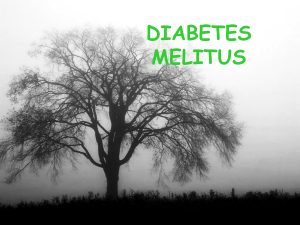
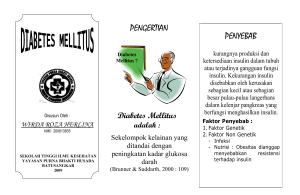
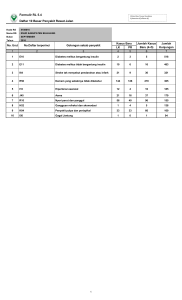
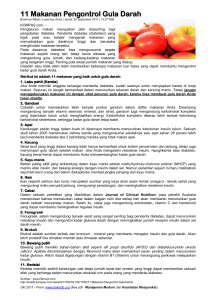
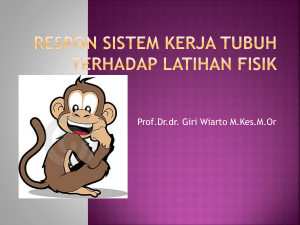
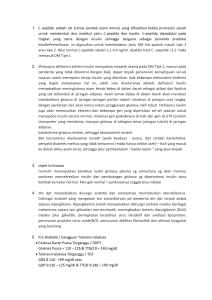
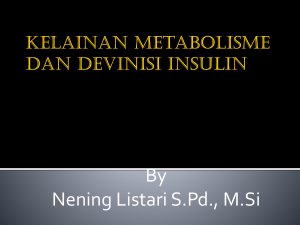

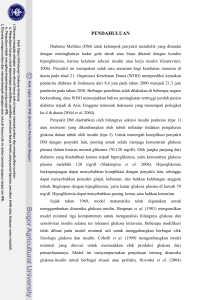
![[makalah] DIABETES MELITUS](http://s1.studylibid.com/store/data/000135979_1-e200463769db1b92b2940e32c68e2506-300x300.png)