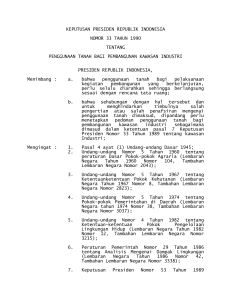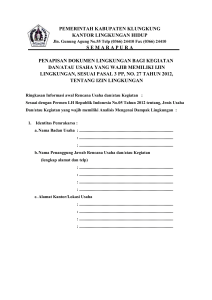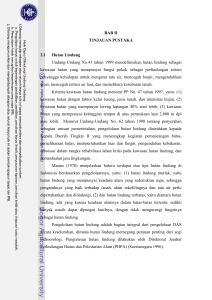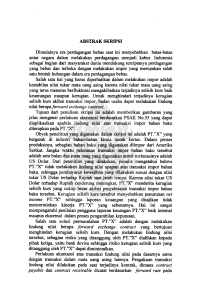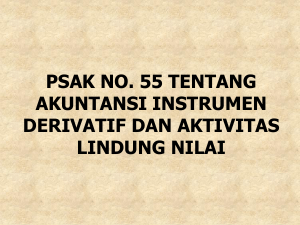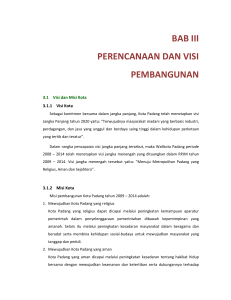A Case Study In Register 45b Bukit Rigis Protection
advertisement

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pertumbuhan penduduk demikian pesat berimplikasi terhadap deplesi sumberdaya alam. Semakin jumlah penduduk meningkat, semakin banyak kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi dan dapat bersumber dari sumberdaya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam yang ditempuh dengan berbagai kebijakan dan mengimplementasikannya ke dalam program pembangunan. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari masyarakatpun mengelola sumberdaya alam sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonominya. Satu di antara berbagai sumberdaya alam potensial yang masih menjadi sektor tumpuan masyarakat dan Pemerintah Indonesia saat ini adalah hutan. Dalam ekosistem hutan terdapat fungsi lingkungan yang mencakup fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis. Selain itu, ekosistem hutan amat penting tidak hanya bagi kehidupan manusia namun juga bagi kelangsungan flora dan fauna di dalamnya. Berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sesuai dengan U.U. tersebut, Pemerintah mengelola kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan lindung memiliki keterkaitan erat dengan fungsi lingkungan yang bersumber dari hutan. Fungsi lingkungan tersebut tercermin dari definisi hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dari definisi yang terdapat di dalam U.U. RI Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi lingkungan kawasan hutan lindung lebih ditekankan atas pertimbangan ekologis. Selain itu, dalam keterkaitannya dengan perubahan iklim global, hutan memiliki fungsi sebagai rosot karbon (Murdiyarso, dkk., 1998). Dalam mewujudkan fungsi lingkungan tersebut, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan hutan secara lestari. Kenyataannya adalah bahwa saat ini banyak kawasan hutan dengan kemampuan dalam menyediakan fungsi lingkungan yang semakin menurun. Hal 2 tersebut diantaranya disebabkan oleh salah penetapan kebijakan yang diikuti dengan salah pengelolaan. Masalah kebijakan pengelolaan kehutanan tidak terlepas dari masalah agraria dan penting untuk dibenahi dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Kebijakan tersebut ternyata terlalu kaku karena: (1) keliru dalam merumuskan masalah, (2) penyusunan kebijakan yang tidak partisipatif, (3) lemahnya sinkronisasi antara kebijakan dan implementasi di lapang, (4) lemahnya koordinasi lintas sektor, dan (5) lemahnya kemampuan aparatur. Selain itu, adanya cara pandang yang sempit para birokrat kehutanan yang memisahkan pembangunan kehutanan dengan pembangunan pertanian dan manusia menjadikan kebijakan pengelolaan hutan amat bersifat sektoral (Robinson. 1998). Akibatnya, produk kebijakan kehutanan gagal berfungsi (malfunction). Contoh produk kebijakan yang hingga kini masih belum menjadi dokumen publik dan lemah legitimasinya dalam mengatur pemanfaatan hutan adalah dokumen Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang seharusnya diharapkan dapat berfungsi menjadi dasar penetapan status dan perencanaan tataguna kawasan hutan negara. Selain masalah kebijakan, masalah sosial ekonomi seperti pertumbuhan penduduk dan kemiskinan ditengarai menjadi penyebab lainnya sehingga hutan semakin tidak mampu menyangga fungsi lingkungan. Adanya tekanan penduduk ke dalam kawasan hutan diduga telah mengakibatkan tidak terkendalinya konversi hutan ke dalam bentuk penggunaan lainnya seperti lahan pertanian, perladangan dan permukiman. Ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 utamanya hingga saat ini semakin mendorong pergerakan penduduk masuk ke dalam kawasan hutan untuk bertahan hidup. Masalah tersebut menjadi semakin rumit ketika wilayah-wilayah hutan yang mendapat tekanan adalah wilayah yang berstatus kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Terhadap masalah-masalah tersebut, pada dasarnya Pemerintah telah melakukan upaya penanganan yang diindikasikan oleh terjadinya perubahan orientasi kebijakan pembangunan kehutanan yaitu: (1) Pergeseran penekanan dari aspek ekonomi (orientasi pada laba/keuntungan) kepada suatu orientasi dengan penekanan keseimbangan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi hutan; (2) Pergeseran dari kebijakan dan pengembangan hutan dengan penekanan pada pengelolaan hasil kayu, kepada suatu orientasi dengan penekanan pada 3 pengelolaan hutan multiguna yaitu bahwa, selain kayu, hutan dapat memberikan keuntungan lain seperti pengaturan hidrologis, produk hutan non-kayu lainnya, rekreasi, dan pengaturan iklim mikro; dan (3) Memberikan penekanan pada pembangunan kehutanan berbasis masyarakat (Community Based Forestry) untuk memperkuat perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat setempat/lokal (Hutabarat, 2001). Selain itu, pemerintah amat menyadari bahwa pengelolaan hutan secara lestari sulit dicapai dengan baik tanpa partisipasi masyarakat setempat. Kebijakan dan orientasi kebijakan secara konkrit dituangkan ke dalam berbagai produk peraturan dan perundangan yang mengatur desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan. Diberikannya sejumlah kewenangan oleh Pemerintah kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota seperti adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan suatu contoh devolusi dan telah membentuk tatanan pemerintahan baru, termasuk dalam kebijakan dan pengaturan pengelolaan kehutanan. Selain itu, lahirnya kedua UU tersebut merupakan tanggapan terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan politik baik dari dalam negeri maupun dari masyarakat internasional (Hutabarat. 2001). Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, Pemerintah harus memberikan sebagian besar wewenangnya kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota, terutama dalam lingkup kegiatan operasional. Namun hingga tahun 2001, sebanyak 11 buah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)1 yang menindaklanjuti substansi UU Nomor 41 Tahun 1999 belum juga mendapat pengesahan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal tersebut menempatkan Pemerintah dalam posisi yang lemah karena: 1) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku efektif Mei 1999; oleh karena berbagai RPP pengelolaan kehutanan belum disahkan, banyak pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang bersentuhan dengan pengelolaan kehutanan dengan 1 RPP-RPP tersebut yaitu: 1) Perencanaan Kehutanan, 2) Pengelolaan hutan, 3) Hutan Kota, 4) Hutan Adat, 5) Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, serta Pelatihan dan Perluasan Hutan, 6) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Hutan, 7) Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan, 8) Perlindungan Hutan, 9) Pengawasan Hutan, dan 10) Hutan Kemasyarakatan, 11) Pengelolaan Dana Reboisasi (Sumber: Wawancara dengan Biro Hukum Departemen Kehutanan, 2002). Baru pada tahun 2002 telah dikeluarkan dua buah PP yaitu PP No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Dan PP No.35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. 4 interpretasinya sendiri terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 41 Tahun 1999; 2) Seringkali interpretasi tersebut melahirkan berbagai perbedaan visi, misi, dan konsep strategis antar-tataran pemerintah sehingga menimbulkan berbagai konflik; dan 3) Belum selesainya berbagai PP pengelolaan kehutanan yang mengatur lebih jauh tentang pelimpahan wewenang kepada masyarakat misalnya seperti hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan derajat partisipasi masyarakat, turut menjadi sumber konflik akibat adanya gugatan-gugatan masyarakat terhadap pengelolaan kehutanan (baik gugatan tentang status dan tataguna hutan) yang belum dapat atau lambat ditangani oleh Pemerintah. Kondisi Pemerintah bahkan semakin melemah ditambah oleh lunturnya kepercayaan masyarakat akibat memburuknya situasi sosial, ekonomi, dan politik serta kegagalan Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Penyelesaian konflik yang tertunda dapat menyebabkan terjadinya eskalasi konflik yang semula mungkin masih dalam taraf tidak ada dan/atau konflik laten akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Menurut Agustino (2001), dalam keadaan Pemerintah terkesan lemah dan lambat dalam menyelesaikan konflik, maka konflik tersebut akan berpotensi anarkis dan menjadi pencetus disintegrasi bangsa, apalagi Negara Indonesia dicirikan oleh masyarakatnya yang pluralis. Saat ini, konflik-konflik yang bersumber pada ketimpangan dan ketidak-adilan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk hutan, merupakan salah satu arena konflik yang frekuensinya relatif tinggi di samping konflik-konflik yang bersumber pada perbedaan ideologi politik golongan. 1.2. Perumusan Masalah Gelombang reformasi 1998 dilatarbelakangi antara lain masalah konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa. Masalah konflik tersebut diantaranya disebabkan oleh: (1) kekuasaan eksekutif yang terpusat di masa lalu (sebelum diberlakukannya UU No./1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah), dan; (2) mekanisme hubungan pusat-daerah yang cenderung menganut sentralisasi kekuasaan sehingga menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan. Seperti telah dinyatakan dalam Sub-bab 1.1, pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan merupakan salah satu arena konflik yang terjadi di 5 Indonesia; Dan hal tersebut kembali ditegaskan di dalam RPJMN 2005-2009 untuk rencana-rencana penyelesaian; Namun demikian di dalam RPJMN 20102014 pemerintah mengakui bahwa hal tersebut masih belum diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata dan mempengaruhi ketidakjelasan hak dan kewenangan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan lestari. Pasca tahun 2005, data statistik kasus konflik konflik sumberdaya alam sulit diperoleh, namun pada umumnya masih berkisar pada konflik-konflik laten berdasarkan data tahun 1999 yang belum selesai ditangani. Bahkan beberapa aksus baru muncul, seperti kasus Register 45A anata masyarakat dengan PT Inhutani di Kabupaten Tulang Bawang, Kasus penolakan koversi kawasan hutan lindung Rawa Pacing menjadi perkebunan sawit, kasus enclave Pengekahan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Bengkunat (tahun 2009) dan yang terkini (tahun 2011) adalah konflik kebijakan HTR-HKm-KDTI di yang keduanay berada di Kabupaten Lampung Barat. Konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan erat kaitannya dengan bagaimana sumberdaya tersebut bisa dimanfaatkan bagi pembangunan masyarakat dan bagaimana kemudian distribusi manfaat tersebut menyebar secara adil dan merata. Menurut Buckles (1999), terdapat empat penyebab timbulnya konflik pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan yaitu: (1) Adanya perbedaan akses antar aktor sosial dan/atau institusi terhadap pusat kekuasaan, yang memiliki akses biasanya menjadi yang paling mampu mengendalikan dan mempengaruhi keputusan pengelolaan sumberdaya alam menurut kehendaknya. Di dalam sentralisasi kekuasaan, aktor dan institusi di pusat biasanya yang paling berpengaruh karena kekuasaan berada di tangan mereka. (2) Aktifitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di suatu wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan di wilayah lainnya (atau sering disebut dengan istilah negative externalities); (3) Adanya peningkatan kelangkaan sumberdaya alam (natural resource scarcity) yang pertumbuhan disebabkan penduduk dan oleh terjadinya peningkatan perubahan permintaan, lingkungan, serta pola pendistribusian yang tidak merata; dan (4) Sumberdaya alam dipergunakan oleh manusia bukanlah semata-mata sebagai material yang diperebutkan, namun juga untuk mendefinisikan 6 hidupnya secara simbolis misalnya sebagai bagian dari cara hidup (petani, nelayan, penggembala), identitas etnis, perangkat gender, dan usia. Dimensidimensi simbolik sumberdaya alam tersebut membuat manusia menganut ideologi dan etik yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan penanganan konflik. Konflik pengelolaan kawasan hutan banyak terjadi di berbagai daerah termasuk Propinsi Lampung. Pada rentang waktu 1998–1999 jumlah konflik pertanahan di Propinsi Lampung yang muncul ke permukaan adalah 380 kasus termasuk konflik pertanahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan (Rencana Strategis Propinsi Lampung 2001-2005). Sebanyak 220 kasus muncul sepanjang Januari-September 1999 dan baru sebesar 20% telah diselesaikan baik melalui peradilan maupun di luar sistem peradilan dengan musyawarah dan mufakat (Gubernur Propinsi Lampung, 2000); sisanya belum ada penyelesaian dan bahkan cenderung semakin berlarut-larut. Hingga tahun 1999, terdapat sebanyak 43 kasus konflik pengelolaan kawasan hutan terjadi di Propinsi Lampung (Lampiran 1), sebuah contoh kasus diantaranya terjadi di Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis Kabupaten Lampung Barat. Konflik di kawasan tersebut dipicu oleh kegiatan masyarakat yang menggarap lahan di dalam kawasan menjadi lahan pertanian dan bahkan ada yang sudah tinggal secara permanen. Konflik di lokasi tersebut diduga telah melibatkan berbagai pihak dengan perbedaan kepentingannya masing-masing dan diduga berpengaruh terhadap fungsi lingkungan dari hutan. Penyebab konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis memiliki kemiripan dengan pernyataan Buckles (1999) tentang sebab-sebab konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam. Oleh karenanya penting untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab konflik dan apa saja akibat yang ditimbulkan terutama berkaitan dengan fungsi lingkungan dari hutan. Pertanyaan penelitian yang ingin diperoleh jawabannya dari konflik yang terjadi di lokasi adalah: 1) Dari perspektif kebijakan kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, agraria, tata ruang, dan otonomi daerah, bagaimanakah pelaksanaan penanganan konflik lingkungan dalam pengelolaan kehutanan di Propinsi Lampung khususnya di kawasan hutan lindung lokasi penelitian? a. Apakah kebijakan-kebijakan operasional? tersebut bisa berjalan secara 7 b. Apakah secara struktural kebijakan tersebut diselenggarakan secara konsisten di setiap tataran pemerintah? c. Adakah konflik yang ditimbulkan? d. Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut mampu memberi solusi untuk penanganan konflik? Ataukah sebaliknya justru mengeskalasi konflik? 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya konflik pengelolaan kawasan hutan di lokasi penelitian? 3) Bagaimanakah gaya konflik yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat konflik? Siapa sajakah pihak-pihak yang berkonflik? Apa tipe konflik yang terjadi dan bagaimana bentuk polarisasinya? 4) Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, bagaimanakah sebaiknya penanganan konflik yang berkaitan dengan pengendalian fungsi lingkungan dari hutan tersebut dilakukan/diputuskan? 1.3. Kerangka Pemikiran Pemecahan Masalah Kondisi krisis yang dihadapi oleh Indonesia saat ini sangat kompleks dan bersifat multi-dimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Kegagalan pembangunan di masa lalu sebagai akibat dari sentralisasi sistem pemerintahan dirasakan menjadi satu diantara penyebabpenyebab lainnya termasuk belum terselenggarakan sistem pemerintahan yang baik (good governance). Menghadapi hal tersebut, pemerintah secara bertahap melakukan langkah-langkah desentralisasi kewenangan berbagai sektor pembangunan. Langkah desentralisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kerangka kebijakan otonomi daerah. Hal tersebut diantaranya didukung oleh upaya desentralisasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk sumberdaya hutan. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan, desentralisasi juga menyentuh pengelolaan kawasan hutan lindung. Secara umum, hutan memiliki fungsi lingkungan yang meliputi fungsi ekonomis, fungsi sosial, fungsi ekologis, dan bahkan politis. Demikian pula halnya dengan fungsi lingkungan dari kawasan hutan lindung. U.U. Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Seiring dengan 8 perubahan orientasi pembangunan kehutanan yang telah diuraikan sebelumnya dalam Sub-bab 1.1, pemerintah sedang berupaya mengembangkan sistem pengelolaan hutan dengan pendekatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), termasuk dalam pengelolaan kawasan hutan lindung, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungannya. Permasalahannya, dari berbagai kasus di lapang, pengelolaan kawasan hutan tersebut sering tidak sesuai dengan fungsi lingkungan (dalam arti luas) yang justru menjadi permintaan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat lokal2, khususnya masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dan hidupnya pada kawasan hutan. Tidak jarang ketidak-sesuaian tersebut menimbulkan berbagai konflik baik konflik land tenure (status dan kepemilikan lahan) maupun konflik akses pengelolaan lahan. Konflik status dan kepemilikan lahan serta akses pengelolaan merupakan konflik lingkungan yang sering terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. Proses penunjukkan dan penetapan status dan tataguna kawasan hutan tersebut yang diikuti dengan konstruksi tata batas dan zonasi kawasan, seringkali dilakukan secara “sepihak” oleh pemerintah tanpa memperhatikan interaksi yang terjadi antara komunitas masyarakat lokal dengan sumberdaya alam yang tersedia di dalam kawasan. Prosesnya cenderung dilakukan tanpa menyertakan partisipasi masyarakat terutama mereka yang telah tinggal menetap antar generasi di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang memiliki kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesamaan sejarah demografi, keterikatan tempat tinggal, serta nilai-nilai kehidupan sosial. Di tingkat lapang, konflik tersebut seringkali ditangani oleh pemerintah melalui pendekatan represif berdasarkan peraturan/perundangan yang “berlaku” dan blueprint tanpa memperhatikan akar masalah yang menyebabkan mengapa masyarakat melakukan gugatan. Tidak jarang, pendekatan represif yang dilakukan tersebut justru malah menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial yang tidak diharapkan. Gugatan status dan kepemilikan lahan dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat atas lahan misalnya, merupakan suatu bentuk perjuangan identitas diri atau simbol sosial dari 2 Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, masyarakat setempat (lokal) adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama. 9 komunitas adat berkaitan. Sedangkan gugatan serupa yang datangnya dari masyarakat pendatang yang telah lama menetap, merupakan akibat dari “ketidak-benaran atau pemutarbalikkan” sejarah status dan kepemilikan lahan sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan negara. Lemahnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik status kepemilikan dan akses pengelolaan lahan kawasan hutan cenderung berpotensi menyulut konflik-konflik lingkungan lainnya. “Pendudukan kembali” atas lahan gugatan yang dilakukan oleh komunitas tertentu biasanya cenderung diikuti oleh konversi lahan ke dalam bentuk penggunaan lain. Masalah lingkungan berikutnya akan timbul ketika konversi lahan tersebut menjadi suatu proses deforestasi tidak dapat balik (irreversible deforestation) yang menuju kepada degradasi hutan berikut fungsi lingkungannya dan berpengaruh negatif terhadap wilayah lainnya. Seperti telah dinyatakan pada Sub-bab 1.2, menurut Buckles (1999) terdapat empat kelompok masalah yang mempengaruhi terjadinya konflik pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan yaitu (1) eksternalitas negatif, (2) kelangkaan sumberdaya alam, (3) ketimpangan distribusi penguasaan sumberdaya alam, dan (4) perbedaan etik lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan penanganan konflik. Eksternalitas negatif terjadi karena sumberdaya alam tercakup (embedded) di dalam suatu lingkungan yang masing-masing komponennya saling berinteraksi sehingga aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di suatu wilayah dapat menimbulkan pengaruh dan dampak lingkungan di wilayah lainnya (Buckles, 1999). Eksternalitas negatif juga mencakup faktor eksternal yang mengakibatkan seseorang mengelola sumberdaya alam yang menurut pendapat umum dilakukan secara tidak lestari misalnya konversi lahan hutan. Dikaitkan dengan kondisi lapang di lokasi penelitian, beberapa peubah eksternalitas negatif yang diduga menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk mengkonversi lahan hutan adalah: (1) bencana alam antropogenik yang menimpa kegiatan pertanian di luar kawasan, (2) harga komoditas yang nantinya akan dibudidayakan di dalam kawasan, (3) informasi pasar yang berkaitan tentang kepastian harga komoditas, (4) pengaruh pasar yang berkaitan dengan kepastian akan aktor yang akan membeli/menampung komoditas yang dihasilkan, dan (5) ketersediaan sarana pendukung terutama jaringan transportasi ke bidang lahan yang dikonversi (lihat Sub-model A Gambar 1.1). 10 Sumberdaya alam merupakan salah satu sumber kehidupan manusia yang ketersediaannya tidak tak terbatas. Peningkatan pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan ketersediaan berbagai bahan pokok seperti produk primer sektor pertanian secara memadai. Di daerah perdesaan terutama di negara-negara berkembang yang memiliki ciri negara agraris, umumnya ketersedian lahan adalah faktor penentu dan merupakan salah satu natural capital yang penting bagi kelangsungan kegiatan pertanian. Oleh karenanya, kelangkaan sumberdaya lahan pertanian yang tersedia di perdesaan dapat memicu terjadinya tekanan penduduk terhadap lahan yang diikuti oleh konversi lahan non-pertanian yang relatif masih subur (dan umumnya lahan tersebut adalah lahan hutan) (Buckles, 1999). Kelangkaan tersebut termasuk kelangkaan status kepemilikan lahan. Dari berbagai kasus, konflik lingkungan akan semakin mudah mencuat apabila ada desakan ekonomi seperti rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga mendorong seseorang masuk ke dalam kawasan hutan diikuti dengan konversi lahan secara tak terkendali dan “ilegal” karena kawasan tersebut berdasarkan statusnya diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung. Di lokasi penelitian, peubah-peubah: (1) luas penguasaan lahan pertanian di luar kawasan, (2) status kepemilikan lahan pertanian di luar kawasan, dan (3) pendapatan rumah tangga diduga mempengaruhi persepsi responden bahwa kebutuhan lahan pertanian perlu ditingkatkan (Sub-model C Gambar 1.1). Konflik lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam terjadi karena sumberdaya alam tercakup di dalam suatu pembagian ruang sosial (shared social space) yang kompleks dan memiliki hubungan yang tidak merata yang terbangun oleh proses interaksi antar-aktor sosial sehingga terjadi ketimpangan distribusi penguasaan dan perbedaan akses (keterlibatan dan hak) individu dan/atau kelompok masyarakat dalam mengelola kawasan hutan (Buckles, 1999) sehingga menimbulkan ketimpangan struktural (Moore, 1996). Di dalam dimensi politik, aktor sosial yang memiliki akses terbesar ke pusat kekuasan biasanya menjadi yang paling mampu mengkontrol dan mempengaruhi keputusan pengelolaan sumberdaya alam3. Pada kondisi sebaliknya, aktor sosial yang jauh dari pusat kekuasaan biasanya cenderung menjadi komunitas 3 Contoh kasus di Sudan Utara, para tuan tanah yang umumnya memiliki status sosial seperti pengusaha, pegawai pemerintah, pensiunan jendral, dan politikus menggunakan “koneksinya” dalam memperoleh akses kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh pembukaan lahan di Pegunungan Nuba, Kordofan Selatan, dan bahkan sebaliknya, Pemerintah Sudan membantu mereka (secara diskriminatif) untuk memperoleh lahan yang terbaik (Buckles, 1999). 11 yang tersubordinasi dan lemah (powerless) (Fisher,S. 2001; Wijardjo, dkk. 2001; Fauzi, 2000; Borini dan Feyerabend, 2000; Robinson, 1998). Selain itu, mereka umumnya dicirikan sebagai kelompok masyarakat yang hampir tak pernah dilibatkan untuk berpartisipasi secara utuh dalam rangkaian proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengendalian pengelolaan sumberdaya alam (Borini dan Feyerabend, 2000; Merchant, 1992). Kelompok masyarakat tersebut umumnya adalah mereka bermukim di dalam dan/atau di sekitar hutan dan bahkan memiliki keterikatan sejarah dengan perubahan status kawasan hutan tersebut (Wijardjo, dkk. 2001). Kelompok tersebut pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang rendah serta lemah dalam pengetahuan terkini terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah spesifik yang belum terpecahkan misalnya konflik. Di lapang, ciri-ciri tersebut diduga terdapat pada kasus konflik yang diteliti. Berdasarkan kondisi yang ada, diduga tingkat ordinasi seseorang dipengaruhi oleh (1) tingkat partisipasi individu yang bersangkutan, (2) tingkat kesejahteraan sosial, dan (3) tingkat keberdayaan pengetahuan dalam penanganan konflik. (Lihat Sub-model B Gambar 1.1). Ketimpangan struktural juga dapat diindikasikan oleh frekuensi keterlibatan seseorang secara aktif dalam menegosiasikan kepentingannya (Kriesberg, 1998). Seseorang pesengketa cenderung akan terlibat secara aktif apabila yang bersangkutan memiliki pemahaman dan/atau persepsi4 yang baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan segala peluang baginya sehingga memiliki posisi tawar yang kuat. Pada saat ini, berkaitan dengan konflik lingkungan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung setidaknya diperlukan pemahaman tentang: (1) status kawasan hutan negara, (2) fungsi lingkungan suatu kawasan hutan, dan (3) desentralisasi pengelolaan kawasan hutan khususnya di Indonesia. Di lokasi penelitian ketiga faktor tersebut diduga mempengaruhi seseorang pesengketa untuk menegosiasikan kepentingannya. (Lihat Sub-model B Gambar 1.1). Di samping itu, ada faktor penting lainnya yaitu: (4) adanya tindakan represif dari pihak luar sehingga seseorang menjadi takut dan tidak mau bernegosiasi. Selain itu, konflik lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya hutan juga disebabkan oleh perbedaan persepsi para pihak dalam memandang fungsi hutan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Buckles (1999) bahwa konflik 12 pengelolaan sumberdaya alam disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi5 antara sumberdaya alam sebagai sumber material versus sebagai simbol sosial. Di lokasi penelitian, yang diduga menjadi penyebab konflik adalah perbedaan persepsi atas hal-hal yang berkaitan dengan fungsi lingkungan dari hutan, pemahaman tentang kebijakan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan, dan pemahanan tentang definisi status kawasan hutan. Pada kasus penelitian, peubah-peubah yang diduga menjadi penyebab perbedaan persepsi karena perbedaan karakteristik responden yaitu: (1) tingkat pendidikan, (2) lama tinggal di kawasan baik secara menetap atau tidak menetap, dan (3) kosmopolitansi seseorang dalam menerima pengetahuan dari luar. Tabel 1.1 Keterangan Gambar 1.1 Bagan Alir Kerangka Pemikiran Hubungan Pengaruh Model Faktor-faktor Yang Menimbulkan Konflik Lingkungan Sub-model A (Eksternalitas) BAA HK IF PP SP KKLK = = = = = = Bencana alam antropogenik (X1) Harga komoditi (X2) Informasi pasar (X3) Pengaruh Pasar (X4) Sarana pendukung (X5) Keputusan Konversi Lahan Kawasan Oleh Responden (X6) Sub Model B (Persepsi dan ketimpangan struktural) TKPR TKSS TKDR TKOR LTRP PKHN PFLH PDPK LPDN TPDR SKR KR = = = = = = = = = = = = Tingkat partisipasi responden (X7) Tingkat kesejahteraan sosial responden (X8) Tingkat keberdayaan responden (X9) Tingkat ordinasi responden (X10) Tindakan represif oleh pemerintah (X11) Persepsi tentang status kawasan hutan negara (X12) Persepsi tentang fungsi lingkungan dari hutan (X13) Persepsi tentang desentralisasi pengelolaan kawasan hutan (X14) Keterlibatan aktif responden dalam berdialog dan negosiasi (X15) Tingkat pendidikan pesponden (X16) Lama tinggal di kawasan (X17) Kosmopolitansi responden (X18) Sub Model C (Kelangkaan) KTLP TPDK PRR PKLT = = = = Penguasaan lahan Pertanian di luar kawasan (X19) Status kepemilikan lahan pertanian yang dikuasai di luar kawasan (X20) Pendapatan Rumahtangga Responden Di Luar Kawasan (X21) Persepsi Tingkat Kebutuhan Lahan Pertanian tambahan (X22) Sub Model D (Etik Lingkungan) PAR PER PRTA ESKO 4 = = = = Etik Antroposentris (X23) Etik Ekosentris (X24) Manifestasi Etika Lingkungan (X25) ESKALASI KONFLIK (X26) Persepsi adalah proses kognitif yang terjadi pada seseorang dalam memahami dan menafsirkan informasi lingkungannya yang diperoleh melalui sensor indranya (Thoha, 1988). 5 Menurut Sarwono (1999), perbedaan persepsi antar individu dan/atau komunitas sosial disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam hal perhatian, harapan, kebutuhan, sistem nilai, dan kepribadian. 13 Sub Model A: Eksternalitas TPDR HK SKR IF PKHN BAA PDPK SP KR PFLH PP KKLK LTRP LPDN Sub Model B: Persepsi dan Ketimpangan Struktural ESKO TKPR TKOR Sub Model C: Kelangkaan PRR TKDR PKLT TKSS TPDK KTLP PRTA PAR PER Sub Model D: Etik Lingkungan Gambar 1.1 Bagan Alir Kerangka Pemikiran Hubungan Pengaruh Model Faktor-faktor Yang Menimbulkan Konflik Lingkungan 14 Adanya perbedaan etik lingkungan merupakan salah satu penyebab konflik pengelolaan sumberdaya alam. Menurut Merchant (1992), etik lingkungan adalah suatu keyakinan tentang keterkaitan antara tata sosial seseorang/kelompok terhadap kelestarian lingkungan hidup disekitarnya yang kemudian dimanifestasikan dalam praktik kehidupannya sehari-hari. Ada tiga etik lingkungan yang terdapat dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan yaitu: (1) etik egosentris/antroposentris, (2) etik homosentris/sosiosentris, dan (3) etik ekosentris. Pandangan lain ada yang menyatukan etik egosentris dan homosentris ke dalam satu kelompok yang disebut etik antroposentris, sementara etik ekosentris tetap di dalam kelompok tersendiri. Di dalam penelitian ini, diduga praktik etik lingkungan yang terjadi pada suatu konflik dipengaruhi oleh etik antroposentris dan etik ekosentris seseorang/kelompok. (Lihat Submodel D Gambar 1.1). Penanganan konflik lingkungan dalam pengelolaan hutan bukan produksi memerlukan kajian awal terhadap data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan: (1) masalah-masalah penyebab konflik atau sering disebut dengan akar konflik, (2) pengetahuan tentang gaya konflik (conflict styles) yang dimanifestasikan oleh masing-masing pihak yang terlibat konflik, (3) tipe konflik, dan (4) polarisasi sifat konflik. Hubungan saling pengaruh antara keempat komponen tersebut kemudian menggambarkan suatu peta konflik. Akar konflik merupakan perbedaan-perbedaan fundamental yang menyebabkan mengapa suatu konflik terjadi. Dari perbedaan tersebut, masingmasing pihak yang terlibat konflik umumnya memanifestasikan responnya terhadap konflik yang dihadapi melalui gaya konflik yang berkaitan dengan kepeduliannya terhadap kepentingan individu/kelompoknya sendiri dan/atau kepentingan individu/kelompok lainnya. Gaya konflik seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap orang/kelompok pihak lain dapat berbentuk saling menghindar, menekan, kompromi, akomodasi, dan kerjasama. Tingkat perbedaan sasaran akan mempengaruhi perilaku para pihak yang berkonflik dan membentuk tipe-tipe konflik yang terjadi seperti apakah tipe konflik tersebut terbuka dan mudah diidentifikasi langsung atau konflik tersebut tertutup/laten sehingga memerlukan identifikasi khusus. Mengingat banyak pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung, pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama biasanya cenderung akan berkelompok, sedangkan yang memiliki kepentingan yang berbeda cenderung akan 15 berseberangan berpolarisasi pada sisi yang berbeda dan/atau berlawanan. Dari polarisasi konflik kemudian diperoleh peta konflik yang terjadi baik secara spasial maupun secara sosial; secara spasial konflik dipetakan dalam batas ruang tertentu berikut “konflik apa” yang terjadi, sedangkan secara sosial konflik dipetakan untuk memperolah gambaran “siapa melawan siapa” yang terlibat di dalam suatu konflik. Model hubungan sebab akibat antar-keempat komponen tersebut amat penting dalam melakukan analisis pemetaan konflik. Secara grafis model tersebut ditayangkan pada Gambar 1.2. Penanganan konflik lingkungan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung secara umum memerlukan pilihan-pilihan pendekatan penanganan dan metode penanganan. Berdasarkan hasil yang dapat diperoleh dari analisis kedua model yang dikembangkan sebelumnya, pendekatan penanganan konflik dipilih secara kognitif kualitatif didasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris melalui proses pengenalan masalah dan keterlibatan diri (peneliti dan responden) secara langsung pada kasus konflik. Penanganan konflik dimaksud mencakup pilihan-pilihan apakah akan dilakukan pengendalian akar konflik, penyelesaian konflik berikut upaya rekonstruksi sosial dan lingkungannya, atau untuk mencegah transformasi konflik baik secara geografis maupun secara lintastataran sosial. Sedangkan metode penanganan konflik menyangkut pilihan- pilihan apakah konflik akan diselesaikan melalui jalur hukum formal atau dengan penanganan konflik alternatif (Alternative Dispute Resolution). Pilihan-pilihan pendekatan dan metode penanganan konflik lingkungan juga ditentukan oleh instrumen kebijakan yang ada seperti apakah pilihan-pilihan tersebut terakomodasi dalam peraturan dan perundangan yang berlaku baik tentang kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, agraria, maupun otonomi daerah. Kewenangan formal penanganan konflik juga amat menentukan apakah suatu konflik cukup ditangani di tingkat lokal dan/atau perlu dalam sekala regional. Perbedaan kebutuhan di tingkat mana penanganan konflik dilakukan akan berimplikasi terhadap perbedaan institusi apa dan/atau siapa saja yang relevan dan berwenang untuk turut serta menangani konflik lingkungan yang terjadi. Seluruh keterkaitan antara fungsi lingkungan yang diharapkan dari pengelolaan kawasan hutan bukan produksi, kebijakan yang mengaturnya, konflik yang ditimbulkan, upaya penanganan konflik, dan dampak konflik terhadap kelestarian fungsi lingkungan dari kawasan hutan tersebut, secara grafis ditayangkan pada Gambar 1.3. 16 Pihak A Pihak B Akar Konflik Perbedaan Kepentinga Perbedaan Struktural Perbedaan Data Perbedaan Nilai Perbedaan Hubungan Sosial Akar Konflik Perbedaan Kepentinga Gaya Konflik Pihak A Terhadap Aktor Lainnya Menghindar Menekan Kompromi Akomodasi Perbedaan Struktural Perbedaan Data Perbedaan Nilai Perbedaan Hubungan Sosial Gaya Konflik Pihak B Terhadap Aktor Lainnya Kerjasama Menghindar Menekan Kompromi Akomodasi Kerjasama PENANGANAN KONFLIK Tipe Konflik Polarisasi Sifat Konflik Tipe Konflik Tipe Konflik Gaya Konflik Pihak C Terhadap Aktor Lainnya Menghindar Menekan Perbedaan Kepentinga Perbedaan Struktural Kompromi Gaya Konflik Pihak D Terhadap Aktor Lainnya Akomodasi Kerjasama Menghindar Menekan Perbedaan Nilai Masalah Hubungan Sosial Perbedaan Kepentinga Perbedaan Struktural Akar Konflik Perbedaan Data Pendekatan Penanganan • Pencegahan Konflik • Penyelesaian Konflik • Pengelolaan Konflik • Resolusi Konflik • Transformasi Konflik Tipe Konflik Kompromi Akomodasi Kerjasama Perbedaan Nilai Perbedaan Hubungan Sosial Akar Konflik Pihak C Gambar 1.2. Bagan Alir Kerangka Pemikiran Model Identifikasi Peta Konflik Perbedaan Data Pihak D Metode Penanganan • Negosiasi • Mediasi • Fasilitasi • Arbitrasi • Proses HUkum 17 ISU LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan Pengelolaan Kehutanan FUNGSI LINGKUNGAN DARI HUTAN Fungsi Ekonomi • Hasil Hutan (Kayu dan Bukan Kayu) • Bukan Hasil Hutan (pertambangan, infrastuktur pelayanan publik ) Fungsi Sosial • Pertumbuhan Penduduk • Kebutuhan Lahan Pertanian Dalam Arti Luas • Ketahanan pangan • • • • • Hak-hak Masyarakat Lokal/adat atas lahan • Pengetahuan subsisten • Kesehatan • Estetika • Budaya Tekanan (pendudukan/okupasi) lahan kawasan hutan oleh masyarakat Pembalakkan liar Konversi lahan tak terkendali Degradasi hutan Kerusuhan Sosial • Keanekaragaman hayati • Plasma nuftah • Habitat satwa • Iklim mikro • Rosot karbon • Pengatur Tata air • Pencegah erosi Konflik Pengelolaan Kawasan Hutan Register 45B dan Register 9 Di Propinsi Lampung PETA KONFLIK • • • PENANGANAN KONFLIK • • Upaya Pengendalian dan/atau Pengurangan Dampak Konflik Kebijakan Otonomi Daerah Fungsi Ekologis DAMPAK KONFLIK • Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pendekatan Penanganan Metode Penanganan • Akar konflik Gaya Konflik Polarisasi sifat konflik Tipe konflik Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung; Studi Kasus Di Lokasi Penelitian Umpan balik Perbaikan Kebijakan Pengelolaan Strategi Penanganan Konflik Kewenangan Penanganan Konflik Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran Model Kognitif Penanganan Konflik Lingkungan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung 18 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari konflik lingkungan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dalam konteks pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengkaji kebijakan-kebijakan kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, agraria, tata ruang, dan otonomi daerah bagi penanganan konflik lingkungan dalam pengelolaan kawasan hutan di daerah khususnya di kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis. 2) Meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konflik dalam pengelolaan kawasan lindung berkaitan dengan fungsi lingkungan dari hutan. 3) Meneliti gaya pengelolaan konflik (conflict style management) yang diragakan oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalam konflik dan polarisasi konflik yang terjadi. 4) Mengembangkan model penanganan konflik lingkungan secara kognitif didasarkan kepada pengalaman yang diperoleh para pihak yang bersengketa. 1.5. Manfaat Penelitian Diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat berupa: (1) Terbangunnya pemahaman bersama bahwa konflik lingkungan adalah sesuatu yang harus dikelola sebelum ia menjadi masalah yang disfungsional. (2) Sumbangsih bagi kalangan pemerintah (perencana, pengambil keputusan kebijakan, dan pelaksana kebijakan), akademisi, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, terutama mereka yang terlibat langsung dengan konflik yang diteliti, tentang bagaimana menangani konflik lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan khususnya kawasan hutan lindung. (3) Bahan pembanding bagi penelitian-penelitian lainnya yang berkaitan dengan penanganan konflik lingkungan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. 1.6. Kebaharuan (Novelties) Kebaharuan (novelties) yang disajikan oleh penelitian disertasi ini adalah: 1) Secara spasial, merupakan penelitian holistik model penangan konflik lingkungan yang pertama kali dilaksanakan di kawasan hutan lindung. 19 2) Secara metodologis, penelitian disertasi ini merupakan penelitian multidisiplin ilmu memadukan hard system analysis dan soft system analysis untuk saling memperkuat satu sama lainnya. Penelitian menyajikan sebuah rangkaian analisis penanganan konflik lingkungan secara holistik, dimulai dari analisis akar konflik, polarisasi, gaya konflik, pemilihan pendekatan penyelesaian, hingga penyelesaian konflik secara kognitif yang kemudian menjadi aksi lanjut (follow up action) para pihak dalam menyelesaikan konfliknya pasca penelitian ini. 3) Penelitian ini menyuguhkan bagaimana beberapa alat assesment (penilaian) dipergunakan di dalam sebuah mekanisme penyelesaian konflik yang dikembangkan. Ketiadaan alat peniliaian tersebut saat ini merupakan tantangan dari berbagai prosedur yang ada dari penerapan berbagai peraturan dan perundangan penyelesaian konflik secara alternatif (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia.