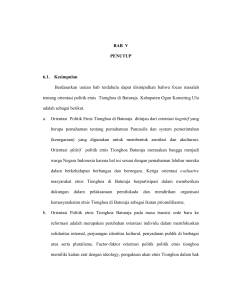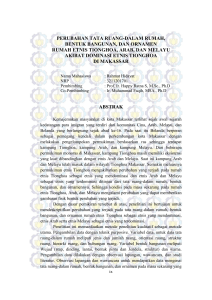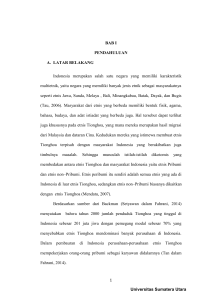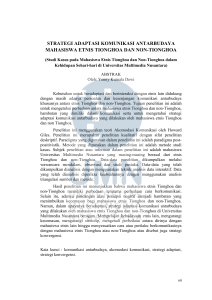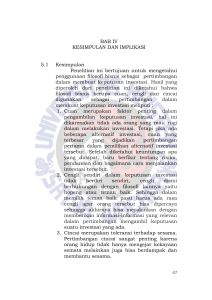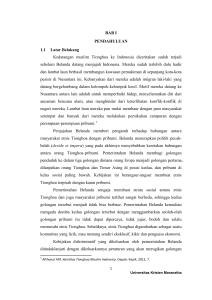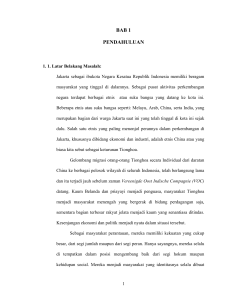`Masalah Cina` di Indonesia
advertisement

BAB I ‘Masalah Cina’ di Indonesia A. Latar Belakang Sejarah panjang keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia cukup banyak meninggalkan dan menyisakan polemik kehidupan sosial, politik, dan budaya bagi identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial HindiaBelanda, kebijakan-kebijakan terhadap etnis Tionghoa mulai diberlakukan. Kehadiran dan keberartian orang-orang etnis Tionghoa seringkali disikapi acuh tak acuh oleh masyarakat Pribumi dan Pemerintah, atau bahkan diekspresikan secara ekstrem, dengan sangat membenci atau justru menyenangi orang-orang etnis ini, namun tetap dalam kondisi-kondisi tertentu saja orang-orang etnis Tionghoa mendapatkan perlakuan tersebut. Pendeknya, terdapat suatu sikap yang tidak menentu terhadap golongan ini, yang juga terlihat pada badan-badan Pemerintah, seperti tercermin pada kebijakan-kebijakan serta peraturan yang diberlakukan sejak zaman kolonial hingga kini. Kenyataan kedua adalah bahwa suatu golongan tidak perlu merupakan kelompok yang besar untuk mempunyai kedudukan yang berarti. Proporsi orang etnis Tionghoa terhadap seluruh penduduk Indonesia adalah sangat kecil dan boleh dikatakan hampir tidak banyak berubah sejak tahun 1930 sampai sekarang. Hanya sekitar 2% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1930 dan 2,6% pada tahun 1965. Kenyataan ketiga, bahwa Indonesia, seperti kebanyakan Negara di Asia Tenggara lainnya, mempunyai apa yang dinamakan “Masalah Tionghoa” 1 atau “Masalah Cina”. Adanya masalah ini dapat diukur terutama dari frekuensi terjadinya tindakan kekerasan terhadap mereka sebagai sasaran langsung maupun tidak langsung. Melihat masalah Tionghoa sebagai bagian dari kenyataan kebhinekaan masyarakat Indonesia ini, mengharuskan suatu pengetahuan dan pengertian yang lebih mendalam mengenai sejarah dan peranan golongan minoritas dalam masyarakat luas. Untuk itu kemudian muncul kesimpulan bahwa walaupun jumlah orang etnis Tionghoa di Indonesia relativ sedikit, mereka merupakan kelompok minoritas yang berarti. Dengan kata lain, meskipun dari segi ekonomi etnis Tionghoa lebih menonjol dari Pribumi, kemungkinan terjadinya benturanbenturan diperbesar dengan adanya segi-segi sosial, budaya, dan politik, dan dasar-dasarnya terbentuk sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan kebijakan ‘devide et impera’nya, yang secara sangat sistematis memisahkan berbagai golongan penduduk dengan golongan lainnya, termasuk golongan etnis Tionghoa. 1 Siapakah orang Tionghoa di Indonesia? Skinner mengemukakan bahwasannya penggolongan etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat didasarkan hanya dari kriteria ras, hukum ataupun budaya yang melatarbelakangi hadirnya etnis Tionghoa di Indonesia, tetapi pada identifikasi sosial. “Di Indonesia seorang keturunan Tionghoa disebut orang Tionghoa, jika ia bertindak sebagai anggota dari dan mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa”. Disebutnya 1 G. Tan, Mely. 1979. Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa. Jakarta. Gramedia 2 bahwa satu-satunya ciri budaya yang dapat diandalkan adalah penggunaan nama keluarga Tionghoa. Namun, sejak tahun 1966 ada anjuran penggantian nama bagi orang-orang keturunan asing yang kemudian mengakibatkan perubahan nama secara massal oleh orang-orang Tionghoa. Mereka yang sudah menjadi warga Negara Indonesia dalam sensus-sensus sejak berdirinya Republik Indonesia tidak dibedakan dari warga Negara Indonesia lainnya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari acap kali mereka sukar dibedakan dari mereka yang dinamakan ‘Pribumi’. Tidak jarang terjadi bahwa seorang yang disangka keturunan Tionghoa, ternyata merupakan orang Manado, Bengkulu atau orang Jawa. Dengan demikian sukar pula untuk diketahui dengan pasti berapa dan siapa sebenarnya warga Negara keturunan Tionghoa di Indonesia. Kalaupun dapat diadakan pembedaan antara orang-orang etnis Tionghoa menurut kewarganegaraannya, masih ada suatu perbedaan pokok lainnya, ialah menurut orientasi kebudayaannya. Kita dapat membedakan antara mereka yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok (berbahasa Tionghoa dirumah, pernah bersekolah di sekolah Tionghoa, mempunyai hubungan kerabat atau dagang dengan orang Tionghoa lain diluar Indonesia), yang biasanya dinamakan orang Tionghoa ‘Totok’; dan mereka yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan setempat, seperti Jawa, Sunda, Ambon Manado, yang dirumahnya menggunakan bahasa setempat; pendeknya, mereka yang telah mengalami proses akulturasi yang mendalam dengan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Orang-orang ini biasanya dinamakan ‘peranakan’. 3 Dalam kenyataannya terlihat bahwa orientasi kebudayaan ini melintasi status kewarganegaraan: seorang Totok biasanya, tapi tidak selalu, warga Negara asing dan ia bisa dilahirkan di luar Indonesia tapi juga di Indonesia; seorang peranakan biasanya, tapi tidak selalu, warga Negara Indonesia dan ia selalu kelahiran Indonesia. Seorang peranakan biasanya, tetapi tidak selalu, dilahirkan dari perkawinan campuran (kebanyakan adalah keturunan dari ayah Tionghoa dan ibu Indonesia), karena itu berdasarkan ras mereka bukan orang tionghoa lagi. Namun pada umumnya masyarakat luas tidak dapat, dan pada waktu dan keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak mau membedakan antara mereka yang warga Negara Indonesia dan yang warga Negara asing, sehingga terdapat kekaburan dan ketidaktepatan mengenai status hukum maupun status sosial dalam masyarakat luas. Dan jikalau tindakan ini dibenarkan dan diteruskan, maka seorang keturunan Tionghoa secara turun temurun tetap diperlakukan seakan-akan ‘sekali Tionghoa tetap Tionghoa’. Dengan kata lain, seorang keturunan Tionghoa selalu diingatkan bahwa ia adalah keturunan Tionghoa dan harus selalu mempunyai dokumen khusus untuk membuktikan kewarganegaraannya. 2 Dari hasil observasi M.G Tan (1976), terdapat kesan bahwa hubungan golongan etnis Tionghoa dengan golongan etnis lainnya cenderung tegang dan saling curiga. Sejalan dengan kesimpulan yang diutarakan oleh Edward M. Bruner pada tahun 1957-1958 dan dilanjutkan pada tahun 1969-1971 dengan judul The 2 Ibid 4 Expression of Ethnicity In Indonesia (1972), bahwasannya keturunan perkawinan campur antara orang Tionghoa dan orang Indonesia tidak membentuk suku bangsa baru. Mereka memilih identitas salah satu orang tuanya yang didasarkan pada status siapa di masyarakat yang lebih tinggi. Pada umumnya mereka lebih memilih identitas Tionghoa karena sebagian besar dari perkawinan campuran itu terdiri dari ayah Tionghoa dan ibu Indonesia. “Ke-Tionghoa-an” mereka, menurut Tan, diwujudkan dalam ciri-ciri kebudayaan mereka, seperti pemujaan terhadap nenek moyang, nilai dan norma tertentu, bahkan kadang-kadang juga nama mereka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 3 Hal ini sangat serupa dengan apa yang terjadi dengan etnis Tionghoa di Indonesia. Disebutkan sebelumnya, bahwa sudah sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda politik ‘pemisahan’ golongan antar etnis telah diberlakukan, termasuk etnis Tionghoa. Keterbatasan akses dan keterbatasan berdemokrasi untuk menempatkan sikap kebangsaan etnis Tionghoa di Indonesia semakin dikebiri oleh Negara, bahkan oleh masyarakatnya. Etnis Tionghoa sangat dibatasi untuk menunjukkan sikap mereka dalam memaknai ke-Indonesia-an nya. Kebudayaan serta kebiasaan yang mereka miliki seperti ‘terpangkas’ dengan adanya aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Negara maupun Pribumi. Stereotip yang tumbuh dan berkembang terlebih sejak masa Orde Baru, semakin menguatkan kelemahan etnis Tionghoa yang kemudian berlabelkan ‘minoritas’, bahkan di Tanah Airnya sendiri ketika mereka telah berasimilasi dan berakulturasi menjadi warga Negara Indonesia. 3 Ibid 5 Pembatasan-pembatasan tersebut menjadi awal mula terbentuknya ‘benteng’ antara etnis Tionghoa dengan Negara dan pribumi. Insecurity terhadap Negara dan pribumi kemudian disebut-sebut sebagai penyebab eksklusif nya etnis Tionghoa dibandingkan dengan pribumi dan etnis lainnya. Eksklusifitas ini yang kemudian mulai berkembang menjadi pola hidup dan kebiasaan, bahkan budaya bagi beberapa lapisan etnis golongan Tionghoa itu sendiri. Seperti misalnya ketika kita melihat banyak dari golongan etnis Tionghoa menengah keatas yang menjadi sangat eksklusif dibanding dengan orang-orang etnis Tionghoa lainnya. Misal, jika kita melihat orang-orang etnis Tionghoa yang tersebar di Ibukota Jakarta. Etnis Tionghoa tersebut kemudian menyebar, dan beraglomerasi pada daerahdaerah tertentu yang menunjukkan identitas mereka masing-masing. Etnis Tionghoa peranakan, yang berasimilasi dengan orang Indonesia, dan kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai pedagang, bertempat tinggal di sekitaran Glodok dan jalan Gajah Mada, yang kemudian orang bilang sebagai ‘Cina Benteng’. Sebutan Cina Benteng muncul karena ada pembedaan latar belakang financial dengan orang Tionghoa ‘Totok’ lainnya, yang beraglomerasi di sekitaran daerah Kelapa Gading dan Pluit, Jakarta Utara. Orang-orang Tionghoa ini dikenal sebagai pengusaha, golongan menengah keatas, yang cukup menguasai pusat perekonomian dan bisnis, baik di Ibukota maupun di daerah-daerah. Padahal sejak zaman dahulu, orang Tionghoa sudah dikenal sebagai pedagang. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Tionghoa di Indonesia mulai bertransformasi menjadi konglomerat yang kapitalis. Tinggal di daerah-daerah pemukiman tertentu yang memisahkan diri dengan pemukiman etnis atau golongan lain. Etnis 6 Tionghoa membangun in-group yang tanpa mereka sadari semakin menjauhkan etnis mereka dengan budaya demokrasi dengan masyarakat Indonesia yang pluralis. Insecurity juga disebut-sebut sebagai faktor yang dijadikan alasan pilihan anak-anak Tionghoa disekolahkan di sekolah-sekolah swasta, terlebih berbasis Yayasan. Perlu diingat bahwasannya pilihan tersebut merupakan hasil dari luka lama yang dirasakan pada pemerintahan masa Orde Baru, dimana kebijakan Soeharto yang mengimbau anak-anak berkebangsaan asing yang tinggal di Indonesia untuk masuk sekolah Negeri dan swasta yang mengajarkan kurikulum nasional. Salah satu bagian kebijakan ini tentang pendirian organisasi mengatur pemberian izin Pemerintah hanya kepada organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, keagamaan, dan jasa pemakaman serta olah raga dan hiburan, dengan jumlah tertentu warga asing (Tionghoa). Pembatasan ini dapat dilihat sebagai upaya Pemerintah untuk menekan segala macam kegiatan politik dan atau gerakan yang melibatkan unsur komunisme (Aimee, 2010). Selain itu, maraknya bullying oleh golongan pribumi kepada etnis Tionghoa di sekolah-sekolah juga menjadi factor insecurity yang dirasakan orang-orang Tionghoa di sekolah Negeri dan swasta pribumi tersebut. Karena adanya pembatasan dan insecurity tersebut, budaya dan bahasa Tionghoa yang sebelumnya, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masih diperbolehkan sekolah nya, pada masa pemerintahan Orde Baru justru dipangkas. Hal tersebut kemudian berdampak pada mind-set dan rational-choice etnis Tionghoa pasca Orde Baru untuk dapat ‘menghidupkan’ kembali kebudayaan dan 7 kebiasaan lama sekolah mereka. Dimana mereka dapat merasakan keamanan dan kelestarian budaya Tionghoa hanya dengan lingkungan yang berisikan orangorang Tionghoa juga. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dipahami bahwasannya pemikiran tentang identitas Indonesia Tionghoa merupakan konsep yang sukar ditangkap dan melibatkan banyak penyebab yang saling berkaitan, terutama sejarah masa lampau etnis Tionghoa di Indonesia. Penyebab yang saling terkait ini dan dapat meliputi teritorialitas, afiliasi agama, pengaruh keluarga, sikap hubungan antara Pribumi dengan Tionghoa, kelas, patriarki, dan pencarian jodoh, semuanya memberi andil kepada corak sistem representasi yang mendasari pola interaksi dan identifikasi diantara orang Indonesia Tionghoa. 4 Dan seiring berjalannya waktu, sejarah etnis Tionghoa dari zaman kolonial Belanda, Orde Baru, Reformasi sampai pada saat ini kemudian semakin mengalami proses pergeseran. Dari etnis minoritas, menjadi etnis dan komunitas yang superior dan bahkan eksklusif. Mereka yang dahulu termarjinalkan, kini memegang kekuatan pada beberapa sektor vital Negara, seperti perekonomian. Pribumi tidak lagi memandang mereka sebagai orang-orang minoritas yang tidak memiliki hak dan akses terhadap Negara dan lingkungan seperti perspektif terdahulu. Namun, justru keadaan berbalik. Kini kebanyakan etnis Tionghoa yang lebih memegang kendali daripada orang-orang Pribumi dan bahkan oleh Negara. Mereka seakan terpisah dari Negara dan masyarakat lainnya, membentuk suatu ‘komunitas’ atau in-group atas dasar kultur subjektifnya, dengan kekuatan finansial, terlebih di dukung 4 Dawis, Aimee Ph.D. 2010. Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas. Jakarta. Gramedia 8 dengan perkembangan stereotip masyarakat akan kehidupan sosial etnis Tionghoa di Indonesia, mereka bertransformasi menjadi etnis yang superior dan eksklusif. Namun tanpa disadari, dengan kebudayaan dan life style etnis mereka sendiri lah yang memperkuat label dan disain ‘minoritas’ tersebut, sehingga “Tionghoa akan tetap Tionghoa”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di bagian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses self-minoritisasi terjadi di Jakarta? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk menyingkap bahwasannya proses inklusi maupun eksklusi, dalam hal ini terkait label ‘minoritas’ terhadap etnis Tionghoa, tidak dapat dilihat hanya melalui perspektif Negara dan masyarakat Pribumi saja. Namun, dapat kita lihat bahwa adanya label ‘minoritas’ terhadap etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang ‘dilestarikan’ oleh etnis Tionghoa itu sendiri melalui kultural subjektif nya yang berupa kebudayaan dan kebiasaan etnis Tionghoa. D. Kerangka Teori Penelitian ini dilakukan untuk menyingkap bahwasannya proses inklusi maupun eksklusi, dalam hal ini terkait label ‘minoritas’ terhadap etnis Tionghoa, 9 tidak dapat dilihat hanya melalui perspektif Negara dan masyarakat Pribumi saja. Namun, dapat kita lihat bahwa adanya label ‘minoritas’ terhadap etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang ‘dilestarikan’ oleh etnis Tionghoa itu sendiri melalui kultural subjektif nya yang berupa kebudayaan dan kebiasaan etnis Tionghoa. Skema dibawah menjelaskan proses praduga adanya self-minoritisasi oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Self-minoritisasi sendiri merupakan istilah yang penulis buat untuk menjelaskan fenomena yang menjadi kecurigaan penulis terhadap kemungkinan label ‘minoritas’, yang baik sengaja maupun tidak sengaja, ‘dilestarikan’ oleh etnis Tionghoa melalui kebudayaan, kebiasaan, serta kehidupan sosial etnis Tionghoa di Indonesia. Negara, masyarakat, dan etnis (Tionghoa maupun etnis lainnya), yang terdapat pada skema dibawah merupakan aktor-aktor yang memiliki perspektif masing-masing terhadap aktor lainnya. Perspektifperspektif tersebut ditunjukkan dengan lingkaran yang masing-masing menunjukan komunitas Negara, Pribumi dan Tionghoa itu sendiri yang saling terkait satu sama lain. Dari perspektif-perspektif yang ada, kemudian berkembang menjadi stereotip yang melekat di masyarakat hingga saat ini. Namun ditengahtengah stereotip yang ada di masyarakat, bahwasannya etnis Tionghoa adalah golongan ‘minoritas’ di Indonesia, patut dipertanyakan apakah jangan-jangan ada praktik self-minoritisasi yang secara sengaja maupun tidak sengaja ‘dibentuk’ dan ‘dilestarikan’ oleh etnis Tionghoa melalui budaya, kebiasaan, dan kehidupan sosialnya sendiri. Sehingga sampai saat ini ‘Masalah Cina’ atau keminoritasan etnis Tionghoa masih menjadi problematika yang belum terselesaikan di Indonesia. 10 Konsep yang penulis coba tawarkan dalam membangun kerangka teori adalah terkait identitas sosial serta turunannya, yakni stereotip. Dalam khazanah psikologi sosial kajian terhadap proses interaksi antarkelompok sosial tersebut kemudian melahirkan sebuah tradisi teoretis yang kuat dan berpengaruh hingga sekarang, yang disebut sebagai teori identitas sosial. Area kajian teori identitas sosial adalah pembahasan tentang perilaku-perilaku individu dalam konteks hubungan antarkelompok yang mencerminkan keberadaan unit-unit sosial lebih besar dimana individu bernaung didalamnya, seperti organisasi-organisasi sosial, sistem-sistem kebudayaan, dan sistem-sistem sosial lainnya yang mana individu cenderung akan menempatkan hal-hal tersebut sebagai rujukan bagi perilakuperilaku sosialnya (Tajfel, 1974). Dengan demikian terdapat pula pola yang relatif stabil mengenai proses terbentuknya perilaku-perilaku individu di level interaksi antarkelompok, yaitu bahwa setiap hal yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan individu pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai, kebiasaankebiasaan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu yang berkembang di level kelompok (Padilla dan Perez, 2003). Dengan kata lain, perilaku individu merupakan fungsi langsung dari sistem-sistem nilai yang berkembang di kelompoknya. 11 SelfMinoritisasi Identitas sosial terbentuk dari keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga individu sebagai bagian dari kelompok sosial yang dinaunginya (Hogg dan Abram, 1990: 2-3). Ia merupakan bagian dari konsep diri individu yang bersumber dari pengetahuan tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial yang menganut nilai, norma, dan ikatan emosional tertentu yang mampu menyatukan anggota-anggotanya (Tajfel, 1982: 2). Dengan demikian, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam sebuah kelompok sosial tertentu melalui mana individu tersebut dengan sengaja menginternalisasi nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya. Teori identitas sosial memiliki tiga asumsi utama. Yang pertama, setiap individu akan berusaha mempertahankan konsep dirinya yang positif. Kedua, konsep diri tersebut lahir dari identifikasi terhadap kelompok sosial yang lebih 12 besar. Dan yang ketiga, upaya individu dalam mempertahankan konsep dirinya yang positif itu cenderung dilakukan dengan membanding-bandingkan kelompoknya dengan kelompok lain (Operario dan Fiske, 1999: 26-54). Proses perbandingan sosial ini umumnya didorong oleh motif persaingan antarkelompok, yang tidak jarang akan berujung pada konflik sosial ketika variabel-variabel struktural seperti distribusi kekuasaan yang tidak adil, hierarki sosial yang terlalu timpang, persaingan memperebutkan sumber daya dan pengaruh, serta upaya mempertahankan harga diri kelompok itu tereskalasi dalam hubungan antarkelompok. Kondisi ini memungkinkan masing-masing kelompok sosial akan mempersepsi kelompok lain (outgroup) sebagai pesaing, ancaman jahat, buruk, sementara dalam waktu yang bersamaan akan muncul kecenderungan yang sebaliknya, yaitu melihat kelompok (ingroup) sendiri sebagai yang lebih baik dan unggul (Padilla dan Perez, 2003). Pembahasan mengenai teori identitas sosial tentu tidak dapat dipisahkan dengan teori kategorisasi diri (self-categorization theory). Menurut Turner dkk (1987: 8-10), realitas sosial merupakan tempat berkembangnya nilai-nilai yang menjadi acuan bagi identitas kelompok, dan dalam perkembangannya kemudian melahirkan batas-batas antarkelompok. Identitas yang mewujud dalam interaksi sosial dengan demikian merupakan penjelmaan dari kegiatan memilih, menyerap, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tersebut, sehingga dalam konteks ini bisa dibaca bahwa pada dasarnya setiap kelompok akan membawa dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing dalam interaksi sosial. Hal ini juga dipahami bahwa kecenderungan sebuah kelompok sosial untuk menyerap 13 nilai-nilai tertentu ketimbang yang lainnya merupakan cara kelompok tersebut dalam membuat batas pembeda antara dirinya dengan kelompok-kelompok lain. Proses yang mewakilinya disebut dengan kategorisasi diri. Bagi individu yang menjadi bagian dari kelompok sosial tersebut selanjutnya akan menempatkan nilai-nilai yang berkembang dalam kelompoknya itu (ingroup) sebagai rujukan dalam berperilaku dan menjadi bagian dari identitas sosialnya, sementara disaat yang bersamaan dia akan bersikap sebaliknya untuk kelompok lain, yaitu cenderung merendahkan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh kelompok lain (outgroup) (Krizan dan Baron, 2007). Kategorisasi diri sebagai bagian tak terpisahkan dari kelompok pada akhirnya akan melahirkan apa yang disebut depersonalisasi (depersonalization) atau kondisi dimana identitas personal semakin melemah dan identitas sosial semakin menguat. Menurut Hogg dan Mullin, depersonalisasi muncul dari motifmotif untuk mereduksi ketidakpastian yang dialami individu. Ketidakpastian itu dapat diredusir bilamana individu bersedia meleburkan dirinya kedalam identitas kelompok yang dapat menjamin rasa aman dan keutuhan. Ketika depersonalisasi terjadi, anggota-anggota kelompok melihat diri mereka sebagai satu kesatuan dan akan melihat individu-individu dari kelompok lain sebagai pihak yang berbeda dengan diri mereka (Hogg dan Mullin, 1999: 254-257). “Identitas sosial merupakan seperangkat ciri-ciri, kepercaayaan, hasrat, atau prinsip-prinsip tindakan yang membuat seseorang berpikir bahwa dirinya secara sosial itu berbeda dari orang lain dalam sejumlah cara, yakni (a) dia bisa memperoleh kebanggan dari dirinya; (b) kalaupun dia 14 tidak mendapat kebanggan itu, dia akan tetap menggunakan identitas tersebut untuk mengarahkan tindakan-tindakannya. Sebab tanpa hal itu, dia tidak akan tahu tentang bagaimana cara bertindak dan apa yang mesti dilakukan; atau (c) dia merasa tidak dapat mengubahnya sekalipun dia mengkehendakinya.” (Fearon, 1999: 25) Syarat (b) dan (c) secara langsung berhubungan dengan counterexample. Syarat (b) menjelaskan kondisi dimana kita terkadang melihat identitas personal sebagai seperangkat prinsip atau norma yang secara fundamental mengarahkan dan membentuk perilaku sehari-hari kita tanpa kita menyadari mengapa kita mempercayainya begitu saja. Sementara (c) menjelaskan kondisi dimana kita acap kali harus menerima atau melakukan hal-hal tersebut diluar kendali kita, meskipun kita sebenarnya telah mencoba untuk tidak mengakui atau melakukannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam kehidupan kita memiliki aspek-aspek atau atribut-atribut tertentu yang menuntut kita untuk menerimanya begitu saja. 5 Meskipun orang-orang Tionghoa tidak mengakui bahwa mereka adalah bagian entitas yang minoritas, namun karena secara objektif Negara dan masyarakat (pribumi) selama berpuluh-puluh tahun bahwa mereka adalah minoritas, akhirnya mereka harus mengakui identitas mereka di Indonesia sebagai entitas minoritas dan menjalani kehidupan sehari-hari layaknya kaum minor dengan segala keterbatasan. Afif, Afthonul. 2012. Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri. Depok. Kepik 5 15 Sebagaimana telah disinggung diatas, kategorisasi diri ini kemudian berdampak pada munculnya fenomena depersonalisasi. Depersonalisasi terjadi ketika dalam diri individu muncul kebutuhan untuk mereduksi ketidakpastianketidakpastian dalam lingkungan sosialnya, yaitu dengan jalan meleburkan diri kedalam kelompok sehingga muncul perasaan aman dan utuh (Hogg dan Mullin, 1999: 261-162). Ketika depersonalisasi ini terjadi, anggota-anggota kelompok akan melihat satu sama lain sebagai entitas homogen (outgroup homogenity) yang berbeda dengan diri mereka (Schaller, 1992). Dengan demikian, kategorisasi sosial pada dasarnya adalah proses pengelompokan sosial yang lebih bersifat emosional daripada rasional. Selain faktor pengkategorisasian diri, kemudian ada juga faktor perbandingan sosial yang memperkuat dalam pembentukan identitas minoritas etnis Tionghoa di Indonesia. Tajfel menyebutkan bahwa manfaat perbandingan sosial antar kelompok bagi anggota-anggota kelompok bukan hanya kemudian mereka lebih mampu menjelaskan siapa diri mereka yang sebenarnya, tetapi juga mampu mengevaluasi secara positif signifikansi dan relevansi perbandingan sosial itu guna mencapai keunikan identitas kelompok mereka (Tajfel, 1972: 296). Faktor lain mengapa perbandingan sosial itu penting bagi individu juga karena adanya motif untuk mengurangi ketidakpastian-ketidakpastian kondisi sosial individu. Ketika individu merasa kurang mampu mengatasi ketidakpastianketidakpastian situasi di lingkungan sosialnya, maka secara naluriah akan muncul kebutuhan untuk menggabungkan diri kedalam kelompok yang dianggap mampu memberikan jaminan rasa aman. Sementara dalam konteks relasi antara kelompok 16 yang tidak aman, kreativitas sosial ditampilkan dalam bentuk-bentuk perlakuan yang lebih merepresentasikan antagonisme kelompok, bentuknya yang paling nyata adalah dengan memperkuat dan menegaskan supremasi ideologi kelompok dihadapan kelompok lain. Konsekuensinya, diskriminasi sosial tidak lagi bersifat laten, melainkan sudah menjadi manifestasi dalam hubungan antar kelompok. Kompetisi sosial dilakukan, superioritas kelompok secara sengaja akan ditunjukkan melalui tindakan-tindakan diskriminasi yang bersifat langsung dengan maksud untuk membuat kelompok lain tidak berdaya dan tetap mengakui superioritas kelompok yang berstatus tinggi atau berbeda. 6 Hal-hal tersebut kemudin bisa dipahami sebagai bentuk eksklusi sosial. Eksklusi sosial dipahami sebagai dinamika proses atas multidimensi progresif yang memecahkan ‘ikatan sosial’ pada level individu dan kelompok. Dengan demikian, ikatan sosial, yakni relasi sosial, institusi-institusi serta identitasidentitas diimajinasikan atas dasar ‘rasa memiliki’. Eksklusi sosial kemudian ‘menghalangi’ partisipasi penuh yang telah ditentukan secara normatif atas kegiatan-kegiatan yang diberikan masyarakat dan menghiraukan akses informasi, sumber-sumber, kemampuan bersosial, pengetahuan serta identitas, kemudian mengikis harga diri dan mengurangi kemampuan untuk mencapai tujuan personal. 7 Perlu ditekankan juga bahwa eksklusi dan inklusi sosial merupakan antonim yang tidak sempurna sehingga bisa dipahami tergantung pada konteks Ibid. Disarikan dari: Silver, Hilary. 2007. The process of social exclusion: the dynamics of an evolving concept. Department of Sociology Brown University Providence, Rhode Island, USA 6 7 17 permasalahan yang terjadi. Dalam konteks Tionghoa, adanya diskriminasi yang mereka terima dan dipahami sebagai bentuk eksklusi Pribumi terhadap kelompok etnis Tionghoa bisa jadi merupakan bentuk inklusi yang sebaliknya juga dilakukan etnis Tionghoa sebagai upaya menjaga eksistensi mereka dalam kehidupan sosialnya. Seperti halnya seseorang yang hidup sendiri dan menutup diri, kemudian diartikan bahwa hal tersebut merupakan hal yang merugikan karena idealnya ada keluarga yang secara ekonomi, sosial, dan kultural dapat membantu seseorang tersebut dalam melanjutkan hidup. Namun, ia memilih untuk hidup sendiri, terlepas dari orang lain dan memilih untuk hidup tidak bergantung pada orang lain. Sehingga kemudian hal ini dipandang sebagai sebuah ‘keuntungan’ yang dipilih karena dengan demikian ia dapat mengekspresikan dirinya tanpa harus menimbulkan konflik sosial. 8 Sama halnya dengan apa yang terjadi pada etnis Tionghoa di Indonesia. Proses inklusi dan eksklusi kemudian menimbulkan ambivalensi terhadap identitas Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa yang dieksklusikan Pribumi pada kenyataannya memang termarjinalkan, namun tidak sepenuhnya terisolasi secara sosial. Hal ini dapat dilihat ketika etnis Tionghoa pada satu sisi tereksklusikan oleh Pribumi, namun disatu sisi mereka menginklusikan diri dalam kelompok etnis Tionghoa untuk mendapatkan kepastian-kepastian dalam kehidupan sosialnya sehingga dipandang sebagai kelompok yang eksklusif dan superior oleh Pribumi. 8 Ibid. 18 Indonesia Pasca Orde Baru memberikan gambaran yang lebih beragam mengenai kondisi orang Tionghoa di Indonesia. Tekanan Negara yang semakin melonggar memberikan kesempatan kepada mereka untuk menampilkan identitasnya secara lebih terbuka. Namun, tidak bisa dilupakan begitu saja bahwa orang Tionghoa Indonesia saat ini merupakan subjek sejarah yang telah mewarisi pengalaman hidup spesifik dengan kelompok etnis lainnya, sehingga mereka sudah sepantasnya dipandang secara berbeda. Identitas mereka saat ini dapat dianggap sebagai konsekuensi dari ikhtiar mendefinisikan diri yang digerakkan oleh momen-momen psikologis yang kompleks, semacam koeksistensi antara tindakan mengingat, melupakan, dan berharap sekaligus. H.C Triandis (1972), seorang ahli psikologi sosial terkemuka dewasa ini menunjukkan gagasan yang disebutnya kultur subjektif, yang berarti cara khas suatu golongan kebudayaan dalam memandang lingkungan sosialnya. Sebagian besar konflik antargolongan yang telah terjadi, menurut Triandis, diakibatkan oleh kultur subjektif yang berbeda-beda. Kemanapun kita memandang, kita akan melihat konflik. Dari berbagai konflik yang terjadi ada yang berlatar belakang kepentingan golongan, agama, ataupun ideologi. Walaupun latar belakangnya berbeda-beda, semua konflik itu bisa meningkat jadi agresi, menghancurkan umat manusia, dan merusak proses ekologi makhluk hidup. Seperti juga dirumuskan oleh Herskovits (1955: 305), kultur bagi Triandis berarti bagian dari lingkungan manusia yang merupakan hasil cipta manusia. Kultur subjektif adalah cara khas suatu komunitas kultur dalam memandang, atau dalam istilah teknisnya mempersepsi lingkungan yang merupakan hasil ciptaan 19 manusia. Triandis berpendapat bahwa dalam analisis kultur subjektif, stereotip adalah konsep sentral, sedangkan kategori merupakan unsur dasar yang paling penting. Semua golongan melakukan kategorisasi (Kluckhohn, 1954), namun kategorisasi masing-masing kultur berbeda-beda. Menurut Turner dkk (1987: 810), realitas sosial merupakan tempat berkembangnya nilai-nilai yang menjadi acuan bagi identitas kelompok, dan dalam perkembangannya kemudian melahirkan batas-batas antar kelompok. Identitas yang mewujud dalam interaksi sosial dengan demikian merupakan penjelmaan dari kegiatan memilih, menyerap, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tersebut, sehingga dalam konteks ini bisa dibaca bahwa pada dasarnya setiap kelompok akan membawa dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing dalam interaksi sosial. Hal ini juga dipahami bahwa kecenderungan sebuah kelompok sosial untuk menyerap nilai-nilai tertentu ketimbang yang lainnya merupakan cara kelompok tersebut dalam membuat batas pembeda antara dirinya dengan kelompok-kelompok lain. Proses yang mewakilinya disebut dengan kategorisasi diri. Bagi individu yang menjadi bagian dari kelompok sosial tersebut selanjutnya akan menepatkan nilainilai yang berkembang dalam kelompoknya itu (ingroup) sebagai rujukan dalam berperilaku dan menjadi bagian dari identitas sosialnya, sementara disaat yang bersamaan dia akan bersikap sebaliknya untuk kelompok lain, yaitu cenderung merendahkan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh kelompok lain (outgroup) (Krizan dan Baron, 2007). Stereotip sendiri adalah kategori khusus tentang keyakinan yang mengaitkan golongan-golongan etnis dengan atribut-atribut pribadi. Stereotip 20 dianggap sebagai unsur sentral dalam analisis kultur subjektif. D.T. Campbell (1967: 821) memberikan petunjuk bahwa semakin besar perbedaan yang nyata tentang kebiasaan-kebiasaan tertentu, segi-segi penampilan fisik, atau bendabenda kebudayaan, semakin besar kemungkinan hal-hal itu akan tampil pada gambaran stereotip dari kelompok tertentu tentang kelompok lain. Menurut Lippman (1922: 1), stereotip adalah gambar dikepala yang merupakan rekonstruksi dari keadaan lingkungan yang sebenarnya. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa stereotip merupakan salah satu mekanisme penyederhana untuk mengendalikan lingkungan, karena keadaan lingkungan yang sebenarnya terlalu luas, terlalu majemuk, dan bergerak terlalu cepat untuk bisa dikenali segera (1922: 16). Gambaran kita tentang keadaan lingkungan itulah yang menentukan apa yang kita lakukan. Dengan demikian, tindakan-tindakan seseorang tidaklah didasarkan pada pengenalan langsung terhadap keadaan lingkungan sebenarnya, namun berdasarkan gambaran yang dibuatnya sendiri atau yang diberikan kepadanya oleh orang lain (1922: 25). Seperti yang kita tahu bahwasannya label ‘minoritas’ telah melekat bagi etnis Tionghoa di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda. Selama itu pula sejarah Cina di Indonesia telah banyak membentuk stereotip yang kemudian berkembang di masyarakat menjadi ‘keajegan’ atau kultur sosial. Stereotip itu sendiri lahir dari perspektif-perspektif yang ditimbulkan dari Negara dan masyarakat, baik dari regulasi-regulasi bentukan Negara maupun kehidupan sosial di masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Sehingga kemudian dari perspektif, berkembang menjadi stereotip, dan sampai pada akhirnya lahirlah label 21 ‘minoritas’ tersebut untuk etnis Tionghoa sebagai identitas yang melekat sampai sekarang. Adanya kontinuitas terhadap proses pelabelan tersebut, kemudian seperti membuat ‘zona nyaman’ bagi orang-orang etnis Tionghoa terhadap kehidupan ‘minoritas’ sosial nya di Indonesia, baik kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Indikasi adanya ‘zona-nyaman’ tersebut kemudian menjadi keingintahuan penulis terhadap adanya praktik self-minoritisasi oleh etnis Tionghoa tersebut. Proses self-minoritisasi ini boleh dibilang masih ‘kasat mata’, diluar pemikiran mainstream yang ada di masyarakat bahwasannya label ‘minoritas’ tersebut lahir karena adanya sejarah kelam etnis Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menempatkan proses self-minoritisasi tersebut didalam proses terbentuknya identitas, baik melalui stereotip yang dibentuk oleh Negara maupun masyarakat. Penting untuk diketahui, bahwasannya tulisan ini merupakan salah satu studi psikologi sosial yang mengupas ‘masalah Cina’ terkait label minoritas yang telah melekat dalam kelompok etnis Tionghoa di Indonesia. Psikologi sosial adalah disiplin ilmu yang memahami, menjelaskan dan memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan individu yang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan orang lain yang dilihatnya, atau bahkan hanya dibayangkannya (Gordon Alport, 1968). Hal tersebut dapat dijelaskan melalui adanya respon yang diberikan etnis Tionghoa melalui budaya dan kehidupan sehari-harinya terhadap proses stereotyping yang diberikan oleh pihak Negara dan pribumi, yang kemudian melahirkan proses self-minoritisasi oleh orang-orang Tionghoa tersebut. 22 E. Definisi Konseptual E.1. Identitas dan Kultur Subjektif Merupakan suatu hal yang melekat dalam diri individu yang merupakan hasil konstruksi sosial. Dalam konteks etnis, identitas sendiri dimaknai sebagai suatu ke’khas’an yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok etnis, yang berbeda dengan etnis lainnya, baik dari segi bahasa, adat istiadat, nilai dan norma, maupun kebiasaannya. Dalam praktiknya, konsep kultur subjektif, yakni cara khas suatu golongan kebudayaan dalam memandang lingkungan sosialnya, membantu dalam melihat bagaimana identitas tersebut terbentuk dalam suatu kelompok etnis. E.2. Stereotyping dan Labeling ‘Minoritas’ Terhadap Etnis Tionghoa Dalam pembentukan identitas, stereotip yang lahir dari konsep kultur subjektif berperan sebagai ‘penyumbang’ lahirnya identitas yang melekat dalam diri individu, kelompok, maupun kelompok etnis. Stereotip sendiri adalah kategori khusus tentang keyakinan yang mengaitkan golongan-golongan etnis dengan atribut-atribut pribadi. Kontinuitas Negara dan masyarakat diluar etnis Tionghoa selama berpuluh-puluh tahun dalam stereotyping kemudian memberikan identitas yang sampai sekarang terlestarikan dalam kelompok etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas. Dibalik itu, yang harus kita akui bahwasannya etnis Tionghoa tidak lantas menjadi benar-benar minoritas ketika mereka kemudian justru ‘mengeksklusifkan’ diri ditengah label minoritas yang dilekatkan kepada mereka. 23 E.3. Self-Minoritisasi Self-minoritisasi adalah istilah yang dibuat penulis sebagai suatu proses individu maupun kelompok dalam upaya meminoritaskan diri sendiri. Dalam hubungannya dengan identitas etnis, self-minoritasasi dapat dilakukan dengan berbagai cara internal melalui kebudayaan maupun adat istiadat, kebiasaan individu atau kelompok, yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Selfminoritasasi dalam kasus Tionghoa disebut-sebut terjadi karena kuatnya stereotip yang ada di masyarakat mengenai etnis Tionghoa sehingga mereka merasa insecure untuk kemudian menutup diri dari berbagai hal yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kemudian masyarakat semakin memandang mereka sebagai kelompok minoritas. F. Definisi Operasional Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan cara pandang antara Negara, Pribumi dan etnis Tionghoa tentang bagaimana mereka menilai dan saling melekatkan stereotip satu sama lain. Lebih jauh dikhususkan tentang bagaimana Pribumi dan Tionghoa yang saling melekatkan stereotip yang kemudian membangun sekat dalam kehidupan sosial diantara keduanya. Adanya sekat-sekat pembeda dalam kehidupan sosial Pribumi dan Tionghoa kemudian membentuk sebuah zona nyaman, yang secara sengaja maupun tidak sengaja diciptakan oleh etnis Tionghoa, dimana etnis Tionghoa ‘merasa’ dapat hidup terlepas dari ketidakpastian dan ketidakamanan yang mereka 24 terima ditengah-tengah Pribumi. Kehidupan dalam ‘zona nyaman’ etnis Tionghoa ini meliputi kategorisasi diri dalam hal nilai, norma, kebudayaan serta ‘life style’ yang lebih jauh dipergunakan kelompok etnis Tionghoa sebagai rujukan dalam berkehidupan sosial, hingga akhirnya semakin menguatkan sekat pembeda antara Pribumi dengan Tionghoa melalui stereotip yang semakin dilekatkan oleh Pribumi dan Negara. G. Metode Penelitian Penelitian yang akan dilakukan ini akan mencoba melihat bagaimana pembentukan label minoritas terhadap etnis Tionghoa di Indonesia dilakukan oleh internal kelompok etnis Tionghoa itu sendiri melalui kultur subjektifnya. Disamping dari catatan sejarah yang ada bahwa lahirnya identitas minoritas bagi etnis Tionghoa merupakan hasil konstruksi identitas yang dilakukan oleh Negara dan Pribumi melalui proses stereotyping. Kepentingan utama penelitian ini bukan untuk menghasilkan data yang dapat di perlakukan umum (generalisasi), tetapi lebih merupakan “penggambaran kental” atau “thick description” (cf. Geertz, 1974, h. 45) sehingga pendekatan yang lebih sesuai digunakan adalah pendekatan kualitatif. Digunakannya metode ini dilandasi akan kebutuhan pemahaman terhadap pembentukan identitas kultur subjektif etnis Tionghoa dalam kaitannya dengan proses stereotyping oleh Negara dan Pribumi yang menghasilkan label minoritas bagi etnis Tionghoa. 25 Lebih jauh lagi, bahwa pada konteks penelitian ini realitas yang terbentuk tidaklah bersifat tunggal. Hal ini sejalan dengan anggapan jika penelitian kualitatif menganggap sebuah realitas sosial merupakan hasil konstruksi pemikiran dan bersifat holistis, tidak seperti penelitian kuantitatif yang mengandaikan bahwa realitas sosial bersifat tunggal, konkret dan teramati. 9 Fleksibilitas juga menjadi faktor lain mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian, mengingat kemungkinan ketidaksesuaian data yang diperoleh dari informan atau data lapangan terhadap hipotesis sebelumnya. Dan yang terakhir, penulis memahami bahwa penelitian ini tidak akan bebas nilai dari nilai-nilai yang ada disekitar penulis nantinya. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah etnometodologi. Etnometodologi pada dasarnya adalah ‘anak’ dari fenomenologi Schutzian. Ia mengangkat reflective glance yang dianggap penting oleh Schutz dalam memberikan makna bagi perilaku dalam investigasi sosiologis. Garfinkel, penemu etnometodologi berpendapat bahwa ciri utama etnometodologi adalah ‘reflektif’-nya. Ini berarti bahwa cara orang bertindak dan mengatur struktur sosialnya sama dengan prosedur pemberian nilai terhadap struktur tersebut. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk mewawancarai narasumber yang dirasa berkompeten dan memiliki pengetahuan maupun pengalaman yang cukup mengenai proses stereotyping maupun proses pembentukan identitas apapun terhadap etnis Tionghoa. Target utama penulis adalah narasumber dari etnis Hendarso, Emy Susanti. Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. Dalam Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana: Jakarta. 2007. Halaman 168 9 26 Tionghoa yang mengalami ‘pembatasan’ dalam kehidupan sehari-harinya dan dikenai stereotip oleh lingkungan sekitarnya. Penggunaan etnometodologi dalam penelitian ini juga dibantu dengan metode ilustrative case study yang membantu dalam menggambarkan keadaan psiko-sosial narasumber ketika diwawancarai tentang pengalaman hidupnya sebagai etnis Tionghoa yang termarjinalkan. Wawancara dalam metode etnometodologi diarahkan pada respon etnis Tionghoa terhadap stereotip-stereotip yang berkembang mengenai etnisnya, sehingga penulis kemudian dapat mengetahui bagaimana kemudian mereka bertindak dan menilai struktur sosialnya sama halnya dengan bagaimana prosedur pemberian nilai tersebut dilakukan terhadap etnis mereka. Hal ini yang penulis kira dapat membantu untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana reflective glance itu bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang dinilai sebagai bentuk self-minoritisasi etnis Tionghoa di Jakarta. Dengan demikian diharapkan penulis dapat menemukan makna dari reflektif yang dialami oleh narasumber yang menjadi ciri utama dari etnometodologi. Sementara, studi literatur digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang sekiranya menyokong dan memperkuat argumen penulis dalam penelitian ini. Fenomenologi sendiri menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah dimana peneliti dengan pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan saling pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu. 10 10 Alsa, Asmadi. 2003. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR 27 Dengan demikian, manusia dianggap melakukan hal ini secara terus-menerus serta secara praktis manusia menciptakan dan membuat ulang dunia sosial. Dalam memberikan penilaian dan mencipta dunia, manusia dianggap sangat kompeten dan terampil dalam menjelaskan setting pengalaman sosial setiap hari. Etnometodologi berusaha menggunakan kompetensi ini untuk mengemukakan pemahaman yang semestinya tentang bagaimana dunia sosial bekerja yang tidak diinterpretasikan oleh sosiolog lain. 11 Dalam implementasi observasinya, penulis mencoba melihat bagaimana reflective glance, yang merupakan respon terhadap stereotyping oleh Pribumi dan Negara terhadap etnis Tionghoa kemudian dapat mempengaruhi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, terutama di daerah Pluit dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, serta beberapa daerah di Bekasi. Untuk kemudian, penulis dapat melihat dan menemukan makna atas kebudayaan dan kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa yang mereka jalani sebagai kelompok minoritas sehingga diharapkan penulis akan melihat tahap pengkategorisasian diri yang nantinya akan berujung pada proses self-minoritasasi pada etnis Tionghoa tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui individu yang mempunyai pengalaman pada suatu fenomena melalui teknik observasi dan wawancara sistematik, kemudian membangun deskripsi gabungan mengenai esensi sebuah pengalaman untuk seluruh individu. Deskripsi tersebut terdiri dari kejadian sosial yang dapat diamati lewat indera (what) untuk kemudian memberikan penafsiran terhadap kejadian sosial yang terjadi (how). Kekuatan dari 11 Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. 28 metode ini adalah pendekatan yang holistik, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dari objek yang diamati. Namun disamping itu juga terdapat kelemahan seperti rawan penginterpretasian dan objektivitas, juga penggeneralisasian yang dianggap tidak bisa berlaku secara umum karena membatasi diri pada suatu setting tertentu. G.1. Teknik Pengumpulan Data G.1.1. Objek Penelitian Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan objek penelitian terhadap kelompok etnis Tionghoa golongan menengah keatas di daerah Jakarta. Jakarta sebagai lokasi penelitian ini tidaklah penulis pilih secara acak. Dalam banyak hal, Jakarta sebagai ibukota Negara sekaligus kota metropolitan menarik para pelajar/mahasiswa, kaum professional muda, pebisnis dan aktivis dari berbagai Provinsi untuk datang dan mengadu nasib disana. Dengan demikian Jakarta merupakan percampuran identitas yang majemuk. Kerusuhan anti-China pada Mei 1998 bermula juga di Jakarta, dan inilah kerusuhan yang berlangsung lebih parah dari kota-kota lain. Jakarta merupakan pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia: disinilah kelompok-kelompok lobi Tionghoa dan berbagai organisasi nonpemerintah dapat menyampaikan agenda-agenda mereka kepada pengambil kebijakan. Di Jakarta jugalah dampak berbagai kebijakan resmi pasca-1998 paling cepat kelihatan. Jakarta merupakan tempat yang paling semarak bagi warga Indonesia-Tionghoa untuk mengartikulasikan kembali identitas mereka: dalam beberapa tahun terakhir ini, lembaga-lembaga kursus bahasa Mandarin 29 bermunculan di berbagai tempat, begitu pula pers dan media massa berbahasa Mandarin serta organisasi-orgnanisasi politik, sosial dan keagamaan dikalangan komunitas Tionghoa. Jakarta juga menjadi tempat berbagai identitas ketionghoaan yang berbeda saling berinteraksi. Tidaklah selalu mudah untuk mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan warga ‘Jakarta keturunan Tionghoa’. dalam penelitian ini, istilah ‘Tionghoa Jakarta’ mengacu pada komunitas Tionghoa yang bersifat lintasdaerah yang berasal dari berbagai Provinsi yang berbeda, yang belajar, bekerja, atau bermukim di Jakarta. Istilah ini juga merujuk pada warga Tionghoa ‘asli’ Jakarta, baik encek maupun encim (istilah yang mengandung pengertian lelaki dan perempuan totok dari generasi tua) di kawasan Glodok, Jakarta Pusat, dan para ‘Hitachi’ (Hitam tapi China) atau yang lazim disebut China Betawi di Kota Tangerang. Meskipun penulis tidak melakukan survei di berbagai Provinsi di Indonesia dan mengamati beragam perbedaan identitas ketionghoaan di berbagai daerah, penelitian yang ditulis didalam skripsi ini tidak bisa diabaikan begitu saja hanya karena semata-mata terbatas pada ketionghoaan di Jakarta. Dengan meneliti keragaman komunitas Tionghoa di ibukota ini berarti penulis telah mengkaji berbagai pandangan yang berbeda di dalam satu tempat, yakni Jakarta. 12 G.1.2. Jenis Data Penelitian ini memfokuskan pada proses self-minoritisasi yang mungkin dilakukan etnis Tionghoa atas dasar kultur subjektifnya, baik kebudayaannya 12 Disarikan dari Prawacana dalam buku Yau Hoon, Chang. 2012. Identitas Tionghoa PascaSuharto: Budaya, Politik dan Media. Jakarta. Yayasan Nabil dan LP3ES. 30 maupun kebiasaan mereka. Kita menempatkan etnis Tionghoa sebagai obyek material untuk menjelaskan dan membaca bagaimana sebenarnya identitas yang mereka sandang sampai saat ini sebagai golongan ‘minoritas’ merupakan hasil konstruksi kehidupan mereka sendiri sepanjang sejarah Tionghoa di Indonesia. Untuk itu, penulis dalam penelitian ini membutuhkan data sebagai berikut: 1. Konstruksi historis stereotip terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. 2. Proses stereotyping dan interaksi antara Negara, masyarakat (Pribumi) dan etnis Tionghoa dalam pembentukan identitas ‘minoritas’ untuk etnis Tionghoa di Indonesia 3. Data-data terkait kebudayaan dan kebiasaan etnis Tionghoa di tengah-tengah masyarakat yang bersifat ‘eksklusif’, yang semakin memperkuat batasan dan perbedaan identitas dengan masyarakat etnis lainnya 4. Respon golongan etnis Tionghoa terhadap kehidupan bermasyarakat tersebut yang kemudian dipahami sebagai proses self-minoritisasi. G.1.3. Sumber Data Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa cara, antara lain wawancara, observasi, dan analisis riwayat hidup yang merupakan bagian dari teknik wawancara. Wawancara dalam suatu penelitian adalah semua yang berhubungan dengan aktivitas mencari keterangan dengan 31 perbincangan secara langsung (face to face). 13 Lowongan dalam data yang tidak dapat dicatat dari observasi harus diisi dengan data yang didapat dari wawancara (Paul 1953: 441-442); Koentjaraningrat 1986; 129). 14 Wawancara ini dilakukan dengan etnis Tionghoa dari beberapa golongan yang tesebar dalam beberapa kawasan di Jakarta Utara dan Bekasi, juga dengan masyarakat sekitar yang berinteraksi dengan kelompok etnis Tionghoa tersebut. Beberapa orang yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini antara lain adalah: 1. Monica Suryanata dan keluarga (Etnis Tionghoa golongan menengah kebawah) 2. Jason Iskandar (Etnis Tionghoa, Mahasiswa UGM asal Jakarta) 3. Beberapa pengusaha (Etnis Tionghoa golongan menengah keatas) 4. Masyarakat pribumi (diluar etnis Tionghoa) Kemudian lebih dari itu, wawancara dapat dikembangkan dengan metode analisis life history untuk memperoleh pandangan dari dalam: melalui reaksi, tanggapan, interpretasi, dan penglihatan para warga terhadap dan mengenai masyarakat atau etnis yang bersangkutan, sehingga diperoleh pengertian yang mendalam dan detail. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terkait datadata yang ada dilapangan dengan lokus seperti yang sudah disampaikan sebelumnya serta obyek dan lingkungan terkait data-data yang diperlukan. Lebih jauh penulis juga melakukan obrolan non-formal dengan beberapa actor yang 13 Musta’in Mashud. Teknik Wawancara. Dalam Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana: Jakarta. 2007. halaman 69-70 14 Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 100 32 terkait maupun memiliki peranan dalam proses self-minoritasasi oleh etnis Tionghoa. Dan untuk data-data sekunder, dibantu lewat referensi-referensi dari buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen, baik digital maupun tidak, yang memuat pembahasan-pembahasan terkait dengan etnis Tionghoa maupun fenomenafenomena terkait lainnya. G.1.4. Teknik Analisis Data Pada kenyataannya, analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 15 Reduksi data dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas untuk menggolongkan data, mengarahkan, membuang data-data yang tidak relevan, dan melakukan pengorganisasian atas data dengan sedemikian rupa. Dilanjutkan dengan penyajian data yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan menunjukkan data-data yang relevan tersebut dalam format teks maupun dengan format yang lain, seperti tabel, grafik, dan lain sebagainya. Dan sentuhan terakhirnya adalah verifikasi data atau kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan pemikiran yang mendalam serta kritis atas temuan-temuan yang ada, baik data sekunder maupun primer, juga relevansinya terhadap konsepsi-konsepsi yang menjadi guide dalam penelitian ini. 15 Dikutip dari Miles and Huberman (1994:429) dalam Data Management and Analysis Methods 33 H. Sistematika Penulisan Penelitian ini nantinya akan terbagi kedalam lima bab. Bab pertama merupakan bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab kedua sebelumnya akan me-refresh sedikit tentang siapakah etnis Tionghoa di Indonesia. Kemudian lebih jauh, pada bab dua ini akan dipaparkan perihal konteks penelitian, yakni bagaimana stereotip terhadap etnis Tionghoa pertama kali dikonstruksikan, baik oleh Negara maupun masyarakat pribumi, sampai pada akhirnya ‘terlembagakan’ dalam diri etnis Tionghoa di Indonesia. Bab ketiga akan menjelaskan proses stereotyping dan interaksi antara Negara, masyarakat (Pribumi) dan etnis Tionghoa dalam pembentukan identitas ‘minoritas’ etnis Tionghoa di Indonesia. Kemudian pada bab empat akan dipaparkan hasil observasi dan wawancara penelitian terhadap kebudayaan dan kebiasaan hidup sehari-hari etnis Tionghoa, bagaimana hal tersebut kemudian dimengerti sebagai proses pembentukan identitas etnis Tionghoa, untuk kemudian lebih jauh dipahami sebagai proses self-minoritisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu bab lima, penulis akan mengungkapkan intisari dan kesimpulan dari penelitian ini serta sumbangan apa yang sekiranya mampu diberikan oleh penelitian ini bagi studi mengenai ‘Masalah Cina’ yang masih belum terselesaikan di Indonesia. 34