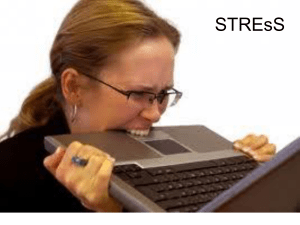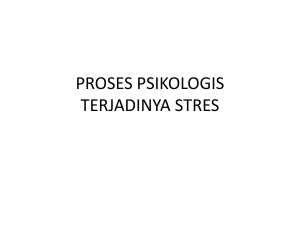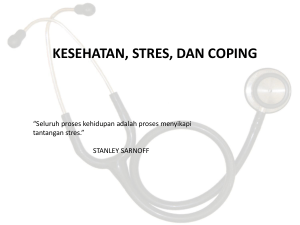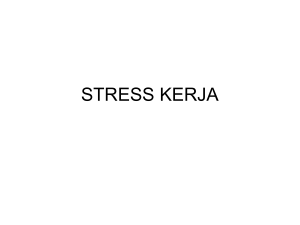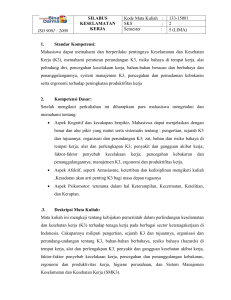14 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kejadian Stres Kerja di Masyarakat
advertisement

14 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kejadian Stres Kerja di Masyarakat Kejadian stres kerja maupun masalah kesehatan mental lainnya pada pekerja dapat diibaratkan sebagai sebuah fenomena gunung es. Kasus-kasus yang terdeteksi hanyalah sebagian kecil dari sejumlah kasus yang luas yang kenyataannya telah terjadi di masyarakat. Masalah ini sudah semestinya menjadi perhatian yang serius dewasa ini. ILO (International Labor Organization) pada tahun 2003 merintis penyusunan peraturan perundangan tentang kekerasan dan stres kerja untuk kalangan praktisi finansial dan profesional (Giga dan Hoel, 2003). Sudah terbukti bahwa stres kerja berkontribusi terhadap terjadinya lesu kerja (Kitaoka-Higashiguchi dkk., 2004; Okada dkk., 2005; Tsai dkk., 2009), berkembangnya perilaku maladaptasi seperti minum-minuman keras dan merokok dan kondisi-kondisi kesehatan seperti depresi (Kawakami, 2010b), kecemasan, kegugupan, penurunan fungsi imunitas tubuh (Male dkk., 2006), kelelahan, gangguan jantung (Baker dan Karasek, 2000; Kawano, 2008) low back pain (Ghaffari dkk., 2008), kerusakan DNA (Inoue, 2009) dan penurunan fungsi kognitif (Seeman dkk., 1997). Selain itu, berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh ILO maka disepakati bahwa stres kerja dapat memicu timbulnya kekerasan di tempat kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas kerja dan kesan terhadap perusahaan serta menurunkan kesejahteraan 14 15 pekerja (Giga dan Hoel, 2003). Berdasarkan data North Western National Life Company, Amerika tahun 1997 ditemukan bahwa 40% pekerja menghadapi stres yang ekstrim dalam pekerjaan mereka. Negara-negara maju yang tergabung dalam Three Post Industrial Countries yaitu negara-negara Uni Eropa, Jepang dan Amerika, sepakat untuk mentaati sepenuhnya hasil-hasil dari “The Tokyo Declaration on WorkRelated Stress and Health” yang telah dilaksanakan pada bulan November tahun 1998 di Tokyo yang menyatakan untuk masa ke depan sangat dibutuhkan kerjasama penelitian-penelitian dan upaya-upaya pencegahan terhadap stres kerja (Baker dan Karasek, 2000; Haratari dan Kawakami, 1999). Data dari The Second European Survey on Working Condition pada tahun 1996 menunjukkan 28% pekerja merasakan bahwa pekerjaan mereka menyebabkan stres. Di Negara Jepang, proporsi pekerja yang dilaporkan mengalami kecemasan yang berat, kekhawatiran atau stres sehubungan dengan pekerjaan atau kehidupan kerja menunjukkan peningkatan dari 53% pada tahun 1982 menjadi 63% pada tahun 1997 (Baker dan Karasek, 2000; Haratari dan Kawakami, 1999). Penelitian oleh Hoel dkk., pada tahun 2001 (dalam Giga dan Hoel, 2003) menemukan bahwa sepertiga komunitas pekerja di negara berkembang mengalami tingkat stres dari tinggi sampai sangat tinggi. Data-data survei lainnya menyatakan 1/3 dari pengalaman kerja pekerja menunjukkan stres di tempat kerja dan adanya peningkatan hampir 50% pengeluaran biaya-biaya perawatan kesehatan bahkan mendekati peningkatan 200% pada pekerja yang mengalami stres dan depresi pada tingkat yang berat. Demikian juga halnya di negara berkembang. 16 Peningkatan ini juga terjadi berdasarkan hasil pengamatan di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, penelitian tentang stres kerja telah beberapa kali dilakukan, diantaranya Prayitno pada tahun 1993, meneliti 52 orang staf di perusahaan minyak lepas pantai menunjukkan bahwa yang terpapar pada stresor berat ditemukan 40,38% dan yang menderita penyakit jantung koroner 4,5%. Penelitian yang dilakukan terhadap perawat wanita di RSUPN dr. Cipto Mangunkusuma Jakarta didapatkan prevalensi gejala gangguan mental emosional sebesar 17,7%. Penelitian yang dilakukan terhadap pilot dan kopilot sipil suatu perusahaan penerbangan di Jakarta didapatkan prevalensi subjek yang status emosionalnya terganggu sebesar 39,4% (Ambarwati, 2004). Berdasarkan laporan dari seorang Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Gani, menyatakan di Indonesia terdapat sekitar 50 juta jiwa penduduk yang mengalami gangguan jiwa. Angka ini berdasarkan atas estimasi WHO yang menyebutkan satu dari empat orang menderita gangguan jiwa (Balitbang Depkes, 1999). Data hasil penelitian Balitbang Depkes pada tahun 1997 menyatakan bahwa 600 ribu jiwa penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa sehingga dalam setahun kehilangan enam juta hari kerja atau Rp. 31,9 triliun (Balitbang Depkes, 1999). 2.2 Stres Kerja pada Pekerja Bank Pekerja bank merupakan kelompok pekerja pada sektor finansial yang dalam pekerjaan kesehariannya bekerja di dalam kantor dan secara rutin mengoperasikan komputer. Saat ini penelitian-penelitian tentang masalah human computer interaction 17 (HCI) dan stres yang ditimbulkannya menjadi semakin diminati. Bidang cognitive ergonomics yang juga termasuk dalam lingkup HCI ini merupakan aspek kajian khusus yang sangat menarik meskipun terasa agak kompleks. Hampir semua aktivitas perkantoran saat ini melibatkan penggunaan komputer. Di masa depan, dampak negatif sedentary work dan stres teknologi pada penggunaan komputer semakin nyata menimbulkan risiko beberapa penyakit yang dihubungkan dengan aktivitas ini, selain dampak positif yang dirasakan sangat membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tergolong rumit. Hampir seluruh waktu kerja karyawan bank adalah jenis pekerjaan pengoperasian komputer dan merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Karyawan melakukan tugas-tugas perbankan sehari-hari yang dominan menggunakan komputer, diantaranya: meng-input data-data tabungan maupun kredit nasabah serta transaksi-transaksi pembayaran melalui perbankan, menyusun laporan kredit bermasalah, penyusunan proposal pengembangan nasabah-nasabah baru dan beberapa laporan rutin yang harus disetorkan tepat waktu kepada pihak Bank Indonesia. Pesatnya kemajuan teknologi perbankan yang melibatkan sistem komputerisasi harus diikuti dengan dukungan sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi ini dengan cepat. Pada umumnya operator komputer menemukan masalah dalam tugasnya akibat gangguan komputer pada saat digunakan dan menimbulkan perasaan stres mental yang bermakna. Selain itu, kekhawatiran pada saat harus mengaplikasikan teknologi baru dalam bidang perbankan dapat menimbulkan sikap negatif sehingga masalah semakin dirasakan kompleks, apalagi 18 diperberat oleh perasaan khawatir akan kehilangan kesempatan kerja (Kroemer dan Grandjean, 2000). Bank Swasta Nasional “X”, tempat penelitian ini dilakukan berlokasi di Denpasar. Merupakan bank komersial yang secara eksklusif melayani sebagai mitra strategis perbankan bagi sektor keuangan mikro Indonesia. Perusahan ini mulai beroperasi sepenuhnya pada tahun 2009, di mana sebelumnya dalam rentang tiga tahun sejak tahun 2006 melewati masa peralihan dari manajemen bank terdahulu yang mengalihkan pengoperasiannya. Investasi perusahan tergolong berskala besar yang melibatkan dana-dana investasi lokal dan asing. Selain memiliki kantor pusat yang berlokasi di Denpasar, perusahaan juga memiliki kantor manajemen pusat yang berlokasi di Jakarta dan kantor cabang di Surabaya. Sebanyak 50 orang (yang bertugas di kantor pusat di Denpasar) karyawan dan karyawati berada di bawah perusahaan ini, dan melakukan aktivitas perbankan dengan target kerja yang tinggi. Waktu kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 WITA, dengan diselingi waktu istirahat makan siang selama satu jam yang dimulai pada pukul 12.00 dan dilakukan secara bergiliran. 2.3 Stres Kerja dari Aspek Fisiologi (Psiko-Neuro-Imunologi) 2.3.1 Definisi stres Pembahasan tentang stres kerja dan dampaknya bagi kesehatan dalam dunia kerja saat ini tidak lepas dari penelusuran materi keilmuan lebih dalam tentang ergonomi yang dipadukan dengan aspek psiko-neuro-imunologi. Telaah tentang ilmu 19 ini banyak diminati pakar ergonomi dan biomedis dewasa ini. Semakin banyak fakta yang dapat membuktikan hubungan antara penurunan produktivitas kerja dan risiko kejadian penyakit infeksi dengan pengalaman emosi yang tidak menyenangkan akibat stres kehidupan ataupun aspek perilaku lainnya. Stres dalam kehidupan maupun pekerjaan tidak bisa dihindari. Mekanismenya melibatkan komunikasi dua jalur antara otak (korteks, regio ventromedial prefrontal) dan sistem kardiovascular, imun (Anonim a, 2003; Anonim b, 2008), dan sistem lainnya melalui sistem saraf otonom dan sistem neuro-hormonal (McEwen, 2007; Li dan Sinha, 2008). Temuan konsep hubungan imuno-behavior berawal dari penelitian dasar yang berfokus pada mekanisme selular dan molekular antara sistem saraf dan sistem imun. Peneliti dalam bidang ini telah menemukan adanya hubungan selular dan aktivitas molekular yang menjelaskan sirkuit neuroimunologis. Hal ini sejalan dengan tingginya ketertarikan para pakar ergonomi dalam mengkaji lebih jauh tentang penyebab dan dampak dari stres kerja terhadap dan kualitas kehidupan kerja. Istilah stres diperkenalkan pertama kali oleh Cannon pada tahun 1914 dan Selye pada tahun 1956 dalam area psikologi dan ilmu kedokteran (McEwen, 2007). Selye mendefinisikan stres sebagai reaksi dari organisme terhadap situasi yang menguntungkan (eustress) dan situasi yang merugikan (distress). Dikatakan bahwa stres penting dalam reaksi berantai dalam mekanisme neuroendokrin. Akibat rangsangan pada sel-sel diotak akan terjadi peningkatan sekresi hormon-hormon terutama adrenalin dan noradrenalin dari kelenjar adrenal. Hormon-hormon ini disebut sebagai hormon penampilan karena berfungsi untuk menjaga tubuh dalam 20 keadaan siaga penuh. Efek dari hormon ini adalah meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah serta meningkatkan gula darah dan metabolisme (Kroemer dan Grandjean, 2000). Menurut Selye dan Mc Ewen, pada prinsipnya mekanisme tubuh terhadap berbagai stresor atau pemicu stres merupakan gambaran yang serupa atau dengan karakteristik tertentu yang dapat dianggap sama. Mekanismenya melibatkan komunikasi dua jalur antara otak dan sistem kardiovaskuler, imun, dan sistem lainnya melalui sistem saraf otonom dan sistem neuro-hormonal (McEwen, 2007). Tubuh akan selalu berespon terhadap stres akibat adanya rangsangan di pusat penerimanya yaitu di hipokampus dan hipotalamus yang terletak dalam area sistem limbik, lalu diikuti reaksi berantai berupa pengaktifan Hypothalamo-PituitaryAdrenal Axis (HPA-axis) dan Sympatetic-Adreno-Medular Axis (SAM-axis) (Appels dan Kop, 2007). Rangsangan dapat berupa stres fisik maupun psikologis. Aktivasi SAM-axis dan HPA-axis tidak hanya menggambarkan respon organisme terhadap stres, tetapi juga penting untuk proses homeostasis normal dan proses metabolisme (Lavallo dan Thomas, 2000, dalam Sonnentag dan Fritz, 2006). Katekolamin dan kortisol memicu mobilisasi energi, menyediakan gula darah untuk aktivitas fisik dan mental, dan meningkatkan sirkulasi darah. Dengan demikian, katekolamin dan kortisol menginisiasi dan mengawali proses yang membantu organisme untuk menghadapi tuntutan kebutuhan. Kortisol memiliki pola sirkadian yang kuat, di mana konsentrasi puncaknya pada pagi hari. Jika dihubungkan dengan stresor, Dickerson dan Kemeny (2004) dalam Sonnentag dan Fritz (2006), menemukan bahwa puncak 21 respon kortisol dapat diobservasi 21-40 menit setelah onset stresor. Hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan penentuan waktu dalam pengukuran kadar hormon ini di dalam darah. Secara fisiologis, menurut Selye, stres dalam istilah umum adalah suatu sindrom yang meliputi repons non-spesifik dari organisme terhadap rangsangan dari lingkungan. Selye membagi proses stres dalam tubuh melalui tiga fase yaitu: (1) fase alarm reaction; (2) fase resistance reaction; dan (3) fase exhaustion reaction. Pada fase I atau alarm reaction (reaksi kewaspadaan), seluruh sistem tubuh diubah menjadi keadaan siaga. Perubahan fisiologis yang terjadi adalah berpusat di hipotalamus yang mengisyaratkan kepada kelenjar adrenal untuk melepaskan adrenalin ke saluran darah. Sebagai akibatnya darah mengalir dari kulit dan visera ke otot dan otak. Hasil redistribusi menyebabkan kulit tampak pucat dan terasa dingin, berdebar–debar, darah mengalir cepat dan bersiap untuk lari atau melawan ancaman yang ada. Pada fase ini juga dilepaskan hormon lain terutama Adenocorticotropin Hormone (ACTH) yang mengaktifkan kelenjar adrenal sehingga kortikoid dilepaskan ke dalam aliran darah yang membawa pesan kelenjar ke organ lain. Limpa dimobilisasi untuk melepaskan lebih banyak sel darah merah ke dalam aliran darah. Lambung melepaskan asam hidroklorik yang digunakan untuk mencernakan makanan. Ada satu hormon lagi yang dilepaskan yaitu nor adrenalin, hormon ini menimbulkan perasaan euforia dan kepuasan. Sedangkan hormon adrenalin dan kortikosteroid dapat dipandang sebagi hormon kecemasan. Fase ini tidak berlangsung lama. 22 Pada fase II yaitu resistance reaction (reaksi pertahanan), tubuh mengerahkan seluruh daya tahannya untuk mengadakan perlawanan terhadap faktor–faktor yang menyebabkan stres. Tubuh berusaha melakukan adaptasi terhadap stres yang terjadi, akan tetapi daya tahan tubuh terbatas. Dalam fase ini daya tahan sudah naik di atas taraf daya tahan normal, dan bila stres terjadi terus–menerus dan berat, maka akan berlanjut ke fase III . Pada fase III atau Exhaustion reaction (reaksi kelelahan), terjadi kelelahan / keletihan sehingga adaptasi yang baru dibangun runtuh. Daya tahan tubuh melemah, energi untuk adaptasi habis dan fase ini berkaitan dengan terganggunya kesehatan individu. Pada umumnya individu akan bereaksi terhadap rasa tidak nyaman yang timbul dari setiap stres dalam bentuk perilaku, kognitif (alam pikiran) dan emosi atau mood. Reaksi ini pada individu dapat muncul sebagai mekanisme penanggulangan. Mekanisme penanggulangan atau mekanisme coping terhadap stres berfungsi sebagai stabilisator yang dapat menolong individu untuk mempertahankan penyesuaian psikososial selama periode stres tersebut. Apabila penanggulangannya berhasil, individu tidak akan menderita penyakit fisik dan gangguan mental-emosional. Sebaliknya apabila mekanisme penanggulangan stres tidak berhasil, maka individu tersebut akan menderita penyakit sebagai proses maladapatasi terhadap stres. Proses maladapatasi terjadi karena fungsi menjaga homeostasis oleh kortisol maupun mediator-mediator lainnya tidak lagi berperan secara fisiologis. 23 Istilah stres dari teori Selye seringkali membingungkan, dan kemudian saat ini populer informasi tentang istilah lain yang lebih jelas menggambarkan pengertian batasan stres yang sifatnya dapat berakibat maladaptif atau merugikan. Menurut McEwen (2007), terdapat dua sisi penting respon stres. Satu sisi, tubuh memberi respon terhadap berbagai pengalaman atau kejadian dengan mengeluarkan mediatormediator kimia, misalnya katekolamin yang meningkatkan frekuensi detak jantung dan tekanan darah. Mediator-mediator tersebut memicu proses adaptasi terhadap stresor yang sifatnya akut. Jadi mempunyai efek proteksi terhadap ancaman fungsi tubuh. Sisi lainnya, peningkatan yang kronis dari mediator-mediator tersebut dapat berakibat perubahan patofisiologis. Adanya mekanisme yang saling berlawanan dari mediator-mediator tersebut, yaitu bersifat memproteksi maupun menimbulkan kerusakan, dan juga karena istilah stres menimbulkan kebingungan untuk dapat menggambarkan kondisi pastinya, maka Sterling dan Eyer (dalam McEwen 2007) memperkenalkan istilah allostasis yang secara literatur berarti achieving stability through change. Istilah ini diartikan sebagai proses aktif dari tubuh memberi respon kepada kejadian-kejadian sehari-hari dan menjaga homeostasis. Karena peningkatan allostasis secara kronis dapat berakibat timbulnya kondisi patofisiologis, maka McEwen memperkenalkan istilah allostatic load atau overload yang mengacu kepada akibat stres yang berlebih atau manajemen allostasis yang tidak adekuat, seperti tidak terhentinya respon tubuh ketika sudah tidak dibutuhkan, tidak bisa memulai respon dengan adekuat terhadap stresor awal, ataupun tidak habituating terhadap stresor yang 24 sama dan berkepanjangan yang pada akhirnya mengganggu respon allostatic (McEwen, 2007; Bellingrath, 2009). 2.3.2 Definisi stres kerja dan job stress model a. Definisi stres kerja Stres kerja dalam bahasa Iggrisnya diistilahkan dalam beberapa term yaitu job stress atau work stress atau work-related stress. Stres kerja adalah kondisi distress (pengertian oleh Selye) atau allostatic load (istilah oleh McEwen) yang dihubungkan dengan faktor pekerjaan akibat stres fisik maupun psikologis. WHO mendefinisikan stres kerja sebagai gambaran reaksi-reaksi tubuh yang muncul ketika pekerja dihadapkan kepada tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengetahuannya, keterampilannya atau kemampuannya dan yang menantang kemampuannya untuk melakukan coping. Reaksi-reaksi yang dimaksud dapat dalam bentuk respon-respon fisiologis, respon-respon emosi, respon-respon kognitif, dan reaksi-reaksi perilaku (WHO, 2007). Stres kerja dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas kerja, penampilan dan kesan terhadap perusahaan. Fenomena tentang stres menjadi semakin jelas diketahui setelah dalam dua dekade terakhir para ahli psikologi dan ahli ilmu-ilmu sosial misalnya McGrath pada tahun 1976, Lazarus pada tahun 1977, Harrison pada tahun 1978, Caplan dkk. pada tahun 1980 dan Cox pada tahun 1985 dan 2006) melakukan penelitian-penelitian detail terutama dalam aspek stres okupasi atau stres yang dihubungkan dengan faktor 25 pekerjaan (Kroemer dan Grandjean, 2000). Pengertian atau definisi work-related stres menurut Cox adalah reaksi emosi dan psiko-fisiologis terhadap aspek yang tidak menyenangkan dan bahaya dari pekerjaan, lingkungan kerja dan organisasi kerja. Merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh tingkat kesiagaan yang tinggi dan distress dan sering dikarenakan oleh perasaan tidak mampu melakukan coping. Definisi ini mengacu pada definisi yang dibuat oleh the European Commission’s Working Group on Stress pada tahun 1997 (Cox dan Griffiths, 2005). Pengertian stres kerja ini tentunya tidak lepas dari pengertian stres yang ditemukan oleh Selye sebelumnya. Sebelum terjadi stres, perlu terdapat stresor atau pemicu stres yang cukup bermakna dan spesifik untuk setiap individu. Penerimaan dan reaksi selanjutnya terhadap stres itu berbeda–beda pada masing–masing individu dan bisa merupakan reaksi yang menyangkut segi fisiologis, psikologis dan tingkah laku. Penelitianpenelitian saat ini tentang stres didasarkan pada asumsi bahwa stres, yang disimpulkan dari gejala-gajala dan tanda-tanda faal, perilaku, psikologik dan somatik adalah hasil dari tidak/kurang adanya kecocokan antara orang (dalam arti kepribadian, bakat dan kecakapanya) dan lingkungannya, yang mengakibatkan ketidak mampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif (Munandar, 2001). Pada umunya kita merasakan stres sebagai suatu kondisi yang negatif, jika mengakibatkan timbulnya suatu penyakit fisik maupun mental atau perilaku yang tidak wajar, hal ini disebut distres. Akan tetapi hipotesis lainnya memberikan penjelasan bahwa sementara stres meningkat, prestasi juga akan 26 bertambah sampai batas tertentu. Bila stres meningkat sehingga melampaui batas tertentu, maka prestasi akan menurun (Kroemer dan Grandjean, 2000; Munandar, 2001). Stres kerja maupun bentuk-bentuk pemicu stres lainnya akan menimbulkan respon biologis yang secara teori hampir sama yang dikenal sebagai general adaptation respons. Efek stres akan diterima oleh sistem limbik. Jalur informasi dapat dihantarkan ke korteks serebri maupun ke bagian lain dalam sistem limbik seperti amigdala, talamus dan terutama ke hipotalamus. Rangsangan pada hipotalamus dapat mengaktifkan HPA-Axis (Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis) dan SAM-Axis (Sympatetic-Adreno-Medular Axis). Hipotalamus menghasilkan CRH (corticotropic releasing hormon) yang memicu sekresi ACTH (adenocorticotropic hormon) dari hipofise. Selain CRH, hipotalamus juga mensekresikan AVP (arginine vasopresin). AVP mengaktifkan SAM-axis. HPA-Axis menghasilkan mediator berupa kortisol, dan SAM-Axis menghasilkan mediator epinefrin dan nor epinefrin. b. Job stres model Perkembangan studi-studi tentang stres kerja dewasa ini tidak terlepas dari konsep teori tentang stres kerja yang pertama kali dipopulerkan oleh Karasek pada tahun 1979. Konsep Karasek ini dikenal sebagai the job demands-control (JD-C) model atau deman-control-support (DCS) model (Kawakami, 2010a; Inoue, 2010). Model lainnya masing-masing adalah Levi‟s model yang populer pada tahun 1972, ”balance theory” of worksite stress yang dipopulerkan oleh Carayon dkk. pada tahun 27 1999, ”person-environment fit” yang populer pada tahun 1980 (Sanders, 2004), NIOSH model (Hurrel dan McLaney, 1988), Effort-reward imballance (ERI) model (Siegrist, 1996), dan sebuah konsep yang dikenal sebagai Organizational Justice Concept (Inoue, 2010, di mana konsep ini melengkapi JD-C model dan ERI model). Dalam penelitian ini, kajian yang dilakukan mengacu pada model stres kerja NIOSH model, yaitu konsep yang secara skematis dapat dilihat dalam skema pada Gambar 2.1. 1. Work environment improvement Job stressors Personal factors Stress reaction Gender, age, personality, marital status Psychological Physical 2. Supervisor education/training Support from supervisors, coworkers, and family/friends Behavioral Illness Disease/Injury Role stress Interpersonal conflict Lack of job control Job overload Responsibility for people Work organization Work and task condition etc. 3. Individualoriented stress management From the US NIOSH Job Stress Model (Hurrell & McLaney, 1988) Buffering factors Gambar 2.1 NIOSH Job Stres Model (Sumber: Hurrel dan McLaney, 1988) Bagan di atas menggambarkan bahwa stresor yang dihubungkan dengan pekerjaan adalah kondisi-kondisi kerja yang memicu reaksi-reaksi akut, atau strain- 28 strain pada pekerja. Reaksi-reaksi tersebut menggambarkan dominan atau tidaknya respon-respon fisiologis maupun perilaku. 2.3.3 Pembangkit stres kerja (stresor) Munculnya reaksi stres dapat sebagai akibat adanya stresor dari faktor pekerjaan (yaitu segala kondisi kerja yang berakibat terjadinya reaksi-reaksi akut, atau berbagai strain pada pekerja) yang dapat berinteraksi dengan tiga faktor lainnya yaitu faktor-faktor individu, faktor-faktor di luar pekerjaan, dan buffer factors (Hurrell dan McLaney, 1988). Interaksi mind-body bekerja melalui dua cara, yaitu: faktor-faktor psikologi dapat berkontribusi terhadap berbagai gangguan fisik, dan sisi lainnya gangguan-gangguan fisik dapat mempengaruhi pikiran dan mood individu (Kroemer, 2009). Masalah-masalah ergonomi yang tidak diantisipasi secara holistik dapat menjadi pembangkit stres kerja. Stres yang intensif dan berlangsung lama berdampak kepada perubahan perilaku dan perasaan. Faktor tugas, organisasi dan lingkungan (termasuk di dalamnya kondisi psikososial akibat relationship yang tidak harmonis) yang tidak sesuai dengan kapasitas pekerja atau dirasakan mekanisme coping tidak adekuat berakibat munculnya respon mal-adaptasi. Respon tersebut dapat berakibat tubuh mengalami kelelahan fisik maupun mental yang pada umumnya lebih dominan tampak sebagai gejala general malaise (Cox dan Griffiths, dalam Wilson dan Corlet, 2005) dan memicu timbulnya mood yang negatif. Tampak dalam skema model stres dalam Gambar 2.1 di atas, bahwa stresor dapat beragam. Umumnya, relathionship 29 yang tidak harmonis adalah stresor yang bermakna (Kawakami, 2010a). Selain itu, tuntutan beban pekerjaan terlalu berat atau terlalu rendah, sangat kompleksnya beban kerja, tanggung jawab yang berlebihan, pekerja tidak punya hak atau tidak diikutkan dalam mengorganisasikan pekerjaan (lack of job control), konflik karena tuntutan yang tinggi akan kualitas dan produktivitas, ketidaknyamanan lingkungan kerja ataupun kurangnya dukungan sosial dari atasan dan teman kerja merupakan bentukbentuk stresor yang ada di tempat kerja (Manuaba, 2005; Kroemer, 2009). Pemahaman yang holistik tentang faktor risiko potensial penyebab stres kerja sangat membantu dalam merancang isi dari suatu program manajemen stres kerja tersebut (Tsutsumi dkk., 2009). Analisis beberapa pakar ilmu kesehatan jiwa menyatakan bahwa proses globalisasi menimbulkan transformasi komunikasi dan informasi di berbagai kawasan dunia yang memberikan dampak terhadap perubahan nilai-nilai sosial dan budaya. Keadaan ini membutuhkan kemampuan penyesuaian dan mengatasi masalah yang tinggi, di samping dukungan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya nilai-nilai sosial budaya yang tanggap terhadap berbagai perubahan. Kondisi demikian sangat rentan terhadap stres, kecemasan, konflik, ketergantungan obat psikotropika, perilaku seksual yang menyimpang yang dapat digolongkan sebagai masalah psikososial (Nasution, 2011). Manuaba (2000) mengatakan bahwa tuntutan pekerjaan (job demand) dan kapasitas kerja harus selalu seimbang, sehingga dicapai kinerja atau performance yang maksimal. Beban tugas yang terlalu tinggi ataupun rendah (underload) dapat menurunkan performance yang terindikasi dari beberapa parameter, seperti: kualitas 30 produk, produktivitas, ketidaknyamanan, kelelahan, stres, kecelakaan dan penyakit. Beberapa variabel yang berperan yang termasuk dalam aspek tuntutan pekerjaan (Gambar 2.2), diantaranya: karakteristik tugas dan tempat kerja, material, organisasi dan lingkungan. Sedangkan variabel-variabel yang menjadi komponen kapasitas kerja yaitu: kapasitas fisiologis dan psikologis (Manuaba, 2000). Karakteristik material Karakteristik tugas/tempat kerja Tuntutan tugas Karakteristik organisasi Karakteristik pribadi Kapasitas fisiologik Kapasitas pekerja Karakteristik lingkungan Kapasitas psikologik Kapasitas biomekanik Kualitas produk Stres Kelelahan Kecelakaan Discomfort Penyakit Injury Produktivitas Performance Gambar 2.2 Hubungan antara tuntutan tugas, kemampuan, dan performance seseorang (Sumber: Manuaba, 2000) Dalam konsep Manuaba pada Gambar 2.2 di atas, dijelaskan bahwa antara tuntutan tugas (task) dengan kapasitas kerja (work capacity) harus selalu dalam kondisi seimbang, tidak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika tuntutan tugas terlalu tinggi melampaui kapasitas kerja akan berakibat tekanan terhadap pekerja, tetapi jika tuntutan tugas lebih rendah individu akan menjadi pasif dan kurang termotivasi 31 Tiga faktor yang mempengaruhi keseimbangan tersebut adalah: (a) Kapasitas pekerja (worker capacity) mencakup: (1) Personal characteristics (karakteristik pribadi) berkaitan dengan faktor usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama dan kepercayaan, status kesehatan, kesegaran tubuh/kebugaran fisik, dan sebagainya; (2) Physiological capacity (kemampuan fisiologis) meliputi kemampuan dan daya tahan kardio-vaskular, saraf otot, panca indera, dan sebagainya; (3) Psychological capacity (kemampuan psikologis) berhubungan dengan kemampuan mental, waktu reaksi, kemampuan adaptasi, stabilitas ekonomi, dan sebagainya; (4) Biomechanical capacity (kemampuan mekanik) berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian, tendon dan jalinan tulang; (b) Tuntutan tugas/aktivitas (task demands) mencakup: (1) Task/workplace characteristics (karakterik tugas/tempat kerja) yang ditentukan oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe, kecepatan dan irama kerja, dan sebagainya; (2) Organization characteristics (karakteristik organisasi) yang berhubungan dengan jam kerja dan jam istirahat, kerja malam dan bergilir, cuti dan libur, manajemen, dan sebagainya; (3) Environmental characteristics (karakteristik lingkungan) yang berkaitan dengan manusia teman setugas, suhu dan kelembaban, bising dan getaran, penerangan, sosial budaya, tabu, norma, adat dan kebiasaan, gas, cairan, debu, dan sebagainya; dan (c) Unjuk kerja (performance). Hasil interaksi antara tuntutan tugas dan kapasitas kerja berupa luaran dalam bentuk performance/unjuk kerja sangat ditentukan oleh rasio dari besarnya tuntutan tugas dengan besarnya kapasitas kerja atau kemampuan individu yang bersangkutan. Apabila tuntutan tugas lebih besar 32 daripada kemampuan seseorang, maka akan memberi dampak pada performance berupa: rasa kurang/tidak nyaman, kelelahan, overstress, kecelakaan, cedera, rasa sakit, dan penyakit. Semuanya akan diikuti dengan menurunnya kualitas performance dan produktivitas. Sebaliknya, apabila kemampuan seseorang lebih besar daripada tuntutan tugas, maka akan terjadi: kejenuhan, kebosanan, kelesuan, munculnya rasa sakit, dan penurunan produktivitas. Agar performance optimal dan maksimal, maka perlu adanya keseimbangan dinamis antara tuntutan tugas dengan kemampuan atau kapasitas kerja seseorang, sehingga tercapai kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif (Manuaba, 2000). Konsep Manuaba ini juga sejalan dengan konsep Kumashiro (2003) tentang produktivitas sumber daya manusia di tempat kerja. Dalam konsep Kumashiro, kapasitas kerja bergantung pada keterampilan, pengalaman dan pengetahuan, yang didukung oleh motivasi kerja (yang dipengaruhi oleh adanya insentif dan faktorfaktor higene) dan kemampuan kognitif. Sebagai dasar dari kapasitas kerja adalah kondisi kesehatan yang mencakup kapasitas fisik, mental, dan fungsi sosial. Konsep Manuaba maupun konsep Kumashiro menjelaskan bahwa kapasitas kerja yang optimal sangat diperlukan pekerja untuk menghadapi tuntutan tugas-tugas/pekerjaan. Dalam kondisi kapasitas kerja yang rendah sementara tuntutan kerja dirasakan semakin kompleks maka stresor akan dirasakan bermakna dan berakibat timbulnya stres kerja. Dalam model stres kerja, selain beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat memicu timbulnya reaksi stres, beberapa faktor lainnya juga dihubungkan sebagai 33 faktor yang dapat memperberat maupun sebagi penetral kondisi stres pada individu (Matteson dan Ivancevich, 1982). Permasalahan dalam keluarga, krisis kehidupan, kesulitan keuangan, keyakinan pribadi dan organisasi yang bertentangan, konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan perusahaan, semuanya dapat merupakan tekanan pada individu dan pada pekerjaannya. Sebagaimana halnya stres di pekerjaan mempunyai dampak yang negatif pada kehidupan keluarga dan pribadi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa peristiwa-peristiwa kehidupan pribadi dapat meringankan akibat-akibat dari pembangkit stres organisasi. Jadi dukungan sosial dan keluarga berfungsi sebagai bantal penahan dari stres. Faktor sosial budaya merupakan faktor yang berperanan penting dalam manajemen stres kerja. Persepsi, perilaku individu, motivasi dan kebutuhan (need) dalam aktivitas sehari-hari sangat dipengaruhi oleh faktor ini. Budaya ke-Timur-an dan tradisi mempengaruhi sikap dan cara individu bereaksi. Sehingga kebijakan perusahaan dan cara-cara komunikasi di tempat kerja antara atasan dan bawahan maupun sesama pekerja yang tidak mempertimbangkan faktor budaya dapat merusak hubungan sosial yang memicu timbulnya stres kerja. Budaya daerah Bali, tempat penelitian ini dilakukan, yang telah menjadi aset bagi industri pariwisata tentunya mewarnai kehidupan pekerja. Pekerja yang terikat adat setempat akan memerlukan kebijakan untuk mendapatkan ijin pada saat harus terlibat dalam acara-acara adat. Jika aturan larangan ijin bagi karyawan oleh perusahaan diterapkan sangat kaku dan tidak empati maka akan menimbulkan konflik bagi karyawan dan dirasakan sebagai tekanan atau stresor (Sutjana, 2010). Selain itu, disediakannya tempat menghaturkan 34 sesajen di tempat kerja yang fungsinya melindungi seluruh karyawan akan memberi perasaan aman dan menyenangkan bagi pekerja (Sutjana, 2010). Sehingga akan menimbulkan suasana kerja yang lebih baik dan berfungsi sebagai buffer terhadap stres. Kecakapan merupakan variabel lain yang ikut menentukan stres tidaknya situasi yang dihadapi. Kecakapan meliputi intelegensia, pendidikan dan latihan yang akan membentuk mekanisme coping dari individu. Jika seseorang menghadapi masalah yang ia rasakan tidak mampu ia pecahkan, sedangkan situasi tersebut ia rasakan sebagai situasi yang mengancam dirinya, maka ia mengalami stres akibat kegagalan mekanisme coping dan menimbulkan ketidak-berdayaan (distress). Sebaliknya jika ia merasa mampu atau mekanisme coping dari individu berhasil, maka ia akan merasa ditantang dan motivasinya meningkat. Dengan menerapkan program manajemen stres kerja diharapkan mekanisme coping individu dimaksimalkan sehingga lebih meningkatkan kapasitasnya dalam mentoleransi stresor (Cooper dan Payne, 1990). Peranan faktor umur pada individu dalam memberikan respon terhadap situasi yang potensial menimbulkan stres tampaknya banyak dipengaruhi faktor lain. Mereka yang usianya sudah lanjut (di atas 60 tahun) jelas menurun kemampuannya dalam beradaptasi, karena adanya penurunan fungsi organ di dalam badan. Penelitian pada kelompok usia lebih dari 40 tahun dan di bawah 40 tahun, dengan indikator adrenalin dan tekanan darah, mendapatkan hasil bahwa kelompok umur di atas 40 tahun lebih rentan dalam menghadapi stres. Menentukan batas umur yang dianggap rentan 35 terhadap stres tampaknya sulit karena berfluktuasi tergantung beberapa hal, antara lain derajat dan beban kerja, bergilir atau tidak bergilir, lingkungan kerja, kecepatan perubahan teknologi dan sebagainya. Faktor perbedaan jenis kelamin tampaknya masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian penulis mengatakan bahwa mungkin faktor jenis kelamin berpengaruh untuk beradaptasi (Evolahti dkk., 2006) tetapi banyak penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna antara pria dan wanita. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bing Wantoro terhadap karyawan perbankan sebuah bank di Jakarta tahun 1996 didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel jenis kelamin terhadap gangguan kesehatan jiwa (Ambarwati, 2004). Faktor sosial budaya sangat berperan dalam mekanisme stres maupun coping individu. Tuntutan dan aturan-aturan/ norma budaya setempat yang dirasakan memberatkan akan menimbulkan konflik dan menimbulkan stres. Di sisi lain budaya tertentu yang memungkinkan individu bisa ”saling berbagi rasa” dalam kegiatankegiatan budaya yang menyenangkan dalam suasana yang hangat akan menjadi buffer dan mengurangi perasaan stres yang dirasakan. Dukungan sosial juga merupakan faktor yang penting bila seseorang menghadapi situasi yang berpotensi terhadap timbulnya stres. Banyak peneliti mencoba untuk mendefinisikan dukungan sosial ini, antara lain mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan perasaan seseorang merasa diperhatikan dan dihargai orang lain, serta menjadi bagian dan diterima oleh komunitas. Peranan dukungan sosial ini sangat besar bagi seseorang dalam menangkal efek buruk dari stres, 36 membuat individu lebih luwes berperan dalam menghadapi stresor tersebut. Biasanya isteri/suami adalah individu yang paling penting dalam hal ini, walaupun anggota keluarga yang lain, teman, atasan juga mempunyai peranan penting dalam mendukung seseorang menghadapi pekerjaan yang penuh stres. Tidak mempunyai dukungan sosial sudah merupakan stres tersendiri bagi individu tersebut. Walaupun secara teori dukungan sosial sangat penting peranannya, tetapi dalam penelitian, masalah dukungan sosial ini sangat luas, meliputi beragam sub-variabel yang harus diukur baik kualitas maupun kuantitasnya. 2.3.4 Pengukuran kondisi stres kerja Diperlukan alat ukur untuk mengevaluasi kondisi stres pada pekerja serta stresor yang muncul sebagai akibat kondisi kerja yang belum ergonomis. Penilaian dimulai dengan mengevaluasi secara umum kondisi kerja memakai mental health action checklist (MHACL) (Kobayashi dkk., 2008; Kogi, 2010) sehingga dapat menemukan permasalahan secara dini dan penerapan strategi pengelolaannya menjadi lebih terukur. Jika dibandingkan dengan ergonomics checkpoints (ILO, 2010), MHACL lebih singkat, mudah diaplikasikan dan lebih mengarah kepada masalahmasalah ergonomi khususnya kondisi-kondisi kerja yang berhubungan dengan risiko pemicu stres kerja maupun risiko gangguan mental lainnya. Menurut Cox (dalam Kroemer dan Grandjean, 2000), stres dapat merupakan kondisi psikologis yang bersifat individual, sehingga sebagai langkah awal, pengukuran stres kerja dapat difokuskan pada kondisi psikologis individu (Kroemer 37 dan Grandjean, 2000; George dan Steven, 2003). Langkah pertama adalah menggali informasi tentang pengalaman emosi atau suasana hati seseorang sehubungan dengan situasi di tempat kerja. Artinya bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan metode yang sifatnya subjektif. Dalam perkembangannya saat ini kebanyakan studi-studi di lapangan tentang stres kerja memakai kuesioner untuk tujuan melakukan survei kondisi-kondisi kerja, stresor yang potensial, kesehatan dan kesejahteraan pekerja, kepuasan kerja dan kondisi suasana hati. Sebagian peneliti mengkombinasikan penggunaan kuesioner dengan pengukuran parameter fisiologis dalam darah (Harenstam, 1990; Söderfeldt dkk., 2000; Theorell dkk., 2001; Persson dkk., 2003; Evolahti dkk., 2006; Kawaguchi dkk., 2007), urin (Lueken dkk., 1997; Goldstein, dkk., 1999; Hansen dkk., 2003; Schnorpfeil dkk., 2003; Bellingrat dkk., 2009; Hansen dkk., 2009;) maupun saliva (Fox dkk., 1993; Steptoe dkk., 2000; Hanson dan Maas, 2000; Kunz-Ebrecht dkk., 2004; Alderling dkk., 2006; Eller dkk., 2006; Harris dkk., 2007; Rydstedt dkk., 2008; Chandola dkk., 2008; Maina dkk., 2009). Pengukuran dengan kuesioner dapat mengukur stresor, reaksi stres baik dalam bentuk respon psikologis maupun fisik serta faktor-faktor yang sifatnya sebagai buffer serta kepuasan kerja (Kroemer dan Grandjean, 2000; NIOSH, 2008; Shimomitsu, dalam Kawakami, 2010a). Dalam penelitian ini, kuesioner yang dipakai adalah kuesioner Brief Job Stress Questionnaire (BJSQ) yang dipublikasikan oleh Shimomitsu pada tahun 2000 (Kawakami, 2010a). 38 Kepuasan Kerja juga dipakai sebagai indikator stres kerja (NIOSH, 2008; Shimomitsu, 2000). Kepuasan kerja juga dihubungkan dengan kondisi-kondisi kesehatan pekerja mencakup masalah-masalah psikologis, seperti lesu kerja, harga diri yang rendah, depresi dan kecemasan (Wada dkk., 2009). Mengacu pada Herzberg‟s two-factors theory, idealnya pekerjaan harus dirancang dengan memasukkan faktor-faktor rewarding untuk menjamin adanya kepuasan kerja (Siregar, 2006; Kroemer, 2009). Kedua faktor tersebut yaitu: faktor motivator (mencakup: promosi, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan perkembangan personal, keterlibatan, tanggung jawab, dan pencapaian); faktor higene (mencakup: kualitas pengawasan, upah, aturan-aturan perusahaan, hubungan dengan orang lain, kondisi kerja dan keamanan kerja). Menurut Herzberg, ada lima faktor yang dapat menciptakan kepuasan kerja, yaitu: pencapaian, keterlibatan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan advancement (Kroemer, 2009). Saat ini, beberapa penelitian menemukan bahwa gangguan muskuloskeletal yang sifatnya akut maupun kronis pada pekerja banyak dihubungkan dengan kondisi emosional di tempat kerja (Rolf dan Rohmet, 1998; Kroemer, 2009; Treaker, 2010). Stres dapat mengakibatkan ketegangan otot yang berakibat rasa sakit terutama pada kepala, leher, bahu dan punggung (Kroemer, 2009; Edwards, 2010). Banyak penelitian yang telah membuktikan adanya kontribusi faktor psikososial terhadap gangguan-gangguan muskuloskeletal yang dihubungkan dengan pekerjaan. Edwards menyatakan, penelitian pertama yang terpublikasi pada tahun 1970-an telah memberi 39 gambaran bahwa job-related stress, dukungan sosial, dan kondisi emosi berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal (Edwards, 2010; Kawakami, 2010b). Stres kerja dan beberapa masalah-masalah lainya yang berhubungann dengan kondisi kerja dan gangguan kesehatan secara umum lainnya dapat menurunkan kemampuan kerja. Untuk mengetahui seberapa besar dampak negatif yang sudah ditimbulkan akibat kondisi tersebut maka perlu dilakukan penilaian dengan menggunakan kuesioner WAI (Tuomi dkk., 1998). WAI adalah alat ukur yang pada saat ini dipakai secara praktis dalam pelayanan kesehatan kerja. WAI mulai disosialisasikan pada saat program yang mempromosikan konsep tentang work ability (WA) pada kisaran tahun 1990 sampai dengan tahun 1996. Dasar dari konsep WA adalah berbagai bukti ilmiah dalam identifikasi faktor-faktor yang meningkatkan maupun menurunkan kemampuan kerja (Ilmarinen, 2003). WA dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu: kapasitas fungsional dan kondisi kesehatan secara umum, kompetensi berupa pengetahuan dan keterampilan, tata nilai berupa sikap dan motivasi, serta kondisi kerja yang mencakup manajemen, paparan di lingkungan kerja dan tuntutan masyarakat. Menurut Ilmarinen, pemantauan WA secara berkesinambungan akan membantu mempertahankan kemampuan kerja karyawan (Ilmarinen, 2003). WA diukur dengan kuesioner WAI yang diciptakan oleh Finnish Institute of Occupational Health pada tahun 1980-an (Tuomi dkk., 1998). WAI dapat dipakai untuk menilai efektivitas program manajemen stres kerja karena telah dibuktikan adanya hubungan antara WAI dengan penilaian kondisi kesehatan mental karyawan di perusahaan (Kumashiro, 2003). Berdasarkan konsep WA (Ilmarinen, 40 2003), peningkatan kemampuan kerja akan diikuti oleh perbaikan kualitas kerja dan produktivitas, kualitas hidup individu dan kesejahteraan. Secara skematis konsep tersebut dapat dilihat pada skema pada Gambar 2.3. Health Functional Capacities Adjustment of work environment Promotion Of Work Ability 45+ Adjustment of psychosocial work environment Professional Competence Good Work Ability, Health and Competence Functional Capacities Good Productivity Good Quality of Work and Quality of Work Life and Well-Being Good Retirement, Meaningful, Successful and Productive “Third Age” Gambar 2.3 Konsep dalam Promosi Work Ability. (Sumber: Ilmarinen, 2003). Secara objektif, salah satu parameter yang dapat dipakai untuk mengukur stres adalah kadar hormon kortisol dalam darah. Selain kortisol, beberapa pameter fisiologis lainnya yang juga dihubungkan dengan kondisi stres diantaranya: 8hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG) (Inoue dkk., 2009), epinephrine dan norepinephrine, dehydroepiandrosterone-sulphate (DHEA-S), waist/hip-ratio (WHR), glycosylated haemoglobin (HbA1c), high-density lipoprotein (HDL), total 41 cholesterol/HDL-ratio, tekanan darah sistolik dan diastolik, tumor-necrosis-factoralfa (TNF-a), C-reactive protein (CRP), fibrinogen, D-dimer, persentase lemak tubuh, trigliserida, dan glukosa darah (Bellingrath dkk., 2009), testosterone, oestrogens, prolactin, melatonin, thyroxin, immunoglobulin (Ig) A, IgG, dan IgM (Hansen dkk., 2009). Studi-studi tersebut dapat mengungkap lebih jelas tentang stres dan dampaknya bagi kesehatan melalui mekanisme biologis. Akan tetapi masih diperlukan penggalian secara lebih mendalam tentang mekanisme perubahanperubahan parameter fisiologis tersebut dalam tubuh akibat stres. Dipakainya parameter kortisol darah untuk menilai efek aplikasi program Ergo-JSI dalam penelitian ini karena perubahan kadar kortisol mampu menggambarkan perubahan mekanisme rangsangan di hypothalamus dan pusat emosi yang berlanjut kepada rangsangan pada HPA-axis dan SAM-axis akibat telah dilakukannya program manajemen stres kerja. Jika dapat dibuktikan perbaikan kadar kortisol menjadi ke kondisi homeostasis, akan memberi gambaran bahwa hormon-hormon lainnya yang berhubungan dengan mekanisme stres maupun marker-marker respon imunitas juga dalam kondisi yang homeostasis. Pengukuran kortisol dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Bali juga aplikatif, karena tergolong pemeriksaan laboratorium rutin yang tidak menyulitkan dalam hal ketersediaan reagen pemeriksaan. Kortisol merupakan glukokortikoid yang dominan pada manusia, dan hormon ini diproduksi dalam zona fasikulata korteks adrenal. Peningkatan konsentrasi kortisol lebih sering dihubungkan dengan situasi mobilisasi energi tubuh. Situasi yang bersifat menantang secara berkepanjangan di sisi lain dihubungkan dengan 42 konsentrasi kortisol yang rendah, dan irama diurnal yang normal yang digambarkan oleh tingginya kadar kortisol darah pagi hari akan tidak tampak. Sekresi kortisol hampir seluruhnya diatur oleh ACTH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Sekresi ACTH diatur oleh hormone pelepas atau faktor-faktor dari hipotalamus berupa CRF (Ueta, 2008). CRF disekresikan ke dalam pleksus kapiler utama dari sistem portal hipofisis di puncak median hipotalamus dan kemudian dibawa ke kelenjar hipofisis anterior, dan CRF merangsang sekresi ACTH. Badan sel neuron yang mensekresi CRF terutama terletak di nucleus paraventrikular hipotalamus. Nukleus ini selanjutnya menerima banyak hubungan saraf dari sistem limbik dan bagian otak bagian bawah. Efek utama ACTH terhadap sel-sel adrenokortikal adalah mengaktifkan adenil siklase dalam membran sel. Adenil siklase ini selanjutnya akan menginduksi pembentukan cAMP dalam sitoplasma sel, mencapai efek maksimumnya dalam waktu kira-kira tiga menit. cAMP ini selanjutnya akan mengaktifkan enzim-enzim intraselular yang menyebabkan terbentuknya hormon adrenokortikal. Langkah yang paling penting dari ACTH yang sudah dirangsang dalam mengatur sekresi adrenokortikal adalah mengaktifkan enzim protein kinase A yang menyebabkan perubahan awal dari kolestrol menjadi prognenolon. Perangsangan dalam jangka waktu panjang pada korteks adrenal oleh ACTH tidak hanya akan meningkatkan aktivitas sekretoriknya namun juga menyebabkan hipertrofi dan proliferasi sel-sel adrenokortikal, khususnya pada zona fasikulata dan retikularis, tempat kortisol dan androgen disekresikan. 43 Kortisol mempunyai banyak fungsi metabolik seperti mengatur metabolisme protein, karbohidrat dan lemak. Efek akhirnya adalah menyediakan pasokan energi untuk mengantisipasi kebutuhan yang meningkat pada saat tubuh teraktivasi, misalnya saat kondisi stres. Peran kortisol dalam membantu tubuh mengatasi stres diperkirakan berkaitan dengan efek metaboliknya. Kortisol menguraikan simpanan lemak dan protein, memperbesar simpanan karbohidrat serta meningkatkan ketersediaan glukosa darah. Peningkatan simpanan glukosa, asam amino, dan asam lemak ini bertujuan untuk mempertahankan nutrisi bagi otak dan menyediakan bahan pembangun untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Keseluruhan mekanisme sekresi kortisol akibat respon stres dan pengaturannya dapat dilihat dalam Gambar 2.4. Gambar 2.4 Mekanisme Pengaturan Kortisol. (Sumber: Guyton dan Hall, 2006). 44 Selain efek kortisol pada sumbu hipotalamus-hipofisis-korteks adrenal, terdapat bukti bahwa ACTH mungkin berperan mengatasi stres. Karena ACTH adalah salah satu dari beberapa peptide yang mempermudah proses belajar dan perilaku, beralasan jika peningkatan ACTH selama proses stres psikososial membantu tubuh agar lebih siap menghadapi stresor serupa di masa mendatang dengan mempermudah individu mempelajari respon perilaku yang sesuai. Selain itu, ACTH bukan satu-satunya produk yang dikeluarkan dari vesikel simpanan di hipofisis anterior. Pemutusan molekul prekursor besar proopiomelanokortin menghasilkan tidak saja ACTH tetapi juga β-endorfin yang mirip morfin dan senyawa-senyawa serupa. Senyawa-senyawa ini disekresikan bersama ACTH setelah mendapat stimulasi dari CRH selama stres. Diduga bahwa β-endorfin, sebagai opiat endogen yang kuat, mungkin berperan menyebabkan analgesia (penurunan persepsi nyeri) seandainya terjadi cedera fisik akibat stres. Selanjutnya juga dispekulasikan bahwa peptide-peptida yang dikeluarkan itu berperan antara lain dalam proses belajar dan perubahan suasana hati. Respon-respon hormonal lain di luar kortisol juga berperan dalam keseluruhan respon metabolik terhadap stres. Sistem saraf simpatis dan epinefrin yang dikeluarkan atas perintahnya menghambat insulin dan merangsang glukagon. Perubahan-perubahan hormonal ini bekerjasama untuk meningkatkan kadar glukosa dan asam lemak darah. Epinefrin dan glukagon yang kadarnya dalam darah meningkat selama stres, meningkatkan glikogenolisis dan (bersama kortisol) glukoneogenesis di hati. Semua efek tersebut berperan meningkatkan kadar gula 45 darah. Selama stres, selain terjadi perubahan-perubahan hormon yang memobilisasi simpanan energi, hormon-hormon lain secara bersamaan juga diaktifkan untuk mempertahankan volume dan tekanan darah selama keadaan darurat. Sistem simpatis dan epinefrin berperan penting dengan langsung bekerja pada jantung dan pembuluh darah untuk meningkatkan fungsi sirkulasi. Selain itu, sistem renin angiotensinaldosteron juga diaktifkan sebagai akibat dari penurunan aliran darah ke ginjal yang dipicu oleh sistem simpatis. Sekresi vasopresin juga meningkat selama keadaan stres. Secara kolektif, hormon-hormon ini meningkatkan volume plasma dengan mendorong retensi garam dan H2O. Diperkirakan peningkatan volume plasma ini merupakan tindakan pencegahan untuk membentu mempertahankan tekanan darah sekiranya terjadi pengeluaran akut cairan plasma melalui perdarahan atau keringat berlebihan selama masa darurat tersebut. Vasopresin juga diperkirakan mempermudah proses belajar, yang berdampak pada adaptasi terhadap stres di masa mendatang. Semua respon individual terhadap stres yang telah dijelaskan di atas dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh hipothalamus. Hipotalamus menerima masukan mengenai stresor fisik dan emosi dari hampir semua daerah di otak dan dari banyak reseptor di seluruh tubuh. Sebagi respon, hipotalamus secara langsung mengaktifkan sistem saraf simpatis, mengeluarkan CRH untuk merangsang ACTH dan kortisol, dan memicu pengeluaran vasopresin. Dengan cara ini, selama stres hipotalamus mengintegrasikan berbagai respon baik dari sistem saraf simpatis maupun sistem endokrin. Hampir setiap jenis stres fisik atau stres mental dalam 46 waktu beberapa menit saja sudah dapat sangat meningkatkan sekresi ACTH dan akibatnya sekresi kortisol juga akan sangat meningkat. Sekresi kortisol ini sering meningkat sampai 20 kali lipat. Rangsangan sakit yang disebabkan oleh jenis stres fisik apapun atau kerusakan jaringan, pertama dihantarkan ke atas melalui batang otak dan akhirnya ke puncak median hipotalamus. Kemudian CRF disekresikan ke dalam sistem portal hipofisis. Dalam beberapa menit seluruh rangkaian pengaturan mengarah kepada sejumlah besar kortisol di dalam darah. Sekresi kortisol bervariasi secara individual. Rentang kadar normal kortisol dalam darah dipengaruhi secara diurnal. Kadar paling tinggi pada pagi hari dan paling rendah sekitar tengah malam. Efek ini dihasilkan dari perubahan siklus sinyal dari hipotalamus selama 24 jam. Bila seseorang mengubah kebiasaan tidur sehari-harinya, maka akan timbul perubahan siklus ini juga. Salah satu alasan mengapa siklus ini begitu penting adalah karena pengukuran kadar kortisol dalam darah hanya akan berarti bila dinyatakan dalam istilah waktu dari siklus sewaktu pengukuran itu dibuat (McPhee dan Ganong, 2006; Guyton dan Hall, 2006). Secara teori, kortisol yang tinggi di dalam darah dapat berakibat gangguan penampilam kognitif, mengubah suasana hati dan perilaku, serta dihubungkan dengan sejumlah masalah kesehatan lainnya seperti penurunan imunitas dan respon-respon peradangan dengan segala konsekuensinya (Sherwood, 2001; Hughes, 2005; Hansson dkk., 2008). Banyak penelitian yang belum bisa membuktikan hubungan yang kuat antara marker-marker biologi seperti halnya kortisol terhadap tingkat stres. Wiholm (2006) 47 dalam penelitian ekperimental pada 116 orang insinyur perancang sistem dan perangkat lunak sistem telekomunikasi, menemukan bahwa program intervensi stres manajemen dapat menimbulkan perubahan marker biologi dalam tubuh. Dalam penelitian ini dicoba memakai penanda biologi dengan mengukur kortisol darah sebagai alat diagnostik dan mengevaluasi keberhasilan program pengendalian stres di tempat kerja. Peneliti lain juga melakukan pengukuran parameter biologi lainnya sehubungan dengan stres kerja. Parameter-parameter tersebut diantaranya: kadar hormon prolaktin darah, testosteron, dan dehidroepiandosteron (Wiholm, 2006), selain penelitian oleh Hughes (2005) yang memakai parameter kadar kortisol darah yang ternyata mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Penelitian oleh Theorell dkk. (2001) sejalan dengan penelitian oleh Hughes, membuktikan bahwa kadar kortisol yang tinggi dapat diturunkan secara signifikan dengan teknik manajemen stres dalam bentuk program pelatihan pada supervisor maupun penerapan program relaksasi (Theorell dkk., 2001; Hughes, 2005). Tetapi penelitian lainnya mendapatkan hasil yang menunjukkan belum ditemukan perubahan kadar kortisol darah yang signifikan sebagai efek stres kerja dan manajemennya. Tampaknya perbedaan teknik manajemen stres akan mempengaruhi kuatnya pengaruh manajemen stres terhadap kadar kortisol darah. Sehingga masih dibutuhkan penelitian-penelitian pada saat ini untuk menguatkan teori-teori yang ada serta menemukan jenis marker biologi yang benar-benar dapat menjadi alat bukti secara objektif tentang efektifitas penerapan program manajemen stres di tempat kerja. 48 Chida dan Steptoe (2008) dalam penelitian meta-analisis menyatakan bahwa kadar kortisol darah pagi hari mempunyai hubungan yang positif terhadap stres kerja dan stres kehidupan secara umum. Menurut Hughes (2005), kadar kortisol yang tinggi dalam darah sudah terbukti dapat diturunkan dengan teknik manajemen stres berupa program relaksasi. Pada penelitian ini, dengan peningkatan kemampuan coping dan turunnya stresor eksternal yang terjadi oleh efek intervensi manajemen stres pada individu dapat memberi efek penurunan kadar kortisol darah. 2.4 Peranan Aplikasi Ergonomi dalam Manajemen Stres Kerja 2.4.1 Aspek legal manajemen stres di tempat kerja Besar tidaknya masalah stres kerja bukan merupakan acuan untuk dilaksanakan ataupun tidaknya program manajemen stres di tempat kerja. Upaya pencegahan yang adekuat serta penanganan secara dini kondisi stres pada pekerja dapat menurunkan biaya-biaya kompensasi serta meningkatkan produktivitas kerja. Program manajemen stres kerja bertujuan menerapkan berbagai teknik untuk membantu pekerja mengatasi stres. Targetnya adalah menurunkan jumlah pekerja dengan keluhan psikosomatik dan mangkir yang diakibatkannya serta meningkatkan kepuasan kerja (Direktorat Bina Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, 2007). Dasar hukum dari program ini adalah UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis; dan UU No.13 tahun 2003 49 tentang ketenagakerjaan pasal 4 yang menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan antara lain membudayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Depkes RI, 2007). Landasan hukum lainnya adalah: UU no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Kepmenaker 02/1980 tentang pemeriksaan kesehatan, Kepmenaker 03/1982 tentang pelayanan ksehatan kerja, Kepres no. 22 tahun 1993 tentang penyakit akibat kerja, Permenaker 04/1987 tentang P2K3 dan UU no 3/92 tentang asuransi kesehatan (Jamsostek) (Nasution, 2011). 2.4.2 Ergo-JSI, sebuah program manajemen stres kerja yang berbasis ergonomi Istilah manajemen stres dipakai oleh karena stres tidak bisa dihindari dan merupakan komponen kehidupan. Prinsip dasar program manajemen stres di tempat kerja hendaknya memakai prinsip ergonomi. Pendekatan ini dapat dilakukan dalam semua tahap program manajemen stres kerja secara umum, yang menurut Kompier dan Cooper (2008) mengelompokkan aktivitas program manajemen stres dalam bentuk pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam merancang program manajemen stres kerja, faktor budaya harus menjadi landasan penyusunan program, agar program dapat bermanfaat secara maksimal. Sutjana (2010) menyatakan bahwa implementasi ergononomi harus selalu mempertimbangkan faktor budaya agar implementasi dapat berhasil dengan sukses. Masyarakat Bali dikenal memiliki keterkaitan dengan faktor budaya yang sangat kuat. Sistem religius yang memberi corak pada sistem sosial sangat kuat mempengaruhi 50 aktivitas masyarakat sehari-hari baik dalam bekerja maupun aktivitas di luar pekerjaan. Sistem religius ini idealnya dapat menjadi buffer dalam mekanisme stres yang dirasakan. Akan tetapi faktor kepribadian juga tampaknya akan sangat kuat mempengaruhi apakah sistem buffer ini dapat maksimal ataupun tidak. Sehingga meskipun individu sudah memiliki sistem religius yang kuat akan tetap memiliki risiko mengalami stres kerja yang tentunya membutuhkan manajemen yang sesuai. Saat ini belum banyak industri-industri yang menyadari sepenuhnya akan manfaat dilakukannya program manajemen stres di tempat kerja. Masalah-masalah psikologis pekerja sering terlupakan dan belum dianggap sangat berperan dalam penampilan kerja maupun produktivitas kerja. Penelitian tentang manfaat program manajemen stres terhadap kapasitas individu dalam mengantisipasi stres dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai negara. Penelitian oleh Williams dkk., (2009) pada 110 orang pekerja yang merupakan partisipan sebuah grup pelatihan William LifeSkills dari berbagai daerah di Amerika, menemukan bahwa program manajemen stres yang berisi program peningkatan kemampuan coping dapat menurunkan faktor-faktor risiko gangguan kesehatan. Di Indonesia sampai saat ini upaya-upaya penerapan strategi manajemen stres kerja di masyarakat industri tampak belum memuaskan. Banyak perusahaan yang belum menyadari akan dampak buruk dari kondisi stres kerja yang ternyata telah dialami oleh karyawannya. Termasuk juga dalam aktivitas penelitian. Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia masih terbatas pada penemuan fakta-fakta 51 tentang kejadian stres kerja pada karyawan (Ambarwati, 2004). Belum sampai kepada penemuan strategi yang efektif sebagai solusi dari kondisi tersebut. Upaya-upaya untuk menemukan sebuah program manajemen stres di tempat kerja sedang terus dilakukan oleh pelaku-pelaku industri dan pakar-pakar kesehatan kerja. Banyak jenis program yang mengutamakan program relaksasi berupa meditasi yang tentunya masih perlu dibuktikan efektifitasnya. Sehingga dunia kerja masih tetap berhadapan dengan masalah dalam menemukan sebuah program manajemen stres yang aplikatif dan dapat dijalankan secara berkesinambungan. Menurut Manuaba (2005), penerapan ergonomi merupakan penerapan ilmu yang menempatkan manusia sebagai unsur pertama, terutama kemampuan, kebolehan dan batasannya. Ergonomi merupakan bidang ilmu tentang teori dan aplikasi yang bertitik tolak kepada usaha menciptakan keserasian antara pekerja dengan kondisi kerjanya. Tujuan ergonomi adalah mempelajari interaksi antara manusia dan elemenelemen lainnya dalam sistem untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan penampilan seluruh sistem (Caple, 2009). Dengan mengerti dan melaksanakan ergonomi, dapat membangun pengetahuan tentang karakteristik manusia, kapabilitas maupun kapasitas dan keinginan-keinginan, yang berperan secara mendasar dalam kepuasan manusia dan kemudian dimanfaatkan pengertian tersebut untuk memperbaiki interaksi antar individu terhadap sesuatu yang digunakan dan terhadap lingkungan di mana individu melakukan sesuatu (Axelsson, 2000; Manuaba, 2005; Wilson, 2005). Penerapan ergonomi juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi, 52 komitmen, tercapainya kualitas produk ataupun produktivitas serta kepuasan kerja yang tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Sehubungan dengan manajemen stres, penerapan ergonomi bertujuan untuk mengubah peralatan, metode, informasi dan lingkungan kerja agar tidak cepat dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres (Munandar, 2001; Manuaba, 2005). Menurut Munandar, secara umum perubahan yang dilakukan dapat mencakup perubahan organisasi, cara kerja, peralatan, kondisi lingkungan fisik, misalnya bising, getaran, tekanan panas atau dingin yang ekstrim dan faktor berbahaya lainnya melalui peningkatan otonomi dan kontrol terhadap fungsi tugas dan jadwal kerja. Melalui analisis yang holistik dapat dirancang organisasi atau pola pekerjaan baru yang secara umum menggambarkan kondisi kerja yang lebih ergonomis dan mengacu pada prinsip perbaikan tiada henti (Munandar, 2001; Khai dan Kawakami, 2002; Kumashiro dkk., 2007). Secara teori, program manajemen stres dapat diawali dengan identifikasi kondisi kerja yang menimbulkan stres pada pekerja. Langkah selanjutnya adalah perancangan dan implementasi intervensi yaitu pemilihan dan aplikasi teknik-teknik peningkatan kapasitas kepribadian dan penerapan ergonomi sesuai dengan permasalahan yang ada, dan diakhiri dengan evaluasi keberhasilan program (Pheasant, 1991; Debra dkk., 1996; Susy-Purnawati, 2007). Langkah-langkah dalam program ini hendaknya dilaksanakan dengan pendekatan ergonomi partisipatori agar keberhasilan program menjadi lebih nyata dan berkesinambungan. Pendekatan ini telah mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan bersifat partisipatif. 53 WHO memberi acuan tentang strategi mengelola stres kerja yang mencakup lima langkah. Langkah-langkah yang dimaksud dapat dilihat dalam bagan pada gambar 2.6. 1. Detecting signs of work-related stress and taking preparatory actions 5. Evaluating the intervention (s) 4. Implementing an action plan 2. Analysing risk factors and risk groups 3. Designing an action plan Gambar 2.6 Process of Stress Prevention (Sumber: WHO, 2007) Konsep WHO tersebut di atas dapat dijadikan acuan tahap-tahap perancangan maupun pelaksaan termasuk evaluasi program, tetapi harus diingat bahwa dalam setiap tahap prinsip-prinsip ergonomi partisipatori harus selalu diaplikasikan dan menjadi jiwa dari program. Idealnya penyelenggaraan program manajemen stres yang paripurna memerlukan internal resources, yaitu tim yang terdiri dari: occupational health services, human resources management/personnel, training department, orang lain yang punya tanggung jawab dalam kesejahteraan dan kesehatan pekerja, dan external resources yang terdiri dari ergonomist, psikolog, counselor dan dokter kesehatan kerja. Sebuah program manajemen stres yang diperkenalkan dalam penelitian ini adalah berupa program penerapan ergonomi, yang diberi nama program manajemen stres kerja Ergo-JSI. Nama Ergo-JSI merupakan singkatan dari ergonomics job stress intervention. Program Ergo-JSI ini memadukan upaya-upaya penerapan ergonomi 54 dan peningkatan kemampuan individu dalam mekanisme coping, serta mempertimbangkan faktor sosial budaya setempat sehingga perbaikan bersifat aplikatif dan berkesinambungan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya Ergo-JSI merupakan manajemen stres kerja dengan pendekatan organisasi dan berorientasi individu. Pendekatan organisasi yang dimaksud dalam Ergo-JSI mencakup perbaikan karakteristik pekerjaan (task), perubahan organisasi, dan perbaikan kondisi lingkungan kerja. Perubahan dalam aspek organisasi berupa perubahan kondisi kerja termasuk proses pengambilan keputusan (misalnya peningkatan partisipasi karyawan terhadap keputusan yang relevan), mengupayakan terciptanya iklim dukungan termasuk umpan balik yang lebih membangun dalam hal penampilan kerja, serta mengupayakan sistem distribusi reward yang adil. Mengingat adanya keterbatasan sumber daya dalam penelitian ini, tentunya beberapa perbaikan kondisi kerja dilakukan hanya berdasarkan prioritas masalah yang disepakati secara partisipatori bersama pihak perusahaan. Pendekatan partisipatori dalam perbaikan kondisi kerja terbukti dapat menghasilkan perubahan secara maksimal. Kelebihan dari pendekatan partisipatori sudah terbukti dalam beberapa upaya perbaikan kondisi ergonomi di tempat kerja (Khai dan Kawakami, 2002; Manuaba, 2003a; Kumashiro dkk., 2007; Manuaba, 2008; Kogi, 2008; Manothum dkk., 2008). Perbaikan kondisi kerja dalam Ergo-JSI dilakukan dengan memaksimalkan peran personal-personal di bagian electronic data processing (EDP) dalam mengantisipasi perangkat lunak sistem perbankan yang harus dioperasikan secara komputerisasi oleh karyawan. Akses kepada personal EDP dibuat menjadi lebih 55 terbuka untuk mengantisipasi setiap gangguan dalam proses kerja yang berhubungan dengan teknis komputerisasi. Hal ini dapat mengurangi stres teknologi yang merupakan stresor umum pada pekerja yang bekerja memanfaatkan teknologi komputer. Ergo-JSI juga memuat perbaikan kondisi kerja dengan cara melakukan perbaikan postur kerja karyawan, pengaturan waktu kerja dan istirahat agar pengorganisasian tugas menjadi lebih ergonomis yang bertujuan untuk mengurangi kelelahan pada saat mengoperasikan komputer. Secara teori kelelahan yang berlebihan dapat memicu mood negatif (perasaan tidak nyaman) pada pekerja. Lingkungan kerja yang didominasi oleh masalah kurangnya intensitas penerangan diperbaiki dengan cara memaksimalkan sistem pencahayaan alami dan pengaturan posisi stasiun kerja terhadap arah pencahayaan. Menurut Kroemer (2009), pemanfaatan penerangan alami dapat meningkatkan kenyamanan dan memciptakan perasaan menyenangkan bagi individu. Perbaikan kondisi kerja tentunya mempunyai batasan-batasan karena harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan (mencakup prioritas dan pertimbangan sumberdaya yang ada). Selain itu, mengacu pada Towner (2002), bahwa makin ke depan sumber permasalahan kondisi kerja tentunya juga semakin kompleks. Sedangkan sumber daya yang ada belum mencukupi untuk melakukan perbaikan kondisi kerja secara menyeluruh secara serentak. Sebuah prinsip aplikasi ergonomi yang juga bisa menjadi acuan adalah prinsip do more with less. Keterbatasan ini menjadi alasan bahwa program manajemen stres Ergo-JSI juga dibuat berorientasi individu. Pendekatan ini diaplikasikan melalui pelatihan peningkatan 56 kemampuan/keterampilan problem focus coping individu (Hawari, 2002; Shimazu 2010; Smith, 2002). Pelatihan peningkatan kemampuan coping dalam program ErgoJSI bertujuan untuk dapat mengubah stresor yang membangkitkan respon negatif (di area sistem limbik otak) dapat dipersepsikan berbeda menjadi respon yang lebih positif oleh individu (Montgomery, 2008), sehingga individu akan mampu memaksimalkan fungsi kognitif dalam mencari solusi dari setiap kondisi yang tidak menyenangkan di tempat kerja serta berpikir tentang masa depan (memaksimalkan fungsi kognitif tingkat tinggi/fungsi luhur otak manusia). Yang dimaksud dengan pemberdayaan mekanisme coping adalah upaya dalam bentuk peningkatan keterampilan problem-focus coping yaitu personal skill training dan manajemen waktu (Smith, 2002; Shimazu, 2010). Personal skill training dapat disesuaikan dengan jenis stresor yang dihadapi pekerja. Hal yang mencirikan bahwa Ergo-JSI merupakan program manajemen stres kerja yang berbasis ergonomi, salah satunya adalah rancangan pembelajaran manajemen stres dalam kelas yang dibuat ergonomis. Isi program juga mencakup strategi manajemen stres kerja yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi sosial budaya karyawan di Indonesia. Isi program yang utama selain melakukan perbaikan kondisi kerja agar faktor penyebab stres yang berasal dari lingkungan kerja dapat diturunkan juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kondisi emosi dan kognitif sehubungan dengan peristiwa stres kerja serta meningkatkan keterampilan individu dalam aspek komunikasi yang asertif dan keterampilan manajemen waktu. Pemberdayaan individu yang didapatkan dari aplikasi program manajemen stres 57 Ergo-JSI akan menjadi modal utama bagi karyawan dalam meningkatkan penampilan kerja dan membentuk pertahanan yang kuat terhadap risiko stres kerja ataupun penyakit psikosomatis yang dihubungkan dengan pekerjaan. Faktor budaya merupakan faktor yang berperanan penting dalam mekanisme timbulnya stres kerja. Perbedaan budaya dapat berakibat timbulnya hubungan kerja yang tidak harmonis yang memicu stres kerja jika masing-masing individu tidak menerapkan keterampilan komunikasi yang memadai. Salah satu materi pembelajaran manajemen stres dalam kelas yang diberikan dalam Ergo-JSI memaparkan tentang peranan faktor budaya terhadap timbulnya stres dan juga menjadi pertimbangan dalam penanggulangan stres. Secara mekanisme biologi, program ini dapat menurunkan risiko penyakit akibat maladaptasi terhadap stres. Mekanismenya melibatkan proses dikendalikannya kemungkinan pengaktifan berkepanjangan SAM-axis dan HPA-axis pada kondisi stres yang memicu reaksi-reaksi sebagai respon neuro-hormonal yang menjauhi keadaan homeostasis dalam tubuh. Selain itu, program manajemen stres Ergo-JSI juga dapat meningkatkan kemampuan kerja individu. Langkah-langkah penerapan program secara lebih rinci mengacu pada teori-teori ergonomi akan diuraikan dalam paparan berikut. 58 2.4.3 Identifikasi kondisi stres pada pekerja, analisis karakteristik tugas, organisasi dan lingkungan kerja. Identifikasi kondisi stres pada pekerja dilakukan untuk mengetahui besarnya masalah stres di tempat kerja dan faktor pencetusnya. Identifikasi stres dapat dilakukan dengan kuesioner-kuesioner yang disertai dengan pemeriksaan beberapa parameter fisiologis yang berhubungan. Dalam waktu yang bersamaan juga perlu dilakukan evaluasi kondisi kerja untuk mengetahui adanya stresor yang berhubungan dengan faktor pekerjaan dan mencari beberapa alternatif solusi untuk mengantisipasi stresor tersebut. Kegiatan ini dapat menggunakan ergonomic check point (ILO, 2010) dan checklist lainnya (menggunakan metode focus group discussion) (Corlett, 2005) yang menggambarkan kondisi kerja secara umum. Salah satu checklist yang dipakai dalam penelitian ini adalah Mental Health Action Checklist (MAHCL) (Yoshikawa dkk., 2007). Dari kegiatan identifikasi ini dapat diketahui jenis stresor yang ada di tempat kerja. Pada langkah perancangan dan implementasi teknik-teknik manajemen stres hendaknya sudah mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik dan melibatkan partisipasi dari berbagai komponen yang akan terlibat, sehingga dapat ditemukan pilihan cara-cara manajemen stres yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kondisi pekerja. 2.4.4 Perbaikan kondisi kerja dalam aspek karakteristik tugas (task) Karakteristik pekerjaan di industri perbankan saat ini didominasi oleh aktivitas pengoperasian komputer dalam mengaplikasikan teknologi perbankan 59 terkini. Teknologi informatika yang berkembang sangat pesat membuat pengguna merasa sangat bergantung pada teknologi ini. Tidak dapat dipungkiri lagi dampak positif dari pemanfaatan teknologi komputer. Akan tetapi, seirama dengan perkembangan teknologi ini, muncul juga beberapa dampak negatif dari aspek human computer interaction ini. Kemampuan kognitif dalam penguasaan teknologi komputer sangat dituntut agar kinerja bisa optimal. Gangguan-gangguan software maupun hardware komputer saat pengoperasian akan menjadi stresor yang sangat bermakna bagi penggunanya. Beban kerja yang terlalu komplek ataupun terlalu ringan, dan sikap kerja yang sedenteri dalam waktu berkepanjangan juga menjadi sumber masalah kesehatan dalam jangka waktu lama. Pengaturan waktu istirahat aktif dan waktu kerja yang tidak ergonomis akan berakibat kelelahan muncul lebih cepat. Jenis pekerjaan yang tergolong monoton juga akan menjadi stresor dan berakibat lesu kerja dan penurunan produktivitas kerja. Penerapan ergonomi dalam bentuk pengaturan beban kerja kuantitatif maupun kualitatif, perbaikan stasiun kerja dan sikap kerja merupakan solusi dari permasalahan di atas. Sikap kerja yang ergonomis didukung oleh pengaturan istirahat aktif yang memadai akan mebantu melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Sistem eliminasi bahan-bahan sampah metabolisme juga menjadi semakin baik, dan tubuh terhindar dari kelelahan yang bermakna. Variasi tampilan data dan jenis tugas dalam pekerjaan komputerisasi mampu menghilangkan kebosanan dan perasaan stres sehingga pada akhirnya meningkatkan penampilan dan kepuasan kerja. Beban kerja yang sangat berat dan kompleks melebihi kapasitas kerja akan membuat individu 60 merasa frustrasi dan muncul perasaan stres dengan segala konsekuensinya (Tsai dkk., 2009). Analisis tugas yang seksama dilanjutkan dengan redisain penugasan yang mempertimbangkan kemampuan, kebolehan dan batasan akan memaksimalkan kapasitas kerja dan pada akhirnya tercapai produktivitas kerja dan kepuasan kerja yang tinggi. 2.4.5 Perbaikan kondisi kerja dalam aspek organisasi Pengaturan organisasi kerja merupakan hal yang sangat menarik dan memerlukan kreativitas tinggi untuk bisa diterapkan secara aplikatif. Menurut Manuaba (2005), perpaduan antara konsep total quality management dengan konsep ergonomi akan menciptakan kualitas produk yang mampu bersaing dan produktivitas kerja yang tinggi disertai oleh kondisi kerja yang lebih manusiawi. Keterlibatan semua lini dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah perbaikan dalam organisasi kerja. Line produksi yang dirancang secara ergonomis menjadi jaminan tercapainya produktivitas kerja yang tinggi. Kesempatan masingmasing individu dalam sistem kontrol atas pekerjaannya, serta kemungkinan adanya fleksibilitas dalam target kerja dapat mencegah pekerja mengalami stres kerja. Faktor lainnya yang juga berperan dalam menurunkan risiko stres kerja adalah sistem supervisi yang friendly, adanya jaminan akan karir, kejelasan peran dan garis penugasan, dukungan sosial baik dari teman sekerja maupun atasan, budaya organisasi yang positif, iklim komunikasi yang penuh keterbukaan antara pimpinan 61 dan bawahan, serta sistem rewards yang mengacu pada pertimbangan atas prestasi kerja dan senioritas (grading system). Adanya perimbangan antara waktu kerja dan istirahat juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pengaturan organisasi kerja. Istirahat seringkali diartikan sebagai hal yang dapat mengurangi angka produktivitas kerja. Konsep U-shape telah memberi gambaran dengan jelas bagaimana lama jam kerja dihubungkan dengan produktivitas (Grandjean, 2000). Karasek (1992), dalam metaanalisisnya menyatakan bahwa program pencegahan stres telah terbukti selain berdampak bagi kesehatan pekerja juga meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas tampak lebih jelas pada program yang melakukan perbaikan dalam organisasi selain intervensi stres yang sifatnya sebagai pendekatan individu. Perbaikan kondisi kerja atau organisasi dilakukan dengan pendekatan ergonomi partisipatori agar sistem kerja dan produksi menjadi lebih manusiawi, mampu bersaing dan berkesinambungan (Manuaba, 2005; Kogi, 2008; Sutajaya, 2009 ; Tsutsumi dkk., 2009). Perubahan dalam aspek organisasi berupa: reorganisasi garis kekuasaan, restrukturisasi unit-unit organisasi, perubahan dalam proses pengambilan keputusan (misalnya peningkatan partisipasi karyawan terhadap keputusan yang relevan), mengupayakan terciptanya iklim dukungan termasuk umpan balik yang lebih membangun dalam hal penampilan kerja, mengupayakan sistem distribusi reward yang adil (Cooper dan Payne, 1990; Munandar, 2001; Manuaba, 2005). Program perbaikan harus dilakukan secara partisipatori berdasarkan hasil analisis kerja serta mengacu kepada prinsip upaya perbaikan yang berkesinambungan (Khai 62 dan Kawakami, 2002; Kumashiro dkk., 2007; Kogi, 2008). Melalui penerapan ergonomi partisipatori dapat dirancang organisasi, pola pekerjaan baru bagi pekerjaan yang dirasakan memiliki beban berlebihan serta risiko bahaya atas suatu pekerjaan dapat dikurangi. Beban kerja kuantitatif berlebihan dapat dikurangi dengan rotasi kerja maupun penambahan tenaga kerja, sedangkan beban kerja kualitatif berlebih dapat dikurangi dengan mengurangi derajat kemajemukan keterampilan yang diperlukan ataupun tanggung jawab dari seorang pekerja. Sebaliknya bagi pekerjaan dengan beban terlalu sedikit dapat dilakukan job enlargment maupun job enrichment (Khai dan Kawakami, 2002; Manuaba, 2005; Kumashiro dkk., 2007). Pembelajaran manajemen stres dalam kelas untuk mengadekuatkan mekanisme coping individu dapat dimulai dengan program pemahaman diri dengan memberi edukasi pada pekerja tentang mekanisme terjadinya stres, gejala-gejala stres, hal-hal dalam diri maupun faktor dari luar (stresor) yang dapat berperan dalam timbulnya stres, dampak stres terhadap kesehatan, serta keterampilan untuk mengurangi stres (misalnya dengan meningkatkan kecerdasan emosi, assertive skill, komunikasi, manajemen waktu dan pelatihan relaksasi) (Cooper dan Payne, 1990; Winfried dan Peter, 1998; Munandar, 2001; Shimazu dkk., 2006; Kroemer, 2009). Melalui upaya-upaya ini, mekanisme adaptasi akan menjadi positif dalam menghadapi tuntutan tugas sehingga diharapkan yang terjadi adalah respon adaptasi yang sifatnya fisiologis. Dengan edukasi ini diharapkan pekerja dapat mengenali secara dini kondisi stres masing-masing dan menyadari hal-hal dalam dirinya maupun faktor-faktor lainnya yang merupakan stresor dari kondisi stres yang dialami. Untuk 63 selanjutnya diharapkan terjadi pemberdayaan diri sehingga pekerja akan memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap situasi-situasi yang dapat merupakan sumber stres dan tahu cara-cara untuk menanggulangi stres yang dialami. Van der Klink (2001) membuktikan bahwa intervensi dalam bentuk cognitive–behavioral efektif meningkatkan quality of work life. Pekerjaan yang sifatnya sedentary work sepanjang waktu kerja (misalnya pada pekerja kantor, termasuk juga pada pekerja di sektor finansial) (Treaker, 2010) harus diimbangi dengan istirahat pendek yang sifatnya aktif, dapat dalam bentuk kegiatan peregangan di tempat kerja. Hal ini dapat bermanfaat dalam memperbaiki sistem sirkulasi darah sehingga dapat mengurangi kelelahan dan mencegah timbulnya gangguan muskuloskeletal dan mengurangi stres. Treaker (2010) mengatakan bahwa pekerja-pekerja kantor modern memerlukan aktivitas fisik yang lebih besar untuk mencegah timbulnya penyakit metabolik di kemudian hari. 2.4.6 Perbaikan kondisi kerja dalam aspek lingkungan kerja Lingkungan kerja yang nyaman adalah penangkal stres dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ketika lingkungan kerja dirasakan panas, bising, pencahayaan yang kurang atau kesilauan, atau tata kerumahtanggaan yang semrawut, akan mengganggu konsentrasi, memicu munculnya emosi negatif dan perasaan mudah marah. Hormon-hormon stres lalu dengan mudah membanjiri tubuh yang diikuti oleh-perubahan-perubahan emosi maupun perilaku. Perbaikan kondisi lingkungan kerja dengan mengatur temperatur dan kelembaban ruangan, mengatur 64 penataan pencahayaan alami maupun buatan serta pengendalian bising akan membuat suasana kerja nyaman dan lebih produktif. Moral kerja juga menjadi positif. Dalam penelitian ini, perbaikan lingkungan dilakukan dengan memaksimalkan penerangan alami dengan membuka korden, membuat kaca jendela selalu bersih dan mengatur penempatan monitor komputer. Hal ini dilakukan agar intensitas penerangan dapat ditingkatkan sesuai besarnya intensitas yang dibutuhkan untuk pekerjaan kantor yang membutuhkan ketelitian, yaitu minimal 300 lux dan terhindar dari kesilauan. Pemanfaatan penerangan alami juga membuat pekerja merasa dapat berinteraksi maksimal dengan lingkungan di luar ruangan yang secara teori dapat meningkatkan perasaan nyaman dan menyenangkan (Kroemer dan Grandjean, 2000). Selain itu, memaksimalkan daily light juga merupakan tindakan untuk meningkatkan efisiensi yang merupakan salah satu prinsip penerapan ergonomi. 2.4.7 Evaluasi program Evaluasi program sangat penting dilakukan untuk menilai apakah program dapat berjalan sesuai perencanaan awal dan efektif bagi pekerja dan organisasi. Permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang ditemukan dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kelanjutan program dapat semakin sempurna dan efektivitasnya dapat semakin ditingkatkan. Evaluasi program dapat dilakukan memakai acuan parameter yang dipakai dalam identifikasi awal. Hasil evaluasi program hendaknya didiskusikan untuk menilai dan mencari 65 strategi untuk memperbaiki kegagalan yang terjadi. Berhasil tidaknya program manajemen stres di tempat kerja juga sangat tergantung dari bagaimana budaya organisasi di tempat tersebut. Budaya organisasi menunjukkan sikap dan nilai-nilai staf yang dikembangkan di tempat kerja dan keyakinan mereka terhadap organisasi. Budaya organisasi akan mempengaruhi bagaimana permasalahan-permasalahan digali dan dicarikan solusinya termasuk permasalahan stres kerja (Debra, 1996). Dalam penelitian ini, efek program Ergo-JSI sebagai sebuah bentuk program manajemen stres kerja dinilai dengan parameter-parameter psikofisiologis berupa: stresor, distres psikologis, keluhan muskuloskeletal, WAI, kadar kortisol darah dan kepuasan kerja. Akhirnya dengan melaksanakan program manajemen stres di tempat kerja diharapkan akan tercipta budaya organisasi yang lebih positif, suasana kerja yang menyenangkan, produktivitas kerja meningkat, dan pada akhirnya quality of work life dan image perusahan akan meningkat.