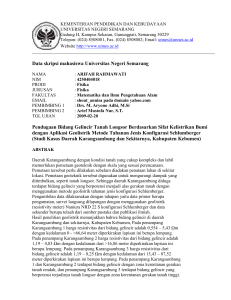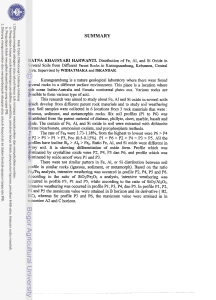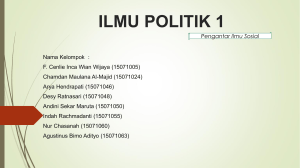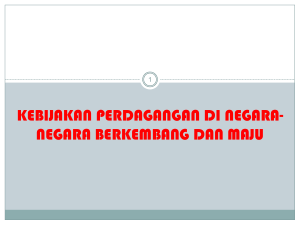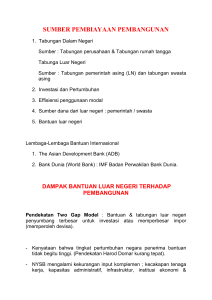BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Paradigma pariwisata
advertisement
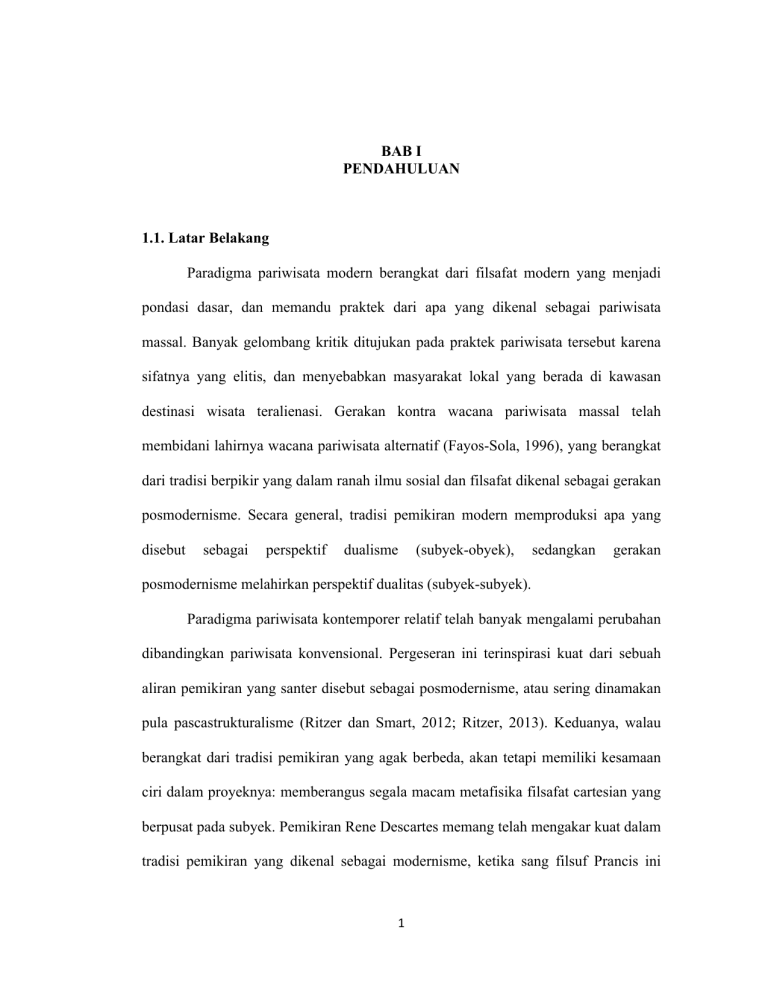
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Paradigma pariwisata modern berangkat dari filsafat modern yang menjadi pondasi dasar, dan memandu praktek dari apa yang dikenal sebagai pariwisata massal. Banyak gelombang kritik ditujukan pada praktek pariwisata tersebut karena sifatnya yang elitis, dan menyebabkan masyarakat lokal yang berada di kawasan destinasi wisata teralienasi. Gerakan kontra wacana pariwisata massal telah membidani lahirnya wacana pariwisata alternatif (Fayos-Sola, 1996), yang berangkat dari tradisi berpikir yang dalam ranah ilmu sosial dan filsafat dikenal sebagai gerakan posmodernisme. Secara general, tradisi pemikiran modern memproduksi apa yang disebut sebagai perspektif dualisme (subyek-obyek), sedangkan gerakan posmodernisme melahirkan perspektif dualitas (subyek-subyek). Paradigma pariwisata kontemporer relatif telah banyak mengalami perubahan dibandingkan pariwisata konvensional. Pergeseran ini terinspirasi kuat dari sebuah aliran pemikiran yang santer disebut sebagai posmodernisme, atau sering dinamakan pula pascastrukturalisme (Ritzer dan Smart, 2012; Ritzer, 2013). Keduanya, walau berangkat dari tradisi pemikiran yang agak berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan ciri dalam proyeknya: memberangus segala macam metafisika filsafat cartesian yang berpusat pada subyek. Pemikiran Rene Descartes memang telah mengakar kuat dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai modernisme, ketika sang filsuf Prancis ini 1 mendeklarasikan rapalan kaum rasionalis yang terkenal itu: cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada). Artinya, subyek yang berpikir ini, dengan menggunakan instrumen rasionalitasnya akan selalu mampu mengontrol obyek di luar dirinya (Hardiman, 2012). Implikasinya cukup jauh: eksistensi manusia ditentukan ketika ia menggunakan kemampuan daya pikirnya. Aroma antroposentris ini merambah ke seluruh dimensi kehidupan. Demikian juga semua disiplin ilmu, logika modern dijadikan rujukan untuk memperoleh kebenaran. Racikan pas antara logika formal aristotelian dengan subyektivitas cartesian melahirkan apa yang populer dinamakan metode ilmiah. Metode khas inilah yang disepakati sebagai satu-satunya cara dalam memperoleh pengetahuan yang benar dalam maskapai keilmuan. Standarisasi ini ternyata tidak hanya berada dalam demarkasi akademis, ketika posisi ilmu/sains ternyata merambah ke semua relung kehidupan manusia (Habermas dalam Hardiman, 2000). Teknologi yang merupakan anak kandung dari sains telah menunjukkan hasilnya yang gilang-gemilang. Hal ini menjadikan apa yang ilmiah adalah terhormat, dan apa yang tidak ilmiah akan ditolak, atau minimal diterima setengah hati sampai suatu kelak diverifikasi secara ilmiah. Klaim rasionalitas ilmiah ini menemui titik universalitasnya, ketika apa yang distandarisasikan oleh kelompok sainstis (subyek) menjadi dasar dalam menundukkan apapun yang dianggap sebagai obyek (Sindhunata, 1987). Berikutnya, yang juga khas dari modernisme adalah pandangannya tentang arus sejarah yang memiliki tujuan akhir ideal (teleologisme). Ini merupakan keyakinan bahwa masa depan pasti memiliki telos, menuju arah yang lebih baik jika 2 dipandu dengan rasionalitas ilmiah. Demikianlah, keyakinan metafisis ini menjadi optimisme khas kaum modernis. Dalam konteks inilah, sains menjadi ideologis (Hardiman, 2012). Proyek modernisme ini melahirkan jenis dualisme berikutnya (selain oposisi antara subyek-obyek), yaitu oposisi biner (Piliang, 2003). Pemikiran yang berasal dari tradisi linguistik ini pada intinya berangkat dari pandangan dasar bahwa adanya sesuatu (tanda) karena kaitannya dengan sesuatu yang lain. Dalam sebuah struktur oposisi biner yang ideal, segala sesuatu arti/makna dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori (x) ataupun kategori (y). Suatu kategori (x) tidak bakalan ada dengan sendirinya tanpa berhubungan secara struktural dengan kategori (y). Kategori (x) masuk akal bila dan hanya bila karena dia bukan kategori (y). Tanpa kategori (y), ikatan dengan kategori (x) tidak bakalan ada, dan kategori (x) juga tidak ada. Dalam sistem biner, hanya ada dua sign/tanda yang hanya memiliki makna bila masingmasing beroposisi dengan yang lain. Suatu kategori jadi eksis/bermakna karena ditentukan oleh ketidak-eksis-an/ketidakbermaknaan kategori yang lain. Implikasinya, sesuatu akan bermakna ketika menidakkan yang lain. Dalam konteks inilah memunculkan apa yang disebut sebagai the others/liyan/yang lain (Sarup, 2011). Pariwisata konvensional adalah pariwisata modern, yang terinspirasi dari logika berpikir cartesian tersebut. Bentuk konkretnya adalah pariwisata massal (Baiquni, 2010). Pariwisata jenis ini dipandang memiliki beberapa cacat bawaan. Pertama, dengan paradigma modernnya, pariwisata ini mengusung standarisasi yang 3 menjadi rujukan universal. Ia mengusung seperangkat aturan yang harus diterima secara taken for granted (tanpa perlu dipertanyakan lagi secara kritis) dalam pembangunan pariwisata dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Aturan ini bisa berupa kode etik, regulasi, tata kelola ideal, dan kajian keilmuannya. Hal ini membawa kepada problem legitimasi. Siapa yang memiliki otoritas untuk memproduksi aturan tersebut? Atas klaim apa sehingga apa yang diproduksi tersebut sahih? Dan, lewat mekanisme apa sehingga aturan tersebut berlaku universal? Berikutnya adalah, kedua, yang menjadi telos (tujuan) dalam pariwisata modern adalah pertumbuhan. Logika pertumbuhan berangkat dari kerangka pikir pembangunanisme/developmentalisme, yaitu suatu paham yang dijadikan model ideal oleh semua negara di dunia pasca era kolonialisasi. Setelah kolonialisasi yang dilakukan oleh negara dunia pertama berakhir, diperlukan tata relasi baru antara negara yang terlibat, mantan kolonial dan yang dijajah (Fakih, 2002). Yang dibutuhkan pertama kali oleh mereka yang dijajah pasca kemerdekaan adalah menjawab pertanyaan: what’s next? Para negara kolonialis menawarkan resep mudah: pembangunan. Menjadi tidak mudah adalah ketika para negara yang pernah dikolonialisasi ini tentu saja tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan, terutama dalam konteks kualitas sumber daya manusianya untuk mengerjakan pembangunan tersebut. Terjadilah fenomena pengiriman pelajar ke negara dunia pertama untuk menimba ilmu dalam rangka pembangunan negaranya nanti. Munculah paradoks, walau de jure mereka merdeka dalam artian fisik, tetapi de facto tetap terjajah secara 4 mind-sett. Suatu kolonialisme model baru. Sebuah neokolonialisme. Mengapa demikian? Jawabannya mudah, yang terjadi adalah ketergantungan antara negara dunia ketiga terhadap negara dunia pertama ketika model pembangunan yang diterapkan pada hakekatnya adalah formulasi dari negara pertama. Dan, tentu saja bukannya nir-kepentingan. Kepentingan negara pertama terepresentasikan ketika model, teknik, dan filosofi pengelolaan pembangunan negara bekas jajahan tersebut merupakan proyeksi wacana mereka (Fakih, 2002). Developmentalisme terkait erat dengan kapitalisme. Mansour Fakih (2002) menyebutkan bahwa developmentalisme merupakan salah satu manifestasi dari kapitalisme. Fakih bermetamorfosa dari mengemukakan tiga tahapan; kapitalisme pertama, dalam tahapan kolonialisme, sejarahnya lalu, kedua, developmentalisme, dan, ketiga, yang terakhir, globalisasi. Kapitalisme sebagai sebuah sistem, berpondasikan filsafat liberalisme dan neo liberalisme. Pembangunan ekonomi negara menjadi kredo yang ditawarkan negara dunia pertama. Artinya, the economic first, the politic and the others next. Logika kapitalisme ekonomi adalah akumulasi kapital yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalisme tidaklah mempersoalkan dimana dan bagaimana kapital atau modal itu terakumulasi (apakah hanya di tangan segelintir orang ataukah ditangan rakyat banyak), yang terpenting adalah ada akumulasi yang dialokasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Logika pertumbuhan ekonomi ini berbenturan dengan logika pemerataan ekonomi (yang merupakan ciri dasar sosialisme ekonomi). 5 Akibatnya, para pelaku ekonomi akan berlomba mengakumulasi kapital dan negara akan mendukung sepenuhnya praktek tersebut melalui kebijakan liberalisasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya praktek-praktek konglomerasi, yang tidak jarang juga dibarengi dengan praktek-praktek monipoli, oligopoli, atau bentuk-bentuk perilaku ekonomi yang berpotensi ketidakadilan. Di bawah paradigma pengutamaan pembangunan ekonomi kapitalis inilah pariwisata modern disapih. Logika pertumbuhan dijadikan dasar tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata. Artinya, jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata dalam suatu Negara akan menjadi indikator apakah pariwisatanya berhasil atau gagal. Tentu, hal ini merujuk pada statistik kunjungan wisatawan setiap tahunnya, apakah grafiknya naik, stagnan, atau turun. Semakin menunjukkan trend positif ketika grafik kunjungan wisatawan setiap tahunnya meningkat. Stagnan berarti kurang berhasil, dan jika grafik menurun artinya gagal. Selanjutnya, yang menjadi problem ketiga dari pariwisata modern adalah logika oposisi biner yang melekat padanya. Hal ini mengandaikan adanya kebutuhan akan the others/liyan/yang lain agar salah satu pihak eksis. Dalam aroma ekonomistik yang kental, pembangunan pariwisata yang dioperasikan dikendalikan oleh pihak yang memiliki modal ekonomi yang kuat. Terjadilah kolaborasi, semacam simbiosis mutualisme di antara elit. Pertanyaannya adalah: siapa menguasai siapa? Jika merujuk pada konsep stake holders pariwisata, yaitu para pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi pariwisata, mereka terdiri dari: pebisnis (swasta), penguasa (negara), 6 dan masyarakat lokal, maka pihak bisnis yang ditopang oleh negaralah yang cenderung mendominasi. Dalam konteks ini, masyarakat lokal cenderung menjadi penonton, menjadi the others/liyan/yang lain. Tidak terlibat dan dilibatkan dalam pembangunan pariwisata yang, ironisnya, berlangsung di wilayahnya. Wacana pembangunan pariwisata yang lebih memberi penekanan pada keberhasilan (pertumbuhan) secara ekonomis dewasa ini telah menuai berbagai kritik dari berbagai pihak (Leiper, 1990). Hal ini dipandang telah menyebabkan beberapa masalah jika ditilik dari dua sudut pandang, yaitu: pertama, aspek daya dukung (fisik/lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi itu sendiri), dan, kedua, aspek keberlanjutannya. Kontra wacana terhadap developmentalisme dimulai sekitar medio 1980an ketika lembaga-lembaga yang concern terhadap permasalahan lingkungan mulai gencar melancarkan kritiknya. International Union for the Conservation of Nature (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP), dan World Wildlife Fund (WWF) mendeklarasikan “world conservation strategy”guna memperjuangkan tiga hal: 1. Mempertahankan proses-proses ekologi yang pokok beserta sistem pendukungnya. 2. Memelihara keanekaragaman hayati. 3. Menjamin penggunaan ekosistem berikut spesiesnya secara berkelanjutan. 7 Selanjutnya, pada tahun 1987, World Commission on Environment and Development yang diketuai oleh Brundtlandt mewacanakan konsep Sustainable Development (SD), yang didefinisikan sebagai: “pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya.” Konsep SD lalu diadaptasi ke dalam bidang pariwisata oleh Burns dan Holden (1997) menjadi Sustainable Tourism Development (STD). Konsep ini merupakan sebuah model yang mengintegrasikan aspek lingkungan fisik (place), lingkungan budaya (host community), dan wisatawan (visitor). Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah Community Based Tourism (CBT) (Suansri, 2003). Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). CBT menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut haruslah secara mandiri melakukan mobilisasi aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan. Melalui konsep CBT, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi 8 pariwisata, untuk itu para individu diberi keterampilan untuk mengembangkan small business. Wacana tentang geowisata merupakan salah satu bentuk kreasi pariwisata yang merupakan kontra wacana terhadap pariwisata massal. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan jenis atraksi yang ditawarkan, geowisata masuk dalam klasifikasi pariwisata minat khusus (Ansori, 2012). Artinya, daya tarik wisata yang dikembangkan lebih banyak berbasis pada pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik. Inilah yang menjadikan sifat massal yang melekat pada pariwisata modern terlucuti. Dengan tawaran atraksi yang terbatas, daya tarik wisata yang berbasis pada bentang alam ini melakukan proses seleksi alami untuk wisatawan yang datang, yaitu mereka yang tertarik dan memiliki minat pada bentang alam geologis dengan berbagai keunikan dan sejarahnya. Keunggulan dikreasinya geowisata bagi suatu destinasi adalah dianggap mampu mengeliminir atau meminimalisasi berbagai dampak negatif dari pariwisata modern yang berakar dari filsafat modern. Dualisme res cogitans Descartes telah membawa alienasi para liyan yang dianggap tidak memiliki instalasi rasionalitas. Para “the others” yang teralienasi ini cenderung menimpa masyarakat lokal di mana aktivitas pariwisata eksis. Dengan terseleksinya wisatawan yang datang, sehingga lebih diutamakan turis yang berkualitas daripada kuantitas, membawa arti pada energi yang diberikan dalam konteks pelayanan pariwisata menjadi lebih hemat. Artinya, secara logika, tidak dibutuhkan pemborosan sumber daya dalam aktivitas pariwisata 9 yang dikembangkan, dengan memperhatikan carrying capacity yang ada pada suatu destinasi (Liu, 1994). Praktek pariwisata yang berlangsung di Karang Sambung memiliki beberapa keunikan tersendiri. Pertama, walaupun telah berlangsung praktek pariwisata yang dinamakan sebagai geowisata Karang Sambung, ternyata belum semua pemangku kepentingan yang berada dalam ranah memiliki sense of belonging, dalam arti praktek geowisata yang berlangsung masih elitis, dengan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Informasi Konservasi Kebumian (BIKK) Karangsambung yang merupakan instansi kepanjangan tangan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), selanjutnya akan disebut BIKK-LIPI, yang berperan sebagai produsernya. Kedua, tafsir para aktor yang berada di Karang Sambung masih multi penafsiran terhadap alam, yang belum semua memiliki pandangan tentang konteks relasi mereka dengan alamnya adalah ranah pariwisata. Eksklusivitas penafsiran para aktor terhadap ranah Karang Sambung berangkat dari primordialisme tertentu, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ini artinya, ego sektoral terbingkai dalam ranah, ketika beragam penafsiran terhadap ranah berbasiskan kepentingan masing-masing aktor. Dan, ketiga, hal ini berdampak kepada eksistensi praktek pariwisata di Karang Sambung karena belum terstrukturnya bingkai pemaknaan aktor terhadap ranah bersama, sebagai ranah pariwisata. Seperti yang telah diuraikan mengenai berbagai dampak buruk pariwisata modern yang beroperasi dalam bentuk pariwisata massal, sejatinya dengan dipilihnya praktek geowisata di Karangsambung, pariwisata yang dibangun sudah berada pada 10 jalur yang benar. Fakta bahwa wilayah ini merupakan bentangan alam yang menyimpan informasi geologi bernilai ilmiah tinggi yang berada dalam kawasan yang relatif tidak luas (22.157 Ha), merupakan modal dasar bagi dikembangkannya pariwisata minat khusus (Ansori, 2012). Tetapi ironisnya, terjadi pula fakta terjadinya penambangan liar secara massif yang dilakukan oleh sebagaian masyarakat lokal Desa Karangsambung di sepanjang aliran Sungai Luk Ulo guna dieksploitasi pasirnya yang terkenal bermutu tinggi, dan eksploitasi batu gunung yang merupakan situs geologi bernilai ilmiah tinggi. Dan, lebih ironisnya lagi, operasi penambangan ini tepat terjadi di depan dan di sekitar kantor LIPI berada. Diperlukan pemikiran untuk mengatasi problem tafsir yang masih manasuka diantara para aktor yang berada di ruang sosial Karangsambung. Tafsir mereka berbasis kepentingan pribadi atau kelompok, yang masing-masing memiliki bingkai pemaknaan berbeda terhadap lingkungannya. Dua mainstream tafsir utama terhadap ranah direpresentasikan oleh dua aktor utama: BIKK-LIPI dengan tafsir geologisnya, dan penambang dengan tafsir material-ekonomisnya. Artinya, belum ada struktur yang memadai di ranah Karangsambung, yang menampung aspirasi bersama. Untuk itu diperlukan upaya untuk dekonstruksi struktur lama yang berangkat dari penafsiran masing-masing, ke produksi struktur baru yang berangkat dari penafsiran bersama terhadap ranah. Untuk itu pemikiran dualitas agensi struktur yang diperkenalkan oleh Giddens dan Bourdieu akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini, guna mengatasi dualisme tafsir yang terjadi. 11 Selain itu, diperlukan pula cara pandang baru terhadap alam fisik, ketika masih terjadi keberjarakan subyek-obyek. Dalam level tertentu, cara pandang para aktor dalam ranah Karangsambung masih terperangkap dualisme Cartesian tersebut. Posisi manusia yang merasa berposisi lebih tinggi dibandingkan alam menyebabkan alam hanya menjadi obyek an-sich. Dibutuhkan cara pandang filsafat baru yang mampu mengatasi perangkap dualisme Cartesian tersebut. Filsafat fenomenologi yang diperkenalkan Merleau Ponty (Hardiman, 2007) dianggap memadai guna mengatasi problem dualisme subyek-obyek yang berbasis res cogitans, menuju ke arah dualitas subyek-subyek yang berlandaskan inkorporealitas. Cara pandang ini akan membawa relasi antara agen dengan alam, dalam kedudukannya yang setara dan tergantung secara resiprokal. Penelitian ini akan mencoba mengatasi perangkap dualisme yang terjadi di Karangsambung dalam dua tingkatan, yaitu: pertama, dualisme yang terjadi di tingkatan relasi antara agensi/aktor dengan struktur yang sedang beroperasi di ranah, dan, kedua, dualisme antara manusia dengan lingkungan fisiknya. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan fenomena yang ada di Karangsambung, penelitian ini berusaha menyingkap praktek geowisata terjadi di Karang Sambung, dengan ikhtiar untuk menjawab pertanyaan yang diformulasikan menjadi tiga hal, yaitu: 1. Bagaimana praktek geowisata yang terjadi di Karangsambung? 2. Bagaimana posisi para aktor dalam relasinya dengan lingkungan alamiah Karangsambung? 12 3. Apa implikasi relasi tersebut bagi keberlanjutan praktek pariwisata di Karangsambung? 1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian yang diformulasikan di atas. 1.3.1. Tujuan Umum Secara umum penelian ini ingin memahami praktek Geowisata Karangsambung, tafsir para aktor yang berada dalam ranah yang berimplikasi pada keberlanjutan praktek pariwisata di Karang Sambung. 1.3.2. Tujuan Khusus Secara spesifik beberapa hal yang ingin diketahui melalui penelitian ini adalah: 1. Praktek geowisata di Karangsambung, menyangkut latar belakang terjadinya, agen yang memroduksi, aktivitas yang berlangsung, serta posisinya dalam bingkai relasi antar aktor yang berada dalam ranah pariwisata di Karangsambung. 2. Mengetahui posisi para aktor konteks relasinya dengan lingkungan alamiah Karangsambung, menyangkut cara pandang masing-masing kelompok aktor terhadap alam fisik Karangsambung. 3. Mengetahui implikasi dari relasi tersebut bagi keberlanjutan praktek pariwisata di Karangsambung, menyangkut problem struktur yang ada saat ini, dan alternatif produksi struktur pariwisata yang diperlukan sehingga mampu mewadahi aspirasi para aktor di ranah Karangsambung. 13 1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Manfaat Akademik Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi kajian kritis tentang praktek pariwisata yang beroperasi pada ranah yang di dalamnya para aktor memiliki vested interest masing-masing, dan menjadi bahan diskusi bagi kajian strukturasi tentang pariwisata dengan pendekatan sosiologi pariwisata, yang masih dirasa kurang dalam penelitian pariwisata, serta mendorong bagi penelitian lebih lanjut guna pengembangan ilmu pariwisata. Bagi institusi pendidikan akan menambah perbendaharaan penelitian pariwisata dan menjadi bahan dalam pengajaran, pengabdian masyarakat, serta landasan bagi penelitian lebih lanjut. 1.4.2. Manfaat Praktis Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis bagi pemangku kepentingan, yaitu BIKK-LIPI, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dan Masyarakat Lokal di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung, khususnya Desa Karangsambung, dalam rangka pengambilan keputusan tentang model pembangunan pariwisata di Karangsambung ke depan. Dalam konteks pragmatis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi awal guna mendesain program yang mampu mengakomodasi kepentingan para aktor yang berada dalam ranah pariwisata yang diproduksi bersama. 14