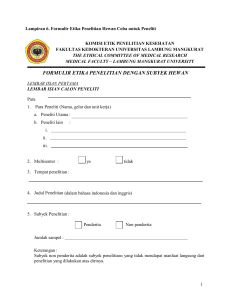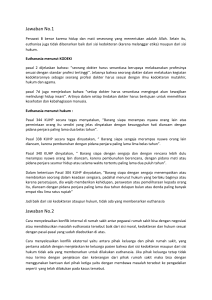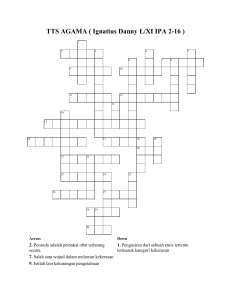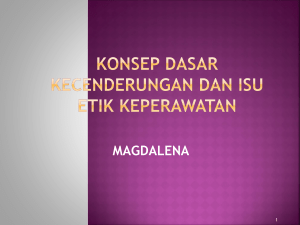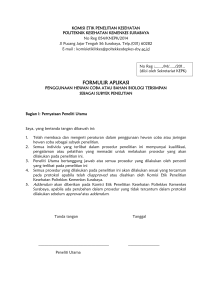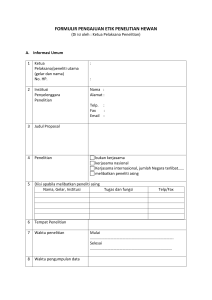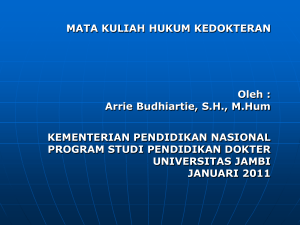TINJAUAN “EUTHANASIA” DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
advertisement

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Euthanasia dalam perspektif HAM merupakan pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi. Dilihat dari segi perundang-undangan dewasa ini, belum ada pengaturan yang baru dan lengkap tentang euthanasia. Tetapi bagaimanapun juga, karena masalah euthanasia menyangkut soal keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pengaturan atau Pasal yang sekurang-kurangnya mendekati unsur-unsur euthanasia itu. Adapun Pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Pasal yang paling mendekati dengan masalah tersebut peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2, Bab IX Pasal 344 KUHP. Persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan universal. Setiap kejadian yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan di manapun akan bernilai tidak baik. Memang ada di beberapa bagian di bumi ini perbedaan nuansa dalam memandang persoalan hak asasi manusia. Sebagai contoh, sebuah suku di Irian Jaya membunuh tawanan perang dalam kasus perang antar suku dianggap bukan suatu penistaan terhadap kemanusiaan, sementara daerah lain penyiksaan terhadap orang/tawanan dianggap pelanggaran besar hak asasi. Tindakan mencabut hak hidup, merendahkan nilai dan martabat kemanusiaan merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pewarnaan nilai lokal dalam pelaksanaan 1 hak asasi manusia, tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dengan menghapus tindakan yang non manusiawi. Masyarakat yang peduli soal hak asasi manusia (HAM), mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka hanya berbicara dan bersetuju di antara mereka sendiri. Mereka belum berhasil membawa pihak lain, sebagai aktor yang sangat dominan, yaitu pemerintah ke dalam forum diskursus (discourse) atau wacana itu. Apalagi mengajaknya untuk mencari kemungkinan konsensus mengenai HAM. Para aktifis di luar pemerintahan dan para pemimpin pemerintahan masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing bekerja dengan definisi yang berbeda mengenai HAM, masingmasing punya urutan-urutan prioritas sendiri mengenai apa yang harus dilakukan dan punya patokan sendiri bagaimana mengukur keberhasilan mereka. Hak hidup harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum. Itulah sebabnya negara hukum yang baik menjunjung tinggi hak asas manusia. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Menyangkut jiwa manusia dalam KUHP terdapat pada Pasal 338, 339, 340, 341. Selain dapat membaca bunyi pasal-pasal itu sendiri, kita pun dapat mengetahui bagaimana pembentuk Undang-undang memandang jiwa manusia. Secara singkat, dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda) menganggap jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga, dibandingkan dengan milik manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap perbuatan apapun motif dan 2 coraknya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar oleh negara. Masalah keselamatan jiwa daripada warga negara, dilindungi oleh negara. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat, dan kepentingan orang yang dituntut, ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman. Pandangan dari pembentuk undang-undang Hindia Belanda masih tetap dianut oleh pemerintah masa Orde Baru. Ini terbukti dalam KUHP, perihal keselamatan dan keamanan jiwa manusia masih dijamin dengan tanpa perubahan sedikit. Kenyataan, sampai sekarang tanpa membedakan agama, ras, warna kulit dan ideologi, keselamatan dan keamanan jiwa manusia Indonesia dijamin oleh undang-undang. Hal ini merupakan pencerminan daripada prinsip equality before the law yang tentunya harus juga diterapkan terhadap keamanan dan keselamatan jiwa manusia. 3 B. Perumusan Masalah Permasalahan dalam penulisan Tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah atas dasar hak untuk menentukan nasib sendiri praktek euthanasia bisa dibenarkan 2. Bagaimana keterkaitan antara etika kedokteran dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam kasus euthanasia ? 3. Bagaimana peran dan prospek Hukum hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup pasien pada praktek euthanasia ? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut 1. Menganalisa apakah dengan Hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu hak dasar yang diakui oleh Instrumen Hak Asazi Manusia bisa menjadi dasar pembenaran praktek euthanasia 2. Menganalisa bagaimana keterkaitan antara etika kedokteran dan Hukum Hak Asasi Manusia dengan euthanasia. 3. Menganalisa bagaimana peran dan prospek Hukum hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan pada hak hidup pasien pada praktek euthanasia 4 D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan fraktis untuk: 1. Secara teoretis, memberikan pemahaman adanya keterkaitan erat antara Hukum HAM khususnya menyangkut perlindungan pasien dalam praktek euthanasia dan etika kedokteran. 2. Secara praktis, memberikan gambaran tentang pentingnya penegakkan hukum HAM dalam konteks praktek kedokteran terutama yang menyangkut hak mempertahankan hidup bagi pasien pada kasus euthanasia. 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Terminologi Tentang Euthanasia Euthanasia dikenal sebagai tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri lantaran kehilangan peluang dan harapan. Hal ini biasanya dilakukan oleh penderita penyakit parah dengan peluang hidup yang sangat kecil. Tindakannya sendiri berupa “suntik mati” demi menepis penderitaan yang berkepanjangan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, khususnya dalam dunia kedokteran, hal “merampas nyawa”, baik atas permintaan sendiri karena suatu penyakit yang mustahil disembuhkan maupun atas dasar perikemanusiaan pasti menimbulkan konflik, antara etika kedokteran, hukum pidana,dan hak asaz manusian pada kasus euthanasia. Dalam hal ini Bruce Vodiga dalam tulisannya “Euthanasia and the right to die, moral, ethical and legal perspective” (II T/Chicago, Kent Law Review, Vol 51, Summer 1974, Number 1), mengungkapkan bahwa masalah euthanasia bukan saja masalah semantik, tetapi juga masalah substansi. Berkaitan dengan masalah euthanasia ini, Dr. J.E. Sahetapy, S.H., dalam tulisannya pada majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, membedakan euthanasia ke dalam tiga jenis, yaitu : 1. Action to permit death to occur 2. Failure to take action to prevent death 3. Positive action to cause death. 6 Dari ketiga perbedaan euthanasia tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pada jenis euthanasia yang pertama, kematian dapat terjadi karena pasien sungguh menginginkan kematian. Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya tidak dapat disembuhkan walaupun telah diadakan pengobatan dan perawatan secara baik. Oleh sebab itu pasien meminta kepada dokter untuk tidak memberikan pengobatan kepadanya guna penyembuhan penyakit yang dideritanya itu. Dalam hal ini Dokter memberikan izin segala permohonan si pasien, jadi kematian si pasien terjadi atas kerja sama antara pasien dan dokter yang semula merawatnya. Jenis euthanasia inilah yang biasa disebut sebagai euthanasia dalam arti yang pasif (permission). Pada banyak kasus, euthanasia dilakukan karena permintaan seseorang yang sudah sekarat. Tapi ada juga kasus euthanasia yang dilakukan tim dokter, karena sang pasien sudah tidak sanggup lagi untuk memohon. Dari sisi etika, boleh tidaknya euthanasia masih terus diperdebatkan banyak kalangan. Bahkan tak semua negara mengizinkan praktik euthanasia. Meskipun ada sejumlah kalangan menilai alasan ‘meringankan penderitaan’ itu masuk akal, yang pasti semua agama melarangnya. Menurut Islam, Allah yang menentukan panjangpendeknya umur manusia. Jika saatnya tiba, kematian itu tak dapat ditunda. Tak seorang pun bisa mati tanpa izin Allah. Sebagaimana firmanNya bahwa barangsiapa yang melakukan bunuh diri, Allah tidak akan membukakan pintu surga baginya. (Sahih Bukhari). Kematian bisa terjadi karena kelalaian atau kegagalan seorang dokter dalam melakukan pengobatan. Hal ini terjadi bilamana dokter mengambil suatu tindakan guna mencegah kematian, tetapi ia tidak mengerjakan apa-apa, karena ia 7 tahu bahwa pengobatan yang akan diberikan kepada pasien Euthanasia jenis yang kedua ini sia-sia belaka. sama dengan euthanasia jenis pertama. perbedaannya terletak pada tindakan membiarkan pasien mati dengan sendirinya tanpa mengadakan pencegahan. Pada jenis pertama, tindakan membiarkan timbul antara pasien dan dokter yang merawatnya, sedangkan pada jenis yang kedua, tindakan timbul hanya dari satu pihak saja, yaitu dari dokter yang merawatnya. Euthanasia terjadi karena tindakan yang aktif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Euthanasia jenis ini dokter yang bersifat aktif dalam mempercepat kematian pasien dengan memberikan obat dosis tinggi yang langsung menimbulkan kematian. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 344 KUHP, sesuai dengan jenis euthanasia yang ketiga, yaitu euthanasia yang bersifat aktif. Masalahnya sekarang, dapatkah Pasal 344 KUHP diterapkan atau dipakai sebagai dasar penuntutan oleh Jaksa pada kasus euthanasia. Mengapa tidak ! Kalau tidak, pasti Pasal 344 KUHP itu tidak diciptakan. Tetapi waktu Pasal itu diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda, dahulu dunia ilmu kedokteran belum semaju seperti sekarang ini. Dalam Pasal tersebut dinyatakan: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri” ditambah pula dengan kata-kata “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” (lopdiens uitdrukkelijk en ernstig verlangen). Perumusan ini pasti menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian, karena dapat dibayangkan, bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati sudah pulang ke alam baka. Oleh sebab itu, pernyataan dengan kesungguhan hati ini tidak boleh diucapkan secara lisan, sebaiknya dalam bentuk yang tertulis dan 8 ditandatangani oleh saksi-saksi, sehingga pada proses pembuktian di pengadilan nanti, surat pernyataan ini dapat dipakai sebagai alat bukti. Timbul masalah lagi, bagaimana jika yang bersangkutan tidak mampu lagi berkomunikasi dalam bentuk dan dengan cara apapun, sehingga tidak dapat menyatakan dengan kesungguhan hati ? Karena kita tahu bahwa dalam masalah euthanasia biasanya pasien dalam keadaan mati tidak, hidup pun tidak (in a persisten vegetative state). Sebagai contoh yang sangat populer adalah yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kasus Karen Ann Quinlan, yang telah berada dalam suatu “persistent vegetative state”. Mengenai kasus ini akan dibahas pada bab yang berikutnya. Dalam hal yang demikian dapatkah seorang dokter dituntut berdasarkan Pasal 344 KUHP. Kalau dilihat dari perumusan, baik dalam konteks penafsiran yang dikenal dalam dunia ilmu hukum, maupun dalam bentuk penafsiran baru, menurut penulis Pasal 344 KUHP ini sulit diterapkan pada kasus euthanasia, karena untuk membuktikan apakah pasien dengan sungguhsungguh menginginkan kematiannya sendiri, sulit untuk dibuktikan karena pasien yang sudah sakit parah apalagi kalau sudah dinyatakan koma oleh Dokter tidak mungkin memberikan peryataan sendiri. Bagaimana dengan Pasal 340 KUHP, dapatkah penuntut umum (jaksa) menuntut seorang dokter berdasarkan Pasal tersebut, sebagaimana bunyi pasal 340 KUHP : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Ataukah dapat menuntutnya pula berdasarkan Pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan biasa (doodslag) yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja merampas 9 nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Apabila kita perhatikan lebih lanjut, dari ketiga Pasal tersebut di atas, yaitu Pasal 338, 340 dan 344 KUHP, tiga-tiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Pasal 338 KUHP merupakan aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP aturan khususnya, karena dengan dimasukkannya unsur “dengan rencana lebih dahulu.” Oleh sebab itu, Pasal 340 KUHP ini biasa dikatakan sebagai Pasal pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Begitu pula jika diperhatikan lebih lanjut, bahwa Pasal 344 KUHP pun merupakan aturan khusus daripada Pasal 338 KUHP. Hal ini, karena di samping Pasal 344 KUHP tersebut mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, pada Pasal 344 KUHP ditambahkan pula unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.” Jadi masalah euthanasia ini dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni Pasal 338 dan Pasal 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut sebagai concursus idealis, dalam sistem pemberian pidana. Concursus ideals diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang menyebutkan bahwa (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu aturan, jika berbeda aturan yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal 63 (2) KUHP ini mengandung asas Lex specialis de rogat legi generali, yaitu bahwa peraturan-peraturan yang khusus mengalahkan peraturan- 10 peraturan yang sifatnya umum. Yang dimaksud sebagai peraturan khusus disini yakni Peraturan pidana yang memuat unsur-unsur yang termuat dalam peraturan pidana umum, juga memuat peraturan-peraturan pidana yang tak termuat dalam peraturan pidana khusus. Sehubungan dengan adanya concursus idealis ini, Hazewinkel Suringa, mengatakan sebagai berikut : “Ada concursus idealis, apabila pernyataan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, (noodzakelijk – co ipso) juga masuk dalam peraturan pidana lain, baik karena banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifkannya aturan-aturan lain berhubungan dengan cara dan tempat perbuatan itu dilakukan, orang yang melakukan, dan obyek terhadap apa perbuatan itu dilakukan.” Dengan adanya hal-hal seperti tersebut di atas, menurut penulis masalah euthanasia bisa menyangkut dua aturan hukum, yaitu Pasal 338 dan 344 KUHP, dan yang dapat diterapkan Pasal 344 KUHP. Apabila tidak terdapat asas lex specialis derogat legi generali yang disebutkan dalam Pasal 63 (2) KUHP, maka aturan pemidanaan yang dipakai adalah Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana penjara pada Pasal 338 (yaitu 15 tahun), lebih berat daripada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 344 KUHP (yang hanya 12 tahun). Hal ini dapat dimengerti karena dalam concursus idealis diterapkan sistem absorbsi, sebagaimana disebutkan Pasal 63 (1) KUHP, yang memilih ancaman pidana yang terberat. Oleh sebab itu, dalam KUHP kita, hanya ada satu Pasal saja yang mengatur tentang masalah euthanasia, yaitu Pasal 344 KUHP. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya 11 melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Berlainan keadaannya di Inggris, dimana tidak ada ketentuan yang tertulis (statutory definition) tentang pembunuhan berencana (murder). Di Inggris hanya ada pembedaan antara lawful homicide (pembunuhan yang sah) dan unlawful homicide (pembunuhan yang tidak sah). Disamping itu dibedakan pula secara tajam antara actus reus (perbuatan pidana) dan mens rea (pertanggungjawaban pidana), dengan mengembangkan jurisprudensi yang ada di sana. Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa euthanasia di Indonesia dilarang. Larangan ini terdapat dalam Pasal 344 KUHP, yang sampai sekarang masih berlaku. Akan tetapi perumusan dalam Pasal 344 KUHP, dalam dapat menimbulkan kesulitan bagi jaksa untuk menerapkannya penuntutan berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itulah,menurut hemat penulis maka sebaiknya bunyi Pasal 344 KUHP tersebut dapatlah kiranya untuk dirumuskan kembali, berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi sekarang, dan telah disesuaikan dengan perkembangan di bidang medis. Dan rumusan baru tersebut diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan proses penuntutan apabila terjadi kasus yang bersangkutan dengan masalah euthanasia. B. Euthanasia Dikaitkan Dengan Tugas Profesional Dokter Tugas profesional dokter begitu mulia dalam pengabdiannya kepada sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat kemajuankemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Untuk itu setiap dokter perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemuliaan profesi dokter tersebut tetap 12 terjaga dengan baik. Para dokter, umumnya semua pejabat dalam bidang kesehatan, harus memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan. Keahlian di bidang ilmu dan teknologi dapat memberi manfaat yang besar kalau dalam prakteknya disertai oleh norma etik dan moral. Hal tersebut diinsyafi oleh para dokter di seluruh dunia, dan hampir tiap Negara telah mempunyai kode etik kedokterannya sendiri-sendiri. Pada umumnya kode etik tersebut didasarkan pada Sumpah Hipokrates, yang dirumuskan kembali dalam pernyataan Himpunan Dokter Sedunia di London bulan Oktober 1949 dan diperbaiki oleh Sidang ke-22 himpunan tersebut di Sydney bulan Agustus 1968. Sejak permulaan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui akan adanya beberapa sifat fundamental yang melekat secara mutlak pada diri seseorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Oleh sebab itu, para dokter di seluruh dunia mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut dalam suatu etik profesional yang sepanjang masa mengutamakan penderita yang minta berobat serta keselamatan dan kepentingan penderita tersebut. Sejak permulaan sejarah kedokteran para dokter berkeyakinan bahwa suatu etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas asas etik yang mengatur hubungan antara manusia pada umumnya. Di samping itu harus memiliki akar dalam filsafat masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus dalam masyarakat itu. Secara universal, kewajiban dokter tersebut telah tercantum dalam Declaration of Genewa yang merupakan hasil musyawarah Ikatan Dokter Sedunia di Genewa pada bulan September 1948. Dalam deklarasi tersebut antara lain 13 dinyatakan sebagai berikut : “I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception, even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.” Khusus di Indonesia, pernyataan semacam ini secara tegas dicantumkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pernyataan Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, tertanggal 23 Oktober 1969. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 30 Agustus 1969 No. 55/WSKN/1969. Dalam bab II Pasal 9 dari Kode Etik Kedokteran Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa : “Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani.” Dengan demikian berarti, di negara mana pun di dunia, seorang dokter mempunyai kewajiban untuk “menghormati setiap hidup insani mulai saat terjadinya pembuahan.” Dalam hal ini berarti pula bahwa bagaimanapun gawatnya sakit seorang pasien, setiap dokter tetap harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Mungkin pasien itu sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi, atau sudah dalam keadaan sekarat akan tetapi dalam hal ini, dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidup manusia, sebagaimana yang diucapkan dalam sumpahnya. Semua perbuatan yang dilakukan dokter terhadap pasien dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus memberi pertolongan guna mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Walaupun kadang-kadang ia terpaksa melakukan operasi yang sangat membahayakan, tetapi tindakan ini diambil setelah dipertimbangkan 14 secara mendalam, bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa, supaya sipasien terhindar dari ancaman maut. Sekalipun dalam operasi tersebut mengandung banyak resiko. Untuk itu, sebelum operasi dimulai, perlu adanya pernyataan persetujuan secara tertulis dari pasien dan keluarganya. Karena naluri terkuat daripada manusia adalah mempertahankan hidupnya, dan ini juga termasuk salah satu tugas seorang dokter, maka menurut etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan : 1. Menggugurkan kandungan (abortus provocatus) Tidak hanya dalam dunia kedokteran, ternyata masalah abortus provocatus ini pun dalam hukum pidana kita juga dilarang. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Pasal 346 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Disamping Pasal 346 KUHP di atas, masih banyak Pasal-pasal lain yang menyatakan bahwa abortus provocatus ini merupakan tindak pidana, misalnya Pasal-pasal 347, 348 dan Pasal 349 KUHP. Walaupun abortus provocatus ini merupakan perbuatan yang terlarang, namun hal ini masih dapat diterobos oleh seorang dokter, dengan pertimbangan untuk pengobatan, apabila perbuatan itu merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa si ibu dari bahaya maut. Keputusan untuk melakukan abortus provocatus ini harus diambil sekurang-kurangnya oleh dua dokter, dengan persetujuan tertulis daripada perempuan yang hamil dan suaminya, atau 15 keluarganya yang terdekat. Abortus jenis inilah yang disebut sebagai abortus provocatus therapeuticus. Bagaimanapun abortus provocatus itu bentuknya, dan dengan alasan apapun, dalam kehidupan masyarakat disamping dianggap sebagai kejahatan KUHP, juga merupakan barang yang tabu, karena dilarang baik oleh agama, juga sangat bertentangan dengan susila kemasyarakatan. Dalam hubungan ini Nasroen Yasabari S.H., mengatakan bahwa, abortus merupakan arang yang tercoreng di kening dan lumpur yang terpoles di muka, serta aib yang berat bagi keluarga. 2. Euthanasia Karena penderitaan yang tidak tertahankan lagi, tidak mustahil pasien yang penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan, minta agar hidupnya diakhiri saja. Sampai sebegitu jauh, tidak semua orang setuju akan prinsip euthanasia. Para dokter pun demikian halnya. Pada umumnya kelompok yang menentang, mengemukakan alasan yang bertitik tolak dari segi religius. Menurut pandangan mereka bahwa segala sesuatu yang dialami manusia sudah takdir dari Tuhan yang harus diterima sebagai suatu karunia. Dengan demikian apabila seseorang mengalami penderitaan dalam hidupnya seperti mengalami sakit yang parah harus bisa diterima sebagai suatu cobaan hidup, karena betapapun berat cobaan yang dialami, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Oleh sebab itu mengakhiri hidup seseorang yang sedang menerima cobaan dari Tuhan tidak dibenarkan, apapun alasannya.Sebagaimana argumentasi yamg dikemukakan dalam penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Bab II, Pasal 9, yang sekaligus juga mencerminkan sikap atau pandangan para dokter di Indonesia, tentang prinsip euthanasia. 16 Sebaliknya bagi kelompok yang menyetujui euthanasia, disertai dengan argumentasi bahwa perbuatan itu, dilakukan atas dasar perikemanusiaan. Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasien, yang telah berulang kali minta kepadanya agar penderitaannya itu diakhiri saja. Dalam hubungan ini dr. R.Soerarjo Darsono, Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi, Semarang, memberikan contoh sebagai berikut : a. Seorang wanita yang telah hamil tua, mengalami kecelakaan yang sangat parah, sehingga lehernya putus dan mati. Masalahnya sekarang, bagaimana dengan bayi yang masih berada dalam perut sang ibu itu, yang menurut pemeriksaan dotker masih hidup. Bagaimana sikap seorang dokter dalam menghadapi keadaan demikian. Apakah harus membuka perut si wanita tadi, dan mengambil bayinya, ataukah membiarkannya begitu saja ? jika dilakukan, apakah tidak mendahului kehendak Tuhan ? jadi merupakan suatu hal yang sangat dilematis. Dalam hal ini ada pendapat diantara para dokter yang mengatakan : 1) harus di buka, demi keselamatan dan kelangsungan hidup si bayi, 2) biarkan saja, biar Tuhan yang mengeluarkan. b. Seorang yang menderita penyakit kanker ganas, pada stadium permulaan memang tidak terasa sakit, namun pada stadium akhir, sakitnya bukan main dan hampir mendekati dosis kematian. Dalam hal demikian, ada sebagian dokter yang beranggapan sebaiknya diberi obat penghilang kesadaran dalam dosis yang tinggi yang bisa saja menyebabkan orang tersebut mati dengan alasan untuk menghindari agar jangan terjadi penularan penyakit ini. Di lain pihak menghendaki agar jangan diberi obat, dan jika terpaksa diberinya, maka 17 setidak-tidaknya hanya untuk mengurangi rasa sakitnya saja, dan dokter tetap melindungi kehidupan pasien ini. Dalam ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu : 1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir. 2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang. 3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Dari ketiga jenis euthanasia di atas, ternyata pada jenis yang ketiga inilah yang senada dengan euthanasia yang dilarang oleh hukum pidana kita, dan diatur dalam Pasal 344 KUHP. Di beberapa negara maju seperti Eropa dan Amerika mulai banyak terdengar suara-suara yang pro terhadap prinsip euthanasia ini. Mereka berusaha mengadakan suatu gerakan untuk menguatkannya dalam undang-undang negaranya. Negara bagian Australi, Northern Territory menjadi negara pertama di dunia yang mengijinkan euthanasia dengan Uunya. Meskipun hal itu tidak berlangsung lama, dengan adanya keputusan senat Australia sehingga harus ditarik kembali. Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan Undangundang yang mengijinkan euthanasia yang mulai berlaku sejak tanggal 1 april 2002. Pasien-pasien yang mengalami sakit manahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri hidupnya. Bagi orang yang kontra terhadap prinsip euthanasia, berpendapat bahwa tindakan demikian itu sama saja dengan membunuh. Kita di Indonesia, sebagai 18 Negara yang beragama dan ber-Pancasila, percaya kepada kekuasaan mutlak daripada Tuhan Yang Mahaesa. Segala sesuatu diciptakan-Nya, dan penderitaan yang dibebankan kepada manusia, ada arti dan maksudnya. Oleh sebab itu, dokter harus mengerahkan segala kepandaian dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhiri hidup C. “Euthanasia” dan Hak-hak Asasi Manusia Setiap makhluk hidup, termasuk manusia akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, dan diakhiri dengan kematian. Dari berbagai siklus kehidupan di atas, kematian merupakan salah satu yang masih mengandung misteri yang sangat besar. Proses pembuahan yang rumit mulai dapat dikenali dan dipelajari, bahkan akhir-akhir ini sudah dapat dilakukan proses pembuahan buatan, yang meniru proses alamiah, dan terjadilah inseminasi buatan, yang tidak menimbulkan masalah etika pada dunia hewan, tetapi menjadi sangat kompleks dalam dunia manusia. Berbagai macam penyakit juga dapat dikenali satu demi satu, dan sebagian besar penyakit infeksi sudah dapat disembuhkan, sebagian besar penyakit non infeksipun sudah dapat dikendalikan, walaupun belum dapat disembuhkan. Semua upaya tersebut di atas, dilakukan oleh manusia mempunyai hakikat untuk memperoleh jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ataupun gangguan dalam proses pembuahan, kelahiran dan kehidupan itu sendiri yang akhirnya dapat menunda proses akhir dari seluruh rangkaian kehidupan di dunia, yaitu kematian. 19 Negara dalam usahanya melindungi dan mempertahankan hidup manusia, kadang justru terjadi suatu peristiwa yang sangat kontradiktif. Dikatakan sangat kontradiktif, karena sementara negara melindungi hak-hak asasi manusia, terutama “hak untuk hidup”, sementara itu pula manusia diakhiri hidupnya lewat jalan yang dianggapnya legal, yaitu lewat pengadilan dengan menjatuhkan pidana mati. Pandangan yang menentang adanya euthanasia yang mendasarkan dari segi religius, seirama dengan pandangan dari segi hak asasi manusia. Kita tahu bahwa dalam Universal Declaration of Human Rights dari PBB telah mencantumkan sejumlah hak-hak asasi manusia. Begitu pula dalam UndangUndang Dasar 1945, walaupun tidak secara terperinci seperti yang terdapat dalam deklarasi PBB itu. Diantara sekian banyak hak-hak asasi manusia itu mungkin hanya hak untuk mati saja yang tidak ada. Walaupun kedengarannya sangat ganjil, tetapi hal ini cukup mengundang minat para ahli untuk memperbincangkannya, karena “hak untuk mati” ini dipandang telah tercakup pengertiannya dalam “hak untuk hidup” yang selama ini dicantumkan secara tegas. Pandangan yang menentang prinsip euthanasia di atas akan berbenturan argumentasinya, dengan nasib seorang tertuduh yang divonis mati yang pada umumnya masih ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Atau dengan perkataan lain ingin menggunakan “hak untuk hidup”-nya. Disadari atau tidak, bahwa jeritan hati kecilnya, pasti mengatakan keinginannya untuk tidak mati. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa hakim telah memaksa kematian seseorang yang sebenarnya masih ingin hidup terus. Saya berpikir dapatkah sistem penghukuman yang terdapat pada Pasal 10 KUHP yang diperuntukan bagi 20 terpidana mati dimana cara mengeksekusinya dengan tembak mati, dirubah dengan cara dieuthanasia, paling tidak kalaupun penerapan Pasal 10 KUHP itu sampai sekarang masih dipakai sebagai hukum positif di Indonesia, namun cara pelaksanaan eksekusinya lebih manusiawi (sebagaimana yang diatur dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia), dimana terdakwa bisa mati tanpa harus merasakan sakit sebagaimana kalau harus ditembak, karena sebenarnya secara pribadi saya tidak setuju dengan hukuman mati. Menurut saya itu sama halnya dengan kita mendahului kehendak Tuhan. Lebih dari itu kalau kita memahami betapa setiap orang tidak pernah berpikir atau ingin menjadi orang jahat, karena biasanya keadaannlah yang mendesak seseorang sampai berbuat jahat. Selain itu orang yang sudah merasa bersalah tanpa kita hukumpun batinnya sudah merasa terhukum atas apa yang diperbuatnya. Demikian juga untuk orang yang sudah sekarat, kalau dia bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang menimpanya atas ijin dari Allah yang harus diterimanya sebagai suatu cobaan hidup, dia pasti akan berpikir seribu kali untuk menyerah dengan cara minta untuk disuntik mati. Namun kembali bahwa manusia hanyalah mahluk biasa yang kadang tidak bisa menerima begitu saja nasib yang menimpanya, apalagi kalau hal itu berkaitan dengan suatu penyakit yang difonis dokter tidak mungkin untuk sembuh dan jalan satu-satunya yang masih mungkin ialah, mengakhiri hidup si pasien tersebut, agar penderitaannya dapat segera berakhir. Nah, bila kematian untuk menghilangkan penderitaan memang diminta oleh pasien, karena tidak ada lagi jalan lain, apakah permohonan untuk dieuthanasia itu tidak dapat dikabulkan. Apakah kehendak untuk mati dalam kasus semacam ini tidak dapat dikatakan 21 sebagai suatu “hak asasi” dalam hal ini sebagai “hak untuk mati” ? Jika telah diakui bahwa manusia mempunyai sejumlah hak asasi, apakah dipandang sebagai suatu kesalahan apabila mengakui pula adanya “hak untuk mati” pada kasus euthanasia?. Inilah persoalan yang sangat rumit yang harus bisa dipecahkan oleh kita semua Hakim juga manusia biasa dapat menentukan kematian seseorang, yang mungkin masih segar bugar, dan sebenarnya orang tersebut masih menginginkan untuk hidup, mengapa pasien yang juga sebagai manusia biasa, menderita sakit yang tak terhingga, tidak dapat menentukan kematian atas dirinya sendiri ? Bukankah kematian yang diminta pasien itu merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai suatu tujuan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Bila jalan pikiran seperti tersebut di atas diterima untuk menyetujui prinsip euthanasia, maka kehendak pasien untuk mati itu juga merupakan suatu asasi. Oleh karena itu, apabila seorang dokter menolak permintaan mati seseorang pasien yang sangat menderita, karena sakit yang tak dapat disembuhkan lagi, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sejalan dengan ini, dalam dunia kedokteran, orang yang menyetujui prinsip euthanasia, dilakukan atas dasar perikemanusiaan terhadap sesama manusia, barangkali dapat ditempuh jalan tengah yang bertitik tolak pada prinsip euthanasia. Jadi, seorang tertuduh yang dijatuhi pidana mati, hendaknya diberi kesempatan untuk mempergunakan hak asasinya, yaitu “hak untuk hidup”. Dengan cara tersebut di atas, baik “hak untuk hidup” dan “hak untuk mati”, kiranya sama-sama dihargai oleh hukum, terutama hukum pidana. Dengan diakuinya “hak untuk hidup” dan “hak untuk mati” dari manusia, dimaksudkan 22 untuk melindungi manusia terhadap penganiayaan atau penyiksaan dan kekejaman serta untuk melindungi terhadap tindakan yang tidak berperikemanusiaan dari sesama umat manusia. Hak asasi manusia yaitu hak-hak dasar yang dimiliki manusia melekat dalam dirinya, bukan diberikan oleh masyarakat dan hukum positif melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusi. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari bahasa asing “Droit de I’homme (bahasa Perancis), Human Rights (bahasa Inggris). Dalam pemakaiannya di beberapa negara, dikenal pula istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang dinyatakan sama dengan Human Rights seperti Natural Rights, Basic And Indubitable Freedoms, Fundamental Rights, Civil Rights dan lain sebagainya (Prakorso dan Nirwanto, 1984: 28). Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia dimulai di Inggris pada tahun 1688, di Inggris terjadi perebutan kekuasaan antara Raja James II (Katholik) dengan saudaranya Mary II (Protestan) yang dimenangkan oleh Mary II/William II (suaminya). Konflik tersebut dinamakan Gloriuos Revolution (Revolusi Besar). Kemudian Raja William II menyusun Declaration and Bill of Rights 1689, berisi pengakuan bahwa hak-hak rakyat dan anggota parlemen tidak boleh diganggu gugat (dituntut) atas dasar ucapan-ucapannya. Adanya Bill of Rights tersebut merupakan awal menuju ke monarkhi konstitusional (Anonimous, 1983, p. 209). Bill of Rights merupakan salah satu dokumen penting untuk menghormati hak asasi manusia. Kalau kita lihat kembali perkembangan perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat, pada tahun 1776 disusunlah Piagam Bill of Rights (Virginia). Piagam tersebut merupakan kesepakatan 13 negara Amerika Serikat yang 23 pertama. Dalam Bill of Rights tersebut memuat ketentuan antara lain: semua manusia, karena kodratnya, bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan (dirampas) dengan sifat kemanusiannya. Hak tersebut antara lain; hak hidup/kebebasan, hak memiliki, hak kebahagiaan dan keamanan. Kemudian hak asasi manusia dipertegas lagi lewat Declaration of Independence, 1788, asasnya pengakuan persamaan manusia, Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Pengakuan hak asasi manusia dipertegas lagi oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang diucap pada tahun 1941. unngkapan Franklin D. Roosevelt dikenal dengan Four Freedom, isinya: 1. Kebebasan (kemerdekaan) berbicara (freedom to speech) 2. Kebebasan beragama (freedom to religion) 3. Kebebasan dari kemiskinan (freedom from want) 4. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear) Dengan demikian, dalam hak asasi manusia terkandung beberapa sumpah yang dapat dibenarkan: a. Hak asasi manusia berasal/bersumber dari Tuhan sering disebut hukum alam diberikan/dimiliki seluruh manusia perindividu tanpa membedakan status orang perorang, b. Dalam hak asasi mengarah/mengutamakan lebih dahulu kepuasaan batin (spiritual need) semua pihak yang dapat memberi konstribusi positif dan aktif pada kepuasan lahir (biological need), 24 c. Penjabaran/aplikasi hak asasi manusia berkembang terus seirama dengan perkembangan pikir, budaya, cita-cita manusia dan iptek, d. Manusia yang kehilangan hak asasi manusianya, ia menjadi robot hidup yang hanya bernapas. e. Keberadaan hak asasi manusia tetap “melekat” pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil/dicabut, kecuali ada pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku, lewat keputusan hukum yang adil dan benar, f. Keberadaan negara, antara lain untuk menghormati dan mempertahankan hak asasi manusia sesuai dengan kesepakatan bersama demi pengembangan martabat kemanusiaan, g. Kesabaran memiliki dan melaksanakan hak asasi harus dikaitkan pula dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi. Sebagaimana diketahui, salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, agar cepat tercapai, kata Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh H.A. Masyhur Effendi, “negara hukum (Allgemeene Staatslehre) akan lahir, apabila sudah dekat sekali identiet der Staatsordnung mit de rechtsordnung – identitas susunan negara dengan susunan hukum – semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat, semakin dekat kita pada pelaksanaan negara hukum yang sempurna”. Dengan demikian, negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak azasi manusia tidak dapat dan tidak tepat untuk disebut sebagai negara hukum. Para ahli Eropa Kontinental (Eropa daratan), antara lain Immanuel Kant, Julius Sthall menyebut rechsstaat, sedangkan para ahli hukum Anglo Saxon (Inggris atau 25 Amerika) memakai istilah Rule of Law. Sthall menyebut adanya empat unsur dari rechsstaat yaitu: 1. Adanya pengakuan hak asasi manusia, 2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, 3. Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur), 4. Adanya Peradilan tata Usaha Negara. Dalam Rule of Law menurut A. V. Dicey mengandung tiga unsur dari rechsstaat:: 1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang, 2. Persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law), 3. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law) dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Dari sudut pandang ini terbukti bahwa dengan disusunnya seperangkat aturan hukum yang utama, dan bagaimana hak asasi manusia dilindungi, karena tanpa adanya perlindungan hukum yang disepakati bersama, nasib hak asasi manusia hanya akan merupakan satu kekuatan potensial yang sulit direalisasikan. Persoalan hukum lebih lanjut, yaitu bagaimana mengkonstitusikan nilai-nilai hak asasi dalam satu negara, sehingga setiap pejabat negara, pimpinan masyarakat maupun semua warga negara menjadi terikat secara konstitusional untuk melaksanakannya, sehingga penyelewengan atau tindakan di luar konstitusi (tindakan inkonstitusional atau akonstitusional) akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kalau dikaitkan dengan hasil keputusan dalam pertemuan para ahli hukum di Bangkok 1965 yang 26 diselenggarakan oleh International Comission of Jurist, telah memperluas makna atau syarat Rule of Law sebagai berikut: 1. Adanya perlindungan konstitusional, 2. Adanya kehakiman yang bebas dan tidak memihak, 3. Pemilihan umum yang bebas, 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroperasi, 6. Pendidikan warga negara (civil education). Adanya persamaan prinsip dengan ide hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa antara negara hukum dengan penegakan hak asasi merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda. Hal ini membawa konsekuensi kepada kita untuk memilih sekaligus mengisi konsep hukum apa dan bagaimana yang ditetapkan. Dalam menetapkan konsep tersebut, berbagai aspek pasti akan mendapat pertimbangan (aspek kultural, sosial, ide, pandangan hidup/citacita/tujuan bangsa yang bersangkutan dan lain-lain), serta berkaitan pula dengan bagaimana cara mengimplementasikan, mengatur, menyusun struktur/mekanisme yang tepat dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, ada keserasian antara cita-cita hukum, baik dalam arti umum dan khusus. Lewat cara penyajian dalam satu struktur yang tepat, akan menghasilkan keputusan yang tepat pula. Tanpa adanya keserasian tersebut, maka cita-cita hukum yang begitu indah dan mulia akan tetap berada pada alam abstrakt dan menjadi bagian dari ius constituendum (hukum yang masih dianggap perlu, namun belum efektif) tidak menjadi ius constitutum (hukum yang telah ada/hukum positif). Dari pasangan ini 27 terbukti bahwa faktor “pengaturan/penyaluran” serta ide dan cita-cita bangsa yang bersangkutan memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana mengalokasikan begitu banyak ide, cita-cita besar bangsa dalam berbagai kekuatan/kelompok/lembaga yang tepat dengan pembagian tugas yang tegas pula, diharapkan akan menghasilkan satu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Kepuasan tersebut akan relatif langgeng manakala segi-segi keterbukaan dan dinamika masyarakat menjadi pegangan dan perhatian para pejabat negara. Kalau dianalisa lebih dalam, hukum itu sendiri hakikatnya mempunyai jati diri dan kepribadian. Keberadaan hukum, merupakan satu substansi yang sudah ada. Keberadaan hukum itu sendiri bergumul dan menyatu dengan inti hukum yang paling murni, keseimbangan/keadilan. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, hukum selain berisi kaidah/cita-cita, tetapi berfungsi juga sebagai alat untuk mengubah/merekayasa masyarakat berfungsi (as a tool of social engineerin) sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosce Pound. Posisi hukum semakin mantap bilamana tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dipadukan. Dengan demikian kerja/tugas dan peranan hukum akan mudah dipahami, terutama dalam menghadapi masalah-masalah konkrit yang timbul dalam masyarakat, sehingga cita-cita hukum dapat segera terlaksana. Karena itu, terciptanya yang dianggap adil, atau terciptanya keseimbangan yang dianggap seimbang secara proporsional dan utuh, harus dikaitkan pula dengan fungsi hukum secara konkrit dalam masyarakat, sehingga tingkah laku yang diatur, pada hakikatnya demi ketertiban, kebenaran dan keadilan pula. Dari uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa hukum dalam masyarakat yang semakin moderen memerlukan sistem pemerintahan yang moderen pula, terutama 28 didalam mengikutsertakan warga masyarakat dalam membuat suatu produk hukum. Negara dilihat dari sisi dan pendekatan hukum, merupakan organisasi yang didirikan dan dipercaya untuk melindungi warga negaranya dengan hak menetapkan/menyusun seperangkat aturan hukum (baik tertulis, maupun tidak) semata-mata demi kebahagiaan, ketenteraman, kemakmuran bersama, serta berkewajiban dan bertanggungjawab pula atas pelaksanaannya secara objektif. Istilah asas hukum (general principal of law), menurut kamus Webster berarti basic, rule of conduct dan integrity, atau menurut Merriam Webster Pocket Dictionary, mengandung makna antara lain source, origin, basic truth of law; dengan demikian, menurut Sunaryati Hartono, “suatu asas hukum harus berperan sebagai sumber (source) atau asal (origin) yang mengandung suatu kaidah atau kebenaran dasar (basic truth) yang memberi arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkrit, sehingga seluruh bidang hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh” (Hartono, 1987;6). Karena itu beberapa Pasal tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 1945, antara lain Pasal 27 (2), 28, 29, 31 dan dalam berbagai undang-undang pokok yang ada, merupakan asas hukum yang perlu segera diperinci. 29 BAB III METODOLOGI PENELITIAN Untuk meneliti tentang euthanasia dalam perspektif hukum hak asasi manusia metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis dan filosofis pengaturan HAM tentang hak hidup dan larangan mencabut hak hidup seseorang. Dengan tahapan penelitian sebagai berikut: 1. Identitas Bahan-Bahan Hukum Meliputi studi kepustakaan tentang bahan hukum primer dan sekunder serta tertier yang menjadi objek penelitian terutama menyangkut masalah doktorinal yang menjadi asas dan landasan pengaturan dibidang hak asasi manusia tentang hak hidup dan atau hak untuk mempertahankan kehidupan. 2. Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berupa studi dokumen untuk melihat azas-azas hukum, sistimatika hukum dan sinkronisasi dan peraturan (Soekamto, 1984:30). Data lain yang dikumpulkan berupa bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder seperti buku-buku, Jurnal, Mediamasa dan bahan-bahan lain yang menyangkut etika kedokteran dan hak asasi manusia. Pengumpulan data lain berupa kecenderungan praktek euthanasia dalam praktek kedokteran sebagai bahan untuk membandingkan doktrin hukum tentang HAM dan ilmu kedokteran. 30 3. Analisa Bahan Hukum Analisa data meliputi analisa secara deksriptif yuridis untuk menggambarkan asas hukum dan sistimatika pengaturan tentang undang-undang praktek kedokteran disinkronisasikan dengan undang-undang tentang HAM, untuk mendapatkan gambaran yang tepat terhadap landasan perlindungan hak hidup dalam praktek kedokteran. 31 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Euthanasia Dikaitkan Dengan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam praktek euthanasia merupakan problematik yang spesifik apakah itu melanggar hak asasi manusia atau tidak. Dalam praktek biasanya pasien yang sekarat tidak mampu lagi menyatakan kehendaknya atau membuat pilihan dan nasib dari pasien itu sudah berada di tangan dokter. Biasanya dalam praktek apa yang menjadi kehendak pasien diwakili oleh keluarga atau orang yang paling dekat yang menyetujui untuk melakukan tindakan medik. Masalah euthanasia ini timbul, yaitu dari adanya suatu dilema di atas, apakah seorang dokter mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup seorang pasien, atas permintaan pasien itu sendiri atau dari keluarganya, dengan dalih untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan. Persoalan yang paling spesifik disini menyangkut siapakah yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika terjadi praktek euthanasia apakah dokter, pasien atau keluarga yang menyetujui dilakukan praktek euthanasia. Kriteria kematian karena permintaan sendiri (self determination) dan kematian karena malpraktek yang dilakukan oleh dokter masih merupakan problematik dalam penentuan konteks pelanggaran hak asasi manusia. Dengan diketemukannya alat-alat kedokteran modern seperti “respirator” dan sistem transplantasi, maka kriteria kematian justru lebih sulit untuk diterapkan. Dikatakan, bisa saja suatu waktu pernapasan dan peredaran darah seseorang 32 mendadak berhenti. Apakah yang demikian sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut sudah meninggal. Apabila kita menganut definisi daripada kematian pada umumnya secara yuridis tradisional, maka dalam keadaan tersebut orang itu sudah dapat dikatakan meninggal. Dalam banyak kasus, pengadilan selalu beranggapan bahwa selama orang masih bernapas, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan meninggal. Namun dalam perkembangan, dimana definisi kematian merupakan persoalan medis, orang dalam keadaan koma tapi masih bernapas, belum tentu sudah meninggal, walaupun seluruh organ sudah mati tapi produksi listrik pada otak masih merangsang maka belum dapat dikatakan mati. Jadi untuk memastikan adanya kematian, perlu dilakukan oleh tim dokter, yang terdiri dari dokter yang merawatnya ditambah dengan seorang atau lebih neurolog. 1. Euthanasia dari aspek ilmu kedokteran Dalam perspektif ilmu kedokteran kriteria kematian dan menghilangkan nyawa terhadap pasien yang sedang sekarat menjadi hal yang mudah sekaligus rumit. Aspek kematian dalam perspektif ilmu kedokteran tentu tidak sama dengan kematian pada umumnya yang dikenal orang terutama pasien yang dalam keadaan koma yang sudah kehilangan kesadarannya. Kapan terjadinya pembunuhan atau pelanggaran atas hak hidup dari pasien yang dalam keadaan koma sangat sulit dibuktikan dan memerlukan saksi ahli dalam hal ini tim dokter spesialis. Penderita yang sudah sekarat dan tidak sadar berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, tetapi masih mampu hidup karena dibantu dengan sebuah respirator dengan demikian hidup pasien tersebut tergantung sepenuhnya kepada bantuan respirator itu. Apabila respirator ini dicabut, maka hidup si pasien akan 33 segera berakhir. Masalahnya sekarang menjadi pelik dan rumit, bila seorang pasien yang sudah sekarat dan tidak sadar selama berbulan-bulan, dan mengetahui bahwa tidak lama lagi maut akan merenggut nyawanya, ia atau keluarganya memohon kepada dokter untuk mengakhiri penderitaannya dengan jalan mencabut”respirator tersebut. Bagaimana sikap seorang dokter dalam menghadapi kenyataan seperti ini. Dalam konteks mana self determination atau hak meminta mati dari pasien diterapkan terutama menyangkut batasan-batasan yuridis terhadap hak tersebut. Dalam keadaan seperti ini apakah keluarga berhak mewakili pasien memintakan hak untuk mati sebagai implementasi dari self determination. Aspek lain menyangkut bagaimana dengan dokter yang menyetujui permintaan tersebut, apakah dokter itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena mencabut kehidupan seseorang. Hal inilah yang sangat sulit untuk dipecahkan, sebab disatu sisi pasien merasa sudah tidak sanggup untuk menanggung penderitaan, karena ia sadar bahwa segala usaha atau bantuan yang diberikan baik oleh Dokter maupun keluarganya sudah tidak ada gunanya, dan dia merasa bahwa dia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, begitupun halnya dengan Dokter, dia dahadapkan pada dua pilihan yaitu antara perasaan kasian melihat penderitaan pasien yang sudah sekarat dan kode etik kedokteran yang harus dipeganngnya teguh yakni bahwa bagaimanapun keadaan pasien, sebagai seorang dokter dia berkewajiban untuk memberikan dan mengusahakan penyembuhan sebaik mungkin. Ditambah lagi dengan nantinya dia harus bertanggungjawab atas perbuatannya dihadapan hukum karena melanggar hak asazi manusia (mencabut nyawa) dengan membantu 34 atau membiarkan seorang pasien mati dengan cara tidak memberikan lagi pertolongan medik. Dalam Universal Declaration Of Human Rights dari PBB telah mencantumkan sejumlah hak-hak asasi manusia. Begitu pula di dalam UndangUndang Dasar 1945, walaupun tidak secara terperinci seperti yang terdapat dalam deklarasi PBB itu. Di antara sekian banyak hak-hak asasi manusia itu mungkin hanya hak untuk mati saja yang tidak ada. Walaupun kedengarannya sangat ganjil, tetapi hal ini cukup mengundang minat para ahli untuk memperbincangkannya, karena “hak untuk mati” ini dipandang sebagai telah tercakup pengertiannya di dalam “hak untuk hidup” yang selama ini dicantumkan secara tegas. Jenis kematian menurut cara terjadinya, meliputi: orthothanasia, dysthanasia dan euthanasia. Orthothanasia dan dysthanasia, kiranya tidak perlu dibahas karena permasalahan dibatasi pada pokok masalah dalam tulisan. Dan jenis kematian yang ketiga, yang masuk dalam kategori euthanasia atau biasa disebut juga sebagai mercy killing. Pada prinsipnya hak untuk mati sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab dokter. Tanggung jawab dokter dibagi dalam dua bagian yaitu tanggung jawab profesional dan tanggungab jawab hukum. Tanggung jawab profesional dokter diatur dalam kode etik kedokteran yang disebut “Tuchtrecht” artinya seorang dokter mempunyai tanggung jawab profesional terhadap sejawatnya dan profesinya. Dengan demikian apabila terbukti melakukan kesalahan, misalnya karena kelalaian, maka dikenakan tanggung jawab hukum dan diadili. (Soekanto, 1989;147) Sebagai seorang manusia biasa, sang dokter tidak sampai hati menolak permintaan dari pasien dan keluarganya itu. Apalagi keadaan sipasien yang sudah 35 sekarat berbulan-bulan dan dokter tahu bahwa pengobatan yang selama ini diberikannya itu sudah tidak berpotensi lagi. Dikatakan mati, masih bernapas, sekalipun secara “artificial”. Dipihak lain jika dokter memenuhi permintaan pasien dan atau keluarganya itu maka dokter telah melanggar sumpah dan hukum. Sebab melalui pertolongannya itu, misalnya dengan mencabut “respirator”, ia telah mengakhiri hidup seseorang penderita, apalagi seseorang penderita tersebut telah dipercayakan kepadanya untuk selalu dijaga mengenai kehidupannya. Dia telah melanggar sumpah dokter yang telah diucapkannya sebelum menjalankan profesinya sebagai dokter. Maka menurut hemat penulis, sekalipun atas dasar hak untuk menentukan nasib sendiri, seseorang tidak dibenarkan meminta dirinya dieuthanasia,dan keluarga atau dokter juga tidak boleh melakukan tindakan euthanasia hanya atas dasar kasihan. Sebab kalau kita berpikir lebih jauh sebenarnya disaat yang sedang sangat sulit itulah kita diuji seberapa besar keimanan kita kepada Allah, karena sebenarnya betapapun beratnya penderitaan yang dialami pasti ada hikmah dibalik semua itu. Karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan manusia untuk menyelesaikannya. Meskipun hak menentukan nasib sendiri (the right of self determination) tidak disebutkan secara eksplisit dalam Universal Deciaration of Human Rights, namun hak untuk menentukan nasib sendiri ini diatur secara khusus pada Instrumen Hukum hak Asazi manusia yakni dalam ICCPR. Pada hakekatnya hak ini merupakan hak alas bagi hak-hak dasar tertentu, termasuk hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Dalam deklarasi yang disebut di atas ditemukan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagai berikut: 36 Pasal 3 : "Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan dirinya" Pasal 5 : "Tak seorangpun boleh disiksa dan dianiaya atau diperlakukan dengan bengis, tak berperikemanusiaan atau diperkosa hak-hak asasinya ..." Pasal 9 : "Tak seoran-pun boleh ditahan dengan sewenang-wenang…..” Pasal 12 : "Tak seorangpun boleh digangu kepasiniannya (privacynya) maupun kerahasiaan surat-menyuratnya…” Pasal 18 : "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan suara dan kata hatinya..." Lebih lanjut Leenen mengemukakan bahwa dalam "International Covenant of Civil and Political Rights" (1966) terdapat beberapa ketentuan mengenai hak-hak dasar individual yang penting sekali dalam hubungannya dengan menentukan nasib sendiri (Zef-beschikkingsrecht), sebagai berikut: Pasal 1 : "Setiap orang mempunyai hak menentukan nasib sendiri" Pasa1 6 : "Setiap orang mempunyai hak untuk hidup ... Tak seorang-pun boleh dirampas nyawanya dengan semena-mena" Pasal 7 : "Tak seorangpun boleh disiksa dan dianiaya atau diperlakukan dengan bengis, tak berperikernanusiaan dan diperkosa hak-hak asasinya..., khususnya tanpa persetujuannya tak seorangpun boleh diobati dan dirawat atau diikutsertakan dalam eksperimentasi medik" Pasa1 9 : "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan dirinya" 37 Pasal 10 : "Orang-orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dengan menghormati harkat dan martabatnya sebagai manusia" Pasal 17 : "Tak seorangpun boleh dilecehkan kepasiniannya (privacynya) atau kerahasiaan surat-menyuratnya Pasal 18 : "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan suara dan kata hatinya….” Pasal-pasal diatas pada prinsipnya mengemukakan hak-hak dasar dari manusia yang tidak bisa dilecehkan termasuk hak-hak kepasiniannya (privasi) yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun (Leenen, 1978;57). Konsep dasar hak asasi manusia terfokus pada hak setiap orang atas kebebasan dan keamanan terhadap diri sendiri termasuk pasien yang tidak pengidap menyakit menular. Penahanan atas orang-orang yang mengidap penyakit menular, satu dan lain guna mencegah penyebaran penyakit menular tersebut adalah sah. Kemudian penahan sah atas orang-orang yang terganggu perkembangan pertumbuhan jiwanya, para pemakai minuman keras secara berlebihan, kecanduan obat bius dan gelandangangelandangan.” Khusus untuk pasien menular maka penerapan atas asas kebebasan dibatasi karena bisa membahayakan orang lain. Mengenai keamanan diri seseorang, tampaknya masih perlu dirinci lebih lanjut lagi, terutama ruang lingkup jangkauannya. Setiap orang mempunyai hak agar kehidupan pribadi dan keluarganya dihormati, demikian pula kerahasiaan surat-menyuratnya.” Hak ini berlaku umum dan tidak hanya terbatas pada intervensi pihak penguasa saja. Jadi pada prinsipnya setiap individu berhak mendapat perlindungan dari pemerintah 38 terutama menyangkut hak-hak pribadi termasuk hak asasi manusia. Konsep perlindungan yang harus diberikan pemerintah menyangkut jaminan rasa aman, jaminan ketenangan dan kebebasan untuk beraktifitas. Hak ini tidak mengenal pembatasan, sekalipun suara atau kata batin dalam situasi dan kondisi tertentu tidak dapat dijangkau. Namun dalam kaitan ini perlu diatur lebih lanjut mengenai apa yang disebut keberatan-keberatan suara batin. Saat ini tampaknya belum ada satu negara pun yang mengatur masalah hak-hak menentukan nasib sendiri warganegara dalam pelayanan kesehatan secara konstitusional. Padahal menurut penulis hal ini bisa menjadi alasan sesesorang untuk mendapatkan hak tersebut. Dalam artian apabila tidak ada pembatasan mengenai seberapa jauh atau dalam hal apa self determination bisa dimiliki oleh seseorang maka hal ini bisa menimbulkan salah penafsiran. Karena seperti yang tertuang dalam Instrumen Hukum Hak Azazi manusia Internasional (ICCPR), bahwa self determination itu diperuntukan bagi negara yang dibawah tekanan negara lain atau orang yang ingin mendapatkan suaka. Nah, kalau hal ini tidak dipertegas atau dibatasi, maka self determination tersebut bisa jadi dasar bagi seseorang yang sudah sakit parah untuk minta dirinya di euthanasia.Padahal dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia tidak saja mengatur mengenai hak Asazi setiap orang tapi juga diatur mengenai kewajiban dasar dan pembatasan dan larangan terhadap Hak-hak tersebut. Untuk itu menurut hemat penulis sebaiknya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN memikirkan pengaturan hal-ikhwal tentang hak-hak asasi pada umumnya dan hak menentukan nasib sendiri secara regional melalui traktat, dan untuk pemerintah Indonesia lebih mempertegasnya lagi dalam suatu aturan, 39 sehingga hal tersebut bisa menjadi landasan bagi orang, keluarga dan Dokter dalam menghadapi kasus euthanasia. Hak menentukan nasib sendiri adalah hak fundamental manusia. Sekalipun hak tersebut berbeda antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain, namun pada hakekatnya keinginan manusia untuk mengatur kehidupan sendiri sesuai dengan pandangan pribadinya, mengadakan pilihan-pilihannya sendiri, bahkan merencanakan sendiri pembentukan dan pengambilan keputusan untuk dirinya sendiri merupakan sesuatu yang diakui umum. Memang tak dapat disangkal bahwa dalam masyarakat yang berwatak kolektivitas tidak sama luas-lingkup hak dasar ini dibandingkan dengan apa yang berlaku bagi warganegara masyarakat yang individualistis. Jadi, dapat disimpulkan di sini, otonomi manusia merupakan fundamen eksistensinya, sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Internasional Hak-Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu hak asasi manusia diperolehnya kerana ia manusia. Hak ini asli dan murni, tidak diberikan kepada manusia oleh negara atau masyarakat, sekalipun tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam negara dan masyarakat terdapat pembatasanpembatasan tertentu terhadap hak-hak asasi tersebut.Untuk itu menurut penulis memang harus ada batasan dalam hal mana self determination dapat digunakan oleh setiap orang. Pendekatan filosofi terhadap hak menentukan nasib sendiri bertolak dari pemikiran bahwa manusia itu mempunyai kebebasan dan otonomi untuk menentukan kehendaknya sendiri. Henkel dalam bukunya “Einfhrung in die Rechtsphilosophie” 1964, menguraikan hak menentukan nasib sendiri sebagai 40 berikut “der von Sinn, Zweck-und Werrerfassen getragenen, geistgelenkten willenssteurung” (Kehendak yang secara sadar diarahkan oleh jiwa menuju sesuatu tujuan yang pasti). Namun tujuan disini tampaknya terlalu luas dan samarsamar, karena penentuan nasib sendiri dapat diarahkan, baik secara positif maupun negatif. Dengan adanya hak menentukan nasib sendiri maka manusia diberi pula tanggung jawab. Tanpa hak menentukan nasib sendiri, tidak mungkin manusia dapat menilai benar atau salah dalam tindakan-tindakannya. Selain mempunyai kebebasan, pada hakikatnya manusia ditentukan pula oleh faktor-faktor lain, seperti aspek-aspek biologis, psikis dan sosial. Sebagaimana Leenen mengungkapkan bahwa interaksi berbagai faktor tersebut telah menempatkan manusia dalam suatu keadaan dimana ia harus hidup dalam keterkaitan antara hak dan kebebasan. Manusia merupakan makhluk biologik. Psikis dan sosial, kenyataan ini memberikan kepadanya kemampuan untuk bertindak bebas dalam keterkaitan itu. Hak menentukan nasib sendiri dalam pelayanan kesehatan tampaknya akan memegang peranan penting dikemudian hari, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dalam kurun waktu lima puluh tahun belakangan ini memperlihatkan gebrakangebrakan dan lonjakan-lonjakan yang luar biasa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hak yang disebut di atas itu. Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa sisi permintaan dalam pelayanan kesehatan jauh melebihi sisi penawaran, maka akan lebih terasa lagi campur tangan birokrasi dan hal ini bisa menjadi ancaman bagi hak-hak asasi manusia, terutama hak menentukan nasib sendiri. Maka menurut hemat penulis pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan lebih menitik beratkan perhatian kepada masyarakat 41 bawah dengan cara memberi pasilitas atau pelayanan kesehatan murah kepada mereka yang kurang mampu untuk menghindari terjadinya kasus euthanasia, sebab seperti yang kita ketahui bahwa selain penderitaan yang sudah tidak tertahankan, penyebab orang minta dirinya untuk di euthanasia karena tidak adanya biaya untuk berobat, apalagi bagi orang yang difonis dokter bahwa penyakitnya tidak mungkin disembuhkan pada umumnya mengidap penyakit ganas yang proses penyembuhannya memerlukan biaya yang sangat mahal. Disinilah dituntut keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang mungkin bisa terjadi. Untuk itu perlu dikemukakan di sini bahwa hak menentukan nasib sendiri sebagai hak alas (basisrecht) hak-hak lain dalam pelayanan kesehatan harus dilihat dari konteks sosialnya. Dalam hubungan ini kita tidak hanya menelaah hak manusia secara individu, melainkan hak-hak manusia seanteronya. Karena bagaimanapun juga syarat pertama dan utama di sini ialah hukum harus memberikan kepada seluruh warga negara kedudukan yang setara dan hak-hak yang sama secara proporsional. Untuk itu menurut penulis sebaiknya pemerintah lebih bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat terutama orang-orang yang menderita penyakit yang difonis dokter tidak mungkin untuk sembuh, yang kerena keterbatasan dan keadaan yang miskin sering menyerah pada nasib sampai-sampai momohon untuk disuntik mati demi meringankan penderitaan baik untuk dirinya dan keluarganya karena merasa tidak mungkin lagi untuk sembuh dan hanya menjadi beban keluarga. 2. Euthanasia, Suicide dan Ajaran Agama 42 Dalam konteks pemahaman agama, hidup adalah milik Tuhan dan tidak seorangpun yang berhak mengambil kehidupan kecuali Tuhan Sang Pencipta yang mengambilnya. Prinsip tersebut menyebabkan, dalam agama orang membagi kematian dalam dua bentuk yaitu kematian karena kehendak Tuhan dan kematian bukan karena kehendak Tuhan (kehendak diri sendiri) atau kesengajaan membiarkan kematian terjadi. Dalam konteks pengajaran agama pembunuhan atau bunuh diri merupakan dosa karena mengakhiri hak hidup sebagai pemberian Tuhan dan hanya Tuhanlah yang berhak mencabut nyawa seseorang. Itulah sebabnya pembunuhan dan bunuh diri dilarang oleh agama. Masalah euthanasia biasanya dikaitkan dengan masalah suicide atau bunuh diri. Dalam hukum pidana, masalah suicide yang perlu dibahas adalah apakah seseorang yang mencoba bunuh diri atau membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri itu dapat dipidana, karena dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, seseorang yang gagal melakukan bunuh diri dapat dipidana. Jadi, perbuatan bunuh diri yang gagal ini merupakan Strafbaarfeit. Begitu pula di negara Israel, percobaan bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dilihat dari segi agama, baik itu agama Islam, Kristen, Katholik, dan sebagainya, maka euthanasia dan suicide merupakan perbuatan yang dilarang. Sebab masalah kehidupan dan kematian seseorang itu hanya berasal dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Jadi, perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada tindakan penghentian hidup yang bukan berasal dari Yang Mahaesa itu, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, oleh karenanya tidak dibenarkan. 43 Dalam hal ini agama Islam, yang secara mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia, jelas melarang adanya euthanasia dan suicide. Sehubungan dengan hal ini, Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Annas r.a. sebagai berikut : “Bahwa Rasulullah pernah bersabda : Janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena kesukaran yang menimpanya. Jika memang sangat perlu dia berbuat demikian, maka ucapkanlah doa sebagai berikut : Ya Allah ! Panjangkanlah umurku, kalau memang hidup adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku manakala memang mati lebih baik bagiku.” Dari bunyi Hadits tersebut di atas, dinyatakan secara jelas bahwa euthanasia itu dilarang dalam ajaran Islam. Disamping itu banyak sekali ayat-ayat suci Alquran dan Hadits-hadits Nabi yang lain, yang melarang adanya suicide, karena kebosanan akan hidup, dan umumnya karena takut akan tanggung jawab hidup. Tindakan demikian ini sangat diharamkan oleh ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Alquran seperti di bawah ini : a.Surat An Nisa’ ayat 29 : “Hai orang-orang beriman. Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” b.Surat Al An’aam ayat 151 : “Katakanlah ! Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yakni : Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anakanakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada 44 mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu supaya kamu memikirkannya.” c. Surat Al Isra’ ayat 31 : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarant. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” d.Surat Al A’raf ayat 34 : “Bagi tiap-tiap umat itu ada batas waktu tertentu (ajal / mati), sebab itu bila datang waktunya itu, mereka tidak dapat mengulurkan barang seketika dan tidak pula dapat mempercepatnya”. Dari ayat-ayat Alquran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam melarang orang untuk melakukan bunuh diri (Surat An-Nisa’ ayat 29) karena Tuhan adalah kasih dan sayang kepadanya. Larangan keras seseorang membunuh orang lain, karena takut akan kemiskinan dan kemelaratan (Surat Al An’aam ayat 151 dan Surat Al Isra’ ayat 31). Sedang Surat Al A’raf ayat 34 mengajarkan bahwa masalah mati dan hidup manusia itu ada di tangan Tuhan, sehingga manusia tidak dapat menentukannya. Motif pembunuhan pada umumnya karena ketakutan akan penderitaan hidup atau kemiskinan, dan selanjutnya karena bosan akan hidup. Semua tindakan kriminil yang berpangkal kepada ketakutan hidup, dibenci oleh Tuhan. Larangan bukan saja terhadap tindakan pembunuhan, bahkan juga meminta mati saja dilarang keras oleh Islam. 45 Menurut keterangan Annas bin Malik r.a. (yang diriwayatkan oleh Ahmad), pernah Nabi berkunjung kepada seseorang yang sangat menderita sewaktu “sekarat” menghadapi kematian. Peristiwa itu sangat mengejutkan Nabi, kasihan melihat penderitaan dahsyat pada akhir hayatnya orang itu. Lalu terjadilah tanya-jawab antara Nabi dengan dia : + Apakah pernah Anda mendoa atau meminta sesuatu kepada Allah ? - Ada ! Saya meminta Allah supaya segala siksaan yang akan saya terima di akhirat nanti biarlah Tuhan melakukannya di dunia. + Subahhanallah ! Pasti anda tidak akan kuat menanggungnya ! Bukankah Saya sudah mengajarkan doa yang berbunyi, “Ya Allah, Berikanlah kami kebahagiaan di dunia, serta peliharalah kami dari siksa neraka.” Dengan adanya larangan pada Hadits Nabi tersebut, maka kedua pihak tidak boleh : meminta mati karena tidak tahan penderitaan dunia, begitu juga meminta siksaan di dunia supaya nanti di akhirat tidak disiksa lagi. Dalam kedua peristiwa ini, Nabi memperingatkan doa yang selalu diajarkannya, supaya mohon bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ditinjau dari segi agama Kristen (Katholik / Protestan) yang juga banyak dianut oleh bangsa Indonesia, apa yang diuraikan di atas pun merupakan suatu tindakan yang dilarang. Disamping itu, diajarkan pula bahwa soal hidup dan matinya seseorang itu berada di tangan Tuhan. Sebagai contoh dapat diambil dari Kitab Injil Perjanjian Baru karangan Matius dari hal kuatirkan nyawanya, sebagai berikut : “Sebab itu Aku berkata kepadamu : Janganlah kamu kuatir akan hal nyawamu, yakni apakah yang hendak kamu makan atau minum atau dari hal 46 tubuhmu, apakah yang hendak kamu pakai. Bukankah nyawa itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih dari pakaian ?”(Pil. 4:6, 1 Ptr. 5:7, 1 Tim. 6:6, Ibr. 13:5). “Siapakah di antara kamu dengan kuatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun ?” Dari ajaran ini, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah nyawa seseorang itu adalah lebih penting dari hal-hal lainnya, dan hidup serta matinya seseorang itu ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu manusia tidak akan dapat menentukannya, bila telah dikehendaki Tuhan, manusia tak akan dapat mempercepat ataupun memperlambat barang sedikitpun. Selanjutnya, pandangan religius dari kelompok yang menentang prinsip euthanasia yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dialami manusia itu, sudah menjadi kehendak Tuhan, sebab hal ini mengandung makna dan tujuan tertentu. Tetapi disamping itu, oleh Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk menghilangkan penderitaannya. Namun dalam hal, pengobatan untuk penyembuhan dan menghilangkan penderitaan sudah tidak mungkin lagi dan jalan satu-satunya yang masih mungkin ialah, mengakhiri hidup si pasien tersebut, agar penderitaannya itu dapat segera berakhir. Apabila kematian untuk menghilangkan penderitaan memang diminta oleh pasien, karena merasa jalan lain untuk menghilangkan penderitaan itu sudah tidak ada lagi, mengapa permohonan euthanasia tidak dapat dikabulkan ? Apakah kehendak untuk mati dalam kasus semacam ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu “hak asasi” yang dalam hal ini sebagai “hak untuk mati” ? Jika telah diakui bahwa manusia mempunyai sejumlah hak asasi, apakah dipandang sebagai suatu kesalahan apabila kita mengakui pula adanya “hak untuk mati” terhadap kasus, khususnya kasus semacam ini.Persoalan inilah yang harus kita sikapi bersama, khususnya dalam terang hukum keenam 47 yaitu”jangan membunuh”. Maka menurut penulis, dalam menghadapi masalah ini kita harus lebih dapat memahami tentang berbagai hal, dengan terburu-buru mangatakan bahwa euthanasia sama dengan pembunuhan sama salahnya dengan tanpa pikir panjang mengatakan euthanasia merupakan hak asazi setiap orang. Mengapa?, sebab persoalan kita tidak menyajikan pilihan hitam-putih yang sederhana. Misalnya, pertama, sungguh sulit untuk kalau bukan mustahil menentukan bahwa suatu penyakit benar-benar tidak dapat disembuhkan, kapan orang dapat menentukan dengan pasti bahwa orang yang sakit parah tidak mungkin disembuhkan. Bagaimana mendefinisikan istilah tidak dapat disembuhkan itu? Apakah kanker termasuk didalamnya? Sekarang, mungkin ya. Tapi siapa yang mengetahui perkembangan selanjutnya, beberapa bulan lagi, atau beberapa tahun lagi. Kedua, siapakah yang berhak menentukan bahwa nyawa si A atau si B, tidak perlu dipertahankan lagi? Apakah yang bersangkutan? kalau ya, bukankah dalam pengalaman sehari-hari kita sering mendengar orang yang mengalami sedikit kesulitan begitu mudah mengucap”lebih baik aku mati saja sekarang”padahal itu reaksi spontan belaka. Kalau begitu, apakah keluarga yang lebih berhak mengambil keputusan? mungkin saja. Tapi siapa yang dapat menjamin, bahwa keputusan yang bulat selalu berarti keputusan yang benar? Bagaimana kalau tidak tercapai kesepakatan antara keluarga tersebut. Bagaimana bila dokter? Lebih masuk akal lagi, tapi jangan lupa seorang dokter hanya mempertimbangkan satu aspek saja, yaitu aspek fisik dari kehidupan manusia. Padahal kita tahu bahwa, kehidupan lebih dari itu. Bahkan ada banyak bukti, termasuk kesaksian Paulus, bahwa justru disaat dalam penderitaan yang terdalam, seseorang sering menemukan kekayaan rohani dan sukacita batiniyah yang tak 48 terkatakan. Dan yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, mengabsahkan euthanasia mudah sekali berakses pada pembenaran terhadap pembunuhan semena-mena. Dan keberatan yang paling fundamental adalah bahwa, tak seorangpun dan tidak satu lembagapun di muka bumi ini, yang pernah diberi mandat oleh Tuhan, untuk menjadi pemegang kuasa atas hidup-mati manusia, bahkan atas hidup matinya sendiri. Jadi, apakah dengan demikian saya ingin mengatakan secara mutlak bahwa euthanasia no? tidak juga, yang ingin saya kemukakan disini, pertama bahwa pada dasarnya secara prinsipil, euthanasia tidak dapat dibenarkan, bahwa euthanasia tidak dikehendaki Allah. Dan sebagai konsekuensinya, tidak boleh ada hukum apapun yang mengabsahkan atau membenarkannya. Namun dalam realitas kehidupan menunjukan bahwa selalu saja ada situasi-situasi khusus, yang menuntut kebijakan, keluwesan dan pengecualian dari kita. Bahwa dalam menghadapi situasi ini kekakuan berakibat lebih buruk, jadi memang ada keadaan tertentu, dimana mempertahankan kehidupan berakibat lebih buruk dari pada merelakan kematian. Dalam hal ini, mempraktekan euthanasia tetap salah, bila toh terpaksa dilakukan ia harus dilakukan dengan gentar, penuh penyesalan dan permohonan pengampunan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan syarat, pertama bahwa, keputusan diambil, setelah benar-benar tidk ada kemungkinan lain yang lebih baik, kedua keputusan diambil oleh semua pihak yang terkait, dan setelah mempertimbangkan semua faktor dan terakhir keputusan dilaksanakan, tidak dengan aktif membunuh (misalnya dengan menyuntikan racun) melainkan dengan sekedar membiarkan penderita meninggal secara wajar. 49 Dasar pemikiran seorang hakim dalam menjatuhkan pidana mati, biasanya didasarkan demi kepentingan masyarakat, karena jika tertuduh dibiarkan begitu saja, dapat membahayakan masyarakat dan keamanan negara. Akan tetapi hendaknya jangan dilupakan, bahwa menyelamatkan kepentingan umum dan keamanan negara, bukan satu-satunya jalan dengan menjatuhkan pidana mati. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dan negara tidak harus dilakukan dengan jalan menjatuhkan pidana mati terhadap si terdakwa, sebab masih banyak cara yang dapat ditempuh, misalnya dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, dan lainlain, asal harus diikuti pengawasan efektif dan pembinaan yang kontinyu, sehingga orang yang dipidana penjara ini dapat berubah sikapnya, untuk kembali ke jalan yang benar dan insyaf. Kiranya sejalan dengan ini, maka dalam dunia kedokteran, bagi orang yang menyetujui prinsip euthanasia dilakukan atas dasar perikemanusiaan terhadap sesama manusia, yang tengah menderita sakit, yang tak dapat disembuhkan lagi, seperti di Indonesia sekarang ini, barangkali dapat ditempuh jalan tengah yang bertitik tolak pada prinsip euthanasia. Jadi, seorang tertuduh yang dijatuhi pidana mati, hendaknya diberi kesempatan untuk mempergunakan hak asasinya, yaitu “hak untuk hidup” dan “hak untuk mati”. Apabila tertuduh yang divonis mati tersebut dianggap menerima kematian atas dirinya. Dengan demikian ia dianggap telah mempergunakan “hak untuk mati”-nya, dan pidana mati yang telah dijatuhkan dapat dengan segera dieksekusi. Sebaliknya, bila tertuduh menolak putusan hakim, berarti tertuduh masih ingin hidup, karena ia telah mempergunakan “hak untuk hidup”-nya. Dengan demikian harus dicarikan 50 jalan keluarnya, sehingga kehidupan terdakwa ini betul-betul dilindungi oleh hukum dan dihargai hak asasinya. Dengan cara tersebut di atas, baik “hak untuk hidup” dan “hak untuk mati”, kiranya telah sama-sama dihargai oleh hukum, terutama hukum pidana. Dengan diakuinya “hak untuk hidup” dan “hak untuk mati” dari manusia ini, dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap penganiayaan atau penyiksaan dan kekejaman serta untuk melindungi terhadap tindakan yang tidak berperikemanusiaan dari sesama umat manusia sebagaimana diatur dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Dilihat dari segi perundang-undangan dewasa ini, belum ada pengaturan yang baru dan lengkap tentang euthanasia ini. Tetapi bagaimanapun juga, karena masalah euthanasia menyangkut soal keselamatan jiwa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya mendekati unsur-unsur euthanasia itu. Maka satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Yang paling mendekati dengan masalah tersebut adalah peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2, Bab IX Pasal 344 KUHP. Sebelumnya, kalau diperhatikan pasal-pasal lain yang menyangkut jiwa manusia dalam KUHP ini, seperti Pasal 338, 339, 340, 341, dan lain-lain, maka selain dapat membaca bunyi pasal-pasal itu sendiri, kita pun dapat mengetahui bagaimana sebenarnya pembentuk undang-undang mengenai, pandangannya 51 terhadap jiwa manusia itu. Secara singkat, dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda), menganggap bahwa jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga. Oleh sebab itu, setiap perbuatan apapun motif dan coraknya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar oleh negara. Jadi masalah keselamatan jiwa daripada warga negara, selalu dilindungi negara. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut. “Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat, dan kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.” (Prodjodikoro, 1977;16) Pasal 344 KUHP, disebutkan bahwa :“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari bunyi Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati “membunuh” atau dengan perkataan lain “merampas nyawa” orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolongnya, sekalipun atas permintaan yang bersangkutan karena 52 menderita sakit parah yang tak tersembuhkan misalnya. Namun dalam masa-masa mendatang, karena sesuatu hal tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong sulit untuk dihindari. Lain di pengadilan, lain pula dengan dunia medis. Apabila di pengadilan seorang hakim dapat menentukan kematian seseorang melalui pidana mati yang dijatuhkannya, dalam dunia medis, seorang dokter bahkan diwajibkan senantiasa melindungi mahluk hidup insani, sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Masalah “hak untuk mati” di dunia, terutama di negaranegara maju, masa kini sangat intensif dipermasalahkan. Seorang pasien yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi dari segi medis, kemudian diminta oleh keluarganya supaya penderitaannya dihentikan saja oleh dokter, sering terjadi di negara-negara maju dewasa ini. Bahkan keluarga pasien yang sudah tidak ada harapan lagi itu, mengajukan permintaan kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang supaya memberikan legalisasi untuk mati. Masalah “hak untuk mati” atau the right to die ini berhubungan erat dengan definisi daripada kematian. Hal ini timbul sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa profesi medis pada dewasa ini, sudah mampu menciptakan alatalat maupun mengambil tindakan-tindakan yang dapat memungkinkan seseorang yang mengalami kerusakan otak (brain death), tetapi jantungya tetap hidup dan berdetak dengan bantuan sebuah “respirator”. Di negara-negara maju sudah banyak yang memberikan definisi tentang kematian, tetapi definisi yang diajukan itu hanya bersifat khusus. Jadi, sampai sekarang belum ada yang memberikan definisi kematian secara umum, dan untuk segala tujuan yang bersifat umum. Definisi khusus ini biasanya akibat kemajuan yang telah dicapai dalam bidang 53 medis, sehingga hanya merupakan salah satu kriteria saja, dan terbatas untuk tujuan-tujuan operasi transplantasi organ tubuh (anatomical gifts). Sebagai suatu contoh dapat disebutkan di sini definisi kematian yang telah diterima oleh The American Association tahun 1975, yang menyatakan bahwa kematian adalah : “For all legal purpose, a human body with irreversible cessation of total brain function, according to medical practice, shall be considered dead.” Definisi kematian ini diterima sebagai akibat daripada perkembangan ilmu kedokteran, sehubungan dengan “organ transplants”, pencabutan hak-hak untuk menopang kehidupan seseorang dan menghentikan segala tindakan untuk menghidupkan kembali. Pada perkembangan selanjutnya American Medical Association, tahun 1977 menyatakan tentang suatu definisi perundang-undangan tentang kematian dengan kriteria tersebut di atas. Jauh sebelum itu, yakni tahun 1968 di Amerika Serikat telah ditetapkan didalam The Uniform Anatomical Gift Act bahwa seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih, dapat memberikan seluruh atau sebagian dari badannya pada saat kematiannya untuk tujuan-tujuan riset, pengobatan dan transplantasi. Jadi, jelas bahwa sebenarnya definisi kematian yang bersifat umum itu sangat diperlukan dan tidak hanya terbatas untuk tujuan transplantasi organ saja. Dengan demikian maka seseorang yang “incompetent” yang masih hidup karena dibantu dengan life support system, bisa dicabut life support system-nya, sekalipun tindakan ini akan berakibat kematian bilamana sudah terdapat bukti-butki yang tak dapat dibantah lagi, bahwa kematian biologis tak dapat dielakkan lagi. Hal inilah yang termasuk dalam pengertian “hak untuk mati”. 54 Dalam ilmu kedokteran, dijumpai apa yang disebut sebagai “mati suri” dan “mati yang sebenarnya”. Disamping itu jika dilihat dari saat terjadinya kematian, akan didapati istilah-istilah somatic death dan biological death yang disebut sebagai “mati” dalam ilmu kedokteran adalah biological death. Tetapi dalam perkembangannya yang selanjutnya, waktu yang dua jam itu dapat diperpanjang sampai waktu 24 jam. Selama waktu 24 jam ini orang yang telah meninggal tadi dites secara medis terus-menerus, apakah seluruh sel-sel tubuh manusia ini sudah tidak berfungsi lagi atau tidak. Jadi hal ini hanya merupakan percobaan medis saja. Sekarang masalahnya, bagaimana dengan istilah kematian dalam ilmu hukum ? Biasanya definisi mati yang dipakai di pengadilan-pengadilan terhadap kasus yang terjadi, baik didalam maupun diluar negeri, menganggap bahwa apabila masih bernapas, belum dikatakan mati. Jadi dikatakan mati, apabila orang tersebut sudah tidak bernapas lagi. Memang pada banyak kasus yang terjadi, misalnya pembunuhan, yang menyebabkan kematian, pada umumnya orang yang dibunuh tersebut, setelah tidak bernapas lagi, kemudian dikubur begitu saja. Dengan demikian proses selanjutnya di pengadilan, hakim mendefinisikan bahwa orang tersebut mati terbunuh, yang akhirnya terdakwanya dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang mengatur tentang pembunuhan itu. Kalau dipakai definisi demikian, dan dihubungkan dengan masalah euthanasia, seorang yang sudah tidak bernapas, sedang otaknya masih merangsang, jadi belum dikatakan sebagai brain death, apakah ini juga disebut sebagai mati oleh pengadilan ? Oleh karena itulah, perlu dirumuskan suatu definisi tentang kematian yang bersifat umum, yang dapat menjangkau masalah medis dan juga dalam berbagai kasus yang berhubungan 55 dengan hukum, terutama hukum pidana. Hal ini sangat penting dalam menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan euthanasia, yang selama ini belum dapat ditolerir di Negara-negara yang sedang berkembang, terutama di Indonesia. Walaupun euthanasia merupakan perbuatan yang terlarang dan diancam pidana seperti diatur Pasal 344 KUHP, namun pencantuman larangan ini dirasakan kurang efisien, karena sampai sejauh ini belum ada kasus yang sampai ke pengadilan. Oleh sebab itu, untuk perkembangan selanjutnya, penulis ingin mengetengahkan dua kemungkinan terhadap masalah euthanasia, dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap perumusan Pasal 344 KUHP, ataukah menyatakan bahwa perbuatan euthanasia itu sebagai suatu perbuatan yang tidak dilarang, dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai “dekriminalisasi”. Apabila yang ditempuh adalah tetap mempertahankan euthanasia dalam segala bentuknya sebagai perbuatan yang terlarang, maka perumusan Pasal 344 KUHP perlu ditinjau kembali. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada penuntut untukl memudahkan dalam mengadakan pembuktian terhadap kasus yang terjadi. Selama ini mungkin saja euthanasia ini terjadi di Indonesia. Apakah dengan terjadinya euthanasia itu kemudian penuntut umum dapat membuktikannya ? Sulit rasanya hal ini untuk dipecahkan. Sepanjang yang pernah ditanyatakan oleh penulis kepada para dokter, memang euthanasia (aktif) di Indonesia belum pernah terjadi., kalaupun mungkin ada kasus yang sebenarnya merupakan kasus euthanasia tapi karena pada umumnya masyarakat tidak banyak tahu tentang dunia medis, maka hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai contoh, seorang suami yang meminta tim Dokter sebuah rumah sakit di 56 Jakarta untuk melakukan tindakan euthansia terhadap istrinya, dengan alasan tidak tega melihat kondisi istrinya yang terbaring ditempat tidur tanpa ada harapan untuk sembuh setelah melahirkan anaknya yang kedua, apalagi biaya yang kian menumpuk dan tidak mampu ia bayar mendorongnya untuk mendesak tim Dokter untuk melakukan euthanasia tersebut. Namun permohonanya ditolak karena euthanasia dilarang di Indonesia (permohonan yang dilakukan oleh Hasan Kusuma untuk istrinya agian Isan Nauli tergolek koma setelah operasi cecar/22 oktober 2004) tetapi dengan kemajuan dan perkembangan keadaan yang semakin maju, tidak mustahil euthanasia ini dilakukan secara diam-diam. Karena jelas bahwa para dokter di Indonesia yang terhimpun dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, menganut paham bahwa hidup dan mati tidak merupakan hak daripada manusia, melainkan hak dari Tuhan Yang Mahaesa. Oleh sebab itu, para dokter di Indonesia, tidak menganut prinsip euthanasia, sebab di samping masalah mati itu merupakan hak daripada Tuhan Yang Maha Esa, juga melanggar Sumpah Hipokrates yang pernah diucapkan para dokter. Kemungkinan kedua adalah menyatakan bahwa euthanasia merupakan perbuatan yang tidak terlarang, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini misalnya : A. Bagi pasien yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup menurut ukuran dokter, B. Usaha penyembuhan yang dilakukan sudah tidak berpotensi lagi. C. Pasien dalam keadaan in a persistent vegetative state. 57 Bagi pasien yang dalam keadaan seperti ini, sebaiknya euthanasia dapat dilakukan. Disamping syarat-syarat limitatif tersebut, dapat ditambahkan lagi, misalnya dengan disertai permohonan tertulis dari pasien atau keluarganya, dengan membubuhkan tanda tangannya, dan pada surat permohonan tersebut ditandatangani pula oleh saksi-saksi. Jadi, euthanasia hanya dapat dilakukan terhadap pasien yang memenuhi syarat-syarat tertentu tadi, dan tetap dilarang bila dilakukan terhadap orang yang masih sehat, dan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ini dimaksudkan dengan dibolehkannya euthanasia agar tidak disalahgunakan penggunaannya. B. Keterkaitan Etika Kedokteran dan Hak Asasi Manusia Dalam Praktek Euthanasia Aspek hukum dan HAM yang berkaitan dengan praktek euthanasia yaitu keterkaitan antara dokter dengan ilmu pengetahuannya dan pasien dengan penyakitnya dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dokter mempunyai kewajiban untuk menyembuhkan dan menolong pasien agar supaya bisa mempertahankan hidup, sedangkan pasien mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dan mendapatkan perlindungan dari malpraktek yang mengancam jiwanya. Disinilah hal yang mendasar yang menunjukkan keterkaitan antara ilmu kedokteran dan perlindungan hak asasi manusia terutama hak pasien untuk mempertahankan kehidupannya. Pasien berada pada posisi yang lemah (bargaining position) dan biasanya pasien akan menurut semua kemauan dan keinginan dari dokter yang merawatnya. Bargaining position dari pasien inilah 58 yang menyebabkan pasien rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit dimana dia dirawat. Nasib dari pasien tergantung daripada dokter atau rumah sakit yang merawatnya apalagi kalau pasien dalam posisi koma dan tidak sadarkan diri yang menderita sakit yang berkepanjangan. Apabila seorang dokter dapat mengupayakan kesembuhan atau paling kurang mengurangi rasa sakit bagi pasien, maka hubungan antara dokter dengan pesien dapat bermuara pada hal-hal yang melegakan kedua pihak. Namun dapat juga kita sadari bahwa dokter hanya manusia biasa, yang punya kelebihan dan kekurangan, terutama dengan ilmu pengetahuannya. Artinya dalam situasi tertentu seorang dokter, dapat saja melakukan hal-hal yang menurut pandangan umum di anggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, tapi menurut logika seorang dokter, hal itu tidak bertentangan dengan pengetahuan yang ia miliki. Dalam perjanjian terapeutik, dokter wajib berusaha menyembuhkan pasien melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dengan penuh kehati-hatian, cermat dan teliti atas kepercayaan yang diberikan pasien, Sementara pasien wajib membayar pelayanan. Jadi antara dokter dengan pasien dalam proses penyembuhan penyakit telah terjadi kontrak terapeutik. Menurut Chrisdiono M Achadiat (1996) : Kontrak terapeutik digunakan ketika terjadi hubungan profesional antara dokter dengan pasiennya, khususnya berkaitan dengan usaha memperoleh kesembuhan. Namun dalam praktek kontrak terepautik sering terjadi salah penafsiran baik oleh dokter maupun oleh pasien. Beberapa kalangan dokter berasumsi, kontrak terapeutik tidak dapat digangu-gugat atau dengan kata lain kebal hukum. Sedangkan disisi lain pihak pasien tidak menyadari 59 arti suatu kontrak terapeutik khususnya mengenai isi atau objek perjanjian tersebut. Objek dari perjanjian terapeutik itu sebenarnya adalah usaha yang sebaik-baiknya dari sang dokter dan bukan untuk harus menyembuhkan Seringkali terdengar pasien menuntut dokter, karena penyakitnya tidak berhasil disembuhkan. Keterkaitan antara ilmu kedokteran dan hak asasi manusia dalam euthanasia yaitu antara etika (kode etik) kedokteran dan perlindungan hak hidup bagi pasien dengan masalah tanggung jawab medik dari dokter sesuai dengan etika profesi dimana dokter boleh mengambil tindakan apapun termasuk mencabut nyawa pasien asal tidak bertentangan dengan etika Profesi. Di beberapa Negara Eropa dan Amerika mulai banyak terdengar suara yang pro-euthanasia. Mereka mengadakan gerakan untuk mengukuhkannya dalam Undang-undang. Sebaliknya yang kontra-euthanasia berpendapat, bahwa tindakan demikian sama dengan pembunuhan. Bagi kita di Indonesia, sebagai umat beragama dan ber-Pancasila percaya kepada kekuatan mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala yang diciptakanNya dan penderitaan yang dibebankan kepada mahlukNya mengandung makna dan maksud tertentu. Dokter harus mengerahkan segala kepandaian dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara kehidupan, tidak untuk mengakhirinya. Menurut Gunawan konflik akan selalu terjadi dalam pemikiran dokter yang melakukan euthanasia. Dua kepentingan yang bertentangan akan timbul. Apakah tindakan euthanasia ini hanyalah semata-mata untuk menolong penderita melepaskan diri dari rasa sakit dan penderitaannya atau apakah ada orang lain yang lebih membutuhkan alat pernapasan buatan. Konflik bisa menjadi 60 berkepanjangan sejalan dengan majunya teknologi kedokteran. Untuk transplantasi ginjal misalnya, memerlukan organ ginjal yang masih segar. Organ demikian bisa diperoleh dari tubuh manusia yang mati batang otak, dimana sirkulasi darahnya masih normal, berkat digunakannya alat pacu jantung, maka euthanasia dapat dilakukan untuk memperoleh donor ginjal itu. 1. Aspek Etika Kedokteran dalam euthanasia Jika kita ingin menyoroti aspek etis dari euthanasia, perlu dimulai dengan membedakan euthanasia sukarela (voluntir) dengan euthanasia tidak sukarela (involuntir). Telah dijelaskan,bahwa euthanasia dengan suka rela terjadi bila ada kesepakatan antara dokter dan pasien sedangkan euthanasia tidak sukarela dilakukan tidak atas permintaan pasien. Walaupun euthanasia sukarela kerap kali dibicarakan dalam kaitan dengan pembahasan etika mengenai bunuh diri, namun ada dua alasan untuk membicarakan dua hal itu tersendiri. Yang pertama, bunuh diri jelas merupakan suatu perhentian ditengah jalan dalam proses kehidupan dan berlangsung dalam suatu konteks non-medis. Alasan kedua, euthanasia merupakan antisipasi dari kematian yang pasti dan tidak dapat dihindarkan akibat suatu penyakit.Sementara Euthanasia tidak sukarela menjadi lebih kompleks karena pasien yang bersangkutan tidak kompeten. Dengan demikian pasien tidak ikut serta dalam keputusan.. 2. Etika kedokteran dalam euthanasia pasif dan aktif Perbedaan lain yang penting juga adalah euthanasia aktif dan pasif. Tindakan euthanasia tidak dapat dibenarkan secara moral, apabila itu berarti tindakan yang mempunyai tujuan dan cara-cara yang secara langsung menentang perikemanusiaan, karena menghendaki kematian pasien. Tindakan semacam itu 61 bisa disebut sebagai euthanasia aktif . Disebut “euthanasia aktif ” karena mempunyai tujuan kepada kematian pasien sendiri, atau karena cara-cara yang dipakai secara langsung akan menyebabkan kematian. Misalnya, dokter menyuntikkan obat yang diketahui akan mengakhiri hidup pasien. Alasan utama mengapa orang menolak euthanasia aktif karena menghentikan kehidupan manusia dengan cara demikian merupakan pelanggaran tanggung jawab manusia. Karena Tuhan adalah pencipta dan mempunyai kuasa penuh atas hidup dan mati. Euthanasia aktif menimbulkan kesulitan moral yang serius. Tetapi konteks kesulitan-kesulitan ini, yaitu keadaan tanpa harapan seorang pasien, juga merupakan pertimbangan moral yang penting. Dengan demikian, perdebatan etis tentang euthanasia aktif ini berlangsung antara sebuah motif bagi perbuatan kita, yaitu rasa kasihan terhadap pasien, dan sebuah aturan moral yang juga berlaku bagi perbuatan kita, yaitu jangan membunuh. Euthanasia aktif tidak dapat dibenarkan secara moral, karena tindakan semacam itu sengaja mangakhiri kehidupan sebelum waktunya. Walaupun ada nilai lain yang cukup tinggi yang akan dicapai dengan tindakan itu, misalnya untuk menghindari pasien dari rasa sakit yang berat, tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Sebab, kehidupan merupakan nilai yang lebih tinggi daripada pembebasan manusia dari rasa sakit yang berat. Tindakan itu tidak dapat dibenarkan, walaupun atas permintaan pasien dan kelurganya. Sebab mereka pun tidak mempunyai hak menentang kehendak Tuhan saat kematian atau akhir dari kehidupan manusia. Tentu saja, tindakan euthanasia aktif lebih tidak dapat dibenarkan lagi, apabila hal itu dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan dari pasien dan keluarganya. 62 3. Bantuan dokter untuk menyelesaikan masalah pasien Apabila euthanasia dimengerti sebagai bantuan dokter pada pasien yang sudah mendekati akhir hidupnya dengan cara yang sesuai dengan perikemanusiaan, maka euthanasia itu mempunyai nilai moral yang tinggi. Dalam tindakan semacam itu, baik motivasi maupun caranya tidak bertentangan dengan rasa hormat terhadap martabat manusia. Sebagai contoh, dokter memberikan pilihan analgetik kepada seseorang penderita kanker yang tidak dapat disembuhkan lagi dengan obat, maupun dengan tujuan agar pasien itu tidak terlalu berat menderita sakit akibat kanker itu. Tujuannya baik, yakni untuk meringankan rasa sakit. Caranya pun baik, yakni dengan memberikan pil-pil penenang yang mengurangi rasa sakit. Namun akibat dari pemberian pil-pil tersebut bisa saja membuat pasien mati. Euthanasia semacam ini disebut euthanasia aktif tidak langsung. Disebut euthanasia karena pemberian pil-pil analgetik semacam itu dapat sedikit mempercepat datangnya kematian, sekalipun kematian itu tidak dikehendaki dokter. Maksud pemberian pil adalah membantu agar rasa sakit berkurang, dengan demikian meringankan penderitaan pasien. Tindakan euthanasia aktif tidak langsung masih sesuai dengan sumpah Hipoccrates yang berjanji akan mempergunakan cara pengobatan yang menurut pengetahuan dan pendapat (nya) adalah yang terbaik untuk pasien-pasien (nya) dan tidak akan merugikan siapa pun. 4. Penghentian perawatan Tindakan lain dari dokter yaitu dengan tidak memberi pengobatan karena dia tahu bahwa pengobatan yang dilakukan percuma dengan melihat kondisi dari pasien tersebut (euthanasia pasif).. Misalnya dokter mencabut respirator pada 63 pasien yang menurut pemeriksaan dinyatakan telah mengalami kematian batang otak dan berada dalam keadaan vegetatif persisten. Contoh lain, misalnya pasien yang menderita kerusakan ginjal menolak usul dokter untuk mencuci darahnya atau menerima ginjal baru, karena ia yakin bahwa cara itu akan membawa beban financial (materi) yang terlalu berat bagi keluarganya. Dokter harus menerima keputusan pasien itu, walaupun hal itu akan mengakibatkan kematian pasien. Euthanasia pasif seperti itu dapat dibenarkan secara moral, asal alasan yang dikemukakan oleh pasien sungguh jujur, sementara dokter pun tetap meneruskan cara-cara perawatan yang “biasa”. Kalau dokter tahu bahwa pasien berasal dari keluarga kaya raya, sehingga akan mampu membiayai proses cuci darah atau transplantasi ginjal, dokter mengusulkan agar pasien akan menggunakan cara-cara itu. Namun, pasien tetap mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya, dan dokter harus menghormati keputusan itu. Yang jelas, harus tetap diperhatikan bahwa manusia tidak diwajibkan untuk mempertahankan hidupnya dengan caracara yang luar biasa. Maka, atas permintaan pasien dan keluarganya, dokter dapat menghentikan atau mencegah pemberian perawatan atau pengobatan terhadap pasien, walaupun tindakan itu akan menyebakan kematian pasien. 5. Mengedepankan etika kedokteran dan perlindungan hak hidup pasien Sejak terwujudnya praktek kedokteran, masyarakat mengetahui dan mengakui adanya beberapa sifat mendasar yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah yang tidak diragukan. Oleh sebab itu, para dokter di seluruh dunia mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut 64 dalam suatu etik profesional yang sepanjang masa mengutamakan penderita yang minta berobat serta keselamatan dan kepentingan penderita tersebut. Dokter merupakan profesi tertua yang telah memiliki kode etik. Kode etik tersebut didasarkan pada sumpah Hipoccrates, yang dirumuskan kembali dalam pernyataan Himpunan Dokter se-dunia di London bulan Oktober 1949 dan diperbaiki dalam sidang ke-22 himpunan tersebut di Sidney bulan Agustus 1968. Kode etik adalah pemandu sikap dan perilaku. Pada hakikatnya, dokter sendirilah yang menentukan sikap dan tindakannya sesuai dengan hati nuraninya. Dokter harus memahami apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika kedokteran dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 6. Pengaruh sumpah dokter terhadap euthanasia Aspek yang penting yang menyangkut keterkaitan ilmu kedokteran dan hak asasi manusia dalam praktek euthanasia menyangkut sumpah dokter. Tindakan medis dari dokter selalu didasarkan pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Itulah sebabnya tindakan-tindakan medis bersifat rahasia dan tertutup Peraturan pemerintah tahun 1969 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia yang bunyinya sama dengan Deklarasi Jenewa 1948 dan Deklarasi Sidney 1968 menyebutkan bahwa: “saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan………”. “saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan…………”. Sedangkan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Pasal 9, Bab II tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa: “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani”. 65 Dengan demikian, menurut etika kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan pengguguran kandungan (abortus provokatus) maupun mengakhiri hidup seorang yang sakit (euthanasia) meskipun menurut pengetahuan dan pangalamannya tidak akan sembuh lagi. Problematika yang timbul disini apakah dokter dalam menanganai pasien yang sedang dalam keadaan koma mengedepankan sumpah dokter atau melindungi hak asasi dari pasien untuk hidup. Paradoks ini memang belum diatur dalam satu aturan yang positif bila kedua hal ini berbenturan, mana yang harus dikedepankan, apakah etika kedokteran atau hak asasi manusia. Dalam ilmu hukum dikenal asas hukum yaitu lex specialis derogat legi generalie tentang pemberlakuan aturan-aturan khusus yang mengesampingkan aturan-aturan umum dalam satu keadaan. Dalam penanganan euthanasia, kalau asas hukum ini diterapkan tentunya dokter akan menjadi bingung, manakah yang harus dikedepankan, etika atau perlindungan hak asasi manusia 7. Batasan tentang kepastian kematian pasien Akan tetapi apabila pasien sudah dipastikan mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi otaknya sama sekali, maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati walaupun jantungnya masih berdenyut. Apabila seorang dokter akan mencabut alat respirator harus mempunyai bukti yang cukup kuat, bahwa alat itu sudah tidak mempunyai manfaat lagi. Penghentian tindakan terapeutik harus diputuskan oleh dokter yang berpengalaman yang sering mengalami kasus serupa dan sebaiknya hal itu dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan dokter lain yang juga berpengalaman, selain harus pula 66 dipertimbangkan keinginan pasien, keluarga pasien, dan kualitas hidup terbaik yang diharapakan. Dengan demikian, dasar etik moral untuk melakukan euthanasia adalah memperpendek atau mengakhiri penderitaan pasien dan bukan mengakhiri hidup pasien. Hal ini sesuai dengan pendapat Profesor Olga Lelacic yang menyatakan bahwa: “Dalam kenyataan, pasien yang meminta dokter untuk mengakhiri hidupnya, sebenarnya tidak ingin mati, tetapi ingin mengakhiri atau ingin lepas dari penderitaan karena penyakitnya (Samil, 1994;127). 8. Penerapan delik pidana dalam praktek euthanasia Dokter yang melakukan praktek euthanasia dalam perspektif hukum pidana telah melakukan pembunuhan, status dokter disebut pembunuh atau pelaku perbuatan pidana. Sehubungan dengan hal ini, J.E. Sahetapy, Universitas Airlangga Surabaya, pernah mengadakan suatu research terhadap masalah euthanasia di Indonesia. Beliau mengatakan dalam tulisannya yang dimuat pada Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa pengadilan-pengadilan di Indonesia ini, belum pernah menangani kasus yang bertalian dengan Pasal 344 KUHP. Hal ini disebabkan karena: 1. If euthanasia has occured, it has never been discovered or reported to law enforcement agencies, 2. Death was not considered euthanasia by the victim’s family or they are ignorant of the law, 3. Although medical technology has reached an advanced stage in Indonesia, the latest medical equipments to prolong life in hospital are not yet available except probably in some hospital in Jakarta. 67 Seperti diketahui, bahwa Pasal 344 KUHP,yang dikenal sebagai Pasal euthanasia yang aktif menyatakan bahwa : Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri, yang menyatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Tetapi perumusan Pasal 344 KUHP menimbulkan kesulitan di dalam pembuktian, yakni dengan adanya kata-kata “atas permintaan sendiri”, yang disertai pula kata-kata “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Dapat dibayangkan bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati tersebut telah meninggal dunia. Kemudian timbul masalah lagi, bagaimana jika orang yang bersangkutan itu tidak mampu untuk berkomunikasi ? Untuk memberikan gambaran yang jelas, sebagai bahan perbandingan, akan dikemukakan contoh kasus yang terjadi diluar negeri, sebagai berikut : Kasus pertama, terjadi pada tahun 1976 di New Jersey, Amerika Serikat, yang terkenal sebagai kasus Karen Ann Quinlan. Karena si gadis manis berusia 21 tahun, yang dipungut oleh keluarga Quinlan, ia menderita penyakit dan dalam keadaan yang disebut in a persistent vegetative state, mati tidak, hidup pun tidak. Karen hanya dapat bertahan dengan bantuan sebuah “respirator”. Keadaan Karen bagaikan patung bertulang terbungkus kulit, bagaikan kerangka mayat saja. Dapatkah dikatakan bahwa Karen masih hidup ? Bukankah Karen sudah tidak dapat berbicara lagi ? Jangankan makan, bernapas pun sulit, jadi hidupnya tergantung pada mesin. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa apabila “respirator” tersebut dilepaskan, akan berakibat lebih lanjut terhadap otaknya dan Karen pun akan segera mati. Tetapi dalam hal ini dokter menolak menghentikan penggunaan “respirator” tersebut. Kemudian Quinlan (ayah angkatnya) menuntut agar Karen dinyatakan sebagai incompetent dan Quinlan ditunjuk sebagai 68 guardian yang diizinkan untuk menghentikan segala tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup Karen. Selanjutnya pengadilan menolak tuntutan Quinlan tersebut, tetapi New Jersey Supreme Court menyatakan dalam putusan banding, bahwa seseorang mempunyai suatu hak yang disebut right to privacy dan khusus dalam kasus Karen ini, bilamana Karen dapat melakukannya, dia pasti menolak penggunaan “respirator” karena penderitaan yang dialaminya sangat hebat. Karen membutuhkan 24 jam terus-menerus perawatan yang intensif, antiviotiks, bantuan “respirator”, catheter dan feeding tube. Jadi jelas dalam hal ini kepentingan Karen melebihi kepentingan para dokter yang merawatnya, dan negara. Pada akhirnya Supreme Court memerintahkan agar the life support apparatus dicabut tanpa adanya pertanggungan jawab sipil maupun kriminil. Kasus yang kedua, terjadi di Florida, Amerika Serikat, tahun 1978, yang terkenal dengan kasus Sats v. Perlmutter. Abe Perlmutter, berusia 73 tahun, dalam keadaan sadar dan kompeten, mederita penyakit yang disebut sebagai incurably amytropic lateral sclerosis. Penyakit ini sangat fatal, sebab dapat mengakibatkan one’s muscles to wear away. Diagnosa terhadap Perlmutter menyatakan bahwa dia hanya akan tahan hidup selama satu tahun, dan akan segera mati, dalam waktu satu jam setelah “respirator”-nya dicabut. Dia sudah tiga kali mencoba sendiri untuk mencabut “respirator” itu, dan minta dengan sangat kepada anak perempuannya untuk mencabut alat tersebut. Para dokter dan rumah sakit, menolak memberikan izin kepadanya untuk mencabut “respirator” tersebut, sebab takut akibat hukumnya. Kemudian pengadilan (the Lower Court) mengatakan bahwa Perlmutter hendaknya diizinkan untuk mencabut “respirator” tersebut. State Attoney General mengajukan banding, dan Distric Court of 69 Appeals memperkuat keputusan tersebut. Tetapi The State Attorney General tidak melanjutkan kasasinya lebih lanjut. Akhirnya Perlmutter meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 1978, 41 jam sesudah “respirator”-nya dicabut. Dari contoh dua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa euthanasia di Amerika Serikat diizinkan oleh hukum, walaupun terbatas kepada situasi dan kondisi tertentu. Euthanasia dalam arti pasif dapat terjadi bilamana seseorang yang “competent’ menggunakan hak untuk menolak medical treatment, sekalipun akan mengakibatkan kematian atas dirinya sendiri. Begitu pula euthanasia dalam arti aktif, dapat terjadi bilamana seseorang yang incompetent sesuai dengan putusan pengadilan yang diminta oleh keluarganya untuk mencabut life support system’s yang dapat mengakibatkan kematian si pasien, seandainya keadaan pasien tersebut sudah tidak mungkin dapat diharapkan kesembuhannya. 10. Euthanasia dalam hukum positif Indonesia Sekarang bagaimana halnya di Indonesia. Apakah kasus Karen Ann Quinlan yang bikin heboh di Amerika Serikat itu dapat terjadi di Indonesia ? Kiranya tidak mustahil kasus seperti ini terjadi di Indonesia, apabila rumah sakit di Indonesia telah mempergunakan alat-alat kedokteran yang serba modern seperti “respirator”, heartlung machines, organ transplants dan sebagainya, yang dapat mencegah matinya seseorang pasien secara teknis untuk beberapa hari, minggu dan bahkan mungkin untuk beberapa tahun. Problema yang selanjutnya adalah seandainya kasus Karen Ann Quinlan dan Staz v. Perlmutter ini benar-benar terjadi di Indonesia, apakah para dokter dapat dituntut dengan Pasal 344 KUHP ? Kalau dilihat dari perumusan Pasal 344, baik dalam konteks penafsiran, menurut hemat penulis Pasal ini tidak dapat 70 diterapkan, karena rumusan Pasal tersebut yang mencantumkan adanya unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” tidak dapat dibuktikan. Kita tahu bahwa Karen dalam keadaan in competent serta dalam keadaan mati tidak, hidup pun tidak. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, berbicara, bergerak pun tidak dapat, apalagi menyatakan permintaan untuk mati, yang harus diucapkan sendiri oleh Karen bukan oleh orang lain sekalipun keluarganya. Di samping itu pasal tersebut mengandung makna bahwa jiwa manusia harus tetap dilindungi, tidak saja dari ancaman orang lain, tetapi juga dari usaha orangnya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, karena sama saja dengan bunuh diri yang dilarang oleh agama, dan hukum pidana positif Indonesia. Walaupun demikian, untuk masa-masa mendatang, dalam rangka Ius constituendum hukum pidana, rumusan Pasal 344 KUHP tersebut, perlu untuk dirumuskan kembali, agar dapat memudahkan bagi penuntut umum dalam hal pembuktiannya. Hal ini perlu ditempuh mengingat sejak terbentuknya KUHP, sampai sekarang belum ada kasus yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang sampai ke pengadilan, yang disebabkan karena : a. Bila terjadi masalah yang berhubungan dengan Pasal tersebut, tidak pernah dilaporkan kepada polisi, atau pejabat yang berwenang. b. Kebanyakan orang Indonesia masih awam terhadap hukum, apalagi terhadap masalah euthanasia c. Alat-alat kedokteran di Indonesia, belum begitu modern, sehingga jarang terjadi pencegahan kematian secara teknis. Perumusan kembali dimaksud, agar supaya memperhatikan serta memperhitungkan pula perkembangan 71 dan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Kematian janganlah dipandang sebagai suatu fungsi terpisah dari konsepsi hidup sebagai suatu keseluruhan. Namun manusia bukanlah suatu robot belaka. Karena itu, mau tidak mau, konsepsi “hak untuk hidup” tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan “hak untuk mati”. Hal ini berarti relevansi konsepsi pengertian perbuatan pidana menjadi nyata, terutama apabila putusan pengadilan secara jelas dan tegas, membedakan dan memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam kasus diatas, maka persoalannya bukanlah semata-mata patuh dan takut terhadap hukum saja, apakah hukum hanya suatu alat dalam kerangka konsepsi hidup manusia. Ataukah hukum menjadi suatu tujuan yang memperhamba manusia. Dengan demikian hukum, juga termasuk hukum Indonesia, baik saat ini, ataupun untuk masa yang akan datang, seyogyanya jangan bersifat kaku dan statis. Hukum itu hendaknya lebih bersifat fleksibel dan dinamis, berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat. Dengan sifat yang fleksibel dan dinamis tersebut, diharapkan dapat memecahkan segala persoalan, baik yang terjadi pada masa sekarang, maupun masa yang akan datang. C. Prosfek Hukum HAM Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pasien Dari Praktek Euthanasia The rights of Health merupakan hak dari pasien dalam perawatan kesehatan, tercakup didalamnya hak mempertahankan kehidupan. Dalam Mukadimah Statuta WHO disebut adanya hak atas kesehatan, dalam konsep Statuta tersebut tertulis "the right to health care", tetapi karena satu dan lain hal 72 dokumen internasional ini menyebut "the right to health". Timbul pertanyaan, apakah kata care ini sengaja dihilangkan dan tidak diberi komentar dalam memori penjelasan? Konon salah satu alasan mengapa care ini dikeluarkan ialah uraian modern tentang kesehatan yang dirumuskan sebagai: ."Suatu keadaan yang ditandai oleh kesejahteraan fisik, mental dan sosial, dan bukan semata-mata ketiadaan sakit, penyakit dan cacat." Konsep tersebut senada dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang tampaknya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Ketentuan tersebut merumuskan antara lain: “……hak memperoleh perlindungan kesehatan untuk setiap orang tanpa membedakan ras, status, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan politik, dan sebagainya". Secara yuridis "hak atas kesehatan" pada hakekatnya kurang rasional, contoh, Seorang konglomerat misalnya dapat saja memberi segudang obat- obatan, menyewa dokter pribadi, namun segenggam kesehatan, sampai saat ini belum ada yang dapat memasokkannya kepada yang bersangkutan. Ini barangkali takdir Ilahi bahwa ada hal-ikhwal yang tak dapat dibeli dengan uang, baik oleh sang konglomerat, maupun yang melarat. Oleh karena itu aspek kesehatan tidak dapat dijadikan obyek persetujuan (terapeutik). Nah, kalau begitu apa saja yang dapat dijadikan obyek sebuah kontrak? Dalam kaitan ini, pemeliharaan kesehatan sebagai kumpulan sarana dan prasarana guna melindungi, menunjang dan meningkatkan kesehatan manusia merupakan salah satu benda hukum, yang mendapatkan perhatian yuridis. Ringkasnya, pelayanan kesehatan (pemeliharaan kesehatan dalam arti sempit) merupakan obyek persetujuan pengobatan dan perawatan.Yang dapat digolongkan pelayanan kesehatan antara lain ialah pemeriksaan medik, diagnosis, terapi, anestesi, menulis resep obat-obatan, 73 pengobatan dan perawatan di rumah sakit, peningkahan pasien, kontrol, pelayanan pasca perawatan, pemberian keterangan medik, pemberian informasi, kerja sama vertikal penyelenggara pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Hak atas pemeliharaan kesehatan dalam arti luas diakui umum sebagai hak sosial, satu dan lain karena pemeliharaan kesehatan (termasuk pelayanan kesehatan) sebagai sistem memberikan ruang dan peluang kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan, disediakan atau ditawarkan oleh pergaulan hidup, Leenen menyebutkan hak-hak partisipasi (participatie rechten), dan isi hak-hak ini sedang berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Jadi hak dasar sosial ini mengandung tanggung jawab (bandingkan Pasal 29 Universal Deciaration of Human Rights, yang berbunyi: "Everyone has duties to the community" dan seterusnya). Dan salah satu tanggung jawab ialah ikhtiar untuk mempertahankan hak-hak dasar individu, antara lain hak untuk menentukan nasib sendiri. Sesungguhnya hak atas pemeliharaan kesehatan mempunyai jangkauan yang luas sekali jika dibandingkan dengan hak atas pelayanan kesehatan, yang pada hakikatnya merupakan hak orang sakit, setidaktidaknya hak orang yang mencari pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 25 Universal Declaration Of Human Rights tercantum ketentuanketentuan yang rnenyangkut hak-hak atas pemeliharaan kesehatan, yang secara tidak langsung berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan, sebagai berikut: 1. Setiap orang berhak atas suatu taraf hidup, yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk didalamnya pangan, pakaian, dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya yang diperlukan. Hak-hak ini mencakup hak atas tunjangan dalam hal terjadi pengangguran, 74 sakit, cacat, usia lanjut atau kehilangan mata pencaharian, yang disebabkan oleh situasi dan kondisi diluar kehendak yang bersangkutan. 2. Ibu dan anak mempunyai hak atas pemeliharaan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang sah maupun diluar kawin, menikmati perlindungan sosial yang sama. Perlindungan terhadap kesehatan dirumuskan dalam Pasal 12 persetujuan definitif Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai berikut: A. Negara-negara yang merupakan pihak dalam persetujuan ini mengakui hak setiap orang atas kesehatan tubuh dan jiwa, yang diupayakan sebaik mungkin; B. Langkah-langkah yang diambil negara-negara yang merupakan pihak pada persetujuan ini, guna merealisasikan hak ini selengkap mungkin, antara lain meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mencapai: a) Pengurangan jumlah anak yang lahir mati dan kematian anak pertumbuhan dan pengembangan anak secara sehat dan upaya yang seiring dengan itu; b) Perbaikan aspek-aspek higiena lingkungan hidup dan lingkungan kerja; c) Pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit epidemik dan endemik. d) Menciptakan suasana yang memberikan jaminan kepada setiap orang yang bilamana menderita sakit akan memperoleh bantuan dan pelayanan medik. Kalau pemeliharaan kesehatan berada dalam bidang makro, maka pelayanan kesehatan lebih mengatur pelayanan kesehatan yang merupakan hubungan langsung antara penyelenggara pelayanan kesehatan (dokter, perawat dan lain-lain) dan pencari bantuan pelayanan tersebut, secara mikro. Secara 75 teoretis relasi dokter-pasien ini dapat kita bagi dalam tiga jenis kontrak, yang dapat berakhir dengan suatu kontrak, sebagai berikut: 1. Hubungan dokter-penderita. Seseorang menemui dokter karena ia merasakan ada sesuatu yang mengancam kesehatannya. Nalurinya membisikkan bahwa ada gejala-gejala sakit dan penyakit yang sedang menggerogotinya. Orang lain pun dapat melihat bahwa seseorang tertentu dirundung sakit dan penyakit, dan memanggil atau menyuruh memanggil dokter. Dalam hubungan seperti ini dokter adalah dewa penyelamat. 2. Hubungan dokter-pesien. Seseorang pergi ke dokter berdasarkan gejala-gejala yang sudah diantisipasi (self-Milling prophecy). Pasien telah mengetahui, atau setidak-tidaknya mengira telah mengetahui gejala-gejala tersebut dan dokter hanya menegaskan benar tidaknya asumsi tersebut. 3. Hubungan dokter-konsumen. Relasi jenis ini pada umumnya kita temui pada pemeriksaan medik preventif. Misalnya, seseorang pergi ke dokter atas kemauan pihak ketiga, yang mungkin saja negara, majikan, dan sebagainya. Dokter memeriksa orang yang disuruh pihak ketiga tersebut dan berikhtiar menemukan penyakit yang belum diketahui, menegakkan diagnosis, dan jika dianggap perlu diikuti oleh terapi. Sekalipun tujuan pertama adalah pemeriksaan preventif, namun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh tindakan-tindakan kuratif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran telah menyebabkan bidang pelayanan kesehatan menjadi semakin komplek. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan makin canggih saja, dan makin mahal pula. Dalam sistem kesehatan seperti ini tampaknya dokter bukan lagi sumber otoritas satu-satunya 76 melainkan harus membagi kemampuan dan kehormatannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada satu sisi Iptek akan mengambilalih peran dokter. Saat ini Iptek terutama dalam bidang diagnostik, telah menjadikan dokter (umum) seorang spesialis, malahan seorang pemasok jasa pelayanan kesehatan tersebut mulai memperlihatkan perilaku konsumen, yang dalam perkembangannya tidak mau begitu saja menerima pelayanan jasa. Adapun rincian hak-hak pasien dalam konteks hak asasi manusia yaitu: 1. Hak atas informasi Dalam konteks HAM dokter dan pasien berkedudukan sederajat dan pasien harus mendapatkan haknya termasuk hak informasi. Hak-hak tersebut yakni pasien harus diperlakukan sederajat termasuk untuk mendapatkan informasi dan kebenaran diagnosa atas penyakitnya. Dari informasi ril pasien, dokter akan menyampaikan kepada pasien pendapat dan pandangannya. ia perlu pula menginformasikan pasien mengenai rencana pengobatan dan perawatan, berapa lama pengobatan dan perawatan itu akan berlangsung dan efek-efek yang perlu diantisipasi, seperti ketidaknyamanan yang akan dialami, sifat dan bentuk komplikasi, dan sebagainya Selama berlangsungnya konsultasi pasien-dokter ini, maka arus informasi dari pasien ke dokter dan sebaliknya, berjalan tak putus-putus. Dalam kenyataan banyak sekali pasien melalaikan pemberian informasi kepada dokter, bukan karena ia tidak mau, tapi tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Pada umumnya pasien takut atau malu mengemukakan sesuatu yang serba salah, apalagi kepada seseorang yang dianggapnya ahli dalam bidang medik. Dan kalau memberitahukan yang benar, ia khawatir sakit dan penyakitnya, apalagi bila itu 77 membawa nista baginya, diketahui orang banyak. Yuridis, hak atas informasi ini, seperti pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dalam struktur relasi dokterpasien, termasuk hukum perikatan dan hukum persetujuan. Namun, perlu ditambahkan disini bahwa tentang hal ini tidak banyak yang diatur secara eksplisit. Baik peradilan maupun doktrin menganggap hubungan hukum tersebut lebih dikuasai oleh kebiasaan, hukum kebiasaan dan itikad baik, daripada peraturan perundang-undangan. Penelitian di beberapa negara maju menunjukkan bahwa pada urnumnya dokter yang menjadi anggota perhimpunan profesi menyerahkan aspek hukum dalam pelayanan medik kepada perhimpunan yang antara lain memberikan perlindungan bagi para anggotanya dalam berbagai bidang, hubungan kemasyarakatannya. Malahan banyak penyelenggara pelayanan medik yang dengan setia taat pada ketetapan, keputusan dan pedoman kerja yang dikeluarkan oleh perhimpunan profesi, menganggap dirinya sudah sadar hukum, mengetahui undang-undang dan aturan-aturan yang setara dengan itu. Dengan perkataan lain: jika perhimpunan profesi itu sendiri tidak membentuk peraturan-peraturan internalnya sendiri, maka penguasalah yang akan membuatnya. Hal inilah yang barangkali menyebabkan sementara para penyelenggara pelayanan medik beranggapan bahwa peraturan internal yang pada hakikatnya lebih bersifat petunjuk dan pedoman kerja daripada suatu aturan yuridis formal berlaku secara umum. Sebagai contoh tentang apa yang dikemukakan diatas adalah suatu putusan Majelis Tata Tertib Medik Pusat Belanda mengenai hak atas informasi ini. Pada tahun 1967 Majelis tersebut memutuskan bahwa dokter mempunyai hak informasi 78 dan bukan sebagaimana menurut logikanya harus mempunyai kewajiban untuk memberi informasi. Secara teori mungkin saja dokter sama sekali tidak memberi informasi, namun dalam praktek keharusan untuk memberi informasi pada umumnya dilihat sebagai suatu kewajiban. Secara formal dokter harus meminta persetujuan pasien untuk diobati dan dirawat. Pada tindakan-tindakan serius dan penuh risiko dokter harus memperoleh izin pasien. Namun, prosedur ini tidak mempunyai makna sedikitpun bilamana pasien tidak diberikan informasi yang memadai dan yang dilakukan dalam bahasa yang ia tidak kuasai. Pada umumnya persetujuan pasien dianggap telah diberikan secara diam-diam. Di Amerika Serikat mengenai informasi dan persetujuan antara kedua pihak diungkapkan dalam istilah "informed concent", yang dalam Permenkes No. 585 Tahun 1989 dialihbahasakan sebagai persetujuan tindakan medik. Informed di sini diartikan sebagai (pihak) yang telah memperoleh informasi dari (pihak) lain, sedangkan consent bukan saja mengandung arti mengerti lingkup informasi yang diberiakan itu, tetapi juga setuju akan dilakukan tindakan medik atas dirinya berdasarkan informasi tersebut. Pada umumnya dapat dikemukakan disini, bahwa masalah "informed consent" merupakan sesuatu yang baru di dunia kedokteran, baik di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan hat tersebut pada hakikatnya merupakan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medik pada satu sisi, dan kesadaran hukum masyarakat serta semakin kritisnya kaum konsumen terhadap hasil dan ikhtiar pemasaran barang dan jasa modern pada sisi lain. Dalam praktek masalah "informed consent" menimbulkan berbagai problematik bagi para penyelenggara pelayanan kesehatan, terutama persoalan 79 bahwa tidak selalu dapat ditentukan dengan tepat apa yang terbaik dalam peristiwa medik yang kongkrit, penyelesaian mutlak tidak dapat diandalkan di sini, karena pada pemberian informasi terjadi suatu dialog antara dokter dan pasien, yang harus terselenggara dengan itikad baik. Apalagi kalau dipikir bahwa dalam proses pemberian informasi ini dokter sudah harus memberikan suatu pertimbangan sebelum melakukan tindakan. Bukankah sakit dan penyakit tidak berlangsung menurut skema dan sketsa yang tetap dan teratur? Demikian pula kenyataan bahwa banyak sekali terjadi informasi sang dokter yang disalahartikan, suatu gejala yang serius kadangkala diremehkan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu sangat tinggi relevansi disini bahwa dokter menuangkan dalam berkas mediknya informasi yang diberikannya kepada pasien, saat diberikannya informasi tersebut dan alasan mengapa itu diberikan, maupun alasan mengapa telah ditahannya atau tidak diberikannya informasi tersebut sesuai dengan kebenaran. Sebaliknya, hakim dan pasien pada hakikatnya memberikan penilaian kemudian (pasca akta), jika peristiwa dan kejadian telah menjadi kenyataan. Kewajiban memberikan informasi masih dapat pula diberikan lebih lanjut secara rasional. Namun informasi itu bukan merupakan suatu keharusan, melainkan lebih bersifat petunjuk. Petunjuk pertama adalah bahwa dalam hal terdapat keragu-raguan apakah pasien telah mengerti apa yang diinformasikan, maka kita harus bertolak dari anggapan bahwa pemberian informasi kepadanya kurang memadai. Sesungguhnya disini kita berhadapan dengan permasalahan bahwa pasien dihadapkan kepada suatu materi yang cukup sulit untuk tidak disebut rumit, yang harus dicerna dalam kondisi yang lebih sulit lagi. Petunjuk selanjutnya ialah bahwa di dalam pemberian informasi ini dokter hanya wajib 80 melakukannya yang baginya memberikan kepastian. Jadi, tidak dimaksudkan di sini bahwa kepastian mutlak tentang diagnosis dan prognosis harus diinformasikan, melainkan perkiraan-perkiraan, yang diambilnya itu, bertumpu pada dasar-dasar yang rasional. Dan perlu diperhatikan, bahwa jangan sekali-kali dokter mengungkapkan prasangka yang tak beralasan sebagai suatu kebenaran. Pasien yang belum dewasa, alias dibawah umur dalam rangka kewajiban urnum dokter memberikan informasi, pasien tersebut mempunyai juga hak atas informasi tentang apa yang akan dilakukan dengan dirinya. Namun pemberian informasi di sini lazimnya dihubungkan dan disesuaikan dengan umur yang bersangkutan. Hak atas informasi tersebut dimiliki orang yang belum dewasa terlepas dari persetujuan orang tua untuk itu, walaupun kita ketahui bahwa orang tua mempunyai kekuasaan orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam Bab 3 telah kita bahas hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan, yang mulai berlaku pada saat manusia itu lahir. Hak menentukan nasib sendiri merupakan pula salah satu hak manusia yang penting. Tubuh manusia dari bagian ujung kaki dan ujung rambutnya mewujudkan manusia selaku manusia. Jadi, para orang tua tidak mempunyai patrin notestas atas tubuh anak-anaknya. Tambahan pula bahwa anak-anak tersebut pada hakikatnya harus dilindungi terhadap tindakan-tindakan para orang tuanya. Tujuan kekuasaan orang tua, bukan pemberian suatu hak menentukan nasib sendiri atas anak-anaknya, melainkan pemberian kewajiban peningkatan dan pembinaan atas anak-anaknya agar mereka berangsur-angsur memiliki hak menentukan nasib sendiri setelah dewasa. Apa yang dimiliki anak tersebut selaku subyek hukum dalam kerangka hak-hak asasi manusia sejak kelahirannya, harus 81 dikembangkan oleh para orang tuanya. Pengertian kekuasaan orang tua tidak didefinisikan secara identik dalam undang-undang. Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: "Para orang tua mempunyai kewajiban mernelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa". Lebih lanjut Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan bahwa "Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua" Dari kedua ketentuan tersebut dapat kita jabarkan bahwa kekuasaan orang tua sebagai suatu kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, pendidikan, bantuan dan perlindungan kepada anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur. Apalagi kalau diingat bahwa para orang tua.dapat dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan tersebut dalam hal mereka tidak sesuai atau tidak mampu menjalankan kekuasaan itu. Secara yuridis kekuasaan orang tua lebih banyak memperlihatkan aspekaspek hukum harta kekayaan. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang kebelumdewasaan seseorang. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Kalau Undang-Undang Perdata Belanda menyatakan seseorang telah dewasa jika ia menginjak usia delapan belas tahun, maka di Indonesia yang notabene meresepsi Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, masih saja menganggap umur dua puluh satu tahun sebagai batas kedewasaan menurut 82 hukum. Padahal secara fisik tampaknya orang-orang Asia lebih cepat dewasa dan mandiri daripada orang-orang Eropa. Itulah sebabnya perlu dipertimbangkan, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan untuk mempergunakan batas umur progresif dalam penilaian anak-anak dibawah umur bertalian dengan hak menentukan nasib sendiri, hak atas informasi dan pemberian persetujuan tindakan medik. Jika seseorang mencapai umur dua puluh satu tahun maka pada umumnya ia cukup (bekwaam) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. ia diberi status dewasa yang pada hakikatnya merupakan suatu pengertian hukum (perdata). ia memiliki legal competency dan pada umumnya cakap bertindak untuk dirinya sendiri, tanpa diwakili lagi oleh orang lain. Namun, tidak semua orang dewasa cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Orang dewasa yang terus menerus dirundung kedunguan, gangguan jiwa atau mata gelap harus diletakkan dibawah pengampuan (onder curatele gesteld), demikian pula jika yang bersangkutan hidup boros (pasa1433 KUHPerdata). Kalau dalam praktek perundang- undangan, kita jumpai kekecualian yuridis seperti apa yang diuraikan diatas, maka tidak terlalu salah jika dalam rangka pelayanan kesehatan, yang lebih peka lagi permasalahannya, diterapkan batas umur progresif bagi orang-orang yang belum dewasa. Dan lebih khusus lagi dalam kerangka "informasi consent" dengan Segala seluk-beluknya, hal tersebut perlu mendapatkan prioritas. Belanda, misalnya Kelompok Kerja Perhimpunan Hukum Kesehatan yang telah mengadakan penelitian dalam bidang ini berpendapat bahwa dokter berhak untuk memberikan informasi baik kepada pasien yang belum dewasa maupun para 83 orang tua atau walinya, kecuali pihak yang dibawah umur tersebut menaruh keberatan atasnya. Suatu kekecualian terhadap apa yang disebut terakhir ialah tidak memberikan informasi kepada para orang tua akan merugikan pasien yang belum dewasa. Lain pula pendapat Leenen yang pada dasarnya menganggaap pemberian informasi sebagai suatu kewajiban sedangkan pasien berwenang untuk meminta informasi. Namun, betapapun juga selayaknyalah dalam hal dokter meng hadapi pasien-pasien yang belum atau hampir dewasa, maka para orang tua harus diberikan informasi kecuali jika pasien tersebut menaruh keberatan atasnya, atau dokter mempunyai alasan-alasan kuat memperkirakan bahwa pasien yang bersangkutan tidak menghendaki hal itu. Dapat disimpulkan disini bahwa pada umumnya dalam memberikan informasi seperti yang diuraikan diatas kepada pasien dibawah umur haruslah dibicarakan terlebih dahulu dengan orang tua mereka, kecuali karena alasan-alasan seperti yang diuraikan diatas hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Keadaan di Amerika Serikat tampaknya sudah "a step ahead" karena di beberapa negara bagian telah memberlakukan undang-undang khusus tentang persetujuan pasien-pasien dibawah umur untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohcontoh dalam bidang ini adalah antara lain pengobatan dan perawatan penyakit kelamin, donor darah, ketergantungan pada obat bius dan minuman keras, pemeriksaan setelah perkosaan, reseptur pil keluarga berencana dan lain-lain. Ada pula undang-undang, sebagai pelengkap apa yang disebut di atas, memberikan ketentuan-ketentuan tentang keabsahan persetujuan pasien dibawah umur, diatas empat belas tahun untuk pengobatan dan perawatan penyakit-penyakit spesifik. Bahkan suatu statuta yang dikeluarkan oleh negara bagian Luisiana telah 84 melangkah lebih lanjut lagi dengan memberikan keabsahan persetujuan anak di bawah umur tanpa batas-batas umur yang ditetapkan dengan jelas bagi mereka yang dirundung atau merasa dirundung sakit dan penyakit. Selanjutnya dapat disampaikan kutipan hukum yurisprudensi di Arnerika Serikat sebagai berikut: "The United States Supreme Court has deciared that the provisions of a statute imposing a bianket requirement of parentel consent before a minor female could obtain and abortion (when otherwise entitled to one) were unconstitutional "See Pianned Parenthool of Central Mo. v. Danforth, 428 U.S. 52 (1976). Dalam kasus yang lain diputuskan: "The parental consent for an abortion could be required if the state provides an alternative procedure whereby the patient could dispense with such consent if she could show either that she is sufficiently mature to make the decision or that the abortion would be in her best interest. See Belloti v. Baird, 433 U.S. 622 (1979) (plurality decision). Dapat terjadi bahwa para orang tua menolak memberikan persetujuan untuk pengobatan dan perawatan medik pada anak-anak mereka yang belum dewasa. Beberapa penulis terkenal seperti Leenen, Rang, Van der Mijn berpendapat bahwa pasien-pasien di bawah umur yang sudah lebih tua, dokter dapat bertolak dari anggapan bahwa persetujuan pasien-pasien tersebut sudah cukup, kecuali untuk tindakan-tindakan yang tergolong berat. Dalam suatu tindakan medik yang secara medik perlu dilakukan, maka dalam kasus seperti itu pada umumnya timbul pertentangan kepentingan antara para orang tua dan anak. Jadi, sesuai dengan anggapan para pakar Belanda tersebut maka kepentingan anak yang diutamakan. Anak tersebut memiliki hak-hak asasi manusia dan harus 85 dilindungi terhadap akibat-akibat yang secara fisik dan psikhis merugikan, yang pada hakikatnya disebabkan oleh penolakan para orang tua tersebut. Sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh para pelopor hukum kesehatan di Belanda tersebut dapat dijalankan di negara mereka, satu dan lain karena berbagai pranata pendukung sudah dilembagakan di sana. Antara lain kita kenal beberapa lembaga hukum seperti peletakan dibawah pengawasan (ondertoezichtstelling) vide Pasal 254 BW jo Pasal 257 BW. Malahan ada yang menganjurkan diterapkannya tindakan-tindakan perlindungan terhadap anak untuk suatu kasus insidental atau jika ini terlalu berat untuk dilaksanakan, maka hendaknya dipertimbangkan adanya kemungkinan agar diselesaikan melalui intervensi hakim yang dapat memberikan persetujuan penyelenggaraan pelayanan medik. Suatu contoh dari yurisprudensi Belanda adalah putusan Pengadilan Tinggi Den Haag 26 Oktober 1965, N.J. 1967, 121, yang memutuskan peletakan di bawah pengawasan seorang anak yang berumur tiga tahun yang menderita kelainan pada matanya. Tanpa pelayanan medik yang memadai hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan tak terpulihkan pada retina. Pada pemeriksaan tingkat pertama peletakan dibawah pengawasan ditolak (karena para orang tua menolak), tapi Pengadilan Tinggi berpendapat lain. Contoh lain dalam kaitan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Dordrecht 27 Juni 1973, N.J. 1973, 432, mengenai seorang anak dengan kelainan jantung yang serius, dan yang memerlukan pembedahan "cito". Sang ibu memberikan persetujuannya, tapi ayahnya menolak, atas dasar pertimbangan keagamaan. Sang ayah dibebaskan dari kekuasaan orang tua, sehingga pada saat itu hanya ibu anak tersebut yang menjalankan kekuasaan 86 orang tua. Berdasarkan pemberian persetujuan ini pembedahan dapat dilaksanakan. Seperti telah diketengahkan diatas, para orang tua tidak mempunyai wewenang menentukan nasib kehidupan anak-anaknya dan dalam hal ada penolakan seperti itu maka perlu diambil tindakan seperlunya terhadap para orang tua. Apa yang dapat ditolak oleh para orang dewasa berdasarkan keyakinan, kepercayaannya, tidak boleh mereka terapkannya kepada anak jika karenanya anak tersebut terancam nyawanya. Sedangkan beberapa penulis antara lain Roodde Boer mengemukakan bahwa perundang-undangan sendiri mengakui keberatankeberatan berdasarkan suara batin para orang tua yang pada umumnya merupakan panutan anak-anaknya. Kembali kepada permasalahan pemberian informasi kepada para pasien yang belum dewasa pada hakikatnya kita berpatokan pada kemampuan intelektual pihak yang diberi informasi untuk dapat menerima dan mencerna kesemuanya itu sehingga tanpa paksaan atau desakan memberikan persetujuan agar dilakukan tindakan-tindakan medik atas dirinya. 2. Hak untuk menentukan nasib sendiri dikaitkan dengan "informed consent" Hak-hak dasar individu, membuka hati para penyusun Code Neurenberg untuk menerapkan dua hal. Pertama, mereka dapat memilih jalan untuk kembali pada rumusan Hippocrates lama dengan menggarisbawahi bahwa pemeriksaan hanya dapat dilakukan bilamana hal itu dapat dibenarkan karena membawa keuntungan bagi pasien/naracoba. Kedua, mereka dapat berpaut pada pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat, dan mereka dapat mengendalikannya terhadap ekses yang mungkin timbul dengan jalan memberikan bentuk pada salah satu asas yang mempunyai 87 daya membatasi kecenderungan-kecenderungan tersebut. Para penyusun dan perumusan kode tersebut telah memilih cara yang disebut terakhir. Pasal kedua kode Neurenberg menjadikan terang-benderang bahwa asas bermanfaat bagi pergaulan hidup, namun, masalah "informed consent" sebagai pasal pertama ialah dimasukkan ke dalam, bukan untuk memudahkan pencapaian keuntungankeuntungan sosial, melainkan sebagai syarat dan ketentuan pembatasan. Hal tersebut akan menyebabkan pengambilan kesimpulan yang tidak dapat ditawartawar lagi. Setiap orang yang dalam pelayanan medik mengajukan persyaratan "informed consent" untuk alasan-alasan lain kecuali nilai-nilai yang menganggap persetujuan sebagai alat untuk memudahkan pemeriksaan bagi manfaat pergaulan hidup, harus mengakui bahwa para individu mempunyai tuntutan-tuntutan tertentu terhadap pergaulan hidup. Walaupun "informed consent" dapat meningkatkan manfaat bagi pasien dalam pergaulan hidup, namun akan transparan dari tujuan primernya berada di atas tujuan lain pretensius ini. "Informed consent" dalam peristiwa-peristiwa tersebut sebagai alasan untuk mengesampingkan hak-hak individu tertentu demi kepentingan baik para pihak yang bersangkutan (manfaat-bagi-pasien/nara-coba, maupun orang-orang lain serta manfaat bagi pergaulan hidup). Khususnya hak individu menentukan nasib sendiri menyebabkan informed consent mutlak diperlukan bagi semua tindakan dan bahkan atas semua pelanggaran terhadap suasana kehidupan pribadi seseorang. Asas otonomi hak menentukan nasib sendiri memberikan suatu dasar bebas dan mandiri bagi persyaratan informed consen, yang terkadang dijabarkan dari kekhawatiran pemberian perlindungan individu terhadap risiko-risiko, maupun melindungi pergaulan hidup terhadap penelitian- 88 penelitian yang paling luas. Dengan mempergunakan otonomi tersebut sebagai dasar maka pemberian persetujuan dapat dipandang sebagai negosiasi pembuatan kontrak. Sesungguhnya ada bukti yuridis yang kuat bahwa teori penentuan nasib sendiri tentang informed consent ini merupakan dasar filosofis syarat pemberian persetujuan. Pada hakikatnya ada petunjuk-petunjuk bahwa para penyusun pedoman pemeriksaan eksperimental mengakui bahwa baik "informed consent" maupun hak-hak lainnya tidak tunduk pada permasalahan mengenai manfaat dan mudaratnya hal tersebut bagi para pasien dan pergaulan hidup. Nah, dalam hal pemberian pertimbangan merupakan suatu conditio sine qua non, maka komisikomisi pertimbangan mempunyai tiga buah tugas sensial, yakni untuk menetapkan apakah: a. Risiko-risiko bagi para pasien diatur sedemikian rupa sehingga seimbang dengan jumlah manfaat yang diperoleh pasien tersebut dan kepentingan memperoleh pengetahuan, agar keputusan untuk memperkenankan pasien dapat dibenarkan. b. Hak-hak dan kesehatan masing-masing pasien dilindungi sepatutnya; dan c. Diperoleh informed consent yang secara yuridis berhasilguna dan berdayaguna serta menurut cara yang memadai dan serasi. Jika benar asas menentukan nasib sendiri adalah dasar yang sebenarnya bagi doktrin informed consent maka tampaknya hanya ada satu penjelasan yang mungkin kita jumpai dalam kenyataan bahwa penilaian tentang perlindungan hakhak individu (sub 2) tergantung pada penilaian risiko bagi pasien (sub 3). Untuk menjelaskan hal ini Veatch mengemukakan dua buah pikiran mengenai otonomi 89 (right to self-determination) sebagai dasar bagi "informed consent". Dasar yang pertama disebutnya "doktrin penentuan nasib sendiri yang berdayakerja lemah". Menurut teori ini sang individu hanya mempunyai hak menentukan nasib sendiri atas tindakan-tindakan pada tubuh atau kepasiniannya (privacy), bilamana penerapan penentuan nasib sendiri menyentuh secara hakiki kesejahteraannya. Dalam hal ini hak individu untuk menentukan nasib sendiri terbatas pada bidang, yang di dalamnya diambil risiko-risiko. Pada sisi lain, kata beliau, kita dapat berbicara tentang "doktrin penentuan nasib sendiri dengan daya kerja lengkap". Bilamana individu senantiasa harus diperlakukan sebagai tujuan dan sebagai alat, maka orang tersebut memiliki otonom di semua bidang kehidupan dan tidak hanya dalam peristiwa-peristiwa di mana manfaat dan mudarat asasi dipertaruhkan. Sebenarnya perlu diperkirakan dalam batas-batas tertentu bahwa hak menentukan nasib sendiri memberikan kepada individu hak untuk mengadakan pilihan yang pada hakikatnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya sendiri. Jika dirumuskan seperti itu, maka tampaknya tidak mungkin bahwa hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan hak atas ikhtiar untuk mengejar kesejahteraan, dilakukan dengan syarat "hanya dalam situasi dan kondisi dimana risiko dan manfaat memainkan peranan. Dari apa yang diuraikan diatas, dan mengingat pula bahwa relasi antara dokter dan pasien tersebut adalah persetujuan dalam arti hukum, maka kepada pasien perlu diberikan kepastian hukum yang menjadi haknya. Hak atas informasi perlu direalisasikan terutama karena sifat kondisi pelayanan medik sarat dengan pembatasan-pembatasan yang kadang-kadang menghimpit perwujudan hak 90 tersebut dalam praktek. Van der Mijn merumuskannya sebagai berikut: "Tidak dapat disangkal bahwa disini kita berhadapan dengan suatu hak mutlak dalam arti bahwa dokter wajib mengemukakan semua peristiwa, pandangan dan harapan kepada setiap pasien tentang semua kondisi dan koneksi. Disini kita jumpai suatu hak relatif yang dibatasi oleh keadaan fisik dan psikhis pasien maupun oleh ketidakpastian yang pada umumnya dihadapi sang dokter. Namun, demikian lanjutnya, bagi pasien dan keluarganya, karena mulai disadari bahwa haruslah lebih banyak keterbukaan diperlihatkan dalam hubungan dokter dengan pasien, agar pasien merasakan tanggungjawabnya sendiri dalam tindakan-tindakan yang diambil untuk mempertahankan kesehatannya". Sesungguhnya hak atas informasi ini sudah diatur secara formal walupun pada tahun 1981 dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transpiantasi alat dan atau jaringan tubuh. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi: "Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi". Kemudian ayat (2 )pasal ini memuat ketentuan bahwa "Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut". ' Hak atas informasi, kalau tidak mau disebut "informed consent" anno 1981 dan anno 1989 mengandung beberapa perbedaan. Pertamaa, hanya mengatur pemberian persetujuan mengenai pencangkokan alat dan jaringan tubuh yang 91 bersifat khusus, sedangkan yang disebut terakhir mengenai pemberian persetujuan yang bersifat umum. Kedua, saat situasi dan urgensi penerbitan peraturan kedua peraturan perundang-undangan tersebut jauh berbeda. Yang pertama berlangsung dalam suasana yang relatif tenang, sedangkan yang kedua sarat dengan kasus (Muhidin di Sukabumi, Adriani di Jakarta dan sebagainya). Ketiga, sanksi terhadap pelanggaran pada yang satu lebih bersifat hukum pokok (hukum pidana, perdata), sedangkan bagi yang lain hanya bersifat hukum tata-tertib. 3. Hak-hak Atas Keutuhan Tubuh Manusia adalah jiwa, roh dan badan. Ia merupakan suatu kesatuan. Kita tidak dapat berbicara mengenai manusia hanya tubuhnya dan tidak pula hanya roh dan jiwanya. Dengan kata lain tubuh manusia ikut menentukan keberadaan individu sebagai manusia. Dalam makna tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia tidak memiliki tubuhnya, melainkan ia adalah tubuh itu sendiri dan tubuh ini pada hakikatnya menempatkan manusia dalam ruang dan waktu. Dengan tubuh tersebut manusia dikenal oleh sesamanya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa ketubuhan manusia mempunyai nilai besar dimata hukum. Sesungguhnya relasi antara tubuh dan jiwa sejak dahulu merupakan problematik filosofis yang utama. Kenyataan bahwa manusia adalah tubuhnya tidak mengurangi peristiwa bahwa selaku demikian secara holistik ia juga mempunyat aspek kebendaan, suatu barang, yang dapat dimiliki. Strasser, dalam tulisannya "Bouwstenen voor een filosofische anthropologie, 1965, 33 e.v."), mengemukakan bahwa manusia mengalami dan menjalani tubuhnya melalui cara baik "quasi-objectief" maupun "quasisubjectief". Dalam sudut pandangan objectif maka tubuh bagi manusia 92 merupakan sesuatu obyek yang dapat diikhtiarkan umtuk dikuasai . Namun, tubuh dapat dipandang pula secara subjektif, karena ia adalah "het vehikel van onrc intentionele acten". ia memberikan peluamg bagi manusia untuk menjadi manusia. Dalam ilmu pengetahuan hukum maka posisi yuridis tubuh manusia merupakan materi pengkajian dan diskusi. Bukankah didalam lalu-lintas hukum tubuh manusia ini mernpunyai posisi khusus? Sejajar denigan pertanyaan apakah manusia adalah atau mempunyai tubuhnya, maka pada satu sisi tubuh ini dipandang sebagai "benda berwujud", yang dapat menjadi obyek eigendom, pada sisi lain ia merupakan bagian (atau pernah nrerupakan bagian) pribadi manusia, sehingga ia dibedakan dari benda-benda lain yang beredar dalam lalu lintas hukum. Sebagai analogi dengan eigendom maka tampak dari manusia dapat menentukan nasib tubuhnya. Misalnya menjalani atau menolak pengobatan dan perawatan medik, menyerahkan organ-organ tertentu untuk maksud dan tujuan transplantasi pada masa hidupnya (misalnya organ berpasangan seperti ginjal), maupun setelah ia mati (misalnya ginjal, selaput bening atau kornea, jantung), menyumbangkan darah atau sperma, menjual rambut, bahkan menghibahkan tubuhnya pascamati kepada sebuah laboratorium anatomis untuk maksud dan tujuan ilmiah. Selain itu manusia dapat menetapkan cara pengurusan tubuh tersebut setelah ia meninggal dunia dikuburkan atau dikremasikan. Disini tampak pula adanya kesejajaran dengan ketentuan-ketentuan hukum waris. Walaupun demikian tubuh tersebut tidak sirna dengan benda-benda lain. Kenyataan bahwa tubuh ikut membentuk atau telah membentuk pribadi manusia, maka diletakkan pula pembatasan dalam memiliki tubuh tersebut. 93 Dengan demikian penghibahan jenazah kepada sebuah laboratorium anatomi merupakan sesuatu yang terpuji, namun akan sangat bertentangan dengan asas kepatutan dan kesucian untuk menyerahkan tubuh kepada sebuah kebun binatang sebagai makanan bagi binatang-binatang buas. Sesungguhnya tubuh manusia memainkan peran penting dalam pelayanan kesehatan. Dengan sendirinya hak menentukan nasib sendiri tentang tubuh timbul kepermukaan, misalnya mengizinkan tindakan-tindakan medik atas tubuh, sedangkan permasalahan inseminasi buatan, sterilisasi, transeksualitas, eutanasia, dan sebagainya maka hak menentukan nasib sendiri atas tubuh merupakan salah satu inti permasalahan. Dalam rangka donasi organ-organ, maka Dierkons dalam kaitan ini mengutarakan dalam bukunya "Lichaam en lijk" bahwa donor tidak boleh mengorbankan kehidupan dan kesehatannya untuk kepentingan pasien dan bahwa dokter dalam hubungan ini hanya boleh bertindak bila ia tidak menghadapi resiko kehilangan donor sebagaimana harapannya memenangkan pasiennya. Permasalahan lain yang berhubungan dengan hak atas keutuhan tubuh adalah hak untuk mengurung diri sendiri dan hak untuk mati, yang juga menyangkut kekuasaan atas tubuh sendiri. Kekuasaan orang lain atas tubuh tanpa izin orang yang bersangkutan sangat terbatas jumlahnya. Para orang tua rnisalnya mempunyai kekuasaan orang tua atas anak-anak mereka yang belum dewasa, namun mereka tidak mempunyai kekuasaan memiliki tubuh anak-anak yang disebut tadi. Penguasa pun hanya memiliki kekuasaan terbatas atas keutuhan tubuh para warganegaranya. Namun untuk itu harus ada alasan-alasan khusus. Contoh, Undang-undang Pembasmian 94 Penyakit menular, ketentuan-ketentuan pengurusan jenazah di Amerika Serikat misalnya tes darah wajib untuk pengemudi, dan sebagainya. Dalam pelayanan kesehatan istilah penentuan nasib sendiri hanya muncul kepermukaan secara sporadis. Pada umumnya dipakai istilah wajib wafak yang mempunyai muatan yuridis yang tegas. Yang dimaksudkan dengan wajib wafak ialah kewajiban pasien untuk membiarkan dirinya mengalami tindakan-tindakan medik untuk mempertahankan kesehatannya. Di samping kewajiban tersebut pasien mewafak banyak hal satu dan lain karena ketidaktahuan atau kebelumdewasaan, sehingga dalam kenyataannya melebihi yang diperlukan, seperti waktu tunggu yang panjang dan tindakan-tindakan kekanak-kanakan. Namun ia sama sekali tidak menyadari hal tersebut dan ia menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut tanpa mengeluh. Dapat dikemukakan disini bahwa dalam praktek pasien sedikit sekali menggunakan hak. Tidak ada pihak-pihak, termasuk para penyelenggara pelayanan kesehatan, yang datang kesisi ranjang pasien untuk memberitahukan hal tersebut. Untuk menentukan apa yang akan dilakukan atas tubuh seseorang, maka pertarna-tama diperlukan informasi. Bagaimana seseorang dapat menentukan apa yang ia ingini atau tidak menghendakinya lagi, jika ia tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan, bila ia tidak diberi informasi mengenai diagnosis, terapi dan lain-lain. Tambahan pula selain terhadap pasien hak ini berperan pula bagi lingkungan sang pasien (keluarga dekat, mitrakawin, apalagi hal-hal tersebut menyangkut pasien-pasien tua-renta, anak-anak dan pasien koma). Jika kepada pasien dan para dokter pada umumnya sangat hemat dengan informasi, maka penyuluhan terhadap kaum keluarga pasien hanya ala kadarnya saja. 95 Seperti telah diuraikan di atas, bahwa sekalipun pasien telah diberikan informasi secara memadai namun harus ada pendamping agar dapat membentuk dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak akan mengandalkan hak menentukan nasib sendiri yang ia miliki. Dokter dan penyelenggara pelayanan medik lainnya pun tampaknya tidak memberikan pasien hak menentukan nasibnya. Mereka pun menghadapi kendala, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Pada umumnya dokter bukan penyuluh yang baik padahal pemberian informasi yang memadai diikuti oleh pendamping membantu pasien menerapkan hak menentukan nasib sendiri. Dalam situasi dan kondisi tertentu dokter menghadapi permasalahan internal tentang apa yang menurutnya layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat saja terjadi bahwa dengan memegang teguh keyakinannya sendiri, secara etis ia dimintakan untuk tidak saja melakukan tindakan medik tertentu, melainkan hal itu merupakan alasan baginya untuk tidak merujuk lebih lanjut ke instansi penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya. Dengan demikian pada hakikatnya ia telah menutup pintu pasien ke arah pernanfaatan hak menentukan nasib sendiri. Salah satu kelemahan yang nampak dalam bidang ini ialah kurangnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai disiplin dan keahlian satu dengan yang lain pada satu sisi, dan kurang diadakannya kontak langsung dengan pasien berikut keluarganya. Akhirnya perlu disimak pula hal-ikhwal yang berkaitan dengan tanggungjawab penyelenggara pelayanan medik, baik yuridis maupun etis. 4. Hak atas Kepasinian (privacy) Kepasinian dapat dirumuskan sebagai kebebasan pribadi individu untuk mengasingkan diri dari pergaulan hidup untuk berada dalam kalangan keluarga 96 sendiri atau berada sendirian sebatang kara. Pengisolasian diri inilah yang dicari secara sukarela dan untuk sementara waktu oleh individu atau kelompok manusia. Dalam pemisahan diri dari kalangan dan khalayak inilah, yang menurut Westin (1970) dan beberapa peneliti, merupakan saripati pengertian kepasinian (privacy). Saat ini pengertian kepasinian pada umumnya telah diberikan fungsifungsi positif. Salah satu ialah bahwa dengan mengundurkan diri untuk sementara waktu atau hidup sebatang kara, terciptalah peluang untuk membebaskan diri dari ketegangan- ketegangan emosional kehidupan sosial dan berbagai peran yang dimainkan individu bersangkutan, mengharuskannya terpenuhi bermacam-macam persyaratan, antara lain terus-menerus membulatkan tekad, kewaspadaan dan sebagainya. Selama ia berada dalam pengasingan ia dapat men"charge" kembali dirinya dengan memperoleh kekuatan baru dan gairah kerja yang meluap-luap. Kepasinian yang dialami seperli ini merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan Gejala kepasinian (privacy) ini ditandai dan diwarnai suatu proses materiil dan non materiil. Yang menyangkut sisi non materiil disini ialah upaya melindungi suasana kehidupan pribadi yang berhubungan dengan kesehatan, pola hidup seseorang dan pendirian serta keyakinannya terhadap campur tangan pihak ketiga yang tidak diingini. Sedangkan sisi materil terangkat dalam bentuk kebutuhan dapat menarik diri untuk sementara waktu dalam suasana ruang dan peluang yang memadai. Kepasinian dan penentuan nasib sendiri, terkait erat satu dengan yang lain. Inti hak atas kepasinian adalah hak atas khalwat, pengasingan diri ditempat yang sunyi untuk menenangkan pikiran, menyepikan diri ditempat yang sunyi. Bahkan hak atas kepasinian ini dalam pelayanan kesehatan terangkat ke 97 permukaan dalam suatu situasi hukum, yang melindungi individu dan keyakinan pribadinya. Sebagai ajaran panutan diakui bahwa perlu dijunjung tinggi agar setiap orang dapat mempercayakan sesuatu kepada penyelenggara pelayanan kesehatan atau instansi yang memberikan pelayanan kesehatan. Dasar hukum tersebut meletakkan kewajiban diatas pundak dokter dan mitra kerjanya pada satu sisi dan berbagai sarana kesehatan pada sisi lain. Mengenai hal ini diatur juga dalam KUHP Pasal 322 yang berbunyi: "Barangsiapa sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Dapat dikemukakan disini bahwa karena rahasia tersebut adalah hak milik pasien sehingga ia dapat membebaskan dokter dari kewajiban berdiam diri, setidak-tidaknya mengenai hal-ikhwal yang menyangkut kepentingannya. Namun, bilamana dokter mengetahui bahwa pasien telah memberikan persetujuannya tidak berdasarkan alasan-alasan yang memadai, maka kewajiban menyimpan rahasia dokter tetap berlaku, karena pasien tidak dapat membebaskan dokter dari kewajiban yuridisnya. Dalam situasi dan kondisi tertentu tanpa kewajiban yuridis atau persetujuan pasien tampaknya kewajiban berdiam diri dokter dapat gugur. Hal tersebut dapat terjadi demi kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Contoh kepentingan pribadi disini adalah pasien sakit ayan tinggal sebatang kara, sedangkan contoh kepentingan umum disini ialah seorang pasien sedang mengadakan rencana pembunuhan yang diketahui dokter. Kalau kewajiban yuridis rahasia profesi tetap ditetapkan pembuat undang-undang, kepentingan mana yang harus dijunjung tinggi, maka dalam situasi dan kondisi seperti ini 98 timbang-menimbang antara kepentingan-kepentingan harus dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani kewajiban. Dalam hal ini terjadi benturan antara dua kepentingan tampaknya dokter harus mencari jalan keluar melalui etika medik. Namun bagaimanapun juga keputusan ada ditangan dokter yang berhak menerobos rahasia profesinya jika dalam mempertahankan kewajibannya tersebut ada kekhawatiran terjadinya akibat-akibat yang dapat merugikan pasien, pihak ketiga maupun kepentingan umum. Dalam kerangka benturan antara berbagai kewajiban dapat pula diajukan disini permasalahan khusus ialah pemberian keterangan kepada pihak kepolisian. Demi kepentingan penyidikan misalnya dapat saja terjadi bahwa pihak kepolisian mendatangi rumah sakit untuk memperoleh keterangan mengenai seseorang yang diopname, katakan saja karena luka. Aturan dasar disini ialah bahwa dokter yang mengobati dan merawat tidak boleh memberikan keterangan kepada polisi, mengenai keberadaan seseorang dalam rumah sakit. Pada dasarnya para pasien harus dapat mendatangi dokter dan rumah sakit tanpa kekhawatiran untuk ditangkap. Rahasia profesi berada diatas penyidikan kepolisian, yang merupakan salah satu latar belakang pengaturan kewajiban berdiam diri dan hak untuk mengundurkan diri selaku saksi. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus tunduk pada aturan tersebut dan tidak berikhtiar memperoleh keterangan mengenai kehadiran seseorang di rumah sakit atau keadaannya melalui karyawan rumah sakit. Kepada karyawan rumah sakit harus diinstruksikan untuk tidak memberikan keterangan yang berkaitan dengan apa yang tersebut di atas kepada polisi. Pihak kepolisian harus mendatangi dokter yang mengobati dan merawat, yang harus mengadakan timbang-menimbang 99 antara benturan berbagai kewajiban yang dihadapinya. Di negeri Belanda sendiri hal tersebut dipecahkan dengan jalan menyerahkan persoalan tersebut kepada kejaksaan dan bukan kepada pihak kepolisian. Dalam hal tertentu dokter dapat memberikan keterangan kepada dokter yang telah ditunjuk oleh pihak kepolisian, asalkan identitas orang yang bersangkutan sudah diketahui polisi. Bagaimanapun juga hal tersebut tetap merupakan pengungkapan rahasia profesi, sekalipun dalam benturan berbagai kewajiban sebagai pegangan, pada umumnya dokter akan luput dari tuntutan. Tidak pula tertutup kemungkinan bahwa pasien sebagai pemilik rahasia tersebut memberi persetujuan untuk memberikan keterangan kepada polisi, maka dalam hal ini dokter berhak memberikannya. Pembukaan rahasia disini mempunyai sifat yang sama sekali lain. Kenyataan bahwa dokter memberikan keterangan-keteranaan mengenai pasien kepada dokter-dokter lain, bagi rahasia profesi hal tersebut tidak mernpunyai makna sama sekali, satu dan lain karena dokter tersebut juga berkewajiban berdiam diri terhadap para teman sejawatnya. Bagaimanapun juga dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan sang dokter, hal tersebut diperlukan dan dalam kaitan ini tidak dapat dicegah bahwa beberapa data pasien diungkapkan. Dengan demikian, para dokter yang berperanserta pada "medical audit" tersebut memiliki rahasia profesi sendiri. Penerobosan rahasia profesi oleh dokter yang mengobati dan merawat pasien dalam forum "medical audit", selama tidak ada peraturan perundang-undangan untuk itu, mempunyai sifat adanya pertentangan antara berbagai kewajiban yang dihadapi dokter. 100 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Right to self determination tidak bisa menjadi dasar untuk pembenaran praktek euthanasia bukan pelanggaran hak asasi manusia. Pada prinsipnya seorang pasien yang dalam keadaan koma atau kritis tidak berdaya, tidak bisa mempertahankan hak-haknya dan mengajukan pilihan hukum. Posisi yang lemah (bargaining power) dari pasien rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dokter. 2. Keterkaitan etika kedokteran dan HAM terutama menyangkut kewenangan dari dokter untuk menerapkan etika kedokteran atau perlindungan hak-hak asasi manusia pasien dalam praktek euthanasia. Pilihan dari dokter itu menentukan terlindungnya hak-hak hidup dari pasien. Kalau dokter memilih untuk mengedepankan etika kedokteran maka hak-hak hidup dari pasien sulit dilindungi. 3. Perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien dalam praktek euthanasia masih rentan dan belum jelas terutama menyangkut batasan-batasan pelanggaran HAM yang dilanggar oleh dokter dan batasan-batasan perlindungan terhadap pasien. Dalam praktek seringkali pasien menyerahkan kepada keluarga untuk menentukan nasibnya. Sikap keluarga atau orang-orang yang terdekat dari pasienlah yang sangat menentukan dilindunginya hak hidup dari pasien atau tidak. 101 B. SARAN 1. Harusnya ada dana khusus baik dari Pemerintah, terutama Pemda untuk meringankan beban keluarga bagi pasien yang menderita sakit parah. 2. Pemerintah harus segera menetapkan aturan mengenai euthanasia dalam iusconstitutum. 102 DAFTAR PUSTAKA Achadiat. C.M. 2002. Euthanasia yang semakin Kontroversial. Medika/arsip/01 2002/top-1.htm. Achadiat. C.M. 1996. dalam Suara Pembaharuan. 28 Nopember. Anonimous. 1983. Grolier Academic Encyclopedia. Grolier International. Anonimous. 2007. Undang-undang Hak Asasi Manusia. Penerbit. Visi Media. Bertens. 2005. Etika. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Budiarjo, M. 1987. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia, Jakarta. Budiman. A. 1993. Posisi Tawar Menawar Rakyat Dalam Hak Asasi Manusia. Jawa Pos. Selasa Pahing. 2 Februari Effendi. H.A. M. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Ghalia Indonesia. Jakarta. Gunawan. 1991. Memahami Etika Kedokteran. Yogyakarta. Penerbit Kanisius. Hadiwardoyo. P. 1989. Etika Medis. Jakarta: Pustaka filsafat. Hilman, 2004. Euthanasia. Sebuah pemikiran. 1004/12/0801.htm Karyadi. P.Y.2001. Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,Penerbit. Media Pressindo. Leenen. 1978. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. Samson Uitgeverij Alphen aan de Rijn/Brussel. Mahasin. A. 1979. Hak-hak Asasi Manusia: Dari Konstitusional ke Persoalan Struktural. PRISMA No. 12 Desember. Notohamidjodjo. D. 1970. Demi Keadilan Dan Kemanusiaan. BPK. Gunung Mulia. Jakarta. Oemar. S. A. 1991. Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Jakarta. Penerbit Erlangga. Prakoso. D. dan D. A. Nirwanto. 1984. Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Prodjodikoro. W. 1977. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Sumur. Bandung. Rahardjo. S. 1989. Asas-Asas Hukum Nasional. BPHN. Jakarta. 103 Runciman. W.H. 1972. The Three Dimension of Social Inequity, dalam Andree Beteille (ed)., Social Inequality. Penguin Books. Englan. Samil. R. S. 1994. Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah). Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sanit. A. 1985. Hak Asasi Manusia, Kelas dan Negara : Keperluan Akan Suatu Mekanisme; KEADILAN No. 1 Tahun III. Schuyt. C.J.M. 1980. Keadilan dan Efektifitas Dalam Pembangunan Kesempatan Hidup, yang dikutip oleh T. Mulya Lubis, Pembangunan dan Hak-hak Asasi Manusia. PRISMA No. 1. Smith. H. 1995. The Religion of Man (Agama agama manusia). Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Soekanto. 1989. Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan). Penerbit. IND-Hill-Co. Jakarta. Sunaryati. H. 1987. Peranan dan Kedudukan Azas-Azas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional. FH. UNPAR. Bandung. Tengker. F. 2005. Hak Pasien. Penerbit. CV Mandar Maju. Jakarta. Veronica. Ch 2005. Penyalahgunaan Euthanasia Pasif. 2005/0205/27/hikmah/ utama02.htm William. J. R. 2006. Medical Ethics Manual. Sagiran. 2006 (alih Bahasa), Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiya. Yogyakarta. Wiradharma. D. 1996. Hukum Kedokteran. Binarupa Aksara. Jakarta. Zaini. D. (Penerjemah). 2003. Qur,an Karim dan Terjemahan Artinya. UII Press. Yogyakarta. 104