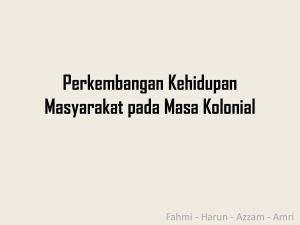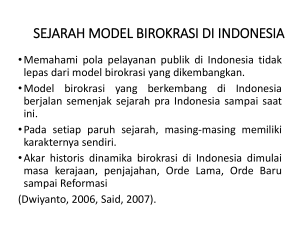Sistem Perkebunan Masa Hindia
advertisement
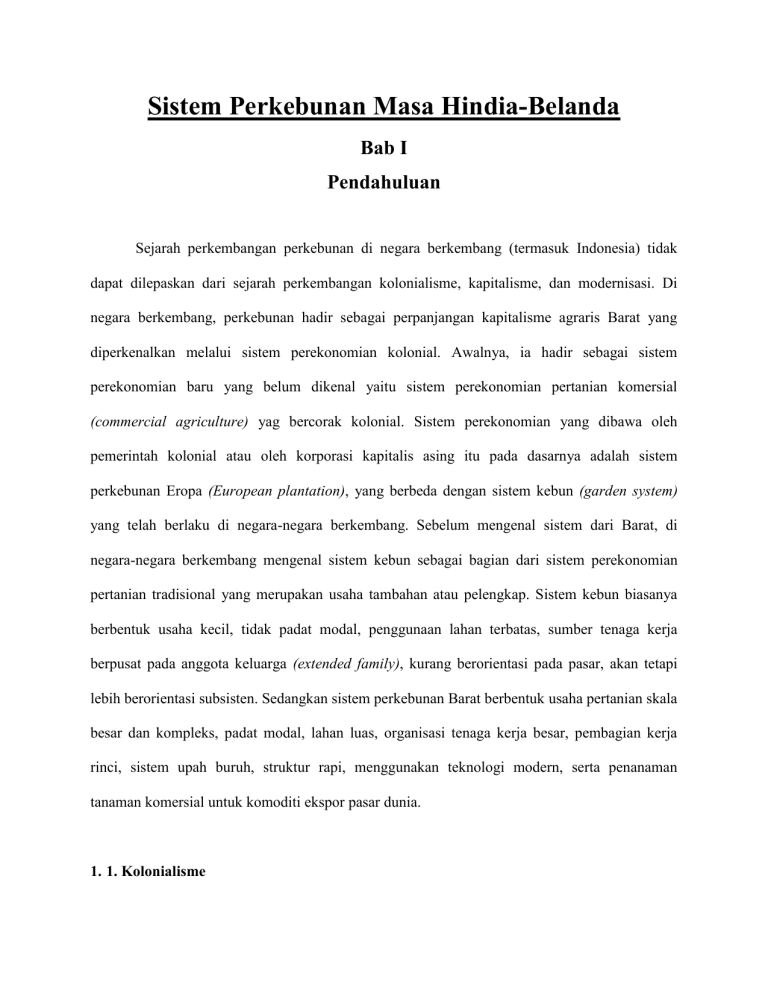
Sistem Perkebunan Masa Hindia-Belanda Bab I Pendahuluan Sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang (termasuk Indonesia) tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Di negara berkembang, perkebunan hadir sebagai perpanjangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Awalnya, ia hadir sebagai sistem perekonomian baru yang belum dikenal yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (commercial agriculture) yag bercorak kolonial. Sistem perekonomian yang dibawa oleh pemerintah kolonial atau oleh korporasi kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa (European plantation), yang berbeda dengan sistem kebun (garden system) yang telah berlaku di negara-negara berkembang. Sebelum mengenal sistem dari Barat, di negara-negara berkembang mengenal sistem kebun sebagai bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional yang merupakan usaha tambahan atau pelengkap. Sistem kebun biasanya berbentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga (extended family), kurang berorientasi pada pasar, akan tetapi lebih berorientasi subsisten. Sedangkan sistem perkebunan Barat berbentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, padat modal, lahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, sistem upah buruh, struktur rapi, menggunakan teknologi modern, serta penanaman tanaman komersial untuk komoditi ekspor pasar dunia. 1. 1. Kolonialisme Hampir seluruh negara berkembang (developing countries atau underdeveloped countries) memiliki pengalaman historis dengan perkembangan kolonialisme. Ekspansi kekuasaan kolonial pada abad ke-19 merupakan gerakan kolonialisme yang paling besar pengaruhnya dalam membawa dampak perubahan berbagai aspek di negara-negara yang mengalami penjajahan serta terjadi transformasi struktur politik ekonomi tradisional ke arah struktur politik ekonomi kolonial dan modern. Dampak penting gerakan kolonialisme adalah timbulnya sistem kolonial (colonial system) dan situasi kolonial (colonial situation) di negara jajahan yang pada akhirnya menciptakan sistem hubungan kolonial antara penguasa kolonial dan penduduk pribumi yang dikuasai, dan antara pihak negara jajahan dengan negara induknya. Ciri pokok kolonial adalah prinsip dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi yang berpangkal pada doktrin pengejaran kejayaan (glory), kekayaan (gold), dan penyebaran agama (gospel). Sistem dominasi, eksploitasi, dan diskriminasi yang berlaku dalam sistem kolonial telah menciptakan jurang perbedaan serta hubungan ketergantungan antara pusat dengan daerah, dan antara negara induk dengan jajahan. Hubungan ketergantungan ini mencakup berbagai hal seperti modal, teknologi, pengetahuan, keterampilan, organisasi dan kekuasaan. Perbedaan yang ada sejak hadirnya sistem perkebunan di lingkungan masyarakat agraris tradisional di tanah jajahan (oleh beberapa pihak) dianggap telah menciptakan tipe perekonomian kantong (enclave economics) yang bersifat dualistis (dualistic economy) yakni kehadiran komunitas sektor perekonomian modern (yang berorientasi ekspor dan pasaran dunia) di tengah-tengah lingkungan komunitas sektor perekonomian tradisional (yang bersifat subsisten). 1. 2. Kolonialisme dan Modernisasi di Indonesia Seperti negara-negara berkembang lainnya (sebelum masuknya sistem perkebunan kolonial), di Indonesia juga telah berkembang sistem kebun terlebih dahulu. Sistem ini bahkan berlaku sampai masa penjajahan VOC pada abad ke-17—18. Proses perkembangan sistem perkebunan berlangsung sejajar/sinergis dengan perkembangan politik kolonial. Pertumbuhan sistem perkebunan berlangsung dalam dua fase perkembangan yaitu fase perkembangan industri perkebunan negara ke fase industri perkebunan swasta, serta beriringan dengan perkembangan orientasi politik kolonial dari orientasi politik konservatif ke politik liberal. Pada masa awal abad ke-19, golongan konservatif menguasai pemerintahan. Mereka melakukan politik eksploitasi dengan penyerahan paksa (1830-1870). Eksploitasi produksi pertanian diwujudkan dalam bentuk usaha perkebunan negara berdasar sistem tanam wajib/tanam paksa. Pelaksanaan sistem ini dijalankan melalui alat birokrasi pemerintah sehingga menuntut perangkat birokrasi yang mapan yang mengimbangi perkembangan sistem perkebunan. Hal itu ditandai dengan proses birokratisasi berupa sentralisasi administrasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Perkembangan ini juga menuntut kebutuhan pegawai perkebunan sehingga terjadi gejala peningkatan edukasi yang ditandai dengan lahirnya sekolah calon pegawai. Selain itu, sebelumnya, proses agro-industrialisasi juga melahirkan perkembangan komunikasi dan transportasi seperti jalan Anyer-Panarukan. Selanjutnya, sejak tahun 1870-an terjadi pergeseran kebijaksanaan politik dari politik konservatif ke politik liberal. Hal ini diikuti dengan perubahan kebijaksanaan politik drainage, yaitu politik eksploitasi tanah jajahan yang semula dikelola negara, kemudian diganti oleh perusahaan awasta. Perubahan kebijaksanaan politik tersebut dalam perkembangannya menuntut peningkatan intensifikasi sistem administrasi serta penekanan orientasi kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Perkembangan pada awal abad ke-20 ini mendasari perubahan orientasi kebijaksanaan politik yang baru lagi yaitu Politik Etis. Bab II Masa Pra-Kolonial: Sistem Kebun pada Masa Tradisional 2. 1. Dari Ladang ke Kebun Dari berbagai perkembangan ragam pertanian di kepulauan nusantara, terdapat empat sistem pertanian yang telah lama dikenal di daerah Indonesia yaitu (1) sistem perladangan (shifting cultivation), yaitu jenis kegiatan pertanian yang berpindah-pindah, penanaman tanaman yang berumur pendek; (2) sistem persawahan (wet rice cultivation sistem); (3) sistem kebun yang menggarap tanaman (perdu) berusia panjang (perennial) atau tanaman penghasil panenan (crops) yang ditanam pada lahan tetap; dan (4) sistem tegalan (dry field), yaitu tipe kegiatan penanaman tanaman pangan (food crops) secara tetap pada daerah lahan kering. Semua sistem tersebut telah berlaku sebelum kedatangan bangsa Eropa, bahkan masih ada yang berlaku hingga saat ini. Sistem perladangan ditandai oleh sifat imitasi ekologis, pertanian tidak tetap, aneka ragam tanaman, dan berkaitan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Sedangkan sistem persawahan merupakan bangunan alam sekitar artifisial yang ditanami tanaman khusus, didukung lingkungan pedesaan padat penduduk, sistem irigasi yang kompleks yang determinan dengan pertumbuhan penduduk yang kompleks pula. Selain itu, sistem persawahan juga memiliki kecendrungan untuk merespon kenaikan penduduk melalui intensifikasi. Seperti halnya sistem peladangan dan persawahan, sistem kebun juga telah tua, setidaknya sejak 1200 M. Dalam perkembangannya, sistem kebun mengalami berbagai ragam bentuk, baik penanaman tanaman campuran, penanaman satu jenis tanaman, tanaman usia pendek maupun panjang. Berbeda dengan sawah, kebun kurang menuntut tenaga kerja besar. Kebun juga tidak menuntut lokasi istimewa, asalkan iklim dan pengeringan tanah yang baik serta jarak pasar yang tidak jauh. Sekali dibangun di suatu tempat, kebun bisa terus berlangsung lama sehingga hal ini mendasarkan dugaan Terra bahwa sistem perkebunan campuran di Jawa Timur telah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1200 M. Di Jawa Tengah bahkan lebih jauh sebelum itu. Begitu juga dengan kebun karet dan kopi di Sumatera sejak akhir abad ke-19, serta berbagai perkebunan lain di wilayah nusantara. 2. 2. Kebun Komoditi Perdagangan Salah satu perubahan yang lebih penting daripada variasi daerah ialah perubahan dari sistem ladang ke sistem kebun permanen yang menanam tanaman perdagangan. Kebun bertanaman campuran merupakan salah satu tipenya. Kebun ini diduga telah berkembang di Jawa Tengah sebelum abad ke-10. Perkembangan yang sudah cukup tua juga terjadi di Sumatera dan Sulawesi Selatan, disamping di daerah Nusa Tenggara. Berbeda dengan kebun campuran yang subsisten, sejumlah daerah di luar Jawa sebelum abad ke-19 telah mengembangkan kebun tanaman perdagangan (gardens of commercial crops) seperti kopi, lada, kapur barus, dan rempah-rempah. Berdasarkan laporan perjalanan yang ada, berbagai komoditi tersebut telah lama diperdagangkan serta telah mendorong pertumbuhan kebun-kebun tanaman komersial dan mendongkrak aktivitas perdagangan internasional. Proses komersialisasi itu diawali dengan hubungan simbiotik antar daerah yang diwujudkan dalam bentuk hubungan perdagangan. Maksud dari hubungan simbiotik adalah hubungan perdagangan yang saling menguntungkan bukan hanya dilihat dari sisi pendapatan, akan tetapi dilihat dari pemenuhan komoditi yang dibutuhkan satu sama lain. Contoh corak pertukaran komoditi perdagangan simbiotik antara lain adalah pesisir Jawa-Sulawesi yang menukar emas ditukarkan dengan tekstil India. Selain meningkatnya pertumbuhan kebun komoditi komersial, meningkatnya proses komersialisasi di daerah pantai pada abad ke-16 juga mendorong pertumbuhan kelahiran kerajaan-kerajaan Islam, dan pertumbuhan kota-kota emporium di sepanjang pantai Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Pertumbuhan kerajaan dan kota-kota emporium ini sekaligus diikuti dengan kemunduran kerajaan Majapahit dan kota-kota emporiumnya. Kotakota Bandar emporium di jawa yang tumbuh dari abad ke-11 sampai abad ke-16 seperti Tuban, Sidayu, Jaratan, Lasem, Brondong, Canggu, Gresik, Surabaya, Demak, dan Jepara. Kota-kota ini memiliki hubungan perdagangan dengan kota Bandar emporium di daerah timur seperti Ternate, Tidore, Makasar, dan Banjarmasin. Kota Bandar emporium yang ada di daerah barat adalah Malaka, Aceh, dan Palembang. Kedudukan pusat Jawa sebagai daerah persawahan juga dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan agraris yang berlangsung silih berganti pada masa pra-kolonial. Kerajaan itu antara lain adalah Mataram lama, Jenggala, Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Berbeda dengan di Jawa, kerajaan-kerajaan lain di Maluku (Ternate dan Tidore) mengandalkan surplus tanaman kebun, yaitu bahan rempahrempah karena mereka tidak memiliki basis persawahan seperti yang dimiliki kerajaan Jawa. Surplus poduksi komoditi perdagangan yang dimiliki kerajaan umumnya didasarkan atas hak monopoli raja terhadap bahan perdagangan yang ada di wilayah kekuasaannya. Ada beberapa bentuk organisasi proses produksi. Pertama, raja menerima produksi komoditi perdagangan dari para kepala penguasa lokal, atas dasar penyerahan wajib/upeti. Pala dan cengkih lebih banyak dikelola oleh penguasa lokal, Orang Kaya. Kedua, raja selain menerima upeti juga memilki kebun sendiri. Menurut van Leur, sturktur perekonomian dan perdagangan Indonesia dengan Eropa pada hakikatnya mirip. Akan tetapi, mengapa kegiatan perdagangan dan masyarakat Indonesia tidak meningkatkan kemajuan perkembangan ekonomi seperti yang dicapai oleh Eropa? Mengenai hal ini, ada beberapa faktor yang mendasarinya yakni struktur geografis wilayah perdagangannya, struktur sosial, serta perkembangan pengetahuan dan teknologi yang melatarbelakangi perkembangan selanjutnya, terutama perkembangan kapitalisme dan kolonialisme. Struktur geografi kepulauan Indonesia yang luas dan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lainnya menyebabkan biaya pengangkutan perdagangan menjadi mahal sehingga yang “bermain” hanya golongan raja dan bangsawan saja. Selain itu, di Indonesia belum mengenal organisasi perdagangan seperti di Eropa sehingga perdagangan di Indonesia menjadi lemah dalam menghadapi persaingan dengan pihak luar. Perkembangan pengetahuan dan teknologi di Eropa tidak dijmpai di Indonesia sehingga kegiatan perdagangan dan ekonomi berjalan lambat dan statis selama beberapa periode. Bab IV Perkebunan pada Masa Pemerintahan Konservatif (1800—1830) 4.1. Konflik Politik Konservatif dan Liberal: 1800—1812 Peralihan pemerintahan VOC ke pemerintahan Hindia Belanda dalam rentang waktu abad ke-18 sampai abad ke-19 memberikan latar perkembangan sistem perkebunan di Indonesia pada abad ke-19. Pergantian politik pemerintahan ini ditandai dengan kebangkrutan VOC yang disebabkan berbagai faktor seperti kecurangan pembukuan, korupsi, pegawai yang lemah, sistem monopoli dan sistem paksa yang membawa kemerosotan moral dan penderitaan penduduk. Pada saat yang sama, Negeri Belanda juga sedang mengalami dampak buruk akibat perang menghadapi Inggris. Sementara itu, Negeri Belanda sendiri sedang berada dalam pengaruh kekuasaan kekaisaran Perancis di bawah Napoleon sebagai akibat dari perang yang dilakukan Perancis dengan negeri-negeri tetangganya. Oleh karena itu semua, maka perpindahan pemerintahan VOC ke tangan pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad itu tidak membawa banyak perubahan. Masih pada saat yang sama, di Eropa sedang terjadi perluasan paham dan cita-cita liberal sebagai akibat dari Revolusi Perancis. Paham liberal itupun masuk ke Negeri Belanda. Salah satu tokohnya adalah Dirk van Hogendorp. Ia adalah juru bicara kaum liberal Belanda yang sering mengajukan gagasan baru kepada pemerintahan Belanda untuk menjalankan politik kolonialnya di Indonesia dengan berdasarkan kebebasan dan kesejahteraan umum. Kaum liberal juga mengusulkan perubahan sistem pemerintahan tidak langsung ke sistem pemerintahan langsung serta mengusulkan untuk mengganti sistem tanam paksa dengan sistem pajak. Gagasan itu tentu saja ditentang oleh kelompok lain khususnya kaum konservatif yang hendak mempertahankan sistem dagang dari politik VOC. Dua gagasan tersebut (sistem pajak dan sistem dagang) mempengaruhi poltik kolonial Belanda selama periode tahun 1800 sampai sekitar tahun 1870. Dihadapkan kepada kenyataan tersebut, pemerintah kolonial lebih cenderung memilih kebijaksanaan politik kaum konservatif yang dianggap realistis dan mudah dilaksanakan. Namun dalam perkembangan penerapannya, idealisme liberal banyak dilaksanakan pendukungnya di tengah-tengah menjalankan garis politik konservatif. Daendels (1808—1816) dan Raffles (1811—1816) adalah dua contoh penguasa yang menganut idealisme liberal. Mereka memperjuangkan kebebasan perseorangan baik dalam hak milik tanah, bercocok tanam, berdagang, menggunakan hasil tanaman, maupun dalam kepastian hukum dan keadilan. Banyak upaya yang dilakukan Daendels dengan berbagai cara untuk mewujudkan idealismenya, namun tidak semua gagasan tersebut dilaksanakanya karena kenyataan yang mendesak untuk mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Pada masa Raffles, upaya pembaharuan yang paling menonjol adalah pengenalan sistem pemungutan pajak tanah (land rent). 4.2. Sistem Pajak Tanah: 1812—1816 Pengenalan sistem pajak tanah oleh Raffles adalah bagian integral dari gagasannya tentang sistem sewa tanah (landelijk stelsel) di tanah jajahan yang berupaya memperbaiki sistem paksa VOC yang dianggapnya memberatkan dan merugikan penduduk. Ia menganggap bahwa gagasannya akan menguntungkan kedua belah pihak, baik negara maupun penduduk). Dalam pengaturan pajak tanah, Raffles dihadapkan dengan dua pilihan, antara penetapan pajak secara perseorangan atau satu desa. Akhirnya Raffles lebih memilih penetapan pajak secara perseorangan karena khawatir adanya ketergantungan peduduk kepada penguasa pribumi serta menghindari penindasan yang sangat mungkin terjadi dialami rakyat. Penetapan pajak tersebut berpangkal pada peraturan tentang pemungutan semua hasil penanaman baik di lahan sawah maupun di lahan tegal, dan didasarkan pada kesuburan tanah yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu terbaik (I), sedang (II), dan kurang (III), dengan rincian sebagai berikut: A. Pajak Tanah Sawah: Golongan I 1/2 hasil panenan Golongan II 2/5 hasil panenan Golongan III 1/3 hasil panenan B. Pajak Tanah Tegal: Golongan I 2/5 hasil panenan Golongan II 1/3 hasil panenan Golongan III 1/4 hasil panenan Pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk padi atau beras. Penarikannya dilakukan oleh petugas pemungut pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak tanah ini mengalami berbagai hambatan yang timbul di lapangan. Berbagai penyelewengan, ukuran tanah, dan berbagai masalah lainnya mengakibatkan gagalnya pelaksanaan sistem tersebut. Setelah Belanda menerima kembali tanah jajahannya dari Inggris, mereka dihadapkan keraguan dalam memilih sistem yang akan diterapkan karena melihat realitas di lapangan serta dihadapkan dengan tuntutan negeri induk yang mendesak. Para penguasa kolonial sesudah tahun 1816, seperti para Komisaris Jenderal (1816—1819), Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819—1826), dan Du Bus de Gisignies pada awalnya berniat untuk melanjutkan gagasan liberal, akan tetapi realitas keuangan negeri induk yang mengalami kemerosotan membuat mereka terpaksa menerapkan politik eksploitasi tanah jajahan. Akan tetapi, mereka mencari cara untuk menerapkan kebebasan sehingga kebijakan politiknya bersifat dualistis. Sementara itu, sistem pemungutan pajak tetap berjalan seperti masa Raffles tetapi mengalami beberapa perubahan seperti penetapan pajak kepada desa. Berbeda dengan masa Raffles, pemerintah kolonial Belanda sesudah tahun 1816 menjalankan fungsionalisasi dengan mempertahankan kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal (tradisional) di samping sebagai pegawai pemerintah kolonial yang bertanggung jawab terhadap pungutan pajak. 4.3 Sistem Sewa Tanah (Landelijk Stelsel): 1816—1830 Sistem sewa tanah (landelijk stelsel) yang menjadi dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Raffles membawa pengaruh arah kebijaksanaan politik pemerintah kolonial Belanda selama periode 1816—1830. Gagasan Raffles pada dasarnya ingin melepaskan segala unsur paksaan dan sifat feodalisme dalam pemerintahan yang pernah dijalankan oleh VOC. Semangat Revolusi Perancis dan keberhasilannya dalam memerintah India membuat ia begitu yakin dengan penerapan gagasannya. Padahal, banyak perbedaan struktur dan kondisi sosial yang membedakan semuanya dengan masyarakat Jawa yang dipimpinnya. Persamaan gagasan Raffles dengan tokoh liberal Belanda Dirk van Hogendorp adalah mengenai defungsionalisasi penguasa pribumi untuk menghapuskan sistem feodal yang berlaku karena dianggapnya mematikan kreativitas dan swadaya rakyat. Dalam hal perdagangan, Raffles maupun Dirk menginginkan keleluasaan petani dalam menamam tanaman perdagangan yang dapat diekspor, sedangkan pemerintah bertugas untuk menyediakan perangkat dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk menyusun kebijaksanaan politik perekonomian baru itu, Raffles merumuskan tiga asas perubahan. Pertama, menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan rodi, dan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk menentukan jenis tnaman yang hendak ditanam dan diperdagangkan tanpa adanya unsur paksaan. Kedua, pengawasan tanah secara terpusat dan langsung serta penarikan pendapatan dan pungutan sewa oleh pemerintah tanpa perantaraan para bupati. Bupati tetap sebagai pegawai dengan bedasar asas pemerintahan Barat. Ketiga, didasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemilik tanah, maka para petani dianggap sebagai penyewa tanah (tenant) milik pemerintah. Oleh karena itu, mereka diwajibkan membayar sewa tanah (land rent). Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah tidak dapat diberlakukan di seluruh Jawa karena terbentur dengan banyaknya tanah partikelir (tanah milik swasta). Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal Elout, Busykes, dan Van der Capellen (1816—1819), sistem sewa tanah mengalami berbagai kesulitan dari para petaninya yang walaupun telah diberikan kebebasan tetapi tidak memiliki semangat tinggi dalam melakukan garapannya sehingga hasilnya tidak memuaskan (seperti yang terjadi di Cirebon dan sebelah timurnya). Dalam upaya meningkatkan ekspor dan kemakmuran rakyat, pemerintah Komisaris Jenderal membuka kontrak-kontrak antara pengusaha Eropa dengan kepala desa. Akan tetapi hal itu juga mengalami kendala karena berbagai faktor seperti lemahnya lalu lintas komersial di desa, tidak adanya pengalaman dagang, belum meresapnya ekonomi uang, serta berbagai kecurangan yang terjadi. Melihat kenyataan bahwa banyak faktor yang tidak mendorong rakyat untuk melakukan pertanian ekspor, maka Van der Capellen pada masa pemerintahannya melakukan politik perlindungan dengan melakukan berbagai pembatasan kegiatan perdagangan, kepemilikan tanah, dan lain-lain terhadap orang asing (Cina, Eropa, dsb). Berbeda dengan Van der Capellen yang memberikan pembatasan bagi orang asing, Du Bus de Gisignies (1826—1830) justru menarik dan mendorong pengusaha-pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan perekonomian di tanah jajahan. Menurut Du Bus, untuk meningkatkan produksi ekspor, perlu dilakuakan dua tindakan. Pertama, milik tanah bersama (communal bezit) perlu diganti dengan milik tanah perseorangan (individueel grondbezit). Pada intinya, di satu sisi Du Bus ingin mendorong kinerja petani agar bekerja lebih keras sedangkan di sisi lain Du Bus hendak menjalankan sistem sewa tanah dengan jalan memperkuat pengaruh Barat dalam kegiatan ekonomi di pedesaan. Namun upaya Du Bus hanyalah mimpi yang mustahil diwujudkan karena saat itu terjadi Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama lima tahun (1825—1830). Dari seluruh gambaran upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintahan yang mencoba menerapkan sistem sewa tanah tadi, dapat disimpulkan bahwa selama hampir 20 tahun (1810— 1830), sistem sewa tanah mengalami kegagalan mewujudkan tujuannya untuk memakmurkan rakyat dan meningkatkan produksi ekspor. Pada awalnya, gagasan yang dilontarkan Raffles ini memang memilki berbagai kelemahan dikarenakan persepsi Raffles yang menganggap sistem yang berhasil diterapkan di India ini juga akan berhasil diterapkan di Jawa. Akan tetapi, Raffles tidak memikirkan bahwa struktur sosial serta kondisi sosial yang jauh berbeda antara sebagian daerah India yang sudah dapat melepaskan diri dari ikatan feodalisme serta sudah cukup lama mengenal sistem ekonomi dibandingkan dengan keadaan Jawa yang masih kental dengan ikatan feodal dan kondisi masyarakatnya yang sebagian besar masih belum memahami sistem ekonomi. Pada masa selanjutnya, setelah tahun 1830, ketika Gubernur Jenderal Van den Bosh memegang pemerintahan, sistem sewa tanah dihapuskan. Sebagai gantinya, ia menghidupkan kembali sistem penanaman dengan unsur paksaan bahkan dengan cara yang lebih keras dibandingkan masa sebelumnya.