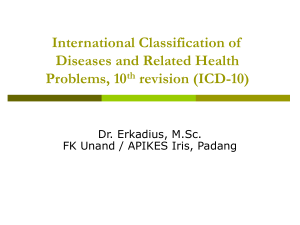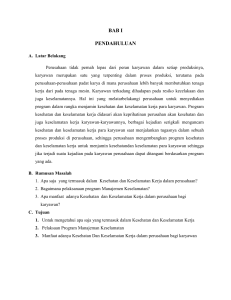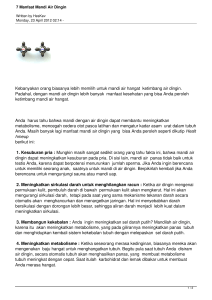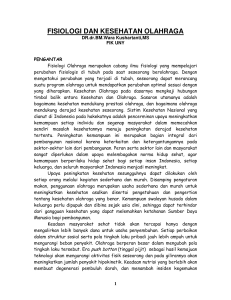PTH - inasnacc inasnacc
advertisement

Daftar Isi Laporan Penelitian Korelasi antara Tipe Hematoma Intrakranial dengan Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) Radian Ahmad Halimi, Iwan Fuadi, Tatang Bisri .................................................................... 1–7 Laporan Kasus Tatalaksana Anestesi pada Pendarahan Intraserebral Spontan Non Trauma Muhammad Dwi Satriyanto, Siti Chasnak Saleh ...................................................................... 8–16 Penatalaksanaan Perioperatif Hipofisektomi Transsphenoidal: Pendekatan Endoskopik Endonasal Sandhi Christanto, Bambang Suryono, Tatang Bisri, Siti Chasnak Saleh ................................... 17–27 Pengananan Anestesi pada Operasi Olfactory Groove Meningioma Silmi Adriman, Dewi Yulianti Bisri, Sri Rahardjo, A. Himendra Wargahadibrta ....................... 28–33 Penatalaksanaan Perioperatif Cedera Kepala Traumatik Berat dengan Tanda Cushing Wahyu Sunaryo Basuki, Bambang Suryono, Siti Chasnak Saleh ................................................... 34–42 Tatalaksana Anestesi pada Microvascular Decompression (MVD) Bau Indah Aulyan Syah, Siti Chasnak Saleh, Sri Rahardjo ....................................................... 43–9 Kerusakan Barier Pertahanan Alamiah: Sawar Darah Otak Ardana Tri Arianto, MH Soedjito ............................................................................................. 50–60 Tinjauan Pustaka Terapi Hipotermia pada Stroke Hemoragik Bau Indah Aulyan Syah, Iwan Fuadi, Sri Rahardjo.................................................................... 61–8 Interaksi Otak-Paru pada Neurocritical Care Dewi Yulianti Bisri, Tatang Bisri .............................................................................................. 69–77 Korelasi antara Tipe Hematoma Intrakranial dengan Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) Radian Ahmad Halimi, Iwan Fuadi, Tatang Bisri Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung–Indonesia Abstrak Latar Belakang dan Tujuan: Keluhan sakit kepala setelah cedera otak traumatik (COT) disebut sebagai Post Traumatic Headache (PTH), yang dapat terjadi setelah cedera otak ringan, sedang atau berat. Tujuan penelitian ini untuk menemukan korelasi antara tipe hematoma intrakranial dengan kejadian dan beratnya PTH. Subjek dan Metode: Penelitian observasional cohort prospektif pada 31 pasien, umur13–59 tahun, laki-laki dan perempuan, yang mengalami COT ringan atau sedang. Pengambilan sampel secara consequetive sampling. Parameter yang dicatat adalah umur, jenis kelamin, berta badan, Glasgow Coma Scale (GCS), tipe hematoma intrakranial, kejadian PTH dan beratnya PTH dengan menggunakan skor numeric rating scale (NRS). Analisis korelasi linier dengan dua variable dengan analisis korelasi Spearman. Korelasi dianggap signifikan bila koefisien korelasi (R) > 0,4 dan p<0,05. Hasil: Seratus persen pasien subdural hematoma (SDH) dan Intracerebral Hematoma (ICH) mengalami post traumatic headache dan hanya 70,6% pada pasien EDH. Pasien dengan depressed fractur tanpa perdarahan intrakranial mengalami PTH sebanyak 33,3%. Simpulan: Perdarahan yang terjadi dibawah duramater menunjukkan kejadian PTH yang paling tinggi. Kata kunci: Cedera otak traumatik, hematoma intrakranial, numeric rating scale, post traumatic headache JNI 2015; 4 (1): 01–7 The Correlation between Type of Intracranial Hematoma with The Incidence and Severity of Post Traumatic Headache (PTH) Abstract Background and Objective: Headache occurs after Traumatic Brain Injury (TBI) is known as Post Traumatic Headache (PTH), which could manifest after a mild, moderate, or severe head injury. The aim of this study is to evaluate the correlation between type of intracranial hematoma with the incidence and severity of PTH. Subject and Method: This prospective observational cohort study was performed in 31 patients aged from 13–59 years old with mild or moderate TBI usig a consequetive sampling retrieval. Parameters recorded in this study were age, gender, weight, GCS, type of hematoma intracranial, the incidence of PTH, and severity of pain of PTH using the numeric rating score (NRS) score. Linear correlation analysis of two variables was calculated using Spearman correlation analysis. The correlation is significant if the correlation coefficient (R) > 0.4 and p < 0.05. Result: One hundred percent of subdural hematoma (SDH) and intracerebral hematoma (ICH) patients were experienced PTH and only 70,6% in epidural hematoma (EDH) patients. PTH also found in 33.3% of patient with depressed fracture without intracranial bleeding. Conclusion: Hematoma under duramater causes the highest incidence of PTH. Key words: intracranial hematoma, numeric rating scale, traumatic brain injury, post traumatic headache JNI 2015; 4 (1): 01–7 1 2 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Cedera otak traumatik (COT) merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan pada masyarakat Barat.1 Kejadian COT memiliki insidensi yang tinggi terutama pada usia muda.2 The Center for Disease Control (CDC) melaporkan bahwa pada pasien dengan COT terhitung sekitar 1,4 juta pasien perlu dirujuk ke ruang gawat darurat, 275.000 ribu pasien perlu dilakukan rawat inap di rumah sakit, dan 52.000 pasien meninggal setiap tahunnya.3 Angka kejadian keseluruhan COT di Amerika Serikat terhitung 538,2 per 100.000 populasi atau sekitar 1,5 juta kasus baru di tahun 2003. Telah dilaporkan angka kejadian yang lebih rendah di negara Eropa (235 per 100.000) dan Australia (322 per 100.000).4 Pada daerah industri seperti Amerika, sebanyak 45% mekanisme penyebab COT adalah akibat kecelakaan kendaraan bermotor, 30% karena mekanisme jatuh, 10% akibat kecelakaan kerja, 10% kecelakaan rekreasi, dan 3% karena kecelakaan akibat kekerasan.5 Berdasarkan tingkat keparahannya COT dibagi menjadi derajat ringan, sedang, dan berat. Tingkat keparahan COT ini tentu mempengaruhi beratnya gangguan neurologis dan fungsionalnya. Di Amerika Serikat angka kejadian kecacatan jangka panjang akibat COT berkisar antara 3,2–5,2 juta penduduk atau 1–2% dari total populasi, dengan insidensi terjadinya cedera kepala berat adalah 10%, 10% mengalami cedera kepala sedang, dan 80% mengalami cedera kepala derajat ringan.6 Saat ini penatalaksanaan COT dilakukan berdasarkan konsep COT primer atau sekunder. Terapi pembedahan karena adanya lesi pada otak merupakan terapi inisial pada COT primer. Identifikasi, pencegahan, dan penatalaksanaan terhadap COT sekunder merupakan fokus prinsip pada manajemen neurointensif.4 Pada pasien COT primer dengan lesi intrakranial, dapat dilakukan terapi konservatif atau terapi pembedahan, tergantung pada jumlah volume perdarahannya. Adanya hematoma dan edema pada COT dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Selain itu adanya mekanisme kaskade cedera molekuler saat awal terjadinya trauma yang kemudian berkembang hingga beberapa hari, dan diikuti oleh edema otak, peningkatan tekanan intrakranial dapat menyebabkan terjadinya kematian pada sel dan mengeksaserbasi cedera kepala.4 Suatu studi prospektif menunjukkan bahwa pada satu tahun setelah terjadinya COT, 72,6% pasien mengeluh nyeri kepala dimana 47,2% pasien mengeluh nyeri ringan, dan 25,4% pasien mengeluh nyeri derajat sedang hingga berat.7 Keluhan nyeri kepala yang timbul setelah terjadinya COT dikenal sebagai Post Traumatic Headache (PTH) yang dapat terjadi setelah cedera kepala ringan, sedang, atau berat. Gejala PTH biasanya hilang dalam 3 bulan, namun pada beberapa kejadian telah dilaporkan gejala tersebut ada yang menetap.8 Secara keseluruhan angka kejadian PTH terjadi sekitar 4% dari seluruh nyeri kepala simptomatis. Suatu penelitian menyatakan bahwa 31,3–90% pasien mengalami nyeri kepala hingga 1 bulan, 47–78% hingga 3 bulan, 8,4–35% hingga 1 tahun, dan 25% pasien hingga 4 tahun.5 Didapatkan beberapa jenis nyeri kepala yang terjadi setelah COT antara lain; nyeri kepala tipe migraine, nyeri kepala tipe tension, nyeri kepala tipe cervicogenic dan nyeri kepala tipe rebound. Pada kebanyakan pasien, PTH dapat sembuh spontan dalam beberapa bulan, akan tetapi, ada sebagian kasus PTH yang menetap.9 Suatu penelitian melaporkan bahwa 87,3% pasien dengan PTH mengeluh nyeri kepala tipe tension 10% yang terjadi setiap harinya dengan intensitas nyeri derajat sedang (verbal rating scale adalah 6).1 Kriteria diagnostik PTH tidak memerlukan fenotip nyeri kepala secara spesifik. Kualitas nyeri kepala dalam bentuk apapun dapat diterima untuk dilakukannya diagnosis, karena tidak terdapat karakteristik PTH dengan bentuk yang khusus.1 Post Traumatic Headache merupakan suatu permasalahan medis dan sosioekonomi serius, yang memerlukan penanganan tepat dan adekuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya nyeri kepala kronis.1 Suatu penelitian menunjukkan bahwa ketika PTH dapat terdiagnosa dengan cepat dan penatalaksanaan PTH dilakukan secara adekuat, maka pada kebanyakan pasien dengan gejala PTH dapat disembuhkan. Apabila PTH tidak dapat disembuhkan maka akan dimodulasi dan menetap hingga waktu yang lama.10 Antara kejadian trauma dan dimulainya nyeri kepala akan Korelasi antara Tipe Hematoma Intrakranial dengan Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) berkorelasi dengan waktu dilakukannya terapi.11 Berdasarkan data-data diatas maka rentang waktu dari mulai terjadinya hematoma, edema, iskemia hingga dimulainya terapi, akan sangat berperan dalam menentukan hasil luaran pasien, yang biasanya dinilai dengan Glasgow Outcome Scale (GOS) atau GOSE (extended GOS), dengan salah satu parameter dari GOSE adalah gangguan fungsi kognitif dan PTH.9 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara tipe hematoma intrakranial dengan kejadian dan beratnya PTH. II. Subjek dan Metode Penelitian observasional kohort prospektif dilakukan pada 31 pasien yang menjalani operasi kraniotomi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dengan kriteria inklusi pasien pria atau wanita dengan cedera kepala derajat ringan atau sedang, umur antara 13 hingga 59 tahun, pada pemeriksaan CT-scan kepala didapatkan hematoma intrakranial, hematoma ekstra aksial, atau fraktura terdepresi, dan mendapatkan kembali kesadarannya setelah terapi pembedahan kraniotomi. Kriteria eksklusi adalah pasien yang memiliki cedera servikal, riwayat nyeri kepala berulang sebelum terjadinya trauma, dan yang sedang dalam pengaruh alkohol atau intoksikasi obat-obatan. Kriteria pengeluaran adalah pasien yang tidak mendapatkan kembali kesadarannya setelah lebih dari 2 minggu pascakraniotomi, meninggal selama masa penelitian, dan dengan gangguan fungsi kognitif yang dinilai dengan menggunakan skoring Mini Mental State Examination (MMSE). Parameter yang dicatat pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, berat badan, GCS, tipe hematoma intrakranial, rentang waktu dari mulai terjadinya COT hingga dilakukannya terapi pembedahan kraniotomi, angka kejadian PTH yang dinilai setelah pasien sadar penuh dan dinilai hingga 1 minggu, derajat beratnya PTH dinilai dengan menggunakan skor numeric rating scale (NRS). Dilakukan analisis korelasi linear dua variabel yang dihitung berdasarkan analisis korelasi Spearman. Hubungan korelasi bermakna bila koefisien korelasi (R) >0,4 dan nilai p <0,05. 3 III. Hasil Penelitian Data hasil penelitian terlihat pada tabel-tabel dibawah ini. Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian Variabel n(%) Umur Pasien (tahun) Berat Badan (Kg) Jenis Kelamin Laki-laki 22 (71,0%) Perempuan 9 (29,0%) Rentang Waktu (jam) NRS Score GCS Pasien PTH PTH (+) PTH (-) Rerata (SD) 26,96 (12,06) 60,77 (7,92) Median 25 60 13,09 (5,78) 11,32 (1,97) 12,00 5,00 11,00 22 (71%) 9 (29,0%) Keterangan: NRS: Numeric Rating Scale; GCS: Glasgow Coma Scale; PTH: Post Traumatic Headache Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata usia pasien dalam penelitian ini adalah 26,96 tahun dengan usia termuda 14 tahun dan usia tertua 52 tahun. Rata-rata berat badan pada pasien ini adalah 60,77 kg dengan berat badan terendah adalah 48 kg dan berat badan tertinggi adalah 80 kg. Sebagian besar jenis kelamin pada penelitian ini adalah laki-laki, rentang GCS pada penelitian ini adalah 9 pada rentang bawah dan 15 pada rentang atas. Selain itu rentang waktu kejadian pada penelitian ini adalah 6 jam hingga 12 hari, dengan rentang penilaian NRS berkisar antara 0 hingga 8, dan sebagian besar pasien mengalami PTH. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pasien dengan EDH sebanyak 17 (54,8%) pasien merupakan jumlah terbanyak dengan angka kejadian PTH sebanyak 12 (70,58%) pasien. Jumlah pasien dengan SDH sebanyak 5 (16,1%) pasien memiliki angka kejadian PTH sebanyak 5 (100%). Jumlah pasien dengan ICH sebanyak 2 (6,5%) memiliki angka kejadian PTH sebanyak 2 (100%) pasien, pasien dengan fraktura terdepresi sebanyak 3 4 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Tabel 2. Kejadian PTH Berdasarkan Jenis Diagnosa Preoperatif Diagnosa Preoperatif EDH SDH ICH Diagnosa Fraktura Terdepresi Fraktura Terdepresi + ICH EDH + SDH EDH +ICH Total Count % within total Total Count % within total Count 17 54,8% 5 PTH (+) 12 70,6% 5 % within total Count % within total Count % within total Count % within total Count % within total Count % within total 31 100,0% 16,1% 2 6,5% 3 9,7% 2 6,5% 1 3,2% 1 3,2% 23 74% 100% 2 100% 1 33,3% 1 50% 1 100% 1 100% 8 26% PTH (-) p-value 5 29,4% 0 0% 0 0% 2 66,7% 1 50% 0 0% 0 0% 0,994 Keterangan:Nilai p pada variabel kategorik dengan uji Chi-Square. Dengan alternatif uji Kolmogorov Smirnov atau uji Fisher Exact apabila syarat dari Chi-Square tidak terpenuhi.Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. Tanda * menunjukkan p value <0,05 artinya signifikan atau bermakna secara statistik. EDH: Epidural Hematoma; SDH: Subdural Hematoma; ICH: Intrakranial Hematoma Tabel 3. Derajat berat PTH berdasarkan nilai skor NRS Variabel Skor NRS Nilai p Diagnosa Preoperatif 0,25 EDH 5,27 (1,34) Mean (SD) 6,00 Median 4,00 Range SDH 5, 80 (1,64) Mean (SD) 5, 00 Median 4, 00 Range ICH Mean (SD) Median Range 7,00 (1,41) 7,00 2,00 Keterangan: Untuk data numerik Nilai p dihitung berdasarkan uji ANOVA apabila data berdistribusi normal serta alternatif uji Krusskall Wallis apabila data tidak berdistribusi normal. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. EDH: Epidural Hematoma; SDH: Subdural Hematoma; ICH: Intrakranial Hematoma; NRS: Numeric Rating Scale (9,7%) dengan angka kejadian PTH sebanyak 1 (33,33%) orang. Jumlah pasien dengan diagnosa campuran antara fraktura terdepresi dengan ICH sebanyak 2 (6,5%) orang dengan angka kejadian PTH sebanyak 1 (50%) pasien, sedangkan jumlah pasien dengan diagnosa EDH kombinasi dengan SDH sebanyak 1 (3,2%) pasien dengan kejadian PTH sebesar 1 (100%) pasien, dan diagnosa EDH kombinasi dengan ICH sebanyak 1 (3,2%) pasien dengan kejadian PTH sebesar 1(100%) pasien. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p sebesar 0,99 (nilai p >0,05), maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara diagnosa preoperatif dengan kejadian PTH. Kejadian PTH pada SDH dan ICH 100% sedangkan pada EDH 70,6%, fraktura terdepresi 33,3%. IV. Pembahasan Nyeri kepala adalah gambaran yang menonjol untuk pasen dengan cedera kepala ringan dan sindroma pascaconcusio, terutama pada cedera Korelasi antara Tipe Hematoma Intrakranial dengan Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) 5 akibat kecelakaan lalulintas. Keluhan yang paling menetap setelah cedera adalah sakit kepala dan sakit leher. Kondisi yang sangat sakit ini dapat terjadi dalam kombinasi dengan keluhan kognitif seperti berkurangnya perhatian, gangguan memori, kecepatan berpikir lambat, melengkapi gambaran sindroma pascaconcusio yang menetap. Nyeri dapat mengganggu tidur dan menimbulkan depresi, mempengaruhi efisiensi kognitif dan gangguan kognitif yang tidak dapat didiagnosa meningkatkan depresi dan kecemasan, yang mana dapat meningkatkan kondisi nyeri.12 dan lebih lama dari 30 hari pada 24,3% kasus.13 PTH adalah nama umum untuk nyeri yang terlokalisir pada kepala dan leher, terjadi setelah trauma kepala dengan penyebab dan patogenesis yang bervariasi. Sakit kepala umumnya disebabkan karena cedera scalp, struktur intrakranial dan leher. Sulit untuk memisahkan apakah PTH betul-betul disebabkan karena faktor organik atau psikogenik. Kemungkinan kedua faktor tersebut terlibat tapi dengan perbedaan derajat beratnya penyakit.13 Penyebab PTH dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.14 Post-traumatic headache (PTH) adalah satu dari beberapa gejala sindroma pascatrauma. Karena itu, mungkin dihubungkan dengan gangguan somatik, psikologik atau kognitif. Penyebab simptom (keluhan) ini pada seseorang dengan cedera otak traumatik ringan atau cedera whiplash (hentakan) masih kontroversi dalam hal penjelasan dari mulai kerusakan neuron sampai pura-pura sakit. PTH dapat dibagi atas tensiontype, migrain, atau cervicogenic headache. Patogenesis PTH masih belum diketahui dengan betul, tapi mungkin dari jalur sakit kepala. Masalahnya, timbul dari meningkatnya PTH setelah cedera ringan, sehingga sulit untuk menentukan hubungan kausa-efek. Terbukti ada hubungan terbalik antara beratnya cedera otak dengan kejadian PTH, terutama tipe kronis. Faktor psikologis dipercaya memegang peranan dalam penyebab, dan terapi PTH kronis.13 Evaluasi seseorang dengan PTH masih sulit. Walaupun kebanyakan kasus PTH sembuh dalam 6–12 bulan, banyak pasien dengan sakit kepala berlarut-larut dan menetap. Disebabkan karena umumnya PTH tidak ditemukan hal yang objektif, sehingga sering kontroversial apakah keluhan (simptom) itu nyata, psikogenik, atau mengarang-ngarang. Walaupun ketentuan kriteria International Headache Society (IHS) bahwa PTH mempunyai onset dalam 1 minggu setelah trauma, tapi telah diketahui ada yang dimulai dalam waktu yang lebih lambat.13 Dari review beberapa penulis, kronik PTH terlihat hanya dalam kasus yang sangat jarang dan selalu dihubungkan dengan lesi intrakranial organik. Kalau betul akibat organis, disini pentingnya dan merupakan salah satu alasan dilakukan proteksi otak perioperatif bukan saja pada pasien dengan cedera kepala berat, tetapi juga pada pasien dengan cedera kepala ringan.9 Relatif sedikit informasi tentang karakteristik sakit kepala pada sindroma pascatrauma (posttraumatic syndrome). Secara definisi, sakit kepala yang berkembang dalam waktu 1 minggu setelah cedera kepala (atau dalam waktu 1 minggu setelah pemulihan kesadaran) disebut sebagai PTH. Pada edisi pertama klasifikasi International Headache Society (HIS), waktu interval antara trauma dan permulaan sakit kepala adalah 14 hari, berkurang 1 minggu dalam edisi terakhir. Dari penelitian ini, seperempat pasien mengalami simptom hanya setelah 30 hari dari cedera kepala.13 Migrain tanpa aura (39%) dan headache sakit kepala tipe tension kronis (34,1%). Interval waktu antara saat terjadinya cedera otak dengan onset sakit kepala kurang dari 7 hari ada 48,7% kasus Walaupun serabut yang sensitif berada dalam titik lesi dan regenerasi anomali umum pada sakit kepala lokal, ini mungkin sebagian dari penjelasan untuk sakit kepala yang dimulainya terlambat dari tipe sakit kepala yang lain seperti migrain dan sakit kepala tipe tension.9 Beberapa penulis percaya bahwa PTH adalah manifestasi disfungsi otak diperburuk oleh cedera otot skelet. Sakit kepala akut bisa diprovokasi oleh lesi pada jaringan scalp. Stimulus pada jaringan otot skelet dapat memprovokasi perubahan neuroplastik pada neuron dari nukleus trigeminal caudal, yang memicu fenomena wind up dan sensibilisasi. Dengan stimulus kontinyu ada peningkatan sensitivitas neuron cornu dorsalis, 6 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Tabel 4. Penyebab Sekunder dari PTH akut Kondisi Epidural hematoma Subdural hematoma Intracerebral hematoma Kontusio serebral Pemeriksaan CT-scan CT-scan CT-scan CT-scan Trombosis sinus venosus serebral Magnetic Resonance venography, angiography Diseksi vaskuler MRI, angiography Fraktur servical spine CT-scan Diagnosis Lucid interval diikuti ngantuk, coma Geriatri Focal neurological defisit Perburukan secara bertahap, gejala neurologik focal. Sakit kepala hebat, papil edema, negatif CT Defisit neurologic fokal Spasme leher, mielopathi Dikutip dari: Levin M, Ward TN. 14 Tabel 5. Penyebab Traumatik dari Sakit Kepala yang Menetap Trombosis vena serebral Disautonomic cephalalgia Hidrosefalus Hipotensi intrakranial (kebocoran CSF) Hipertensi intrakranial (pseudotumor cerebri) Neuralgia (oksipital, supraorbita) Neuroma Kejang pascatrauma Subdural hematoma Cedera temporomandibula Whiplash atau cedera cervical spine Dikutip dari: Levin M, Ward TN.14 memprovokasi peningkatan aktivitas spontan, mengurangi ambang nyeri dan merubah proses stimulus aferent yang mana dapat menerangkan sumber dan rumatan PTH.13 Setelah suatu cedera kepala berat, pasien mungkin mengalami sakit kepala akibat dari oprasi pada tulang kepalanya atau atau masih ada kumpulan kecil darah atau cairan diruang intrakranial. Sakit kepala juga bisa setelah cedera kepala ringan, sedang atau cedera kepala berat, setelah penyembuhan tahap pertama telah berlangsung. Sakit kepala ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain perubahan dalam otak akibat cedera, cedera leher dan tulang kepala yang belum pulih seluruhnya, tegangan dan stres, atau efek samping pengobatan.8,15-17 Klasifikasi beratnya cedera kepala difokuskan pada 3 parameter yaitu: 1) lama dan dalamnya kehilangan kesadaran (loss of consciousness/LOC), 2) lamanya gangguan memori yang dihubungkan dengan kejadian (amnesia retrograde dan anterograde, PTA posttraumatic amnesia), dan 3) Skor Glasgow Coma Scale (GCS). Cedera kepala ringan didefinisikan apabila: LOC < 30 menit, PTA < 24 jam, GCS >13.18 V. Simpulan Intrakranial hematoma tipe SDH dan ICH mempunyai kejadian PTH 100% sedangkan pada EDH 70,6% dan fraktura terdepresi 33,3% maka walaupun secara statistik tidak signifikan tapi secara klinis semakin cedera tersebut mengenai jaringan otak maka makin sering kejadian PTH. Daftar Pustaka 1. Obermann M, Keidel M, Diener HC. Post traumatic headache: is it for real? Crossfire debates on headache: pro. Headache Currents 2010; 710–15. 2. Bullock MR, Chestnut R, Ghajaar J, Gordon D, Harti R, Newell DW, et al. Introduction. Neurosurgery 2006; 58 (suppl3):S1–3. 3. Bullock MR, Chestnut R, Ghajaar J, Gordon D, Harti R, Newell DW, et al. Surgical management of acute epidural hematomas. Korelasi antara Tipe Hematoma Intrakranial dengan Kejadian dan Beratnya Post Traumatic Headache (PTH) Neuro Surgery 2006; 58 (Suppl3): S2:7–15. 4. Finkel AG. Concussion and post traumatic headache. Information For Health Care Professionals. (www. AmericanHeadacheSociety.org). 5. SeifertTD, Evans RW. Post traumatic headache: a review. Curr Pain Headache Rep 2010. 6. Heegaard W, Biros M. Traumatic brain injury. Emerg Med Clin N Am 2007; 25:655–78. 7. Sherman KB, Bell KR. Traumatic brain injury and pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 17 2006:473–90. 8. Lew HL, Lin PH, Fuh JL, Wang SJ, Clark DJ, Walker WC. Characteristic and treatment of headache after traumatic brain injury. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006: 619–27. 9. DeGuise E, LeBlanc J, Feyz M, Meyer K, Duplantie J, Thomas H, et al. Long term outcome after severe traumatic brain injury: the McGill interdisciplinary prospective study. J Head Trauma Rehabil 2008;(5): 294–303. 10. Zasler N. Post traumatic headache: Clinical caveats. Rev Cubana Neurol Neuroar 2014; 4(2):105–8. 11. Martins HAL, Ribas VR, Martins BBM, Ribas RMG, Valenca MM. Post traumatic headache. Arq Neuropsiquiatr 2009; 67(1):43–45. 7 12. Sherman KB, Goldberg M, Bell KR. Traumatic brain injury and pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2006;17: 473–90 13. De Lima Martin HA, Ribas VR, Martins BBM, Ribas RMG, Valenca MM. Posttraumatic headache. Arq Neuropsiquiatr 2009;67(1):43–45. 14. Levin M, Ward TN. Headache. Dalam: Silver JM, McAllister TW, Yudofsky SC, eds. Textbook of traumatic brain injury, 2nd ed. Washington: American Psychiatric Pub Inc;2011,343–50 15. Hoge CW, McGurk D, Thomas JL, Cox AL, Engel CC, Castro C A. Mild traumatic brain injury in U.S. Soldiers returning from Iraq. N Engl J Med 2008; 358(5): 453–63. 16. Marcus DA. Disability and chronic posttraumatic headache. Headache 2003; 43(2): 117–21. 17. Mihalik JP, Stump JE. Collins MW, Lovell MR, Field M, Maroon JC. Posttraumatic migraine characteristics in athletes following sports-related cocussion. J Neurosurg 2005;102(5):850–55. 18. McAllister TW. Mild brain injury. Dalam: Silver JM, McAllister TW, Yudofsky SC, eds. Textbook of traumatic brain injury, 2nd ed. Washington: American Psychiatric Pub Inc;2011,239–57. Tatalaksana Anestesi pada Pendarahan Intraserebral Spontan Non Trauma Muhammad Dwi Satriyanto**), Siti Chasnak Saleh**) Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Eka Hospital Pekanbaru Riau **) Departemen Anestesiologi dan Reanimasi, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo–Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya *) Abstrak Pendarahan Intraserebral (PIS) adalah ekstravasasi darah yang masuk kedalam parenkim otak, yang dapat berkembang ke ruang ventrikel dan subarahnoid, yang terjadi secara spontan dan bukan disebabkan oleh trauma (non traumatis) dan salah satu penyebab tersering pada pasien yang dirawat di unit perawatan kritis saraf. Kejadian PIS berkisar 10–15% dari semua stroke dengan angka kematian tertinggi tingkat dari subtipe stroke dan diperkirakan 60% tidak bertahan lebih dari satu tahun. Laki-laki 18 tahun, datang dengan keluhan penurunan kesadaran setelah sebelumnya merasakan lemas pada anggota gerak kanan yang terjadi tiba-tiba saat mengendarai kendaraan. Pada pemeriksaan didapatkan kesadaran GCS E3M5V2 dengan hemodinamik cukup stabil, dan terdapat hemiplegi dextra. Pasien dirawat di perawatan intensif selama 4 hari, karena kesadaran menurun menjadi E2M4V2 maka dilakukan MSCT ulangan, dan ditemukan PIS bertambah (kurang lebih 30cc) dibandingkan dengan MSCT sebelumnya dengan midline shift lebih dari 5mm. Diputuskan untuk dilakukan tindakan kraniotomi evakuasi segera dengan pemeriksaan penunjang yang cukup. Tindakan kraniotomi evakuasi pada pasien PIS menjadi tantangan bagi seorang spesialis anestesiologi, sehingga diperlukan pengetahuan akan patofisiologi, mortalitas PIS dan tindakan anestesi yang harus dipersiapkan dan dikerjakan dengan tepat. Kata Kunci: perdarahan intraserebral spontan/non trauma, tatalaksana anestesi JNI 2015;4 (1): 08–16 Anesthesia Management in Spontaneous-Non Traumatic Intracerebral Hemorrhage Abstract Intracerebral hemorrhage (ICH) is the extravasations of blood into the brain parenchyma, which may develop into ventricular and subarachnoid space, that occurs spontaneously and not caused by trauma (non-traumatic), and one of the most common causes in patients treated in the neurological critical care unit. ICH represents approximately 10–15% of all strokes with the highest mortality rates of all stroke subtypes and about 60% of patients with ICH may not survive within the first year. A 18 years old male with loss of consciousness after suffering from sudden right limb weakness while driving a vehicle. On examination, the level of consciousness (GCS) was E3M5V2 with stable hemodynamic and right hemiplegia. Patients was managed in intensive care unit (ICU) for 4 (four) days, and because of the decreasing level of consciousness to E2M4V2, the MSCt test was performed and the result revealed an ICH (approximately 30cc) compared to the previous MSCt with more than 5mm midline shift. Immediate craniotomy evacuation was then performed. Craniotomy evacuation in ICH patients is challenging for an anesthesiologist.Therefor, require a thorough understanding of the pathophysiology as well as mortality of ICH and anesthetic management should be prepared and done properly. Key words: anesthesia management, spontaneous / non traumatic intracerebral hemorrhage JNI 2015;4 (1): 08–16 8 Tatalaksana Anestesi pada Pendarahan Intraserebral Spontan Non Trauma I. Pendahuluan Perdarahan intraserebral (PIS) spontan atau nontraumatik adalah ekstravasasi darah yang masuk kedalam parenkim otak dan dapat berkembang ke ruang ventrikel dan subarahnoid, yang terjadi spontan dan bukan disebabkan oleh trauma (non traumatis). PIS merupakan salah satu penyebab tersering pada pasien yang dirawat di unit perawatan kritis saraf. Dari semua stroke, 10–30% adalah PIS yang mempunyai angka kematian tertinggi dari subtipe stroke. Diperkirakan sekitar 50–60% dari pasien dengan PIS tidak bertahan lebih dari satu tahun dan dikatakan juga hanya 30% masih dapat hidup selama 6 bulan setelah kejadian.1-3 PIS secara umum diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder. PIS Primer, didefinisikan sebagai pendarahan spontan dari arteriol kecil klasik yang rusak karena hipertensi kronis di regio subkortikal otak atau amiloid angiopathy di regio kortikal otak. PIS primer diperkirakan sekitar 80% dari semua kasus, sedangkan PIS sekunder merupakan perdarahan sebagai hasil dari beberapa keadaan patologik vaskular yang mendasarinya atau penyebab lainnya, yaitu arteriovenous malformation (AVM), neoplasma intrakranial, angioma kavernos, angioma vena, trombosis venaserebral, koagulopati (baik primer atau karena obat, seperti pada pasien terapi warfarin kronis), vaskulitis, kokain atau penggunaan alkohol dan berubah menjadi stroke hemoragik dari stroke iskemik.3-8 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kejadian PIS diperkirakan 10–20 kasus per 100.000 penduduk per tahun, yang tampaknya meningkat dengan usia (diatas usia 45 tahun) dan lebih umum pada laki-laki. Orang Afrika Amerika dan orang Jepang di Jepang telah diidentifikasi memiliki insiden lebih tinggi secara signifikan terhadap PIS. Berdasarkan pada teori bahwa prevalensi PIS lebih tinggi pada hipertensi, yang merupakan faktor risiko yang diketahui untuk terjadinya PIS, antara kedua populasi tersebut dan dibandingkan dengan kulit putih maka dapat dijelaskan bahwa kejadian PIS terjadi lebih tinggi. Menariknya, ada beberapa data mengenai populasi di Jepang bahwa kolesterol serum 9 yang rendah dapat menjadi faktor risiko yang relevan sebagai predisposisi terjadinya PIS.1-2 Tanda klasik dari PIS adalah serangan sakit kepala yang mendadak, penurunan kesadaran, adanya defisit fokal neurologis yang makin memburuk. mual muntah, dan peningkatan tekanan darah, dapat juga terjadi kejang. PIS yang luas dapat menimbulkan letargi, stupor dan koma.2,4,7 II. Kasus Laki-laki 18 tahun dengan PIS pada regio temporoparietal sinistra telah dilakukan tindakan kraniotomi evakuasi sito pada tanggal 19 September 2011. Anamnesa Pasien datang dengan keluhan (alloanamnesateman pasien) penurunan kesadaran. Keluhan tambahan: ketika sedang naik motor (dibonceng) tiba-tiba pasien terjatuh sendiri, saat itu pasien memakai helm, pingsan tidak ada, dari mulut telinga hidung tidak ada keluar darah, terdapat luka lecet sekitar wajah, setelah itu pasien mulai tidak sadarkan diri. Muntah dan kejang disangkal. Tidak ada riwayat diabetes mellitus dan hipertensi, penggunaan obat-obatan disangkal. Sebelumnya pasien sering mengeluh sakit kepala dan hilang bila minum obat warung. Pemeriksaan Fisik Pasien tampak sakit berat dengan kesadaran GCS E3M5V2, pada pemeriksaan mata didapatkan pupil kanan dan kiri bulat isokor dengan diameter 3mm, reflek cahaya baik. Hemodinamik dengan tekanan darah 130/65mmHg, nadi 68 x/menit, suara jantung murni, tidak ada murmur, suhu 37 oC, respirasi frekuensi 22 kali/menit spontan dengan oksigen binasal kanul 3L/menit SpO2 100%, pemeriksaan abdomen tidak didapatkan kelainan, pada ekstrimitas terdapat kesan hemiplegi dextra. Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 16,2g%, Lekosit 13,400/mm3, Hematokrit 44,7% Trombosit 303000 μL, Natrium 140 mEq/L, Kalium 4.2 mEq/L, Chlorida 100 mEq/L, Gula darah sewaktu 132 mg/dL. Pemeriksaan analisa gas darah pH 7,42, PaO2 103 mmHg, PaCO2 10 Jurnal Neuroanestesi Indonesia 43 mmHg, TCO2 28,4 mEq/L, HCO3 27 mEq/L, BE 2,1, SpO2 97,9%. Pemeriksaan foto thorak jantung tidak ada kardiomegali dengan Cardio Thoracic Ratio (CTR) kurang dari 50% dan paru ditemukan infiltrat di parakardial kanan. Pada pemeriksaan MSCt kepala awal didapatkan; pada jaringan tulang tidak terdapat garis fraktur. Sulci, sistern dan sistem ventrikel dalam batas normal, tidak melebar. Tampak lesi hiperdens pada lobus frontal kiri disertai area hipodens disekitarnya. Efek masa (+); deviasi struktur garis tengah tidak ada. Diferensiasi substantia alba dan grisea baik. Ventrikel lateral dekstra sinistra, ventrikel III dan IV tidak melebar. Kesan: Intraserebral hematoma pada lobus sinistra. Diputuskan pasien dirawat di unit pelayanan intensif (High Care Unit/ HCU) untuk di observasi ketat. Selama perawatan keasadaran tidak berubah dengan hemodinamik stabil. Pada hari ke 4 perawatan terjadi penurunan kesadaran GCS E2M4V2 dan dilakukan MSCt kepala ulang dan dibandingkan dengan MSCt sebelumnya; tampak intraserebral hematoma pada ganglia basal kiri bertambah luas disertai perifokal edema yang menimbulkan efek massa ke kanan lebih dari 5mm. Pada pemeriksaan didapatkan kesadaran yang menurun, namun kondisi fisik sebelum tindakan operasi masih sama seperti awal masuk, dengan hemodinamik tetap stabil, kemudian diputuskan untuk dilakukan kraniotomi evakuasi sito. Gambar 1. Foto MSCt Kepala Pertama Pengelolaan Anestesi Jam 20.40 wib, pasien dimasukan ke kamar operasi lalu dipasang alat monitor standar, EtCO2, posisi pasien supine dengan kepala slight head up, lalu dilakukan oksigenasi 7 L/menit dengan sungkup. Jam 20.50 wib, dilakukan induksi dengan memberikan fentanyl 150mcg intravena perlahan selama 2 menit, propofol 150mg, untuk fasilitasi intubasi diberikan vecuronium 7mg, lalu lidokain 90mg kemudian diberi propofol 50mg ulangan, setelah sekitar 90 detik dilakukan intubasi dengan pipa endotrakhea nonkinking dengan nomor 7,5 balon. Mata diberi salep dan ditutup dengan plester kertas 3 lapis. Rumatan isofluran 0,8–1 MAC, oksigen/udara ruang 50%, fentanyl 50mcg/30menit, ventilasi kendali dengan vecuronium 2mg/30menit dengan menggunakan syringe pump, modus ventilator yaitu volume control (VC) dengan tidal volum 540mL, frekuensi napas 14 kali/menit, T. Inspirasi 11.7, minute volume tercapai 6,5–7L/ menit. Setelah dilakukan dreaping dan sebelum dilakukan insisi kulit kepala ditambahkan fentanyl 50mcg, ditambah fentanyl 50mcg lagi sebelum dilakukan bor pada tulang tengkorak untuk evakuasi. Sebelum tulang tengkorak atau kranium di buka, diberikan manitol 20% dengan dosis 0,5 gram/kgBB habis dalam 15 menit. Setelah kranium dibuka, tampak duramater tidak tegang, dan ketika duramater dibuka tampak otak yang lunak/slack brain. Gambar 2. Foto MSCt Kepala Kedua Tatalaksana Anestesi pada Pendarahan Intraserebral Spontan Non Trauma 11 Gambar 3. Monitoring Tekanan Darah, Denyut Jantung, Saturasi selama Tindakan Operasi Selama operasi 2 jam 30 menit hemodinamik cukup stabil, dengan perdarahan sekitar 500cc, total diuresis selama operasi 1300cc, sedangkan input cairan selama operasi adalah NaCl 0,9% 500cc dan RL 500cc total 1000cc. Tigapuluh menit sebelum operasi selesai diberikan ondansetron 8mg intravena. Pengelolaan Pascabedah Setelah selesai operasi pasien dipindahkan langsung ke ICU, dilakukan resusitasi otak dengan pernapasan dikontrol dengan ventilator modus volume control ventilation (VCV), dengan vecuronium 4mg/jam, propofol 20mg/jam selama 24 jam, analgetik tramadol 100mg/8jam. Selama perawatan di ICU, hemodinamik dan respirasi cukup stabil. Hari ke 2 pasien di ekstubasi dengan GCS E4M5V4, sampai hari ke 4 pasien dipindahkan ke high care unit (HCU). Perawatan di HCU selama 3 hari, kondisi pasien semakin baik dengan hemodinamik yang stabil dan pasien dipindahkan ke ruang perawatan biasa dengan E4M5V5, hemipilegi dextra dengan motorik kanan 2–2. Setelah 4 hari perawatan di ruangan pasien diperbolehkan pulang. III. Pembahasan PIS merupakan bentuk stroke yang paling destruktif. Secara klinik ditandai dengan cepatnya perubahan atau penurunan neurologis akibat dari peningkatan tekanan intrakranial. Diagnosa dapat ditegakkan dengan mudah yaitu dengan menggunakan MSCt kepala atau dengan MRI kepala.1-5 PIS didefinisikan sebagai perdarahan yang terjadi secara spontan dan terjadi ekstravasasi darah tersebut ke dalam parenkim otak. Bentuk PIS yang non-traumatis ini terjadi 10% sampai 30% dari semua kejadian stroke yang dirawat di rumah sakit, yang menimbulkan tingkat kecacatan tinggi, serta morbiditas dan mortalitas yang tinggi juga sekitar 30% sampai 50% dalam 30 hari setelah kejadian. Kematian pada 1 tahun pertama bervariasi dimana: 51% terjadi pada PIS yang deep, 57% pada PIS lobar, 42% pada PIS cerebellar dan 65% pada PIS di batang otak.5 Beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya PIS yaitu hipertensi, kadar kolesterol yang rendah, konsumsi minuman beralkohol yang banyak, merokok. Semua hal ini merupakan faktor resiko yang masih dapat di perbaiki atau diubah. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat di ubah seperti umur, jenis kelamin, etnik (orang Jepang dan Afrika – Amerika). Penelitian mengatakan bahwa hipertensi meningkatkan resiko terjadinya PIS lebih dari dua kali lipat, terutama pada pasien kurang dari 55 tahun yang menghentikan pengobatan antihipertensinya. 12 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Hipertensi menyebabkan vaskulopati pembuluh darah kecil yang kronik ditandai dengan fragmentasi, degenerasi dan akhirnya ruptur, hal ini ini terjadi pada pembuluh darah kecil Gambar 4. Tempat yang paling sering dan sumber dari PIS Perdarahan intraserebral paling sering mencakup lobus serebral, berasal dari penetrasi cabang kortikal dari arteri cerebri anterior, media dan posterior (A); Basal ganglia, berasal dari lenticulo-striata ascending cabang dari arteri cerebri media (B); Thalamus, berasal dari thalmogeniculate ascending cabang dari arteri cerebri posterior (C); Pons, berasal dari paramedian cabang dari arteri basilaris (D); dan Cerebelum, berasal dari penetrasi cabang dari arteri serebelar posterior inferior, anterior inferior atau superior (E). yang penetrasi ke dalam otak (lipohyalinosis). Seringkali terjadi pada basal ganglia dan thalamus (50%), region lobar (33%) dan pada batang otak serta serebelum (17%).1-8 Kadar kolesterol yang rendah telah diimplikasikan sebagai salah satu faktor terjadinya PIS primer. Hal ini berdasarkan beberapa penelitian secara kasus kontrol dan cohort, namun pada penelitian terbaru, pada pasien yang baru mengalami stroke atau transient ischemic attack, diberi artovastatin 80mg perhari dapat menurunkan kejadian stroke dan kejadian kardiovaskuler selama 5 tahun, namun hal ini masih menjadi kontroversi.5-7 Intake alkohol berat merupakan salah satu faktor terjadinya PIS, pada penelitian kasus kontrol terbaru. Pada teori dikatakan bahwa alkohol dapat mempengaruhi fungsi platelet, fisiologi koagulasi darah dan perubahan fragilitas pembuluh darah. Sedangkan merokok sebenarnya tidak ada hubungan dengan peningkatan resiko terjadinya PIS, walaupun pada suatu penelitian retrospektif menemukan bahwa perokok dengan hipertensi meningkatkan resiko PIS, efeknya adalah dengan dimediasinya hipertensi dan bukan karena tembakaunya. Hal ini sama dengan PIS mungkin sebagai suatu komplikasi dari insiden atau penggunaan kokain yang kronik.5-8 Cereberal amyloid angiopathy, merupakan faktor resiko yang penting untuk terjadinya PIS pada orang tua. Hal ini ditandai dengan depositnya β amiloid protein pada pembuluh darah kecil dan sedang di otak dan leptomeningens, yang akan menjadi nekrosis fibrinoid. Ini menjadi penyakit yang sporadis, dan berhubungan dengan penyakit Alzheimer’s atau dengan sindrom familial (Apolipoprotein ε2 dan ε4 allele).8 Penggunaan CT-scan kepala yang luas, secara dramatis memberikan perubahan dalam pendekatan diagnostik pada penyakit ini, dan adanya CT-scan menjadi pilihan dalam mengevaluasi PIS. Evaluasi yang dilakukan adalah mengenai ukuran dan lokasi dari hematoma, penyebarannya ke sistem ventrikel, derajat edema dan kerusakan secara anatomis. Volume hematoma dapat dengan mudah dihitung dari hasil CT-scan dengan manggunakan metode (ABC)/2, suatu turunan dari formula menghitung volume bola. Magnetic Resonance Imaging (MRI) sangat sensitif untuk mengetahui adanya PIS. Pada penelitian HEME dikatakan MRI dan CT mempunyai kemampuan yang sama dalam mendeteksi PIS yang akut, namun pada PIS yang kronik MRI lebih baik.5 CT-angiografi tidak rutin digunakan pada beberapa center, tapi telah terbukti mampu menolong memperkirakan perkembangan hematoma dan outcome. CTangiografi ini mutlak dikerjakan pada pasien dengan PIS sekunder seperti kemungkinan adanya aneurisma, malformasi arteri-vena, trombus di sinus duramater atau di vena kortikal; Subarachnoid Bleeding; sangat kuat disarankan juga pada pasien PIS primer dengan Intraventricular Hemorrhage dan pasien muda tanpa hipertensi dengan lobar PIS.5,8 Cepatnya perubahan neurologis dan hilangnya kesadaran, sehingga dapat terjadi gangguan Tatalaksana Anestesi pada Pendarahan Intraserebral Spontan Non Trauma 13 pada reflex untuk tetap mempertahankan jalan napas. Kegagalan dalam mempertahankan jalan napas ini mengakibatkan komplikasi seperti terjadinya aspirasi, hipoksemia dan hiperkarbia. Sehingga dibutuhkan segera tindakan untuk mempertahankan jalan napas dengan melakukan pemasangan pipa endotrakheal, dengan menggunakan tehnik Rapid Sequence Induction (RSI) dengan obat dengan onset cepat dan lama kerja singkat seperti propofol, suksinilkolin. Pada pasien dengan tekanan intrakranial (TIK) meningkat dipertimbangkan pemberian premedikasi dengan menggunakan lidokain intravena pada tindakan RSI. hematoma atau ini hanya respon terhadap peningkatan TIK yang terjadi dari bertambahnya volume PIS guna mempertahankan CPP.1-5 Secara umum American Heart Association (AHA) telah membuat Guidelines bahwa tekanan darah sistolik lebih dari 180mmHg atau MAP lebih dari 130mmHg harus di terapi dengan infus obat antihipertensi terus menerus seperti labetalol, esmolol, atau nicardipin. Sedangkan terapi oral dan sublingual sudah tidak dipilih lagi. Meskipun belum ada penelitian kapan waktu yang tepat pemindahan terapi antihipertensi intravena ke terapi peroral, proses ini umumnya dimulai setelah 24 sampai 72 jam setelah kondisi pasien stabil.5 Cairan resusitasi isotonik dan vasopresor di indikasikan pada pasien syok. Pemberian cairan yang mengandung dekstrose harus dihindari, untuk mencegah terjadinya hiperglikemi pada pasien cedera kepala. Pemeriksaan yang diperlukan adalah pemeriksaan hematologi, biokimia darah, profil koagulasi, foto thorak, kalau perlu dilakukan echokardiogram.1-3 Peningkatan tekanan darah yang ekstrem setelah PIS harus diterapi dengan agresif tapi dengan hati-hati untuk mengurangi resiko terjadi perluasan hematoma tersebut, dengan tetap mempertahankan tekanan perfusi serebral (cerebral perfusion pressure/CPP). Penurunan tekanan darah yang terlalu agresif setelah PIS dapat menjadi predisposisi terjadinya penurunan yang hebat tekanan perfusi serebral dan terjadi iskemik yang selanjutnya dapat meningkatkan TIK berlanjut terjadi kerusakan saraf.1-8 Penyebaran hematoma dapat terjadi karena perdarahan yang menetap atau perdarahan kembali dari satu arteriole yang ruptur. Beberapa peneliti melaporkan bahwa perluasan hematoma berasal dari perdarahan yang ada masuk ke daerah penumbra yang iskemik sekitar hematoma. Namun penelitian oleh Brott dkk., mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang memperlihatkan antara perkembangan hematoma dan tingkat tekanan darah, tetapi penggunaan obat antihipertensi mungkin telah menutupi efek negatif terhadap hubungan ini. Tingkat tekanan darah mempunyai hubungan dengan peningkatan TIK dan volume hematoma tetapi ini sulit untuk menjelaskannya, apakah hipertensi yang menyebabkan perluasan Pada pasien koma, direkomendasikan menggunakan monitor TIK dan titrasi vasopresor untuk mempertahankan CPP antara 70-90mmHg. Pada umumnya tidak masalah dengan tingginya tekanan darah, tetapi MAP harus tidak boleh berkurang 15–30% selama 24 jam pertama.5 Penelitian pada keadaan darurat terhadap pengontrolan TIK yang berhubungan dengan pasien yang stupor dan koma atau adanya suatu tanda-tanda yang menggambarkan adanya herniasi batang otak (yaitu pupil anisokor atau motor posturing), untuk itu dilakukan tindakan untuk menurunkan segera TIK sebelum dilakukan tindakan pembedahan, maka dilakukanlah suatu tindakan; kepala di elevasi sampai 30 derajat, pemberian manitol 20% (1–1,5mg/BB) dengan tetesan yang cepat, pasien di hiperventilasi agar didapatkan PaCO2 26–30mmHg. Sebagai second line terapi atau pasien sedikit mengalami hipotensi maka diberikan cairan saline 0,9% yang dapat diberikan melalui kateter vena sentral (central venous catheter/CVC). Pemberian kortikosteroid merupakan kontra indikasi pada pasien ini berdasarkan beberapa penelitian yang tidak mendapatkan efikasi pada pasien PIS yang diberikan kortikosteroid.5 Penggunaan antikoagulan seperti warfarin, meningkatkan resiko PIS sebesar 5–10 kali dan sekitar 15% kasus PIS dihubungkan dengan penggunaan obat ini, target yang dicapai adalah INR dibawah 1,4 dengan pemberian fresh frozen plasma (FFP) sebagai reversalnya atau konsentrat dari komplek protrombin dan vitamin K, setelah itu di cek kembali koagulasi. 14 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Pemberian FFP harus dengan pengawasan karena dapat menyebabkan gagal jantung kongestif.5,8 Observasi pasien di ICU paling sedikit 24 jam pertama setelah kejadian merupakan suatu tindakan yang sangat direkomendasi, karena resiko penurunan neurologis sangat tinggi selama periode ini dan karena mayoritas pasien dengan perdarahan batang otak dan serebelar telah menekan tingkat kesadaran dan memerlukan bantuan ventilator. Penilaian yang dilakukan di ICU untuk memantau fungsi kardiovaskuler yang optimal pada pasien PIS termasuk tekanan pembuluh darah arteri invasif, CVC, dan monitor kateter arteri pulmonal. Pemasangan drainase eksternal ventrikel dilakukan pada pasien dengan penurunan kesadaran (GCS skor< 8), tanda akut hidrosephalus atau efek masa intrakranial berdasarkan CT scan, dan untuk meminimalkan TIK serta mengurangi resiko terjadinya ventilator associated pneumonia (VAP) pada pasien yang menggunakan ventilator maka kepala pasien ditinggikan 30o.5 Kebutuhan cairan isotonik seperti NaCl 0,9% sekitar 1ml/kg/jam, harus diberikan pada pasien PIS sebagai standar cairan agar mendapatkan kondisi yang euvolemik dan diuresis setiap jam harus lebih dari 0,5 cc/kgbb. Pemberian cairan NaCl 0,45% atau dextrose 5% dalam air dapat memperberat edema serebral dan meningkatkan TIK karena terjadi perbedaan osmolaritas, yang menyebabkan cairan berpindah ke jaringan otak yang cedera. Hipo-osmolaritas sistemik (<280mOsm/L) harus diterapi agresif dengan manitol atau hipertonik saline 3%. Kondisi euvolemik harus tetap dipertahankan dengan mengetahuinya dari CVP yang terpasang (5– 8mmHg), penilaian ini harus diperhatikan terutama pada pasien yang menggunakan ventilator.2-5 Tujuan pemberian hipertonik saline selain sebagai resusitasi cairan juga mempertahankan osmolaritas agar tetap hiperosmolar (300–320mOsms/L) dan hipernatremi (150–155mEq/L) yang dapat mengurangi bengkaknya sel dan TIK. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah overload cairan, edema paru, hipokalemi, kardiak aritmia, asidosis metabolik hiperkloremik dan delutional koagulopati. Hipertonik saline harus secara bertahap diturunkan pemberiaannya dan kadar serum tidak boleh turun lebih dari 12mEq/L dalam 24jam, untuk menghindari rebound edema serebral dan peningkatan TIK.5 Pencegahan kejang akut harus dilakukan dengan pemberiaan fenitoin 17mg/kgBB sebagai loading dose kemudian 100mg setiap 8 jam. American Heart Association (AHA) memberi rekomendasi bahwa pemberiaan anti-epileptik diberikan sampai 1 bulan setelah bebas dari kejang. Penelitian mengatakan kejadian kejang setelah 30 hari PIS adalah 8% dan resiko terjadinya status epileptikus adalah 1% sampai 2%.5 Demam atau suhu >38,3 oC pada pasien PIS sering ditemui, terutama pasien dengan Intra Ventricle Haemorhagic (IVH) dan hal ini harus diterapi secara agresif. Demam yang terjadi setelah PIS memperlihatkan adanya hubungan dengan outcome yang buruk. Hipertermi dapat memperburuk iskemia otak yang telah mengalami cedera dengan melepaskan neurontransmiter eksitotoksik, proteolisis, radikal bebas dan produksi sitokin, blood-brain barrier compromise dan apoptosis. Selain itu juga terjadi hiperemia, bertambahnya edema otak dan meningkatkan TIK. Standar umum untuk pasien dengan suhu lebih dari 38,3 oC, di terapi dengan acetaminophen dan cooling blankets.5 Hiperglikemi adalah suatu prediktor yang poten terhadap kematian dalam 30 hari, pada pasien diabetik atau non-diabetik dengan PIS. Efek merusak dari hiperglikemi telah dilakukan penelitian pada sindrom vaskuler yang akut. Pada pasien stroke iskemik kejadian hiperglikemi 20–40% dari pasien dan ini dihubungkan dengan infark yang meluas, outcome fungsional yang jelek, tinggal di rumah sakit menjadi lebih lama, tingginya biaya perawatan dan meningkatnya resiko kematian.5 Tatalaksana atau manajemen anestesi yaitu dengan melakukan tindakan resusitasi akut pada pasien PIS sesuai dengan aturan umum yaitu “ABC”, Airway atau jalan napas, Blood pressure atau tekanan darah dan Cerebral perfusion atau perfusi serebral. Jalan napas harus selalu bebas, karena pada pasien dengan GCS kurang atau sama dengan 8 atau tidak dapat mempertahankan jalan napas harus dilakukan intubasi. Keadaan saturasi yang baik adalah tidak cukup dan tidak mencerminkan tekanan parsial dari karbon Tatalaksana Anestesi pada Pendarahan Intraserebral Spontan Non Trauma dioksida di arteri (PaCO2), jadi walaupun saturasi normal, satu hal yang harus dipastikan bahwa pasien ini tidak mengalami hiperkarbi karena ini dapat memperburuk hipertensi intrakranial.5 Sebaiknya dilakukan pemasangan CVC dan jalur arteri, guna mengontrol tekanan darah yang baik dan agresif, dimana hipertensi dan hipotensi harus dihindari. Tekanan perfusi otak adalah perbedaan tekanan yang bertanggung jawab terhadap cerebral blood flow (CBF) atau aliran darah serebral dan ini menyebabkan terjadinya iskemi otak. Tekanan perfusi otak didefinisikan sebagai Mean Arterial Pressure (MAP) atau tekanan arteri rerata dikurangi Intracranial Pressure atau tekanan intrakranial (TIK) dengan persamaan CPP=MAP–TIK.5,6 Definisi peningkatan tekanan intrakranial adalah jika TIK melebihi 20 mmHg selama 5 menit. Tujuan pengobatan adalah menurunkan TIK kurang dari 20 mmHg dan CPP 60–70mmHg. Hipertensi intrakranial dapat diterapi dengan membuat drainase cairan cerebrospinal (shunt), menurunkan volume otak atau cerebral blood volume (CBV) atau dengan sedasi dan menurunkan metabolisme otak6, serta mencegah semua hal yang dapat meningkatkan TIK seperti melakukan induksi atau laringoskopi dengan smooth dan gentle sehingga hemodinamik tidak bergejolak, mencegah pasien batuk, meninggikan kepala dan menempatkan kepala pada posisi yang netral.6,7 Pengobatan terhadap volume otak bertujuan untuk menurunkan TIK dengan menggunakan tehnik osmoterapi yaitu dengan pemberian manitol 0,25 sampai 0,5 gram/kgBB setiap 4 jam dan furosemid 10mg setiap 2 sampai 8 jam. Osmolaritas serum dan konsentrasi sodium harus dipantau ketat dengan target osmolaritas kurang dari 310mOsm/L dan normonatremia. Pemberian cairan berguna untuk mempertahankan status euvolemia atau sedikit “kering” untuk menghindari berkembangnya edema otak.6 Hipokarbi (PaCO2 25–35mmHg) menurunkan TIK dengan mekanisme vasokonstriksi cerebral dan tindakan ini sangat efektif pada kasus kritis dengan cara melakukan hiperventilasi. Pada 15 hiperventilasi yang ekstrim atau berlebihan (PaCO2< 20mmHg) dapat menyebabkan iskemi dengan menurunkan aliran darah ke otak, sehingga hiperventilasi tidak digunakan untuk waktu yang lama, karena menjadi tidak efektif terhadap penyesuaian metabolik pada alkalosis respiratorik dan rawan terjadi rebound peningkatan TIK saat kembali pada normokapni. Sedasi dan paralisis dengan pelumpuh otot dapat mengurangi peningkatan TIK dan ini juga bekerja mencegah agitasi dan mengejan serta menurunkan metabolisme otak. Bila TIK masih tetap tinggi dapat dilakukan barbiturate koma.1,2,4,5 Outcome pasien PIS akan lebih baik, jika pasien dirawat khusus di ICU. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa mortalitas setelah PIS dihubungkan dengan rendahnya skor PIS. Skor PIS merupakan prediktor yang tepat, berdasarkan hasil yang dinilai adalah mortalitas dalam waktu 30 hari.6,7 Tabel 1. Penentuan Skor PIS6,7 Komponen GCS Volume (cm3) 3–4 5 – 12 13 – 15 PIS ≥ 30 < 30 IVH Ya Tidak Infratentorial Ya PIS Tidak Umur (tahun) ≥ 80 < 80 Skor 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Rentang skor PIS adalah 0 sampai 5 dan PIS skor dari kohort itu didistribusikan di antara berbagai kategori. Tidak ada pasien dengan skor PIS 0 yang meninggal, sedangkan semua pasien dengan skor PIS lebih dari 5 akan meninggal. Dalam 30 hari, tingkat kematian bagi pasien PIS dengan skor 1, 2, 3 dan 4 adalah 13%, 26%, 72%, dan 97%, masing-masing. Tidak ada pasien dalam kohort PIS memiliki skor PIS lebih dari 6 karena tidak ada pasien dengan PIS infratentorial 16 Jurnal Neuroanestesi Indonesia memiliki volume hematoma lebih dari 30cm3. Mengingat bahwa tidak ada pasien dengan PIS skor 5 bertahan hidup, sedangkan skor PIS 6 berhubungan dengan risiko kematian sangat tinggi.6,7 Terapi pada pasien PIS dapat dilakukan secara medis seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya dan dengan terapi pembedahan. Tindakan pembedahan dapat berupa pemasangan ventrikel drainase ataupun dengan pembedahan kraniotomi evakuasi perdarahan. Namun tidak semua pasien PIS dapat menjalani kraniotomi ini, adapun pasien yang tidak perlu dilakukan tindakan kraniotomi adalah pasien dengan perdarahan yang sedikit (volume 10–20 cc) atau defisit neurologis yang minimal dan pasien dengan skor GCS < 4.8 Sedangkan pasien yang dapat dilakukan tindakan pembedahan adalah 1) pasien dengan perdarahan serebelar dengan diameter >3 cm (volume >14cc) dengan gangguan neurologis yang buruk atau telah ada penekanan di batang otak dan hidrosephalus karena sumbatan di ventrikel, yang harus segera menjalani evakuasi perdarahan sesegera mungkin, 2) PIS yang berhubungan dengan kelainan struktur seperti aneurisma, AVM atau angioma kavernosa dapat dioperasi jika pasien mempunyai outcome yang bagus dan lesi dari struktur vascular tersebut dapat dijangkau dengan pembedahan, 3) Pasien muda dengan perdarahan lobar yang moderate atau luas yang secara klinis memburuk.6 Tindakan kraniotomi merupakan tindakan pembedahan pada pasien dengan PIS dan telah banyak dilakukan penelitian untuk hal ini. Beberapa penelitian memperlihatkan pada pasien dengan perubahan kesadaran dengan pembedahan mengurangi resiko kematian tanpa memperbaiki fungsionalnya dan pada evakuasi yang sangat awal, mengalami perbaikan selama 3 bulan.6,8 mengobati komplikasi sistemik yang terjadi, mempercepat pemulihan dan mencegah atau memperlambat kekambuhan dan komplikasi. IV. Simpulan 7. Hemphill JC, Bonovich DC, Besmertis L, Manley GT, Johnston SC, Tuhrim S. The ICH score: a simple, reliable grading scale for intracerebral. Stroke.2001; 32:891–7. Stroke perdarahan merupakan penyakit berat dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi terhadap outcome klinis dan gejala sisanya. Penting sekali memahami secara teliti setiap aspek penyakit ini dan kemungkinan komplikasi yang akan didapat sehubungan tindakan anestesi yang akan dilakukan. Tujuan umum adalah meminimalkan kerusakan saraf, mencegah dan Daftar Pustaka 1. Feen ES, Lavery AW, Suarez JI. Management of nontraumatic intracerebral hemorrhage. Dalam: Suarez JI, Tarsy D, eds. Critical Care Neurology and Neurosurgery. New Jersey: Humana Press; 2004, 353–64. 2. Manoach S, Charchaflieh JG. Traumatic brain injury, stroke and brain death. Dalam: Newfield P, Cottrell J, eds. Handbook of Neuroanesthesia, 4th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007, 432–44. 3. Stoelting RK, Dierdorf SF. Anesthesia and Co-Existing Disease, 4th edition, Philadelphia: Churchill Livingstone; 2002, 160–1 4. Rost N, Rosand J. Intracerebral hemorrhage. Dalam: Torbey MT, eds. Neurocritical Care. New York: Cambridge University Press; 2010, 143–59. 5. Rincon F, Mayer SA. Review clinical review: critical care management of spontaneous intracerebral hemorrhage. Critical Care. 2008; 12(6):237–52. 6. Jabbour PM, Awad IA, Huddle D. Hemorrhagic cerebrovascular disease. Dalam: Layon AJ, Gabrielli A, Friedman WA, eds. Textbook of Neurointensive Care. Philadelphia: Saunders; 2004,155–78. 8. Dubourg J, Messerer M. State of the art in managing nontraumatic intracerebral hemorrhage. Neurosurg Focus. 2011; 30(6):1–7. Penatalaksanaan Perioperatif Hipofisektomi Transsphenoidal: Pendekatan Endoskopik Endonasal Sandhi Christanto*), Bambang Suryono**), Tatang Bisri***), Siti Chasnak Saleh****) Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Mitra Keluarga Sidoarjo, **)Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada–RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta, ***)Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran-RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, ****) Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga–RSUD Dr. Soetomo Surabaya *) Abstrak Tumor kelenjar hipofisa sering dijumpai dan mewakili kurang lebih 10% dari semua neoplasma otak yang terdiagnosa. Meski tersedia terapi medis, pendekatan pembedahan menjadi lebih sering dilakukan. Pendekatan transsphenoidal endonasal endoskopik dipilih karena memiliki keuntungan untuk mencapai regio sella secara cepat dengan resiko kerusakan otak dan komplikasi pascabedah yang minimal. Pengetahuan dan keahlian dokter anestesi tentang pembedahan endoskopik basis kranii dibutuhkan untuk memenuhi kriteria dalam menyediakan keadaan anestesi yang aman, yang akan memainkan peran penting dalam menghasilkan luaran yang diharapkan. Seorang wanita 25 tahun dibawa ke rumah sakit dengan penurunan kesadaran pasca seksio sesarea. Pada pemeriksaan ditemukan edema otak, dan hidrosephalus yang kemudian dilakukan pintas ventrikuloperitoneal. Pemeriksaan lebih lanjut didapatkan massa kistik suprasellar dan pembedahan hipofisektomi transsphenoidal melalui jalur endonasal endoskopik dipilih sebagai pendekatan surgikal. Pasien dengan kelainan hipofisa serta pendekatan pembedahan endoskopik memberikan tantangan tersendiri bagi dokter anestesi. Peralatan endoskopik berteknologi tinggi, pertimbangan intraoperatif yang berhubungan dengan tehnik ini, membutuhkan pengelolaan anestesi yang baik selama periode perioperatif, sehingga dokter anestesi dapat memberikan anestesi yang aman selama prosedur pembedahan dan memberi kontribusi besar bagi keberhasilan dan kemajuan pembedahan endoskopik basis kranii. Kata kunci: hipofisektomi transsphenoidal, penatalaksanaan perioperatif, tumor hipofisa JNI 2015;4 (1): 17–27 Abstract Perioperative Management of Transsphenoidal Hypophysectomy: Endoscopic Endonasal Approach Pituitary gland tumor represents 10% of all brain neoplasms. Although medical therapy is available, surgical approach becomes commonly performed. The transsphenoidal via endoscopic endonasal is preferred because it has advantage of rapid access to the sella region with minimal traumatic risk to the brain as well as post-operative complications. The highly advance technology, the position of neurosurgeon when performing the surgery and other intraoperative consideration present a unique challenge which require a thorough understanding and the skill of anesthesia management that is tailored to the needs of safe anesthesia for this technique. A 25 years old woman was admitted to hospital following a decreased in level of conciousness after sectio cesarea and found to have edema cerebri and hydrocephalus. Ventricular peritoneal shunt was performed immediately. Further examination revealed a cystic mass in suprasellar region and transsphenoidal hypophysectomy via endonasal endoscopic route was chosen as surgical approach. Patient with pituitary disease and endoscopic method present challenges to the anesthesiologist. High technology equipment and techniques, as well as other intraoperative considerations mandate the skillfulness of anesthesia management throughout the perioperative periode. Those considerations will ensure the neuroanestesiologist for a safe anesthesia and continue to make contributions to the development of full endoscopic skull base surgery. Key words: perioperative management, pituitary adenoma, transsphenoidal hypophysectomy JNI 2015;4 (1): 17–27 17 18 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Tumor kelenjar hipofisa mewakili kurang lebih 10% dari seluruh neoplasma otak yang terdiagnosis.1 Meskipun merupakan tumor jinak, pasien dengan penyakit hipofisa memberikan tantangan unik bagi dokter anestesi karena peran penting kelenjar ini pada sistem endokrin serta pembesarannya dapat menekan struktur-struktur penting disekitarnya dan memberikan tanda serta gejala klinis yang signifikan.1,2 Tantangan bagi dokter anestesi dimulai dari persiapan preoperatif berlanjut pada masa pembedahan sampai ke periode pascabedah. Keberhasilan penatalaksanaan pasien dengan tumor hipofisa memerlukan pendekatan multi disiplin dan sangat bergantung dari kualitas perawatan perioperatif.1 Pendekatan surgikal dilaksanakan pada kasus dimana terapi medikal dirasakan tidak memberi hasil atau terdapat indikasi dilakukan operasi.2 Saat ini jalur pembedahan pilihan untuk mencapai tujuan terapi adalah melalui pembedahan transsphenoidal, hal ini disebabkan laju komplikasi pascabedah yang rendah dan akses langsung ke area sella dengan lebih mudah tanpa retraksi jaringan otak yang dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tersebut.2 Salah satu tehnik pembedahan transsphenoidal adalah dengan pendekatan endonasal endoskopik, dimana pendekatan ini menjadi lebih sering ditemui saat ini karena dihubungkan dengan rendahnya angka komplikasi (nasal, dental, kosmetik), serta pemulihan yang lebih cepat.3 Pendekatan endoskopik endonasal ini juga memberikan keuntungan yang jelas dibandingkan pendekatan tradisional sublabial transseptal mikroskopik karena menghilangkan insisi sublabial, diseksi mukosa septum nasi, frakturasi septum nasi sehingga menurunkan morbiditas pascabedah.3 Keuntungan lain yang bisa didapat adalah alat endoskopik dapat masuk lebih dalam ke sella tursica dan area supra sella untuk mencari sisa tumor yang tidak dapat di akses dengan pembedahan mikroskopik.3 Tehnik endoskopik dan penggunaan peralatan yang bertehnologi tinggi memerlukan penatalaksanaan anestesi yang cakap. Pertimbangan neuro- anestesi spesifik untuk pendekatan pembedahan endonasal bersama dengan pertimbangan umum neuro-endokrin pasien dengan penyakit hipofisa memerlukan penanganan yang teliti mulai periode preoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif. II. Kasus Seorang wanita 25 tahun berat badan 55 kg dengan diagnosa hidrosephalus kausa massa kistik suprasellar. Pasien rujukan dari Madura pasca seksio sesarea dengan preeklamsia berat dan penurunan kesadaran. Pasien sebelumnya dibawa ke rumah sakit Sampang karena mengalami nyeri kepala hebat dan bertambah gelisah. Beberapa jam setelah operasi pasien mengalami penurunan kesadaran kemudian dirujuk ke Surabaya. Di rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya didapatkan pasien dengan GCS E3V1M4 dan CT-scan menunjukkan adanya pendarahan intraventrikular, edema serebri yang selanjutnya dilakukan pemasangan VP shunt. Pemeriksaan preoperatif Anamnesis Keluhan nyeri kepala, mual dan muntah, gangguan penglihatan, penglihatan ganda, riwayat kejang. Riwayat penyakit dahulu, pasien memiliki riwayat menstruasi yang tidak teratur, pernah mengalami amenorrhea hingga 6 bulan, serta 8 tahun pernikahan namun belum pernah hamil sampai sekarang (riwayat infertil). Sejak usia kehamilan 1 bulan sering mengeluh sakit kepala yang dirasa makin berat dan riwayat mata kabur sehingga sering menabrak saat berjalan. Pasien dan keluarga tidak memiliki riwayat perdarahan atau kecenderungan untuk berdarah, riwayat sakit berat lainnya tidak didapatkan, riwayat pemakaian obat-obatan sebelumnya tidak ada termasuk obat-obatan hormonal maupun obat yang memicu perdarahan. Pasien sedang dalam pengobatan dengan obat dexamethasone 5 mg tiap 8 jam yang sudah berlangsung 8 hari pemberian. Pemeriksaaan Fisik Status generalis: Jalan napas bebas, laju napas 16 x/menit, suara napas vesikular, tidak didapatkan ronki maupun Penatalaksanaan Perioperatif Hipofisektomi Transsphenoidal: Pendekatan Endoskopik Endonasal 19 wheezing, perfusi hangat kering merah, tekanan darah 130/80 mmHg, laju nadi 80 x/menit teratur, lain-lain tidak didapatkan kelainan. Status Neurologis GCS 4-4-6, pupil isokor 3mm/3mm refleks cahaya +/+, pemeriksaan motorik dalam batas normal, sensorik sulit dievaluasi, pemeriksaan saraf kranialis tidak didapatkan kelainan Pemeriksaan Mata Gangguan penglihatan kesan tidak didapatkan, pemeriksaan lapang pandang sulit dievaluasi, gerakan bola mata kesan normal, fundus okuli mata kanan dan kiri dalam batas normal. Pemeriksaan Laboratorium Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 13,7 g%, leukosit 13.800/mm3, trombosit 320.000/mm3, hematokrit 42,6%, masa prothrombin 11,9 detik (kontrol 12,9 detik), APTT 25,3 detik (kontrol 25,2 detik), SGOT 115 U/L, SGPT 265 U/L, bilirubin direk 0,92 mg/dL, bilirubin total 1,1 mg/dL, ureum 22 mg/ dL, kreatinin 0,65 mg/dL, Natrium 136 mmol/L, kalium 3,7 mmol/L, albumin 3,4 g/dL, kortisol 26,69 mcg/dL, prolaktin > 200 ng/mL, FT4 0,93 ng/dL, TSH 0,85 mcU/mL. Pemeriksaan MRI didapatkan massa solid kistik dengan komponen darah di intrasella sampai suprasella ukuran 3,8x 3,3x 3,4 cm yang mendesak chiasma optikum ke superior, mendesak ventrikel tiga, tampak hidrosephalus yang berkurang dibandingkan CT-scan sebelumnya, terpasang VP shunt dengan ujung distal di ventrikel lateralis, pergeseran struktur garis tengah tidak didapatkan. Pemeriksaan MR-Angio didapatkan sirkulus Wilisii tampak paten dan tidak tampak aneurisma maupun malformasi vaskular. Pada foto polos toraks dan pemeriksaan elektrokardiografi tidak didapatkan kelainan. Penatalaksanaan Anestesi Premedikasi diberikan dexamethasone 5 mg dan midazolam 2 mg intravena. Evaluasi tanda vital prainduksi didapatkan tekanan darah 130/80 mmHg, laju nadi 80–85x/menit, laju napas 16x/menit, saturasi oksigen 99%. Induksi anestesi dimulai dengan pemberian fentanyl 75 Gambar 1. Gambaran Massa Solid-Kistik di Daerah Sella mcg pelan dilanjutkan berturut-turut propofol 70 mg, atracurium 30 mg, propofol dosis kedua 20 mg. Intubasi dilakukan setelah dirasa kedalaman anestesi cukup dan dipasang pipa endotrakeal non kinking nomor 7 dengan balon. Pipa endotrakeal diposisikan di sudut mulut kiri difiksasi rapat dan dipasang tampon intraoral. Selama proses induksi tekanan darah berkisar 95–120/60–80 mmHg, laju nadi antara 70–80x/ menit. Posisi pasien terlentang dan kepala sedikit menengadah. Rumatan anestesi dilanjutkan dengan isoflurane < 1% – O2/udara tekan medik, propofol kontinyu 2–3 mg/kg/jam, atracurium 5 mcg/kg/menit. Pasien dipasang jalur intravena tambahan di kaki untuk mempermudah akses intravena serta jalur intraarteri untuk monitoring selama operasi berlangsung. Ventilasi mekanik diatur, moda volume control dipilih dengan volume tidal 8 mL/kgBB, frekuensi napas 12 x/ menit, PEEP 0, FiO2 0,5. Pengaturan ventilasi mekanik ditujukan untuk mendapatkan keadaan normokapnea yang dapat dilihat dari pemantauan kadar End Tidal CO2 (ETCO2 durante operasi 32–33 mmHg) dan analisa gas darah (pH 7,43, pCO2 35 mmHg, pO2 195 mmHg, SaO2 100%). Selama operasi berlangsung tekanan darah diatur dan dipertahankan antara 95–100/50–60mmHg dengan menyesuaikan dosis propofol infusi dan penambahan obat analgesik fentanyl berkala (total fentanyl 175 mcg). Status hemodinamik pasien selama operasi relatif stabil namun terdapat 20 Jurnal Neuroanestesi Indonesia gejolak hemodinamik yaitu tekanan darah dan laju nadi turun secara tiba-tiba (tekanan darah sampai 60/30 mmHg dan nadi 30x/menit irregular) saat dilakukan pengambilan tumor secara kuretase. Selama proses ini tekanan darah didapatkan antara 130–140/70–80 mmHg, mengejan dan batuk selama ekstubasi tidak didapatkan. Gejolak hemodinamik ini berhenti saat stimulasi pengambilan tumor dihentikan dan tanpa pemberian obat apapun. Hal ini terjadi sampai dua kali dan akhirnya setelah diskusi dengan ahli bedah saraf, intensitas kuretase dikurangi dan dilakukan dengan lebih berhati-hati maka kejadian ini tidak terulang lagi. Menjelang akhir operasi tekanan darah dikembalikan ke nilai awal (±120/80 mmHg) dengan mengurangi dosis propofol untuk membantu ahli bedah mencari fokus perdarahan yang mungkin tidak terdeteksi selama dilakukan kontrol hipotensi. Operasi berlangsung 3,5 jam dengan total perdarahan <100 mL, total pengeluaran urin 400 mL, cairan rumatan NaCl 0,9% 1000 mL. Pasien dengan kesadaran preoperatif yang baik, pengelolaan jalan napas preoperatif yang tidak sulit, serta selama operasi tidak terdapat kejadian yang dapat menyebabkan gangguan pascabedah maka direncanakan untuk dilakukan ekstubasi di kamar operasi. Proses membangunkan dari anestesi diusahakan sehalus mungkin dan meminimalkan batuk, mengejan serta gejolak hemodinamik berlebihan karena dapat memberikan penyulit pascabedah yang tidak diinginkan. Setelah pasien bernapas spontan adekuat, dilakukan pengisapan, obat anestesi dimatikan, pasien di ekstubasi sadar dengan sebelumnya diberikan lidokain 1,5 mg/kgBB intravena. Penatalaksanaan Pascabedah Setelah selesai operasi pasien di rawat di ruang perawatan intensif untuk dilakukan pengawasan ketat mengantisipasi penyulit yang dapat terjadi pada periode pascabedah. Selama perawatan pasien di posisikan slight head up, diberikan O2 masker 5 l/menit, infus NaCl 0,9% 1500 mL/ 24 jam. Ketorolac 30 mg tiap 8 jam sebagai analgesik, ranitidin 50 mg tiap 12 jam, dexamethasone 5 mg tiap 8 jam serta ceftriakson 1 g tiap 12 jam. Bila tidak terdapat keluhan seperti mual dan muntah serta pasien sadar baik direncanakan untuk diberikan asupan peroral. Pengawasan ketat terhadap tanda-tanda vital, kesadaran, produksi urin dan keluhan lain dilakukan secara terus menerus. Setelah pasien dapat berinteraksi dan lepas dari pengaruh anestesi, pasien ditanya dan diperiksa tentang keluhan maupun gejala yang mungkin timbul akibat penyulit pascabedah. Pada pemeriksaan tidak didapatkan keluhan nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan dan gangguan lapang pandang. Penglihatan ganda tidak didapatkan, gerakan bola mata tampak normal dan pada pemeriksaan inspeksi tidak didapatkan cairan yang keluar dari hidung. Hasil produksi urin 3 jam pertama didapat kurang lebih 80 mL tiap jamnya. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan gula darah acak 96 mg/ dL, kadar natrium darah 138 mmol/L, kalium 4,0 mmol/L Gambar 2. Grafik Monitoring Tekanan Darah dan Nadi Intraoperatif Hari pertama pascabedah kami dapatkan pasien tidak merasakan adanya keluhan seperti nyeri kepala, mual maupun muntah, jalan napas bebas, laju napas 16-18x/menit, saturasi oksigen 99100%, perfusi hangat kering merah, tekanan darah 110/60 mmHg, laju nadi 60–65 x/menit teratur kuat angkat, suhu tubuh 36,5 0C. Derajat kesadaran GCS 4–5–6, pupil isokor, reflek cahaya normal, produksi urine 50–80 mL tiap jamnya. Diberikan O2 nasal 2 l/menit, diet tinggi kalori tinggi protein dan tambahan susu 100 mL diberikan tiap 6 jam, serta terapi lain tetap. Pasien dipindahkan ke ruang intermediate dengan tetap diawasi secara ketat. Pada hari Penatalaksanaan Perioperatif HipofisektomiTranssphenoidal: Pendekatan Endoskopik Endonasal kedua kondisi tetap baik, pasien dipindahkan ke ruangan kemudian hari ketujuh dipulangkan. III. Pembahasan Tumor kelenjar hipofisa dianggap sebagai penyakit yang jarang dan mewakili kurang lebih 10% dari semua neoplasma otak yang terdiagnosis. Namun akhir-akhir ini tumor hipofisa cukup sering ditemui karena terdapat kecenderungan peningkatan angka penemuan kasus baru. Hal ini disebabkan adanya ketersediaan metode diagnostik neuro imaging yang lebih akurat, serta makin banyaknya ahli endokrin yang mampu mendiagnosis kelainan dengan lebih baik.4,5 Meskipun terapi medis tersedia untuk hampir semua kasus, tapi bukan merupakan tindakan kuratif, sehingga pendekatan surgikal dengan tujuan utama pengambilan tumor dilakukan dengan harapan mengurangi bahkan menghilangkan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut.1 Dalam prakteknya pengambilan tumor diharapkan terjadi remisi endokrin serta dekompresi struktur di sekitar hipofisa yang sebelumnya mengalami penekanan oleh pembesaran tumor tersebut.6 Fossa hipofisa dapat dicapai dengan rute transsphenoidal, transethmoidal atau transkranial. Pendekatan transsphenoidal merupakan jalur pembedahan pilihan dan menjadi prosedur yang makin sering dilakukan.1,7 Hal ini disebabkan oleh banyaknya keuntungan antara lain akses cepat ke regio sella dengan resiko minimal terjadinya trauma dan perdarahan otak, serta penyulit pascabedah yang rendah.6 Salah satu tehnik pendekatan transsphenoidal yang dapat digunakan adalah melalui jalur endonasal endoskopik. Pendekatan ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan pendekatan tradisional sublabial transseptal mikroskopik sebab pada tehnik endonasal endoskopik tidak dilakukan insisi sublabial, diseksi mukosa septum nasi, frakturasi septum nasi sehingga insiden morbiditas lebih rendah.4 Keuntungan lain dari tehnik endoskopik adalah dimungkinkan alat tersebut untuk masuk lebih jauh ke dalam sella tursica dan regio supra sella untuk mencari sisa tumor yang tidak dapat di akses dengan pembedahan mikroskopik.4 Tehnik dan peralatan endoskopik yang canggih bersama 21 dengan peralatan monitoring intraoperatif membutuhkan penatalaksanaan anestesi yang khusus. Pertimbangan spesifik neuro-anestesi untuk pembedahan endonasal endoskopik perlu dipahami oleh para dokter anestesi dalam memastikan luaran yang baik dari tehnik pembedahan ini.2 Penatalaksanaan Perioperatif Penilaian preoperatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari praktik anestesi yang aman. Tujuan dari pemeriksaan preoperatif adalah untuk memeriksa riwayat medis pasien termasuk kejadian neurologis sehingga diperoleh pengertian tentang penyakit pasien, manifestasi sistemik yang ditimbulkan, dan obat-obatan yang digunakan dalam terapi. Dari pemeriksaan preoperatif kita dapat mengetahui kondisi pasien tersebut, melakukan optimalisasi, mempersiapkan dan merencanakan tindakan anestesi yang sesuai dan aman untuk pasien tersebut.8 Seperti layaknya pasien bedah saraf lainnya penilaian preoperatif yang seksama dan teliti dalam menilai jalan napas, penilaian status umum dan neurologik pasien diperlukan juga pada pasien dengan kelainan di daerah sella.9 Adenoma hipofisa memiliki keunikan tersendiri dibanding lesi intrakranial lainnya. Peran penting kelenjar hipofisa dalam fungsi endokrin, menjadikan kelainan hipofisa dihubungkan dengan gangguan-gangguan organ lain di tubuh manusia yang merupakan akibat hiperfungsi maupun hipofungsi kelenjar hipofisa.1,5 Kelainan hiperfungsi paling sering dijumpai adalah prolactine secreting adenoma, dimana gangguan menstruasi serta riwayat infertil seperti pada kasus ini merupakan gejala klinis yang diakibatkan oleh kelainan hipofisa tersebut diatas.1 Hiperfungsi adenoma juga dapat mengakibatkan pelepasan adreno corticotropin hormon (ACTH) dan growth hormon (GH) menimbulkan penyakit Cushing dan akromegali yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan prolactine secreting adenoma. Pada kondisi ini perlu dicari dan dievaluasi dengan pemeriksaan preoperatif yang teliti 22 Jurnal Neuroanestesi Indonesia dan menyeluruh agar persiapan dan perbaikan dapat dilakukan demi menjamin kelancaran dan keamanan pengelolaan pasien selama periode perioperatif.1 Kedekatan kelenjar hipofisa dengan banyak struktur penting disekitarnya dapat memberikan gejala penekanan lokal yang spesifik.7 Gangguan penglihatan dapat terjadi akibat penekanan langsung pada chiasma optikus atau pada pembuluh darah yang memberi vaskularisasi daerah tersebut.7 Gangguan pergerakan bola mata atau penglihatan ganda dapat terjadi bila pembesaran tumor memberikan penekanan pada syaraf kranial yang bertanggung jawab pada pergerakan bola mata.9 Melihat adanya gangguan diatas maka pemeriksaan visual oleh ahli neuro-ophtalmologi sebaiknya dilakukan terutama bila terdapat keluhan visual atau bila makroadenoma membesar ke arah suprasella.9 Gejala peningkatan tekanan intrakranial (TIK) seperti nyeri kepala yang disertai mual, muntah dan papil edema sampai gangguan kesadaran dapat juga terjadi pada pasien dengan massa di daerah sella seperti halnya pada kasus pembesaran massa intrakranial lainnya. Peningkatan TIK pada tumor hipofisa dapat disebabkan oleh karena pembesaran tumor secara langsung atau secara tidak langsung akibat obstruksi aliran cairan serebro-spinal (CSS) di daerah ventrikel tiga.1 Bila terdapat peningkatan TIK, adalah penting dilakukan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi TIK seperti menghindari obstruksi aliran darah balik kranial dan penggunaan manitol preoperatif serta menghindari hal-hal yang dapat meningkatkan TIK selama periode perioperatif.1 Pemberian kortikosteroid tetap dilanjutkan pada periode preoperatif dan diberikan tiap 6–8 jam sampai 24 jam pascaoperasi untuk kemudian dilakukan evaluasi kadar kortisol darah sebelum pemberiannya diturunkan dan diganti dengan sediaan oral.1,6 Management Intraoperatif Terdapat ruang lingkup yang luas dalam tehnik anestesi untuk pembedahan tumor hipofisa. Seluruh prinsip dasar neuroanestesi dapat diterapkan dan modifikasi tehnik dasar tergantung dari ukuran dan perluasan tumor serta pendekatan pembedahan yang dipilih.1,7 Meskipun aliran darah otak (ADO) regional, autoregulasi, reaktifitas terhadap CO2 pada sebagian besar pasien tumor hipofisa dilaporkan normal, namun pada kasus kami didapatkan riwayat peningkatan TIK ( nyeri kepala, penurunan kesadaran, hidrosephalus) dan pada pemeriksaan preoperatif didapatkan kesadaran dibawah normal (GCS 4–4–6), serta masih adanya massa intrakranial maka tindakan induksi-intubasi dapat dapat memicu gejolak intrakranial yang membahayakan pasien. Seperti pada pasien tumor supratentorial lainnya, perlu diperhatikan beberapa hal selama tindakan induksi- intubasi antara lain seperti kontrol jalan napas dan pernapasan untuk mencegah hipoksia dan hiperkapnea, kontrol tekanan darah dan reaksi simpatis dengan mengatur kedalaman anestesi serta pemberian analgesik yang adekuat untuk mencegah gejolak hemodinamik dan intrakranial, mencegah sumbatan aliran vena kranial dengan memposisikan kepala netral dan head up.7 Tindakan diatas akan memperbaiki posisi pasien pada kurva tekanan-volume intrakranial, memastikan perfusi otak adekuat dan mencegah peningkatan TIK selama proses intubasi berlangsung.7 Pada pembedahan endoskopik basis kranii, seorang anestesi dihadapkan pada lingkungan operatif yang unik. Ahli bedah saraf menggunakan alat bertehnologi tinggi dan berada pada posisi yang sekiranya optimal bagi dirinya.3 Namun hal ini menyebabkan dokter anestesi memiliki akses yang kurang menguntungkan terhadap pengelolaan jalan napas pasien. Dalam mengantisipasi hal ini pipa endotrakeal non kinking digunakan untuk mencegah pipa tersebut menjadi buntu dan terlipat. Setelah pipa endotrakeal diposisikan menjauhi area pembedahan, perhatian khusus dalam fiksasi dilakukan. Pemasangan tampon intraoral selain dapat membantu fiksasi juga dapat mengurangi pengembunan yang dapat mengganggu visualisasi selama proses endoskopi. Jalur intravena, intraarterial, selang napas diatur sebaik mungkin agar tidak mengganggu proses pembedahan dan aman bagi proses anestesia. Akses intravena tambahan dapat dipasang di ekstremitas bawah Penatalaksanaan Perioperatif Hipofisektomi Transsphenoidal: Pendekatan Endoskopik Endonasal untuk memudahkan pemberian obat dan cairan.3 Pendekatan endonasal endoskopik untuk pembedahan tumor hipofisa meliputi tindakan antara lain dilatasi-diseksi intranasal, manipulasi konkha nasalis, serta frakturasi untuk mencapai daerah sella tursica. Struktur-struktur diatas kaya akan pembuluh darah, dan mudah terjadi perdarahan intraoperatif yang akan berpengaruh pada proses pembedahan dengan mengaburkan anatomi struktur pada lapangan operasi, mengotori lensa endoskopik, sehingga kesulitan operasi menjadi lebih besar.3,10 Situasi demikian akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi antara lain kerusakan otak, orbita, saraf-saraf penting disekitarnya dan bahkan pembuluh darah besar yang ada di sekitar regio sella.10 23 Pertimbangan yang hati-hati pada semua faktor yang berkaitan dengan kontrol perdarahan dilakukan sepanjang periode perioperatif. Pemeriksaan preoperatif sebaiknya meliputi riwayat tendensi perdarahan dari pasien dan keluarga, penggunaan obat-obatan anti platelet dan antikoagulan.10 Pemeriksaan fisik tanda perdarahan (echimosis, purpura), pemeriksaan laboratorium (jumlah dan fungsi trombosit, faal koagulasi) sangat membantu untuk mengidentifikasi adanya tendensi perdarahan dari pasien yang dapat mengganggu pelaksanaan tindakan operasi endoskopik.10 Mediator-mediator inflamasi menyebabkan terjadinya vasodilatasi, transudasi dan edema di mukosa sino-nasal akan memudahkan terjadinya perdarahan intraoperatif sehingga pemberian kortikosteroid preoperatif selain mencegah gangguan hemodinamik akibat supresi hipothalamus-pituitary-adrenal axis (HPA axis) juga menguntungkan dalam mengurangi tendensi perdarahan karena efek anti inflamasiantiedematus yang dimilikinya.10 intraoperatif antara lain: 1. Posisi kepala: elevasi kepala dapat menurunkan tekanan darah rerata pada bagian yang tubuh yang lebih tinggi kurang lebih 2 mmHg tiap 2,5 cm diatas posisi jantung. Posisi elevasi dapat menurunkan aliran vena balik dari ekstremitas bawah sehingga menurunkan total kehilangan darah serta menunjang proses hemostasis lapangan operasi dibandingkan dengan posisi terlentang. Tehnik ini dilakukan secara berlahan untuk menghindari perubahan tekanan darah yang tiba-tiba.10 2. Tehnik ventilasi: tehnik ventilasi dengan tercapainya keaadaan normokapnea atau hipokapnea ringan dianjurkan untuk meminimalkan perdarahan serta optimalisasi lapangan operasi.10 Seperti yang kita ketahui, hiperkapnea menghasilkan vasodilatasi dan peningkatan ADO yang menyebabkan perdarahan menjadi lebih banyak.10 3. Tehnik anestesi: Hipotensi terkontrol dengan obat anestesi inhalasi akan menurunkan tekanan darah arteri melalui vasodilatasi perifer yang disebabkan blokade receptor alfa.3 Namun konsentrasi obat anestesi inhalasi yang tinggi dapat meningkatkan ADO, meningkatkan TIK dan mengganggu otoregulasi serebral.10 Tehnik balans narkotik-anestesi inhalasi dengan suplemen infus propofol banyak dianjurkan untuk menurunkan kebutuhan anestetika inhalasi serta menghindari efek samping yang dapat ditimbulkan.3,10 4. Obat anti hipertensi: obat anti hipertensi seperti labetalol, esmolol merupakan terapi lanjutan bila ketiga tehnik diatas tidak bekerja secara maksimal dalam mengendalikan tekanan darah.3,10 Pengendalian perdarahan intraoperatif juga dapat dilakukan oleh dokter anestesi dengan mengatur tekanan darah dalam lingkup batas bawah dari nilai normalnya yang sering dikenal dengan tehnik hipotensi terkontrol, namun tehnik ini cukup memberikan tantangan karena pembedahan endonasal menimbulkan respon simpatetik yang kuat.3 Beberapa modalitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengendalian perdarahan Hal terpenting dalam melakukan tehnik hipotensi terkontrol adalah memastikan perfusi organorgan penting tetap terjaga serta menghindari efek toksik dari obat yang digunakan.11 Dalam menjaga perfusi selama tekanan darah yang relatif rendah, harus dijaga tekanan pengisian jantung (cardiac filling pressure) dan aliran balik jantung (venous return) tetap adekuat. Derajat hipotensi yang aman bervariasi tergantung riwayat klinis 24 Jurnal Neuroanestesi Indonesia pasien, namun pada umumnya MAP antara 65– 70 mmHg dapat ditoleransi dengan baik karena diyakini dapat mencegah terjadinya hipoperfusi pada organ-organ penting.10,11 Pengawasan tekanan darah intraarterial, pengawasan produksi urine intraoperatif, serta parameter dasar lainnya diperlukan untuk pengawasan adekuasi dari perfusi organ penting selama periode operasi.10,11 Pemberian topikal vasokonstriktor oleh ahli bedah saraf selain dapat melebarkan rongga hidung juga dapat meminimalkan perdarahan intraoperatif. Namun pengawasan status hemodinamik selama pemberian perlu dilakukan karena obat-obatan tersebut dapat memberikan efek samping berupa gejolak hemodinamik.10 Meskipun pendekatan endonasal endoskopik merupakan prosedur minimal invasif dan lebih tidak traumatis namun dihubungkan dengan stimulasi nyeri yang hebat baik pada saat fase nasal, sphenoidal maupun fase sellar.3,12 Besarnya stimulasi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah arterial yang tiba-tiba dan menyebabkan usaha pengendalian perdarahan serta peningkatan kualitas lapangan operasi menjadi lebih sulit.12 Dalam mengendalikan nyeri operasi tersebut diperlukan kedalaman anestesi yang adekuat serta dosis obat analgesik yang cukup. Pada kasus kami hemodinamik relatif stabil meskipun terdapat beberapa lonjakan hemodinamik melebihi target yang diharapkan namun setelah dilakukan penyesuaian dosis obat anestesi dan penambahan fentanyl hal tersebut dapat diatasi. Pada beberapa kasus lain tindakan seperti diatas kadang tidak cukup dalam mengendalikan status hemodinamik sehingga diperlukan penambahan obat anti hipertensi seperti labetalol dan esmolol.12 Penggunaan dexmedetomidine sebagai adjuvan obat anestesi atau melakukan blok ganglion sphenopalatina dalam pengendalian nyeri operasi juga banyak dijumpai di penelitian-penelitian yang lain.3,12,13 Pada saat pengambilan tumor hipofisa dengan cara kuretase, terjadi perubahan mendadak dari status hemodinamik berupa bradikardia, aritmia, dan hipotensi. Perubahan ini menunjukkan dugaan terjadinya refleks trigeminal kardiak trigeminal cardiac reflex/TCR yang dipicu oleh stimulasi pembedahan. Perubahan tersebut terjadi beberapa kali saat kuretase dari adenoma dan hilang ketika stimulasi dihentikan. Setelah komunikasi dengan ahli bedah dilakukan, intensitas kuretase dikurangi maka TCR ini tidak muncul lagi sampai akhir operasi. Refleks trigeminal kardiak didefinisikan sebagai refleks kardiak yang dipicu oleh stimulasi saraf trigeminal dan cabang-cabangnya dimana saja sepanjang perjalanannya dengan reaksi klinis berupa bradikardi, hipotensi (penurunan lebih dari 20% nilai basal), apnea dan gastrik hipermotilitas.14,15 Refleks trigeminal kardiak perifer sudah dikenal sejak awal abad ke 20 dalam bentuk refleks okulo-kardiak akibat stimulasi divisi ophthalmik saraf trigeminal, namun istilah sentral TCR sebagai akibat stimulasi bagian intrakranial baru diperkenalkan oleh Schaller tahun 1999.14,15 Mekanisme yang mendasari sentral TCR saat ini masih belum sepenuhnya dimengerti, namun diduga sama seperti reflek okulo-kardiak yang telah lama diketahui jauh sebelumnya.15 Dengan minimnya pengetahuan fisiologi dari sentral TCR, pengenalan faktor resiko yang diduga berhubungan dengan TCR menjadi sangat penting. Faktor resiko yang saat ini sudah diketahui antara lain hiperkapnea, hipoksia, anestesi dangkal, sifat dari stimulus pembedahan (kekuatan dan lama stimulus).15 Insidens TCR pada pembedahan basis kranii mencapai 8–18%.16 Schaller meneliti 117 pasien yang dilakukan transsphenoidal hipofisektomi untuk mencari penyebab timbulnya TCR. Pada penelitian tersebut didapatkan respon penurunan laju nadi dan tekanan darah saat reseksi tumor bagian lateral dekat sinus kavernosus, sehingga disimpulkan bahwa TCR terpicu oleh struktur yang melewati sinus tersebut (cabang 1 dan 2 dari saraf trigeminal).14 Banyak penulis mengatakan bahwa TCR adalah respon sementara yang hilang dengan dihentikannya stimulus yang dikenakan, namun bentuk yang berat dari TCR (bradikardia hebat, asistol) dapat membahayakan jiwa dan membutuhkan pemberian obat-obatan vagolitik untuk menghentikan reflek tersebut.14,15 Penatalaksanaan TCR dapat diklasifikasikan Penatalaksanaan Perioperatif Hipofisektomi Transsphenoidal: Pendekatan Endoskopik Endonasal sebagai berikut:15 identifikasi faktor resiko, pengawasan ketat parameter kardiovaskular selama prosedur pembedahan, bila TCR terjadi maka tindakan yang dilakukan adalah menghentikan manipulasi pembedahan dan pemberian obat-obatan vagolitik atau adrenalin bila tidak hilang saat stimulus dihentikan atau terjadi bentuk yang berat dari TCR. Kaitan TCR dengan kasus yang kami kerjakan, faktor resiko hiperkapnea dan hipoksia sepertinya bukan merupakan penyebab karena selama periode intraoperatif tidak ditemukan terjadinya tanda-tanda tersebut diatas. Demikian pula keadaan anestesi yang dangkal tidak terjadi karena pengendalian tekanan darah yang dikerjakan membutuhkan kedalaman anestesi yang adekuat. Hal yang mungkin menjadi penyebab adalah intensitas stimulus pembedahan serta lokasi dimana kuretase sedang dilakukan. Komunikasi dengan ahli bedah saraf untuk lebih berhati-hati dan mengurangi intensitas kuretase dari tumor ternyata cukup membantu dalam pengelolaan TCR pada kasus kami tanpa dilakukan pemberian obat-obatan vagolitik. Menjelang akhir pembedahan, ahli bedah saraf akan melakukan evaluasi lapangan operasi untuk melihat adanya sumber perdarahan, dalam hal ini tekanan darah pasien dapat dikembalikan ke lingkup harga normal (sistolik 110–130 mmHg) dengan demikian titik perdarahan dapat diidentifikasi dan pengelolaan perdarahan dapat dilakukan secara optimal.3 Terkadang ahli bedah juga meminta untuk dilakukan manuver valsava dengan meningkatkan tekanan intratorakal sampai 30-40mmHg yang memungkinkan untuk mendeteksi adanya kebocoran cairan serebrospinal (CSS) persisten.3 Smooth emergence dari anestesia merupakan hal yang sangat penting karena mengejan hebat saat masih terintubasi serta batuk yang berlebihan saat ekstubasi dapat menyebabkan perdarahan pada tempat pembedahan serta terlepasnya graft lemak yang sebelumnya terpasang.3 Semua hal yang disebutkan diatas dapat memicu terjadinya komplikasi lanjutan seperti infeksi pascabedah dan kebocoran permanen dari CSS.3 Penggunaan lidokain 1,5 mg/kgBB dapat menekan respon batuk dan mencegah gejolak hemodinamik saat 25 pasien mulai bangun dan dilakukan ekstubasi.17 Pendekatan lain untuk memastikan smooth emergence adalah memastikan pernapasan spontan adekuat saat pasien masih terintubasi dan teranestesi, dilakukan penghisapan intra oral sampai bersih kemudian pasien dilakukan ekstubasi dalam keadaan anestesi yang dalam. Dengan tehnik ini pasien dapat bangun tanpa adanya stimulasi yang disebabkan oleh pipa endotrakeal.3 Penanganan Pascabedah Salah satu fokus penanganan pascabedah adalah kewaspadaan dan pengawasan ketat terhadap terjadinya abnormalitas neuroendokrin termasuk disini antara lain gangguan keseimbangan cairan, diabetes insipidus (DI), Syndrome Inappropriate Anti Diuretic Hormon (SIADH).1 Reseksi hipofisa dengan pendekatan transsphenoidal sangat jarang mengakibatkan DI permanen, namun DI temporer sebagai akibat manipulasi dan edema stalk pituitary dapat muncul pada hari pertama sampai hari ketiga pascaoperasi.7 Karena sebagian besar pasien pascabedah transsphenoidal adalah sadar baik dan alert, maka mekanisme rasa haus yang dimiliki masih intak serta akses masukan cairan peroral yang tidak terganggu sehingga defisit cairan pascabedah, hiperosmolaritas, dan hipernatremia berat jarang terjadi.1 Gejala yang menimbulkan kecurigaan akan terjadinya DI antara lain poliuria (>3mL/kgBB/ jam), urin hipotonis (berat jenis urine <1,005), dan hipernatremia (>145 mmol/L), sehingga pengeluaran urin dan berat jenisnya harus diawasi secara ketat selama periode pascabedah.5 SIADH dilaporkan terjadi pada 9–25% kasus pada pasien yang menjalani pembedahan transsphenoidal.5 Manifestasi klinis biasanya muncul seminggu setelah operasi dan dikenali bila didapatkan pasien dengan produksi urine yang menurun dengan status hidrasi yang normal (sedikit hipervolemia) serta fungsi ginjal yang normal, kadar natrium serum yang rendah (<135 mmol/L), serum osmolalitas yang rendah (<280 mOsm/L).5 Gangguan cairan dan elektrolit lain yang dapat terjadi adalah cerebral salt wasting (CSW). CSW sangat jarang terjadi pada pembedahan transsphenoidal dan harus dibedakan dari SIADH. Sindroma ini ditandai dengan adanya peningkatan 26 Jurnal Neuroanestesi Indonesia produksi urin, hipovolemia, hiponatremia pada pasien dengan lesi serebral.5 Penatalaksanaan gangguan ini adalah mengganti cairan dan natrium yang hilang. Dari keterangan diatas pengawasan ketat dari produksi urin serta kadar elektrolit serum sangat penting untuk menghindari terjadinya penyulit selama periode pascabedah hipofisa.5 yang diberikan preoperatif diteruskan sampai beberapa hari pascabedah kemudian dosis diturunkan sampai nanti diganti dengan dosis oral 20 mg pagi hari dan 10 mg sore hari, namun demikian penggantian sebaiknya didasari oleh kadar kortisol plasma saat jam 08.00 pagi yang diukur pada hari pertama sampai ketiga.5 Disfungsi saraf kranial dan kebocoran cairan serebrospinal Pada awal periode pascabedah pasien harus menjalani pemeriksaan fisik terutama untuk menilai fungsi saraf kranial yang berhubungan dengan pembedahan antara lain pemeriksaan ketajaman penglihatan, pergerakan bola mata dan ada atau tidaknya penglihatan ganda.1,5 Kedekatan beberapa saraf kranialis (saraf kranialis II sampai VI) dengan kelenjar hipofisa dapat menyebabkan terjadinya penyulit yang sangat ditakuti.5 Adanya penemuan gangguan neurologis baru setelah pembedahan menjadi indikasi untuk dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI bahkan dapat dilakukan reeksplorasi di kamar operasi terutama pada kasus dengan defisit penglihatan atau lapangan penglihatan.1,5 Pasien juga ditanya tentang adanya rhinorrhea atau keluarnya cairan melalui hidung sebagai bukti adanya kebocoran CSS. Bila kebocoran CSS terjadi terus menerus dan terlihat bila pasien menunduk serta berhubungan dengan nyeri kepala maka diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Cairan dikumpulkan untuk pemeriksaan laboratorium dan bila terbukti tejadi kebocoran maka terapi terbaik adalah melakukan tindakan operatif untuk menutup defek.1,5 Keluhan tersering yang diungkap oleh pasien setelah pembedahan transsphenoidal adalah nyeri kepala. Keluhan ini dapat diobati dengan NSAID seperti ketorolac atau parasetamol.1 Narkotik dapat diberikan namun dengan penuh kehatihatian terutama pada pasien dengan riwayat obtructive sleep apnea.1 Mual dan muntah juga merupakan penyulit pascabedah yang cukup sering terjadi sehingga profilaksis farmakologis seperti pemberian golongan ondansentron merupakan tindakan yang bijaksana.1 Pendekatan permasalahan endokrin periode pascabedah dilakukan secara tim yang terdiri dari ahli bedah, ahli anestesi, dan ahli endokrin.5 Kortikosteroid IV. Simpulan Pasien dengan tumor hipofisa memerlukan pendekatan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi antara ahli bedah, ahli anestesi, dan ahli endokrin. Penatalaksanaan perioperatif yang optimal tergantung dari pengertian mendalam dari penyakit tersebut, pengetahuan tentang proses pembedahan hipofisa, pengertian tentang potensi komplikasi yang dapat terjadi beserta penanganannya. Dengan makin maraknya pembedahan endoskopik basis kranii beserta kemajuan lain yang menyertainya maka penatalaksanaan neuroanestesi harus disesuaikan dengan kebutuhan pembedahan tersebut. Pengetahuan dan tindakan anestesi yang berhubungan dengan pembedahan endoskopik dapat menjadikan dokter anestesi terus memberi kontribusi yang besar dalam kemajuan penanganan penyakit yang menggunakan tehnik endoskopik. Daftar Pustaka 1. Nemergut EC, Dumont AS, Barry UT, Laws ER. Perioperative management of patients undergoing transsphenoidal pituitary surgery. Anesth Analg 2005;101:1170–81. 2. Uygur ER, Levent G, Saka C, Belen D, Yigitkanli K, Simsek S, et.al. Sublabial transseptal approach to pituitary adenomas with special emphasis onn rhinological complications. Turkish Neurosurgery 2008; 18(4): 425–30. 3. Kabil M, Shahinian HK. Anesthetic considerations in endoscopic skull base surgery. Dalam: Shahinian HK, eds. Endoscopic skull base surgery a Penatalaksanaan Perioperatif Hipofisektomi Transsphenoidal: Pendekatan Endoskopik Endonasal comprehensive guide with illustrative cases. Tontowa: Humana press; 2008, 5–9. 4. Santos ARL, Neto RM, Veiga JC, Viana J, Scaliassi NM, Lancellotti CL. Endoscopic endonasal transsphenoidal approach for pituitary adenomas. Arq Neuropsiquiatr 2010;68(4):608–12. 5. Horvat A, Kolak J, Gopcevic A, Ilej M, Gnjidic Z. Anesthetic management undergoing pituitary surgery. Acta Clin Croat 2011; 50:209–16. 6. Smith M, Hirsch NP. Pituitary disease and anesthesia. Br. J. Anesth.2000; 85(1):3–14. 7. Matjasko MJ. Anesthetic consideration in patients with neuroendocrine disease. Dalam: Cotrell JE, Smith DS, eds. Anesthesia and Neurosurgery. Misouri: Mosby; 2001, 591– 609. 8. Sivanaser V, Manninen P. Preoperative assessment of adult patients for intracranial surgery. Anesthesiology Research and Practice 2010;10 9. Zada G, Woodmansee WW, Iuliano S, Laws ER. Perioperative management of patients undergoing transsphenoidal pituitary surgery. Asian Journal of Neurosurgery 2010; 5: 1–6. 10. Thongrong C, Kasemsiri P, Carrau RI, Bergese SD. Control of bleeding in endoscopic skull base surgery. Current concepts to improve 27 hemostasis. ISRN Surgery 2013;10. 11. Marshall WK, Mostrom JL. Neurosurgical diseases of the spine and spinal cord: anesthetic considerations. Dalam: Cotrell JE, Smith DS, eds. Anesthesia and Neurosurgery. Misouri: Mosby; 2001, 557–90. 12. Ali AR, Sakr SA, Rahman AS. Bilateral sphenopalatine ganglion block as adjuvant to general anaesthesia during endoscopic trans-nasal resection of pituitary adenoma. Egyptian Journal of Anaesthesia 2010; 26: 273–80. 13. Brady T. Anesthetic management of pituitary tumor resection with dexmedetomidine. AANA Journal. 2010; 78(2). 14. Abdulazim A, Stienen MN, Eshkevari PS, Prochnow N, Sandu N, Bohluli B, et al. Trigeminocardiac reflex in neurosurgery. Current knowledge and prospects, viewed 23 October 2014, http://www.intechopen.com. 15. Arasho B, Sandu N, Spiriev T, Prabhakar H, Schaller B. Management of the trigeminocardiac reflex. Facts and own experience. Neurology India. 2009; 57(4): 375–80. 16. Amirjamsidhi A, Abbasioun K, Etezadi F, Ghasemi SB. Trigeminocardiac reflex in neurosurgical practice. Surgical Neurology International. 2013;4:126. Penanganan Anestesi pada Operasi Olfactory Groove Meningioma Silmi Adriman*), Dewi Yulianti Bisri**), Sri Rahardjo***), A. Himendra Wargahadibrta**) Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh, **)Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran–Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, ***)Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada–Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta *) Abstrak Angka kejadian Olfactory Groove Meningioma adalah 10–15% dari total meningioma yang terjadi di intrakranial, dimana tumor ini berasal dari basis cranii anterior. Manifestasi klinis berupa penurunan penciuman akibat terjepitnya saraf olfaktori dan apabila tumor cukup besar dan menekan saraf optikus, pasien akan mengalami penurunan penglihatan, bahkan buta. Pada kasus ini dilaporkan seorang wanita berusia 38 tahun, GCS 15 dengan diagnosis olfactory groove meningioma akan dilakukan operasi kraniotomi untuk pengangkatan tumor. Pasien datang dengan keluhan tidak bisa melihat dan tidak bisa mencium bebauan. Hasil CT Scan menunjukkan gambaran hiperdens berbentuk enhancing lesion pada regio frontal. Pasien dilakukan tindakan anestesi umum dengan intubasi. Induksi dengan propofol, fentanyl, lidokain dan vecuronium. Pengelolaan cairan perioperatif dengan ringerfundin, manitol dan furosemid. Pembedahan dilakukan selama 6 jam. Pasca bedah, pasien dirawat di Unit Perawatan Intensif (Intensive Care Unit/ ICU) selama 2 hari sebelum pindah ruangan. Kata Kunci: Olfactory groove meningioma, tumor supratentorial JNI 2015;4 (1): 28–33 Anesthesia Management for Olfactory Groove Meningioma Removal Abstract Olfactory Groove Meningioma, a type of meningioma is primarily derived from anterior cranial base, manifest in approximatelly 10-15% of meningioma cases. Clinical manifestations include smelling disorder and blurred vision or even cause blindness due to compression of the tumor to the optic nerve. This case reported a 38 years old woman with GCS 15 and diagnosed with olfactory groove meningioma, planned for a craniotomy tumor removal under general anesthesia. She was admitted to hospital due to blurred vision and smelling disorder. Computed Tomography (CT) scan showed a enhancing lesion in the frontal region. Induction of anesthesia was done using propofol, fentanyl, lidocaine and vecuronium. Ringerfundin, manitol and furosemide were used for perioperative fluid management. The surgery was conducted for 6 hours. Patient was managed in the Intensive Care Unit post operatively for 2 days prior to ward transfer Key words: Olfactory groove meningioma, supratentorial tumor JNI 2015;4 (1): 28–33 28 Penanganan Anestesi pada Operasi Olfactory Groove Meningioma I. Pendahuluan Tumor intrakranial terdiri dari tumor supratentorial dan infratentorial dimana pembatasnya adalah tentorium. Salah satu jenis tumor supratentorial adalah meningioma.1 Salah satu jenis tumor meningioma adalah Olfactory Groove Meningioma (OGM) yang berasal dari garis tengah fossa anterior pada dasar crimbiformis di etmoidalis.2 Olfactory Groove Meningioma termasuk 10–15% dari semua meningioma intrakranial. Olfactory Groove Meningioma tumbuh secara perlahan, sering bilateral daripada unilateral, bersifat asimetris dan dapat mengkompresi lobus frontal secara progresif.1 Olfactory Groove Meningioma dapat mengenai sella dan jika ukurannya cukup besar dapat mempengaruhi penglihatan dengan cara menekan saraf optik dan asma optikum. Manifestasi klinis lain berupa sakit kepala disertai dengan anosmia dan perubahan kepribadian.3 Masalah psikiatri bahkan dapat muncul secara berkepanjangan sebelum terjadi defisit neurologis. Kejang, hemiparese dan afasia juga dapat terjadi pasien dengan OGM.4 Olfactory groove meningioma biasanya terkait erat dengan tumor sellae tuberculum, tetapi manifestasi klinis dan outcome pembedahannnya berbeda. Hal ini berkaitan dengan Chiasma optikum, tumor tuberculum sellae dapat menunjukkan gejala klinis dini. Defisit visual dapat terjadi bahkan jika tumorrnya kecil.5 Olfactory groove meningioma merupakan salah satu tumor intrakranial yang terbesar yang bisa kita lihat. Brain computer tomography (CT) scan dan magnetic resonance imaging (MRI) dapat menunjukkan lokasi meningioma di pertengahan subfrontal, sejauh mana tumor dan edema otak yang terjadi disekitarnya. Magnetic Resonance Imaging juga dapat mendefinisikan hubungan tumor dengan saraf optik dan arteri serebral anterior, serta ekstensi ke dalam sinus etmoidalis. Reseksi bedah merupakan pilihan pengobatan untuk kebanyakan OGM, tetapi ukuran tumor, vaskularisasi, struktur saraf yang terganggu dan invasi tumor ke dalam paranasal meningkatkan resiko pada saat pembedahan.2 Pengelolaaan anestesi pada kasus tumor supratentorial disini 29 adalah menghindari terjadinya cedera otak sekunder dengan cara pengelolaan intrakanial dengan mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, mencegah terjadinya kejang, vasospasme pembuluh darah, dan herniasi. Pada sistemik mencegah terjadinya hiperkapni, hipoksemi, hipotensi, hipertensi,hipoglikemi, hiperglikemi, hiposmolaliti, menggigil dan hipertermi. Oleh karena itu dokter anestesi perlu mengerti patofisiologi tekanan intrakranial, perfusi cerebral dan CMRO2, sehingga dapat mengurangi terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, otak yang bengkak dan tegang selama periode perioperatif.6 II. Kasus Anamnesa Perempuan, 38 tahun datang ke Poliklinik Bedah Saraf dengan keluhan tidak bisa melihat pada kedua mata sejak 8 bulan sebelum masuk rumah sakit. Awalnya pasien merasa kabur dan mengalami penurunan penglihatan dan makin lama pasien tidak bisa melihat sama sekali dalam 3 bulan ini. Pasien juga mengeluhkan sakit kepala dan tidak bisa mencium bebauan atau wewangian yang ada di sekitarnya. Selama nyeri kepala dan keluhan tidak bisa melihat tersebur, pasien sering marah-marah yang tidak semestinya, perilaku pasien juga cenderung berubah semenjak keluhan tersebut muncul. Pemeriksaan Fisik Pada pemeriksaan didapatkan GCS 15, hemodinamik stabil, pupil isokor dan diameter normal di kedua mata, visus tidak dinilai, tidak dijumpai kelemahan anggota gerak atas maupun bawah. Pemeliharaan Laboratorium Hasil dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan Hb 14,6 gr/dl; Ht 34%; Leukosit 14.300/ul; Trombosit 477.000 /ul; LED 65 mm/ jam; CT/BT 7’/2’; Ureum/ Kreatinin 21/0,8 mg/ dl; Asam urat 7,5 mg/dl; Gula Darah Acak 155 mg/dl; Na/K/Cl 141/4,3/105 meq/L. Hasil CT-Scan menunjukkan terlihat gambaran hiperdens homogen berbentuk enhancing 30 Jurnal Neuroanestesi Indonesia jam dengan total perdarahan 500 cc. Gambar 1. CT-scan Kepala Kontras Potongan Axial sebelum Operasi lesion pada regio frontal yang dicurigai massa seperti olfactory groove meningioma. Pasien ini dilakukan kraniotomi untuk pengangkatan massa. Berikut hasil CT-Scan sebelum operasi Pengelolaan Anestesi Pasien dilakukan induksi dengan pemberian fentanyl 150 ug titrasi, lidokain 60 mg, propofol 90 mg titrasi dan vecuronium 4,5 mg. Satu menit sebelum tindakan intubasi diberikan tambahan propofol 30 mg. Intubasi dilakukan dengan menggunakan laringoskope Macintosh dengan pipa endotrakheal non kinking nomor 7, kedalaman 18 cm pada tepi bibir. Untuk pemeliharaan anastesi diberikan sevoflurane dengan udara dan O2 (50:50), fentanyl kontinyu 1–2 µg/Kg/jam dan vecuronium kontinyu 0,06 mg/KgBB/jam. Pengelolaan cairan selama tindakan digunakan cairan ringerfundin dan diuretik (manitol dan furosemid). Pemantauan selama operasi dilakukan evaluasi terhadap tekanan darah sistolik, diastolik, end tital CO2, saturasi oksigen, gelombang EKG, pemasangan stetoskop prekordial, produksi urin melalui kateter urin dan insersi pipa nasogastrik. Pembedahan dilakukan dengan pendekatan subfrontal. Saat periosteum dibuka duramater tampak slack brain, dilakukan eksisi tumor dengan bantuan miroskop. Dilakukan penutupan durameter, kulit tutup lapis demi lapis dengan meninggalkan sebuah vacum drainage setelah operasi selesai. Pembedahan dilakukan selama 6 Pascabedah Pascabedah, pasien dirawat di Unit Perawatan Intensif (Intensive Care Unit/ ICU) selama 2 hari sebelum pindah ruangan. Hari pertama di ICU, pasien masuk pukul 20.00 dan dalam kontrol ventilator (pressure control, FiO 40 %, RR 12 x/menit, P-inspirasi 14, PEEP 3, Vt 270–320 cc, Sat 99%) selama 6 jam dan dilakukan weaning bertahap serta eksubasi pukul 09.00 keesokan hari. Selama di ICU pasien mendapatkan sedasi fentanyl 25 µg/jam. Satu jam sebelum ekstubasi fentanyl dihentikan. Terapi lain di ICU adalah cefriaxone, ranitidin, deksametason, metoclopramide, mannitol, asam traneksamat, metamizole, Phenobarbital dan vitamin C. Pemeriksaan laboratorium pascabedah di ICU didapatkan Hb 11,6 gr/dl; Ht 35,4%; Leukosit 21.160 /ul; Trombosit 334.000 /ul; Ureum/ Gambar 2. Hasil CT-scan Non Kontras setelah Dilakukan Operasi Kreatinin 15,5/0,63 mg/dl; Gula darah acak 163 mg/dl; Na/K/Cl 136/3,34/113 meq/L. Hari kedua di ICU, pasien bernapas spontan, kondisi haemodinamik stabil, status neurologis tidak ada penurunan, pasien dipindahkan ke ruangan. III. Pembahasan Olfactory groove meningioma yang disajikan dalam laporan kasus ini adalah penyakit yang Penanganan Anestesi pada Operasi Olfactory Groove Meningioma langka dan terjadi sekitar 10% dari semua jenis meningioma. Olfactory groove meningioma berasal dari basis kranii anterior, umumnya di tulang ethmoid, planum sphenoidale atau frontospenoidal. Olfactory groove meningioma menerima suplai dari pembuluh darah arteri ethmoidal anterior dan posterior. Bagian terlemah dari dasar tengkorak membuatnya rentan terhadap infiltrasi tulang yang mendasarinya. Hal ini juga dapat membuat tumor meluas ke sinus paranasal dan rongga hidung, menekan saraf penciuman di bagian lateral dan posterior kiasma optikus. Penekanan pada lobus frontal juga menimbulkan perubahan dalam fungsi kognitif dan perilaku pasien.2,4 Tumor ini tumbuh secara lambat sehingga gejala biasanya baru muncul jika ukuran tumor sudah besar dan mengkompresi jaringan otak. Jika tumor dapat diakses, pengobatan dilakukan dengan pembedahan pengangkatan tumor. Terapi radiasi atau radiosurgery bisa dilakukan jika ada tumor yang tersisa atau jika operasi tidak memungkinkan.2 31 50–150 mmHg, karena jika MAP kurang dari dari 50 mmHg maka dapat menyebabkan iskemi serebral dan jika MAP lebih dari 150 mmHg akan menyebabkan perdarahan dan edema serebral. Stimulasi simpatis dan parasimpatis harus dicegah karena dapat menyebabkan perubahan aliran darah otak dan mengeser kurva autoregulasi. Pada operasi tumor otak pemberian kadar oksigen tinggi dengan PaO2 >200 mmHg harus dihindari karena dapat terjadi vasokontriksi serebral dan menyebabkan iskemi jaringan otak. Taget PaO2 antara 100 sampai 200. mmHg.15 Target PaCO2 25–30 mmHg untuk menurunkan aliran darah otak, tekanan PaCO2 dibawah 20 mmHg harus dihindari karena dapat menyebabkan vasokontriksi dan iskemi jaringan otak. Bila Hematokrit meningkat di atas nilai normal, aliran darah otak akan menurun karena ada peningkatan viskositas darah. Hipotermi memperlambat metabolisme serebral sehingga dapat menurukan aliran darah ke otak.15 Prosedur operasi untuk pengangkatan tumor intrakranial seperti ini membutuhkan teknik anestesi yang khusus. Seorang ahli anestesi dituntut untuk dapat melakukan induksi yang baik dan memonitor kondisi pasien selama operasi untuk mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan intrakranial dapat menyebabkan perubahan sistemik seperti hipertensi dan perubahan irama jantung, serta dapat menyebabkan spasme arteri serebral dan berujung pada serebral iskemi dan serebral infark.6 Tugas anastesi pada kasus ini selain memberikan fasilitas untuk tindakan pembedahan juga harus mampu mengendalikan tekanan intrakranial, volum otak dan melindungi jaringan saraf dari iskemi dan mengurangi perdarahan selama pembedahan. Maka perlu dilakukan berbagai tindakan dan pemberian obat untuk mengendalikan tekanan intrakranial, serta melakukan proteksi otak.15 Kasus ini menggunakan kombinasi propofol dan fentanyl sebagai induksi. Propofol pertama kali dikenalkan sebagai obat anestesi intravena pada tahun 1977 oleh Kay dan Rolly.7 Propofol telah menjadi obat pilihan selama kraniotomi. Propofol secara signifikan menurunkan aliran darah otak (sebanyak 30%) dan tekanan intrakranial, menurunkan metabolisme otak (CMRO2 sebanyak 30%) dan meningkatkan tekanan perfusi serebral pada pasien yang menjalani kraniotomi untuk tumor otak.6,8 Selain itu, propofol juga memiliki efek neuroprotektif. Mekanisme neuroprotektif mencakup penurunan metabolisme otak, aktivitas antioksidan, aktivasi reseptor gammaaminobutyric acid (GABA), mencegah kerusakan mitokondria dan interaksinya dengan sistem endocannabinoid.9 Selain itu, pemberian fentanyl yang dikombinasikan dengan propofol juga dapat mengurangi respon stres selama intubasi dan mempercepat proses pemulihan setelah tindakan pembedahan selesai dilakukan.7 Untuk mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu autoregulasi, PaCO2, PaO2, simpatis-parasimpatis, hematokrit dan temperatur. Autoregulasi dipertahankan konstan pada MAP Pada kasus ini, sevoflurane digunakan sebagai anestesi inhalasi yang menggunakan air dan O2 dengan perbandingan 50:50. Sevoflurane dipilih karena memiliki kelarutan dalam darah yang cepat (0.63) serta uptake dan eliminasi 32 Jurnal Neuroanestesi Indonesia yang cepat. Selain memiliki efek vasodilatasi pembuluh darah yang paling rendah (jika dibandingkan dengan isoflurane, ethran dan halothan), sevoflurane juga memiliki efek neuroprotektif berupa antinekrotik dan antiapoptosis. Efek neuroprotektif ini dimediasi oleh mitochondrial KATP channel (mitoKATP) yang mengganggu mekanisme kematian neuronal.6,10 Sebelum intubasi dilakukan, pasien juga diberikan lidokain secara intravena dengan dosis 1–1,5 mg/ kgBB.6 Lidokain merupakan salah satu anestesi lokal yang bekerja dengan cara memblokir saluran Na, menghambat influks Na dan mengurangi cedera pascatraumatik. Lidokain diberikan untuk mencegah terjadinya gejolak hemodinamik; menghambat kenaikan tekanan darah dan frekuensi nadi, serta mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial saat intubasi dilakukan. Lidokain yang diberikan dalam kasus ini sebanyak 60 mg intravena saat sebelum intubasi.11 Obat pelumpuh otot yang digunakan pada kasus ini adalah vecuronium. Vecuronium termasuk ke dalam kategori obat pelumpuh otot nondepolarisasi. Vecuronium digunakan dengan dosis 0,1 mg/ kgBB, memiliki waktu onset 2,3 menit dan dengan waktu pemulihan 45–80 menit.12 Vecuronium diketahui dapat mencegah terjadinya edema serebral dengan tidak meningkatkan aliran darah otak sehingga baik diberikan pada pasienpasien yang menjalani pembedahan intrakranial.6 Pengelolaan cairan pada pasien bedah saraf sangat penting. Selama tindakan pembedahan, diperlukan keseimbangan yang baik antara pemeliharaan perfusi jaringan dan meminimalisasi terjadinya edema serebral. Pengelolaan cairan dilakukan untuk menjaga keadaan normovolemia dan osmolalitas serum normal dengan cara mempertimbangkan kebutuhan dan pergantian cairan yang keluar melalui urin.13 Pada kasus ini digunakan cairan ringerfundin yang bersifat sedikit hiperosmolar (osmolaritas 304 mOsm/L) sehingga dapat menarik air dari interstitial otak. Ringerfundin lebih dipilih dibandingkan RL atau NaCl 0,9% untuk mencegah terjadinya hiperkloremik asidosis dan peningkatan tekanan intrakranial, serta mencegah terjadinya edema serebral saat resusitasi cairan.14 Diuretik selama pembedahan intrakranial umum digunakan sebagai terapi kenaikan tekanan intrakranial. Diuretik yang digunakan pada kasus ini adalah kombinasi furosemid dan manitol. Furosemid merupakan salah satu diuretik kuat yang dapat diberikan dengan dosis 0,5–1 mg/ kgBB dengan onset 30 menit. Sedangkan manitol merupakan diuretik osmotik yang bekerja dengan cara menarik cairan serebral masuk ke dalam intravaskular dan menurunkan viskositas darah sehingga menurunkan aliran darah otak dan tekanan intrakranial selama pembedahan.6,13 Posisi pasien menjadi faktor penting pada pengangkatan tumor intrakranial. Tujuan utamanya adalah menempatkan aksis utama tumor dengan dasar optimal akses dari operator. Namun, berbagai posisi yang digunakan dapat memiliki banyak implikasi bagi ahli anestesi. Pada kasus ini digunakan posisi supine dengan reverse trendelenburg atau head up sekitar 15– 30°. Posisi ini efektif dalam mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial akut dengan memperhatikan tekanan rata-rata arteri (mean arterial pressure/ MAP) dan tekanan perfusi serebral (cerebral perfusion pressure/ CPP). Penelitian juga melaporkan bahwa posisi reverse trendelenburg 10° terbukti dapat mengurangi tekanan intrakranial dan MAP dengan perubahan minimal pada CPP.13,15 IV. Simpulan Telah dilaporkan sebuah laporan kasus, seorang perempuan berusia 38 tahun dengan diagnosa Olfactory groove meningioma. Pasien datang dengan gangguan penciuman dan penurunan penglihatan. Prosedur pengangkatan tumor telah berhasil dilakukan dengan anestesi umum dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi selama operasi. Daftar Pustaka 1. Kesari S, Saria M, Lai A. American Brain Tumor association. Meningioma. 2012. Diunduh dari http://www.abta.org/secure/ meningioma-brochure.pdf 2. Ciuera AV, Lencean SM, Rizea RE, Brehar Penanganan Anestesi pada Operasi Olfactory Groove Meningioma FM. Olfactory groove meningiomas: a retrospective study on 59 surgical cases. Neurosurg Rev 2012;35:195–202. 3. Fox D, Khurana VG, Spetzler RF. Olfactory Groove/ Planum Sphenoidale Meningiomas. Meningioma textbook. 2012, 327–32 4. Liu JK, Christiano LD, Patel SK, Tubbs RS, Eloy JA. Surgical nuances for removal of olfactory groove meningiomas using the endoscopic endonasal transcribriform approach. Neurosurg Focus, 2011; 30 (5):E3. 5. Cross LJ. Australia Brain Tumor Information. 2010. Diunduh dari http://www.btai.com.au/ images/factsheetpdfs/Page%2010to11.pdf 6. Cottrell JE, Young WL, Cottrell and Young’s Neuroanesthesia. 5th ed. Mosby; 2010. 7. Bisri T. Dasar-Dasar Neuroanestesi, Edisi ke2. Bandung: Saga Olah Citra. 2008, 1–74. 8. Bajwa SJS, Bajwa SK, Kaur J. Comparison of two drug combinations in total intravenous anesthesia: propofol-ketamine and propofolfentanyl. Saudi J Anaesth. 2010; 4(2): 72–79. 9. Rasmussen M, Juul N, Christensen SM, Jόnsdόttir KY, Gyldensten C, VesteergaardPoulsen P, et al. Cerebral blood flow, blood volume and mean transit time response to propofol and indomethacin in peritumor and contralateral brain regions. Anesthesiology. 2010; 112: 50–56. 33 10. Sakabe T, Matsumoto M. Effects of anesthetic agents and other drugs on cerebral blood flow, metabolism and intracranial pressure. Dalam: Cottrell and Young’s Neuroanesthesia, 5th ed. 2010, 78–90. 11. Adamezyk S, Robin E, Simerabet M, Kipnis E, Tavernier B, Vallet B, Bordet R, et al. Sevoflurane pre- and post-conditioning protect the brain via the mitochondrial KATP channel. Br. J Anaesth. 2010; 104(2): 191–200. 12. Kuzak N, Harrison DW, Zed PJ. Use of lidocaine and fentanyl premedication for neuroprotective rapid sequence intubation in the emergency department. Can J Emerg Med. 2006; 8(2): 80–84. 13. Fang Y, Zhang H, Liu W, Li Y. A comparison of three inductions regiments using succinylcholine, vecuronium, or no muscle relaxant: impact on the intraoperative monitoring of the lateral spread response in hemifacial spasm surgery: study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2012; 13(160). 14. Kulshrestha A, Bajwa SJS. Anaesthetic considerations in intracranial neurosurgical patients. J Spine Neurosurg. 2013; S1. 15. Bisri T. Penanganan Neuroanestesia dan Critical Care: Cedera Otak Traumatik. Bandung: FK Unpad. 2012, 209–28. 16. Dinsmore J. Anaesthesia for elective surgery. Br J Anaesth. 2007; 99: 68–74. Penatalaksanaan Perioperatif Cedera Kepala Traumatik Berat dengan Tanda Cushing Wahyu Sunaryo Basuki*), Bambang Suryono**), Siti Chasnak Saleh***) *)Departemen Bedah Gawat Darurat dan Anestesi Rumah Sakit Angkatan Darat Brawijaya Surabaya, **) Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada–RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ***)Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga–RSUD Dr. Soetomo Surabaya Abstrak Cedera kepala traumatik merupakan masalah utama kesehatan dan sosial ekonomi, penyebab kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Meskipun ada cara diagnosis yang canggih dan penatalaksanaan yang mutakhir, prognosis pasien cedera kepala traumatik masih tetap jelek. Derajat keparahan cedera primer merupakan faktor utama yang menentukan luaran; sedangkan cedera sekunder karena hipotensi, hipoksemia, hiperkarbia, hiperglikemia, dan hipoglikemia setelah cedera awal menyebabkan kerusakan lebih lanjut dari jaringan otak dan memperjelek luarannya. Cedera kepala traumatik berat adalah cedera kepala dengan glasgow coma scale score antara 3 sampai 8. Tanda Cushing adalah tanda kenaikan tekanan intrakranial yang tinggi dan tanda herniasi. Penatalaksanaan cedera kepala difokuskan pada pengelolaan dan pencegahan cedera sekunder. Seorang wanita 54 tahun, berat badan 50 kg, tinggi badan 155 cm dibawa ke unit gawat darurat rujukan dari rumah sakit lain karena kecelakaan lalu lintas, jatuh dari sepeda motor. Dilakukan resusitasi dan stabilisasi; jalan nafas bebas; laju nafas 10–16x/ menit; tekanan darah 180/100 mmHg; laju nadi 50–55x/menit; skor GCS E2M2V1; pupil kiri dan kanan isokor 3 mm, reaksi cahaya lambat. Pemeriksaan CT-Scan menunjukkan perdarahan intraserebral frontal basal kanan, ukuran 7,5 x 4,4 x 2,2 cm, perkiraan volume 40 cc, dan perdarahan kiri kecil; perdarahan subarahnoid mengisi sulkus temporal kanan; midline shift ke kiri 2,6 mm; dan edema serebri luas. Segera dilakukan kraniotomi evakuasi perdarahan untuk menyelamatkan pasien. Penatalaksanaan cedera kepala perioperatif meliputi evaluasi yang cepat, resusitasi pembedahan dini, dan tatalaksana terapi intensif dapat memperbaiki luaran penderita cedera kepala Kata Kunci: Cedera kepala traumatik berat, penatalaksanaan perioperatif, tanda Cushing JNI 2015;4 (1): 34–42 Perioperative Management of Severe Brain Injury with Cushing’s Sign Abstract Traumatic brain injury (TBI) is a major health and socioeconomic problem, as well as a common cause of death and disabilty worldwide. Despite modern diagnostic tools and advancement in the treatment, prognosis of TBI patients remains poor. Severity of primary injury is the determining factor of outcome in TBI. Secondary injury, caused by hypotension, hypoxemia, hypercarbia, hyperglycemia, and hypoglycemia, following primary injury can cause further brain damage and worsen patient’s outcome. Severe TBI is brain injury with Glasgow Coma Scale score (GCS) of 3 to 8. Cushing’s sign is a sign of high intracranial pressure and herniation. Management of TBI is focused on managing and preventing secondary injury. A 54 years-old female patient (50 kg, 155 cm) was admitted ro the emergency unit due to motorcycle accident. Upon resuscitation and stabilization, the airway was secured, respiratory rate 10-16 times/minute, blood pressure 180/100 mmHg, pulse 50-55 beats/ minute, and GCS E2M2V1. Pupils were isochoric, with 3 mm diameter. Direct light reflex was slow. CT-scan revealed a 40 cc right frontobasal intracranial hemorrhage with a size of 7.5 x 4.4 x 2.2 cm3; subarachnoid hemorrhage was occupying the right temporal sulcus; 2.6 mm midline shift to the left; and extensive cerebral edema. Craniotomy for evacuation of intracranial hematoma was performed. Perioperative managements including rapid evaluation, early surgical resuscitation, and intensive care can improve patients’ outcome. Key words: Cushing’s sign, perioperative management, severe traumatic brain injury 34 JNI 2015;4 (1): 34–42 Penatalaksanaan Perioperatif Cedera Kepala Traumatik Berat dengan Tanda Cushing I. Pendahuluan Cedera kepala traumatik adalah salah satu masalah kesehatan utama dan masalah sosialekonomi yang menjadi penyebab kematian pada dewasa maupun anak-anak, serta kecacatan di dunia. Di Amerika Serikat, lebih dari 1,7 juta orang mengalami cedera kepala setiap tahunnya dan sekitar 290 ribu orang menjalani perawatan, 51.000 kasus kematian serta 80.000 orang mengalami cacat permanen. Di Uni Eropa menyebabkan sekitar 1 juta orang menjalani perawatan serta 50 ribu kematian dan sekitar 10 ribu orang menjadi cacat. Cedera kepala traumatik banyak terjadi pada usia dewasa 15–19 tahun, anak-anak usia 0–4 tahun dan usia tua 65 tahun atau lebih. Pria lebih banyak daripada wanita dengan penyebab utama adalah jatuh atau kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan bermotor. Cedera kepala diklasifikasikan menurut derajatnya dengan skor Glasgow Coma Scale pasca resusitasi, yaitu cedera kepala ringan (GCS 13–15), cedera kepala sedang (GCS 9–12), dan cedera berat (GCS <8). Perkembangan penatalaksanaan pasien dengan cedera kepala prahospital dan perawatan intensiv telah meningkat dan penatalaksanaannya berbasis bukti-bukti kejadian yang ada.1 Pedoman penatalaksanaan tersebut telah dikembangkan oleh Brain Trauma Foundation (BTF) pada tahun 1996 dengan menerbitkan pedoman penatalaksanaan cedera kepala traumatik berat. Pedoman tersebut direvisi kedua dan ketiga yang dipublikasikan pada tahun 2000 dan 2007.1,3 Patofisiologi dari cedera kepala meliputi cedera kepala primer dan sekunder.Cedera kepala primer adalah kerusakan yang disebabkan trauma mekanis terhadap tulang kepala dan jaringan otak, sedangkan cedera sekunder merupakan proses komplek yang mengikuti dan memperberat cedera primer yang terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari. Penyebab cedera sekunder bisa intrakranial bisa ekstrakranial atau sistemik. Penyebab intrakranial misalnya epidural, subdural, intraserebral hematoma, edema serebral, peningkatan ICP. Penyebab sistemik seperti hipoksemi, hiperkapni, 35 hipotensi, anemi, hipertensi, hipoglikemi, hipertermi, sepsis. Penatalaksanaan cedera kepala difokuskan pada pencegahan dan pengelolaan cedera sekunder.1- 4 Hal ini melandasi penatalaksanaan mutakhir cedera kepala yang terdiri dari resusitasi dan stabilisasi pra rumah sakit dan unit gawat darurat, pembedahan serta penatalaksanaan terapi intensif.1-3 II. Kasus Wanita 54 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 155 cm dibawa ke unit gawat darurat rujukan dari rumah sakit lain. Penderita mengalami kecelakaan lalu lintas jatuh dari motor 8 jam sebelum datang ke UGD. Pemeriksaan Fisik Airway: bebas, terpasang mayo. Breathing: 10–16x/menit tidak ada jejas di leher dan dada. Gerak dada simetris kecil dan lemah, suara nafas vesikuler, tidak ada ronkhi maupun wheezing. Circulation: perfusi hangat kering, merah, tekanan darah 180/95 mmHg, laju nadi 50-55x/ menit. Disability: kesadaran pasca resusitasi E2 M2 V1 pemeriksaan pupil kanan dan kiri 3 mm, reaksi lambat, terdapat lateralisasi, bagian kiri tubuh lebih aktif, ada hematom di belakang kepala, ada jejas di bahu kiri dan pergelangan tangan kiri dan paha kiri. Jejas tempat lain tidak ada. Bagian tubuh lain tidak ada kelainan. Segera dilakukan tindakan resusitasi dan stabilisasi. Diberikan O2 dengan ventilasi bag and mask. Posisi head up sudah tepasang colar neck, diberikan cairan Ringerfundin. Dilakukan intubasi di unit gawat darurat. Intubasi cepat dengan obat-obatan propofol 2 mg/kg, vecuronium 5 mg, lidokain 1,5 mg/kg, fentanyl 50μg. Posisi pasien head up, posisi Inline dengan colar neck dilepas bagian depan. Monitor yang digunakan untuk tekanan darah non invasif, EKG, pulse oxymeter. Pada waktu intubasi, tekanan darah 160/90 mmHg, laju nadi 79x/menit, saturasi 98–100%, EKG irama sinus, diberikan manitol 200 ml dalam 30 menit, cairan rumatan Ringerfundin. Catatan dari pemeriksaan 36 Jurnal Neuroanestesi Indonesia di rumah sakit yang pertama didapatkan RR 30 x/menit, N 105 x/menit, tekanan darah 176/95 mmHg dan GCS E3 M2 V1. Empat puluh lima menit kemudian kejang selama 2 menit, diberi diazepam 10 mg intravena. Satu jam kemudian kejang lagi mendapat diazepam 5 mg intravena. Pemberian O2 8 l/menit, cairan RL 1000 ml. Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan CT-Scan didapatkan perdarahan Intra Cerebral Frontal Basal kanan dengan ukuran 7,5 x 4,4 x 2,2 cm dengan perkiraan volume 40 cc, dan kiri ukuran kecil. Perdarahan Subarahnoid mengisi sulkus temporal kanan. Mid Line Shift minimal ke kiri sejauh 2,6 mm. Edema Serebri luas. Garis fraktur tipis mastoid kanan dan Hematosinus Spheniodalis kanan. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan hemoglobin 12,1 gr%, leukosit 15.700/mm3, trombosit 444.000/mm3, waktu perdarahan 1,5 menit, waktu pembekuan 9 menit, waktu protrombin 13 detik, APTT 36/detik, SGOT 28, SGPT 28, ureum 44 mg/dl, kreatinin 1,0 mg/dl, natrium 143 mMol/l, kalium 4,2 mMol/l, gula darah sewaktu 141 mg/dl. Pemeriksaan analisa gas darah setelah intubasi PH 7,44 , PCO2 36,5 mmHg, PO2 131,9 mmHg, HCO3 26,4, O2 Saturasi 99,0 BE 2,4 AA DO2 38,8. Pengelolaan Anestesi Pada waktu di unit gawat darurat mendapat propofol tambahan 2 kali sebanyak total 100 mg dan vecuronium 3 mg. Meja operasi diposisikan head up 15o. Evaluasi sebelum pemeliharaan anastesi laju nadi 102 x/menit, tekana darah 160/95 mmHg, saturasi oksigen 99%, suhu 37 oC. Kemudian dilakukan ventilasi mekanik dengan volum tidal 8 ml/kg berat badan, frekuensi napas 12x/menit, I : E Ratio 1 : 2, PEEP 0, FIO2 50%. Propofol 2–8 mg/kg/jam dengan syringe pump, vecuronium 0,8–1 μg/kg/menit. Fentanyl 100μg, sevoflurane 1–1,5%, O2 dan udara bebas. Cairan rumatan adalah Ringerfundin 1,5 ml/kg/ jam. Sebelum membuka duramater diberikan manitol 100 ml dalam 30 menit. Hemodinamik stabil selama duramater mulai dibuka dengan rerata tekanan darah 80–100 mmHg, nadi 70–95 x/menit, saturasi oksigen 98–100%, otak cukup slack. Operasi trepanasi evakuasi hematom dan dekompresi berlangsung selama 3 jam. Total perdarahan 450 ml, urin produksi 1100 ml, cairan masuk Ringerfundin 1000 ml, koloid voluven 500 ml, hemodinamik tetap stabil dengan tekanan darah rerata antara 70–90 mmHg, saturasi oksigen 97–100%, temperatur 36,8–37,0 oC, laju nadi antara 70–100 x/menit, end tidal CO2 28– 35 mmHg. Operasi selesai, pasien pre-operatif dengan cedera kepala berat GCS 5, edema serebri, pergeseran garis tengah, pernah kejang dan ada tanda Cushing maka diputuskan tidak dilakukan ekstubasi tetapi dirawat di ICU dengan ventilator. Tulang kepala disimpan di bank jaringan. Foto Polos Leher AP Lateral, Foto Thorak, Pelvis, Femur, Tidak ada Fraktur Gambar 1.1 Gambaran Perdarahan Intraserebral Basal Frontal Kanan dan Kiri Gambar 1.2 Gambaran Perdarahan Intraserebral Basal Frontal Kanan dan Kiri dan Perdarahan Intraserebral Parietal Kanan. Penatalaksanaan Perioperatif Cedera Kepala Traumatik Berat dengan Tanda Cushing Gambar 1.3 Tekanan Darah Rerata dan Laju Nadi selama Operasi. Perawatan Pascabedah Pasien dirawat di ruang intensif dibantu dengan ventilasi mekanik dengan modus PCMV 12 FIO2 40% TV 400, PEEP 3, Propofol 25–50 mg/jam, fentanyl 50 μg/jam, dexketoprofen 3x50 mg, omeprazol 2x40 mg, odancetron 3x4 mg, phenitoin 3x100 mg, antibiotik ceftazidim, nimodipin, citicholin, intravena. Cairan Ringerfundin 1500 ml dan NaCl 0,9% 500 ml dalam 24 jam, manitol 4x100 ml. Posisi head up 15o. Dilakukan pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, gula darah, analisa gas darah. Perawatan Hari Pertama Saturasi stabil baik 97–100%, hemodinamik stabil dengan tekanan darah rerata 70–100 mmHg, 37 laju nadi 70–95x/menit, temperatur 36,5–37 oC, CVP 8 Cm H2O. Hasil CT Scan ulang, sebagian besar perdarahan sudah dievakuasi, tampak sisa bintik-bintik minimal perdarahan di frontal kiri kanan, SAH sudah banyak berkurang, perdarahan minimal kontusio kortikal temporal kanan, tidak ada pergeseran garis tengah. Hasil laboratorium hemoglobin 10,8 g/dl, hematokrit 35,4, trombosit 202.000/μl, gula darah 134 mg/dl, natrium 146 mMol/l, kalium 3,6 mMol/l. Hasil gas darah PH 7,44 PCO2 36,9 mmHg, PO2 204 mmHg, HCO3 23,7, O2 Saturasi 98%, BE 2,8 dengan oksigen 30%. Perawatan Hari Kedua Status generalis keadaan umum baik: tensi, nadi, saturasi oksigen, CVP, suhu, produksi urinecukup. Sonde mulai diberikan iso kalori 6x50 ml. Perawatan hari ketiga Keadaan umum baik tekanan darah 120–140/80– 90 mmHg, nadi 65–90 x/menit, saturasi oksigen 97–99%, suhu 36,9 oC. Evaluasi kesadaran setelah propofol dihentikan, didapat GCS E3 M5 VX, kemudian dilakukan weaning. Perawatan hari keempat Status generalis kondisi umum baik, tensi, nadi, suhu, saturasi, produksi urine CVP, baik. Pada pemeriksaan neurologis GCS E4 M6 VX, pupil isokor, 3 mm, RC+/+, motorik 5/5, tidak ada kejang, saraf kranialis tidak ada gangguan. Pasien cukup kuat kemudian dilakukan ekstubasi. Perawatan lanjutan Pada hari kelima dan keenam pasien kondisi umum baik, status neurologis baik, dipindah ke ruang intermediate. Hari ketujuh pasien Gambar 1.4 Gambar CT-Scan Post Op di hari ke–20 38 Jurnal Neuroanestesi Indonesia dipindah ke ruangan, GCS 4, 5, 6. Evaluasi CTScan di ruangan hari ke-20 post op hasilnya normal. Pasien pulang setelah setelah dilakukan Kranioplasti. III. Pembahasan Fokus penatalaksanaan cedera kepala pada saat ini adalah mencegah cedera primer serta menghindari dan mengelola cedera sekunder. Landasan dari pengelolaan cedera kepala traumatik adalah resusitasi dan stabilisasi di tempat kejadian, kecepatan dan ketepatan transportasi, resusitasi di unit gawat darurat, evakuasi pembedahan, kontrol Tekanan Intra Kranial (TIK), menjaga tekanan perfusi otak, monitoring multimodal, optimalisasi lingkungan fisiologis. Periode perioperatif sangat penting pada pengelolaan cedera kepala traumatik. Penatalaksanaan pada periode pra rumah sakit merupakan titik kritis untuk mencegah terjadinya cedera sekunder, tetapi ini jarang dilakukan karena pasien dikelola oleh tenaga kesehatan setelah tiba di rumah sakit. 1- 3, 6-7 Penatalaksanaan di rumah sakit pertama adalah resusitasi dan stabilisasi, pembebasan jalan nafas, pemberian oksigen, resusitasi cairan dan pemberantasan kejang telah dilakukan. Pada waktu dalam perjalanan transportasi ke rumah sakit kedua resusitasi dan stabilisasi untuk mencegah cedera sekunder tetap dilakukan. Datang di UGD rumah sakit kedua dilakukan survei primer menyeluruh serta dilakukan resusitasi terhadap cedera yang mengancam jiwa. Diberikan oksigen 8–10 l/menit, ventilasi dengan Jackson Reese, pemberian Ringer Fundin 100 cc/jam. Dari rumah sakit pertama sudah diberi cairan RL 1000 cc, terpasang collar neck. Pasien disiapkan intubasi, head up 15o–30o diberikan manitol 200 ml karena juga terdapat tanda Cushing. Intubasi sering dilakukan untukm enghilangkan obstruksi jalan nafas, kontrol ventilasi, proteksi terhadap resiko aspirasi. Intubasi dilakukan dengan indikasi yaitu: GCS <8, pernafasan ireguler, frekuensi nafas <10 x/menit atau > 40x/menit, volume tidal < 3,5 ml/Kg berat badan, kapasitas vital <15 ml/Kg berat badan, PaO2 < 70 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg. Disamping mencegah dan mengelola hipoksi dan hiperkarbi, penting juga menjaga stabilitas kardiovaskular karena hipotensi dan hipertensi dapat memperburuk luaran. Hipotensi yang terjadi pada cedera kepala membahayakan hemodinamik otak dan menyebabkan iskemiaotak, oleh karena itu penting untuk menjaga tekanan darah optimal termasuk juga pemilihan cairan untuk resusitasi dan penggunaan vasopresor bila dianggap penting.5-7 Brain Trauma Foundation Guidelines telah merekomendasikan menghindari hipotensi (sistolik <90 mmHg) dan mempertahankan tekanan perfusi otak (CPP) 50–70 mmHg. Cairan isotonis kristaloid non glukosa merupakan pilihan utama, kecuali apabila terjadi hipoglikemi maka kristaloid yang mengandung glukosa dipertimbangkan. Yang ingin dicapai adalah kondisi normotensi, normovolemi, normoglikemi. Hipertensi sering terjadi karena pelepasan katekolamin oleh proses trauma serta usaha dalam mempertahankan perfusi otak akibat peningkatan TIK dapat mengurangi respon tekanan darah. Penggunaan adrenergik blocking agent dipertimbangkan bila usaha pengendalian TIK tidak dapat menurunkan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol dapat merugikan karena meningkatkan pembentukan edema dan TIK.5, 6, 10 Pada cedera kepala traumatik apabila didapatkan hipertensi yang dipikirkan pertama adalah tanda cushing lebih dahulu. Tujuan resusitasi pada cedera kepala selanjutnya adalah pengendalian Tekanan Intrakranial. Bila pasien head up 15o–30o perlu diwaspadai efek samping penurunan tekanan darah yang akan memperberat iskemia.6 Penilaian neurologik meliputi fungsi kesadaran dengan menggunakan skor GCS serta penilaian pupil meliputi ukuran, respon terhadap cahaya, simetris kanan kiri. Pemeriksaan radiologi seperti CT-Scan tanpa kontras adalah pilihan, serta pemeriksaan x-ray untuk daerah lainnya seperti cervical, pelvis, femur. CT-Scan kepala dapat menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan TIK seperti adanya pergeseran garis tengah, adanya massa intrakranial seperti hematom.6,-8 Penatalaksanaan Perioperatif Cedera Kepala Traumatik Berat dengan Tanda Cushing GCS pada pasien ini setelah resusitasi sebelum intubasi adalah 5. Dengan GCS 5 dan pola nafas yang pendek dan kecil maka dilakukan segera intubasi di unit gawat darurat. Permasalahan perioperatif pada pasien ini adalah masalah pernafasan: resiko hipoksi dan hiperkarbi yang disebabkan obstruksi jalan nafas karena kesadaran menurun. Masalah sirkulasi: pasien dengan hipertensi dan bradikardi dapat memperberat edema serebri. Pasien beresiko hipotensi karena induksi untuk intubasi sehingga memperberat iskemi yang sedang berlangsung. Masalah neurologi: pasien dengan kondisi kesadaran menurun menunjukkan adanya peningkatan Intra Kranial sehingga terjadi iskemi. Tanda cushing menunjukkan adanya herniasi. Penatalaksanaan Anestesi Penatalaksanaan nestesi pada pasien cedera kepala traumatik bertujuan mengendalikan Tekanan Intra Kranial dan memelihara tekanan perfusi serebral, melindungi jaringan saraf dari iskemi dan cedera (Brain Proteksi Otak), menyediakan kondisi pembedahan yang adekuat (slack brain). Hal ini dikenal dengan prinsip ABCDE Neuro Anestesi yaitu:5 A) airway, jalan nafas yang selalu bebas sepanjang waktu, B) breathing, ventilasi kendali untuk mendapatkan oksigenasi adekuat dan normokapnea, C) circulation, menghindari peningkatan atau penurunan tekanan darah yang berlebihan, menghindari faktor mekanis yang meningkatkan tekanan venaserebral, menjaga kondisi normotensi, normoglikemi, isoosmolar selama anestesi, D) drugs, menghindari obat dan tehnik anestesi yang dapat meningkatkan TIK, dan beri obat-obatan yang mempunyai efek proteksi otak, E) environment, kontrol temperatur dengan target suhu inti 35o di kamar operasi. Pasien dibawa ke ruang operasi sudah dalam kendali ventilasi karena diintubasi di unit gawat darurat, dan selama dilakukan tindakan diagnostik tetap dilakukan kendali ventilasi dengan relaksan. Tindakan induksi intubasi mempertimbangkan keadaan klinis dan stabilitas hemodinamik. Induksi dilakukan dengan dosis titrasi propofol intra vena total 2mg/Kg berat badan, obat pelumpuh otot non depol dipergunakan fentanyl 1μg/Kg berat badan diberikan untuk mengurangi 39 respon hemodinamik sewaktu laringoskopi dan intubasi, lidokain 1,5 mg/Kg diberikan 90 detik sebelum laringoskopi untuk mencegah peningkatan Tekanan Intrakranial (TIK) lidokain diberikan setelah laju nadi bisa dinaikkan dengan tindakan hiperventilasi sebelumnya. Obat anestesi dan tehnik anestesi yang dipergunakan untuk rumatan anestesi dipilih yang mempunyai kemampuan menurunkan TIK, mempertahankan tekanan perfusi serebral (CPP), menjaga stbilitas kardiovaskular dan memiliki efek proteksi otak terhadap bahaya iskemia.1, 5, 6 Anestesi inhalasi menurunkan metabolisme otak dan menyebabkan vasodilatasi serebral yang akan meningkatkan aliran darah otak (CBF), dan TIK pada konsentrasi lebih dari 1 MAC. Dengan menggunakan obat tersebut pada konsentrasi yang rendah efek vasodilatasi serebral dapat diminimalisir.1 Obat anestesi inhalasi nitrous oxide meningkatkan metabolisme otak dan menyebabkan vasodilatasi serebral yang mengakibatkan TIK meningkat, pemakaiannya pada cedera kepala traumatik sebaiknya dihindari.1 Obat anestesi Intravena Thiopental dan Propofol mempunyai sifat kerja menurunkan CMRO2 dan CBF sehingga menurunkan TIK. Selain itu obat ini memiliki efek minimal pada autoregulasi dan reaktivitas terhadap CO2 sehingga menguntungkan untuk anestesi pada cedera kepala. Pada pasien ini dipergunakan kombinasi obat anestesi sevofluran dan propofol kontinyu dengan tujuan mendapat level anestesi yang cukup tanpa gejolak hemodinamik dan gejolak susunan saraf pusat dengan mengambil keuntungan dari sifat obat tersebut seperti sifat neuro protektif, sambil meminimalkan efek vasodilatasi sevofluran dengan cara mengatur konsentrasi propofol kemudian mempertahankan level anestesi intra operasi pengaturan sistem respirasi cedera kepala traumatik yang berat yaitu dengan menyesuaikan ventilasi mekanik sehingga didapatkan kondisi normokapnea dengan PaCO2 sekitar 35 mmHg dan mengatur fraksi oksigen sampai didapat PaO2 100–200 mmHg. Pada operasi ini dipasang monitor ETCO2 yang hasilnya berkisar 30–35. PEEP yang terlalu besar harus dihindari karena 40 Jurnal Neuroanestesi Indonesia dapat meningkatkan tekanan intra torakal yang mengganggu drainase vena serebral dan meningkatkan TIK.1, 5, 8 Sistem sirkulasi intraoperatif diatur untuk mendapatkan kondisi normovolemi, normotensi, isoosmoler juga normoglikemi.5, 8 Pada operasi neuro surgical pada umumnya pasien dibangunkan dari anestesi secepatnya, sehingga status neurologis dapat dievaluasi secepatnya sebagai hasil dari tindakan pembedahan. Secara umum pada pasien cedera kepala terdapat edema serebri atau berpotensi mengalami edema serebri, sehingga ada istilah slow weaning dan delayed Extubation. Pulih sadar lambat (Late Emergence) dapat dilakukan pada kondisi:6, 8derajat kesadaran praoperasi buruk, resiko terjadi edema atau memperberat edema-nya seperti pada operasi yang lama, perdarahan banyak, dekat area vital, operasi ekstensif, praoperasi pengelolaan jalan nafas sulit. Pada pasien ini derajat kesadaran pra-operasi buruk, serta terdapat edema sehingga diputuskan tidak dilakukan ekstubasi. Penatalaksanaan terapi intensif cedera kepala setelah dilakukan resusitasi dan stabilisasi di unit gawat darurat dan sudah dilakukan tindakan operasi, selanjutnya dirawat di ruang perawatan intensif. Perawatan di ICU terdiri dari perawatan umum yang ketat dan perawatan lain yang bertujuan:4, 5, 11stabilisasi pasien, optimalisasi oksigen dan hemodinamik otak, mencegah dan melakukan terapi Hipertensi intrakranial, mempertahankan CPP yang stabil dan adekuat, mencegah dari cedera sekunder. Pasien segera dipindah ke ICU setelah operasi selesai. Tindakan lanjutan seperti ventilasi mekanik untuk menjamin oksigenasi dan mencegah hipoksi, mempertahankan kondisi normokapnea untuk mengendalikan aliran darah otak sehingga dapat menurunkan TIK. Ventilasi mekanik dilakukan dengan menggunakan obat sedatif. Analgetik yang adekuat diberikan untuk mendapatkan kondisi yang nyaman dan aman. Kondisi yang tidak nyaman dari nyeri dapat menyebabkan respon stres seperti takikardi, meningkatkan konsumsi oksigen hipermetabolisme, meningkatkan katekolamin endogen, dan meningkatnya TIK.12, 15 Pemberian analgetik yang adekuat dapat menurunkan konsumsi oksigen 15%, disamping dapat mencegah naiknya tekanan darah yang dapat menyebabkan perdarahan intrakranial setelah kraniotomi pasien kritis setelah tindakan operasi sering mengalami kecemasan, yang bisa diatasi dengan sedasi. Pengalaman yang tidak menyenangkan dapat menyebabkan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).15 Propofol digunakan karena menekan metabolisme serta mempunyai waktu paruh yang pendek sehingga evaluasi derajat kesadaran dapat segera dilakukan setelah obat dihentikan. Efek hipotensi dan Propofol Infusion Syndrome perlu diwaspadai.3, 4, 6. Analgesia kontinyu fentanyl dan dexketoprofen diberikan karena efeknya minimal pada hemodinamik.15 Posisi head up 15o–30o dilakukan untuk mengurangi tekanan intrakranial dengan memperbaiki drainase Vena Serebral. Posisi ini ini bisa menyebabkan hipotensi yang akan menurunankan perfusi serebral, memperberat iskemi sehingga akan mempengaruhi luaran.3, 5, 6 Hemodinamik dijaga kestabilan dengan mencegah hipotensi dan hipertensi. Hipotensi akan memperburuk edema otak dan akan meningkatkan TIK. Pengendalian edema otak dan TIK dapat dilakukan dengan pemberian cairan hiperosmoler seperti manitol. Manitol bekerja sebagai dioretika osmotik dengan cara meningkatkan osmolaritas serum dan membuat perbedaan tekanan osmotik. Pemeriksaan osmolaritas serum dilakukan untuk mengevaluasi adanya peningkatan osmolaritas akibat manitol, bila osmolaritas serum lebih dari 320 mOsm/Kg H2O bisa terjadi efek balik peningkatan TIK, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit serta gagal ginjal.3, 8, 11 Terapi Cairan dan Nutrisi Tujuan utama pengelolaan cairan pada cedera kepala traumatik adalah mempertahankan keadaan dan memelihara kondisi Euvolemi atau Hipervolemi sedang (CVP 8–10 mmHg) karena balan cairan yang negatif berhubungan dengan luaran yang jelek.3 Cairan kristaloid isotonik dipergunakan, dan cairan normal salin cairan yang terpilih, cairan yang sedikit hipotonis seperti Ringer Laktat bukan merupakan pilihan Penatalaksanaan Perioperatif Cedera Kepala Traumatik Berat dengan Tanda Cushing 41 resusitasi pasien cedera kepala terutama dalam jumlah yang banyak karena dapat menyebabkan penurunan osmolaritas serum. Sedangkan cairan hipotonis seperti ½ NS, ¼ NS, D5, D5 ½ NS, D5 ¼ NS harus dihindari. Cairan yang mengandung glukosa seperti D10 atau lebih harus dihindari pada waktu 24 sampai 48 jam pertama terkecuali pada kondisi hipoglikemi.3, 4, 6, 16 Pengelolaan cairan pada cedera kepala bertujuan supaya tercapai keadaan normovolemi, normotensi, normoglikemi dan iso osmolar. Pasien ini diberikan cairan pasca operasi dengan cairan Ringer Fundin dan NaCl 0,9% yang bersifat iso osmolar tanpa glukosa. konstipasi juga dilakukan fisioterapi. Pemberian obat-obat neuroprotektif masih banyak dilakukan penelitian karena belum ditemukan hasil yang signifikan. Monitoring pada pasien cedera kepala traumatika penting dilakukan untuk optimalisasi terapi.4 Hal ini berguna untuk mendeteksi dini proses-proses yang mengakibatkan cedera sekunder, seperti proses sistemik atau proses intra kranial. Yang umumnya secara rutin digunakan adalah elektrokardiografi, pulseoxymetri, endtidal CO2, tekanan vena sentral, tekanan darah arterial, temperatur sistemik, urine output, pemeriksaan laboratorium gas darah, serum elektrolit, gula darah dan osmolaritas plasma.8, 9, 12 Kontrol Gula Darah Pasien dengan cedera kepala berat sering mengalami stres hiperglikemi karena pelepasan dari stress hormon yang akan menghambat pengeluaran insulin dan kerja insulin, hiperglikemi ini dihubungkan dengan luaran yang jelek. Kadar glukosa yang diharapkan pada fase akut adalah 80–180 mg/Dl, karena kontrol glukosa yang ketat yang menyebabkan hipoglikemi juga akan mempengaruhi luaran.3,16 Pada pasien ini glukosa berkisar pada konsentrasi 141–180 mg/dl. Kondisi hipermetabolik, hiperkatabolik dengan perubahan fungsi gastro intestinal juga sering terjadi pada pasien cedera kepala. Hal ini menyebabkan malnutrisi yang akan meningkatkan mortalitas. Pemberian nutrisi sejak awal direkomendasikan bila stabilitas hemodinamik baik. Brain Trauma Foundation merekomendasikan pemberian 140 % dari kebutuhan basal (± 30 Kcal/Kg berat badan) pada pasien non paralisa, 100 % dari kebutuhan basal (± 25 Kcal/Kg berat badan) pada pasien dengan relaksan.3,16 Nutrisi enteral lebih dipilih, tetapi bila ada trauma abdomen atau ada residu gastrik maka dipilih kombinasi dengan nutrisi parenteral.4 Pasien ini mulai diberikan nutrisi pada hari kedua. Pemberian peroral dapat dilakukan tanpa keluhan. Monitoring neurologis seperti pemeriksaan neurologis secara klinis meliputi derajat kesadaran (GCS) pemeriksaan pupil, motorik, sensorik, saraf kranialis segera dilakukan setelah CT Scan tidak didapatkan perdarahan di kepala dan edema serebri berkurang. Pemeriksaan neurologis lain seperti monitor TIK dan saturasi oksigen vena jugularis (SJVO2 ) untuk pasien yang belum dapat dievaluasi kesadarannya karena perlu ventilasi mekanik, pemberian sedas, atau pemberian obat pelumpuh otot. Pemeriksaan luaran perlu dilakukan seperti dengan GOSE.12, 14. Perawatan Lainnya Perawatan lain adalah perawatan harian seperti perubahan posisi berkala, kebersihan oral, kulit, perawatan mata, pencegahan infeksi, ulkus, deepvein trombosis, pencegahan peptik ulcer, Pemberian bowel regimen untuk mencegah IV. Simpulan Pedoman penatalaksanaan cedera kepala traumatik telah mengalami perbaikan. Periode peri operatif merupakan periode yang kritis karena pada periode ini penanganan yang cepat, tepat akan mempengaruhi luaran dari pasien dengan cedera kepala. Pada periode ini kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan cedera sekunder bisa cepat diketahui dan dilakukan pengelolaannya sehingga cedera sekunder dapat dihindari dan dicegah serta diterapi. Penanganan cedera kepala yang meliputi pengelolaan jalan nafas, respirasi, optimalisasi hemodinamik, pengendalian TIK dan tindakan pembedahan serta tindakan lanjutan lainnya di ruang intensif. Hal itu semua memerlukan kerjasama, pemahaman semua yang terlibat sehingga hasilnya bisa optimal. Telah dilakukan penanganan peri operatif pada wanita usia 54 tahun dengan cedera kepala traumatik berat 42 Jurnal Neuroanestesi Indonesia dengan tanda Cushing secara menyeluruh sampai pasien keluar rumah sakit. Luaran yang didapat masih memerlukan evaluasi untuk mengetahui adanya gangguan fungsi kognisi pasien. V. Daftar Pustaka 1. Curry P, Viernes D, Sharma D. Perioperative management of traumatic brain injury. Int J Crit Illn Sci. 2011;1(1):27–35. 2. Moppet IK. Traumatic brain injury: assessment, resuscitation and erly management. Br J Anaesth. 2007;99:18–31. 3. Haddad S, Arabi YM. Critical care management of severe traumatic brain injury in adults. SJTREM. 2012;20:12. 4. Helmy A, Vizcaychipi M, Gupta AK. Traumatic brain injury: intensive care management. Br J Anaesth. 2007;99:32–42. 5. Bisri T. Penanganan neuroanesthesia dan critical care: cedera otak traumatik. Bandung: Universitas Padjadjaran; 2012. 6. Gopinath SP, Robertson CS. Management of severe head injury. Dalam: Cotrell JE, Smith DS, eds. Anesthesia and Neurosurgery. USA: Mosby Inc; 2001, 663–85 7. Mangat HS. Severe traumatic brain injury. American Academy of Neurology. 2012;18 (3):532–46. 8. Tolani K, Bendo AA, Sakabe T. Anesthetic management of head trauma. Dalam: Newfield P, Cottrell JE, eds. Handbook of Neuroanesthesia. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012, 98–115. 9. Steiner LA, Andrews PJD. Monitoring the injured brain: ICP and CBF. Br J Anaesth. 2006;97(1):26–38. 10. Czosnyka M. Monitoring intracranial pressure. Dalam: Matta BF, Menon DK, Tunner JM, ed. Textbook of Neuroanaesthesia and Critical Care. London: Greenwich Medical Media; 2000; 99–109. 11. Yarham S, Absalom A. Anesthesia for patients with head injury. Dalam: Gupta AK, Gelb AW, eds. Essentials of Neuro Anesthesia and Neuro intensive care. Philadelphia: Saunders; 2008; 150–54. 12. Bendo AA. Perioperative management of adult patients with severe head injury. Dalam: Cottrel JE, Young WL, eds. Cottrell and Young’s Neuroanesthesia, Philadelphia: Mosby; 2010; 17–326. 13. McEwen J, Huttunen KTH, Lam AM. Monitors during anesthesia: effects of anesthetic agents on monitors. Dalam: Leroux PD, Levine JM, Kofke WA, eds. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013; 71–81. 14. Balu R, Detre JAA, Levine JM. Clinical assessment in the neurocritical care unit. Dalam: Leroux PD, Levine JM, Kofke WA., eds. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013; 84–98. 15. Terhune KP, Ely EW, Pandharipande PP. Pain, sedation, and delirium in critical illness. Dalam: Leroux PD, Levine JM, Kofke WA. eds. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013; 99–113. 16. Bassin SL, Bleck TP. Glucose and nutrition. Dalam: Leroux PD, Levine JM, Kofke WA, eds. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013; 121–130 Tatalaksana Anestesi pada Microvascular Decompression (MVD) Bau Indah Aulyan Syah*), Siti Chasnak Saleh**), Sri Rahardjo***) Departemen Anestesi Perawatan Intensif dan Manajemen Nyeri Rumah Sakit Awal Bros Makassar, **)Departemen Anestesiologi & Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga–RSUD Dr. Soetomo Surabaya, ***) Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada–RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta *) Abstrak Microvascular decompression (MVD) nervus kranialis merupakan salah satu terapi untuk trigeminal neuralgia, spasme hemifacialis, dan neuralgia glosspharyngeal. Seorang wanita 52 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan utama kedutan pada wajah sebelah kiri selama 17 tahun dan telah berobat ke beberapa dokter, termasuk suntikan botoks, namun hasilnya tidak memuaskan. Pemeriksaan MRI otak menunjukkan persilangan arteri cerebellaris anterior inferior (AICA) kiri dengan N. VII di daerah entry zone. Hal ini dapat menyebabkan TIC fasialis kiri. Pasien ini didiagnosis dengan spasme hemifasialis sinistra dan akan menjalani prosedur MVD. Pasien dianestesi dengan teknik anestesi umum intubasi endotrakea dengan menerapkan prinsip-prinsip neuroanestesia. Pada pasien ini tidak ditemukan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, namun dalam memfasilitasi pembedahan untuk dekompressi saraf yang tertekan, sangat penting untuk menurunkan volume otak. Karena itu, diterapkan beberapa metode, seperti hiperventilasi volunter, pemberian mannitol 20% 150mL dengan mempertahankan batas autoregulasi. Kombinasi anestesi inhalasi (sevofluran 0,6-1,5%) dan intravena (propofol kontinyu 60–100mg/ jam), relaksasi dengan vecuronium kontinyu 2,5–4,5mg/jam. Cairan rumatan dipilih ringer fundin 400ml dan NaCl 0,9% 500ml melalui 2 jalur intravena. Operasi berjalan selama 2 jam, pendarahan sebanyak 150mL, urin 1000mL dilakukan ekstubasi segera setelah operasi selesai. Pasca anestesi, pernapasan dan hemodinamik stabil dan adekuat. Pemeriksaan neurologis di ruang pemulihan didapatkan kedutan menghilang. Kata kunci: microvascular decompression, spasme hemifasialis JNI 2015;4 (1): 43–9 Anesthesia Management for Microvascular Decompression (MVD) Abstract Microvascular decompression (MVD) cranial nerves as a therapy for trigeminal neuralgia, hemifacial spasm, and glosso pharyngeal neuralgia. A 52 years old female, came to the hospital due to the twitching on the left side of her face. She had been experiencing the twitching for over 17 years, had been treated by several doctors, including Botox injection, but with no satisfying outcome. MRI examination showed intercrossing of the left anterior inferior cerebellar artery (AICA) with the seventh cranial nerve in the area of entry zone. The condition caused the left facial TIC. She was diagnosed with left hemifacial spasm and planned for a MVD procedure. The patient was anesthetized with endotracheal intubation under general anesthesia using neuroanesthesia principles. There was no sign of increased intracranial pressure. Nevertheless, it is importance to facilitate the nerve decompression procedure by reducing the brain volume that can be perform with several methods, such as voluntary hyperventilation, administering mannitol 20% 150 mL while maintaining the autoregulation level. Combination of inhalation (sevofluran 0,6-1,5%) and intravenous anesthesia (propofol continuously 60–100mg/ hour) was chosen, relaxation was obtained with continuous vecuronium 2,5-4,5mg/hr. Maintenance of intravenous fluids were Ringer fundin 400ml and NaCl 0,9% 500ml delivered via two intravenous routes. The operation was last for 2 hours, the amount of bleeding was 150 mL, and the urine was 1000 mL. The patient was extubated immediately after the operation. Breathing and hemodynamic post anesthesia were both stable and adequate. Neurological examination in the recovery room revealed no more twitching observed. Key words: hemifacial spasm, microvascular decompression JNI 2015;4 (1): 43–9 43 44 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Prosedur microvascular decompression (MVD) dilaporkan pertama kali untuk meredakan trigeminal neuralgia (TN) pada tahun 1952 dan 1959, dan untuk dekompressi nervus fasialis pertama kali pada tahun 1962 oleh Gardner dan Sava1. Saat ini MVD nervus kranialis merupakan salah satu terapi untuk TN, spasme hemifasialis (hemifacial spasm/HFS)2, dan neuralgia (vago) glossopharyngeal. Prosedur ini juga dilaporkan dapat meredakan tinnitus, vertigo3, hyperactive gag reflex, disfungsi nervus okulomotoris, nervus abdusen4, dan hipertensi.1 fokal/protrusion ringan ke posterior. Hasil MRBrain MRA menunjukkan persilangan AICA (arteri cerebellaris anterior inferior) kiri dengan N. VII di daerah entry zone dapat menyebabkan TIC fasialis kiri (Gambar 1). II. Laporan Kasus Seorang wanita 52 tahun, berat badan 62 kg, tinggi badan 155 cm, masuk ke rumah sakit dengan keluhan utama kedutan pada wajah sebelah kiri sejak tahun 1997 (17 tahun sebelum masuk rumah sakit). Pasien telah sering ke beberapa dokter, disuntik botox tidak ada perbaikan. Didiagnosis dengan spasme hemifasialis sinistra yang akan dilakukan microvascular decompression (MVD). Pemeriksaan Fisik Pada pemeriksaan fisis ditemukan keadaan umum GCS 15, tekanan darah 140/90 mmHg, laju jantung 82 kali per menit. Pemeriksaan Laboratorium Laboratorium darah menunjukkan Hb 14,30 g/dl, leukosit 5,9 ribu/UL, trombosit 245 ribu/µL, LED 16 mm, hitung jenis eosinofil 1%, netrofil batang 2%, netrofil segmen 57%, limfosit 33%, monosit 7%, PT 14,4 detik, APTT 32,9 detik, natrium 135 mmol/L, kalium 3,7 mmol/L, kalsium total 10,8 mmol/L, ion kalsium (Ca++) 1,16 mmol/L, protein total 7,4 gr/dL, albumin 4,2 g/dL, SGOT 14 U/L, SGPT 16 U/L, ureum 33 mg/dL, kreatinin 1,10 mg/dL. Pada pemeriksaan foto torak tidak ada kelainan pada jantung dan paru, kedua sinus dan diafragma baik. Pada pemeriksaan MR-cervikal ditemukan spondilosis ringan fase diskogenik yang meliputi C2–3, C3–4, C4–5, C5–6, C6–7. Diskus intervertebralis C2–3, C5-6, dan C6–7 menonjol Gambar 1. MR-Brain MRA Kompressi Nervus Fasialis Pengelolaan Anestesi Pasien posisi supine, sebelum induksi dilakukan hiperventilasi spontan. Pasien diinduksi dengan fentanyl 100 μg dan campuran propofol 100 mg dengan lidokain 2% 40 mg. Setelah itu diberikan rocuronium 50 mg, dan lidokain 2% 40 mg. Dilakukan intubasi dengan pipa endotrakhea non kinking no. 7. Rumatan anestesi dengan oksigen: udara = 3 L/menit : 2 L/menit, sevoflurane 0,6–1,5 vol %. Propofol kontinyu 60-100 mg/jam melalui syringe pump dan vecuronium kontinyu 2,5–4,5 mg/jam. Selama operasi diberikan tambahan fentanyl 50 μg dan propofol 50 mg. Ventilator diatur dengan tidal volume 500 cc, pernapasan 12 kali per menit, I : E = 1: 2. Operasi dilakukan dengan posisi Park Bench, dan berjalan selama 2 jam, dengan cairan intraoperatif terdiri dari Ringerfundin (RF) 400 cc, NaCl 0,9% 500cc, dan Mannitol 150 cc. Hemodinamik dijaga dalam batas autoregulasi. Sebelum ekstubasi diberikan lidokain 40 mg iv, dan prostigmin: atropine sulfat 1 mg : 0,5 mg. Setelah ekstubasi, tekanan darah 180/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, adekuat. Tatalaksana Anestesi pada Microvascular Decompression (MVD) Total produksi urin 1000 cc, dengan perdarahan 100 cc. Pengeloaan Pascabedah Setelah operasi pasien diobservasi di ruang pemulihan. Pada pemeriksaan tidak ditemukan gangguan neurologi dan kedutan pada wajah sudah menghilang. Pascabedah pasien dikembalikan ke ruang perawatannya. Sebagai analgetik diberikan ketesse 50mg/iv pascaoperasi dan untuk di ruangan diberikan ketesse 50mg + pethidin 50 mg diencerkan dengan NaCl 0,9% sampai 50 ml dan diberikan dengan dosis 2 ml/jam. III. Pembahasan Spasme hemifasialis (hemifacial spasm/HFS) Spasme hemifasialis/HFS merupakan kondisi kontraksi involunter, berulang/repetitif, dan unilateral dari otot-otot yang dipersarafi oleh nervus fasialis (cranial nerve [CN] VII)2. Kondisi ini sering terjadi terutama pada orang dewasa muda, dewasa, dan usia lanjut. Patofisiologi HFS Spasme hemifasialis tipikal disebabkan oleh iritasi nervus fasialis akibat kompressi pembuluh darah pada daerah root exit zone (RExz), yang akhirnya menyebabkan spasme intermitten dan involunter yang awalnya melibatkan muskulus orbikularis okuli dan menyebar ke muskulus mentalis. Suatu penelitian neurofisiologi terdahulu (Nielsen, 1985) ditemukan adanya demielinisasi aksonal dan hipereksitabilitas motonukleus fasialis pada HFS, serta respon penyebaran ke lateral (lateral spread response/LSR). Fenomena elektrofisiologi 45 pada motonukleus fasialis ini menyebabkan aktivitas ortodromik pada cabang perifer CN VII dan demyelinisasi4. Kompresi pembuluh darah pada spasme hemifasialis umumnya oleh arteri serebellaris anterior inferior atau arteri vertebralis yang menekan nervus fasialis5. Seiring dengan bertambahnya usia, arteri bertambah lebar dan besar dan bisa saja mengenai nervus kranialis, termasuk N. VII. Iritasi mekanik akibat pulsasi pembuluh darah menyebabkan lesi demielinisasi fokal di daerah RExz, sehingga terjadi transmisi ephaptic dan crosstalk antara dua serat saraf. Pembedahan untuk membebaskan kompressi neurovaskuler dengan melakukan transposisi jaringan lunak antara pembuluh darah dan saraf dapat mengembalikan fungsi saraf yang tertekan menjadi normal6. Microvascular Decompression (MVD) untuk HFS Tujuan MVD adalah untuk membebaskan tekanan terhadap nervus kranialis. Untuk melakukan MVD, insisi linear dilakukan di belakang telinga pada sisi saraf yang tertekan. Diseksi dilakukan hingga tulang, dan beberapa burr holes dibuat. Burr holes diperbesar hingga seperti kraniektomi atau dengan mengangkat bone flap. Kraniektomi dilakukan di bawah sinus transversus dan di medial sinus sigmoid agar ada akses ke sudut cerebellopontine. Selsel udara mastoid di lindungi dengan bone wax untuk mencegah kebocoran cairan serebro spinal. Setiap perdarahan sinus vena dikontrol, dan dura di buka. Dengan otak yang relaks, serebellum di retraksi. Jika ada pembuluh darah di sekitar 46 Jurnal Neuroanestesi Indonesia saraf kranialis yang menghalangi, pembuluh darah tersebut harus dibebaskan secara hatihati. Pemantauan saraf fasialis dan EMG dapat dilakukan selama intraoperatif untuk melindungi nervus kranialis. Setelah saraf kranialis bebas dari kompressi, dura ditutup, lapisan lainnya juga ditutup. Posisi operasi pasien bisa lateral, prone, supine, atau duduk (sangat jarang).5 MVD pada nervus kranilis VII (fasialis) merupakan terapi yang efektif untuk HFS. Satu penelitian pada 326 operasi MVD untuk HFS, luaran yang didapatkan yang sangat baik dilaporkan dengan tercapainya 88% bebas spasme dalam 24 jam pascabedah. Bahkan 8 pasien rawat jalan mereka bebas spasme hingga 90,8% saat keluar dari rumah sakit. Hanya 7,7% pasien yang masih menderita gejala spasme (efek terapi MVD lambat).7 Penyembuhan spasme yang tertunda mungkin menandakan waktu yang diperlukan untuk remielinisasi daerah yang rusak, begitu pula dengan yang diperlukan untuk kembalinya eksitabilitas normal motoklonus fasial4. Terapi non bedah untuk HFS seperti injeksi toksin botulinum (BT) intramuskuler tidak memiliki efekvitas jangka panjang. Satusatunya pengobatan berefek jangka panjang adalah operasi dan dekompressi mikrovaskuler (MVD) retromastoid nervus fasialis, dianggap efektif dalam mengobati 90% pasien.2 Selama pembedahan, pemantauan auditory evoked responses batang otak dilakukan secara rutin untuk mendeteksi disfungsi nervus VIII. Pemantauan nervus VIII (vestibulokokhlearis) penting karena saraf ini membuat pasien dapat mendengar dan mampu mempertahankan keseimbangan dan posisi tubuh mereka. Alat pemantauan intraoperatif lain yang penting adalah elektromiografi dan rekaman LSR, yang membantu ahli bedah untuk menentukan apakah dekompressi yang adekuat telah tercapai. LSR yang ditimbulkan oleh stimulasi cabang nervus fasialis menunjukkan gangguan elektrofisiologi yang konsisten dengan HFS.7 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komplikasi gangguan pendengaran pasca MVD dapat dikurangi bila pada periode intraoperatif diterapkan pemantauan neurofisiologis dengan brainstem auditory evoked potential/BAEP. Hingga saat ini, pemantauan BAEP masih menjadi evaluasi pendengaran yang paling sensitif pada pasien yang teranestesi. BAEP juga bisa menjadi indikator adanya manipulasi pada daerah batang otak, termasuk struktur setinggi nervus auditorius (N. VIII) atau bila nukleus koklearis (pusat pendengaran) ikut termanipulasi. Perubahan gelombang BAEP bahkan terjadi lebih dini dibanding fluktuasi perubahan laju jantung dan tekanan darah, sehingga dianggap sebagai indikator manipulasi batang otak dibanding parameter kardiovaskuler tradisional.8 Dannenbaum et al, melaporkan bahwa dari 114 pasien MVD untuk terapi spasme hemifasialis tanpa menggunakan pemantauan neurofisiologis, ditemukan 86% pasien yang bebas spasme selama 10 tahun pascabedah. Ditemukan satu orang dengan kehilangan pendengaran subtotal, dan 10 kasus dengan delayed facial palsy (2 diantaranya tidak sembuh sempurna). Karena itu, mereka menyimpulkan bahwa MVD aman dan efektif untuk terapi spasme hemifasialis meskipun tanpa pemantauan neurofisiologis. Namun demikian, Samii dkk melaporkan bahwa komplikasi ketulian masih menjadi komplikasi utama (8,3%). Kebanyakan kasus tersebut (66%) terjadi pada era sebelum penggunaan pemantauan BAEP secara rutin pada MVD untuk spasme hemifasialis. Moller dan Moller melaporkan bahwa insidensi defisit pendengaran pascabedah berkurang dari 10% menjadi 2,8% setelah penggunaan BAEP secara rutin. Bahkan, Radtke dkk, melaporkan penurunan dari 6,6% menjadi 0%. yang jelas, pemantauan BAEP akan memberi konfirmasi terjaganya pendengaran selama operasi MVD, bahkan pada beberapa penelitian memberi pandangan kedua bagi ahli bedah saraf untuk mengidentifikasi RExz. Bila dipandang dari segi umur, teknik MVD dilaporkan aman dan efektif hingga usia 75 tahun. Yang jelas, pasien juga memenuhi persyaratan dapat menerima anestesi umum.9 MVD dapat mengobati kedutan dan nyeri akibat kompressi saraf kranialis hingga angka penyembuhan 90%.6 MVD jelas dianggap prosedur yang tidak berbahaya. Namun demikian, mortalitas pembedahan masih ditemukan sekitar 0,3% Tatalaksana Anestesi pada Microvascular Decompression (MVD) dan risiko infark atau perdarahan batang otak ditemukan sekitar 1–2%. Ini menunjukkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan pembedahan otak terbuka lain dan angka komplikasi tersebut tidak akan ditolerir bila ada terapi lain dengan efek terapeutik yang sama namun dengan risiko yang lebih rendah. Sayangnya, saat ini belum ada yang sebaik MVD.6 Meskipun relatif jarang, kehilangan pendengaran pascabedah merupakan salah satu komplikasi MVD yang bisa bersifat permanen. Ketulian dianggap terjadi akibat manipulasi yang berlebihan terhadap saraf kranialis VIII. Pada penelitian Jannetta dkk., rerata komplikasi kehilangan pendengaran berkisar 2,6% pada pasien dengan spasme hemifasialis dan 1% pada pasien dengan neuralgia trigeminus. Cedera serebellum berkisar 0,68%.8 Anestesi untuk MVD Prosedur operasi MVD memerlukan kraniotomi total untuk dekompressi saraf kranialis. Pasien dengan hipertensi preoperatif sebaiknya diberikan antihipertensi preoperatif untuk memudahkan manajemen tekanan darah intra dan pascabedah. Teknik anestesi terpilih adalah anestesi umum demi fasilitasi kraniotomi total. Tekanan intrakranial (TIK) umumnya tidak meningkat pada pasien yang akan menjalani operasi. Namun demikian, menurunkan volume otak (umumnya dengan mannitol 0,25–0,5 g/kgBB atau drain lumbar untuk mengeluarkan cairan serebrospinal), penting untuk memberikan ruang bagi ahli bedah untuk mengidentifikasi dan membebaskan tekanan saraf yang bermasalah tanpa melakukan retraksi otak yang berlebihan dalam proses tersebut. Induksi anestesi paling bagus dengan obat-obat yang menurunkan volume otak seperti pentotal (2–5 mg/kgBB) atau propofol (1–2 mg/kgBB), diikuti dengan relaksan otot dan intubasi endotrakheal.5 Rumatan anestesi untuk MVD umumnya dengan rumatan standar. Desfluran dilaporkan meningkatkan risiko post operative nausea vomiting (PONV). Tekanan darah dipelihara dalam batas normal selama operasi. Hiperventilasi untuk menjaga PaCO2 25–30 47 mmHg membantu dalam menurunkan volume otak dan meningkatkan ruang kerja ahli bedah. Sekali saraf telah diisolasi, hiperventilasi harus dihentikan. Drain spinal dapat digunakan untuk mengeluarkan cairan serebrospinalis (CSS) selama operasi dan meningkatkan ruang paparan. Drain biasanya dibuka saat dura dibuka dan ditutup segera setelah pembedahan pada saraf kranialis berhenti. Selama pembedahan, TIK dijaga di bawah 20 mmHg dan tekanan perfusi serebral (cerebral perfusion pressure)/CPP di atas 50–70 mmHg. Iskemia serebral bisa terjadi bila CPP kurang dari 40–50 mmHg.3 Penggunaan mannitol intravena yang digunakan untuk menurunkan volume otak pada pasien ini dapat meningkatkan osmolaritas darah, sehingga menginduksi perpindahan cairan dari otak ke dalam pembuluh darah. Karena itu, efikasi mannitol tergantung pada intak tidaknya sawar darah otak. Manfaat mannitol untuk menurunkan volume otak dapat dipengaruhi oleh gagal ginjal dan oligouria. Pada pasien ini, tidak ditemukan trauma pada sawar darah otak, gagal ginjal, maupun oligouria. Mannitol seringkali dikombinasi dengan furosemide dosis kecil (0.1–0.2 mg/kg) untuk mencapai efek sinergis untuk menurunkan TIK dalam jangka waktu yang lama. Pemberian furosemide secara tunggal tidak secara otomatis menurunkan TIK. Mekanisme dasar efeknya tidak jelas. Furosemid tidak meningkatkan osmolaritas plasma sehingga tidak menurunkan kandungan air otak. Hanya furosemide dengan dosis kuat yang dapat menurunkan produksi CSF. Bila dikombinasi dengan mannitol, furosemide meningkatkan osmolaritas plasma dan menghambat mekanisme regulatoris seluler ionik aktif, sehingga mencegah berkurangnya volume intraseluler serebral. Hiperventilasi yang dilakukan pada pasien ini juga bertujuan untuk menurunkan volume otak. Hiperventilasi bekerja dengan cara vasokontriksi pembuluh darah otak sehingga tidak dibenarkan dilakukan dalam waktu yang lama. Induksi dengan pentotal atau propofol juga bertujuan untuk mengurangi volume otak.10 Pentotal juga menyebabkan vasokontriksi serebral dengan cara menghambat pembentukan nitric. 48 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Propofol dengan dosis 6 mg/kgBB per jam dapat menurunkan aliran darah otak (cerebral blood flow/CBF) melalui supresi metabolik.10 Sebenarnya, pentotal dan propofol memiliki efek vasokonstriktor serebral, namun propofol lebih frontal dan berefek terutama pada batang otak, sedangkan pentotal lebih dominan berefek pada daerah oksipital. Secara in-vitro efek hipnotik propofol menunjukkan sifat vasodilator dengan cara menghambat saluran natrium dan kalsium. Namun, secara in vivo, justru berefek vasokonstriktor. Mekanisme dasar vasokonstriksi ini adalah akibat efek penurunan metabolisme secara konkomitan. Penelitian pada pasien sukarelawan menunjukkan bahwa propofol menurunkan metabolisme serebral dengan cara menurunkan CBF. Ini menunjukkan bahwa vasodilatasi instrinsik yang diinduksi propofol diimbangi oleh depresi metabolik serta dengan penurunan CBF. Rumatan anestesi yang dipilih pada pasien ini adalah sevofluran. Sevofluran dapat menurunkan CBF akibat efeknya yang menurunkan metabolisme serebral pada konsentrasi kurang dari 1 MAC. Efek ini sangat unik mengingat sevofluran adalah anestetika volatil, karena secara in-vitro dan invivo pada percobaan sebelumnya menunjukkan bahwa zat volatil lain seperti halotan, desfluran, dan isofluran merupakan vasodilator poten yang meningkatkan CBF meskipun ketiganya menurunkan metabolisme serebral. Saat pengakhiran (emergence) anestesi, ekstubasi ETT dapat dilakukan bila tidak ada komplikasi. Hipertensi pascabedah dapat terjadi, sehingga sebaiknya dikontrol. Obat antihipertensi yang umum dipakai adalah esmolol atau Na nitroprusside secara kontinyu. Antiemetik profilaksis (seperti ondansetron 4–8 mg) sebaiknya diberikan 30 menit sebelum ekstubasi. Asetaminofen 1 gr iv dan/atau infiltrasi anestetik lokal di kulit kepala dapat dipertimbangkan untuk analgesia pascabedah. Beberapa ahli anestesi menggunakan pemantauan CVP, EMG, dan SSEP.11 Karena posisi pasien biasanya dengan posisi kepala “far lateral”, maka bantalan bahu dan bantal di antara kedua kaki sebaiknya dipasang.7 Komplikasi yang harus diwaspadai adalah PONV, sehingga terapi multimodal perlu dipertimbangkan.12 Selain itu, pemulihan pascabedah kadang disertai kejadian edema atau perdarahan otak, namun jarang ditemukan. Angka kesuksesan umumnya 75–95%, dengan angka rekurensi berkisar 3,5% per tahun.2 An J dkk, melaporkan bahwa teknik anestesi intravena total yang dalam dengan induksi propofol dan sufentanyl serta rumatan dengan propofol dan remifentanyl dapat menurunkan kejadian disfungsi kognitif pascabedah dibandingkan teknik anestesi yang dangkal.2 Posisi Park-bench merupakan modifikasi posisi lateral untuk memfasilitasi lapangan operasi ahli bedah pada daerah fossa posterior. Tangan bagian atas diposisikan di sepanjang sisi lateral badan dan bahu bagian atas di fiksasi ke meja operasi. Ekstremitas bawah sedikit fleksi, dan bantal di tempatkan di antara dua kaki (biasanya di antara lutut). Reverse Trendelenburg dan fleksi yang bermakna sebaiknya dihindari karena dapat mengarah ke stasis vena dan penurunan aliran balik vena ke jantung.13 IV. Simpulan Dilaporkan sebuah laporan kasus seorang wanita 52 tahun dengan spasme hemifasilis sinistra. Prosedur microvascular decompression telah berhasil dilakukan dengan anestesi umum dengan tetap menerapkan kaidah-kaidah neuroanestesi. Daftar Pustaka 1. Simpson BA, Amato-Watkins A, Hourihan MD. Hemibody pain relieved by microvascular decompression of the contralateral caudal medulla: case report. Pain. 2014;155(8):1667–72. 2. Thirumala PD, Shah AC, Nikonow TN, Habeych ME, Balzer JR, Crammond DJ, et al. Microvascular decompression for hemifacial spasm: evaluating outcome prognosticators including the value of intraoperative lateral spread response monitoring and clinical Tatalaksana Anestesi pada Microvascular Decompression (MVD) characteristics in 293 patients. Journal of clinical neurophysiology: official publication of the American Electroencephalographic Society. 2011;28(1):56–66. 3. Zhang L, Yu Y, Yuan Zhang J. Microvascular cochleovestibular nerve tinnitus and vertigo. 2012;60(5):495–7. Y, Xu J, Xu X, decompression of in patients with Neurology India. 4. De Ridder D, Menovsky T. Neurovascular compression of the abducent nerve causing abducent palsy treated by microvascular decompression. Case report. Journal of neurosurgery. 2007;107(6):1231–4. 5. Karim AA, Shuer LM, Chang SD. Neurosurgery. Dalam: Jaffe RA, editor. Anesthesiologist's Manual Of Surgical Procedures. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014;120–5. 6. Monstad P. Microvascular decompression as a treatment for cranial nerve hyperactive dysfunction – a critical view. Acta Neurol Scand. 2007;115(187):30–3. 7. Wang X, Thirumala PD, Shah A, Gardner P, Habeych M, Crammond D, et al. Microvascular decompression for hemifacial spasm: focus on late reoperation. Neurosurgical review. 2013;36(4):637-43; discussion 43–4. 8. Lee CC, Liao CH, Lin CF, Yang TF, Hsu SP, Yen YS, et al. Brainstem auditory evoked potential monitoring and neuro- 49 endoscopy: two tools to ensure hearing preservation and surgical success during microvascular decompression. Journal of the Chinese Medical Association: JCMA. 2014;77(6):308–16. 9. Ashkan K, Marsh H. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia in the elderly: a review of the safety and efficacy. Neurosurgery. 2004;55(4): 840-8; discussion 8–50. 10. Detry O, De Roover A, Honore P, Meurisse M. Brain edema and intracranial hypertension in fulminant hepatic failure: pathophysiology and management. World journal of gastroenterology: WJG. 2006;12(46):7405– 12. 11. Minahan RE, Mandir AS. Neurophysiologic intraoperative monitoring of trigeminal and facial nerves. Journal of clinical neurophysiology: official publication of the American Electroencephalographic Society. 2011;28(6):551–65. 12. Meng L, Quinlan JJ. Assessing risk factors for postoperative nausea and vomiting: a retrospective study in patients undergoing retromastoid craniectomy with microvascular decompression of cranial nerves. Journal of neurosurgical anesthesiology. 2006;18(4):235–9. 13. Rozet I, Vavilala MS. Risks and benefits of patient positioning during neurosurgical care. Anesthesiology Clinics. 2007;25(3):631–x. Kerusakan Barier Pertahanan Alamiah: Sawar Darah Otak Ardana Tri Arianto, MH Soedjito Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret RSUD Dr. Moewardi Surakarta Abstrak Sawar Darah Otak (SDO) adalah struktur membran yang secara primer memisahkan serta memfiltrasi darah ataupun zat dari sirkulasi sistemik yang masuk ke dalam sirkulasi otak. Sawar Darah Otak merupakan penghalang fisik antara pembuluh darah lokal dan sebagian besar dari sistem saraf pusat itu sendiri, dan tempat berhentinya zat makromolekul. Konsep Sawar Darah Otak pertama kali diperkenalkan oleh Paul Ehrlich. Paul Ehrlich menemukan bahwa injeksi intravena perwarna ke dalam aliran darah meninggalkan noda pada seluruh jaringan di sebagian besar organ kecuali otak. Pada trauma kerusakan sawar darah otak banyak diakibatkan oleh rusaknya integritas membrane sawar darah otak dan pada tumor disebabkan oleh peningkatan permeabilitas sawar darah otak akibat invasi sel tumor. Pada keadaan trauma, disfungsi sawar darah otak dapat terjadi secara cepat ataupun lambat, gangguan dari kompleks tight junction dan integritas membran menghasilkan peningkatan permeabilitas seluler. Sedangkan tumor otak dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas sawar darah otak, pembengkakan jaringan sekitar tumor, dan terjadi absorpsi serta pengeluaran cairan dan protein dengan cairan serebrospinal di ventrikel. Terapi kortikosteroid menurunkan ekspresi dari vascular endothelial growth factor (VEGF) yang diproduksi edema yang terikat dengan sel endotel. Pengelolaan perioperatif penting untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang sawar darah otak dikarenakan kompleksitas dari anatomi, fisiologi, fungsi transpor sampai hubungan antara sawar darah otak dengan gangguan neurologis seperti yang terdapat pada kasus cedera otak traumatik dan tumor otak. Kata kunci: sawar darah otak, gangguan neurologis JNI 2015;4 (1): 50–60 Disruption of Natural Defense Barrier: Blood-Brain Barriere Abstract The blood brain Barrier (BBB) is a structural membrane that separates and filters blood and subtances that enters the cntral nervous system from systemic circulation. It is a physical barrier between the local blood vessels and most parts of the central nervous system itself, and the flow of macro substances. The concept of the blood brain barrier was first introduced by Paul Ehrlich. He found that intravenous injection of dyes into the bloodstream stained all the tissues in most organs except the brain. In traumatic brain injury, vascular disruption causes damage to integrity of the membrane BBB while in case of tumor, there's an increase of permeability due to tumor cell invasion. In traumatic brain injury , the onset of BBB dysfunction can be immediate or delayed, increased cellular permeability is the result of thr damage of the tight junction complex and membrane integrity. Brain tumor can increase the permeability of BBB edema in the surrounding area, and cause absorption and excretion of cerebrospinal fluid and protein in to the ventricel. Corticosteroid therapy can reduce the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in the edematous endothelial cells. Perioperative mamagemrnt requires comprehensive knowledge of the complexity of blood brain barrier's anatomy, physiology, transport function, and the relation between BBB with neurologic dysfunctions which are commonly seen in traumatic brain injury and tumor. Key words: blood–brain barrier, neurologic disfunction JNI 2015;4 (1): 50–60 50 Kerusakan Barier Pertahanan Alamiah: Sawar Darah Otak I. Pendahuluan Sawar Darah Otak (SDO) secara definisi adalah struktur membran yang secara primer memisahkan serta memfiltrasi darah ataupun zat dari sirkulasi sistemik yang masuk kedalam sirkulasi otak. Sawar darah otak berfungsi untuk melindungi otak dari bahan-bahan kimia dalam darah, dimana fungsi metabolik masih dapat dilakukan. Sawar darah otak ini terdiri dari sel-sel endotelial, yang tersusun sangat rapat di kapiler otak. Kepadatan yang tinggi lebih banyak membatasi lewatnya substansi-substansi dari aliran darah dibandingkan sel-sel endotelial kapiler tubuh lainnya. Proyeksi sel-sel astrosit mengelilingi sel endotelial SDO, menyediakan dukungan biokimia untuk sel tersebut. SDO berbeda dengan blood-cerebrospinal fluid barrier yang menyerupainya, suatu sel-sel koroid pada pleksus koroideus, dan dari blood-retinal barrier, yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari SDO.1 Neuron-neuron, sel-sel glia, cairan ekstraseluler otak dipisahkan dari darah oleh sawar darah otak. Sawar darah otak dicirikan sebagai lapisan seluler yang sempurna dan kontiniu dan sel-sel endotel yang disegel oleh tight junction. Komunikasi selke-sel normal antara astrocit, perisite, endotel dan neuropil yang mengelilingi penting bagi ekspresi fenomena sawar darah-otak dan mekanisme homeostatisnya. Transpor, fungsi yang dimediasi reseptor dan enzim, memainkan peran penting dalam regulasi komposisi cairan ekstraseluler otak. Molekul, diatas ukuran yang dibatasi, yang bersirkulasi dalam darah dapat memperoleh akses menuju jaringan interstisial hanya jika terdapat sistem transpor khusus untuk molekul tersebut yang terdapat dalam endotel kapiler otak. Sistem demikian untuk asam amino, transferin, insulin, Ig G, dan albumin terkationasi menjamin bahwa susunan saraf pusat (SSP) secara tetap menerima senyawa yang dibutuhkan.2 Penulisan tinjauan pustaka ini penting untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang SDO dikarenakan kompleksitas dari anatomi, fisiologi, fungsi transpor sampai hubungan antara SDO dengan gangguan neurologis, serta dalam bagian anestesiologi dan bedah yang banyak terkait 51 dengan gangguan fungsi SDO yang menyertai gangguan neurologis seperti yang terdapat pada kasus cedera otak traumatik dan tumor otak. II. Tinjauan Pustaka Sawar darah otak adalah suatu istilah yang menunjukkan suatu sistem kompleks dari filter metabolik, fisik dan transport atau suatu sawar (barier) yang mengontrol masuknya kandungan bahan kimiawi dari darah ke otak. Sawar ini mempertahankan lingkungan fisikokimia yang optimal dan stabil untuk berkerjanya sistem saraf pusat.3 Sejarah dan Riwayat Otak berfungsi dalam suatu lingkungan yang terkontrol-baik, terpisah dan milieu perifer. Mekanisme yang mengontrol lingkungan unik otak adalah sawar darah otak. Zat pewarna yang larut air diinjeksikan ke sirkulasi perifer, tidak mewarnai otak ataupun cairan cerebro spinal fluid (CSF), meskipun plexus choroid terwarnai. Eksperimen lanjutan menunjukkan bahwa zat warna yang sama yang disuntikkan ke ruang subaraknoid mewarnai otak dan CSF, tetapi tidak mewarnai jaringan perifer. Pengamatan yang diambil dan studi zat wama membawa kepada konsep sawar antara darah dan otak.2 Peneliti selanjutnya menggunakan zat warna bersifat basa yang sangat larut dalam lemak dan mampu melintasi sawar darah otak (Friedemann, 1942), menunjukkan bahwa otak terwarnai dengan transpor langsung zat warna melintasi mikrovaskulatur cerebral. Broman (1941) berpendapat bahwa fungsi sawar pada sawar darah otak berlangsung melalui sel-sel endotel kapiler dan bukan pada astrocyte end feet. Debat apakah astrocytic end feet atau endotel kapiler yang berperan pada sawar darah otak dihentikan oleh studi sitokimia elektron mikroskop oleh Reese dan Karnovsky (1967), dan selanjutnya oleh Brightmann dkk (1969). Peroksidase horseradish (BM=43.000) digunakan untuk memvisualisasikan sawar darah otak. Tidak semua pembuluh darah cerebral sepenuhnya kedap. Daerah bocor, kurang memiliki SDO endotel, terletak di posisi strategis di garis tengah 52 Jurnal Neuroanestesi Indonesia dari sistem ventrikel, dan secara kolektif disebut sebagai organ circumventricular (C Vos). Paling sering, daerah ini tidak dilindungi oleh SDO untuk alasan yang berhubungan dengan fungsi fisiologis.4,5 Dua fitur pada endotel serebral yang penting dalam membentuk sawar darah otak adalah tight junctions dan frekuensi rendah vesikel yang dihubungkan dengan transpor transendotel. Keberadaan sawar tersebut pertama kali oleh Paul Ehrlich pada akhir abad ke-19. Erhlich adalah seorang bakteriologis yang sedang mempelajari pewarnaan, yang digunakan pada beberapa penelitian untuk membuat struktur yang kecil dapat terlihat. Ketika disuntikkan, beberapa zat warna akan mewarnai seluruh organ hewan kecuali otak. Saat itu, Ehrlich menyatakan hal ini yaitu otak tidak menyerap cukup zat warna. Untuk memahami mekanisme pembentukan SDO, harus diteliti juga urutan generasi sel dan pembentukan SDO dalam SSP berkembang.6 Selanjutnya, pada percobaan berikutnya tahun 1913, Edwin Goldmann (salah satu murid Ehrlich) menyuntikkan zat warna ke cairan spinal otak secara langsung. Ia menemukan bahwa pada kasus ini otak menjadi berwarna, tetapi tidak pada bagian tubuh. Ini dengan jelas mendemonstrasikan adanya sawar di antara keduanya. Saat itu, dinyatakan bahwa pembuluh darah itu sendiri berfungsi sebagai barrier, karena Gambar 1. Kapiler pembuluh darah otak7 membran sebelumnya tidak dapat ditemukan. Konsep mengenai sawar darah otak/blood brain barrier (istilahnya hematoencephalic barrier) diajukan oleh Lisa Stern tahun 1921. Ini tidak disetujui hingga ditemukannya mikroskop elektron pada riset medis tahun 1960an dimana membran tersebut dapat dilihat. Selain fungsi penghalang telanjang endotel, SDO matang terdiri dari sistem selular kompleks dengan morfologi yang sangat khusus. Otak kapiler dibentuk oleh sel endotel yang terhubung ke dirinya sendiri dan juga terhubung ke sel endotel tetangga.5 Anatomi Sawar Darah Otak Sawar darah otak adalah suatu membran yang sangat resisten terhadap proses difusi dan memisahkan cairan intersisial otak darah. Pemeriksaan susunan saraf pusat dengan menggunakan mikroskop elektron memperlihatkan bahwa lumen kapiler darah dipisahkan dari ruang ekstra seluler oleh:2 sel endotelial di dinding kapiler, membran basalis di luar sel endotel, dan kaki-kaki astrosit yang menempel pada lapisan luar dari dinding kapiler. Sawar darah otak merupakan suatu membran yang tidak permeabel, yang secara anatomi histologi terdiri atas dua elemen. Elemen pertama berupa endotelium sel kapiler otak yang saling berhubungan erat sehingga dapat menahan pergerakan molekul yang mempunyai diameter 20Ǻ atau lebih. Elemen kedua berupa astrosit Gambar 2. Pembuluh darah kapiler susunan saraf pusat dan kapiler sistemik5 Kerusakan Barier Pertahanan Alamiah: Sawar Darah Otak yang masuk melingkari endotelial sel tersebut. Bentukan ini terdapat di seluruh otak kecuali plexus koroideus.3 Dengan menggunakan electron dense-marker seperti lanthanum dan horseradish peroksidase terlihat bahwa substansi tersebut tidak dapat menembus sel endotel kapiler karena adanya tight junction diantara sel tersebut, sehingga tight junction sangat berperan di dalam sawar darah otak. Beberapa bagian otak tidak mempunyai sawar darah otak dan mempunyai struktur sel yang berbeda. (Gambar 2) Pada daerah tersebut protein dan molekul-molekul organik yang kecil dalam darah dapat masuk ke susunan saraf pusat. Fisiologi Diseluruh tubuh selain otak, dinding-dinding kapiler (pembuluh darah terkecil) dibuat dari sel-sel endotel yang fenestrata, berarti mereka memiliki celah kecil yang disebut fenestrasi. Bahan kimia yang larut dapat melewati celah ini, dari darah ke jaringan atau dari jaringan ke darah. Selanjutnya di otak, sel-sel endotel ini tersusun lebih rapat disebut dengan tight junction. Ini membuat SDO menghambat gerakan seluruh molekul kecuali yang mampu melewati membran sel dengan kelarutan dalam lemak (misalnya: oksigen, karbondioksida, etanol, dan hormonhormon steroid) dan yang dapat melewati sistem transpor spesifik (misalnya: gula dan asam amino). Substansi dengan berat molekul lebih dari 500 dalton (500 u) biasanya tidak dapat melewati SDO, dimana molekul yang lebih kecil dapat melewatinya. Sebagai tambahan, selsel endotel memetabolisme molekul-molekul tertentu untuk mencegah mereka masuk ke SSP. Contohnya: L-DOPA, prekursor dopamin, dapat menembus SDO, dimana dopamin sendiri tidak dapat menembusnya.5 Dalam kimia, berat dihitung tidak dalam kg tetapi dalam Dalton. Faktanya, terungkap bahwa hanya molekul yang berat molekulnya kurang dari 500 dalton yang dapat menembus SDO. Sekarang berat molekul 500 dalton tidak sangat besar. Air memiliki berat molekul 18 dalton, insulin juga tidak begitu besar. Virus-virus (dengan berat molekul dalam hitungan juta) jauh lebih besar daripada ini, dan bakteri sangat jauh lebih besar 53 lagi. Jadi jarang untuk bahan kimia, virus, dan bakteri dapat menembus SDO dan masuk ke otak.8 Sebagai tambahan dari tight junction yang berfungsi mencegah transpor anatara sel-sel endotel, ada 2 mekanisme untuk mencegah difusi pasif melalui membran sel. Sel-sel glia yang mengelilingi kapiler otak menyediakan rintangan kedua untuk molekul-molekul yang hidrofilik, dan konsentrasi yang rendah dari protein interstitial di otak mencegah akses molekul hidrofilik. SDO melindungi otak dari aliran bahan-bahan kimia dalam darah. Banyak fungsi tubuh dikendalikan oleh hormon dalam dalam darah, dan ketika sekresi hormon-hormon tersebut dikendalikan oleh otak, hormon-hormon ini umumnya tidak memasuki otak dari darah. Ini akan mencegah otak untuk langsung memonitor tingkat hormon. Dalam tujuan untuk mengendalikan sekresi hormon secara efektif, ada tempat khusus dimana neuron dapat “mencontohkan” komposisi sirkulasi darah. Di tempat ini, SDO lemah; tempat ini termasuk tiga “organ sirkumventrikular”, yaitu organ subfornikal, area postrema, dan organum vasculosum dari lamina terminalis (OVLT).6 Fungsi Sawar Darah Otak Pada keadaan normal terdapat sawar yang semipermeabel dan berfungsi untuk melindungi otak dan medula spinalis dari substansi yang membahayakan. Fungsi sawar darah otak adalah melindungi otak dari berbagai variasi substansi darah, terutama senyawa toksik.5 Ada tiga fungsi penting sawar darah otak adalah: fungsi anatomi, fungsi biokimika, fungsi regulasi. Berikut ini akan dijelaskan masing masing fungsi tersebut secara lebih mendalam.5,9 Fungsi Anatomi Secara anatomis sawar darah otak melindungi otak dari bermacam-macam toksin eksogen yang berasal dari darah. Fungsi ini dapat terjadi karena struktur sawar darah otak yang mempunyai tight junction antara sel endotel yang tidak permeabel terhadap molekul berukuran besar. Fenetrasi yang terdapat pada kapiler organ lain tidak terdapat pada kapiler otak, begitu juga vesikel pinositik, yang penting bagi makromolekul pada kapiler jaringan lain. Jika integritas kapiler dalam 54 Jurnal Neuroanestesi Indonesia keadaan tidak baik, perisit yang terletak pada dinding kapiler akan meningkatkan aktifitas fungsi sawar darah otak. Perisit adalah sel fagosit yang bertanggung jawab untuk mempertahankan homeostasis antara darah dan otak serta sebagai sawar terhadap makromolekul, perisit juga mempunyai kemampuan untuk regulasi dari proliferasi, diferensiasi dan pembentukan endotel tight junction. Astrosit juga berperan dalam fungsi anatomi yang berperan dalam kontrol dinamika mikrosirkulasi, dilatasi arteriol dipicu oleh aktifitas neuron yang tergantung pada respon aktifitas kanal kalsium pada jaringan astrosit dan juga berperan untuk regulasi suplai energi untuk mendukung aktifitas fungsional neuron.7 Fungsi Biokimia Fungsi biokimia sawar darah otak adalah untuk transport selektif dari zat-zat, tersusun oleh enzim-enzim dalam sel endotel pembuluh darah kapiler otak. Plasma borne biogenic dapat dimetabolisme oleh monoamin oksidase sehingga dapat melindungi otak dari pemecahan epinefrin sistemik. Transport oleh asam amino secara signifikan dapat menyebabkan penetrasi prodrug levodopa pada sawar darah otak sehingga dopamin dapat dimetabolisme untuk pengobatan pasien parkinson. Fungsi Regulasi Agar dapat mencapai otak, cairan ekstraseluler dari darah harus melewati/menembus epitel koroid atau endotel kapiler. Zat dapat segera masuk apabila molekul dapat larut dalam air (plasma) dan membran lipid serta berukuran kecil jadi semakin larut lemak dan berukuran kecil maka akan semakin mudah menembus SDO. Molekul yang lain ada yang memerlukan protein pembawa agar dapat menembus sawar darah otak. Transport Glukosa Glukosa adalah sumber energi terbesar yang diperlukan oleh otak. Lebih 98% energi yang dipergunakan untuk menunjang fungsi saraf dapat dari pembakaran glukosa dalam darah. Transport aktif glukosa dibantu oleh protein pembawa yang spesifik. Di dalam cairan serebrospinal, konsentrasi glukosa hanya 2/3 dari konsentrasi dalam darah. Hal ini disebabkan karena glukosa secara konstan dipergunakan oleh otak. Kadar glukosa otak relatif lebih stabil dibandingkan dengan kadar glukosa dalam darah, sebab sistem transport akan berhenti/jenuh pada saat terjadi peningkatan glukosa dan akan aktif bila kadar glukosa plasma menurun (pada keadaan hipoglikemi). Keadaan glukosa ini sangat penting untuk menjaga agar fungsi saraf tetapi normal. Pada keadaan hiperglikemi yang berat dengan kadar glukosa dalam plasma darah meningkat tiga kali, benda keton dan asam laktat akan terakumulasi dalam otak dan akan menekan fungsi saraf sehingga terjadi koma diabetik. Pada keadaan hipoglikemi yang berat susunan saraf pusat menjadi overaktif, pasien akan mengalami mental confusion, berkeringat dengan nadi yang cepat. Hipoglikemi akan menyebabkan kerusakan neuron-neuron otak jika energi utama yang dibutuhkan oleh otak tidak terpenuhi (insulin koma). Transport ion Kadar ion kalium dalam cairan ekstraselular otak dan cairan serebrospinal adalah 3 mmol/I, sedangkan kadar ion kalium dalam darah antara 4-5 mmol/I. Kadar ion kalium dan natrium dalam otak diatur oleh natrium-kalium-ATPase yang terletak pada endotel membran sel pembuluh darah kapiler otak. Neurotransmisi yang optimal memerlukan kadar kalium yang konstan di dalam otak. Hal ini dapat dicapai dengan menghentikan difusi ion kalium ke otak melalui transport yang spesifik di endotel yang secara aktif mengatur kadar ion kalium. Na+/K+ ATPase banyak terdapat di kapiler otak.10 Mikrovaskuler otak mengandung 500 kali Na+/ K+ ATPase dan 1,6 kali di pleksus koroid. Na+ / K+ ATPase secara aktif mengubah dan mengatur kadar ion kalium dalam otak. Pada glioma maligna kemungkinan terdapat peningkatan Na+/K+ ATPase yang akan menyebabkan peningkatan Na dan air yang akan menyebabkan terjadinya edema vasogenik. Kortikosteroid dapat menghambat aktivitas Na+/K+ ATPase pada glioma, sehingga beberapa penulis memperkirakan bahwa efek terapi kortikosteroid adalah berkurangnya Na+/ K+ ATPase. Selain transport kalium dan ion natrium, ion bikarbonat juga dapat menembus Kerusakan Barier Pertahanan Alamiah: Sawar Darah Otak sawar darah otak walaupun sistem transport spesifiknya belum diketahui.11 Transport Asam Amino Sebagian besar asam amino netral dapat melalui sawar darah otak melalui sistem transport berbeda, yaitu sistem L, sistem A dan sistem ASC. Sistem L cenderung berkaitan dengan asam amino netral yang bercabang atau rantai dengan bentuk cincin (leusin, valin), merupakan asam amino yang tergantung dengan ion natrium dan secara kompetitif dihambat oleh asam 2 aminobisikloheptan-2-karboksilat. Sistem A cenderung berikatan dengan asam amina netral dengan pendek (alanin, serin), tergantung pada natrium dan dihambat oleh asam alfametilaminisobutirat. Sistem ASC cenderung berikatan alanin, serin dan sistein, tergantung dengan natrium dam tidak sensitif terhadap asam 2-aminosikloheptan-2-karboksilat dan sama affametilaminisobutirat.12 55 menganggu fungsi normal otak, seperti epinefrin yang terdapat banyak di dalam sirkulasi sebagai respon terhadap stress fisik ataupun emosional akan dapat mengganggu fungsi otak bila dapat mencapai otak dengan mudah. Sawar Darah Otak dan Gangguan Neurologis Terdapat hubungan antara sawar darah otak dengan gangguan neurologis, dimana SDO sendiri dapat rusak dalam beberapa penyakit penyimpanan lisosom yang berperan pada gejalagejala neurologis, masalah secara langsung disebabkan oleh terkumpulnya produk-produk yang tersimpan dalam sel-sel otak. Karena adanya SDO, terapi penggantian enzim sekarang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit penyimpanan lisosom yang tidak dapat mencapai sel otak. Beberapa hubungannnya antara lain: Transport vitamin dan mineral Otak memerlukan semua vitamin, kecuali vitamin K dan vitamin D. Hampir semua vitamin dapat menembus sawar darah otak melalui sistem transport yang berbeda. Proses transport vitamin diatur sebagai berikut: Pada saat kadar vitamin dalam darah tinggi, sedangkan dalam otak sudah cukup, maka mediator transport akan menghalangi masuknya vitamin ke otak. Pelepasan vitamin yang lambat melalui sawar darah otak bertujuan untuk mencegah kehilangan vitamin yang tiba-tiba di otak. Hal ini terjadi pada keadaan defisiensi. Untuk mengembangkan dan mempertahankan fungsinya otak juga memerlukan trace metals seperti Zn, Fe, Cu dan Meningioma.5 Transport elemen-elemen tersebut bergantung pada adanya ion bebas, organomolekule atau metalloprotein. Besi dapat masuk ke otak melalui ikatan kompleks transferin dengan reseptor endotel spesifik dan melalui endositosis.5 Kelainan anatomi 11 Kernicterus adalah suatu kondisi pada neonatus dengan otak (terutama striatum) tampak berwarna kuning. Hal ini terjadi karena penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, karena terdapat rhesus incomtabilitas antara kedua orang tuanya. Dahulu diperkirakan hal ini terjadi karena imaturitas dari sawar darah otak, tetapi pada kenyataannya maturitas tight junction telah terjadi pada usia kehamilan 12 minggu. Dalam keadaan normal bilirubin dengan protein plasma tidak dapat melewati sawar darah otak. Fungsi tersebut belum sempurna pada beberapa bayi baru lahir sehingga sebagian besar bilirubin dalam keadaan bebas dan dapat menembus sawar darah otak. Pendapat lain mengatakan bahwa imaturitas dari sawar darah otak pada bayi baru lahir berdasarkan pada: a) terdapat peningkatan protein dalam cairan serebrospinal pada bayi baru lahir, b) terdapat bilirubin didalam otak pada beberapa bayi imatur yang disebut kernicterus, c)terdapat perbedaan penetrasi beberapa substans di dalam otak, pada bayi lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Neurotransmiter Sawar darah otak impermeabel terhadap epinefrin, norepinefrin, asetilkholin, dopamin. Sehingga apabila sistem sawar darah otak ini tidak ada, maka efek dari neurotransmiter tersebut dapat Edema otak Definisi dari edem otak adalah peningkatan kandungan air di dalam jaringan otak. Edema otak dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu: 1) e d e m a otak sitotoksik, 2) edema otak interstisial, 3) 56 Jurnal Neuroanestesi Indonesia edema otak vasogenik Edema otak sitotoksik disebabkan karena akumulasi cairan intraseluler, yang biasanya terjadi pada hipoksia otak. Hipoksia berpengaruh terhadap mekanisme pompa Na+ ATP pada membran sel, menyebabkan akumulasi Na intraseluler, kemudian air akan masuk ke sel untuk mempertahankan tekanan osmotik. Dengan demikian edema yang terjadi adalah edem intraseluler primer dan akan berpengaruh terhadap sel endotel, astrosit dan neuron. Pembengkakan sel tersebut mengakibatkan ruang interstisial akan menyempit.13 Edema otak interstisial merupakan akibat dari peningkatan tekanan intraventrikuler dan hidrosefalus, sehingga menyebabkan transudasi cairan serebrospinal. Edema otak vasogenik merupakan akibat dari peningkatan permeabilitas sawar darah otak, dapat terjadi pada tumor otak dan abses otak. Tight junction menjadi tidak kompoten, sehingga menyebabkan cairan plasma masuk ke ruang interseluler. Edema vasogenik ini banyak dijumpai pada trauma, tumor, dan abses. Pada keadaan normal mekanisme autoregulasi akan bekerja keras jika terjadi hiperkapnia berat atau hipertensi berat. Bila aliran darah kapiler meningkat cukup besar dapat terjadi kerusakan tight junction. Penelitian pada hewan memperlihatkan bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya aktivitas pinositosis,akibatnya timbul peningkatan cairan di ekstraseluler dan edema otak.13 Trauma otak Pada keadaan trauma, disfungsi SDO dapat terjadi secara cepat ataupun lambat, gangguan dari kompleks tight junction dan integritas membran menghasilkan peningkatan permeabilitas seluler. Cedera menyebabkan stres oksidatif dan peningkatan produksi mediator proinflamasi dan meningkatkan regulasi dari ekspresi adhesi molekul sel pada permukaan endotel otak yang memicu influx dari sel proinflamasi menuju parenkim otak yang terkena trauma.14 Terdapat juga bukti yang mengacu bahwa cedera otak dapat mengubah ekspresi ataupun aktifitas dari SDO yang terkait transport. Proses patofisiologi gangguan ini mengacu pada interaksi fungsional normal antara sel glia dengan endotel serebrovaskuler, dimana mungkin berkontribusi terhadap disfungsi dari SDO. Terdapat kesepakatan yang berkembang dimana pada posttrauma terjadi perubahan fungsi dari SDO adalah salah satu faktor utama yang menentukan progesivitas dari cedera. Pengamatan terhadap disfungsi SDO pascacedera berimplikasi pada rusaknya sel saraf, gangguan fungsi otak (gangguan kesadaran, memori dan gangguan motorik). Struktur pembuluh darah serebral dan Gambar 3. Sawar Darah Otak dan Trauma Kepala Kerusakan Barier Pertahanan Alamiah: Sawar Darah Otak 57 Gambar 4. Mekanisme dan Respon SDO terhadap Trauma endotelnya dapat rusak karena trauma, dengan demikian terjadi kerusakan pula pada tight junction. Kerusakan mikrovaskuler posttrauma, berhubungan dengan proses terjadinya edema otak vasogenik yang terjadi akibat kerusakan integritas sawar darah otak, akibatnya terjadi akumulasi natrium dan protein didalam parenkim otak dan ekspansi cairan osmoler ke ekstraseluler.14 Disrupsi dari integritas dinding pembuluh darah mikro di otak yang disebabkan oleh benturan secara cepat mengaktivasi kaskade koagulasi. Pembentukan dari trombosit dan lekosit-agregasi trombosit terlihat pada daerah pial dan parekim vena. Koagulasi intravaskuler pascatrauma ini dinamakan fenomena “No-reflow” setelah iskemia serebral yang mengakibatkan penurunan signifikan aliran darah pada jaringan perikontusional otak. Meskipun disrupsi mekanik dari integritas vaskuler dan peningkatan permeabilitas dari SDO berhubungan dengan gangguan fungsi dari SDO yang muncul pascatrauma menyebabkan faktor darah seperti albumin dan fibrinogen masuk kedalam otak secara non selektif.14 Peningkatan permeabilitas SDO pasca trauma terhadap molekul dengan ukuran besar dapat disebabkan oleh peningkatan permeabilitas paraseluler dari sawar endothelial yang berhubungan dengan perubahan ekspresi, distribusi dan fungsi dari tight junction SDO.14 Tumor Otak Tumor otak terbanyak dibagi menjadi dua yaitu glioma dan astrositoma. Pada glioma terutama yang paling ganas yaitu glioblastoma mempunyai karakter hiperseluler tegas, pleomorfik, mitosis jumlah besar, focus nekrosis sentral dan banyak vaskularisasi. Literatur menyebutkan perubahan mrfologi pembuluh darah tumor terjadi dalam jumlah sangat banyak tetapi tergantung dari pembentukan dari fenestrasi, perubahan jumlah caveola dan mitokondria, pengecilan dari lamina basal, peningkatan ruang perivaskuler dan perisit. Sawar yang kehilangan fungsi dapat terlihat dengan pemeriksaan MRI dengan memberikan contras. Pada kontras standar tidak dapat menembus SDO tetapi terjadi sawar yang terkompromasi pada glioblastoma, astrositoma tingkat awal kurang agresif jika dibandingkan dengan glioblastoma. Pembuluh darah astrositoma terlihat masih banyak yang normaldan menunjukkan sedikit gangguan pada SDO, gangguan terhadap SDO semakin bertambah seiring dengan tingkat dari astrositoma tetapi agresifitasnya masih dibawah glioblastoma. Hasilnya derajat edema yang terjadi tergantung dari derajat kerusakan dari SDO.1,13 58 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Gambar 5. SDO dan Tumor Otak1 Tumor otak dapat menyebabkan: (1). Peningkatan permeabilitas sawar darah otak, sehingga albumin dan protein lain dapat melewati sawar darah otak; (2). Pembengkakan jaringan sekitar tumor; (3) Terjadi absorpsi dan pengeluaran cairan dan protein dengan cairan serebrospinal di ventrikel. Penyebaran air dan protein di jaringan otak tidak hanya menyebabkan terbentuk suatu massa, tetapi juga mengganggu keseimbangan elektrolit yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi neuron normal. Gumerloc mengemukakan bahwa tumor otak akan merubah permeabilitas sawar darah otak secara signifikan bila ukuran diameter tumor mencapai lebih dari 3–4 mm, akan menyebabkan peningkatan vesikel pinositosis, tight junction dan fenetrasi, kemudian jumlah kapiler akan bertambah, ruangan perivaskuler bertambah dan akhirnya menyebabkan berkurangnya fungsi sawar darah otak.1,13 Kortikosteroid dan Tumor Otak Penggunaan kortikosteroid pada edema otak terutama berhubungan secara primer ataupun sekunder dengan tuomer otak telah digunakan sejak tahun 1960an. Beberapa mekanisme dari kortikosteroid mengurangi edema telah diperkenalkan diantaranya inhibisi fospolipase A2 dari kaskade asam arakidonat, stabilisasi membrane lisosom dan peningkatan mikrosirkulasi sekitar tumor. Mekanisme terapi kortikkosteroid dalam menurunkan pembentukan edema, dimana pada studi terbaru menunjukkan bahwa kortikosteroid menurunkan ekspresi dari VEGF yang diproduksi edema yang terikat dengan sel endotel, VEGF merupakan factor permeabilitas vaskuler yang berfungsi sebagai pengatur dari angiogenesis dan permeabilitas vaskuler. VEGF mempunyai permeabilitas vaskuler yang sangat kuat bahkan lebih kuat dibandingkan histamin.15 Efek penurunan edema oleh kortokosteroid berlangsung cepat, penurunan permeabilitas vaskuler mulai terlihat 1 jam pasca pemberian kortikosteroid. Dexamethason merupakan kortikosteroid yang banyak digunakan, dan dexamethason enam kali lebih poten dibandingkan dengan prednisolon. Dexamethason mempunyai efek mineralkortikoid yang lebih kecil dibandingkan dengan kortikosteroid yang lain sehingga retensi dari natrium lebih sedikit yang menyebabkan pembentukan edema lain juga menurun. Pemberian dexamethason 4, 8, dan 16 mg per hari didapatkan peningkatan yang sama dari fungsi neurologis, tetapi efek samping yang ditimbulkan tetap berbanding dengan dosis. Infeksi Target kuman patogen yang menyebabkan ensefalitis adalah endotel sawar darah otak, sedangkan kuman patogen yang menyebabkan meningitis adalah efitel pleksus koroideus. Masuknya kuman patogen melalui penetrasi pada paraseluler dan transeluler. Kerusakan Kerusakan Barier Pertahanan Alamiah: Sawar Darah Otak 59 sawar darah otak mungkin disebabkan karena terjadi migrasi lekosit dari darah dalam jumlah besar melalui dinding kapiler otak. Kerusakan sawar darah otak ini secara klini berguna untuk pemberian antibiotika yang tidak larut dalam lemak. Infeksi susunan saraf pusat, mekanisme terjadinya kerusakan sawar darah otak tidak hanya karena adanya kuman patogen dalam meningen, tetapi juga karena terjadinya fragmentasi dinding sel, endotoksin, dan aktifitas dari sel-sel lekosit. 7 Pada kasus edema otak dapat dibedakan menjadi 3 yaitu edema otak interstitial, edema otak vasogenik dan edema otak sitotoksik. Edema otak interstisial akibat dari peningkatan tekanan intraventrikuler menyebabkan transudasi cairan serebrospinal. Edema otak vasogenik akibat dari peningkatan permeabilitas sawar darah otak, tight junction menjadi tidak kompoten, sedangkan edema otak sitotoksik merupakan akibat dari kegagalan fungsi pompa Na-K ATPase. Penyakit auntoimun Tight junction pada sel endotel pembuluh darah otak dapat dilalui oleh limfosit yang tergolong dalam T-sel. Pada beberapa penyakit saraf yang disebabkan oleh otoimum seperti, Guillain-Barre Syndrome, motoneuron disease, demyelinisasi polineuropati, terjadi serangan imunologi pada sel endotel mikrovaskuler oleh glikolipid. Secara langsung autoantibodi menyebabkan kerusakan selular yang luas, yang berakibat terjadi peningkatan permeabilitas sawar darah otak.16,17 Pada rusaknya sawar darah otak kasus trauma banyak diakibatkan oleh rusaknya integritas vaskuler, peningkatan aktivitas kaskade koagulasi dan juga peningkatan produksi faktor-faktor proinflamasi. Tumor otak dapat menyebabkan: Peningkatan permeabilitas sawar darah otak, sehingga albumin dan protein lain dapat melewati sawar darah otak dan pembengkakan jaringan sekitar tumor akibat kerusakan tight junction SDO. Kortikosteroid dapat digunakan untuk penatalaksanaan edema otak akibat tumor otak dengan cara menurunkan efek VEGF serta menurunkan permeabilitas SDO sehingga edema perifokal sekitar tumor menjadi berkurang dengan dexamethason menjadi pilihan utama karena efek mineralokortikoid yang lebih minimal. IV. Simpulan Konsep sawar darah otak telah dijabarkan oleh Ehrlich lebih dan 100 tahun lalu. Sawar darah otak berfungsi melindungi otak dari lingkungan darah dan memelihara homeostasis lingkungan mikro otak dan sawar darah otak merupakan suatu dinding yang impermeable, serta untuk melindungi otak dari berbagai gangguan yang dapat menyebabkan disfungsi otak. Dalam beberapa keadaan, fungsi sawar darah otak ini dapat terganggu, keadaan ini ada yang menguntungkan dan digunakan untuk terapi pada kelainan susunan saraf pusat Edem otak sitotoksik disebabkan karena akumulasi cairan intra seluler, yang biasanya terjadi pada hipoksia otak. Hipoksia berpengaruh terhadap mekanisme pompa Na+ ATP pada membran sel, menyebabkan akumulasi Na intraseluler, kemudian air akan masuk ke sel untuk mempertahankan tekanan osmotik. Dengan demikian edem yang terjadi adalah edem intraseluler primer danakan berpengaruh terhadap sel endotel, astrosit dan neuron. Pembengkakan sel tersebut mengakibatkan ruang interstisial akan menyempit. Daftar Pustaka 1. Deeken JF, Loscher W. The Blood-brain barrier and cancer: transporters, treatment, and trojan horses. lin Cancer Res 2007;13(6): 1663–47. 2. Zuiham. Sawar Darah Otak. Jurnal Kedokteran Nusantara 2005;38(2): 199–203. 3. Saleh SC. Neuroanestesi Klinik. Surabaya: Airlangga press; 2013 4. Gitau EN, Newton CR. Blood-brain barrier in falciparum malaria. Tropical Medicine and International Health 2005; 10 (3): 285–92. 5. Elga de Vries, Alexandre Prat. The blood– brain barrier and its microenvironment basic physiology to neurological disease. New York: Taylor & Francis Group, LLC;2005. 60 Jurnal Neuroanestesi Indonesia 6. Richard D, Zhou L, Kebede AA, Barres BA. Pericytes required for blood–brain barrier integrity during embryogenesis. Nature 2010;468: 562 – 68. 12. Hawkins RA, O’Kaney RL, Simpson IA, Vina JR. Structure of the blood–brain barrier and its role in the transport of amino acids. The journal of nutrition 2006. 7. Lawther BK, Kumar S, Krovvidi H. Blood– brain barrier. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain 2011;11(4) 13. Susan N, Wolburg-Buchholz K, Mack AF, Wolburg H, Fallier-Becker P. The Bloodbrain barrier in brain tumours. Department of Neurosurgery, University of Tübingen. Germany;2012. 8. Hartanto OS. Perubahan sawar darah otak pada proses inflamasi. Jurnal Berkala Neurosains. 2006;7(2): 49–57. 9. Van Inge R. Targeted liposomes for drug delivery across the bloodbrain barrier. Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Utrecht Nederland 2011. 10. Hsuchou H, Kastin AJ, Tu H, Markadakis EN, Stone KP, Wang Y, et al. Effects of celltype specific leptin receptor mutation on leptin transport across the BBB. Peptides 2011;32: 1392–9 11. Nitta T, Hatta M, Gotoh S, Seo Y, Sasaki H, Hashomoto N, et al. Size-selective loosening of the blood-brain barrier in claudin-5-deficient mice. J Cell Biol, 2003; 161(3):653–60. 14. Adam C, Zink BJ, Szmydynger-Chodobska J. Blood-brain barrier pathophysiology in traumatic brain injury. Transl Stroke Res. December 2011; 2(4): 492–516. 15. Kaal ECA, Vecht CJ.. The management of brain edema in brain tumors. Curr Opin Oncol 2004;16:593–600. 16. Su EJ, Fredriksson L, Geyer M. Activation of PDGFCC by tissue plasminogen activator impairs blood-brain barrier integrity during ischemic stroke. Nature Medicine 2008;14(7):731–37 17. Praveen B, Braun A, Nedergaard M. The blood–brain barrier: an overview Structure, regulation, and clinical implications. Neurobiology of Disease 2004;16(1): 1–13 Terapi Hipotermia pada Stroke Hemoragik Bau Indah Aulyan Syah*), Iwan Fuadi**), Sri Rahardjo**) Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Rumah Sakit Awal Bross Makasar, **)Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran–RSHS Bandung, ***)Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada-RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta***) *) Abstrak Terapi antipiretik merupakan salah satu terapi yang dianjurkan untuk pasien stroke karena peningkatan suhu tubuh dianggap berhubungan dengan luaran neurologis yang buruk. Namun demikian, belum ada rekomendasi yang paling tepat untuk kontrol demam baik secara farmakologi maupun mekanik akibat kurangnya temuan klinik. Saat ini, hipotermi terapeutik dianggap satu-satunya metode neuroprotektif yang sukses dalam meningkatkan luaran pasien stroke iskemik. Istilah neuroprotektif disini mengacu pada memelihara atau melindungi cedera saraf yang reversibel agar tidak rusak atau mengalami kematian sel. Metode hipotermi dianggap berpengaruh terhadap sejumlah jalur patofisiologi stroke. Pada penelitian in vitro, hipotermi mencegah edema serebral dan kerusakan sawar darah otak. Selain itu, mencegah aktivasi mikroglia, produksi radikal bebas, dan pelepasan neurotransmitter eksitotoksik serta asam laktat dan piruvat. Selain itu, cerebral metabolic rate (CMR), apoptosis dan respon inflamasi lokal juga berkurang. Hipotermi otak secara lokal dilaporkan menurunkan ekspresi gen interleukin-1b dan pembentukan edema vasogenik pada model perdarahan intraserebrial binatang. Hipotermi terapeutik dianggap lebih efektif bila dimulai lebih awal setelah onset gejala. Durasi hipotermia yang lebih lama juga memiliki efek neuroprotektif persisten dalam jangka waktu lama. Namun demikian, terapi hipotermia memiliki beberapa komplikasi terhadap jantung, paru-paru, immunologi, hematologi, dan metabolik. Komplikasi yang paling sering dilaporkan adalah pneumonia, bradikardi, aritmia, dan trombositopenia. Evaluasi efektivitas hipotermia sulit dievaluasi pada pasien yang tersedasi karena pemeriksaan neurologis harian seringkali membingungkan. Kata kunci: Antipiretik, stroke, stroke hemorrhagik, terapi hipotermi JNI 2015;4 (1): 61–8 Hypothermia Therapy in Hemorrhagic Stroke Abstract Antipyretic is among one of the suggested therapies for stroke patients. The reason is because increase in body temperature is considered related to bad neurological outcomes. However, there is no best recommendation available for controlling the temperature, neither pharmacologically nor mechanically due to less clinical practices findings available. Currently, therapeutic hypothermia is considered as the one and only successful neuroprotective in enhancing the ischemic strokes patients’ outcomes. The term neuroprotective refers to protecting or conserving various types of reversible neurological injuries from damage or further cell impairment. In vitro studies showed hypothermia prevent cerebral edema and blood brain barrier damage, as well as successfully proven effective in preventing microglia activation, free radical production, and release of exotoxic neurotransmitters, lactic acid and piruvate. In addition, cerebral metabolite rate (CMR), apoptosis, and local inflammatory response are also decreased. Local brain hypothermia is reported could lowering the 1b-interleukin gen expression and establishment of vasogenic edema among animal models with intracerebral hemorrhage. Therapeutic hypothermia is considered highly effective when initiated early in subsequent to the symptom onset. Longer duration of cooling is related to a more persistent neuroprotective effect in long periode. Despite its effectiveness, therapeutic hypothermia could generate several complications affecting the heart, lung, immunology, hepatology and metabolic states. The most common complications are pneumonia, bradicardia, arrhythmia, and thrombocytopenia. Evaluation to the effectiveness of hypothermia is difficult to measure in sedated patients due to difficulty in defining the patient’s neurological states on day to day bases Key words: Antipyretic, hemorrhagic stroke, hypothermia therapy, stroke 61 JNI 2015;4 (1): 61–8 62 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan Stroke merupakan penyebab kematian kedua di seluruh dunia dan penyebab pertama kecacatan di negara dengan pendapatan tinggi.1 Saat ini, pilihan terapi stroke masih mengecewakan bahkan tidak ada terapi yang efektif untuk stroke hemorragik selain kontrol tekanan darah dan manajemen efek sekundernya. Beberapa panduan (guidelines) menganjurkan terapi antipiretik untuk pasien stroke berdasarkan hubungan antara peningkatan suhu tubuh dengan luaran neurologis yang buruk.2-4 Kenyataannya, belum ada rekomendasi tepat yang diajukan sebagai metode kontrol demam, baik secara farmakologi maupun mekanik akibat kurangnya temuan uji klinik. Namun demikian terdapat beberapa data eksperimental yang menganjurkan beberapa macam metode neuroproteksi yang dimediasi oleh kontrol suhu pada berbagai macam model binatang dengan cedera otak akut. Selain itu, hipotermi terapeutik tampaknya satu-satunya metode neuroprotektif yang sukses dalam meningkatkan luaran pasien stroke iskemik.5 Stroke hemorrhagik/HS (perdarahan intraserebral/ intracerebral hemorrhage (ICH)) merupakan sroke yang sangat berbahaya dan berkisar 15% dari seluruh jenis stroke. Perdarahan bisa terjadi akibat riwayat traumatic brain injury (TBI), iskemia fokal, dan spontan akibat terapi anti trombotik.6 Mortalitas 30-hari ICH mencapai angka 52%.7 Setelah fase akut ICH, morbiditas dan mortalitas tinggi khususnya diakibatkan oleh pembentukan edema peri-hemorragik dan space-occupying edema yang secara bertahap berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial (TIK). Meskipun penyebab alami edema tidak diketahui, edema kebanyakan meningkat selama minggu pertama, dan mencapai maksimal pada minggu kedua setelah onset perdarahan. II. Pengaruh Peningkatan Suhu pada Stroke Peningkatan suhu tubuh dan otak dipengaruhi oleh serangkaian patofisiologis, termasuk peningkatan kadar asam amino eksitatoris (seperti glutamat dan dopamin), radikal bebas, asam laktat dan piruvat; kerusakan sawar darah otak (blood-brain barrier/ BBB); gangguan fungsi enzim, dan penurunan stabilitas sitoskeletal.8 Kejadian tersebut mengarah pada edema serebral, penurunan tekanan perfusi serebral, hingga peningkatan risiko cedera sekunder. Pada beberapa jenis stroke, seperti stroke iskemik, perdarahan subaraknoid, dan perdarahan intraserebral, intensitas efek di atas terlihat berbeda pada masing-masing jenis stroke.8 Pada tikus, penghangatan eksternal membuat kerusakan neuronal akibat iskemik bertambah luas sehingga sangat memungkinkan peningkatan suhu tubuh menjadi salah satu penyebab buruknya luaran pada stroke.8 Suatu meta-analisis menunjukkan hubungan antara demam (peningkatan suhu tubuh) dengan perburukan luaran pada pasien dengan stroke dan cedera otak lain dengan cakupan 39 studi klinik dan 14.431 pasien.4 Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu tubuh secara signifikan berhubungan dengan angka mortalitas yang tinggi, bertambahnya angka kecacatan, meningkatnya tingkat keparahan penyakit, perburukan luaran fungsional, dan bertambah lamanya perawatan di rumah sakit dan unit perawatan intensif (intensive care unit/ICU).9 Anti-piretik Secara Farmakologik pada Manajemen Stroke Suatu penelitian multisenter (29 senter) yang melibatkan 1400 pasien dengan stroke iskemik atau perdarahan intraserebral, yang dilakukan selama 5 tahun, dimana pasien menerima parasetamol 6 kali sehari selama 3 hari atau placebo. Hanya 70% pasien yang menerima terapi penuh. Rerata suhu tubuh 24 jam setelah terapi parasetamol berkisar 0,26 °C lebih rendah dibanding kelompok plasebo, namun tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah pasien yang mengalami perbaikan setelah 3 bulan. Yang menarik, pasien yang demam (37–39 °C) saat awal penelitian memiliki luaran yang baik setelah mendapatkan parasetamol. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian antipiretik pada pasien stroke yang tidak demam bukanlah pendekatan yang adekuat.10 Terapi Fisik pada Pasien Stroke Strategi yang menjanjikan untuk terapi fisik demam pada pasien stroke telah banyak direkomendasikan, namun data yang tersedia Terapi Hipotermia pada Stroke Hemorragik bahkan lebih terbatas dibanding pendekatan farmakologi (Tabel 1).9 Beberapa penelitian yang melakukan pendekatan kombinasi terapi fisik dengan asetaminofen atau antipiretik standar lain dalam kasus terapi antipiretik atau terapi fisik menunjukkan hasil yang gagal. Akibatnya, hasil tersebut tidak secara eksklusif menunjukkan efek pendinginan fisik, namun adiksi atau super-adiksi beberapa terapi obat antipiretik.9 Dalam satu penelitian, cooling blanket dengan sirkulasi udara yang dikombinasi dengan asetaminofen tidak efektif menurunkan suhu dalam 24 jam pada 113 pasien bila dibandingkan asetaminofen tunggal. Sistem sirkulasi air mencapai penurunan demam yang signifikan, namun tidak ada data dalam hal luaran fungsional.11 Dua penelitian lain menggunakan jalur kateter vena sentral untuk kontrol suhu pasien dengan demam (≥38.0 °C) diikuti pemberian asetaminofen, ibuprofen, bahkan petidin dan terapi fisik cooling blanket, iced packed, dan gastric lavage. Keduanya menunjukkan kontrol suhu tubuh yang efektif, namun hanya satu penelitian yang menunjukkan luaran fungsional setelah 6 bulan, yang sayangnya menunjukkan hasil yang tidak efektif.12, 13 Pengaruh Induksi Hipotermi pada Stroke Salah satu tujuan utama penelitian mengenai metode terapi stroke adalah untuk identifikasi metode neuroprotektif yang dapat diterapkan dalam uji klinik. Istilah neuroprotektif berarti memelihara atau melindungi cedera saraf yang reversibel agar tidak rusak atau tidak mengalami kematian sel. Beberapa obat yang diduga bersifat neuroprotektif (114 obat) dalam percobaan binatang14 ternyata tidak terbukti efektif dalam randomized control trial (RCT) manusia.15 Saat ini hipotermi terapeutik dipertimbangkan sebagai kandidat yang menjanjikan untuk stroke. Metode ini dianggap berpengaruh terhadap sejumlah jalur patofisiologi stroke. Selain itu, hipotermi telah digunakan untuk meningkatkan luaran neurologis dan angka ketahanan hidup pasien koma yang diterapi dalam 6 jam pasca henti jantung.9 Percobaan binatang (model in vitro) menunjukkan bahwa hipotermi mencegah edema serebral dan 63 kerusakan BBB. Selain itu, mencegah aktivasi mikroglia, produksi radikal bebas, pelepasan neurotransmitter eksitotoksik asam laktat, piruvat, cerebral metabolic rate (CMR), apoptosis dan respon inflamasi lokal juga berkurang.8,16 Hipotermi lebih efektif bila dimulai lebih awal setelah onset gejala. Hipotermi yang dimulai 90– 120 menit menunjukkan angka ketahanan hidup yang lebih tinggi dan luaran fungsional yang lebih baik dibanding normotermi, namun terapi setelah 180 menit menunjukkan efek yang tidak adekuat dibanding kontrol. Durasi hipotermia juga berpengaruh. Hipotermia moderat yang dilakukan selam 5 jam ternyata memiliki efek neuroprotektif persisten hingga 5 hari.9 Secara umum, hipotermi dibagi menjadi hipotermi berat dengan suhu <28 °C, hipotermi sedang/moderat dengan suhu 28–33 °C, dan hipotermi ringan dengan suhu 33–36°C. Saat ini, kebanyakan penelitian menggunakan hipotermi ringan hingga sedang karena efek samping hipotermia seperti hipokalemia, gangguan irama dan konduksi jantung, komplikasi infeksi dan koagulopati. Selain itu, hipotermi berat juga memerlukan sedasi dan ventilasi mekanik yang justru berhubungan dengan efek samping lain atau evaluasi defisit neurologis yang tidak tepat. Secara khusus, uji klinik membagi induksi hipotermia menjadi dua kelompok: kelompok dengan pasien yang tersedasi dan menerima ventilasi mekanik dan kelompok pasien yang menerima cooling dalam keadaan sadar.9 Terapi Cooling pada Pasien dengan Ventilasi Mekanik Sekitar 100 pasien stroke menerima terapi hipotermi moderat selama sedasi dan ventilasi mekanik, semua pasien menerima cooling dengan target suhu 33 °C, yang diukur melalui termistor buli-buli. Hipotermi dimulai antara 4–24 jam setelah onset gejala, dan dipelihara selama 48–72 jam. Angka mortalitas ditemukan sekitar 44% pada awal penelitian, dibandingkan 78% pada kelompok terapi standar. Pada penelitian tersebut, cooling efektif dalam mengontrol tekanan intrakranial (TIK). Namun demikian, peningkatan TIK sekunder yang kadang-kadang melebihi nilai TIK awal dan memerlukan terapi Intervens N dkk, Endovascular 102 cooling + asetaminofen, ibuprofen, pethidine, cooling blanket Cooling blanket 47 (sirkulasi air) + asetaminofen Endovascular 296 cooling + asetaminofen, ibuprofen, cooling blanket, iced packed, gastric lavage SAH, IS, 2 ICH ≥35,5 Jumlah pusat Suhu penelitian (°C) I C H , 1 ≥38,3 SAH, IS, TBI, dan lain-lain S A H , 1 ≥38,3 IS, ICH, TBI SAH, IS, 13 ≥38,0 ICH Penyakit 7-14 3 1 Buli-buli Buli-buli Timpani tubuh Durasi terapi Pengukuran (hari) 1 Timpani D e m a m Positif, 0,0 ( h i n g g a vs 4,3°C, p = 14 hari) 0,0001 Hasil (Prim EP) N o r m o - Negatif, 5,5 vs t e r m i a 44,2% p=0,19 selama 24 jam D e m a m Positif, 4,1 selama 24 vs 16,1°C, jam p=0,001 D e m a m Positif, 2,87 selama 72 vs 7,92°C, jam p<0,001 Prim EP Keterangan : n=jumlah pasien yang diikutsertakan, ICH = intracerebral hemorrhage, SAH = subarachnoid hemorrhage, IS = ischemic stroke, TBI = traumatic brain injury, Prim EP = Primary End Point Broessner 2009 Diringer, 2004 Mayer dkk, 2004 Cooling blanket Cooling blanket 220 (sirkulasi udara) + asetaminofen Referensi, Tahun Table 1.Penelitian Randomized Trial Prospektif yang Mencakup Terapi Kombinasi Fisik dan Antipiretik.9 64 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Terapi Hipotermia pada Stroke Hemorragik osmotik ditemukan signifikan pada beberapa pasien saat fase rewarming (penghangatan). Periode penghangatan merupakan fase yang paling kritis pada semua pasien yang menjalani terapi hipotermi karena semua kematian disebabkan oleh adanya peningkatan TIK hingga menyebabkan terjadinya herniasi pada fase ini. Karena dasar inilah, banyak dianjurkan kombinasi terapi cooling dan pembedahan dekompressif dengan target efek neuroprotektif dan kontrol TIK yang efektif. Seperti kebanyakan pasien dengan perawatan lama, pneumonia merupakan efek samping mayor yang sering dijumpai, namun ini sukses diterapi dengan antibiotik.17 Terapi Cooling pada Pasien Sadar Sejauh ini, jumlah penelitian pada pasien yang tidak tersedasi masih terbatas. Suatu publikasi penelitian studi prospektif melakukan hipotermia pada 17 pasien yang dibandingkan dengan 56 pasien kontrol. Kompensasi berupa menggigil diatasi dengan petidine 25–50 mg. Pendekatan ini menurunkan suhu hingga 36,8–35,5 °C selama terapi. Ditemukan kecenderungan mortalitas yang lebih rendah pada pasien yang menerima hipotermi, namun tidak signifikan. Penelitian lain menggunakan kombinasi terapi antipiretik dan hipotermia, dengan suhu dipelihara antara 36 dan 37 °C selama 24 jam pada 18 pasien yang berbaring pada cooling matras yang diperfusi dengan air dan menerima terapi petidin. Target suhu dicapai kecuali pada 2 pasien, dan tidak ada efek samping utama yang ditemukan. Pada penggunaan metode cooling endovascular pertama pada 18 pasien sadar selama 24 jam, ditemukan pertumbuhan lesi yang lebih rendah pada gambaran MRI dibanding 22 pasien normotermi. Tiga belas pasien mencapai suhu target dengan rerata waktu 77 ± 44 menit dan hipotermi ditoleransi baik semua pasien. Terapi Hipotermia pada Stroke Hemorrhagik Penelitian yang memantau efek hipotermia pada stroke iskemik sudah cukup banyak. Sayangnya, hanya sebagian kecil uji klinik yang memantau efek hipotermia, terutama jangka panjang pada pasien stroke hemorrhagik. Penelitian tersebut melaporkan bahwa hipotermia mengurangi edema dan defisit fungsional, dan tidak berhubungan 65 dengan efek samping negatif.6 Kebalikan dari penelitian iskemi serebral, hipotermi tidak secara konsisten meningkatkan derajat pemulihan atau mengurangi cedera otak pada kebanyakan studi SH. Hal ini terjadi mungkin karena hipotermi tidak efektif sebagai cytoprotectant untuk SH (sesuai dengan penelitian binatang). Namun demikian, beberapa penelitian binatang menunjukkan bahwa hipotermi bisa bersifat neuroprotektif pada ICH dengan cara mengurangi pembentukan edema melalui berbagai macam mekanisme.18 Pengalaman pertama penggunaan hipotermia pada terapi ICH oleh Howell dkk pada tahun 1956. Hipotermia dengan suhu 30°C – 32°C diinduksi pada 8 pasien dengan ICH spontan. Meskipun gejala herniasi membaik pada semua pasien, namun 6 pasien meninggal akibat komplikasi sistemik, dan yang paling sering adalah aspirasi. Dari cerita anekdot mengenai penelitian ini, mereka menginduksi hipotermi dengan kantong es, alkohol, dan bahkan membuka jendela di tengah-tengah musim dingin di Kanada saat itu. Data pertama yang menunjukkan kesuksesan penerapan hipotermi pada pasien stroke hemorragik (perdarahan intraserebral) dilakukan pada tahun 2010 oleh Kollmar dkk. Dua belas pasien dengan perdarahan intraserebral (>25 cc) diterapi dengan hipotermi ringan hingga 35 °C, yang dipelihara dengan alat endovaskular selama 10 hari. Hipotermi efektif mencegah pembentukan edema perihemorragik pada pasien aktif, sedangkan pasien grup kontrol menunjukkan progresi volume edema yang signifikan seiring dengan waktu. Hipotermi jangka panjang yang dimulai dalam 12 jam setelah onset gejala sangat efektif sebagai terapi anti-edema karena mencapai angka ketahanan hidup yang sangat baik setelah 90 hari (100%). Namun demikian, pneumonia banyak ditemukan pada pasien kelompok hipotermi.17 Terapi hipotermi juga pernah dievaluasi pada manajemen perdarahan subarachnoid (subarachnoid hemorrhage/SAH). Gasser dkk melakukan terapi pada 21 pasien dengan SAH dan edema serebral yang parah untuk melihat efek hipotermi jangka panjang (>72 jam). Sembilan persen diterapi <72 jam dan 66 Jurnal Neuroanestesi Indonesia 12% lebih dari 72 jam. Efek ketidaktergantungan fungsional setelah 3 bulan tercapai pada 48% pasien, namun luaran tidak berbeda antara pasien dengan kontrol (tanpa hipotermi). Komplikasi infeksi ditemukan sama pada kedua kelompok.19 Pada penelitian lain, hipotermi otak secara lokal dilaporkan menurunkan ekspresi gen interleukin1b dan pembentukan edema vasogenik pada model perdarahan intraserebral babi.20 Komplikasi Hipotermia Induksi hipotermia terapeutik merupakan prosedur perawatan intensif yang harus dilakukan dengan pemantauan kontinyu. Karena kebanyakan pasien yang menerima terapi adalah pasien sakit kritis, maka mereka lebih rentan terhadap komplikasi. Komplikasi ini tampaknya berkaitan dengan derajat hipotermi. Secara umum, hipotermi ditoleransi baik, namun komplikasi dapat mencakup: 1) jantung: aritmia, bradikardi, penurunan kontraktilitas jantung, dan hipotensi; 2) immunologi: immunosupresi; 3) hematologi: trombositopenia dan koagulopati ringan; dan 4) metabolik: menggigil, hiperglikemia, hipokalemia, ileus, dan diuresis yang diinduksi dingin. Komplikasi yang paling sering dilaporkan adalah pneumonia, diikuti bradikardi asimtomatik, aritmia jantung, dan trombositopenia. Pneumonia tampaknya terjadi lebih sering pada pasien terintubasi yang menjalani cooling. Cooling endovaskuler dengan selimut hangat untuk mengatasi menggigil merupakan alternatif cooling permukaan dan dapat menurunkan derajat pneumonia. Fase paling berbahaya dari hipotermi terapeutik adalah pada periode penghangatan. Perhatian utama harus ditujukan pada pasien stroke dengan massa intrakranial dan peningkatan TIK. Penghangatan yang cepat dapat mengarah ke systemic inflammatory response syndrome (SIRS) dengan vasodilatasi sistemik, hipotensi, dan refleks peningkatan TIK. Karena itu, ditetapkan suatu aturan penghangatan pada pasien dengan peningkatan TIK sebaiknya dengan kecepatan 0,1 °C per jam. Kecepatan yang lebih tinggi 0,25–0,33 °C per jam dapat ditoleransi pada pasien tanpa masalah TIK. Komplikasi hipotermi biasanya sulit dievaluasi pada pasien yang tersedasi. Pasien yang tersedasi dan menerima terapi hipotermi seakan-akan tetap bertahan dalam sistem sehingga membingungkan pemeriksaan dan prognosis neurologis. Ini menjadi suatu issue utama pada pasien stroke yang memerlukan pemeriksaan neurologis harian.19 Masih dalam Penelitian 1. Target suhu. Target suhu optimal masih belum ditentukan. Kebanyakan penelitian fokus pada suhu 35 atau 33 °C. 2. Durasi hipotermi. Saat ini, beberapa data menganjurkan 12–24 jam durasi terapi berdasarkan uji klinik cedera otak akut dan henti jantung. Namun demikian, terapi hipotermi sebaiknya diiringi dengan pemeriksaan parameter kerusakan sel saraf seperti MRI dan biomarker serum.9 3. Mode ventilasi selama hipotermia. Terdapat dua metode ventilasi yang dilakukan, yaitu α-sat atau pH-stat. Keduanya memberikan efek yang berbeda pada aliran darah otak (cerebral blood flow/CBF). pH-stat: pH dan hasil analisis gas darah (AGD) lain diukur berdasarkan suhu aktual pasien, dengan target memelihara pH 7,4 dan paCO2 5,3 kPa (40 mmHg). α-stat (alpha-stat): pH dan hasil AGD lain diukur pada suhu 37 °C, bukan suhu aktual pasien, dengan target yang sama. TIK ditemukan lebih tinggi pada pHstat dibandingkan alpha-stat. pH-stat juga menunjukkan peningkatan CBF dibanding α-stat. 4. Teknik kontrol suhu. Cooling eksternal atau internal mewakili pendekatan ini. Sejauh ini, tidak ada metode optimal antara keduanya. Masih menjadi pertanyaan apakah cooling eksternal dapat ditoleransi baik oleh pasien sadar. Sebaliknya, pendekatan endovaskuler bersifat invasif dan memerlukan penanganan kompleks pada situasi darurat. 5. Terapi antishivering. Pendekatan farmakologi seperti petidin tampaknya efektif pada pasien stroke yang sadar. Namun, opioid memiliki efek samping seperti sedasi, mual, dan muntah. Hal ini tidak nyaman buat pasien bahkan bisa meningkatkan risiko aspirasi. Terapi Hipotermia pada Stroke Hemorragik 67 6. Infeksi. Satu efek samping utama selama terapi hipotermi yang paling penting adalah pneumonia. Patogenesis komplikasi ini masih tidak diketahui pasti. Namun efek samping ini selalu dapat diterapi dengan antibiotik yang adekuat.9 4. Greer DM, Funk SE, Reaven NL, Ouzounelli M, Uman GC. Impact of fever on outcome in patients with stroke and neurologic injury: a comprehensive meta-analysis. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2008;39(11):3029–35. III. Simpulan 5. van der Worp HB, Sena ES, Donnan GA, Howells DW, Macleod MR. Hypothermia in animal models of acute ischaemic stroke: a systematic review and meta-analysis. Brain: a journal of neurology. 2007;130(Pt 12):3063–74. Data yang tersedia saat ini belum dapat menentukan apakah terapi hipotermi efektif secara rutin diterapkan pada pasien stroke, terutama stroke hemorrrhagik. Teknik cooling yang efektif sudah ditetapkan dan dapat memelihara hipotermi yang stabil. Namun, efikasi (manfaat) pendekatan ini terhadap luaran fungsional masih harus dikonfirmasi oleh RCT yang besar. Daftar Pustaka 1. Kolominsky-Rabas PL, Heuschmann PU, Marschall D, Emmert M, Baltzer N, Neundorfer B, et al. Lifetime cost of ischemic stroke in Germany: results and national projections from a population-based stroke registry: the Erlangen Stroke Project. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2006;37(5):1179–83. 2. Adams HP, Jr., del Zoppo G, Alberts MJ, Bhatt DL, Brass L, Furlan A, et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, Clinical Cardiology Council, Cardiovascular Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational tool for neurologists. Circulation. 2007;115(20):e478–534. 3. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland). 2008;25(5):457–507. 6. MacLellan CL, Clark DL, Silasi G, Colbourne F. Use of prolonged hypothermia to treat ischemic and hemorrhagic stroke. Journal of neurotrauma. 2009;26(3):313–23. 7. Broderick J, Connolly S, Feldmann E, Hanley D, Kase C, Krieger D, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage in adults: 2007 update: a guideline from the American Heart Association/ American Stroke Association Stroke Council, High Blood Pressure Research Council, and the Quality of Care and Outcomes in Research Interdisciplinary Working Group. Circulation. 2007;116(16):e391–413. 8. Dietrich WD, Atkins CM, Bramlett HM. Protection in animal models of brain and spinal cord injury with mild to moderate hypothermia. Journal of neurotrauma. 2009;26(3):301–12. 9. Kallmunzer B, Kollmar R. Temperature management in stroke - an unsolved, but important topic. Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland). 2011;31(6):532–43. 10. den Hertog HM, van der Worp HB, van Gemert HM, Algra A, Kappelle LJ, van Gijn J, et al. The paracetamol (acetaminophen) in stroke (PAIS) trial: a multicentre, randomised, placebo-controlled, phase III trial. The Lancet Neurology. 2009;8(5):434–40. 11. Mayer SA, Kowalski RG, Presciutti M, 68 Jurnal Neuroanestesi Indonesia Ostapkovich ND, McGann E, Fitzsimmons BF, et al. Clinical trial of a novel surface cooling system for fever control in neurocritical care patients. Critical care medicine. 2004;32(12):2508–15. 12. Broessner G, Beer R, Lackner P, Helbok R, Fischer M, Pfausler B, et al. Prophylactic, endovascularly based, long-term normothermia in ICU patients with severe cerebrovascular disease: bicenter prospective, randomized trial. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2009;40(12):e657–65. 13. Diringer MN. Treatment of fever in the neurologic intensive care unit with a catheterbased heat exchange system. Critical care medicine. 2004;32(2):559–64. 14. O'Collins VE, Macleod MR, Donnan GA, Horky LL, van der Worp BH, Howells DW. 1,026 experimental treatments in acute stroke. Annals of neurology. 2006;59(3):467–77. 15. Molina CA, Montaner J, Abilleira S, Arenillas JF, Ribo M, Huertas R, et al. Time course of tissue plasminogen activator-induced recanalization in acute cardioembolic stroke: a case-control study. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2001;32(12):2821–7. 16. Kollmar R, Schwab S. Hypothermia in focal ischemia: implications of experiments and experience. Journal of neurotrauma. 2009;26(3):377–86. 17. Kollmar R, Staykov D, Dorfler A, Schellinger PD, Schwab S, Bardutzky J. Hypothermia reduces perihemorrhagic edema after intracerebral hemorrhage. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2010;41(8):1684–9. 18. Kawanishi M, Kawai N, Nakamura T, Luo C, Tamiya T, Nagao S. Effect of delayed mild brain hypothermia on edema formation after intracerebral hemorrhage in rats. Journal of stroke and cerebrovascular diseases: the official journal of National Stroke Association. 2008;17(4):187–95. 19. Samaniego EA. Therapeutic Hypothermia in Acute Stroke. Dalam: Sadaka F, editor. Therapeutic Hypothermia in Brain Injury: InTech; 2013. 20. Wagner KR, Beiler S, Beiler C, Kirkman J, Casey K, Robinson T, et al. Delayed profound local brain hypothermia markedly reduces interleukin-1β gene expression and vasogenic edema development in a porcine model of intracerebral hemorrhage. Dalam: Hoff J, Keep R, Xi G, Hua Y, editors. Brain Edema XIII. Acta Neurochirurgica Supplementum. 96: Springer Vienna; 2006, 177–82. Interaksi Otak-Paru pada Neurocritical Care Dewi Yulianti Bisri, Tatang Bisri Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin-Bandung Abstrak Pasien cedera otak traumatik (COT) berat merupakan kasus trauma yang paling sering masuk ke ruang terapi intensif dan kemudian terjadi multiple organ dysfunction dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Disfungsi neurologik berat dihubungkan dengan terjadinya edema paru dan cedera paru yang akan memperburuk outcome, dapat terjadi pada cedera otak traumatik, subarachnoid hemorrhage, status epileptikus, dan mati otak. Ventilasi mekanis yang sering digunakan dalam pengelolaan pasien sakit kritis, juga dapat memicu respons paru dan organ lain termasuk otak akibat terjadinya inflamasi. Pengaruh dari paru ke otak terlihat bahwa kebanyakan pasien yang selamat dari acute respiratory distress syndrome (ARDS) menunjukkan kemunduran kognitif yang menetap saat dipulangkan. Mekanisme yang mendasarinya belum diketahui, tapi hiperglikemia, hipotensi dan hipoksia/ hipoksemia di ICU secara nyata berkorelasi dengan outcome neurologik yang tidak baik tersebut. Sebaliknya, pengaruh dari otak ke paru terlihat bahwa sepertiga dari pasien COT terjadi acute lung injury (ALI), yang memperburuk outcome, tapi penyebabnya belum jelas, namun kemungkinan mekanismenya antara lain neurogenic lung/pulmonary edema, mediator inflamasi, infeksi nosokomial, dan efek buruk dari terapi neuroproteksi. Neurogenic pulmonary edema merupakan komplikasi cedera SSP yang telah dikenal dengan baik akibat pelepasan katekolamine masif. Sebagai simpulan pada pasien dengan cedera otak dan gagal nafas akut, pencegahan dari cedera otak iskemik dan penggunaan strategi proteksi paru yang hati-hati merupakan hal yang utama. Sejak cross-talk antara otak dan paru diketahui dapat terjadi melalui berbagai jalur yang berbeda, pengendalian variabel fisiologis merupakan hal penting untuk proteksi otak. Kata kunci: cedera otak traumatik, interaksi otak-paru, neurocritical care Brain-Lung Interaction in Neurocritical Care JNI 2015;4 (1): 69–77 Abstract Severe traumatic brain injury patient is one of the most frequent traumatic cases admitted to intensive care unit (ICU) and develop multiple organ dysfunction with high rate of morbidity and mortality. Severe neurological dysfunction associated with pulmonary edema and pulmonary injury which can further worsen clinical outcome has been observed in traumatic brain injury, subarachnoid hemorrhage, status epilepticus, and in brain death cases. Mechanical ventilation that is commonly used in the management of critically ill patients can also trigger pulmonary and other organs responses including the brain, in relation to the inflammation caused. The effect from lung to the brain can be seen by the fact that many acute respiratory distress syndrome (ARDS) survivors showed a persistent cognitive deterioration when discharge. The underlying mechanisms remains unknow, but hyperglycemia, hypotension and hypoxia/hypoxemia in ICU are significantly correlated with this unfavorable neurological outcome. On the other hand, the effect from brain to the lung can be seen by the fact that one-third of acute brain injury patients develop acute lung injury (ALI), that worsen the clinical outcome, but the cause remaining obscure. The possible mechanisms include neurogenic lung edema, inflammatory mediators, nosocomial infection, and the adverse effect of neuroprotective therapy. Neurogenic pulmonary edema is a well-recognized complication of central nervous system insult attributed to a massive catecholamine release. As conclusion in patient with brain injury and acute lung injury, prevention of inadvertent ischemic brain insult and the use of protective lung strategies are mandatory. Since the cross-talk between the brain and lungs may occurs through different pathway, greater control of physiological variables might be important to protect the brain. Key words: brain-lung interaction, neurocritical care, traumatic brain injury JNI 2015;4 (1): 69–77 69 70 Jurnal Neuroanestesi Indonesia I. Pendahuluan II. The Brain-Lung-Brain Axis Cedera otak atau cedera paru adalah penyebab paling sering masuknya pasien ke unit perawatan kritis dan pasien ini sering berkembang menjadi multiple organ dysfunction dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi.1 Ventilasi mekanis sering merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam bagian life support pada pasien ini, dengan tujuan untuk memperbaiki pertukaran gas dan menurunkan muscle workload. Akan tetapi, disamping efek terapeutik tersebut, ventilasi mekanis dapat menimbulkan kerusakan paru dan inflamasi (barotrauma) yang dapat menyebar ke organ bagian distal. Hal ini karena ada umpan balik (feedback) dan selanjutnya berperan pada terjadinya cedera paru akibat ventilator. Ketidakseimbangan homeostasis perifer ini berdasarkan pada berbagai jalur cross-talk antara paru dengan organ-organ lain, termasuk otak.1 Pada pasien yang sakit kritis, disfungsi neurologik mungkin merupakan penanda sekunder dari adanya kerusakan, dan substrat neuroanatomi mengalir dan menganggu organ lain. Beberapa laporan menunjukkan bahwa respons inflamasi lokal dalam susunan saraf pusat (SSP) dapat menimbulkan perubahan sistim imun dan respons inflamasi sistemik.1 Bukti-bukti klinis adanya brain-lung interaction (crosstalk brainlung) adalah pasien dengan acute respiratory distress syndrome (ARDS) sering menunjukkan adanya gangguan fungsi kognitif yang menetap pada saat pasien dipulangkan. Sebaliknya pasien cedera otak traumatik, subarachnoid hemorrhage (SAH), status epileptikus, mati batang otak menunjukkan adanya edema dan kerusakan paru.1,2 Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada cross talk otak-paru. Dari setiap bagian tubuh ada “percakapan”, semua “bagian” aktip “ bercakap” untuk kelangsungan hidup. Sebagai contoh cross talk otak-jantung adalah pada peningkatan tekanan intrakranial. Bila tekanan intrakranial meningkat, maka tekanan darah meningkat karena tekanan perfusi otak adalah tekanan darah rata-rata dikurangi tekanan intrakranial, sehingga peningkatan tekanan darah (Cushing’s respons) adalah sebagai mekanisme pertahanan tubuh supaya tidak terjadi iskemia, jadi disini ada “percakapan” otak dengan jantung. Disfungsi neurologikal berat dan cedera dihubungkan dengan kecenderungan berkembangnya edema paru dan cedera paru (lung injury) yang dapat memperburuk outcome klinis. Keadaan ini dapat dilihat pada cedera otak traumatik, SAH aneurisma, status epileptikus, dan mati otak.2 Lebih baru, penelitian telah menunjukkan bahwa kelainan paru kritis seperti cedera paru akut (acute lung injury/ALI) dan ARDS mungkin bertanggung jawab untuk cedera otak dan outcome neurokognitif yang buruk. Seraya implikasi dari penemuan ini dipertimbangkan, mekanisme biologik yang mendasarinya membutuhkan klarifikasi.2 Penelitian menggunakan model porcine untuk mengevaluasi efek independen dan kombinasi dari hipertensi intrakranial akut dan ARDS eksperimental pada cedera paru dan kerusakan otak. Mereka mencatat bahwa marker (penanda) cedera paru bertambah dengan adanya hipertensi intrakranial akut dan terjadi peningkatan selanjutnya bersamaan dengan adanya hipertensi intrakranial acut/ARDS. Lebih jauh, kadar kerusakan otak meningkat pada ARDS dan lebih meningkat pada kombinasi hipertensi intrakranial acut/ARDS. Penelitian menunjukkan edema paru setelah cedera otak traumatik adalah akibat tidak balansnya pelepasan katekholamine yang menimbulkan venokonstriksi pulmonal dan atau gagal ventrikel kiri.2 Lebih nyata bahwa paru dan otak menunjukkan suatu terintegrasi fisiologikal adalah bila terjadi cedera pada salah satu (paru atau otak) akan mempengaruhi yang lainnya. Efek ini dimediasi melalui jaringan sinyal yang kompleks termasuk jalur neural, inflamatori, imunologik, dan neuroendokrin. Dibutuhkan penelitian fisiologikal untuk menerangkan bagaimana edema paru berkembang setelah cedera otak, khususnya kontribusi dari disfungsi ventrikel kiri, venokonstriksi pulmonal, dan kebocoran kapiler atau kegagalan stres.2 Dapatkah ada satu tindakan untuk membatasi disfungsi paru setelah suatu cedera otak traumatik Interaksi Otak-Paru pada Neurocritical Care akut? Satu penelitian randomized controll trial (RCT) besar tentang proteksi paru selama ventilasi mekanis pada ALI atau ARDS secara konsisten mengeksklusi pasien dengan cedera neurologik dengan argumen bahwa seting proteksi paru, seperti positive and expiratory pressure (PEEP) yang tinggi dan hiperkapnia permisif dapat mempengaruhi fisiologi intrakranial. Akan tetapi, penelitian terbaru mendukung bahwa strategi ventilasi proteksi paru mungkin aman dan efektif dalam mengelola ALI/ARDS dan cedera otak berat.2 Penelitian juga dibutuhkan untuk menjelaskan konsekuensi neurologik pada ALI/ARDS. Efek ini sebagian dimediasi oleh mekanisme hipoksik. Satu penelitian eksperimental besar dengan bukti-bukti klinis menunjukkan bahwa sepsis adalah suatu injuri pada otak melalui rentang mekanisme, dan hasil dari penelitian cohort prospektif besar, menunjukkan bahwa ada satu hubungan antara sepsis dan penurunan kognitif. Masuk akal bahwa efek sepsis pada otak mungkin relevan pada disfungsi otak pada ALI/ARDS. Dibutuhkannya penelitian untuk menunjukkan adanya hubungan ini dan untuk menentukan strategi terapi spesifik (misalnya meningkatkan pasokan oksigen otak atau menurunkan sinyal neuroinflamasi), mungkin dapat memperbaiki outcome neurologik dan kognitif.2 III. Interaksi Otak-Paru Dari Paru ke Otak Multiple organ dysfunction syndrome (MODS) adalah penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas pada pasien ARDS. Hal yang menarik adalah kebanyakan pasien yang selamat dari ARDS menunjukkan kemunduran kognitif yang menetap saat dipulangkan. Mekanisme yang mendasarinya belum diketahui, tapi hiperglikemia, hipotensi dan hipoksia/hipoksemia di ICU secara nyata berkorelasi dengan outcome neurologik yang tidak baik tersebut. Integritas fungsi otak bergantung pada oksigen dan glukosa. Kontrol gula darah yang ketat menurunkan kejadian polineuropati pada pasien kritis. Hipoksemia berpengaruh pada disfungsi otak akibat ARDS dan menimbulkan atropi 71 serebral. Respons terhadap hipoksia disebabkan karena hypoxia-inducible transcription factor (HIF)-1 alpha dan HIF-2 alpha yang mengatur ekspresi beberapa gen yang berhubungan dengan angiogenesis, metabolisme energi, cell survival atau pertumbuhan stem cell neural. Tidak ada konsensus tentang kerja HIF pada neuron yang survival setelah iskemia/hipoksia. Hipoksia akan memicu gangguan oksidatif phosphorilase dan pembentukan radikal bebas diusulkan sebagai mekanisme penyakit neurodegeneratif kronis.1 Pertanyaan penelitian laboratorium yang baru tentang mekanisme tepat bagaimana ALI dapat memicu kerusakan neuron. Integritas hippocampus diperlukan untuk belajar, memori, dan kognisi. Pada penelitian model porcine, lebih tingginya tingkatan kerusakan neuron hippocampus berhubungan dengan hipoksemia yang dipicu oleh cedera paru daripada yang dipicu oleh penurunan pasokan oksigen, sehingga kemungkinan penyebabnya adalah adanya respons imun akibat ALI.1 Endotel sawar darah otak (blood-brain barrier) dan sawar darahparu (blood-lung barrier) yang normal, akan mentransdusi sinyal dari darah ke sel otak atau sel paru. Menariknya, pada beberapa keadaan kedua barier menjadi lebih permeabel, memfasilitasi jalur komunkasi humoral antara otak dan paru.1 Pemberian endotoksin pada tikus menggambarkan adanya inflamasi sistemik bersama dengan Gambar 1. Pengaturan Aliran Darah Otak Aliran darah otak diatur oleh autoregulasi, PaCO2, dan PaO2. 72 Jurnal Neuroanestesi Indonesia PGE: Prostaglandin E NO: Nitric Oxide NST: Nucleus of the solitary tract CVOs: circumventricular organs IL-6: Interleukin-6 IL-1B: Interleukin-1B TNF-alpha: Tumor Necrotizing Factor Alpha ALI: Acute Lung Injury ARDS: Acute Respiratory Distress Syndrome Gambar 2. Jalur komunikasi antara perifer (paru) dan SSP selama ventilasi mekanis. SSP menerima informasi melalui 3 jalur: humoral, neural, selular.4 aktivasi mikroglia dan astroglia SSP. Keadaan ini diikuti dengan kematian sel dalam berbagai daerah di otak, dengan hipokampus merupakan daerah yang paling rentan. Pada pasien dengan septik syok, telah diobservasi adanya kerusakan sawar darah otak, yang dinilai dengan magnetic resonance imaging (MRI). Keadaan ini juga dihubungkan dengan outcome yang buruk dan delirium akibat sepsis. Bukti ini mendukung bahwa ALI mungkin mempunyai implikasi pada disfungsi otak setelah dirawat di ICU, akan tetapi mekanismenya masih belum dimengerti dengan jelas.1 Gambar 1 menunjukkan bahwa bila terjadi hipoksemia atau hiperkarbia, maka aliran darah otak meningkat sebagai akibat dari vasodilatasi serebral. Peningkatan aliran darah otak ini akan menimbulkan terjadinya bertambah beratnya edema otak dan lebih tingginya tekanan intrakranial dan resiko terjadinya iskemia otak bertambah besar. Adanya interaksi paru-otak terlihat dengan adanya hipoksemia dan atau hiperkarbia dapat memperburuk fungsi otak.3 Pasien dengan ALI atau ARDS masuk ke ICU menunjukkan perubahan neuropsikologis dan mempunyai efek buruk pada kualitas hidup.4 Jalur komunilasi paru-otak dapat melalui berbagai jalur antara lain jalur humoral, jalur neural dan jalur seluler. Efek inflamasi dari paru dengan meningkatnya kadar IL-6, TNF-alpha, IL-1B akan menyebabkan terjadinya inflamasi di otak. Sebaliknya pada cedera otak tertutup, juga dikeluarkan sitokin proinflamasi.4 Ventilasi mekanis dapat memicu respons paru dan organ lain termasuk otak akibat terjadinya inflamasi. Ventilasi mekanis yang sering digunakan dalam pengelolaan pasien sakit kritis, dapat memicu respons inflamasi, yang mungkin berperan dalam gagal organ yang lebih distal. Jadi, mungkin ada cross-talk kompleks antara paru dan organ lain termasuk otak. Yang menarik, pasien yang selamat dari ALI atau ARDS sering mengalami perburukan kognitif saat dipulangkan dari rumah sakit. Disfungsi neurologik mungkin merupakan penanda sekunder dari cedera. Interaksi otak-paru sedikit dibahas pada literatur, tapi bukti-bukti terbaru mendukung bahwa paru dan otak dapat memicu inflamasi melalui berbagai mediator. 5 Satu penelitian melaporkan morpho-fungsional dan efek biokimia dari ventilasi mekanis dengan volume tidal rendah (8 mL/kg) dan tinggi (30 mL/ kg) pada paru dan otak tikus yang sehat. Ventilasi mekanis mempunyai pengaruh (impact) serius pada struktur dan fungsi paru, menimbulkan ventilator-associated lung injury (VALI) dan memicu kerusakan organ perifer, termasuk otak. Dalam hal ini, ventilasi mekanis dan sedasi pada paru sehat dan paru yang sakit telah dilaporkan berhubungan dengan gangguan neurologik, memori dan disfungsi kognitif. Sebaliknya, cedera otak mungkin memperberat kerusakan paru, kemungkinan dengan memicu komplikasi Interaksi Otak-Paru pada Neurocritical Care Gambar 3. Korelasi Cedera Paru Akut dengan Cedera Otak. 5 paru yang lebih tinggi dan akan merubah outcome neurologik. Secara keseluruhan, informasi tentang jalur cross-talk multipel antara otak dan paru sangat terbatas. 5 Mediator inflamasi dari paru akan menimbulkan inflamasi di otak dan demikian juga sebaliknya inflamasi otak akan menimbulkan inflamasi di organ lain diantaranya paru. Dari Otak ke Paru Telah jelas bahwa cedera otak sendiri dan sekuele neurologisnya adalah penyebab utama dari kematian atau disabilitas. Meskipun demikian, bukti yang muncul menunjukkan bahwa disfungsi ekstraserebral, terutama gagal nafas, sering terjadi dan meningkatkan morbiditas serta mortalitas. Dua penelitian melaporkan bahwa sepertiga dari pasien cedera otak akut terjadi ALI, yang memperburuk outcome, tapi penyebabnya belum jelas. Mekanismenya antara lain neurogenic lung/pulmonary edema, mediator inflamatori, infeksi nosokomial, dan efek buruk dari terapi neuroproteksi. Cedera otak mungkin meningkatkan kerentanan paru terhadap cedera lainnya atau insult iskemik reperfusi, maka meningkatkan risiko gagal paru. Pada penelitian hewan model kelinci dengan cedera otak masif, diketahui adanya peningkatan cedera paru akibat ventilator bila dibandingkan dengan hewan dengan otak yang intact pada seting ventilator yang sama. 1,6 73 Neurogenic pulmonary edema (NPE) merupakan komplikasi cedera SSP yang telah dikenal dengan baik. Telah ditunjukkan sebagai akibat adanya pelepasan katecholamine masif setelah cedera otak masif, yang menyebabkan krisis hipertensi dan diikuti dengan hipotensi neurogenik. Penelitian telah dilakukan dengan mencegah cedera paru inflamasi pada tikus dengan dengan mencegah respon hipertensi dengan memberikan alpha-adrenergic antagonist. Strategi ini dapat mengurangi inflamasi sistemik dan memelihara integritas membran kapilar-alveolar. Pada penelitian yang sama, pengendalian hipotensi neurogenik dengan noradrenalin memperbaiki respon inflamasi sistemik dan oksigenasi. Sejak up-regulation dari mediator proinflamasi terjadi pada semua organ, terapi antiinflamasi dini dan obat vasoaktif bisa dibenarkan dalam pengelolaan donor yang mati otak.1,6 Mikroglia otak dan astrosit menjadi sumber utama dari mediator inflamasi selama cedera otak akut. Peningkatan permeabitas sawar darah otak mengijinkan pasase mediator dari otak ke perifer, memprovokasi perbedaan transcranial yang dapat memulai komplikasi sekunder dan disfungsi multiorgan. Penelitian eksperimental dengan membuat cedera perdarahan serebral, meningkatkan ekspresi molekul adhesi intraseluler dan faktor jaringan pada otak dan paru, dan paru menunjukkan rekruitment netrofil yang progresif dengan disrupsi struktur alveolar. Lebih jauh, cedera otak traumatik (COT) pada tikus secara progresif merusak membran intraseluler dari pneumosit tipe 2 dan secara persisten meningkatkan lipid peroksidase pada paru. Pertahanan fungsi imun pada jalan nafas mungkin telah berubah pada stadium awal COT. Menariknya, terjadinya kerusakan ultrastruktur dini epitel tracheobronchial telah diketahui pada tikus model COT. Penemuan ini mendukung bahwa perubahan dini pada mekanisme pertahanan jalan nafas bertanggung jawab pada tingginya kejadian ventilator associated pneumonia (VAP) pada pasien COT.1,6 Sistim saraf otonom juga berperan dalam neuro-imun crosstalk. Inflamasi sistemik sebagian dikontrol oleh nerves vagus (jalur 74 Jurnal Neuroanestesi Indonesia antiinflamatori) dan dalam skenario critical care, kendali dipengaruhi oleh cedera otak akut dan sedasi. Aktivasi sistim saraf simpatis mungkin termasuk dalam “remote” prekondisioning iskemik. Iskemik prekondisioning adalah suatu mekanisme endogen yang dapat memproteksi organ yang berbeda (misalnya otak atau paru) melalui perkembangan adaptasi lokal atau respons remote terhadap iskemia. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) Acute respiratory distress syndrome pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967 oleh Ashbaugh dkk, sebagai “acute onset of tachypnoe, hypoxemia and loss of compliance after a variety stimuli”. The ARDS Definition Task Force (definisi Berlin) telah merevisi definisi American-European Consensus Conference (AECC) yang telah dipakai sejak tahun 1994.7 Mekanisme iskemik prekondisioning termasuk triger dan mediator dan rantai second massenger kompleks yang termasuk adenosine, nitrix oxida, heat shock protein, mitogen-activated protein kinase, dan mitokhondria ATP-dependen potassium channel.1 Neurogenic pulmonary edema disebabkan karena pada cedera otak traumatik terjadi pelepasan katecholamine secara masif yang dapat menimbulkan vasokonstriksi pulmonal dan sistemik. Vasokonstriksi pulmonal dapat menimbulkan peningkatan tekanan vena Tabel 1. Kriteria dan Klasifikasi ARDS Definisi AECC Akut onset Onset Gambaran toraks Edema Paru Klasifikasi Definisi Berlin Dalam 7 hari dari adanya faktor resiko (lihat tabel dibawah) Tidak ada faktor resiko ditentukan secara formal Opasitas bilateral pada toraks foto Opasitas bilateral konsisten dengan edema paru pada toraks foto atau CT. PAOP ≤18 mmHg atau tidak ada bukti diterangkan dengan gagal jantung atau klinis dari peningkatan tekanan atrium kiri overload cairan. Diperlukan echocardiographi atau pengukuran objektif lainnya ALI PaO2/FiO2 ≤300 ARDS PaO2/FiO2 ≤200 Ringan 200 <PaO2/FiO2 ≤300 Sedang 100 <PaO2/FiO2 ≤200 Berat PaO2/FiO2 ≤100 Dikutip dari: Bersten AD.7 Faktor resiko untuk terjadinya ARDS terlihat pada tabel 2 dibawah ini: Tabel 2. Faktor Resiko untuk ARDS Langsung Pneumonia Aspirasi isi lambung Kontusio paru Tidak Langsung Sepsis non-pulmonal Trauma multiple Transfusi masif Emboli lemak Near drowning Cedera inhalasi Cedera reperfusi Pankreatitis Bypass kardiopulmonal Dikutip dari: Bersten AD.7 Interaksi Otak-Paru pada Neurocritical Care 75 Gambar 4. Patofisiologi Neurogenic Pulmonary Edema.8 Dikutip dari: Gopinath SP, Robertson CS. Dalam: Cottrell JE, Smith DS, eds. Anesthesia and neurosurgery, 3rd ed., St Louis: Mosby Year Book Inc; 1994 pulmonal dan tekanan kapiler paru dan terjadi edema paru akut dan perdarahan paru.8 IV. Implikasi Terapeutik Pencegahan kelainan neurologis sekunder terhadap ARDS adalah sangat penting, tapi sayangnya informasi yang dapat mempengaruhi managemen klinis masih langka. Mencegah hipoksemia dan mempertahankan tekanan arteri yang adekuat dan glisemia mempunyai efek positif pada outcome neurologik. Mencegah insult iskemik sekunder setelah cedera otak traumatik berat sering digunakan untuk pendekatan terapi. Aliran vaskuler yang tinggi akan memicu terjadinya cedera paru (tekanan perfusi otak >70 mmHg beresiko terjadinya ARDS).1 Kejadian ARDS 5 kali lebih tinggi pada COT berat bila aliran darah otak dipertahankan dengan tekanan perfusi serebral >70 mmHg. Beberapa aspek dari ventilasi mekanis di neurocritical care mempunyai implikasi pada cedera otak dan cedera paru. Gangguan elastanse paru pada hari kelima pada pasien dengan kerusakan otak dengan ventilasi mekanis tanpa PEEP, mendukung suatu efek akibat cedera otak terhadap organ distal. Pada konteks yang sama, aplikasi level PEEP yang kurang hati-hati meningkatkan dead space alveolar bisa merubah hemodinamik serebral. PEEP yang menimbulkan distensi berlebihan dan dihubungkan dengan peningkatan PaCO2 akan diikuti dengan peningkatan tekanan intrakranial. Walaupun rekomendasi berdasarkan evidencebase spesifik tentang bagaimana mengeset ventilator pada cedera paru dan otak akut sedikit, klinisi harus dapat melakukan proteksi pada kedua organ tersebut.1 Faktor yang menimbulkan cedera otak sekunder (pada COT, tumor, stroke) dapat sistemik dan intrakranial. Faktor sistemik adalah hipoksemia, hipotensi, anemia, hipokarbia, hiperkarbia, pireksia, hiponatremia, hipoglikemia, 76 Jurnal Neuroanestesi Indonesia hiperglikemia. Faktor intrakranial adalah hematoma, peningkatan tekanan intrakranial, seizure, infeksi, dan serebral vasospasme. Pengelolaan neuroanesthesia sama dengan neuro ICU sama dengan Brain Resuscitation yaitu ABCDE Neuroanestesi dan Critical Care yaitu mencegah dan mengobati cedera otak sekunder yang dapat dilakukan dengan teknik ABCDE neuroanestesi yaitu:3A) airway: jalan nafas bebas sepanjang waktu, B) breathing: ventilasi kendali, normokapnia pada COT dan sedikit hipokapnia pada tumor otak, C) circulation: hindari lonjakan tekanan darah, hindari peningkatan tekanan vena serebral, normovolemia, iso-osmoler, normoglikemia, D) drugs: hindari obat dan teknik anestesi yang akan meningkatkan tekanan intrakranial, berikan obat yang berefek proteksi otak, E) environment : pengendalian suhu dengan target 35 oC di kamar oprasi. Sedangkan metode Brain Protection adalah basic methods: airway, breathing, circulation, hipotermi - low normothermia, farmakologik dengan anestetika intravena, anestetika inhalasi, lidokain, mannitol, magnesium, erythropoietin, alpha-2 agonists dexmedetomidine. Jadi drugs dalam neuroanestesi sama dengan proteksi otak secara farmakologik. Penerapan pengetahuan interaksi otak-paru adalah pada ABCE neuroanestesi atau basic method dan hipotermi pada brain protection. Terapi tersebut dengan mempertimbangkan interaksi paru-otak yang mana pencegahan hipoksemia dan target normokapnia pada breathing adalah supaya tidak terjadi vasodilatasi serebral, kenaikan tekanan intrakranial, dan iskemia otak. Terapi hipertensi intrakranial pada COT berat berdasarkan Brain Trauma Foundation Guideline tahun 2007 adalah:9,10 pasang monitor tekanan intrakranial, pertahankan tekanan perfusi otak 50–0 mmHg. First-tier therapy: drainase ventricular (bila tersedia), mannitol 0,25–1 g/kg iv (bisa diulang bila osmolaritas serum <320 mOsm/L dan pasien euvolemik), hiperventilasi untuk mencapai PaCO2 level 30–35 mmHg. Second-tier therapy: Hiperventilasi untuk mencapai PaCO2 <30 mmHg (dianjurkan dipantau saturasi oksigen bulbus vena jugularis/ SJO2, dan atau aliran darah otak), dosis tinggi barbiturat, hipotermi, dekompresif kraniektomi. Terapi peningkatan tekanan intrakranial juga berdasarkan interaksi otak-paru yang mana pengaturan ventilasi pada first-tier dan secondtier disebabkan karena CO2 memegang peranan penting dalam pengaturan aliran darah otak. V. Simpulan Pada pasien dengan cedera otak dan gagal nafas akut, pencegahan dari cedera otak iskemik dan penggunaan strategi proteksi paru adalah hal yang utama. Sejak cross-talk antara otak dan paru diketahui dapat terjadi melalui berbagai jalur yang berbeda, pengendalian variabel fisiologis menjadi penting untuk proteksi otak, kecuali bila bukan organ utama yang cedera. Kerusakan otak setelah cedera paru akut dapat merupakan suatu lapangan baru dari riset yang menarik untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien sakit kritis. Daftar Pustaka 1. Gonzalvo R, Marti-Sistac O, Blanch L, Lopez-Aguilar L. Bench-to-bedside review: brain-lung interaction in the critically ill-a pending issue revisited. Critical Care 2007;11(216):1–5 2. Stevens RD, Puybasset L. The brain-lungbrain axis. Intensive Care Med 2011;37:1054– 56 3. Bisri T. Penanganan Neuroanestesia dan Critical Care: Cedera Otak Traumatik. Bandung; Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, 2012. 4. Lopez-Aguilar L, Fernandez-Gonzalo MS, Turon M, Quilez ME, Gomez-Simon V, Jodar MM, et al. Lung-brain interaction in the mechanically ventilated patient. Med Intensiva 2013;37(7):485–92 5. Pelosi P, Rocco PRM. The lung and the brain: a dangerous cross talk. Critical Care 2011;15:168 Interaksi Otak-Paru pada Neurocritical Care 6. Lee K, Rincon F. Pulmonary complication in patient with severe brain njury.Critical Care Research and Practice. Vol 2012, article ID 207247.do:10.1155/2012/207247 7. Bersten AD. Acute respiratory distress syndrome. Dalam: Bersten AD, Soni N, eds. Oh’s Intensive Care Manual. China: Butterworth Heinemann Elsevier; 2014,382– 91 8. Gopinath SP, Robertson CS. Management of severe head injury. Dalam: Cottrell JE, Smith DS, eds. Anesthesia and neurosurgery, 77 3rd ed., St Louis: Mosby Year Book Inc; 1994,661–80. 9. Bullock MR, Povlishock JT. Guideline for the management of severe traumatic brain injury. Brain Trauma Foundation Guideline 2007 10. Bendo AA. Perioperative management of adult patient with severe head njury. Dalam: Cottrell JE, Young WL, eds. Cottrell and Young’s neuroanesthesia; 2011, 317–25. Indeks Penulis A A. Himendra Wargahadibrata, 28 Ardana Tri Arianto, 50 B Bambang Suryono, 17, 34 Bau Indah Aulyan Syah, 43, 61 D Dewi Yulianti Bisri, 28, 69 I Iwan Fuadi, 1, 61 M Muhammad Dwi Satriyanto, 8 MH. Sudjito, 50 R Radian Ahmad Halimi, 1 S Sandhi Christanto, 17 Silmi Adriman, 28 Siti Chasnak Saleh, 8, 17, 34, 43 Sri Rahardjo, 28, 43, 61 T Tatang Bisri, 1, 17, 69 W Wahyu Sunaryo Basuki, 34 Indeks Subjek A Antipiretik, 61 O Olfactory groove meningioma, 28 C Cedera otak traumatik, 1, 69 Cedera kepala traumatik berat, 34 Cedera kepala pascatrauma, 1 P Perdarahan intraserebral spontan/nontrauma, 8 Penatalaksanaan perioperatif, 17, 34 Post traumatic headache, 1 G Gangguan neurologis, 50 S Spasme hemifasialis, 44 Sawar darah otak, 50 Stroke, 61 Stroke hemoragik, 61 I Interaksi otak paru-paru, 69 H Hematoma intrakranial, 1 Hipofisektomi transsphenoidal, 17 M Microvascular decompression, 43 N Neurocritical care, 69 Numeric rating scale, 1 T Tanda cushing, 34 Terapi hipotermia, 61 Tumor hipofisa, 17 Tumor supratentorial, 28 Pedoman Bagi Penulis 1. Ketentuan Umum Redaksi majalah Jurnal Neuroanestesia Indonesia menerima tulisan Neurosains dalam bentuk Laporan Penelitian, Laporan Kasus, Tinjauan Pustaka, serta surat ke editor. Naskah yang dipertimbangkan dapat dimuat adalah naskah lengkap yang belum dipublikasikan dalam majalah nasional lainnya. Naskah yang telah dimuat dalam proceeding pertemuan ilmiah masih dapat diterima asalkan mendapat izin tertulis dari panitia penyelenggara. 2. Judul Bahasa Indonesia tidak melebihi 12 kata, judul bahasa Inggris tidak melebihi10 kata. 3. Abstrak Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta tidak boleh lebih dari 250 kata. Abstrak Penelitian: Terdiri dari IMRAD (Introduction, Method, Result, and Discussion). Dalam introduction mengandung latar belakang dan tujuan penelitian. Dalam Discussion diakhiri oleh Simpulan. Contoh Penulisan Abstrak Penelitian: Latar Belakang dan Tujuan: Disfungsi kognitif pascaoperasi (DKPO) sering terjadi dan menjadi masalah serius karena dapat menurunkan kualitas hidup pasien yang menjalani pembedahan dan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui angka kejadian DKPO pada pasien yang menjalani operasi elektif di GBPT RSU dr. Sutomo dan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Subjek dan Metode: Penelitian ini melibatkan 50 orang sampel berusia 40 tahun atau lebih yang menjalani pembedahan lebih dari dua jam. Dilakukan serangkaian pemeriksaan fungsi kognitif praoperasi dan tujuh hari pascaoperasi. Domain kognitif yang diukur adalah atensi dan memori. Faktor yang diduga mempengaruhi kejadian DKPO dalam penelitian ini adalah usia, tingkat pendidikan dan durasi operasi. Hasil: Tujuh hari pascaoperasi 30% sampel mengalami gangguan atensi, 36% sampel mengalami gangguan memori dan 52% sampel mengalami disfungsi kognitif pascaoperasi. Pemeriksaan kognitif yang mengalami penurunan bermakna adalah digit repetition test, immediate recall, dan paired associate learning. Analisa logistik regresi variabel usia (p=0,798), tingkat pendidikan (p=0,921) dan durasi operasi (p=0,811) terhadap kejadian DKPO menunjukkan hubungan yang tidak bermakna. Namun bila dianalisa pada masing masing kelompok usia tampak bahwa persentase pasien yang mengalami DKPO konsisten lebih tinggi pada usia ≥50 tahun, tingkat pendidikan ≤6 tahun dan durasi operasi ≥180 menit Simpulan: Kejadian disfungsi kognitif pada pasien yang menjalani operasi elektif di GBPT RSU dr. Sutomo cukup tinggi. Faktor usia, tingkat pendidikan dan durasi operasi tampaknya mempengaruhi kejadian DKPO meskipun secara statistik tidak signifikan. Kata kunci: anestesi umum, atensi, kognitif pascaoperasi, memori Abstrak Laporan Kasus: Terdiri dari Pendahuluan, Kasus, Pembahasan, simpulan Contoh Penulisan Abstrak Laporan Kasus: Abstrack Meningoencephaloceles are very rare congenital malformations in the world that have a high incidence in the population of Southeast Asia, include in Indonesia. Children with anterior meningoencephaloceles should have surgical correction as early as possible because of the facial dysmorphia, impairment of binocular vision, increasing size of the meningoencephalocele caused by increasing brainprolapse, and risk of infection of the central nervous system. In the report, we presented a case of a 9 monthsold baby girl with naso-frontal encephalocele and hydrocepahalus non communicant, posted for VP shunt (ventriculo-peritoneal shunt) and cele excision. Becaused of the mass, nasofrontal or frontoethmoidal and occipital meningoencephalocele leads the anaesthetist to problems since the anaesthesia during the operation until post operative care. Anaesthetic challenges in management of meningoencephalocele, which most of the patients are children, include securing the airway with intubation with the mass in nasofrontal or nasoethmoidal with its associated complications and accurate assessment of blood loss and prevention of hypothermia pengelolaan hemodinamik dan jantung, 2) jalan nafas dan ventilasi, 3) evaluasi fungsi neurologic dan kebutuhan pemantauan tekanan intracranial atau drainase ventrikel atau keduanya. Key words: Anaesthesia, difficult ventilation, difficult intubation, naso-frontal, meningoencephalocele, padiatrics Contoh cara penulisannya: Abstrak Tinjauan Pustaka: Terdiri dari Pendahuluan, Isi, dan Simpulan Abstrak Stroke hemoragik merupakan penyakit yang mengerikan dan hanya 30% pasien bertahan hidup dalam 6 bulan setelah kejadian. Penyebab umum dari perdarahan intracranial adalah subarachnoid haemorrhage (SAH) dari aneurisma, perdarahan dari arteriovenous malformation (AVM), atau perdarahan intraserebral. Perdarahan intraserebral sering dihubungkan dengan hipertensi, terapi antikoagulan atau koagulopati lainnya, kecanduan obat dan alcohol, neoplasma, atau angiopati amyloid. Mortalitas dalam 30 hari sebesar 50%. Outcome untuk stroke hemoragik lebih buruk bila dibandingkan dengan stroke iskemik dimana mortalitas hanya sekitar 10-30%. Stroke hemoragik khas dengan danya sakit kepala, mual muntah, kejang dan defist neurologic fokal yang lebih besar. Hematoma dapat menyebabkan letargi, stupor dan koma. Disfungsi neurologic dapat terjadi dari rentang sakit kepala sampai koma. Pengelolaan dini difokuskan pada: 1) Kata kunci: perdarahan intracranial, stroke perdarahan Diakhir abstrak dibuat kata kunci yang ditulis berurutan secara alphabet, 3-5 buah. 4. Cara Penulisan Makalah Penulisan Daftar Pustaka: • Nomor Kepustakaan berdasarkan ürutan dating”di dalam teks, Vancouver style. Jumlah kepustakaan minimal 8 dan maksimal 20 buah. • Dari Jurnal: 1. Powers WJ. Intracerebral haemorrhage and head trauma. Common effect and common mechanism of injury. Stroke 2010;41(suppl 1):S107-S110. 2. Qureshi A, Tuhrim S, Broderick JP, Batjer HH, Hondo H, Hanley DF. Spontaneus intracerebral haemorrhage. N Engl J Med 2001,344(19):1450-58. Dari Buku: 1. Ryan S, Kopelnik A, Zaroff J. Intracranial hemorrhage: Intensive care management. Dalam: Gupta AK, Gelb AW, eds. Essentials of Neuroanesthesia and Neurointensive Care. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008, 22936. 2. Rost N, Rosand J. Intracerebral Hemorrhage. Dalam: Torbey MT, ed. Neuro Critical Care. New York: Cambridge University Press;2010,143-56. Materi Elektronik Artikel Jurnal dalam Format Elektronik Lipton B, Fosha D. Attachment as a transformative process in AEDP: operationalizing the intersection of attachment theory and affective neuroscience. Journal of Psychotherapy Integration [Online Journal] 2011 [diunduh 25 November 2011]. Tersedia dari: http://www.sciencedirect.com 5. Jumlah halaman Laporan Kasus : 10-12 halaman Laporan Penelitian : 15 halaman Tinjauan Pustaka : 15-20 halaman Surat Pembaca : 1 halaman Ditik 1,5 spasi, Times New Roman, 11 font. Penanggungjawab, pemimpin, dan segenap redaksi Jurnal Neuroanestesi Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada mitra bebestari: Prof. Siti Chasnak Saleh, dr., SpAnKIC,KNA (Universitas Airlangga ‒ Surabaya) Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., SpAnKNA,KMN (Universitas Airlangga ‒ Surabaya) Dr. Sri Rahardjo, dr., SpAnKNA, KAO (Universitas Gadjah Mada ‒ Yogyakarta) Dr. Sudadi, dr., SpAnKNA (Universitas Gadjah Mada ‒ Yogyakarta) Dr. M. Sofyan Harahap, dr., SpAnKNA (Universitas Diponegoro ‒ Semarang) Abdul Lian, dr., SpAnKNA (Universitas Diponegoro ‒ Semarang) MH. Sudjito, dr., SpAnKNA (Universitas Sebelas Maret ‒ Surakarta) Dr. Hamzah, dr., SpAnKNA (Universitas Airlangga ‒ Surabaya) Atas kerjasama yang terjalin selama ini, dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Neuroanestesi Indonesia, semoga kerjasama ini dapat berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang Redaksi FORMULIR PESANAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : ………………………………………………………………... Alamat Rumah : ………………………………………………………………... ………………………………………………………………... ……………….. Kode pos…………………………................. Telepon …………………………Faks …………………......... HP ………………………………E-mail…………................... Alamat Praktik : ………………………………………………………………... Telepon …………………………Faks ………………............. Alamat Kantor : ………………………………………………………................ ……………………….. Kode pos…………………………….. Telepon …………………………Faks ……………………...... Mulai berlangganan : ………………………………. s.d ……………………………... Saya bermaksud untuk berlangganan JNI secara teratur dengan mengirimkan biaya berlangganan sebesar Rp. 250.000,00 per tahun** Pembayaran melalui : □ Langsung ke Sekretariat Redaksi Jl. Prof. Dr. Eijkman No. 38 – Bandung 40161 Mobile : 087722631615 JNI dikirimkan ke* : □ □ □ Alamat Rumah Alamat praktik Alamat Kantor Bandung, ………………………………… Hormat Saya ( * pilih salah satu ** foto kopi bukti transfer mohon segera dikirimkan/faks ke Sekretariat Redaksi *** termasuk ongkos kirim untuk wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten )