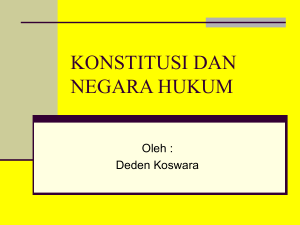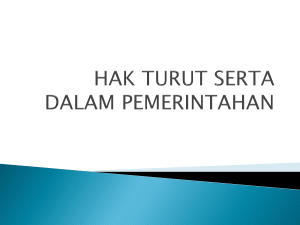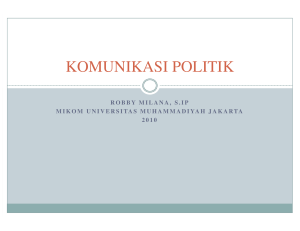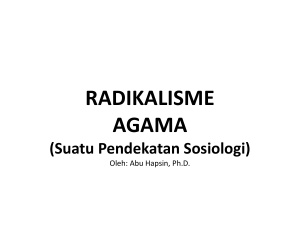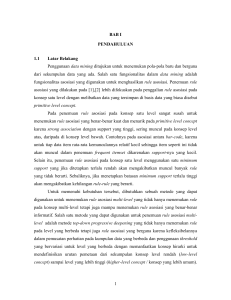RADIKALISME A. Pengertian Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang artinya akar, sumber atau asal mula. Istilah radikal memiliki arti ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang mengenut paham radikal (Widiana, 2012). Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan. Berikut definisi dan pengertian radikalisme dari beberapa sumber buku: 1. Menurut Kartodirdjo (1985), radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. 2. Menurut Rubaidi (2007), radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. 3. Menurut Hasani dan Naipospos (2010), radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. 4. Menurut Partanto dan Al Barry (1994), radikalisme adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. B. Ciri – Ciri Radikalisme Menurut Masduqi (2012), seseorang atau kelompok yang terpapar paham radikalisme ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah Nabi yang tak pernah melakukan kesalahan ma’sum padahal mereka hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri maka secara langsung mereka telah bertindak congkak merebut otoritas Allah. 2. Radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya samhah (ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. 3. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. 4. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi. 5. Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain sebagai ahli bid’ah dan sesat. 6. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengan mereka sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah. Sedangkan menurut Rubaidi (2007), ciri-ciri gerakan radikalisme dalam agama ditandai dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. 2. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. 3. Karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Quran dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. 4. Menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadits. 5. Gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah. C. Faktor Penyebab Radikalisme Menurut Azyumardi (2012), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau sumber masalah tumbuhnya paham radikalisme pada seseorang adalah sebagai berikut: 1. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat AlQuran. Pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (mainstream) umat. 2. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. 3. Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat, sehingga sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. 4. Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi. 5. Melalui internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Selain itu, menurut Hikam (2016), terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia, yaitu: a. Faktor Geografi Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi sekaligus ,rentang terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dan merupakan negara kepulauan, perlindungan keamanan yang konprenshif sangat diperlukan. b. Faktor Demografi Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (schools of thought) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal. c. Faktor Sumber Kekayaan Alam Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengkampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah. d. Faktor Ideologi Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya. e. Faktor Politik Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya check and balances sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensil. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya Destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan (Preasure Grups). f. Faktor Ekonomi Kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik di tingkat regional maupun internasional. g. Faktor Sosial Budaya Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya cosmopolitan dan pop (popular culture) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial dan sebagainya). Kondisi anomie dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kawula muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadap pengaruh negatif seperti hedonism dan kekerasan. h. Faktor Pertahanan dan Keamanan Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang. D. Kelebihan dan Kelemahan Radikalisme Kelebihan Radikalisme Penganut radikalisme punya tujuan yang jelas dan sangat yakin dengan tujuan tersebut. Penganut radikalisme memiliki kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar dalam mewujudkan tujuannya. Kelemahan Radikalisme Penganut radikalisme tidak dapat melihat kenyataan yang sebenarnya karena beranggapan bahwa semua yang berseberangan pendapat adalah salah. Umumnya memakai cara kekerasan dan cara negatif lainnya dalam upaya mewujudknya tujuannya. Penganut radikalisme menganggap semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah musuh yang harus disingkirkan. Penganut radikalisme tidak perduli dengan HAM (Hak Asasi Manusia). E. Pencegahan Radikalisme Menurut Azyumardi (2012), deredikalisasi dilakukan dengan enam pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Adapun penjelasan pendekatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu; 1) pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, serta 2) pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokersa, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan. 2. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, redukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrindoktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad melainkan identik dengan aksi terorisme. 3. Resosialisasi adalah program yang dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana dan narapidana teroris dalam bersosialisasi, berbaur dan menyatu dengan masyarakat. Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti publik lecture, workshop, dan lainnya. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif. 4. Pembinaan wawasan kebangsaan adalah memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan, dan kebangsaan Indonesia. 5. Pembinaan keagamaan adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan keagamaan mengacu pada moderasi ideologi, yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. 6. Pendekatan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan deradikalisasi. Dunia usaha mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, dunia usaha juga memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat lebih kreatif dan mandiri. HAM DAN RULE OF LAW A. Pengertian HAM Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia, sesuai dengan kodratnya. Menurut ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah singkat timbulnya HAM a. Inggris Magna Charta (1215) : terlahir karena protes keras kalangan bangsawan atas pemerintahan John Lackland (1199-1216),seorang raja inggris yang pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. Petition Of Right (1628) : perselisihan raja Charles 1 dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The House Of Common). Bill Of Right (1689) : ditandatangani oleh raja Willem III sebagai hasil dari The Glorious Revolution. b. Perancis Trias Politica : disusun oleh Montesque yang berisi tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Declaration des Droits de’L Home et du Citoyen : pernyataan HAM dan warga negara, diumumkan pada tanggal 27 Agustus 1789. c. Amerika Serikat The Four Freedom : Freedom of Speech : kebebasan berbicara Freedom of Religion : kebebasan beragama Freedom of Fear : kebebasan dari rasa takut Freedom of Want : kebebasan dari kemelaratan B. Hak Asasi Manusia di Indonesia Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, antara lain : Periode 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949 berlaku UUD 1945. Periode 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950 berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode 17 agustus 1950 sampai tahun 1959 berlaku UUDS 1950. Periode 5 juli 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945. Dalam UUD 1945 butir-buti hak asasi manusia hanya tercantum beberapa saja. Sementara konstitusi RIS 1945 dan UUDS 1950 hampir bulat-bulat mencantumkan isi deklarasi HAM dari PBB. Pada awal orde baru, salah satu tujuan pemerintah adalah melaksanakan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 serta berusaha untuk melengkapinya. Tugas untuk melengkapi HAM ini ditangani oleh panitia MPRS yang kemudian menyusun rancangan piagam hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara yang dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968. Pada awal reformasi itu diselenggarakan pula sidang istimewa MPR (1998) yang salah satu ketetapannya berisi piagam HAM. C. Pengertian Rule of Law Rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke 19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi, kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut. Rule of law lahir dengan semangat yang tinggi, bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan lainlain, kemudian mengambil alih dominasi dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit dan kerajaan. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “Rule Of Law”.Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of law (Fried Man,1959) dibedakan antara : 1. Pengertian formal (in the formal sence) yaitu ‘organized public power’ atau kekuasaan umum yang terorganisasikan. 2. Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan ‘menegakkan rule of law’ karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk. Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law, tapi pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat/bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial (Sunarjati Hartono,1982). Dalam penelitian historis komparatifnya di Inggris, Belanda dan AS tentang Rule of Law, Sunarjati Hartono: 1. Setiap bangsa memiliki faham rule of law yang berbeda-beda. 2. Penegakan rule of law tidak dg sendirinya mengakibatkan tegaknya negara hukum. 3. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki (materiil) yaitu pelaksanaan dari just law agar terciptanya negara hukum yg membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya. 4. Pelaksanaan rule of law & terjaminnya negara hukum (inggris), tidak saja warga negaranya yg tunduk pada hukum, melainkan pemerintahannya juga sebagai ‘untergeordnet’ pada hukumnya. 5. Faham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum & keadilan di Amerika pada HAM & di Belanda lahir dari faham kedaulatan negara. Rule Of Law sebagai suatu institusi sosia yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri (Satjipto Raharjo ; 2003). Rule of Law tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi netral. Rule of Law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial. Rule of Law adalah suatu legalisme literal (bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat obyektif, tidak memihak, dan otonom). D. Prinsip – Prinsip Rule of Law di Indonesia Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945) 1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3) 2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1) 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1) 4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2) Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil/ Hakiki : 1. Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law 2. Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982) 3. Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003) 4. Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara. 5. Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003). E. Kaitan HAM dengan Rule of Law Dalam hal ini dapat dipahami beberapa kesimpulan penting dari Randall P. Peerenboom yang melakukan penelitian kaitan antara rule of law dengan hak asasi manusia. Pertama adalah bahwa kaitan antara rule of law dengan hak asasi manusia adalah kompleks. Peerenboom menyatakan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah prinsip-prinsip rule of law, tetapi adalah kegagalan untuk menaati prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi yang jelas menurutnya adalah bahwa rule of law bukanlah ‘obat mujarab’ yang dapat mengobati semua masalah. Bahwa rule of law saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Peerenboom menyatakan bahwa rule of law hanyalah satu komponen untuk sebuah masyarakat yang adil. Nilai-nilai yang ada dalam rule of law dibutuhkan untuk jalan pada nilai-nilai penting lainnya. Dengan demikian rule of law adalah jalan tetapi bukan ‘tujuan’ itu sendiri. Berkaitan dengan hak asasi manusia sendiri, terutama hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah menarik bahwa Peerenboom menyatakan rule of law sangat dekat dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya dia menyatakan bahwa memperhitungkan pentingnya pembangunan ekonomi bagi hak asasi manusia maka dia menyatakan agar gerakan hak asasi manusia memajukan pembangunan. Di sini sangat penting untuk diingat bahwa menurut Peerenboom sampai sekarang kita gagal untuk memperlakukan kemiskinan sebagai pelanggaran atas martabat manusia dan dengan demikian hak ekonomi, sosial dan budaya tidak diperlakukan sama dalam penegakan hukumnya seperti hak sipil dan politik. Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, menurutnya rule of law saja tidak akan cukup untuk dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa adanya perubahan tata ekonomi global baru dan adanya distribusi sumber alam global yang lebih adil dan seimbang. Oleh karena itu menurutnya pemenuhan hak ekonomil, sosial dan budaya juga memerlukan perubahan yang mendasar pada tata ekonomi dunia. Terakhir yang harus dicatat adalah peringatan Peerenboom tentang bahaya demokratisasi yang prematur. Menurutnya kemajuan hak asasi manusia yang signifikan hanya dapat tercapai dalam demokrasi yang consolidated, sementara demokrasi yang prematur mengandung bahaya yang justru melemahkan rule of law dan hak asasi manusia terutama pada negara yang kemudian terjadi kekacauan sosial (social chaos) atau pun perang sipil (civil war). Hal lain yang penting dikemukakan oleh Peerenboom adalah bahwa rule of law membutuhkan stabilitas politik, dan negara yang mempunyai kemampuan untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum yang fungsional. Stabilitas politik saja tidak cukup. Dalam hal ini dibutuhkan hakim yang kompeten dan peradilan yang bebas dari korupsi. Pada intinya Peerenboom menyatakan bahwa walaupun rule of law bukanlah obat mujarab bagi terpenuhinya hak asasi manusia, namun demikian, adalah benar pelaksanaan rule of law akan menyebakan kemajuan kulitas hidup dan pada akhirnya terpenuhinya hak asasi manusia. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI A. Pengertian Korupsi Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006:281-282). Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (the abuse of public office for private gain). Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suapmenyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006: 19-20). Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. B. Jenis Korupsi Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18): 1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. 2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. C. Bentuk Korupsi Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. 2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. 3. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. 4. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. 5. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. 6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. 7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Jeremy Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam Toward a General Theory of Official Corruption menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu: 1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan. 2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. 3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana. 4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya. 5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras. 6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. 7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu. 8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi. 9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul. 10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu. 11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemrintah. 12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang. 13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan. 14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan. 15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya. 16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. 17. Perkoncoan, menutupi kejahatan. 18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos. 19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan D. Strategi Pencegahan Korupsi Strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan Kemenaker, yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Lalu KPK membagikan tiga tahapan strategi yang dapat digunakan. Pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. GEO-POLITIK DAN GEO-STRATEGIS A. Geo – Politik Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, adapun pengertian geopolitik menurut para ahli berikut ini: 1. Frederich Ratzel Menurut Frederich Ratzel, pengertian geopolitik adalah suatu ilmu politik yang menjadi peletak dasar-dasar suprastruktur untuk kekuatan suatu negara dalam mewadahi pertumbuhannya. 2. Peter Haggett Pengertian geopolitik ialah cabang ilmu geografi yang mengkaji mengenai aspek keruangan pemerintah, mencakup hubungan regional, atau hubungan internasional, yang ada di muka bumi. 3. Preston E. James Preston E. James berpendapat bahwa, pengertian geopolitik merupakan sistem dalam hal menempati suatu ruang yang ada di permukaan bumi. 4. Rudolf Kjellen Pengertian geopolitik ialah suatu seni serta praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. 5. Sunarso Geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara dimana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah- masalah geografi wilayah suatu bangsa. Perwujudan Wawasan Nusantara Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik; Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi; Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya; Perwujudan kepulauan nusantara sebagaisatu kesatuan pertahanan keamanan; Batas wilayah NKRI Wilayah daratan; Wilayah perairan; Wilayah udara; Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara 1. wadah (contour); 2. Isi (content); 3. Tata laku (conduct). Tujuan Wawasan Nusantara Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati. Manfaat Wawasan Nusantara 1. diterima dan diakuinya konsepsi wawasan nusantara di forum internasional; 2. pertambahan luas wilayah territorial Indonesia; 3. pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat; 4. penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia; 5. wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Implikasi persoalan dari penerapan wawasan nusantara a) persoalan garis batas/wilayah Indonesia dengan negara lain yaitu batas darat, laut dan udara; b) masuknya pihak luar ke dalam wailayah yurisdiksi Indonesiayang tidak terkendali dan terawasi; c) adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terluar Indonesia; d) sentimen kedaerahanyang suatu saat berkembang dan dapat melemahkan pembangunan berwawasan nusantara. B. Geo – Strategis Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi gografis dan ruang dimana bangsa Indonesia berada, maka selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Dengan demikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya, disamping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, SDA, lingkungan regional maupun internasional. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi dengan demikian jika wawasan nusantara merupakan geopolitik Indonesia maka disini ketahanan nasional merupakan geostrateginya yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan nusantara. Geostrategi juga merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan didalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Wujud/wajah Ketahanan Nasional 1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi; 2. Ketahanan national sebagai metode; 3. Ketahanan Nasional sebagai doktrin. Unsur-unsur (Gatra) dalam ketahanan nasional a) gatra penduduk; b) gatra wilayah; c) gatra sumber daya alam; d) gatra bidang ideologi; e) gatra bidang politik; f) gatra bidang ekonomi; g) gatra di bidang sosial budaya; h) gatra di bidang pertahanan keamanan; Pembelaan Negara Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. 1. Pasal 27 (3) UUD 45 menyebutkan : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 (1) UUD 45 menyebutkan : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. DAFTAR PUSTAKA Depdiknas. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Pius, A.P. dan Al-Barry, M.D. 1994. Kamus Ilmiyah Populer. Surabaya: Apollo. Azyumardi, Azra. 2012. Akar Radikalisme Keagamaan Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama. Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, No.2, Vol.1. Hikam, Muhammad A.S. 2016. Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi). Jakarta: Kompas Media Nusantara. Azhar, Muhammad, 2003, Pendidikan Antikorupsi, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi. Pokja Geostrategi dan Tannas. 2012. Modul Geostrategi Indonesia. Lemhannas RI.