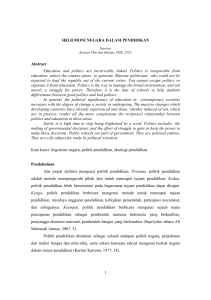Antonio Gramsci tentang Krisis dan Kebangkitan Kapitalisme Global indoprogress.com/2013/11/antonio-gramsci-tentang-krisis-dan-kebangkitan-kapitalisme-global/ November 15, 2013 Judul Buku : Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga Penulis : Muhadi Sugiono Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun Terbit : 1999 (cet. 1), 2006 (cet. 2) Tebal : 261 hlm. + xvi Peresensi : Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, alumnus Jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL UGM *) ATONIO Gramsci, seorang Marxis Italia, memang tidak banyak menulis buku. Ia tercatat hanya menulis satu buah buku. Itupun buku yang merupakan kumpulan dari catatan-catatannya di penjara, yang sudah barang tentu terserak, tidak rapi. Namun, siapa sangka, catatan yang ia tulis dari balik penjara Mussolini itu mampu memberikan wacana yang menjadi panduan, baik bagi aktivis maupun intelektual kiri di seluruh dunia. Gramsci dikenal sebagai seorang intelektual Marxis yang banyak memberi landasan pada perkembangan studi-studi Marxisme di bidang sosial dan budaya. Catatan penjaranya memberikan banyak ilham bagi para penulis untuk membaca fenomenafenomena sosial, tak terkecuali Hubungan Internasional. Meskipun tidak hidup sebagai seorang intelektual dalam pengertian yang kita kenal sekarang (Gramsci adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia sebelum ditangkap Mussolini), karyanya mengilhami banyak intelektual, baik dari sisi sebelah kanan, tengah maupun kiri, untuk menulis tentang berbagai tema dari kerangka berpikir yang ia tulis. Tak terkecuali dalam studi Hubungan Internasional (HI). Sebetulnya, tidak banyak karya dan studi dalam Hubungan Internasional yang menulis dalam perspektif Gramscian ini, terlebih dalam khazanah akademik Indonesia. Terinspirasi dari karya-karya Robert Cox, Stephen Gill, Joseph Femia, serta Robert Gilpin, Muhadi Sugiono, seorang akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mencoba untuk menggunakan perspektif Gramscian dalam mengulas perkembangan dan perubahan diskursus pembangunan global. Buku yang diangkat dari tesis pascasarjana penulisnya ini melihat bahwa perspektif Gramsci relevan untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bertransformasi menjadi kekuatan produktif yang menggeret perubahan diskursus dalam pembangunan. 1/13 Sistematika buku ini dibagi menjadi tiga bagian berikut. Bab I menjelaskan mengapa perspektif Gramscian penting untuk dijadikan pisau analisis dalam studi HI. Bab II mengupas munculnya Keynesianisme sebagai diskursus hegemonik pasca-Perang Dunia II hingga tahun 1970an. Bab III mengulas krisis yang dialami oleh Keynesianisme dan munculnya neoliberalisme yang digawangi oleh intelektual-intelektual Kanan Baru. Mengapa Gramsci Penting dalam Studi HI? Sejak Robert Cox menulis buku Power, Production, and World Orders (1977), perspektif Gramscian mulai diperkenalkan dalam studi Hubungan Internasional. Perspektif ini seperti menjadi ‘undangan untuk angkat kaki dari tatanan dunia yang berlaku saat ini dan mempertanyakan apa jadinya tatanan itu’ (Cox, 1981 via Sugiono, 1999: 17). Karya Cox meramaikan perdebatan dalam studi Hubungan Internasional (HI) yang kala itu masih didominasi oleh pendekatan realisme, yang menerima begitu saja konsep ‘kepentingan nasional,’ ‘negara sebagai aktor tunggal,’ dan sejenisnya, dalam Hubungan Internasional. Walaupun Gramsci tidak menulis spesifik dalam tema Hubungan Internasional, teori Gramsci tentang Hegemoni menjadi satu batu loncatan untuk memahami bagaimana sebuah kekuatan dunia dikonsolidasikan. Inilah yang menjadi concern utama dari Muhadi Sugiono, ketika mendiskusikan analisis Gramsci secara teoretik. Teori Gramsci berada di bawah satu tema tunggal ‘hegemoni’ (h. 19). Gramsci mendefinisikan ‘hegemoni’ sebagai ‘kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual’ yang mengimplikasikan adanya kepatuhan secara sadar atas kekuasaan seseorang (h. 31). Dalam perspektif ini, kekuasaan dibangun bukan melalui koersi, kekerasan, dan paksaan, melainkan melalui konsensus atau kontrol (h. 35). Bagaimana hegemoni tersebut diciptakan? Proses penciptaan hegemoni memerlukan apa yang disebut sebagai ‘blok historis,’ atau ‘hubungan resiprokal antara wilayah aktivitas etik, politik, maupun ideologis dengan wilayah ekonomi.’ Blok historis adalah aliansi dari berbagai kekuatan sosial yang disatukan secara politis dalam satu perangkat ide-ide hegemonik’ (h. 42). Hegemoni itu sendiri diciptakan melalui praktek penundukkan dan persetujuan. Sementara menundukkan dan memenangkan persetujuan kelompok lain, sebuah kelompok harus mampu menciptakan ‘blok historis’ guna memperjuangkan ide-idenya menjadi sebuah pandangan dunia yang universal. Oleh sebab itu, ‘ide’ memainkan peran penting (h. 39). Agar sebuah kelompok bisa menundukkan dan memenangkan persetujuan dari kelompok lain, maka ia mesti melakukan ‘importasi’ ide. Karenanya, bagi Gramsci, sebuah ide hanya akan menemukan momentum transformatifnya jika ia menjadi ideologi. Menurut Gramsci, sebuah ide tidak lahir secara spontan, ia pasti ‘memiliki pusat informasi, iradiasi, persebaran, persuasi… yang mengembangkan dan menghadirkan keduanya dalam realitas politik mutakhir’ (h. 40). Artinya, untuk menciptakan dan memproduksi hegemoni, sebuah kelompok membutuhkan ideologi dimana ideologi tersebut mesti 2/13 memiliki basis material, didorong oleh seorang ‘intelektual,’ dan kemudian menjadi pandangan universal. Hanya dengan kondisi itulah maka penundukkan dan persetujuan menjadi mungkin dilakukan. Konsekuensi logisnya, untuk menciptakan hegemoni diperlukan seorang ‘intelektual organik’ yang mampu menggerakkan blok historis dengan ide-idenya. Menurut Gramsci, setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual (di masyarakat). Setiap kekuatan sosial yang hegemonik, ditopang oleh intelektual yang memproduksi pengetahuan dan memberi legitimasi pada tatanan yang dibangun oleh kekuatan sosial tersebut (h. 44). Peran sentral intelektual inilah yang kemudian membawa kekuatan tersebut menjadi kekuatan yang hegemonik. Namun, tentu saja, pada dasarnya, ada kekuatan-kekuatan lain yang saling berkontestasi dan berupaya untuk menjadi hegemon. Oleh sebab itulah, Gramsci melihat bahwa status hegemonik sebuah kekuatan sosial akan sangat ditentukan oleh kemampuannya memenangkan ‘perang posisi,’ yaitu ‘proses transformasi kultural yang menghancurkan posisi hegemonik tertentu’(h. 46). Untuk menghancurkan hegemoni, maka perlu diciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan krisis hegemonik itu terjadi sehingga membuka jalan bagi adanya perubahan sosial. Pendekatan Gramscian sebagaimana dianalisis oleh Sugiono (dan juga, dalam beberapa hal, Cox) sangat menekankan aspek suprastruktur (ide) dibanding produksi. Hal ini terlihat jelas pada kerangka berpikir Sugiono yang melihat Gramsci ‘melampaui pandangan determinisme ekonomi Marx’ (h. 13). Akan tetapi, pandangan ini bukannya tanpa sanggahan. Lorenzo Fusaro, misalnya, melihat bahwa Gramsci, secara fundamental, justru mengambil kerangka berpikir yang sangat Marxian – dalam arti sejarah ia pandang sebagai sesuatu yang ‘objektif’ dan ‘independen dari hubungan sosial manusia’ karena ia memiliki pijakan pada relasi produksi yang dilakukan oleh manusia (Fusaro, 2011). Dalam analisis Fusaro, hegemoni pada dasarnya harus dilihat dalam kerangka hubungan produksi yang material, bukan sekadar transformasi ide-ide. Bahwa ide-ide, dalam analisis Gramscian, adalah penting, tetapi ia bersifat instrumental. Hal ini sebetulnya diakui sendiri oleh Cox dalam karyanya yang terbaru, The Political Economy of Plural World (2004), bahwa realitas manusia dilahirkan mula-mula dari produksi, walaupun ia sendiri malu-malu untuk mengakui bahwa argumennya berasal dari Marx (Cox, 2004: 31. cf. p. 27). Femia (2008) cukup tepat ketika mengritik pandangan Cox dan perspektif serupa yang ‘terpengaruh’ oleh pandangan post-Marxisme yang memiliki problem dalam melihat sisi objektif dari pemikiran Gramsci. Hal ini bisa berakibat pada ‘reduksi’ pandangan Gramsci menjadi anti-saintifik dan membuat kita gagal menjadikan Gramsci sebagai pisau analisis yang memadai dan objektif untuk mengiris tabir yang meliputi realitas sosial, wa bil khusus realitas kapitalisme global kontemporer. 3/13 Dengan demikian, untuk memahami Gramsci, dan lebih jauh, menjadikan Gramsci sebagai ‘pisau’ untuk mengupas perkembangan kapitalisme global kontemporer, kita tidak cukup melihat hanya pada kerangka gagasan/ideologi, tetapi juga fondasi apa yang memungkinkan gagasan itu terbentuk. Pada titik inilah kita meletakkan konsep ‘hegemoni’. Ada ungkapan menarik dari Gramsci, bahwa ‘a class is dominant in two ways, that is, it is “leading” and “dominant”…. one should not count solely on the power and material force which such a position gives in order to exercise political leadership or hegemony’ (Gramsci, 1929: 41 via Fusaro, 2011). Ungkapan ini memberikan clue untuk memahami ‘hegemoni’ dalam cara yang berbeda – bukan tujuan; melainkan strategi untuk mengokohkan kekuasaan. ‘Hegemoni’ perlu dipahami sebagai cara/strategi untuk melegitimasi kekuasaan material (power and material force) yang sudah dibangun. Sehingga, bukan hanya gagasan yang menentukan, tetapi basis material apa yang menyebabkan gagasan tersebut bisa bertahan. Dalam perspektif ini, kita dapat melihat bahwa hegemoni adalah cara peneguhan kekuasaan setelah menguasai basis produksi. Maka, ‘intelektual organik’ bisa kita pahami sebagai ‘intelektual yang merepresentasikan kelompok sosial tertentu dalam relasi produksi yang ada di masyarakat, dan membawa gagasan-gagasan untuk membuat tatanan yang ia bentuk bisa bertahan secara hegemonik. Keberadaan intelektual bersifat instrumental terhadap relasi produksi yang ada. Dari Keynesianisme ke Kanan Baru Buku ini, walaupun hanya pada sisi tertentu, membawa Gramsci pada perdebatanperdebatan yang ada dalam studi Hubungan Internasional. Fenomena Hubungan Internasional, jika mengacu pada kerangka berpikir a la Gramscian yang sudah dibangun di atas, akan bertumpu pada basis produksi dan bagaimana sebuah gagasan dibangun untuk mempertahankan produksi kapitalis tersebut. Dengan demikian, kapitalisme global dibangun dengan logika hegemoni yang melibatkan para intelektualintelektual organik yang berjuang membangun tatanan tersebut. Perspektif ini tidak melihat Hubungan Internasional sebagai ‘hubungan antar-negara’ (sebagaimana mainstream dalam studi Hubungan Internasional), melainkan sebagai hubungan antara kelas-kelas sosial yang saling berkontestasi di level global. Negara masuk sebagai kekuatan sosial yang relatif terhadap proses produksi dan hanya salah satu kelompok yang saling mengartikulasikan kepentingannya pada skala global (Robinson, 2005). Formasi kapitalisme di tingkat global, jika dibaca dalam perspektif ini, bukanlah sebuah formasi yang ‘tercipta dengan sendirinya.’ Formasi kapitalisme saat ini adalah formasi kapitalisme hegemonik yang diciptakan dan diperjuangkan oleh para intelektual organik, baik Keynesian maupun intelektual Kanan Baru. Hegemoni tersebut tentu saja diciptakan melalui pembuatan ide-ide yang menjadi pandangan dunia universal. Guna menjadi pandangan dunia, maka ide tersebut ‘diekspor’ oleh 4/13 para intelektual, baik Keynesian dan Kanan Baru, ke negara-negara Dunia Ketiga, melalui pelbagai teori tentang pembangunan dan dipraktikkan menjadi kebijakan sehari-hari oleh pemerintah yang bersangkutan. Oleh sebab itulah buku ini melihat bahwa pada dasarnya, kebijakan pembangunan di suatu negara bukanlah kebijakan yang ‘netral’ dan dibuat berdasarkan pilihan rasional pemerintah, melainkan oleh importasi gagasan. Inilah yang menjelaskan, mengapa transformasi diskursus pembangunan di negara Dunia Ketiga sangat terkait dengan perubahan diskursus pembangunan di tingkat global (cf. Robison, 1986; Escobar, 1995). Keberadaan kapitalisme di Dunia Ketiga sangat dipengaruhi oleh ‘ideologi’ yang membuat diskursus tersebut beroperasi, serta intelektual-intelektual organik yang menerjemahkan ‘ide’ dan mengoperasikannya sehingga menjadi kekuatan hegemonik. Universalisasi ide itulah yang kemudian menentukan bagaimana kapitalisme berubah wujud dan menjadi hegemonik di seluruh dunia. Pertanyaannya, bagaimana kemudian ‘hegemoni’ tersebut bekerja dalam perkembangan ekonomi politik internasional kontemporer? Muhadi Sugiono memulai analisisnya terhadap transformasi kapitalisme global pada tataran ekonomi-politik dunia pasca-perang. Perang Dunia (PD) II melahirkan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai pemenang, dan menyisakan sebuah pertanyaan: seperti apa tatanan baru yang hendak dibangun? Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung kepada para pemenang PD II, dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu momentum kunci dari rekonstruksi hegemoni AS pasca-Perang ini adalah terciptanya konsensus yang difasilitasi oleh ekonom John Maynard Keynes dan negara-negara industrialis pemenang perang tersebut. Setelah PD II, terjadi perdebatan tajam antara dua kelompok berpengaruh di Amerika Serikat tentang masa depan ekonomi dunia. Kelompok pertama menginginkan tata perekonomian dunia yang liberal dan terbuka tanpa ada intervensi yang terlalu kuat dari negara. Kelompok ini diwakili oleh orang-orang berpengaruh di Wall Street dan Departemen Luar Negeri AS. Sementara itu, kelompok kedua yang diwakili oleh Departemen Keuangan AS dan Partai Buruh Inggris menginginkan peran negara dalam mengatur perekonomian (h. 64). Masuknya Keynes menengahi perdebatan di antara kedua kubu ini. Keynes memperkenalkan model pembangunan ekonomi yang teregulasi – meletakkan negara sebagai sentral kehidupan ekonomi— tapi juga menjaga produktivitas industri melalui model ekonomi berbasis demand (permintaan) Menurut Keynes, ekonomi pasar yang tak terkendali (bebas) hanya akan melahirkan kontradiksi karena ia menyebabkan penyimpangan dari full employment (h. 97). Oleh sebab itu, kapitalisme perlu diorganisasikan dan direncanakan melalui campur tangan negara. Ekonom Keynesian percaya bahwa ekonomi harus diatur melalui intervensi pada sisi demand, yaitu dengan menyuntikkan dana pembangunan sehingga industri tumbuh. Logika ekonomi semacam ini sangat bertumpu pada moda produksi massal khas Fordisme yang membangun produksi dengan skala besar. Negara menginvestasikan dana yang cukup besar untuk membangun produksi nasional, namun konsekuensinya, negara juga harus mempertahankan demand yang ia dapatkan dari 5/13 konsumsi. Oleh sebab itulah negara harus menjamin daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Dengan model seperti ini, buruh mendapatkan upah yang tinggi karena produktivitas harus dipertahankan. Ide semacam inilah yang ditanamkan pada relasi produksi di tingkat global, dan membuat ‘negara’ pada saat itu menjadi instrumen kelas kapitalis yang sangat efektif untuk melakukan akumulasi. Menurut Sugiono, kemenangan ide Keynesianisme itu dilakukan oleh Amerika Serikat melalui dua cara. Pertama, memenangkan ide tersebut pada negara-negara sekutunya. Kemenangan ide ini menemui momentumnya pada Marshall Plan, ketika Amerika Serikat menggunakan kekuatan ekonominya untuk membantu ekonomi negara-negara sekutunya tersebut. Hal penting yang patut diperhatikan adalah bahwa Marshall Plan menciptakan semacam ‘blok historis’ yang bertujuan untuk ‘menciptakan perimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial di dunia’ (h. 68). Kekuatan Marshall Plan juga ditopang oleh sistem Bretton Woods yang memberikan konstruksi hegemonik bagi kekuatan finansial AS (Strange, 1971 via Sugiono, 1999: 66). Bretton Woods ini selanjutnya memberikan peluang bagi Dollar untuk menjadi alat tukar perdagangan internasional yang hegemonik. Marshall Plan, dengan demikian, menjadi cara AS untuk memenangkan pertarungan di lapangan ekonomi global. Kedua, setelah ide tersebut beroperasi melalui Marshall Plan dan Bretton Woods System, AS memperluas hegemoninya ke negara-negara Dunia Ketiga melalui gagasan tentang pembangunanisme. Era setelah Perang Dunia II adalah era dekolonisasi, yang mengimplikasikan munculnya negara-negara baru merdeka, dimana Amerika Serikat, menurut Muhadi, sangat getol mendukung proses dekolonisasi tersebut. Tentu saja hal ini tidaklah netral dari kepentingan AS, sebab pada dasarnya, motif utama dari dukungan tersebut adalah perluasan hegemoni (h. 76). Dengan munculnya Keynesianisme, negara-negara industri maju mengalihkan perhatiannya dari penyerapan surplus ekonomi dari negara-negara koloni menjadi produksi berbasis domestik. Akan tetapi, tentu saja, mereka memerlukan bahan baku yang hanya bisa didapatkan dari negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka itu. Dengan demikian, dekolonisasi sebetulnya menjadi strategi yang lain dari bentuk eksploitasi ekonomi. Negara-negara yang baru merdeka tersebut, tentu sangat berkepentingan dengan dana pembangunan yang berasal dari luar negeri. Oleh sebab itulah, sebagaimana dikutip oleh Escobar (1995), Amerika Serikat menawarkan berbagai strategi pembangunan kepada negara-negara Dunia Ketiga, menanamkannya di negara-negara tersebut, dan dengan demikian menempatkan negara-negara tersebut di bawah hegemoninya. Pembangunan, dengan begitu, menjadi pintu masuk AS untuk menanamkan ide-ide Keynesian di negara Dunia Ketiga dan menjadikan ide tersebut sebagai ‘pandangan dunia’ yang universal, terutama bagi negara-negara baru merdeka tersebut. Salah satu ‘modus operandi’ dari penanaman diskursus tentang pembangunan itu dilacak oleh Sugiono dari teori-teori modernisasi, yang hingga tahun 1980an menjadi diskursus utama pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga. Teori modernisasi 6/13 menempatkan pembangunan sebagai cara untuk mengubah sesuatu yang tradisional menjadi modern. Sebagaimana diulas oleh Escobar (1995), negara-negara Dunia Ketiga diposisikan sebagai ‘terbelakang,’ ‘kurang gizi,’ ‘tradisional,’ dan sebagainya. yang implikasi pentingnya adalah menjadikan mereka sebagai entitas yang modern dan maju. Dan untuk mencapai ‘kemajuan’ tersebut maka mereka harus melihat model tertentu yang dianggap maju. Pada titik inilah hegemoni AS beroperasi. AS memberikan dana pembangunan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan multilateral (IMF, World Bank/IBRD), dan memberikannya kepada negara-negara Dunia Ketiga melalui kondisionalitas tertentu. Kondisionalitas ini penting untuk dilihat sebagai sebuah cara untuk memberikan parameter kemajuan tertentu yang harus dicapai suatu negara agar dikategorikan maju. Salah satu ide yang bisa dijadikan contoh adalah teori Rostow tentang pembangunan yang linier sebagai arah utama pembangunan. Teori Rostow memberikan gambaran yang jelas mengenai pembangunan khas Keynesian yang dipandu oleh negara dan bertumpu pada industrialisasi (h. 107-108). Teori Rostow ini dapat kita lihat pada konteks Indonesia di awal Orde Baru, yang secara mentah-mentah menelan teori ini dan menjadikannya panduan pembangunan nasional (Robison, 1986). Ringkasnya, kita lihat: logika pembangunan Keynesian yang menjadi proyek hegemoni AS, masuk melalui logika pembangunan dan ditanamkan di negara-negara Dunia Ketiga melalui instrumen utang luar negeri. Akan tetapi, pada tahun 1970an, terjadi krisis ekonomi dunia yang ditandai oleh penurunan produktivitas ekonomi negara-negara industri maju, terutama AS (h. 117). Krisis menyebabkan hegemoni Keynesian yang dipandu dan dikawal oleh Amerika Serikat mendapatkan tantangan yang serius dari berbagai kalangan baik dari sebelah kiri maupun kanan. Bisa dikatakan, Keynesianisme sebagai hegemoni mengalami krisis organik yang disebabkan kegagalannya dalam menghadapi berbagai goncangan. Logika ekonomi Keynesian yang sangat percaya pada produksi dan peran negara dalam perencanaan serta intervensi demand, mengalami kontradiksi manakala terjadi penurunan produktivitas dan keterbatasan pasar dalam melakukan ekspansi akumulasi (h. 123). Kegagalan negara dalam menjaga stabilitas konsumsi dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya ekspansi akumulasi membuat kondisi ekonomi dunia kemudian melemah. Ditambah dengan surutnya harga minyak minyak dunia yang menjadi mata pencaharian utama negara-negara Dunia Ketiga. Dalam perspektif Gramscian, hal ini dipandang sebagai ‘krisis organik’ ketika hegemoni kemudian menghadapi goncangan di sana-sini. Dari sini, Sugiono melihat bahwa ada satu gagasan baru yang muncul dan dengan cepat menggantikan Keynesianisme sebagai ‘hegemoni,’ yakni gagasan neoliberalisme yang dikampanyekan oleh intelektual-intelektual Kanan Baru. Gagasan ini dibawa oleh kalangan Libertarian Kanan yang memiliki perspektif cenderung anarkis. Kalangan yang tidak percaya terhadap bentuk-bentuk teknokratisme negara ini segera menyerang 7/13 fondasi ekonomi Keynesian yang mereka anggap “otoritarian” dan “tidak efisien.” Secara ideologis, mereka mengampanyekan ‘kembalinya pasar’ dan memuja ‘kebajikan pasar’ sebagai solusi atas perekonomian dunia yang carut-marut (h. 129). Mengapa gagasan kelompok Libertarian Kanan Baru ini dengan cepat menggantikan Keynesianisme sebagai Hegemon? Salah satu faktor yang paling penting untuk menjelaskan ini, selain krisis yang menerpa dunia, adalah keberhasilan mereka memenangkan gagasan tentang kebajikan pasar dari manajemen ekonomi Keynesian. Para intelektual mereka yang berpengaruh, seperti Milton Friedman, Robert Nozick, atau Deepak Lal, dengan sengit menuduh logika Keynesian sebagai penyebab krisis ekonomi global. Friedman, misalnya, menganggap kebijakan-kebijakan sosial dan intervensi negara Keynesian sebagai sesuatu yang tidak adil, ‘memicu kemalasan,’ serta mengancam kehidupan pribadi (h. 136-137). Dengan mengagungkan kebajikan pasar, para pemikir Kanan Baru ini menganggap bahwa negara tidak boleh banyak mengganggu cara kerja pasar dan membiarkan pasar mengatur dirinya sendiri. Manusia, menurut mereka, harus diberi kebebasan menentukan nasibnya sendiri dan negara-negara harus dipaksa untuk bersaing satu sama lain dalam menawarkan iklim investasi yang kompetitif, sehingga pasar bisa bergerak secara sempurna (h. 144). Serangan-serangan ini menandai krisis dan transformasi dalam kapitalisme global. Namun, yang paling penting dari transformasi itu adalah basis material yang menyebabkan gagasan mereka bisa menjadi hegemonik. Muhadi melihat bahwa di samping krisis ekonomi yang mendera dunia pada saat itu, naiknya beberapa figur konservatif yang sehaluan dengan para intelektual Kanan Baru di beberapa negara (terutama Inggris dan Amerika Serikat), menjadi momentum penting bagi kemenangan logika Kanan Baru dalam ekonomi politik global. Sebagaimana tesis Gramsci, status hegemonik sebuah gagasan akan sangat ditentukan oleh kolaborasinya dengan kekuatan ekonomi dan politik yang material. Keberadaan Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, membawa perubahan fundamental dalam politik Inggris, dimana Thatcher membawa agenda politik Kanan Baru dalam kebijakan-kebijakan publiknya, antara lain dengan kebijakan privatisasi besar-besaran, liberalisasi, dan kebijakan-kebijakan pro-pasar. Menariknya, agenda politik Thatcher dilakukan dengan tangan besi, antara lain dengan mendisiplinkan serikat-serikat buruh yang resisten terhadap kebijakan liberalisasinya. Hal ini, sebagaimana diulas oleh Muhadi, adalah satu paket dengan doktrin Kanan Baru yang melegitimasi adanya represi dan koersi terhadap aktivitas apapun yang dianggap mengganggu mekanisme pasar (h. 148). Thatcher menjadi contoh penting bagaimana negara berfungsi sebagai ‘polisi’ yang mengamankan pasar dari gangguan orang-orang yang ingin menentangnya. Di bagian dunia lainnya, Ronald Reagan yang baru saja terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, tampak dengan jelas mengampanyekan ‘kebajikan pasar’ dalam forum-forum internasional dan perundingan yang diikuti oleh Amerika Serikat. Ia membawa Amerika Serikat tampil sebagai juru kampanye utama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dunia. Tak hanya itu, dengan menggunakan kekuatan 8/13 diplomatik AS, Reagan ‘memanfaatkan jaringan transfer finansial untuk memperkokoh hegemoni ide-idenya’ (h. 160). AS yang tadinya cukup baik hati kepada negara-negara berkembang dalam memberikan bantuan, kini mulai terlihat pelit dan mulai ‘jual mahal.’ Reagan memperkenalkan model-model policy dialogue untuk memberikan bantuan, yang dengan jelas dicatat oleh Muhadi sebagai cara untuk mengimpor gagasannya kepada negara-negara Dunia Ketiga (h. 161). Seperti halnya bangunan hegemoni AS pasca-Perang Dunia II, peran serta lembagalembaga keuangan internasional kemudian menjadi penting sekali. Beriringan dengan munculnya ‘Pembagian Kerja Internasional Baru’ yang, menurut para pendukung globalisasi neoliberal, adalah bentuk peleburan batas-batas negara dalam industri manufaktur yang memungkinkan adanya ekspansi kapital ke negara-negara Dunia Ketiga (Robison, 2000), dimana IMF dan Bank Dunia segera menjadi ‘pilar’ utama ekspansi gagasan-gagasan pasar ke seluruh dunia. Dua lembaga ini, sejak didirikan, telah terbukti menjadi alat untuk meneguhkan hegemoni dari Amerika Serikat sebagai kekuatan politik utama dunia. Kebijakan paling nyata yang merefleksikan peran dua lembaga ini dalam proyek hegemoni Kanan Baru adalah Structural Adjustment Programmes (SAP), yang dikampanyekan di negara-negara Dunia Ketiga. Penjadwalan kembali utang dan berubahnya kondisionalitas bantuan menjadi instrumen paling penting untuk menanamkan hegemoni mereka. Dengan menawarkan paket kebijakan yang sangat liberal dan mengagungkan kebajikan pasar, IMF dan Bank Dunia mampu menanamkan hegemoni Kanan Baru ke negara-negara ini. Sebagai contoh, demikian Sugiono, ketika berhadapan dengan krisis ekonomi, solusi yang ditawarkan adalah memangkas peran negara secara penuh dan menganggap krisis tersebut terjadi karena intervensi pemerintah dalam perekonomian (h. 163). Hal ini memberikan jalan yang sangat terbuka bagi kapitalisme untuk menguniversalisasi gagasannya ke negara-negara Dunia Ketiga, dan dengan demikian, menjadikan gagasan ‘Kanan Baru’ sebagai gagasan hegemonik baru. Analisis Sugiono ini bisa memberikan gambaran yang cukup baik mengenai bagaimana fondasi kapitalisme global dibangun. Namun, ada yang terlupakan. Buku ini tidak banyak menyinggung kekuatan-kekuatan internasional lain yang memiliki kepentingan sangat besar untuk meminimalisasi peran ‘negara.’ Kelompok ini satu paket dengan kekuatan yang disebut oleh Willam Robinson sebagai ‘hegemoni transnasional’ – mereka yang beroperasi secara lintas negara (Robinson, 2005: 3). Salah satu yang cukup dominan adalah kelompok kapitalis finansial yang memang beroperasi secara lintas negara dan sangat berkepentingan terhadap reduksi peran negara, terutama setelah tahun 1980an. Namun, tentu saja, hegemoni logika Kanan Baru tersebut memiliki keterbatasan yang pada gilirannya berujung pada krisis status hegemonik mereka. Hal ini terjadi pascaKrisis Asia 1997 yang tidak sempat diungkap dalam buku ini (terbit 1999, tesis 1994). Untuk menyempurnakan analisis tersebut, ada baiknya uraian Carroll (2010) disimak. 9/13 Pasca-krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, dan kritik-kritik hebat yang dilancarkan oleh para kritikus neoliberalisne terkemuka seperti James Ferguson (1994) atau Arturo Escobar (1995) yang mengkritik cara kerja Bank Dunia di negara-negara Dunia Ketiga, ada semacam ‘perubahan’ kerangka berpikir Bank Dunia tentang pembangunan. Pada tahun 1999, Bank Dunia merilis beberapa proyek pembangunan yang menggunakan ‘modal sosial’ sebagai cara untuk menginternalisasi mekanisme pasar. Toby Carroll menyebutnya sebagai ‘socio-institutional neoliberalism’ (SIN). Model ini, sebagaimana kata Carroll, mulai muncul sejak gagasan pembangunan neoliberal yang dipropagandakan kelompok Kanan Baru mengalami kontradiksi, terutama di Afrika (h. 45). Gagasan ini mengandaikan efektifnya mekanisme pasar jika disandingkan dengan penataan pelayanan publik yang efisien, kepastian hukum, serta tata pemerintahan yang akuntabel – gagasan yang kemudian dikenal secara luas sebagai ‘Good Governance’ (Conable, 1989 via Carroll, 2010: 45; Hakim, 2011). Di samping itu, Conable – mantan Presiden Bank Dunia 1986-1991 – juga meng-address perlunya ‘membangun kapasitas Afrika’ yang manifestasinya adalah membangun masyarakat yang sehat, punya kapasitas individual yang baik, serta mampu membangun kerangka kelembagaan yang mendorong prakondisi bagi pasar yang efektif dan efisien. Gagasan ini kemudian diterjemahkan secara lebih luas pasca-Krisis Asia 1997. Indonesia menjadi ‘laboratorium’ bagi penerapan kerangka berpikir baru tentang kapitalisme. Pada tahun 1999, Bank Dunia menginisiasi proyek pembangunan sosial yang mencoba memasukkan nalar SIN ke dalam pembangunan masyarakat melalui ‘Proyek Pembangunan Kecamatan’ (Li, 2012). Proyek ini, sebagaimana dicetuskan oleh para teknokrat Bank Dunia seperti Scott Guggenheim, memberikan komitmen pendanaan untuk mengembangkan modal sosial dan kapasitas ekonomi individual. Naiknya para ekonom dan teknokrat liberal, seperti Boediono (Wakil Presiden tahun 2009), menyebabkan gagasan ini bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada tahun 2007, proyek ini berubah menjadi ‘Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM)’ yang berada di bawah Tim Nasional Pengentasan Kemiskinan (TNPK). Proyek ini segera menjadi ‘best practice,’ menyebar ke negara lain melalui tangan Bank Dunia, dan segera menjadi hegemon baru. Apa yang menarik dari logika SIN ini, menurut perspektif Gramscian, adalah kemampuannya untuk meng-address kegagalan pendekatan neoliberal yang sangat anti-Negara dan, secara lebih jauh, memasukkan negara di bawah hegemoni pasar. Krisis ekonomi di akhir abad ke-20 menyebabkan gagasan neoliberal mengalami ‘krisis organik.’ Para pendukung SIN, yang pada hakikatnya sebenarnya juga kaum liberal dengan wajah berbeda, mengampanyekan mekanisme baru melalui struktur teknokrasi Bank Dunia di bawah John Wolfensohn. Para teknokrat Bank Dunia ini adalah ’intelektual organik’ dari gagasan SIN. Secara politis, kemenangan gagasan ini sangat ditentukan oleh ‘siapa’ yang memegang peran penting dalam pengambil keputusan di Amerika Serikat. Dengan demikian, posisi SIN sebagai hegemoni baru juga tak terlepas dari kekuatan ekonomi-politik yang berada di belakangnya: Amerika Serikat. 10/13 Beberapa Catatan dan Implikasi bagi Gerakan Sosial Dari buku ini, kita bisa melihat bagaimana kapitalisme global bisa menghadapi krisis dan di saat bersamaan, memperbarui dirinya sendiri. Kemampuan kapitalisme dalam berkuasa, jika menilik analisis Gramscian yang dipakai sebagai kerangka berpikir oleh Muhadi Sugiono, akan sangat ditentukan dari: (1) adanya ‘intelektual organik’ yang menelurkan ide-ide dan strategi praktis; (2) adanya kekuatan ekonomi dan politik yang menopang ide tersebut; serta (3) adanya transfer dan universalisasi ide tersebut di seluruh dunia. Dengan demikian, buku ini memberikan sumbangsih yang sangat berharga untuk memahami cara kerja kapitalisme di level global. Akan tetapi, tentu saja buku ini tak lepas dari beberapa keterbatasan. Apa yang kurang dari buku ini adalah penjelasan mengenai mengapa kapitalisme pasca-1945 bisa bertahan. Walaupun ada gagasan-gagasan hegemonik yang menyebabkan kapitalisme bisa kokoh, seperti gagasan Keynesianisme dan Libertarianisme yang men-sustain-kan tatanan dunia yang dibangun oleh kapitalisme, tetapi buku ini kurang menyoroti sisi produktif/basis material di mana gagasan itu bisa tumbuh. Kita mungkin bisa memahami keterbatasan hal ini karena kurang tersedianya space untuk melakukan analisis pada bagian itu. Maka, perlu untuk memperkaya dengan beberapa karya lain yang secara cukup komprehensif menggambarkan bagaimana basis material dari kapitalisme global. Selain itu, buku ini tidak memberikan implikasi, baik secara teoretis maupun praktis, terhadap gerakan-gerakan sosial yang melawan kapitalisme. Atas dasar itulah, saya merasa perlu memberikan gambaran bagaimana agar buku ini bisa memberikan relevansi bagi gerakan-gerakan sosial yang tengah berlawan tersebut. Melalui perspektif Gramscian, kita dapat memahami bahwa untuk membangun perlawanan terhadap kapitalisme global, tidak cukup hanya mengandalkan massa di lapangan. Massa dan pengorganisasian memang penting, tapi tanpa ‘intelektual organik’ yang memandu dan mengarahkan massa dalam gerakan, hegemoni akan sangat susah dilawan. Pengalaman kapitalisme dalam membangun hegemoninya tidak terlepas dari peran para intelektual organik, baik Keynesian, Kanan Baru, maupun SIN. Oleh sebab itu, pembangunan pengetahuan yang integral dengan gerakan massa menjadi sangat penting. Seperti kata Lenin (1905), tanpa teori yang revolusioner tidak akan praktik yang revolusioner. Gerakan tidak hanya membutuhkan para agitator lapangan sebagai ‘juru pukul’, tetapi juga ‘koran’ sebagai juru bicara dan ‘intelektual’ sebagai juru pikir. Mengefektifkan para intelektual dalam aktivitas pergerakan inilah yang merupakan pekerjaan rumah dari gerakan-gerakan sosial di Indonesia saat ini. Tanpa para intelektual organik yang secara konsisten melakukan perlawanan terhadap hegemoni teknokrat dan intelektual liberal dalam ruang pengambilan keputusan politik di Indonesia, gerakan sosial hanya akan menemukan jalan buntu. 11/13 Dengan kata lain, dalam perspektif Gramscian, hal penting yang perlu dilakukan adalah menciptakan para intelektual dan menghubungkan mereka dengan gerakan-gerakan perlawanan. Intelektual-lah yang memandu, mengarahkan, serta mengonstruksi bangunan yang menjadi alternatif dari tatanan sistem yang ada saat ini. Intelektual tersebut adalah intelektual yang ideologis dan memiliki keberpihakan pada kekuatan massa yang berlawan terhadap eksploitasi kapitalisme. Demikianlah, dengan memahami cara kerja kapitalisme, hegemoninya, dan bagaimana menemukan kelemahan dari sistem tersebut, buku ini cukup recommended untuk dibaca. Terlebih bagi para penstudi HI yang ingin belajar lebih banyak tentang ekonomi politik internasional dari perspektif yang berbeda. Beberapa kekurangan yang ada di buku ini ditujukan sebagai sebuah ikhtiar dan dorongan agar studi HI di Indonesia lebih berkembang dan lebih bervariasi dalam perspektif – tidak didominasi oleh karyakarya kaum realis atau liberal semata. ‘Ala kulli hal, semoga buku ini mampu memberikan ‘kesadaran kritis’ bagi kita tentang apa yang terjadi di dunia saat ini dan, yang terpenting, bagaimana cara keluar dan mengubahnya!.*** Bacaan tambahan: Carroll, Toby. 2010. Delusion of Development: The World Bank and the PostWashington Consensus in Southeast Asia. London and New York: Palgrave. Escobar, Arturo. 1995. Encountering Development: The Making and Unmaking of The Third World. Princeton: Princeton University Press. Ferguson, James. 1994. The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: Minnesota University Press. Fusaro, Lorenzo. 2011. Gramsci’s concept of hegemony at the national and international level. Fermia, Joseph. 2008. “Gramsci, Epistemology, and International Relations Theory”. Paper presented at the Political Studies Association conference, Swansea, April 2008 Hakim, Luqman-nul. 2011. “Governance and New Mode of Governing: Indonesia as Metaphor”. Jurnal Sosial Politik 15 (2): 111-123. Lenin, Vladimir J. (1905). What is To Be Done? Retrieved from http://www.marxists.org/ Li, Tania Murray. 2012. The Will to Improve: Pembangunan dan Kekuasaan di Indonesia (pent: Heri Santoso dan Pujo Semedi). Jakarta: Marjin Kiri. Robinson, William. 2005. “Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony” Critical Review of International Social and Political Philosophy, Vol. 8 (4): 1-16. 12/13 13/13