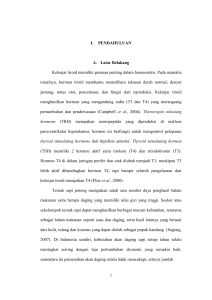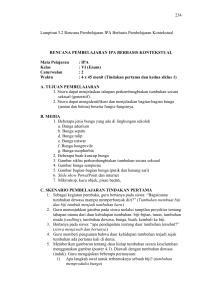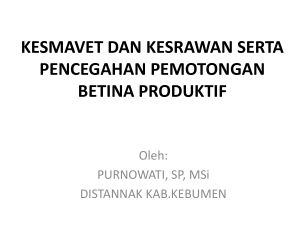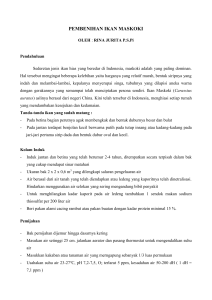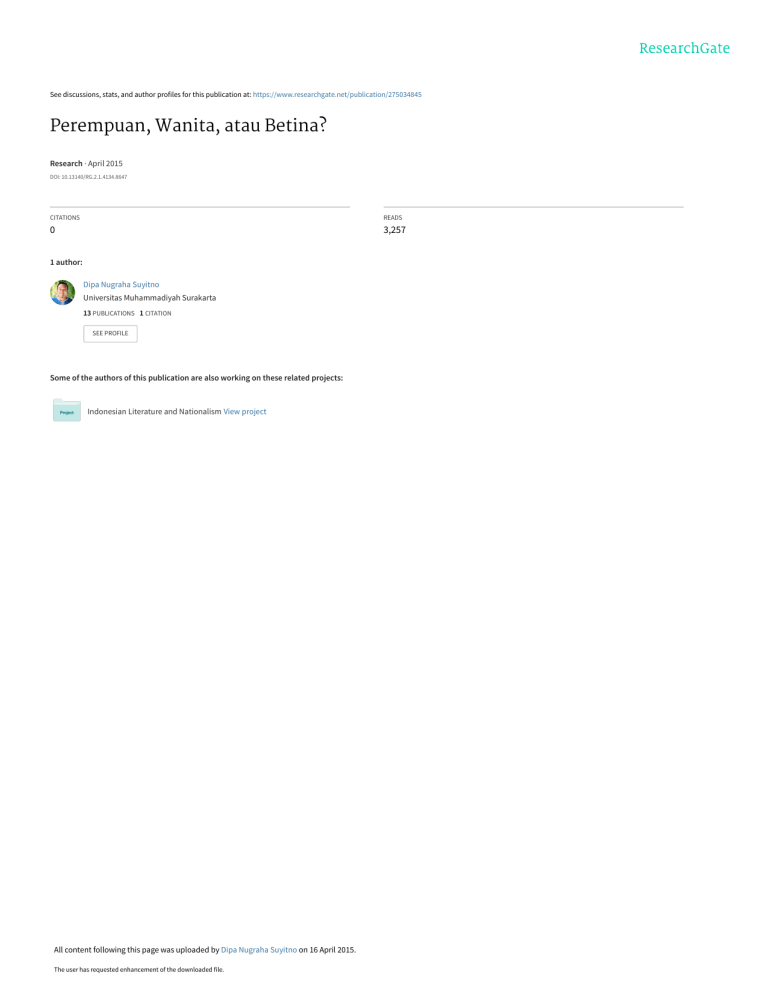
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/275034845 Perempuan, Wanita, atau Betina? Research · April 2015 DOI: 10.13140/RG.2.1.4134.8647 CITATIONS READS 0 3,257 1 author: Dipa Nugraha Suyitno Universitas Muhammadiyah Surakarta 13 PUBLICATIONS 1 CITATION SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Indonesian Literature and Nationalism View project All content following this page was uploaded by Dipa Nugraha Suyitno on 16 April 2015. The user has requested enhancement of the downloaded file. Perempuan, Wanita, atau Betina? Dalam bahasa Indonesia masih terus ada belum lekang perdebatan mengenai tafsir nilai kata perempuan, betina, dan wanita. Perdebatannya adalah seputar pada manakah dari ketiganya yang mempunyai nilai kata lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan lainnya. Apakah hal ini penting? Ya bagi para pejuang hak-hak perempuan/wanita/betina karena ada keyakinan bahwa istilah yang tepat untuk menyebut diri mereka adalah langkah awal di dalam melakukan perjuangan melawan peliyanan. Telaah mengenai makna ketiga kata tersebut misalnya kita dapati dalam tulisan Sudarwati dan Jupriono Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik (1997). Sudarwati dan Jupriono mengerucut pada kesimpulan bahwa kata perempuan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan betina atau wanita. Kesimpulan itu kita dapati lewat kalimat sebagai berikut: Di sini jelas sekali bahwa jika yang kita maksudkan adalah sosok yang mengalah, rela menderita demi pria pujaan, patuh berbakti, maka pilihlah kata wanita. Maka, yang tepat tetaplah "Darma Wanita" memang dimaksudkan untuk berbakti. Tetapi, jika kita berbicara soal peranan dan fungsinya, soal pemberdayaan kedudukan, soal pembelaan hak asasi, soal nasib dan martabatnya, tidak ada jalan lain, gunakan kata perempuan, semisal "peranan perempuan dalam perjuangan", "gerakan pembelaan hak-hak perempuan pekerja" (Sudarwati dan Jupriono, 1997). Menurut mereka kata perempuan berasal dari kata ”empu” yang secara etimologis, berasal dari kata empu (tuan; orang yang mahir/berkuasa; kepala; hulu; yang paling besar; maka kita kenal kata empu jari 'ibu jari', empu gending 'orang yang mahir mencipta tembang'), berhubungan dengan kata ampu (sokong; memerintah; penyangga; penjaga keselamatan; wali; mengampu artinya menahan agar tak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh; kata mengampukan berarti memerintah (negeri); ada lagi pengampu penahan, penyangga, penyelamat sehingga ada kata pengampu susu 'kutang' alias 'BH'), kemudian menjadi empuan --> puan Pendapat tersebut juga dapat dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Zoetmulder (dalam Pudjiastuti, 2009: 5) bahwa kata perempuan berasal dari kata mpu, empu, ampu artinya orang yang terhormat; tuan; atau yang mulia. Sedangkan wanita dianggap lebih rendah nilai karena terbentuk dari proses metathesis dan kontoid dari kata betina (Sudarwati dan Jupriono, 1997) dan pendapat hampir senada juga dituturkan oleh Gustaaf Kusno (2011). Proses tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: Simpulan yang diberikan oleh Sudarwati dan Jupriono (1997) menganggap bahwa kata perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi dari kata wanita. Mereka mendasarkan simpulan ini sebab kata wanita berasal dari: proses metathesis dan kontoid dari kata betina, sebagaimana ilustrasi di atas, bahasa Sanskerta/Jawa Kuno vanita yang artinya 'yang diinginkan'. Kata ini diserap oleh bahasa Jawa Kuno (Kawi) menjadi wanita, ada perubahan labialisasi dari labiodental ke labial: [v]-->[w]; dari bahasa Kawi, kata ini diserap oleh bahasa Jawa Modern; lalu dari bahasa Jawa, kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia (Slametmuljana, 1964: 59 – 62). Lepas dari argumen Sudarwati dan Jupriono (1997) mengenai perempuan – betina – wanita, berseberangan ada pendapat Umar Junus di dalam Dari Peristiwa ke Imajinasi: Wajah Sastra dan Budaya Indonesia pada bab 5 yang berjudul Betina – Perempuan – Wanita. Junus berpendapat bahwa jika hendak mengajukan argumen tentang ketiga istilah tersebut di dalam domain gerakan feminisme, maka sebaiknya dipakailah kata wanita. Junus (1983: 21) memulai argumennya dengan definisi ’betina’. Betina menurut istilah dikaitkan dengan binatang. Lalu ia juga setuju bahwa dari ’betina’ yang ber-metathesis muncullah kata ’wanita’ (1983: 26). Kata ’perempuan’ menurutnya (1983: 22) secara etimologi berasal dari kata mpu dan demikian maka kata ’perempuan’ adalah bentuk domestikasi (karena mpu berarti yang membuat, menghasilkan [anak] --> maka istilah 'perempuan' adalah bentuk pengandangan) dibanding kata betina – wanita. Betina atau wanita berarti sesuatu yang ’binatang’ atau ’yang dekat dengan alam’ atau dengan kata lain ’belum terjinakkan’. Perlu ditambahkan pula pendapat lain yang mendudukkan posisi kata betina yang dianggap sebagai asal kata wanita sebagai lebih netral misalnya bahwa di dalam masyarakat Palembang kata betino lazim dipakai tanpa ada muatan melecehkan (Gustaaf, 2011). Jikalau menetapi bahwa kata perempuan adalah lebih tinggi nilainya maka bakal pula timbul masalah lain. Masalah tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: Sebagai simpulan dapatlah dikatakan bahwa kata: betina tidaklah mutlak dikatakan bahwa sebagai bentuk yang melecehkan perempuan JIKA diversuskan dengan jantan. Pejantan yang tangguh (Sheila on 7, 2004) dengan betina yang hebat (Junus: 1983: 21) adalah bentuk oposisi biner. Jika bentuk ’pejantan yang tangguh’ adalah sebuah pelecehan terhadap laki-laki maka bolehlah dikatakan bahwa istilah ’betina’ juga merupakan pelecehan. Dan demikian juga menafikan bahwa istilah betina dapat berkonotasi netral jika menilik penggunaannya pada masyarakat Palembang. Pun jika kata ini dianggap sebagai asal dari kata wanita, maka konotasi buruk (peyoratif) terhadap kata wanita di dalam terminologi pergerakan pembebasan wanita adalah menjadi absurd. wanita tidaklah bisa mutlak dikatakan sebagai bentuk pelecehan juga jika merujuk pada istilah Sanskrit vanita yang artinya: ’yang diinginkan’. Apa yang salah dengan istilah yang diinginkan? Bukankah laki-laki juga suka menjadi yang diinginkan. Sebab bagaimanapun juga dikotomi oposisi biner laki-laki – wanita[1] selalu mengalami tarik ulur. Misal: Jika wanita bisa pretty mengapa laki-laki tidak pretty juga?[2] Jika wanita adalah objek yang membuat berkeringat atau hot mengapa laki-laki tidak ada pantangan kita sebut serupa? Hal ini sebenarnya senada dengan apa yang diungkapkan oleh Julia Kristeva dan Elizabeth Grosz (dalam Dipa Nugraha, 2011) bahwa tarik ulur tentang ini bakal terus terjadi. perempuan juga tidak bisa mutlak dikatakan sebagai mempunyai nilai lebih baik dibanding kata betina maupun wanita. Meskipun kadang dirujukkan dengan argumen lain bahwa wanita adalah wani ditata[3] yang artinya rendah dibanding empu, namun jika kita lihat argumen Junus bahwa kata wanita justru lebih dahsyat di dalam konteks anti-domestikasi dan justru perempuan adalah bentuk kata yang menyiratkan domestikasi maka pendapat yang merendahkan nilai kata wanita dan meninggikan kata perempuan perlu dikaji ulang. Jika melihat pada munculnya kata Puan[4] yang ujungujungnya JUGA merupakan bentuk yang dipengaruhi adanya bentuk Tuan karena phallogocentrism oposisi biner maka bukankah Puan kembali jadi subordinat? Sebagai penutup tulisan ini, tidaklah salah jika merujuk pada pendapat Lao Tzu yang kemudian diadaptasi oleh Kristeva (dalam Dipa Nugraha, 2011) bahwa bagaimanapun, oposisi biner di dalam bahasa adalah hal yang tak terelakkan. Tarik ulur selalu terjadi dan bentuk penyamaran oposisi biner atau penggugatannya justru malah akan menafikan pembedaan yang memang diperlukan di dalam bahasa sebagai bagian dari pembentuk realitas; bukan di dalam konteks hegemoni-subordinasi namun karena kebutuhan akan pembentukan realitas. Penggugatan oposisi biner dapat diartikan justru akan mengaburkan dan menafikan pembedaan sebagai unsur pembentuk realitas dan akibatnya malah bisa chaos yang muncul. Jikalau isu yang diadaptasi dari Gramsci mengenai hegemoni hendak diaplikasikan ke dalam ranah bahasa dalam bentuk adanya dugaan hirarki hegemonik patriarkal di dalam bahasa hendak terus digaungkan maka itu merupakan sebuah proyek yang terlalu besar untuk ditangani karena bakal menggoncangkan realitas. Jikalau perspektif-nya diubah sebagaimana pemikiran Lao Tzu dan sudah disadari oleh Kristeva bahwa oposisi biner adalah niscaya, maka bergerak lincah[5] di dalam konstruksi realitas yang bersumber dari oposisi biner justru merupakan hal yang cerdas dan harmoni justru akan muncul ketika memaklumi dan berdamai dengannya bahwa sejak awal bahasa memang dibentuk demikian. Bukan dengan persangkaan bahwa man (laki-laki) memarjinalkan the other (liyan) dengan oposisi biner tersebut namun karena kemendesakan ketiadaan nama (Lao Tzu dalam Tao Te Ching, pasal 1). Memahami ini berarti justru memahami realitas sehingga tidak ada gugatan. Dengan tidak adanya gugatan lagi karena menyadari bahwa man dan woman adalah koeksisten maka harmoni akan tercapai (dan itulah jalan Tao). Dalam konteks perbincangan tulisan ini, biarlah ada jantan sebagai ko-eksisten dari betina, biarlah pria menjadi pair dari wanita, dan biarkan pula laki-laki menjadi oposisi biner dari perempuan. Jika hendak mengadakan tata ulang, maka kecermatan menelisik di dalam oposisi biner yang merupakan stigmatisasi buruk atau stereotip-lah yang sebenarnya dimaksudkan di dalam konsep awal Gramsci. Bedakan antara apa yang telah diperbincangkan di atas dengan oposisi biner yang bukan ko-eksisten serupa white vs. negro sehingga muncul usaha pemberontakan oposisi biner tersebut menjadi white vs. black, karena berdasar argumen bahwa jika ada white, ada red, mengapa tidak ada black namun malah negro yang artinya slave? Contoh serupa sebagaimana dilakukan oleh Sugihastuti (2005: 111-120). Di dalam bukunya Rona Bahasa dan Sastra Indonesia, Sugihastuti mempermasalahkan istilah: pelacur dan WTS[6]. Menurutnya pelacur tidak bersinonim dengan WTS. Sebab jika demikian adalah sinonim maka akan menuding bahwa hanya wanita saja yang dapat melacur. Jika dalam kenyataannya dapat kita temui bahwa tidak hanya wanita saja yang dapat melacur, maka akan muncul pula istilah Pria Tuna Susila. Dengan kata lain, pelacur adalah hipernim bagi WTS dan PTS. Dari sini pula muncul sebuah kemendesakan untuk menyeimbangkan wacana bahwa wanita dan pria berpunya potensi yang sama untuk melacurkan diri. Sekali lagi kudu diperjelas apakah oposisi biner yang ada adalah bentuk ko-eksistensi ataukah bentuk stereotip? Jika dan hanya jika memang ada argumen yang jelas dan meyakinkan bahwa oposisi biner tersebut bukan sebagai yang dan yin, positif dan negatif [7] yang ko-eksisten, maka silakan digugat! DAFTAR PUSTAKA Dipa Nugraha. 2011. Sastra dan Jender. Diakses Sabtu 14 Mei 2011 pukul 6:13 WIB dari: http://dipanugraha.blog.com/2011/04/02/sastra-dan-jender/ Junus, Umar. 1983. Dari Peristiwa ke Imajinasi: Wajah Sastra dan Budaya Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. Kusno, Gustaaf. 2 Januari 2011. Apa Pasal ’Wanita’ Sama dengan ’Betina’ diakses 16 Mei 2011 dari laman: http://bahasa.kompasiana.com/2011/01/02/apa-pasal-wanita-sama- dengan-betina/ Pudjiastuti, Titik. 2009. Sita Berperasaan Perempuan sebuah makalah dalam Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture, and History. ANRC, Gonda Foundation, EFEO, KITLV Jakarta, 26 – 28 Mei 2009. Sheila on 7. 2004. ”Pejantan yang Tangguh” di dalam album Pejantan yang Tangguh. Sony BMG. Slametmuljana. 1964. Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara. Jakarta: PN Balai Pustaka. Sudarwati dan D. Jupriono. 1997. Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik dalam FSU in the Limelight Vol. 5, No. 1 July 1997. Sugihastuti. 2005. Rona Bahasa dan Sastra Indonesia: Tanggapan Penutur dan Pembacanya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [1] Dipakai istilah wanita. Meski demikian boleh diganti dengan perempuan atau betina. [2] Bandingkan lagu “Pretty Woman” oleh Roy Orbison dengan “Pretty Boy” oleh M2M. [3] Ada pendapat bahwa berdasarkan etimologi rakyat Jawa (folk etimology, jarwodoso atau keratabasa, kata wanita dipersepsi secara kultural sebagai 'wani ditata'; terjemahan leksikalnya 'berani diatur' (dalam Sudarwati dan Jupriono, 1997). Namun perlu pula disanggah bahwa ini adalah bentukan plesetan gaya Jawa bukan asal mula bagaimana kata 'wanita' dibentuk. Jadi bukan wani ditata menjadi wanita namun dari adopsi dari Sanskrit vanita menjadi wanita lalu diplesetkan oleh orang Jawa sebagai wani ditata. Kata yang menjadi plesetan orang Jawa adalah misal: amandel aman tur ndedel yang artinya kurang lebih bahwa amandel itu tidak mengapa namun bisa merepotkan. Meskipun demikian, bentuk 'wanita' yang diplesetkan menjadi 'wani ditata' juga merupakan bentuk pen-subordinasi-an kepada 'wanita' oleh pria Jawa (bukan pria Indonesia). [4] Penggunaan kata ‘puan’ di dalam bahasa Indonesia misalnya dapat dilihat di dalam lagu “Selamat Pagi” oleh Indy. [5] Bergerak lincah di sini diartikan sebagai membuat bahasa sebagai sebuah media yang boleh dimainkan siapa saja; bukan seperti Kredo-nya Sutardji, namun bagaimana memanfaatkan bahasa dalam ranah semiotikanya. Misalnya apakah ada yang melarang jikalau mengatakan: ”Suamiku adalah betina kesayanganku.” atau ”Perempuan berseragam itu sungguh gagah dan membikin gerah.”. [6] Sebenarnya Sugihastuti di dalam simpulannya mengenai isu terkait juga membahas mengenai pemakaian istilah Pekerja Seks (Komersial) atau PSK sebagai padan terjemah istilah sex worker, namun penulis melihat argumen Sugihastuti kuranglah kuat. Pun jika hendak dimasukkan ke dalam tulisan ini, pembahasan Sugihastuti tentang istilah PSK tidaklah relevan. [7] Meskipun oposisi biner yang demikian menjadi gugatan Helene Cixous bahwa atribut seperti negatif, lemah, malam dilekatkan kepada perempuan, namun pada wacana yang jauh sebelumnya telah dikembangkan oleh Lao Tzu di dalam kitabnya Tao Te Ching, pembedaan tersebut justru mengkonstruk realitas dan posisi keduanya bukan hirarki vertical namun side by side as one entity. Penghapusan salah satu akan menghapuskan lainnya, dan dalam gerak post-feminism (maaf jika dipakai kata post karena penulis percaya dan melihat bahwa gerakan feminisme memang sudah menuju ke arah post; ke arah sebagaimana secara pesimis dinyatakan oleh Elizabeth Grosz (tentang ini silakan baca tulisan saya Sastra dan Jender)) makin tampak bahwa wacana Kristeva-lah (yang merupakan proposisi daur ulang (?) Lao Tzu) yang paling masuk akal mengenai tata ulang bahasa dan realitas yang tidak lagi memencilkan wanita (/perempuan/betina) sebab segala wacana tentang itu harus dikembalikan pada the beginning there was word (meminjam istilah Perjanjian Baru; silakan dibaca di dalam tulisan saya yang lain The Hypogramatic Reading of Tao Te Ching, Bible, and Koran) bahwa oposisi biner adalah kemendesakan dan tak terelakkan di dalam pembangunan realitas dan ia adalah ko-eksisten. Kemudian jika Anda masih tertarik dengan wacana pemerkaya bahwa by nature memang wanita dengan laki-laki adalah berbeda, silakan Anda baca buku dari Louann Brizendine; "The Female Brain" dan "The Male Brain". View publication stats