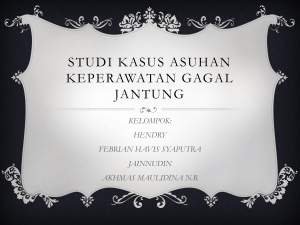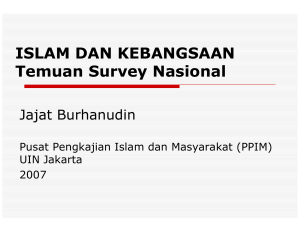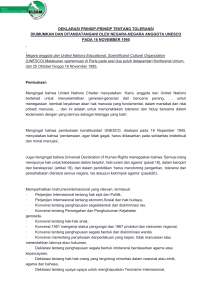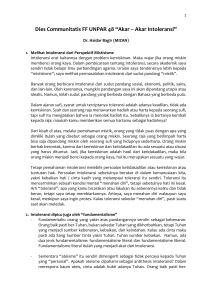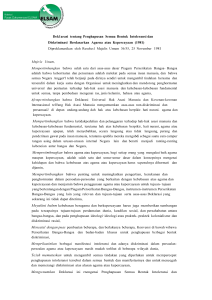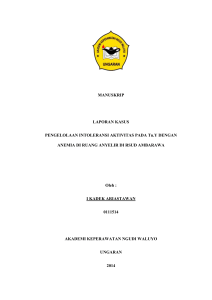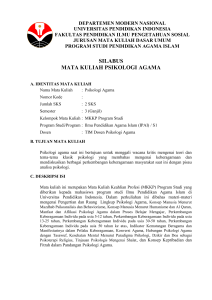Uploaded by
Hasna Aulia
Intoleransi; Implikasi Gagal Paham Beragama

Intoleransi; Implikasi Gagal Paham Beragama Oleh : Hasna Aulia Aktivis Pers Mahasiswa di LPM Invest UIN Walisongo Semarang Praktik intoleransi oleh beberapa umat beragama seakan menjadi tren di Indonesia dewasa ini. Namun gejala serupa sebenarnya banyak terjadi juga di berbagai negara. Misalnya Amerika Latin, di mana penyebaran agama sarat akan kekerasan. Pertanyaannya adalah apa benar agama sebagai sumber kekerasan? Bukankah pada dasarnya semua agama itu nonviolence (antikekerasan)? Secara konseptual, intoleransi adalah sikap tidak tenggang rasa terhadap sesama. Dalam hal ini terjadinya praktik diskriminasi, baik fisik maupun sosial. Parahnya, intoleransi kerap terjadi antarumat beragama yang notabene paham dengan ajaran-ajaran agamanya. Seperti yang tercatat dalam sejarah, sejak dahulu banyak perselisihan dan kasus intoleransi antarumat beragama, bahkan tak jarang perselisihan tersebut berujung pada peperangan. Indonesia merupakan negara yang multiagama dan multibudaya, yang tentu saja tidak lepas dari ancaman jerat praktik intoleransi. Dari sekian banyak kasus intoleransi, perselisihan rumah ibadahlah yang kerap terjadi. Menurut hasil pemantauan Kepolisian Republik Indonesia di tahun 2010 sampai 2012, tercatat sebanyak 196 kasus pengrusakan, penyerangan, dan protes terhadap pendirian tempat ibadah. Rinciannya: sebanyak 142 kasus terjadi di tempat ibadah Kristiani, 20 kasus di tempat ibadah Islam, 6 kasus di tempat ibadah Hindu, dan 2 kasus di tempat ibadah lainnya. Menurut Guru Besar Perbandingan Agama UIN Syarif Hidayatullah, M. Ridwan Lubis dalam buku Hubungan Umat Beragama ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan tersebut. Pertama, sebagian umat beragama melihat mayoritas atau minoritas menjadi lambang kualitas keberagamaan. Padahal populasi umat beragama tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas keberagamaan, melainkan tergantung dari komitmen umat terhadap wawasan, penghayatan, pengamalan, jaringan serta keberadaan lembaga-lembaga keagamaan. Kedua, masyarakat menganggap bahwa rumah ibadah adalah wujud dari eksistensi umat beragama. Keberadaan kelompok umat beragama lain belum siap diterima hegemoni umat tertentu. Di sisi lain, masih banyak pendirian rumah ibadah yang tidak mengindahkan peraturan baik dari pusat maupun daerah. Ketiga, masyarkat belum benar-benar memahami makna kebangsaan. Di mana setiap negara memiliki jarak yang sama terhadap negara, pun negara memiliki jarak yang sama terhadap semua warga negara. Faktor-faktor tersebutlah yang memicu umat beragama seakan berkontestasi mengunggulkan agamanya masing-masing tanpa memedulikan hak-hak kelompok lain. Salah Mengenal Tuhan Menurut Nasution (1986) agama adalah ikatan (dari kekuatan gaib dan tidak dapat ditangkap panca indra) yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Sedangkan beragama adalah menganut atau memeluk agama. Singkatnya, agama adalah suatu ajaran. Sedangkan beragama adalah kegiatan melakukan atau menganut ajaran. Menurut Ibnu Khaldun agama merupakan kekuasaan integrasi, perukun, dan pemersatu. Terbukti dari beberapa ajarannya, misalnya agama Buddha yang sangat menjunjung tinggi ahimsa (antikekerasan) dan ajaran pokok kebajikan kasih sayang. Perintah kasih sayang antar sesama juga tercermin dalam kitab suci Hindu. Salah satunya terjemahan Artawa Veda 3. 30. “Aku jadikan engkau sehati, satu pikiran, bebas dari kebencian, kasihilah satu sama lain seperti sapi mengasihi anaknya yang ia lahirkan,...” Dalam Islam pun tak luput akan perintah perdamian, seperti yang tersurat dalam AlQuran yaitu “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Qs. Al-Hujurat : 10). Ensiklik paling terkenal yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII pada 11 April 1963, bahkan menegaskan pemahaman Gereja Katolik tentang bagaimana menciptakan perdamaian di dunia. Ensikliknya Pacem In Terris (Damai di Bumi) ini kemudian yang memantik munculnya dokumen Konsili Vatikan II dan paus-paus sesudahnya. Kalimat pembukanya tertulis bahwa hal yang paling dirindukan seluruh manusia adalah kedamaian di bumi. Kedamaian itu akan tegak hanya jika perintah Allah ditaati dengan setia. Maka merupakan kekeliruan jika suatu kelompok mengatasnamakan agama sebagai dasar melakukan kekerasan atau intoleransi. Karena menurut Francois Houtart “secara apologis kandungan agama-agama adalah nonviolence, dan manusia lah, baik individu atau kolektif yang menyelewengkan maknanya”. Dari sini dapat diketahui bahwa konflik antar umat beragama sejatinya bermula dari kekeliruan umat beragama itu sendiri dalam memahami agamanya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Maka pemahaman terhadap Tuhan pun harus diutamakan jika ingin tercipta kedamaian. Hal ini selaras dengan paham Khonghucu, bahwa dalam rangka menuju kesempurnaan hidup dengan memahami Tian (Tuhan) hanya dapat dicapai melalui pemahaman manusia terhadap sesamanya. Nah, upaya untuk mencapai pemahaman terhadap Tuhan, agama, dan manusia dapat diterapkan sejak dini melalui pendidikan keluarga. Orang tua sangat berperan penting dalam menumbuhkan pondasi pemikiran anaknya. Dengan cara memperkenalkan Tuhan secara komprehensif dan menanamkan nilai-nilai agama secara humanis, setidaknya akan menumbuhkan nalar generasi penerus bangsa yang berbudi. Tidak selasai sampai di situ, pendidikan di sekolah oleh guru dan di lingkungan oleh tokoh agama juga perlu diperhatikan agar pemahaman terhadap Tuhan dan agama tidak menyimpang. Doktrin bahwa Tuhan menyayangi semua makhluk tanpa melihat perbedaan, bahwa agama adalah simbol kerukunan dan kedamaian, bahwa kasih sayang antar manusia adalah upaya beribadah kepada Tuhan, harus ditegakkan agar kontestasi keberagamaan hilang. Sehingga tercapai prinsip agama yang sesungguhnya yaitu perdamaian.